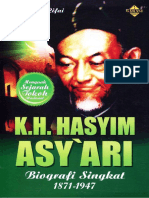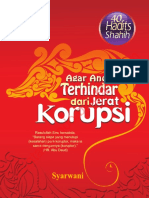100 Tahun Bung Karno
100 Tahun Bung Karno
Diunggah oleh
dancent sutantoHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
100 Tahun Bung Karno
100 Tahun Bung Karno
Diunggah oleh
dancent sutantoHak Cipta:
Format Tersedia
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran
Soekarno Muda
Baskara Wardaya
PADA tanggal
17 Mei 1956
Presiden
Soekarno
mendapat
kehormatan
untuk
menyampaikan
pidato di
depan
Kongres
Amerika
Serikat dalam
rangka
kunjungan
resminya ke
negeri
Dok Kompas
tersebut.
Sebagaimana
dilaporkan
dalam halaman pertama New York Times pada hari berikutnya, dalam
pidato itu dengan gigih Soekarno menyerang kolonialisme. Perjuangan
dan pengorbanan yang telah kami lakukan demi pembebasan rakyat
kami dari belenggu kolonialisme," kata Bung Karno, "telah berlangsung
dari generasi ke generasi selama berabad-abad." Tetapi, tambahnya,
perjuangan itu masih belum selesai. "Bagaimana perjuangan itu bisa
dikatakan selesai jika jutaan manusia di Asia maupun Afrika masih
berada di bawah dominasi kolonial, masih belum bisa menikmati
kemerdekaan?" pekik Soekarno di depan para pendengarnya.
Menarik untuk disimak bahwa meskipun pidato itu dengan keras
menentang kolonialisme dan imperialisme, serta cukup kritis terhadap
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (1 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
negara-negara Barat, ia mendapat sambutan luar biasa di Amerika
Serikat (AS). Namun, lebih menarik lagi karena pidato itu menunjukkan
konsistensi pemikiran dan sikap-sikap Bung Karno. Sebagaimana kita
tahu, kuatnya semangat antikolonialisme dalam pidato itu bukanlah
merupakan hal baru bagi Bung Karno. Bahkan sejak masa mudanya,
terutama pada periode tahun 1926-1933, semangat antikolonialisme dan
anti-imperialisme itu sudah jelas tampak. Bisa dikatakan bahwa sikap
antikolonialisme dan anti-imperialisme Soekarno pada tahun 1950-an
dan selanjutnya hanyalah merupakan kelanjutan dari pemikiran-
pemikiran dia waktu muda.
Tulisan berikut dimaksudkan untuk secara singkat melihat pemikiran
Soekarno muda dalam menentang kolonialisme dan imperialisme-dan
selanjutnya elitisme-serta bagaimana relevansinya untuk sekarang.
Antikolonialisme dan anti-imperialisme
Salah satu tulisan pokok yang biasanya diacu untuk menunjukkan sikap
dan pemikiran Soekarno muda dalam menentang kolonialisme adalah
tulisannya yang terkenal yang berjudul Nasionalisme, Islam dan
Marxisme". Dalam tulisan yang aslinya dimuat secara berseri di jurnal
Indonesia Muda tahun 1926 itu, sikap antikolonialisme tersebut tampak
jelas sekali. Menurut Soekarno, yang pertama-tama perlu disadari adalah
bahwa alasan utama kenapa para kolonialis Eropa datang ke Asia
bukanlah untuk menjalankan suatu kewajiban luhur tertentu. Mereka
datang terutama "untuk mengisi perutnya yang keroncong belaka."
Artinya, motivasi pokok dari kolonialisme itu adalah ekonomi.
Sebagai sistem yang motivasi utamanya adalah ekonomi, Soekarno
percaya, kolonialisme erat terkait dengan kapitalisme, yakni suatu sistem
ekonomi yang dikelola oleh sekelompok kecil pemilik modal yang tujuan
pokoknya adalah memaksimalisasi keuntungan. Dalam upaya
memaksimalisasi keuntungan itu, kaum kapitalis tak segan-segan untuk
mengeksploitasi orang lain. Melalui kolonialisme para kapitalis Eropa
memeras tenaga dan kekayaan alam rakyat negeri-negeri terjajah demi
keuntungan mereka. Melalui kolonialisme inilah di Asia dan Afrika,
termasuk Indonesia, kapitalisme mendorong terjadinya apa yang ia sebut
sebagai exploitation de l'homme par l'homme atau eksploitasi manusia
oleh manusia lain.
Soekarno muda menentang kolonialisme dan kapitalisme itu. Keduanya
melahirkan struktur masyarakat yang eksploitatif. Tiada pilihan lain
baginya selain berjuang untuk secara politis menentang keduanya,
bahkan jika hal itu menggelisahkan profesornya. Pada suatu pagi di awal
tahun 1923, sebagai seorang mahasiswa Soekarno dipanggil untuk
menghadap Rektor Technische Hoge School waktu itu (THS), sekarang
Institut Teknologi Bandung (ITB), yakni Profesor Klopper. Kepada
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (2 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
mahasiswanya, sang profesor mengatakan, "Kamu harus berjanji bahwa
sejak sekarang kamu tak akan lagi ikut-ikutan dengan gerakan politik."
"Tuan," jawab Soekarno, "Saya berjanji untuk tidak akan mengabaikan
kuliah-kuliah yang Tuan berikan di sekolah." "Bukan itu yang sama
minta," sanggah si profesor. "Tetapi hanya itu yang bisa saya janjikan,
Profesor," jawab Soekarno lagi.
Sebagai suatu sistem yang eksploitatif, kapitalisme itu mendorong
imperialisme, baik imperialisme politik maupun imperialisme ekonomi.
Tetapi Soekarno muda tak ingin menyamakan begitu saja imperialisme
dengan pemerintah kolonial. Imperialisme, menurut dia, "bukanlah
pegawai pemerintah; ia bukanlah suatu pemerintahan; ia bukan
kekuasaan; ia bukanlah pribadi atau organisasi apa pun." Sebaliknya, ia
adalah sebuah hasrat berkuasa, yang antara lain terwujud dalam sebuah
sistem yang memerintah atau mengatur ekonomi dan negara orang lain.
Lebih dari sekadar suatu institusi, imperialisme merupakan "kumpulan
dari kekuatan-kekuatan yang kelihatan maupun tak kelihatan."
Soekarno mengibaratkan imperialisme sebagai "Nyai Blorong" alias ular
naga. Kepala naga itu, menurut dia, berada di Asia dan sibuk menyerap
kekayaan alam negara-negara terjajah. Sementara itu tubuh dan ekor
naga itu ada di Eropa, menikmati hasil serapan tersebut. Bersama
dengan kolonialisme dan kapitalisme, imperialisme merupakan tantangan
besar bagi setiap orang Indonesia yang menghendaki kemerdekaan.
Anti-elitisme
Selain kolonialisme dan imperialisme, di mata Soekarno muda ada
tantangan besar lain yang tak kalah pentingnya untuk dilawan, yakni
elitisme. Elitisme mendorong sekelompok orang merasa diri memiliki
status sosial-politik yang lebih tinggi daripada orang-orang lain, terutama
rakyat kebanyakan.
Elitisme ini tak kalah bahayanya, menurut Soekarno, karena melalui
sistem feodal yang ada ia bisa dipraktikkan oleh tokoh-tokoh pribumi
terhadap rakyat negeri sendiri. Kalau dibiarkan, sikap ini tidak hanya bisa
memecah-belah masyarakat terjajah, tetapi juga memungkinkan
lestarinya sistem kolonial maupun sikap-sikap imperialis yang sedang
mau dilawan itu. Lebih dari itu, elitisme bisa menjadi penghambat sikap-
sikap demokratis dalam masyarakat modern yang dicita-citakan bagi
Indonesia merdeka.
Soekarno muda melihat bahwa kecenderungan elitisme itu tercermin kuat
dalam struktur bahasa Jawa yang dengan pola "kromo" dan "ngoko"-nya
mendukung adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Untuk
menunjukkan ketidaksetujuannya atas stratifikasi demikian itu, dalam
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (3 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
rapat tahunan Jong Java di Surabaya pada bulan Februari 1921,
Soekarno berpidato dalam bahasa Jawa ngoko, dengan akibat bahwa ia
menimbulkan keributan dan ditegur oleh ketua panitia. Upaya Soekarno
yang jauh lebih besar dalam rangka menentang elitisme dan
meninggikan harkat rakyat kecil di dalam proses perjuangan
kemerdekaan tentu saja adalah pencetusan gagasan marhaenisme.
Bertolak dari pertemuan pribadinya dengan petani Marhaen, Soekarno
merasa terpanggil untuk memberi perhatian yang lebih besar kepada
kaum miskin di Indonesia, serta kepada peranan mereka dalam
perjuangan melawan kolonialisme yang kapitalistik itu. Kaum Marhaen
ini, sebagaimana kaum proletar dalam gagasan Karl Marx, diharapkan
akan menjadi komponen utama dalam revolusi melawan kolonialisme
dan dalam menciptakan suatu tatanan masyarakat baru yang lebih adil.
Dalam kaitan dengan usaha mengatasi elitisme itu ditegaskan bahwa
Marhaneisme "menolak tiap tindak borjuisme" yang, bagi Soekarno,
merupakan sumber dari kepincangan yang ada dalam masyarakat. Ia
berpandangan bahwa orang tidak seharusnya berpandangan rendah
terhadap rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Ruth McVey, bagi
Soekarno rakyat merupakan "padanan mesianik dari proletariat dalam
pemikiran Marx," dalam arti bahwa mereka ini merupakan "kelompok
yang sekarang ini lemah dan terampas hak-haknya, tetapi yang nantinya,
ketika digerakkan dalam gelora revolusi, akan mampu mengubah dunia."
Kompleks
Lantas, langkah-langkah apa yang diusulkan oleh Soekarno untuk
melawan kolonialisme, imperialisme serta elitisme itu? Pertama-tama ia
mengusulkan ditempuhnya jalan nonkooperasi. Bahkan sejak tahun 1923
Soekarno sudah mulai mengambil langkah nonkooperasi itu, yakni ketika
ia sama sekali menolak kerja sama dengan pemerintah kolonial. Dalam
kaitan dengan ini ia kembali mengingatkan bahwa motivasi utama
kolonialisme oleh orang Eropa adalah motivasi ekonomi. Oleh karena itu
mereka tak akan dengan sukarela melepaskan koloninya. "Orang tak
akan gampang-gampang melepaskan bakul nasinya," kata Soekarno,
"jika pelepasan bakul itu mendatangkan matinya." Oleh karena itu pula ia
yakin bahwa kemerdekaan tidak boleh hanya ditunggu, melainkan harus
diperjuangkan.
Langkah lain yang menurut Soekarno perlu segera diambil dalam
menentang kolonialisme dan imperialisme itu adalah menggalang
persatuan di antara para aktivis pergerakan. Dalam serial tulisan
Nasionalisme, Islam dan Marxisme ia menyatakan bahwa sebagai bagian
dari upaya melawan penjajahan itu tiga kelompok utama dalam
perjuangan kemerdekaan di Indonesia-yakni para pejuang Nasionalis,
Islam dan Marxis-hendaknya bersatu. Dalam persatuan itu nanti mereka
akan mampu bekerja sama demi terciptanya kemerdekaan Indonesia.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (4 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
"Bahtera yang akan membawa kita kepada Indonesia Merdeka," ingat
Soekarno, "adalah Bahtera Persatuan."
Pada saat yang sama Soekarno juga mengingatkan bahwa perjuangan
melawan kolonialisme itu lebih kompleks daripada perjuangan antara
kelompok pribumi melawan kelompok kulit putih. Pada satu sisi perlu
dibedakan antara "pihak Sini" yakni mereka yang mendukung, dan "pihak
Sana" yakni mereka yang menentang perjuangan kemerdekaan. Pada
sisi lain perlu disadari pula bahwa kedua "pihak" itu ada baik di kalangan
pribumi maupun di kalangan penguasa kolonial.
Seruan-seruan Soekarno itu pada tanggal 4 Juli 1927 dilanjutkan dengan
pendirian Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebagai tujuan utamanya
dicanangkan untuk "mencapai kemerdekaan Indonesia." Guna memberi
semangat kepada para aktivis pergerakan, pada tahun 1928 ia menulis
artikel berjudul Jerit Kegemparan di mana ia menunjukkan bahwa
sekarang ini pemerintah kolonial mulai waswas dengan semakin kuatnya
pergerakan nasional yang mengancam kekuasaannya. Ketika pada
tanggal 29 Desember 1929 Soekarno ditangkap dan pada tanggal 29
Agustus 1930 disidangkan oleh pemerintah kolonial, Soekarno justru
memanfaatkan kesempatan di persidangan itu. Dalam pleidoinya yang
terkenal berjudul Indonesia Menggugat dengan tegas ia menyatakan
perlawanannya terhadap kolonialisme. Dan tak lama setelah dibebaskan
dari penjara pada tanggal 31 Desember 1931 ia bergabung dengan
Partai Indonesia (Partindo), yakni partai berhaluan nonkooperasi yang
dibentuk pada tahun 1931 untuk menggantikan PNI yang telah
dibubarkan oleh pemerintah kolonial.
Mendua
Menarik untuk disimak bahwa meskipun Soekarno amat berapi-api dalam
melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme, sebenarnya
perlawanan itu tidak total, dalam arti tidak sepenuhnya dimaksudkan
untuk menuntaskan ketiga tantangan itu. Hal ini tampak misalnya ketika
ia mendirikan PNI. Di satu pihak memang dengan jelas digariskan bahwa
tujuan utama PNI adalah mencapai Indonesia merdeka. Tetapi di lain
pihak cita-cita kemerdekaan itu tidak disertai hasrat untuk mengubah
sistem politik yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem
politik yang sama sekali baru. Alih-alih perubahan total, Soekarno-
sebagaimana banyak aktivis pergerakan waktu itu-berkeinginan bahwa
negeri yang merdeka itu nanti akan ditopang oleh sistem yang mirip
dengan sistem yang menopangnya saat terjajah. Hanya elitenya akan
diganti dengan elite baru, yakni elite pribumi.
Pemakaian Soekarno atas gagasan-gagasan Marxis amat selektif. Ia
tertarik dengan pengertian proletariat-nya Marx, tetapi ia memperluasnya
menjadi Marhaenisme. Di satu pihak perluasan itu membuat revolusi
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (5 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
menjadi lebih jauh daripada sekadar pertarungan antara buruh pabrik
melawan para kapitalis, tetapi di lain pihak hal ini juga membuat fokus
revolusi menjadi kabur. Kekaburan ini menjadi bertambah ketika disadari
bahwa pemerintah kolonial, yakni pihak yang mau dilawan oleh kaum
Marhaen, melibatkan juga banyak sekali pejabat dan pegawai pribumi.
Dan dalam hal ini rupa-rupanya Soekarno memang tidak bermaksud
mengadakan suatu perubahan total. "Kita berjuang bukan untuk melawan
orang kaya," tulisnya di harian Fikiran Rakjat tahun 1932, "melainkan
untuk melawan sistem."
Betapapun "galak"-nya Soekarno muda dalam menentang kolonialisme
dan imperialisme dengan menggunakan prinsip nonkooperasi, ternyata ia
tidak selalu konsisten. Sekitar bulan-bulan Agustus-September 1933,
sebagaimana dilaporkan oleh pemerintah kolonial, ia menyatakan
mundur dari keanggotaan Partindo, memohon maaf, dan meninggalkan
prinsip nonkooperasi. Ia bahkan dilaporkan bersedia untuk bekerja sama
dengan pemerintah penjajah Belanda. Lepas dari benar atau tidaknya
laporan pemerintah itu, berita ini mengagetkan dan mengecewakan para
pendukung gerakan kemerdekaan waktu itu. Mereka kecewa karena
tokoh perjuangan yang mereka agung-agungkan, telah menyerah. Dalam
koran Daulat Ra'jat edisi 30 November 1933 Mohammad Hatta bahkan
menyebut peristiwa ini sebagai "Tragedie-Soekarno." Hatta amat
menyesalkan inkonsistensi serta lemahnya semangat perlawanan tokoh
taktik nonkooperasi itu.
Berhubungan dengan sikap anti-elitismenya perlu dilihat bahwa
meskipun dalam pidato dan tulisan-tulisannya Soekarno tampak melawan
elitisme, tetapi sebenarnya bisa diragukan apakah ia sepenuhnya
demikian. Hal ini tampak misalnya dalam pidato yang ia sampaikan pada
tanggal
26 November 1932 di Yogyakarta, kota pusat aristokrasi Jawa. Dalam
pidato itu Soekarno mengajak setiap orang, apa pun status sosialnya,
untuk bersatu demi kemerdekaan. Tetapi sekaligus ia menegaskan
bahwa bersama Partindo dirinya tidak menginginkan perjuangan kelas.
Dalam tulisan Nasionalisme, Islam dan Marxisme, sebagaimana disinyalir
oleh McVey, sebenarnya Soekarno sama sekali tidak sedang bicara
dengan rakyat banyak. Dalam tulisan itu ia, menurut McVey, "tidak
menyampaikan imbauannya kepada kelompok-kelompok radikal
pedesaan dan proletar yang telah memelopori pemberontakan komunis
setahun sebelumnya, atau kepada para santri-santri taat pejuang Islam,
atau kepada rakyat kebanyakan di dalam maupun di sekitar wilayah
perkotaan yang bergabung ke dalam PNI yang didirikan oleh Soekarno
saat mereka sedang mencari pegangan di tengah lunturnya nilai-nilai
tradisional." Soekarno, sebaliknya, lebih mengalamatkan imbauannya
kepada sesama kaum elite pergerakan, atau kepada apa yang disebut
oleh McVey sebagai "elite metropolitan," yang keanggotaannya biasanya
ditentukan oleh tingkat pendidikan Barat yang diperoleh seseorang.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (6 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
Kelompok elite metropolitan yang dituju oleh tulisan Soekarno itu
sebenarnya jumlahnya amat kecil, dan kebanyakan dari mereka tinggal di
kota-kota dengan pengaruh Eropa, seperti misalnya Bandung, Surabaya,
Medan atau Jakarta. Di satu pihak, kelompok elite ini mempunyai
komitmen yang tinggi terhadap kemerdekaan Indonesia serta telah
berpikir dalam rangka identitas nasional dan tidak lagi dalam rangka
identitas regional seperti generasi pendahulunya. Di lain pihak, kelompok
ini tidak melihat perlunya mengadakan suatu revolusi sosial yang akan
secara total mengubah sistem yang ada, dengan segala corak kolonial-
kapitalisnya. Yang lebih mendesak menurut para aktivis generasi ini
adalah melengserkan elite pemerintahan kolonial asing dan
menggantinya dengan elite lokal yang dalam hal ini adalah diri mereka
sendiri. Dengan kata lain, mereka menghendaki adanya revolusi
nasional, tetapi bukan revolusi sosial.
Dalam kaitannya dengan rakyat banyak, anggota kelompok elite ini
merasakan perlunya dukungan rakyat dalam perjuangan melawan
pemerintah kolonial. Pada saat yang sama mereka berupaya mengikis
sikap-sikap tradisional rakyat yang mereka pandang sebagai penghalang
bagi langkah menuju dunia modern, yakni dunia sebagaimana tercermin
dalam kaum kolonialis Barat.
Perasaan yang serupa tampaknya juga dimiliki oleh Soekarno. Bagi
Soekarno muda, massa rakyat-betapapun tampak penting sebagai
simbol dan sebagai potensi politik-sebenarnya lebih dibutuhkan sebagai
sumber dukungan baginya dalam mengambil langkah-langkah politis.
Oleh karena itu tidak mengherankan, sebagaimana pernah dikeluhkan
oleh Hatta, jika kontak Soekarno dengan rakyat kebanyakan itu
sebenarnya amat sedikit, terbatas pada kontak melalui pidato-pidato
yang penuh tepuk tangan dan sorak-sorai.
Dikatakan oleh Bernhard Dahm, penulis biografi Bung Karno, di satu
pihak Soekarno menentang sikap rakyat yang mudah pasrah pada nasib,
tetapi di lain pihak ia "membutuhkan sorak-sorai tepuk tangan (mereka)
guna mendukung rasa percaya dirinya." Dengan demikian tampak
adanya sikap mendua (ambivalen) dalam sikap-sikap Soekarno terhadap
kapitalisme, imperialisme maupun elitisme: Di satu pihak ia membenci
ketiganya. Di lain pihak, sadar atau tidak, ia melihat bahwa beberapa
aspek di dalam ketiganya layak untuk dipertahankan atau setidaknya
untuk tidak dikutak-katik.
Tidak sendirian
Pertanyaannya, mengapa Soekarno mengambil sikap mendua itu?
Pertama-tama perlu disadari bahwa bagaimanapun juga Soekarno
adalah anak zamannya. Ia merupakan bagian dari generasi pergerakan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (7 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
pada tahun 1920-an. Berbeda dengan generasi 1908 yang berorientasi
pada perubahan sistem tanpa disertai kuatnya gagasan mengenai
Indonesia merdeka, generasi Soekarno lebih berorientasi pada
pentingnya kemerdekaan, tetapi lemah dalam hal perjuangan demi
perubahan sistem. Lebih dari itu, generasi tahun 1920-an - dengan lebih
banyak lulusan pendidikan Barat - cenderung untuk justru
mempertahankan sistem pemerintahan Barat yang ada, tetapi dengan
menggeser elite kolonialnya untuk diganti dengan elite lokal.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Takashi Shiraishi, berbeda dengan
generasi pendahulu yang menekankan ketokohan individu, generasi
Soekarno menekankan kepartaian. Tetapi pada tahun 1920-an partai-
partai itu mengalami banyak pertentangan internal yang di mata
Soekarno akibatnya bisa fatal bagi gerakan menuju kemerdekaan. Pada
tahun 1920, misalnya, terjadi pertentangan dalam tubuh Sarekat Islam,
terutama antara apa yang disebut sebagai "SI Putih" dengan lawannya,
"SI Merah." Pertentangan ini kemudian mendorong lahirnya Partai
Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1923 gerakan nasionalisme
mengalami kemandekan total, ditandai dengan dibubarkannya National-
Indische Partij (NIP) pada tahun itu, dan suburnya gerakan-gerakan yang
lebih bercorak internasional, khususnya gerakan Islam dan Komunis.
Pada tahun 1926-1927 PKI memutuskan untuk berontak terhadap
pemerintah kolonial Belanda, tetapi karena kurangnya dukungan
masyarakat, pemberontakan itu gagal. Soekarno sadar bahwa jika
perpecahan itu tidak diatasi sekarang, hal itu bisa berakibat fatal bagi
perjuangan kemerdekaan selanjutnya.
Jika Soekarno muda tampak terpisah dari rakyat, sebenarnya ia tidak
sendirian. Banyak tokoh elite perjuangan pada zamannya juga demikian.
Ketika membubarkan PNI pada tanggal 25 April 1931, misalnya, para
pemimpin partai itu tidak banyak berkonsultasi dengan rakyat
kebanyakan yang menjadi anggotanya. Akibatnya rakyat menjadi
kecewa, membentuk apa yang disebut "Golongan Merdeka," dan
memperjuangkan pentingnya pendidikan rakyat.
Tentang perubahan sikap atau permohonan maaf Soekarno kepada
pemerintah kolonial, hal itu perlu dilihat dalam konteksnya. Waktu
dipenjara untuk kedua kalinya, Soekarno muda adalah bagaikan ikan
yang dipisahkan dari "air"-nya, yakni massa yang biasa mendukungnya,
dan yang membuatnya bersemangat dalam perjuangan kemerdekaan.
Dalam penjara itu ia disel sendirian selama delapan bulan tidak hanya
tanpa harapan akan adanya keringanan hukum, melainkan juga
dibayang-bayangi kemungkinan pembuangan ke "neraka" Boven Digul.
Dalam keadaan demikian tidak mengherankan jika sebagai manusia
Soekarno ada unsur menyerah.
Berdampak luas
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (8 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
Apa pun latar belakang sikap-sikap itu, pola hubungan elite rakyat yang
diambil oleh Soekarno dan para aktivis pergerakan waktu itu rupa-
rupanya memiliki dampak yang luas. Ketika pada tahun 1933-1934
Soekarno serta para pemimpin lain ditangkap dan diasingkan oleh
Belanda, gerakan kemerdekaan mengalami kemacetan total. Tanpa
adanya elite metropolitan itu seolah-olah rakyat tidak bisa lagi bergerak
dalam perjuangan demi kemerdekaan. Pergerakan itu baru muncul
kembali ketika para pemimpin yang diasingkan itu dibebaskan oleh
Belanda saat mereka terancam oleh kedatangan balatentara Jepang.
Bahkan pada masa revolusi sendiri bisa dipertanyakan apakah
sebenarnya rakyat yang ikut gigih bertempur dan berkorban
mempertahankan kemerdekaan itu mendapat kesempatan yang
maksimal dalam menentukan arah revolusi. Dalam tulisannya mengenai
pola hubungan antara elite dan rakyat pada zaman revolusi, Barbara
Harvey menyatakan bahwa hubungan itu tidak hanya amat lemah, tetapi
juga berakibat cukup fatal bagi revolusi kemerdekaan itu sendiri.
Lemahnya hubungan antara para pemimpin nasional di tingkat pusat
dengan rakyat di desa-desa, menurut dia, "merupakan faktor utama bagi
gagalnya elite kepemimpinan untuk menggalang dan mengarahkan
kekuatan rakyat demi terwujudnya tujuan-tujuan revolusi."
Dengan kata lain, sebenarnya rakyat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam
proses bernegara. Jika ini benar, mungkin tak terlalu mengherankan jika
PKI-meskipun pada tahun 1948 ditekan besar-besaran setelah peristiwa
Madiun-dalam waktu singkat berkembang pesat pengikutnya. Ini antara
lain karena di dalam PKI banyak rakyat merasakan bahwa justru dalam
partai yang menekankan antikemapanan (baca: anti-elite metropolitan)
itu kepentingan dan cita-cita mereka mendapat tempatnya. Dalam Pemilu
1955 PKI bahkan berhasil memperoleh suara terbanyak keempat.
Sayang sekali bahwa keterpisahan antara elite dan masyarakat itu pada
zaman pasca-Soekarno tidak mengecil, melainkan justru membesar.
Meskipun sejak naiknya Orde Baru pada akhir 1960-an aksespara elite
kepada rakyat kebanyakan telah terbuka semakin luas-antara lain
dengan naiknya tingkat pendidikan, semakin tersedianya sarana-sarana
komunikasi dan menguatnya ekonomi-akses itu tak sepenuhnya
termanfaatkan. Di bawah orde yang katanya "baru" itu tetap saja rakyat
menjadi komponen massal yang dalam proses bernegara, berada di
bawah kontrol elite metropolitan sebagai penentu hampir semua
kebijakan yang ada.
Tak jarang bahwa upaya-upaya untuk mendorong partisipasi rakyat lebih
luas justru harus berhadapan dengan tindakan militer yang keras.
Meminjam istilahnya Benedict Anderson, bisa dikatakan bahwa society-
nya boleh baru, tetapi state (baca: elite)-nya tetap yang lama. Tak kalah
sayangnya tentu saja adalah bahwa tumbangnya sistem pemerintahan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikoloniali...Anti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (9 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno Muda -- Jumat, 1 Juni 2001
militeristik masa Orde Baru tidak disusul dengan tumbuh suburnya
demokrasi, melainkan dengan kaotiknya kehidupan politik, yang konon
justru dimulai dari kalangan elitenya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa
sekarang ini di lapisan bawah rakyat merasa semakin kecewa terhadap
perilaku, komentar-komentar, serta percekcokan yang lahir di antara
kelompok elite politik yang ada.
Ketika pada tahun 2001 bangsa ini memperingati seratus tahun lahirnya
Soekarno dan lima puluh enam tahun Proklamasi Kemerdekaan, kita
masih dilanda berbagai ketidakpastian, yang salah satu akarnya adalah
keterpisahan antara elite dengan rakyatnya.
Masih panjang
Dengan sedikit meminjam seruan Bung Karno yang terkenal, sekarang ini
kita perlu "membangun dunia baru." Tetapi upaya untuk membangun
dunia yang baru itu kiranya harus dimulai dengan terlebih dahulu
"membangun Indonesia baru." Dan upaya membangun Indonesia baru itu
mungkin harus dimulai dengan membangun elite politik yang benar-benar
lahir dari kalangan rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dalam Indonesia yang baru itu diharapkan tiada lagi-kalaupun ada kecil
peranannya-kelompok elite yang hanya sibuk berebut kekuasaan dan
pengaruh.
Hal ini bisa terjadi jika para aktivis muda reformasi sekarang ini tidak
enggan untuk belajar dari para aktivis pergerakan generasi tahun 1920-
an. Di satu pihak meneruskan sikap militan generasi itu dalam
memperjuangkan cita-cita bersama dan rela berkurban demi cita-cita itu.
Di lain pihak menolak kecenderungan untuk mewarisi sistem
pemerintahan sebelumnya, yakni kecenderungan untuk mengganti elite
lama dengan elite yang baru tetapi yang pola dan orientasi politiknya
tetap sama. Dengan demikian akan bisa diharapkan lahirnya elite politik
yang benar-benar berorientasi pada semakin terwujudnya demokrasi.
"Kaki kami telah berada di jalan menuju demokrasi," lanjut Presiden
Soekarno dalam pidatonya di depan Kongres AS itu. "Tetapi kami tidak
ingin menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa kami telah
menempuh seluruh jalan menuju demokrasi," sambungnya. Ia sadar
bahwa meskipun selama bertahun-tahun bangsa Indonesia telah
beperang melawan kolonialisme, imperialisme dan elitisme, jalan menuju
demokrasi masih tetap panjang. Tetapi Bung Karno juga sadar bahwa
betapapun panjangnya sebuah perjalanan, ia harus dimulai dengan
langkah-langkah pertama.
* Baskara Wardaya SJ mahasiswa ilmu sejarah pada Universitas
Marquette, Milwaukee, Wisconsin, AS.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Antikolonial...nti-elitisme%20dalam%20Pemikiran%20Soekarno%20.htm (10 of 11)4/3/2005 11:04:48 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over"
Spiritualitas Bung Karno
Bambang Noorsena
Setelah dahulu pada zaman-zaman sebelumnya Brahma-Wishnu-
Ishwara menjelma dalam berbagai raja-raja di dunia, kini pada
zaman kaliyuga turunlah Sri Jinapati (Buddha) untuk meredakan
amarah Kala. Sebagaimana Sidharta Gautama, sebagai titisan Sri
Jinapati, Sutasoma putra Mahaketu raja Hastina, keturunan
Pandawa, meninggalkan kehidupan istana dan memilih hidup
sebagai seorang pertapa.Pada suatu hari, para pertapa mendapat
gangguan dari Porusada, raja raksasa yang suka menyantap daging
manusia. Mereka memohon kepada Sutasoma untuk membunuh
raksasa itu, tetapi permintaan itu ditolaknya. Setelah dalam olah
spiritualnya Sutasoma mencapai kemanunggalan dengan Buddha
Wairocana, akhirnya ia kembali ke istana dan dinobatkan menjadi
Raja Hastina. Sementara itu, Porusada yang ingin disembuhkan dari
sakit parah pada kakinya, bernazar akan mempersembahkan
seratus raja sebagai santapan Bathara Kala. Tetapi, Sutasoma
menyediakan diri disantap oleh Kala, asalkan seratus raja itu
dibebaskan. Kerelaan ini sangat menyentuh hati Kala, bahkan
Porusada pun menjadi terharu. Dewa Siwa yang menitis pada
Porusada akhirnya meninggalkan tubuh raksasa itu, karena
disadarinya bahwa Sutasoma adalah Buddha sendiri. Mangka
Jinatwa lawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, tan hana
dharma mangrwa (Hakikat Buddha dan hakikat Siwa adalah satu,
berbeda-beda dalam perwujudan eksoterisnya tetapi secara esoteris
satu. Tidak ada dualisme dalam kebenaran agama).
SUATU malam di tahun 1962, bertempat di Pura Ubud, tatkala langit
Pulau Dewata cerah bermandikan cahaya purnama. "Saya sangat
terkesan dengan ucapan Sutasoma tadi," kata Bung Karno usai
pementasan wayang sambil menghampiri I Nyoman Granyam,
seorang dalang dari Sukawati, yang khusus diundangnya untuk
melakonkan Porusaddhasanta (Porusada yang ditenangkan) atau
yang lebih dikenal dengan lakon Sutasoma itu.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (1 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
Lalu Bung Karno mensitir ungkapan bahasa Jawa kuno yang
dimaksud, "Nanging hana pamintaku uripana sahananing ratu
kabeh" (Tetapi permohonanku, hidupkanlah raja-raja itu semua).
Itulah ucapan Sutasoma kepada raksasa Porusada, sambil
menyerahkan dirinya sebagai santapan Kala, asal seratus raja itu
dibebaskan.
Ada dua hal yang perlu digarisbawahi dari penggalan karya Mpu
Tantular ini. Pertama, dari karya Tantular ini berasal dari istilah
"mahardhika" (yang menjadi asal kata merdeka), "Pancasila" dan
seloka "bhinneka tunggal Ika"-ungkapan yang menurut Dr Soewito
dalam tulisannya Sutasoma, A Study in Javanese Wajrayana (1975)-
"is a magic one of great significance and it embraces the sincere
hope the whole nation in its struggle to become great, unites in frame
works of an Indonesian Pancasilaist community".
Kedua, perhatian yang diberikan Bung Karno pada ucapan
Sutasoma yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi
kesejahteraan umat manusia. Yang kedua ini juga tidak kurang
penting, sebab ternyata jalan yang sama akhirnya ditempuh oleh
Bung Karno demi menyelamatkan bangsanya dari pecahnya "perang
saudara" pasca-Gestok (Gerakan 1 Oktober) 1965. Jadi, yang
pertama terkait erat dengan pandangan religi Bung Karno,
khususnya dalam melacak pandangan-pandangan dasar
keagamaannya, sedangkan yang kedua menyangkut religiusitas
atau penghayatan keagamaannya.
Memang, kini ungkapan Bhinneka Tunggal Ika tercantum sebagai
seloka dalam lambang negara kita dalam makna kebangsaan yang
lebih kompleks. Akan tetapi, makna semula ungkapan ini penting kita
kedepankan kembali, justru karena secara khusus kita kaitkan
dengan wacana religi dan religiusitas Bung Karno di atas. Begitu
juga, istilah Pancasila yang juga tercantum dalam karya Tantular ini,
aslinya berasal dari kelima hukum moral Buddhis: "Pancasila ya
gegen den teki away lupa" (Pancasila harus dipegang teguh jangan
sampai dilupakan). Salah satu sila dari Pancasila Buddhis adalah
larangan untuk membunuh sesama makhluk hidup (Panapati
vermanai sikkapadam samadiyami) yang kiranya menjiwai kisah
Sutasoma dan mengilhami pilihan moral Bung Karno untuk lebih baik
dirinya sendiri tenggelam demi keutuhan bangsa dan negara yang
sangat dicintainya.
Bung Karno di mata kawan dan lawan politiknya
Bung Karno adalah sosok yang total kontroversial. Di mata lawan-
lawan politiknya di Tanah Air-nya sendiri, ia dianggap mewakili sosok
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (2 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
politisi kaum abangan yang "kurang islami". Mereka bahkan
menggolongkannya sebagai gembong kelompok "nasionalis
sekuler". Akan tetapi, di mata Syeikh Mahmud Syaltut dari Cairo,
penggali Pancasila itu adalah Qaida adzima min quwada harkat al-
harir fii al-balad al-Islam (Pemimpin besar dari gerakan kemerdekaan
di negeri-negeri Islam). Malahan, Demokrasi Terpimpin, yang di
negerinya sendiri diperdebatkan, justru dipuji oleh syeikh al-Azhar itu
sebagai, "lam yakun ila shuratu min shara asy syuraa' allatiy ja'alha
al-Qur'an sya'ana min syu'un al-mu'minin" (tidak lain hanyalah salah
satu gambaran dari permusyawaratan yang dijadikan oleh Al Quran
sebagai dasar bagi kaum beriman).
Di mata lawan politiknya di Barat, seperti tampak dari ucapan Willard
A Hanna, Bung Karno adalah "politisi tanpa identitas dan tanpa
prinsip, yang berpadu dalam dirinya nabi dan playboy, tukang sulap
dan tukang obat". Tetapi, orang-orang Arab menamakannya ra'is,
dan orang-orang Mesir di Kota Cairo menjulukinya al-hakim. Tak
seorang pun meragukan popularitasnya di negeri-negeri Islam itu.
Nama besar Bung Karno diabadikan antara lain dalam Qamus al-
Munjid. Konon, hanya dua tokoh Indonesia yang dicatat dalam
kamus karya Louise Ma'louf, seorang Arab-Kristen itu. Soekarno,
dan satunya lagi Syeikh Nawawi al-Bantani.
Tatkala memuncaknya ketegangan antara Israel dan negara-negara
Arab soal status Palestina, pers sensasional Arab yang salah paham
dengan pencabutan sebutan Deicidium (pembunuh Tuhan) kepada
kaum Yahudi, menyambut Bung Karno, "Juara untuk kepentingan-
kepentingan Arab telah tiba". Pada pihak lain, Tahta Suci Vatikan
sendiri memberikan kepadanya tiga gelar penghargaan kepada
presiden pertama dari Republik yang mayoritas Muslim itu.
Gaya religius Bung Karno
Relevansi mengemukakan faham keagamaan Bung Karno ini,
minimal terkait erat dengan pertanyaan: Seberapa jauhkah
peranannya dalam menentukan masa depan Indonesia, berangkat
dari pluralisme agama yang merupakan problem tersendiri apabila
tidak diberikan perhatian khusus dalam membangun sebuah
bangsa? Kenyataan ini dikemukakan, dengan sepenuhnya
menyadari bahwa mengemukakan spiritualitas Bung Karno adalah
juga merupakan bagian dari kontroversi itu sendiri.
"Gaya religius Soekarno adalah gaya Soekarno sendiri," tulis Clifford
Geertz dalam Islam Observed (1982). Betapa tidak? Kepada Louise
Fischer, Bung Karno pernah mengaku bahwa ia sekaligus Muslim,
Kristen, dan Hindu. Di mata pengamat seperti Geertz, pengakuan
semacam itu dianggap sebagai "bergaya ekspansif seolah-olah
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (3 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
hendak merangkul seluruh dunia". Sebaliknya, ungkapan semacam
itu-pada hemat BJ Boland dalam The Struggle of Islam in Modern
Indonesia (1982)-"hanya merupakan perwujudan dari perasaan
keagamaan sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya Jawa".
Bagi penghayatan spiritual Timur, ucapan itu justru "merupakan
keberanian untuk menyuarakan berbagai pemikiran yang mungkin
bisa dituduh para agamawan formalis sebagai bidah".
Ungkapan Bung Karno ini, di mata para penghayat tasawuf bukanlah
hal yang asing. Dengarlah, Ibn Al-'Arabi (1076-1148)
mendendangkan kesadaran yang sama. "Laqad shara qalbiy qabilan
kulla shuratin, famar'a lighazlanin wa diir liruhbanin wa baytun li
autsanin wa ka'batu thaifi wal wahu tawrati wa mushafu qur'anin
(Hatiku telah siap menerima segala simbol, apakah itu biara rahib-
rahib Kristen, rumah berhala, Kabah untuk thawaf, lembaran Taurat
atau mushaf Al Quran).
"Panteis-monoteisme" Bung Karno?
Ketika menerima gelar doctor honoris causa (doktor kehormatan) di
Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Bung Karno menyebut bahwa
tauhid yang dianutnya sebagai Panteis-monoteis. Bung Karno yakin
bahwa Tuhan itu satu, tetapi Ia hadir dan berada di mana-mana.
Tentu saja di kalangan Islam dan Kristen, istilah panteisme ini bisa
mengundang salah paham. Kontan saja, orang langsung
menghubungkannya dengan sosok legendaris Syekh Siti Jenar, "Al-
Hallaj"-nya orang Jawa.
Di satu pihak, dalam berbagai kesempatan Bung Karno mengritik
paham kalam asy'ariyah mengenai ketidakcukupan 20 sifat Allah,
berbareng dengan kritiknya terhadap paham taqlid dan kejumudan-
kejumudan kaum tradisionalis pada zamannya. Kritik Bung Karno ini
bisa dilacak dari kegandrungannya pada paham rasionalisme Islam
klasik Mu'tazilah dan pemikiran-pemikiran pembaru Islam khususnya
Jamaluddin al-Afghani. Tetapi pada pihak lain, Bung Karno tidak bisa
melepaskan diri dengan warisan keagamaan Jawa yang sangat
kental berciri mistik.
Karena itu, menarik sekali dalam deskripsinya mengenai tauhid,
Bung Karno merujuk juga Baghawad Gita. "The Gospel of Hinduism"
itu pun dikutipnya begitu bebas, sambil di sana-sini membuat
penekanan dengan frasa-frasa buatannya sendiri. Tuhan ada di
mana-mana. Bahkan juga, Bung Karno mengutip sabda Khrsna:
"I am in the smile of the girl" (pada pidato di tempat lain, "Ik ben in de
glimlach van het meisje"-Aku ada dalam senyum simpul gadis yang
cantik). Tetapi, frasa ini ternyata ciptaan Bung Karno sendiri, dari
kata aslinya dalam bahasa Sansekerta: "tejas tejaswinam aham". Di
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (4 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
antara semua keindahan, Akulah kecantikan" (Bhagawad Gita X,36).
Menurut saya, Bung Karno belum sampai menjadi seorang panteis
tulen, atau menganut monisme radikal-menurut istilah PJ Zoetmulder
SJ-yang sama sekali menyangkal bahwa segenap realitas itu lebur
menyatu tanpa dualitas.
Sebab di mata Bung Karno, penekanan pada aspek tasybih
(imanensi) Tuhan, sama sekali tidak menghapuskan aspek tanzih
(transendensi)-Nya. Barangkali, istilah yang tepat untuk
menggambarkan keyakinan Bung Karno adalah
"panentheisme" (pan, "segala sesuatu"; en, "dalam" dan theos,
"Tuhan"). Jadi, segala sesuatu ada dalam Tuhan. Maksudnya,
totalitas segenap realitas yang diciptakan ada dalam Tuhan, tetapi
Tuhan sendiri melebihi totalitas tersebut. Kita dapat
membandingkannya dengan ucapan Imam al-Ghazali (wafat 1111),
At Tauhid al-khalis an layaraha fii kulli syai'in ilallah (Tauhid sejati
adalah penglihatan atas Allah dalam segala sesuatu). Juga, menurut
Ibn al-'Arabi, segenap alam semesta adalah tajjali atau penampakan
dari Allah.
Indonesia sebagai sebuah mitos
Akan tetapi, apa pun rincian dari perkembangan legitim dalam faham
teologisnya, yang jelas dengan latar belakang pandangan
teologisnya itu, Bung Karno sangat mengakrabi alam semesta. Dan
kunci untuk mengerti hal itu adalah Tat Twam Asi (Aku adalah dia,
dia adalah aku). Mencintai sesama berarti mencintai Tuhan, bahkan
mencintai alam berarti mencintai Pencipta-Nya. Dan cinta Bung
Karno terhadap kosmos itu diawali dari Bumi tempat kakinya
berpihak, Bumi pertiwi Indonesia yang disapanya dengan takjub dan
hormat sebagai "Ibu". Bagi Bung Karno, Indonesia telah menjadi
sebuah mitos. Mungkin karena itu, Agus Salim dan A Hassan
mengkhawatirkan nasionalisme Bung Karno akan jatuh kepada
faham ashabiyah (spirit of clan), yang menjurus kepada tindakan
syirk atau pemberhalaan.
Lebih jelas lagi, kita bisa mengikuti deskripsi Bung Karno mengenai
nasionalisme Indonesia yang diungkapkan begitu berapi-api: "Bukan
saya berkata Tuhan adalah Indonesia", kata Bung Karno, "tetapi
Tuhan bagiku tercermin pula dalam Indonesia". Sang Putra Fajar itu
tidak dapat menahan hentakan-hentakan gelora jiwa dalam dadanya
yang begitu mencintai negerinya, sampai harus bercakap akrab dan
berdendang takjub dengan sungai-sungainya, pohon-pohonnya,
langit biru dan awan gemawannya, ombak laut dan pantai-pantainya.
Singkat kata, di mata Bung Karno, Indonesia adalah satu totaliteit
daripada segala perasaan yang terkandung dalam kalbu yang
membuatnya rela untuk berjuang.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (5 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
Gambaran ini, seperti pernah ditulis Bung Karno sendiri,
mengingatkan kita pada sebuah seloka dari Ramayana karya
pujangga Valmiki, mengenai cinta dan bakti kepada Janani
Janmabhumi- yaitu agar setiap orang mencintai Tanah Airnya seperti
ia mencintai ibu kandungnya sendiri. Meskipun sikap ini bisa
ditafsirkan secara ekstrem, seperti pembelaan Kumbakarna terhadap
negeri Alengka yang diteladankan dalam Serat Tripama (karya
Mangkunegara IV).
Ksatria berwujud raksasa ini ketika terjadi perang antara Rama
dengan Rahwana, akhirnya tetap membela Tanah Airnya.
Alasannya, bukan karena ia mendukung kejahatan Rahwana, tetapi
karena ia tidak tega melihat Tanah Airnya: yang sumur dan
ladangnya sehari-hari ia makan dan minum itu, diinjak-injak oleh
pasukan musuh, sekalipun musuhnya itu berada di pihak yang
benar. Sikap Kumbakarna ini, bisa saja diartikan sebagai sikap right
or wrong my country. Namun, Bung Karno tidak akan sampai
menafsirkan nasionalisme dalam makna seekstrem itu, karena
penolakannya yang tegas terhadap chauvinisme, dan sebagai
gantinya Bung Karno menawarkan sebuah "nasionalisme yang
tumbuh subur dalam tamansari perikemanusiaan". My Nasionalism is
humanity, begitu ucapan Gandhi yang acap dikutipnya.
Spiritualitas Bung Karno juga berciri "sakramentalis". Sebagaimana
nabi-nabi semitis dari zaman dahulu, Bung Karno "believed in the
beauty of holiness" (percaya kepada kecantikan dari keagungan),
berbeda dengan orang-orang Yunani yang "believed in the holiness
of beauty" (percaya pada keagungan dari kecantikan) sehingga
memberhalakan alam itu (Max I. Dimont, 1995). Sebagaimana "jiwa
kosmis" Fransiskus dari Asisi, alam raya dinilainya bukan hanya
bernilai profan, melainkan sekalian makhluk adalah sakramen Sabda
Ilahi yang menunjuk kepada pribadi Ilahi. Dalam diri Bung Karno,
gaya religiusnya yang unik ini: "religius intelektual artistik"-menurut
istilah Clifford Geertz-tidak dapat dilepaskan dari warisan
tradisionalisme Jawa dan darah seni Bali dari ibunya. "Ingat, aku
adalah anak Ida Ayu Nyoman Rai, keponakan Raja Singaraja, wanita
dari Bali", kata Bung Karno pada suatu saat.
Tak ayal, Bung Karno, seperti para pujangga Jawa kuno (yang karya-
karyanya masih dilestarikan di Bali)-"berbakti kepada
keindahan" (ahyun ing kalangwan) karena keyakinan bahwa Tuhan
sendirilah "tattwa ning lango" (inti segala keindahan). Bukankah para
sufi mendendangkan tembang yang sama? Tidak seorang pun dari
mereka yang berzikir mengagungkan asma-Nya, kecuali
bersenandung dengan syair-syair mereka. Kullu jamilun min
jamalullah (Semua keindahan adalah berasal dari keindahan Allah).
Juga, Inallaha jamilun wa yahibuj jamal (Allah itu mahaindah dan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (6 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
mencintai keindahan).
"Passing over" spiritualitas Bung Karno
Latar belakang warisan keluarga Soekarno seperti yang diuraikan di
atas, sudah barang tentu membentuk dan menentukan sosialisasi
pemikiran keagamaan selanjutnya. "Spiritualitas semesta" (holistic
spirituality) Bung Karno itu-untuk tidak menyebutnya sinkretisme
(percampuran) agama-agama, suatu istilah yang sama sekali tidak
tepat dalam menggambarkan kecenderungan dasar pemikiran Jawa
yang sebenarnya-khususnya tampak dari bahasa teologisnya yang
"melintas batas" (passing over) berbagai agama dan tradisi spiritual.
Hal itu tampak dari pidato-pidato tanpa teks, ketika ia
mengemukakan perbandingan-perbandingan dari berbagai agama,
tamsil-tamsil dari ajaran Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Ayat-
ayat suci itu dikutipnya bahkan di luar komunitas agama yang
menganutnya. Misalnya, tanpa ragu-ragu ia mengutip Injil atau
Bhagawad Gita di forum Islam.
Warisan keberagaman itu bukan diterimanya sebagai kontradiksi
atau pertentangan, sebaliknya sebagai suatu kekayaan rohani
berdasarkan kesadarannya akan kesatuan transendental agama-
agama. Dalam menggembleng rakyatnya, Bung Karno, misalnya
sering mengutip Al Quran. ar Ra'd 11: Innallaha laa yughayiru maa bi
qaumin hatta yughayiru ma bi anfusihim (Allah tidak mengubah nasib
sesuatu kaum sehingga kaum itu mengubah sendiri nasibnya).
Tetapi kita juga mendengar dari Bung Karno kutipan dari Bhagawad
Gita (II,47) ketika menekankan prinsip yang sama: Karmany
ewadhikaras te maphalesu kadacana (Berjuanglah dengan tanpa
menghitung-hitung untung rugi bagimu).
Bahkan Bung Karno pernah membuat terperanjat Mr Siegenbeek
van Heukelom yang mengadilinya di Landraad Bandung tahun 1930.
"Ik ben een revolutionaire" (Saya seorang revolusioner), tegas Bung
Karno. Tetapi kata dia selanjutnya: "Ik werk niet met bommen en
granaten" (Saya bekerja tanpa bom dan granat). Hakim kolonial itu
sangat kaget, karena Bung Karno menyebut bahwa Yesus adalah
seorang yang revolusioner, meskipun Ia bekerja tanpa kekerasan.
"Revolusi", kata Bung Karno, adalah "eine Umgestaltung von
Grundaus" (perubahan sampai ke akar-akarnya), baik dalam hal
politik maupun dalam ajaran keagamaan. Dalam suatu pidatonya,
Bung Karno di luar kepala dapat menghapal Injil Yohanes Pasal 1
dalam bahasa Belanda.
Sebagai seorang Muslim, Bung Karno meyakini petunjuk-petunjuk
wahyu dalam
Al Quran dan Hadits, tetapi ayat-ayat suci berbagai agama tersebut
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (7 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
juga turut memperkaya spiritualitasnya. Hal itu dapat dimengerti,
sebagaimana ditulis Cindy Adams, karena kesadaran Bung Karno
bahwa kebenaran itu tunggal dan satu-satunya suara kemanusiaan
adalah Kata dari Tuhan (Sukarno An Autobioghraphy, 1965).
Menariknya, seperti diungkapkannya sendiri, spiritualitasnya yang
begitu luas dan "melintas batas" agama-agama itu, lahir dari "mi'raj-
nya dunia pemikiran", sebagaimana pendakian seorang salik juga
disebut "uruj mir'raj". Hua al-khuruj 'an kulli syai'in siwallah (Keluar
dari segala sesuatu yang bukan Allah). Bung Karno memakai
ungkapan sejajar, "Saya naik ke langit, mi'raj dalam dunianya
pemikiran. Bung Karno, in the world of the mind, bertemu dengan
tokoh-tokoh dunia, seperti Thomas Jefferson, Garibaldi, Mustafa
Kemal Atarturk, Mustafa Kamil, Karl Marx, Engel, Stalin, Trosky,
Dayananda Saraswati, Krisna Ghokale dan Aurobindo Gosye. Kalau
ada hadits Nabi berbunyi Utlubul ilma' wa lau bissin (Tuntutlah ilmu
sampai ke negeri Cina), Bung Karno juga in the world of the mind
pergi ke Tiongkok "minum teh bersama Sun Yat Sen", atau
mengalami saat-saat "duduk bersila dengan Gandhi".
Meskipun Bung Karno menimba, menimba dan menimba dari tokoh-
tokoh "negeri seberang" itu, namun akhirnya Bung Karno kembali ke
realiteit-nya Indonesia, tatkala pada saatnya ia harus menentukan
masa depan dan kelangsungan bangsa menghadapi kenyataan
pluralisme yang menjadi warisan sejarah beratus-ratus tahun,
termasuk di dalamnya pluralisme agama.
Ketika Ernest Renan mengucapkan pidatonya yang terkenal di
Sorbone tahun 1882, "Qu'est ce qu'une Nation" (Apakah suatu
bangsa itu?), salah satu aspek yang ditekankannya adalah bahwa
nasionalisme modern tidak dapat lagi didasarkan atas kesamaan
agama. Pada zaman itu, agama masih menjadi unsur perekat
negara Belgia yang berdiri tahun 1830. Dari pidato Renan ini,
bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia, telah menggali
konsepnya tentang hakikat suatu bangsa. Meskipun Bung Karno
menimba konsep nasionalisme dari Renan, namun nasionalisme
Indonesia mendapat pijakan historis yang lebih kokoh. Bukan hanya
baru abad ke-19, tetapi sejak zaman Majapahit, Mpu Tantular, tidak
hanya telah diletakkan landasan politis bagaimana mengatasi
pluralisme agama, melainkan malah sudah dikembangkan landasan
teologis yang lebih memadai.
Bung Karno juga "berdialog spiritual" dengan Mpu Tantular, lalu
dikembangkanlah kesadaran yang kini oleh teolog agama-agama
acap disebut sebagai philosophia perennis yang meyakini bahwa
kebenaran abadi berada di pusat semua tradisi spiritual, apakah itu
sanatha dharma dalam Hinduisme, al-hikmah al-khalidah dalam
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (8 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
istilah sufi Islam, atau logos spermatikos (benih sabda Ilahi) dalam
pemikiran patristik Kristen. Sesungguhnya kebenaran itu satu dan
tidak terbagi, meskipun mewujud dalam simbol-simbol yang secara
eksoteris berbeda-beda. Prinsip kasunyatan Tantular ini, oleh Bung
Karno diterjemahkan secara politis dalam sila "Ketuhanan Yang
Maha Esa" dalam Pancasila, berbareng dengan dibabtisnya seloka
Bhinneka Tunggal Ika dalam lambang negara. Dengan sila pertama
itu, Bung Karno telah membebaskan bangsanya dari "keharusan
menantikan pesawat penyelamat dari Moskwa atau seorang kalifah
dari Istanbul". Maksudnya, Indonesia tidak menjadi negara Islam,
karena bertentangan dengan realitas kemajemukan bangsa, tetapi
juga bukan negara sekuler, karena melawan degup hati sanubari
rakyat yang sangat religius.
Relung-relung religiusitas Bung Karno
Bukan rahasia lagi, Bung Karno dijatuhkan oleh sebuah creeping
coup d'etat (kudeta merangkak) yang dirancang sangat sistematis.
Pada hari-hari terakhirnya, Bung Karno harus menjalani via dolorosa
(jalan sengsara) di sebuah "karantina politik". Sendiri dan sepi. Bung
Karno tetap menjadi Bapak yang mencintai semua rakyatnya,
meskipun orang-orang di sekelilingnya telah mengkhianatinya. Saat
itu, di tengah-tengah badai fitnah dan ancaman pecahnya perang
saudara, ibu pertiwi laksana harimau lapar hendak memangsa
anaknya sendiri. Dan seperti Sutasoma, Bung Karno justru
menyerahkan dirinya sendiri, rela tenggelam demi keutuhan bangsa
dan negaranya. "Cak Ruslan, saya tahu saya akan tenggelam.
Tetapi ikhlaskan Cak, biar saya tenggelam asalkan bangsa ini
selamat, tidak terpecah belah", tegasnya kepada Ruslan Abdulgani.
Bung Karno sadar, pilihan moral itu ibarat salib yang harus
dipikulnya menuju "puncak Kalvari politik yang kejam". Masih
menurut Cak Ruslan, Bung Karno terakhir kali menerima delegasi
mahasiswa dari GMKI dan PMKRI pada tahun 1967. Pada waktu itu
Bung Karno mengutip sabda Yesus: "Lihat, Aku mengutus kamu
seperti domba di tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu
cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati". Juga, "Mereka akan
menyesah kamu, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa
dan raja-raja" (Injil Matius 10:16-18). Maka Bung Karno menempuh
jalan ahimsa (tanpa kekerasan), ketika drama pengalihan kekuasaan
itu bahkan hanya berlangsung 2-3 babak saja. Semua berjalan
begitu cepat dan rapi. Sang Penyambung Lidah Rakyat pun akhirnya
tenggelam, meskipun Orde Baru yang "menjambret" kekuasaannya
tidak pernah mampu menguburkan pengaruhnya yang besar.
Demikian jiwa kenegarawanan Bung Karno. Sejarah juga mencatat,
dengan spiritualitasnya yang lapang, terbuka, inklusif dan toleran itu,
Bung Karno telah berhasil mempersatukan bangsa yang majemuk ini
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20T...anPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (9 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
menjadi satu.
Kini di tengah-tengah fenomena politisasi agama pada tahun-tahun
terakhir, kita diingatkan dengan semboyan kaum sufi yang kiranya
dapat kita terapkan untuk Bung Karno: "ash Shufi laa madzaba lahu
ila madzab al-haqq"-seorang sufi tidak mempunyai religi kecuali religi
Kebenaran.
* Bambang Noorsena Penulis buku Religi dan Religiusitas Bung
Karno, pendiri Institute for Syriac Christian Studies (ISCS).
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
● Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bhinneka%20...nPassing%20Over%20Spiritualitas%20Bung%20Karn.htm (10 of 11)4/3/2005 11:04:49 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
Bagus Takwin
"AKU ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena
rakyat, aku berjuang karena rakyat dan aku penyambung lidah
rakyat." Pengakuan ini meluncur dari Soekarno, Presiden RI
pertama, dalam karyanya Menggali Api Pancasila. Sadar atau tidak
sadar ia mengucapkannya, terkesan ada kejujuran di sana.
Soekarno, sang orator ulung dan penulis piawai, memang selalu
membutuhkan dukungan orang lain. Ia tak tahan kesepian dan tak
suka tempat tertutup. Dari pidato dan tulisannya yang
memperlihatkan betapa mahirnya ia menggunakan bahasa, tersirat
sebuah kebutuhan untuk selalu mendapat dukungan dari orang lain.
Gejala berbahasa Soekarno, Bung Karno, merupakan fenomena
langka yang mengundang kagum banyak orang. Wajar kalau muncul
pertanyaan "Apakah kemahiran Soekarno menggunakan bahasa
dengan segala ma-cam gayanya berhubungan dengan
kepribadiannya?" Analisis terhadap kepribadian Soekarno melalui
autobiografi, karangan-karangannya, dan buku-buku sejarah yang
memuat sepak terjangnya dapat membantu memberikan jawaban.
Dengan menggunakan pendekatan teori psi-kologi individual dari
Alfred Adler (Hall dan Lindzey, 1985) dapat dipahami bagaimana
Proklamator Kemerdekaan RI ini bisa menjadi pribadi yang berapi-
api, pembakar semangat banyak orang, gagah dan teguh sekaligus
sensitif, takut pada kesendirian, dan sangat membutuhkan dukungan
sosial.
Pribadi yang kesepian
Di akhir masa kekuasaannya, Soekarno sering merasa kesepian.
Dalam autobiografinya yang disusun oleh Cindy Adams, Bung
Karno, Penyambung Lidah Rakyat, ia menceritakannya.
"Aku tak tidur selama enam tahun. Aku tak dapat tidur barang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
sekejap. Kadang-kadang, di larut malam, aku menelepon seseorang
yang dekat denganku seperti misalnya Subandrio, Wakil Perdana
Menteri Satu dan kataku, 'Bandrio datanglah ke tempat saya, temani
saya, ceritakan padaku sesuatu yang ganjil, ceritakanlah suatu
lelucon, berceritalah tentang apa saja asal jangan mengenai politik.
Dan kalau saya tertidur, maafkanlah.'... Untuk pertama kali dalam
hidupku aku mulai makan obat tidur. Aku lelah. Terlalu lelah."
(Adams, 2000:3)
"Ditinjau secara keseluruhan maka jabatan presiden tak ubahnya
seperti suatu pengasingan yang terpencil... Seringkali pikiran
oranglah yang berubah-ubah, bukan pikiranmu... Mereka turut
menciptakan pulau kesepian ini di sekelilingmu."
(Adams, 2000:14)
Apa yang ditampilkan Soekarno dapat dilihat sebagai sindrom orang
terkenal. Ia diklaim milik rakyat Indonesia. Walhasil, ia tak bisa lagi
bebas bepergian sendiri menikmati kesenangannya (Adams,
2000:12). Namun, melihat ke masa mudanya, kita juga menemukan
tanda-tanda kesepian di sana. Semasa sekolah di Hogere Burger
School (HBS), ia menekan kesendiriannya dengan berkubang dalam
buku-buku, sebuah kompensasi dari kemiskinan yang dialaminya.
Kebiasaan ini berlanjut hingga masa ia kuliah di Bandung. Soekarno
terkenal sebagai pemuda yang pendiam dan suka menarik diri
(Adams, 2000:89-91).
Indikasi kesepian juga kita dapatkan dalam ceritanya tentang
penjara. Malam-malam di penjara menyiksanya dengan ruang yang
sempit dan tertutup. Dinding-dinding kamar tahanannya terlalu
menjepit dirinya. Lalu muncullah perasaan badannya yang
membesar hingga makin terjepit dalam ruang tahanan itu.
"Yang paling menekan perasaan dalam seluruh penderitaan itu
adalah pengurungan. Seringkali jauh tengah malam aku merasa
seperti dilak rapat dalam kotak kecil berdinding batu yang begitu
sempit, sehingga kalau aku merentangkan tangan, aku dapat
menyentuh kedua belah dindingnya. Rasanya aku tak bisa bernafas.
Kupikir lebih baik aku mati. Suatu perasaan mencekam diriku, jauh
sama sekali dari keadaan normal." (Adams, 2000:135)
Lebih jauh lagi ke masa kecilnya, Soekarno sering merasa sedih
karena hidup dalam kemelaratan sehingga tak dapat menikmati
benda-benda yang diidamkannya. Di saat anak-anak lain dapat
menikmati makanan jajanan dan mainan, Karno hanya dapat
menyaksikan mereka dengan perasaan sedih. Lalu ia menangis
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
mengungkapkan ketidakpuasan sekaligus ketakberdayaannya.
Selain itu, di lingkungan sekolah ia harus berhadapan dengan anak-
anak Belanda yang sudah terbiasa memandang remeh pribumi.
Pengalaman yang cukup traumatis terjadi di masa lima tahun
pertama. Soekarno pernah berturut-turut menderita penyakit seperti
tifus, disentri, dan malaria yang berujung pada penggantian
namanya dari Kusno menjadi Karno, nama seorang tokoh
pewayangan putra Kunti yang berpihak pada Kurawa demi balas
budi dan kewajiban membela negara yang menghidupinya. Sakit
yang melemah-kan secara fisik dapat berpengaruh terhadap kondisi
psikis. Sangat mungkin muncul perasaan lemah, tak berdaya, dan
terasing pada diri Soekarno kecil. Untungnya dilakukan penggantian
nama disertai penjelasan dari ayahnya tentang makna pergantian
nama yang memberinya kebanggaan karena menyandang nama
pejuang besar.
Pengalaman sakit-sakitan dan hidup dalam kemiskinan tampak
membekas kuat dalam ingatan Soekarno. Di masa tuanya, ia
menafsirkan kegemarannya bersenang-senang sebagai kompensasi
dari masa lalunya yang dirampas kemiskinan (Adams, 2000). Ada
semacam dendam terhadap kemiskinan dan ketidakberdayaan yang
telah berkilat dalam dirinya. Dendam yang kemudian
menggerakkannya pada semangat perjuangan kemerdekaan dan
keinginan belajar yang tinggi.
Mitos-mitos dari masa kecil
Sejak kecil, Soekarno sudah menyimpan mitos tentang diri-nya
sebagai pejuang besar dan pembaru bagi bangsanya. Ibunya, Ida
Nyoman Rai, menceritakan makna kelahiran di waktu fajar.
"Kelak engkau akan menjadi orang yang mulia, engkau akan menjadi
pemimpin dari rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam setengah
enam pagi di saat fajar mulai menyingsing. Kita orang Jawa
mempunyai suatu kepercayaan, bahwa orang yang dilahirkan di saat
matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dulu. Jangan
lupakan itu, jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini
putra dari sang fajar." (Adams, 2000:24)
Tanggal kelahiran Soekarno pun dipandangnya sebagai pertanda
nasib baik.
"Hari lahirku ditandai oleh angka serba enam. Tanggal enam bulan
enam. Adalah menjadi nasibku yang paling baik untuk dilahirkan
dengan bintang Gemini, lambang kekembaran. Dan memang itulah
aku sesungguhnya. Dua sifat yang berlawanan." (Adams, 2000:25)
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno melihat dirinya yang terdiri dari dua sifat yang berlawanan
sebagai satu kemungkinan pertanda nasibnya di dunia politik.
"Karena aku terdiri dari dua belahan, aku dapat memperlihatkan
segala rupa, aku dapat mengerti segala pihak, aku memimpin semua
orang. Boleh jadi ini secara kebetulan bersamaan. Boleh jadi juga
pertanda lain. Akan tetapi kedua belahan dari watakku itu
menjadikanku seseorang yang merangkul semua-nya."
Kejadian lain yang dianggap pertanda nasib oleh Soekarno adalah
meletusnya Gunung Ke-lud saat ia lahir. Tentang ini ia menyatakan,
"Orang yang percaya kepada takhayul meramalkan, 'Ini adalah
penyambutan terhadap bayi Soekarno," Selain itu, penjelasan
tentang penggantian nama Kusno menjadi Karno pun memberi satu
mitos lagi dalam diri Soekarno kecil tentang dirinya sebagai calon
pejuang dan pahlawan bangsanya.
Kepercayaan akan pertanda-pertanda yang muncul di hari kelahiran
Soekarno memberi semacam gambaran masa depan dalam benak
Soekarno sejak masa kecilnya. Dalam kerangka pemikiran Adler,
gambaran masa depan itu disebut fictional final goals (tujuan akhir
fiktif). Meskipun fiktif (tak didasari kenyataan), tetapi gambaran masa
depan ini berperan menggerakkan kepribadian manusia untuk
mencapai kondisi yang tertuang di dalamnya (Adler, 1930:400).
Riwayat hidup Soekarno memperlihatkan bagaimana gambaran
dirinya di masa depan dan persepsinya tentang Indonesia
menggerakkannya mencapai kemerdekaan Indonesia.
Bombasme bahasa dan keinginan merengkuh massa
Setelah menjadi presiden, Soekarno berpidato tiap tanggal 17
Agustus. Di sana dapat kita temukan kalimat-kalimat muluk,
penggunaan perumpamaan elemen-elemen alam yang megah dan
hiperbolisme bahasa. Dari tahun ke tahun pidatonya makin gegap-
gempita, mencoba membakar semangat massa pendengarnya
dengan retorika kata-kata muluk.
Dari kalimat-kalimat itu dapat dibayangkan seperti apakah kondisi
psikis orang yang menggunakannya. Dalam pidatonya tanggal 17
Agustus 1949, contohnya, ia berseru, "Kita belum hidup dalam sinar
bulan purnama, kita masih hidup di masa pancaroba, tetaplah
bersemangat elang rajawali." Di sini ada indikasi ia menempatkan
diri sebagai orang yang bersemangat elang rajawali sehingga
memiliki hak dan kewajiban untuk menyerukan pada rakyatnya agar
memiliki semangat yang sama dengannya.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
Seruan-seruan yang sering dilontarkan dalam pidatonya adalah
tentang perjuangan yang harus dilakukan tak henti-henti.
"Kemerdekaan tidak menyudahi soal-soal, kemerdekaan malah
membangun soal-soal, tetapi kemerdekaan juga memberi jalan untuk
memecahkan soal-soal itu."
(Pidato 17 Agustus 1948)
"Tidak seorang yang menghitung-hitung: Berapa untung yang
kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban
untuk mempertahankannya."
(Pidato 17 Agustus 1956)
"Karena itu segenap jiwa ragaku berseru kepada bangsaku
Indonesia: "Terlepas dari perbedaan apa pun, jagalah Persatuan,
jagalah Kesatuan, jagalah Keutuhan! Kita sekalian adalah machluk
Allah! Dalam menginjak waktu yang akan datang, kita ini se-olah-
olah adalah buta."
(Pidato 17 Agustus 1966)
Selain ajakan untuk berjuang, tersirat juga dari petikan-petikan
tersebut bahwa Soekarno memandang dirinya sebagai orang yang
terus-menerus berjuang mengisi kemerdekaan. Pengaruh fictional
final goals-nya terlihat jelas, Soekarno yang sejak kecil
membayangkan diri menjadi pemimpin bangsanya dengan
kepercayaan tinggi menempatkan dirinya sebagai guru bagi rakyat.
"Adakanlah ko-ordinasi, ada-kanlah simponi yang seharmonis-
harmonisnya antara kepentingan sendiri dan kepentingan umum,
dan janganlah kepentingan sendiri itu dimenangkan diatas
kepentingan umum."
(Pidato 17 Agustus 1951)
"Kembali kepada jiwa Proklamasi .... kembali kepada sari-intinya
yang sejati, yaitu pertama jiwa Merdeka Nasional... kedua jiwa
ichlas... ketiga jiwa persatuan... keempat jiwa pembangunan."
(Pidato 17 Agustus 1952)
"Dalam pidatoku "Berilah isi kepada kehidupanmu" kutegaskan:
"Sekali kita berani bertindak revolusioner, tetap kita harus berani
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
bertindak revolusioner.... jangan ragu-ragu, jangan mandek setengah
jalan..." kita adalah "fighting nation" yang tidak mengenal "journey's-
end"
(Pidato 17 Agustus 1956)
Keinginannya untuk merengkuh massa sebanyak-banyaknya tampak
dari kesenangannya tampil di depan massa. Bombasme-
kecenderungan yang kuat untuk menggunakan kalimat-kalimat
muluk dan ide-ide besar yang tidak disertai oleh tindakan konkret-
praktis untuk mencapainya yang ditampilkannya dapat diartikan
sebagai usaha memikat hati rakyat. Pidato-pidatonya banyak
mengandung gaya hiperbola dan metafora yang berlebihan seperti
"Laksana Malaikat yang menyerbu dari langit", "adakanlah simfoni
yang seharmonis-harmonisnya antara kepentingan sendiri dan
kepentingan umum", "Bangsa yang gila kemuktian, satu bangsa
yang berkarat", dan "memindahkan Gunung Semeru atau Gunung
Kinibalu sekalipun." Simak kutipan-kutipan berikut bagaimana gaya
bahasa yang digunakan untuk memikat massa.
"Janganlah melihat ke masa depan dengan Mata Buta! Masa yang
lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca mata
benggalanya dari pada masa yang akan datang."
(Pidato 17 Agustus 1966)
"Atau hendakkah kamu menjadi bangsa yang ngglenggem"? Bangsa
yang 'zelfgenoegzaam'? Bangsa yang angler memeteti burung
perkutut dan minum teh nastelgi? Bangsa yang demikian itu pasti
hancur lebur terhimpit dalam desak mendesaknya bangsa-bangsa
lain yang berebut rebutan hidup!"
(Pidato 17 Agustus 1960)
Kita mau menjadi satu Bangsa yang bebas Merdeka, berdaulat
penuh, bermasyarakat adil makmur, satu Bangsa Besar yang
Hanyakrawati, gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kertaraharja, otot
kawat balung wesi, ora tedas tapak palune pande, ora tedas gurindo.
(Pidato 17 Agustus 1963)
Gaya menggurui dari tahun ke tahun makin jelas terlihat dalam
pidato Soekarno. Ia makin sering membuka pidatonya dengan
kalimat "Saya akan memberi kursus tentang". Pengaruh gambaran
masa kecilnya tentang Soekarno sebagai pembuka fajar baru bagi
bangsanya makin tegas. Ia tak menyadari bahwa gambaran itu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
bersifat fiktif, tak didasari kenyataan. Soekarno melambung tinggi
dengan ide-idenya dan cenderung mengabaikan kondisi konkret
bangsanya terutama kondisi ekonomi.
Strategi penyebaran ideologi dalam tulisan Soekarno
Lalu jadilah Soekarno sebagai ideolog yang piawai menyebarkan
kepercayaan-kepercayaannya. Strategi penyebaran ideologi yang
oleh Terry Eagleton (1991) terdiri dari rasionalisasi, universalisasi,
dan naturalisasi, dengan baik dimanfaatkan Soekarno dalam tulisan-
tulisannya.
Rasionalisasi tampil dalam argumentasi-argumentasi yang
diusahakan tersusun selogis mungkin dan menggunakan rujukan-
rujukan teori-teori ilmuwan terkemuka seperti Herbert Spencer,
Havelock Ellis, dan Ernst Renan. Rasionalisasi dapat ditemukan
dalam setiap karangannya, termasuk penggunaan data statistik demi
memperkuat pendapatnya.
Strategi universalisasi dalam tulisan dan karangan Soekarno
melibatkan ajaran-ajaran agama kutipan dari tokoh ternama dalam
sejarah dan peristiwa penting dalam peradaban manusia. Gagasan-
gagasannya seolah berlaku universal dan diperlukan di mana-
mana."Firman Tuhan inilah gitaku, Firman Tuhan inilah harus
menjadi pula gitamu: "Innallaha la yu ghoiyiru ma bikaumin, hatta yu
ghoiyiru ma biamfusihim"
(Pidato 17 Agustus 1964)
"Asal kita setia kepada hukum sejarah dan asal kita bersatu dan
memiliki tekad baja, kita bisa memindahkan Gunung Semeru atau
Gunung Kinibalu sekalipun."
(Pidato 17 Agustus 1965)
"Tetapi Tanah Air kita Indonesia hanya satu bahagian kecil saja dari
pada dunia! Ingatlah akan hal ini! Gandhi berkata: "Saya seorang
nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan."
(Pidato Lahirnya Pancasila,
1 Juni 1945)
Strategi naturalisasi merupakan usaha menampilkan sebuah ideologi
atau kepercayaan sebagai sesuatu yang tampak alamiah. Ini banyak
ditemukan dalam pidato-pidato Soekarno. Penjelasan-penjelasannya
tentang Pancasila sangat jelas menggunakan naturalisasi.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
"Ke Tuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Peri Kemanusiaan,
Kedaulatan Rakyat, Keadilan Sosial. Dari zaman dahulu sampai
zaman sekarang ini, yang nyata selalu menjadi isi daripada jiwa
bangsa Indonesia."
(Pancasila sebagai Dasar Negara, hal:38)
Bukan hal yang aneh jika Soekarno berkembang menjadi seorang
ideolog. Kepercayaan sejak kecil tentang kemuliaan, kepeloporan
dan kepemimpinannya, mendorong kuat Bung Besar ini
menyebarkan kebenarannya. Gambaran diri yang fiktif dan mistis ini
pula yang memberinya kepercayaan diri tampil berapi-api di depan
lautan massa.
Dari mitos ke ideologi, dari kesepian ke kekuasaan
Merujuk Adler, benang merah perkembangan kepribadian Soekarno
jadi begitu jelas. Masa dewasanya merupakan proyeksi dari
keinginan masa kecil. Soekarno membayangkan dirinya sebagai
pembaru bangsa sejak kecil. Ia tumbuh sebagai manusia yang
penuh dengan gagasan-gagasan yang terbilang baru di masa
hidupnya. Kegemaran akan buku dan belajar berbagai hal tak lepas
dari cita-cita yang digenggamnya erat-erat: menjadi penyelamat
bangsa. Disiplin belajar yang dibiasakan ayahnya berpengaruh besar
terhadap hal ini. Hingga di usia melampaui 60 tahun, ia masih gemar
membaca. Kamar tidurnya penuh dengan buku sekaligus kutunya
(Adams, 2000). Daya serapnya pun luar biasa.
Perpaduan berbagai aspek kepribadian dengan kualitas luar biasa
inilah yang memungkinkannya tampil sebagai orator dengan
wawasan begitu luas. Kondisi sosial dan budaya masyarakat
Indonesia juga berperan penting bagi perkembangan Soekarno.
Mitos akan datangnya Ratu Adil, kepercayaan terhadap titisan dewa
dan kepemimpinan politik yang tak lepas dari aspek spiritualitas
memompa Soekarno berkembang menjadi tokoh yang dikultuskan.
Namun, sehebat-hebatnya ia mempengaruhi massa, seluas-luasnya
wawasan di benaknya dan sebesar-besarnya kekuasaan yang
dimilikinya, Bung Karno tak bisa lepas dari kebutuhannya untuk
selalu memperoleh dukungan sosial. Kesepian menjadi derita yang
menyakitkan hingga akhir hayatnya. Apa yang dilakukannya untuk
memperoleh dukungan massa di sisi lain menjadikannya sebagai
orang yang terasing, terpencil dari rakyat.
Dari kacamata Alfred Adler (1930), penyakit yang diderita Soekarno
kecil bisa jadi membekas pada kepribadiannya di masa-masa
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
berikutnya. Kesakitan yang diderita Soekarno itu bisa menimbulkan
perasaan lemah, tak berdaya, dan tersiksa yang disebut Adler
sebagai pe-rasaan inferioriti. Jika perasaan ini tidak ditangani secara
tuntas maka akan timbul kecemasan yang mendukung munculnya
perasaan inferioriti baru di ta-hap berikutnya hingga terakumulasi
menjadi kompleks inferioriti-sebuah kondisi kejiwaan yang ditandai
dengan perasaan rendah diri berlebihan dan kecemasan yang tinggi
terhadap lingkungan sosial.
Untungnya lingkungan keluarganya memberi perhatian dan
semangat yang memadai, terutama ibu, sehingga ia dapat
menemukan perasaan aman dan nyaman di sana. Ia lalu sering
tampil sebagai pemimpin yang dominan. Namun, ini pun
memunculkan suatu ketergantungan akan afeksi. Hingga dewasa
kebutuhan afeksi itu tak jua tercukupi. Ia mengaku selalu
membutuhkan wanita sebagai pegangan.
Penggantian nama Kusno menjadi Karno dan penjelasan maknanya
juga menjadi cara yang baik untuk menangani perasaan inferioriti
yang dialami Soekarno kecil. Ia dapat menyusun sebuah
pemahaman di benaknya bahwa apa yang dialami merupakan
sesuatu yang wajar sebagai seorang calon pahlawan besar sekelas
Karna putra Kunti. Demikian pula dengan mitos-mitos tentang
dirinya. Namun, ini pun mengakibatkan dirinya cenderung terpaku
pada hal-hal besar dan mengabaikan hal-hal kecil.
Dalam kondisi-kondisi penuh dukungan lingkungan sosial, Soekarno
bisa memperoleh perasaan superioritas, perasaan aman dan
nyaman menghadapi dunia. Untuk itu, ia selalu berusaha menarik
perhatian banyak orang agar selalu berada di sekelilingnya, berpihak
padanya. Pidatonya yang penuh kalimat bombastis merupakan cara
memikat hati orang lain seperti seorang perayu yang tak ingin
kehilangan kekasihnya. Namun, di saat-saat kesepian ia bisa
mengalami perasaan frustrasi dan depresi. Ia sangat tidak menyukai
kesendirian. Tragisnya, hukuman ini yang ia terima di akhir hidup,
menjadi seorang tahanan rumah dan meninggal dalam kesepian.
Penutup
Liku-liku kepribadian Soekarno menunjukkan ada beberapa
kelemahan pada dirinya. Lepas dari kekurangan-kekurangannya, ia
adalah orang besar. Kekurangan yang dimiliki adalah kekurangan
yang sangat wajar dimiliki oleh manusia. Namun, kelebihannya dan
cara mengatasi kekurangannya merupakan hal yang luar biasa. Ia
mampu melampaui banyak orang dengan kelebihannya.
Analisis ini sekadar menunjukkan bahwa sebagai manusia biasa,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Besar, Ideolog yang Kesepian -- Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno memiliki kelemahan, tetapi bukan untuk mengecilkan arti
sebagai manusia dengan segudang prestasi. Soekarno tetap layak
menjadi orang yang dipuji, dihormati, dan dikenang selalu baik
sebagai orang yang berjasa mendirikan Republik Indonesia maupun
sebagai pribadi yang selalu terus berusaha mencapai kebaikan bagi
dirinya dan orang lain.
* Bagus Takwin Pengajar psikologi di Fakultas Psikologi Universitas
Indonesia.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
● Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
● Bung Karno, Seni, dan Saya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Bes...g%20Kesepian%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (10 of 11)4/3/2005 11:04:51 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
Aiko Kurasawa
MENGAPA Soekarno, Bung Karno, memutuskan bekerja sama
dengan Jepang pada waktu Indonesia diduduki oleh tentara Jepang?
Riwayatnya bagaimana?
Pada waktu tentara Jepang masuk Indonesia, pada awal tahun
1942, Bung Karno ada di Sumatera. Dia dibuang oleh Belanda,
pertama ke Ende, Flores, lalu ke Bengkulu. Dia sudah 13 tahun
dibuang ke luar Jawa dengan istrinya, Ny Inggit Garnasih.
Riwayat Bung Karno bertemu dengan utusan tentara Jepang dan
dibawa kembali ke Jawa yang ditulis dalam otobiografinya,
mengisahkan, waktu ada kabar tentara Jepang akan segera
mendarat di Sumatera, petugas Belanda datang ke rumah Bung
Karno di Bengkulu. Mereka memutuskan membawa Bung Karno ke
Padang, dan dari sana membawanya ke Australia bersama dengan
petinggi Belanda.
Belanda mungkin takut Bung Karno akan dimanfaatkan oleh Jepang.
Agar tidak diketahui Jepang yang sudah mendekati pantai barat
Sumatera, Bung Karno dan istrinya, disuruh jalan kaki di dalam
hutan menuju ke Padang. Beberapa hari kemudian mereka keluar
dari hutan, naik bus ke Padang. Waktu itu situasi Kota Padang
sangat kacau, dan kebanyakan orang Belanda sudah lari. Ternyata
sudah tidak ada kapal lagi yang bisa membawa Bung Karno ke
Australia, artinya Bung Karno ditinggalkan Belanda. Dan, menurut
Bung Karno, itulah kesalahan besar Belanda. Dia memutuskan
tinggal di Padang, menumpang di rumah teman. Seminggu
kemudian, tentara Jepang memasuki kota ini.
Suatu hari, seorang perwira tentara Jepang, Kapten Sakaguchi dari
Barisan Propaganda, mendatangi tempat tinggal Bung Karno.
Menanyakan kondisinya. Mereka berkomunikasi dalam bahasa
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
Perancis. Dan Sakaguchi mengundang Bung Karno ke Bukittinggi,
Markas Besar Angkatan Darat Jepang Ke-25. Bung Karno dibawa ke
sana dan dipertemukan dengan Kolonel Fujiyama.
Beberapa minggu lewat, tanpa kemajuan apa-apa. Lantas ada
perintah dari Jawa agar Bung Karno dipulangkan ke Jakarta. Tentu
saja Bung Karno senang sekali, dan pada bulan Juli 1942-empat
bulan sesudah penjajahan militer Jepang dimulai-Bung Karno dan
istrinya kembali ke Jakarta dengan naik kapal dari Palembang.
Dalam memoar Jenderal Imamura, Panglima Besar Pertama
Angkatan Darat Jepang Ke-16 yang menduduki Pulau Jawa, ada
cerita tentang pemulangan Bung Karno itu. Pada suatu hari,
pemerintahan militer Jepang menerima permintaan dari pemuda-
pemuda Indonesia agar Jepang membebaskan Bung Karno yang
sedang dibuang di Bengkulu. Barisan Propaganda (Sendenbu)
Jepang di Jawa yang waktu itu dipimpin Letkol Keiji Machida,
mempertimbangkan dampaknya. Ia menyimpulkan, Bung Karno
sangat berguna. Ia pun memerintahkan agar mencari Bung Karno di
Sumatera. Mungkin di situlah Kapten Sakaguchi, atas perintah dari
Jakarta, mencari Bung Karno.
Pembesar-pembesar Nanpo Sogun (Markas Besar Tertinggi di
Daerah Selatan) yang ada di Singapura waktu itu, ragu-ragu. Mereka
khawatir munculnya dampak negatif pembebasan Bung Karno. Bung
Karno dianggap sebagai seorang nasionalis yang sangat fanatik.
Sebaliknya, Jenderal Imamura tidak peduli, dan menyetujui
keputusannya Sendenbu.
Menurut catatan Jenderal Imamura, tidak lama sesudah Bung Karno
kembali ke Jawa, Bung Karno minta bertemu Imamura. Tentu saja
Jenderal Imamura setuju, dan Bung Karno diterima.
Kepala Barisan Propaganda Letkol Keiji Machida memberi
keterangan sedikit lain. Menurut dia, pertemuan itu diselenggarakan
atas prakarsa Barisan Propaganda. Agar pertemuan itu bisa diterima
oleh Jenderal Imamura, Machida memakai pelukis Basuki Abdullah
sebagai alasan. Basuki Abdullah dikirim untuk melukis Jenderal
Imamura, sedangkan Bung Karno dan Bung Hatta mendampingi.
Letkol Machida pun mengatakan, Bung Karno adalah saudara
Basuki Abdullah.
Dalam memoar Jenderal Imamura, diceritakan juga tentang seorang
pelukis yang bernama Basuki Abdullah yang pernah melukis
Imamura. Menurut ingatannya, pelukis itu adalah saudara Soekarno.
Saya tidak mengerti kenapa Machida harus memakai alasan
demikian. Mungkin saja alasannya sederhana, Machida khawatir
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
pertemuan panglima Jepang dan pemimpin Indonesia itu dan saya
kurang yakin apakah pertemuan itu adalah pertemuan pertama
antara Bung Karno dan Imamura.
Bukti terjadinya pertemuan adalah sebuah foto Jenderal Imamura
dengan Basuki Abdullah, Bung Karno, Bung Hatta, dan Machida
yang memegang lukisan Imamura hasil karya Basuki Abdullah.
Kejadian ini sangat menarik, sebab pelukis yang terkenal itu pernah
melukis Panglima Besar Tentara Jepang.
Tentang Bung Karno, Jenderal Imamura punya kesan sebagai sosok
yang tenang, santun, bicaranya sopan. Juru bahasa yang dipakai
pada waktu itu adalah seorang pemuda Jepang yang lahir di
Kalimantan dan dididik di sekolah Belanda. Meskipun umurnya baru
18 tahun, kemampuan bahasanya sangat baik.
Pada pertemuan pertama itu, Jenderal Imamura menanyakan
apakah Bung Karno siap bekerja sama dengan Jepang. Menurut
Imamura, ia tidak mekso. Dia memberi pilihan antara "bekerja sama"
atau "bersikap netral". Dia hanya mengatakan kalau Bung Karno
menentang Jepang, terpaksa akan dipakai cara-cara kekerasan.
Jenderal Imamura juga tidak menjanjikan kemerdekaan, karena
Pemerintah Jepang masih punya rencana untuk menguasai terus
Indonesia. Imamura hanya berjanji, akan meningkatkan situasi
keamanan dan memperbaiki kedudukan bangsa Indonesia.
Catatan Bung Karno tentang pertemuan dengan Jenderal Imamura
tidak bertentangan dengan tulisan Imamura. Katanya, Imamura tidak
memaksa Bung Karno bekerja sama dengan Jepang. Imamura juga
tidak pernah menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Imamura
mengatakan, semua keputusan tergantung pada kaisar, bahkan dia
pun tidak tahu bagaimana status Indonesia di kemudian hari.
Sesudah pertemuan dengan Imamura, Bung Karno berunding
dengan teman-temannya selama beberapa hari. Akhirnya diputuskan
untuk bekerja sama dengan Jepang. Sesuai dengan otobiografinya,
maksud pertama Bung Karno bukan untuk "membantu" Jepang,
tetapi "memanfaatkan" kesempatan itu untuk memperbaiki nasib
bangsa Indonesia. Memang besar risikonya, tetapi Bung Karno
mungkin merasa yakin bisa mengatasinya. Bung Karno
memperkirakan tentara Jepang tidak akan tinggal lama di Indonesia.
Mereka nanti akan segera kalah. Oleh karena, itu dia pikir sebaiknya
tidak menentang Jepang secara terbuka.
Kerja sama pemimpin Filipina dengan Jepang pun mungkin jadi
pertimbangan Bung Karno. Meskipun situasi Filipina berbeda dengan
Indonesia, tetapi Filipina sudah diberi otonomi oleh Ame-rika sejak
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
tahun 1936, dan sudah dijanjikan diberi kemerdekaan penuh pada
tahun 1946. Harapan itu dihancurkan oleh masuknya tentara
Jepang. Presiden Quezon melarikan diri bersama pasukan Amerika,
sambil memerintahkan kepada anak buahnya agar berpura-pura
kerja sama dengan Jepang demi keselamatan bangsa. Mereka yang
bekerja sama dengan Jepang antara lain adalah Jose P Laurel-ayah
mantan Wakil Presiden Laurel-dan Benigno S Aquino-ayah
almarhum Benigno Aquino Junior-sekaligus mertua mantan Presiden
Cora-zon Aquino. Waktu Amerika kembali dan menguasai Filipina,
para pemimpin Filipina yang bekerja sama dengan Jepang dituntut
sebagai pengkhianat dan diadili. Tetapi, sesudah Filipina mendapat
kemerdekaan penuh pada tahun 1946, proses pengadilan mereka
dihentikan. Dengan kata lain, pemimpin pemerintahan baru mengerti
kenapa mereka terpaksa bekerja sama dengan Jepang.
(2) Bung Karno dalam film Jepang
Bung Karno diberi tugas memimpin organisasi rakyat, seperti Pusat
Tenaga Rakyat (Putera) dan Jawa Hokokai. Ia juga diberi tugas
memberikan ceramah dan pidato untuk membangkitkan rasa benci
terhadap Belanda dan rasa nasionalisme yang sudah lama ditindas
Belanda. Dia sering menjadi "bintang film" dalam propaganda
Jepang. Pada zaman pendudukan Jepang, film adalah media yang
sangat menonjol sebagai sarana komunikasi. Tentara Jepang
mempelajari strategi itu dari Nazi dan membuat banyak film
propaganda dan film berita.
Pada waktu itu, angka buta huruf di kalangan rakyat Indonesia masih
tinggi. Oleh karena itu, film yang sifatnya audio-visual, lebih mudah
dimengerti dan punya dampak lebih besar daripada media cetak.
Kantor cabang sebuah perusahaan film Jepang, Nippon Eigasha,
dibuka di Jakarta. Dan mereka setiap bulan meluncurkan dua film
berita dan dua film "budaya" (istilah terjemahan dari bahasa Jerman,
artinya hampir sama dengan film dokumenter yang dibuat untuk
maksud pendidikan dan propaganda).
Bung Karno sendiri dimasukkan hampir setiap bulan, baik dalam film
berita maupun film budaya. Dalam film-film itu ia menyampaikan
pidato yang cukup panjang. Suara dan wajah Bung Karno
ditayangkan dan tersebar ke seluruh Pulau Jawa dalam film 35 mm.
Filmnya diputar tidak hanya di gedung bioskop di kota, tetapi juga
dibawa ke seluruh pelosok oleh Barisan Propaganda dan diputar di
lapangan. Penduduk diajak nonton secara gratis. Meskipun Bung
Karno sudah sangat terkenal di antara kaum intelektual, tetapi belum
dikenal di kalangan rakyat biasa. Dengan film-film itu mereka mulai
mengenal wajah dan suara Bung Karno.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
Rakyat mulai tertarik pada pidato Bung Karno yang isinya
membangkitkan rasa nasionalisme Indonesia. Padahal, sebenarnya
Jepang meminta Bung Karno menyampaikan pidato yang
menggerakkan rakyat untuk bekerja sama dengan Jepang demi
kepentingan usaha peperangan Asia Timur Raya. Bung Karno
ternyata berhasil agak mengesampingkan "pesan sponsor" itu.
Dalam usaha menggerakkan hati rakyat, dia hati-hati memilih
kosakata yang tidak berbau fasisme, dan menghindari kosakata
yang mementingkan kepentingan Jepang. Di lain pihak, dia juga
pintar. Dia tidak memakai kosakata yang menyinggung perasaan
tentara Jepang. Misalnya, dia selalu memakai istilah kesejahteraan,
kebahagiaan dan kemuliaan bangsa, sebaliknya tak pernah
memakai istilah "kemerdekaan" bangsa sebelum September 1944.
Menarik sekali menganalisis isi pidato Bung Karno. Berikut ini
beberapa contoh pidato Bung Karno yang pernah ditayangkan
melalui film.
Contoh 1:
"Marilah kita bekerja bersama-sama agar supaya lekas tercapai cita-
cita kita bersama, yaitu Asia Raya." (Yaeshio, 1942). Dia sering
memakai istilah "Asia Raya". Konotasi kata ini ambigu. Kalau
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak selalu berarti
fasisme Jepang, tetapi Asia yang raya atau "Asia untuk bangsa
Asia".
Contoh 2:
"Masyarakat baru yang kita sedang susun itu, tak mungkin kekal
kalau kita tidak mencapai kemenangan akhir, karena itu marilah kita
taruhkan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya, tahanlah
menderita, tahanlah kesukaran. Kebesaran kita tidak dapat kita capai
di atas kasur bantalnya kesenangan, kebesaran kita itu hanyalah kita
bisa capai di dalam api unggunnya perjuangan." (Menoedjoe ke Arah
Mengambil Bagian Pemerintahan Dalam Negeri, Oktober, 1943).
Pidato ini, berjudul Upacara Pembukaan Chuo Sangiin, hanya
menyinggung saja perjuangan bangsa Indonesia dan tidak berbau
fasisme dan militerisme Jepang.
Contoh 3:
"Kita harus... mengulangi di dalam hati kita, bulatkan di dalam hati
kita, bahwa peperangan sekarang ini bukanlah hanya peperangan
Dai Nippon saja, tetapi adalah peperangan kita pula, peperangan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
seluruh Benua Asia, baik dari rakyat Indonesia maupun Filipina,
maupun Burma, maupun Thai, maupun Tiongkok, maupun
Manchukuo. Seluruh rakyat di Benua Asia ini adalah ikut berperang.
Pada tanggal 8 Maret yang lalu, di lapangan Ikada ini pula, saya
telah gemblengkan di dalam kamu punya hati semuanya, bahwa
kamu semuanya, kita semuanya adalah ikut berperang. Bung Karno
ikut berperang! Bung Hatta ikut berperang! Kusumo Utoyo ikut
berperang!" (Jawa News, No 15 Oktober 1943).
Apa yang dimaksud dalam pidato ini adalah solidaritas bangsa Asia
menghadapi kekuatan Barat. Bung Karno menginterpretasi perang
Jepang sebagai perang bangsa Asia sendiri, dan menganggap
Amerika dan Inggris sebagai musuhnya sendiri. Agitasi anti-Barat
bisa dilihat dalam pidato berikut yang disampaikan pada bulan April
1943.
Contoh 4:
"Saudara-saudara, musuh kita yang terbesar yang selalu
merusakkan keselamatan dan kesejahteraan Asia dan juga
merusakkan keselamatan dan kesejahteraan Indonesia ialah
Amerika dan Inggris. Oleh karena itu di dalam peperangan Asia
Timur Raya ini, maka segenap kita punya tenaga, segenap kita
punya kemauan, segenap kita punya tekad harus kita tujukan
kepada hancur-leburnya Amerika dan Inggris itu. Selama kekuasaan
dan kekuatan Amerika dan Inggris belum hancur-lebur, maka Asia
dan Indonesia tidak bisa selamat."
Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah, "Hancurkan kekuasaan
Amerika. Hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris
kita linggis!" (ulang tiga kali) (Jawa News, No 2 April 1943).
(3) Pernikahan dengan Fatmawati
Di satu pihak, zaman Jepang adalah zaman berjuang dalam
berbagai kesulitan sebagai seorang nasionalis, tetapi zaman ini juga
merupakan zaman sangat bahagia untuk kehidupan pribadi Bung
Karno. Dia akhirnya memutuskan hubungan perkawinan dengan
Inggit Garnasih dan menikah lagi dengan Fatmawati.
Bung Karno jatuh cinta pada Fatmawati, salah seorang murid Bung
Karno sewaktu mengajar di sekolah Muhammadiyah di Bengkulu.
Inggit adalah istri yang membantu dan memberi dukungan pada
Bung Karno selama 20 tahun dalam masa susah dan penuh
penderitaan. Ny Inggit adalah pembuka jalan bagi Bung Karno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
menjadi pahlawan dan pemimpin bangsa. Tanpa bantuannya, Bung
Karno tidak bisa mendapatkan kedudukan itu. Sedangkan
perpisahan itu diawali dengan perselisihan dengan Ny Inggit yang
sudah dinikahi selama 20 tahun, tidak juga melahirkan anak.
Padahal, Bung Karno ingin punya anak.
Akan tetapi, karena Ibu Inggit tidak setuju Bung Karno punya istri
kedua, padahal Bung Karno ingin punya anak, akhirnya ia
menceraikan Ny Inggit dan menikahi Ny Fatmawati pada Juni 1943,
kurang lebih setahun setelah Bung Karno kembali ke Jawa.
Pada waktu itu, secara kebetulan Bung Karno sedang menghadapi
berbagai persoalan di bidang politik. Gerakan Putera tidak berjalan
baik dan diancam dibubarkan, kemerdekaan untuk Burma (kini
Myanmar) dan Filipina diumumkan, tetapi Indonesia tidak diberi
kesempatan. Bung Karno sangat kecewa atas keputusan Jepang itu.
Bung Karno berhasil mengatasi kesulitan dan kekecewaan itu berkat
kegembiraan dalam kehidupan pribadinya.
Tidak lama kemudian foto Fatmawati dimuat di halaman depan
majalah Jawa Baru edisi tanggal 1 Januari 1944, yang tentu saja
mengejutkan bangsa Indonesia. Dalam foto itu Ibu Fatmawati
mengenakan kimono-pakaian tradisional Jepang-hadiah istri
Perdana Menteri Tojo yang diberikan ketika Bung Karno
mengunjungi Jepang pada bulan November 1943. Selama satu
tahun masih sebagai istri Bung Karno di bawah bendera Jepang,
setahu saya, foto Inggit tidak pernah dimuat dalam majalah atau
koran Jepang. Ny Inggit tidak pernah muncul di muka umum.
Pada tahun 1944, anak pertama Bung Karno, Guntur, lahir. Betapa
besar kebahagiaan Bung Karno dan Ny Fatmawati. Panglima Besar
Jepang memberi nama Jepang kepadanya, yaitu "Osamu". Osamu
adalah kode Angkatan Darat Ke-16 yang menduduki Jawa, yang
artinya "memerintah". Kebetulan pada waktu itu ada seorang bidan
wanita Jepang, yang dikirim ke Indonesia untuk membantu Jawa
Hokokai dan Fujinkai. Bidan ini-namanya Sanko Sakigawa-sangat
akrab dengan Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Karno segera
memperlihatkan bayinya kepada Sakigawa, sekaligus meminta
nasihat tata cara mengasuhnya.
(4) Pergaulan dengan orang Jepang
Pemerintahan militer Jepang tidak terlalu mencampuri ke-giatan dan
upaya Bung Karno menggerakkan massa. Hal itu mungkin
disebabkan Bung Karno berhasil meyakinkan petinggi Jepang
tentang kesetiaannya terhadap Jepang. Dalam pergaulan sehari-hari
dengan orang Jepang, dia terlihat cukup sabar, sopan, dan ramah.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
Akhirnya terbangun kepercayaan orang Jepang terhadap Bung
Karno. Bung Karno sendiri menulis dalam otobiografinya, "Tentara
Jepang tidak pernah percaya saya penuh", tetapi setahu saya, Bung
Karno belum pernah dicurigai oleh pihak Jepang, sedangkan Moh
Hatta sering dilihat dengan mata kecurigaan sehingga akhirnya
pernah ada rencana tentara Jepang membunuhnya di Puncak Pass
atau menahan dia di Jepang pada waktu dia mengunjungi ke Jepang
bersama Soekarno pada bulan November 1943.
Ada episode yang membuktikan betapa pihak Jepang memberi arti
penting bagi sosok Bung Karno. Sewaktu Bung Karno mengunjungi
Jepang dan bertemu dengan Kaisar Hirohito pada bulan November
1943, Kaisar menjabat tangan Bung Karno. Padahal, menurut
kebiasaan Kerajaan Jepang, kaisar hanya berjabat tangan dengan
seorang kepala negara. Artinya perlakuan kepada Bung Karno itu
sangat istimewa.
(5) Sikap keras Bung Karno
Meskipun demikian, Bung Karno kadang-kadang mengambil sikap
keras terhadap Jepang. Sesudah janji "kemerdekaan di kemudian
hari"diumumkan pada September 1944, Bung Karno menangis
dengan gembira bersama kawan-kawan Jepang. Tetapi, lama-
kelamaan dia tahu pemerintahan militer Jepang tidak serius dan
tidak segera mengambil langkah-langkah realisasi-enam bulan bulan
lewat tanpa kebijakan apa-apa-Bung Karno tidak bisa sabar lagi.
Dengan keras ia meminta petinggi Jepang segera bertindak. Sikap
Bung Karno begitu keras sehingga Miyoshi-seorang pejabat
Gunseikanbu-khawatir akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan
kalau tidak diambil tindakan sebelum 9 Maret 1945-hari ulang tahun
keempat Jepang menduduki Indonesia. Dengan demikian, pada hari
itu diumumkan akan dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), meskipun di pihak
Jepang belum ada konsensus dengan para panglima yang
menduduki pulau-pulau lain di Indonesia.
Ada satu episode yang menceritakan kekerasan sikap Bung Karno.
Suatu hari sesudah De-klarasi Koiso, dia mengirim sebuah surat
kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di
Jepang. Surat itu sampai ke asrama mahasiswa Kokusai Gakuyukai
di Tokyo pada tanggal 24 September 1944. Menurut Kusnaeni, yang
waktu itu belajar di Jepang, Bung Karno menulis, Perjuangan untuk
kemerdekaan Indonesia lebih penting daripada janji Jepang. Bung
Karno tak lagi menaruh harapan pada Deklarasi Koiso, karena dia
merasa kemerdekaan bukan suatu barang yang akan diberi, tetapi
harus direbut dengan perjuangan.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
Menyambut hadirnya BPUPKI, Bung Karno mengambil prakarsa
aktif. Dalam waktu singkat menyediakan bahan Piagam Jakarta,
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Dia sering mendesak kawan-
kawan lain dengan mengatakan "Indonesia merdeka selekas-
lekasnya" dan "Indonesia merdeka sekarang juga". Dia mengatakan,
"Kemerdekaan itu tampaknya seperti perkawinan. Siapakah yang
menunggu sampai gajinya naik, sampai, katakanlah, 500 gulden,
dan menunggu sampai rumah yang dibangunnya selesai?"
Dalam perhitungan Bung Karno, Jepang mulai memihak bangsa
Indonesia sejak setuju pembentukan BPUPKI. Menu-rut Bung Karno,
Dai Nippon Teikoku (Kerajaan Jepang Raya) dalam mempersiapkan
kemerdekaan Indonesia tidak lebih daripada peranan seorang bidan,
dan yang mengambil kemerdekaan haruslah bangsa Indonesia
sendiri. Dia merasa menang dalam "judi". Dan di sanalah mulai
terjadi kemenangan untuk Indonesia.
(6) Bung Karno dalam kenangan teman Jepang
Saito Shizuo, pegawai tinggi Gunseikanbu dan Duta Besar Jepang di
Indonesia tahun 1961-1966 menilai Bung Karno adalah cooperator,
tetapi bukan pengagum Jepang. Dia menilai Bung Karno selalu
memilih solusi yang praktis dan menghindari bertabrakan dengan
Jepang.
Sesudah Indonesia merdeka, Bung Karno masih mempertahankan
persahabatan dengan orang-orang Jepang yang pernah
memperlihatkan simpati terhadap bangsa Indonesia. Menurut
Jenderal Imamura, sewaktu dia ditahan Belanda di Cipinang sebagai
penjahat perang dengan ancaman hukuman mati, Soekarno diam-
diam menyampaikan pesan melalui pegawai Cipinang tentang
rencana menculik dan merebutnya ke tangan Republik Indonesia.
Saya tidak tahu apakah rencana ini betul-betul berasal dari Soekarno
yang memimpin Pemerintah RI di Yogyakarta waktu itu, atau berasal
dari orang lain.
Menurut catatan Nishijima, anak buah Laksamana Maeda dan yang
juga hadir dalam rapat persiapan Naskah Proklamasi di rumah
Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, Bung Karno memberi
perhatian kepada nasib Maeda yang kurang baik di masa
pascaperang. Dan pernah pada tahun 1950, ia menawarkan
sumbangan mobil atau uang yang memadai kepada Maeda.
Akhirnya sumbangan itu berbentuk uang yang diberikan kepada
Maeda. Lalu, pada tahun 1958, ketika Bung Karno mengunjungi
Jepang pertama kali sesudah perang, ia pun menengok Maeda yang
sedang sakit.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno di Bawah Bendera Jepang -- Jumat, 1 Juni 2001
Bung Karno adalah orang yang tidak melupakan bantuan dan
simpati yang pernah diberikan dalam situasi sulit. Bung Karno
menghargai bantuan beberapa orang Jepang yang memberi
kesempatan membuka jalan ke arah Indonesia merdeka. Saya,
sama sekali tidak percaya pada teori bahwa pendudukan Jepang
memberi jalan ke Indonesia merdeka, atau Jepang menduduki
Indonesia untuk memerdekakan Asia. Tetapi, saya juga tidak
membantah kenyataan bahwa beberapa orang Jepang dalam
kapasitas pribadi menunjukkan simpati pada rakyat Indonesia. Dan,
mungkin Bung Karno menangkap maksud baik mereka, dan selalu
berusaha membalas budi.
* Aiko Kurasawa Pengajar di pascasarjana Keio University, doktor
ilmu sejarah politik dari Universitas Cornell (1987) dengan disertasi
"Mobilisasi dan Kontrol" di Indonesia.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...era%20Jepang%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (10 of 11)4/3/2005 11:04:52 AM
Bung Karno, Arsitek-seniman -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Karno, Arsitek-seniman
Eko Budihardjo
PENDIDIKAN kesarjanaan Bung Karno sebetulnya adalah Teknik
Sipil, yang diraihnya di Institut Teknologi Bandung. Namun,
perhatiannya terhadap dunia perancangan arsitektur sungguh luar
biasa. Pandangannya sangat jauh ke depan, lebih jauh ketimbang
tokoh-tokoh lain pada zamannya. Banyak sekali karya arsitektur di
Jakarta yang sekarang menjadi kebanggaan bangsa, sebagai
tetenger atau landmark, yang bersumber dari gagasan-gagasannya
yang brilyan. Memang, bukan Bung Karno sendiri secara pribadi
yang merancang, tetapi cetusan idenya yang orisinal dan otentik
itulah yang menjadi jiwa atau semangat dari karya-karya arsitektur
yang bermunculan. Siapa yang tidak kenal dan tidak kagum dengan
Monas atau Monumen Nasional, yang sudah menjadi trademark dan
landmark-nya Jakarta, bahkan bisa disebut sebagai tetenger-nya
Indonesia. Mirip seperti Eiffel-nya Kota Paris (Perancis), Patung
Liberty-nya New York (Amerika Serikat), atau Open House-nya
Sydney (Australia).
Sampai saat ini, Monas dan lingkungan atau
ruang terbuka di sekitarnya masih juga terlihat sebagai kawasan
yang amat bermartabat, menumbuhkan rasa bangga sebagai warga
(civic pride). Sebagai suatu ruang publik yang dapat dinikmati oleh
segenap warga kota maupun pendatang, menyiratkan suasana
demokrasi dan keterbukaan. Monas dengan Lapangan Merdekanya
yang luas dapat disebut sebagai oase, bahkan mungkin malah
surganya kota, mengacu pada pendapat seorang pakar bahwa park
is urban paradise.
Arsitek-seniman
Sepanjang pengetahuan saya, Bung Karno adalah seorang insinyur
sipil yang memiliki jiwa arsitek dan seni budaya dengan kadar yang
tinggi. Bahkan bisa dikatakan lebih arsitek ketimbang arsitek yang
sesungguhnya. Sangat jarang pimpinan negara yang memiliki
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karno...rsitek-seniman%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 5)4/3/2005 11:04:53 AM
Bung Karno, Arsitek-seniman -- Jumat, 1 Juni 2001
perhatian besar pada dunia arsitektur. Boleh saja George Pompidou
dari Perancis bangga dengan Pompidou Center-nya di Kota Paris,
yang dikenal sebagai salah satu karya arsitektur berciri Post-Modern.
Namun, ditilik dari keberagaman karya yang digagas oleh Bung
Karno, tampak jelas bahwa Bung Karno jauh lebih unggul sebagai
negarawan yang juga arsitek dan seniman sekaligus. Bukan hanya
karya arsitektur yang berupa gedung-gedung atau monumen-
monumen saja yang menjadi bidang gulat dan perhatiannya. Patung-
patung, taman-taman, kawasan, bahkan sampai-sampai skala kota
pun digagas dan direalisasikan.
Patung Pembebasan Irian Ja-ya, Patung Selamat Datang di
Bundaran Hotel Indonesia, Patung Pancoran, Patung Pak Tani di
Menteng dan lain-lain, semua itu dibangun pada zaman Presiden
Soekarno. Dari kacamata perkotaan, kehadiran patung-patung yang
beraneka ragam itu betul-betul menyiratkan keindahan kota sebagai
suatu karya seni sosial (a social work of art). Bisa menjadi titik
referensi agar kita tahu sedang ada di mana, supaya tidak
kehilangan arah.
Taman Merdeka di seputar Monas dan kawasan pusat olahraga
dengan ruang terbuka yang begitu luas di Senayan, merupakan
warisan Bung Karno yang layak kita syukuri bersama. Dalam skala
yang lebih makro, sebagai seorang presiden yang berwawasan
nasional, tidak berpikir sempit, memikirkan kemungkinan
memindahkan ibu kota negara kita dari Jakarta ke luar Jawa. Kalau
tidak salah lokasi Palangkaraya di Kalimantan Tengah yang dipilih
sebagai salah satu alternatif, dan kemudian mulai dirancang serta
terus dibangun. Sayang sekali, karena berbagai kendala gagasan
terobosan yang inovatif itu tidak terlaksana. Kendati begitu, toh, Kota
Palangkaraya ternyata berkembang dengan baik sampai sekarang.
Senang sayembara
Yang tidak kalah menarik dari Bung Karno dalam kiprahnya sebagai
seorang arsitek adalah bahwa beliau sangat senang dengan karya-
karya unggulan yang dihasilkan melalui sayembara.
Monas yang terbangun sekarang pun semula adalah hasil
sayembara. Menurut tokoh arsitek senior Prof Ir Sidharta, pemenang
pertamanya dulu tidak ada, pemenang kedua adalah arsitek
Friedrich Silaban (sudah almarhum) dan pemenang ketiga adalah
tim mahasiswa dari ITB. Rancangan yang memenangkan sayembara
tersebut kemudian dikolaborasi oleh tim arsitek Istana (kalau tidak
salah di bawah pimpinan Soedarsono) dengan beberapa perubahan
sehingga terbangun seperti yang tampak sekarang ini.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karno...rsitek-seniman%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 5)4/3/2005 11:04:53 AM
Bung Karno, Arsitek-seniman -- Jumat, 1 Juni 2001
Prinsip bahwa karya terbaiklah yang dipilih dan disetujui untuk
dibangun, antara lain melalui proses sayembara, merupakan suatu
prinsip yang dewasa ini banyak ditinggalkan oleh para pejabat. Tidak
heran bila yang banyak bermunculan di kota-kota besar di Indonesia
adalah bangunan-bangunan yang termasuk kategori junk
architecture atau arsitektur sampah. Orang-orang itu lupa bahwa
kaidah paling dasar dari suatu karya arsitektur masih tetap saja
seperti yang dicanangkan Vitruvius ratusan tahun yang silam, yaitu
utilitas (fungsi atau kegunaan), firmitas (konstruksi atau kekokohan),
dan venustas (estetika atau keindahan). Nah, aspek terakhir yang
menyangkut estetika atau keindahan itulah yang tak pernah
dilupakan oleh Bung Karno.
Begitu pula ketika muncul gagasan Bung Karno untuk
menyelenggarakan Conference of the New Emerging Forces
(Conefo) lantas dirancang gedung pertemuan yang sekarang
menjadi Gedung MPR/DPR, dengan perancang dan pembangun
antara lain Ir Sutami, Ir Soejoedi, dan Ir Nurpontjo.
Dari kisah itu terlihat bahwa gagasan dan pemikiran Bung Karno
sejak dulu sudah mengglobal. Globalisasi baginya bukan sekadar
slogan kosong, melainkan sudah diaktualisasikan dalam kiprahnya
sehari-hari.
Tak berpikir sempit
Mengenai perencanaan atau arsitek yang dipilihnya, asal memang
kompeten, tak peduli dari mana asalnya atau apa agamanya, selalu
ada peluang dia pilih untuk mengaktualisasikan gagasan-
gagasannya dalam wujud nyata. Manakala Friedrich Silaban terpilih
untuk merancang Gedung Pola, barangkali bukanlah berita. Tetapi,
kalau Silaban yang sama, notabene seorang Kristen, terpilih untuk
merancang Masjid Istiqlal kebanggaan kita semua, bukankah itu
merupakan berita yang mestinya mengejutkan?
Gedung Hotel Indonesia sebagai gedung jangkung pertama di Kota
Jakarta, saya dengar dirancang oleh Sorensen, seorang arsitek
Swedia. Patung Tani di Menteng juga bukan karya seorang pribumi
melainkan karya pematung mancanegara. Artinya, Bung Karno
bukanlah tokoh yang primordial, chauvinistic berpikir sempit,
melainkan sebaliknya. Dan, yang tidak kalah membanggakan adalah
bahwa pemikiran dan gagasannya pun dipakai juga di mancanegara.
Ketika saya menunaikan ibadah haji pada tahun 1996, saya
memperoleh informasi bahwa bangunan dua lantai tempat para
jemaah haji melakukan sai (berjalan dan berlari dari bukit Safa ke
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karno...rsitek-seniman%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 5)4/3/2005 11:04:53 AM
Bung Karno, Arsitek-seniman -- Jumat, 1 Juni 2001
Bukit Marwah pulang-pergi) dibangun atas saran Bung Karno.
Semula bangunannya tidak bertingkat. Begitu jemaahnya setiap
tahun bertambah, semakin berjubel padat, akibatnya sangat
menyulitkan dan menyengsarakan bagi para jemaah. Usulan Bung
Karno sebagai seorang insinyur sipil sungguh sangat tepat untuk
mengatasi kesumpekan itu.
Dalam suasana hiruk-pikuk perpolitikan yang penuh dengan
manuver-manuver pertarungan kekuasaan yang
amat keji dan mencekam seperti yang kita lihat dan kita rasakan
akhir-akhir ini, sungguh amat kita rindukan tokoh negarawan seperti
Bung Karno. Pemimpin negara yang tidak hanya tinggi kadar
nasionalismenya, tetapi juga memiliki jiwa sebagai arsitek dan
seniman yang berbudaya, menciptakan karya-karya nyata yang
bermanfaat bagi bangsa.
* Eko Budihardjo Ketua Dewan Pembina Persatuan Sarjana
Arsitektur Indonesia dan Ketua Kehormatan Ikatan Arsitek Indonesia
Cabang Jawa Tengah.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karno...rsitek-seniman%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 5)4/3/2005 11:04:53 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
Maruli Tobing
JANUARI 1965 mendung menyelimuti Jakarta. Rakyat letih dan
cemas. Isu kudeta merebak di tengah inflasi meroket. Bahan-bahan
kebutuhan pokok lenyap di pasaran. Setiap hari rakyat harus sabar
berdiri dalam antrean panjang untuk menukarkan kupon pemerintah
dengan minyak goreng, gula, beras, tekstil, dan kebutuhan lainnya.
Rupiah nyaris tidak ada nilainya.Di hampir segala pelosok kota di
Jawa, barisan pengemis menadahkan tangan, berharap orang lain
mengasihani. Di pesisir selatan Jawa Tengah dan Timur, kelaparan
mirip hama, merembet dari desa ke desa lainnya. Di Kabupaten
Gunung Kidul, DIY, misalnya, ribuan penduduk berbondong-bondong
meninggalkan desa menuju kota dengan berjalan kaki. Dalam
eksodus dengan perut kosong itu, mereka memakan daun-daunan
dan apa saja yang dilihat sepanjang jalan. Sedang rekannya yang
tidak kuat menahan derita dan kemudian tewas, mayatnya ditinggal
begitu saja.
Inilah kondisi Republik Indonesia yang tercabik-cabik oleh pertikaian
dan perang saudara. Sejak pengakuan kedaulatan, nyaris tidak ada
hari dilalui tanpa konflik terbuka. Mirip kapal bocor di tengah
terjangan badai dahsyat, republik yang baru belajar merangkak itu
nyaris tenggelam. Bahkan, ketika babak-belur menghadapi agresi
bersenjata Belanda, pecah Peristiwa Madiun (1948). Setelah itu
gelombang badai perang saudara susul-menyusul menghantam
republik.
Di Jawa Barat, SM Kartosuwirjo memproklamirkan DI/ TII, diikuti oleh
Daud Beureueh di Aceh dan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Di
Maluku, mereka yang kecewa pada pemerintah pusat, bergabung
dengan elemen-elemen eks tentara kolonial, membentuk RMS
(Republik Maluku Selatan). Belanda ikut pula membantu
persenjataan melalui Papua Barat.
Belum lagi usai pemberontakan DI/TII dihadapi, muncul PRRI dan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (1 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
Permesta di Sumatera dan Sulawesi. Ketika gerakan pemberontak
ini mulai dapat dipatahkan, Indonesia terseret dalam konfrontasi
merebut Papua Barat, yang kemudian diberi nama Irian Jaya. Usai
perhelatan besar ini, lahir pula konfrontasi menentang pembentukan
federasi Malaysia tahun 1963.
Semua ini menguras energi nasional. Pembangunan ekonomi
terbengkalai. Kehidupan di berbagai sektor morat-marit. Namun bagi
angkatan darat, keadaan ini membuka peluang untuk tampil sebagai
garda republik. Mereka mentransformasikan organisasinya menjadi
kekuatan sosial, politik dan ekonomi. Bung Karno tidak mampu
mengimbangi permainan Angkatan Darat, yang bergerak secara
sistematis dengan roda organisasinya.
Bung Karno sendiri bukannya tidak menyadari keadaan yang
membahayakan itu. Namun, semangat revolusionernya yang tidak
pernah pudar, yang dirumuskannya sebagai "maju terus pantang
mundur," mengharuskan bekerja sama dengan Angkatan Darat.
Tanpa dukungan angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Darat,
semangat itu tidak akan terdengar gaungnya, karena revolusi tidak
dapat lepas dari konfrontasi dan sejenisnya. Sedang konfrontasi
membutuhkan angkatan perang.
Bagi Angkatan Darat di bawah Kolonel Nasution, inilah jembatan
emas menuju puncak kekuasaan. Transformasi itu mencapai
puncaknya pada periode Orde Baru. Atau seperti tulis Adam
Schawarz dalam bukunya A Nation in Waiting, Indonesia in 1990's,
mereka yang tadinya berada di bawah pemerintahan sipil, berbalik
mendominasi sipil.
ANGKATAN Darat sendiri sesungguhnya penuh dengan bisul konflik.
Namun, dialihkan kepada sipil, hingga membuat citra sistem
demokrasi parlementer mengalami degradasi. Jatuh-bangunnya
kabinet menjadi bulan-bulanan. Bahkan dianggap sebagai
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Elite politik
diidentikkan dengan pengacau. Sedang jajaran pejabat sipil dituding
korup dan tidak becus mengurus pemerintah.
Padahal nyaris tidak satu pun konflik yang membahayakan bangsa
absen dari keterlibatan para perwira Angkatan Darat. Singkatnya,
konflik bersenjata yang terjadi selama ini sebagai solusi terhadap
masalah-masalah politik, baik itu Peristiwa Madiun, DI/TII, RMS,
PRRI-Permesta, hingga G30S, tidak lepas dari konflik dalam tubuh
angkatan perang Indonesia, khususnya Angkatan Darat. Bahkan
gelombang perang saudara yang melanda Aceh dan Maluku, juga
tidak luput dari intervensi sejumlah anggota militer.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (2 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
Sebagai institusi, tindakan paling berani dilakukan pada 17 Oktober
1952. KSAD Kolonel AH Nasution marah setelah konsep
reorganisasi dan rasionalisasi Angkatan Darat tidak didukung
pemerintah. Selain mengerahkan 30.000 orang menuntut
dibubarkannya kabinet, di depan Istana, perwira yang loyal kepada
Nasution juga
mengarahkan meriam ke Istana.
Percobaan kudeta ini gagal, karena Bung Karno tidak mempan
digertak. Sebaliknya, Nasution malah dipecat. Waktu itu pemerintah
terpaksa menolak gagasan Nasution akibat munculnya protes dari
para perwira eks Pembela Tanah Air (Peta). Dalam hal ini Nasution
bukannya melakukan konsolidasi menyelesaikan masalah internal,
sebaliknya justru mencari sasaran ke Istana.
Sejak peristiwa itu, Angkatan Darat makin percaya diri. Apalagi
setelah berhasil mendesak mundur Kabinet PM Ali Sastroamidjojo
tahun 1955. Tanggal 15 November 1956, Kolonel Zukifli Lubis malah
mencoba melakukan kudeta dengan menduduki Jakarta. Perwira
yang loyal kepada Nasution itu berhasil menghempang masuknya
beberapa batalyon pasukan Siliwangi ke Jakarta. Setahun kemudian,
30 November 1957, Saleh Ibrahim, ajudan Kolonel Lubis, mencoba
membunuh Bung Karno dalam apa yang kemudian dikenal sebagai
Peristiwa Cikini.
Semua peristiwa itu bersumber pada konflik intern Angkatan Darat.
Bung Karno mendukung penunjukan kembali Nasution sebagai
KSAD pada tahun 1955. Ia menaruh harapan besar atas rencana
reorganisasi dan rasionalisasi Nasution yang pernah ditolaknya. Tapi
kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Konflik internal Angkatan
Darat makin memanas. Para panglima militer di daerah malah
mengambil alih pemerintahan dari tangan sipil, dan memberlakukan
darurat perang. Puncaknya adalah PRRI-Permesta, 1958.
Disadari atau tidak, harapan Bung Karno untuk "mengandangkan"
Angkatan Darat dan menjauhinya dari kudeta militer, mirip suatu
kemustahilan. Angkatan darat telanjur ikut dalam proses politik.
Lantas jika muncul ambisinya untuk memperoleh kekuasaan politik
lebih besar, jelas sulit untuk dihempang.
Persoalannya, seperti kata Harold Crouch dalam bukunya The Army
and Politics in Indonesia, Angkatan Darat lahir dari situasi
perjuangan politik kemerdekaan. Embrionya adalah laskar-laskar
yang dibentuk oleh masing-masing partai maupun organisasi politik.
Faksi-faksi menjadi lumrah. Seperti halnya dalam politik, Angkatan
Darat juga tidak bisa dilepaskan dari kegiatan bisnis.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (3 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
Jika pendapat ini diformulasikan dalam suatu proposisi, maka
sebaliknya adalah benar bahwa penolakan Angkatan Darat terhadap
demokrasi parlemen tidak dapat dilepaskan dari substansi sistem
parlementer, yang mustahil memberi tempat bagi hegemoni militer.
Dengan konsep one men one vote saja, Angkatan Darat tidak akan
pernah di atas sipil. Pendapat yang hampir sama dikemukakan
Adam Schwarz.
BUNG Karno yang sejak
awal tidak menyukai sistem demokrasi parlementer, gusar setelah
kabinet baru hasil Pemilu 1955, mengabaikan perintahnya agar PKI
disertakan. PKI secara mengejutkan berhasil menempati urutan ke-4
dalam jumlah perolehan suara pada Pemilu 1955. Namun,
Mohammad Hatta yang anti-PKI dan memandang sistem
parlementer masih yang terbaik, merespons Bung Karno dengan
mengundurkan diri sebagai wapres pada tanggal
1 Desember 1956.
Mundurnya Hatta, meningkatnya perlawanan di daerah, dan
pertarungan antar-elite politik di Jakarta, tidak membuat Bung Karno
mundur. Tanggal 21 Februari 1957, secara resmi diumumkan
Demokrasi Terpimpin berikut kabinet Nasakom (koalisi PNI,
Masyumi, NU, dan PKI), didampingi Dewan Nasional sebagai
penasihat. Dewan ini beranggotakan wakil-wakil golongan fungsional
yang ada dalam masyarakat.
Ada beberapa argumentasi Bung Karno menyertakan PKI. Antara
lain agar partai ini ikut bertanggung jawab atas kebijakan
pemerintah. Selama ini kabinet hanya jadi bulan-bulanan PKI. Tapi di
balik itu sesungguhnya Bung Karno ingin menciptakan kekuatan
tandingan bagi Angkatan Darat untuk mencegah kudeta maupun
konsentrasi kekuasaan yang berlebilihan.
Bagi Bung Karno, PKI yang merupakan partai komunis ketiga
terbesar di dunia dalam jumlah anggota, dapat pula dipakai
mencegah subversi imperialis AS dan sekutu-sekutunya melalui
solidaritas negara-negara sosialis.
Sebaliknya PKI merasa aman di bawah payung Bung Karno.
Sebagai balas budi, PKI merapatkan barisan mendukung
kepemimpinan Bung Karno secara konsekuen, dan mengganyang
mereka yang menentang Pemimpin Besar Revolusi. Kedekatan
Bung Karno dengan PKI menimbulkan kejengkelan di kalangan
Angkatan Darat dan juga parpol, khususnya Masyumi dan PKI.
Tahun 1960 Nasution memerintahkan penangkapan Aidit dan
anggota politbiro PKI lainnya. Namun, segera dibebaskan setelah
intervensi Bung Karno.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (4 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
Dalam konteks Perang Dingin yang sedang mencapai titik didih
ketika itu, sikap politik Bung Karno dipandang Presiden Eisenhower
sebagai membahayakan kepentingan AS di Asia Tenggara. Terlebih
lagi setelah PKI mendapat suara yang begitu besar dalam pemilu.
Sedang sukses Konferensi Asia Afrika di Bandung adalah bukti
Soekarno condong ke kiri. Maka jika awal 1950 Gedung Putih masih
hati-hati menyikapi Bung Karno, setelah pertengahan 1950-an
pendapatnya bulat, Bung Karno berbahaya. CIA, Dinas Intelijen AS,
mulai menyusun rencana rahasia.
CIA sendiri sebenarnya sudah sejak tahun-tahun sebelumnya
bergerak di Indonesia. Tapi operasinya terbatas pada memberi
dukungan dan bantuan keuangan bagi kelompok anti-PKI. Salah
satu parpol yang anti-PKI dan anti-Bung Karno, pernah mendapat
bantuan satu juta dollar AS. Dana yang ditransfer melalui Hongkong
itu untuk membiayai kampanye Pemilu 1955.
Peristiwa Cikini yang hampir menewaskan Bung Karno adalah
indikasi perubahan sikap AS. Bung Karno sendiri menuding CIA
dalangnya, walaupun sulit membuktikannya. Tapi tahun 1975 komisi
yang diprakarsai Senator Frank Chuch mengusut kegiatan CIA,
menemukan indikasinya. Di depan komisi ini, Richard M. Bissel Jr,
mantan wakil direktur CIA pada masa pemerintahan Eisenhower,
mengaku dinas intelijen pernah mempertimbangkan membunuh
Bung Karno. Namun perencanaannya terbatas pada mengumpulkan
aset yang memungkinkan untuk melaksanakannya.
Bagi Eisenhower, tidak ada jalan lain kecuali menetralisasi (baca:
meniadakan) Bung Karno, entah dengan cara apa pun. Sebab, jika
Indonesia jatuh ke tangan komunis, Malaysia hanya tinggal
menunggu waktu saja, kemudian Thailand dan negara-negara
tetangganya.
Kebijakan garis keras ini diteruskan oleh Presiden Kennedy dan
Lyndon B Johnson. Tapi apa sesungguhnya yang membuat AS
habis-habisan intervensi di wilayah RI tidak lebih dari upaya untuk
mempertahankan kepentingan ekonomi dan geopolitiknya, karena
kekayaan sumber alam Indonesia disebut menempati urutan kelima
di dunia. Jepang, misalnya, sangat bergantung pada pasokan bahan
bakar minyak dari Indoensia.
Selain kepentingan ekonomi, posisi Indonesia yang strategis di jalur
pelayaran internasional menjadi penting bagi geopolitik AS. "Vietnam
dan negara tetangganya boleh jatuh ke tangan komunis, tapi kita
tidak akan melepaskan Indonesia dengan taruhan apa pun," ujar
Eisenhower dalam pidato awal 1950.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (5 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
Tahun 1962, satu memorandum Presiden Kennedy dengan PM
Inggris Macmillan, berisi kesepakatan untuk "melikuidasi" (baca:
membunuh) Presiden Soekarno, jika ada peluang untuk itu. Tahun
1966, setahun setelah meninggalkan posnya sebagai duta besar AS
di Jakarta, Howard Jones mengatakan, sedikitnya ada tiga kali
percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno setelah
Peristiwa Cikini. Semuanya hampir berhasil.
Dalam bukunya Killing Hope, William Blumn malah menyebut, CIA
dengan bantuan agen FBI di Los Angeles, membuat film cabul
dengan pemeran pria mirip Bung Karno. Di situ dikisahkan, wanita
kulit putih teman kencannya, ternyata agen Soviet yang sedang
melakukan pemerasan.
Mantan anggota CIA menambahkan, dinas intelijen AS pernah pula
menyebarkan berita bohong mengenai tindakan tidak senonoh Bung
Karno terhadap pramugari Soviet dalam suatu penerbangan. Semua
ini, ujar Blumn, dimaksud untuk mendiskreditkan Bung Karno.
Namun tidak berhasil, karena rakyat Indonesia masih mencintai
pemimpinnya itu.
Mantan penerbang CIA, Poultry Fletcher yang menulis buku The
Secret War, menyebut begitu ambisiusnya Gedung Putih menggusur
Bung Karno, hingga operasi rahasia membantu PRRI-Permesta
merupakan terbesar dalam sejarah CIA. Mantan kolonel penerbang
AU-AS ini mengatakan, CIA telah menyiapkan peralatan militer bagi
40.000 personel PRRI-Permesta. CIA juga mengoperasikan 15
pesawat pembom B-26 yang dikemudikan penerbang Taiwan,
Korsel, Filipina, dan AS.
Akan tetapi sejarawan terkemuka George McT Kahin (Subversion as
Foreign Policy) mengatakan, AS memasok sebagian besar
persenjataan bagi 8.000 personel pemberontak di Sumatera. AS
juga melibatkan elemen-elemen Armada VII dan kapal-kapal selam
untuk memasok senjata.
Setelah PRRI-Permesta mulai surut, Gedung Putih menerapkan
politik bermuka dua. Selain membantu militer dan perguruan tinggi
Indonesia, CIA masih mensuplai senjata bagi sisa-sisa Permesta
dan DI/TII. Bantuan program pelatihan militer AS kepada TNI
meningkat drastis antara tahun 1960-1965.
David Ransom dalam tulisannya Ford Country: Building an Elite for
Indonesia mengatakan, pada periode itu AS mengirim Guy Pauker
untuk menginfiltrasi Angkatan Darat melalui pembenahan Sekolah
Komando Angkatan Darat (Seskoad). Pauker juga membangun
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (6 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
jaringan dengan intelektual PSI dan Masyumi, yang sejak lama
dikenal CIA dan disebut sebagai patriot. Pauker mengenalkan
konsep bakti sosial, yang tidak lain adalah bagian dari teror dan
perang urat syaraf, dalam kurikulum Seskoad. Istilah "sapu bersih"
pertama kali digunakan oleh Pauker. Menurut Dr Peter Dale Scott
(How the US and the Overthrow of Sukarno, 1965-1967), Pauker dan
sahabatnya, Mayjen Suwarto, merancang struktur kurikulum yang
menyiapkan Angkatan Darat mengambil alih bisnis dan
pemerintahan.
Selain pembenahan Seskoad, CIA membantu program pendidikan di
AS bagi perwira Angkatan Darat. Menjelang tahun 1965, sedikitnya
dua pertiga perwira menengah dan tinggi Angkatan Darat pernah
dididik di AS.
DENGAN diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, porsi kekuasaan
Angkatan Darat makin besar. Sebagai golongan fungsional, kini
mereka berhak mempunyai wakil di pemerintahan. Kekuasaannya
makin tidak tertandingi lagi, karena sebelum mengembalikan
mandatnya PM Ali Sastroamidjojo memenuhi permintaan Nasution
bagi keadaan darurat perang (SOB) secara nasional.
Nasution dengan cerdik segera memerintahkan para perwiranya
mengambil alih perusahaan-perusahaan eks Belanda dari tangan
buruh. Melalui perusahaan yang disita Pemerintah RI ini, Angkatan
Darat berkembang menjadi kekuatan ekonomi. Kampanye merebut
Irian Jaya, yang berubah menjadi konfrontasi meletihkan, juga atas
prakarsa Nasution dengan membentuk Front Nasional.
Nasution secara ajaib berhasil mengangkat Angkatan Darat menjadi
kekuatan sosial, politik, dan ekonomi, hanya dalam tempo dua tahun.
Sedang Bung Karno yang gembira diakhirinya sistem parlementer,
tidak keberatan atas SOB. Ia mengira SOB akan menunjang
pelaksanaan Demokrasi Terpimpin secara konsekuen. Padahal
kedua hal ini merupakan jembatan emas bagi Angkatan Darat
menuju puncak kekuasaan.
Demikian pula ketika November 1958 ia menawarkan konsep Jalan
Tengah (dwifungsi) dan kembali ke UUD 1945, yang disebutnya
untuk mencegah kudeta militer. Bung Karno menyambutnya gembira
melalui Dekrit 5 Juli 1959, kembali ke UUD 1945, serta pembubaran
Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955.
Sejak itu hampir sepertiga anggota kabinet diisi kalangan militer.
Demikian pula pemerintahan di daerah. Tahun 1964 misalnya, dari
24 jabatan gubernur 12 dipegang oleh perwira Angkatan Darat.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (7 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
Angkatan Darat de facto sudah memegang kendali kekuasaan RI. Itu
sebabnya ketika Bung Karno menyerukan konfrontasi terhadap
Malaysia, 1963, reaksi Angkatan Darat agak dingin. Mereka tidak
lagi melihat ada manfaatnya.
Bung Karno amat terpukul setelah kemudian mendapat laporan dari
TNI AU dan AL pada tahun 1964. Kedua angkatan ini mengalami
kerugian yang besar dalam konfrontasi, akibat Angkatan Darat
belum juga melakukan ofensif, sementara formasi dari udara dan
laut sudah dibuka. Akhirnya AU dan AL mengandalkan tenaga
sukarelawan.
Wakil Panglima Siaga Mayjen Soeharto, yang juga Pangkostrad,
ternyata bukan saja enggan bergerak, tapi malah melakukan kontak-
kontak rahasia dengan Malaysia dan Singapura untuk menghindari
konfrontasi. Melalui kurirnya, Kolonel Ali Moertopo, berulang kali
diadakan pertemuan dengan Norman Breddway, pakar perang urat
syaraf MI-6, dinas intelijen Inggris, dan juga penasihat politik
panglima militer Inggris di Singapura.
TANGGAL 21 Januari 1965 pukul 21.48, satu telegram dari Kedubes
AS di Jakarta masuk ke Deplu di Washington. Isinya informasi
pertemuan pejabat teras Angkatan Darat pada hari itu. Mengutip
seorang perwira tinggi yang hadir disebutkan, ada rencana untuk
mengambil alih kekuasaan jika Bung Karno berhalangan. Kapan
rencana ini akan dijalankan, tergantung pada keadaan konflik yang
sedang dibangun beberapa pekan ke depan. Dalam 30 atau 60 hari
kemudian Angkatan Darat akan menyapu PKI.
Arsip telegram yang tersimpan di Lyndon B Johnson Lybrary dengan
nomor kontrol 16687 itu menyebut, berberapa perwira yang hadir
malah menghendaki agar rencana itu dijalankan tanpa menunggu
Soekarno berhalangan.
Maret tahun itu juga Dubes Howard Jones, sebagai mana
dikemukakan George Kahin, mengatakan kepada pejabat senior
Pemerintah AS, "dari sudut pandang kami tentu saja percobaan
kudeta yang ternyata gagal, merupakan perkembangan yang paling
efektif untuk membelokkan arah politik Indonesia". (Dan Angkatan
Darat mendapat kebebasan untuk menghancurkan PKI). Tahun
sebelumnya, Dubes Jones pernah membujuk Jenderal Nasution
agar Angkatan Darat mengambil tindakan tegas terhadap PKI.
Dalam analisa intelijen AS, merontokkan PKI akan membuat Bung
Karno lumpuh. Atau meminjam pendapat Dr John W. Tate (From the
Sukarno to the Soeharto Regimes), PKI merupakan pendukung
utama Bung Karno. Tanpa PKI, Presiden Soekarno akan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (8 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
berhadapan dengan Angkatan Darat dan kelompok Islam yang
menudingnya sekuler.
Bulan Agustus 1965 tiba-tiba muncul isu merosotnya kondisi
kesehatan Presiden Tidak jelas dari mana sumber isu ini, walaupun
disebut-sebut nama tim dokter RRC. Namun dalam kabel perwakilan
CIA di Jakarta dengan nomor TDCS-314/ 11665-65, salah satu
bagian mengutip informasi dari salah satu pembantu dekat Soekarno
mengenai penyakit ginjal presiden yang sangat kronis. "Diperkirakan
Soekarno bisa saja meninggal mendadak dalam waktu dekat".
Dua pekan kemudian muncul pamflet gelap yang mengungkap detail
rapat-rapat CC-PKI, membahas kemungkinan mengambil alih
kekuasaan jika Bung Karno meninggal secara mendadak. Isi pamflet
itu menimbulkan kecemasan di kalangan perwira tinggi Angkatan
Darat, karena memuat daftar nama-nama jenderal yang akan
dihabisi. Sebaliknya, PKI juga mendapat pamflet gelap yang berisi
rencana detail Dewan Jenderal merebut kekuasaan dan kemudian
akan mengeksekusi pimpinan dan kader-kader PKI.
Dua minggu sebelum meletusnya G30S, Dubes AS yang baru
Marshall Green, meminta CIA meningkatkan propaganda menyerang
Bung Karno. Demikian pula MI-6, yang terus-menerus menyiarkan
berita menyesatkan. Pada waktu hampir bersamaan, muncul berita
di salah satu surat kabar di Jakarta mengenai kapal bermuatan
senjata kiriman RRC untuk PKI, sedang berlayar dari Hongkong
menuju Jakarta. Menurut Ralph McGehee (The Indonesian
Massacres and the CIA), surat kabar Malaysia itu sendiri mengutip
sebuah surat kabar di Bangkok. Sedang Bangkok mengutip sebuah
kantor berita yang memperoleh informasi dari sumber di Hongkong.
Mantan veteran CIA itu menyebut, inilah rekayasa disinformasi.
Bahkan kemudian dibuat dokumen-dokumen palsu hingga sulit
dibedakan dengan aslinya, seperti halnya juga dokumen (palsu) PKI
berikut daftar nama jenderal yang akan dibunuh. Dengan cara ini
CIA berhasil menimbulkan ketegangan dan saling curiga yang
gawat. Sebuah pemantik kecil akan menyulutnya menjadi banjir
darah.
Puncak dari semua ini adalah ketika sekelompok perwira dipimpin
Letkol Untung, mantan bawahan Soeharto di Kodam Diponegoro,
mencoba anggota Dewan Jenderal kepada Bung Karno. Namun
entah bagaimana kemudian, atas perintah Syam (Kamaruzaman),
para jenderal itu dieksekusi.
Syam-yang disebut-sebut tokoh misterius-menurut berbagai peneliti
asing, pernah menjadi kader PSI dan dekat dengan Soeharto ketika
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (9 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
di Semarang. Syam juga disebut-sebut sebagai intel Kodam Jaya,
yang berhasil disusupkan dalam tubuh PKI. Dalam pengakuannya
kepada aparat yang memeriksa, ia dipercaya DN Aidit membentuk
Biro Khusus untuk menginfiltrasi TNI. Anehnya, kecuali Aidit, tidak
satu pun jajaran anggota Politbiro maupun CC PKI yang mengetahui
ihwal Biro Khusus. Suatu hal yang sesungguhnya mustahil dalam
organisasi partai yang berideologi marxisme. Aidit sendiri dieksekusi
Angkatan Darat, sehari setelah ditangkap di tempat
persembunyiannya di Solo. Eksekusi ini membuat tertutupnya
kemungkinan membuktikan ada tidaknya Biro Khusus itu.DOKTOR
Peter Dale Scott melihat banyak keanehan dalam peristiwa ini.
Contohnya saja, dua pertiga dari kekuatan satu brigade pasukan
para komando, ditambah satu kompi dan satu peleton pasukan
lainnya, yang merupakan kekuatan keseluruhan G30S, sehari
sebelumnya diinspeksi Mayjen Soeharto. Sedangkan pasukan elite
dari Batalyon 454 dan 530 Banteng Raiders datang ke Jakarta atas
radiogram Pangkostrad Mayjen Soeharto untuk parade HUT ABRI 5
Oktober. Kedua batalyon pendukung utama G30S ini sejak tahun
1962 rutin memperoleh bantuan pelatihan AS.
Dalam siaran RRI tanggal
1 Oktober, tambah Peter Scott, Letkol Untung mengatakan, Presiden
Soekarno berada dalam keadaan aman di bawah perlindungan
Dewan Revolusi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Bung Karno
berada di tempat lain. Dalam susunan Dewan Revolusi yang
berkuasa, Untung sama sekali tidak menyebut nama Bung Karno.
Melalui corong RRI tersebut Untung mengatakan adanya rencana
jahat Dewan Jenderal untuk menggulingkan Bung Karno. Pasukan
didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal pasukan ini
disiapkan untuk parade HUT ABRI 5 Oktober. Untung sendiri ikut
dalam perencanaan parade tersebut. Anehnya lagi, di seberang
stasiun RRI yang dikuasai gerakan ini terletak markas utama
Kostrad, yang sama sekali tidak disentuh.
Sama seperti Biro Khusus, peran Untung yang sesungguhnya sulit
diketahui. Ia mengalami nasib yang sama seperti Aidit. Dieksekusi
ketika tertangkap dalam pelarian ke Jawa Tengah.
Situasi Jakarta sendiri tidak menentu setelah meletusnya G30S.
Namun, Norman Reedway, pakar perang urat syaraf MI-6 yang
berpangkalan di Singapura, mengaku bekerja sama dengan CIA
menyebarkan disinformasi keterlibatan PKI. Saluran radio Indonesia
sempat ditutup mereka dan dimunculkan berita dari BBC yang
seolah-olah mendapat laporan dari Hongkong, mengenai
keterlibatan RRC membantu PKI dalam gerakan tersebut.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (10 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
Presiden Johnson melalui radiogram tanggal 9 Oktober 1965
memberi petunjuk ke Kedubes AS di Jakarta. Isinya antara lain
berbunyi, inilah saat kemenangan yang paling tepat bagi pimpinan
Angkatan Darat untuk bertindak, karena posisi mereka sangat
menentukan atas kekuasaan Soekarno. Jika momentum ini tidak
dimanfaatkan, bukan mustahil akan mendapat pembalasan yang
lebih keras dari oposisi. Tapi jika Angkatan Darat memenangkannya,
Soekarno tidak akan pernah kembali berkuasa.
Itu pula sebabnya ketika utusan Mayjen Soeharto meminta bantuan
melalui Kedubes AS di Jakarta untuk mempersenjatai milisi Muslim
menghancurkan PKI di Jateng dan Jatim, Gedung Putih segera
memenuhinya dengan bersembunyi di balik kiriman bantuan obat-
obatan. Bahkan, seperti ungkap wartawati Kathy Cadane,
Pemerintah AS melalui Kedubesnya di Jakarta memberi daftar nama
5.000 kader PKI kepada Mayjen Soeharto melalui Adam Malik.
Kolonel Latief-yang dalam pledoinya menyebut amat sangat dekat
dengan mantan komandannya, Mayjen Soeharto-mengaku telah dua
kali menyampaikan informasi mengenai rencana kudeta Dewan
Jenderal itu. Namun, Soeharto tidak memberi reaksi apa pun. Latief
yang disebut-sebut pada masa itu sebagai orang kedua setelah
Letkol Untung, berkesimpulan dalam pledoinya, Dewan Jenderal itu
terbukti memang ada dan berhasil menggulingkan Bung Karno.
Tapi apa pun bukti-bukti sejarah yang kelak diperoleh dalam
peristiwa ini, semua tidak akan menolong 500.000-1 juta jiwa korban
tewas dibunuh dalam tragedi berdarah itu hanya karena diduga
kader, anggota atau simpatisan PKI. Pengungkapan kasus ini
kembali tidak akan bisa pula memulihkan penderitaan 700.000 orang
rakyat Indonesia, berikut keluarganya, yang ditangkap dan disiksa
selama bertahun-tahun atas tuduhan yang sama.
Laporan CIA tahun 1967 menyebut, pembantaian setelah peristiwa
G30S sebagai salah satu peristiwa yang sangat mengerikan dalam
abad kedua puluh. Tidak kalah dengan pembantaian yang dilakukan
Nazi Jerman.
Inilah yang disebut sebagai tumbal tujuh Pahlawan Revolusi. Banyak
elite politik kita yang hingga saat ini bangga atas pembantaian rakyat
Indonesia itu. Kekejaman mereka atas kematian tujuh Pahlawan
Revolusi dianggap pantas dibayar dengan nyawa sedemikian
banyak.
Padahal, menurut Peter Dale Scott, empat dari enam perwira tinggi
pro Jenderal Yani yang mengikuti pertemuan pejabat teras Angkatan
Darat pada Januari 1965, tewas dalam peristiwa G30S bersama
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (11 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S -- Jumat, 1 Juni 2001
pimpinan Angkatan Darat tersebut. Ahmad Yani sendiri dikenal
sebagai sangat loyal kepada Bung Karno. Sedangkan tiga dari lima
jenderal anti-Yani, termasuk Mayjen Soeharto, adalah figur utama
dalam menumpas G30S. "Tidak seorang pun di antara jenderal anti-
Bung Karno menjadi target Gestapu," tulis Peter Scott. Sedang yang
dialami Jenderal Nasution disebutnya sebagai salah sasaran.
Pangkostrad, orang kedua setelah KSAD, yang memegang komando
pasukan, malah tidak masuk dalam target G30S. Bahkan posisi
pasukan pendukung utama G30S, berada di lapangan Monas, persis
berhadapan dengan Markas Mayjen Soeharto.
Peter Scott melihat peristiwa ini lebih merupakan konflik intern
Angkatan Darat, yang kemudian digiring menghancurkan PKI untuk
mengisolir Bung Karno. Tapi peneliti lainnya ada yang melihat
peristiwa ini memang melibatkan unsur PKI. Ada beragam versi. Tapi
di Indonesia sendiri Angkatan Darat di bawah Jenderal Soeharto
berhasil membentuk opini publik ke arah penghakiman Bung Karno,
sebagai terlibat dalam G30S.
Bung Karno dipaksa mendelegasikan kekuasaan melalui Surat
Perintah 11 Maret (Supersemar) kepada Jenderal Soeharto. Seperti
halnya misteri G30S, Supersemar juga tidak dapat dibuktikan
kebenarannya. Apakah benar ada, apakah benar sudah
ditandatangani Soekarno. Naskah aslinya sendiri "lenyap".
Berbekal Supersemar, Soeharto membubarkan PKI untuk mengisolir
Bung Karno. Proklamator ini, seperti dikemukakan Adam Schwarz
dan John Tate, kembali dipaksa menyerahkan kedudukannya,
setelah diancam akan diseret ke pengadilan. Bung Karno akhirnya
lengser dan dikenai status tahanan rumah. Ia diinterogasi secara
maraton oleh perwira militer. Proklamator dan Bapak Bangsa ini
menjadi pesakitan oleh bangsanya sendiri.
Lantas apakah masuk akal Proklamator ini terlibat dalam
pembunuhan para jenderal yang loyal kepadanya, dan tidak disukai
oleh Soeharto yang anti-Bung Karno?
* Maruli Tobing Wartawan Kompas.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Ka...20Menuju%20G30S%20--%20Jumat,%201%20Juni%20.htm (12 of 13)4/3/2005 11:04:54 AM
Bung Karno, Seni, dan Saya -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Karno, Seni, dan Saya
Daoed Joesoef
SEWAKTU ber-
SMA di
Yogyakarta
selama periode
revolusi fisik,
saya
menggabungkan
diri pada
organisasi
Seniman
Indonesia Muda
(SIM) dan dipilih
menjadi
Dok Kompas ketuanya di saat
organisasi itu
mula-mula
didirikan pada tahun 1946. Organisasi ini berpusat di Solo, dengan S
Soedjojono sebagai Ketua Umum SIM, dan mempunyai dua cabang, di
Yogya dan Madiun. Anggota SIM cabang Yogya tidak banyak jumlahnya,
namun terdiri dari para pelukis senior yang sudah "jadi", yaitu Affandy,
Hendra, Roesli, Soedarso, Dullah, Hariadi, dan beberapa pelukis muda
"harapan", seperti Troeboes, Zaini, Nasyah Djamin, Nazhar, Soeharto, dan
Tino Sidin.Sanggar SIM di Alun-alun Lor sering dikunjungi oleh tamu-tamu
negara dari negara asing, atas anjuran Bung Karno, dan ada kalanya SIM
diminta membawa koleksi lukisan anggota-anggotanya ke Istana Negara
untuk dipamerkan oleh Presiden kepada para tamu.
Pada suatu pagi, tiba-tiba datang utusan dari Bung Karno yang meminta
SIM segera membawa karya-karya yang bermutu ke Istana. Saya memang
tinggal sendirian di sanggar dan kebetulan belum berangkat ke sekolah.
Mengingat waktu yang disediakan hanya dua jam, tidak ada kesempatan
bagi saya untuk mengabarkan hal ini kepada para anggota senior yang
tinggal bertebaran jauh dari sanggar. Maka saya sendirilah-seorang diri-
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...20dan%20Saya%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 8)4/3/2005 11:04:56 AM
Bung Karno, Seni, dan Saya -- Jumat, 1 Juni 2001
yang akhirnya membawa lukisan-lukisan dengan andong ke Istana Negara
di Jalan Malioboro.
Tidak lama setelah lukisan siap dipajang di serambi depan Istana, dari
ruang dalam keluar ketiga Bung Besar, yakni Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.
Rupanya mereka ingin melihat lebih dahulu lukisan-lukisan yang ada
sebelum membanggakannya nanti di muka para tamu. Bung Karno
menanyakan kepada saya-dengan nada kebapakan-apakah tidak
keberatan kalau mereka berbahasa Belanda. Saya katakan sama sekali
tidak, karena saya mengerti bahasa tersebut.
Sebelum Jepang datang, saya sudah sempat duduk di kelas satu MULO.
"Wel, in dat geval mag ik u dan verzoeken, meneer de voorzitter, om mee
te praten met ons?!", kata Bung Karno dengan nada kepresidenan, namun
dengan sikap bercanda. "Met genoegen, meneer de president," jawab
saya, "en dank u zeer."
Lalu sambil berkeliling menatap lukisan satu per satu, yang untuk sebagian
besar bercorak ekspresionistis dan impresionistis, Bung Karno dan Bung
Sjahrir bertukar pikiran mengenai apresiasi masing-masing. Dalam
berdiskusi mereka saling "bertutoyer" saja-kelihatan intim sekali-namun
saya tetap membahasakan mereka dengan sebutan "u". Walaupun umur
saya jauh lebih muda dan bicara Belanda saya tentu tidak selancar
mereka, saya tidak merasa mereka remehkan. Mereka mendengarkan
dengan saksama uraian dan ulasan saya, termasuk tentang pendapat
mereka, dan tidak memotong pembicaraan sebelum saya selesai
berbicara.
Dari perdebatan seni itu saya berkesimpulan bahwa Bung Karno lebih
merupakan seorang "pencinta seni" (kunst liefhebber). Bagi dia seni lukis,
atau seni rupa pada umumnya, adalah identik dengan keindahan visual.
Maka itu tidak mengherankan kalau dia menggandrungi lukisan-lukisan
wanita cantik dari Basoeki Abdoellah. Wanita dengan kecantikan wajah
dan kemolekan tubuhnya adalah by nature simbol dari keindahan par
excellence. Inilah idee fixe yang kiranya menentukan pula sikap dan
perlakuannya terhadap wanita. Baginya, tarikan atau jalannya kuas yang
ekspresif tidak begitu penting untuk diperhatikan apalagi diperhitungkan.
Kalaupun dia "tertarik" pada lukisan Affandy yang serba impresionistis dan
karya Soedjojono yang begitu ekspresif, saya pikir-menurut kesan saya-
karena dia telah mengenal baik kepribadian dan kemanusiaan kedua
seniman tersebut dan naluri humanitasnya-bukan penalaran seninya-
mengakui ketinggian mutu seni karya-karya mereka.
Bung Sjahrir, sebaliknya, mengesankan benar-benar seorang "pengenal
seni" (kunstkenner) dan sangat mengetahui sejarah perkembangan seni
rupa modern. Saya sendiri sebelumnya tidak menduga bahwa
pengetahuan umumnya tentang seni sedalam dan seluas itu. Mungkin
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...20dan%20Saya%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 8)4/3/2005 11:04:56 AM
Bung Karno, Seni, dan Saya -- Jumat, 1 Juni 2001
sekali selama studi di negeri Belanda dahulu dia telah melihat sendiri
lukisan-lukisan modern yang asli di berbagai museum Eropa. Dia ternyata
seorang intelektual hasil tempaan nalar akademis Eropa Barat yang
berpembawaan luas. Dia dan Bung Karno lama memperdebatkan "konsep"
seni mengingat "keindahan visual" tidak selalu disepakati sebagai "de
standaard" mutu seni. Akhirnya kedua Bung Besar menantang jawaban
saya yang, menurut Bung Karno, memegang leiderschap SIM cabang
Yogyakarta, Ibu Kota Republik Indonesia, "membawahi" beberapa pelukis
senior yang dia kenal baik.
Saya katakan bahwa "keindahan" bukan berupa "harga mati" yang terpatri
di mata atau kertas uang, bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain
dengan nilai yang sama tetap. Tidak ada seorang pun yang berani
mengatakan bahwa apa yang diperlukan bagi kreasi suatu seni yang baik
adalah sebuah konsep yang baik mengenai seni. Namun, saya bisa
mengatakan bahwa suatu konsep seni yang tidak memadai dapat
menghambat-bahkan merusak-jalannya kreativitas. Di kalangan para
seniman sendiri mungkin ada yang tidak tertarik secara khusus pada teori
estetika dan di antara mereka yang mungkin relatif lemah dalam teori
tersebut, atau bahkan tidak mempedulikannya sama sekali, tentu ada yang
mungkin mampu mengombinasikan bakat kreasi artistik dengan flair untuk
estetika. Kelihatannya bila pikiran tidak bisa menjelaskan, naluri punya
alasan-alasannya sendiri. Maka bila otak manusia belum mampu
mengatur, biarkanlah kodrat alam membimbing sewajarnya. Dalam
berkarya perlu bagi seniman tetap memupuk individualitas, eigen
persoonlijkheid, dalam artian tidak ikut-ikutan dan bisa menjelaskan sendiri
mengapa karyanya dianggap baik dan waardig genceg untuk dipamerkan.
Selama perdebatan seni ini Bung Hatta diam saja. Sikapnya bagai "guru"
yang sedang mengawasi "murid-muridnya" sedang bertengkar. Dia ikut
mendengarkan dengan serius, menatap muka setiap pembicara dan
sesekali tersenyum lembut. Saya berkeringat dingin bukan karena
berdebat dengan Bung Karno dan Bung Sjahrir, tetapi karena tahu sedang
diawasi terus-menerus oleh Bung Hatta. Saya tidak yakin kalau tokoh yang
saya kagumi ini tidak tertarik pada seni. Betapa tidak. Saya ingin benar
ketika masih remaja di zaman Belanda dahulu saya pernah menghadiri
malam deklamasi di gedung organisasi Jong Islamieten Bond (JIB) di
Medan. Ketika itu para anggota senior dari JIB membacakan berbagai
soneta, sajak, dan syair dari beberapa pujangga "Pulau Masa Depan",
yaitu Muhammad Jamin, Sanusi dan Armijn Pane, Sutan Takdir
Alisyahbana, Tengku Amir Hamzah, dan ... Mohammad Hatta.
Cobalah perhatikan tanda tangan negarawan kita yang satu ini. Ia benar-
benar merupakan ekspresi dari suatu jiwa seni. Sebagai tanda tangan ia
bukan sembarang ungkapan jati diri, tetapi merupakan pula suatu gubahan
kaligrafis yang bermutu, suatu persenyawaan yang sungguh artistik dari
dua jenis huruf, yaitu Latin dan Arab.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...20dan%20Saya%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 8)4/3/2005 11:04:56 AM
Bung Karno, Seni, dan Saya -- Jumat, 1 Juni 2001
***
SATU kejadian lain lagi, masih di Yogyakarta, menambah kenangan
pribadi saya dengan Bung Karno, humanis dan pencinta seni. Saya diajak
oleh pelukis Affandy menemui Bung Karno di Istana Negara. Dia ingin
menjual lukisannya kepada Bung Presiden karena istrinya sakit berat dan
perlu uang untuk obat serta dokter. Walaupun kunjungan ini mendadak
dan tanpa membuat janji lebih dahulu, Bung Karno, toh, bersedia
menerima Sang Pelukis dengan ramah. Mereka berbicara dengan akrab
dalam bahasa Belanda. Setelah mendengar maksud kedatangan Affandy,
Bung Karno lama termenung dan diam saja. Akhirnya dengan suara
bernada rendah dia berkata: "Mas, terus terang sekarang ini saya tidak
punya uang. Tapi, terimalah pulpen saya ini. Nama saya ada diukir di situ.
Barangkali saja bisa dijual dan pakai uangnya untuk biaya pengobatan
yang diperlukan."
Pak Affandy menolak pemberian pulpen itu sambil berkata dengan lirih,
"Bung, terima kasih. Saya butuh uang, bukan pulpen. Saya juga tidak tahu
di mana bisa menjualnya. Lagi pula jangan-jangan saya nanti dituduh
mencuri." Mendengar ucapan Affandy yang terakhir itu Bung Karno tertawa
terbahak-bahak. Tanpa disadari, Pak Affandy dan saya ikut pula tertawa
sejadinya. Lalu Bung Karno bangkit dari duduknya, berdiri dan menepuk
bahu Pak Affandy. "Tunggu sebentar Mas Affandy", katanya, "saya akan
menemui Bu Fat di dalam." Tidak lama kemudian, Bung Karno keluar, lalu
memilih sebuah lukisan yang ditawarkan, dan memberikan sebuah amplop
kepada Sang Pelukis. "Terimalah ini, saya pinjam dulu dari Bu Fat, diambil
dari uang belanja sehari-hari", katanya. "Jumlahnya memang tidak
seberapa. Kekurangannya akan saya angsur bulan depan. Sudah saya
perintahkan kepada dokter kepresidenan supaya memeriksa Bu Affandy di
rumah. Tolong tinggalkan alamat rumah kepada ajudan sebelum pulang."
Setelah mengucapkan terima kasih kami berdua segera meninggalkan
Bung Karno dengan membawa sisa lukisan yang tidak dibeli. Di tengah
jalan saya katakan kepada Pak Affandy betapa mahal harga pulpen Bung
Karno itu di kemudian hari, lebih-lebih kelak bila revolusi Indonesia telah
selesai dan berhasil. "Ah, dik", jawab Sang Maestro, "bila harus menunggu
selama itu tanpa uang buat beli obat, istri saya sudah keburu mati." Saya
pikir-pikir, betul juga ungkapan polos Pak Affandy ini.
Mengingat betapa pentingnya karya seni sebagai wahana untuk
menaikkan citra bangsa, berdasarkan pengalaman berpameran di Istana
selama ini, saya pikir ia bisa juga dipakai sebagai wahana diplomasi untuk
menembus blokade Belanda. Kira-kira sama dengan diplomasi beras
dengan India dari Sutan Sjahrir. Saya lalu menulis surat kepada Presiden
Soekarno. Di situ saya usulkan supaya pemerintah mengirim Pak Affandy
berpameran di luar negeri agar Indonesia dikenal luas di kalangan
internasional dan dengan demikian menguak tabir kebohongan Belanda
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...20dan%20Saya%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 8)4/3/2005 11:04:56 AM
Bung Karno, Seni, dan Saya -- Jumat, 1 Juni 2001
yang selalu mengecilkan martabat bangsa kita.
Saya pilih Pak Affandy, karena pelukis kita yang satu ini sudah memiliki
koleksi yang cukup untuk berpameran tunggal. Dia betul-betul kreatif,
siang dan malam terus berkarya. Kalau sedang melukis seperti orang
kesurupan dan mutu lukisannya pantas dibanggakan. Pada Pak Affandy
bisa saja dititipkan karya pelukis-pelukis lainnya, dan kalau keuangan
negara memungkinkan diikutsertakan pula satu atau dua pelukis
senior.
Perbuatan saya ini disalahkan oleh Ketua Umum SIM karena dianggap
melampaui wewenang Ketua Cabang SIM tanpa berkonsultasi lebih dahulu
dengan pengurus pusat. Saya dipanggil ke Solo dan diadili di dalam rapat
yang dihadiri oleh pelukis-pelukis senior dan yunior yang ada di pusat.
Setelah Ketua Umum SIM menjatuhkan vonisnya yang menyatakan saya
bersalah, saya bangkit dan mendatangi mejanya. Saya gebrak meja itu
dan berkata keras, "Persetan!". Saya segera keluar dari ruang rapat dan
langsung pulang ke Yogyakarta.
***
DI tahun 1960-an Bung Karno membiarkan-kalaupun bukan membenarkan-
penghancuran Gedung Proklamasi, rumah kediamannya dahulu, yang
terletak di Jalan Pegangsaan Timur. Bersamaan dengan itu diruntuhkan
pula sebuah tugu kecil sederhana di halaman gedung yang biasa disebut
Tugu Proklamasi. Ketika itu ada yang mengkritik penghancuran tersebut,
dan saya kira per-buatan destruktif ini memang merupakan satu blunder
yang sangat tercela.
Apa pun alasan penghancuran ini, Bung Karno telah melenyapkan satu
saksi penting dari sejarah bangsa, padahal di Yogya dahulu dia sering
mengatakan kepada pemuda-pelajar betapa pentingnya orang
mempelajari sejarah. Maka, sebagai tanda protes, ketika proses
penghancuran gedung bersejarah itu sedang dilaksanakan, saya kirim
sebuah lukisan cat air kepada Bung Karno. Lukisan ini berukuran 15 x 20
cm dan di situ saya gambarkan Bung Karno berhadap-hadapan dengan
saya. Lukisan saya beri judul "Soekarno sainganku". Saya kirim per pos
dan sebagai pengirim saya sebut: Daoed Joesoef, ex-voor-zitter van SIM
Yogyakarta.
Pernah terpikir oleh saya apakah perbuatan Bung Karno ini bukan suatu
gerak refleks spontan dari seorang seniman. Bukankah seorang seniman
biasa menghancurkan karyanya-lukisan, patung, partitur musik-bila dia
kesal atau tidak puas dan orang lain tidak berhak melarangnya karena
yang dihancurkannya itu adalah miliknya sendiri. Hal seperti ini memang
sering terjadi dalam sejarah.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...20dan%20Saya%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 8)4/3/2005 11:04:56 AM
Bung Karno, Seni, dan Saya -- Jumat, 1 Juni 2001
Namun, yang dihancurkan oleh Bung Karno itu bukan sekadar bangunan
rumah miliknya sendiri. Yang dilenyapkannya bersama-sama dengan
kehancuran rumah dan tugu di Pegangsaan Timur itu adalah sebuah bukti
otentik dari suatu sejarah kolektif, sejarah perjuangan nasional, walaupun
memang diakui betapa besar peranannya dalam kejadian bersejarah yang
pantas dibanggakan itu.
Di awal tahun 1950-an, halaman Gedung Proklamasi sering menjadi
tempat berkumpul para pemuda yang dahulu turut aktif dalam perjuangan
revolusi fisik di daerah-daerah. Halaman ini cukup luas, teduh, dan di senja
hari cukup nyaman sebagai ajang pertemuan. Pertemuan itu sendiri terjadi
secara spontan, tanpa rencana apa dan oleh siapa pun sebelumnya.
Masing-masing datang atas keinginannya sendiri, termasuk saya, dan lalu
terjalinlah perkenalan yang akrab. Dengan membentuk lingkaran di atas
rumput, setiap orang duduk menceritakan pengalaman masing-masing,
anekdot suka duka berjuang dalam kesatuan Tentara Pelajar (TP), Tentara
Republik Indonesia Pelajar (TRIP), atau pasukan perjuangan kedaerahan
lainnya. Pernah satu kali saya gelar di muka mereka semua sketsa
perjuangan yang saya buat di tempat kejadian selama di Sumatera dan di
berbagai front Jawa Tengah sewaktu aksi polisional Belanda yang
pertama.
Namun, lama-kelamaan, dari hari ke hari, cerita-cerita nostalgia ini
berubah menjadi ungkapan kejengkelan dan ketidakpuasan tentang
suasana politik dan tingkah laku para elite partai. Mereka asyik saling
memaki dan menuduh, tetapi diam-diam sibuk memperebutkan aset yang
berangsur-angsur ditinggal Belanda, berupa pabrik, perkebunan, rumah,
dan harta benda lainnya. Yang paling menjengkelkan para peserta
pertemuan di halaman rumah Pegangsaan Timur ini bukanlah
keserakahan para Bapak itu saja, tetapi kenyataan bahwa para pemuda
eks-pejuang sudah ikut memperebutkan harta karun. Idealisme mulai sirna
dan masing-masing mulai menyalahgunakan surat-surat perjuangan masa
lalu sebagai kunci masuk ke khazanah harta peninggalan Belanda,
padahal dahulu baik TP maupun TRIP telah berikrar akan berjuang demi
kemerdekaan tanpa pamrih pribadi.
Oleh karena jengkel dan muak melihat keadaan itu, beberapa orang
pemuda mengumpulkan dokumen-dokumen perjuangan pribadi untuk
dibakar sebagai bukti dari tekad tidak akan menggunakan partisipasi
perjuangan masa lalu guna mendapatkan berbagai keistimewaan dan
fasilitas. Dan pembakaran ini dilakukan dengan khidmat, pada suatu senja,
di kaki tugu sederhana yang ada di halaman depan Gedung Proklamasi.
Saya pernah mendapat kesempatan melihat-lihat keadaan rumah
bersejarah ini dari dalam. Tanpa saya minta, kesempatan ini ditawarkan
oleh Bapak dan Ibu Moenar S Hamidjojo yang saya kenal sejak remaja di
Medan. Suami-istri terpelajar ini adalah tokoh-tokoh pergerakan yang
berkiprah di bidang pendidikan, kepanduan, dan pembinaan semangat
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...20dan%20Saya%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 8)4/3/2005 11:04:56 AM
Bung Karno, Seni, dan Saya -- Jumat, 1 Juni 2001
kebangsaan di kalangan remaja. Di awal tahun 50-an ini, Pak Moenar
rupanya ditarik oleh Pemerintah Pusat ke Jawa dan sementara menunggu
penempatannya di jajaran pemerintahan daerah Jawa Tengah, dia dan
istrinya diizinkan tinggal di Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur
sekaligus menjaga keamanannya.
Saya kadang-kadang mampir menjenguk mereka di siang hari kalau ada
kuliah malam hari di Salemba. Mungkin karena melihat saya lelah sekali,
pada suatu hari yang cukup terik, mereka menawarkan saya istirahat
sejenak di ruang tengah. Tikar yang mereka berikan saya gelar di lantai.
Sebelum tertidur saya bayangkan kesibukan, ketegangan, kecemasan,
dan harapan yang dialami oleh orang-orang di rumah ini menjelang
pembacaan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Kira-kira sebulan setelah saya dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan di tahun 1978, saya diundang untuk memberikan pidato
dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei,
bertempat di Gedung Pola yang dahulu dibangun Bung Karno di atas
puing reruntuhan Gedung Proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur.
Keengganan berpidato di tempat itu saya katakan terus terang kepada
panitia perayaan. Mereka jelaskan bahwa yang diundang cukup banyak:
tokoh-tokoh dari generasi pergerakan di zaman Belanda, zaman Jepang,
zaman revolusi fisik dan pemuda, mahasiswa, pelajar, pramuka serta
pimpinan dari berbagai organisasi sosial, termasuk tiga orang mantan
Menteri P dan K, dua di antaranya asal Aceh. Maka satu-satunya tempat
yang mampu menampung orang sebanyak itu dengan ongkos sewa yang
relatif murah adalah Gedung Pola yang berdiri di atas lahan Gedung
Proklamasi dahulu.
Sesudah berpidato, saya tidak segera pulang. Saya jalani perlahan-lahan
halaman gedung, di mana terdapat patung Bung Karno dan Bung Hatta,
sambil mencoba membayangkan semua yang telah terjadi di sini,
termasuk apa-apa yang pernah saya lakukan sendiri. Beberapa orang dari
panitia penyelenggara peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanpa diminta
mengiringi saya berkeliling. Salah seorang di antaranya memberanikan diri
untuk menanyakan mengapa saya dahulu sangat menyesali
penghancuran Gedung Proklamasi. "Karena saya pernah makan dan tidur
di situ", jawab saya singkat.
*Daoed Joesoef Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan
mantan Ketua Dewan Direktur Centre for Strategic and International
Studies (CSIS).
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Kar...20dan%20Saya%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 8)4/3/2005 11:04:56 AM
Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Bung Karno dan Tiga Pelukis Istana
Agus Dermawan T
BUNG Karno telah sampai di ketinggian sebuah bukit di Kintamani,
Pulau Bali. Ia terpaku lama di situ. Angin dingin yang lewat dan
menyapu hemnya yang putih, dengan mata terpejam dihayati.
Sementara awan-awan tipis yang berarak pada jarak "selemparan
batu" dibiarkan menyusun komposisinya sendiri. Dan nun di bawah
sana rumpun-rumpun perdu dan hamparan lembah tak henti
menerima bayang-bayang awan, yang sebentar ada, sebentar tiada.
"Dullah, Soekarno harus membuat sesuatu di sini. Soekarno dan
rakyatnya harus bisa menikmati surga ini. Soekarno dan dunia musti
punya tempat untuk menyaksikan lukisan Tuhan ini!" kata Bung
Karno kepada Dullah yang berdiri patuh di dekatnya.
Dullah tentu saja tersentak, dan kemudian berpikir. Dalam perjalanan
pulang menuju Istana Tampaksiring, Dullah mengusulkan sesuatu
kepada Bung Karno.
"Bagaimana kalau di tempat Bapak tadi dibangun gazebo? Agar
nanti Bapak dan semua orang mempunyai sudut pandang yang khas
untuk menatap keindahan Kintamani?"
Bung Karno menoleh kepada Dullah, dan kemudian berkata.
"Buatlah sketsanya, nanti kau serahkan kepadaku."
Beberapa bulan kemudian masyarakat Bali tahu, bahwa di tempat
Bung Karno berdiri tadi telah berdiri sebuah pesanggrahan, halte
istirah, atau gazebo. Beberapa tahun kemudian masyarakat
Indonesia diam-diam datang ke gazebo itu, untuk menyapukan
pandangannya ke hamparan alam yang alangkah indahnya.
Beberapa puluh tahun kemudian orang-orang dari seluruh dunia
datang ke Kintamani, dan berduyun-duyun untuk menghormati alam,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karn...ukis%20Istana%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 8)4/3/2005 11:04:57 AM
Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana -- Jumat, 1 Juni 2001
dengan mata takjub dan terharu. Jutaan orang itu berdiri di tempat
dahulu Bung Karno memandangi lembah dan awan-awan.
ITULAH salah satu tugas pelukis Istana Presiden. Ya,
mempresentasikan gagasan Soekarno", kisah Dullah tahun 1980-an.
Selama ini orang memang menganggap tugas pelukis Istana
hanyalah melukis, atau mengurus lukisan-lukisan yang ada di Istana
belaka. Padahal lebih dari itu. Di sini pelukis Istana serius bekerja
memelihara kecintaan Bung Karno kepada seni rupa. Merespons
kemauan Bung Karno atas sejumlah manifestasi seni. Dan,
mewujudkan aspirasi seni Presiden, dalam apa pun bentuknya.
"Banyak tugas ekstra di luar Istana. Namun, semua tetap bermuara
pada keindahan, yang merupakan esensi dari lukisan," kata Dullah.
Dullah adalah pelukis Istana Presiden yang bertugas tahun 1950-
1960. Setelah itu Bung Karno mengangkat Lee Man-fong, yang
bekerja pada 1961-1965, dan Lim Wawim yang bablas bertugas
1961 sampai 1968.
Dullah memang figur yang beruntung. Ia berkenalan dengan Bung
Karno lewat pelukis Sudjojono pada tahun 1944. Kala itu pria
kelahiran Solo 1919 ini sedang dalam proses bergabung dengan
Putera (Pusat Tenaga Rakjat) yang dipimpin oleh Bung Karno,
Mohamad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Mansyur. Satu organisasi
yang didirikan untuk mendampingi benteng kebudayaan Jepang,
Keimin Bunka Sidhoso.
Bung Karno sangat banyak mengenal seniman, oleh karena itu
sesungguhnya Dullah bisa dengan mudah terlupakan. Namun,
Dullah secara tak sengaja sempat menanamkan kenangan di benak
Bung Karno. Kejadian di tahun 1945, di sebuah
"ruang rahasia" Balai Pustaka, Jakarta Pusat, adalah amsalnya.
Suatu kali Bung Karno meminta kepada Sudjojono, agar seniman-
seniman memproduksi poster perjuangan. Sudjojono
mendelegasikan tugas ini kepada pimpinan Balai Pustaka, sebagai
pihak yang bisa menangani grafis. Pimpinan Balai Pustaka lalu
meminta Affandi untuk menggambar posternya. Affandi pun meminta
Dullah untuk jadi modelnya: pejuang perkasa yang sedang berteriak
membahana dengan tangan menjotos angkasa. Poster yang diberi
teks "Boeng Ajo Boeng!" oleh penyair Chairil Anwar itu kemudian
digandakan oleh Baharrudin MS, Abdul Salam dan lain-lain, untuk
kemudian disebarkan ke antero wilayah perjuangan.
Bung Karno terpana melihat poster yang provokatif itu. Dan ia lantas
bertanya kepada Sudjojono, siapa yang jadi model. Sudjojono tentu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karn...ukis%20Istana%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 8)4/3/2005 11:04:57 AM
Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana -- Jumat, 1 Juni 2001
menjawab: Dullah. Begitu mendengar nama Dullah, Bung Karno
tergelak-gelak.
"Dullah? Belanda pasti tidak menyangka bahwa model dalam poster
itu orangnya kecil. Kecil!"
Indonesia Merdeka. Bung Karno menjadi Presiden RI pertama.
Urusan politik memang menjadi prioritas. Namun, rasa cintanya
kepada seni, terutama seni lukis, sungguh tak bisa ditinggalkan. Dan
karena dirinya merasa tak mungkin lagi pelukis-meski sesungguhnya
ini cita-cita Bung Karno sejak muda-ia mulai berkonsentrasi jadi
pengumpul lukisan. Ia ingin jadi kolektor sejati. Bukankah
mengumpulkan lukisan adalah manifestasi dari apresiasi mendalam
atas seni? Dan bukankah apresiasi yang mendalam merupakan
katarsis? Bung Karno memang menganggap seni sebagai "api
penyucian".
Berkenaan dengan dunia mengoleksi itu ia melihat Istana
Kepresidenan bisa menjadi wahana. Bung Karno memperlihatkan
keinginannya agar Istana Kepresidenan tak sekadar jadi rumah
politik, tapi juga rumah seni yang merefleksikan hati sebuah bangsa.
Dari sini lantas timbullah hasrat mengangkat pelukis Istana. Pada
saat itulah ia teringat nama Dullah, si kecil model poster, yang juga
dikenal sebagai pelukis gagah berani dalam Agresi Militer II di
Yogyakarta 1948. Dullah pun dipanggil. Bagi Dullah, ini adalah
jabatan yang sangat mengagetkan, dan membuat dirinya shock
berhari-hari.
"Alea jacta east! Dadu pertaruhan sudah kulemparkan. Dan kau
harus menerima, Dullah", kata Bung Karno seolah meniru Julius
Caesar.
Namun, bekerja di Istana Presiden Soekarno ternyata tidak
senyaman yang dibayangkan. Tuntutan Bung Karno atas keindahan
Istana sangat kompleks. Dullah harus membenahi ratusan lukisan
koleksi Bung Karno yang sudah ada. Untuk kemudian menyeleksi,
memajang di dinding-dinding Istana Negara, Istana Merdeka,
Gedung Agung Yogyakarta, Istana Bogor, sampai Istana
Tampaksiring. Merestorasi lukisan-lukisan yang luka. Lalu
mendisplai lagi dan seterusnya. Di luar itu, Dullah sering diajak Bung
Karno mencari lukisan, mendekati pelukis, berdiskusi seni. Bahkan
berjalan jauh di luar Istana sambil membahas upaya penghormatan
atas keindahan alam, seperti pembangunan gazebo di bukit
Kintamani...
Sepuluh tahun berjalan, pada 1960 Dullah minta diri keluar dari
Istana. Ia ingin jadi pelukis bebas. Bung Karno terperangah, sambil
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karn...ukis%20Istana%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 8)4/3/2005 11:04:57 AM
Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana -- Jumat, 1 Juni 2001
bertanya.
"Kurang opo tho kowe?" (Kurang apa kamu?)
Dullah tak menjawab. Pokoknya ia minta keluar. Sampai akhirnya
Bung Karno berkata lanjut.
"Saiki aku ngerti. Kowe ora kurang opo-opo. Mung kurang
ajar!" (Sekarang aku mengerti. Kamu tidak kurang apa-apa. Hanya
kurang ajar!"), kata Bung Karno sambil menepuk-nepuk pundak
Dullah. Dullah melihat, mata Bung Karno berkaca-kaca.
"Bila dihadapkan pada soal-soal yang politis, Bapak dengan sigap
akan menangkis. Namun, jika dibelitkan problem seni lukis, Bapak
serta merta menangis", kenang Dullah.
TENTU Dullah tidak meninggalkan Bung Karno begitu saja. Ia
mengusulkan agar pelukis Lee Man-fong diangkat untuk
menggantikannya. Bung Karno setuju.
Lee Man-fong adalah pelukis kelahiran Guangzhou, Cina, tahun
1913. Ayahnya, seorang pedagang dengan 10 anak, membawanya
ke Singapura. Ketika ayahnya meninggal tahun 1930, Man-fong
harus bekerja keras menghidupi Ibu dan adik-adiknya.
Kepandaiannya dalam menggambar advertensi dan melukis
digunakan sebaik-baiknya. Namun bekerja di Singapura dirasanya
tak cukup. Tahun 1932 ia berlabuh di Jakarta, dan mencoba
peruntungannya sekuat tenaga. Jakarta ternyata tempat yang bisa
memenuhkan hasratnya sebagai seniman. Iklim kesenirupaannya
bagus. Ketegangan antara kelompok nasionalis semacam Persagi
(Persatuan Ahli-ahli Gambar Indonesia) dan komunitas kunstkring
Hindia Belanda menurut dia merangsang kreasi dan elan vital.
"Saya suka Indonesia," itulah kata-kata yang sering diucapkan.
Karena itu, ketika Jepang ekspansi dan menjajah Indonesia, Man-
fong ikut berteriak menolak. Sampai akhirnya ia masuk penjara,
1942, dan siap disiksa. Untung ia ditolong oleh Takahashi Masao,
seorang opsir yang bertugas membuat ikebana untuk para sipir.
Masao tertarik kepada potensi artistik Man-fong selama dalam
tahanan. Namun begitu, tak kurang dari enam bulan pelukis serba
bisa ini meringkuk dalam bui.
Tahun 1946, Bung Karno mulai mendengar nama Lee Man-fong,
ketika si pelukis berpameran tunggal di Jakarta. Bahkan, Bung Karno
selintas tahu bahwa Man-fong akhirnya memperoleh beasiswa
Malino dari petinggi Belanda, Van Mook. Di Eropa, Man-fong
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karn...ukis%20Istana%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 8)4/3/2005 11:04:57 AM
Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana -- Jumat, 1 Juni 2001
memperoleh sukses lewat berbagai pameran. Kembali ke Indonesia
sebentar, dan lantas berangkat lagi untuk bikin pergelaran, dari Den
Haag sampai Paris.
Tahun 1952, Man-fong balik hidup di Jakarta. Bung Karno semakin
terpikat kepadanya. Lalu, bersama Dullah ia mengunjungi pelukis ini
di rumahnya di Jalan Gedong, Jakarta. Spirit Man-fong semakin
terpicu. Seni lukis bagi Man-fong tak lagi cuma alat ekspresi
individual, namun juga sebagai perabot yang membantu sebuah
pengabdian. Lantaran
itulah pada tahun 1955 ia lalu mendirikan perkumpulan Yin Hua.
Organisasi ini mengumpulkan para pelukis Tionghoa. Yin Hua, yang
bermarkas di Lokasari, Jakarta Kota, sering mengadakan pameran.
Dan Bung Karno tidak lupa mengunjungi. Bahkan, ketika seni lukis
Yin Hua bertandang ke Tiongkok tahun 1956, dan Man-fong
bertindak sebagai ketua delegasi, Bung Karno dengan salut
merestui.
Hubungan Bung Karno dan Man-fong terjalin baik. Lukisan Man-fong
yang perfek, manis, teknis, estetik dan justru terbebas dari
paradigma gelora perjuangan, sangat selaras dengan jiwa seni Bung
Karno. Karya-karya Man-fong dipandangnya sebagai ventilasi dari
kesibukan revolusi. Memang, sang presiden memiliki pandangan
tidak terbelenggu kepada tema tertentu. Hal ini terdata di kemudian
hari, bahwa tema perjuangan ternyata hanya mencakup tak lebih
dari 10 persen belaka dari seluruh koleksinya yang beribu-ribu.
"A thing of beauty is a joy forever", adalah ucapan yang sering keluar
dari bibir Bung Karno. Itu sebabnya lukisan wanita cantik, alam
benda yang elok, pemandangan yang tenteram, sudut kampung
yang adem, sangat membahagiakannya. Singkat kata, riwayat,
pribadi dan karya-karya Man-fong cocok dengan Bung Karno.
Hingga usulan Dullah agar Man-fong menggantikannya jadi pelukis
Istana, diterimanya dengan sukacita.
TAHUN 1961, Lee Man-fong diangkat resmi. Dan sejak itu pula ia
yang tadinya masih warga negara Tiongkok, menjadi warga negara
Indonesia. Namun, Man-fong sesungguhnya bukanlah orang
kantoran. Lingkungan Istana yang protokoler, punya jam kerja, serta
harus 'menurut' Sang Bapak, sungguh bukan pekerjaan mudah
baginya. Man-fong lantas membawa sahabatnya, Lim Wasim, dan
diusulkan jadi asistennya. Bung Karno tidak menolak.
Lim Wasim adalah pelukis kelahiran Bandung 1929. Ia pernah
belajar kepada Mochtar Apin, Abedy dan Sudjana Kerton. Dan
kemudian melanjutkan belajarnya di Chang Yang I Shu Xue Yuan
atau Institut Seni Sentral Beijing tahun 1950. Dan, pada tahun 1956,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karn...ukis%20Istana%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 8)4/3/2005 11:04:57 AM
Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana -- Jumat, 1 Juni 2001
ia mengajar di Xian I Shu Xue Yuan, atau Institut Seni Provinsi Xian.
Tahun 1959, kembali ke Indonesia.
Bung Karno sendiri telah mengenal Wasim beberapa bulan
sebelumnya. Waktu itu, 1960, Wasim sedang membantu Man-fong
mengerjakan mural (lukisan dinding) Puspita dan Margasatwa di
Hotel Indonesia. Hotel ini, atas instruksi Bung Karno sedang dikemas
rapi untuk menyambut Asian Games IV, Jakarta.
Di Istana Presiden, Man-fong mendapat gaji Rp 5.000 sebulan.
Sedangkan Wasim Rp 4.000. Gaji ini sama dengan empat hari
Wasim bekerja di sanggar Tjio Tek Djien, yang terletak di kawasan
Cideng, Jakarta. Sebuah studio seni yang menstimulasi para pelukis
untuk berkreasi, yang pendiriannya atas dorongan Bung Karno pula.
"Bekerja untuk Bapak sama dengan sekolah mencintai seni.
Lantaran itu saya tak pernah memikirkan gaji," kata Wasim.
Di Istana Wasim ternyata jauh lebih aktif dari Man-fong. Dan itu
sudah diramalkan. Tugas Wasim seperti juga kerja utama Dullah
dulu. Di antaranya yang paling membanggakan adalah tugas melukis
sosok Bung Karno untuk dibawa Presiden ke luar negeri. Karena
banyak kepala negara yang meminta gambar "Bung Karno Sang
Kolektor" sebagai kenang-kenangan.
Ketika Bung Karno turun dari kekuasaan awal tahun 1966, koleksi
yang ada sekitar 2.300 bingkai. Jumlah yang bukan main! Bahkan
ada yang menyebut, inilah koleksi lukisan terbesar seorang Presiden
di seputar Bumi, kala itu. Dan ketika kekisruhan politik dimulai, apa
boleh buat, Lee Man-fong yang tak berpolitik terpaksa "lari" ke
Singapura. Dullah selama beberapa tahun berdiam diri di rumah,
lantaran diincar sebagai Soekarnois. Dan Lim Wasim?
"Syukur saya tetap dipertahankan di Istana sampai tahun 1968. Tapi
dengan pekerjaan yang tak jelas. Dan tiap pagi harus apel, tiap kali
harus lapor," kisahnya.
Hasil pengabdian para pelukis Istana itu dinampakkan lewat buku
monumental Lukisan-lukisan dan Patung-patung Koleksi Presiden
Sukarno. Yang pertama disusun Dullah, terbit dalam 2 jilid tahun
1956. Dan disusul dua jilid berikutnya 1961. Buku ini disempurnakan
oleh Lee Man-fong, dan terbit 1964 dalam lima jilid. Lalu jilid VI
sampai X disusun oleh Lim Wasim, yang rencananya diluncurkan
pada ulang tahun Bung Karno 6 Juni 1966. Sayang kekacauan politik
meledak, dan proyek prestisius yang sudah sampai tahap blue print
itu batal.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karn...ukis%20Istana%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 8)4/3/2005 11:04:57 AM
Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana -- Jumat, 1 Juni 2001
Pada 20 Juni 1970 Bung Karno wafat. Banyak orang mengatakan
bahwa Bung Karno pergi karena sakit fisik lantaran politik. Namun
tiga pelukis Istananya memperkirakan, Bung Karno wafat karena
dirundung "kesedihan lukisan". Bayangkan, selama lebih dari 40
bulan Bung Karno dipisahkan dengan koleksi seninya. Dan itu
adalah ribuan anak-anak emasnya, buah-buah spiritualnya, yang
diburu dan dipeluk selama duapertiga hidupnya!
* Agus Dermawan T Penyusun buku Dullah, Lee Man-fong, Lim
Wasim, dan Koleksi Istana Presiden RI.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
● Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Bung%20Karn...ukis%20Istana%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 8)4/3/2005 11:04:57 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
Julius Pour
"BANYAK suami menilai istrinya
bagaikan mutiara. Tetapi sebenarnya,
mereka justru merusak dan tidak
menghargai kebahagiaan istrinya?
Mereka memuliakan istrinya, mereka
cintai sebagai barang berharga, mereka
anggap 'mutiara', tetapi sebagaimana
orang selalu menyimpan mutiara di
dalam kotak, demikian pula mereka
menyimpan istrinya dalam kurungan atau
'pingitan'. Bukan untuk
memperbudaknya, bukan untuk
menghinanya, bukan untuk
Inggit Garnasih merendahkannya, begitu katanya.
Melainkan untuk menjaga, untuk
menghormati, untuk memuliakan.
Perempuan mereka anggap sebagai
Dewi, tetapi selalu mereka jaga, awasi
dan selalu 'dibantu' sehingga menjadi
insan yang sampai mati justru tidak akan
pernah
bisa menjadi dewasa"Hal ini
dikemukakan Soekarno dalam Sarinah,
buku yang secara rinci mengemukakan
pandangan Bung Karno terhadap
perempuan. Bahwa mereka, adalah
bagian mutlak perjuangan kemerdekaan,
oleh karena itu peran sertanya sejajar
Fatmawati
dan sangat dibutuhkan.
Sarinah diterbitkan di Yogyakarta tahun
1947, di tengah perang kemerdekaan.
Tetapi yang menarik, buku tersebut
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
sengaja ditulis Bung Karno. Sementara
kita tahu, hampir semua karyanya pada
umumnya berasal dari transkrip pidato
dan jarang yang sengaja dipersiapkan
sebagai buku. "Atas permintaan banyak
orang, apa yang pernah saya kursuskan,
kemudian saya tulis dan saya lengkapi,
Sarinah inilah hasilnya," katanya dalam
pengantar buku.
Awal tahun 1946, akibat tekanan politis
dari Pemerintah Belanda yang tidak
menghendaki bekas jajahannya merdeka,
Dewi Pemerintah Republik terpaksa
mengungsi dari Jakarta. Dan di Yogya,
setiap dua minggu sekali, Bung Karno
menyelenggarakan kursus wanita di
ruang belakang Istana Kepresidenan.
Bahan-bahan kursus, dengan bantuan
Mualliff Nasution, sekretaris pribadinya,
dikumpulkan, dilengkapi, dan ditulis ulang
oleh Bung Karno, dipersiapkan menjadi
buku.
Bahwa judul bukunya demikian,
alasannya sederhana. "Saya namakan
Sarinah, sebagai tanda terima kasih.
Yurike Sanger
Ketika masih kanak-kanak, pengasuh
saya bernama Sarinah. Ia mbok saya. Ia
membantu Ibu saya, dan dari dia saya
telah menerima rasa cinta dan rasa
kasih. Dari dia saya menerima pelajaran
untuk mencintai orang kecil. Dia sendiri
orang kecil, tetapi budinya besar.
Semoga Tuhan membalas kebaikannya."
Sarinah hadir dalam kehidupan Bung
Karno sejak tinggal di Mojokerto, Jawa
Timur, pertengahan tahun 1917.
Sebagaimana dikisahkan melalui
Haryati Sukarno, An Autobiography as Told to
Cindy Adams, dia dilahirkan di Surabaya
(1901) dengan nama Kusno. Oleh karena sejak kecil sering sakit,
sesuai kebiasaan setempat, ayahnya mencari nama baru, Soekarno.
"Karena itu, Soekarno menjadi namaku sebenarnya dan satu-
satunya. Pernah ada wartawan goblok menulis nama awalku Ahmad.
Sungguh menggelikan. Namaku hanya Soekarno. Dan memang,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
dalam masyarakat kami, tidak luar biasa memakai satu nama.
Di Mojokerto, Bung Karno kecil tinggal bersama ayahnya, seorang
guru, Raden Soekemi Sosrodihardjo. Ibunya, Ida Ajoe Njoman Rai,
keturunan bangsawan Bali, dan Sukarmini kakak kandungnya yang
dua tahun lebih tua. Sesudah beberapa waktu, datang orang kelima,
sosok yang disebutnya, "Bagian rumah tangga kami. Dia tidak
pernah kawin, tidur dengan kami, makan apa yang kami makan,
tetapi tidak mendapat gaji sepeser pun. Dialah yang mengajarku
untuk mengenal cinta kasih, tetapi bukan dalam pengertian
jasmaniah. Dan mulai mengajarku mencintai rakyat."
Dengan nada plastis yang digemarinya, Bung Karno melukiskan,
"Selagi Sarinah memasak di gubuk kecil dekat rumah, aku selalu
duduk di sampingnya. Dia kemudian mengatakan, Karno, yang
terutama engkau harus mencintai ibumu. Akan tetapi kemudian
engkau harus mencintai rakyat jelata. Engkau harus mencintai
manusia pada umumnya."
Bung Karno menambahkan, "Sarinah adalah nama biasa. Akan
tetapi, Sarinah yang ini bukan wanita biasa. Ia adalah satu
kekuasaan yang paling besar dalam hidupku."
Kurang kasih sayang ibu
Sangat menarik mencermati kedekatan Bung Karno dengan ibunya,
sebagaimana pernah dipesankan Sarinah. Ternyata, tidak ada buku
atau tulisan yang khusus dipersembahkan Bung Karno kepada
ibunya. Dalam otobiografinya, namanya hanya sepintas disebutkan,
memberikan pangestu sewaktu Bung Karno masih kecil. Selain itu,
sebelum tidur, sering menceriterakan kisah kepahlawanan. Dan
semasa perang kemerdekaan, menghardik para gerilyawan yang
mencoba menghindari pertempuran.
Bagaimana sesungguhnya keakraban Bung Karno dengan ibunya,
dan dengan begitu penghargaannya kepada kaum wanita, sempat
menumbuhkan beragam analisis. Kita bisa saja berspekulasi, oleh
karena terlampau diagungkan, sosok Sarinah mungkin hanya
imajiner. Sulit mencari bukti, apakah Sarinah benar-benar ada. Dan
jika demikian, apakah memang begitu besar perannya dalam
membentuk kepribadian Bung Karno?
Prof SI Poeradisastra, dalam kata pengantar buku Kuantar ke
Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno (terbit tahun
1981) pernah mempersoalkan masalah ini. Ada foto Bung Karno
sedang menjumpai ibunya. Dia berlutut di hadapan wanita tua
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
tersebut dengan sangat khidmat. Tetapi, demikian Poeradisastra,
dua hal tetap menjadi pertanyaan.
Pertama, mengapa Ida Ajoe tidak pernah menengok putranya, baik
ke Jakarta maupun ketika masih berada di Yogyakarta? Hal tersebut
tidak dia lakukan, bahkan juga sesudah tahun 1950, sewaktu
kedaulatan Republik Indonesia sudah diakui dunia internasional;
ketika suasana mulai tenang dan Bung Karno telah dikukuhkan (lagi)
sebagai presiden.
Perjalanan ke Jakarta dilakukan hanya saat suaminya wafat di
zaman Jepang. Sedangkan sampai sekitar tahun 1950, sewajarnya
ibu ini belum terlalu sepuh untuk tidak sanggup mengunjungi putra
dan cucunya yang sudah menetap di Istana Negara, Jakarta. Apa
yang sebenarnya terjadi?
Kedua, mengapa sampai ada dua monumen kasih sayang dari Bung
Karno kepada Sarinah? Buku tentang perjuangan kaum wanita, dan
nama toko serba ada pertama di Indonesia. Tetapi, justru tidak ada
kenangan khusus untuk Ida Ajoe Njoman Rai?
Atas dasar dua pertanyaan tersebut, Poeradisastra menarik
kesimpulan, "Bung Karno adalah penderita kekurangan kasih sayang
ibu, sehingga dia akhirnya malah mengidealkan dan mengidolakan
Sarinah, sebagai wanita tua yang sepenuhnya memberikan kasih
sayangnya."
Dalam impian, "kehilangan" sebuah kasih sayang mungkin saja bisa
dipenuhi dengan cara menampilkan sosok Sarinah. Namun, dalam
kenyataan sehari-hari, perasaan "kehilangan" tersebut tampaknya
baru bisa diperoleh sesudah hadir Inggit Garnasih, induk semang
Bung Karno ketika berkuliah di THS Bandung.
Benih cinta pertama
"Aku sangat tertarik kepada gadis-gadis Belanda. Aku ingin sekali
mengadakan hubungan cinta dengan mereka," begitu pernyataan
Bung Karno. Alasannya sangat luas dan mendasar. Sebagai lelaki
tampan yang sejak remaja sangat percaya diri, Bung Karno
mengaku, "Hanya inilah satu-satunya jalan yang kuketahui untuk
bisa memperoleh keunggulan terhadap bangsa kulit putih dan
membikin mereka tunduk kepada kemauanku."
Mungkin saja semua pernyataan tersebut benar. Tetapi juga
mungkin, daya khayal Bung Karno sangat melambung. Oleh karena
dia kemudian mengungkapkan, cinta pertamanya tertuju kepada
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
Pauline Gobee, anak gurunya. Kemudian muncul deretan nama,
semuanya gadis keturunan Belanda, yakni Laura, Raat, Mien
Hessels.
Bagaimanapun, sesuatu yang semula mungkin belum sempat dia
bayangkan, hidup perkawinan justru sudah dimulai Bung Karno
ketika usianya belum genap 20 tahun. Tahun 1921, di Surabaya, dia
menikah dengan Siti Oetari, gadis usia 16 tahun, putri sulung tokoh
Serikat Islam, Haji Oemar Said Tjokroaminoto, pemilik rumah
tempatnya menumpang ketika dia di sekolah lanjutan atas. Beberapa
saat sesudah menikah, Bung Karno meninggalkan Surabaya, pindah
ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.
Tjokroaminoto, ayah mertuanya, membantu mencarikan tempat
indekos dengan menghubungi teman lamanya, Sanusi, seorang
guru.
Bencana sering datang bagai pencuri, mendadak dan tidak terduga.
Begitu Bung Karno tiba di Bandung, dijemput Sanusi di stasiun dan
langsung diajak ke rumahnya, api gairah sudah mulai menyala.
"Sekalipun aku belum memeriksa kamar, tetapi jelas ada keuntungan
tertentu di rumah ini. Keuntungan utama justru berdiri di pintu masuk
dalam sinar setengah gelap. Raut tubuhnya tampak jelas, dikelilingi
oleh cahaya lampu dari arah belakang. Perawakannya kecil,
sekuntum bunga cantik warna merah melekat di sanggul dengan
senyum menyilaukan mata. Namanya Inggit Garnasih, istri Haji
Sanusi."
Menurut Bung Karno, "Segala percikan api yang memancar dari
anak lelaki berumur dua puluh tahun, masih hijau dan belum punya
pengalaman, telah menyambar seorang perempuan dalam umur tiga
puluhan tahun yang matang dan berpengalaman." Percikan gairah
tersebut tidak hanya berhenti membakar Bung Karno. Secara
bersamaan menghanguskan simpul tali perkawinan yang baru satu
tahun dia jalani. Meskipun alasannya, kata Bung Karno, "Oetari dan
aku tidak dapat lebih lama menempati satu tempat tidur, bahkan satu
kamar pun tidak. Jurang antara kami berdua semakin lebar. Sebagai
seseorang yang baru saja kawin, kasih sayangku kepadanya hanya
sebagai kakak."
Siti Oetari dicerai dan dikembalikan kepada Tjokroaminoto.
Sementara itu, menurut Bung Karno, Sanusi adalah seorang tukang
judi yang setiap malam terus-menerus menghabiskan waktunya di
tempat bilyar. Maka mudah diduga apa yang bakal terjadi, "Aku
seorang yang sangat kuat dalam arti jasmaniah dan pada hari-hari
itu belum ada televisi. Hanya Inggit dan aku berada di rumah yang
selalu kosong. Dia kesepian. Aku kesepian. Perkawinannya tidak
betul. Perkawinanku tidak betul. Adalah wajar, hal-hal yang demikian
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
itu kemudian tumbuh".
Apa pun alasannya sehingga mereka berdua menjadi dekat,
Poeradisastra tetap menilai Inggit Garnasih seorang wanita luar
biasa. "Kekasih satu-satunya yang mencintai Soekarno tidak karena
alasan harta dan takhta, yang selalu memberi dan tidak pernah
meminta kembali. Satu-satunya wanita yang bersedia menemani
Soekarno dalam kemiskinan dan kekurangan."
Ditambahkannya, "Saya harus meminta maaf sebesar-besarnya
kepada semua janda Soekarno, dengan segala jasa dan segi
positifnya masing-masing. Tetapi saya harus mengatakan bahwa
hanya Inggit merupakan tiga bentuk dalam satu kepribadian, yakni
ibu, kekasih, dan kawan yang selalu memberi tanpa pernah
meminta. Kekurangannya, Inggit tidak melahirkan anak."
Inggit Garnasih lebih tua 15 tahun dari Bung Karno sehingga lebih
dewasa dalam bersikap ketika menghadapi saat-saat gawat. Wanita
Sunda ini bagaikan induk ayam yang sayapnya selalu siap memberi
perlindungan. Janda cerai selama empat bulan tersebut kemudian
menikah dengan Bung Karno pada pertengahan tahun 1923.
Selama 20 tahun hidup perkawinannya bersama Bung Karno,
dengan setia dia menjenguk suaminya ketika disekap di Penjara
Sukamiskin. Dengan kesetiaan luar biasa mengikuti suaminya
menjalani pengasingan di Flores, sambil mengajak ibu dan dua anak
angkatnya. Asmi, ibu mertua Bung Karno, tutup usia ketika
mendampingi menantunya di tempat pembuangan.
Memulai hidup baru lagi
Ada sebuah kalimat bersayap, hidup dimulai pada usia 40 tahun.
Pada usia tersebut Bung Karno mungkin ingin merintis hidup baru,
dengan memakai alasan sangat mendasar, soal anak.
Dengan kebesaran jiwa yang sulit dicari bandingannya, Inggit
akhirnya menyerahkan Bung Karno kepada Fatmawati, bekas putri
angkatnya dalam masa pembuangan di Bengkulu. Gadis yang
ternyata berani dan bahkan sudah menjalin kasih sayang dengan
ayah angkatnya, dan yang kemudian menjadi istri dari bekas suami
ibu angkatnya.
Bencana dimulai dengan kedatangan Hassan Din bersama istri dan
putrinya, Fatmawati, untuk mencari tempat indekos di Bengkulu.
Secara kebetulan usia anak gadis tersebut sepadan dengan Ratna
Djuami, anak angkat Bung Karno. Maka hari itu juga, Fatmawati
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
langsung ditinggal pulang dan diserahkan pengawasannya kepada
pasangan Bung Karno-Inggit. Pesona Fatmawati dilukiskan oleh
Bung Karno, "Rambutnya seperti sutera di belah tengah dan
menjurai ke belakang berjalin dua. Dengan senang hati aku
menyambutnya sebagai anggota baru keluarga kami." Sesudah
beberapa waktu tinggal bersama, Bung Karno berkomentar, "Aku
senang terhadap Fatmawati. Kuajari dia bermain bulu tangkis. Ia
berjalan-jalan denganku sepanjang tepi pantai yang berpasir,
sementara alunan ombak berbuih putih memukul-mukul mata kaki."
Dalam perjalanan waktu, hubungan mereka semakin bertambah
erat. Meskipun, menurut Bung Karno, "Apa yang ditunjukkan
Fatmawati kepadaku adalah sekadar pemujaan kepahlawanan.
Umurku lebih 20 tahun dari padanya dan dia memanggilku Bapak.
Bagiku dia hanya seorang gadis yang menyenangkan, salah seorang
dari anak-anak yang selalu mengelilingiku untuk menghilangkan
kesepian yang mulai melarut dalam kehidupanku. Yang kuberikan
kepadanya kasih sayang seorang bapak."
Walau disembunyikan, akhirnya Inggit menyadari terjadinya percikan
bunga-bunga cinta. "Aku merasa ada sebuah percintaan sedang
menyala di rumah ini. Sukarno, jangan coba-coba menyembunyikan
diri. Seseorang tidak bisa berbohong dengan sorot matanya."
Bung Karno masih mencoba berkilah, "Jangan begitu. Dia itu tidak
ubahnya seperti anakku sendiri."
Inggit mengingatkan, "Menurut adat kita, perempuan tidak rapat
kepada laki-laki. Kebiasaan anak gadis lebih rapat kepada si ibu,
bukan kepada si bapak. Hati-hatilah, Engkau harus mendudukkan
hal ini menurut cara yang pantas."
Bung Karno kemudian semakin sadar, "Fatmawati sudah menjadi
perempuan cantik. Umurnya sudah 17 tahun dan ada kabar akan
segera dikawinkan. Usia istriku mendekati usia 53 tahun. Aku masih
muda, kuat dan sedang berada pada usia utama dalam kehidupan.
Aku ingin anak, istriku tidak dapat memberikan. Aku menginginkan
kegembiraan hidup, Inggit tidak lagi memikirkan soal-soal demikian"
Menurut versi Bung Karno, dengan cara sopan dia sudah pernah
mengajukan izin untuk bisa menikahi Fatmawati. Dalam buku
Kuantar ke Gerbang, karya Ramadhan KH berdasar wawancara
dengan Inggit Gar-nasih, Bung Karno sambil menahan tangis
bertanya, "Bukankah aku bisa mengawininya, sementara kita tidak
usah bercerai?"
"Oh, dicandung? Ari kudu dicandung mah, cadu. (Oh dimadu? Kalau
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
harus dimadu, pantang aku)," jawab Inggit sengit. "Boleh saja kau
kawin, tetapi ceraikan diriku lebih dulu."
Akhirnya Bung Karno menceraikan Inggit setelah Jepang menduduki
Indonesia dan mereka berdua pulang ke Jawa. Pada bulan Juni
1943, Bung Karno kawin dengan Fatmawati memakai cara nikah
wakil, sebab mempelai putri masih tertinggal di Sumatera. Bulan
November 1944, lahir putra pertama, Mohammad Guntur. Bung
Karno langsung mengucapkan syukur, "Aku tidak sanggup
melukiskan kegembiraan yang diberikan kepadaku. Umurku sudah
43 tahun dan akhirnya, Tuhan Maha Pengasih mengkaruniai kami
seorang anak."
Menyembunyikan nama istri
Dalam autobiografinya yang terbit bulan November 1965 tetapi
dikerjakan Cindy Adams sejak tahun 1963, Bung Karno
mengungkapkan semua kisah perkawinannya, mulai dari Oetari,
Inggit, Fatmawati sampai ke Hartini. Tetapi, melarang
dicantumkannya kisah pernikahan dengan Naoko Nemoto (Maret
1962), Haryati (Mei 1963), dan Yurike Sanger (Agustus 1964).
Nama Dewi dan Haryati baru muncul dalam buku kedua Cindy
Adams, terbit tahun 1967 dengan judul, My Friend the Dictator. Oleh
karena itu buku tersebut juga masih melupakan Yurike Sanger,
pelajar SMA berusia 16 tahun, bekas anggota "pagar ayu" Barisan
Bhinneka Tunggal Ika. Kepada Majalah Swara Kartini, Yurike sempat
mengungkapkan bahwa Bung Karno pernah berjanji kepadanya,
"Adiklah, istri Mas yang terakhir".
Di antara semua pernikahannya, yang kemudian memicu persoalan
justru ketika menikahi Hartini. Wanita asal Ponorogo kelahiran tahun
1924 ini mengungkapkan, bertemu pertama dengan Bung Karno
tahun 1952 di kota tempat tinggalnya, Salatiga, Jawa Tengah.
"Bapak langsung menyatakan sangat tertarik kepada diri saya."
Malahan ketika diberi tahu bahwa sudah punya lima orang anak,
muncul komentar spontan, "Benar, sudah lima orang anak dan masih
tetap secantik ini?"
Cinta pandangan pertama tersebut muncul seketika, dan Bung
Karno menyebutkan, "Aku jatuh cinta kepadanya. Dan kisah
percintaan kami begitu romantis sehingga orang dapat menulis
sebuah buku tersendiri mengenai hal tersebut." Jatuh cinta bisa
terjadi kapan dan di mana saja. Tetapi, yang kemudian menyulut
reaksi pro-kontra, khususnya di kalangan wanita pada masa itu, oleh
karena Bung Karno masih terikat perkawinan dengan Fatmawati,
sementara status Hartini, ibu rumah tangga dengan lima orang anak.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
Suasananya lebih diperburuk oleh karena secara kebetulan Dewan
Perwakilan Rakyat sedang membicarakan Keputusan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 1952 untuk mengatur tunjangan pensiun bagi janda
pegawai negeri. Isu paling utama, bagaimana pembayaran gaji
dilakukan jika istri pegawai negeri lebih dari satu? Isu ini kemudian
mengangkat persoalan, apakah seorang pegawai negeri boleh
mengambil istri baru? Dan kalau diizinkan, bagaimana
persyaratannya?
Dengan munculnya isu itu, sejumlah ormas wanita penentang
keputusan pemerintah melakukan unjuk rasa dan mengirim delegasi
ke berbagai pihak. Termasuk menghadap Presiden Soekarno, yang
saat itu sedang menjalin percintaan backstreet dengan Hartini.
Mereka meminta Presiden memberi teladan dan ikut
memperjuangkan lahirnya sebuah undang-undang perkawinan yang
adil, sebagaimana dulu semangatnya pernah disebutkan Bung Karno
dalam buku Sarinah. Para pimpinan ormas wanita tersebut
mengemukakan, seandainya Presiden menghendaki poligami,
minimal dia wajib untuk mengikuti ketentuan hukum Islam dan harus
meminta persetujuan istri pertama lebih dahulu.
Ketegangan antara Bung Karno dengan ormas-ormas wanita
penentang poligami mencapai puncaknya ketika Fatmawati, berkat
dukungan kuat dari sebagian besar ormas wanita memutuskan
"meninggalkan Istana Negara dan memulai kehidupan baru, terpisah
dari suaminya."
Dilengkapi tekad Bung Karno yang tampaknya sudah tidak bisa
disurutkan, setelah menjalin cinta gelap antara Jakarta-Salatiga,
bulan Juli 1953, Bung Karno menikah dengan Hartini di Istana
Cipanas. Bertindak sebagai wali nikah, oleh karena Bung Karno tidak
bisa hadir, komandan pasukan pengawal pribadi Presiden, Mangil
Martowidjojo.
Bung Karno mengungkapkan, "Fatmawati sangat marah atas
perkawinan ini. Sebetulnya dia tidak perlu marah. Istriku pertama
dan juga yang kedua adalah pemeluk Islam yang saleh serta
menyadari hukum-hukum agama." Ditambahkannya, "Aku tidak
menceraikan Fatma karena anak kami sudah lima orang. Bagi orang
Barat, mengawini istri kedua selalu dianggap tidak beradab, tidak
sopan dan tindakan kejam."
Sayang, Bung Karno ternyata tidak hanya berhenti sampai kepada
istri kedua. Cindy Adams tanpa sengaja bertemu Haryati di Istana
Tampaksiring, Bali, semasa mengikuti kunjungan Presiden Filipina
Diosdado Macapagal. Tampaknya, Haryati waktu itu sudah lebih
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
dulu dikirim ke Bali untuk mendahului rombongan resmi.
Haryati menjelaskan, "Kami menikah di Jakarta bulan Mei 1963 dan
Bapak berpendapat, sangat bijaksana kalau pernikahan ini tidak
usah diumumkan kepada masyarakat luas. Kami berdua saling
mencintai, tetapi menghadapi berbagai kesulitan. Selain itu, Bapak
sudah mempunyai tiga istri dan usianya sekarang 63 tahun,
sedangkan saya baru
23 tahun." Kesulitan semacam ini tidak hanya menimpa Haryati.
Oleh karena situasi serupa juga pernah dijalani Ratnasari Dewi.
Dalam My Friend the Dictator, Dewi mengungkapkan, "Saya
dikenalkan kepada Bapak di Hotel Imperial Tokyo oleh para rekan
bisnis dari Jepang". Pertemuan pertama tersebut membawa kesan
sangat dalam. Tidak lama kemudian, Bung Karno mengundangnya
ke Jakarta, untuk bertamasya selama dua minggu.
Kunjungan tersebut diakhiri dengan perkawinan pada awal Maret
1962, setelah Naoko Nemoto pindah agama dan Bung Karno
memilihkan nama sangat indah, Ratnasari Dewi. Tetapi perkawinan
tersebut membawa korban. Ibu Naoko, seorang janda, kaget dan
langsung meninggal mendengar putrinya menikah dengan orang
asing. Disusul hanya 26 jam sesudahnya, Yaso, saudara lelaki
Naoko, melakukan bunuh diri. "And I was so alone. I had lost my
whole family."
Dewi menjelaskan, "Mengingat situasi serba tidak menguntungkan,
mengambil orang asing sebagai istri baru, maka selama beberapa
waktu pernikahan kami disembunyikan. Saya merasa sangat
tersiksa, harus selalu sendirian dan bersembunyi di rumah. Satu-
satunya kegembiraan, Bapak sangat memperhatikan segala macam
keperluan saya. Bapak menyulutkan rokok saya, Bapak dengan setia
membawakan buah-buahan."
Kelemahan dan kekuatan
Tulisan ini bukan untuk menunjukkan kelemahan kepribadian Bung
Karno sebagai seorang lelaki. Tetapi ingin mengungkapkan betapa
kemudian Bung Karno melupakan pesan Sarinah, semakin berani
menyerempet bahaya, dan bahkan, melalaikan persyaratan aturan
perkawinan menurut hukum Islam. Ketika otobiografi Bung Karno
terbit, para istri Bung Karno kecewa. Hartini sangat marah, sebab
namanya hanya muncul selintas, sedangkan Inggit dan Fatmawati
diceriterakan panjang lebar.
Ratnasari Dewi bahkan sempat mengamuk, hanya karena namanya
sama sekali tidak disebut. Yang justru paling senang dengan buku
tersebut adalah Bung Karno, oleh karena dia langsung
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (10 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
memerintahkan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia.
Tidak ada malaikat di antara manusia, setiap orang memiliki
kelemahan dan kekurangan. Wanita pada satu sisi merupakan titik
lemah Bung Karno, tetapi di sisi lain sesuatu yang mampu
memberikan gairah dan semangat hidup. "I'm a very physical man. I
must have sex every day," katanya dengan kebanggaan meluap
kepada Cindy Adams.
Maka, sebuah kelemahan bisa berubah menjadi kekuatan,
tergantung kepada situasi dan kondisi yang dihadapi. Tetapi ketika
usianya sudah semakin lanjut, dilengkapi keruwetan pribadi akibat
semakin kompleksnya pengaturan jadwal oleh karena yang harus
dikelolanya semakin banyak, ketajaman analisis yang selama ini
dimiliki Bung Karno mulai tumpul.
Akan tetapi, seberapa besar minus nilai Bung Karno sebagai lelaki,
sama sekali tidak menghilangkan perannya sebagai pejuang
kemerdekaan. Dan juga tidak akan melenyapkan sumbangannya
dalam memimpin perjuangan untuk kemerdekaan bangsa dan Tanah
Airnya, Indonesia, yang sangat dicintainya.
Mengamati perjalanan Bung Karno-sebagai akibat masa kecil yang
mungkin kurang bahagia-dia berusaha mengimbangi dengan
mengembangkan daya khayal sangat dahsyat. Khayalan tersebut
tercipta dengan hadirnya sosok Sarinah; seorang wanita yang jauh
lebih tua, lebih matang sekaligus punya kemampuan melindungi dan
memberikan selimut kehangatan kepada batin Bung Karno. Oleh
karena itu menjadi jelas, mengapa perkawinannya dengan Siti Oetari
hanya bertahan kurang dari dua tahun. Kekosongan tersebut
kemudian dipenuhi Inggit Garnasih, wanita sederhana yang rela
mengabdi dengan sepenuh jiwa raganya.
Sering orang mempersoalkan, derita Bung Karno jauh lebih ringan
dibanding para pejuang kemerdekaan Indonesia lainnya. Mereka
diasingkan ke Digul atau Banda, sementara Bung Karno "hanya" ke
Flores dan Bengkulu. Tetapi, di Digul atau Banda, mereka tidak
terpencil, karena ada ratusan atau paling tidak sejumlah rekan lain
dengan semangat dan daya nalar setara. Di sisi lain, Bung Karno
harus tinggal sendirian, tanpa ada teman dengan tingkat intelektual
sepadan di sekitarnya. Sungguh beruntung, dalam kesendirian
tersebut di sampingnya tetap hadir Inggit Garnasih.
Sesudah Inggit terpaksa dan dipaksa surut ke belakang, frekuensi
"ketergelinciran" Bung Karno semakin sering terjadi. Bung Karno
yang merasa tetap perkasa, semakin tua justru semakin tambah
percaya diri. Malahan mungkin merasa tidak memerlukan sayap
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (11 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger -- Jumat, 1 Juni 2001
pelindung, yang selama ini tanpa dia sadari menghangatkan
batinnya.
Ia mengkhayalkan dirinya burung rajawali yang sanggup terbang
sendirian menjelajah angkasa luas. Ia mungkin lupa, dalam
kekosongan jiwa, rajawali tersebut telah merapuh, tidak ubahnya
burung pipit yang selalu harus berusaha mencari perlindungan.
* Julius Pour Wartawan Kompas.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
● Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
● Bung Karno, Seni, dan Saya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dari%20Siti...rike%20Sanger%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (12 of 13)4/3/2005 11:04:58 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian
Nasional
Taufik Abdullah
KALAU sejarah hanyalah one damned thing after another, sudah
pasti hasil usaha rekonstruksi peristiwa masa lalu itu tidak bisa
merangsang terjadinya perdebatan akademis dan politis, bahkan
filosofis. Kalau memang demikian, kita dengan enteng bisa
menghapal tanggal 5 Juli 1959 sebagai saat ketika Presiden
Soekarno mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa UUD
Sementara 1950 tak berlaku lagi dan Indonesia kembali memakai
UUD 1945. Tanggal itu diingat tanpa rangsangan emosional dan
intelektual apa pun. Dalam suasana seperti ini pula kita bisa
menghapal bahwa pada tanggal 10 November 1945 Kota Surabaya
dibom tentara Sekutu secara besar-besaran, dan pada tanggal 19
Desember 1948 tentara Belanda berhasil menduduki Yogyakarta
dan menawan presiden, wakil presiden, dan beberapa orang
anggota kabinet. Semua hanya rentetan peristiwa belaka tanpa
makna apa pun. Semua hanyalah rentetan peristiwa yang datang
dan lewat begitu saja.
Akan tetapi, sayangnya, sejarah tidaklah semata-mata rentetan
peristiwa. Ada patokan atau kriteria tertentu yang menyebabkan
sebuah kejadian tercatat sebagai peristiwa sejarah, dan dari yang
tercatat itu ada pula yang diperlakukan sebagai sesuatu yang
penting. Lebih penting lagi, peristiwa yang dianggap penting itu
kerap kali pula menjadi sasaran berbagai corak penilaian dan
tafsiran. Tingkat significance dari kejadian yang terpilih untuk "masuk
sejarah" itu biasanya dilihat dalam kaitannya dengan kejadian-
kejadian yang terjadi sebelumnya, dan dengan berbagai kejadian
yang kemudian datang menyusul. Jika dianggap penting maka
peristiwa itu pun sering pula dijadikan sebagai batas dari yang
"sebelum" dan yang "sesudah". Kerap kali juga terjadi bahwa
peristiwa yang dianggap "penting" itu dikenakan penilaian dan
tafsiran yang bertolak dari luar sejarah-entah dari praduga teoretis
dan filosofis, atau ideologis-dan malah juga dari kepentingan politik.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (1 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
***
PERDEBATAN tentang makna atau significance peristiwa sejarah
adalah hal biasa, karena orang ingin juga mengambil hikmah dan
kearifan dari peristiwa itu. Setidaknya demikianlah halnya dari sudut
anggapan yang mengatakan sejarah sebagai lukisan dari perilaku
masyarakat dan manusia. Tetapi bukan tak mungkin, dengan
pengajuan sebuah peristiwa sejarah orang ingin mendapatkan
landasan legitimasi bagi klaim politik atau, bisa juga, ideologis. Atau,
kebalikannya, peristiwa itu mungkin pula dipakai sebagai pembuktian
dari sesuatu yang ingin diingkari.
Oleh karena itu, tidak perlu diherankan benar kalau banyak juga
orang yang melihat peristiwa 5 Juli 1959 sebagai awal dari zaman
otoritarianisme dan sentralisme di Tanah Air. Bukankah sejak Dekrit
Presiden itu dikeluarkan lembaga legislatif praktis tidak lagi berdaya
menghadapi kekuasaan eksekutif? Bukankah pula sejak itu
dorongan sentralisasi semakin kuat dan kencang juga? Semakin
kuat pemerintahan, maka semakin kentallah otoritarianisme itu, dan
semakin kuat pula sentralisasi kekuasaan. Hal ini berlanjut sampai
dengan terjadinya lengser keprabon pada bulan Mei 1998 yang lalu.
Sebaliknya, tentu tidak pula perlu dianggap sebagai suatu keanehan
kalau ada juga yang bertahan dengan pendapat bahwa tanggal itu
secara simbolis menandai awal keberhasilan Indonesia untuk
menemukan kembali "kepribadian nasional"-nya.
Pandangan itu bukan saja dikatakan oleh sang pencetus ide
"demokrasi terpimpin", Bung Karno, tetapi juga oleh ilmuwan asing.
Dalam komentar panjangnya tentang buku Herbert Feith (The
Decline of Constitutional Democracy in Indonesia), Harry Benda
praktis beranggapan demikian. Sebab ia mengatakan bahwa
lahirnya Demokrasi Terpimpin bisa dilihat sebagai saat ketika
Indonesia kembali ke jalur sejarahnya yang otentik. Hanya saja
dengan mengatakan ini Benda kelihatannya ingin juga menekankan
bahwa demokrasi bukanlah salah satu ciri dari kebudayaan
Indonesia. Maka jangan heran kalau ada juga peneliti asing yang
menyebut sistem Demokrasi Terpimpin itu sebagai "Mataram Baru".
Namun begitu, kalau ada orang yang lebih suka melihat peristiwa itu
sesuai dengan judul pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959
yang mengatakan bahwa "kembali ke UUD '45" adalah pertanda dari
"the rediscovery of our Revolution", tentu bisa dimaklumi juga.
Kita tidak perlu memperdebatkan tepat atau tidaknya tafsiran yang
beraneka ragam ini. Hanya saja salah satu kecenderungan umum
dalam perdebatan sejarah ialah semakin sering makna sebuah
"peristiwa" diperdebatkan, maka semakin pentinglah tempatnya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (2 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
dalam rekonstruksi sejarah. Kalau telah begini, berbagai pertanyaan
hipotetis dan teoretis biasanya diajukan pula terhadap peristiwa yang
dianggap penting itu. Apakah, umpamanya, peristiwa 5 Juli 1959
sebuah "keharusan sejarah" yang tidak terelakkan? Atau, barangkali,
peristiwa ini sebuah "kecelakaan sejarah", yang tak semestinya
terjadi? Atau, boleh jadi juga peristiwa itu tak lebih daripada contoh
dari pengingkaran konstitusional dari sebuah sistem kekuasaan?
Apa pun mungkin jawab yang diberikan, yang pasti ialah segera
setelah peristiwa itu terjadi proses pembentukan realitas baru pun
bermula pula. Tragis atau bukan, realitas yang terbentuk itu sampai
kini masih mewarnai kehidupan kenegaraan kita.
***
KALAU peristiwa 5 Juli 1959 itu dikaji kembali, maka sebuah
kesimpulan yang tidak terhindarkan ialah bahwa peristiwa itu adalah
klimaks dari rentetan krisis sosial-politik yang semakin mengental
sejak hasil dari dua Pemilu 1955-satu untuk Parlemen dan satu lagi
untuk Konstituante-diumumkan. Apa pun mungkin sifat dari Dekrit
Presiden itu, yang pasti ialah bahwa setelah diumumkan Indonesia
tidak lagi sama dengan keadaan sebelumnya. Peristiwa itu berdiri
sebagai batas simbolis antara tatanan politik yang sebelum dan yang
sesudahnya. Sejak saat itu Soekarno mempunyai kebebasan relatif
untuk mewujudkan kebijaksanaan politiknya, sebagai Kepala Negara
dan Pemerintah.
Ironis mungkin, tetapi sejak itu pula ia lebih bebas mengadakan
intensifikasi dari peranannya sebagai pemimpin bangsa. Secara
konstitusional ia adalah Kepala Negara dari sebuah sistem politik
yang Presidensial dan-sebagaimana ia juga suka mengatakannya-
Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, tetapi ia lebih suka
menyebut dirinya sebagai Penyambung Lidah Rakyat dan Pemimpin
Besar Revolusi.
Maka, apa pun mungkin corak penilaian sejarah atau politik terhadap
Demokrasi Terpimpin, namun secara empiris harus dikatakan juga
bahwa dalam episode ini Soekarno dengan sadar menjadikan dirinya
sebagai perpaduan dari legitimasi konstitusional dengan keharusan
dan kesahihan ideologis. Karena itu, barangkali tidaklah terlalu
berlebihan kalau dikatakan bahwa dari sudut kajian sejarah episode
Demokrasi Terpimpin bisa pula diperlakukan sebagai "laboratorium"
penyelidikan tentang kepemimpinan Soekarno, sebagai Kepala
Negara/Pemerintahan dan sebagai pemimpin bangsa. Bisakah
keduanya saling mendukung? Atau, mungkin saling menjegal? Kalau
seandainya demikian, yang manakah yang lebih keras bersuara?
Saat-saat menjelang Dekrit Presiden 5 Juli adalah salah satu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (3 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
episode yang terpadat dalam sejarah kontemporer kita. Dalam waktu
sekitar dua tahun itu sedemikian banyak peristiwa yang muncul
bertubi-tubi bahkan berhimpitan satu dengan yang lainnya.
Barangkali hanya "masa transisi Habibie" (Mei 1998-Oktober 1999)
yang bisa menyaingi kepadatan episode ini. Semua bermula dari
hasil Pemilu 1955 yang ternyata gagal meletakkan dasar kestabilan
politik. Pemilu ini hanya menghasilkan keseimbangan kekuatan
partai-partai yang bersaingan politik di Parlemen dan yang
bertentangan ideologis di Konstituante. Pemilu ini juga seakan-akan
menunjukkan bahwa secara politik dan ideologis Indonesia terdiri
atas Jawa, yang didominasi oleh Partai Nasional Indonesia (PNI),
Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan luar
Jawa, yang sebagian besar berada di belakang Masyumi. Partai
"modernis Islam" ini bukan saja merupakan satu-satunya partai yang
mendapatkan kursi di semua daerah pemilihan, tetapi juga menjadi
pemenang di sepuluh dari 15 daerah pemilihan.
***
DALAM konteks sistem kenegaraan yang mengharuskan perdebatan
masalah sosial-politik diselesaikan di parlemen dan masalah dasar
negara dan konstitusi di Konstituante, "kekikukan" dalam dinamika
politik tidak terhindarkan. Sebuah partai bisa menemukan
kesesuaian dengan partai lain di parlemen, tetapi berada dalam kubu
yang berbeda di Konstituante atau sebaliknya.
Dalam suasana intensifikasi politik ini Hatta menyadari bahwa ia tak
lagi bisa bekerja sama dengan Soekarno. Ia meletakkan jabatan
sebagai Wakil Presiden (Desember 1956) dan secara simbolis
meniadakan "perwakilan" luar Jawa dalam kepemimpinan puncak
nasional. Kabinet Ali Sastroamidjojo II, yang merupakan koalisi PNI-
Masyumi-NU dan beberapa partai kecil, akhirnya tak bisa menahan
badai politik yang terjadi dalam tubuhnya.
Dalam suasana krisis kabinet ini Presiden Soekarno merasa perlu
untuk menunjuk seorang "warga negara" biasa, yang kebetulan
bernama Soekarno dan kebetulan pula seorang presiden, sebagai
formatur kabinet. Di tengah tudingan tentang terjadinya tindakan
inkonstitusional, kabinet ahli yang dipimpin Djuanda pun terbentuk.
Tetapi perdebatan konstitusional dan politik semakin menaik. Usaha
Kabinet Djuanda untuk mengadakan rekonsiliasi nasional, dengan
mengusahakan kemungkinan kembalinya Hatta ke dalam
pemerintahan gagal berantakan.
Usaha pembunuhan Soekarno di sekolah Cikini bukan saja
menimbulkan tragedi kemanusiaan, tetapi juga peristiwa politik yang
menggagalkan usaha penyatuan "dwitunggal". Konflik Irian Barat
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (4 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
semakin meningkat dengan "diambil-alihnya" perusahaan-
perusahaan Belanda oleh organisasi buruh, yang langsung atau
tidak berafiliasi dengan PKI. Pemerintah pun terpaksa melakukan
nasionalisasi. Maka sekian ribu warga negara Belanda pun
meninggalkan Indonesia, dengan segala kerusakan ekonomi yang
diakibatkannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang melarang keturunan Cina
untuk berdagang di daerah pedesaan bukan saja menyebabkan
terjadinya eksodus mereka-khususnya dari Jawa Barat-tetapi juga
ketegangan RI dengan RRT. Sementara itu konflik daerah-pusat pun
semakin menajam juga. Dalam proses selanjutnya batas-batas
antara hasrat daerah dengan pertentangan politik dan ideologi pun
menjadi kabur, seperti juga menjadi kaburnya batas antara
perdebatan politik dengan teror politik, yang dialami para penentang
"konsepsi Presiden".
Dalam suasana inilah para pembangkang militer di Sumatera
mengeluarkan ultimatum yang menuntut penggantian Kabinet
Djuanda dengan kabinet yang dipimpin oleh Hatta dan/atau Sultan
Hamengku Buwono IX. Penolakan atas ultimatum ini menyebabkan
mereka tidak mempunyai pilihan lain selain dari memproklamasikan
PRRI. Dan Permesta pun segera menyusul. Perkiraan PRRI/
Permesta bahwa pemerintah pusat akhirnya bersedia berunding,
ternyata hanya impian belaka. Operasi militer dilancarkan dan
menjelang pertengahan tahun 1958 sudah kelihatan bahwa
pemerintah tandingan yang berpusat di Sumatera Barat itu tidak lagi
merupakan ancaman yang serius. Sementara itu kekuatan politik
yang beragam-ragam itu mengalami pengentalan, dengan Soekarno
sebagai sumbunya. Maka yang tinggal hanya dua kemungkinan saja,
yaitu pro atau anti-Soekarno.
***
BEGITULAH-untuk memperpendek cerita-ketika akhirnya Presiden
Soekarno terbujuk juga oleh argumen Nasution untuk "kembali ke
UUD 1945", Indonesia telah melalui berbagai corak krisis, mulai dari
hubungan daerah-pusat dan pertentangan partai-partai di pusat
pemerintahan sampai dengan konflik internasional.
Ketika Dekrit 5 Juli dikeluarkan, Soekarno dan TNI AD telah
merupakan kekuatan politik yang paling utama. Konflik presiden dan
TNI yang terjadi dalam "Peristiwa 12 Oktober" (1952) telah
memberikan pada keduanya pelajaran yang sangat berharga.
Dengan ucapannya yang terkenal-"Aku tidak mau jadi diktator"-
presiden menolak tuntutan TNI AD agar membubarkan parlemen,
yang mereka anggap telah terlalu mencampuri urusan internal
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (5 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
militer.
Sejak itu Soekarno semakin menyadari bahwa kedudukannya
sebagai Kepala Negara, yang dikatakan "can do no wrong",
bukanlah peranan yang sesuai bagi dirinya. Sejak itu pula AH
Nasution mulai memikirkan tempat yang sesuai bagi militer dan UUD
yang menjanjikan kestabilan politik. Dengan argumen sejarah ia
mengajukan UUD 1945 dan dengan argumen sejarah juga ia
menemukan "jalan tengah" bagi militer. Kesempatan untuk
mewujudkan itu datang dalam berbagai gejolak radikalisasi politik.
Pengambilalihan beberapa perusahaan Belanda yang dilakukan
buruh menyebabkan pemerintah mengadakan nasionalisasi dan
menugaskan TNI AD untuk menjalankannya. TNI AD mendapat
kesempatan untuk "berkenalan dengan dunia bisnis".
Pemberontakan PRRI/Permesta, yang memancing intervensi asing
sekaligus menaikkan wibawa TNI dan Soekarno. Keberhasilan TNI
mengatasi ancaman PRRI/Permesta dan pelaksanaan SOB, hukum
bahaya perang, bukan saja telah menjadikan TNI AD di bawah
Nasution semakin terkonsolidasi, tetapi juga semakin merupakan
kekuatan politik yang harus diperhitungkan.
Sementara itu, sejak terbentuknya zaken Kabinet Djuanda dan
dibubarkannya Konstituante dan juga parlemen hasil pemilu, partai-
partai mengalami kemunduran yang luar biasa. Liga Demokrasi yang
dilahirkan beberapa tokoh partai sebagai protes terhadap
pembubaran parlemen hanya bisa bertahan sebentar. Masyumi,
partai yang paling "menjengkelkan" Soekarno, dan PSI, dibubarkan
(1960), dengan alasan bahwa ada tokoh dari kedua partai itu terlibat
dalam PRRI/Permesta. Tetapi PKI, yang berada di luar percaturan
elite politik di pusat pemerintahan, karena penolakan partai-partai
lain dan militer, selangkah demi selangkah berhasil menggarap
masyarakat bawah.
Dalam pemilu daerah yang diadakan pada tahun 1957 di Pulau
Jawa, PKI menunjukkan bahwa partai ini telah menjadi yang
terbesar. Lebih penting lagi selama tahun-tahun krisis politik, di
bawah pimpinan yang muda dan pragmatis, PKI berhasil
mendekatkan dirinya dengan Soekarno. Partai ini selalu muncul
sebagai pembela dan pendukung garis politik dan ideologis Presiden
Soekarno. Sebaliknya, betapapun mungkin TNI AD ingin
menghambat gerak maju PKI, presiden selalu tampil sebagai
pembela. Jika perlu Presiden Soekarno bersedia membuka dengan
resmi Kongres PKI yang dihalang-halangi TNI AD.
***
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (6 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
MAKA, demikianlah Demokrasi Terpimpin ditandai dengan semakin
kuatnya kedudukan politik Soekarno, TNI AD, dan PKI. Masalah
yang terberat dihadapi Soekarno ialah menjamin kesetiaan militer,
memelihara dukungan politik PKI, dan menghalangi kemungkinan
terjadinya konflik terbuka antara TNI AD dengan PKI. Bagaimana
keseimbangan dari kedua kekuatan besar ini tanpa membiarkan
salah satu menjadi lemah? Bagaimanapun juga TNI harus
merupakan sebuah kekuatan yang disegani di dalam maupun di luar
negeri. Bukankah perjuangan Irian Barat semakin meningkat?
Bukankah pula ancaman kekuatan anti-revolusioner, sebagaimana
dirumuskan Manipol-USDEK (dokumen politik yang dikatakan
Soekarno sebagai "hadis-nya Pancasila") masih gentayangan?
Sebaliknya PKI bukan saja sebuah kekuatan revolusioner yang
diyakini Soekarno "bisa dijinakkan"-nya, tetapi juga sebuah partai
yang dianggapnya bisa dengan memahami orientasi pemikirannya.
Alasan empiris dari pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli ialah bahwa
Konstituante telah gagal mendapatkan 2/3 suara untuk menentukan
Indonesia kembali ke UUD 1945. Tetapi dalam pidatonya yang
terkenal, The Discovery of Our Revolution, yang disampaikan pada
peringatan ulang tahun kemerdekaan kelihatan bahwa ada dua
alasan utama, yang sejak lama telah menjadi obsesi Bung Karno.
Pertama, bahwa demokrasi liberal bertentangan dengan
"kepribadian nasional". Dalam pidatonya, ia menekankan kembali
pidatonya di hari kemerdekaan 1957. "Demokrasi kita adalah
demokrasi, yang"-sambil mengatakannya dalam bahasa
Belanda-"tak meninggalkan apa-apa selain dari kemerdekaan itu
sendiri". Karena itulah demokrasi kita harus bercorak "negara-
sentris, bukan yang membawa orang menjadi ego-sentris atau
kelompok-sentris atau partai-sentris atau kronis-sentris". Maka
demokrasi yang diinginkan adalah yang terpimpin yang sesuai
dengan tradisi luhur bangsa, yaitu "musyawarah dan mufakat".
Kedua, kembali mengulangi tema lamanya ialah "revolusi belum
selesai". Tema inilah yang paling keras mengental dalam pidatonya
ini. "Inilah logika revolusi", kata Bung Karno, "sekali telah kita mulai
kita harus melanjutkannya sampai semua cita-citanya terwujud. Ini
adalah hukum mutlak dari revolusi, yang tak bisa dibantah, tak bisa
diperdebatkan lagi. Karena itu jangan katakan 'Revolusi telah
selesai', padahal revolusi masih terus berjalan". Ia pun menegaskan
juga revolusi Indonesia yang "multikompleks" atau-sebagaimana,
katanya, disebut seorang ilmuwan asing-"a summing-up of many
revolutions in one generation" .
Kedua konsep ideologis ini-"revolusi yang multikompleks"-dan
"kepribadian nasional" bukan hal baru, tetapi dikeluarkan sebagai
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (7 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
pendukung dekrit, keduanya bisa berfungsi terobosan terhadap
impas politik. The Discovery of Our Revolution dikeluarkan di saat
wacana ideologis sedang mengalami kebuntuan dan di waktu
perdebatan dasar negara sedang mengalami kemacetan. Tetapi,
meskipun kedua pasang ideologi bisa sangat persuasif bagi mereka
yang telah bosan dengan sistem demokrasi yang semakin mandul,
kedua konsep menunjukkan dengan jelas sikap anti-pluralisme politik
Soekarno.
Pada hakikatnya kedua konsep ini bercorak hegemonik dan anti-
wacana. Bagaimanakah bisa dilawan dengan begitu saja konsep
"kepribadian nasional", betapapun kaburnya, tanpa dibayangi
ancaman tuduhan "tidak nasionalis". Bagaimanakah akan dihadapi
wacana "revolusi belum selesai" tanpa ancaman tuduhan sebagai
reaksioner? Dalam wacana yang semakin hegemonik ini, tidaklah
terlalu sukar untuk menebak golongan masyarakat mana yang telah
mulai kehilangan kepercayaan kepada sistem parlementer yang
terlalu ingin mencampuri semua hal. Tidaklah pula terlalu sukar
untuk memperkirakan, golongan mana atau partai apa yang melihat
kedua pasang wacana itu sebagai wahana yang mungkin
membebaskannya dari keterpencilan pembagian kekuasaan.
***
KONSEP Revolusi Indonesia yang dikatakan sebagai sesuatu yang
"congruent with social conscience of man" dan yang "multikompleks"
itu membagi dunia atas dua kekuatan yang antagonistik dan
mengidentifikasi musuh-musuh revolusi dengan jelas. Dalam
perwujudannya revolusi itu berarti "membongkar", "membangun",
"retooling", "rebuilding" dan "herodening" semuanya.
Diterapkan ke dalam sistem dan perilaku politik maka konsep
tentang revolusi ini memberikan kepada TNI suasana yang
congenial, sesuai, bagi klaim sejarah mereka. Ajukanlah pertanyaan
yang heroik tentang revolusi nasional, maka siapakah yang akan
diuntungkan secara ideologis? Setelah para pemimpin Republik
ditawan Belanda, siapakah yang melanjutkan perjuangan, kalau
bukan TNI? Bukankah pula TNI selalu mengatakan bahwa mereka
berasal dari rakyat, dan karenanya akan selamanya menghirup nilai
yang hidup di kalangan rakyat. Jadi, mengapa tidak mereka
menyokong konsep "kepribadian bangsa"? Bagaimanapun Bung
Karno bukan saja seorang pemimpin bangsa dan ideolog, ia adalah
pula Presiden/Panglima Tertinggi. Kalau demikian, sang Presiden
pun mempunyai sekian peralatan kekuatan untuk menjaga jangan
sampai kesetiaan TNI kepada panglimanya berkurang.
Bagi PKI "revolusi" adalah jalan yang harus ditempuh untuk
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (8 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
mewujudkan masyarakat tanpa-kelas, sebagaimana diajarkan
marxisme-leninisme. Maka, terlepas dari latar belakang sosial Bung
Karno yang "borjuis", PKI bisa melihat bahwa ajarannya sejajar
dengan faham yang telah mereka anut. Bukankah Bung Karno
berkali-kali mengatakan ia adalah penganut Marxist, meskipun
bukan dalam pengertian ideologi dan filsafat, tetapi sebagai
landasan teori sejarah dan sosial. Jika Manifesto Politik merumuskan
makna revolusi, menunjukkan lawan dan kawan revolusi, dan
sebagainya, maka USDEK berarti UUD 1945, Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian
Nasional.
Jadi, USDEK bisa juga dilihat PKI sebagai "nasionalisasi" dari
keprihatinan ideologis mereka. Apalagi Bung Karno adalah juga
seorang Presiden yang sewaktu-waktu bisa memberikan
perlindungan politik dan hukum bagi kehadiran dan aktivitas partai
ini. Maka bisalah dipahami kalau PKI melihat Soekarno sebagai
"pelindung" dan menyebutnya sebagai "aspek pro-rakyat" dalam
pemerintahan. Aidit bahkan membuat hipotesa sejarah, jika
seandainya Bung Karno yang berkuasa (bukannya Hatta) di tahun
1948, maka "peristiwa provokasi Madiun" tidak akan terjadi. Ia pun
mengatakan pula bahwa Bung Karno adalah gurunya dalam
marxisme-leninisme.
Salah satu kelemahan dari ideologi yang bersifat hegemonik dan
antiwacana ialah pengikutnya cenderung membuat interpretasi
sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sifat anti-wacana yang
terlekat itu dengan mudah menutup pintu bagi pengujian terbuka
keabsahan interpretasi.
Dalam situasi ini hanya ucapan sang "Nabi" yang menjadi ukuran
keabsahan. Mestikah diherankan kalau dalam persaingan untuk
mendekati Soekarno, Presiden dan Pemimpin Besar Revolusi,
perbedaan penafsiran semakin lama semakin membesar juga. Kalau
telah begini benih-benih konflik terbuka semakin tumbuh juga. Maka
kalau perbedaan penafsiran ini dikenakan ke lapangan politik, maka
kemungkinan terjadinya tabrakan kepentingan semakin tak
terelakkan. Tanpa disadarinya, Soekarno telah menjadi satu-satunya
penyangga dari konflik terbuka antara TNI AD, yang diejek PKI
sebagai "kapitalis birokrat/kabir" (karena keterlibatannya dalam
bisnis), dengan partai yang telah mendapat kehormatan sebagai
unsur "kom" dari pilar politik Demokrasi Terpimpin, Nasakom. Ketika
sang penyangga itu goyah, maka semua hambatan pun mencair.
Sedemikian mencairnya hambatan itu, seakan-akan analogi literer
Hatta bahwa Soekarno adalah kebalikan dari Mephistopheles (tokoh
dalam drama Goethe, Faust), kekuatan jahat yang mendatangkan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pre...i,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (9 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional -- Jumat, 1 Juni 2001
kebaikan, terwujud dalam kenyataan empiris yang prosais. Maka
bersama Soekarno kita pun menangis, karena di hadapan kita telah
terhampar lembaran yang terhitam dalam sejarah Indonesia.
Demikianlah, ternyata memang tanggal 5 Juli 1959 bukan hanya
sebuah tanggal dari terjadinya sebuah peristiwa. Tanggal ini dan
tanggal-tanggal lain yang dicatat sejarah sebagai "penting" bisa
memberi berbagai rangsangan perasaan dan renungan intelektual
tentang nasib bangsa, negara, dan kemanusiaan.
* Taufik Abdullah Sejarawan, Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dekrit%20Pr...,%20dan%20Kepribadian%20Nasional%20--%20Jumat.htm (10 of 11)4/3/2005 11:05:00 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Desoekarnoisasi: Delegitimasi yang Tak Tuntas
Agus Sudibyo
TAHUN 1996,
Soeharto gelisah. Ia
ingin Golkar menang
besar dalam Pemilu
1997, namun tak bisa
menutup mata dari
perkembangan yang
terjadi di tubuh Partai
Demokrasi Indonesia
(PDI). Saat itu,
semakin nyata bahwa
PDI menjadi tempat
berlabuh bagi
kerinduan terhadap
figur Soekarno dan
segala rupa
kekecewaan terhadap
rezim Orde Baru.
Maka Soeharto pun
mengambil jalan
pintas, memadamkan
pengaruh simbol-
simbol Soekarno di
Kompas/kartono ryadi tubuh PDI sebelum
pemilu berlangsung.
Sebuah kongres partai
yang prematur kemudian direkayasa, dan tergusurlah Megawati dari
pucuk pimpinan partai berlambang kepala banteng itu. Tak lama
kemudian, meletus Tragedi 27 Juli 1996 yang akhirnya justru
menjadi titik balik dari kebangkrutan rezim Orde Baru.
Ini bukan yang pertama kali rezim Orde Baru berusaha
memadamkan pengaruh Soekarno. Hubungan antara Orde Baru
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (1 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
dengan Soekarno memang hubungan yang menarik. Sejak awal
kepemimpinannya, Soeharto memandang faktor Soekarno sebagai
ancaman bagi legitimasi kekuasaannya. Soeharto bukan hanya
memaksa Soekarno untuk turun dari kekuasaan, namun juga
menggusur kekuatan-kekuatan soekarnois dari panggung
pemerintahan dan militer.
Uniknya, setelah Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970, situasi
tidak semakin membaik bagi Orde Baru. Jasad yang tak berdaya itu
justru meninggalkan pengaruh yang semakin merepotkan Orde Baru.
Soekarno sebagai institusi politik, ideologi dan sebagai dramatic-
person dalam memori kolektif bangsa Indonesia seakan-akan
menjadi hantu yang membuat penguasa Orde Baru tak pernah tidur
nyenyak. Maka tak henti-hentinya dilakukan usaha untuk memutus
mata rantai pengaruh Soekarno dalam kehidupan birokrasi, militer,
serta dalam kehidupan masyarakat. Segala sesuatu yang berbau
Soekarno selalu dicurigai, ditekan, bahkan kalau perlu diberangus.
Rezim Orde Baru secara sistematis dan kontinu menggunakan
perangkat-perangkat kekuasaannya untuk melakukan apa yang
disebut sebagai desoekarnoisasi.
Karantina politik
Soekarno meninggal dalam status tahanan rumah. Sungguh tragis
nasib Sang Proklamator ini di pengujung hidupnya. Ia digiring dalam
sebuah karantina politik, diasingkan dari berbagai hal yang
membuatnya merasa bermakna, yakni anak-istri, teman seiring,
pengikut-pengikut setia, kerumunan massa dan pidato-pidato yang
menggairahkan. Bahkan, untuk sekadar menyalurkan hobi berjalan-
jalan dan membaca surat kabar pun Soekarno sempat tak diizinkan.
Seperti yang telah diwasiatkan almarhum, keluarga Soekarno
hendak memakamkan almarhum di Batu Tulis, Bogor. Namun,
sebagai penguasa Orde Baru, Soeharto berkehendak lain. Bagi
Soeharto, Bogor terlalu dekat dengan Jakarta dan pemakaman Bung
Karno di sana dikhawatirkan suatu hari dapat menimbulkan dampak
negatif bagi Orde Baru. Soeharto juga menolak usul pemakaman
Bung Karno di taman makam pahlawan di Jakarta. Blitar, nun jauh di
sana, tempat asal orangtua Bung Karno, dianggap "aman" untuk
memakamkan Putra Sang Fajar.
Upacara pemakaman Soekarno dilaksanakan dengan sederhana
dan singkat. Teks pidato pemerintah yang dibacakan Jenderal M
Panggabean dibuat sedapat mungkin seimbang dalam
menggambarkan kebaikan dan keburukan Bung Karno. Namun,
Soeharto juga menunjukkan penghormatannya terhadap Soekarno
dengan mengumumkan hari berkabung nasional, sekaligus
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (2 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
menggelar upacara pemakaman secara militer.
Dalam hal ini, Soeharto tampak sangat hati-hati dan
memperhitungkan benar dampak keputusan yang diambilnya pada
momentum kematian Soekarno. Soeharto sadar masyarakat masih
banyak yang mengidolakan Soekarno, dan dalam kondisi seperti ini,
mengontrol secara ketat proses pemakaman Soekarno dapat
menimbulkan gejolak yang tidak menguntungkan. Prioritas Soeharto
lebih pada upaya menghindari situasi eksplosif yang bisa muncul
akibat suasana emosional di kalangan pendukung Soekarno.
Dengan kata lain, Soeharto berusaha untuk mengontrol sekaligus
menghormati pengaruh Bung Karno, sebuah taktik yang
dipertahankan selama memimpin Orde Baru.
Prediksi Soeharto akan situasi eksplosif itu cukup masuk akal.
Kematian Soekarno begitu menggemparkan masyarakat. Ribuan
orang berbondong-bondong untuk memberi penghormatan terakhir
bagi Soekarno. Media massa memberitakan bagaimana ratusan ribu
manusia menyemut di jalan-jalan yang dilalui rombongan jenazah
Bung Karno dari Lapangan Udara Bugis Malang, menuju Kota Blitar,
Jawa Timur. Harian Kompas (22/6/1970) menggambarkan Kota
Blitar yang kecil dan sederhana mendadak sontak menjadi penuh
sesak oleh manusia. Orang-orang dari berbagai daerah datang
dengan menggunakan mobil, truk, angkutan umum, sepeda motor,
sepeda bahkan berjalan kaki untuk menyaksikan pemakaman
Soekarno.
Meskipun demikian, masyarakat sesungguhnya menyambut
kematian Soekarno dengan gamang. Situasi politik waktu itu
membuat masyarakat tidak berani terang-terangan mengekspresikan
kesedihan atas meninggalnya Soekarno. Meskipun telah diumumkan
hari berkabung nasional, masyarakat Blitar baru berani mengibarkan
bendera setengah tiang setelah ada instruksi dari Gubernur Jawa
Timur M Noer. Mereka berani keluar rumah, bergerombol dan
memperbincangkan apa yang terjadi setelah orang-orang dari luar
daerah berdatangan untuk menyaksikan pemakaman Soekarno.
(Kompas, 23/06/70)
Suasana serupa juga terjadi di Jakarta. Warta Minggu (5/7/70)
memberitakan sedikit sekali pejabat tinggi, pemimpin masyarakat,
instansi atau perusahaan yang berani memasang iklan
belasungkawa di surat kabar. Warta Minggu mencatat mereka yang
berani memasang iklan duka cita adalah DPP PNI, DPP IPKI,
Keluarga Yayasan Rehabilitasi Sosial BU NALO, Keluarga
Sudarmoto Djakarta, PT Hotel Indonesia Internasional, Brigdjen H
Sugandhi, DPP Djamiatul Muslimin Indonesia, DPP GMNI, Fraksi
PNI DPR GR dan PPK Kosgoro. "Jang lain2 mungkin 'tidak berani'
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (3 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
pasang iklan, atau tidak melihat keuntungannja jang njata," tulis
Warta Minggu.
Setelah Soekarno wafat, represi terhadap hal-hal yang berbau
Soekarno justru semakin meningkat. Pada awal dekade 1970-an,
diskusi tentang Bung Karno sangat dibatasi. Sebuah larangan tak
resmi diberlakukan terhadap publikasi tulisan-tulisan politik Bung
Karno. Nama presiden pertama Indonesia ini jarang, atau bahkan
tidak pernah sama sekali, disebut-sebut oleh unsur-unsur rezim Orde
Baru. Meskipun keyakinan bahwa Soekarno adalah perumus
Pancasila begitu mengakar kuat dalam skema pemahaman
mayoritas bangsa Indonesia, referensi yang mengaitkan Bung Karno
dengan Pancasila hampir sepenuhnya diingkari oleh pemerintahan
Orde Baru.
Praktik desoekarnoisasi itu merupakan kontinum dari politik yang
dijalankan Orde Baru pada saat-saat sebelumnya. Konsolidasi politik
pasca-G30S/1965 bukan hanya dilakukan dengan membersihkan
tubuh birokrasi dan militer dari unsur-unsur PKI dan simpatisannya,
namun juga dari unsur-unsur soekarnois. Amputasi politik dalam
skala masif dialami kalangan loyalis Soekarno di berbagai tingkatan
birokrasi dan militer. Ada yang sekadar digeser posisinya, dipecat,
dipenjarakan, bahkan ada yang turut dilenyapkan dalam huru-hara
politik yang penuh darah itu.
Lewat fusi paksa selepas tahun 1973, PNI sebagai simbol
kelembagaan yang paling langsung dari Soekarno, dipaksa
meleburkan diri dalam wadah yang justru lebih sempit, Partai
Demokrasi Indonesia (PDI). Orang-orang PNI yang masih
Soekarnois tak diberi pilihan lain, bahkan teror-teror langsung dan
sistematis dialami aktivis-aktivis PNI di pusat dan terutama sekali di
daerah yang berusaha melakukan perlawanan.
Rezim Orde Baru juga sempat melarang penggunaan gambar dan
simbol Soekarno dalam kampanye Pemilu 1987, meskipun
pelarangan ini terbukti tidak efektif. Pelarangan gambar Soekarno ini
merupakan ekspresi permukaan dari tindakan sistematis rezim Orde
Baru untuk menggunakan status legal-formalnya guna menyudahi
eksistensi Soekarno sebagai ideologi dan institusi politik. Demikian
juga ketika Orde Baru menghalangi usaha Rachmawati Soekarno
untuk mendirikan Universitas Bung Karno tahun 1984. Yang terakhir
dan paling fenomenal, rezim Orde Baru secara kasar menggusur
Megawati Soekarnoputri dari pucuk pimpinan PDI tahun 1996.
Pancasila dan
Bung Karno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (4 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
Khalayak nasional pernah dibikin heboh oleh artikel berjudul Proses
Perumusan Pancasila Dasar Negara di Sinar Harapan, 3 Agustus
1981. Artikel ini ditulis Nugroho Notosusanto yang ketika itu sebagai
Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI. Dalam artikelnya, Nugroho
menyatakan Soekarno bukan orang pertama yang merumuskan lima
prinsip Pancasila. Menurut Nugroho, perumus utama Pancasila
adalah Muhammad Yamin, Supomo, baru kemudian Soekarno.
Peran Soekarno hanyalah dalam hal memunculkan istilah Pancasila.
Bertolak dari premis ini, Nugroho juga menggugat keabsahan
tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila.
Menarik untuk dicatat, premis yang merupakan reevaluasi terhadap
sejarah Pancasila ini paralel dengan perubahan kebijakan rezim
Orde Baru. Soeharto kemudian menghapus peringatan lahirnya
Pancasila pada tanggal 1 Juni, dan melarang semua bentuk
peringatan pada tanggal itu. Meskipun menimbulkan keberatan dari
berbagai pihak, rezim Orde Baru secara terang-terangan justru
mengabsahkan premis Nugroho. Tahun 1982, Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan artikel Nugroho itu
menjadi sebuah booklet 69 halaman yang dijadikan bacaan wajib
bagi para guru pengajar pelajaran Pendidikan Moral Pancasila
(PMP).
Ada hal yang kurang relevan dalam tulisan Nugroho. Perumusan
Pancasila adalah proses sejarah yang terjadi tahun 1945, namun
Nugroho menghubung-hubungkannya dengan apa yang terjadi pada
dekade 1960-an. Nugroho menegaskan, generasi muda perlu diberi
tahu pengalaman sejarah Orde Lama di mana ideologi marxisme-
leninisme berkembang, agar mereka tidak mengulangi salah langkah
pada masa itu, semata-mata hanya karena tidak tahu. Nugroho juga
melihat pencabutan kekuasaan pemerintahan dari Soekarno oleh
MPRS tahun 1967 adalah "faktor yang menjulang tinggi" di dalam
persoalan pengamanan Pancasila dari ancaman ideologi marxisme-
leninisme sebagaimana yang dimaksud oleh Ketetapan MPRS No
XXV/ MPRS/1966.
Selanjutnya, menurut Nugroho, penghormatan terhadap jasa-jasa
Soekarno seharusnya tidak membutakan mata masyarakat terhadap
"kenyataan bahwa selama zaman Orde Lama itu, Bung Karno
memberikan keleluasaan bergerak kepada PKI, dan bahkan
mendukung partai itu dengan menyingkirkan kekuatan-kekuatan
Pancasilais yang dapat mengimbangi kaum komunis..."
Perlu dipertanyakan apa relevansi ditampilkannya "tafsir" sejarah itu.
Sebab Nugroho tidak sedang berbicara tentang ancaman
komunisme terhadap Pancasila, atau "kesaktian" Pancasila dalam
menghadapi berbagai rongrongan. Proses perumusan Pancasila
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (5 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
notabene berhenti pada 18 Agustus 1945 ketika PPKI mengesahkan
UUD 1945, dan tentu saja berbeda dengan "proses perjalanan
Pancasila sebagai dasar negara". Nugroho terlalu jauh masuk dalam
pembahasan tentang sepak terjang politik Soekarno sehingga sedikit
keluar dari konteks bahasan lahirnya Pancasila.
Di sisi lain, Nugroho juga menegaskan rumusan Pancasila 1 Juni
1945 rentan terhadap ancaman komunisme. Nugroho menunjukkan
bagaimana tokoh PKI seperti DN Aidit dan Nyoto pernah
menggunakan sila internasionalisme, salah satu sila dalam
Pancasila rumusan 1 Juni, untuk mendukung ide-ide komunismenya.
Sebuah kesimpulan yang simplistik. Legitimasi atas rumusan
Pancasila 1 Juni juga datang dari berbagai pihak, dengan latar
belakang dan alasan yang berbeda dengan yang diutarakan tokoh
PKI tadi.
Dua minggu setelah artikel Nugroho itu dimuat, Institut Soekarno-
Hatta mengumumkan "Deklarasi Pancasila" yang berisi penegasan
bahwa tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Deklarasi
ini ditandatangani 17 tokoh masyarakat yang sebagian mempunyai
latar belakang antikomunis. Mereka di antaranya adalah Jusuf
Hasyim (pemimpin PPP), Usep Ranawijaya (pemimpin senior PDI),
HR Dharsono (mantan Sekretaris Jenderal ASEAN) dan Jenderal
(Purn) Hugeng. Deklarasi ini dibacakan di Monumen Soekarno-
Hatta, Jalan Proklamasi Jakarta pada pukul 00.00, 17 Agustus 1981.
Sebuah pemandangan yang menarik. Sejumlah tokoh dengan
otoritas politik yang tinggi melakukan perlawanan simbolis terhadap
seorang ahli sejarah yang baru saja menggugat sebuah versi
sejarah. Kompetensi akademis dilawan secara politis.
Dalam kacamata Brooks, tindakan Nugroho di atas mendapat restu
pemerintah, sebagai bagian dari usaha untuk menciptakan
"keseimbangan" perspektif tentang Soekarno. Peningkatan idealisasi
terhadap Soekarno di kalangan loyalis Soekarno dan generasi muda,
diimbangi dengan usaha-usaha untuk menegaskan makna penting
Soekarno dalam konteks sejarah. Kebangkitan kekuatan nostalgis
terhadap Soekarno dan semakin kuatnya mitos-mitos tentang
Soekarno sekitar tahun 1978 cukup mengkhawatirkan Orde Baru
sehingga Nugroho diinstruksikan untuk melakukan counter dengan
menciptakan gambaran-gambaran yang negatif tentang Soekarno.
Meskipun premis-premisnya sempat memicu kontroversi, Nugroho
dipromosikan pemerintah menjadi Rektor UI tahun 1982. Setahun
kemudian, Nugroho diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan. Dalam jabatan yang terakhir ini, Nugroho pernah
diinstruksikan Soeharto untuk merevisi pelajaran sejarah sekolah
dengan menekankan instabilitas politik di era kepemimpinan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (6 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno tahun 50-an. Berawal dari sinilah kemudian bermunculan
konstruksi-konstruksi unfavourable tentang Soekarno dalam buku
teks sejarah.
Konstruksi unfavourable tentang Soekarno diidentifikasi Leigh dalam
buku teks Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka. Buku ini terdiri dari
empat volume: volume 1 dan 2 menjelaskan sejarah era
kepemimpinan Soekarno. Volume 1 (1945-1949) diawali dengan
sampul foto Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan 1945.
Dalam kacamata Leigh, foto yang memperlihatkan Soekarno sedang
menundukkan pandangannya ini cenderung menafikan kharisma
Soekarno. Buku ini terdiri dari 254 halaman dilengkapi dengan foto
atau gambar. Namun, foto Soekarno hanya dimunculkan 14 kali dan
menurut Leigh rata-rata berupa foto yang sulit diamati karena
berukuran kecil atau foto dengan sudut pengambilan yang kurang
tepat.
Leigh membandingkannya dengan foto-foto Letkol Soeharto. Di
antaranya adalah foto yang menonjolkan wajahnya, serta foto yang
menunjukkan dia sedang di tengah-tengah kerumunan prajurit, yang
menggambarkan peran pentingnya dalam Serangan Oemoem I
Maret 1949 di Yogyakarta. Foto yang lain berupa foto sepenuh
halaman Soeharto dengan para veteran perang, serta foto Soeharto
dengan Sultan Yogyakarta. Foto-foto ini, menurut Leigh,
memperteguh citra Soeharto sebagai militer yang bersih dan sosok
pemimpin yang terpercaya.
Periode 1945-1949 merupakan puncak karier Soekarno sebagai
negarawan maupun politisi. Namun, eksistensi Soekarno justru
dikecilkan atau dikeluarkan dari teks resmi pemerintah yang
membahas sejarah periode itu. Eksklusi terhadap eksistensi
Soekarno bersandingan dengan inklusi terhadap eksistensi militer di
era revolusi fisik, dengan penonjolan peranan Soeharto pada
momentum Serangan Oemoem 1 Maret.
Satu fakta yang sangat menarik juga ditemukan Leigh dalam soal-
soal ujian untuk materi sejarah tingkat sekolah dasar. Dalam soal-
soal pilihan berganda itu, Soekarno ternyata banyak ditempatkan
pada pilihan jawaban yang salah untuk pertanyaan-pertanyaan
seputar Pancasila, perjuangan melawan penjajah, dan penumpasan
pemberontakan pascakemerdekaan. Sebaliknya, Leigh tidak
menemukan satu pun soal ujian yang menempatkan nama Soeharto
dalam pilihan jawaban yang salah. Fakta ini menurut Leigh dapat
berdampak buruk terhadap persepsi siswa terhadap peranan
Soekarno maupun Soeharto dalam sejarah.
Komunisme dan Soekarno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (7 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
Dalam buku Tiga Puluh Tahun Indonesia Merdeka Volume 3. (1965-
1974), Leigh mencatat beberapa penyajian yang berdampak buruk
terhadap citra Soekarno. Misalnya foto Soekarno dengan pemimpin
PKI Aidit, karikatur yang menggambarkan Soekarno menjadi bahan
tertawaan mahasiswa berkaitan dengan masalah PKI, serta foto tim
dokter dari RRC sedang memberikan perawatan medis kepada
Soekarno. Foto-foto ini ditampilkan dalam deskripsi peristiwa
G30S/1965.
Dalam buku ini, peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto
dijelaskan dalam term pergantian kekuasaan, dan bukannya dalam
term perebutan kekuasaan (coup d'etat). Soekarno dihadirkan
sebagai personifikasi Orde Lama yang diidentifikasi dengan
instabilitas politik, kemerosotan moral, dan krisis ekonomi.
Sebaliknya, Soeharto digambarkan sebagai personifikasi Orde Baru
yang berhasil menyelamatkan bangsa dari kondisi-kondisi kacau
warisan Orde Lama.
Tahun 1968, Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh meluncurkan
buku The Coup Attempt of the September 30 Movement in
Indonesia. Buku ini menegaskan kesimpulan rezim Orde Baru bahwa
PKI adalah kekuatan di balik peristiwa G30S/1965 yang telah diberi
kesempatan Soekarno untuk berkembang pesat pada akhir dekade
50-an dan awal dekade 60-an. Rezim Orde Baru secara implisit
menyimpulkan kontribusi Soekarno dalam peristiwa September
1965. Buku ini merupakan reaksi atas buku Ben Anderson dan Ruth
McVey berjudul Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in
Indonesia yang menyimpulkan ABRI sebagai pemain utama dalam
peristiwa G30S/1965. Pada tahun 1978, Nugroho juga
mengoordinasi penyusunan Buku Putih G30S Tahun 1965 dengan
kesimpulan yang sama dengan buku pertama tadi.
Hal yang tak kalah menarik adalah sikap rezim Orde Baru ketika
Kolonel (Purn) Soegiarso Soerojo mempublikasikan buku Siapa
Menabur Angin Akan Menuai Badai tahun 1988. Buku ini sarat
dengan tuduhan bahwa Soekarno seorang
Marxis, komunis, serta terlibat dalam G30S/1965. Menanggapi
penerbitan buku ini, Mensesneg Moerdiono dengan tegas
menyatakan bahwa secara politik Soekarno memang salah.
"Buktinya ada Tap MPRS tahun 1967, yang mencabut
kekuasaannya dan tidak diterima pelaksanaan Nawaksara-nya," ujar
Moerdiono. Dengan mengutip hasil Sidang MPRS 1967, Ketua BP-7
Oetoyo Oesman juga menyatakan, "Itulah kesalahan (Soekarno-
pen) yang bertautan dengan Peristiwa G30S/PKI. Yakni, kesalahan
di bidang politik dan kesalahan yuridis. Dua kesalahan itu yang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (8 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
menyebabkan Soekarno dikoreksi oleh wakil rakyat yang duduk
dalam lembaga tertinggi negara MPRS di tahun 1967." Ketika
berbagai pihak mempertanyakan keabsahan buku itu, Jaksa Agung
Sukarton Marmosudjono menyatakan substansi buku karya
Soegiarso itu tidak mengganggu ketertiban umum sehingga tidak
perlu dilarang.
Media massa dalam hal ini benar-benar dimanfaatkan rezim Orde
Baru untuk melakukan delegitimasi terhadap Soekarno. Namun,
media ternyata tak hanya memberi ruang kepada tafsir kebenaran
negara tentang seluk-beluk G30S/1965, tetapi juga kepada tafsir-
tafsir alternatif. Untuk memenangkan perdebatan di media yang
kompetitif itu, tak pelak rezim Orde Baru menempatkan figur yang
otoritatif dan berkompeten, seperti terwakili oleh figur Moerdiono,
Oetoyo Oesman, dan Sukarton.
"Mikul dhuwur
mendhem jero"
Namun, desoekarnoisasi dalam berbagai bentuknya bukan satu-
satunya dimensi dalam sikap politik Orde Baru terhadap Soekarno.
Sebab menentukan sikap terhadap Soekarno, ternyata menjadi
suatu hal yang dilematis bagi Orde Baru. Terus-menerus
mendiskreditkan Bung Karno ternyata bukan pilihan yang tak
mengandung risiko. Pada akhirnya, pertimbangan-pertimbangan
politislah yang lebih menentukan apakah Orde Baru harus
mendelegitimasi atau melegitimasi Soekarno.
Dalam ulang tahun PDI tahun 1978, Ali Moertopo mengumumkan
rencana Presiden Soeharto untuk memugar kompleks makam
Soekarno di Blitar. Rencana ini menjadi kontroversial dan
mengundang kecurigaan karena bertolak belakang dengan
perlakuan rezim Orde Baru terhadap Soekarno sebelumnya.
Menurut Brooks, ada tiga kemungkinan di balik rencana itu. Pertama,
Soeharto benar-benar ingin menghormati Soekarno. Kedua, rencana
itu merupakan bagian dari strategi untuk menghadapi Pemilu 1992.
Ada kepentingan politis untuk menetralisasi kekecewaan kalangan
loyalis Soekarno atas sikap negara Orde Baru terhadap Soekarno
sebelumnya. Kekecewaan ini dapat menimbulkan sikap apriori,
bahkan antipati terhadap partai pemerintah (Golkar), dan sebaliknya
menimbulkan dorongan untuk memilih partai politik yang
"berseberangan" dengan pemerintah. Ketiga, rencana yang dapat
menimbulkan efek rehabilitasi nama Soekarno bertujuan untuk
mengalihkan perhatian masyarakat dari aksi-aksi protes mahasiswa
yang cenderung semakin semarak tahun 1977-1978.
Tahun 1985, nama Soekarno (Hatta) diabadikan sebagai nama
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (9 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Desoekarnoisasi:Delegitimasi yang Tak Tuntas -- Jumat, 1 Juni 2001
bandara udara terbesar di Indonesia. Setahun kemudian, Orde Baru
juga mengesahkan Soekarno-Hatta sebagai pahlawan proklamator
kemerdekaan RI dan membangun Tugu Proklamator untuk
mengenang jasanya. Beberapa pengamat menilai "eforia" Soekarno
ini bisa jadi merupakan strategi untuk mengalihkan perhatian
masyarakat dari krisis ekonomi akibat anjloknya harga minyak pada
awal dekade 1980-an. Krisis ini dapat melemahkan legitimasi
kekuasaan Soeharto pada Pemilu 1987.
Pada titik ini terlihat Soeharto menerapkan dua pendekatan yang
berbeda terhadap Soekarno. Ia secara diam-diam berusaha
mendiskreditkan Soekarno dan mengontrol pengaruhnya. Ketika
taktik ini kurang berhasil, Soeharto berusaha untuk mewarisi
popularitas Soekarno dengan menempatkan diri sebagai bagian dari
kontinum kekuasaan yang telah digerakkan Soekarno. Kombinasi
antara containment dan cooptation ini menjadi ekspresi dasar dari
falsafah mikul dhuwur mendhem jero. Soeharto dapat menunjukkan
penghormatannya kepada Soekarno sekaligus membelenggu
mitologi-mitologi tentang Soekarno dengan selalu menekankan
bahwa Soekarno telah melakukan berbagai kesalahan.
Entah ada hubungannya dengan sikap di atas atau tidak, yang jelas
desoekarnoisasi tak pernah berakhir tuntas. Romantisisme terhadap
Soekarno hingga kini belum sepenuhnya pudar. Simbol-simbol
Soekarno masih menjadi sarana yang efektif untuk menggalang
massa dalam pemilu. Beberapa jajak pendapat yang dilakukan
media massa juga menunjukkan generasi yang tak mengenal hiruk-
pikuk perpolitikan era Soekarno dan yang notabene tak dididik untuk
"melek" politik pun banyak yang mengagumi Soekarno melebihi
tokoh sejarah yang lain.
Meminjam istilah Cornelis Lay, Soekarno bukan saja terus bertahan
sebagai ideologi dan pemikiran politik, namun dari waktu ke waktu
mendapatkan impor energi yang semakin besar dari kegagalan Orde
Baru dalam merumuskan ideologi bagi bangsa Indonesia yang
ingin mereka bangun.
* Agus Sudibyo Peneliti pada Institut Studi Arus Informasi Jakarta,
menulis buku Citra Bung Karno, Analisis Berita Pers Orde Baru.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Desoekarnoi...0yang%20Tak%20Tuntas%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (10 of 11)4/3/2005 11:05:01 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Di Seberang Jembatan Emas
Franz Magnis-Suseno SJ
WAKTU Soekarno, Bung Karno, menulis brosurnya Mencapai
Indonesia Merdeka, 1933 (saya memakai terbitan Yayasan
Pendidikan Soekarno/Yayasan Idayu, Jakarta 1982), pergerakan
nasional di Indonesia kelihatan hang. Sesudah pemberontakan
komunis 1926/1927 dan krisis ekonomi dunia 1928, pemerintah
kolonial dengan sangat represif menindas kaum nasionalis
Indonesia. Sedangkan kaum nasionalis sendiri tidak bersatu tentang
bagaimana perjuangan kebangsaan mereka harus diteruskan.
Dalam situasi ini, Bung Karno menyerukan bahwa "di timur matahari
mulai bercahaya, fajar mulai menyingsing". Kalau kaum Marhaen
percaya akan cita-cita mereka, mereka, begitu Bung Karno, tidak
dapat dikalahkan.Banyak pembaca sudah mencatat sesuatu yang
dalam tulisan ini mau sedikit ditelusuri: Betapa Bung Karno dalam
brosur ini terpengaruhi oleh pemikiran Lenin tentang revolusi
sosialis. Berikut ini saya akan menunjukkan keterpengaruhan itu, lalu
mempertanyakan sejauh mana Bung Karno dapat dikatakan
menganut leninisme untuk, akhirnya, menarik beberapa kesimpulan.
1. Mengalahkan kapitalisme dan imperialisme
Yang langsung menarik perhatian: Tujuan perjuangan kemerdekaan
menurut Bung Karno bukan kemerdekaan itu sendiri, melainkan
pembebasan dari "kapitalisme dan imperialisme". Kalau
"imperialisme" jelas karena tak terpisah dari kolonialisme. Tetapi
bahwa Bung Karno begitu saja, dalam tradisi wacana marxis murni,
menganggap masa pascakolonial sebagai pascakapitalis, bagi
banyak dari kita terasa asing. Tujuh puluh tahun sesudah Bung
Karno kita semua sudah tahu bahwa sosialisme dalam arti
penggantian mekanisme pasar dengan perekonomian berdasarkan
perencanaan sentral negara sudah gagal, kita menyaksikan
kejayaan masyarakat konsumis pasca-Perang Dunia II yang justru
berdasarkan ekonomi pasar, kita barangkali sudah membaca Third
Way-nya Anthony Giddens yang-seperti banyak ilmuwan lain-
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
menganggap dikotomi "sosialisme lawan kapitalisme" sebagai jauh
ketinggalan (third way itu bukan jalan ketiga di antara sosialisme dan
kapitalisme, melainkan antara bentuk-bentuk perekonomian
pascadikotomi itu!).
Akan tetapi, di tahun 1920-an dan 1930-an, abad ke-20 situasi masih
lain. Komunisme dan sosialisme radikal baru saja muncul di
panggung dunia. Negara-negara demokratis di Eropa dengan
perekonomian "kapitalis" mengalami kesulitan besar (dan akan
dilanda oleh fasisme). Dalam situasi itu tidak mengherankan bahwa
para nasionalis Indonesia dengan sendirinya menolak kapitalisme
yang memang jelas mendorong perkembangan kolonialisme ke
imperialisme sejak permulaan abad ke-19. Penolakan itu tidak khas
Bung Karno saja. Hatta, HOS Tjokroaminoto, dan banyak tokoh lain
sama saja menolak kapitalisme.
2. Ajaran Lenin tentang revolusi sosialis
Namun, ciri "leninis" brosur Mencapai Indonesia Merdeka bukan
hanya karena penolakan terhadap kapitalisme itu. Sebagaimana
mau saya perlihatkan, seluruh strategi perjuangan untuk merebut
kemerdekaan yang diajukan Bung Karno mengikuti, kadang-kadang
secara harfiah, apa yang ditulis Lenin antara lain dalam dua buku
yang paling termashyur, What is to be Done? (1903) dan The State
and Revolution (1917).
Demi perbandingan, mari kita lihat garis besar teori revolusi sosialis
Wladimir I Lenin sebagaimana dimuat dalam dua buku itu. Lenin
mengembangkan pandangannya berhadapan dua faham yang
ditolaknya dengan tajam: ekonomisme dan anarkisme (sindikalis).
Pandangan ekonomisme mengatakan bahwa revolusi sosialis tidak
perlu diusahakan. Kapitalisme akan- karena dinamikanya sendiri-
semakin runtuh dan dengan demikian menciptakan situasi yang
matang untuk revolusi.
Melawan pandangan itu Lenin menegaskan bahwa revolusi sosialis
hanya terlaksana apabila proletariat mau melaksanakannya. Tak
akan ada revolusi tanpa kesadaran sosialis-revolusioner. Akan
tetapi, kesadaran sosialis tidak dapat timbul dengan sendirinya.
Proletariat dengan sendirinya hanya akan mencapai sebuah
kesadaran "serikat buruh" (trade unionalist), artinya, berdasarkan
pengalaman langsung perjuangan di tempat kerja mereka selalu
hanya akan menuntut upah lebih tinggi dan kondisi-kondisi kerja
lebih baik.
Kesadaran sosialis yang sungguh-sungguh, karena itu, harus
dimasukkan dari luar ke dalam proletariat. Hal itu juga jelas karena
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
sosialisme merupakan sebuah teori ilmiah yang hanya dapat
dimengerti oleh orang-orang yang terlatih secara intelektual, tetapi
tidak oleh kaum buruh yang tidak memiliki pendidikan tinggi.
Memasukkan kesadaran revolusioner ke dalam proletariat adalah
tugas partai. Inti leninisme adalah ajaran tentang peran kunci partai.
Partai harus merupakan partai pelopor yang terdiri atas kaum
revolusioner profesional purnawaktu. Partai itu harus memimpin
proletariat. Partai sendiri diatur menurut asas sentralisme
demokratis: Demokratis, karena para pemimpin dipilih dalam
musyawarah partai itu, sentralistik karena sesudah pimpinan dipilih,
pimpinan harus ditaati dengan mutlak dan partai dipimpin secara
sentralistik dan hierarkis dari atas.
Apakah revolusi memang perlu? Ada aliran dalam marxisme yang
berpendapat bahwa sosialisme dapat diciptakan tanpa revolusi.
Untuk itu, cukup kalau proletariat memakai mekanisme demokrasi.
Bukankah proletariat akan merupakan mayoritas masyarakat? Kalau
begitu, proletariat melalui pemilihan umum dapat mencapai
mayoritas dan mengadakan sosialisme melalui undang-undang.
Lenin menolak garis pikiran ini. Baginya demokrasi hanyalah tipuan
borjuasi yang kalau proletariat membatasi diri padanya, akan
mematikan semangat revolusioner proletariat. Dalam kerja sama
dengan borjuasi sosialisme tidak mungkin tercapai.
Lawan kedua Lenin adalah kaum anarko-sindikalis. Mereka
menuntut agar sesudah revolusi negara dengan segala aparatnya
dihapus. Tetapi bagi Lenin anggapan ini naif. Meskipun sesudah
revolusi kekuasaan politik dipegang oleh proletariat, namun semua
struktur kekuasaan masih sama dengan masa kekuasaan borjuasi.
Oleh karena itu, perlu proletariat mengadakan kediktatoran dulu
untuk menghancurkan borjuasi dan kapitalisme. Maka, untuk
mewujudkan sosialisme sebagai tujuan terakhir, proletariat harus
memantapkan dulu monopoli kekuasaan dalam tangannya. Dan
karena lawan sementara ini hanya kalah secara politik, serta
proletariat masih minoritas terhadap kelas-kelas sekutu, kaum tani
dan borjuasi kecil, maka bukan demokrasi, melainkan kediktatoran
proletariat yang perlu dibikin.
3. Massa aksi dan partai pelopor
Mari kita sekarang melihat pandangan Bung Karno tentang
perjuangan demi Indonesia Merdeka. Yang sangat mencolok dalam
tulisan yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka adalah bahwa
hal merdeka- yang tentu saja tidak pernah hilang dari fokus Bung
Karno: "syarat yang pertama ialah: kita harus merdeka" (41)-seakan-
akan terdesak oleh sebuah keprihatinan lebih jauh, yaitu penolakan
terhadap kapitalisme dan imperialisme. Bung Karno sangat khawatir
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
jangan sampai sesudah Indonesia merdeka, Indonesia jatuh ke
tangan "kaum ningrat dan kaum kapitalis". Kemerdekaan bukan
tujuan atau nilai pada dirinya sendiri, melainkan "jembatan". "Kita
harus merdeka agar supaya kita bisa leluasa bercancut tali wanda
menggugurkan stelsel kapitalisme dan imperialisme" (41). Tujuan
perjuangan kaum marhaen adalah "suatu masyarakat yang adil dan
sempurna," jadi "yang tidak ada tindasan dan hisapan," dan oleh
karena itu "tidak ada kapitalisme dan imperialisme"(41). Seperti telah
saya sebutkan di atas, penolakan kapitalisme dan imperialisme
bukan khas Bung Karno, melainkan menjadi pandangan seluruh
tokoh nasionalis waktu itu, namun menunjukkan pengaruh perspektif
Leninis.
Karena itu, kaum Marhaen tidak cukup asal berjuang. Mereka harus
berjuang dengan kesadaran yang tepat. Mengikuti bahasa Lenin,
Bung Karno menegaskan bahwa yang perlu adalah kesadaran yang
radikal. Radikal bagi Bung Karno berarti sadar akan adanya dua
golongan dalam masyarakat yang berlawanan. Bung Karno tidak
memakai bahasa "pertentangan kelas", tentu karena faham
"Marhaen" justru mau menegaskan bahwa analisa kelas marxis tidak
cocok dengan kenyataan sosial di Indonesia. Namun, ia
menegaskan bahwa kaum Marhaen harus selalu sadar bahwa ada
yang "sana" dan yang "sini", ada "golongan 'atas'" dan "golongan
'bawah'" dan bahwa antara dua-duanya hanya bisa ada
pertentangan. "Sana dan sini tidak bisa diakurkan, sana dan sini
tidak bisa dipungkiri atau ditipiskan antitesenya, sana dan sini akan
selamanya bertabrak-tabrakan satu sama lain" (47) karena "inilah
yang oleh kaum marxis disebutkan dialektiknya sesuatu
keadaan" (ib.).
Seperti Lenin menolak kemungkinan untuk mencapai sosialisme
secara damai, begitupun Bung Karno menuntut sikap nonkooperasi.
Nonkooperasi bukan hanya dengan pemerintahan kolonial, tetapi
juga dalam arti "tidak mau duduk di dalam dewan-dewan kaum
pertuanan" (49). Oleh karena itu, seperti Lenin membedakan antara
kesadaran "serikat buruh" dan "kesadaran sosialis revolusioner",
Bung Karno membedakan "massa aksi" yang radikal dari massale
actie yang hanya kelihatan radikal (62). Dalam yang terakhir "kaum
lunak" sekadar membatasi diri pada "rapat-rapat umum". Begitu
misalnya Sarekat Islam "dulu tidak bisa membangkitkan massa aksi
karena ia tidak berdiri di atas pendirian yang radikal". Artinya, ia tidak
mempunyai perspektif "sana-sini", perspektif Marhaen lawan kaum
ningrat dan kaum kapitalis (63). "Massa aksi" harus "100 persen
radikal: perlawanan sonder damai, kemarhaenan, melenyapkan cara
susunan masyarakat sekarang, mencapai cara susunan masyarakat
baru" (ib.).
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
Namun, lagi-lagi mengikuti Lenin, Bung Karno menegaskan bahwa
"kesadaran kemarhaenan" akan terlalu lama kalau ditunggu
berkembang dengan sendirinya. Harus ada satu partai Marhaen
yang berjalan di depan. Seperti perjuangan proletariat harus dipimpin
oleh partai pelopor, begitu perjuangan kaum Marhaen harus dipimpin
oleh sebuah "partai pelopor". "Partai yang memegang obor, partailah
yang berjalan di muka, partailah yang menyuluhi jalan yang gelap
dan penuh dengan ranjau-ranjau itu sehingga menjadi jalan
terang" (37). Partai itu "memimpin massa", "memegang komando",
"harus memberi ke-bewust-an pada pergerakan massa", "memberi
keradikalan". Adalah tugas partai untuk "menjelmakan massa yang
tadinya onbewust dan hanya raba-raba itu menjadi suatu pergerakan
massa yang bewust dan radikal, yakni massa aksi yang insaf akan
jalan dan maksud-maksudnya" (37). "Partai yang dengan gagah
berani pandai memimpin dan membangkitkan bewuste massa aksi"
"kemenangan sudah bisa datang" (38). Maka, partai harus "memberi
pendidikan dan keinsafan pada massa buat apa ia berjuang, dan
bagaimana ia harus berjuang" (67). Partai harus menjaga dan
menyalakan "radikalisme" yang tidak melupakan tujuan akhir dalam
massa.
Namun, justru karena itu perlu ada partai yang terus-menerus
mengingatkan tujuan perjuangan yang sebenarnya. Partai perlu
menjaga agar rakyat jangan sampai karena "tertarik oleh manisnya
hasil-hasil kecil itu lantas lupa akan maksud besar", yaitu mencapai
"puncak gunung Indonesia Merdeka" (69). Secara lebih konkret,
yang harus dilakukan oleh partai pelopor itu adalah mengadakan
"propaganda di mana-mana, kursus di mana-mana, perlawanan di
mana-mana, anak-anak organsiasi, vakbond-vakbond, sarekat-
sarekat tani, majalah-majalah dan pamflet-pamflet" (72).
Partai sendiri, mengikuti Lenin, harus waswas terhadap dua macam
lawan, yaitu reformisme dan "anarcho-syndicalisme" (65). "Tiap-tiap
anggota partai yang nyeleweng ke arah reformisme harus ditendang
dari kalangan partai zonder pardon dan zonder ampun" (64;
ungkapan "tanpa maaf dan tanpa ampun" hampir di setiap halaman
The State and Revolution diulangi Lenin).
Kalau pada Lenin kaum reformasi adalah kaum sosial demokrat
Internasionale II yang mengharapkan bahwa sosialisme dapat
diwujudkan secara demokratis, maka bagi Bung Karno kaum
reformis adalah kaum "kooperasi", mereka yang mau mencapai
kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bekerja sama dengan
pemerintahan Belanda. Mengharapkan kemerdekaan dari kerja
sama dengan kaum kolonialis adalah percuma. Mereka hanya akan
melepaskan kekuasaan kalau dipaksa. Bung Karno mengutip Karl
Marx: "Tak pernahlah sesuatu kelas suka melepaskan hak-haknya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
dengan ridanya kemauan sendiri" (55). Maka, tak mungkin ada
kemerdekaan yang tidak diperjuangkan oleh rakyat dalam "massa
aksi".
Faham "anarcho-syndikalisme" langsung diambil alih dari Lenin.
Lenin menolak tuntutan mereka agar sesudah revolusi sosialis
negara dengan segala aparatnya dihapus. Sesudah revolusi
kekuatan negara perlu dipegang oleh proletariat untuk
menghancurkan para musuh proletariat. Yang dimaksud Bung Karno
dengan anarcho-syndikalisme adalah "penyelewengan ke arah amuk-
amukan zonder pikiran, penyelewengan ke arah perbuatan-
perbuatan atau pikiran-pikiran cap mata gelap" (65). Melawan
penyelewengan itu partai pelopor harus menegakkan "disiplin":
"Disiplin, disiplin yang kerasnya sebagai baja, disiplin yang zonder
ampun dan zonder pardon menghukum tiap-tiap anggota yang
berani melanggarnya, adalah salah satu nyawa dari partai pelopor
itu!" Di dalam partai pelopor Marhaen tidak boleh ada demokrasi.
Sebagai prinsip kepemimpinan dalam partai Bung Karno mengambil
"democratisch centralisme"-nya Lenin. "Partai di dalam kalbu sendiri
tidak boleh berdemokrasi dalam makna segala 'isme' boleh
leluasa" (64). Dan ia mengutip "seorang pemimpin besar": "Di dalam
partai tak boleh ada kemerdekaan pikiran yang semau-maunya saja;
kokohnya persatuan partai itu adalah terletak di dalam persatuan
keyakinan" (65).
Lalu apa yang harus dilakukan menurut Bung Karno, apabila
Kemerdekaan sudah tercapai? Bung Karno menegaskan bahwa
perjuangan dengan perolehan kemerdekaan belum selesai. Harus
dipastikan bahwa kaum Marhaen dan bukan kaum ningrat dan kaum
kapitalis yang memegang kekuasaan. Kemerdekaan harus dilihat
sebagai "hanyalah sebuah jembatan, sekalipun suatu jembatan
emas!" (76). Harus disadari bahwa "di seberang jembatan itu jalan
pecah jadi dua: satu ke dunia keselamatan Marhaen, satu ke dunia
Kesengsaraan Marhaen; satu ke dunia Sama Rata Sama Rasa, satu
ke dunia sama Ratap sama Tangis" (ib.). "Kereta Kemenangan" di
atas jembatan itu jangan "dikusiri oleh lain orang selainnya
Marhaen" (ib.). Jadi, harus dipastikan bahwa kaum Marhaen, dan
bukan kaum ningrat dan kaum kapitalis mengambil alih kekuasaan.
Oleh karena itu, Bung Karno menolak demokrasi politik sebagai
tujuan revolusi. Untuk memastikan bahwa kaum Marhaen, dan
bukan pihak lain, "menggenggam kekuasaan pemerintahan" (46)
demokrasi tidak memadai. Mengikuti kritik Lenin terhadap
demokrasi, Bung Karno menunjuk pada Revolusi Perancis di mana
rakyat jelata "akhirnya ternyata hanya diperkuda belaka oleh kaum
borjuis yang bergembar-gembor 'demokrasi'" (77). Karena kekayaan
dan penguasaan media komunikasi, kaum borjuasi akan menjadi
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
penguasa yang sebenarnya. Menurut Bung Karno "negeri-negeri
sopan", Amerika Serikat, Belgia, Denmark, Swedia, Swiss, dan
Jerman dikuasai oleh kapitalisme, dan karena itu di semua negara
itu "rakyat jelata tidak selamat, bahkan sengsara kelewat
sengsara" (79). Dan ia mengutip seorang Caillaux bahwa "kini Eropa
dan Amerika ada di bawah kekuasaan feodalisme baru" (81). Maka,
yang harus tercapai bukanlah demokrasi, melainkan "kekuasaan 100
persen pada rakyat", bukan hanya kekuasaan politik, melainkan
kekuasaan ekonomis (bdk 82).
Istilah untuk apa yang diidam-idamkan Bung Karno adalah "sosio-
demokrasi" dan "sosio-nasionalisme" (83). Ia tidak menguraikan
secara konkret operasional apa yang dimaksud dengan dua istilah
itu. Memang, "tidak boleh ada satu perusahaan lagi yang secara
kapitalistis menggemukkan kantong seseorang borjuis ataupun
menggemukkan kantong burgerlijke staat" (82). Tetapi, kata
"sosialisme" atau "sosialisasi hak milik produktif" tidak kita temukan.
Selain bahwa "penyakit individualisme" harus disembuhkan dengan
"benih 'gotong royong'" sehingga terwujud "'manusia baru' yang
merasa dirinya 'manusia masyarakat' yang selamanya
mementingkan keselamatan umum" serta petunjuk pada "koperasi-
koperasi yang radikal, vakbond-vakbond dan srikat-srikat tani
radikal" tidak ada petunjuk lagi.
4. Soekarno dan Leninisme
Dari uraian di atas kelihatan betapa Bung Karno terpengaruh oleh
pemikiran Lenin. Apakah penghapusan kapitalisme sebagai tujuan
revolusi, perlunya kesadaran radikal dalam kaum Marhaen, perlunya
perspektif "sana" dan "sini", perlu adanya partai pelopor, penolakan
terhadap cara damai atau kooperatif untuk mencapai kemerdekaan,
perang terhadap reformisme dan "anarcho-syndicalisme",
penegasan bahwa sesudah kemerdekaan tercapai, perjuangan
belum selesai karena harus dipastikan bahwa kaum Marhaen dan
bukan kaum ningrat dan kaum kapitalis yang memegang kekuasaan,
serta bahwa untuk itu demokrasi tidak cocok, semua itu mengikuti
garis pikiran Lenin.
Jadi, Bung Karno seorang leninis? Itulah pertanyaan yang sekarang
perlu diajukan. Saya bertolak dari perbedaan yang langsung
mencolok. Bung Karno bukan hanya tidak bicara tentang proletariat,
melainkan juga tidak tentang kelas-kelas. Bung Karno bicara tentang
"kaum Marhaen". Di sini tidak perlu diceriterakan kembali bagaimana
Bung Karno sampai ke nama itu. Yang mau dikatakannya dengan
memakai istilah itu jelas: Bahwa pemisahan keras dan terinci antara
pelbagai kelas yang khas bagi marxisme tidak sesuai dengan
kenyataan di Indonesia. Di Indonesia yang mencolok adalah
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
pertentangan antara "orang kecil" dan "kaum atas", dan "orang kecil"
bukan kata dari perbendaharaan marxisme. Apakah perbedaan ini
relevan? Jawaban hanya dapat berbunyi: Perbedaan ini bersifat
prinsipiil dan berarti bahwa Bung Karno-berbeda dari persepsinya
sendiri-bukan seorang Marxis sama sekali. Bagi Karl Marx justru
tidak semua "kelas bawah" di segala zaman bersifat revolusioner.
Agar sebuah kelas dapat diharapkan menumbangkan kapitalisme
(tujuan yang juga diiyakan oleh Bung Karno), situasi khas kelas itu
dalam proses produksi harus kondusif ke perkembangan kesadaran
kelas revolusioner itu. "Orang kecil" bagi analisa Marxis terlalu kabur,
tidak dapat dipakai.
Dilihat dari perbedaan perspektif sangat mendalam ini, perbedaan-
perbedaan "kecil" lainnya antara bahasa Lenin dan bahasa Bung
Karno justru relevan. Pertama, partai pelopor Bung Karno tidak
memiliki ciri-ciri partai pelopor Lenin. Kedua, tidak ada syarat-syarat
keanggotaan, syarat bahwa anggota harus kaum revolusioner
profesional purnawaktu dan sebaiknya diambil dari kaum intelektual.
Tidak ada faham ajaran revolusioner ilmiah yang karena itu tidak
dapat diketahui oleh proletariat yang kurang berpendidikan, dan
karena itu harus dimasukkan dari luar ke dalamnya oleh partai. Bung
Karno, lebih dekat dengan Marx daripada Lenin, melihat fungsi partai
membuat sadar apa yang sudah dimiliki massa Marhaen secara tak
sadar. "Kesadaran" pada Bung Karno lain daripada kesadaran
revolusioner pada Lenin karena yang terakhir dimaksud sebagai
kepercayaan pada sebuah teori dan pandangan dunia, yaitu
Materialisme, Dialektis, dan Historis.
Ketiga, tak ada sama sekali pada Bung Karno padanan terhadap
kediktatoran proletariat yang dalam kenyataan, tetapi juga menurut
ucapan Lenin, dilaksanakan sebagai kediktatoran partai komunis di
atas proletariat. Tak ada tanda bahwa Bung Karno sesudah revolusi
politik mengharapkan penghancuran total terhadap struktur
kepemilikan dalam masyarakat sebagaimana menjadi program
Lenin. Wacana "sosio-demokrasi" dan "sosio-nasionalisme" hanya
diisi dengan menunjuk pada "koperasi radikal", serikat buruh dan
serikat tani "radikal" tanpa menjelaskan apa itu "radikal", unsur-unsur
mana semua, barangkali yang "radikal" itu juga terdapat dalam
negara-negara "kapitalis" di Barat. Bung Karno bukan seorang
revolusioner sosial.
Maka, retorika leninis Bung Karno jangan menipu kita. Di sini tidak
bicara seorang leninis, melainkan seorang yang mencita-citakan
pembebasan rakyatnya dari penindasan kolonialisme dan
keterpurukan di bawah kaum feodal tradisional serta kapitalisme
baru. Bahasa keras Lenin yang tidak pernah main-main melainkan
merupakan cetak biru prinsip-prinsip yang akan dilaksanakan begitu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
ia memegang kekuasaan, dipakai Bung Karno bukan karena ia
seorang Leninis, melainkan karena menyediakan kamus ungkapan-
ungkapan bersemangat yang sangat cocok untuk menjadi wahana
romantika revolusi yang mempesona.
5. Akhirul kata
Tidak ada tanda apa pun bahwa Bung Karno sendiri menganggap
diri sebagai seorang le-ninis. Jauh lebih masuk akal bahwa Bung
Karno-sama seperti rekan-rekan nasionalisnya lain-melihat kepada
Revolusi Oktober dengan simpati, bukan karena menyetujuinya,
melainkan karena di sini ada bangsa besar yang membebaskan diri
dari kapitalisme. Berbeda dengan anggapan Bung Karno sendiri,
marhaenisme-yang dalam pandangan saya jauh lebih realistik
daripada analisa kelas Marx yang tidak pernah peka terhadap apa
yang sebenarnya menggerakkan orang-bukan sebuah marxisme.
Namun, kecenderungan untuk seakan-akan lebur dalam romantika
bahasa program revolusi Lenin yang sedikit pun tidak romantik,
menunjuk juga pada kelemahan Bung Karno yang akan menjadi
faktor dalam kejatuhannya. Bahwa pergerakan nasional Indonesia
ditentukan oleh tiga alam makna, yaitu nasionalisme, Islam, dan
marxisme, pasti betul. Namun, waktu Bung Karno 35 tahun
kemudian melontarkan triade itu sebagai nasionalisme, agama, dan
komunisme (Nasakom), Bung Karno masuk ke dalam sebuah
perangkap daripadanya ia tidak lepas lagi. Romantikanya
membuatnya tidak percaya bahwa omongan "progresif-revolusioner"
kaum komunis Indonesia, wacana keras revolusioner mereka, bukan
romantika hiperbolis sebagaimana ia sendiri memahaminya dalam
"Mencapai Indonesia Merdeka", melainkan sebuah program keras
dan realistik untuk merebut kekuasaan, bukan demi "kaum Marhaen"
Indonesia, melainkan demi kekuasaan komunis sedunia.
Bung Karno jatuh cinta dengan kata revolusi, tetapi tidak memahami
implikasi kata itu, yaitu bahwa struktur pemilikan masyarakat yang
ada harus dihancurkan dan bahwa penghancuran itu, sebagaimana
disadari sepenuhnya oleh Lenin, hanya dapat melalui kediktatoran
partai yang tidak takut memakai senjata teror. Maka, ia tidak siap
dalam hati untuk melepaskan kaum komunis yang andaikata secara
dini dilarang, barangkali dapat luput dari pembunuhan mengerikan
yang akhirnya menimpa apa pun yang berbau komunis.
Dan masih satu hal. Lain daripada Hatta-yang juga mengkritik bahwa
demokrasi Barat tidak sampai ke bidang ekonomi-Soekarno tidak
mengembangkan sikap hati yang positif terhadap demokrasi (Barat!).
Begitu saja ia termakan oleh hasutan anti demokrasi Lenin-dengan
tidak memperhatikan bahwa mayoritas kaum sosialis sedunia 1918
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Di Seberang Jembatan Emas -- Jumat, 1 Juni 2001
memilih demokrasi daripada sosialisme yang berdasarkan teror (dan
karena itu berpisah dengan Lenin). Ketertutupan hati Bung Karno
terhadap demokrasi prosedural, tendensinya ke arah populisme,
merupakan sebuah tragika ka-rena Bung Karno tentu akan bisa
menjadi pendidik bangsanya ke arah demokrasi yang paling baik.
* Prof Dr Franz Magnis-Suseno SJ Rohaniwan, menulis lebih dari
300 karangan dan 26 buku, terutama bidang etika, filsafat, dan
pandangan dunia Jawa; sekarang Direktur Program Pascasarjana
STF Driyarkara, Jakarta.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
● Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
● Bung Karno, Seni, dan Saya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Di%20Seber...batan%20Emas%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (10 of 11)4/3/2005 11:05:03 AM
Dunia MenurutSang Putra Fajar -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Dunia Menurut Sang Putra Fajar
Budiarto Shambazy
DENGAN baju kebesaran berwarna putih, lengkap dengan kopiah
dan kacamata baca, Bung Karno tidak mempedulikan protokoler
Sidang Umum.
Biasanya, setiap kepala negara berpidato sendiri saja. Tetapi, untuk
pertama kalinya, Bung Karno naik ke podium didampingi ajudannya,
Letkol (CPM) M Sabur. Lima tahun kemudian, per tanggal 1 Januari
1965, Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Ia
memrotes penerimaan Malaysia, antek kolonialisme Inggris, menjadi
anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK)-PBB. Ketika mendengar
instruksi Pemimpin Besar Revolusi Indonesia itu dari PTRI New
York, Sekjen PBB U Thanh menangis sedih, tak menyangka BK
begitu marah dan kecewa.
Bung Karno dikenal sering kecewa dengan kinerja DK-PBB. Sampai
sekarang pun kewenangan DK-PBB yang terlalu luas masih sering
terasa kontroversial. Misalnya, ketika mereka-terutama AS, Inggris
dan Perancis-bersama Sekjen Koffi Annan, menjatuhkan sanksi-
sanksi tak berperikemanusiaan atas Irak. Sudah lama memang Bung
Karno tidak menyukai struktur PBB yang didominasi negara-negara
Barat, tanpa memperhitungkan representasi Dunia Ketiga yang
sukses unjuk kekuatan dan kekompakan melalui Konferensi Asia-
Afrika di Bandung tahun 1955. Untuk itulah, setiap tahun Bung Karno
coba mengoreksi ketimpangan itu dengan memperjuangkan
diterimanya Cina, yang waktu itu diisolasi Barat.
"Kita menghendaki PBB yang kuat dan universal, serta dapat
bertugas sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itulah, kami
konsisten mendukung Cina," kata Bung Karno. Wawasan berpikir
Bung Karno waktu itu ternyata benar. Cina bukan cuma lalu diterima
sebagai anggota, namun juga menjadi salah satu anggota tetap DK-
PBB. Puluhan tahun lalu, Bung Karno sudah memproyeksikan Cina
sebagai negara besar dan berpengaruh, yang harus dilibatkan dalam
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dunia%20Men...Putra%20Fajar%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 8)4/3/2005 11:05:04 AM
Dunia MenurutSang Putra Fajar -- Jumat, 1 Juni 2001
persoalan-persoalan dunia. Dewasa ini, Cina sudah memainkan
peranan penting dalam mengoreksi perimbangan kekuatan regional
dan internasional, yang sudah terlalu lama dijenuhkan oleh penyakit
yang berjangkit Perang Dingin.
Kini hampir semua warga dunia sudah familiar dengan kata
"globalisasi" atau saling keterkaitan (linkage) antar-bangsa, baik
secara politis maupun ekonomis. Dan dalam pidato To Build the
World Anew, Bung Karno sudah pernah mengucapkannya. "Adalah
jelas, semua masalah besar di dunia kita ini saling berkaitan.
Kolonialisme berkaitan dengan keamanan; keamanan juga berkaitan
dengan masalah perdamaian dan perlucutan senjata; sementara
perlucutan senjata berkaitan pula dengan kemajuan perdamaian di
negara-negara belum berkembang," ujar Sang Putra Fajar.
Di mana pun di dunia, Bung Karno tak pernah lupa membawakan
suara Dunia Ketiga dan aspirasi nasionalisme rakyatnya sendiri.
Siapa pun yang tidak suka kepadanya pasti akan mengakui sukses
Bung Karno memelopori perjuangan Dunia Ketiga melalui Konrefensi
Asia-Afrika atau KTT Gerakan Nonblok. Inilah Soekarno yang serius.
Jika sedang santai dalam saat kunjungan ke luar negeri, Bung Karno
menjadi manusia biasa yang sangat menyukai seni. Kemana pun,
yang tidak boleh dilupakan dalam jadwal kunjungan adalah
menonton opera, melihat museum, atau mengunjungi seniman
setempat. Hollywood pun dikunjunginya, ketika Ronald Reagan dan
Marilyn Monroe masih menjadi bintang film berusia muda.
Ia pun tak segan memarahi seorang jenderal besar jago perang,
Dwight Eisenhower, yang waktu itu menjadi Presiden AS dan
sebagai tuan rumah yang terlambat keluar dari ruang kerjanya di
Gedung Putih dalam kunjungan tahun 1956. Sebaliknya, Bung Karno
rela memperpanjang selama sehari kunjungannya di Washington
DC, setelah mengenal akrab Presiden John F Kennedy. Waktu
berkunjung ke AS, banyak wartawan kawakan dari harian-harian
besar di Amerika-mulai dari The New York Times, The Washington
Post, LA Times, sampai Wall Street Journal-menulis dan memuat
pidato dan pernyataannya yang menggugah, foto-fotonya yang
segar, sampai soal-soal yang mendetail dari Bung Karno.
Kunjungan-kunjungannya ke luar negeri, memang membuat Bung
Karno menjadi tokoh Dunia Ketiga yang selalu menjadi sorotan
internasional. Sikapnya yang charming dan kosmopolitan,
kegemarannya terhadap kesenian dan kebudayaan,
pengetahuannya mengenai sejarah, bahasa tubuhnya yang
menyenangkan, mungkin menjadikan Bung Karno menjadi tamu
agung terpenting di abad ke-20, yang barangkali cuma bisa
ditandingi oleh Fidel Castro atau JF Kennedy.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dunia%20Men...Putra%20Fajar%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 8)4/3/2005 11:05:04 AM
Dunia MenurutSang Putra Fajar -- Jumat, 1 Juni 2001
PERUMUSAN politik luar negeri sebuah negara yang baru merdeka
setelah Perang Dunia Kedua, lebih banyak dipengaruhi oleh kepala
negara/pemerintahan. Mereka sangat berkepentingan untuk
menjaga negara mereka masing-masing agar tidak terjerumus ke
dalam persaingan ideologis dan militer Blok Barat melawan Blok
Timur. Lagi pula, netralitas politik luar negeri semacam ini waktu itu
berhasil menggugah semangat "senasib dan sepenanggungan" di
negara-negara baru Asia dan Afrika, untuk menantang bipolarisme
Barat-Timur melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955.
Di Indonesia, peranan Bung Karno dalam menjalankan politik luar
negeri yang bebas dan aktif, jelas sangat dominan sejak ia mulai
memerintah sampai akhirnya ia terisolasi menyusul pecahnya
peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Ia bahkan menjadi
salah satu founding father pembentukan Gerakan Nonblok (GNB)
sebagai kelanjutan dari Konferensi Bandung. Penting untuk
digarisbawahi pula, Bung Karno pada awalnya menjadi satu-satunya
pemimpin Dunia Ketiga yang dengan sangat santun menjalin serta
menjaga jarak hubungan yang sama dan seimbang, dengan negara-
negara Barat maupun Timur.
Hubungan Bung Karno dengan Washington pada prinsipnya selalu
akrab. Akan tetapi, Bung Karno merasa dikhianati dan mulai
bersikap anti-Amerika ketika pemerintahan hawkish Presiden Dwight
Eisenhower mulai menjadikan Indonesia sebagai tembok untuk
membendung komunisme Cina dan Uni Soviet pada paruh kedua
dasawarsa 1950. Sewaktu Moskwa dan Beijing terlibat permusuhan
ideologis yang sengit, Bung Karno juga relatif mampu menjaga
kebijakan berjarak sama dan seimbang (equidistance) terhadap Cina
dan Uni Soviet.
Lagi pula, Bung Karno dengan sangat pandai menjalankan politik
luar negeri yang bebas dan aktif. Bobot Indonesia sebagai negara
yang besar dan strategis, peranan penting Indonesia dalam
menggagas GNB, dan posisi "soko guru" sebagai negara yang baru
merdeka, benar-benar dimanfaatkannya sebagai posisi tawar yang
cukup tinggi dalam diplomasi internasional. Oleh sebab itulah,
pelaksanaan politik luar negeri yang high profile ala Bung Karno,
tidak pelak lagi, membuat suara Indonesia terdengar sampai ke
ujung dunia.
Mengapa ia akhirnya kecewa kepada Washington sehingga
hubungan bilateral AS-Indonesia semakin hari semakin memburuk?
Sebab Bung Karno tahu persis sepak terjang AS-juga Inggris,
Australia dan Malaysia-ketika membantu pemberontakan PRRI-
Permesta. Lebih dari itu, setelah kegagalan pemberontakan itu,
Pemerintah AS memasukkan Bung Karno dalam daftar pemimpin
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dunia%20Men...Putra%20Fajar%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 8)4/3/2005 11:05:04 AM
Dunia MenurutSang Putra Fajar -- Jumat, 1 Juni 2001
yang harus segera dilenyapkan karena menjadi penghalang
containment policy Barat terhadap Cina. Juga ada beberapa alasan
domestik yang membuat Washington kesal terhadap Bung Karno,
seperti sikapnya kepada Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pada lima tahun pertama dekade 1960, hubungan Indonesia dengan
Cina meningkat pesat. Mao Zedong sangat menghormati Bung
Karno yang memberikan tempat khusus kepada komunis, dan
sebaliknya Bung Karno mengagumi perjuangan Mao melawan
dominasi AS dan Rusia di panggung internasional. Istimewanya
hubungan Bung Karno dengan Mao ini tercermin dari gagasan
pembentukan Poros Jakarta-Beijing. Bahkan kala itu poros ini
sempat akan diluaskan dengan mengajak pemimpin Korut Kim Il-
sung, pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh, dan pemimpin Kamboja
Norodom Sihanouk.
Tatkala memutuskan untuk keluar dari PBB, Bung Karno
mencanangkan pembentukan New Emerging Forces sebagai reaksi
terhadap Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme). Ia juga
bercita-cita membentuk sendiri forum konferensi negara-negara baru
itu di Jakarta, sebagai reaksi terhadap dominasi PBB yang dinilainya
terlalu condong ke Barat. Sungguh patut disayangkan, wadah kerja
sama Dunia Ketiga ini hanya sempat bergulir sampai pesta olahraga
Ganefo belaka.
***
SEPERTI telah disinggung di atas, dominasi Bung Karno dalam
perumusan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sangat dominan.
Persepsi, sikap, dan keputusan Bung Karno dalam mengendalikan
diplomasi Indonesia, bersumber pada pengalaman-pengalamannya
dalam kancah perjuangan dan pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Mungkin karena terlalu banyak krisis yang
dihadapi Bung Karno selama ia memimpin, membuat pelaksanaan
politik luar negerinya menjadi high profile dan agak bergejolak.
Akan tetapi, gejolak-gejolak tersebut, juga sikap Bung Karno
menghadapi politik Perang Dingin, tidak dapat dikatakan sebagai
sebuah kelemahan ataupun penyimpangan dari politik luar negeri
yang bebas aktif. Justru yang terjadi, Bung Karno senantiasa
mencoba menghadirkan gagasan-gagasannya tentang dunia yang
damai dan adil, dengan mengedepankan posisi Indonesia sebagai
kekuatan menengah yang menyuarakan nasib Asia dan Afrika.
Penting pula untuk ditegaskan, perilaku internasional Bung Karno
pada kenyataannya memang berhasil mengangkat derajat
masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga dalam menghadapi
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dunia%20Men...Putra%20Fajar%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 8)4/3/2005 11:05:04 AM
Dunia MenurutSang Putra Fajar -- Jumat, 1 Juni 2001
kemapanan politik Perang Dingin. Malahan jika menghitung
akibatnya, ada kekhawatiran besar di negara-negara adidaya
terhadap internasionalisasi sukarnoism yang akan membahayakan
posisi mereka.
Jika berbicara mengenai sumber-sumber yang mempengaruhi
"politik global" Bung Karno, sesungguhnya mudah untuk
memahaminya. Ia lahir dari persatuan antara dua etnis, Bali dan
Jawa Timur. Ia menikahi pula gadis dari Pulau Sumatera. Ia
beberapa kali dipenjarakan penjajah Belanda di berbagai tempat di
Nusantara, membuatnya mengenal dari dekat kehidupan berbagai
etnis. Pendek kata, ia lebih "Indonesia" ketimbang menjadi seorang
yang "Jawasentris."
Dalam pandangan Bung Karno, dunia merupakan bentuk dari
sebuah "Indonesia kecil" yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Dan
ini betul. Bung Karno seakan-akan membawa misi untuk membuat
agar semua bangsa berdiri sama tinggi dan setara di dunia ini, sama
dengan upayanya berlelah-lelah mempersatukan semua suku
bangsa menjadi Indonesia. Meskipun Indonesia cuma menyandang
kekuatan menengah, Bung Karno sedikit banyak memiliki sebuah
"visi dunia" seperti para pemimpin negara adidaya, yang waktu itu
merupakan sebuah utopia belaka.
Pengalaman pahit menghadapi penjajah Belanda serta Jepang,
merupakan sumber utama bagi Bung Karno untuk membawa
Indonesia menjadi anti-Barat di kemudian hari. Kebijakan anti-
komunisme yang dijalankan Barat untuk membendung pengaruh Uni
Soviet, menurut Bung Karno merupakan sebuah pemasungan
terhadap sebuah penolakan terhadap hak kesetaraan semua bangsa
di dunia untuk bersuara. Persepsi Bung Karno mengenai perjuangan
GNB pun serupa, yakni memberdayakan Dunia Ketiga untuk
mengikis ketimpangan antara negara-negara kaya dengan yang
miskin.
Pada hakikatnya, wawasan Bung Karno tentang perlunya
memperjuangkan ketidakadilan internasional itu, masih relevan
dengan situasi politik dan ekonomi global saat ini. Entah sudah
berapa banyak dibentuk fora-fora kerja sama politik dan ekonomi
internasional, yang masih gagal menutup kesenjangan antara yang
kaya dengan yang miskin, seperti Dialog Utara-Selatan, atau G-15.
Sampai saat ini pun, PBB masih belum melepaskan diri dari
genggaman kepentingan-kepentingan negara-negara Barat di
Dewan Keamanan.
***
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dunia%20Men...Putra%20Fajar%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 8)4/3/2005 11:05:04 AM
Dunia MenurutSang Putra Fajar -- Jumat, 1 Juni 2001
ANDAIKAN saja Bung Karno tidak tersingkir dari kekuasaan, apa
yang sesungguhnya telah ia lakukan dalam ruang lingkup politik
global? Mungkin saja, satu-satunya kegagalan-kalaupun itu layak
disebut sebagai kegagalan-adalah
ingin menantang atau mengubah (to challenge) tata dunia yang
"stabil" pada masa itu.
Stabilitas, atau equilibrium global pada saat itu, suka atau tidak,
diatur oleh perimbangan kekuatan antara Barat dengan Timur.
Kedua blok yang berseteru meyakini bahwa perdamaian abadi
hanya bisa dicapai dengan sebuah lomba senjata yang seimbang,
baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
Pengaturan perimbangan kekuatan itu bersifat pasti, matematis, dan
mengamankan dunia dari ancaman instabilitas. Itulah jadinya
pembentukan NATO dan Pakta Warsawa, serta perjanjian hot line
dan anti-tes senjata nuklir antara JF Kennedy dengan Nikita
Kruschev. Stabilitas global AS-Uni Soviet inilah yang juga menjamin
peredaan ketegangan dan tercegahnya perang antara Eropa Barat
dengan Eropa Timur, antara Korut dan Korsel di Semenanjung
Korea, antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan di daratan Asia
Tenggara, dan antara Kuba dengan AS.
Pada prinsipnya, akan selalu ada pemimpin yang ingin mengubah
stabilitas semu semacam ini. Upaya-upaya yang membahayakan
kemaslahatan perimbangan kekuatan tersebut, akan selalu
menimbulkan krisis politik atau krisis militer. Bagi para penjamin
stabilitas, seorang Bung Karno memang hanya merupakan sebuah
ancaman yang akan menimbulkan krisis politik, bukan krisis militer.
Oleh sebab itulah perlu ditekankan sekali lagi, pihak-pihak Barat-
khususnya AS dan Inggris-sudah sampai pada kesimpulan bahwa
Bung Karno mesti dilenyapkan.
Sayang sekali, inisiatif-inisiatif diplomasi Bung Karno terhenti di
tengah jalan saat ia diisolasi dari kekuasaannya. Betapapun, banyak
doktrin dari politik luar negeri yang dijalankannya, dilanjutkan oleh
para penggantinya. Warisan Bung Karno bukan hanya menjadi
diorama yang bagus dilihat-lihat, tetapi juga masih kontekstual untuk
zaman-zaman selanjutnya.
Tidak pada tempatnya bagi kita untuk menyesali politik
luar negeri Bung Karno, seperti yang pernah dilakukan oleh
pemerintahan Orde Baru. Apakah kebijakan lebih buruk ketimbang
politik luar negeri yang cuma mengemis-ngemis bantuan luar negeri?
Apakah melepas Timor Timur juga merupakan kebijakan yang lebih
baik? Apakah berwisata ke luar negeri tanpa tujuan, lalu
mendengang-dengungkan poros Cina-Indonesia-India juga lebih
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dunia%20Men...Putra%20Fajar%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 8)4/3/2005 11:05:04 AM
Dunia MenurutSang Putra Fajar -- Jumat, 1 Juni 2001
hebat dari politik global Bung Karno?
Sesuai dengan julukan Sang Putra Fajar, Bung Karno membuka
matanya melihat terang benderang dunia saat fajar menyising,
tatkala sebagian dari kita masih terlelap menutup mata. Dunia versi
Bung Karno adalah dunia yang mutlak harus berubah menjadi
tempat yang lebih adil dan setara bagi semua. Kita pernah beruntung
memiliki seorang duta bangsa, yang sekaligus juga seorang diplomat
terulung yang pernah dimiliki Indonesia.
* Budiarto Shambazy Wartawan Kompas.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Dunia%20Men...Putra%20Fajar%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 8)4/3/2005 11:05:04 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
In Nugroho Budisantoso
ANDAI Soekarno dan Hatta tidak berpisah sebagai Dwitunggal,
barangkali jalan sejarah Indonesia akan berbeda. Boleh saja kita
berandai-andai seperti itu, tetapi yang terjadi pada sejarah adalah
bahwa pada waktu itu, 1 Desember 1956, Hatta mengundurkan diri
sebagai wakil presiden, dan dengan demikian Dwitunggal bercerai.
Pengunduran diri Hatta dalam situasi bangsa yang masih belum
menentu pasca-Pemilihan Umum 1955 ini mengundang banyak
pertanyaan. Sebab, dalam situasi seperti itu justru dibutuhkan
seorang Hatta yang dikenal sangat jernih, tegas, dan tanpa
kompromi dalam mengurus pemerintahan. Apa yang membuat Hatta
tidak pernah datang kembali dengan Soekarno sebagai Dwitunggal?
Hatta sepertinya meninggalkan tanggung jawab untuk ikut
memikirkan bangsa dan negara yang sedang kacau. Hatta justru
seakan memilih tidak berbuat apa-apa di luar arena. Dan memang
selepas perceraian Dwitunggal itu, Hatta seakan menghilang dari
hiruk-pikuk politik. Suaranya hampir-hampir bahkan tidak terdengar;
juga pada saat peristiwa besar terjadi pada 1965 yang melibatkan
sejumlah tentara dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Benarkah
Hatta meninggalkan tanggung jawab? Padahal, semua tahu bahwa
dalam rentang waktu yang panjang sejak tahun 1920-an, dalam
kegusaran dan kegelisahan akan situasi bangsa dan negerinya,
seperti halnya Soekarno, Hatta dengan gigih ingin memberikan jalan
keluar bagi bangsa dan negerinya. Kondisi konkret rakyat Indonesia
yang sengsara di bawah penjajahan menjadi tatapan mata Soekarno
dan Hatta.
Keduanya berpikiran, pada rakyat yang terbelenggu itu harus dibuka
kedok-kedok yang menutup kesadaran bahwa mereka sengsara
karena ditindas dan dijajah. Maka, tidak mengherankan kalau
keduanya berbuat sesuatu agar kepada rakyat disuntikkan
kesadaran untuk bisa melihat sejelas-jelasnya siapa dirinya sendiri,
di mana posisinya sekarang ini, dan ke mana langkah mesti diayun.
Bahkan, demi rakyat, mereka berdua tidak memperhitungkan lagi
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (1 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
konsekuensi-konsekuensi fisik dari kampanye-kampanye
penyadaran yang dijalankan. Penjara dan tanah pengasingan tidak
berarti apa-apa dibanding mutiara yang bersinar dalam hati dan budi
rakyat yang sadar akan kemerdekaan hidup yang mesti direbut.
Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa dalam diri Soekarno dan
Hatta bangkit perasaan mendalam akan tanggung jawab terhadap
kehidupan. Perasaan ini akan terusik terus-menerus kalau di dalam
lapangan kehidupan selalu dijumpai segala bentuk ketimpangan.
Ketimpangan-ketimpangan itu pada dasarnya mengisyaratkan
adanya gerak dunia yang lupa akan tanggung jawab, lupa akan
kehidupan yang semestinyalah dipelihara baik-baik. Disadari bahwa
dibutuhkan usaha terus-menerus untuk mengembalikan gerak dunia
agar ingat akan tanggung jawab terhadap kehidupan. Dan,
sepertinya Hatta memilih mundur dan berpisah dari Dwitunggal untuk
tujuan itu. Hatta mengambil posisi untuk memberi ingat kepada
Soekarno yang dipandangnya sudah berjalan dalam gerak lupa akan
tanggung jawab. Hatta memberi ingat, dan selalu memberi ingat
meskipun lebih sering tidak didengarkan. Hatta kemudian memang
hanya tampak seperti orang yang berseru-seru di padang gurun.
Ketika bersepakat menjadi Dwitunggal
Perpisahan Dwitunggal itu belum terbayang saat Soekarno dan
Hatta rujuk ketika Jepang menguasai Indonesia, sekalipun orang
tahu bahwa antara mereka berdua ada perbedaan prinsip dan pilihan
tindakan. Dengan disaksikan Sjahrir, Soekarno dan Hatta bersepakat
mengakhiri pertentangan panjang pada tahun 1930-an mengenai
jalan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai Indonesia
merdeka. Sebagaimana diketahui, Soekarno memilih jalan aksi
massa, di mana ia sendiri datang ke tengah-tengah massa, dan
membangkitkan kesadaran di sana. Sebab, bagi Soekarno politik
adalah machtsvorming dan machtsaanwending-pembentukan
kekuatan dan pemakaian kekuatan dari massa rakyat yang bersatu.
Sedangkan Hatta mengambil jalan kaderisasi. Sebab, katanya,
janganlah rakyat terlalu tergantung pada satu pemimpin.
Ketergantungan ini hanya menyebabkan pergerakan pupus di
tengah jalan sewaktu si pemimpin ditangkap. Menurut dia,
"Pergerakan kita tak boleh tinggal pergerakan pemimpin, yang hidup
dan mati dengan pemimpin itu. Akan tetapi pergerakan kita harus
menjadi 'pergerakan pahlawan-pahlawan yang tak punya nama',
artinya pergerakan rakyat sendiri, yang tidak tergantung kepada
nasibnya pemimpin."
Kecuali itu di antara keduanya juga berkembang perselisihan
mengenai sikap nonkooperasi yang harus dijalankan. Soekarno yang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (2 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
mempunyai latar belakang pendidikan di Bandung, berpandangan
bahwa sikap nonkooperasi ditunjukkan dengan menolak segala
sesuatu yang berbau penjajah, termasuk Tweede Kamer.
Sedangkan Hatta yang mengenyam pendidikan di Belanda
berpendapat bahwa sikap nonkooperasi harus ditunjukkan dalam
sikap perlawanan terus-menerus kepada penjajah sungguh pun
duduk di Tweede Kamer.
Namun, ketika Jepang menduduki Indonesia, dirasakan oleh
Soekarno dan Hatta bahwa suatu tugas yang jauh lebih besar
berada di depan mata, dan itu tidak dapat dilakukan seorang
perseorangan. Sembari keduanya berjabat tangan erat, Soekarno
waktu itu berkata kepada Hatta, "Inilah janji kita sebagai Dwitunggal.
Inilah sumpah kita yang jantan untuk bekerja berdampingan dan
tidak akan berpecah hingga negeri ini mencapai kemerdekaan
sepenuhnya." Karena keduanya dikenal publik, maka perjuangan
secara publik yang mereka tempuh, sedangkan Sjahrir yang
menyaksikan jabat tangan itu mengambil jalan perjuangan bawah
tanah. Menurut Soekarno, pembicaraan antara mereka bertiga waktu
itu amatlah singkat. Namun, sering kali di kemudian hari, konsepsi
mengenai Dwitunggal kelihatan seperti sudah dipersiapkan dan
dikerjakan dengan perhitungan yang saksama.
Berbeda dengan Sjahrir yang berjuang di bawah tanah, strategi
perjuangan secara publik dari Soekarno dan Hatta jelas sekali
langsung menggambarkan keduanya sebagai kolaborator Jepang.
Tentu saja keduanya menyangkal sangkaan itu. Hatta misalnya
menjelaskan bahwa keterlibatannya sebagai penasihat pemerintah
militer Jepang justru untuk melindungi rakyat. Demikian pula dengan
keberadaan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) bersama Soekarno.
Rakyat tetap menjadi tatapan mata akan strategi perjuangan yang
dijalankan. Sedapat mungkin rakyat dilindungi dan mendapat
keuntungan dalam situasi saat itu. Bahkan, Soekarno pernah berujar
kepada Hatta bahwa dalam kondisi semacam itu, dengan biaya
Pemerintah Jepang, rakyat akan dididik dalam menyelenggarakan
pemerintahan. Pada dasarnya, mereka sama sekali tidak sudi tunduk
di bawah penjajahan. Hatta dalam rapat umum di Lapangan Ikada, 8
Desember 1942, bahkan pernah berpidato, "Bagi pemuda Indonesia,
ia lebih suka melihat Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada
mempunyainya sebagai jajahan orang kembali."
Soekarno dan Hatta pada gilirannya memang dikenal sebagai
pemimpin rakyat Indonesia. Dapat dikatakan, di mana Soekarno ada
di situ pun Hatta. Strategi perjuangan publik di bawah pendudukan
Jepang mengantarkan keduanya untuk kemudian juga berperan
penuh dalam masa-masa ketika Jepang dipukul mundur oleh Sekutu
pada pertengahan 1945. Keduanya seperti sudah melupakan sama
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (3 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
sekali pertentangan faham yang terjadi pada tahun 1930-an, dan
seia-sekata dalam pikiran dan tindakan. Kalau sebelumnya mereka
dapat dikatakan saling mencela, pada saat-saat itu keduanya saling
membela. Sebagai Dwitunggal, keduanya sangat menonjol dalam
detik-detik Proklamasi kemerdekaan. Hatta menulis dalam Memoir-
nya bahwa Dwitunggal itulah yang kemudian dipilih menjadi Presiden
dan Wakil Presiden RI untuk pertama kalinya. Dikatakan oleh
Soekardjo Wirjopranoto bahwa konstruksi Dwitunggal untuk presiden
dan wakil presiden itu unik dalam sejarah, dan merupakan suatu
keharusan bagi Indonesia di masa itu.
Perjalanan Dwitunggal dalam pemerintahan sejak Proklamasi
Kemerdekaan memang telah melewati sejumlah kondisi yang
berbeda, yang berkaitan dengan strategi politik. Awalnya, Soekarno
dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden dalam sebuah
kabinet presidensial. Namun, ternyata di mata internasional
Soekarno dianggap sebagai kolaborator Jepang yang tentu saja
menyulitkan perundingan-perundingan diplomasi yang dijalankan.
Terhadap ini, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
(KNIP) mengusulkan agar untuk sementara waktu dibentuk kabinet
parlementer untuk menangkis serangan-serangan dari luar negeri
terhadap Soekarno atas nama rakyat. Seperti sudah diketahui,
anggota-anggota KNIP diangkat oleh Soekarno dan Hatta untuk
menggantikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang
mempunyai cap "Tokyo". Soekarno dan Hatta menyetujui usul Badan
Pekerja itu. Dan, kemudian Soekarno mengangkat Sjahrir sebagai
perdana menteri dengan alasan bahwa presiden mendelegasikan
kekuasaan kepada perdana menteri untuk mengatasi kesulitan
sementara waktu. Setelah berubah konfigurasinya sebanyak tiga
kali, kabinet Sjahrir jatuh, dan Soekarno mengambil alih. Formasi
kabinet selanjutnya di bawah pimpinan Amir Sjarifuddin yang
kemudian digantikan pula oleh Kabinet Hatta.
Sementara itu, perjuangan secara publik Dwitunggal di masa
pendudukan Jepang yang mengesankan tindakan kolaborasi sering
digunakan rival politik Soekarno dan Hatta; setidaknya, itu pernah
dilakukan oleh Muso yang menyebut keduanya sebagai pedagang
romusha. Bahkan, Sjahrir menurut Soekarno, juga sering
menggunakan keterlibatan dengan Jepang untuk mencelanya
sebagai pengecut. Tuduhan sebagai pengecut kembali mereka
terima ketika keduanya ditangkap di Yogyakarta karena waktu itu
mereka tetap tinggal di kota dan tidak terjun bergerilya bersama
rakyat dan tentara. Namun, sebenarnya dengan penangkapan itu,
justru sosok Dwitunggal sebagai pemimpin nasional semakin
bersinar daripada muncul sebagai pemberontak yang lari ke hutan.
Pada saat dipercaya menjadi perdana menteri (1948-1950), yaitu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (4 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
pasca-Kabinet Amir Sjarifuddin yang memberikan kepada
pemerintahannya hasil-hasil Perjanjian Renville, Hatta sungguh
menunjukkan kepiawaiannya dalam mengurus pemerintahan. Selain
keberhasilan dalam perjuangan memperoleh kedaulatan dalam
Konferensi Meja Bundar, sejumlah hal dijalankan termasuk
penghematan, rasionalisasi dalam tentara dan pegawai negeri, serta
juga penanganan atas membeludaknya pengangguran. Hingga
kemudian dapat dibuktikan bahwa pemerintahan Hatta, meskipun
dalam situasi darurat, berhasil memperluas sawah menjadi 75.000
hektar, membentuk sejumlah koperasi pertanian, mengendalikan
harga-harga, dan mencegah penimbunan. Bahkan, mulai dipikirkan
secara serius Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang
berdasarkan otonomi yang luas. Sering dikatakan bahwa Dwitunggal
Soekarno-Hatta dengan Soekarno sebagai presiden dan Hatta
sebagai wakil presiden sekaligus perdana menteri ini merupakan
kombinasi kepemimpinan yang sangat cocok dalam situasi Indonesia
yang sulit di masa-masa awal kemerdekaan.
Namun, bagaimanapun kombinasi kepemimpinan seperti itu ada
dalam suasana darurat. Seperti dikatakan Hatta dalam pidatonya di
depan Badan Pekerja KNIP pada tanggal 16 Februari 1948,
"Presiden dan saya berpendapat bahwa satu-satunya jalan untuk
mengatasi krisis politik yang merugikan negara ialah mengadakan
sementara waktu pemerintahan yang bersifat kabinet presidensiil,
menunggu terbentuknya kabinet parlementer yang kuat."
Namun, harus diakui bahwa konfigurasi kepemimpinan nasional
sejak Dwitunggal ini sepertinya tidak pernah secara tuntas
diselesaikan baik dalam rangka demokrasi parlementer, demokrasi
terpimpin, maupun sesudahnya. Bahkan, dengan kembalinya pada
tahun 1959 UUD 1945 yang sejak awal dikonstruksi untuk keadaan
darurat, sebenarnya dilanggengkan juga konfigurasi kepemimpinan
nasional yang darurat.
Peran Soekarno dan Hatta dalam pemerintahan
Sejak diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, sebagai
presiden, Soekarno tidak dapat mengambil tindakan sendiri, dan
kekuasaannya dikurangi sedikit demi sedikit. Perdana menteri
bertanggung jawab kepada parlemen. Bahkan, sebagai Panglima
Tertinggi Angkatan Bersenjata, keputusan presiden harus
ditandatangani juga oleh Menteri Pertahanan. Satu-satunya hak
prerogatif presiden adalah menunjuk seorang atau sejumlah orang
untuk membentuk kabinet. Menurut Bernard Dahm, kondisi seperti
itu terjadi ada kaitan dengan munculnya Sjahrir dalam pemerintahan.
Munculnya Sjahrir memang seperti sudah menjadi tuntutan zaman.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (5 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
Ia yang tidak tampil dalam kerja sama dengan Jepang, logis untuk
menjadi pihak perunding dengan Belanda. Dan, berbeda dengan
Soekarno, Sjahrir sering dikatakan tidak mempunyai prasangka
terhadap orang-orang Belanda. Pendidikan di Barat
mengonstruksikan dalam dirinya bentuk demokrasi yang semestinya
dijalankan, yang tentu saja berbeda dengan konstruksi demokrasi
Soekarno.
Mengenai kekuasaan presiden itu, Hatta mengungkapkan bahwa
sejak keluarnya Maklumat Wakil Presiden No X pada pertengahan
Oktober 1945, KNIP mempunyai hak legislatif. Sebelumnya, menurut
UUD 1945 pada aturan peralihan, segala kekuasaan dijalankan oleh
presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Hatta
menambahkan bahwa mulai saat itu, "secara berangsur-angsur
kekuasaan yang lain akan diberikan kepada badan yang berhak
berdasarkan trias politika."
Pertentangan pandangan akan peran Hatta dalam pemerintahan pun
sejak pertengahan 1950 muncul secara menonjol. Waktu itu, RIS
bubar menjadi negara kesatuan RI. Dari satu pihak ada yang
mengharapkan, terutama dari golongan Masyumi, Hatta merangkap
jabatan wakil presiden dan perdana menteri, sedangkan dari pihak
lain, yaitu PNI dan PSI, mengharapkan Hatta menjabat salah satu
saja. Dalam waktu-waktu kemudian, mengenai ini, Hatta pernah
berujar bahwa Sjafruddin Prawiranegara, salah seorang pemimpin
Masyumi, mengusulkan agar Hatta menjabat sebagai wakil presiden
saja. Hanya saja, kalau kondisi bangsa sulit, Hatta kembali
merangkap sebagai perdana menteri yang bertanggung jawab
kepada parlemen. Usulan Sjafruddin ini terkenal dengan sebutan
escape clause. Usulan ini tidak disetujui kubu PNI dan PSI, dan
perdebatan terus berlangsung. Akhirnya, Hatta menyerahkan kepada
mereka putusan apa saja yang akan diterimanya dengan lapang
dada. Kemudian, Presiden Soekarno, sebagai kepala negara,
menunjuk Mohamad Natsir sebagai formatur kabinet. Presiden dan
wakil presiden dalam pemerintahan Kabinet Natsir dan sesudahnya
tampak hanya berperan sebagai penasihat saja.
Dwitunggal Soekarno-Hatta sepertinya kemudian tinggal menjadi
simbol pemimpin bangsa yang tidak mempunyai gigi dalam
pemerintahan. Soekarno memang masih duduk sebagai kepala
negara, namun Hatta? Menyaksikan situasi politik sekacau apa pun,
Hatta tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan sesuatu
tindakan secara konstitusional, kecuali membantu tugas-tugas
Soekarno. Dalam situasi seperti itu apa yang harus dibuat? Sebuah
artikel dalam harian Fikiran Rakjat tertanggal 9 Oktober 1954
memuat komentar seperti ini, "Sejauh yang kita lihat dan dengar,
Hatta bisa mengendalikan dirinya dan tetap berada di dalam batas-
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (6 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
batas konstitusional; dengan kata lain, ia tidak mencampuri urusan
eksekutif. Tetapi sejauh yang kita ketahui, merupakan siksaan bagi
Soekarno untuk tetap berada di dalam batas-batas konstitusional
dan tidak campur tangan dalam eksekutif".
Hubungan Dwitunggal semakin renggang
Masa-masa Dwitunggal sebagai simbol itu sering dilukiskan Hatta
sebagai masa di mana dirinya dan Soekarno mulai berselisih faham.
Kondisi ini ada kaitannya dengan kedekatan baru Soekarno dengan
PKI yang sangat memusuhi Hatta. Dikatakan oleh Hatta di kemudian
hari bahwa "sejak kita meninggalkan UUD 1945 berganti dengan
UUD 1950, arti dan kedudukan Dwitunggal mulai berubah dan makin
berkurang. Hal itu digunakan sebaik-baiknya oleh PKI dalam taktik
dan perjuangan politiknya, sehingga proses merosotnya daya ikat
dan kegunaan Dwitunggal itu makin cepat dan bahkan antara kami
berdua sering timbul berbagai salah pengertian. Akibatnya tercermin
pula dalam berbagai urusan kenegaraan yang kalau dulu diatasi
dengan kewibawaan dan kenegarawanan yang terletak dalam
lembaga Dwitunggal itu, lama-lama menjadi masalah-masalah yang
tidak teratasi, atau diatasi dengan cara-cara yang menimbulkan
keretakan-keretakan baru yang makin berlarut-larut."
Perselisihan faham antara Soekarno dan Hatta sebenarnya mulai
bersemi sejak 1949 di mana di bawah Konstitusi RIS Hatta sebagai
perdana menteri mempunyai kedudukan kepemimpinan yang lebih
kuat dibandingkan Soekarno. Namun demikian, seperti dipaparkan
oleh Mavis Rose, Soekarno memang mempunyai pesona terutama
di kalangan orang-orang Jawa sehingga memungkinkan dirinya
untuk menyarankan kembali adanya negara kesatuan. Sebab,
negara Indonesia Serikat dengan federalismenya dalam pandangan
Soekarno mengundang regionalisme yang dapat memecah
persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, meskipun secara publik
Dwitunggal kelihatan sebagai kombinasi kepemimpinan yang sangat
sesuai dan melengkapi satu dengan yang lain, sebenarnya terjadi
tarik-menarik gagasan mengenai bagaimana mengatur bangsa dan
negara. Pada titik ini, keduanya seperti ingin sungguh mewujudkan
tanggung jawabnya kepada rakyat. Hingga, rakyat harus sampai
pada perasaan bahwa mereka memerintah diri sendiri sebagai
bangsa yang merdeka dalam negara yang dibentuknya sendiri.
Mengenai bentuk negara kesatuan itu, Hatta sebaliknya
mengungkapkan bahwa gagasan negara kesatuan tidak selalu
berarti mencegah separatisme. Sebab, justru "suatu sistem federal
dalam kenyataan sesuai dengan kepulauan yang terpencar-pencar
dan bisa diperkirakan akan memperkuat rasa persatuan". Dalam
pikiran Hatta, semakin terdesentralisasi suatu sistem pemerintahan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (7 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
semakin rakyat dapat mengusahakan menyelesaikan persoalannya
sendiri, tanpa harus tergantung elite penguasa. Di sini Hatta seperti
mengingatkan kembali akan pentingnya kaderisasi dan pendidikan
yang menghasilkan suatu organisasi yang tidak tergantung pada
satu pemimpin. Mengenai federalisme, sebenarnya Hatta sudah
menjadi penganjur paling depan mengenai Indonesia sebagai
negara federal sebelum Perhimpunan Indonesia mulai
membicarakan bentuk negara yang merdeka.
Lalu, apa sebenarnya konsepsi "persatuan" dari keduanya? Dengan
memperhatikan gagasan Soekarno mengenai politik machtsvorming
dan machtsaanwending, orang mempersepsikan persatuan seperti
ada kaitannya dengan massa yang bergerak. Bahkan, Soekarno
pernah mengatakan bahwa "massa bukanlah cuma rakyat jelata
yang berjuta-juta saja, massa adalah rakyat jelata yang sudah
terluluh mempunyai semangat satu, kemauan satu, roh dan nyawa
satu. Massa adalah berarti deeg, jeladren, luluhan. Ia dus bukan
gundukan rakyat jelata saja yang berlain-lainan semangat dan
kemauan".
Kecuali itu, pada diri Soekarno juga selalu melekat gagasan
persatuan nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom) di
mana ketiganya menurut Dahm saling bertentangan. Ketiganya
menjadi satu ketika mendapatkan musuh bersama kolonialisme dan
imperialisme Barat. Pendekatan yang dipakai Soekarno ini sangat
khas bersifat sinkretisme Jawa. Bahkan, menurut catatan
Onghokham, dalam merumuskan Pancasila pun, Soekarno memeras
kelima sila menjadi tiga, yang kemudian menjadi satu sila saja, yaitu
"gotong royong". Soekarno sungguh menekankan abstraksi dalam
melihat persatuan. Bagaimanapun abstraksi mengandung potensi
untuk meniadakan keunikan, dan hak-hak individu rakyat dapat
dikesampingkan.
Adapun menurut Hatta, persatuan harus dimengerti sebagai "satu
bangsa Indonesia yang tidak dapat dibagi-dibagi. Di dalam pangkuan
bangsa yang satu itu boleh terdapat pelbagai paham politik. Dan tiap-
tiap aliran paham haruslah mendapat kesempatan bergerak, untuk
membuat propaganda bagi asas sendiri, dan tidak mesti dicekek
dengan kata wasiat 'persatuan'". Sebab, bagi Hatta, "kepahaman
rakyat dan kepahaman borjuis atau ningrat tidak dapat disatukan.
Persatuan segala golongan ini sama artinya dengan mengorbankan
asas masing-masing". Hatta di sini menekankan pluralitas.
Sementara hubungan antara Soekarno dan Hatta semakin
renggang, terjadi konflik mendalam di antara partai-partai. Bahkan,
mereka cakar-cakaran. Krisis dalam pemerintahan tidak dapat
dihindarkan. Hasil Pemilu 1955 diharapkan dapat mengatasi krisis.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (8 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
Namun, ternyata tidak ada pemenang mutlak. Situasi krisis tidak
menunjukkan perubahan. Dalam situasi seperti itu, Soekarno
menunjukkan akan membangun suatu penyelesaian dengan
menggalang kekuatan dari rakyat Jawa, PNI, PKI, NU, Partai Murba,
dan juga dengan menggandeng kepala staf Angkatan Darat yang
berpengaruh, Nasution. Soekarno pada Oktober 1956 bahkan
pernah berpidato mengajak untuk mengubur semua partai. Dan,
kemudian memperkenalkan satu sistem demokrasi baru, yaitu
Demokrasi Terpimpin. Dalam diri Soekarno seperti ada kegusaran
terus mengenai konsepsi persatuan yang diidam-idamkannya sejak
awal. Sepertinya, pada Demokrasi Terpimpin, Soekarno melihat
celah yang mengarah ke terjadinya konsepsi persatuan nasionalnya.
Hatta, dalam situasi seperti itu menurut UUDS semestinya bertugas
membantu Soekarno. Namun, hati Hatta tidak kuasa menahan
kecewa. Sebab, dengan mendukung Soekarno berarti mengebiri
demokrasi multipartai dan parlementer yang merupakan unsur pokok
dari kedaulatan rakyat yang sudah sejak awal diperjuangkannya.
Demokrasi parlementer memang sedang terganggu, tetapi untuk
menegakkan demokrasi bukan dengan mematikannya. Menjelang
mundur dari Dwitunggal, yaitu saat berpidato di Universitas Gadjah
Mada, Hatta menyerukan bahwa sejak 1950 pemerintahan
dijalankan dalam demokrasi parlementer yang tanpa demokrasi dan
tanpa parlemen sehingga yang terjadi anarki politik. Kekuasaan
sesungguhnya tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi dalam
dewan partai yang tidak bertanggung jawab.
Hatta mundur
Hatta mundur dari Dwitunggal pada 1 Desember 1956. Dikatakannya
bahwa meskipun ia meninggalkan jabatan wakil presiden, tetapi
rakyat sekali-kali tidak pernah ditinggalkannya. Hatta sepertinya
yakin bahwa posisi "oposisi" akan lebih membantu dalam rangka
memperbaiki kondisi carut-marut negerinya daripada mandul
sebagai wakil presiden. Hatta melihat bahwa perselisihan didalam
pemerintahan telah melupakan wajah-wajah pucat dan tubuh-tubuh
kering dari rakyat Indonesia yang miskin dan kekurangan pangan. Ia
memberi ingat akan tujuan semula kemerdekaan yang harus segera
diwujudkan, yaitu perbaikan kondisi kesejahteraan rakyat. Kecuali
itu, dilihatnya bahwa kebijakan perekonomian pusat tidak
menguntungkan daerah-daerah luar Jawa. Dalam mata Hatta,
pemberontakan regional dapat muncul sebagai suatu "letusan
kekecewaan" dan suatu "konflik kejiwaan antara pusat dan daerah".
Setelah berpisah, hubungannya dengan Soekarno tetap dijalin
dengan surat-menyurat. Dalam surat-suratnya itu, Hatta kerap
bersuara keras menentang kebijakan Soekarno yang sudah menjauh
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (9 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
dari mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, peringatan-peringatan
Hatta sering kurang diperhatikan Soekarno. Ia terus menggulirkan
konsepsi Demokrasi Terpimpin dengan didukung orang-orang di
sekelilingnya. Kecuali itu Hatta juga bersuara di surat kabar. Namun,
begitu surat kabar yang memuat tulisan Hatta diberangus, kemudian
tidak ada yang berani memuat gagasan-gagasan Hatta. Hatta
menyayangkan tindakan pemberangusan ini, sebab yang dirugikan
pasti banyak pihak. Tindakan kekerasan terhadap buah-buah pikiran
pada dasarnya merugikan diri sendiri. Pemberangusan yang
memakan banyak korban itu yang antara lain memaksa Hatta untuk
tidak bersuara lagi di surat kabar.
Dalam usaha menolong kondisi negeri yang krisis, Hatta
mengungkapkan perlunya orang kembali mencermati kadar rasa
tanggung jawab. Waktu itu, kehampaan tanggung jawab (emptiness
of responsibility) begitu menggejala di mana-mana dalam pelbagai
bentuknya. Kondisi rakyat tidak membangkitkan rasa perasaan apa
pun dalam diri para pengambil ke-putusan. Maka, antara lain Hatta
menganjurkan perubahan dalam sistem pemilihan umum yaitu
dengan diadakannya sistem daerah pemilihan. Sebab, dengan
begitu para wakil rakyat yang terpilih merasa bertanggung jawab
langsung terhadap rakyat. Bukannya bertanggung jawab kepada
partai yang telah menempatkannya sebagai wakil rakyat. Kecuali itu,
dalam perspektif tanggung jawab pemimpin kepada rakyatnya yang
harus dibangkitkan lagi, Hatta menulis Demokrasi Kita dalam
kerangka debat konsepsi demokrasi dengan Soekarno bersama
Demokrasi Terpimpin-nya yang pada dasarnya otoriter.
Tidak dapat disangkal bahwa pada diri Soekarno dan Hatta terdapat
kegelisahan besar untuk membangun dan menyusun bangsa dan
negaranya. Namun, memang harus diakui bahwa perbedaan
pandangan di antara keduanya terus mengikuti kegelisahan itu.
Yang menarik, persahabatan di antara mereka tidak retak sekalipun
ada perbedaan-perbedaan pandangan. Hatta pun sebenarnya masih
didukung sebagai pemimpin oleh kalangan-kalangan tertentu,
terutama dukungan dari rakyat Sumatera. Namun, Hatta tetap teguh
menjalani jalan sunyinya di luar gebyar panggung politik. Maka, ia
pun tidak menggalang dan mengerahkan massa untuk mendukung
butir-butir gagasannya.
Hatta memang tidak pernah datang kembali sebagai Dwitunggal
bersama Soekarno. Tetapi, kekayaan pengalamannya dalam
memperjuangkan rakyat ketika bertentangan dengan Soekarno
maupun ketika duduk bersama dalam Dwitunggal tidak pernah
hilang. Ia telah menghabiskan hidupnya dengan studi, debat, di
penjara, dan diasingkan. Ia pun sebagai Dwitunggal berada di bawah
bayang-bayang Soekarno. Ia lebih banyak diam merenung di dalam
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (10 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal -- Jumat, 1 Juni 2001
hati, tetapi berpikir bening dan jitu dalam strategi. Ia mengerti kapan
harus tampil, dan kapan turun panggung tanpa harus melukai
persatuan yang sudah dibangun bersama teman-temannya sejak
Perhimpunan Indonesia berdiri. Ia mengerti bagaimana menjalin
hubungan persahabatan dengan Soekarno meskipun nasihat-
nasihatnya sering tidak didengar. Ia mengerti kapan keras
menghardik dan kapan lembut menegur. Ia rela meninggalkan
segala-galanya, termasuk jabatan, kalau hati nuraninya terganggu.
Memang, sungguh butuh berlimpah hal untuk mengubah dunia,
seperti kata Bertolt Brecht (1898-1956), penyair Jerman, dalam
Einverstaendnis,
"it takes a lot of things to change the world:
Anger and tenacity. Science and indignation,
The quick initiative, the long reflection,
The cold patience and the infinite perseverance,
The understanding of the particular case and the understanding of
the enseble:
Only the lessons of reality can teach us to transform reality".
* In Nugroho Budisantoso Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat
Driyarkara, Jakarta.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Hatta%20Tak...sebagai%20Dwitunggal%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (11 of 12)4/3/2005 11:05:05 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno dan Gerakan Perempuan
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
Gadis Arivia
MEMBUKA lembaran-lembaran buku bersejarah tentang Soekarno
dan mencari tulisan-tulisan maupun paragraf-paragraf yang penting,
yang menuangkan gagasan Soekarno tentang perempuan,
mengantar kita ke lembaran sejarah pergerakan perempuan di masa
lalu.I
"Banjak orang jang tidak mengerti apa sebabnja saja anggap kursus-
kursus wanita itu begitu penting. Siapa jang membatja kitab jang saja
sadjikan sekarang ini,-jang isinja telah saja uraikan di dalam kursus-
kursus wanita itu dalam pokok-pokoknja-akan mengerti apa sebab
saja anggap soal wanita itu soal jang amat penting. Soal wanita
adalah soal-masjarakat!"
(Soekarno, Sarinah, 1947)
Representasi ini sangat mengesankan ketika melihat gambar-
gambar perjuangan perempuan yang dibalut kain kebaya
menyuarakan aspirasi mereka, bukan hanya soal kepandaian putri,
tetapi bahkan menyerukan perjuangan revolusioner.
Satuan perjuangan yang pertama adalah Lasjkar Wanita Indonesia
atau Lasjwi yang didirikan Aruji Kartawinata di Bandung tahun 1945.
Satuan ini mengangkat senjata dan berangkat ke garis depan medan
pertempuran, bergiat dalam melakukan perawatan prajurit yang
menderita luka, menyelenggarakan dapur umum dan menjahit
seragam prajurit. Satuan-satuan semacam ini menyebar ke seluruh
Jawa, serta Sumatera Tengah dan Selatan, Sulawesi Tengah dan
Selatan.
Di Jakarta terdapat organisasi Wani atau Wanita Negara In-donesia
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (1 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
(1945) yang dipimpin sejumlah tokoh seperti Suwarni Pringgodigdo
(Istri Sedar), Sri Mangunsarkoro, dan Suyatin Kartowiyono. Wani
mendistribusikan beras untuk tujuan perjuangan. Terdapat pula
organisasi-organisasi buruh seperti Barisan Buruh Wanita yang
berhaluan kiri, salah satu tokohnya adalah SK Trimurti.
Jauh sebelum masa perjuangan revolusioner, pergerakan
perempuan sebenarnya sudah dimulai oleh perempuan-perempuan
kelas menengah. Ada beberapa faktor mengapa kelas menengah
mengambil peranan yang penting di sini. Faktor-faktor tersebut
antara lain disebabkan tingkat pendidikan, waktu luang dan juga
akses informasi dan pengetahuan yang mereka miliki. Organisasi
yang cukup kuat misalnya adalah Putri Merdeka, yang dibentuk
tahun 1912 dan mempunyai afiliasi dengan Boedi Oetomo,
organisasi nasionalis pertama yang berdiri tahun 1908. Afiliasi ini
memperlihatkan bagaimana pada saat itu organisasi perempuan
sangat dekat dengan nasionalisme. Simbolisasi ini terlihat pada
Kartini, seorang perempuan priyayi. Isu-isu yang dilontarkan senada
dengan Kartini seperti persoalan pendidikan dan peningkatan
kepandaian putri. Organisasi perempuan kelas menengah lainnya
yang mempunyai nuansa agama adalah Muhammadiyah.
Organisasi perempuan mulai menjadi politis baru terlihat pada tahun
1920-an, ketika organisasi-organisasi politik yang besar seperti
Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis
Indonesia (PKI) mempunyai divisi perempuan. Organisasi-organisasi
perempuan ini mempunyai anggota yang bervariasi dalam latar
belakang sosial dan politiknya. Cakupannya meliputi tingkat kelas
menengah-bawah yang meluas. Isu-isu yang dilontarkan adalah
seputar partisipasi perempuan dalam politik dan keterlibatan
perempuan dalam pengambilan keputusan (decision-making).
Pada suasana seperti inilah hadir Soekarno yang pada akhir tahun
1920-an mulai mengemuka sebagai tokoh nasionalis. Ia mulai
terlibat dalam politik pada tahun 1926, dan satu tahun kemudian
pada tahun 1927 ikut menggagas PNI. Ketika Kongres Ibu diadakan
pertama kali pada tanggal 22 Desember 1928, Soekarno mengambil
kesempatan ini untuk mengemukakan pendapatnya tentang
perempuan.
II
"Berbahagialah kongres kaum ibu: diadakan pada suatu waktu, di
mana masih ada sahadja kaum bapak Indonesia jang mengira,
bahwa perdjoangannja mengedjar keselamatan nasional bisa djuga
lekas berhasil zonder sokongannja kaum ibu; Oleh karena daripada
kaum bapak masih banjak jang kurang pengetahuan akan harganja
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (2 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
sokongan kaum ibu itu; kita tidak sahadja gembira hati akan kongres
itu oleh karena kaum bapak belum insjaf akan keharusan kenaikan
deradjat kaum ibu itu,-kita gembira hati ialah teristimewa djuga oleh
karena di kalangan kaum ibu sendiri belum banjak jang mengetahui
atau mendjalankan kewadjibannja ikut menjeburkan diri di dalam
perdjoangan bangsa, dan belum banjak jang berkehendak akan
kenaikan deradjat itu."
(Soekarno: Kongres Kaum Ibu, 1928)
PIDATO Soekarno pada Kongres Kaum Ibu tahun 1928 ini amat
penting untuk membaca penempatan perempuan dalam pemikiran
Soekarno. Ia menyokong hak-hak perempuan, namun ia
menganggap perjuangan hak perempuan harus nomor dua setelah
perjuangan kemerdekaan. Dan bila perjuangan hak-hak perempuan
itu tercapai, perjuangan tersebut belum cukup karena kepentingan
nasional belum terwujud.
Ia melontarkan pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi kepada kaum
perempuan saat itu: "Apakah kiranja sudah tjukup, jang kaum ibu
Indonesia mendjadi sama haknja dengan kaum bapak Indonesia-hak
kaum bapak Indonesia jang terikat-ikat ini? Apakah kiranja sudah
tjukup, jang kaum ibu Indonesia mendjadi sama deradjatnja dengan
kaum bapak Indonesia,-deradjat kaum bapak Indonesia jang tak
lebih daripada deradjatnja orang djadjahan, tak lebih daripada
deradjatnya putera negeri jang tak merdeka?" (Kongres Kaum Ibu,
1928)
Awalnya dalam Kongres Kaum Ibu, pandangan-pandangan
Soekarno tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Tigapuluh
perempuan yang mengikuti kongres tersebut tetap berkonsentrasi
untuk mendiskusikan isu-isu perempuan dan bukan nasionalisme.
Bahkan, ada tuduhan terhadap Soekarno yang ingin "memolitikkan"
isu-isu perempuan bagi kepentingan politiknya. Terhadap tuduhan
ini, Soekarno mengelak dengan mengatakan bahwa soal perempuan
adalah soal yang luas.
"Kita tidak mempolitikkan soal ini! Kita memudjikan pendirian jang
demikian, tak lain tak bukan ialah oleh karena pada hakekatnja soal
perempuan tidak dapat dipisahkan daripada soal laki-laki. Kita pun
harus memperingatkan, bahwa jang menderita pengaruhnja sesuatu
proses kemasjarakatan, dus djuga proses kolonial sebagai di sini,
ialah bukan sahadja satu bagian, bukan sahadja kaum laki-laki,
tetapi semua manusia laki-perempuan jang berada di dalam
lingkungannja proses kemasjarakatan itu." (Kongres Kaum Ibu,
1928)
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (3 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
Tak lama setelah Kongres Kaum Ibu diadakan, beberapa organisasi
baru terbentuk. Di antaranya adalah Perikatan Perempuan Indonesia
(PPI) yang namanya kemudian berubah menjadi Asosiasi
Perempuan Indonesia (API). Tahun 1935, berganti nama lagi
menjadi Kongres Perempuan Indonesia (KPI).
Dalam kiprah politiknya, kelompok ini kelihatannya mengambil "jalan
tengah" yakni bermain di antara isu-isu perempuan dan
nasionalisme, antara isu perkawinan yakni monogami dengan
pendidikan campuran (anak laki-laki dan perempuan). Kelompok ini
berusaha menjaga harmoni antara kelompok yang berbasis agama
dan yang sekuler.
Kali ini, Soekarno berhasil mencuri perhatian kelompok perempuan
apalagi ide memperjuangkan kemerdekaan dapat merangkul
kelompok-kelompok perempuan berbasis agama yang masih curiga
dengan isu-isu perempuan yang diperjuangkan, seperti hak seorang
istri untuk meminta perceraian bila sang suami mempunyai istri
kedua.
Situasi ini menimbulkan per-debatan yang seru di antara kelompok
perempuan. Maria Ulfah Subadio yang lama aktif di dunia politik dan
kemudian menjadi menteri perempuan pertama Indonesia
merefleksikan ketegangan yang terjadi saat itu, dan menyimpulkan
bahwa: "Kita memang bukan merupakan sebuah gerakan feminis,
kita tidak pernah mendjadi sebuah gerakan feminis, kita berfikir lebih
baik melawan pendjadjahan daripada melawan laki-laki. Djadi, kita
membutuhkan laki-laki sebagai sekutu." (Doran, 1987:104)
Setelah Kongres Perempuan Indonesia berakhir, beberapa
organisasi kelompok perempuan bermunculan untuk mengangkat
persoalan politik negeri. Tahun 1930, Istri Sedar yang dibentuk di
Bandung menyatakan diri ingin meningkatkan status perempuan
Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan. Ide dasarnya adalah
bahwa tidak akan ada persamaan hak antara laki-laki dan
perempuan bila tidak ada kemerdekaan.
Sesudah Jepang menyerah, kaum perempuan dari kalangan parpol
dan ormas berbasis agama seperti Aisyah dan Wanita Katolik
membuat agenda untuk menunjang perjuangan. Hal yang sama
dilakukan juga oleh Wanita Muslimat dari Masyumi.
Istri-istri anggota angkatan bersenjata seperti anggota Bhayangkari
(1945) dan istri-istri Angkatan Laut (1946) melakukan kerja sama
untuk saling membantu dalam perjuangan terutama apabila suami
mereka tewas. Pada Kongres Kaum Perempuan di Klaten pada
bulan Desember 1945, Persatuan Wanita Republik Indonesia
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (4 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
(Perwari) bertekad mendukung revolusi nasional.
III
"Sekarang kita telah Merdeka. Kita telah mempunjai Negara. Kita
telah mempunjai Republik. Bagaimanakah aktiviteit wanita di dalam
perdjoangan Republik kita itu? Inilah soal jang amat penting, jang
diinsjafi sungguh-sungguh oleh semua pemimpin wanita Indonesia.
Malahan bila mungkin, djangan ada seorang wanita pun jang tidak
insjaf, djangan ada seorang pun di antara mereka jang ketinggalan!
Dengan tiada berfaham komunis saja dapat mengagumi ucapan
Lenin: "Tiap-tiap koki harus dapat mendjalankan politik"Maka saja
berkata: "Hai wanita-wanita Indonesia, djadilah revolusioner,-tiada
kemenangan revolusioner, djika tiada wanita revolusioner, dan tiada
wanita revolusioner, djika tiada pedoman revolusioner!" Tiap-tiap
pergerakan jang menghantam, melemahkan, menggempur
imperialisme adalah pergerakan-pergerakan revolusioner." (Sarinah,
1947:247,283)
SEJAK Awal tahun 1930-an Soekarno telah masuk dalam fase baru
dalam perkembangan pemikiran politiknya, yaitu menguatnya
konsep-konsep marxisme di dalam dirinya. Baginya, perjuangan
perempuan yang lebih penting adalah penghancuran kapitalisme.
Hal inilah yang ia tekankan kepada kaum perempuan dengan sekali
lagi menegaskan bahwa "kesetaraan antara laki-laki dan perempuan
tidak tjukup. Ada kebutuhan jang lebih besar lagi jaitu penghancuran
sistem kapitalis". (Doran, 1987:104).
Hampir separuh buku Sarinah, menguraikan pandangan-pandangan
dan pemikiran-pemikiran pergerakan perempuan sosialis. Nama
yang kerap mun-cul di dalam buku ini adalah Clara Zetkin yang oleh
Soekarno dijuluki sebagai "ibu besar" dari pergerakan proletar
sedunia. Ia menceritakan bagaimana Zetkin menggagas Kongres
Perempuan Internasional bersama Rosa Luxemburg. Perjuangan
hak mengikuti pemilihan umum memang merupakan agenda
pertama dari mereka dan ini diperjuangkan melalui Kongres
Perempuan Internasional. Namun, tidak hanya berhenti di sini, ia
juga memperluas perjuangannya dalam soal menggempur
kapitalisme.
Pembesaran figur Zetkin oleh Soekarno sebenarnya cukup
berlebihan dan mengalami polesan yang sedemikian rupa untuk
menjaga kepentingan pemikirannya sendiri yang sedang mengeras
ke arah "kiri". Ia sama sekali tidak menjelaskan protes gerakan
perempuan sosialis akan keberatan mereka terhadap ide-ide dan
aksi-aksi mengalahkan kepentingan perempuan demi kepentingan
ideologi. Ia juga tidak menyinggung betapa Zetkin berusaha
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (5 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
mendiskusikan secara terbuka isu-isu kesetaraan dalam diskusi
perempuan dalam Partai Komunis yang saat itu mendapat teguran
keras dari Lenin. Bagi Lenin apa yang dikerjakan Zetkin-yaitu
mendiskusikan isu-isu perempuan-tidak memberikan kontribusi
dalam perjuangan revolusioner. Menurut Lenin, yang seharusnya
dilakukan oleh Zetkin bukan membuang-buang waktu membicarakan
soal-soal perempuan tetapi membangkitkan gairah dan kesadaran
perjuangan revolusioner menentang kapitalisme pada perempuan.
Sebaliknya, bagi Zetkin, persoalannya jelas bahwa terdapat
kebutuhan bagi perempuan untuk memahami dan menghubungkan
penindasan yang terjadi di bidang "privat" maupun "publik". Ia
mengerti benar mengapa perempuan tertindas dan hal ini tampaknya
sama sekali tidak dipahami oleh Lenin. Marxisme menjelaskan
mengapa kapitalisme mengakibatkan adanya pembagian kerja
antara perempuan dan laki-laki, pemi-sahan antara perempuan di
dunia domestik dan laki-laki di dunia publik. Tetapi, marxisme tidak
menjelaskan mengapa sebelum ada kapitalisme pemisahan tersebut
sudah terjadi. Bagi Zetkin, baik kategori Marx maupun kapital sama-
sama buta terhadap persoalan perempuan.
Tokoh-tokoh feminis sosialis setelah Zetkin kemudian
mengagendakan persoalan perempuan sebagai yang utama, baru
kemudian persoalan kelas. Walaupun feminis sosialis setuju dengan
para feminis marxis bahwa pembebasan perempuan bergantung
pada penghancuran kapitalisme, namun mereka juga sadar bahwa
kapitalisme tidak dapat dihancurkan bila patriarki tidak dimusnahkan.
Bagi mereka materi atau hubungan ekonomi masyarakat tidak akan
mengalami perubahan yang berarti bila ideologi patrarki tidak
dirubah. Perempuan dengan demikian harus berperang melawan
dua musuh sekaligus, yakni kapitalisme dan patriarki. Baru di sana
pembebasan yang sejati terhadap perempuan bisa terwujud.
Pada tahun 1950-an, badan organisasi perempuan diakui bukan lagi
hanya satu. Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang dibentuk pada
tahun 1946 untuk menunjang perjuangan kemerdekaan, bubar.
Kongres Wanita Indonesia hanyalah salah satu upaya untuk
memfasilitasi kontak di antara organisasi perempuan, namun tidak
memiliki otoritas melakukan keputusan sendiri. Organisasi
perempuan yang cukup kuat saat itu adalah Gerwis, sebuah
organisasi yang independen bertujuan memajukan pendidikan
perempuan dan menyediakan fasilitas penitipan anak. Tahun 1954,
organisasi Gerwis menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan
kemudian menjadi organisasi yang tangguh memiliki paling tidak
satu juta anggota. Walaupun tidak ada hubungan yang resmi antara
Gerwani dan PKI, namun seringkali Gerwani dipandang sebagai
bagian dari divisi perempuan PKI. Hubungan yang erat antara
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (6 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
Gerwani dan pergerakan buruh (SOBSI) serta PKI, membuat
hubungan Gerwani dengan Soekarno menjadi sangat dekat.
IV
"Setelah bayiku berumur dua hari, waktu aku sedang berbaring, pagi-
pagi benar datanglah Bung Karno. Bung Karno du-duk di depanku
dan kemudian berkata: 'Fat, aku minta izinmu, aku akan kawin
dengan Hartini.' Aku dengarkan saja apa yang Bung Karno utarakan
tadi dengan seksama dan tenang. 'Boleh saja,' kataku menjawab,
tetapi Fat minta dikembalikan pada orangtua. Aku tidak mau dimadu
dan anti poligami. Tetapi aku cinta padamu dan juga cinta pada
Hartini, demikian Bung Karno. 'Oo, tak bisa begitu!,'
kataku." (Fatmawati, 1978:80)
PERKAWINAN Soekarno dengan Hartini pada tahun 1954
merupakan tamparan keras bagi kelompok perempuan. Hubungan
Soekarno dengan gerakan perempuan menjadi tegang. Popularitas
Soekarno jatuh dan ide-ide besarnya tentang perempuan di dalam
bukunya Sarinah dipertanyakan. Ketegangan pun terjadi di antara
kelompok perempuan. Nani Suwondo dari Perwari yang mendukung
Fatmawati untuk meninggalkan Istana menyesalkan tindakan
Gerwani, yang tidak memprotes perkawinan Soekarno dengan
Hartini.
Gerwani dituduh lebih berat membela politik dan bukan kepentingan
kaum perempuan. Protes Perwari sebaliknya merugikan
organisasinya sendiri. Banyak anggota Perwari yang mengundurkan
diri dari organisasi karena suami mereka mendapat tekanan di
tempat kerja. Perwari selanjutnya kehilangan dukungan dan tidak
menerima bantuan apa pun. Sujatin Kar-towiyono sebagai Ketua
Perwari pada saat itu banyak menerima tekanan, intimidasi, bahkan
ancaman mati.Setelah perkawinan Soekarno dengan Hartini,
reformasi undang-undang perkawinan berjalan semakin lambat.
Sebelumnya telah terjadi perbedaan pendapat yang mencolok antara
kelompok perempuan yang berbasis agama dengan yang sekuler.
Kemudian setelah Soekarno marah besar pada gerakan perempuan
Indonesia, perjuangan reformasi undang-undang perkawinan
semakin sulit. Baru pada tahun 1954, rancangan undang-undang
perkawinan diajukan pada Kementerian Agama, namun, dibutuhkan
tiga tahun lamanya, dan pada tahun 1957 rancangan tersebut
dibahas dalam sidang kabinet pari-purna. Pada bulan Maret tahun
1958, PNI mengusulkan rancangan undang-undang perkawinan ke
parlemen yang lebih radikal lagi, yakni menuntut monogami bagi
seluruh bangsa Indonesia dan menjamin hak-hak yang sama dalam
penceraian untuk perempuan.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (7 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
Tentunya kata sepakat tidak tercapai dalam parlemen, karena ide ini
tidak didukung oleh kalangan Muslim. Kompromi kemudian dicapai
melalui ga-gasan Bhayangkari, bahwa permaduan diizinkan bagi
suami-istri Muslim, tetapi kitab Un-dang-Undang Perkawinan Sipil
mendasarkan diri pada aspek monogami. Perjalanan perjuangan
undang-undang perkawinan setelah ini masih panjang karena
ditentang Kementerian Agama. Perempuan Indonesia harus
menunggu sampai tahun 1973 untuk mendapatkan undang-undang
perkawinan baru yang melarang poligami.
"Sudah lama bunga Indonesia tiada mengeluarkan harumnja,
semendjak sekar jang terkemudian sudah mendjadi laju. Tetapi
sekarang bunga Indonesia sudah kembang kembali, kembang
ditimpa tjahaja bulan persatuan Indonesia; dalam bulan jang terang
benderang ini, berbaulah sugandi segala bunga-bungaan jang
harum, dan menarik hati jang tahu akan harganja bunga sebagai
hiasan alam jang diturunkan Ilahi. (Soekarno, Kongres Kaum Ibu,
1928)
PRIBADI presiden pertama Republik Indonesia ini memiliki tiga ciri
persona yang menarik, yakni charm, kharisma, dan pamor (sinar
cahaya). Ia juga sangat ahli dalam berkata-kata, sangat puitis dan
sekaligus tajam dilengkapi daya analisa yang kritis. Secara
keseluruhan, ia adalah laki-laki yang cute (elok) dan smart (tampan,
cerdas), sangat menonjol dari laki-laki pada zamannya. Karya
besarnya tentang perempuan yang ia tuangkan dalam bukunya
berjudul Sarinah setebal 329 halaman ini, menunjukkan
keseriusannya dalam membedah persoalan-persoalan perempuan.
Pada bab-bab pertama, ia membahas soal laki-laki dan perempuan,
soal "alam" dan "kultur" serta menunjukkan bagaimana perempuan
didefinisikan oleh kultur. Pada bab-bab berikutnya, ia menjelaskan
keadaan perempuan dan menyatukannya dengan pemikiran-
pemikiran feminisme marxis/sosialis. Pada bab-bab terakhir,
Soekarno mempertegas kewajiban perempuan, yakni ikut serta
menyelamatkan Republik memperkuat Negara Nasional. Ia
menjanjikan bahwa setelah negara terselamatkan, masyarakat adil
dan sejahtera, dan perempuan pada akhirnya akan bahagia dan
merdeka.
Benarkah janji itu terpenuhi? Kaum feminis belajar dari sejarah
bahwa perjuangan bentuk apa pun yang meletakkan perjuangan
perempuan sebagai bukan yang utama, akan mengalami penipuan.
Segala bentuk penipuan terhadap perempuan adalah hal yang biasa
dan sering dialami. Beberapa kali dalam sejarah perempuan diminta
untuk memperjuangkan kemerdekaan dahulu baru kemudian hak-
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (8 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
haknya. Memperjuangkan ideologi dahulu baru hak-haknya?
Memperjuangkan demokrasi dahulu baru hak-haknya? Sudah
seringkali di negara ini dan di belahan dunia lainnya, perempuan
"dipakai" untuk tujuan-tujuan politik tertentu, yang lebih besar dan
lebih agung. Bahkan, Gerwani akhirnya disingkirkan oleh rezim Orde
Baru demi kepentingan politik rezim tersebut.
Seluruh filsafat abad modern memuja ide-ide besar, agung dan
kebenaran mutlak. Soekarno dalam perspektif filsafatnya tidak dapat
dilepaskan dari keterbelengguannya dengan "teori-teori
besar" (grand theory), yang menganggap seluruh entitas ini sebagai
suatu keseluruhan dan universal. Demikian pula pemikiran-
pemikirannya tentang perempuan merupakan suatu entitas yang
tidak dapat dipisahkan dari totalitas universal. Soekarno
menganggap perempuan hanyalah suatu bagian dari suatu subyek
yang lebih besar lagi, yakni revolusi, ideologi, negara, suatu
rasionalitas yang semuanya diterjemahkan dengan cara berpikir
maskulin.
Apakah ide-ide perempuan? Bagaimanakah moralitas dan etika
perempuan? Kehidupan moral perempuan bukanlah da-tang dari ide-
ide besar melainkan dari kehidupan sehari-sehari yang ia jalani:
kehidupan ruang domestik yang ia geluti, ruang pribadi yang
menyangkut kesejahteraan keluarganya, relasi-relasi kecil yang
mempunyai keterikatan emosional, dunia feminitas yang tampak
sederhana dari luar namun sangat kompleks dalam kehidupan
perempuan. Soekarno tidak dapat mengerti pentingnya undang-
undang perkawinan bagi kelompok perempuan, Lenin sulit
memahami mengapa perempuan perlu berdiskusi segala tetek
bengek yang ia anggap buang-buang waktu saja.
Feminisme tidak pernah tertarik untuk membangun suatu teori yang
abstrak dengan prinsip-prinsip universal. Feminisme seringkali
mengambil posisi epistemologis yang menentang suatu pencarian
rasionalistik dan sistem universal. Sebaliknya, pencarian feminisme
selalu ditekankan pada pengalaman moral. Feminis Annette Baier
(1985) mengatakan bahwa perempuan dalam perdebatan moralnya
mempunyai kehendak yang berbeda dari laki-laki, perempuan lebih
menitikberatkan nilai-nilai etika yang berarti bagi kehidupannya.
Perempuan hidup di dalam masyarakat yang nilai-nilai kefemininnya
dianggap remeh dan tidak penting, seluruh eksistensinya sebagai
perempuan disubordinasikan. Dalam masyarakat yang patriarkis,
seluruh aturan universal berlaku pada sistem "aturan laki-laki" (the
law of the father), sifat egois yang berpusat pada kemauan laki-laki
sehingga dunia publik menjadi dominasi laki-laki.
Bagi feminisme amatlah jelas, hak-hak perempuan sebagai manusia
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (9 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan -- Jumat, 1 Juni 2001
harus diperjuangkan terlebih dahulu agar ia setara dengan jenis
manusia lainnya, bila ini telah tercapai, terwujudlah masyarakat yang
adil dan makmur, negara yang merdeka dan demokratis.
Ah, seandainya Soekarno memahami hal ini.
* Gadis Arivia Ketua Yayasan Jurnal Perempuan, staf pengajar
Jurusan Filsafat Fakultas Sastra Universitas Indonesia (UI) dan
Kajian Wanita UI.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
● Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
● Bung Karno, Seni, dan Saya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Kepentingan...entingan%20Perempuan%20--%20Jumat,%201%20Juni.htm (10 of 11)4/3/2005 11:05:07 AM
Koleksi dan Karya Presiden Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Koleksi dan Karya Presiden Soekarno
Presiden Soekarno
Karya : Basuki Abdullah
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Koleksi%20d...en%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 5)4/3/2005 11:05:08 AM
Koleksi dan Karya Presiden Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Judul : Peperangan antara Gatutkatja dan Antasena
Karya : Basuki Abdullah
Judul : Persiapan Gerilya
Karya : Dullah
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Koleksi%20d...en%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 5)4/3/2005 11:05:08 AM
Koleksi dan Karya Presiden Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Judul : Kawan-kawan Revolusi
Karya : S Sudjojono
Judul : Si Denok
Karya : M Pastori (Swiss)
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Koleksi%20d...en%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 5)4/3/2005 11:05:08 AM
Koleksi dan Karya Presiden Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Judul : Potret Seorang Putri
Karya : Soekarno
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Koleksi%20d...en%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 5)4/3/2005 11:05:08 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan
Masa Muda Bung Karno
Sartono Kartodirdjo
PANCAROBA
masa
peralihan
abad ke-19 ke
abad ke-20
ialah ucapan
yang lumrah
diketengahkan
dalam sejarah
Indonesia
bahwa suatu
jiwa zaman
(zeitgeist)
membentuk
kepribadian
Dok Kompas seseorang
yang hidup di
masa itu, dan
sebaliknya pribadi tokoh sejarah menempa jiwa zaman. Abad ke-20
bercirikan nasionalisme serta produk perkembangannya, ialah negara
nasion, maka berbicara tentang Bung Karno tidak lepas dari
nasionalisme, dan sebaliknya perkembangan nasionalisme tidak dapat
lepas dari peran kepemimpinan Bung Karno.Beberapa dasawarsa
menjelang tahun 1900, Indonesia, khususnya Jawa, mengalami
perubahan ekonomi sosial dan politik sebagai dampak modernisasi
seperti pembangunan komunikasi, antara lain kereta api, jalan raya,
telepon, telegraf, industri pertanian dan pertambangan, edukasi dari
sekolah rendah sampai pelbagai pengajaran profesi dalam kedokteran,
teknologi pertanian dan lain sebagainya. Tidak mengherankan apabila
timbul peningkatan mobilitas, pendidikan profesi, ekonomi pasar, serta
ekonomi keuangan dan lain-lain.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (1 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
Kebingungan rakyat dalam menyikapi perubahan itu menciptakan pada
rakyat sejak kira-kira pertengahan abad ke-19 pandangan dunia, seperti
gambaran kuno ialah datangnya kaliyuga atau datangnya kiyamat
(apocalyps). Kedatangan akhiring zaman ditandai antara lain oleh "Pulau
Jawa sudah berkalung besi" (adanya kereta api), anak yang sudah tahu
nilai uang akibat adanya monetisasi, anak tidak lagi mematuhi kata
orangtua, dan sebagainya. Adanya kebingungan berubahnya nilai-nilai,
karangan pujangga terakhir Ranggawarsita maka dalam serat Kalatida
menyatakan "jamannya ialah jaman edan" "Jamane jaman edan sing ora
edan ora keduman... Begja begjane kang lali luwih begja kang eling lan
waspada."
Di sini zaman penuh perubahan nilai-nilai menimbulkan kebingungan,
karena orang kehilangan pegangan sehingga kelakuannya serba aneh
(seperti orang gila). Orang tidak jujur (korup) menjadi kaya dan yang
jujur tidak menjadi kaya akan tetapi yang paling bahagia adalah orang
yang tetap ingat (jujur) serta waspada. Sang pujangga menilai zaman
pancaroba serba negatif, terutama dari pandangan tradisional jadi
konservatif karena perubahan membahayakan masyarakat tradisional,
maka perubahan mengancam tradisi. Ucapan Ranggawarsita tidak lagi
diindahkan pada zaman emansipasi, justru kemajuan yang menjadi
tujuan hidup kaum "kebangkitan" yang disebut dalam sejarah, meskipun
mereka menyebut diri sendiri kaum maju.
***
PARA kaum maju merupakan akar pergerakan nasional atau lazim
disebut kebangkitan nasional. Dari Kartini bersaudara sampai Bung
Karno dan Bung Hatta merupakan proses pergerakan nasionalisme yang
berideologi melawan kolonialisme Belanda, gerakan nasionalisme
merupakan antitesis terhadap kolonialisme. Kolonialisme bercirikan
diskriminasi antara kaum kulit putih dengan kaum kulit berwarna,
ekonomi dualistis, dan segregasi pemukiman.
Faktor-faktor tersebut dilambangkan secara menonjol dalam kehidupan
sehari-hari, membawa dampak pada kaum pribumi, yaitu merasakan
serba rendah (inferior), dalam bahasa kini disebut minder. Golongan
yang terdahulu merasakan hal tersebut adalah kaum intelektual
(terpelajar). Merekalah yang menyadari stigmanya sebagai pribumi yang
sedang mengalami krisis identitas. Meskipun telah terpelajar namun
mereka belum diakui sama status dengan kaum Eropa. Tambahan pula
feodalisme masih sangat kuat di kalangan ambtenar dan priyayi
sehingga kedudukan mereka masih sangat ditentukan oleh ikatan
feodalnya. Dalam pada itu modernisasi telah banyak menghapus
identitas tradisional serta komunal sehingga mereka perlu mencari
identitas baru yang sesuai dengan modernisasi gaya hidup mereka.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (2 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
Mobilisasi, urbanisasi, dan detradisionalisasi memungkinkan ada
pelembagaan solidaritas baru, berupa perkumpulan antara lain Boedi
Oetomo, Sarekat Islam, Pasundan. Kecuali berbentuk forum baru,
organisasi itu berfungsi sebagai identitas kolektif. Di sini kita menghadapi
bentuk ekspresi etno-nasionalisme atau religio-nasionalisme.
Meskipun ketiga emansipator pada dekade pertama abad ke-20 yaitu
Kartini, Wahidin, dan Soetomo sebagai perintis emansipasi memusatkan
perhatian kepada keterlibatan solidaritas nasional masih terbatas, tetapi
dipusatkan perhatiannya pada aspek modernisasi yang bervariasi. Di sini
kita menghadapi fakta historis berupa konvergensi dua proses, yaitu di
satu pihak pada Bangsa Indonesia timbul kesadaran adanya status
serba rendah di bawah sistem penjajahan, sedangkan di pihak lain pada
Bangsa Belanda muncul kesadaran betapa besar penderitaan rakyat
terjajah serta beratnya kewajiban moral dalam pelaksanaan
pemerintahan kolonial.
Adapun dalam masyarakat Belanda sementara itu timbul kepedulian
terhadap situasi Hindia Belanda sebagai negeri yang merosot
kesejahteraannya, di samping itu dirumuskan politik kolonial mission
sacre, yang terwujud berupa gerakan missi dan zending. Dipicu oleh
proses perkembangan dan perubahan konsep kolonialisme, tambahan
pula sebagai ideologi kolonialisme sebagai dampak penyebaran literatur
kolonial sejak Max Havelaar dari Multatuli (EEF Douwes Dekker) sampai
Du Peron. Gambaran tentang Hindia Belanda sebagai jajahan mulai
berubah. Politik etis bertujuan memberikan kemudahan untuk kemajuan
serta kesejahteraan rakyat.
Perlu ditambahkan di sini suatu interpretasi ekonomi bertujuan
industrialisasi pertanian serta penanaman modal, maka fungsi jajahan
berubah, ialah sebagai pasar penanaman modal. Untuk mendorong hal
itu perlu ada perbaikan transportasi serta membuka banyak lahan untuk
perkebunan. Perlu dicatat di sini bahwa ideal dalam politik etis ialah akan
menciptakan kaum terpelajar yang Neerlandophil. Sesungguhnya
pendidikan yang dikembangkan memuat gagasan P Kennedy adalah
dalam jangka panjang menjadi satu bom waktu bagi kolonialisme.
***
MENYINGGUNG lagi masalah emansipasi, ketiga emansipator tersebut
di atas menjadikan pendidikan sebagai dasar modernisasi yang
mencakup tiga segi, yaitu: a. pendidikan wanita, b. biaya pendidikan
(beasiswa), c. pendidikan pada umumnya. Pidato Soetomo dalam
kongres "Jong Java" menyatakan bahwa dewasa itu pembangunan
masih terbelakang. Dipandang dari segi historis politik kolonial
menghasilkan hominies novi (manusia baru) atau priyayi intelegensia
yang akan berperan sebagai modernisator atau aktor intelektualis dalam
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (3 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
profesionalisme teknologi bidang industri, pertanian, kedokteran,
biroktasi, pendidikan, dan sebagainya.
Dalam menyebut pendidikan sebagai unsur politik kolonial perlu
diketengahkan Politik Etis pada awal abad ke-20 dengan trilogi (sic)
sebagai langkah pelaksanaan pidato Ratu Wilhelmina pada tahun 1901
serta merupakan perwujudan ekspresi dari edukasi, irigasi, dan emigrasi.
Pada akhir dekade pertama kita menjumpai kultur gaya hidup kaum maju
yang terdiri atas kaum priyayi inteligensia serta pimpinan bangsawan
atau kaum aristokrasi (Boedi Oetomo). Maka selaras dengan kondisi itu
sifat organisasi, gerakannya tidak mungkin radikal. Kaum pedagang
menengah dan penduduk kota sebagai anggota Muhammadiyah juga
lebih bersifat moderat, sedang SI yang mencakup lapisan menengah
sampai bawah terdiri atas aneka ragam golongan antara lain golongan
petani, golongan pertukangan industrialis rumah tangga, serta pedagang
kecil. Acap kali ideologinya merupakan campuran antara gerakan
tradisional dan setengah modern kota. Meskipun masih bercorak
etnonasionalistis, namun sudah ada komunikasi antara golongan bawah
menengah dan atas.
Contoh yang jelas mengenai bentuk komunikasi tersebut di atas ialah
kongres Jong Java pada 3-5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Kongres itu
sudah dipersiapkan sejak 20 Mei 1908. Bagaimana semangat dan sikap
kaum maju dalam akhir dekade pertama dapat diamati selama kongres
tersebut. Sangat menonjol jenis nasionalisme pertemuan itu ialah
etnosentrisme. Namun, meskipun ada keterbatasan peserta, terutama
dari Jawa, pertemuan itu sudah berhasil menghimpun pelbagai
golongan, antara lain golongan bangsawan, golongan aristokrasi, dokter,
guru, siswa dari pelbagai sekolah. Mereka duduk sama tinggi dan
berbahasa satu.
***
INI semua memberikan makna, bahwa tidak lagi dipatuhi aturan feodal
dan ada komunikasi lebih bebas. Di sini kita melihat tanda-tanda
permulaan dari demokrasi. Dari substansi pembicaraan terbukti
perhatian mereka luas, mencakup kesejahteraan kehidupan rakyat dan
bagaimana mereka menyikapi kebudayaan Barat. Dua hal yang menarik
untuk diungkapkan masa itu ialah, pertama, pidato Soetomo; dan kedua,
dialog antara dokter Tjipto Mangunkoesoemo dan dokter Radjiman
Wedyodiningrat. Dokter Soetomo mengutarakan keadaan negerinya
yang serba terbelakang di pelbagai bidang, antara lain bidang
kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, perumahan, dan
sebagainya.
Pidato itu mencakup pelbagai segi kehidupan rakyat yang sangat
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (4 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
komprehensif, tetapi tidak disinggung masalah politik, diskriminasi sosial
dan serba tertinggal dalam tingkat pendidikan. Sesuai dengan tingkat
kepriyayiannya, dokter Soetomo tidak melancarkan kritik terhadap pihak
kolonial, masih jauh dari retorik serta diskusi Bung Karno dua dekade
kemudian.
Apabila pada masa reformasi sekarang ini perubahan masyarakat
ekonomi sosial politik dan kultural tidak dapat ditinjau lepas dari proses
globalisasi, pada waktu itu perubahan peradaban masyarakat tidak lepas
dari proses westernisasi. Dokter Tjipto Mangunkoesoemo lebih
berpandangan progresif, bahwa kemajuan dapat dicapai dengan
menerima dan menyikapi positif proses westernisasi terutama dalam
segi teknologinya.
Sebagai visi alternatif dokter Radjiman Wedyodiningrat mengutarakan
bahwa mungkin lebih baik tetap bersifat konservatif dalam menghadapi
westernisasi. Bangsa Indonesia telah memiliki kultur atau peradaban
sendiri, lebih-lebih dengan perbendaharaan yang cukup kaya raya,
khususnya dalam hal ini pembicara merujuk kepada kesenian dan
Kesusastraan Jawa. Dengan pandangan seperti tersebut di atas
Radjiman lebih condong mempertahankan kebudayaannya sendiri serta
berhati-hati dalam menerima kebudayaan Barat, sedang dokter Tjipto
Mangoenkoesoemo lebih cenderung menerima westernisasi terutama
yang dimaksud bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Rupanya pada
zaman Soekarno kolonialisme semakin kuat sistem dominasinya
sehubungan dengan ancaman Perang Dunia II serta ancaman ekspansi
Jepang.
Pidato-pidato Soekarno semakin lebih tegas menyerang kolonialisme
dan imperialismenya negara Barat. Nyatanya nasionalisme Indonesia
pada fase-fase perkembangannya merupakan reaksi sesuai dengan
zeitgeist. Lagi pula Soekarno dalam nasionalisme dan ideologinya
menyesuaikan diri dengan visi masa depan. Dalam menghadapi
modernisasi lewat westernisasi oleh para kaum maju, jelas disadari
bahwa tidak ada jalan lain daripada mengutamakan edukasi menurut
sistem Barat. Suatu ide yang telah dikemukakan Ibu Kartini dan Dewi
Sartika, di samping itu juga generasi muda dari kalangan aristokrat.
***
SEPERTI diketahui umum, perhatian para pemimpin modernisasi pada
awal dekade kedua terpusat pada aktivitasnya pada pendirian sistem
pendidikan modern dengan bentuk adaptasi kepada kebudayaan
Indonesia, baik Jawa, Sunda, dan Melayu. Sistem pendidikan
Muhammadiyah, Taman Siswa, dan Kayu Taman di satu pihak memakai
didaktik serta teknik modern sistem Barat, di pihak lain materai mengajar
menurut agama atau kebudayaan. Baik ciptaan KH Mohammad Dahlan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (5 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
maupun dari Ki Hajar Dewantoro dan Mohammad Syafii, bagi
masyarakat pribumi sangat relevan dengan kebutuhan modernisasi
dewasa itu. Meskipun sistem tersebut menjauhi pendidikan politik,
namun secara politis pengaruhnya sangat besar. Lain lagi dengan
organisasi Sarekat Islam yang secara umum membangkitkan kesadaran
agama dan kebudayaan.
Dalam abad ke-19 dan awal abad ke-20 sudah ada tanda-tanda
munculnya revivalisme Islam di Hindia Belanda pada umumnya dan
Jawa khususnya. Sarekat Islam didirikan oleh Haji Samanhoedi di Solo
pada tahun 1911 dan cepat menyebar ke seluruh nusantara dan jumlah
anggota meningkat secara cepat. Maka tidak mengherankan apabila
pemerintah Hindia Belanda sangat waswas sehingga dipraktikkan politik
klasik divide et impera, sehubungan dengan itu maka dilarang untuk
membuat cabang-cabang. Meskipun demikian timbul dominasi pimpinan
Sarekat Islam pusat di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Di sini kita
jumpai seorang tokoh lokal yang rupanya dapat kita anggap selaku
model peran bagi Soekarno, terutama pada keterampilan berpidato di
muka massa, khususnya retorikanya. Tokoh-tokoh pemimpin seperti
dokter Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat, HOS
Tjokroaminoto, dan EEF Dauwes Dekker (Dokter Setia Boedi) yang
menunjukkan sifat menonjol seperti anti-kolonialisme dan radikalisme.
Karakter tokoh-tokoh di atas merupakan model peran yang
memperlihatkan sifat radikal dan kemudian diadopsi oleh Soekarno.
Selain itu tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh beberapa bacaan
tentang marxisme pada massa HBS-nya sangat mempengaruhi alam
pikirannya. Pengalamannya langsung dengan rakyat jelata menimbulkan
perhatian khusus kepada marxisme, sedang pengenalan tentang rakyat
bawah menimbulkan ide populismenya. Adapun religiusnya
mencerminkan pengaruh masa tinggal bersama Tjokroaminoto.
Revivalisme Islam di lingkungan SI sangat meningkatkan kegiatan SI,
yang menimbulkan banyak konflik dan kerusuhan di banyak lokalitas di
Jawa sepanjang pantai utara. Sebab-sebabnya dapat dilacak kembali
pada persaingan dalam perdagangan dengan golongan Tionghoa.
Tambahan pula pada aktivitas penegakan moral antara lain
pemberantasan pelacuran dan perjudian.
***
BICARA tentang radikalisme tidak dapat dilupakan peran Indische Party
yang dipimpin oleh trio tersebut di atas. Meskipun sangat anti-kolonial,
Tjipto Mangoenkoesoemo mendapat penghargaan dari Pemerintah
Hindia Belanda karena jasanya memberantas wabah pes di daerah
Malang. Di tambahkan di sini bahwa Soewardi Soerjaningrat
melancarkan kritik tajam terhadap pesta Belanda memperingati 100
tahun pembebasan Belanda di bawah kekuasan Perancis dalam
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (6 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
artikelnya yang berjudul Bila Saya Seorang Belanda.
Sejak awal dekade kedua suara anti kolonialisme yang dikumandangkan
oleh para pemuka Indische Party selama dekade itu sambung-
sinambung oleh media massa seperti Oetoesan Hindia dan Sinar Djawa,
keduanya adalah surat kabar SI. Sementara itu mulai cukup banyak
pengaruh dari gerakan M Gandhi dengan Swadesi, Satyagraha, dan
Ahimsanya dalam melawan imperialisme Inggris. Gerakan
antikolonialisme Hindia Belanda semakin memuncak pada dekade
ketiga, lebih-lebih di kalangan mahasiswa yang belajar di negeri Belanda
dan terorganisasikan dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Sejak 1923 di
kalangan itu, antara lain karena dipicu oleh gerakan antiimperialisme
oleh komunisme internasional, mulai dilakukan studi yang mendalam
tentang kolonialisme serta dampaknya pada masyarakat Hindia Belanda.
Analisis tentang masyarakat kolonial itu akhirnya menghasilkan suatu
kesimpulan yang dirumuskan secara singkat dalam manifesto politik dan
dimuat dalam majalah PI berjudul Indonesia Merdeka. Di sini perlu
dicatat bahwa pengaruh manifesto politik tentu sampai Hindia Belanda
meskipun kemudian kurang dapat dipopularisasikan pada masyarakat di
kemudian hari.
Meskipun demikian dampaknya pada pergerakan nasional pada
umumnya dan Bung Karno pada khususnya amat besar, khususnya
pada soal proses perjuangan kemerdekaan, swasembada dan negara
kebangsaan yang berdaulat dan berideologi kesatuan (uniti).
Bunyi manifesto politik sebagai berikut:
1. Pemerintah di Indonesia perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia yang
dipilih oleh rakyat Indonesia sendiri.
2. Perjuangan untuk mendapat kemerdekaan tidak membutuhkan
bantuan dari pihak mana pun.
3. Pelbagai unsur di Indonesia perlu dipersatukan sebab tanpa
persatuan itu perjuangan tersebut tidak dapat dicapai.
Gerakan nonkooperasi yang menonjol timbul pada pertengahan dekade
ketiga terutama dari inspirasi manifesto politik. Selanjutnya radikalisme
itu juga merupakan dampak dari dalil Presiden Wilson pada pasca-
Perang Dunia I tentang hak menentukan nasib sendiri.
***
PELAKSANAAN beberapa pokok perjuangan Bung Karno cukup jauh
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (7 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
melampaui jangkauan waktu yang direncanakan (1900-1910). Maka
perlu dibenarkan mengingat bahwa dengan perluasan jangkauan
modernisasi tercipta ruang waktu dalam komunikasi semakin
diperpendek, tercipta apa yang dinamakan semacam semi cyber space
sehingga satu setengah dasawarsa mudah dijangkau. Maka Bung Karno
dalam akhir dekade kedua mudah berkomunikasi dengan ideologi satu
dekade sebelumnya. Proses komunikasi memudahkan integrasi
nasional, membuka batas-batas suku dan kebudayaan, bajunya gerakan
nasionalisme dipercepat dan tidak diragukan bahwa Bung Karno dalam
hal ini telah memperoleh fasilitas komunikasi modern. Dalam pada itu,
kepemimpinannya terhadap massa kritikal dalam ideologi nasionalisme
serta perkembangan integrasi bersamaan dengan pesatnya
perkembangan komunikasi.
Dalam gagasan Bung Karno, kita semua mengetahui bahwa
nasionalisme sangat ditonjolkan dan selalu ditegaskan prinsip kesatuan.
Prinsip itu menjiwai perjuangannya baik pada masa pergerakan maupun
setelah menjadi presiden. Usaha Bung Karno turut menciptakan
kesatuan sebagai ideologi nasionalisme di satu pihak, dan di pihak lain
perjuangan kemerdekaan serta perjuangan pembentukan negara
kebangsaan (nation state).
Catatan: Rupanya sejarah perjuangan ini kurang ditanggapi oleh
masyarakat Indonesia, sehingga masalah kesatuan kurang dihargai dan
dipahami nilainya untuk eksistensi negara Indonesia sendiri. Nation-
building Indonesia memerlukan renasionalisasi atau revitalisasi
nasionalisme Indonesia.
Sebagai epilog perlu dinyatakan di sini bahwa awal periode kehidupan
Soekarno berdasarkan dokumentasi terbatas. Lebih banyak difokuskan
pada konteks sosio-kultural kehidupan masyarakat beserta meal-storm
ideologi politiknya, yang merupakan akar karakter serta corak
perjuangan Soekarno di kemudian hari sewaktu berkiprah dalam arena
pergerakan nasional beserta gaya kepemimpinan di dalamnya.
Dibesarkan dan dikembangkan kepribadiannya pada masa Kebangkitan
Nasional (1900-1910) serta tindak lanjut para perintis selanjutnya (1910-
1930) Bangsa Indonesia sedang menciptakan kebudayaan politik
nasional untuk menggantikan kultur politik kolonial.
Zeitgeist benar-benar memberikan persiapan kepada Bung Karno untuk
memenuhi panggilannya dalam perjuangan nasional dalam pelbagai segi
perjuangan nasional, khususnya ialah:
1. Melawan kolonialisme
2. Membela kepentingan rakyat kebanyakan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (8 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa Muda Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
3. Turut membangun negara nasion terutama berdasarkan ideologi
kesatuannya.
Perlu dicatat di sini bahwa Bung Karno pernah menulis pada secarik
kertas yang berbunyi: "Saya tidak membenci Belanda tetapi membenci
sistem kolonialnya" (arsip Den Haag). Pada masa krisis nasional dewasa
ini, penulis berpendapat bahwa gejala separatisme adalah dampak
timbulnya marginalisasi suku-suku di luar Jawa pada masa Orde Baru
dengan sentralisasi yang sangat kuat, maka suku-suku tersebut
membutuhkan ruang gerak politik untuk beremansipasi sehingga dapat
segera mengejar ketinggalannya. Pelajaran sejarah dapat ditarik dari
perkembangan historis dalam uraian tersebut di atas.
* Sartono Kartodirdjo Sejarawan, guru besar emeritus UGM,
Yogyakarta.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal
Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Latar%20Be...ral%20Dunia%20Kanak-kanak%20dan%20Masa%20Mud.htm (9 of 10)4/3/2005 11:05:09 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
James Luhulima
PERISTIWA penjemputan paksa sejumlah jenderal Angkatan Darat
pada tanggal 30 September 1965 tengah malam, yang dikenal
dengan nama Peristiwa Gerakan 30 September (G30S), sampai saat
ini masih menyimpan misteri.Siapa dalang di balik peristiwa G30S
itu? Partai Komunis Indonesia (PKI), atau Central Intelligence
Agency (CIA), atau jangan-jangan gerakan itu hanya merupakan
letupan dari konflik intern Angkatan Darat saja? Apakah Presiden
Soekarno terlibat? Ataukah Panglima Komando Cadangan Strategis
Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Mayjen) Soeharto? Atau
jangan-jangan peristiwa itu tidak ada dalangnya? Jangan-jangan
semua pihak yang terkait dalam peristiwa itu hanya bereaksi sesuai
dengan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu?
Gerakan yang mengakibatkan tewasnya enam orang jenderal dan
seorang perwira Angkatan Darat itu, memang meninggalkan banyak
pertanyaan, yang masih harus dicarikan jawabannya.
Kalaupun ada yang pasti dari peristiwa penjemputan paksa yang
berlangsung tengah malam itu, adalah berubahnya perjalanan hidup
Presiden Soekarno.
Sinar Matahari yang menyinari Bumi pada tanggal 1 Oktober 1965
dan hari-hari sesudahnya, tidak lagi tampak sama di mata Presiden
Soekarno. Sejak pagi hari itu, perlahan tetapi pasti Presiden
Soekarno mulai surut ke belakang.
Tanggal 1 Oktober 1965 merupakan turning point (titik balik) dalam
perjalanan hidup Presiden Soekarno. Karena peristiwa penjemputan
paksa para jenderal Angkatan Darat, sehari sebelumnya, mengawali
kejatuhan Soekarno dari tampuk kekuasaannya.
Mulai tanggal 1 Oktober 1965, Presiden Soekarno bukan lagi
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
merupakan satu-satunya pemimpin tertinggi di Indonesia. Pada hari
yang sama, Panglima Kostrad Mayjen Soeharto mulai membangun
kekuatan tandingan dengan secara sepihak mengambil alih
pimpinan Angkatan Darat dari tangan Menteri/ Panglima Angkatan
Darat Jenderal Ahmad Yani, yang belum diketahui keberadaannya.
Bukan itu saja, Mayjen Soeharto pun mencegah Panglima Kodam V
Jaya Brigadir Jenderal (Brigjen) Umar Wirahadikusumah memenuhi
panggilan Presiden Soekarno untuk menghadap.
"Sampaikan kepada Bapak Presiden, mohon maaf Panglima Kodam
V Jaya tidak dapat menghadap. Dan, karena saat ini Panglima
Angkatan Darat tidak ada di tempat, harap semua instruksi untuk
Angkatan Darat disampaikan melalui saya, Panglima Kostrad," ujar
Mayjen Soeharto kepada Komisaris Besar Polisi Sumirat dan Kolonel
(Mar) Bambang Widjanarko, Ajudan Presiden Soekarno, yang
menjemput Panglima Kodam V Jaya. (Sewindu Dekat Bung Karno,
Bambang Widjanarko, PT Gramedia, 1988)
Presiden Soekarno kelihatan kurang senang karena Panglima
Kodam V Jaya tidak diizinkan menghadap oleh Panglima Kostrad.
Sebab, Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan bahwa
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Siang hari, dalam pertemuan dengan Menteri/Panglima Angkatan
Udara Laksamana Madya (Laksdya) Omar Dani, Menteri/Panglima
Angkatan Laut Laksdya RE Martadinata, dan Menteri/Panglima
Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo,
Presiden Soekarno memutuskan untuk mengambil alih seluruh
tanggung jawab dan tugas Menteri/Panglima Angkatan Darat, serta
mengangkat Asisten Menteri/ Panglima Angkatan Darat Bidang
Personel Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker Menteri/
Panglima Angkatan Darat.
Usai pertemuan itu, pukul 17.00, Presiden Soekarno memerintahkan
ajudannya, Kolonel Bambang Widjanarko, memanggil Mayjen
Pranoto Reksosamudro untuk menghadap.
Namun, seperti pada pagi harinya, Mayjen Soeharto kembali
menegaskan bahwa untuk sementara ia memegang kendali
Angkatan Darat. Dan, ia tidak mengizinkan Mayjen Pranoto
Reksosamudro menghadap Presiden Soekarno. Dengan alasan, ia
tidak ingin Angkatan Darat kehilangan jenderalnya lagi.
Soeharto tidak berhenti sampai di sana. Ia meminta kepada
Bambang Widjanarko untuk membujuk Presiden Soekarno agar
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.
Namun, pembangkangan terhadap Presiden Soekarno itu, bukanlah
yang pertama kali dilakukan oleh Panglima Kostrad Mayjen
Soeharto. Sebab, di saat Presiden Soekarno gencar berkonfrontasi
dengan Malaysia, di Kostrad dibentuk Operasi Khusus (Opsus) yang
dipimpin Letnan Kolonel (Letkol) Ali Moertopo, dan dibantu Mayor LB
Moerdani, Letkol AR Ramli, dan Letkol Sugeng Djarot. Personel-
personel Opsus secara diam-diam melakukan kontak-kontak rahasia
dengan pihak-pihak di Malaysia untuk mengupayakan perdamaian
antara kedua negara.
Oei Tjoe Tat, salah seorang menteri dalam Kabinet 100 Menteri yang
dipimpin Presiden Soekarno, dalam bukunya yang berjudul Memoar
Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno, terbitan Hasta Mitra
tahun 1995, menggambarkan situasi tanggal 1 Oktober 1965 dan
hari-hari sesudahnya. Oei Tjoe Tat menuturkan, ...dengan cepat
iklim dan suasana politik di ibu kota bergeser 180 derajat. Menurut
pengamatan saya, sejak 1 dan 2 Oktober 1965 kekuasaan de facto
sudah terlepas dari tangan Presiden selaku penguasa Republik
Indonesia. Memang padanya masih ada corong mikrofon, tetapi
inisiatif dan kontrol atas jalannya situasi sudah hilang.
PADA tanggal 30 September 1965, Presiden Soekarno tidak tidur di
Istana Merdeka. Menjelang tengah malam, Presiden Soekarno
meninggalkan Istana Merdeka menuju ke kediaman istrinya, Ny
Ratnasari Dewi, di Jalan Gatot Subroto (kini, Museum Satria
Mandala). Dalam perjalanan ke sana, Presiden Soekarno singgah di
Hotel Indonesia untuk menjemput Ny Dewi, yang tengah menghadiri
resepsi yang diadakan Kedutaan Besar Irak di Bali Room.
Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober 1965, pada pukul 06.30,
Presiden Soekarno ke luar rumah, memasuki mobil kepresidenan
Buick Chrysler hitam dengan nomor polisi B 4747, dan bergegas ke
Istana Merdeka. Pagi hari itu, Presiden Soekarno dijadwalkan
menerima Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena dan Menteri/
Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani pada acara minum
kopi (koffie uurtje) pukul 07.00.
Di dalam mobil, Suparto, sopir pribadi Presiden, memberi tahu
informasi yang diperolehnya dari Komandan Detasemen Kawal
Pribadi (DKP) Komisaris Polisi Mangil Martowidjojo, yakni bahwa
pada pukul 04.00, ada penembakan di rumah Menteri Koordinator
Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata
Jenderal AH Nasution dan rumah Wakil Perdana Menteri II Dr
Leimena, yang letaknya bersebelahan.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Presiden Soekarno langsung memerintahkan Suparto untuk
memberhentikan mobil yang baru bergerak beberapa meter itu. Ia
langsung memanggil Mangil dan meminta penjelasan tentang
penembakan di rumah Nasution dan Leimena itu.
Kemudian Presiden Soekarno bertanya, "Baiknya bagaimana, saya
tinggal di sini dulu atau langsung kembali ke Istana?" Mangil
menjawab, "Sebaiknya Bapak tinggal di sini dulu, karena saya masih
harus menunggu laporan dari Inspektur I Jatiman (Kepala Bagian II
DKP) yang tadi saya perintahkan mengecek kebenaran berita
tersebut. Sampai sekarang, Jatiman belum melaporkan hasilnya."
Mendengar jawaban itu, Presiden Soekarno menghardik Mangil
dengan nada keras, "Bagaimana mungkin, kejadian pukul 04.00
pagi, sampai sekarang belum kamu ketahui dengan jelas...."
Presiden Soekarno kemudian menyuruh Suparto untuk berangkat.
Mobil yang ditumpangi Presiden Soekarno kemudian bergerak
perlahan-lahan meninggalkan rumah Ny Dewi menuju Istana
Merdeka dengan rute Jembatan Semanggi, Jalan Jenderal
Sudirman, Jalan MH Thamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, dan
Jalan Medan Merdeka Utara.
Di depan mobil Presiden Soekarno ada satu jip DKP, dan di
belakangnya, mobil yang ditumpangi Mangil. Saat iring-iringan
rombongan Presiden Soekarno melintas di atas Jembatan Dukuh
Atas, menjelang Hotel Indonesia, Jatiman menghubungi Mangil dan
membenarkan terjadinya penembakan di rumah Jenderal AH
Nasution dan rumah Dr Leimena. Jatiman juga menginformasikan
adanya pasukan Angkatan Darat "yang terasa sangat mencurigakan"
di sekitar Istana, termasuk di kawasan Monumen Nasional (Monas).
Pada saat itu, Jalan Medan Merdeka Barat ditutup dan dijaga oleh
pasukan Angkatan Darat dari Batalyon 530/Para Brigade 3/Brawijaya
dan Batalyon 454/Para/Diponegoro. Kendaraan-kendaraan yang
datang dari arah Hotel Indonesia diharuskan membelok ke kiri.
Mangil tidak sempat menanyakan Jatiman tentang pasukan "yang
terasa sangat mencurigakan" itu, karena iring-iringan rombongan
Presiden Soekarno sudah semakin mendekati Bundaran Air Mancur.
Mangil berpikir cepat: Presiden Soekarno harus dijauhkan dari
pasukan itu. Pada saat yang bersamaan, Wakil Komandan Resimen
Tjakrabirawa Kolonel (CPM) Maulwi Saelan menghubungi Mangil
lewat handy-talkie dan meminta agar Presiden Soekarno jangan
dibawa ke Istana karena banyak tentara yang tidak dikenal. Saelan
meminta agar Presiden Soekarno dibawa ke rumah istrinya yang
lain, Ny Harjati, di kawasan Slipi, di sebelah lokasi Hotel Orchid
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
(sekarang).
Rombongan kemudian membelok ke kiri, memasuki Jalan Budi
Kemuliaan, Tanah Abang Timur, Jalan Jati Petamburan, dan ke arah
Slipi, ke rumah Ny Harjati.
Saelan menunggu Presiden Soekarno di rumah Ny Harjati. Begitu
tiba pada pukul 07.00, Presiden Soekarno segera masuk ke dalam
rumah, diikuti Saelan. Saelan melaporkan tentang penembakan di
rumah Jenderal AH Nasution dan rumah Dr Leimena, serta adanya
pasukan tidak dikenal di sekitar Istana.
Presiden Soekarno terkejut mendengar semua itu. Ia segera
memerintahkan Saelan mengontak semua panglima angkatan.
Namun, pagi itu, jaringan telepon lumpuh sehingga Saelan meminta
sopir pribadi Presiden, Suparto, untuk menghubungi langsung.
Saelan mendatangi Mangil di luar, dan mengupayakan untuk
mencari tempat yang aman bagi Presiden Soekarno. Mangil
mengusulkan agar Presiden Soekarno dibawa ke bekas rumah Sie
Bian Ho di Jalan Wijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang
sudah dibeli Resimen Tjakrabirawa. Usul itu disetujui oleh Saelan.
Namun, setelah Suparto kembali pukul 08.30 dan melaporkan bahwa
ia hanya berhasil mengadakan kontak dengan Menteri/Panglima
Angkatan Udara Laksdya Omar Dani di Pangkalan Angkatan Udara
Halim Perdanakusuma. Saelan berubah pendapat. Ia kemudian
menyarankan agar Presiden Soekarno dibawa ke Halim saja.
Itu sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP)
Tjakrabirawa. Bahwa jika dalam perjalanan pengamanan Presiden
terjadi sesuatu hal yang mengancam keamanan dan keselamatan
Presiden, maka secepatnya Presiden dibawa ke Markas Angkatan
Bersenjata terdekat. Alternatif lain adalah menuju ke Pangkalan
Angkatan Udara Halim Perdanakusuma karena di sana ada pesawat
terbang kepresidenan C-140 Jetstar. Atau, pelabuhan Angkatan
Laut, tempat kapal kepresidenan RI Varuna berlabuh. Atau, bisa juga
ke Istana Bogor karena di sana diparkir helikopter kepresidenan
Sikorsky S-61V.
Kemungkinan-kemungkinan itu dilaporkan kepada Presiden
Soekarno. Dan, Soekarno memutuskan pergi ke Pangkalan Udara
Halim Perdanakusuma.
Saelan kemudian ke luar dan memberi tahu Mangil. Dan, agar tidak
menarik perhatian, Presiden Soekarno menggunakan mobil VW
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Kodok biru laut nomor polisi B 75177. Pengawalan pun hanya
dilakukan oleh anggota DKP yang mengenakan pakaian sipil.
Sekitar pukul 09.30, rombongan Presiden Soekarno tiba di
Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusuma. Presiden
disambut Menteri/Panglima Angkatan Udara Laksdya Omar Dani
dan Komodor Leo Wattimena.
Sekitar pukul 10.00, Brigjen Soepardjo, pimpinan G30S, melapor
kepada Presiden Soekarno bahwa ia dan kawan-kawannya telah
mengambil tindakan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat.
Namun, Presiden Soekarno memerintahkan kepada Soepardjo untuk
menghentikan gerakannya guna menghindari pertumpahan darah.
Presiden Soekarno, pada kesempatan itu, juga menolak permintaan
Soepardjo untuk mendukung G30S.
Presiden Soekarno kemudian memerintahkan ajudannya, Komisaris
Besar Sumirat untuk memanggil Menteri/Panglima Angkatan Laut
Laksdya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian
Inspektur Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, Panglima Kodam V Jaya
Brigjen Umar Wirahadikusumah, Jaksa Agung Brigjen Soetardio, dan
Wakil Perdana Menteri II Dr Leimena.
PANGLIMA Kostrad Mayjen Soeharto, pada tanggal 1 Oktober 1965,
pukul 06.00 diberi tahu oleh Mashuri, tetangganya di Jalan Haji Agus
Salim, Menteng, bahwa pada dini hari terdengar suara tembakan.
Mashuri mencatat bahwa pagi itu, Soeharto sudah mengenakan
pakaian tempur.
Soeharto dalam bukunya yang berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan,
dan Tindakan Saya-Otobiografi seperti yang dipaparkan kepada G
Dwipayana dan Ramadhan KH, terbitan PT Lamtoro Gung Persada
tahun 1989, mengaku bahwa pada 1 Oktober 1965 pukul 00.15 ia
pulang ke rumah, setelah seharian menjaga anaknya, Tommy
(Hutomo Mandala Putra), yang tersiram sup panas, di rumah sakit.
Pada pukul 04.30, ia didatangi oleh Hamid, juru kamera TVRI, yang
baru saja menyelesaikan syuting. Hamid bercerita bahwa ia
mendengar tembakan di beberapa tempat. Setengah jam kemudian,
datang tetangganya, Mashuri, yang juga mendengar suara
tembakan.
Pukul 05.30, datang Broto Kusmardjo yang memberi tahu berita
yang mengejutkan, yakni beberapa pati (Perwira Tinggi) Angkatan
Darat telah diculik. Maka segeralah Soeharto bersiap dengan
pakaian lapangan.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Menurut Komandan Brigade Infanteri I Jayasakti Kodam V Jaya
Kolonel Abdul Latief, yang dianggap sebagai salah satu tokoh
penting di balik peristiwa G30S, seharusnya Mayjen Soeharto tidak
perlu terkejut. Sebab, Mayjen Soeharto sudah diberi tahu
sebelumnya tentang akan dilakukannya penjemputan paksa
terhadap para jenderal pimpinan teras Angkatan Darat.
Latief mengungkapkan bahwa dua hari menjelang tanggal 1 Oktober
1965, ia dan keluarga mendatangi rumah Mayjen Soeharto di Jalan
Haji Agus Salim. Di samping menghadiri acara kekeluargaan, Latief
juga bermaksud memberitahu adanya info bahwa Dewan Jenderal
akan mengadakan coup d'etat terhadap pemerintahan Presiden
Soekarno.
Saat info itu disampaikan, menurut Latief, Mayjen Soeharto
mengatakan bahwa ia sudah mengetahui info itu dari seorang bekas
anak buahnya dari Yogyakarta yang bernama Subagyo, yang datang
sehari sebelumnya.
Dan, malam menjelang terjadinya peristiwa G30S, Latief, yang
datang menjenguk putra Soeharto ke Rumah Sakit Angkatan Darat,
melaporkan akan adanya gerakan pada esok harinya untuk
menggagalkan rencana coup d'etat dari Dewan Jenderal.
Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Mayjen Soeharto tidak
pernah menyebut-nyebut mengenai kedatangan Latief ke rumahnya.
Soeharto hanya menyebut tentang kedatangan Latief ke rumah sakit.
Akan tetapi, itu pun dalam versi yang berbeda.
Dalam wawancara dengan Arnold Brackman dalam buku The
Communist Collaps in Indonesia (1970), Soeharto mengatakan,
Latief datang ke rumah sakit untuk mengecek keberadaannya.
Sedangkan dalam wawancara dengan Der Spiegel bulan Juni 1970,
Soeharto mengatakan, Latief dan komplotannya datang ke rumah
sakit untuk membunuhnya, tetapi tampaknya tidak jadi karena
mereka khawatir melakukannya di tempat umum.
Dan, dalam bukunya yang berjudul Soeharto Pikiran, Ucapan, dan
Tindakan Saya, Soeharto hanya menyebut, kira-kira pukul sepuluh
malam saya sempat menyaksikan Kolonel Latief berjalan di depan
zaal tempat Tommy dirawat.
Oei Tjoe Tat dalam memoarnya menceritakan tentang pertemuan
dan persahabatannya dengan Subagyo, yang namanya disebut
Soeharto dalam percakapan Latief di rumah Soeharto Jalan Haji
Agus Salim dua hari menjelang G30S.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Subagyo yang ditahan bersama Oei Tjoe Tat di rumah tahanan
militer (RTM) menceritakan bahwa ia beberapa kali mendatangi
Mayjen Soeharto untuk memberi tahu akan terjadinya sesuatu yang
membahayakan negara.
Sekitar pukul 06.00, Mayjen Soeharto kemudian berangkat ke
Markas Kostrad, Jalan Medan Merdeka Timur. Di sana ia
mengumpulkan anak buahnya dan melakukan langkah-lang-kah
konsolidasi. Langkah pertama yang diambilnya adalah mengambil
alih kepemimpinan dalam Angkatan Darat yang kosong, karena
Menteri/Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani belum
diketahui keberadaannya.
Menurut Soeharto, sebelum ia berangkat, datang Letkol Sadjiman,
atas perintah Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar
Wirahadikusumah, dan menginformasikan adanya pasukan tak
dikenal di sekitar Monas dan Istana.
Oleh sebab itu, pada pukul 06.30, ia memerintahkan seorang perwira
Kostrad, Kapten Mudjono, untuk memanggil Komandan Batalyon
530/Para Brigade 3/Brawijaya Mayor Bambang Soepeno yang
menempatkan pasukannya di sekitar Monas dan Istana.
Wakil Komandan Batalyon 530 Kapten Soekarbi, yang memimpin
pasukan itu di lapangan, bertanya, apakah ia bisa mewakili, karena
Mayor Bambang Soepeno sedang ke Istana. Perwira itu menjawab
tidak bisa. Namun, pukul 07.30, perwira itu datang lagi dan
mengatakan, Kapten Soekarbi diperbolehkan menggantikan Mayor
Bambang Soepeno. Tidak lama kemudian datang pula menghadap
Wakil Komandan Batalyon 454/Para/ Diponegoro Kapten Koencoro.
Kepada Mayjen Soeharto, Soekarbi dan Koencoro melaporkan
mengenai briefing Mayor Bambang Soepeno yang menyebut tentang
Ibu Kota Jakarta dan Panglima Tertinggi ABRI dalam keadaan
gawat. Serta, ada kelompok Dewan Jenderal yang akan melakukan
kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Mayjen Soeharto
kemudian mengatakan bahwa isi briefing itu tidak benar. Dan,
Mayjen Soeharto memerintahkan kedua wakil komandan batalyon itu
untuk mengambil alih pasukan dan kembali ke Kostrad.
Soekarbi, kini Mayor (Purnawirawan), dalam wawancara yang
dimuat tabloid berita Detak edisi 29 September-5 Oktober 1998,
mengemukakan, kehadiran pasukannya di Jakarta adalah untuk
mengikuti peringatan HUT ke-20 ABRI tanggal 5 Oktober 1965.
Muncul pertanyaan, mengapa dalam radiogram Panglima Kostrad
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Nomor 220 dan Nomor 239 tanggal 21 September 1965, yang
ditandatangani oleh Mayjen Soeharto, isinya perintah agar Batalyon
530/Para Brigade 3/Brawidjaja disiapkan dalam rangka HUT ke-20
ABRI tanggal 5 Oktober 1965 di Jakarta dengan "perlengkapan
tempur garis pertama". Apalagi kemudian, sebagian dari anggota
pasukan itu dilibatkan dalam G30S.
Lepas tengah hari, Ajudan Presiden Komisaris Besar Sumirat yang
diminta untuk memanggil Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar
Wirahadikusumah tiba di Markas Kodam V Jaya di Lapangan
Banteng. Namun, Brigjen Umar Wirahadikusumah tidak ada di
tempat, ia sedang berada di Markas Kostrad Jalan Medan Merdeka
Timur. Sumirat, yang didampingi Ajudan Presiden lainnya, Kolonel
Bambang Widjanarko, kemudian menyusul ke Kostrad. Di Kostrad,
keduanya mendapat penjelasan dari Panglima Kostrad Mayjen
Soeharto bahwa ia melarang Panglima Kodam V Jaya untuk
menghadap, dan Soeharto juga minta keduanya memberi tahu
Presiden Soekarno agar semua instruksi untuk Angkatan Darat
disampaikan melalui dia.
Penjelasan yang sama diberikan sore harinya kepada Kolonel
Bambang Widjanarko, saat Mayjen Soeharto melarang Mayjen
Pranoto Reksosamudro menghadap Presiden Soeharto.
Rupanya, langkah Mayjen Soeharto tidak berhenti di sana.
Kemudian ia juga mengambil alih peranan Panglima Tertinggi ABRI
dari Presiden Soekarno. Dan, secara sepihak, ia memberlakukan
keadaan darurat. Ia juga menelepon Menteri/Panglima Angkatan
Laut Laksdya RE Martadinata, Menteri/Panglima Angkatan
Kepolisian Komisaris Jenderal Soetjipto Joedodihardjo, dan Deputi
Operasi Angkatan Udara Komodor Leo Wattimena. Dan, kepada
mereka, Soeharto memberi tahu untuk sementara pimpinan
Angkatan Darat dipegang olehnya, serta meminta agar mereka tidak
mengadakan pergerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima
Kostrad.
NAMUN, langkah Mayjen Soeharto yang paling efektif adalah
memonopoli media massa sehingga ia dengan leluasa dapat
membentuk opini publik (public opinion) sesuai yang
dikehendakinya. Suatu langkah yang kemudian terus dilanjutnya
selama memerintah negara ini lebih dari 31 tahun.
Soeharto tidak hanya menguasai stasiun Televisi Republik Indonesia
(TVRI) dan mengambil alih stasiun Radio Republik Indonesia (RRI)
dari tangan pasukan G30S, tetapi ia juga menguasai surat kabar.
Melalui Panglima Kodam V Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah,
Soeharto melarang terbit semua surat kabar, di luar surat kabar milik
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Angkatan Darat. Kompas termasuk surat kabar yang tidak diizinkan
terbit. Mulai tanggal 2 Oktober-5 Oktober 1965 media cetak yang
terbit hanya Harian Angkatan Bersenjata, Berita Yudha, kantor berita
Antara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata.
Di mulai dengan pemberitaan RRI, TVRI, dan surat kabar-surat
kabar Angkatan Darat, yang diikuti surat kabar-surat kabar lain mulai
tanggal 6 Oktober 1965, disebarkanlah cerita-cerita tentang
kekejaman G30S. Walaupun hasil visum et repertum terhadap tujuh
korban G30S itu menyebutkan tidak ada penyiksaan seperti yang
digambarkan dalam pemberitaan media massa, berita-berita yang
berisi cerita mendetail tentang penyiksaan itu tidak surut.
Dan, dengan mengontrol media massa, Mayjen Soeharto dapat
dengan leluasa menentukan informasi apa yang ia ingin atau tidak
ingin sampaikan kepada masyarakat.
Itu sebabnya, pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 21.00, melalui RRI
Mayjen Soeharto mengumumkan bahwa ia telah mengambil alih
pimpinan Angkatan Darat. Padahal, saat itu, ia sudah mengetahui
bahwa Presiden Soekarno telah mengambil alih pimpinan Angkatan
Darat dan mengangkat Mayjen Pranoto Reksosamudro sebagai
caretaker.
Pada tanggal 2 Oktober 1965, Presiden Soekarno memanggil
Mayjen Soeharto ke Istana Bogor. Kepada Presiden Soekarno,
Mayjen Soeharto mengatakan, pengambilalihan pimpinan Angkatan
Darat dilakukannya agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan.
Kepada Mayjen Soeharto, Presiden Soekarno memberi tahu bahwa
ia mengambil alih pimpinan Angkatan darat dan mengangkat Mayjen
Pranoto Reksosamudro sebagai caretaker. Menanggapi
pemberitahuan itu, dengan nada mengancam Soeharto mengatakan,
dengan diangkatnya Pranoto sebagai caretaker, ia tidak lagi
bertanggung jawab atas situasi keamanan saat itu. Sebagai alasan,
Soeharto mengatakan, ia tidak ingin terjadi dualisme dalam
kepemimpinan Angkatan Darat.
Mengingat Mayjen Soeharto secara de facto sudah "mengendalikan"
pasukan, maka Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi
Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban
(Pangkopkamtib). Namun, walaupun Mayjen Pranoto Reksosamudro
adalah caretaker Menteri/Panglima Angkatan Darat, tetapi dalam
kenyataannya Pangkopkamtib Mayjen Soeharto-lah yang menguasai
Angkatan Darat.
Bukan itu saja, dengan wewenangnya sebagai Pangkopkamtib,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (10 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Soeharto "membersihkan" Angkatan Darat dari orang-orang yang
dianggap terlibat G30S. Bahkan, Mayjen Pranoto Reksosamudro,
pada tanggal 14 Oktober 1965, ditangkap dengan tuduhan terlibat
G30S. Dengan demikian, Presiden Soekarno tidak mempunyai
pilihan lain kecuali mengangkat Soeharto jadi Menteri/Panglima
Angkatan Darat.
Tetapi Soeharto tidak berhenti. Ia terus mengganggu pemerintahan
Presiden Soekarno-meskipun ia merupakan salah seorang menteri
dalam pemerintahan itu-dengan mengarahkan mahasiswa turun ke
jalan untuk berdemonstrasi. Gangguan itu mencapai puncaknya
pada tanggal 11 Mei 1966, yang ditandai dengan pengerahan
pasukan-pasukan yang tak beridentitas di balik para mahasiswa
yang mengadakan unjuk rasa.
Kehadiran pasukan tak beridentitas itu mengakibatkan Sidang
Kabinet 100 Menteri (Kabinet Dwikora) yang diadakan di Istana
Merdeka dihentikan. Sore harinya, tiga perwira tinggi Angkatan
Darat, yakni Brigjen M Jusuf, Mayjen Basuki Rachmat, dan Brigjen
Amirmachmud, menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor, dan
menyampaikan pesan Letjen Soeharto bahwa kalau ia diberikan
kepercayaan, maka ia bisa mengatasi keadaan. Lahirlah Surat
Perintah 11 Maret, yang lebih dikenal lewat singkatannya,
Supersemar.
Mendapatkan Supersemar, gerakan Soeharto tak tertahankan lagi.
Keesokan harinya, ia langsung membubarkan PKI dan organisasi
massanya, serta menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.
Tanggal 17 Maret 1966, Soeharto menahan 15 menteri anggota
Kabinet Dwikora yang diduga terlibat G30S. Ia juga membersihkan
MPRS dari orang-orang yang diduga terlibat dalam G30S, dan
memasukkan orang-orang yang mendukung. Presiden Soekarno
berulang kali memprotes tindakan Soeharto, dan menyebutnya
sebagai bertindak di luar wewenangnya, tetapi Soeharto tidak peduli.
Situasi itu membuat ajudannya, Bambang Widjanarko menulis dalam
bukunya, Sewindu Dekat Bung Karno, "Berdasarkan Surat Perintah
Sebelas Maret (Supersemar) yang ditandatangani oleh BK sendiri
itulah jalan hidup BK berubah dan karier politiknya berakhir."
PRESIDEN Soekarno sesungguhnya sangat bisa jika ia ingin
bertahan, dan menghadapi rongrongan Panglima Kostrad Mayjen
Soeharto terhadap kekuasaannya.
Masih banyak rakyat yang berdiri di belakangnya, demikian juga
kesatuan-kesatuan Angkatan Bersenjata, seperti Divisi Brawijaya,
Divisi Diponegoro, dan kesatuan-kesatuan Angkatan Udara,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (11 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Angkatan Laut, dan Angkatan Kepolisian. Bahkan, Komandan Korps
Komando (KKO) Mayjen Hartono secara terbuka menyatakan siap
membela Presiden Soekarno.
"Mereka semua menunggu instruksi Presiden untuk bertindak. Dan
instruksi itu tak kunjung... tak kunjung datang," tulis Oei Tjoe Tat di
dalam memoarnya.
Dari orang-orang yang dekat dengan Presiden Soekarno, diketahui
bahwa ia tidak ingin melihat perang saudara merobek-robek Negara
Kesatuan Indonesia.
Oei Tjoe Tat bercerita, "Kalau perlu", demikian menurut sementara
orang menirukan ucapannya, "biarlah aku lepaskan jabatan
kepresidenanku daripada harus menyaksikan perang saudara yang
nantinya bisa dimanfaatkan kekuatan-kekuatan Nekolim."
Cerita ini dipertegas oleh Roeslan Abdulgani, dalam tulisannya di
buku Tuhan, Pergunakanlah Hati, Pikiran dan Tanganku, Pledoi
Omar Dani, terbitan PT Media Lintas Inti Nusantara, tahun 2001.
Dalam pertemuan pada awal tahun 1967 di Istana Bogor, Presiden
Soekarno mengatakan, "Cak! Kalau saya maju selangkah lagi
memenuhi tuntutan mereka, akan pecah perang saudara. Brawijaya
di Jawa Timur sudah mau mengajak saya ke sana. Saya tidak ingin
ada perang saudara. Nekolim terang-terangan akan masuk. Dan kita
akan dirobek-robek. Sekali lagi Cak, relakan saya tenggelam. Asal
jangan bangsa ini dirobek-robek oleh Nekolim dan kaki tangannya."
Pada tanggal 7-12 Maret 1967, berlangsung Sidang Istimewa MPRS.
Sidang itu kemudian mengeluarkan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/
MPRS/ 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara
dari Presiden Soekarno. Ketetapan MPRS itu memutuskan untuk
mencabut kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno,
berlaku surut mulai 22 Februari 1967, dan mengangkat Jenderal
Soeharto sebagai Pejabat Presiden.
Saat menerima berita tentang Ketetapan MPRS itu, Presiden
Soekarno tengah berada di Istana Bogor.
Bambang Widjanarko, dalam bukunya, Sewindu Dekat Bung Karno
menyebutkan, Kelihatan benar betapa terpukul hatinya saat itu.
Lama ia duduk diam tanpa berkata sepatah pun. Akhirnya ia menarik
napas panjang dan berkata, "Aku telah berusaha memberikan segala
sesuatu yang kuanggap baik bagi nusa dan bangsa Indonesia."
* James Luhulima WartawanKompas.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Peristiwa%2...ik%20Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (12 of 14)4/3/2005 11:05:11 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah
Kolonial Belanda
Valina Singka Subekti
MEMAHAMI manusia besar seperti Bung Karno tidaklah mudah.
Setiap episode perjalanan hidupnya merupakan proses menuju
pematangan pribadi sebagai seorang manusia biasa maupun
sebagai pemimpin. Episode itu sangat panjang, sejak ia dilahirkan
sampai akhir hidupnya.Bila kita membaca berbagai tulisan mengenai
Soekarno, tampak benang merah yang memperlihatkan Soekarno
sebagai manusia multidimensi. Di satu sisi adalah manusia yang
sangat rasional ketika berhadapan dengan kepentingan bangsanya,
tetapi di sisi lain ia bisa menjadi sangat emosional ketika berhadapan
dengan penjajah Belanda. Atau ia bisa menjadi sangat sentimental
dan perasa ketika berhadapan dengan perempuan. Boleh dikatakan
Soekarno adalah manusia yang rasional, sekaligus perasa dan
sentimental.
Seluruh perjalanan hidupnya sangat dipengaruhi sifat
personalitasnya itu. Salah satu episode penting adalah masa awal
abad ke-20, khususnya periode 1927 sampai ketika ia dibuang ke
Ende, Flores. Sebagaimana para pemimpin pergerakan kebangsaan
lainnya, penjara atau pengasingan sudah merupakan bagian yang
inheren sebagai konsekuensi perjuangan. Soekarno pun menyadari
hal itu, dan secara mental sudah menyiapkan diri. Untuk
membesarkan hatinya ia suka mengulangi apa yang diucapkan
pemimpin revolusi Perancis, Danton, dalam perjalanan gerobak
sampah sebelum menuju tiang gantungan, "Audace, Danton,
Toujours de l'audace", artinya, "Keberanian, Danton, Junjunglah
Selalu Keberanian"!.
Maka Soekarno tidak pernah berhenti berpidato dari satu tempat ke
tempat lainnya. Ia menggerakkan dan menggelorakan semangat
rakyat untuk merebut kembali kemerdekaan asasinya yang telah
direbut dan dinjak-injak oleh pemerintah kolonial Belanda. Katanya,
"Hayolah kita bergabung menjadi satu keluarga yang besar dengan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (1 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
satu tujuan yang besar, menggulingkan pemerintah kolonial,
melawannya, dan bangkit bersama-sama". Agitasi semacam ini
dilakukannya terus-menerus dalam setiap orasinya di depan rakyat.
Semua tahu, Soekarno adalah singa podium yang mempunyai
kemampuan menerapkan berbagai gaya bahasa orasi seperti
retorika, personifikasi, dan hiperbola. Ia mempersonifikasikan realitas
dengan perumpamaan benda-benda yang mampu mendatangkan
efek 'menekan', dan pidatonya itu mampu menggetarkan emosi
rakyat. Inggit Ganarsih misalnya, menceritakan bagaimana Soekarno
membandingkan potensi ledakan kemarahan rakyat yang selalu
ditekan dan ditindas pemerintah kolonial Belanda dengan Gunung
Kelud yang ketika meledak mendatangkan suara gemuruh hebat.
Kata Soekarno, "Manakala perasaan kita meletus, Den Haag akan
terbang ke udara". Tidak heran rakyat selalu berkerumun manakala
mendengar Soekarno akan berpidato. Ia memang pandai
memainkan emosi rakyatnya.
***
PERIODE 1926 sampai dengan ketika Soekarno ditangkap pada
tahun 1929 merupakan periode bergolaknya semangat perlawanan
terhadap pemerintah kolonial. Pada waktu itu PKI baru saja gagal
dalam pemberontakan melawan Pemerintah Hindia Belanda tahun
1926, sehingga partai tersebut dilarang dan tokohnya seperti
Semaun dan Alimin dikucilkan. Maka PNI mulai berkembang pesat,
sementara Perhimpunan Indonesia di Belanda juga melakukan
propaganda gerakan nasionalis untuk disebarluaskan di Indonesia.
Ada semacam pertemuan kepentingan antara gerakan di Tanah air
dengan yang di negeri Belanda. Tokoh nasionalis mulai bermunculan
seperti Soekarno, Sjahrir, Hatta, Sartono, dan Sukiman, di samping
sebelumnya sudah ada tokoh-tokoh pergerakan dari kalangan
Sarekat Islam seperti HOS Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim.
Ketika agitasi Soekarno dan kawan-kawannya dari kalangan gerakan
nasionalis semakin mampu menciptakan gerakan massa yang sadar
politik dan dianggap membahayakan kedudukan Pemerintah Hindia
Belanda, maka pemerintah kolonial mulai mengawasi segala gerak-
gerik Soekarno dan kawan-kawannya.
Pengalaman pertamanya di penjara adalah ketika ia ditangkap
bersama dengan Gatot, Maskun, dan Supriadinata pada malam
tanggal 29 Desember 1929. Ia dijebloskan ke Penjara Banceuy,
Bandung, selama delapan bulan, sebelum pada akhirnya menetap di
Penjara Sukamiskin selama dua tahun. Di sini Soekarno tidak hanya
dipenjarakan, tetapi juga diasingkan, tidak boleh berkomunikasi
dengan orang luar maupun sesama tahanan. Soekarno mengatakan,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (2 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
hanya cicaklah yang menjadi temannya.
Banceuy adalah penjara tingkat rendah yang didirikan abad ke-19.
Keadaannya kotor, bobrok, dan tua. Di sana ada dua macam sel,
untuk tahanan politik dan tahanan pepetek (rakyat jelata). Kalau
yang pepetek tidur di atas lantai semen, maka yang satu lagi tidur di
atas velbed yang dialasi tikar rumput. Soekarno menceritakan pada
Cindy Adams betapa tertekan dirinya dalam penjara itu. "Tempat itu
gelap, lembab dan melemaskan. Memang, aku telah lebih seribu kali
menghadapi hal ini semua dengan
diam-diam jauh dalam kalbuku sebelum ini. Akan tetapi ketika pintu
yang berat itu tertutup rapat dihadapanku untuk pertama kali, aku
rasanya hendak mati".
Pengadilan politik mulai digelar pada tanggal 18 Agustus 1930 di
pengadilan Landraad, Bandung. Pada tanggal 22 Desember 1930,
Soekarno dijatuhi hukuman empat tahun penjara. Soekarno naik
banding, menyusun pledoi, dan membacakan pidato pembelaannya
yang sangat terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Pidatonya itu
menjelma menjadi suatu dokumen politik historis menentang
kolonialisme dan imperialisme. Di situ Soekarno menampilkan diri
sebagai manusia 'penggerak', juga intelektual muda yang sedang
berusaha memahami persoalan bangsanya berhadapan dengan
kolonialisme Belanda.
Boleh dikatakan isi pidato itu merupakan intisari hasil jelajah pikiran
Soekarno selama 15 tahun belakangan terhadap tulisan para pemikir
besar dunia yang menentang segala bentuk penindasan atau
eksploitasi sesama manusia.
Sejak masih tinggal dengan keluarga HOS Tjokroaminoto di
Surabaya, Soekarno sudah membaca tulisan pemikir-pemikir besar
dunia. Ia membaca Gladstone dari Britania serta Sidney dan
Beatrice Webb yang mendirikan gerakan buruh Inggris. Ia gandrung
pada karya-karya Karl Marx, Friederich Engels, termasuk Lenin dari
Rusia. Karya Karl Kautsky juga dibacanya. Ia pun sangat menyukai
Jean Jacques Rousseau, serta ahli pidato dari Perancis Aristide
Briand dan Jean Jaures. Ia juga sering menyamakan dirinya sebagai
Danton atau Voltaire, karena begitu kagumnya kepada dua orang itu.
Dan sebenarnya cita-cita dan dasar pemikiran politiknya sudah
terbentuk pada tahun 1920 itu, yakni sintesa antara tiga aliran besar
yaitu nasionalisme, marxisme dan Islamisme. Soekarno selalu
mengatakan bahwa menyatukan ketiga aliran itu merupakan
keharusan dalam rangka menyatukan kekuatan bangsa Indonesia
menentang kolonialisme untuk mencapai pintu gerbang
kemerdekaan. Ketiga aliran itu bisa saling mengisi.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (3 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
***
TESIS yang diajukannya dalam Indonesia Menggugat sebenarnya
juga diilhami oleh dasar-dasar pemikiran politiknya itu. Yang paling
dominan adalah analisisnya mengenai kejahatan ekonomi dan
kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan pemerintah kolonial
selama 350 tahun menjajah Indonesia.
Soekarno memaparkan data mengenai penderitaan rakyat
Indonesia. Misalnya dikatakan, penghasilan seorang kepala rumah
tangga marhaen setahun rata-rata 161 gulden, sementara beban
setahun rata-rata 22,50 gulden, sehingga penghasilan bersih
setahun adalah 138,50 gulden. Kalau dihitung, maka rata-rata
pengeluaran setiap bulan adalah 12 gulden dan pengeluaran per hari
0,40 gulden. Maka apabila dimakan untuk lima orang, setiap harinya
adalah sebesar 0,08 gulden per orang. Tidak heran, kondisi rakyat
hari ini makan, besok belum tentu makan. Kondisi kesehatan sangat
buruk, sekitar 20 persen angka kematian, bahkan di kota-kota besar
seperti di Pasuruan, Betawi, dan Makassar bisa mencapai 30 sampai
40 persen kematian setiap tahunnya. Kalaupun bisa bertahan hidup,
badan mereka kurus kering dan sangat kekurangan gizi.
Kata Soekarno, "rakyat kami hidup dalam jajahan yang sengsara,
imperialisme modern telah menunjukkan kejahatannya".
Dengan penghasilan yang hanya sekian gulden per tahun, setiap
marhaen harus membayar pajak 10 persen, sementara bangsa
Eropa pajak setinggi itu hanya dikenakan pada mereka yang
mempunyai penghasilan tidak kurang dari 8.000-9.000 gulden per
tahun. Bayangkan betapa kejamnya penghisapan yang dilakukan
pemerintah kolonial terhadap rakyat Indonesia yang tidak berdaya
itu.
Soekarno dianggap bersalah, dan dijatuhi hukuman empat tahun
penjara, kemudian dipindahkan ke Penjara Sukamiskin, Bandung. Ia
menerima perlakuan relatif baik di sini. Walaupun diasingkan pada
beberapa bulan pertama, namun sesudahnya Inggit, istrinya,
dibolehkan membesuk. Soekarno secara mental lebih kuat
dibandingkan ketika di Penjara Banceuy. Muncul kesadaran untuk
menerima keadaannya dan bahkan kemudian menganggap
penjaranya itu sebagai sekolah. Di Sukamiskin inilah Soekarno mulai
mendalami agama Islam secara intens dengan cara mempelajari isi
Al Quran.
Pembelaan Soekarno Indonesia Menggugat ternyata memperoleh
simpati tidak hanya dari kalangan ahli hukum yang ada di negeri
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (4 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
Belanda, tetapi juga mereka yang terlibat dalam gerakan anti-
imperialisme dan kolonialisme di Eropa Barat. Banyak kritik ditujukan
kepada Pemerintah Hindia Belanda yang memberi hukuman
terlampau berat kepada Soekarno. Karena itu pada akhirnya
hukuman dikurangi menjadi hanya dua tahun. Ia dibebaskan oleh
Gubernur Jenderal De Graeff pada pagi hari tanggal 31 Desember
1931.
Baru beberapa bulan menghirup udara kebebasan, Soekarno
ditangkap lagi dengan tuduhan tetap menyebarkan agitasi melawan
pemerintah kolonial. Memang selepas dari penjara-seperti biasanya-
mulai lagi bergerak memimpin partai. Ia mengadakan pertemuan
massa dan membakar semangat massa dengan berbagai pidatonya.
Seperti kita ketahui ketika Soekarno dipenjara, PNI- partai yang
didirikannya-pecah dan gerakan nasionalis menurun kegiatannya.
Sebagai gantinya berdiri PNI Baru dan Partindo. Soekarno kemudian
bergiat dalam Partindo.
***
UNTUK kedua kalinya Soekarno masuk penjara. Waktu itu usianya
32 tahun. Kali ini mereka mengurung Soekarno dalam sebuah sel
khusus supaya tidak bisa bertemu dengan orang lain. Pemerintah
kolonial Belanda menyadari, kekuatan Soekarno terletak pada
komunikasinya dengan rakyat, karena itu hubungannya dengan
rakyat harus diputuskan. Kalau pada waktu masuk penjara yang
pertama dulu masih ada kesenangan bisa berkomunikasi dengan
tiga kawannya yang lain yang sama-sama ditahan, maka di sini
Soekarno benar-benar dikucilkan. Dan seperti yang diakui oleh
Soekarno, keadaan itu telah membunuh seluruh kekuatannya.
Rakyat atau massa adalah sumber kekuatan Soekarno. Manakala
sumber kekuatan itu ditutup, maka habislah semangatnya.
Maka seperti halilintar di siang bolong, semua orang terkejut ketika
mendengar Soekarno telah menulis surat 'meminta ampun' pada
pemerintah jajahan. Kabar buruk tersebut cepat tersebar di antara
kaum pergerakan dan menjadi bahan pembicaraan. Termasuk Inggit
sendiri, merasa sangat tidak enak mendengar kabar tak sedap itu.
Yang menjadi pertanyaan adalah darimana mereka memperoleh
kabar tersebut?
Ternyata berdasarkan tulisan Ingleson, ada laporan pemerintah
kolonial pada akhir bulan Oktober yang diperkuat oleh pengumuman
pegurus Partindo, bahwa Soekarno telah mengundurkan diri dari
partai, menyesali kegiatannya di masa lalu dan menawarkan kerja
sama dengan pemerintah di masa mendatang.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (5 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
Apa sebenarnya yang sudah terjadi? Apakah memang benar
Soekarno telah meminta ampun kepada pemerintah kolonial Hindia
Belanda?
Sebenarnya tidak banyak orang yang mengetahui mengenai soal
permintaan ampun Soekarno itu. Soal ini memang tidak banyak
ditulis atau dikupas buku-buku yang terbit di Indonesia. Sampai
ketika tahun 1979, John Ingleson, seorang mahasiswa pascasarjana
pada Jurusan Sejarah Universitas Monash, Australia, menulis buku
yang berjudul Road to Exile: The Indonesia Movement, 1927-1934,
diterbitkan oleh Asian Studies Association of Australia, Southeast
Asian Publication Series. Buku yang berasal dari disertasi itu ditulis
berdasarkan penelitian perpustakaan arsip dokumen pemerintah
Hindia Belanda di Kementerian Dalam Negeri Belanda.
Bukunya itu yang kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia dan diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 1983 dengan judul
Jalan ke Pengasingan: Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun
1927-1934 itu tentu saja menggemparkan. Buku itu kontan
menimbulkan perdebatan seputar kebenaran cerita itu. Yang
menarik adalah kolumnis kawakan Rosihan Anwar termasuk yang
percaya dengan surat-surat Soekarno seperti yang terdapat dalam
tulisan Ingleson. Padahal sebenarnya Ingleson sendiri dalam
bukunya itu, selain berpikir kemungkinan kebenaran dari surat-surat
itu, juga tidak mengabaikan kemungkinan surat itu sebagai surat-
surat palsu.
Rosihan Anwar dalam kolomnya berjudul Perbedaan Analisa Politik
antara Sukarno dengan Hatta di Kompas, 15 September 1980,
menulis, "Sebuah perbedaan lain ialah dalam sikap politik terhadap
pemerintah jajahan Hindia Belanda. Hatta bersikap teguh, konsisten
dan konsekuen. Sebaliknya Sukarno, ahli pidato yang bergembar-
gembor, lekas bertekuk lutut, jika menghadapi keadaan yang sulit
dan tidak menyenangkan bagi dirinya".
Seterusnya Rosihan menulis, "Demikianlah dalam kurun waktu satu
bulan, ketika Sukarno berada dalam penjara Sukamiskin di Bandung,
ia menulis empat pucuk surat bertanggal 30 Agustus, 7, 21, dan 28
September 1933 kepada Jaksa Agung Hindia-Belanda. Dalam surat-
surat itu Sukarno memohon kepada Hindia Belanda supaya ia
dibebaskan dari tahanan penjara. Sebagai gantinya Sukarno berjanji
tidak akan lagi ambil bagian dalam soal-soal politik untuk masa hidup
selanjutnya. Ia mencantumkan sepucuk surat yang dialamatkan
kepada dewan pimpinan Partindo dan dalam surat itu ia memajukan
permintaan berhenti dari partai. Selain daripada itu dia mengakui,
betapa tidak bertanggung jawabnya kegiatan-kegiatan politiknya.
Seterusnya ia bertaubat dalam hal pandangan-pandangannya yang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (6 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
bersifat non-koperatif. Apabila pemerintah membebaskannya, maka
dia akan bekerja sama dengan pemerintah. Akhirnya dia
menawarkan akan menandatangani apa saja yang dikehendaki oleh
pemerintah guna memperoleh pembebasannya".
Selanjutnya dalam tulisan kolomnya di harian yang sama, 14
Februari 1981, Rosihan menegaskan kembali pendiriannya yang
cenderung meyakini kebenaran surat-surat tersebut. Ia memberi
contoh bahwa Soekarno pada tanggal 19 Desember 1948 tatkala
tentara Belanda menduduki Lapangan Terbang Maguwo dan sedang
bergerak menuju Kota Yogyakarta, Soekarno menyuruh Kepala
Rumah tangga Istana mengibarkan bendera putih tanda menyerah
pada Belanda dan membiarkan dirinya ditawan tentara Belanda.
Tulisnya, "Ini sekedar ilustrasi, memanglah Sukarno itu lekas
bertekuk lutut atau minta ampun, bila ada berhadapan dengan
kekuatan-kekuatan yang superior atau sedang mengalami ancaman
bahaya dan ketidak-enakan bagi dirinya. Semua ini kedengarannya
tidak sedap bagi mereka yang mengagung-agungkan atau
mengkultuskan pemimpin. Tetapi suka atau tidak suka, saya pikir,
kita sebagai bangsa harus berusaha mendidik diri kita, supaya
mencapai kedewasaan. Marilah kita hadapi realitas ini."
Namun demikian pada akhirnya Rosihan mengatakan bahwa itu
semua sama sekali tidak mengurangi penghargaan kepada
Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan bangsa dan negara
Indonesia. Tulisnya, "Kita mengakuinya sebagai pemimpin yang
besar jasanya bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia".
Tentu saja tulisan Rosihan Anwar itu menimbulkan pro dan kontra,
terutama mereka yang mencintai Soekarno dan menganggapnya
sebagai manusia pejuang tanpa cacat. Yang mengomentari adalah
Mahbub Djunaidi, Ayip Bakar, Anwar Luthan dan Mr Mohammad
Roem. Semuanya menulis di harian ini, Kompas.
Berlainan dengan Rosihan, keempatnya menyangsikan kebenaran
isi surat tersebut. Mr Mohammad Roem dalam tulisannya di Kompas,
25 Januari 1981, berjudul Surat-Surat dari Penjara Sukamiskin,
mempertanyakan apa yang dituliskan oleh Ingleson itu, sebab dibuat
tidak berdasarkan otentitas surat asli. Ia mempertanyakan otentitas
empat surat itu, sebab surat-surat yang dikutip dari arsip Kerajaan
Belanda itu bukanlah tulisan asli Soekarno, melainkan salinan dari
surat asli Soekarno yang diketik oleh pejabat yang diberi wewenang
oleh peraturan pemerintah kolonial waktu itu. Salinan itu diketik dan
tidak membawa tanda tangan asli Soekarno, melainkan hanya
"tertanda" atau ditandatangani oleh Soekarno.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (7 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
Mr Roem pada kesimpulan tulisannya mengatakan, sangat
meragukan kebenaran salinan surat-surat tersebut. Mr Roem
berkata: "Waktu saya membaca surat-surat itu, saya menemukan
beberapa kesalahan dalam bahasa Belandanya. Pengetahuan
bahasa Belanda Bung Karno (HBS) paling sedikit sama dengan
pengetahuan saya (AMS). Di waktu itu, kalau kita membuat surat
dalam bahasa Belanda untuk pembesar Belanda, kita hati-hati benar
jangan sampai membuat kesalahan. Surat Soekarno yang keempat
sangat emosional akhirnya. Meskipun tidak selamanya saya dapat
mengikuti Bung Karno, akan tetapi ini: Het te mooi om waar te zijn,
atau terlalu indah untuk benar".
***
BAGAIMANA sebenarnya salinan surat-surat Soekarno itu
sehinggamembuat Mr Roem tidak yakin?
Surat kedua Soekarno kepada Jaksa Agung tertanggal 7 September
1933 seperti tertulis dalam Laporan Surat Rahasia 1933/1276 adalah
sebagai berikut:
"Saya mohon kepada tuan dan pemerintah untuk melindungi saya
dari proses pengusutan hukum atau penahanan lebih lanjut, dan
untuk memerintahkan pembebasan saya dengan segera. Hukuman
penjara atau penahanan Saya mohon kepada tuan dan pemerintah
untuk melindungi saya dari akan berarti malapetaka bagi saya,
keluarga saya, terutama ibu saya-bagi ibu saya hukuman atas diri
saya itu mungkin berarti kematiannya. Setiap hari dalam tahanan ini
sekarang ini saya menderita kesedihan yang amat sangat dan
perasaan putus asa. Saya akan berterimakasih kepada kemurahan
hati pemerintah dan dengan sepenuh hati bersedia memperlihatkan
rasa terimakasih itu dalam tindakan-tindakan saya setelah bebas
nanti. Maafkanlah sikap saya yang tak tahu syukur setelah
pengampunan yang dulu. Saya telah menyatakan dalam surat saya
terdahulu bahwa sekarang ini jiwa saya sepenuhnya telah berubah.
Di dalam hati, saya telah membuang politik dan memohon tuan
melepaskan saya dengan segera dari penderitaan ini. Setiap jam
dari penahanan ini bagiku bagaikan satu hari penderitaan panjang
dan berat. Selanjutnya saya berharap bahwa tuan akan
mempertimbangkan keadaan pikiran saya sekarang yang patut
dikasihani, dan bahwa janji saya ini cukup memadai sehingga saya
bisa segera dibebaskan. Tetapi, apabila janji yang saya buat ini
belum cukup, maka bermurah hatilah terhadap diri saya (karena
keadaan saya benar-benar parah) dengan memberitahu pejabat
yang berwenang syarat-syarat mana yang masih harus saya penuhi
bagi pembebasan saya. Saya bersedia menerima semua tuntutan.
Penderitaan saya sendiri dan penderitaan keluarga serta ibu saya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (8 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
terlalu besar, penanggungan saya demikian beratnya, sementara
tanpa kepastian ini amat memakan syaraf, sehingga tak mungkinlah
saya tak menerima syarat-syarat itu seluruhnya. Bahkan saya juga
bersedia, bila tuan dan pemerintah benar-benar menghendakinya
sebagai syarat penglepasan saya, untuk mencabut kembali
permintaan saya dulu agar surat-surat saya tetap dirahasiakan, dan
menyatakan setuju kalau pemerintah mengadakan pengumuman
dengan kalimat-kalimat berikut: "Pemerintah telah menerima
permintaan dari Ir Sukarno untuk dibebaskan dengan janji bahwa ia
akan berhenti dari segala kegiatan politik lebih lanjut".
Sementara surat keempat tertanggal 28 September 1933 yang
termuat dalam Laporan Surat Rahasia 1933/1276 yang menurut Mr
Roem adalah terlalu indah untuk benar yaitu, antara lain, sebagai
berikut:
"Saya meratapkan sekali lagi dan sekali lagi permohonan dihadapan
tuan dan pemerintah, kembalikan saya kepada isteri saya dan
kepada ibu saya yang tua dan manis, akan tetapi sakit-sakitan. Saya
sudah berbuat jahat tapi saya menyesalinya yang sedalam-
dalamnya. Limpahkan ampun kepadaku dan dahulukan rasa kasihan
daripada hukum. Saya menjatuhkan diri di hadapan tuan dan
pemerintah agar dibebaskan dari penderitaan".
Roem berpendapat bahwa itu bagian taktik licik Belanda untuk
mengacaukan pikiran rakyat dan mengacaukan barisan perjuangan
pergerakan nasional Indonesia yang pada waktu itu sedang
mencapai puncaknya. Pembunuhan karakter manusia sekaliber
Soekarno akan mampu menghancurkan kekuatan mobilisasi massa
rakyat menghadapi pemerintah kolonial Belanda.
Yang menarik adalah polemik itu tidak selesai sampai di situ, sebab
kemudian Rosihan Anwar menjawabnya kembali dan dijawab sekali
lagi oleh Mr Roem. Kemudian polemik itu ditutup oleh sebuah tulisan
sejarawan Taufik Abdullah berjudul Biografi dan Surat-surat Itu
dalam Majalah Tempo tanggal 28 Februari 1981. Taufik Abdullah
berusaha membedakan antara seseorang sebagai manusia biasa
dan sebagai aktor sejarah. Sebagai manusia biasa seseorang dalam
kediriannya tampil sebagaimana adanya, yang bisa mencintai,
membenci, takut, nekat dan apa saja. Sementara sebagai aktor
sejarah, seorang manusia dapat luluh dalam kaitannya dengan
masyarakat dan dinamika sejarah. Artinya, apa pun yang sudah
berlangsung dalam pengalaman pribadinya sebagai manusia biasa
dengan segala kekuatan dan kelemahannya, tidak akan mengurangi
kontribusinya sebagai manusia pembuat sejarah bangsanya.
Soekarno pernah mengatakan pada Cindy Adams mengenai masa-
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (9 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
"Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda -- Jumat, 1 Juni 2001
masa itu sebagai berikut, "Aku akan dibuang ke salah satu pulau
yang paling jauh. Berapa lamakah? Hingga semangat dan jasadku
menjadi busuk. Aku akan menghadapi pembuangan itu". Namun, hal
ini diceritakan Soekarno pada tahun 1960-an, yaitu pada saat empat
buah surat soal 'minta ampun' belum dipublikasikan, sehingga
Soekarno tidak bisa menjawab tentang kebenarannya.
Apabila demikian halnya, tetap ada baiknya untuk melakukan
penelitian sejarah lebih lanjut mengenai kebenaran dari surat-surat
tersebut. Bagaimanapun surat-surat tersebut berkaitan dengan
periode tertentu yang amat penting dalam sejarah pergerakan
kebangsaan Indonesia.
* Valina Singka Subekti Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Indonesia.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Permintaan%...20pada%20Pemerintah%20Kolonial%20Belanda%20--.htm (10 of 11)4/3/2005 11:05:12 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara
Bersama Soekarno
Daniel Dhakidae
BIOGRAFI yang ditulis
oleh orang lain, apalagi
dalam kategori "as told
to" selalu membagi dua
pendapat antara yang
memuja dan mencaci-
makinya. Tentang
biografi semacam itu
sastrawati Inggris,
profesor sastra dari
University College,
London, AS Byatt,
mengatakan sebagai:
...bentuk rusak dan
upaya mengejar
pengetahuan murahan.
Cerita tuturan mereka
yang tidak mampu
menangkap penemuan
sejati, cerita sederhana
bagi orang yang tidak
mampu menyelam lebih
dalam. Bentuk rumpi dan
kekosongan jiwa yang
sakit. (On Histories and
Stories, Selected
Essays, dalam The New
York Times, 18 Maret
2001).
Penilaian sekeras ini kontra-produktif karena kalau semata-mata itu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (1 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
yang dipakai, hampir tidak terbuka kemungkinan mengenal seorang
lain melalui naskah-naskah warisan.
"Tales of the two presidents"
Ini juga berlaku dalam hal dua orang yang pernah menjadi presiden
Indonesia. Presiden Soekarno dan Soeharto, sama sekali tidak ada
waktu menulis otobiografinya sendiri, karena itu suasana batinnya
tidak pernah diketahui umum secara "asli". Soekarno dengan seluruh
kemampuan intelektualnya untuk merenung, mencernakan, dan
menulis tidak pernah meluangkan waktu menulis tentang dirinya
sendiri selain beberapa keping cerita anekdotal yang tercecer sana-
sini. Soeharto tidak pernah terbukti menulis sesuatu yang berarti
untuk publik, selain pidato-pidato kepresidenan dengan intervensi
begitu banyak tangan dan otak.
Namun, kalau biografi "as told to" menjadi satu-satunya sumber yang
bisa dipakai, maka berikut ini adalah "ucapan asli" dengan mana
kedua presiden itu mengungkapkan dirinya--Soekarno kira-kira
beberapa waktu sebelum atau di sekitar tahun 1965 kepada penulis
Amerika, Cindy Adams, dalam buku Sukarno, An Autobiography as
Told to Cindy Adams, pada saat Soekarno berumur 65 tahun;
Soeharto kira-kira beberapa waktu sebelum atau di sekitar tahun
1989 kepada dua penulis Indonesia, Dwipayana dan Ramadhan,
dalam buku Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya,
Otobiografi Seperti Dipaparkan Kepada G. Dwipayana dan
Ramadhan K.H., pada saat Soeharto berumur kira-kira hampir sama,
67 tahun.
Membandingkan apa yang dikatakan kedua orang ini tentang dirinya
mungkin bisa memberikan wawasan tentang kepribadiannya masing-
masing dan apa yang dibuatnya. Tentang dirinya Soekarno
mengatakan:
"Aku adalah putra seorang ibu Bali dari kasta Brahmana. Ibuku,
Idaju, berasal dari kasta tinggi. Raja terakhir Singaraja adalah paman
ibuku. Bapakku dari Jawa. Nama lengkapnya adalah Raden Sukemi
Sosrodihardjo. Raden adalah gelar bangsawan yang berarti "Tuan".
Bapak adalah keturunan Sultan Kediri... Apakah itu kebetulan atau
suatu pertanda bahwa aku dilahirkan dalam kelas yang memerintah,
akan tetapi apa pun kelahiranku atau suratan takdir, pengabdian
bagi kemerdekaan rakyatku bukan suatu keputusan tiba-tiba. Akulah
ahli-warisnya.
Suatu yang sangat berbeda berlangsung dengan Soeharto, yang
tentang dirinya berkata:
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (2 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Ayah saya, Kertosudiro, adalah ulu-ulu, petugas desa pengatur air,
yang bertani di atas tanah lungguh, tanah jabatan selama beliau
memikul tugasnya itu... Saya adalah keturunan Bapak Kertosudiro
alias Kertorejo ...yang secara pribadi tidak memiliki sawah sejengkal
pun.
Bila diperhatikan ada beberapa perbedaan besar yang menarik
perhatian antara keduanya. Pertama, keturunan ningrat langsung
saja diangkat Soekarno, baik dari pihak ibu maupun dari pihak
bapak. Dari pihak ibu garis keturunan disusur-mundur sampai ke
Raja Singaraja, Bali, dan dari pihak ayah disusur-mundur sampai ke
Sultan Kediri, yang kelak berurusan dengan kerajaan besar
Majapahit.
Sedangkan Soeharto hanya menyebut Desa Kemusuk, desa kecil di
luar Kota Yogyakarta, dan pangkat bapaknya seorang "ulu-ulu,
petugas desa pengatur air". Kedua, bukan saja keningratan akan
tetapi adanya suatu suratan takdir bahwa Soekarno, bukan karena
kemauannya atau keinginan pribadinya akan tetapi sejarah
menetapkan demikian, akan dan bahkan harus memimpin Indonesia
karena dari asal-muasal sebagai bagian dari the ruling class. Ketiga,
meski dengan seluruh kesadaran tentang "silsilah" ke masa lalu dan
suratan takdir ke masa depan tidak satu kata pun disebut Soekarno
tentang harta, milik, atau kekayaan apa pun. Sebaliknya, Soeharto
sudah dalam halaman-halaman pertama membicarakan harta-tanah
sejengkal, tanah jabatan, pangkat bapaknya, yang dalam halaman-
halaman susulannya berbicara lagi tentang kambing, baju dan lain-
lain lagi-meski semuanya dihubungkan dengan "...banyak
penderitaan yang mungkin tidak dialami oleh orang-orang lain".
Keempat, Soekarno bukan saja berbicara tentang keningratan,
suratan takdir, kelas berkuasa dan memerintah akan tetapi tentang
freedom of the people, suatu cita-cita abstrak-filosofis tinggi yang
mencerminkan idealisme Soekarno-isch. Semuanya ini tentu saja
berhubungan dengan kekuasaan, power, akan tetapi Soekarno tidak
berbicara tentang kekuasaan dirinya. Dia berbicara tentang kelas
berkuasa dan bukan tentang dirinya dan kekuasaan akan tetapi
suratan takdir untuk memimpin.
Dalam hal Soeharto bisa dilihat sesuatu yang berbeda karena
Soeharto berbicara tentang kekuasaan. Hal itu bisa diperiksa hanya
dalam satu halaman sebelumnya ketika Soeharto kepada
pewawancara untuk penulisan bukunya, dengan bangga dan sedikit
sombong, mengenang saat ketika dia berdiri di depan forum dunia
tahun 1985 di Food and Agriculture Organization, FAO, milik PBB, di
Kota Roma:
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (3 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Saudara bayangkan, seorang yang lebih dari enam puluh tahun ke
belakang masih anak bermandi lumpur di tengah kehidupan petani di
Desa Kemusuk saat itu naik mimbar dan bicara di depan sekian
banyak ahli dan negarawan dunia, sebagai pemimpin rakyat yang
baru berhasil memecahkan persoalan yang paling besar bagi lebih
dari 160 juta mulut.
Suatu loncatan besar dari suatu desa kecil di Yogyakarta, ke Roma,
kota metropolitan; dari seorang anak berlumur lumpur di Kemusuk
yang langsung dihubungkan dengan mimbar yang harus dipahami
dalam arti ex cathedra, dan berbicara, yang juga harus dipahami
lebih dalam arti memberikan maklumat di depan para ahli dan
negarawan dunia. Dia menyebut dirinya pemimpin rakyat sambil
menjejerkan prestasinya-bukan dalam hubungan dengan freedom of
the people akan tetapi dengan kemampuannya memecahkan soal
paling besar; bukan soal abstrak-filosofis Soekarno-isch akan tetapi
persoalan "lebih dari 160 juta mulut". Ketika dia menyebut rakyat
maka dia reduksikan rakyat itu menjadi bukan orang akan tetapi
mulut.
Satu Abad Bersama Nusantara
Dengan itu sebagai titik tolak-idealisme, sense of destiny, dan apa
yang dicapainya-penerbitan khusus ini mau memeriksa Soekarno
pada hari ulang tahunnya yang ke-100 sebagai suatu gejala historis.
Kalau Soekarno sendiri mungkin tidak dengan mudah menilai
dirinya, semakin besar pula kesulitan itu untuk kita. Kesulitan itu
semakin besar lagi ketika kita harus memeriksa kembali diri
Soekarno-30 tahun setelah meninggalkan dunia ini, 45 tahun setelah
dijatuhkan Soeharto, dan 100 tahun setelah dilahirkan ibunya.
Semuanya menjadi suatu kompleks dari persoalan karena
meninggalnya 30 tahun lalu bukan sekadar seorang yang memenuhi
nasib Sein zum Tode akan tetapi karena kematiannya semakin
menimbulkan soal lagi-betulkah dia mati wajar? Kejatuhannya lebih
membingungkan ketika semuanya berpusat pada pembunuhan
enam jenderal-betulkah PKI yang membunuh dengan konsekuensi
menjatuhkan Soekarno pelindungnya adalah keharusan, atau
mereka dibunuh oleh anak buahnya sendiri para perwira militer
bawahannya dan dengan itu tidak perlu menjatuhkan Soekarno.
Hannah Arendt tidak mengalami kesulitan ketika harus
mengucapkan eulogia kepada Karl Jaspers, filosof eksistensialis-
teman, kolega, yang mendapatkan hadiah perdamaian Jerman.
Tidak ada kata yang lebih pantas, demikian Arendt, daripada puja-
pujian, laudatio, karena, sambil mengutip Cicero dikatakannya "in
laudationibus...ad personarum dignitatem omnia referrentur", dalam
puja-pujian semuanya mengacu kembali kepada kebesaran pribadi-
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (4 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
pribadi itu, terutama karena mereka membuktikan dirinya dalam
hidup.
Di sana justru letak seluruh kegemasan memeriksa Soekarno,
karena jajaran antara dignitas personae dan pembuktian diri dalam
hidup tidak selalu seiring, apalagi persoalan yang ditinggalkan
Soekarno, seperti konsekuensi ekonomi-politik dan karena itu
kemanusiaan yang berasal dari keputusan-keputusannya. Menilai
Soekarno semata-mata dari kebesarannya-kalau bukan pendasar
maka Soekarno adalah penganjur paling vokal nasionalisme
Indonesia, proklamator kemerdekaan-selalu membingungkan dan
juga memusingkan karena di samping kebesaran di sana langsung
menyusul kekerdilan, di samping kecemerlangan langsung menyusul
diletantisme, di samping keberanian revolusioner langsung saja
menyusul kekecutan, dan ke-pengecut-an. (Baca: Valina Singka
Subekti)
Di pihak lain mengecilkan Soekarno hanya karena persoalan yang
ditinggalkannya-semua masalah pra dan pascaperistiwa tanggal 1
Oktober 1965, pembunuhan jenderal-jenderal oleh para perwira
bawahannya--sungguh menyesatkan dari satu ujung ke ujung
lainnya dan bagi generasi-generasi berikutnya menjadi penipuan
terencana. Lantas pertanyaan-untuk siapa pun yang berminat
memeriksa Soekarno secara sungguh-sungguh-harus diajukan
kembali lagi ke dasar paling awal: siapa Soekarno? Apa yang dibuat
Bung Karno? Apa yang ditinggalkan Presiden Republik Indonesia
pertama, Pemimpin Besar Revolusi, dan Penyambung Lidah
Rakyat?
Satu Abad Nusantara Bersama Soekarno
Soekarno adalah seorang cendekiawan yang meninggalkan ratusan
karya tulis dan beberapa naskah drama yang mungkin hanya pernah
dipentaskan di Ende, Flores. Kumpulan tulisannya sudah diterbitkan
dengan judul Dibawah Bendera Revolusi, dua jilid. Namun, dari dua
jilid ini hanya jilid pertama yang boleh dikatakan paling menarik dan
paling penting karena mewakili diri Soekarno sebagai Soekarno. Dari
buku setebal kira-kira 630 halaman tersebut tulisan pertama yang
berasal dari tahun 1926, dengan judul "Nasionalisme, Islamisme,
dan Marxisme" yang paling menarik dan mungkin paling penting
sebagai titik-tolak dalam upaya memahami Soekarno dalam gelora
masa mudanya, seorang pemuda berumur 26 tahun-kira-kira pada
umur yang sama ketika Marx, 30 tahun, dan Engels, 28 tahun,
menulis Manifesto Partai Komunis.
Marx dan Engels membuka manifestonya dengan kata-kata "a
spectre is haunting Europe--the spectre of Communism", ada hantu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (5 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
yang menggerayangi Eropa--hantu komunisme. Soekarno membuka
tulisannya dengan suatu pernyataan keras, semacam Manifesto
Soekarno-isch:
Sebagai Aria Bima-Putera, jang lahirnja dalam zaman perdjoangan,
maka Indonesia-Muda inilah melihat tjahaja hari pertama-tama
dalam zaman jang rakjat-rakjat Asia, lagi berada dalam perasaan tak
senang dengan nasibnja. Tak senang dengan nasib-ekonominja, tak
senang dengan nasib-politiknja, tak senang dengan segala nasib
jang lain-lainnja. Zaman "senang dengan apa adanja", sudahlah lalu.
Zaman baru: zaman m u d a, sudahlah datang sebagai fadjar jang
terang tjuatja.
Paralelisme antara manifesto Marxis dan manifesto Sukarno-isch
bisa dilihat di sini. Soekarno membuka manifestonya yang sarat
dengan simbolisme ketika di sana dikatakan tentang Suluh Indonesia
Muda, majalah bulanan yang didirikannya sebagai organ organisasi
Algemeene Studie Club, yang juga didirikannya: "Sebagai Aria Bima-
Putera, jang lahirnja dalam zaman perdjoangan". Dalam imaji
Soekarno Suluh harus menjadi secerdik-cendekia Gatotkaca, sesakti
dan seulet tokoh wayang itu yang menjadi orang terakhir yang
mengembuskan napasnya di tangan pamannya sendiri. Imaji
Soekarno tentang Gatotkaca tidak jauh dari imaji orang Jawa
umumnya tentang Gatotkaca, yakni berani tak mengenal takut,
teguh, tangguh, cerdik-pandai, waspada, gesit, tangkas dan terampil,
tabah dan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Ia sangat
sakti, sehingga digambarkan sebagai ksatria yang mempunyai 'otot
kawat balung wesi'...sumsum gagala, kulit tembaga, drijit gunting,
dengkul paron... (Ensiklopedi Wayang Purwa, Balai Pustaka, 1991)
"Hantu" Gatotkaca selalu kembali kalau diperlukan kerajaan
Pandawa dalam keadaan krisis dan dalam kalangan keluarga
Pandawa berlaku semacam standing order:"...bila sewaktu-waktu
menghadapi bahaya, agar memanggil Gatotkaca". Gatotkaca di sini
tidak lain dari semacam "hantu", spectre, das Gespenst dalam
Manifesto Karl Marx, yang menurut Derrida hantu itu harus dipahami
dalam arti hantologie-dan bukan ontologie sebagaimana Marx selalu
ditafsirkan--sebagai keadilan yang tidak bisa diredusir lagi.
Dalam manifesto Soekarno, maka dasar berpijak itu berada pada
kemerdekaan dari mana tidak ada reduksi lagi-yaitu kemerdekaan
dalam arti lepas dan melepaskan diri dari kolonialisme asing, Barat.
Kemerdekaan memerlukan beberapa syarat dan salah satu syarat
terpenting adalah persatuan. Hantu kemerdekaan itulah yang selalu
kembali seperti Gatotkaca untuk menuntut keadilan dalam suatu
masa ketika Asia merasa tak senang dengan nasibnya, yaitu nasib
kolonial yang tidak adil. Dalam paham Soekarno kolonialisme itu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (6 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
tidak lain dari soal kekurangan rezeki, dan "kekurangan rezeki itulah
jang mendjadi sebab rakjat-rakjat Eropah mentjari rezeki dinegeri
lain!".
Dalam paham Soekarno di Asia sudah mulai tumbuh keinsyafan
akan tragedi ketika "rakjat-rakjat Eropah itu mempertuankan negeri-
negeri Asia" (untuk para pembaca muda "mempertuankan negeri-
negeri Asia = menguasai, menjajah Asia-Penulis). Keinsyafan akan
tragedi itulah yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat
Indonesia yang walaupun dalam maksudnya sama "ada mempunyai
tiga sifat: nasionalistis, Islamistis dan Marxistis-lah adanja".
Apa yang dipahami Soekarno tentang marxisme? Sebelum masuk
ke dalam apa yang dipahami Soekarno, untuk itu baca Franz Magnis-
Suseno, mari kita lihat beberapa hal teknis tentang orang yang
disanjungnya dan paham yang dipuja. Sungguh mencengangkan
bahwa menulis nama Karl Marx pun, Soekarno menulisnya terbalik,
dalam suatu urutan nama Barat, dengan tiga suku bersama iddle
name. Soekarno menulis bukan Karl Heinrich Marx, akan tetapi
Heinrich Karl Marx. Ketika memberikan acuan kepada Manifesto
Komunis Soekarno mengatakan, di tiga halaman berbeda, bahwa
Manifesto ditulis dan diumumkan tahun 1847--tahun sesungguhnya
adalah bulan Februari 1848. Semua kekeliruan "kecil" di atas harus
dimaafkan karena lebih bisa diterima sebagai kealpaan seorang
sarjana yang baru saja tamat Sekolah Tinggi Teknik di Bandung
dengan gelar insinyur--kalau sudah tamat karena Soekarno
menyelesaikan studinya 25 Mei 1926. (Edisi asli Soeloeh Indonesia
Moeda, tidak diperoleh).
Apa sesungguhnya yang dipahami Soekarno tentang ketiganya?
Bisalah dikatakan di sini bahwa apa yang dicita-citakan Soekarno
adalah suatu mission impossible baik dari segi teoretis maupun dari
segi praktis. Nasionalisme Soekarno adalah jenis nasionalisme
voluntaristik, dengan tekad sebagai modal dengan tujuan hampir
satu-satunya yaitu persatuan tanpa mempedulikan realitas ekonomi-
politik. Karena itu ketika Soekarno mengatakan bahwa:
...asal mau sahadja...tak kuranglah djalan kearah persatuan.
Kemauan, pertjaja akan ketulusan hati satu sama lain, keinsjafan
akan pepatah "rukun membikin sentausa" ...tjukup kuatnja untuk
melangkahi segala perbedaan dan keseganan antara segala fihak-
fihak dalam pergerakan kita ini lebih menjadi wishful thinking baik
pada waktu itu maupun pada waktu ini. (Baca: Baskara Wardaya)
Mengapa persatuan? karena itulah persyaratan bagi kemerdekaan.
Dengan begitu semua yang lain atau tunduk kepada atau harus
ditafsirkan kembali atas dasar persatuan. Persatuan pada gilirannya
akan merumuskan jenis nasionalisme, Islam, dan marxisme. Hampir
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (7 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
seluruh esoterisme Soekarno dan kekhilafan fundamental yang
tersebar sana-sini ketika menafsirkan nasionalisme, Islam, dan
marxisme berasal dari sana. (Baca: Vedi Hadiz)
Soekarno dan suratan takdir
Semakin Soekarno diperiksa, semakin kita tidak mengerti siapa
Soekarno itu selain bahwa suratan takdir itu sudah dipenuhinya yaitu
memimpin Indonesia dalam waktu yang lama-bukan sekadar ketika
menjadi presiden, akan tetapi jauh-jauh sebelum itu, sekurang-
kurangnya sejak mengeluarkan manifesto Soekarno-isch tahun 1926
sampai dijatuhkan militer tahun 1966 di Jakarta. Setelah jatuh pun
Orde Baru tidak mampu menghapus Soekarno dari kenangan publik
dan pujaan massa yang tidak pernah mengenalnya. (Baca: Agus
Sudibyo). Manifesto itu menjadi dasar geloranya, dan juga menjadi
dasar ketidak-tentuan-nya. Namun, sejak itu Soekarno dan
Indonesia hampir tidak terpisahkan, baik bagi bangsanya, maupun
bagi dunia: bagi Asia, Afrika, dan Amerika Latin, Belanda kolonial,
bagi fasisme Jepang, maupun bagi imperialis, Amerika dan Inggris-
baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka.
Secara intelektual dan politik ketika Soekarno menganalisa soal dia
menjadi Marxis. Ketika dia ingin menghanyutkan massa Soekarno
menjadi Leninis dalam jalan pikiran. Namun, ketika harus
memecahkan soal dalam masa krisis, dia menjadi lebih dekat
kepada sesuatu yang sangat dibencinya yaitu menjadi fasis dalam
berpikir dan bertindak. Karena itu dia dan militer seperti aur dan
tebing, yang satu membutuhkan yang lain, meski kemudian dia
dikhianati militer.
Dalam hubungan dengan gerak dan tindakan militer, Soekarno
menempatkan persatuan jauh-jauh lebih penting, sesuatu yang
sangat disukai militer, dari kemerdekaan, terutama dalam arti
kebebasan-Soekarno menjadi anti-Soekarno-sesuatu yang mungkin
lebih diperlukan warganya yang sudah lelah dan letih ditindas
ratusan tahun, oleh tuan-tuan asing-putih-kuning, dan kelak tuan-
tuan sawomatang dari bangsanya sendiri. Tidak ada orang lain yang
lebih paham tentang penderitaan itu dari Soekarno.
* Daniel Dhakidae Kepala Litbang Kompas.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Satu%20Abad...ra%20dan%20Nusantara%20Bersama%20Soekarno%20-.htm (8 of 9)4/3/2005 11:05:13 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno di Masa Krisis PDRI
Mestika Zed
BULAN-
bulan terakhir
tahun 1948
adalah saat
terberat
dalam
perjuangan
kemerdekaan
Republik
Indonesia.
Bukan saja
karena
Republik
yang masih
usia balita itu
Dok Kompas harus
menghadapi
musuh di
depan Belanda-tetapi juga ditusuk dari belakang oleh anak-bangsa
sendiri, yaitu kelompok komunis (PKI) pimpinan Muso yang mendalangi
peristiwa (kudeta) Madiun pada pertengahan September 1948.
Klimaksnya ialah terjadinya serangan (agresi) militer Belanda kedua
pada 19 Desember 1948. Akibatnya nyaris fatal. Ibu kota Republik,
Yogyakarta, diduduki Belanda, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden
Mohammad Hatta beserta sejumlah menteri yang berada di ibu kota
ditangkap. Sejak itu Belanda menganggap Republik sudah tamat
riwayatnya.Akan tetapi, kemenangan militernya itu hanya bersifat
sementara. Walaupun ibu kota Yogya jatuh ke tangan Belanda dan
Presiden Soekarno serta Wakil Presiden Hatta dengan sejumlah
menteri dapat ditawannya, nyatanya Republik tidak pernah bubar
seperti yang dibayangkan Belanda. Suatu titik balik yang tak terduga
oleh Belanda datang secara hampir serentak dari dua jurusan.
Pertama, dari Yogya dan kedua dari Bukittinggi di Sumatera. Beberapa
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
jam sebelum kejatuhan Yogya, sebuah sidang darurat kabinet berhasil
mengambil keputusan historis yang amat penting: Presiden dan Wakil
Presiden memberikan mandat (dalam sumber "menguasakan") kepada
Mr Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat
RI di Sumatera. Jika ikhtiar ini gagal, mandat diserahkan kepada Dr
Soedarsono, Mr Maramis dan Palar untuk membentuk exile-
government di New Delhi, India. Surat mandat tersebut kabarnya tidak
sempat "dikawatkan" karena hubungan telekomunikasi keburu jatuh ke
tangan Belanda. Namun, naskahnya dalam bentuk ketikan sempat
beredar di kalangan orang Republieken.
Kedua, sewaktu mengetahui (via radio) bahwa Yogya diserang, Mr
Sjafruddin Prawiranegara (waktu itu Menteri Kemakmuran) yang
sedang bertugas di Sumatera, segera mengumumkan berdirinya
Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi.
Tindakannya itu mulanya bukan berdasarkan pada mandat yang
dikirimkan Yogya, melainkan atas inisiatif "spontan", Sjafruddin dengan
pemimpin setempat, PDRI pada gilirannya dapat berperan sebagai
"pemerintah alternatif" bagi Republik yang tengah menghadapi "koma".
Sebagaimana terbukti kemudian, selama delapan bulan keberadaannya
(Desember 1948-Juli 1949), PDRI di bawah kepemimpinan Sjafruddin
di Sumatera mampu memainkan peran penting sebagai pusat gravitasi
baru dalam mempersatukan kembali kekuatan Republik yang bercerai-
berai di Jawa dan Sumatera. Bahkan, tidak kurang dari Panglima
Soedirman sendiri, yang kecewa dengan menyerahnya Soekarno-Hatta
kepada Belanda, menyatakan kesetiaannya kepada PDRI dan siap
memimpin perjuangan dengan bergerilya di hutan-hutan belantara
dalam keadaan sakit parah sekalipun.
Sementara itu, kontak-kontak PDRI via India ke dunia internasional
membuat kemenangan militer Belanda semakin tak berarti, suatu
Pyrrhic victory, suatu kemenangan yang terlalu banyak makan korban,
suatu kemenangan sia-sia karena sukses militer yang dicapainya harus
ditarik kembali. Hanya dalam tempo tiga hari setelah kejatuhan Yogya,
tepatnya tanggal 22-23 Desember, Dewan Keamanan PBB buru-buru
mengadakan sidangnya. Semua negara, kecuali Belgia, mengecam
keras tindakan Belanda di Indonesia. Pihak Belanda benar-benar dibuat
sebagai "pesakitan" yang kehilangan muka di panggung pengadilan
dunia.
Resolusi DK-PBB, kemudian juga diperkuat dengan Konferensi Asia di
New Delhi kurang satu bulan kemudian, yang menuntut pembebasan
segera para pemimpin Republik yang ditangkap, begitu juga
pengembalian ibu kota Yogya dan pembentukan pemerintahan
Indonesia yang demokratis tanpa campur tangan Belanda. Dalam
perundingan-perundingan selanjutnya negara bekas penjajah itu tidak
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
bisa lagi mengelak dari campur tangan internasional. Sejak itu,
kebohongan-kebohongan yang direkayasa Belanda lewat manipulasi
informasi untuk mempengaruhi opini dunia semakin kelihatan
belangnya sehingga membuat posisinya semakin terpojok, baik di
Indonesia maupun di mata dunia.
Tulisan ini ingin mendiskusikan sekadarnya tentang posisi Soekarno di
masa PDRI, yang selama ini terkesan ingin dilupakan, baik oleh dirinya
sendiri maupun oleh sejumlah penulis biografinya, dan bahkan juga
dalam wacana sejarah bangsa umumnya. Apakah dilema sejarah yang
dihadapinya dalam kerangka perjuangan diplomasi dan/atau militer
pada masa itu? Apa sebenarnya yang terjadi dalam diri Soekarno
sehingga peranannya dalam masa-masa krisis waktu itu seakan-akan
tenggelam sebagai kawasan terra incognita yang belum banyak
disentuh selama ini?
Pemimpin yang hadir di saat-saat kritis
Telah berpuluh-puluh tahun "Bapak Bangsa" (the founding fathers)-jika
yang dimaksud dengan itu ialah semua tokoh yang ikut merumuskan
konstitusi-berjuang mendirikan sebuah nation-state, negara bangsa
yang akhirnya diproklamasikan 17 Agustus 1945 itu: Republik
Indonesia atau sering disingkat dengan Republik saja. Dalam usianya
yang masih bayi itu, Republik yang dimerdekakan dengan revolusi itu
terpaksa harus menghadapi cobaan yang bertubi-tubi. Namun, belum
pernah terjadi sebelumnya dan juga tidak sesudahnya, kecuali hanya
pada masa agresi kedua, ketika sebuah ibu kota negara jatuh ke
tangan musuh, Presiden dan Wakil Presidennya beserta sejumlah
menteri ditangkap Belanda. Juga belum pernah terjadi sebelumnya,
kecuali pada masa ini, simpati dan dukungan dunia internasional
terhadap Indonesia demikian intensnya. Di atas segala-galanya nasib
Republik pada akhirnya haruslah ditentukan oleh pemimpin dan
bangsanya sendiri.
Salah seorang pemimpinnya yang paling terkemuka ialah Soekarno,
proklamator dan Presiden Republik yang pertama. Ia tak hanya cakap
dalam menghadirkan gagasan, tetapi juga seorang pemimpin yang
selalu hadir memberi "kata-putus" di saat-saat yang paling genting bagi
negara dan bangsanya. Itulah yang terjadi, misalnya, pada saat-saat
genting sebelum Proklamasi, di mana faktor Soekarno bersama Hatta,
menjadi amat menentukan dalam Kasus Rengasdengklok. Bukankah,
situasi kritis pada rapat raksasa yang penuh gejolak di Lapangan Ikada-
satu bulan setelah ia menjadi presiden-hanya dapat didinginkan oleh
Soekarno, hingga hadirin bisa pulang dengan tenang dan pertumpahan
darah dengan Jepang pun akhirnya tak perlu terjadi? Bukankah
Soekarno pula yang dipanggil Sekutu untuk meredakan pertempuran
10 November di Surabaya ketika posisinya yang semakin terjepit dan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
siap melepaskan senjata modern, memerlukan seorang Bung Karno,
demi untuk menghindari semakin banyak korban 'mati-konyol' karena
pasukan bambu runcing yang siap "berjibaku" untuk Tanah Air mereka,
seperti juga dalam pertempuran Ambarawa?
Akan tetapi, di masa kritis pada penghujung tahun 1948, bisakah
Soekarno sebagai pemimpin, membawa bangsanya keluar dari
keadaan gawat itu? Memang tak mudah melihat Bung Karno dalam
potret hitam putih. Seperti dikatakan sejarawan Onghokham (1978), dia
adalah "pribadi yang kompleks dan tokoh penuh aneka warna". Namun,
untuk satu hal, "Bung Karno adalah sebuah gelora", tulis kolumnis
Gunawan Mohamad dalam sebuah esai pendeknya (1991). Sebuah
gelora adalah sesuatu yang menggetarkan. Sebuah gelora juga
merupakan sesuatu yang bisa memesonakan dan bahkan
menghanyutkan. Tetapi, sebuah gelora juga merupakan sesuatu yang
tak punya definisi yang persis. Ia bagaikan nebula yang jauh di langit.
Mungkin gugus itu sehimpun bintang yang bersinar atau barangkali
hanya selapis kabut bercahaya.
Nebula yang bersinar itu ialah harapan yang dipancarkan dari figur dan
pidato-pidatonya yang menggetarkan. Tetapi, harapan juga bisa
berbalik menjadi kekecewaan baru, ketika apa yang dijanjikannya tak
sesuai kenyataan. Itulah yang terjadi pada saat-saat genting sewaktu
agresi Belanda kedua itu.
Pada bulan-bulan terakhir 1948, Bung Karno sangat sibuk mengadakan
perjalanan dan menyampaikan pidato-pidato politiknya yang gegap
gempita, guna mengangkat moral perjuangan yang semakin merosot
karena ditusuk dari muka dan belakang. Di depan ada Belanda, yang
setelah Perjanjian Renville (Januari 1948) terus-menerus menggembosi
dukungan Republik dengan mendirikan negara-negara federal versi
Van Mook. Waktu itu hampir semua wilayah Indonesia sudah berada di
bawah pengaruh Belanda dengan berdirinya negara-negara federal
ciptaan Van Mook di sana, kecuali di tiga daerah: Yogyakarta,
Sumatera Barat, dan Aceh, di mana negara federal tidak mendapat
tempat karena kesetiaan kepada Republik sudah merupakan harga
mati yang tak bisa ditawar-tawar.
Sementara tekanan politik federal Van Mook semakin gencar, terjadi
pula pemberontakan PKI di Solo dan Madiun bulan September 1948.
Pemberontakan itu bukan hanya suatu pengkhianatan, melainkan juga
"tusukan dari belakang", yang memperlemah Republik di saat posisi
Belanda semakin unjuk kekuatan dan diperkirakan akan melakukan
serangan baru setiap saat. Dalam suasana kacau balau dan terombang-
ambing "di antara dua karang" seperti dilukiskan Hatta waktu itu
Soekarno-Hatta adalah "dwitunggal" yang membuat kepastian dalam
ketidakpastian. Sebuah pesan radio dari Presiden Soekarno meminta
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
ketegasan kepada rakyat untuk memilih pemerintahan yang sah atau
Muso.
Pidato-pidato Soekarno menggetarkan, acap kali diselingi dengan
slogan-slogan yang menggugah. Salah satu slogan berbahasa Belanda
yang tidak saja sering diulang-ulanginya dalam setiap kesempatan,
melainkan juga dengan gigih diperjuangkannya sejak muda ialah
samenbundeling van alle krachten (menghimpun segala kekuatan).
"Saya menyaksikan bagaimana pidatonya mampu membangkitkan
kesadaran politik di kalangan rakyat di desa dan di kota", kenang
George McT Kahin, seorang mahasiswa Amerika yang saat itu berada
di Yogya untuk keperluan riset disertasinya. Ia benar-benar mengenal
detak jantung rakyatnya dan "tidak dapat ditandingi oleh pemimpin
mana pun juga", tulis Kahin dalam sebuah risalahnya (1986).
Namun, ucapan Bung Karno yang paling berkesan waktu itu, hingga
sering dikutip-kutip koran dan itu diulanginya lagi lewat radio dan
terakhir dalam pidatonya dua hari sebelum aksi militer Belanda ialah,
"Jika Belanda ngotot menggunakan kekuatan militernya untuk
menghancurkan Republik Indonesia dengan menduduki Yogyakarta,
tujuh puluh juta rakyat Indonesia akan bangkit berjuang dan saya
sendiri akan memimpin perang gerilya." (Merdeka, 29 Mei 1948)
Namun, apa yang terjadi kemudian ialah sebuah kekecewaan. Ketika
Yogya diserang, Soekarno dan pemimpin Republik merencanakan
tetap tinggal di dalam kota, artinya menyerah kepada Belanda. Reaksi
dari kalangan militer, terutama di kalangan para perwira yang tahu
bahwa Soekarno sebelumnya bersedia untuk ikut bergerilya bersama
mereka, telah menimbulkan rasa kecewa yang dalam. Bahkan, perintah
yang dikeluarkan Hatta, pada saat-saat terakhir menjelang kejatuhan
Yogyakarta, agar perjuangan diteruskan, tidak lagi mampu memulihkan
rasa hormat tentara terhadap pemimpin sipil mereka. Peristiwa di atas,
menurut Ulf Sundhaussen (1982) merupakan awal rusaknya hubungan
sipil-militer dalam perpolitikan Indonesia.
Akan tetapi, kekecewaan pada Bung Karno-patahnya kepercayaan
kepada obor, sebuah simbol-tidak hanya merisaukan banyak orang.
Kejadian dramatis di hari itu juga menimbulkan kekecewaan dan
kecemasan Soekarno pribadi. Ia pun senantiasa berada dalam
kecemasan terus-menerus terhadap nasib Republik dan terhadap
nyawanya. "Pada akhirnya saya hanya manusia biasa. Siapa yang tahu
apa rencana mereka terhadap saya? Saya punya perasaan mereka
akan membunuh saya. Tiap kali saya mendengar bunyi yang asing,
saya berpikir: sekarang tiba saatnya; mereka akan membawa saya ke
depan pleton penembak", begitu dituturkannya kepada Cindy Adam,
penulis otobiografinya yang terkenal.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
Walaupun pada akhirnya Presiden dan Wakil Presiden dengan
sejumlah anggota kabinet ditawan Belanda, suasana kritis dan
mencekam waktu itu tidak perlu membuat kedua tokoh puncak Republik
itu kehilangan akal sehat. Pada detik-detik sebelum kejatuhan Yogya,
mereka masih sempat melepas anak panah terakhir dari busurnya:
mandat berdirinya PDRI, sebuah keputusan yang menentukan
perjalanan sejarah Republik selanjutnya. Setelah itu mereka ditangkap
dan tak lagi tahu apa yang terjadi di luar dinding tembok tahanan
mereka.
Menurut keterangan Hatta di belakang hari, keputusan apakah
pemerintah akan tetap berada dalam kota atau ikut bergerilya bukan
atas kemauan pribadi Presiden dan Wakil Presiden, melainkan
keputusan yang ditetapkan kabinet berdasarkan pemungutan suara.
Soekarno dan Menteri Laoh cenderung memilih sikap pertama, artinya
tetap di tempat, sedangkan pihak militer, terutama Panglima Besar
Soedirman, dengan tegas sejak pagi-pagi sudah memutuskan untuk
meninggalkan kota, artinya siap bergerilya dengan prajurit TNI.
Simatupang juga menyarankan agar Presiden dan Wakil Presiden
sebaiknya "ikut perang gerilya". Namun, karena tidak tersedia cukup
pasukan pengawal untuk kedua pemimpin itu, dia bisa menerima sikap
resmi pemerintah. (Hatta, 1982: 541-2)
Hidup dalam pembuangan
Para pemimpin Republik yang ditawan Belanda selepas pendudukan
Yogya, diasingkan pada dua tempat yang berbeda. Tiga orang
pemimpin besar Indonesia: Soekarno, Haji Agus Salim, dan Sutan
Sjahrir ditawan di Brastagi, Sumatera Utara, kemudian dipindahkan ke
Prapat. Selebihnya, termasuk Hatta, dideportasi ke Bangka. Di antara
tokoh yang ditawan di Brastagi, Haji Agoes Salim adalah yang paling
tua, tetapi paling singkat masa penahanannya. Di zaman Belanda ia tak
pernah masuk penjara, kecuali sebentar di zaman Jepang. Karena
penahanan itu dianggap kekhilafan belaka, kemudian ia dibebaskan
dengan "permintaan maaf" dari pembesar Jepang. Tetapi, kejadian
serupa juga dapat ditemukan dalam setiap zaman sejarah Indonesia
merdeka, bahkan juga dalam periode yang lebih belakangan.
Akan tetapi, Soekarno dan Sjahrir sama-sama pernah mengalami hidup
dalam penjara Belanda dalam waktu yang lama. Sjahrir pernah menjadi
Digulis, tahanan kelas berat bersama Hatta dan kawan-kawan di Digul,
Papua, kemudian dipindahkan ke Bandaneira, dekat Ambon. Jika
dihitung ada sekitar 10 tahun lamanya Sjahrir hidup dalam tahanan
Belanda. Sedang Soekarno juga menghabiskan sebagian besar
waktunya dalam tahanan Belanda. Mula-mula masuk penjara
berdasarkan keputusan "Landraad" Bandung tahun 1930, kemudian ia
dibuang lagi ke Ende, lalu dipindahkan lagi ke Bengkulu. Sewaktu
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
dibebaskan karena Jepang masuk dan Belanda jatuh, Soekarno sudah
menghabiskan usianya dalam tahanan Belanda selama 10 tahun.
Antara Sjahrir dan Bung Karno yang sama-sama ditahan di Brastagi,
kemudian dipindahkan ke Prapat, terdapat beberapa kesamaan nasib
dalam berurusan dengan penjara Belanda. Kecuali ditahan untuk waktu
yang lama-sampai 10 tahun-keduanya adalah korban exorbitante
rechten Belanda, yaitu hak khusus pemerintah kolonial untuk menahan
dengan mengasingkan siapa saja yang dianggap membahayakan rust
en orde (keamanan dan ketertiban). Tentu saja "membahayakan"
menurut tafsiran yang berkuasa. Kalau hal itu dinamakan "kezaliman",
orang tak begitu keliru. Terlebih lagi jika dibandingkan dengan tahanan
biasa, exorbitante rechten, menurut Mr Moh Roem (1983), amat berat.
Sebab, korban exorbitante rechten tidak pernah diberitahu berapa lama
ia akan ditahan dan juga tidak tahu tuduhan yang dikenakan
kepadanya, atau jika pun tahu terasa sekali mengada-ada. Tetapi,
kalau tahanan biasa, bisa mengetahui apa yang dituduhkan kepadanya.
Begitu pula perkaranya akan diperiksa secara terbuka di depan
pengadilan dan ia dapat membela diri atau dibela oleh pengacara. Jika
ia dijatuhi hukuman, ia diberitahu berapa lama vonis hukumannya.
Apa pun namanya, hukuman yang diterima Bung Karno dan Sjahrir
amat mempengaruhi perjalanan hidupnya, dan dengan demikian juga
sejarah bangsanya. Keduanya juga pernah ditahan di akhir hayatnya.
Sjahrir ditahan oleh Soekarno dan tidak sempat menikmati
pembebasan karena dalam masa tahanan ia meninggal dunia di tempat
pengobatannya di Zurich. Soekarno ditawan oleh Soeharto dan sampai
meninggalnya ia juga tak pernah mengalami pembebasan. Namun,
belum pernah terjadi sebelumnya Sjahrir dan Soekarno hidup begitu
dekat kecuali pada masa ini. Mereka tinggal bertiga dengan Haji Agus
Salim dalam satu kamar.
Sjahrir pendiam dan suka marah kalau ketenangannya merasa terusik,
sementara Soekarno adalah pribadi yang ceria suka "membunuh"
waktunya dengan menyanyi atau apa saja yang disukainya. Ketika
mereka dibolehkan pengawal memesan kebutuhan yang diperlukan,
Sjahrir minta dibawakan buku-bukunya, tetapi Soekarno minta
dibawakan kemeja "Arrow". Sekali waktu Bung Karno pernah
mengatakan, "saya tak keberatan menjadi tawanan Belanda karena
ada tujuh cermin di kamar saya...." Sjahrir dibuat jengkel dengan sikap-
sikap Bung Karno yang dianggapnya a bloody old fool atau dengan
umpatan serapah yang tak mengenakkan. Tetapi, inilah klimaksnya.
Bung Karno kalau lagi mandi suka nyanyi. Sekali waktu Bung Karno
menyanyi di kamar mandi dengan suara cukup keras dan bagi Sjahrir
dirasakannya membuat ribut, hingga Sjahrir berteriak (dalam bahasa
Belanda): houd je mond (tutup mulutmu). Soekarno terdiam dan jengkel
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
juga sama Sjahrir. Ketika suatu kali Moh Roem menanyakan kepada
Soekarno mengapa ia benci pada Sjahrir, ia mengatakan,
"Bagaimanapun juga saya adalah Kepala Negara, mengapa dia
menghardik saya seperti itu?"
Dalam kasus lain, sewaktu PM Belanda Willem Drees datang ke
Indonesia, Sjahrir diminta datang ke Jakarta untuk bertemu dengan
Drees. Sjahrir bersedia datang ke Jakarta, tetapi ia tidak kembali lagi ke
Prapat karena sudah dibebaskan Belanda, dengan maksud untuk
memanfaatkannya sebagai "perantara" dalam rencana perundingan
baru, Roem-Roijen. Kejadian ini membuat Bung Karno tambah marah.
"Mengapa ia tidak kembali ke sini" (Prapat). "Kalau begitu ia tidak
setia," sambungnya lagi seperti diceritakannya kepada Haji Agus Salim.
Sepeninggal Sjahrir, di Prapat hanya tinggal dua tawanan, Bung Karno
dan HA Salim. Sejak Februari 1949, keduanya digabungkan dengan
tawanan Republik di Manumbing, Bangka. Tetapi, karena Bung Karno
tidak tahan hawa dingin, ia minta dipindahkan ke Mentok, yang
berhawa panas. Karena beliau tidak mau tinggal di sana sendirian,
maka ditunjuk beberapa orang untuk menemani Bung Karno di sana.
Antara lain H Agus Salim, Mr Moh Roem, dan Ali Sastroamidjojo. Sejak
itu tawanan jadi dua kelompok: Kelompok Manumbing di bawah
pimpinan Bung Hatta dan Kelompok Muntok di bawah pimpinan Bung
Karno.
Ketika prakarsa persetujuan Roem-Roijen dimulai bulan April 1949,
Sjahrir yang sudah dibebaskan, atas saran Hatta, diangkat sebagai
penasihat delegasi perunding Indonesia ke Roem-Roijen. Mulanya
Sjahrir menolak karena mempertanyakan tanda tangan Soekarno
dalam surat keputusan itu. "Apa dia itu? Mengapa dia yang harus
mengangkat saya? Orang yang seharusnya mengangkat saya ialah Mr
Sjafruddin Prawiranegara", (Ketua PDRI di Sumatera). Roem kesal,
tetapi lebih kesal lagi dan marah ialah Bung Karno setelah mendengar
itu.
Pengalaman yang kurang menyenangkan selama dalam masa
tahanan, dan kekecewaan dirinya dan orang-orang yang setia
kepadanya pada saat memilih ditawan Belanda dan bukan bergerilya,
saat kejatuhan Yogya, agaknya merupakan bagian terburuk dalam
memori sejarah pribadi Bung Karno, dan sekaligus penyebab utama
mengapa ia terkesan melupakan sejarah episode PDRI. Baginya,
episode ini seakan-akan eine vergangheit die nicht vergehen will,
sebuah pengalaman masa lalu yang ingin-tapi tak bisa dilupakan-dalam
ingatan kolektif, sebagaimana tercermin dalam otobiografinya yang
ditulis oleh Cindy Adam. Lagi pula, setelah kembali ke Yoyga dan
dalam perundingan-perundingan selanjutnya, bukan Bung Karno, tetapi
Hatta-lah sebagai Perdana Menteri yang menjadi nakhoda Republik
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
hingga pengakuan kedaulatan di pengujung 1949.
PDRI, ujian pertama integrasi bangsa
Pada detik-detik terakhir yang menegangkan sebelum pemimpin
puncak Republik ditawan Belanda, Hatta masih sempat mendiktekan
pidato singkatnya untuk diedarkan ke seluruh wilayah Republik. "Musuh
mau mengepung pemerintah, tetapi Republik tidak tergantung pada
nasibnja orang2 jang mendjadi kepala-negara atau jang duduk dalam
pemerintahan.... Rakjat harus berdjoang terus...." Memang, Republik
tidak hanya punya Soekarno-Hatta, tetapi juga sederetan nama besar
lainnya. Salah seorang yang paling diremehkan agaknya ialah Sri
Sultan Hamengku Buwono IX. Selama tahun-tahun krisis 1948-1950
sesungguhnya dialah tokoh yang memegang kendali dalam mengurusi
intern di bidang militer, ekonomi dan politik di belakang layar. Sjafruddin
Prawiranegara berada jauh dalam hutan di Sumatera, sedangkan
Soekarno-Hatta dalam kerangkeng Belanda di Bangka. Apa jadinya
Republik kalau tidak ada Sri Sultan? Otoritasnya sebagai ahli waris
takhta Yogya tak tersentuh oleh tangan kekuasaan Belanda. Sebagai
Republiekan sejati ia tak hanya menyerahkan takhtanya untuk rakyat,
tetapi berbuat banyak untuk Republik. Tidak hanya menjembatani kubu
PDRI dan Bangka, tetapi juga melindungi kepentingan Republik di
Yogya. Sesungguhnya dialah arsitek utama dalam serangan balik
Republik terhadap kedudukan Belanda di Yogya, yang dikomandoi oleh
Letkol Soeharto pada awal Maret 1949. Dia jugalah yang membiayai
semua keperluan Republik ketika "kembali ke Yogya". Sekitar 6 juta
gulden kekayaan Kraton Yogya diserahkan untuk menghidupi dapur
Republik.
Maka Belanda keliru besar, ketika Yogya jatuh ke tangannya
menyimpulkan bahwa Republik telah dirobohkan. Mereka lupa atau tak
mau peduli bahwa Republik yang diproklamasikan sejak 17 Agustus
1945 itu, telah tercerahkan (enlightened) oleh cita-cita kebangsaan
sejak awal abad lalu. Ia bukanlah sebuah kerajaan, juga bukan hadiah
Jepang, sebagaimana yang ada dalam benak kaum kolonialis Belanda,
melainkan sebuah "negara-bangsa" yang modern yang telah
dipersiapkan sedemikian rupa. Pembukaan UUD '45 dan bangunan
konstitusi itu sendiri, sesungguhnya adalah blue-print dari Republik
yang baru itu, dan keduanya disusun oleh para "bapak bangsa" dengan
penuh kesadaran dan kecerdasan sebuah generasi yang tak ada
duanya. Ketika pimpinan puncak Republik ditawan Belanda, PDRI di
Sumatera mampu memerankan dirinya sebagai faktor integratif, yang
menjadi pusat jaringan perjuangan Republik via India ke dunia
internasional dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX di ibu kota Yogya
dan Jenderal Soedirman di medan gerilya.
Maka, pada masa perjuangan kemerdekaan, khususnya era PDRI, teori
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...Krisis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Masa Krisis PDRI -- Jumat, 1 Juni 2001
politik klasik kolonial tak berlaku lagi, yang selalu percaya bahwa jika
raja atau pemimpin ditawan atau dibujuk, semua akan beres, bisa
ditundukkan. Nyatanya tidak demikian, dan Belanda sempat dibuat
shock karena kemenangan militernya hanya sebuah kemenangan yang
sia-sia.
Sesungguhnya inilah periode di mana proses integrasi nasional
menunjukkan hasil, ketika panggung sejarah beralih dari kota ke desa-
desa dan hutan-hutan, ketika rakyat tidak lagi sekadar pelengkap
penderita, melainkan tokoh sentral di panggung sejarah bangsa. Baik
PDRI maupun militer tidak bisa hidup kalau bukan disubsidi nasibnya
oleh rakyat, tetapi mengapa sekarang semuanya seakan-akan
dilupakan?
Memang wacana sejarah bangsa kita, seperti dikatakan sejarawan
Taufik Abdullah, adalah soal pilihan: ada bagian yang ingin dilupakan
dan yang ingin diingat dan bahkan dipalsukan. Pilihan yang semena-
mena terhadap sejarah bangsa bisa menyesatkan selama kriterianya
ialah like and dislike yang berkuasa. Terserahlah kalau itu sejarah
pribadi. Sejarah PDRI seperti juga biografi Soekarno adalah bagian dari
sejarah bangsa, dan keduanya merupakan wajah kita di masa lalu
dengan segala warna-warninya.
* Mestika Zed Sejarawan, lulusan Vrije Universiteit, Amsterdam, tinggal
di Padang.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial Belanda
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%2...risis%20PDRI%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (10 of 11)4/3/2005 11:05:15 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno di Wilayah "Hyperreal"
Niniek L Karim
SEINGATKU
kurang lebih pukul
20.30 waktu itu
(karena keluarga
kami baru saja
selesai makan
malam yang
selalu di sekitar
pukul 20.00), hari
ketiga Bung
Karno dinyatakan
wafat. Kuangkat
telepon yang
berdering, suara
seorang teman:
"Niek, cepet
ndeloko bulan,
ono gambare
Bung Karno ning
kono! (Niek, cepat
lihatlah bulan, ada
gambarnya Bung
Karno di sana)".
Ayah yang
sedang lewat di depanku menggeleng-gelengkan kepalanya ketika
kuceritakan kata-kata teman itu, lalu masuk ke kamarnya. Ayahku
memang seorang PSI (Partai Sosialis Indonesia), walaupun tidak
pernah aktif berpartai. Penasaran aku keluar mencari bulan, namun
sampai bosan menunggu, kebetulan waktu itu bulan tetap saja
tertutup awan mendung.Esok harinya di sekolah heboh! Saling
bertanya dan mencoba meyakinkan satu sama lain tentang
munculnya gambar Bung Karno di bulan. Tidak semua mengaku
melihatnya memang, tapi hampir seluruh masyarakat Kediri yang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
Soekarnois kala itu percaya bahwa itu adalah kebenaran belaka.
"Bung Karno tidak mati, tapi moksa suatu waktu nanti akan muncul
lagi." Begitulah kepercayaan yang mereka yakini waktu itu, bahkan
mungkin sampai sekarang. Oleh karena itu, tak lama setelah
Soekarno secara resmi dinyatakan wafat, berpuluh truk yang
semuanya penuh berjejalan manusia setiap harinya menuju Desa
Mantingan, Ngawi, untuk bicara atau mendengar pesan-pesan
Soekarno melalui bantuan Mbah Suro-dukun yang menabalkan
dirinya sebagai mediator bagi orang yang ingin bicara dengan
Soekarno-lewat di depan rumah saya, yang memang letaknya di
salah satu jalan yang biasa dilewati kendaraan yang akan keluar
Kota Kediri.
Seorang teman anak saya, lahir tahun l984, l4 tahun setelah
Soekarno wafat-yang wafatnya dalam kondisi dikucilkan karena tidak
populer di mata pemerintahan waktu itu-begitu mengagumi Soekarno
sehingga waktu acara pemberian ijasah lulus SMP-nya memakai
baju ala Soekarno, juga mengoleksi buku-tulisan tentang dan oleh
Soekarno, bercita-cita menjadi seperti Soekarno. Teman anak saya
itu bukan suku Jawa, lahir dan besar di Jakarta setelah Soekarno
meninggal, saya yakin dia bukan satu-satunya pengagum cilik
Soekarno. Di rumah saya jarang sekali membicarakan Soekarno,
namun betapa terheran-herannya saya ketika anak laki-laki saya
berusia 7 tahun menyatakan dia merasa bangga memiliki telinga
yang besar:" ... seperti Bung Karno" katanya. Saya juga yakin bahwa
masih banyak lagi pengagum cilik lainnya di negeri ini.
Tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana kedudukan
Soekarno dalam persepsi pengagumnya di Indonesia. Ingin
menelaah bagaimana persepsi publik terhadap Soekarno dengan
melihat bagaimana beroperasinya faktor-faktor yang dalam telaahan
ilmu sosial mutakhir sekarang sering diistilahkan sebagai
"representasi", "simbol", "simulakra", dan lain-lain.
Dari retorika sampai mitos
Pada tahun 60-an, yang masih bisa saya kenang, setiap kali
Soekarno berpidato hampir semua jalan jadi sepi. Bahkan, tukang
becak di perempatan jalan tempat kami tinggal waktu itu, di Kediri,
Jatim, tidak mau narik, memilih bergerombol di rumah orang yang
memiliki radio-kala itu radio masih "barang mewah", tidak setiap
orang memilikinya, boro-boro televisi di Kediri belum ada yang punya-
untuk ikut mendengarkan pidato Bung Karno. Mereka, atas kemauan
sendiri, tanpa dipaksa, rela tidak dapat uang karena emoh narik,
untuk mendengarkan pidato Soekarno.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
"Kemarin aku baca Ramayana, saudara-saudara, Ramayana. Di
dalam kitab Ramayana itu disebut satu negeri, namanya Utara Kuru.
Utara Kuru, artinya lor-nya negara Kuru. Kuru artinya Kurawa.
Disebutkan di dalam kitab itu bahwa di negeri Utara Kuru tidak ada
panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu, tidak ada manis
yang terlalu, nggak ada pahit yang terlalu. Segalanya itu tenang,
tenang. Ora ono panas, ora ono adem. Tidak ada gelap, tidak ada
terang yang cemerlang. Adem tentrem mbanyu ayu sewindu lawase.
Di dalam kitab Ramayana itu sudah dikatakan, hmm negeri yang
begini tidak bisa menjadi negeri yang besar. Sebab tidak ada oh up
and down up and down. Perjuangan tidak ada"
"tapi orang-orang besar ini satu persatu tidak luput dari salah. Oleh
karena sekedar manusia biasa. Saya ulangi, siapa berani berkata
bahwa Bismark tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa
Meurabeu tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa
Gladstone tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa
Garibaldi tidak pernah bersalah? Siapa berani berkata bahwa Mao
Tse Tung tidak pernah bersalah."
(Pidato Bung Karno pada Peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW
di Istana Merdeka, 1964, dikutip dari album kaset karya Bram
Kampungan berjudul Bung Karno Milik Rakyat Indonesia. Album
Kelompok Kampungan dari Yogyakarta ini pertama kali dirilis pada
tahun l970-an, dirilis ulang tahun l999).
Bung Karno dan pidato-pidatonya selalu memukau publiknya.
Sehingga pada tahun l970-an Bram dan kelompoknya yang
kemungkinan saat itu berusia 20-an tahun, merasa patut merilis
sebuah album kaset yang berlatar reproduksi pidato Soekarno
tersebut. Asumsi yang boleh jadi mendasarinya bahwa khalayak
(musik pop) juga tertarik terhadapnya. Asumsi itu terbukti signifikan
dengan adanya rilis ulang di tahun l999. Rekaman itu diproduksi oleh
sebuah perusahaan komersial, Musica, yang tentunya soal untung-
rugi menjadi perhitungan konkret.
Seperti pidato yang sebagian dikutip di atas, Soekarno menunjukkan
penguasaannya atas retorika yang luar biasa. Bicara dari cerita
Ramayana, Utara Kuru, Kurawa, yang memang diakrabi masyarakat
di desa-desa, sampai ke pemikir-ideolog-pejuang kemerdekaan-
negarawan seperti Otto von Bismarck, Meurabeu, Gladstone,
Giuseppe Garibaldi, dan lain-lain. Didengarkan dengan tekun dan
terkagum-kagum sampai selesai pidato-pidato yang jarang kurang
dari 60 menit lamanya itu oleh publiknya, yang hampir pasti sebagian
besar tidak tahu bahkan mungkin tidak peduli apa dan siapa tokoh-
tokoh yang disebut itu semua.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno memang sebuah mitos bagi sebagian masyarakat dalam
jumlah yang tidak kecil. Maka, sebagaimana pola suatu mitos yang
cenderung diturun-temurunkan ke anak-cucu, bisa kita pahami
teman anak saya yang usia 14 tahun itu kagum berat pada
Soekarno. Bahkan, mungkin saja bisa tertera suatu jejak ingatan
dalam kesadaran kolektif pada masyarakat jauh di masa depan jika
proses turun-temurun itu terjadi secara intensif, sesuai teori tentang
arkhetype dari Carl Gustav Jung.
Dari "Belief" sampai "Hyperreality"
Pidato-pidatonya ditangkap oleh publiknya bukan lagi melalui akal,
melainkan langsung ke area belief, yang dalam The Penguin
Dictionary of Psychology diartikan sebagai penerimaan emosional
terhadap suatu proposisi, pernyataan, atau doktrin tertentu. Tidak
mengerti pun tidak apa-apa, karena pidato yang disebar-luaskan
lewat radio tadi sudah menjadi otonom sebagai "mantra" yang
menciptakan suatu hyperreal thing. Soekarno pun menjadi sebuah
sosok hyperreal, atau dalam bahasa yang sudah dikenal dari studi-
studi sebelumnya tentang Soekarno, bahwa oleh masyarakat
Indonesia di desa-desa ia dianggap "setengah manusia setengah
dewa", "titisan Wisnu", Ratu Adil dan sebagainya. Ia dianggap quasi-
nabi. Dalam autobiografinya yang ditulis oleh Cindy Adams (2000),
Soekarno bercerita bagaimana masyarakat Bali memandangnya
sebagai titisan Wisnu, Dewa Hujan. Ketika Bali dilanda kemarau
panjang, masyarakat Bali mengharap sang Presiden tersebut datang
ke Bali, karena percaya bahwa kedatangannya akan
menganugerahkan hujan. Kebetulan memang, hujan pun turun saat
kedatangannya itu. Maka makin percayalah masyarakat
pengagumnya akan kebesarannya tersebut.
Begitu kuatnya persepsi tentang kekuatan supernatural Soekarno
pada masyarakat, sehingga masyarakat Kediri heboh, setiap malam
keluar rumah menengadah ke bulan, mencari wajah Soekarno.
Beribu-ribu orang dari pelosok-pelosok Jawa Timur, bahkan ada juga
yang dari Jawa Tengah, atau pun pelosok lain di Indonesia,
berbondong-bondong ke Mbah Suro agar bisa "mendengar" pesan-
pesan atau apa pun dari Soekarno.
Kemarin, seorang teman SMA saya yang ketika itu adalah seorang
ketua GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia) mengatakan
bahwa sebagian besar para Soekarnois ini percaya bahwa suatu hari
kelak Soekarno yang moksa itu akan muncul kembali secara "riil",
dan disebutkanlah dua daerah yang salah satunya akan jadi tempat
kemunculan Soekarno. Menurut dia, hampir semua para Soekarnois
ini penuh keyakinan bahwa hal tersebut akan terjadi. Merujuk pada
lima tingkatan belief dari Gillian Bennet dalam bukunya The Tradition
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
of Belief, kategori keyakinan yang sepenuhnya (convinced belief)
adalah yang terdalam letaknya.
Diterima langsung pada area belief tanpa perlu pencernaan akal,
berkembang menjadi mitos, persepsi kekuatan supranaturalnya itu
kemudian masuk ke wilayah kehidupan praktis para pengagumnya.
Dalam psikologi, diakui bahwa belief adalah salah satu motor
penggerak perilaku manusia. Saat isi dari belief mendapat
pembuktiannya dalam kenyataan hidup sehari-hari, maka belief itu
pun menjadi penggerak utama dari tingkah laku, :"Soekarno tidak
bisa mati", dan mereka pun merasa terbuktikan hal tersebut saat
Soekarno beberapa kali terluput dari usaha pembunuhan, seperti
usaha pelemparan granat di Perguruan Cikini, terhindar dari usaha
penembakan ketika Bung Karno shalat Ied, dan tembakan seorang
pilot Angkatan Udara RI dari pesawat. Pembuktian isi belief yang
kebetulan beberapa kali terjadi itu, menciptakan "kebenaran"-nya
sendiri. "Kebenaran" yang secara subyektif dipersepsi sebagai
kenyataan, sehingga secara obyektif pun ia menghasilkan efek
praktis yang nyata. Jadilah Soekarno sebagai sosok hyperreal".
Dari mistifikasi sampai gerakan nasionalisme
Tentu saja, mistifikasi tokoh Soekarno itu berlangsung dalam sebuah
momentum sejarah yang memungkinkan semua itu terjadi. Seperti
referensi-referensi Barat-termasuk nasionalisme-yang dalam
beberapa hal menjadi "mantra". Tahun l940-an dan l950-an
merupakan sebuah fase sejarah di mana dunia menyaksikan
bangkitnya nasionalisme di berbagai belahan dunia, dari Afrika
sampai Asia, dari Mesir, India, sampai Indonesia. Dalam wacana
bangkitnya nasionalisme di berbagai negara itu, muncul nama-nama
yang pada saat berikutnya menjadi penggerak Konferensi Asia Afrika
di Bandung seperti Soekarno sendiri, Nehru, Nasser, dan lainnya.
Mereka menjadi lokomotif kemerdekaan.
Pemikir posmodernis Edward Said mengutip Thomas Hodgkin,
mengatakan, gerakan nasionalisme itu dikobarkan oleh "para nabi
dan pendeta" ("prophet and priest") yang ditulis dalam tanda petik,
untuk menunjukkan bagaimana kira-kira posisi para penggerak itu di
masyarakatnya), yang di antara mereka adalah penyair dan tukang
ramal. Mari kita simak petikan kata-katanya:
"Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di
masa pancaroba, tetaplah bersemangat elang rajawali." (Pidato 17
Agustus 1949)
"Berjuanglah, berusahalah, membanting tulang, memeras keringat,
mengulur-ngulurkan tenaga, aktif, dinamis, meraung, menggeledek,
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
mengguntur, dan selalu sungguh-sungguh, tanpa kemunafikan,
ichlas berkorban untuk cita-cita yang tinggi." (Pidato 17 Agustus
1964)
"Karena itu hai Bangsa Indonesia, janganlah kita mencari
kepeloporan mental pada orang lain. Carilah kepeloporan mental itu
pada diri sendiri. Carilah sendiri konsepsi-konsepsimu sendiri.
Freedom to be free! Freedom to be free!" (17 Agustus 1964).
Bukankah Soekarno juga sering menggunakan kekuatan-kekuatan
ucapan yang puitis seperti kutipan-kutipan di atas, yang kemudian
memberi inspirasi bagi bangsa ini tentang "menjadi Indonesia"?
Nasionalisme, marhaenisme-sebuah sintesa Soekarno atas
marxisme dengan analisisnya tentang berbagai kondisi Indonesia-
Nasakom (akronim "nasional-agama-komunis") yang kelihatannya
merupakan sebagian dari "sinkretisme Jawa"-nya, di benak orang
kebanyakan, termasuk para tukang becak yang suka mangkal di
dekat rumah saya di Kediri dulu, menjadi konsepsi
"agung" (grandeur) yang "keagungan"-nya terbangun seiring media
komunikasi yang kala itu terutama adalah radio yang
menyebarluaskannya, sehingga konsepsi-konsepsi tadi
terinternalisasi pada masyarakatnya.
Singkatnya semangat yang lebih besar, yakni semangat
"independen", semangat "anti-imperialisme", menjelma sebagai
semangat zaman itu.
Bagaimana rincian dari semangat itu harus diterjemahkan dalam
kehidupan berbangsa secara lebih rasional, atau setidaknya harus
dipahami secara lebih kritis, tidaklah terlalu dihiraukan. Yang jelas,
dalam domain yang dihuni Soekarno, di situ ia berperan sebagai
pemimpin kharismatik, politikus flamboyan, orator, pemikir,
budayawan, seniman setingkat (kuasi) nabi. Kondisi sosial-politik
saat itu, bersinergi dengan faktor kepribadiannya yang begitu kuat,
menghasilkan mitos Soekarno sebagai Ratu Adil. Penjajahan lebih
dari 300 tahun, kemiskinan yang dirasakan makin meningkat,
ketidakadilan dan kesenjangan sosial antara pribumi dan nonpribumi
(baik Belanda maupun Asia Timur Jauh) yang diciptakan oleh
pemerintah kolonial Belanda, feodalisme yang dikuatkan oleh
manipulasi kuasa kolonial, bergabung dengan kebutuhan akan
kekuatan supranatural yang dipercayai akan membebaskan
masyarakat tertindas, menjulangkan Soekarno sebagai "juru
selamat" Indonesia.
Dari "simbol" kekuatan sampai ke "battleground"
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
Tesis mengenai Soekarno yang kemudian menjadi hyperreality itu
ditakuti sebagai sebuah "simbol" kekuatan oleh kelompok yang
berkuasa pada masa berikutnya, makin terbuktikan. Kita lihat
bagaimana pada perkembangannya, tokoh ini berikut gagasan-
gagasan beserta kelompok politiknya hendak dibasmi, hendak
disingkirkan dari panggung sejarah oleh rezim politik yang
menamakan dirinya Orde Baru, persis pada wilayah yang disebut
Jean Baudrillard, seorang pemikir posmodernis lain, sebagai
"simulakra", sejenis simulasi (simulasion): tiruan yang tidak memiliki
rujukan, sesuatu yang merujuk pada sesuatu yang tak ada. Meski
tak ada rujukannya, tiruan itu memiliki efek praktis yang obyektif
terhadap tingkah laku sekelompok manusia tertentu.
Mengikuti gagasan Jean Baudrillard, dalam konteks hyperreality hal
yang "nyata" (real) dan "khayalan" (imaginary) bertaut satu sama
lain. Hasilnya adalah apa yang disebut orang pada umumnya
sebagai "kenyataan", yang pada dasarnya menurut istilah Baudrillard
hanyalah "simulakra". Pada zaman ini, kiranya lebih mudah
menerangkan dari sudut pandang tersebut, di mana sebuah simulasi
sering dianggap lebih nyata dari kenyataan itu sendiri, atau mungkin
seperti lirik lagu U2, "even better than the real thing".
Kembali ke Soekarno, bagaimana pemerintahan yang berkuasa
pada fase berikutnya berusaha menggusur dia dari wacana publik?
Dengan menjadikan wilayah simulasi itu sebagai battleground,
kancah peperangan terhadap belief tentang Proklamator RI itu.
Seperti banyak diasumsikan para peneliti dari ilmu-ilmu politik dan
sosial pada masa belakangan ini, tentang bagaimana sistematisnya
penguasa era kemudian berusaha menggunakan media massa
untuk menghancurkan citra Soekarno dan wacana atau kekuatan
yang terbentuk di masanya. Cerita mengenai kisah para jenderal
yang disayat-sayat seluruh tubuh oleh para anggota Partai Komunis
Indonesia (PKI) mengiringi babak kejatuhan Soekarno, telah menjadi
cerita "klasik" yang disebarkan media massa kala itu, yang
belakangan dilawan dengan argumen, bahwa itu semua cuma
rekayasa tentara.
Selama bertahun-tahun pada masa sesudahnya, diciptakanlah
sebuah "fiksi" sebagai sebuah imaginary, bahwa kita selalu dalam
ancaman kekuatan komunis kiri serta berbagai wacana yang
dituduhkan Orde Baru disuburkan oleh Soekarno. Bersama seluruh
wacana di sekelilingnya itulah Soekarno hendak dikubur oleh rezim
Orde Baru.
Betapapun, dinamika media massa berikut berkembangnya teknologi
media ternyata menentukan hukum bahkan perlawanannya sendiri.
Represi terhadap Soekarno, ternyata malah memberi inspirasi
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
kepada pengagumnya untuk mengidentifikasi diri mereka seperti
Soekarno yang mereka bayangkan. Tahun 1970-an, ketika rezim
Orde Baru masih jaya dan intelnya menyusup ke mana-mana, tetap
muncul album kaset Bung Karno Milik Rakyat oleh Kelompok
Kampungan yang dikutip di awal tulisan ini. Tahun 1990-an, dirilis
ulang, sebab dianggap tetap fancy. Padahal untuk khalayak musik
pop masa l970-an atau pun masa kini, perlu dipertanyakan adakah
mereka tahu Bismark, Meurabeu, Gladstone, Garibaldi, tadi?
Mungkin juga tidak, sama halnya dengan rakyat di desa-desa dan
para penarik becak di dekat rumah saya, di Kediri tahun 1960-an.
Dari "self-representation" sampai ke "Latent Envy"
Seperti dikatakan seorang tokoh media, Marshall McLuhan dan
diperkuat oleh Baudrillard bahwa representasi realitas telah
memproduksi realitas tersendiri dari yang mereka mediasikan itu.
Sejak semula, Soekarno agaknya orang yang sangat mampu dan
tahu bagaimana dia harus mempresentasikan dirinya. Bertautan
dengan dinamika media massa, pada gilirannya dia menjadi tokoh
hyperreal.
Di situ ia bisa muncul di bulan seusai wafatnya; menghasilkan
pengikut yang disebut "Soekarnois" yang boleh jadi tak paham benar
apa sebetulnya gagasan-gagasannya namun dengan sangat rela
berpanas-lapar-haus tetap khidmat mendengarkan pidato berjam-
jam tanpa ada yang tertidur. (Tidak seperti yang tampak di televisi
jika Soeharto pidato di depan para anggota DPR ataupun MPR yang
terhormat tapi banyak yang terlelap, pemandangan yang sangat
memuakkan). Banyak orang Indonesia dengan sangat bangga
meniru cara berpakaian Soekarno, bangga punya telinga besar
seperti Soekarno. Dan Soekarno pun dijadikan komoditas
kebudayaan pop ketika orang ingin menikmati sesuatu yang
meledak-ledak).
Mungkin di situlah letak simpul latent envy-iri hati laten-pada
bayangan Soekarno yang selalu menghantui Soeharto. Segala
usaha dilakukannya untuk menghilangkan kekaguman dan harapan
masyarakat terhadap Soekarno, menghilangkan bayangan Soekarno
dari impian massanya. Dari tindakan yang ringan-ringan seperti:
tempat-tempat yang menggunakan nama Soekarno digantinya,
Gunung Soekarnopura diganti dengan Jaya Wijaya, Gelora Bung
Karno diganti Gelora Senayan Jakarta, larangan membawa gambar
Soekarno dalam kampanye pemilihan umum, sampai pada
penumpasan-penumpasan fisik yang tak kalah menakjubkannya.
Dari desukarnoisme sampai kontrol ideologi
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno di Wilayah "Hyperreal" -- Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno sebagai tokoh hyperreal yang selalu menjadi hantu bagi
rezim Orde Baru dengan tokohnya Soeharto, tetap hadir dengan
kokohnya dalam benak para pengagumnya. Berbagai cara yang
dilakukan Orde Baru untuk menggusur "realitas" itu, tampak sia-sia.
Ternyata benak manusia tidak semudah itu untuk dikontrol dengan
pola tertentu.
Apa yang bisa dipelajari dari ini semua?
Usaha-usaha untuk menggusur belief yang sudah membayangi
benak seseorang, bisa-bisa malah menjadi bumerang yang justru
memantapkan dan memapankan kepercayaan itu. Inilah yang patut
dicermati oleh Indonesia dalam menjalani masa-masa yang datang.
Pemberangusan buku-buku berbau ini dan itu, pelarangan isme ini
dan itu, pemaksaan kepercayaan ini dan itu, yang merupakan usaha
kontrol belief manusia, apakah mujarab untuk niat-niat tersebut? Lagi
pula apakah itu jalan yang terbaik bagi keberlangsungan Indonesia
sebagai negara dan bangsa?
* Niniek L Karim Psikolog, dosen pada Fakultas Psikologi
Universitas Indonesia.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno%20...h%20Hyperreal%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 10)4/3/2005 11:05:16 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
M Imam Aziz
TAK berlebihan jika dikatakan kolonialisme telah melahirkan
Indonesia. Dalam pengertian demikian, Indonesia pascakolonial
selalu bergulat dengan ambiguitas yang tak terdamaikan. Bayang-
bayang antikapitalisme, anti-imperialisme sebagai ingatan kolektif
dari pahitnya kolonialisme di satu sisi dan keinginan mewujudkan
tatanan kehidupan sosial-politik berlandaskan nilai-nilai demokrasi di
sisi lain, merupakan salah satu contoh betapa rumitnya kesadaran
itu. Jika ambiguitas itu diterima "begitu saja" pada masa
prakemerdekaan, tetapi tidak mudah mengelolanya pada
pascakemerdekaan.Oleh karena itu, ironi dan tragedi justru banyak
terjadi pada pascakemerdekaan. Para penggagas nasionalisme
seperti Soekarno, Hatta dan sebagainya seolah-olah bergulat di
antara "kata" dan "fakta" politik yang dicoba dirajut untuk
memperoleh maknanya. Dan itu ternyata tidak mudah, dan tak
jarang menemui jalan buntu. Soekarno yang rajin berkata-kata,
antara lain mengenai gagasan besarnya menyatukan kaum
nasionalis, agama dan komunis (1926) menemukan kenyataan yang
sama sekali bertolak belakang, ketika ia mencobanya menjadi fakta.
Gagasan inilah yang mengantarkan Soekarno, yang semula dibalut
atribut kebesaran, pada "kematiannya". Nasib serupa menimpa pada
gagasan besarnya yang lain: marhaenisme, atau nasionalisme
marhaenistis, yang matang dikonsepsikan pada tahun 1932. Bahkan,
mungkin, pada gagasannya mengenai Pancasila. Harus segera
ditambahkan, 'nasib' itu tidak hanya milik Soekarno, tetapi juga
kawan-kawannya seperti Hatta, Sjahrir, Tan Malaka.
Orang tergoda untuk mengatakan, mereka dan gagasan mereka
hanya relevan untuk membebaskan Indonesia dari kekuasaan
kolonialisme. Setelah itu, Indonesia seolah-olah merupakan sebuah
medan pertarungan baru, yang tak pernah terpikirkan. Pada suatu
saat, di zaman Indonesia-merdeka, Soekarno bahkan pernah ingin
dilupakan. Buku-bukunya dilarang. Pikiran-pikirannya diharamkan
(secara resmi hingga saat ini). Tetapi justru karena itu, Soekarno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
menjadi penting kembali saat ini, setelah upaya melupakan
Soekarno (dan kawan-kawan) mengakibatkan krisis-demi-krisis,
yang tak kunjung usai.
Pertanyaan yang muncul, ada apa pada Soekarno? Pada pikiran-
pikirannya? Dan pada perilaku politiknya?
***
SOEKARNO, pertama-tama harus ditempatkan pada seting
pergerakan kebangsaan, yang muncul dan berkembang jauh
sebelum ia merumuskan gagasan-gagasannya dan terjun ke dunia
pergerakan. Dia bukan sang pemula. Usia Soekarno jauh di bawah
para perintis awal nasionalisme, seperti Dr Tjipto. Ketika Boedi
Oetomo dideklarasikan oleh anak-anak School tot Opleiding van
Inlandsche Arsten (Stovia) pada hari Minggu 20 Mei 1908, usia
Soekarno belum genap tujuh tahun. Ketika Boedi Oetomo resmi
berpolitik yang mengibarkan proyek pemerdekaan Tanah Air dan
keutuhan bangsa, Soekarno masih duduk di bangku Europeesche
Lagere School, ELS) sekolah menengah Belanda) di Surabaya. Ia
lahir di Blitar, Jawa Timur, dari sebuah keluarga priayi rendahan.
Kedudukan sosial ekonomi orangtuanya hanya agak sedikit lebih
baik di atas masyarakat miskin di sekitarnya. Karena itu, ia
berkesempatan meneruskan sekolah menengahnya di Surabaya.
Di sana ia tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto, yang dipanggilnya
Pak Tjok, yang usianya 21 tahun di atasnya. Ia tahu, Tjokro adalah
salah seorang pejuang nasionalisme, salah satu pendiri dan
pemimpin Sarekat Islam. "Pak Tjok adalah pujaanku. Aku muridnya",
katanya, meski belakangan ia agak kecewa, karena Tjokro dinilai
tidak mampu memberikan kehangatan langsung pribadinya kepada
pribadi Soekarno yang masih dalam pencarian. "Tak seorang pun
mencintaiku seperti yang kuidamkan". Ia merasa, Pak Tjok hanya
mengajarkan tentang "apa dan siapa dia", bukan tentang "apa yang
ia ketahui atau tentang apa jadiku kelak". Kekecewaannya semakin
bertambah ketika tokoh-tokoh yang datang ke rumah Pak Tjok pun
tak mempedulikan Soekarno. "Mahaputera-mahaputera ini
mengacuhkanku, karena aku masih kanak-kanak". Karena itu ia
memilih mengundurkan diri ke dalam "dunia pemikiran". (Kutipan-
kutipan dari Cindy Adam, Bung Karno...)
Usianya baru belasan, ketika ia tenggelam dalam bacaan buku-buku
filsafat di perpustakan milik ayahnya, seorang teosof. Aneh, jenis
yang digemari adalah jenis buku kerohanian dan "dunia yang lebih
kekal". "Aku menyelam sama sekali ke dalam dunia kebatinan ini.
Dan aku di sana bertemu dengan orang-orang besar". "Di dalam
itulah aku dapat hidup dan sedikit bergembira".
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
Di samping membaca filsafat, ia membaca pikiran-pikiran politik
Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, dan JJ
Rousseau. Juga Karl Marx, Frederick Engels, Lenin, Voltaire,
Danton. Sejauh mana pikiran tokoh-tokoh itu mempengaruhi pikiran-
pikirannya, tampak pada periode perkembangan dan
kematangannya. Paling tidak, ia mulai menuliskan pemikiran-
pemikiran dan mempublikasikan melalui media massa. Konon lebih
500 karangannya dimuat dengan nama-nama samaran: Bima,
Srihana, Abdurrahman. Mungkin karena kemajuan intelektualnya ini,
ia mulai diajak Pak Tjok mengikuti rapat-rapat partai.
Surabaya awal abad ke-20 tampaknya merupakan antitesis Jakarta.
Secara budaya ia lebih terbuka, memungkinkan berkembangnya
pikiran-pikiran kerakyatan, sebagai oposisi budaya priayi yang masih
berkembang. Masuk akal, jika Sarekat Islam (SI) yang semula lahir
sebagai organisasi pedagang di Surakarta, gairahnya lebih tersedot
ke Surabaya.
SI lalu berkembang di Surabaya, di tangan Tjokroaminoto yang
sangat antidiskriminasi. Soekarno berkembang dari situasi yang
sangat dekat dengan sehari-harinya di Surabaya bersama Tjokro.
Bukan kebetulan kalau pemikiran kedua orang itu bercorak
sosialistis. Tetapi berbeda dengan sosialisme Tjokro yang diinspirasi
Islam, Soekarno-mungkin karena bacaan-bacaannya-lebih
cenderung ke sosialisme Marxian. Tetapi karena kurang
memperoleh pendidikan sistematis mengenai pemikiran "sosialisme",
ia kelak tampil menjadi pemikir sosialis eklektik.
Akan tetapi soal eklektikisme ini bukan hanya milik Soekarno, tetapi
milik hampir semua perintis nasionalisme sebelum perang. Dari
sekian orang Indonesia yang mengaku dirinya Marxis, relatif sedikit
saja yang benar-benar mempelajari dan mengadopsi dasar filosofis
teori Marxis. Hanya sedikit di antara mereka yang sungguh-sungguh
pernah berlindung langsung dari tulisan Karl Marx. (Mintz, 7)
Tak diragukan, pembentuk utama corak sosialisme dan nasionalisme
Soekarno adalah situasi penjajahan itu sendiri. Pahitnya
didiskriminasi, kemiskinan rakyat terjajah, itulah yang
menggumpalkan sikap-sikapnya yang jelas-jelas memihak rakyat.
Marxisme dan sosialisme, mendapat sambutan karena ada
penjelasan dan deskripsi tentang kolonialisme. Bagi umumnya
nasionalis Indonesia yang memang membaca karya Marx,
karakterisasinya tentang kolonialisme Eropa sebagai "suatu
perampokan, perbudakan dan pembunuhan terselubung" mendapat
perhatian besar, sama seperti definisi Marxis-Leninis tentang
imperialisme.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
Pada Soekarno, gagasan marxisme dan sosialisme telah
menggumpal di dalam dirinya dalam tiga tema: anti-elitisme, anti-
imperialisme dan antikolonialisme. Anti-elitisme Soekarno terlihat
pada kritiknya yang tajam terhadap ideologi priayi yang masih kental
di tubuh Boedi Oetomo. "Para intelektual harus memikirkan nasib
rakyat", katanya. Kelak tiga tema pemikirannya, dirumuskan kembali
secara cemerlang dalam "Nasionalisme Marhaenistis". Soekarno
semakin jelas berpaham nasionalisme primordial. Soedjatmoko
menyebutnya nasionalisme Jacobin.
***
SURABAYA menggoreskan bekas yang mendalam, mungkin juga
kegalauan di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya ia menyaksikan
sebuah degup pergerakan kebangsaan, yang digerakkan oleh aliran-
aliran utama Islam dan komunisme. Pengalaman ini kelak sangat
mempengaruhi pemikirannya. Pada periode tahun 1916-1921,
Sarekat Islam yang mencapai tahap kematangannya, sangat bersifat
inklusif, mewadahi berbagai pandangan politik, dari pan-Islamis
konservatif, hingga marxisme radikal. SI pernah membuktikan bahwa
gerakan ini mampu mengatasi keanekaragaman isme-isme. Pada
saatnya, pemimpin SI, Tjokroaminoto-pria kelahiran Madiun itu-
mampu memobilisasi kesadaran rakyat, yang terdiri kaum miskin
yang terjajah, hingga ia dianggap penjelmaan Ratu Adil. Karena
sikap pribadinya yang menentang diskriminasi yang dilakukan
pemerintah kolonial, ia juga sering disebut "Gatutkoco Sarekat
Islam". (Noer, 122)
Ia berhasil mengantar SI sebagai partai politik terbesar pertama yang
mampu menarik massa ratusan ribu anggota yang penuh semangat.
Ketika pada tahun 1921 Soekarno meninggalkan Kota Surabaya
yang dijulukinya "dapur nasionalisme" itu, di dalam tubuh SI telah
terbelah menjadi dua, setelah sebelumnya terjadi pergumulan yang
sangat keras, antara kaum Islam yang dibakar semangat pan-
Islamisme seperti Moeis dan Salim, dengan kaum Marxis yang
terobsesi dengan kemenangan Jepang atas Rusia. Semaun adalah
salah satunya. Semula tarikan Semaun tampaknya berpengaruh
dalam SI.
Pada kongres ketiga, tahun 1918 di Surabaya, SI menyepakati
"pemogokan buruh yang teratur untuk memperbaiki nasib, mencari
keadilan dan melawan perbuatan sewenang-wenang... (dan) akan
memajukan ikhtiar kaum buruh buat memperbaiki nasib, mencari
keadilan dan melawan perbuatan sewenang-wenang itu". Partai
bahkan akan membantu pemogokan-pemogokan itu. Pada kongres
tahun berikutnya, ditegaskan lebih rinci mengenai tata cara mogok.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
Tidak hanya itu, pemimpin-pemimpin Sarekat Islam juga bergabung
pada serikat-serikat kerja yang ada untuk memberikan dukungannya.
Tjokroaminoto, Moeis, Salim kemudian juga memberikan bantuan
dalam kepemimpinan pergerakan buruh. (Noer, 135)
Akan tetapi pada bulan Mei 1920, sayap kiri SI membentuk partainya
sendiri, yaitu Partai Komunis Indonesia. Anggota-anggotanya
dibiarkan memiliki keanggotaan ganda di PKI dan di SI, dengan
tujuan mengontrol SI dari dalam. Sebelum berdirinya PKI, para
pemimpin komunis membentuk serikat-serikat kerja di cabang-
cabang SI. Sehingga PKI mampu membangun pengikut-pengikut
yang substansial, terutama lewat serikat-serikat kerja. PKI
mengorganisasi kaum buruh untuk melakukan pemogokan, dan
menggiring mereka menuju konfrontasi dengan Pemerintah Hindia
Belanda. Sementara itu, SI sendiri semakin menekankan watak
Islamnya.
Di bawah arahan Agus Salim, dalam Kongres SI pada tahun 1921 di
Surabaya, SI melarang anggotanya menjadi anggota partai politik
lain, sebagai usaha untuk melindungi watak Islamnya. Tjokroaminoto
sendiri masih di tahanan ketika kongres berlangsung. Menurut Salim,
penetrasi dasar-dasar bukan Islam yang selama ini masuk dalam
lingkungan partai, telah melemahkan partai. "(Kita) tidak perlu
mencari isme-isme lain yang akan mengobati penyakit pergerakan.
Obatnya ada di dalam asasnya sendiri, asas yang lama dan kekal,
yang tidak dapat dimubahkan orang, sungguhpun sedunia memusuhi
dengan permusuhan. Asas itu ialah Islam". Kebijakan ini membuat SI
merosot sebagai suatu kekuatan politik. SI bahkan tidak saja
kehilangan sayapnya yang radikal, bahkan sayap kanan Islamis,
satu demi satu meninggalkan SI.
Organisasi Muslim berdiri bernama Nahdlatul Ulama pada tahun
1926 di Surabaya, melengkapi Muhammadiyah yang berdiri 15 tahun
sebelumnya di Yogyakarta. Tokoh-tokoh kedua organisasi ini,
semula pendukung kuat Sarekat Islam.
Bandung segera menjadi daya tarik baru bagi Soekarno yang selalu
gelisah itu.
Ia menamatkan Technische Hoge School (THS) dan dilantik menjadi
insinyur pada 25 Mei 1926. Di sini ia bertemu dengan tokoh Islam
modernis dari Persatuan Islam, A Hassan.
Di sini pula, konon, ia bertemu dengan petani kecil bernama
Marhaen yang kelak dijadikan ikon 'ajaran-ajaran' populis-nya. Ia
terjun ke dunia politik secara total, pertama dengan ikut mendirikan
Algemene Studie Club Bandung, tahun 1926, dan setahun kemudian
mendirikan Partai Nasional Indonesia.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
Pemikiran nasionalisme Soekarno tampak lebih menemukan
bentuknya. Menurut Soekarno, "nasionalisme Indonesia merupakan
nasionalisme ke-Timur-an, dan sekali-kali bukan nasionalisme ke-
Barat-an", bahwa istilah itu tidak ada hubungannya dengan
chauvinisme ataupun dengan "nasionalisme yang serang
menyerang". Mengenai marhaeinisme nasionalistis, Soekarno
mengatakan "banyak di antara kaum nasionalis Indonesia yang
berangan-angan: "Jempol sekali jikalau negeri kita bisa seperti
negeri Jepang atau negeri Amerika atau negeri Inggris! Armadanya
ditakuti dunia, kotanya haibat-haibat, bank-banknya meliputi dunia,
benderanya kelihatan di mana-mana! ... Kaum nasionalis yang
demikian itu lupa, bahwa barang-barang yang haibat itu adalah hasil
kapitalisme, dan bahwa kaum Marhaen di negeri ini adalah
tertindas... Mereka hanyalah ingin Indonesia-Merdeka sahaja
sebagai maksud yang penghabisan".
(Di Bawah Bendera Revolusi)
Pergulatannya yang tak selalu manis dengan isme-isme, tak
membuatnya kehilangan optimismenya untuk mempersatukan
gerakan-gerakan kebangsaan. Perpecahan dalam tubuh SI mungkin
membuatnya berpikir keras untuk mencari jalan mempersatukan dua
ideologi yang saling bertentangan itu. Pada Majalah Indonesia Muda
edisi pertama, kedua dan ketiga, yang diterbitkan ASC, Soekarno
menulis Nasionalisme, Islam dan Marxisme, suatu uraian yang
paling jelas tentang pokok-pokok pikiran Soekarno, bahwa gerakan-
gerakan Islam, Marxis dan Nasionalis di Indonesia berasal dari suatu
dasar yang sama, yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan
kapitalisme dan imperialisme. Soekarno, jelas sekali mengimbau tiga
kekuatan ideologi politik itu harus bersatu dalam menghadapi musuh
bersama.
Mungkin saja merupakan suatu kebetulan, tulisan Soekarno itu terbit
bersamaan dengan aksi faksi revolusioner dalam PKI yang
melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial di Jawa
Barat, pada November 1926. Eksperimen pemberontakan yang
tampaknya tidak direncanakan dengan baik itu, berakhir menjadi
petaka bagi PKI. Untuk pertama kalinya, PKI dinyatakan sebagai
partai terlarang. Pemimpin-pemimpinnya ditangkap dan ribuan
anggotanya dipenjarakan atau dibuang ke Digul. Mungkin saja,
Soekarno tahu PKI ternyata tidak memiliki organisasi dan kekuatan
yang cukup untuk melaksanakan rencananya secara baik. Tetapi,
sejauh ini ia tak bereaksi negatif atas peristiwa ini.
Sikap Soekarno ini sama dengan sikap Hatta, yang memimpin
Perhimpunan Indonesia di Belanda, juga tidak bereaksi negatif atas
radikalisme PKI itu. Bahkan Hatta marah, ketika alumni PI di
Bandung-yang merancang membuat partai baru-menolak orang PKI
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
untuk menjadi anggotanya, dengan alasan Pemerintah Belanda
sedang melancarkan tekanan-tekanan keras kepada PKI. Ada
kemungkinan, tekanan itu juga akan dilancarkan kepada organisasi-
organisasi yang menerima PKI sebagai anggota. Pada 2 Juni 1926,
Hatta menulis surat kepada Sudjadi,
"Kami yang ada di sini (di Belanda) ... sedang berusaha membentuk
suatu blok nasionalis yang berintikan kaum nasionalis radikal yang
kuat, termasuk orang komunis. Kerja sama dengan orang komunis
tidak ada bahayanya; malahan sebaliknya, asal kita tidak
melengahkan dasar-dasar ideologi kita sendiri, akan bertambah kuat
membentuk blok nasionalis". (Ingleson, 17)
Bagi Hatta, kerja sama itu mudah karena kaum komunis mempunyai
tujuan yang sama, yakni Kemerdekaan Indonesia. "Saya melihat,
bahwa orang komunis Indonesia sebenarnya orang nasionalis yang
tersembunyi", tulis Hatta. Sejauh mereka mengikuti pola perjuangan
kelas seperti teman-temannya di Eropa, maka, kata Hatta, mereka
sama dengan kita. "Apakah mereka kelak akan tetap menjadi
komunis setelah kemerdekaan nanti, marilah kita tunggu". (Ibid, 18)
***
SEPERTI umumnya pemimpin revolusi sezamannya, Soekarno
mengorganisasikan pikirannya dengan lebih dahulu belajar
"menamai" dunianya. Bagi Soekarno sama sekali bukan imajiner,
ketika ia menamai dunianya dengan 'Indonesia', sebagai kulminasi
terbaik yang diangan-angankan oleh orang mengenai Tanah Air
selama masa kolonial. Ia mengenal lebih dari batas-batas tanah
kelahirannya, Jawa. Ia bertemu dengan kaum muda dari Sumatera,
Minahasa, Makassar. Apalagi ia pernah mengalami pembuangan di
Bangka, dan Ende. Pasti pula ia mendengar cerita mengenai Digoel,
tempat pembuangan Hatta dan Sjahrir. Begitu pula, ketika ia
menamai gagasannya dengan Marhaenisme, yang, katanya,
marxisme yang dipraktikkan di Indonesia. Bentuk 'terapan' marxisme
ini adalah program yang kandungannya ingin diwujudkan melalui
koalisi faksi nasionalis, agama dan komunis. Ia memastikan
posisinya dalam tiga kekuatan itu, dengan segala pertaruhannya.
Akan banyak harimau mati karena belangnya. Dan Soekarno mati
karena gagasannya. Era pascakolonial, Soekarno tetap berpegang
pada gagasan yang dikembangkan di Bandung, yang ingin
mempersatukan isme-isme besar: nasionalisme, Islam, dan
komunisme. Untuk yang kedua kalinya, ia menyaksikan Partai
Komunis Indonesia yang dituduh melawan pemerintah, pemimpin-
pemimpinnya ditangkap dan ribuan anggotanya dipenjarakan,
dibunuh atau dibuang. Soekarno di-impeach karena dianggap tidak
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
bisa mempertanggungjawabkan gagasannya.
Sejak semula, Soekarno menggagas nasionalisme yang
primordialistis. Ia mengidentifikasi Indonesia-nya sebagai
keniscayaan dari proses historis yang panjang. "Indonesia" bukan
identitas yang baru. Kolonialisme-lah yang mengubur identitas itu.
Nasionalisme mengemban tugas mengartikulasikan identitas itu
kembali. Corak pemikiran itu kurang menyadari ancaman
tersembunyi dari watak yang melekat pada "negara", betapapun
negara itu dianggap antitesis negara kolonial.
Perjalanan Soekarno selanjutnya diwarnai kegamangannya melihat
rumitnya kenyataan negara yang impersonal, tanpa hati, dan begitu
mudahnya menjadi alat kaum elite memaksakan kepentingan
ekonomi-politiknya. Soekarno, karena lebih berpikir mengenai
"bangsa" (nation building) ketimbang soal state. Padahal guru Marx
wanti-wanti sejak lama soal yang satu ini.
Maka, begitu proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, negara
baru lahir, Soekarno yang didaulat menjadi presidennya, terhenyak
dari dua sisi. Pada sisi pertama, ia melihat Belanda sama sekali tidak
mau kehilangan bekas jajahan mereka begitu saja. Dengan segala
upaya, ia menguasai kembali kota-kota utama, dan berusaha
memecah-belah perlawanan dengan membentuk negara-negara
kecil, suatu negara federal terdiri dari enam negara dan sembilan
daerah istimewa. Tidak hanya itu, Belanda pun masih menguasai
ekonomi Indonesia hingga tahun 1954. Sembilan puluh persen
modal yang ditanam dalam usaha perkebunan adalah modal
Belanda.
Di tengah situasi itu, Soekarno mendapatkan kenyataan pahit lain.
Kawan-kawannya sesama perintis pembebasan, membangkitkan
pemberontakan-pemberontakan lokal dengan menolak tunduk
kepada pemerintah pusat. Kartosuwiryo mendirikan negara Islam
"Darul Islam", Kahar Muzakkar mengupayakan hal yang sama di
tanah Bugis, Daud Beureuh memimpin gerakan otonomi, juga
mengikuti Kartosuwiryo.
Himpitan-himpitan itu membuat Soekarno secara internasional
berada di kubu "anti-imperialis". Ia mengundang negara-negara Asia-
Afrika menyelenggarakan konferensi besar di Bandung (1955). Di
dalam negeri, ia mengubah politiknya tampak secara drastis hanya
mengandalkan dukungan unsur-unsur radikal, menghapus sistem
parlementer dan terutama menasionalisasi sebagian besar kekayaan
asing. Ia, terutama, melihat kelompok militer-yang tak pernah ia
perhitungkan-mengingini sistem politik yang lebih pro-Barat. Sistem
pemerintahan yang baru itu menempatkan dirinya sebagai pusat
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
kekuasaan. Dan sejarah berikutnya menyaksikan pertarungan antara
Soekarno yang nasionalistik dan militer yang pro-Barat. Pertarungan
dimenangkan militer.
Ketika seratus tahun yang lalu, sedikit anak bangsa menggeliat
menggagas identitas nasional mereka, mungkin tak terbayangkan
krisis demi krisis akan menimpa bangsa ini. Justru ketika
kemerdekaan politik diraih. Hak menentukan nasib sendiri terpenuhi.
Bentang Tanah Air "bak untaian zamrud" telah bersatu di bawah
satuan administrasi bernama Republik Indonesia. Lengkap dengan
Merah Putih, burung garuda dan lagu kebangsaan yang penuh
semangat.
Apa lagi yang tersisa dari 'imajinasi' para perintis nasionalisme di
awal abad yang lalu? Tepat di sini kita memperingati 100 tahun hari
jadi Soekarno, salah seorang penggagas nasionalisme, sekaligus
yang 'ditakdirkan' menjadi pelaksana gagasan-gagasannya sendiri.
Akan tetapi, kini kita menyaksikan sebuah bangsa yang letih. Orang
ragu pada penyelesaian krisis, karena sejarah pertarungan politik
saat ini ternyata masih berputar pada sumbu yang sama.
* M Imam Aziz Sekarang dosen di Institut Agama Islam Negeri
Sunan Kalijaga, Yogyakarta.Bahan Bacaan:Abdullah, Taufik, et. al.
Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta: LP3ES, 1988)
Adam, Cindy, Bung Karno Penjambung Lidah Rakjat, terjemahan
(Jakarta: Gunung Agung, tt.)
Aziz, M. Imam dan Iip Zulkifli Yahya, Soekarno-Islam Pertemuan
Marhaen dan Santri, Majalah Basis, Maret-April 2001.
Hobsbauwm, E.J., Nasionalisme Menjelang Abad XXI (Yogyakarta:
Tiara Wacana, 1992
Ingleson, John, Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis
Indonesia Tahun 1927-1934 (Jakarta: LP3ES, 1988)
Mintz, Jeanne S., Mohammed, Marx and Marhaen, the Roots of
Indonesian Socialism (New York: Frederik A Praeger Publisher)
Muljana, Slamet. Prof Dr, Kesadaran Nasional (Jakarta: Yayasan
Idayu, 1966)
Noer, Deliar, Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942
(Jakarta: LP3ES, 1996)
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih -- Jumat, 1 Juni 2001
Pringgodigdo, A.K, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia (Jakarta:
Dian Rakyat, 1986)
Soedjatmoko, Etika Pembebasan, (Jakarta: LP3ES, 1996)
Sukarno, Indonesia Menggugat
Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
● Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa
Awal Kemerdekaan
● Ziarah Kubur Bung Karno
● Soekarno di Masa Krisis PDRI
● Dunia MenurutSang Putra Fajar
● Bung Karno di Bawah Bendera Jepang
● Bung Karno, Seni, dan Saya
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%2...lisme%20Letih%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (10 of 11)4/3/2005 11:05:17 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan
Orde Baru
Vedi R Hadiz
DENGAN Dekrit 5 Juli 1959, Soekarno membubarkan Konstituante
yang bertugas merancang UUD baru bagi Indonesia, serta memulai
periode yang dalam sejarah politik kita disebut sebagai "Demokrasi
Terpimpin". Peristiwa ini sangat penting, bukan saja karena
menandai berakhirnya eksperimen bangsa Indonesia dengan sistem
demokrasi yang liberal, tetapi juga tindakan Soekarno tersebut
memberikan landasan awal bagi sistem politik yang justru kemudian
dibangun dan dikembangkan pada masa Orde Baru. Tapi bukankah
Soekarno amat berbeda dari Soeharto, pendiri Orde Baru yang
menggantikannya lewat serangkaian manuver politik sejak tahun
1965 yang hingga kini masih banyak diselimuti misteri?Tentu banyak
perbedaan antara Soekarno dan Soeharto yang amat gamblang.
Presiden pertama RI dikenal sebagai orator yang ulung, yang dapat
berpidato secara amat berapi-api tentang revolusi nasional,
neokolonialisme dan imperialisme. Ia juga amat percaya pada
kekuatan massa, kekuatan rakyat.
Presiden kedua RI sama sekali bukan orator, jauh lebih tertutup,
serta dikenal sebagai orang yang-meskipun pemerintahannya penuh
dengan kasus kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)-memimpin
proses bergabung kembalinya Indonesia dengan sistem kapitalisme
internasional, setelah sempat hendak diputus oleh pendahulunya. Ia
juga terkesan curiga dengan kekuatan rakyat: kebijaksanaan "massa
mengambang" Orde Baru didasari premis bahwa rakyat harus
dipisahkan dari politik.
Namun, di balik kesan kuat adanya keterputusan antara "Orde
Lama" dan "Orde Baru", terdapat pula beberapa kontinuitas yang
cukup penting. Pertama, dua-duanya sangat anti terhadap hal-hal
yang dapat menyebabkan disintegrasi teritorial Indonesia, dua-
duanya dapat dikatakan sangat "nasionalis" dalam hal itu. Dengan
demikian, baik Soekarno maupun Soeharto amat mementingkan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (1 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
retorika "persatuan" dan "kesatuan". Bahkan, sejak 1956, Soekarno
sudah menuduh partai politik di Indonesia pada waktu itu sebagai
biang keladi terpecah-belahnya bangsa, dan sempat mengajak
rakyat untuk "mengubur" partai-partai tersebut dalam sebuah pidato
yang amat terkenal.
Dengan mengubur partai politik, Soekarno menganggap bahwa
bangsa Indonesia dapat kembali kepada "rel" revolusi yang sejati
dengan semangat persatuan. Soeharto bahkan dikenal lebih
antipartai politik, dengan merekayasa sebuah sistem yang pada
dasarnya didominasi oleh satu "partai negara", yakni Golkar, dan dua
partai "pajangan". Sebenarnya, didirikannya satu "partai negara"
atau "pelopor" adalah ide yang juga lama digandrungi oleh
Soekarno, walau keinginannya tidak pernah menjadi kenyataan di
masa kekuasaannya.
***
SEPERTI Soekarno, Soeharto juga beranggapan bahwa sistem
politik yang didukungnya adalah yang paling "cocok" dengan
"kepribadian" dan "budaya" khas bangsa Indonesia yang konon
mementingkan kerja sama, gotong-royong, dan keselarasan. Dalam
retorika, keduanya mengecam "individualisme" yang katanya lahir
dari liberalisme Barat. Individualisme itu melahirkan egoisme, dan ini
terutama dicerminkan oleh pertarungan antar-partai.
Pada akhirnya, tidaklah terlalu sulit untuk menemukan banyak
kontinuitas antara "Demokrasi Terpimpin"-nya Soekarno dan
"Demokrasi Pancasila"-nya Soeharto, dengan perbedaan bahwa
Soekarno mementingkan politik mobilisasi massa, sedangkan
Soeharto justru sebaliknya. Perbedaan kedua adalah simpati
Soekarno pada gerakan-gerakan anti-imperialisme, dan mungkin
sebagai salah satu konsekuensi, penerimaannya pada Partai
Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor politik yang sah. Soeharto
sendiri menjalankan pembangunan bercorak kapitalis, termasuk
dengan merangkul kekuatan-kekuatan kapitalisme terdepan di dunia,
dan justru telah menutup arena politik untuk kekuatan komunisme.
Tapi dua-duanya, dengan caranya masing-masing, mencanangkan
sistem politik yang berwatak anti-liberal dan curiga pada pluralisme
politik. Dua-duanya mementingkan "persatuan"-yang satu demi
"revolusi" dan yang lainnya demi "pembangunan".
Boleh dikatakan bahwa Orde Lama serta Demokrasi Terpimpin telah
pave the way, membuka jalan, bagi Orde Baru dan "Demokrasi
Pancasila" versi Soeharto. Tidak mengherankan bahwa Soekarno
telah mengawali Demokrasi Terpimpinnya dengan kembali pada
Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Soeharto, di masa
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (2 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
kekuasaannya, selalu bersikeras tentang sifat "sakral" konstitusi,
yang tidak boleh diamandemen.
Sikap menomorsatukan UUD 1945 bukanlah hanya mencerminkan
masalah ideologis atau filosofis yang abstrak, tetapi masalah
kekuasaan yang konkret. Baik Soekarno maupun Soeharto amat
mengerti bahwa UUD '45 memusatkan kekuasaan pada lembaga
kepresidenan, suatu hal yang hari ini justru menjadi masalah dengan
adanya tarik-menarik antara Presiden dan DPR. Hal yang menarik
adalah justru pada tahun 1945 Soekarno pernah berucap bahwa
konstitusi itu hanya bersifat sementara. Sebab, UUD '45 diciptakan
dalam keadaan darurat, jadi sama sekali bukan sesuatu yang "suci",
sebagaimana diklaim oleh Soeharto, dan beberapa aktor politik lebih
kontemporer.
Dalam pengamatan yang lebih seksama, ternyata ada banyak sekali
"utang" Orde Baru pada Orde Lama. Untuk menjelaskan hal ini,
mungkin ada baiknya kita kembali dulu kepada latar belakang
pembubaran Konstituante oleh Soekarno serta kembalinya Indonesia
kepada UUD 1945.
Dalam versi sejarah yang dibaca di sekolah, tahun 1950-an di
Indonesia ditandai oleh ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh
sistem demokrasi parlementer yang berlaku pada waktu itu. Sistem
ini bersifat sangat liberal, dan didominasi oleh partai-partai politik
yang menguasai parlemen. Toh Pemilu 1955-yang dimenangkan
empat kekuatan besar, Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI),
Nahdlatul Ulama (NU) serta PKI-kini masih dianggap sebagai pemilu
paling bebas dan bersih yang pernah dilaksanakan sepanjang
sejarah Indonesia. Namun, sisi lain dari sistem parlemen yang
dikuasai partai ini adalah sering jatuh bangunnya kabinet yang
dipimpin oleh perdana menteri. Selain itu, sejarah yang kita baca di
sekolah akan menekankan pula bahwa integritas nasional terus-
menerus diancam oleh berbagai gerakan separatis, yakni DI/TI,
PRRI/Permesta, dan sebagainya.
Bahwa kabinet sering jatuh bangun pada waktu itu adalah kenyataan
yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa beberapa gerakan separatis
muncul sepanjang tahun 1950-an juga adalah kenyataan, bahkan
Soekarno makin curiga pada partai politik karena dia menganggap
Masyumi, dan juga PSI, terlibat dalam beberapa pemberontakan
daerah. Lebih jauh lagi, Soekarno mendekritkan kembalinya
Indonesia pada UUD 1945 karena kegagalan Konstituante untuk
memutuskan UUD baru untuk Indonesia, akibat perdebatan berlarut-
larut, terutama antara kekuatan nasionalis sekuler dan kekuatan
Islam mengenai dasar negara.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (3 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
Seperti diketahui, salah satu aspek yang penting dari Demokrasi
Terpimpin adalah berpusatnya kekuasaan di tangan eksekutif
(presiden) dan berkurangnya kekuasaan lembaga legislatif, atau
DPR. Hal ini telah difasilitasi dengan kembalinya Indonesia kepada
UUD '45. Bahkan, bentuk parlemen pun diubah dengan
dicanangkannya suatu lembaga yang pada dasarnya memberikan
tempat yang lebih besar untuk golongan-golongan "fungsional"
dalam masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai golongan
"karya". Pada saat yang sama, tempat partai di dalam parlemen juga
dibatasi-sebab menurut Soekarno-politisi partai hanya mewakili
kepentingan partainya, dan yang diperlukan adalah individu-individu
yang dapat mewakili kepentingan "rakyat" atau yang depat
menyuarakan "kepentingan nasional" yang sebenarnya.
Di masa Orde Baru, dengan sistem kekuasaan yang jauh lebih
terpusat dibandingkan pada masa Soekarno, hal ini kemudian
menjadi masalah yang amat besar. Negara-dalam hal ini hampir
tidak bisa dibedakan dari Soeharto, keluarga, sekutu serta kroninya-
mengambil-alih seluruh hak untuk mendefinisikan "kepentingan
nasional" tersebut. Akibatnya, kepentingan nasional menjadi identik
dengan kepentingan segelintir penguasa politik dan ekonomi, dan
segala unsur dalam masyarakat yang menentangnya dinyatakan
sebagai pengkhianat. Bahkan "oposisi" menjadi kata yang kotor.
Mungkin terjadinya hal seperti itu akan sukar dibayangkan oleh
Soekarno sendiri, meskipun ia senang memandang dirinya sebagai
"penyambung lidah rakyat" berada "di atas" konflik-konflik
kepentingan yang sempit.
***
ADALAH penting juga untuk dicatat bahwa salah satu kekuatan
pendukung utama upaya Soekarno untuk memberlakukan
Demokrasi Terpimpin adalah Angkatan Darat. Mengapa Angkatan
Darat mendukung upaya Soekarno? Jawabannya sebenarnya cukup
sederhana. Ada persamaan nasib antara Soekarno dan tentara di
dalam sistem demokrasi liberal yang mementingkan peranan partai
dan parlemen, yakni keduanya tidak mempunyai akses yang
langsung terhadap jalannya roda pemerintahan.
Dengan kata lain, di luar jatuh bangunnya kabinet dalam sistem
liberal tahun 1950-an serta pemberontakan-pemberontakan di
daerah, baik Soekarno dan Angkatan Darat mempunyai kepentingan
nyata untuk membangun suatu sistem politik baru yang memberikan
mereka kekuasaan yang lebih langsung. Bisa dikatakan Soekarno
tidak puas sebagai presiden yang hanya bersifat figure-head,
sedangkan Angkatan Darat telah berkembang menjadi kekuatan
yang juga tidak puas dalam peranan hanya sebagai penjaga
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (4 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
pertahanan dan keamanan belaka. Pembahasan terhadap
kepentingan-kepentingan konkret seperti ini tidak lazim ditemukan
dalam pelajaran sejarah di sekolah pada tahun 1950-an.
Perlu diingat pula bahwa, untuk sebagian, penaklukan terhadap
pemberontakan daerah telah menghasilkan suatu pimpinan
Angkatan Darat yang jauh lebih bersatu dibandingkan sebelumnya.
Jenderal Abdul Haris Nasution telah tampil sebagai pimpinan yang
mampu untuk meredam tantangan yang diajukan oleh komandan-
komandan lokal yang memberontak karena tidak senang dengan
dominasi Jakarta/Jawa. Di samping itu, kondisi darurat yang
dicanangkan untuk menghadapi pemberontakan daerah telah
menempatkan banyak perwira militer sebagai administrator roda
pemerintahan. Lebih jauh lagi, nasionalisasi perusahaan-perusahaan
asing di tahun 1957-yang sebenarnya dipelopori oleh serikat buruh-
telah menempatkan banyak perwira militer di pucuk pimpinan
perusahaan-perusahaan negara yang terbesar. Di antaranya adalah
Ibnu Sutowo yang kemudian mengembangkan Pertamina.
Dengan posisi politik dan ekonomi yang kuat seperti ini, tampaknya
militer tergiur untuk mempunyai peranan yang langsung di dalam
sistem politik. "Demokrasi Terpimpin"-nya Soekarno memberikan
peluang. Di antara golongan "fungsional" atau "karya" yang boleh
duduk dalam parlemen adalah tentara.
Dalam konteks ini, kita perlu mengingat pula bahwa Jenderal
Nasution telah mengajukan apa yang disebut sebagai "jalan tengah"
untuk militer Indonesia. Dalam konsepsi ini, militer Indonesia tidak
akan bersifat intervensionis-dan terlibat dalam kudeta demi kudeta-
sebagaimana di Amerika Latin, namun juga tidak akan tinggal diam
sebagai penonton arena politik, sebagaimana di negeri-negeri Barat.
Walaupun sering dikatakan bahwa maksud awal Nasution telah
dipelesetkan oleh Soeharto, dalam ide ini kita melihat cikal-bakal dari
"dwifungsi" ABRI yang dipraktikkan Orde Baru.
Jadi, bila Soekarno telah memberikan dasar dari konsepsi sistem
politik yang akan dikembangkan dalam versi yang lebih birokratis,
otoriter dan ekslusioner pada masa Orde Baru, Nasution telah
memberikan landasan awal bagi peranan militer di dalamnya.
Nasution pulalah yang pertama mengusulkan bahwa hak pilih tentara
dan polisi dicabut dan diganti oleh hak otomatis memperoleh
perwakilan di badan legislatif. Oleh karena itu, Orde Baru dapat
dipandang sampai tingkat tertentu sebagai hasil yang tidak disengaja
(unintended consequence) dari manuver-manuver politik Soekarno
dan Nasution di tahun 1950-an. Bisa dikatakan bahwa Soeharto
tidak mungkin "ada" secara politik tanpa manuver kedua
pendahulunya itu, masing-masing sebagai pimpinan negara dan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (5 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
tentara.
Tentunya, Soekarno dan Nasution pada waktu itu berada dalam
situasi yang ditandai oleh keharusan untuk bernegosiasi dan bekerja
sama, tetapi juga tidak jarang oleh konflik. Khususnya, militer amat
tidak senang dengan upaya Soekarno untuk mengikutsertakan PKI
dalam pemerintahan, sedangkan Soekarno semakin mengandalkan
PKI sebagai satu-satunya kekuatan politik di awal tahun 1960-an
yang dapat mengimbangi Angkatan Darat.
Dalam pikiran Soekarno, PKI adalah bagian tak terpisahkan dari
"front" nasional menentang imperialisme dan untuk memajukan
revolusi nasional. Ternyata-walaupun cukup "sukses" dalam pemilu
nasional dan lokal sebelumnya-PKI mampu beradaptasi dengan
lingkungan politik baru setelah berakhirnya masa demokrasi
parlementer, seperti juga PNI dan NU (dua elemen lain dari
Nasakom-nya Soekarno).
Konflik militer-PKI sendiri setidaknya sudah berawal pada peristiwa
Madiun, dan diperburuk sejak tentara semakin aktif mengembangkan
ormas untuk melawan dominasi PKI terutama di bidang organisasi
buruh dan tani. Apalagi tentara sejak 1957 berhadapan langung
dengan SOBSI-serikat buruh yang dekat dengan PKI-di perusahaan
nasional yang dikelola militer. Sebagaimana diketahui, konflik militer
dan PKI itu akhirnya berkulminasi dengan peristiwa 1965 yang
hingga kini masih misterius, dan naiknya Jenderal Soeharto ke
pucuk pimpinan negara.
Adalah dalam konteks konflik militer dengan PKI ini jugalah lahir
"bayi" yang kemudian menjadi entitas politik bernama Golkar.
Setelah Soekarno memperjuangkan konsep perwakilan politik
berdasarkan "fungsi" dalam masyarakat, ideolog militer macam
Jenderal Soehardiman juga mengembangkan konsep "karyawan" di
bidang perburuhan dengan mendirikan SOKSI (terutama berbasis
pada perusahaan negara yang dikuasai militer). Akhirnya,
Sekretariat Bersama Golkar (Sekber Golkar) didirikan oleh tentara
untuk menghimpun kekuatan-kekuatan keormasan dan politik yang
berseberangan dengan kekuatan komunis.
Pada dasarnya, militerlah yang kemudian menjadi ahli waris
langsung dari konsep golongan karya yang awalnya diperjuangkan
oleh Soekarno, walau dalam versi tentara, konsep ini bermutasi
menjadi lebih anti-partai, dan bercorak anti-komunis. Dalam
perjalanan sejarah, Golkar dikembangkan di masa Soeharto sebagai
salah satu pilar utama Orde Baru, yakni sebagai wadah untuk
melegitimasikan kekuasaan lewat sejumlah pemilu yang jauh dari
prinsip bebas dan bersih.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (6 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
***
ADALAH menarik bahwa pada masa awal Orde Baru, terjadi pula
perdebatan di antara para pendukungnya sendiri (ketika itu,
termasuk para intelektual dan mahasiswa) tentang peranan partai
politik yang wajar di Indonesia. Intelektual macam Mochtar Lubis pun
menulis di koran Indonesia Raya tentang perlunya lapangan politik
dibersihkan dari partai politik yang identik dengan Orde Lama, yang
katanya menghambat pembangunan. Tentu dia tidak sendiri, karena
pandangan ini dikumandangkan juga oleh banyak intelektual lain-
termasuk yang kemudian menjadi lawan Soeharto yang gigih dan
tokoh gerakan demokrasi-serta sejumlah jenderal.
Perdebatan di antara para pendiri atau pendukung Orde Baru
berkisar sejauh dan secepat manakah partai politik perlu di-'kubur'.
Dalam hal-hal macam ini pulalah kita bisa melihat satu lagi "utang"
Orde Baru-nya Soeharto pada "Orde Lama"-nya Soekarno. Seperti
diketahui, setelah proses perdebatan dan intrik yang panjang,
akhirnya semua partai "sisa" Orde Lama memang difusikan menjadi
Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia di
tahun 1973, disertai oleh Golkar, partainya golongan karya.
Salah satu tokoh yang paling penting dalam proses perekayasaan
sistem politik Orde Baru adalah Jenderal Ali Moertopo. Peranannya
menonjol baik sebagai ideolog maupun sebagai operator politik
utama Soeharto di awal Orde Baru (dengan Aspri dan Opsus-nya).
Jenderal Moertopo menerbitkan beberapa karya yang amat
gamblang menggambarkan dasar-dasar pemikiran, blueprint, politik
Orde Baru. Moertopo bukan seorang Soekarnois, tapi saya kira ada
beberapa aspek dari pemikirannya-yang meskipun mungkin
"dipinjam" dari tempat lain- "bertemu" secara tidak langsung dengan
ide-ide yang sempat diperjuangkan oleh Soekarno di tahun 1950-an.
Salah satu "pertemuan" itu adalah dalam penempatan "negara"
sebagai suatu entitas yang diidealisasikan berada di atas konflik dan
perbedaan dalam masyarakat. Dalam pidato kenegaraan di tahun
1956, Soekarno menyatakan bahwa negara atau bangsa adalah
suatu organisme yang tidak bisa dipilah-pilah, sedangkan strategi
politik Moertopo dicurahkan terutama untuk menjamin bahwa tidak
ada kekuatan dalam masyarakat yang mampu untuk menentang
kemauan negara sebagai pengejewantahan dari kepentingan
bersama.
Menurut David Bourchier (seorang pengamat politik Indonesia
berasal dari Australia), pemikiran Moertopo banyak dipengaruhi oleh
pemikiran Gereja Katolik Eropa awal abad ke-20, yang juga
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (7 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
mengajukan konsep adanya pertalian yang erat, hubungan organik,
antara negara dan masyarakat. Pemikiran ini aslinya dikembangkan
di Eropa sebagai respons terhadap bahaya "fragmentasi"
masyarakat yang disebabkan oleh kemunculan politik perjuangan
kelas yang dimotori oleh kaum sosialis. Menurut Bourchier, Moertopo
mungkin memperoleh gagasan ini dari intelektual Center for
Strategic and International Studies (CSIS) yang sempat menjadi
dapur pemikirannya.
Seperti dikemukakan sebelumnya, Soekarno pun mengkhawatirkan
proses fragmentasi di Indonesia, walaupun lebih menurut aliran
politik atau sentimen kedaerahan. Di masa Orde Baru, ketakutan
akan fragmentasi-atas dasar kelas, agama, atau hal lain-
digabungkan dengan praktik-praktik politik represif yang
membungkam bukan hanya partai, tetapi semua suara oposisi
dengan dalih ancaman terhadap persatuan nasional dan
sebagainya. Bahkan, protes daerah-daerah tertentu mengenai
berbagai kebijakan pemerintah pusat dijawab dengan pengiriman
tentara demi menjamin lestarinya persatuan nasional.
Sekali lagi, tentu ada perbedaan-perbedaan yang penting antara
"visi" Orde Baru dan visi "Demokrasi Terpimpinnya Soekarno".
Setidak-tidaknya retorika Orde Baru di masa awal dibumbui dengan
jargon-jargon teori modernisasi yang dipinjam dari kepustakaan ilmu
sosial Barat, seperti karya Samuel Huntington yang tersohor,
Political Order in Changing Societies. Ironisnya, hal ini terjadi
meskipun sistem politik yang hendak dibangun di Indonesia adalah
yang diklaim bercorak kepribadian nasional yang khas. Sebaliknya,
retorika Soekarno seperti biasa dibumbui oleh jargon-jargon
revolusioner yang cenderung romantis dan yang menekankan
bersatunya pemimpin dengan rakyat.
***
TULISAN ini telah memusatkan perhatian pada beberapa kontinuitas-
mungkin terasa agak ironis-antara Orla dan Orba, meskipun ada
banyak perbedaan di tingkat permukaan. Hal ini dilakukan untuk
menunjukkan betapa relevannya pemikiran dan tindakan Soekarno
pada masa yang jauh melampaui kurun waktu kehidupannya sendiri-
walaupun dalam bentuk unintended consequence-yakni berdiri,
berkembang, dan bercokolnya Orde Baru.
Pada dasarnya, kontinuitas adalah tema yang masih amat relevan
dibicarakan di Indonesia, bahkan dewasa ini karena masih eratnya
kaitan antara aktor-aktor politik di masa reformasi ini dengan
berbagai kepentingan yang menonjol di masa Orde Baru. Bedanya,
kepentingan-kepentingan ini bukan lagi dilindungi oleh negara yang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (8 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru -- Jumat, 1 Juni 2001
otoriter tetapi justru oleh partai-partai yang tumbuh relatif bebas
dalam alam demokratisasi.
Seperti di tahun 1950-an dan 1960-an, perilaku partai politik yang
dianggap mementingkan diri sendiri juga telah menyebabkan banyak
orang menjadi sinis terhadapnya. Apakah sejarah akan berulang dan
partai politik kembali dicap sebagai biang keladi fragmentasi bangsa,
sebagaimana pernah dituduhkan Soekarno?
Mudah-mudahan saja solusi politik yang akhirnya ditemukan oleh
bangsa Indonesia akan sangat berbeda dari solusi yang pernah
muncul sebelumnya. Mudah-mudahan sejarah tidak berulang
dengan naiknya tentara sebagai panglima politik, dan bercokolnya
rezim yang otoriter untuk waktu yang lama.
* Dr Vedi R Hadiz Staf pengajar pada Departemen Sosiologi
Universitas Nasional Singapura.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
Muda
● Tjipto-Soetatmo-Soekarno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Soekarno,%...20Orde%20Lama,%20dan%20Orde%20Baru%20--%20Ju.htm (9 of 10)4/3/2005 11:05:19 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi Indonesia
Selama Masa Awal Kemerdekaan
Thee Kian Wie
PADA
tanggal 2
Januari
1950, HM
Hirschfeld,
Komisaris
Tinggi
(kepala
perwakilan)
Belanda
pertama di
Indonesia
Dok Kompas merdeka,
telah
diterima
dengan
penghormatan penuh oleh Presiden Soekarno, karena di antara para
kepala perwakilan negara asing yang diakreditasi di Indonesia,
Hirschfeld diberikan kehormatan untuk menyerahkan surat
kepercayaan pertama kepada Presiden Soekarno. Tempat terkemuka
yang diberikan Pemerintah Indonesia kepada Belanda juga tercermin
pada nomor pelat yang diberikan kepada kendaraan mobil yang
ditumpanginya, yaitu CD-1. (Meier 1994: 13) Akan tetapi, hanya
sepuluh tahun sesudah peristiwa tersebut, tanggal 17 Agustus 1960,
J van Vixseboxse, kuasa usaha baru Belanda yang baru saja tiba di
Indonesia tanggal 5 Agustus 1960, diminta untuk datang pagi hari ke
Departemen Luar Negeri. Di sana Vixseboxse diberitahu oleh
Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri bahwa ia tidak perlu
menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Soekarno.
Sebab, Presiden Soekarno dalam pidato tahunannya yang akan
diucapkan siang itu di Istana Merdeka akan mengumumkan
pemutusan hubungan diplomatik dengan negeri Belanda karena
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (1 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
"tindakan agresif Belanda mengenai Irian Barat". Yang dimaksud
Presiden Soekarno dengan "tindakan agresif Belanda" adalah
pengiriman kapal induk Karel Doorman oleh Pemerintah Belanda
untuk memperkuat pertahanan Irian Barat. (Meier 1994: 607)
Kedua peristiwa di atas menunjukkan bahwa pengakuan kedaulatan
Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1947 (atau
"penyerahan kedaulatan kepada Indonesia" menurut tafsiran
Belanda) tidak berhasil membawa perbaikan yang berarti dalam
hubungan antara negara bekas penjajah dan bekas jajahannya,
malahan terus merosot dalam tahun-tahun berikutnya. Hal ini
disebabkan pada dasarnya proses dekolonisasi Indonesia belum
dapat diselesaikan dengan tuntas dalam Konferensi Meja Bundar
antara Belanda dan Indonesia yang diadakan di Den Haag, Belanda,
23 Agustus-2 November 1949 untuk merundingkan penyerahan
kedaulatan kepada Indonesia. Dengan kata lain, kemerdekaan politik
Indonesia belum berhasil memutuskan segala ikatan historis dengan
Belanda, baik dalam arti politis dan ekonomi, dan mungkin juga
dalam arti budaya dan psikologi.
Dalam arti politis, kemerdekaan Indonesia belum dianggap tuntas
karena dalam Konferensi Meja Bundar Belanda tidak bersedia
menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, yang menurut Belanda,
sebenarnya bukan termasuk wilayah Indonesia. (Houben 1996: 174-
75) Dihadapi dengan jalan buntu, Indonesia dan Belanda sepakat
bahwa status quo Irian Barat untuk sementara dipertahankan, tetapi
juga bahwa dalam waktu satu tahun status daerah ini akan ditentukan
lebih lanjut melalui perundingan. (Legge 1973: 238)
Akan tetapi, dalam perundingan berikutnya Belanda tetap enggan
untuk menyerahkan Irian Barat. Oleh karena hal ini Soekarno
berpendapat bahwa revolusi nasional belum selesai dan perlu
diteruskan sampai Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia.
Dalam tahun-tahun berikutnya, Presiden Soekarno tak henti-hentinya
menekankan bahwa perjuangan untuk merebut kembali Irian Barat
adalah prioritas utama dalam kebijakan nasional Pemerintah
Indonesia. Meskipun pemimpin-pemimpin nasional lainnya setuju
bahwa Irian Barat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
Indonesia, beberapa di antara mereka berpendapat bahwa sebaiknya
konflik dengan Belanda tentang Irian Barat dibahas secara tidak
mencolok melalui saluran diplomatik biasa, karena Indonesia pada
waktu itu menghadapi berbagai masalah lainnya, termasuk masalah
ekonomi, yang perlu segera ditanggulangi. (Legge 1973: 248)
Dalam tahun-tahun berikutnya, memang ternyata bahwa pada tahap
awal kemerdekaan, banyak energi dan sumber daya nasional yang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (2 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
sebenarnya bisa disalurkan untuk pembangunan ekonomi, justru
dimobilisasi untuk menanggulangi masalah Irian Barat.
Akar-akar nasionalisme ekonomi Indonesia
Selain masalah Irian Barat, kemerdekaan Indonesia sesudah
pengakuan kedaulatan oleh Belanda belum dirasakan sebagai tuntas
oleh para pejuang kemerdekaan, karena berbagai sektor ekonomi
yang penting masih dikuasai Belanda, sedangkan berbagai jabatan
penting dalam birokrasi pemerintah masih dipegang oleh pejabat-
pejabat Belanda. Hal ini bisa terjadi karena dalam rangka persetujuan
Indonesia-Belanda yang telah dicapai dalam Konferensi Meja Bundar
di Den Haag, kepentingan bisnis Belanda tetap dijamin dalam
Indonesia merdeka.
Pembicaraan tentang kelangsungan bisnis Belanda telah menyita
banyak waktu dalam Konferensi Meja Bundar, karena pada tahun
1949 pembangunan ekonomi Belanda-yang mengalami banyak
kerusakan selama Perang Dunia Kedua-belum selesai. Berhubung
dengan hal ini Pemerintah Belanda menganggap penting bahwa
penghasilan dari perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia perlu
diamankan, karena penghasilan ini merupakan sumber pembiayaan
penting bagi pembangunan ekonomi Belanda. (Meier 1994: 46)
Dalam Persetujuan Finansial-Ekonomi (Financieel-Economische
Overeenkomst Finec) yang telah dicapai di Konferensi Meja Bundar,
tuntutan Belanda untuk memperoleh jaminan bahwa bisnis Belanda
dapat tetap beroperasi di Indonesia tanpa hambatan, terpaksa
dipenuhi oleh pihak Indonesia. Oleh karena ini tidak mengherankan
bahwa bahkan seorang sejarawan ekonomi Belanda yang
konservatif, Henri Baudet, menyatakan bahwa Persetujuan Finec
memuat jaminan maksimal yang dapat dicapai bagi kelangsungan
hidup bisnis Belanda di Indonesia. (Baudet & Fennema, 1983: 213)
Indonesia tetap amat penting bagi ekonomi Belanda. Hal ini tercermin
dari suatu perkiraan resmi Belanda yang mengungkapkan bahwa
pada tahun 1950 penghasilan total Belanda yang diperoleh dari
hubungan ekonomi dengan Indonesia (ekspor ke Indonesia,
pengolahan bahan-bahan mentah, penghasilan dari penanaman
modal di Indonesia, transfer uang pensiun dan tabungan, dan lain-
lain) merupakan 7,8 persen dari pendapatan nasional Belanda. Untuk
tahun-tahun berikutnya sampai tahun 1957 sewaktu semua
perusahaan Belanda diambil alih, angka persentase ini adalah: 8,2
persen (1951); 7,0 persen (1952); 5,8 persen (1953); 4,6 persen
(1954); 4,1 persen (1955); 3,3 persen (1956); dan 2,9 persen (1957).
(Meier 1994: 649).
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (3 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
Penurunan dalam arti ekonomi Indonesia bagi Belanda sejak tahun
1953 berkaitan erat dengan merosotnya hubungan ekonomi
Indonesia-Belanda akibat merosotnya hubungan diplomatik dengan
Belanda.
Di samping jaminan ini, Persetujuan Finec juga memuat ketentuan
yang kontroversial yang mewajibkan Pemerintah Indonesia
menanggung utang-utang internal Pemerintah Hindia Belanda
sebelum Indonesia diduduki Jepang tahun 1942 sebanyak 3,3 milyar
gulden (sama dengan 1,13 milyar dollar AS pada kurs devisa yang
berlaku pada waktu itu). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga
diwajibkan menanggung utang eksternal Pemerintah Hindia Belanda
sebesar kurang lebih 70 juta dollar AS. (Meier 1994: 47; McT. Kahin
1997: 26; 314)
Jelas sekali bahwa Konferensi Meja Bundar "mewarisi" utang luar
negeri yang amat besar kepada Pemerintah Indonesia yang sangat
mempersulit upaya Pemerintah Indonesia untuk membiayai
rehabilitasi prasarana fisik yang telah hancur akibat pendudukan
Jepang dan perjuangan fisik melawan Belanda, apalagi
melaksanakan program pembangunan. (Kahin 1997: 27)
Oleh karena itu, Dr Sumitro Djojohadikusumo, yang ikut sebagai
anggota delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar, sangat
menentang konsesi delegasi Indonesia untuk mengambil alih utang-
utang dari Pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, Drs Moh Hatta,
Wakil Presiden RI yang bertindak sebagai ketua delegasi Indonesia,
akhirnya menerima tuntutan pihak Belanda karena ia ingin cepat
menyelesaikan perundingan agar tujuan utama-penyerahan
kedaulatan kepada Indonesia-dapat tercapai dalam waktu
sesingkatnya. (Esmara & Cahyono, 2000: 95-98)
Perkembangan ini pada awal kemerdekaan menyebabkan
nasionalisme ekonomi di Indonesia jauh lebih kuat ketimbang di
negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan hingga sekarang. Jika
nasionalisme ekonomi diartikan sebagai aspirasi sesuatu bangsa
untuk memiliki atau setidak-tidaknya menguasai aset-aset yang
dimiliki atau dikuasai orang asing dan untuk menduduki fungsi-fungsi
ekonomi yang dilakukan oleh orang asing (Johnson 1972: 26), maka
tidak mengherankan nasionalisme ekonomi bangsa Indonesia pada
awal kemerdekaan sangat tersentak oleh kenyataan bahwa bagian
terbesar dari sektor-sektor modern Indonesia (perkebunan-
perkebunan besar, pertambangan, industri-industri padat modal skala
besar, dan sektor jasa-jasa modern, seperti perbankan, perdagangan
besar, dan jasa-jasa pelayanan publik, seperti listrik, air, gas,
komunikasi, dan transport)-diperkirakan meliputi 25 persen dari
Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada waktu itu dan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (4 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
mempekerjakan kurang lebih 10 persen dari angkatan kerja
Indonesia-masih dimiliki atau dikuasai Belanda. (Higgins 1990: 40)
Di samping itu, banyak jabatan senior dan penting lainnya di birokrasi
Pemerintah Indonesia pada awal tahun 1950-an masih diduduki oleh
pejabat-pejabat Belanda, yang pada waktu itu masih berjumlah
kurang lebih 6.000 orang. Misalnya, jabatan Gubernur Bank Java
(Javasche Bank, cikal bakal Bank Indonesia) dan Kepala Direktorat
Dewan Pengendalian Devisa masih tetap dipegang orang-orang
Belanda.(Higgins 1990: 40)
Malahan dalam Dewan Direktur Bank Java hanya terdapat satu
direktur Indonesia, sedangkan yang lainnya semua masih orang
Belanda. Di Departemen Keuangan pun masih ada banyak pejabat
Belanda. Menghadapi keadaan ini, tidak mengherankan aspirasi
utama nasionalisme ekonomi Indonesia pada waktu itu adalah untuk
"merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional", di mana
orang-orang Indonesia menjadi 'tuan di rumah sendiri'.
Kebijakan ekonomi selama kurun waktu 1950-1957
Dihadapi dengan tatanan ekonomi yang masih tetap "kolonial",
Pemerintah Indonesia mengambil berbagai langkah untuk menguasai
dan mengendalikan berbagai sektor dan usaha yang dianggap
strategis. Misalnya, pada tahun 1953 Bank Java dinasionalisasikan
dan diberi nama baru "Bank Indonesia". Sebagai Gubernur orang
Indonesia pertama dari Bank Indonesia diangkat Sjafruddin
Prawiranegara, mantan Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta dan
Kabinet Natsir. (Prawiranegara 1987: 102-03)
Nasionalisasi Bank Java ini dianggap penting sekali, karena
pengendalian peredaran uang dan kredit memang diakui sebagai
unsur pokok dari kedaulatan sesuatu negara. (Anspach 1969: 137)
Sebenarnya Pemerintah Indonesia pada awal tahun 1950-an agak
enggan melakukan nasionalisasi besar-besaran dari perusahaan-
perusahaan Belanda, karena merasa terikat dengan Persetujuan
Finec hasil Konferensi Meja Bundar. Keengganan ini juga disebabkan
kabinet-kabinet pertama pada paruh pertama tahun 1950-an (Kabinet
Natsir, Kabinet Sukiman, dan Kabinet Wilopo) pada umumya masih
terdiri atas orang-orang nasionalis moderat dan pragmatis yang
menyadari bahwa peran penting perusahaan-perusahaan dan
pejabat-pejabat Belanda, meskipun tidak menyenangkan, masih
diperlukan untuk sementara waktu.
Meskipun demikian, pada akhir tahun 1952 Kabinet Wilopo
mengambil keputusan tegas untuk menasionalisasi perusahaan-
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (5 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
perusahaan listrik swasta Belanda. (Anspach 1969: 145)
Menurut persetujuan Finec, nasionalisasi perusahaan-perusahaan
Belanda bisa dilakukan jika hal ini dianggap perlu untuk kepentingan
nasional dan disetujui oleh kedua belah pihak. Di samping itu jumlah
kompensasi harus diputuskan oleh seorang hakim atas dasar nilai riil
usaha yang dinasionalisasikan. (Meier 1994: 46-47)
Selain nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik, Pemerintah
Indonesia atas desakan keras golongan nasionalis pada tahun 1954
juga menasionalisasikan perusahaan penerbangan Garuda
Indonesian Airways yang didirikan pada tahun 1950 sebagai usaha
patungan antara perusahaan penerbangan Belanda KLM dan
Pemerintah Indonesia. Dalam usaha itu kedua belah pihak masing-
masing memegang 50 persen saham dari perusahaan ini. Dalam akta
pendirian Garuda, Pemerintah Indonesia diberi opsi untuk membeli
saham mayoritas sesudah 10 tahun, sedangkan pengendalian
manajemen dipegang oleh KLM.
Dalam tahun-tahun berikutnya KLM mulai menjual sebagian dari
sahamnya kepada Pemerintah Indonesia, tetapi di lain pihak KLM
enggan sekali menyerahkan pengendalian manajemen kepada pihak
Indonesia. Akan tetapi, nasionalisasi Garuda oleh Kabinet Ali
Sastroamidjojo I dibarengi juga dengan pengambilalihan
pengendalian manajemen oleh pihak Indonesia. Sejak itu peran KLM
hanya terbatas pada pemberian bantuan teknis kepada Garuda.
(Anspach 1969: 146)
Upaya Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sektor industri
manufaktur modern yang dikuasai dan dikendalikan oleh orang
Indonesia sendiri dimulai dengan Rencana Urgensi Ekonomi yang
bertujuan mendirikan berbagai industri skala besar. Menurut rencana
ini, pembangunan industri-industri akan dibiayai dulu oleh
pemerintah, tetapi kemudian akan diserahkan kepada pihak swasta
Indonesia, koperasi, atau dikelola sebagai usaha patungan antara
pihak swasta nasional dan Pemerintah Indonesia. (Anspach 1969:
163)
Gagasan tentang peran perintis Pemerintah Indonesia dalam
industrialisasi Indonesia agak mirip dengan peran yang dilakukan
Pemerintah Jepang selama tahap awal industrialisasi Jepang selama
zaman Meiji. Sayang sekali, pelaksanaan Rencana Urgensi Ekonomi
berjalan tersendat-sendat, dan pabrik-pabrik yang sempat dibangun
beroperasi dengan hasil yang mengecewakan. Oleh karena itu,
rencana ini dihapus pada tahun 1956 dan diganti dengan Rencana
Pembangunan Lima Tahun Pertama (1955-1960) yang telah disusun
oleh Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh Ir Djuanda. (Anspach
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (6 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
1969: 163)
Untuk menyusun kekuatan tandingan terhadap kepentingan ekonomi
Belanda, Pemerintah Indonesia pada tahun 1950 meluncurkan
Program Benteng. (Djojohadikusumo 1986: 35)
Hal ini diusahakan melalui pengembangan golongan wiraswasta
pribumi yang tangguh dan dengan menempatkan sektor ekonomi
yang penting, yaitu perdagangan impor, di bawah pengendalian
nasional. Untuk mencapai tujuan ini, lisensi-lisensi impor disalurkan
ke pengusaha-pengusaha nasional, khususnya pengusaha-
pengusaha pribumi. Diharapkan dengan modal yang dapat dipupuk
dari perdagangan impor, para pengusaha pribumi Indonesia mampu
melakukan diversifikasi ke bidang lain, seperti perkebunan besar,
perdagangan dalam negeri, asuransi, dan industri-industri substitusi
impor, seperti yang dirintis beberapa perusahaan pribumi, misalnya
perusahaan milik Dasaad Musin dan Rahman Tamin. (Anspach 1969:
168)
Ditinjau dari segi pengendalian nasional atas perdagangan impor,
Program Benteng cukup berhasil karena pada pertengahan tahun
1950-an kurang lebih 70 persen dari perdagangan impor sudah
dilakukan oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. (Burger 1975: 171)
Namun, dalam waktu singkat sudah kelihatan bahwa Program
Benteng mengandung berbagai kelemahan, terutama dengan
munculnya banyak 'importir aktentas', yaitu orang yang tidak
memanfaatkan peluang baik untuk memperoleh keterampilan dan
pengalaman dalam perdagangan impor, tetapi justru menjual lisensi
impor yang mereka peroleh kepada importir lain, kebanyakan importir
etnis Cina.
Dengan demikian, Program Benteng justru membuka peluang bagi
'kegiatan perburuan rente' (rent-seeking activities) sehingga kurang
berhasil dalam mengembangkan golongan wiraswasta nasional sejati
yang tangguh dan mandiri. Hal ini sebenarnya sejak awal sudah
disadari oleh Profesor Sumitro, salah seorang arsitek Program
Benteng, yang dalam suatu wawancara pernah menyatakan bahwa
jika "dari bantuan dari Program ini kepada 10 orang, tujuh orang
ternyata adalah benalu, tiga orang lainnya masih bisa muncul
sebagai wiraswasta sejati". (Djojohadikusumo 1986: 35)
Kelemahan-kelemahan yang melekat pada Program Benteng
mendorong Pemerintah Indonesia mengadakan penyaringan ketat
untuk mengeliminasi importir semu atau tidak mampu. Akibat
penyaringan ini jumlah importir yang terdaftar berhasil dikurangi, dari
4.300 sampai kurang lebih 2.000. (Burger 1975: 171)
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (7 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
Akan tetapi, perkembangan politik dalam negeri setelah pertengahan
tahun 1950-an, khususnya pergolakan di daerah, mengalihkan
perhatian pemerintah kepada bahaya perpecahan bangsa.
Penyelundupan komoditas-komoditas ekspor dari daerah-daerah luar
Jawa mengakibatkan pasokan devisa bagi Pemerintah Indonesia
banyak berkurang sehingga mengurangi devisa untuk menunjang
Program Benteng. Hal ini termasuk kegagalan untuk
mengembangkan wiraswasta nasional yang tangguh, akhirnya
mendorong Pemerintah Indonesia menghapus Program Benteng.
Karena Program Benteng ini dianggap sebagai upaya pokok utuk
pengembangan wiraswasta nasional, maka kegagalan Program
Benteng menciptakan iklim yang makin condong untuk
menasionalisasikan usaha-usaha Belanda yang dianggap
menghambat pengembangan wiraswasta nasional. (Anspach 1969:
179)
Sementara itu, hubungan dengan Belanda makin merosot akibat
pertikaian tentang Irian Barat. Rasa permusuhan terhadap Belanda
makin memuncak sewaktu Sidang Umum PBB pada akhir November
1957 gagal menerima mosi Indonesia yang mendesak Belanda
merundingkan status Irian Barat dengan Indonesia. Presiden
Soekarno memberikan reaksi keras terhadap putusan ini, dan
mengimbau rakyat Indonesia untuk membangun kekuatan yang
dapat memaksa Belanda menyerahkan Irian Barat. Dalam waktu
dekat suatu kampanye raksasa muncul di Jakarta dan di tempat-
tempat lain terhadap perusahaan-perusahaan dan milik Belanda
lainnya, yang berakhir dengan pengambilalihan semua perusahaan
Belanda. Meskipun dalam kampanye waktu itu tidak ada seorang
Belanda pun hilang nyawanya, namun dalam waktu singkat puluhan
ribu orang Belanda meninggalkan Indonesia. (Legge 1973: 292-93)
Aksi massa untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda
menjadikan Pemerintah Indonesia mengambil alih pengendalian atas
perusahaan-perusahaan Belanda dengan fait accompli. Untuk
mengendalikan perkembangan yang memprihatinkan, pemerintah
memutuskan mengambil alih pengendalian atas perusahaan-
perusahaan Belanda yang diambil alih massa. (Legge 1973: 293-94)
Pada tahun 1958, perusahaan-perusahaan Belanda ini
dinasionalisasikan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia, dan
diubah statusnya menjadi perusahaan negara. Dengan kejadian ini,
setelah beroperasi selama kurang lebih 350 tahun di Indonesia,
seluruh bisnis Belanda hengkang dari Indonesia.
Penutup
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (8 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda untuk sebagian besar
memang berhasil memenuhi aspirasi nasionalisme ekonomi
Indonesia untuk "menjadi tuan di rumahsendiri". Di samping itu tidak
dapat disangkal bahwa dengan tetap bercokolnya bisnis Belanda,
ruang gerak Pemerintah Indonesia untuk merombak struktur
kepemilikan ekonomi kolonial menjadi sangat terbatas. Selain
kekurangan dana untuk membayar kompensasi kepada perusahaan
Belanda yang dinasionalisasikan, pada waktu itu belum ada cukup
wiraswasta dan manajer nasional yang dapat mengelola perusahaan-
perusahaan yang dinasionalisasikan. (Glassburner 1971: 94)
Memang di atas kertas, Pemerintah Indonesia secara gradual dapat
mengembangkan suatu golongan wiraswasta nasional dan manajer
profesional yang cukup tangguh.
Pengembangan wiraswasta nasional diusahakan melalui Program
Benteng, tetapi program ini, dengan beberapa pengecualian, telah
gagal dalam mengembangkan wiraswasta nasional yang tangguh.
Manajer-manajer profesional diharapkan dapat muncul dari kalangan
manajer Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda.
Jika keadaan politik pada waktu itu telah mengizinkan, maka
perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasikan sebenarnya juga
dapat menarik manajer-manajer Indonesia keturunan Cina yang
bekerja di perusahaan-perusahaan milik pengusaha etnik Cina,
seperti dilakukan pimpinan Central Trading Company (CTC),
perusahaan dagang milik negara pertama yang telah didirikan di
Bukittinggi selama perjuangan fisik melawan Belanda. (Daud 1999:
44-45)
Pentingnya pengembangan sumber daya manusia Indonesia untuk
keberhasilan pembangunan nasional Indonesia juga telah ditekankan
oleh nasionalis moderat, seperti Sjafruddin Prawiranegara. (1987:
106)
Akan tetapi, tetap berlangsungnya dominasi bisnis Belanda dalam
alam Indonesia merdeka dan sikap kaku Pemerintah Belanda yang
terus menolak merundingkan status Irian Barat tidak memberikan
peluang bagi pemimpin-pemimpin moderat-seperti Moh Hatta,
Sjafruddin Prawiranegara, dan Djuanda-untuk menempuh kebijakan
yang gradual dan hati-hati, dan akhirnya memberikan peluang bagi
pemimpin yang lebih radikal, terutama Presiden Soekarno, untuk
menempuh kebijakan yang konfrontatif yang berakhir dengan
nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.
Langkah ini tidak berhasil memecahkan berbagai masalah ekonomi
gawat yang dihadapi Indonesia pada waktu itu, terutama laju inflasi
yang tinggi akibat pembiayaan defisit (deficit financing) anggaran
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan%...Ekonomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (9 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
pemerintah yang besar yang disebabkan oleh displin fiskal yang
lemah dan merajalelanya pasar gelap devisa karena apresiasi riil
(overvaluation) rupiah yang diakibatkan oleh laju inflasi yang tinggi.
Keadaan ini juga memaksa Pemerintah Indonesia memberikan
perhatian yang makin besar pada pengendalian jumlah cadangan
devisa dan emas yang terbatas sehingga masalah-masalah ekonomi
lainnya diabaikan. (Mackie 1971: 58-67)
Lagi pula, vakum ekonomi yang telah ditinggalkan oleh hengkangnya
pengusaha-pengusaha Belanda dengan cepat diisi oleh pengusaha-
pengusaha Indonesia keturunan Cina dan etnis lainnya, dan bukan
oleh pengusaha-pengusaha pribumi. Dalam perkembangan
selanjutnya hal ini akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi
baru, terutama selama masa Orde Baru, yang hingga kini pun masih
belum dapat dipecahkan dengan tuntas. Suatu masalah lain adalah
bahwa dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda,
Pemerintah Indonesia dalam sekejap mata memiliki ratusan
perusahaan negara baru, hal mana memang telah sangat
memperbesar pengendalian nasional atas berbagai sektor ekonomi
yang strategis maupun yang kurang strategis. Akan tetapi, dalam
perkembangan selanjutnya perusahaan-perusahaan negara (kini
disebut BUMN), terutama selama Orde Baru, telah membuka peluang
bagus untuk praktik-praktik KKN, khususnya dengan menjadikannya
sebagai sapi perahan oleh oknum-oknum pemerintah yang korup.
Dengan demikian, banyak perusahaan negara tidak bisa beroperasi
secara efisien dan menghasilkan penerimaan yang berarti bagi kas
negara, malahan sering harus diberikan subsidi oleh pemerintah.
Tidak mengherankan bahwa dalam program reformasi ekonomi
Indonesia yang digulirkan setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997/98,
privatisasi BUMN merupakan salah satu prioritas pemerintah,
meskipun pelaksanaannya lamban sekali.
Jakarta, 12 Mei 2001
* Thee Kian Wie
sejarawan ekonomi pada Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan,
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PEP-LIPI), Jakarta.
Acuan
Abdullah, Taufik, (editor), 1997, The Heartbeat of Indonesian
Revolution, PT Gramedia Pustaka Utama in Cooperation with
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan...konomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (10 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
Program of Southeast Asian Studies, LIPI, Jakarta.
Anspach, Ralph, 1969, Indonesia, dalam: Golay, et. al., 1969, hlm
111-202.
Baudet, H. & M. Fennema, et.al., 1983, Het Nederlands belang bij
Indie (Kepentingan Belanda di Indonesia), Het Spectrum, Utrecht.
Burger, D.H., 1975, Sociologisch-Economische Geschiedenis van
Indonesie - Deel II: Indonesia in de 20e Eeuw (Sejarah Sosiologi
Ekonomi Indonesia, Jilid II: Indonesia dalam Abad ke-20), Koninklijk
Instituut voor de Tropen, Amsterdam.
Daud, Teuku Mohamad, 1999, Survey of Recent Developments,
dalam: Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 35, no. 3,
December, hlm 41-50.
Djojohadikusumo, Sumitro, 1986, Recollections of My Career, dalam:
Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 22, no. 3, December,
hlm 27-39.
Esmara, Hendra, & Heru Cahyono, 2000, Sumitro Djojohadikusumo-
Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, Pustaka Sinar Harapan,
Jakarta.
Glassburner, Bruce, 1971a, Economic Policy-Making in Indonesia,
1950-1957, dalam: Glassburner (editor), 1971b, hlm 70-98.
, - , (editor), 1971b, The Economy of Indonesia - Selected Readings
Cornell University Press, Ithaca and London.
Golay, Frank; Ralph Anspach; M. Ruth Pfanner; & Eliezer B. Ayal,
1969, nderdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia
Cornell University Press.
Higgins, Benjamin, 1990, hought and action: Indonesian economic
studies and policies in the 1950s dalam: Bulletin of Indonesian
Economic Studies, Vol. 26, no. 1, hlm 37-47.
Houben, Vincent, 1996, Van Kolonie tot Einheidstaat (Dari Jajahan
Sampai Negara Kesatuan), Semaian 16, Vakgroep Talen en Culturen
van Zuidoost-Azie en Oceanie, Rijksuniversiteit te Leiden.
Johnson, Harry, 1972, The Ideology of Economic Policies in the New
States, dalam: Wall (editor), 1972.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan...konomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (11 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tantangan dan Kebijakan Ekonomi IndonesiaSelama Masa Awal Kemerdekaan -- Jumat, 1 Juni 2001
Kahin, George McT., 1997, Some Recollections from and
Recollections on the Indonesian Revolution, dalam: Abdullah (editor),
1997, hlm 10-28.
Legge, J.D., 1973, Sukarno - A Political Biography, Penguin Books.
Mackie, J.A.C., 1971, The Indonesian Economy, 1950-1963, dalam:
Glassburner (editor), 1971b, hlm 16-69.
Meier, Hans, 1994, Den Haag-Djakarta - De Nederlands-
Indonesische betrekkingen 1950-1962 (Den Haag-Djakarta-
Hubungan negeri Belanda-Indonesia, 1950-1962), Aula paperbacks,
Het Spectrum B.V., Utrecht.
Prawiranegara, Sjafruddin, 1987, Recollections of My Career, dalam:
Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 23, no. 3, December,
pp. 100-07.
Wall, David, (editor), 1972, Chicago Essays in Economic
Development, University of Chicago Press.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tantangan...konomi%20IndonesiaSelama%20Masa%20Awal%20Ke.htm (12 of 13)4/3/2005 11:05:20 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Tjipto-Soetatmo-Soekarno
Takashi Shiraishi
SOEKARNO adalah generasi kedua dari nasionalis Indonesia yang
mewarisi pencapaian generasi yang mendahuluinya yang diwakili
orang-orang seperti Douwes Dekker, Tjokroaminoto, Sneevliet,
Semaoen, Haji Fachroddin, dan Haji Misbach di zaman pergerakan
pada seperempat pertama abad ke-20. Soekarno tidak
mempertanyakan kenapa rakyat dipisahkan oleh garis ideologis
Islam, marxisme, dan nasionalisme. Ia menerima kenyataan ini
begitu saja dan menganjurkan agar Islam, marxisme dan
nasionalisme bersatu. Ia menerima apa adanya nasionalisme
Indonesia dan tidak mempertanyakan kenapa nasionalisme
Indonesia dan bukannya nasionalisme Jawa. Ia menerima
demokrasi, yaitu kerakyatan, sebagai dasar untuk Indonesia
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
merdeka. Ia memberi marhaenisme sebagai namanya, tanpa
mempertanyakan dalam bentuk apa kerakyatan seharusnya
berbentuk. Dengan mewarisi semua yang dicapai generasi yang
mendahuluinya, tesis, antitesis segala tanpa sintesis, ia menjadi
orang yang penuh kontradiksi.
Ini penting sekali jika kita ingin memahami bagaimana kebudayaan
dan nasionalisme Jawa membentuk idenya mengenai demokrasi dan
nasionalisme. Pada kenyataannya ia mewarisi dua cabang pemikiran
nasionalisme dan demokrasi yang satu sama lain saling
bertentangan. Kedua aliran pemikiran itu paling jelas diwakili oleh
Soetatmo Soeriokoesoemo dan Tjipto Mangoenkoesoemo pada
1910-an dalam perdebatan mengenai nasionalisme, perkembangan
kebudayaan Jawa, dan demokrasi.
Tjipto dikenal baik sebagai nasionalis Indies (Hindia), seorang dokter
Jawa, anggota dan pendiri Indische Partij, yang akhirnya menjadi
mentor Soekarno pada pertengahan 1920-an. Sedangkan Soetatmo,
berasal dari lingkungan Paku Alam di Yogyakarta, adalah pendukung
nasionalisme Jawa. Ia juga pemimpin jurnal berbahasa Belanda
Wederopbouw (Rekonstruksi) pada 1910-an. Ia lantas bergabung
dengan Soewardi Soerjaningrat, yang kemudian dikenal sebagai Ki
Hadjar Dewantara, untuk mendirikan Taman Siswa. Pada awal 1920-
an, ia menjadi ketua pertama Taman Siswa, dengan Soewardi
sebagai sekretarisnya. Apa ide mereka mengenai nasionalisme,
perkembangan kebudayaan Jawa, dan demokrasi, yang kemudian
diwarisi oleh Soekarno dan pada akhirnya diteruskan kepada orang-
orang Indonesia sekarang? Pertama-tama mari kita membicarakan
Soetatmo dan kemudian Tjipto.
***
SEBAGAI orang Boedi Oetomo, Soetatmo Soeriokoesoemo, seperti
kebanyakan pendukung nasionalisme Jawa, mengatakan bahwa
nasion dapat dan mesti dibangun atas dasar kebudayaan dan
bahasa yang dipakai orang banyak. Nasionalisme Jawa memiliki
dasar yang dapat ditemukan dalam kebudayaan, bahasa, dan
sejarah orang Jawa. Sementara nasionalisme Indies sama sekali
tidak eksis landasannya atau setidaknya merupakan kreasi
pemerintah kolonial Belanda. Dalam pandangan Soetatmo hanya
nasionalisme Jawa yang memiliki dasar kebudayaan yang kuat
sebagai landasan komunitas politik untuk masa depan.
Apa yang dimaksudkan oleh Soetatmo ketika ia membicarakan
kebudayaan Jawa dan bagaimana kebudayaan itu dapat
berkembang? Ia mengatakan bahwa opvoeding, pembinaan,
merupakan inti pokok kebudayaan Jawa dan dasar perkembangan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
Jawa. Dalam pandangannya, wilayah moral dalam diri manusia
merupakan orde tertinggi yang dikendalikan kekuatan Ilahi, dan
dalam kebudayaan Jawa tugas pembinaan moral diserahkan kepada
pandita yang hidup dalam asketisme dan jauh dari hiruk-pikuk
persoalan sosial, terus-menerus berusaha mengendalikan diri dan
berusaha mengatasi semua perbedaan yang timbul karena
perbedaan garis partai, agama atau kepentingan. Lebih jauh dari itu
seorang pandita belajar memahami hukum tertinggi. Namun, pandita
tidak lagi berada di sini, ia telah lama hilang dalam sejarah, sehingga
yang sekarang tersisa sebagai sumber pokok kebijakan Jawa, dan
sarana pendidikan moral untuk orang Jawa adalah wayang.
Soetatmo melihat perkembangan yang sedang terjadi saat itu penuh
dengan keraguan. Ia percaya betul, seperti juga nasionalis Jawa
lainnya, bahwa puncak kejayaan Jawa telah dicapai pada masa
Majapahit, setelah itu sejarah Jawa penuh dengan cerita
kemunduran dan mencapai titik terendahnya setelah dijajah Belanda.
Ia menggambarkan suasana waktu itu pada buku kecil berjudul
Sabdo-Panditto-Ratoe (diterbitkan tahun 1920) seperti berikut:
"Saat ini, Indies sedang mengalami kekacauan, neraka; orang tidak
lagi bisa membedakan antara teman dan musuh. Pemerintah
memainkan peran ganda, sesekali menjadi teman, namun pada saat
lain berubah menjadi musuh; sekarang progresif, tapi kemudian bisa
berubah menjadi reaksioner. Orang berkelahi melawan temannya
sendiri, dan bergandengan tangan dengan musuhnya, padahal pada
saat yang sama mereka sama-sama yakin sedang melawan musuh.
Tak seorang pun tahu di mana ujung dari kekacauan ini dan
kerusuhan muncul di mana-mana; ningrat melawan bukan-ningrat,
kromo berhadapan dengan ngoko, kapital lawan buruh, pemerintah
melawan yang diperintah, pemerintah melawan rakyat; masyarakat
sudah jungkir balik dan berantakan. Itulah gambaran mengenai
Indies saat ini."
Dalam pandangan Soetatmo, sistem politik yang sedang berjalan di
Indies tidak benar. Ia membandingkan negara Indies dengan sebuah
keluarga yang "bapaknya cerewet dan ibunya sibuk mengurus diri
sendiri, sehingga lupa tugasnya terhadap anak-anak". "Jika ibu terus-
menerus menolak tugasnya, kecelakaan tak terhindarkan. Dan ketika
kecelakaan terjadi, anak-anak adalah pemenangnya. Aturan akan
kacau, sebagai akhir bapak dan ibu harus menaatinya. Dan itulah
gambaran negara yang berlandaskan demokrasi."
Soetatmo sangat mengerti bahwa gelombang yang menuju negara
demokratis tak terhindarkan. Ia juga memperhatikan dengan sedih
orang-orang menerima dengan penuh antusias datangnya
demokrasi. Namun, ia percaya bahwa volksregeering atau
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
pemerintahan rakyat yaitu demokrasi adalah ilusi. Karena "jika setiap
individu memiliki hak sama, mereka tak punya tugas untuk dipenuhi,
setiap individu bersandar pada dirinya, haknya sendiri dan tak ada
masyarakat yang mungkin bertahan. Anak-anak akan mengurus
dirinya sendiri, karena mereka menekankan bahwa setiap orang
harus menghormati haknya. Tak akan ada persatuan sama sekali,
tetapi hanya perbedaan-perbedaan, tak ada keteraturan tetapi
kekacauan."
Lantas apa jalan keluarnya? Soetatmo mengatakan bahwa
pembinaan moral adalah kuncinya. Ia melihat opvoeding yang
diberikan pandita-ratoe sebagai jalan dan kunci baik untuk
perkembangan kebudayaan Jawa maupun jawaban atas demokrasi.
Ia mengatakan bahwa pembinaan moral harus diarahkan oleh
pandita yang sangat mengerti aturan tertinggi, demokrasi harus
diarahkan pandita-ratu yang bijaksana. Ia menulis dalam Sabdo-
Panditto-Ratoe:
"Persamaan dan persaudaraan... harus juga disampaikan dengan
benar; tetapi bukan persamaan dalam demokrasi, yang berbicara
mengenai persamaan hak, tetapi persamaan dalam keluarga, anak
tertua memainkan peranan penting dalam urusan domestik rumah,
sehingga ia mendapatkan hak yang lebih banyak daripada adik-
adiknya yang lebih mudah dan masih banyak bermain. Tak ada
persamaan hak dalam keluarga seperti itu, tetapi di antara anak-
anak aturan mengenai persamaan dan persaudaraan telah cukup
dilaksanakan seperti makna yang terkandung di dalamnya."
Dengan kata lain, "apa yang dikatakan Bapak itu baik, karena Bapak
itu benar! Itulah keluarga ideal, begitu juga negara." Adalah Bapak/
yang bijaksana/pandita-ratoe yang mesti mengarahkan demokrasi
dan perkembangan kebudayaan Jawa.
***
SEPERTI nama jurnalnya Wederopbouw, yang artinya rekonstruksi,
nasionalisme Jawa seperti yang dianjurkan oleh Soetatmo
Soeriokoesoemo adalah ideologi restorasi yang dilihatnya sebagai
kunci untuk pembaharuan atas aturan sosial Jawa dan merupakan
jawaban atas demokrasi, partisipasi rakyat dalam politik. Soetatmo
menggarisbawahi pentingnya pandita/pandita-ratoe. Karena ia
percaya bahwa itu adalah tugas nasionalis Jawa untuk memainkan
peran pandita, bertanggung jawab atas opvoeding, pembinaan, dan
merestorasi kebudayaan Jawa dan bahwa tokoh pergerakan, yang
sering disebut satria (sebagai kebalikan dari pandita), hanya
menimbulkan kekacauan pada kebudayaan dan aturan sosial Jawa.
Pemikiran Soetatmo mengenai opvoeding (pembinaan/tut wuri
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
handayani), negara kekeluargaan dan pandita-ratoe yang bijaksana
memberi landasan pada teori Soewardi tentang demokrasi dan
leiderschap (kepemimpinan), yang pada akhirnya diwarisi oleh
Soekarno dalam rumusannya yang tertuang pada Demokrasi
Terpimpin.
Tjipto Mangoenkoesoemo, demokrat sejati, tidak setuju dengan
Soetatmo dan tetap mendukung ide nasionalisme Indies. Dalam
pandangannya, Soetatmo tidak mengerti perkembangan sejarah
dunia. Tidak diragukan lagi bahwa Indies terdiri dari banyak
kelompok etnis yang berbeda dalam budaya dan bahasanya seperti
yang dikatakan Soetatmo. Tetapi Jawa sudah lama kehilangan
kedaulatannya dan menjadi bagian dari Hindia Belanda yaitu Indies.
'Tanah air' orang Jawa bukan lagi Jawa, tetapi Indies dan adalah
tugas pemimpin nasional untuk merumuskan nasionalisme Indies.
Tjipto lantas menggambarkan nasion untuk Indiers sebagai landasan
masa depan Indies merdeka, sementara nasion Jawa seperti yang
dibayangkan Soetatmo berlandaskan identitas kebudayaan Jawa.
Tjipto tidak melihat inti kebudayaan Jawa dalam opvoeding,
pembinaan, ia malah menyebutnya sebagai Hinduisme, ko-
eksistensi antara rakyat dan dewa, sistem kasta, dan wayang.
Menurut dia, hinduisme menjadi halangan bagi perkembangan
kebudayaan Jawa. Contoh yang baik adalah sistem kasta, yang
masih memegang kokoh prinsip suksesi berdasarkan garis
keturunan untuk jabatan bupati. Sistem kasta ini menjadi pilar
pemerintahan Hindia Belanda dan hanya menimbulkan kesulitan
kreativitas bagi orang Jawa. Tetapi waktu telah berubah dan orang
Jawa harus berubah seiring dengan itu. Masa kejayaan Majapahit
telah lama berlalu. Restorasi kejayaan Majapahit tidak mungkin
menjadi tujuan untuk orang Jawa pada abad ke-20. Dan dalam
pandangannya bukan opvoeding, pembinaan, yang bisa
meningkatkan kesejahteraan rakyat juga. Yang penting dan harus
dilakukan orang Jawa adalah mempelajari ilmu pengetahuan Barat
untuk tujuan ini.
Dalam pandangan Tjipto, pendapat Soetatmo soal opvoeding,
pembinaan, cuma ilusi. Soetatmo mengatakan bahwa pandita mesti
mampu mengendalikan diri dan mengerti aturan-aturan Ilahi. Tjipto
tidak setuju, karena kebudayaan Jawa dalam pandangannya tidak
berhasil menekan egoisme walaupun menempatkan posisi yang
tinggi pada moral ketimbang materi dan juga tidak memberikan
ruang bagi materi untuk berkuasa di atas pengorbanan kehidupan
yang lebih bermoral. Sebaliknya, seseorang harus dapat memetik
pelajaran dari sejarah Jawa, katanya, bahwa orang-orang di masa
lampau melakukan praktik asketisme dan meditasi serta
mengendalikan nafsunya hanya untuk keselamatan anak-cucunya di
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
masa depan, biasanya tujuan konkretnya adalah mencari berkah
Tuhan, sehingga salah seorang dari keturunannya nanti akan
menjadi raja di tanah Jawa. Dalam pandangannya sama sekali
bukan opvoeding, pembinaan, yang akan menyumbangkan
kesejahteraan untuk rakyat banyak. Dan dalam pandangannya,
kebudayaan dan bahasa Jawa memang tidak berguna untuk tujuan
ini.
Lantas apa yang harus dilakukan, dalam perspektif Tjipto, untuk
perkembangan kebudayaan Jawa? Bagaimana pandangannya
tentang demokrasi dalam kaitan dengan kebudayaan Jawa? Tjipto
mengatakan bahwa orang Jawa sebaiknya bereinkarnasi menjadi
orang Indier sehingga kebudayaan Jawa mengambil alih karakter
baru secara total, karena kebudayaan Jawa dengan segala
elemennya yang sudah usang dan sekarang hanya menjadi
halangan bagi perkembangan rakyat akan mati dalam proses
transformasi orang Jawa menjadi orang Indier. Itu karena hinduisme,
seperti yang terwujud secara melembaga dalam sistem kasta, sejak
lama telah menekan kreativitas dan inisiatif rakyat. Rakyat hanya
bisa dibebaskan dari kematian moral ini jika kebudayaan Jawa
dihancurkan dan orang Jawa bereinkarnasi menjadi orang Indier.
Dalam pandangan Tjipto, merekonstruksi kembali kebudayaan Jawa
seperti yang dianjurkan Soetatmo adalah resep yang salah bagi
demokrasi dan perkembangan kebudayaan Jawa. Soetatmo lebih
melihat rakyat sebagai obyek yang harus diarahkan, kawulanya
Bapak/pandita-ratu yang bijaksana. Tjipto percaya bahwa rakyat
akan berubah sejalan dengan berjalannya sejarah dan partisipasi
orang banyak dalam politik, yang merupakan inti dari pergerakan
secara umum, memberikan tekanan atas transformasi orang Jawa
menjadi orang Indier.
Tjipto sepenuh hati menerima datangnya demokrasi dan melihat
perkembangan pergerakan sebagai lahirnya orang Indier. Siapakah
orang Indier? Dalam makalah yang diberikan pada acara Kongres
Indiers Pertama di Semarang pada 1913 dan diberi judul Beberapa
Pandangan tentang Jawa, Sejarah dan Etika, Tjipto menyerang
kolonialisme Belanda pada sisi otorianisme dan eksploitasi kapitalis
serta menyalahkan priyayi karena kehilangan integritas dan
otonominya karena menjadi bawahan Belanda dan bermain-main
dengan persoalan Jawa bagi kepentingan tuan mereka: Belanda.
Ia mengatakan, serangan dari penjajah Belanda dan Hindu Jawa
yang menghancurkan karakter bebas dan tegas yang semula dimiliki
orang Jawa, yang ujungnya berakhir pada kehancuran Jawa itu
sendiri. Melihat sejarah Jawa dalam perspektif ini, Tjipto lantas
bertanya, siapakah "kita" contohkan untuk hidup dalam masa yang
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
mengenaskan ini dan mendapatkan kembali keteguhan dan
kebebasan sebagai karakter. Dalam pandangannya, hal tersebut
terdapat dalam diri Dipanegara sebagai satria yang menentang
kehancuran moral. Menurut dia:
"Apa yang kita lihat pada Pangeran Dipanegara? Seorang
pemberontak biasa yang terdorong oleh nafsu meraih untung atau
ambisi telah menyerahkan negerinya pada apa yang jadi momok
bagi tiap orang-perang? Apakah fanatisme bodoh macam ini yang
membuatnya mengibarkan panji-panji pemberontakan? Saya
percaya, saya akan dibenarkan jika meniadakan pertanyaan ini. Ada
tugas mulia yang harus dilaksanakan. Ia merasa ditakdirkan untuk
melaksanakan tugas ini. Baik kalau begitu! Dengan energi dan
kegigihan luar biasa ia mengikuti arah hidupnya (yang sudah
ditakdirkan). Ia memang gagal. Tetapi, saya pikir Anda seperti juga
saya, tidak boleh menilai kerja orang semata dari keberhasilannya.
Di samping itu, memang bukan maksud saya menilai ketangguhan
Dipanegara. Saya hanya mau menunjukkan bahwa kebalikan
dengan apa yang dipercaya beberapa orang, orang Jawa itu
sebenarnya punya dasar etika yang dalam, suatu dasar untuk
membangun sumber moral yang mestinya membuat kita jadi optimis
akan kemungkinan bangkitnya zaman keemasan kita.
Perhatian Tjipto di sini adalah etika dan moral, sebagaimana ia
melihat Dipanegara sebagai satria yang menentang kehancuran
moral, ia mengajak audiensnya untuk bersikap seperti satria dan
meneguhkan karakter moralnya. Pandangannya tentang satria
sangat berbeda jauh dari pengertian asalnya, serta bebas dari
pengaruh hinduisme yang menekankan hanya kepada kualitas
moral.
Maka tidak mengherankan ketika mengetahui bagaimana ia melihat
reinkarnasi orang Jawa menjadi Indiers, kelahiran kembali Jawa,
harapannya agar Indies merdeka dari Belanda, dan feodalisme
Jawa. Dalam suratnya yang dikirimkan kepada kawan Belandanya
pada 1916, ia menulis:
"Mengapa orang Belanda, yang tidak bodoh dalam banyak hal,
ternyata telah menghabiskan banyak waktu sampai akhirnya sadar
ke mana ia harus melangkah beserta koloninya, padahal mestinya ia
bisa memikirkannya sejak dulu? Jawaban pertanyaan ini, saya pikir,
terutama karena sifat patuh orang Jawa, yang selalu bilang ja atau
amin pada apa pun yang dibebankan padanya tanpa prasangka
bahwa sebagai manusia ia juga punya hak asasi yang tak bisa
dikesampingkan begitu saja; di distrik-distrik gula khususnya, ia
demikian sering diinjak-injak. Singkatnya, karena kurangnya
semangat perlawanan (oppositiegeest) maka kita "tidak punya hak",
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
baik secara langsung maupun tidak.
Tanpa terasa saya sampai ke hal kedua yang ingin saya bicarakan
denganmu - sehingga kamu tidak salah menilai saya, misalnya
mengaitkan dengan sifat baik yang justru tidak ada pada saya.
Obat untuk penyakit apa pun sebenarnya sangat mudah jika
penyakitnya diketahui. Dalam kasus kami sekarang semuanya sudah
jelas, saya pikir, bahwa (masalahnya) karena kurangnya semangat
perlawanan. Budaya Jawa tak membolehkan munculnya kritik
terhadap kebijakan pemegang kuasa - sebaliknya, budaya ini
mengharuskan kita tunduk tanpa syarat pada pandangan penguasa.
Soesoehoenan, misalnya, boleh menyatakan bahwa ia adalah
keturunan Adam dan Arjuna, semata-mata untuk menjadikan dirinya
berasal dari sumber yang suci dan hebat, sehingga ia bisa
mengontrol kita dan membuat kita merasa sebagai manusia biasa,
keturunan kromo atau Soeto yang tidak akan berhasil dalam setiap
pemberontakan. Oleh karena dewa-dewa adalah nenek moyang
Soesoehoenan maka tak perlu dibilang bahwa mereka jelas
membela pemegang kuasa ini.
Akan tetapi, izinkan saya kembali menjelaskan obat kami. Saya bisa
bilang bahwa itu tak lain adalah "pengorganisasian rasa tidak puas",
sama seperti yang akan dikatakan De Locomotief. Oposisi harus
dilakukan terhadap pemegang kuasa, dengan wajar dan jika
mungkin dengan pengetahuan (nyata) tentang hal-hal tersebut.
Tetapi, jika terbukti tidak bisa, oposisi demi oposisi semata. Tolong
jangan anggap ini sebagai ekspresi antipati saya terhadap dominasi
Belanda, sebab saya pun akan tetap beroposisi jika orang Jawa
yang berkuasa. Kamu tahu lebih banyak dari pada saya bahwa di
dalam BB (Binnenlandsch Bestuur), misalnya, ada pejabat-pejabat
yang luar biasa takutnya terhadap kritik yang tajam. Jujur saja, inilah
alasan mengapa saya justru melakukannya (yaitu mengekspresikan
kritik yang tajam) pada tempat pertama, kedua, dan ketiga.
Betapapun, kekhawatiran adalah cara yang baik untuk mencegah
terjadinya penyimpangan kekuasaan."
Tidak perlu komentar panjang mengenai apa yang dikatakan Tjipto.
Itu adalah pembentukan karakter, menempa orang Jawa menjadi
satria seperti Dipanegara dengan cara menghadapkan mereka pada
serangkaian kesulitan dan kesusahan, yang dianggap Tjipto sebagai
obat untuk "orang Jawa yang mudah diatur". Dan ia melihat bahwa
satria Indiers yang bereinkarnasi akan menjadi landasan bagi
kemerdekaan Indies.
***
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Tjipto-Soetatmo-Soekarno -- Jumat, 1 Juni 2001
SUDAH jelas kiranya bahwa Soekarno mewarisi dua aliran pemikiran
yang berkembang pada nasionalis generasi pertama seperti yang
diwakili Soetatmo dan Tjipto. Tetapi Soekarno bukanlah pemikir, ia
adalah seorang yang mementingkan tindakan. Maka ia menyerap
segala hal walaupun itu mengandung kontradiksi di dalamnya, tesis
dan antitesis semua, yang kemudian terwujud secara berbeda-beda
dalam hidupnya.
Pada tahun 1920-an, ketika bersama Tjipto, Soekarno bicara seperti
Tjipto, menyuarakan perlunya national spirit ditempa menjadi
national will yang akhirnya akan mewujud dalam bentuk aksi
nasional. Pada masa 1960-an, sebaliknya, ia menyuarakan
Demokrasi Terpimpin, yang didapatnya dari konsep demokrasi dan
leiderschap (kepemimpinan) dari Ki Hadjar Dewantara, yang sangat
dipengaruhi oleh visi Soetatmo mengenai negara kekeluargaan di
bawah kendali Bapak/yang bijaksana/pandita-ratu.
* Takashi Shiraishi, Profesor Ilmu Sejarah di Universitas Kyoto,
Jepang.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
● Soekarno, Ketika Nasionalisme Letih
● Dekrit Presiden, Revolusi, dan Kepribadian Nasional
● "Permintaan Maaf" Soekarno pada Pemerintah Kolonial
Belanda
● Hatta Tak Pernah Kembali sebagai Dwitunggal
● Bhinneka Tunggal Ika dan"Passing Over" Spiritualitas Bung
Karno
● Antikolonialisme dan Anti-elitisme dalam Pemikiran Soekarno
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Tjipto-Soetatmo-Soekarno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (9 of 10)4/3/2005 11:05:22 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
English Nederlands
>Jumat, 1 Juni 2001
Ziarah Kubur Bung Karno
Emmanuel Subangun
HIKMAH dari kehidupan bersama dalam negara Indonesia selama
lebih dari separuh abad ini adalah tak terbantahkannya kenyataan
bahwa kekuasaan politik tidak pernah bersifat tunggal, melainkan
selalu bersifat ganda, tak menentu. Bung Karno sebagai orang
pergerakan, karena itu, juga harus diterima dalam watak
majemuknya. Selalu ada sifat tak terduga, atau mungkin diabolik,
dalam sepak terjangnya, dan hal itu mudah dimengerti asalkan kita
bisa membaca dengan baik naskah yang dia tulis (atau pidato yang
dia ucapkan), tindakan yang dia lakukan, dan akibat politik yang dia
timbulkan.S ehingga dengan demikian, dari awal kita melihat bahwa
cara baca kita terhadap Bung Karno bukanlah cara baca yang naif-
maka tulisan ini berjudul Ziarah Kubur Bung Karno- tetapi
sepenuhnya adalah tulisan yang bersifat atau mengandung cacat.
Tidak netral seperti bayi, tapi adalah bacaan atas Bung Karno seperti
pikiran, perasaan, dan tindakan yang dilakukan oleh jutaan warga
masyarakat yang datang ke Blitar, di mana Bung Karno tidur untuk
selamanya. Dia tidak musnah, tidak lenyap, tapi semata pralaya,
semata berpindah ke alam yang lain, dan mereka yang hidup masih
dan selalu punya kesempatan untuk bertemu, mengeluh atau
mungkin minta petunjuk dan pelipur hati.
Bacaan atas Bung Karno, dalam keadaan alam pergerakan
Indonesia hari-hari ini, tidak mungkin untuk ditelaah semata-mata
secara obyektif, dalam asas paling pokok dari positivisme alias otak
adalah cermin yang bersih, dan lewat konsep-konsep yang dibentuk
oleh akal, lalu benda-benda di luarnya ditangkap secara netral,
karena benda-benda itu bisa dibagi menjadi dua dan hanya dua,
yakni res extensa dan res cogitans. Hal pertama dalam fakta dan
data, dan hal kedua adalah makhluk manusia yang berpikir dan
hanya berpikir. Alam berpikir modern Cartesian seperti ini jelas tak
memadai untuk kepentingan kita hari-hari ini. Akan jauh lebih
memadai pola pikir yang sepenuhnya tradisional, yakni alam pikir
metaforik yang menarik makna dari perasaan, dari metafor, dari
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (1 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
pengalaman, dan bukan dari konsep, dari analisa abstrak.
Pengalaman kita bernegara selama ini telah memberi hikmah yang
penting. Dari zaman Bung Karno sudah amat jelas bahwa sebuah
political goodwill tidak memadai untuk menggerakkan sebuah
bangsa keluar 100 persen dari negara kolonial. Dan pengalaman
selama Orde Baru memberi pelajaran amat berharga bahwa negara
modern yang bersendi pada tentara dan pegawai negeri adalah
sebuah anakronisme sejarah: hendak keluar dari negara kolonial,
tetapi dengan menghidupkan sebuah negara pegawai
(beamtenstaat). Dan masa transisi yang kita alami sekarang
memberikan wajah amat pasti bahwa sebagai bangsa dan negara,
sebuah unit yang bernama Indonesia itu, sekarang sedang dalam
krisis konjungtural, struktural, dan politik. Artinya, dari segi tatanan
world system, kejatuhan rezim bisa dilihat sebagai keteledoran
dalam investasi dan pengelolaan valuta asing, yang lalu memiliki
efek domino.
Dana menganggur dari pasar modal dunia secara sembrono ditelan
mentah-mentah oleh para kapitalis semu kita, dan akhirnya
membawa keruntuhan ekonomi. Sementara di dalam negeri
rapuhnya sistem politik segera tak bisa disembunyikan lagi ketika
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) semakin jelas
bukan semata-mata sebagai alat negara, tapi sepenuhnya alat
penguasa. Dan, karena itu juga sebagai alat penguasa tentara tidak
bisa dipisahkan dari sejuta kepentingan yang berkecamuk di dalam
negeri-artinya bukan semata-mata dwifungsi, tapi multifungsi!-
sehingga posisi khususnya juga runtuh. Akhirnya perimbangan
kekuasaan "istana presiden" yang berubah menjadi "istana raja"
Jawa semakin tidak peka pada pergeseran zaman. Sehingga secara
politik memang tidak bisa bertahan lagi.
Dalam keadaan semacam itulah, saya membaca sejarah, naskah
dan ingatan akan Bung Karno. Bukan bacaan cartesian, bukan
bacaan lawan/kawan secara ideologis, tapi adalah bacaan yang
paling tradisional. Metaforik, semacam ziarah kubur. (1)
Politik aliran dan golongan
Salah satu budaya politik amat penting yang dibawa oleh tentara
dalam sistem politik di Indonesia adalah sebuah budaya elite yang
menggantikan budaya pelopor. Dengan menjadikan massa rakyat
sekadar sebagai penonton yang boleh berpolitik sekali dalam lima
tahun dalam "pesta demokrasi", maka selain ritualisme politik, hal
lain adalah pergeseran pengertian politik yang setali tiga uang
dengan barang najis. Elitisme politik berakibat pada penajisan politik.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (2 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
Dan, hal ini harus dipahami dalam hubungan dengan soekarnoisme.
Soekarnoisme secara deskriptif bisa dibaca dari kutipan kisah seperti
ini:
"Megapa Anda tidak membubarkan PKI?" tanya saya kepada
Soekarno ketika saya berkunjung ke Indonesia, beberapa minggu
sebelum ia dipecat (Soekarno diturunkan Maret 1966).
"Kita tidak dapat menghukum suatu partai secara keseluruhan
karena kesalahan beberapa orang," jawabnya. Saya katakan
padanya bahwa ia telah dapat melakukannya dalam tahun 1960,
ketika ia melarang Masjumi dan PSI.
"Masjumi dan PSI," jawabnya, "telah merintangi penyelesaian
revolusi kami. Akan tetapi, PKI merupakan pelopor kekuatan-
kekuatan revolusi. Kami membutuhkannya untuk pelaksanaan
keadilan sosial dan masyarakat yang makmur."
Saya bertanya, apakah ia masih merasa yakin bahwa konsepnya
mengenai Nasakom, konsep pemersatuan golongan-golongan
nasionalis, agama dan komunis, pada dasarnya benar.
Ia menjawab, "Ya". (2)
Apa yang dikatakan Soekarno tahun l960 itu tetap merupakan
pernyataan keyakinan politik yang dituliskan tahun 1926. Keyakinan
akan pentingnya sebuah partai pelopor yang tidak bisa diperankan
oleh satu partai saja, tetapi harus dibagi peran oleh tiga unsur pokok
yang disebut agama, nasionalis dan komunis yang semua itu
mendapatkan perumusan paling utuh dan menyeluruh dalam dasar
negara Republik Indonesia yang disebut Pancasila!
Dengan demikian amatlah tidak sederhana untuk menafikan Bung
Karno semata-mata sebagai seorang makhluk Jawa yang tidak
mampu berpikir secara rasional, dan dengan menggunakan selera
kepentingan lalu mencari dan menggabungkan apa saja yang
disangka baik, lalu dipadukan sebagai sebuah pandangan hidup.
Kegentingan masalah partai pelopor bukanlah masalah selera, tetapi
masalah himpitan struktural yang tidak mungkin dihindarkan. Dalam
naskah tahun 1926 itu Bung Karno menyebut sebuah via dolorosa
yang harus sepenuhnya disadari, jika partai pelopor itu dilupakan.
Dalam bahasa kaum strukturalis, mereka yang melihat Soekarno
hanya menjalankan model berpikir sinkretis sepenuhnya
menjalankan praktik baca yang disebut oversight, artinya melihat tapi
tak suatu pun yang tampak, karena dalam mencari adequatio rei et
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (3 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
intellectus yang disebut terakhir itu adalah sistem konsep yang
dibangun dalam dan dari pengalaman sejarah negeri dan waktu
yang lain. Demokrasi dengan seluruh uraian ideologis yang
menyertainya sepenuhnya, tidak mungkin dimengerti tanpa sejarah
panjang pembentukan negeri nasional di Eropa, sejarah feodalisme,
ekspansi kapitalisme dan konflik perang dingin.
Nalar pergerakan tidak dapat dilihat secara berjenjang dalam
hubungan dengan nalar "kebenaran" seperti ditata dalam filsafat,
atau disusun dalam dogma agama. Apalagi sekadar ditilik secara
dangkal dengan meninggalkan sinoptik seluruh weltanshauung yang
tak lain akan menjadi api ideologi yang menggerakkan perubahan
masyarakat untuk keluar dari orde kolonial.
Hanya saja ketika tahun 1960-an Soekarno tetap bertahan dengan
Front Persatuan, dia tidak terlalu jeli melihat konflik yang tak
terkendali antara kepentingan politik militer, dengan sayap dalam
sistem politik aliran dan golongan. Soekarno telah menjadi
anakronik.
Sinkretik atau tidak, bukan itu masalah bagi soekarnoisme dalam
sejarah pergerakan. Tetapi pertanyaannya terletak di tempat lain:
mampukah ide fixed "persatuan kesatuan" mengantarkan 200 juta
rakyat untuk keluar dari sebuah rezim kolonial yang tetap bercokol
sampai hari ini?
Upaya untuk membangun sejumlah partai pelopor yang dengan
terus-menerus dijaga oleh Soekarno selama 40 tahun pada akhirnya
sampai pada titik buntu. Dan sementara pikiran itu tidak pernah mati,
sistem politik yang menggantikannya adalah sistem elitis yang
terbukti hari-hari ini kita menuai hasilnya. Malapetaka!
Masyarakat madani
Demi sebuah perbandingan dapatlah kita ambil sebuah naskah dan
pemikiran revolusioner yang lain dari Rusia. Gagasan pergerakan
tetap pada partai pelopor, dan rumusan masalah diletakkan dalam
silogisme yang ketat, yang jika ditanggalkan dari semua kerumitan
akhirnya akan muncul hal seperti ini: Akar masalah dunia modern
adalah ditetapkannya hak milik pribadi sebagai mutlak dan universal.
Hak milik pribadi hanya akan bisa dihapuskan dengan hak milik
bersama. Dan hak milik bersama dijalankan oleh negara.
Oleh karena itu, perjuangan politik paling tinggi adalah merebut
kekuasaan negara dari para pembela hak milik pribadi dan
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (4 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
mengalihkannya pada fungsi-fungsi rasional dalam sistem negara.
Sehingga pada giliran terakhir relevansi "negara" juga hilang, dan
kita hidup dalam "masyarakat". (3)
Dalam teori negara sebagai "alat" penindas seperti itu, memang kita
bisa meletakkannya dalam uraian yang nonsinkretik, karena dari
awal memang dimulai dari silogisme, atau hukum sebab-akibat,
propter/ergo.
Asal saja kita tahu bahwa sejarah Rusia adalah sejarah negara
predator terhadap masyarakat, sebetulnya juga tidak menjadi terlalu
sulit untuk akhirnya kita saksikan pergantian teori negara
instrumentalis ini digantikan dengan konsep negara yang nonkausal,
yang lazim disebut sebagai hubungan negara/masyarakat yang over-
determinatif, artinya hubungan yang melingkar dan seakan-akan tak
langsung antara masyarakat dan negara, sehingga sifat gerakan
politik juga harus menjadi lain sama sekali.
Di Eropa Timur sifat gerakan politik itulah yang disebut dengan
gerakan masyarakat sipil, yang sepenuhnya adalah selundupan
konsep demokrasi dalam sistem otoriter Eropa Timur: masyarakat
yang tidak dipilah dalam garis ideologi (komunis/ nonkomunis), dan
hubungan terbalik masyarakat dan negara. Dan dalam penerapan
sistem politik adalah diperkenalkannya sistem multipartai. (4)
Akan terlalu frontal jika terhadap masyarakat yang baru terbebas dari
sistem komunis, lalu diperkenalkan sebuah sistem yang diberi nama
"kapitalis". Sehingga, meskipun isi ideologi dari masyarakat sipil tak
lain adalah kapitalisme yang cocok untuk Eropa Timur, tidaklah
terlalu mengherankan jika istilah tersebut diambil alih oleh wacana
politik di Indonesia berdasar atas paralelisme pengalaman
psikohistoris antara Indonesia dan Eropa Timur, dengan prakarsa
penuh dari para teknokrat politik Amerika Serikat.
Anehnya, tak seorang pun pernah mempersoalkan bahwa
masyarakat sipil alias madani itu sama anakroniknya dengan front
persatuannya Bung Karno di tahun 1960-an, dalam arti sekarang ini
masyarakat sipil sesuai dengan kepentingan dan wacana ideologis
Amerika Serikat, sedangkan Nasakom, dari awal memang tidak
sesuai dengan kepentingan kapitalisme global seperti itu. Dan
dapatkah Anda membayangkan bagaimana hal itu mungkin terjadi,
sebuah negeri kapitalis pinggiran seperti Indonesia yang hancur
lebur dalam proses penataan ulang sistem kapitalisme global, melalu
jalur pendek yang disebut saluran finansial dan utang, lalu sejumlah
elite nasionalnya sibuk berucap litani tentang kemudaratan
masyarakat sipil, sebuah konsep impor bikinan luar untuk obat
penenang di Eropa Timur itu?
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (5 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
Sejarah negara kita adalah sejarah negara jajahan. Negara jajahan
bukan saja negeri itu diperas untuk negeri induk, tetapi jauh lebih
mendalam dari itu semua, selalu tumbuh anggapan bahwa anak
negeri jajahan adalah sekadar manusia setengah dewasa, yang
tidak mampu berpikir mandiri, bertindak bebas dan bertanggung
jawab. Negara jajahan adalah sebuah penghinaan sejarah atas
harkat kita sebagai manusia, dan bukan semata masalah ekonomi,
politik atau budaya.
Apa yang salah dengan orang Jawa?
Lazimnya orang akan mengatakan bahwa nalar sinkretik amat
dominan pada Suku Jawa, karena suku inilah di Nusantara yang
secara tuntas mengalami penjajahan dan dalam sejarah yang
panjang mengenal gelombang besar peradaban dunia, mulai dari
Hindu/Buddha, Islam dan juga ilmu politik modern. Karena Suku
Jawa ini juga merupakan warga terbesar dari negara Indonesia,
maka seakan teori antropologi gaya Geertz yang trikhotomis (santri,
abangan, priayi) juga bisa menjelaskan proses involutif dari gerak
masyarakat Indonesia.
Dalam bidang politik, semua tinjauan itu hanya menjadi pengetahuan
umum, sejenis common sense yang harus diterima sebagai
"anggapan umum", dan tetap diterima sebagai "anggapan". Sebab,
seperti kita kenal dalam dasawarsa 1970-an dan 1980-an, seakan-
akan program westernisasi itu sudah mencapai titik puncaknya, dan
semua berbicara atas nama negeri industri baru (5), seakan-akan
Indonesia telah menjadi bagian integral, tanpa masalah, dengan
sistem kapitalis global.
Kenyataan hari-hari ini adalah kenyataan yang pahit. Negara dengan
pengalaman dijajah secara habis-habisan mengidap penyakit yang
sangat tidak mudah disembuhkan: negara selalu dimengerti dalam
kaitan rapat dengan bangsa. Sementara negara tak lebih merupakan
sebuah unit dari sistem negara dunia, maka bangsa adalah struktur
pengalaman yang jauh lebih mendalam. Negara harus bisa
menjamin rasa berbangsa, dan masalah ini menjadi mendesak atau
tampak amat mendesak jika dibandingkan dengan sejarah bahwa
Asia lain yang tidak mengenal penjajahan seperti Thailand, Jepang,
Korea atau bahkan Cina. Mereka yang tidak mengalami sindrom
westernisasi ini tidak menderita luka sejarah-via dolorosa-seperti
harus kita terima bersama.
Soekarno mengerti, menjalani, berjuang dan wafat dalam via
dolorosa itu. Bukan semata sebagai warga Suku Jawa yang
irasional, sinkretik dan keras kepala. Sebagai orang pergerakanlah
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (6 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
harga Soekarno dalam sejarah Indonesia mesti ditorehkan.
Sekali lagi, saya membaca Soekarno secara tradisional (metaforis)
dengan mengandalkan pada ingatan, bacaan dan harapan, dan
bukan dalam cara baca modern (obyektif) yang menerapkan sebuah
konsep lain yang lebih sistematis untuk membaca Soekarno yang
sinkretis, juga bukan cara baca pascamodern (simulatif), yang
mengambil Soekarno sebagai sekadar naskah yang memburat dan
terburai.
Oleh karena itu, sepantasnya pula jika tulisan ini ditutup dengan
baris-baris terakhir naskah pemimpin bangsa dan negara itu dari
tahun 1926 tersebut tentang persatuan dan kemerdekaan:
"Kita harus bisa menerima, tetapi juga harus bisa memberi. Inilah
rahasianya persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi, kalau masing-
masing fihak tak mau memberi sedikit-sedikit saja.
Dan jikalau kita semua insyaf bahwa kekuatan hidup itu letakan tidak
dalam menerima, tetapi dalam memberi, jikalau kita semua insyaf
bahwa dalam percerai-beraian itu letaknya benih perbudakan kita,
jikalau kita semua insyaf bahwa permusuhan itulah yang menjadi
asal kita punya "via dolorosa"; jikalau kita insyaf bahwa roh rakyat
kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju sinar yang
satu yang berada di tengah-tengah kegelap-gumpita yang menglilingi
kita ini maka pastilah persatuan itu terjadi, dan pastilah sinar itu
tercapai juga.
Sebab sinar itu dekat!"
Dan, kita menelan kepahitan itu: ternyata sinar itu semakin menjauh,
hari-hari ini.
* Emmanuel Subangun Pengamat sosial politik, direktur Alocita,
Yogyakarta.
Rujukan:
(1) Cara baca cartesian yang menjadi dasar segala rupa positivisme
mengandaikan res cogitans itu ibarat cermin. Semakin bersih dan
berkilau cermin itu, akan semakin "obyektif" bacaan kita. Disebut
bacaan "bebas nilai". Cara baca yang lain adalah bacaan
strukturalis, atau malah pasca strukturalis, lihat Althuser, Louis et al,
Lire Le Capital, Petite Collection Maspero,1968, Paris, dan juga
Baudirallard, Jean, Le System des objets, Denoel-Gonthier, Paris,
1968.
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (7 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Ziarah Kubur Bung Karno -- Jumat, 1 Juni 2001
(2) Banyak buku ditulis mengenai Soekarno, tetapi karya Bernard
Dahm adalah salah satu yang utuh melihat tokoh ini secara kultural
dan meletakkan dalam sejarah Ratu Adil, sehingga dengan
sendirinya muncul kesimpulan sifat sinkretik dari gagasan Soekarno.
Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, LP3ES, 1987, Jakarta, p.
XIV. Dan Onghokham yang memberi pengantar dalam edisi
Indonesia juga sudah mempersoalkan cara pandang kultural Dahm.
Tulisan utama yang menjadi acuan pemikiran saya adalah buah
pena Bung Karno tahun 1926 yang dimuat di Suluh Indonesia Muda,
berjudul Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, dimuat dalam
bagian pertama buku Di Bawah Bendera Revolusi, 1965, Jakarta,
pp.1-23
(3) Teori withering away the state adalah doktrin resmi marxisme
ortodoks, yang kemudian banyak menemukan rumusan baru dalam
tahun 70-an, di Eropa. Naskah klasik untuk negara instrumental itu,
lihat Lenin, N, The State and Revolution, 1917, Petrograd.
(4) Salah satu buku untuk masyarakat sipil, lihat Hefner, RW,
Democratic Civility, New Jersey, 1998. Dan kaitan dengan krisis
komunisme yang melanda Eropa Timur lihat Drach. Marcel Le Crise
dans les pays de L'est, Editions de la Decouverte,1984, Paris.
(5) Optimisme palsu dan hiperbolik tentang Indonesia dan Asia bisa
dilihat dalam buku Naisbitt, John, Megatrends Asia, Simons and
Schuster, New York, 1996, setahun sebelum krisis menyapu negara
kita.
Berita nasional lainnya :
● Satu Abad Bersama Nusantara dan Nusantara Bersama
Soekarno
● Latar Belakang Sosio-kultural Dunia Kanak-kanak dan Masa
Muda Bung Karno
● Bung Besar, Ideolog yang Kesepian
● Bung Karnodan Tiga Pelukis Istana
● Bung Karno, Arsitek-seniman
● Peristiwa G30S, "Titik Balik" Soekarno
● Bung Karno, Perjalanan Panjang Menuju G30S
● Di Seberang Jembatan Emas
● Kepentingan Bangsa Vs Kepentingan Perempuan
● Dari Siti Oetari sampai Yurike Sanger
● Soekarno, Persatuan Nasional, Orde Lama, dan Orde Baru
file:///D|/100%20Tahun%20Bung%20Karno/Ziarah%20K...Bung%20Karno%20--%20Jumat,%201%20Juni%202001.htm (8 of 9)4/3/2005 11:05:23 AM
Anda mungkin juga menyukai
- Citra Indonesia Di Mata Dunia ADokumen366 halamanCitra Indonesia Di Mata Dunia ABudi Santoso DarmawanBelum ada peringkat
- Makalah Bela NegaraDokumen12 halamanMakalah Bela NegaraOon Sayank Iin100% (2)
- Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan KedaulatanDokumen141 halamanSejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo Sampai Dengan Pengakuan KedaulatanDumora FatmaBelum ada peringkat
- Budhy Munawar-Rachman - Agama Dan DemokrasiDokumen24 halamanBudhy Munawar-Rachman - Agama Dan Demokrasimobil bututBelum ada peringkat
- Tugas HAM Kasus MunirDokumen13 halamanTugas HAM Kasus MunirSeru PojiBelum ada peringkat
- TRISAKTIDokumen13 halamanTRISAKTIHesti Wihanda FardaBelum ada peringkat
- Kaum Muda Muslim Milenial 2018Dokumen294 halamanKaum Muda Muslim Milenial 2018Santi RahmaBelum ada peringkat
- Suara Di Balik Prahara - Cetak PDFDokumen398 halamanSuara Di Balik Prahara - Cetak PDFMoko CorpBelum ada peringkat
- Sejarah Gerakan Buruh IndonesiaDokumen94 halamanSejarah Gerakan Buruh Indonesiasupeer yorBelum ada peringkat
- Para Tokoh Perumus Dan Penyusun UndangDokumen15 halamanPara Tokoh Perumus Dan Penyusun UndangAsriyadi LaganiBelum ada peringkat
- Gus Dur Dan Ilmu Sosial Transformatif Sebuah Biografi Intelektual PDFDokumen344 halamanGus Dur Dan Ilmu Sosial Transformatif Sebuah Biografi Intelektual PDFzeppenator_men9730% (1)
- ARAH TATANAN BARU AtevhaDokumen161 halamanARAH TATANAN BARU AtevhaHendryBelum ada peringkat
- Pengantar FilsafatDokumen168 halamanPengantar FilsafatRio SalenussaBelum ada peringkat
- B. Herry Priyono-Agenda IndonesiaDokumen22 halamanB. Herry Priyono-Agenda Indonesiagogol20xxBelum ada peringkat
- Teori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial by WahyudiDokumen158 halamanTeori Konflik Dan Penerapannya Pada Ilmu-Ilmu Sosial by WahyudiDhiny WidyadaryBelum ada peringkat
- Ensiklopedia BPS PDFDokumen254 halamanEnsiklopedia BPS PDFJony Chandra0% (1)
- Upaya Diplomasi Preventif Indonesia Dalam Sengketa Kepulauan SpratlyDokumen15 halamanUpaya Diplomasi Preventif Indonesia Dalam Sengketa Kepulauan SpratlyEduardus (Eduard)Belum ada peringkat
- Kh. Hasyim Asyari Biografi SingkatDokumen148 halamanKh. Hasyim Asyari Biografi Singkatlilix arifinBelum ada peringkat
- Hubungan Internasional Di Asia TimurDokumen181 halamanHubungan Internasional Di Asia TimurRina JunitaBelum ada peringkat
- Perkembangan Pemikiran Modern Dalam IslaDokumen218 halamanPerkembangan Pemikiran Modern Dalam IslaOktarisanti Syahda PutriBelum ada peringkat
- Filsafat Politik-1Dokumen304 halamanFilsafat Politik-1Alif Abdullah ZakariaBelum ada peringkat
- Naskah1424835068 PDFDokumen413 halamanNaskah1424835068 PDFAhmad JaelaniBelum ada peringkat
- KeindonesiaanDokumen18 halamanKeindonesiaanMfh GarritsenBelum ada peringkat
- BKSudibyoDokumen7 halamanBKSudibyoAl AyyubiyBelum ada peringkat
- Menangkal Radikalisme Dalam PendidikanDokumen158 halamanMenangkal Radikalisme Dalam PendidikanMuhammad FakhruddinBelum ada peringkat
- Ketuhanan Yang Maha Esa Perspektif Lintas ImanDokumen555 halamanKetuhanan Yang Maha Esa Perspektif Lintas Imanff abramBelum ada peringkat
- Islam Borju & ProletarDokumen5 halamanIslam Borju & ProletarIskandar ZulkarnaenBelum ada peringkat
- Agar Anda Terhindar Dari Jerat Korupsi PDFDokumen134 halamanAgar Anda Terhindar Dari Jerat Korupsi PDFAkhir ZamanBelum ada peringkat
- 1 4 PBDokumen149 halaman1 4 PBalfia lovitania kBelum ada peringkat
- Post Sekularisme 1Dokumen204 halamanPost Sekularisme 1Ferdiansyah SopandiBelum ada peringkat
- Reformasi 1998Dokumen15 halamanReformasi 1998Mohammad Yusuf Yuwana ArifBelum ada peringkat
- Sejarah Berdirinya Organisasi Otonom MuhammadiyahDokumen85 halamanSejarah Berdirinya Organisasi Otonom MuhammadiyahSai HeviBelum ada peringkat
- Edisi Khusus Desember 2020 FullDokumen308 halamanEdisi Khusus Desember 2020 FullasanBelum ada peringkat
- Intoleransi Dan Politik Identitas Di Indonesia PDFDokumen379 halamanIntoleransi Dan Politik Identitas Di Indonesia PDFJejak DataBelum ada peringkat
- Hasil MUSPIMCAB PC. PMII Kota Bandung 2020 (Final) - 1Dokumen72 halamanHasil MUSPIMCAB PC. PMII Kota Bandung 2020 (Final) - 1Sandi NugrahaBelum ada peringkat
- Pergolakan Ideologi Munculnya PemberontaDokumen10 halamanPergolakan Ideologi Munculnya PemberontaKanti Warih Ade IndrianiBelum ada peringkat
- IsiDokumen262 halamanIsiAnonymous wY4gI6bqv8Belum ada peringkat
- Sebuah Biografi TjokroaminotoDokumen29 halamanSebuah Biografi TjokroaminotoHeru PrabowoBelum ada peringkat
- Ancaman & Strategi Penanggulangan Terorisme PDFDokumen192 halamanAncaman & Strategi Penanggulangan Terorisme PDFDorpaima stc100% (1)
- Kapita Selekta Filsafat Dan Teori TeoriDokumen286 halamanKapita Selekta Filsafat Dan Teori TeoriIrawan SonyBelum ada peringkat
- Memahami Politik Persahabatan Jacques DerridaDokumen14 halamanMemahami Politik Persahabatan Jacques DerridaLuki LukmanBelum ada peringkat
- Suara Bawah Tanah 11Dokumen48 halamanSuara Bawah Tanah 11Beno Aji100% (1)
- Makalah Konflik Sampit Antara Suku Dayak Dan Suku Madura CompressDokumen12 halamanMakalah Konflik Sampit Antara Suku Dayak Dan Suku Madura CompressAhmad MuhajirBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah Perjuangan HMI - Ricky BrahmanaDokumen22 halamanMakalah Sejarah Perjuangan HMI - Ricky BrahmanaRicky BrahmanaBelum ada peringkat
- Ebook-Doktrin Zionisme & Ideologi PancasilaDokumen82 halamanEbook-Doktrin Zionisme & Ideologi PancasilaYudhi Dwi KurniawanBelum ada peringkat
- Proses Perumusan Dan Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaDokumen5 halamanProses Perumusan Dan Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaAbdillah Taqiuddin RifqiBelum ada peringkat
- Modul I Konsepsi Bela Negara PDFDokumen224 halamanModul I Konsepsi Bela Negara PDFAshadaBelum ada peringkat
- Civil Society Melacak Arti, Menyimak Implikasi PDFDokumen13 halamanCivil Society Melacak Arti, Menyimak Implikasi PDFilham muktiBelum ada peringkat
- Bab 3 Bentuk Kedaulatan NegaraDokumen32 halamanBab 3 Bentuk Kedaulatan NegaraYadi Aprianto Dua100% (1)
- Membela Kebebasan Beragama 1Dokumen589 halamanMembela Kebebasan Beragama 1hmi100% (1)
- Vol 8 No 2 Desember 2013Dokumen255 halamanVol 8 No 2 Desember 2013Mahdi AsnaniBelum ada peringkat
- Trip Sekolah Megan: Roh Pemandu, Roh Harimau, Dan Seorang Ibu Yang Menakutkan!Dari EverandTrip Sekolah Megan: Roh Pemandu, Roh Harimau, Dan Seorang Ibu Yang Menakutkan!Belum ada peringkat
- Menuai Apa yang Kami Tabur 2: Menuai Apa yang Kami Tabur, #2Dari EverandMenuai Apa yang Kami Tabur 2: Menuai Apa yang Kami Tabur, #2Belum ada peringkat
- Antikolonialisme Dalam Pemikiran SoekarnoDokumen1 halamanAntikolonialisme Dalam Pemikiran SoekarnoAgus Oh AgusBelum ada peringkat
- Pemikiran Politik Masa RevolusiDokumen26 halamanPemikiran Politik Masa Revolusiraragiani0% (1)