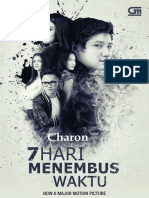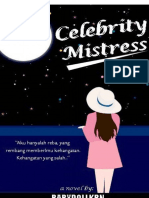Wahai Azarine
Diunggah oleh
Deasy Oka0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1K tayangan21 halamanAnita Cendana terdampar di desa terpencil di Nusa Tenggara Timur untuk mengabdi sebagai dokter relawan. Dia merasa kesepian dan bosan menunggu di depan gubuk tua tanpa sinyal internet. Ayahnya menawarkan untuk menjemputnya pulang ke Jakarta jika dia tidak nyaman, namun Anita memutuskan untuk tetap tinggal.
Deskripsi Asli:
Judul Asli
WAHAI AZARINE
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniAnita Cendana terdampar di desa terpencil di Nusa Tenggara Timur untuk mengabdi sebagai dokter relawan. Dia merasa kesepian dan bosan menunggu di depan gubuk tua tanpa sinyal internet. Ayahnya menawarkan untuk menjemputnya pulang ke Jakarta jika dia tidak nyaman, namun Anita memutuskan untuk tetap tinggal.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1K tayangan21 halamanWahai Azarine
Diunggah oleh
Deasy OkaAnita Cendana terdampar di desa terpencil di Nusa Tenggara Timur untuk mengabdi sebagai dokter relawan. Dia merasa kesepian dan bosan menunggu di depan gubuk tua tanpa sinyal internet. Ayahnya menawarkan untuk menjemputnya pulang ke Jakarta jika dia tidak nyaman, namun Anita memutuskan untuk tetap tinggal.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 21
LEMBARAN PERTAMA
DISCLAIMER
SELURUH NAMA, KARAKTER, TEMPAT, DAN KEJADIAN DI DALAM
CERITA INI ADALAH FIKTIF. TIDAK TERJADI DI DUNIA NYATA.
HARAP BIJAK DALAM MENYIKAPI. APABILA TERDAPAT KESAMAAN
TOKOH ATAU PERISTIWA MAKA ITU HANYA KEBETULAN SEMATA,
TIDAK ADA UNSUR KESENGAJAAN. CERITA INI DIBUAT UNTUK
KEPENTINGAN PUBLIKASI, HIBURAN DAN PEMBELAJARAN SEMATA.
•••
CAST
•••
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan rela
berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.
Tanah air Indonesia.”
Hamdi Ar Rayyan
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan
hidup saya guna perikemanusiaan tidak terpengaruh oleh
pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender,
politik dan kedudukan sosial.”
Anita Cendana
•••
CREDIT
Segala bentuk gambar, gif, serta ilustrasi yang
dibagikan dalam di dalam cerita bukan milik saya, saya
hanya meminjam. Thanks to the owner/company
[01] Prolog
"Nama tokoh, tempat kejadian, konflik ataupun cerita
adalah fiktif. Jika terjadi kesamaan itu adalah
kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan."
.
.
"Berlarilah ke arah angin berhembus Azarine."
•••
"Kenapa tidak mau lepas!"
Keluh seorang perempuan bernama Anita Cendana. Dia
mencoba memutuskan tali tambang yang mengikat
pergelangan tangan serta tubuhnya di kursi kayu. Dia
telah disekap, dikurung dalam rumah gubuk di pedalaman
hutan.
Anita mendongakkan kepala. Dari genting yang berlubang,
bulan menampakkan diri, sedangkan udara malam
menyelinap masuk melalui dinding yang rapuh dan
berlumut.
"Cepat! Ayo cepat."
Dia menyemangati diri saat berusaha memutuskan tali
tambang dengan pisau bedah kecil yang sempat dia
selundupkan.
"Cepat! sebelum mereka datang," tambahnya lagi.
Kedua mata bernetrakan coklat jernih itu menatap penuh
takut pada pintu, berharap para anggota kelompok
kriminal bersenjata yang menculiknya tidak memergoki
tindakannya untuk melepaskan diri.
"Tuhan Alam Semesta, tolonglah aku," serunya,
menyentak-nyentakkan tangan di kursi yang mengikat
tubuhnya.
Penampilan Anita sangat memprihatinkan.
Sudut bibirnya berdarah. Pipinya memar, sudah tak
terhitung berapa kali telapak tangan milik pria bernama
Beto Calvis menampar wajahnya. Orang itu sama sekali
bukanlah manusia.
"Berhasil! Berhasil!"
Anita menghela napas lega saat tali tambang terputus.
Untuk berjam-jam yang dia habiskan melepaskan diri, dia
menggoreskan banyak luka di pergelangan tangannya.
"Harus pergi sekarang," gumam Anita lagi. "Aku harus
melarikan diri."
Dia mengedarkan pandangan ke sekitar. Rumah kayu ini
dijaga ketat. Di luar pintu, Anita yakin gerombolan itu
pasti menghadangnya. Hanya satu jalan keluar yaitu
memanjat dan keluar melalui atap berlubang.
Tanpa berpikir panjang. Anita menaiki tumpukan kayu dan
memanjat ke atap meskipun seng berkarat menggores
lengannya. Kerudung merah yang menutupi kepalanya
terjatuh ke pundak saat angin berhembus, memperlihatkan
tengkuk lehernya yang berhiaskan tato salib kecil
berwarna hitam.
Anita berhasil menaiki atap rumah kayu tempat dia
disekap. Kedua matanya dengan bebas leluasa menjelajahi
hutan yang menjadi markas persembunyian kelompok
kriminal bersenjata yang menculiknya dari Desa Baloko.
"Ayolah Anita! Kamu pasti bisa."
Sejenak Anita ragu untuk melompat dari atap, namun saat
dia mendengar pergerakan di dalam rumah dia tidak bisa
mengurungkan niatnya lagi.
"Tuhanku!"
Perempuan itu terjatuh di tumpukan daun kering.
Bibirnya melontarkan keluh sakit saat nyeri menjalari
pergelangan kaki.
"Jangan sekarang. Tidak ada waktu untuk sakit sekarang!
Aku harus pergi dari sini. Aku tidak mau mati di tangan
manusia bejat itu."
Anita memaksa tubuhnya berdiri dan berlari. Meskipun
kakinya yang terkilir menjadi penghambat, membuat
jalannya pincang.
"Desa Baloko! Desa Baloko pasti berada di bawah gunung,
aku harus turun sekarang."
Anita bicara sendiri. Hanya itu yang bisa memompa
semangatnya. Sesekali dia menoleh ke belakang karena
merasa ada yang mengikuti dan mengejarnya.
Dan benar!
Mereka akhirnya menyadari.
"MELARIKAN DIRI! PEREMPUAN ITU KABUR! DOKTER ITU!"
Teriakan keras memecah keheningan malam dan membuat
Anita semakin mempercepat larinya.
"Ah!"
Anita terjatuh tersungkur, kakinya tersandung batu,
kedua telapak tangannya langsung tergores oleh bebatuan
cadas dan mengeluarkan darah.
"DIA DI SANA! DIA LARI KESANA."
"KEJAR! JANGAN SAMPAI LEPAS."
"KALIAN TIDAK BECUS! BIAR SAYA SAJA YANG MENANGKAPNYA!"
Suara terakhir itu membuat Anita lekas berdiri lagi.
Sosok pria yang berjalan menghampiri menjadi mimpi
buruknya.
"Dia! Tidak, aku harus pergi. Aku harus pergi." Anita
menggelengkan kepala frustasi.
Dia berlari kembali, menuruni gunung dengan cepat,
melintasi pepohonan yang rantingnya terus menggores
tajam tubuhnya.
"Jangan lari Dokter! Menyerah saja. Tenang! Saya tidak
membunuh Anda," seru Beto Calvis.
Sosok pengejar, bernama Beto Calvis mengikuti Anita
berlari.
"Kembalilah pada Beto Calvis. Anda lebih aman bersama
saya. Di hutan ini, babi hutan saja bisa membunuh Anda.
Saya akan melindungi Anda," bujuknya.
"Beto Calvis bangsat!" Anita mengutuk.
Apa pemimpin kelompok kriminal bersenjata itu berpikir
Anita akan menyerahkan diri dengan mudah?
Apa Beto Calvis? Lelaki yang mengaku tidak memiliki
negara akan berpikir Anita ikut dengannya suka rela?
"Jangan harap!" sahut Anita keras dan semakin
memperlaju larinya. "Lebih baik saya mati daripada
harus ikut dengan Anda."
"Kalau begitu sangat disayangkan. Saya harus
melumpuhkan salah satu kaki Anda." Beto menyeringai,
dia mengarahkan pistol tanpa ragu. "Kaki cantik itu
tidak akan pernah bisa mengenakan sepatu merah lagi."
Suara letusan terdengar keras. Bergema. Membuat
penghuni hutan panik bahkan para kelelawar segera
terbang ke angkasa.
Anita terjatuh.
Dia terdiam sejenak. Tubuhnya merasa dingin, keringat
membasahi wajahnya. Dia segera menutup kedua telinga
saat lontaran peluru membelah langit malam. Berondolan
peluru yang tiada henti membuat Anita menelungkupkan
tubuhnya hingga kening menyentuh tanah.
Sumpah serapah menyahuti, teriakan amarah menyelingi.
"BANGSAT! DIA MENYUSUL KEMARI. DIA BERHASIL MENGEJAR
KITA," teriak Beto Calvis.
Kemudian tubuh Anita ditarik paksa, sangat kuat
sehingga membuat kedua kakinya menginjak tanah lagi.
Dan di bawah sinar rembulan yang menjadi satu-satu
penerang, dia melihat sepasang bola mata yang balas
menatapnya.
"Letnan Hamdi?"
Anita berkata tidak percaya. Ternyata lelaki itu
menyusulnya. Mengejar Anita ke pedalaman hutan untuk
menyelamatkannya.
Hamdi lekas menarik Anita ke belakang tubuhnya seraya
berjalan mundur, sedangkan tangan kanannya memegang
pistol masih mengarah pada Beto Calvis. Lelaki itu
menjadi temeng, melindungi Anita dari lontaran peluru.
"Azarine..."
Hamdi memanggil Anita dengan nama Islamnya. Nama
pemberian dari lelaki yang telah tiada dan membawa
Anita untuk menyembah Allah.
"Pada hitungan ketiga! Lari," ucap Hamdi tegas.
Tidak terdengar gentar sedikit pun dari suara Hamdi.
Walaupun dia menghadapi kelompok orang yang mengaku
tidak memiliki tanah kelahiran. Dari orang-orang yang
mengaku telah terusir dari dua negara.
"Ke arah angin berhembus kamu mengerti maksud saya,
'kan?"
Hamdi menoleh dan memberikan seulas senyuman pada
Anita, seperti biasa dia terlihat congkak.
"Dan jangan terharu! Karena setelah ini kamu harus
membayarnya, menikah dengan saya," ucap Hamdi seraya
tertawa kecil.
"Menurut saya itu setimpal dengan apa yang saya lakukan
hari ini. Mempertaruhkan nyawa saya untuk menyelamatkan
kamu."
Hamdi mengalihkan pandangannya kembali. Senyum itu
meluntur dan tergantikan ekspresi dingin. "Dan saya
tidak menerima penolakan sama sekali!"
Genggaman Hamdi di tangan Anita semakin erat saat Beto
Calvis menampakkan sosoknya di balik kabut. Dia
mengarahkan pistolnya.
"LETNAN HAMDI MATI!" raung Beto keras. Disertai suara
peluru dilontarkan menembus malam.
[02] Gasa Si Kuda Menyebalkan
"Dari bawah langit bumi Loro'sae kusampaikan salam"
•••
Anita Cendana terdampar di daerah terpencil di Nusa
Tenggara Timur. Sejauh mata memandang dia hanya melihat
tandus, gersang sedangkan matahari bersinar terik,
membuat ubun-ubun kepalanya berdenyut sakit. Panas
langit dari bumi Loro’sae di musim kemarau, membuat
Anita terus mengipasi wajahnya dengan peta Atambua yang
tak sudah terbentuk lagi karena dijadikan kipas
dadakan.
Sesekali Anita menengadahkan wajah sedangkan telapak
tangan di atas pelipis, namun dia turunkan pandangan
dengan cepat karena sinar matahari menyilaukan mata.
“Panas banget,” keluh Anita, seraya menyeka keringat
yang menetes melalui dagu dengan punggung tangan.
“Lama-kelamaan gue bisa kena heat-stroke.”
Anita tidak tahu dia akan senekad ini. Dia menjauh dari
modernisasi perkotaan, mengucilkan diri ke sebuah desa
terpencil di Nusa Tenggara Timur, mengabdi sebagai
dokter relawan di daerah perbatasan antara dua negara
yaitu Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor
Leste.
“Bosan!” serunya kemudian.
Menunggu lama di depan gubuk tua, di mana dia baru saja
dihantar oleh truk pengangkat barang, dia mengeluarkan
ponsel dari saku jas putih kebanggaan. Berniat mengusir
suntuk dengan bermain game online.
Namun.
“Nggak ada sinyal.”
Anita menghela napas berat. Dia berdiri dan mengangkat
tinggi ponsel ke langit. Berharap menemukan jaringan—
paling tidak menambah satu bar sinyal namun sia-sia,
ponselnya tidak terkoneksi dengan internet.
Dia duduk kembali di atas koper hitam miliknya yang
dijadikan tempat duduk dan memilih membuka pesan
terakhir dari Halim Cendana. Pesan dari ayahnya yang
berada jauh di ibu kota Jakarta.
“Papa bisa mengirimkan helikopter kalau kamu nggak
nyaman di sana. Beritahu Papa dan Papa langsung
menjemput kamu.”
Ayahnya masih berusaha membujuk Anita untuk kembali
pulang ke Jakarta. Anita tidak lupa bagaimana reaksi
Halim Cendana; ayahnya saat dia mengutarakan
keinginannya menjadi dokter relawan.
“Apa? Kamu ingin menjadi dokter relawan di perbatasan?
Jangan konyol Anita! Itu tempat terpencil,” ucap Halim
saat mendengar keinginan Anita melepas pekerjaannya di
Jakarta dan memilih mengabdi sebagai dokter di
perbatasan.
“Aku tetap pergi Pah, aku sudah mengurus semuanya. Aku
sudah mendaftarkan diri di salah satu yayasan sosial.
Aku nggak bisa mundur.” Anita menjawab kala itu. Makan
malam yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi
dingin.
“Apa karena lelaki itu?” terka Halim. “Karena
Dirgantara?”
Nama Dirga membuat Anita kesulitan untuk menelan
makanan. Dia memilih berhenti dan meminum banyak air,
tiba-tiba saja tenggorokannya terasa amat perih.
“Sudah berlalu cukup lama Anita, seharusnya kamu
melepaskannya. Seharusnya kamu mengikhlaskan
kepergiannya,” nasihat Halim. “Sampai kapan kamu
terjebak di masa lalu, kamu hanya akan menyakiti diri
sendiri.”
“Karena itulah aku butuh pergi Pah!” Anita berkata
dengan suara gemetar. “Kalau aku tetap di sini, jujur
aku nggak bisa! Aku selalu melihatnya di mana-mana. Aku
selalu melihat Mas Dirga di depanku, selalu mendengar
suaranya, selalu melihat senyumnya.”
Anita menundukkan kepala, jangan sampai dia menangis
lagi! Sudah tak terhitung air mata yang dia tumpahkan
kepada lelaki yang meninggalkannya dengan cara yang
pedih.
“Aku bisa gila kalau terus seperti ini! Jadi, tolong
biarkan aku pergi Pah. Insya Allah.” Anita menambahkan
seraya menggenggam tangan ayahnya.
Halim mengerutkan kening, terkejut ketika mendengar
putrinya yang mengaku ateis tiba-tiba mengucapkan
lafadz Allah dengan lembut.
“Allah yang akan menjagaku, Insya Allah, Tuhan-nya Nabi
Muhammad yang akan menjagaku. Jadi tolong biarkan aku
pergi Pah.”
Dan setelah itu Halim tidak memperdebatkan lagi tentang
Anita menjadi dokter sukarelawan, Halim bahkan membantu
mengurus kepindahan Anita, memberikan bantuan dan juga
obat-obat medis agar Anita bisa melakukan tugas dengan
baik di perbatasan. Halim terketuk hatinya ketika
mendengar Anita menyebut nama Allah.
Tapi sepertinya Halim mulai mengkhawatirkannya kembali
dan meragukan keputusan Anita.
Anita mendengus.
“Nggak semudah itu, Pah. Anita Cendana nggak mengenal
kata menyerah. Nggak ada dalam kamus hidup Anita.”
Jari-jemari lentiknya segera bermain di layar ponsel,
mengetikkan pesan panjang sebagai balasan untuk Halim
Cendana. Namun beberapa detik kemudian. Anita menepuk
keningnya.
“Kan nggak ada sinyal! Begonya gue,” rutuknya pada diri
sendiri. Dan mengetuk-ngetuk ponselnya ke keningnya
sendiri. “Efek panas! Efek dehidrasi! Mulai deh
berhalusinasi.”
Anita Cendana benar-benar berada di daerah, di mana
jaringan telepon, listrik bahkan transportasi pun sulit
untuk didapat. Apa dia mulai menyesali keputusannya
sekarang?
“Enggak!” tepis Anita. Perempuan itu menepuk pipinya
berkali-kali. “Anita Cendana! Kuatkan diri lo. Bulatkan
tekad lo. Elo pasti bisa menjadi dokter di sini.”
Anita menyemangati diri ratusan kali. Dia tidak boleh
menyesali perjuangannya, mulai dari ibu kota Jakarta,
ke kota Atambua lalu ke Desa Baloko. Dia sudah menempuh
puluhan kilometer untuk sampai di rumah gubuk yang
sekarang dia jadikan halte menunggu.
“Desa Baloko,” ujar Anita seraya menggelar peta kembali
di atas tanah.
Kedua mata Anita beririskan coklat mengamati satu titik
yang bertuliskan ‘Baloko’, mengalihkan perhatiannya
sejenak dari cuaca panas. Dari kota Atambua, Anita
menempuh kurang lebih 30 kilometer dan untuk sampai ke
Desa Baloko dia harus menempuh 20 kilometer lagi.
Topografi daerah ini membuat perjalanan Anita penuh
perjuangan. Dia harus melalui perbukitan, sedangkan
jalan masih tidak tersentuh aspal, didominasi bebatuan
sehingga sulit dilalui oleh mobil ataupun motor.
“Dokter Anita Cendana?”
Sebuah suara mengalihkan perhatian Anita yang terlalu
berkonsentrasi mempelajari peta, dia mendongakkan
kepala dan akhirnya melihat modernisasi di depan mata,
membuat mulutnya sedikit menganga, padahal yang dia
lihat hanyalah jep terbuka kotor karena debu.
Dua orang lelaki turun. Mereka merapikan seragam
tentara sebentar lalu memberikan hormat dengan berdiri
tegap.
“Iya, saya Anita Cendana.”
Anita membenarkan. Dia berhadapan dengan seorang
tentara berkulit coklat sawo matang, namun memiliki
deretan gigi putih di balik senyum lebarnya.
“Saya Serda Fikri Sanjaya, tentara yang bertugas
menjemput dokter.” Si tentara berkulit sawo matang
memperkenalkan diri lalu menyambar koper Anita. “Koper
Dokter bukan? Biar saya muat ke mobil jep.”
Tentara satunya lagi mendekati. Senyumnya tidak
meluntur sejak pertama kali melihat Anita. Lelaki itu
bertubuh tinggi, kedua mata sedikit monolid sedangkan
hidungnya mancung.
“Dan perkenalkan nama saya Serda Muhammad Nicholas.
Anda bisa memanggil saya Serda Ikol.”
“Anita Cendana. Apa kita bisa pergi sekarang?” tanya
Anita, segera menaiki mobil jep tanpa disuruh. “Ke Desa
Baloko butuh berapa jam untuk sampai?”
“Cuma beberapa jam Dokter,” sahut Fikri dan duduk di
bagian kemudi. Dia melirik Anita, terlihat memikirkan
sesuatu.
“Er, apa tidak nyaman buat Dokter?” tanya Fikri melihat
Anita duduk berjejal dengan koper. “Dokter bisa
melepaskan sepatu dan menggantinya dengan…”
Lelaki itu hendak mengambil sandal jepit di bawah
kolong kursi namun Anita segera melindungi kakinya.
Melindungi sepatu hak tinggi merah miliknya yang tak
tergantian. Meskipun dia sekarang berada di daerah
terpencil.
“Tidak perlu, terima kasih. Saya sudah cukup nyaman,”
tolak Anita dengan pandangan mengintimidasi.
“Baiklah. Saya cuma mencemaskan Dokter, soalnya Desa
Baloko memiliki jalan berbatu jadi sulit berjalan
dengan sepatu hak tinggi seperti…”
Fikri menelan bulat perkataannya sebelum bisa
menyelesaikannya, tatapan Anita membuatnya segera
beralih pada kemudi setir dan menyalakan mesin mobil.
“Ikol cepatan naik! Komandan bakal marah kalau kita
datang terlambat,” desaknya pada Ikol yang segera naik,
berdiri dan berpegangan di belakang mobil jep—mengingat
mobil itu sudah dipenuhi koper Anita.
“Berangkat! Berangkat!” seru Ikol berteriak.
Mobil jep yang membawa Anita menuju Desa Baloko adalah
jep terbuka, tidak ada naungan sama sekali sehingga
mata langsung terterpa angin yang tidak berhenti
berhembus. Menghalau debu yang bertebrangan saat mobil
jep melintas jalan tak beraspal, Anita mengeluarkan
kerudung merah dari tas dan langsung dia kenakan untuk
menutupi kepala dan hidung sehingga hanya kedua matanya
bernetrakan coklat saja yang terlihat.
Untuk beberapa saat Anita terdiam, tertegun ketika
mobil jep melintasi padang sabana, walaupun dilanda
musim kemarau dan hijau reremputan mulai tergerus, dia
takjub dengan keindahan padang sabana di Nusa Tenggara
Timur. Langit biru luas tanpa batas sedangkan gunung
Lakaan, gunung tertinggi kedua di pulau Timor menambah
keindahan dari surga yang berada di tapal batas negeri.
Sedangkan kuda-kuda liar berlari berkelompok,
menggiringi kecepatan mobil jep yang membawa Anita ke
Desa Baloko.
Namun perjalanan mereka berubah menjadi ekstrem
kemudian.
Saat mobil jep menanjaki bukit terjal dan padang sabana
mulai tidak terlihat lagi, hanya tandus dan gersang.
Terkadang mobil jep tidak dapat melaju, berlari di
tempat karena bebatuan sehingga Ikol harus turun untuk
mendorong mobil jep saat ban terjebak di lubang.
“Ada berapa dusun di desa Baloko?” tanya Anita ingin
tahu. Saat dia melihat mobil jep tentara lain melewati,
menyapa mereka dengan membunyikan klakson.
“Ada empat Dokter. Baloko Fatu, Nufeha, Rana Pundar dan
Wela Sada,” beritahu Ikol.
“Dan kalian menjaga di pos?” Anita bertanya lagi.
“Kami menjaga di Dusun Baloko Fatu.” Fikri kemudian
memberikan ekspresi sesal pada Anita. “Sangat
disayangkan Letnan Hamdi cukup sibuk, dia memeriksa
penampungan air jadi dia tidak bisa menjemput Dokter.”
Anita tidak peduli siapa yang menjemputnya, yang
terpenting adalah dia sampai ke Desa Baloko secepat
mungkin, ingin sekali dia berbaring, melentangkan
tubuhnya dan tidur. Yang terpenting adalah! Dia ingin
sekali mandi.
“Ah! Untuk Dokter Anita ketahui,” sela Ikol dari
belakang dengan suara keras. “Air bersih sangat minim
di Desa Baloko, para warga bahkan harus menempuh lima
belas kilometer untuk menuju mata air.”
“Lima belas kilometer?” Anita merasa kebahagiaannya
terenggut. Bayangan untuk merendam tubuhnya di air
dingin seketika sirna. “Bagaimana bisa?”
“Karena kanal masih dalam tahap pembangunan Dokter dan
kami juga masih menunggu kedatangan pipa dari kota
Atambua,” jawab Fikri. “Pipa-pipa itu nantinya akan
terhubung ke sumber mata air lalu mengairi dusun-dusun
yang sampai sekarang kesulitan air bersih.”
“Ah! Mereka membuat sambutan untuk Dokter,” seru Ikol
melambaikan tangannya kepada kerumunan orang.
Desa Baloko tampak jelas di depan mata. Banyak orang
menantikan kedatangan Anita.
“Kabar kedatangan Dokter membuat warga sangat senang,”
beber Fikri seraya melebarkan senyum. “Setelah beberapa
bulan tanpa tenaga medis. Akhirnya ada yayasan sosial
yang mengajukan seorang dokter. Apalagi ini juga
pertama kali….” Dia menghentikan mobil di pintu jalan
masuk.
Ikol melompat turun dari mobil jep. Langsung menurunkan
koper dan barang bawaan Anita, sembari dibantu oleh
penduduk desa Baloko.
“Pertama kali apa?” tanya Anita.
“Dokter perempuan pertama yang bertugas di sabuk merah,
perbatasan Indonesia-Timor Leste. Dokter pertama yang
menjadi…” Fikri tersenyum. “Menjadi bunga terindah di
Desa Baloko.”
Anita berdeham. Dia segera mengalihkan pandangannya
dari Fikri ke seorang lelaki bungkuk yang menghampiri.
Lelaki tua itu tersenyum lebar lalu mengalungkan kain
tenun di leher Anita, sebagai ucapan selamat datang di
Desa Baloko.
“Dokter Anita selamat datang di Desa Baloko. Saya tetua
adat Desa Baloko, Tuba.” Lelaki tua itu memperkenalkan
diri dan menjabat tangan Anita. “Saya berharap Dokter
Anita betah saat bertugas di Desa Baloko.”
“Terima kasih untuk sambutannya Bapak.” Anita menjabat
tangan Tuba dan membalas senyuman ramah penduduk desa.
“Seharusnya kalian tidak perlu menyambut kedatangan
saya. Kalian pasti sangat sibuk,” tambahnya penuh
sesal. Terutama setelah melihat banyak dari mereka
menyambut Anita dengan memikul karung jagung di bahu.
“Tidak, tidak. Kami harus tahu sopan santun Dokter. Di
sini. Di desa Baloko, kami menyambut ramah semua orang.
Kami anggap seperti keluarga. Dokter bisa tanya pada
Serda Ikol dan Fikri,” ujar Tuba kepada dua tentara
yang menganggukan kepala segera.
“Benar sekali!” Ikol mengiyakan. “Bapak Tuba membuat
kami nyaman tinggal di sini.”
“Dan perkenalkan ini adalah Kalere.” Tuba menarik
seorang gadis cantik dengan rambut keriting ke hadapan
Anita. “Dia cucu saya. Kalere membantu Dokter di klinik
nanti. Dokter sebelumnya sering meminta tolong pada
Kalere.”
Kalere memeluk Anita tanpa rasa canggung. “Selamat
datang Dokter Anita.” Dan memberikan rangkaian bunga.
“Terima kasih banyak.” Anita tersenyum senang. Merasa
nyaman dengan sikap ramah Kalere. “Untuk berikutnya
mohon bantuan dari Kalere. Saya tidak tahu banyak hal
tentang Desa Baloko.”
“Tentu saja Dokter,” kata Kalere menyanggupi. “Tenang
saja, saya akan menjadi pemandu Dokter di sini.”
“Ini kudanya Tetua,” sela seorang pemuda desa datang
sembari membawa kuda hitam. “Gasa siap mengawal Dokter
Anita mengeliling Desa Baloko.”
“Silakan Dokter Anita,” kata Tuba menuntun Anita,
menarik siku lengannya. “Silakan naik ke pelana Gasa.
Kuda yang paling dicintai di Desa Baloko. Ini sudah
menjadi salah satu tradisi kami menyambut para tamu.”
“Na-Naik kuda? Tu-tunggu Bapak. Saya tidak bisa naik
kuda,” timpal Anita takut.
Sekarang semua penduduk desa bertepuk tangan,
menyemangati Anita untuk menaiki si kuda bernama ‘Gasa’
untuk mengelilingi Desa Baloko.
“Dokter tidak bisa menolak.” Ikol membisiki. “Kita
harus menghormati adat istiadat mereka.”
“Ta-tapi saya tidak bisa naik kuda sama sekali. Tu-
tunggu izinkan saya berkenalan dengan Gasa terlebih
dahulu,” pinta Anita saat Kalere mendesaknya naik.
Anita berhadapan dengan Gasa dan memberikan senyum
canggung pada si kuda.
“Hai Gasa, saya Anita,” sapanya.
Gasa mendengkus dan membuang muka.
Yep!
Anggaplah kesan pertama tidak berjalan baik. Gasa terus
mengais-ngaiskan kakinya ke tanah, menandakan kalau dia
tidak menyukai Anita.
“Yakin dia jantan?” tanya Anita meragu. Karena biasanya
yang bersikap kasar padanya selama ini adalah kaum
perempuan.
“Jantan! Kuda pejantan terbaik,” sahut Tuba mengangguk
penuh keyakinan. “Sini biar saya bantu dokter naik ke
atas pelana.”
Anita meringis. Tuba berumur hampir 80 tahun, bagaimana
bisa dia membantunya menaiki ke atas pelana kuda? Yang
ada rematik yang diderita lelaki tua itu kumat. Anita
tahu! Karena Tuba mengandalkan tongkat untuk
membantunya berjalan.
“Ti-tidak saya bisa sendiri,” tolak Anita. “Daripada
gue membahayakan nyawa orang.” Dia menambahkan dengan
bergumam, hanya dia saja yang mendengar.
“Gasa, kita berteman oke? Cuma untuk hari ini, tolong
jadilah kuda yang baik,” mohon Anita. Dia mengelus
surai Gasa seraya memberikan senyum.
Namun Gasa memalingkan wajah. Mengabaikan Anita.
Sungguh sangat menyebalkan.
“Baiklah! Saya coba naik. Saya pernah melihatnya di
film-film, menunggangi kuda kelihatannya mudah,
lagipula waktu kecil aku juga pernah naik kuda poni,”
ujar Anita percaya diri.
“Tunggu! Biar saya yang bantu Dokter.” Fikri bergegas
maju ke depan, hendak menolong Anita. “Nanti dokter
jatuh, bukan seperti itu caranya. Gasa belum siap Dok!”
“Ya Tuhan Dokter Anita!”
Semua orang berteriak takut saat Anita naik ke atas
pelana namun Gasa si kuda pejantan ternyata belum siap.
Gasa mengelak dari Anita dan berlari pergi.
Yakinlah!
Bokong Anita menjadi korban pertama yang merasakan
sakit saat terhempas di jalan berbatu Desa Baloko.
Dalam hatinya dia mengutuk Fikri yang terlambat
menolongnya.
“Dasar lelaki nggak peka!” batinnya kesal.
“Oh!”
Anita berseru bingung. Dia yang tadi memejamkan mata
menunggu detik-detik dirinya terjatuh ke tanah tapi
merasa aneh saat ada yang menahan punggungnya,
sedangkan lengan kekar melingkar di pinggangnya. Anita
memberanikan diri membuka mata.
Dan…
Di bawah langit Desa Baloko Anita Cendana bertatapan
dengan seorang lelaki berseragam tentara. Wajah datar
tanpa ekspresi. Mirip Gasa! Si kuda pejantan
menyebalkan yang membuatnya terjungkal dari atas
pelana.
“Dapat!” ucap Hamdi, menangkap tubuh Anita sebelum
terjatuh ke tanah.
“Letnan Hamdi!” seru Ikol dan Fikri bersamaan seraya
tersenyum lebar.
Anda mungkin juga menyukai
- Kite NH - My Ex-Husband S Wedding (SFILEDokumen452 halamanKite NH - My Ex-Husband S Wedding (SFILEIrresistible DayBelum ada peringkat
- Post 6239a283421cdDokumen113 halamanPost 6239a283421cdYuni Eka Pangesti75% (4)
- Untouchable Man by ViallynnDokumen460 halamanUntouchable Man by ViallynnAde Ryanta Putra100% (3)
- The Antagonist S Secret - Chocopper (SFILEDokumen467 halamanThe Antagonist S Secret - Chocopper (SFILEGinasti Esalona100% (1)
- Lia Reza Pahlevi - Stay With MeDokumen340 halamanLia Reza Pahlevi - Stay With MeArdilla DewiBelum ada peringkat
- Layout Eccedentesiast Unpublished PartDokumen6 halamanLayout Eccedentesiast Unpublished Partsyifa kBelum ada peringkat
- The Most Wanted GirlDokumen335 halamanThe Most Wanted GirlDheean Boss TangguhBelum ada peringkat
- Surat Untuk RakaDokumen92 halamanSurat Untuk RakaNurrobbikinBelum ada peringkat
- Di Balik JendelaDokumen1 halamanDi Balik Jendelainojayagiri50% (2)
- Unpublished Part SamuelDokumen9 halamanUnpublished Part SamuelJihan SalsabilaBelum ada peringkat
- Akhir Kisah Bersamamu by Fabby AlvaroDokumen750 halamanAkhir Kisah Bersamamu by Fabby AlvaroAudya AR0% (1)
- To Forgive (Extra Chapter - After Story) KaryakarsaDokumen1 halamanTo Forgive (Extra Chapter - After Story) KaryakarsaSania Tul HajiahBelum ada peringkat
- Al VaskaDokumen556 halamanAl VaskaArofah BeaBelum ada peringkat
- Extra Chapter - Behind The StoryDokumen20 halamanExtra Chapter - Behind The StoryNita Rosanti Kim100% (1)
- Khojina - Aku Yang Tak DirindukanDokumen47 halamanKhojina - Aku Yang Tak Dirindukangultomvingkan24100% (1)
- Alnira - Fight For YouDokumen512 halamanAlnira - Fight For YouWira septi larassatiBelum ada peringkat
- 5 6077783971184247039Dokumen805 halaman5 6077783971184247039JustVvBelum ada peringkat
- Bina Afira - Xless Marriage (SFILEDokumen409 halamanBina Afira - Xless Marriage (SFILENimas SellaBelum ada peringkat
- Pit Sansi - Surat Cinta Tanpa Nama PDFDokumen286 halamanPit Sansi - Surat Cinta Tanpa Nama PDFAndan riadini100% (1)
- Citra Novy - Simplify Our Heartbreak, Extra PartDokumen72 halamanCitra Novy - Simplify Our Heartbreak, Extra PartHereiamBelum ada peringkat
- Extra Part Delicate Love: Double Shit!Dokumen111 halamanExtra Part Delicate Love: Double Shit!fifi 0908Belum ada peringkat
- Novl MapsDokumen2 halamanNovl MapsAdika Lazuardy fh0% (2)
- Every Little Thing - Wiwi SuyantiDokumen352 halamanEvery Little Thing - Wiwi SuyantijhyazBelum ada peringkat
- 7 Hari Menembus Waktu PDFDokumen174 halaman7 Hari Menembus Waktu PDFSri Ramdani83% (6)
- Setelah Bumi Milik Senna (SFILEDokumen274 halamanSetelah Bumi Milik Senna (SFILEdian.vierra99Belum ada peringkat
- Pelet Online by Zefanya MonikaDokumen393 halamanPelet Online by Zefanya MonikaRene BaeBelum ada peringkat
- Extra Chapter Aileen & ReganDokumen100 halamanExtra Chapter Aileen & Reganrh rBelum ada peringkat
- Bhian by LinaDokumen94 halamanBhian by LinaKHSBelum ada peringkat
- Ekstra Chapter Lana's Lullaby - Born To Be LovedDokumen41 halamanEkstra Chapter Lana's Lullaby - Born To Be LovedSalnaBelum ada peringkat
- 14 PDFDokumen31 halaman14 PDFRAWBelum ada peringkat
- SeptihanDokumen1 halamanSeptihanFhazira Andani67% (3)
- MR A Vs Miss A Gravitasia PDFDokumen262 halamanMR A Vs Miss A Gravitasia PDFAisyahMuftihaturrahmah0% (1)
- Titik NadirDokumen406 halamanTitik NadirRindiBelum ada peringkat
- Areksa Unpublished PartDokumen8 halamanAreksa Unpublished PartAnnisatul najwaalya100% (1)
- Boom Boom Heart Tamat by Anothermissjoo (SFILEDokumen219 halamanBoom Boom Heart Tamat by Anothermissjoo (SFILERianita SekarBelum ada peringkat
- Extra Part Strawberry CloudDokumen13 halamanExtra Part Strawberry Cloudpekanbaru30809Belum ada peringkat
- Out of Wedlock by DadodadoDokumen433 halamanOut of Wedlock by DadodadoJanatan NikmahBelum ada peringkat
- Kesempatan KeduaDokumen2 halamanKesempatan KeduaRani Rahadina80% (5)
- The Other Side by Alya RantiDokumen269 halamanThe Other Side by Alya RantiLaras DiahBelum ada peringkat
- Post 60cb1ce5e9b76Dokumen16 halamanPost 60cb1ce5e9b76nur faridaBelum ada peringkat
- Gentala Mayang by Crocodileudud (SfileDokumen100 halamanGentala Mayang by Crocodileudud (SfileShandya MaharaniBelum ada peringkat
- Dia, Tanpa Aku - Esti Kinasih PDFDokumen10 halamanDia, Tanpa Aku - Esti Kinasih PDFRima HermayaniBelum ada peringkat
- Gus ImpianDokumen88 halamanGus ImpianRosa Aulia Savitri100% (1)
- Buku Nuraga PDFDokumen272 halamanBuku Nuraga PDFMarkus100% (1)
- (KK) Filthy SecretDokumen489 halaman(KK) Filthy SecretAndy50% (2)
- Making Perfect FamilyDokumen50 halamanMaking Perfect FamilydodottiieeeBelum ada peringkat
- Ryani Muhammad-Hijrah Cinta AfaDokumen436 halamanRyani Muhammad-Hijrah Cinta AfaBunga ApriliaBelum ada peringkat
- Wulan Kenanga - After WeddingDokumen382 halamanWulan Kenanga - After WeddingEtika PramadyaBelum ada peringkat
- Bonus Digital (Ekstra Part Gionatan)Dokumen9 halamanBonus Digital (Ekstra Part Gionatan)Selvi Keyvhln100% (1)
- Azizahazeha - Dosen CantikDokumen219 halamanAzizahazeha - Dosen CantikNirmala HBelum ada peringkat
- Luluk SpesialDokumen84 halamanLuluk SpesialCahyadiKusumaBelum ada peringkat
- Jingga Dalam ElegiDokumen627 halamanJingga Dalam Elegiikaenje100% (6)
- Lizuka Myori - Damn He's My HusbandDokumen366 halamanLizuka Myori - Damn He's My HusbandNiha ZaenBelum ada peringkat
- Cepty Brown - Seputih Melati (BM)Dokumen244 halamanCepty Brown - Seputih Melati (BM)Nia MaimunahBelum ada peringkat
- Kumpul PDF - Asya Story by Sabrina FebriantiDokumen361 halamanKumpul PDF - Asya Story by Sabrina FebriantiNurul Zahra50% (2)
- Celebrity Mistress by Babydoll PDFDokumen264 halamanCelebrity Mistress by Babydoll PDFAnisa Septiani0% (2)
- Sunny Chandlers ReturnDokumen24 halamanSunny Chandlers ReturnYuli SentanaBelum ada peringkat
- WIRO SABLENG Raja Sesat Penyebar RacunDokumen46 halamanWIRO SABLENG Raja Sesat Penyebar RacunAntiKhazar1866Belum ada peringkat
- Wasiat Di Puri ElangDokumen68 halamanWasiat Di Puri ElangAa YandiBelum ada peringkat
- Dendam Pendekar Cacat PDFDokumen105 halamanDendam Pendekar Cacat PDFAudrin SalsabilaBelum ada peringkat