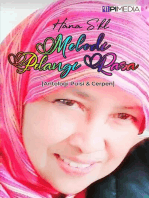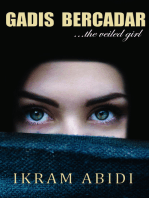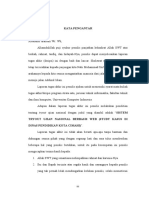Ikebana
Diunggah oleh
Adhityarismawan MoodutoDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Ikebana
Diunggah oleh
Adhityarismawan MoodutoHak Cipta:
Format Tersedia
EFROSINA
Ketika bangun pagi sekali, pada suatu hari, aku takjub ilalang tumbuh sepanjang betisku.
Tubuhku kecut dan pasi, hujan menyiram rambutku semalaman;
seseorang bermuka pucat bermahkota cahaya ke dalam cawan menuangkan cairan merah bagai anggur, seperti darah:
"Untuk kesehatan kita." Kami pun bersulang, aku bersulang, dengan murung.
Tapi demi Tuhan, demi dia, wajahnya jelita dan jenaka.
Aku teringat ibu, lalu kutanyakan padanya telah ia lihatkah pohon di sorga muasal semua penderitaan manusia.
Namun ibu tersayang terlalu jauh dan seruanku begitu rendah.
Angin keras dan riuh, tersesat aku di entah.
Andaikan firdaus, seandainya inferno, dapat diukur dengan kilo jaraknya dan jarum jam berputar sebaliknya.
Barangkali aku menangis, ya, sendirian, bermalam-malam. Keningku rekat ke marmar, jiwaku memar.
Kelopak bunga baobab berguguran dari sembab mataku.
Di kejauhan seluruh masjid bertakbir, para malaikat pulang ke tabir. Meninggalkan sayap mereka di jalan raya.
Aku terikat di tempatku. Para filsuf menyebutnya dunia, aku menyebutnya penjara atau puisi atau jalusi musim semi.
Seseorang dengan sinaran berputar di lingkar kepalanya
menjadi kekasihku yang setia, dan pada suatu senja minggat begitu saja.
Aku patah. Jatuh sakit dan ginjalku lemah.
Aku menunggu, tidak, aku tidak menunggu, aku menunggu, tidak, mustahil aku menunggu, aku menunggu, tidak, ia muskil kembali, ia mungkin kembali.
Wajah yang memukau menyelundup dalam mimpiku. Bagai hujan rusuh menghunjam lebuh kemarau.
Di hari yang lain pusar di lidahku diliput lumut, dan mulutku pun bisu.
Biji gandum liar berjatuhan dari lubang hidungku, disemaikan angin ke seluruh penjuru.
Aku kini buta dan menanti. Bersandar di kursi malas seharian, setelah itu berminggu-minggu, kemudian berbulan-bulan.
"Dungu!" suara asing berbisik di telingaku, "segala sesuatu berubah. Waktu tidak berlari ke punggungmu. Duduk manislah di situ, kenangkan perbuatan santun masa mudamu.
Kutuklah pawai, juga partai, atau apa pun sesukamu."
Sayang, sayang, jangan menuduhku pencaci dan mendakwaku Mephisto atau Samiri. Bukan, sayang, bukan.
Namaku tak jadi beban. Aku bukan Aaron, bukan setan.
Aku pencinta wajah yang pernah datang dan hilang meninggalkan untaian manik cahaya, seperti lira Orfeus bagi madah Eridike yang nestapa.
Aku makanan dalam ususmu, keluhan dukalaramu, aku retina dalam matamu.
Hanya kudengar desir angin.
Maka kepadanya aku berkata: "Kunjungilah negeri terjauh. Temukan dia untukku." Akan kutanggungkan
kesedihanku merangkum ranum senyum itu.
1999-2006
MEJA KAYU
Inilah rahasia senja, usia yang terbuang, maut yang mengundang dan menghindar.
Laut jauh, malam pualam.
Kudengar berbagai suara dari dalam. Pertempuran, tarian Mephisto, erang dan keluh, jamu yang diseduh, sedang dia memungut bayang-bayang:
Luka dan prelude dari duka yang luput.
Ada perempuan matang bergigi kawat, berdiri di sebuah hari, ujung tahun yang basah, di bawah pohon cemara berlampu lebat.
Pengakuanku terbesar padamu: aku berhenti menemui seorang gadis, dan minum kopi lagi.
Semakin jarang aku memberimu ciuman, umurku berkurang dan kesepian.
Telah kuterima kegagalan dan hujatan sebagai cinta.
Aku keluar, sepatuku selalu bersemir coklat, kaus kaki baru dan lembut, ah, bukankah telah lama kering rumput di halaman
dan Chopin di masa silam menulis lagu pedih tentang hujan.
Gerimis dan rincing uang logam, pemantik api dan pipi yang penuh, sudut kotamu terlalu riuh.
Aku bernyanyi, jika sedih aku bernyanyi: Tepislah cintaku, dan esok pagi aku akan bangun di kamar hotelku. Sendiri.
Yang kusayangi selalu pergi.
Inilah rahasia senja, tanpa patahan kenangan dan kehendak memuja mitologi.
Alangkah riang ketika langit terang, kereta langsir, peluit tukang parkir bagai jadwal yang mangkir.
Aku murung dan kecewa, di stasiun Tugu melompat-lompat dan tertawa.
Beriman, Faust, bukan bersedia
keras kepala, untuk senyum seorang perawan, pemimpin yang ribut, sahabat yang memelihara serigala dalam dadanya, untuk bukan apa pun.
Tidak seperti para terusir di tanah-tanah pengungsian, aku cuma sedikit kehilangan:
Daun jatuh, percakapan yang berayun-ayun; dan seorang perempuan lemah melepas kerudungnya, mendedah kecupan, menata surat-surat, hadiah-hadiah remah,
dan mengubur bekas pelukanku di bawah meja kayu.
1999-2006
32 VARIASI PADA C MINOR
Dengan rambut licin dan tubuh bacin di halaman sebuah hotel sepasang remaja berkulit terang dihadang siang yang sinis.
Terkenang tengkukmu yang tegang tadi malam, aku tak harus cemas jika mesti terdesak arak-arakan demonstran di tikungan jalan kota yang makin kotor ini.
Satu atau dua kali seminggu kita selalu menyesal, dan nyaris sebal, terpaksa mandi pagi sekali.
Mungkin harus kita cari cara lain menyatakan cinta yang rutin itu, barangkali dengan belajar origami atau memelihara sejenis reptil.
Tentu saja agak ganjil.
Bagaimana jika sesekali kita tidur di losmen, kau dan aku maksudku, dan pura-pura menjadi pasangan
kawin tamasya?
Seperti telah kuduga, kau tersipu di depan kompor gas yang menyala seraya melihat-lihat menu hari itu dan beberapa jam kemudian, jika aku tak sibuk dan kau tak lupa,
kita akan duduk di bawah tiga puluh menit di ruang makan, menelan sejumlah pertanyaan.
Lalu aku menjadi penyendiri lagi di kamar kerjaku yang angkuh dan dingin dan sunyi.
Pikiran aneh tentang menjadi tua sebelum waktunya muncul tiba-tiba dan dengan kegilaan yang menyenangkan kubayangkan seseorang memainkan 32 Variasi pada C Minor di rumah ini, pada pukul tiga dini hari.
Siapa yang hendak setia bersikap ramah kutelepon setelat itu hanya untuk mendengar telah kutulis sembilan atau sebelas baris puisi liris dan bertanya esok tanggal berapa, mau ke mana, dan apakah tak terlalu berbahaya
menjadi relawan pendamping korban penculikan, penjarahan dan perkosaan di negeriku yang pendendam dan ringan tangan.
Begitulah, mereka masih sangat muda, keluar dari pintu hotel dengan langkah lepas dan kulum puas.
Aku tersenyum sendiri, Bercerita kepadamu sesuatu yang remah dengan perasaan pelarian yang resah,
terbuang dari negerinya sendiri, pada musim orang-orang tergiur partai, bermain musik dan bercinta.
Padahal kau tidur di kamar sebelah dan pekerjaan terakhirku menjelang fajar sekadar memeriksa kembali
apakah telah kukunci semua jendela dan pintu rumah.
1998-2006
ANNE
Anne, dengarkan pohon-pohon berbisik, "Bukankah Listz sungguh cerdas dan pencemas?"
Waldesrauschen dan kulitmu pucat dan hawa pengap mengajari rasa takut dengan keberanian yang bekap.
Di kota ini aku mudah jatuh hati pada gadis beralis gerigis, seperti keluhku padamu, pada langit warna biru.
Malam bertambah panjang seperti ranjang yang bimbang.
Tak masuk akal jika seekor ikan terperangkap rok dalam.
Biarlah keanehan tetap milik setia tiran tua atau Ahasveros yang celaka, katamu.
Di kota ini aku akan terus jatuh hati pada gadis berbibir tipis, seperti sayangku padamu, pada serdadu tak berpeluru.
Dengarkan pohon-pohon itu berbisik, "Bukan. Ini tarian perang."
Seseorang meniup lilin ulang tahun dan kau jilat leherku dan kurangkum ranum dadamu.
Tidak, seperti cinta, keajaiban milik semua orang, juga demonstran yang hilang di jalan, dengan tangan kekal mengepal.
Anne, dengarkan pohon-pohon berbisik, "Dengarlah, demi Tuhan. Ini tangisan negeri yang malang."
1998-2006
IKEBANA
Pot itu terlalu buncit. Di tepi meja sempit ia seperti perut kurcaci, dan Puteri Salju itu tertawa geli.
Merangkai daun pakis dan mawar merah dan gladiul, pada pukul tiga dini hari, bukankah majnun?
Tapi ia berkata, "Adakah cinta tanpa sesuatu yang gila dalam kulum lidahnya."
Dua sendok gula kau susupkan ke dalam cangkir teh panas itu.
"Di ujung bawah singletmu telah kusulam huruf awal namamu," katamu.
Bercakaplah dengan desir angin, dan kutub jendela dan sepatu berdebu itu.
Sebab di pagi hari ketika sejumlah orang masih sembunyi, mungkin dalam mimpi, ia akan pergi dan melupakan sikat gigi di atas meja pucat,
di pinggir kasur lipat, menindih sepucuk pesan singkat,
"Terimalah seluruh keluhku dan rangkai bunga itu dan peluhku yang masih melekat di liat lehermu. Esok aku kembali. Menjemput sepasang sekam matamu dan membacakan sebuah puisi."
Esok, begitu pilu janji itu. Sebab mungkin berarti sebuah senja, di tahun berikutnya, ketika hujan pertengahan bulan penghabisan akan menyentuh alismu
dan payung basah dan kau menangis sendiri di malam yang resah.
Kau pun menulis di halaman sekian buku harian, dengan kesedihan yang enggan.
"Ia datang dengan mata yang tajam. Kata-kata yang menggetarkan tubuh telanjang dan nafas tertahan. Ia datang dengan lambung yang sakit. Cinta yang rumit. Seperti tekstur wayang kulit."
Setelah malam itu, dari langit-langit kamarmu, kerap wajahnya menghimpit sesak dadamu.
1997-2006
MOLTO ALLEGRO
Seperti Neruda lelah menjadi manusia, malam itu aku pergi dan memanggil taksi.
Ke mana? Ke mana saja, jawabku.
Aku pun lewat di depan rumahmu. Namun telah lama kau pergi dari rumah itu, rumah itu, begitu saja, seperti dulu kau lari dari mimpi-mimpiku.
Dari balik jendela, kota sungguh sepi. Bagai gunting di atas genting.
Ajaib benar jika tiba-tiba bertemu Tuhan dan Tchaikovsky di sebuah persimpangan jalan.
Tetapi perempuan-perempuan aneh itu terlalu berani memamerkan tato mereka, di bahu yang terbuka. Aku takut sepatuku berdebu, jadi kuberi mereka lambaian tangan saja.
Berhenti di depan Fame Station seraya mengucapkan terimakasih pada sopir yang mengerti kesedihanku.
Asia-Afrika, kau tidur seperti bayi. Bangun dan peluklah Don Quixote malang ini, pengembara penuh duka, jatuh cinta berulang kali pada perempuan yang sama.
Perempuan yang sama.
Orang dewasa yang selalu takjub pada kemurungan tak terduga.
Setiap satu langkah, kulihat makam ibuku, lembab oleh tangisan masa kecilku.
Seperti Neruda lelah menjadi lelaki, aku berpikir mengakhiri dengan paksa hidupku di sini.
Namun kutemukan Mozart di kamar sebuah hotel dekat Simpang Lima.
Molto Allegro. Molto Allegro. Adakah juga kekasihku menunggu di situ?
Perjalananku berakhir di atas single-bed yang nyaman. Aku tertidur seperti buaian dan dalam mimpiku perempuan bersayap menyelasar tubuhku dengan ciuman-ciuman.
"Sungguhkah kau lelah menjadi lelaki?" bisiknya, ringan bagai udara kamar.
Pagi, kutemukan jawaban kesedihanku malam itu:
Risau atau murung atau kehilangan sepasang alismu yang tebal.
1997-2006
IDA
Hanya harum rambutmu yang mampu membangun kamar-kamar sunyi dalam batinku.
Karena matamu, malam menepis cahaya, kelam menjauh dengan takut dan cemburu.
Sejarah risauku mencatat nama-nama lara bagimu. Namun bagai janji kau tetap setia pada pagi hari, meluruskan untukku baju hari itu, dan aku pun pergi ke riuh yang jauh
(setelah kau cium punggung tanganku).
Di ujung hari di ruang tunggu, kamar-kamar hotel, dan kedai-kedai kopi, bersama daun dan duka kutulis berlembar-lembar puisi dan kubakar kembali.
Senyummulah puisiku.
Di meja makan, tiada yang lebih indah dari percakapan-percakapan.
Kucuri semangkuk kenangan, di tengkukmu, di bahumu, di bibirmu yang lembut karena malu.
Di keriangan meja makan ini kusembunyikan sepuluh tahun ketakutanku pada malam hari dan cinta dan maut yang rahasia.
Dini hari sudah. Kukecup pelan keningmu, di situ mimpi dan bayang-bayang Mengerutkan kisah masa silammu.
Kepada harum rambutmu aku selalu kembali, membuat beberapa pengakuan, menulis sejumlah syair kesedihan.
Ida, Ida, kaukah Antonia dalam tubuh Yuraku yang terluka.
1997-2006
SYAIR KEMURUNGAN
Menulis puisi pada sebuah malam yang sedih. Seseorang bersenandung. Kemurungan riang berpendaran menangkap cahaya pada tirai jendela.
Langit mewarnai malam seperti coklat yang meleleh. Kutunggu kedatangan seorang kawan dengan kata-kata tajam, keluar dari pintu kepiluan. Sia-sia.
Sepasang payudara bergetar, baling-baling berpusing dalam kamar.
Seseorang bergumam bagai desah penujum di depan bola kristal. Tubuhmu pun beserpihan dalam gelap menjadi butiran-butiran cahaya.
Seluruh kesedihan berawal di sini. Pada ujung helai rambutmu yang runcing. Kabut dini hari matamu, segelas sirup markisa dan cinta yang kucium dari hembusan sunyi nafasmu.
Kubaca halaman terakhir buku cerita negeriku di ruang tamu. Di sebuah tempat, lemari es berdengung dingin, begitu pun dadamu.
Seseorang, mencium leherku. Ringan bagai mimpi.
Kutampung tubuhmu yang beserpihan. Angin menyelundup dari lubang pintu, menerbangkan separuh sayap kupu-kupu.
Menyayat separuh tubuhku.
1996-1999
SYAIR KESEDIHAN
Kusadari malam itu, matamu kata-kata. Pohon cemara sendiri dalam hujan, mengubah kelopak-kelopak airmata jadi permainan cahaya.
Aku melihat seorang anak perempuan pada matamu yang ragu. Mencoba helai demi helai sayap rapuh kupu-kupu; bermimpi menyihir batang cemara jadi sepotong coklat raksasa.
Hidup dan mati seorang penyair berkawan kata-kata. Kata adalah ruh dan keajaiban; keriangan dan kesedihan.
Sebab matamu kata-kata malam itu, aku menjadi seorang pencinta.
Kutanggalkan tubuh penyairku dan kuciumi wangi kerudung rambutmu.
Dari dunia yang murung, Zamzam berkata, "Penyair tidak sedih karena ditinggalkan."
Tidak. Penyair adalah pemburu kesedihan.
Bagi penyair, kesedihan yang sempurna sorga yang dijanjikan.
Hanya pencinta yang tidak pernah bersedih karena ia tahu kelak akan ditinggalkan.
Seorang penyair dan seorang pencinta mengembara dalam tubuhku.
Maka biarkan kuiris matamu dengan puluhan kecupan.
Lukai aku dengan kesedihan.
1996-2006
GERIMIS
Di sudut sebuah perpustakaan yang mengandung angin basah pada bingkai-bingkai jendelanya, aku menemukan kembali wajahmu yang gaib itu.
Mencair dari kebekuan kenangan dan malam-malam penuh siraman cahaya bulan purnama.
Aku ketuk pintu terkunci itu, hujan hari terakhir bulan Desember menyisakan butir-butir embun berpendaran pada ujung rambutmu yang jauh.
Begitu sukar memahami dirimu sebagai pertemuan biasa atau kebetulan saja.
Aku kesepian dan tak mengerti.
Wajahmu memandangku di mana-mana, menangis tanpa airmata.
Aku susuri jalan darahku sendiri. Takjub menemukan kepingan-kepingan luka membangun dunianya sendiri.
Di sudut sebuah pura desa yang disapu gerimis sepanjang hari, kukecup kedua kelopak matamu dengan seluruh hatiku.
Dosa begitu manis dalam lidahku, barangkali seperti khuldi.
Dari pagi berkabut itu aku memulai pengembaraanku yang abadi.
Mencari sepucuk pesan dari kata-kata yang tak sempat kau ucapkan.
1994-2006
SEBELUM MAKAN MALAM
Kita cuma bisa bersandar pada waktu, Afuz. Tertegun-tegun menunggu kekuasaan tumbuh dewasa:
Tanpa peluru, sepatu berlumpur darah itu, dan belajar membaca manusia sebagai kumpulan keinginan dan kesedihan.
Bukan fosil atau gambar separuh badan sebagai sasaran tembakan.
Seperti engkau, aku lahir dari sebuah sejarah yang lecak dan selingkuh.
Tetapi kita mencintai negeri yang sama, yang senyumnya bagai impian, seperti pada masa remaja kita mencintai wanita yang sama, yang senyumnya bagai buaian.
Cinta dan kekuasaan bersandar pada waktu, Afuz, seperti babad rambutmu yang menipis dan hikayat luka dalam aliran darahku.
Segalanya menjadi selalu mungkin: Barangkali karena ada rumah kanak-kanak dalam batin kita
yang penuh senyum dan gelak tawa.
Bahkan ketika pecahan mortir dan kenangan menderas dari jauh dan jatuh dua kaki dari lubang persembunyian, juga impian, kita yang rapuh.
Seperti Peter Pan, Tom Sawyer atau Bimbilimbica, kita menunggu hadiah ulang tahun bukan saja dari pasangan paman dan bibi yang tambun dan riang.
Tetapi juga dari sahabat khayalan, Tuhan, serdadu yang mulutnya penuh roti, sepasang granium, tiga grasia, dan peri-peri riuh di hutan-hutan jauh.
1994-2006
PADA WAJAH DAUN-DAUN
Zlata
Pada wajah daun-daun senja yang lembab itu kulihat engkau sendiri menari.
Lambaian demi lambaian telapak tanganmu menciptakan pusaran angin, menjelma badai batinku.
Di negeri tak lagi bernama, malam menggigil dalam pelukanmu.
Ah, seperti liebestraum, gumammu pada angin sambil menyebut sebuah nama.
Barangkali Liszt, Anne, Alice, atau sekeping bunyi muntahan mortir pecah pada dini hari berkabut negeri porak-poranda itu.
Di sini cinta, katamu di masa lalu, kekal pada kesunyian kayu salib dan bulan sabit.
Namun pada senja yang lembab itu,
kulihat engkau pada wajah daun-daun.
Sendiri menari. Riang dan kekanak-kanakan; seperti sejarah negeriku.
Kerlingan demi kerlingan bola matamu menciptakan pusaran duka.
Dalam batinku.
1994-2006
EPISODE TERAKHIR DARI KENANGAN
Ketika waktu berhenti, kota-kota menghapus jejak airmatamu dengan keheningan kenangan.
Aku tak lagi mampu mengingat kapan kisah cinta itu dimulai,
kapan selesai.
Barangkali pada sebuah senja di bising kota asing dan kumuh, pada beranda sebuah hotel di ujung jalan riuh.
Atau dalam kafe tanpa nama, tanpa daftar menu.
Kota-kota berangkat tua dalam batinku. Namun senyummu abadi seperti sebaris sajak Po Chu-i.
Senja yang kusimpan dalam ingatan kini lapuk dan berlumut.
Tetap saja sukar kubedakan keajaiban dongeng dan kepiluan masa silam.
Ketika waktu berhenti, kukenang kembali airmatamu yang menari:
Di situ senja yang tak terlupakan diciptakan. Dan cinta, disapa dengan ribuan nama.
1994-2006
SAYAP KENANGAN YANG TERBAKAR
Empat puluh mil dari kenangan. Bulan jatuh ke dalam lubang kelinci.
Di negeri ajaib ia mengaku bernama Alice dan menulis sepucuk surat cinta pada sebuah tempat tanpa nama, barangkali, kenangan.
Angin menerbangkannya ke negeri-negeri jauh di Timur; tempat anggur dan matahari, syair dan malam hari, berdegup dalam jantung Li Po dan Sa`di.
Berabad-abad sesuatu yang mengaku sejarah menyimpan surat itu. Sayap burung-burung Attar menyampaikan ia padaku.
Kupesan ratusan cermin. Tetapi cermin tak sejernih sungai yang mengalir dalam hutan pagi hari.
Kelopak-kelopak air memantulkan sepasang alismu yang menari.
Alice, akhirnya kutemukan engkau di situ.
Empat puluh mil dari kenangan. Bulan keluar dari dalam lubang kelinci.
Di negeri sepatu serdadu dan selongsong peluru kau tak mengaku bernama apa pun, kepada siapa pun.
Tak mungkin kau tulis sepucuk surat cinta lagi. Sebab kedua tanganmu tertinggal di negeri tanpa peta. Dan kedua matamu jadi ribuan lentera di negeri tanpa cahaya.
Kubuang sejarah dalam diriku untuk mendekap dan mengecup keningmu berulang-ulang.
Tetapi kenangan melebar ribuan mil, dan sayap burung-burung Attar terbakar dalam batinku.
1994-2006
EMPAT MIL DARI KENANGAN
Sepasang angsa di sudut taman pom bensin: Kusaksikan keajaiban dongeng dan biografi bersatu di situ.
Seperti Wilde yang murung di depan sajak Ginsberg dan Rendra.
Kota-kota tanpa patung "Happy Prince" menyimpan dendam dan keinginan diam-diam pada kematian.
Bagai puisi Malna dalam saku celana kekuasaan.
O, ke mana orang-orang pergi begitu bergegas pada dini hari yang riuh ini?
Di luar jendela para penyair, borgol dan selongsong peluru mengubah dirinya menjadi bahasa.
Sayangku, di sebuah tempat dalam kenangan, Sa`di kehilangan lentera, Tardji kehilangan ngiau,
aku kehilangan engkau.
1994-2006
KENANG-KENANGAN
Bagaimana harus kuucapkan pengakuan ini: Aku jatuh cinta berulang kali pada matamu, danau dalam hutan di negeri ajaib yang jauh menyelusup dalam ingatan itu.
Berabad-abad yang lalu, kuucapkan selamat tinggal pada apa pun yang berbau dongeng, atau masa silam.
Tetapi cinta, bukan sebotol coca-cola. Atau film Disney; di sana tokoh apa pun tak pernah mati.
Juga bukan Rumi yang menari.
Sebab pada matamu bertemu semua musim, sejarah, dan sesuatu yang mengingatkan aku pada suatu hari ketika waktu berhenti, dan kusapa engkau mesra sekali.
Kini, bahkan wajahmu samar kuingat kembali.
Haruskah kuucapkan pengakuan ini: Aku jatuh cinta berulang kali pada matamu, danau dalam hutan di negeri ajaib yang jauh menyelusup dalam ingatan itu.
Tetapi cinta, bukan sekotak popok kertas.
Atau sayap sembilan puluh sembilan burung Attar yang terbakar.
Cinta, barangkali, kegagapanku mengecup sepasang alismu.
1994-2006
SELANGKAH DARI MATAMU
Ketika laut tumpah ke dalam matamu, cerita tentang bulan, matahari dan hapalan ilmu bumi bergegas kusimpan di rak buku.
"Akulah Sinbad, si penakluk alam dongeng dan bajak-bajak samudera!" seruku pada daun pintu, dinding kamar dan lambaian rambutmu.
Lalu kugulung kain layarku dan mendirikan kemah-kemah jauh di seberang laut itu.
Berumah di balik bukit membangkitkan pengalaman asing dan kenangan.
Tapi bau lezat rambutmu mengenalkan petualangan yang lain.
Segera aku menjadi pendongeng: Di mataku berpasang-pasang mata kanak-kanak beribu pada laut matamu.
1993-2006
KEDUKAANMU DIKABARKAN BURUNG-BURUNG
Sejak kau tiba-tiba enggan menyapa bunga-bunga daun-daun gugur lebih cepat dari biasanya
dan embun pergi diam-diam tanpa sepucuk pun pesan
kedukaanmu dikabarkan burung-burung pada angin dan senja, mengalir bersama arus sungai-sungai jauh ke kebisuan samudera
Sejak kau enggan bermain bersama kepik-kepik lagi pagi gelisah di depan pintu sepi rindu gelak tawamu yang lepas bagai kanak-kanak yang gembira menemukan mainannya kembali
kedukaanmu dikabarkan burung-burung pada angin dan senja, mengalir bersama arus sungai-sungai jauh ke kedalaman hatiku
1992
SEBAB BAGAI ANGIN
Jangan pergi. Sebab bagai angin aku selalu bersama arah. Tak ada yang bisa sembunyi dari rindu batinku.
Jangan pergi. Sebab bagai angin kelak aku sampai di negeri yang ditujumu. Mungkin lebih dulu.
Biarkan kulabuhkan sampan lempungku di tepian telaga bening matamu itu.
1991-1992
JAKA TARUB
Tentu, itu bukan taman. Pagarnya telah patah-patah
pagar bambu tua lusuh dengan cat yang mengelupas. Saksi bagi banyak peristiwa. Juga bagi duka. Tak ada Mawar
di sana, begitu pula Anggrek dan Melati. Di sudut diam letih bekas batang pohon kertas. Dulu banyak bunganya. Di sudut itu pun ada bekas kolam. Sekarang tak ada airnya.
Pernah kolam itu menjadi tempat bermain yang menyenangkan. Bagi ikan-ikan mas dan mujair. Dulu, selagi penuh airnya, sering aku membayangkan diriku menjadi liliput. Bersama semut-semut
mengarungi kolam itu. Bersampan daun-daun. Segalanya tumbuh di sana begitu saja. Bergantung pada angin dan musim. Tentu, itu bukan kebun bunga. Meskipun tumbuh
Anyelir di tengah-tengahnya. Warnanya semburat kuning. Bagai warna layung. Mereka bagai puteri yang tersesat. Di hutan lebat. Sayang kolamnya tak ada airnya. Jika ada,
mereka tentu mandi di sana. Sekuntum Anyelir kupetik tadi pagi. Kusimpan di jembangan bunga. Kelak ia bakal pulang ke negeri asalnya. Entah di mana.
Seperti Jaka Tarub, aku kembali sendiri.
1991-1999
SEPASANG DAUN GUGUR
Bagai sepasang daun gugur kita bacakan bersama puluhan puisi angin sebelum akhirnya tiba di rumah kekal kita
Kita hamparkan sajadah rerumputan saling membasuhi luka pada sisa-sisa air hujan yang menggenang
di Timur fajar kizib menahmidkan pagi
Dalam cahaya kugenggamkan mahar lempungku pada kedua telapak tanganmu
O, dengarlah! dadaku gemuruh sungai yang bersyukur
1990-1992
Sekilas tentang Penyair:
Cecep Syamsul Hari was born in Bandung, West Java, Indonesia, May 1, 1967. As a poet, his early reputation rested on Kenang-kenangan (1996, Remembrance) and Efrosina (Euphrosyne, first published in 2002, reprinted in 2005).
His works also internationally published in several journals and anthologies such as: Heat Literary International (Sydney, Australia,1999), Beth E. Kolkos Writing in an Electronic World: a Rhetoric with Readings (United States: Longman, 2000), Harry Avelings Secrets Need Words: Indonesian Poetry 1966-1998 (United States: Ohio University Press, 2001), Wasafiri (London, England, 2003), Orientierungen (Bonn, Germany, 2/2006).He had translated several books. Among of those are: Para Pemabuk dan Putri Duyung (selected poems of Pablo Neruda, 1996); Hikayat Kamboja (selected poems of D.J. Enright, 1996); Ringkasan Sahih Bukhari (compilation of Bukhari's hadis, 1997; 1100 pages); Rumah Seberang Jalan (selected short
stories of R.K. Narayan, 2002). Hes also editor of Kisah-kisah Parsi/Persian Tales (C.A. Mees Santport and H.B. Jassin, 2000); Horison Sastra Indonesia/A Perspective of Indonesian Literature (with Taufiq Ismail, et.al; four volumes, 2003); Horison Esai Indonesia/A Perspective of Indonesian Essays (with Taufiq Ismail, et.al; two volumes, 2004). In 2006, he stayed in South Korea as as a Writer-in-Residence. He was invited by Korea Literature Translation Institute (KLTI) and the Korean Ministry of Culture and Tourism (ACPI). Since December 2007 until February 2008 he has staying in Selangor, Malaysia, as a writer in residence by Rimbun Dahan Arts Residencys invitation. Currently, Cecep Syamsul Hari is editor of HORISON, a monthly literary magazine, Jakarta, Indonesia.
Anda mungkin juga menyukai
- Buah Rindu 1Dokumen12 halamanBuah Rindu 1syifakeBelum ada peringkat
- (Monolog) Anak KabutDokumen5 halaman(Monolog) Anak KabutWi Nugraha RohmadBelum ada peringkat
- Kumpulan Karya Puisi Ws RendraDokumen57 halamanKumpulan Karya Puisi Ws RendraZa Bhie50% (2)
- PUISI-PUISI BARUDokumen17 halamanPUISI-PUISI BARUahmad faruqBelum ada peringkat
- Rok Raven - 1-16Dokumen16 halamanRok Raven - 1-16budibasahBelum ada peringkat
- Wangi Kaki IbuDokumen8 halamanWangi Kaki IbuAbid ClaudioBelum ada peringkat
- Puisi Penyair KalbarDokumen83 halamanPuisi Penyair KalbarRoeLeeArtBelum ada peringkat
- Ebook Kumpulan Puisi Ws RendraDokumen62 halamanEbook Kumpulan Puisi Ws RendraarfiBelum ada peringkat
- PETI MATI KEKASIHKU Monolog BandarnaskahDokumen10 halamanPETI MATI KEKASIHKU Monolog BandarnaskahLuffy D'monkeyBelum ada peringkat
- Ibu yang dibunuhDokumen6 halamanIbu yang dibunuhRita AgustiniBelum ada peringkat
- Rotasi RotasiDokumen68 halamanRotasi RotasiRobby Satria ManurungBelum ada peringkat
- Puisi FacebookDokumen35 halamanPuisi FacebookRoman Recehan ImpresionisBelum ada peringkat
- MaryamDokumen8 halamanMaryamMatzen AbdullahBelum ada peringkat
- Datanglah Diriku Yang HilangDokumen3 halamanDatanglah Diriku Yang Hilangalwan7Belum ada peringkat
- Anak KabutDokumen3 halamanAnak KabutjanahromuBelum ada peringkat
- Racauan Oleh Vernanda KrishnaDokumen22 halamanRacauan Oleh Vernanda KrishnaMugi AnggariBelum ada peringkat
- Final PuisiDokumen22 halamanFinal PuisiFitria Tetap SemangatBelum ada peringkat
- Sajak Goenawan MohamadDokumen9 halamanSajak Goenawan MohamadSamuel Adi PutraBelum ada peringkat
- Puisi Puisi Koran Tempo46Dokumen217 halamanPuisi Puisi Koran Tempo46Hagai HutabalianBelum ada peringkat
- DocumentDokumen40 halamanDocumentMahdi SingaparadoBelum ada peringkat
- DarwishDokumen5 halamanDarwishMelodia Metafora100% (1)
- Sajak Pohon TumbangDokumen18 halamanSajak Pohon TumbangDian MardhikaBelum ada peringkat
- Puisi RendraDokumen9 halamanPuisi RendraEko TriyantoBelum ada peringkat
- MardiLuhung LorongDokumen11 halamanMardiLuhung LorongJoshua SentosaBelum ada peringkat
- Kumpulan SajakDokumen73 halamanKumpulan Sajakagung gemaBelum ada peringkat
- Agung Gema Nugraha Kumpulan PuisiDokumen50 halamanAgung Gema Nugraha Kumpulan Puisiagung gemaBelum ada peringkat
- @lampiran PEKSIMIDADokumen33 halaman@lampiran PEKSIMIDAIndah AdeliaBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi SMPDokumen11 halamanKumpulan Puisi SMPRafki TiskaBelum ada peringkat
- Kumpulan Sajak AGUNG GEMA NUGRAHA NYANYIAN CINTA GELANDANGANDokumen67 halamanKumpulan Sajak AGUNG GEMA NUGRAHA NYANYIAN CINTA GELANDANGANagung gemaBelum ada peringkat
- Belajar PuisiDokumen35 halamanBelajar PuisiCase JombangBelum ada peringkat
- Contoh Puisi Lirik Elegi Ode Dan SerenadaDokumen7 halamanContoh Puisi Lirik Elegi Ode Dan SerenadaHantu. LautBelum ada peringkat
- Puisi Terjemahan HB YassinDokumen24 halamanPuisi Terjemahan HB YassinAyege ChristianBelum ada peringkat
- Contoh Puisi BaladaDokumen7 halamanContoh Puisi BaladaOlimpianus SinurayaBelum ada peringkat
- Sebuah Pagi Dan Seorang Lelaki Mati - Noviana KusumawardhaniDokumen2 halamanSebuah Pagi Dan Seorang Lelaki Mati - Noviana KusumawardhaniDian Martha Nurrul AmanahBelum ada peringkat
- Anak YatimDokumen4 halamanAnak YatimMuhammad Luthfi Az ZuhriBelum ada peringkat
- Putri Tidur Dan Pesawat TerbangDokumen4 halamanPutri Tidur Dan Pesawat TerbangHumairah AdiwijayaBelum ada peringkat
- MDokumen114 halamanMagung gemaBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi-Puisi Chairil AnwarDokumen65 halamanKumpulan Puisi-Puisi Chairil Anwarhennyazalea9434Belum ada peringkat
- Puisi AkuDokumen6 halamanPuisi Akududdy_hermawanBelum ada peringkat
- Kumpulan PuisisDokumen16 halamanKumpulan PuisisRizal AdBelum ada peringkat
- Menari Dalam BayanganDokumen4 halamanMenari Dalam BayanganBudi SetiyonoBelum ada peringkat
- PUISI_RENDRADokumen71 halamanPUISI_RENDRAichigoadtBelum ada peringkat
- Tanah Ambarawa yang KucintaDokumen7 halamanTanah Ambarawa yang KucintaTangguhspBelum ada peringkat
- Kumpulan SajakDokumen19 halamanKumpulan SajakRandi Tri AntoniBelum ada peringkat
- Sajak Saut SitumorangDokumen19 halamanSajak Saut SitumorangSoni Tri Harsono100% (1)
- Cinta Dalam GelasDokumen170 halamanCinta Dalam GelasdyahBelum ada peringkat
- Seikat Puisi Ulang TahunDokumen4 halamanSeikat Puisi Ulang TahunFahmy Khoerul HudaBelum ada peringkat
- M.dwi Ridwan W.N - Xi-9 - 20 - Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanM.dwi Ridwan W.N - Xi-9 - 20 - Bahasa IndonesiaIrsyad Hanan r.kBelum ada peringkat
- DEMIKIANLAH WAKTU BICARADokumen10 halamanDEMIKIANLAH WAKTU BICARAReza MuhammadBelum ada peringkat
- PT 1Dokumen3 halamanPT 1Mishelle PepitoBelum ada peringkat
- Antologi Puisi Kategori UmumDokumen12 halamanAntologi Puisi Kategori UmumSiti kamilahBelum ada peringkat
- PuisiIndraTjahyadiDokumen21 halamanPuisiIndraTjahyadiIsnadiarBelum ada peringkat
- Zineuri Vol1Dokumen41 halamanZineuri Vol1Dipantara MaqdisBelum ada peringkat
- Malam Ketika Dia Menembak Dirinya (Kumpulan Cerpen)Dari EverandMalam Ketika Dia Menembak Dirinya (Kumpulan Cerpen)Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Trilogi Pelelangan: Sebuah “Jane Eyre” Zaman Modern (Bahasa Indonesia)Dari EverandTrilogi Pelelangan: Sebuah “Jane Eyre” Zaman Modern (Bahasa Indonesia)Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (7)
- Malaikat Pelindung Gotik (Bahasa Indonesia) (Indonesian Edition)Dari EverandMalaikat Pelindung Gotik (Bahasa Indonesia) (Indonesian Edition)Belum ada peringkat
- Pedoman Beasiswa JFL PDFDokumen18 halamanPedoman Beasiswa JFL PDFMutia AnisaBelum ada peringkat
- Jbptunikompp GDL Yogafebrya 27023 4 4.uniko R PDFDokumen3 halamanJbptunikompp GDL Yogafebrya 27023 4 4.uniko R PDFAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat
- Surat Pengajuan Balita Lembang-PreweddingDokumen1 halamanSurat Pengajuan Balita Lembang-PreweddingAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat
- Surat Pengajuan Balita Lembang-PreweddingDokumen1 halamanSurat Pengajuan Balita Lembang-PreweddingAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat
- LAPORAN INISIASIDokumen24 halamanLAPORAN INISIASIAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat
- TA-Pengetahuan BisnisDokumen17 halamanTA-Pengetahuan BisnisAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat
- Modul 5 - Pemodelan Proses RevisiDokumen15 halamanModul 5 - Pemodelan Proses RevisiAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat
- Contoh CVDokumen3 halamanContoh CVAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat
- Sekolah Cimahi & BandungDokumen7 halamanSekolah Cimahi & BandungAdhityarismawan MoodutoBelum ada peringkat