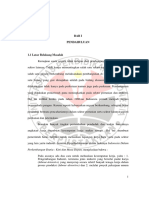Perkembangan Permukiman Dan Tipologi Rum PDF
Perkembangan Permukiman Dan Tipologi Rum PDF
Diunggah oleh
Inoenk PodheyJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Perkembangan Permukiman Dan Tipologi Rum PDF
Perkembangan Permukiman Dan Tipologi Rum PDF
Diunggah oleh
Inoenk PodheyHak Cipta:
Format Tersedia
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/315528123
PERKEMBANGAN PERMUKIMAN DAN TIPOLOGI RUMAH-TINGGAL PADA
PERUMAHAN KARYAWAN PABRIK GULA PESANTREN BARU-KEDIRI
Article · March 2008
CITATIONS READS
0 436
1 author:
Antariksa Sudikno
Brawijaya University
184 PUBLICATIONS 55 CITATIONS
SEE PROFILE
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
Kosmologi Ruang View project
All content following this page was uploaded by Antariksa Sudikno on 23 March 2017.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
PERKEMBANGAN PERMUKIMAN DAN TIPOLOGI
RUMAH-TINGGAL PADA PERUMAHAN KARYAWAN
PABRIK GULA PESANTREN BARU-KEDIRI
Dian Wicaksono, Antariksa, Harini Subekti
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Jl. Mayjen Haryono 167, Malang 65145
e-mail: antariksa@brawijaya.ac.id
ABSTRAK
Pengaruh kolonialisme di setiap wilayah Nusantara sangat luas, hal ini disebabkan
masa penjajahan Belanda sangat lama. Salah satu hasil pengaruh kolonial yang masih
terlihat jejaknya sampai sekarang, yaitu pabrik gula, meskipun secara umum ada
persamaan. Namun, masing-masing mempunyai bentuk perkembangan arsitektur yang
khas, berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dalam mengkaji arsitektur
kolonial Belanda di suatu wilayah, dilakukan dengan jalan mengkaji kasus per kasus.
Metode penelitian ini adalah studi kasus, dengan pendekatan sejarah menyangkut
perkembangan kawasan dengan sudut pandang arsitektur, menyangkut perkembangan
tata permukiman dan tipologi rumah-tinggal. Kasus penelitian adalah perumahan
karyawan Pabrik Gula Pesantren Baru, Kediri. Perpindahan lokasi pabrik dan kantor
merupakan ciri yang menonjol dari pabrik gula ini, sehingga berbeda dengan kondisi
pabrik gula sejenis yang ada di seluruh Indonesia. Kecenderungan gaya arsitektur
kolonial di dalam kompleks pabrik diwarnai dengan gaya arsitektur lain yang membuat
wajah perumahan karyawan ini mempunyai ciri arsitektur yang beragam.Hasil penelitian
ini, yaitu perkembangan tata lingkungan di permukiman Pabrik Gula Pesantren Baru,
yang dibagi menjadi tiga zonasi ruang, yaitu Zona Privat, Zona Semi Publik, dan Zona
Publik (semakin bertambah luas areanya). Ditinjau dari hasil pembagian periodesasi
ternyata mempunyai pengaruh terhadap tipologi rumah-tinggal. Salah satu faktor
penyebabnya, yaitu masa pemerintahan yang berbeda, yaitu tahun 1890 (pemerintahan
kolonial Belanda), tahun 1958 (pemerintahan Orde Lama) dan tahun 1979
(pemerintahan Orde Baru). Ditinjau dari tipologi geometri, fungsi dan zonasi ruang, yaitu
kolonial dan pasca kolonial.
Kata kunci: perkembangan permukiman, tipologi rumah-tinggal, pabrik gula
ABSTRACT
The colonialism power in every region archipelago is extremely wide; this reason
caused of a long time colonization period of the Dutch. One of the colonial influence
records it can be seen awaiting to the recent day, that is the sugar industry, in spite of in
generally is similar. Nevertheless, in that order contain a figure of architecture
development characteristic dissimilar with the others. Because of in the Dutch colonial
architectural studies in an area carry out with case by case. Research methods used in
this study is case study, with historical approach relate to development area
accompanying to the architecture point of view, included the development of settlement
arrangement and housing typology. The research object is employee housing of
Pesantren Baru sugar industry in Kediri. The removal area of industry and office
comprise a characteristic that shown from this sugar industry, in anticipation of dissimilar
with the condition of sugar industry variety which be existent in the entire of Indonesia.
The tendency of colonial architecture style in industrial compound with other a variety of
architecture style that create a face of employee housing contain a variety of
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 49
architecture characteristic.The result of this study is the arrangement development of
housing area. The sugar industry Pesantren Baru devides into three zone spaces that is
private zone, semi private zone and public zone (increasingly widespread area). The
observation result from devide into period it appears contain an influence relating to
housing tipology. The one factors is a various government periods, in 1890 (the Dutch
colonial government), in 1958 (Orde Lama Government) and 1979 (Orde Baru
government). Observe from geometric tipology, function and space zone that is colonial
and pasca colonial.
Key words: settlement development, housing typology, sugar industry
Pendahuluan
Kota Kediri semula adalah sebuah daerah di pedalaman Jawa yang tidak
diketahui, lalu berkembang menjadi nama Kerajaan Panjalu yang besar dan sejarahnya
terkenal hingga sekarang. Menurut penelitian dari para ahli lembaga Javanologi,
Soekarton Kartoadmodjo, Kediri lahir pada Maret 804 Masehi. Sekitar tahun itulah,
Kediri mulai disebut-sebut sebagai nama tempat maupun negara (http://www.sejarah
kediri.ac.id)
Diketahui bahwa Kediri mempunyai bentuk pemerintahan sendiri, yaitu Residen
mulai tahun 1908, namun latar belakang berdirinya Kediri sudah dimulai sebelum
kedatangan kaum kolonial dan adanya pengaruh kekuasaan jaman kerajaan, sehingga
perencanaan tata kotanya sudah terbentuk ketika Kediri masih berbentuk kerajaan
(http://www.sejarah kediri.ac.id). Kota kediri mempunyai latar belakang historis sendiri,
sehingga perencana dari pemerintah kolonial sangat membatasi pembangunan fasilitas-
fasilitas pemerintahan dan fasilitas lainnya, Namun, mereka mendirikan pusat
perindustrian dan perdagangan di tiga wilayah kecamatan Kediri untuk memantapkan
kekuasaannya, yaitu wilayah Kecamatan Ngadirejo (PG. Ngadirejo), Kecamatan
Meritjan (PG. Meritjan), dan Kecamatan Pesantren (PG. Pesantren Baru), sehingga
meskipun secara latar historis wilayah kota Kediri merupakan pusat pemerintahan
kerajaan, kaum kolonial mengikis sedikit demi sedikit pengaruh sistem pemerintahan
kerajaan dengan pembangunan fasilitas industri yang mempunyai corak pemerintahan
yang berbeda dengan mengadopsi sistem pemerintahan Eropa.
Tidak dipungkiri lagi bahwa pabrik gula merupakan elemen penting dalam
perekonomian bagi pemerintahan jaman kolonial Belanda, sehingga pertumbuhannya
sangat pesat dengan berdirinya sejumlah pabrik di seluruh Pulau Jawa dan luar Jawa.
Pabrik gula merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang penting di daerah-
daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pabrik-pabrik gula yang berproduksi
khususnya di Pulau Jawa. Selain itu, banyaknya tenaga kerja dari penduduk sekitar dan
bahan baku tebu yang diambil dari lahan perkebunan penduduk sekitar pabrik dapat
membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong majunya
perekonomian di daerah tersebut. Namun, dampak langsung dari pendirian pabrik
tersebut kebutuhan akan persediaan kayu yang cukup besar, sehingga menyebabkan
hutan lenyap, lahan yang sedianya subur dan dipergunakan untuk menghasilkan beras,
ditanami tebu dan banyak buruh yang diambil dari penduduk sekitar dipekerjakan
secara paksa (Kano et al. 1996:50-51)
Pada awal pembangunan pabrik, perumahan karyawan juga dibangun pada awal
abad ke-19, letaknya berdekatan dengan kompleks pabrik kecuali rumah-tinggal
administratur yang bersambungan langsung dengan kantor TUK dan administrasi di
dalam kompleks pabrik, Dalam perkembangannya setelah kemerdekaan pihak pabrik
membangun lagi perumahan karyawan di sebelah selatan kompleks pabrik berdekatan
dengan gudang gula, bernama Kampung Baru. Tahun 1979 Pabrik Gula Pesantren
lama sudah tidak dapat beroperasi lagi. Hal ini disebabkan karena sudah tidak layaknya
jumlah produksi yang dihasilkannya akibat dari kondisi mesin-mesin produksi yang
sudah tua dan rusak, Sebagai gantinya disebelah selatan pabrik gula lama dibangun
50 arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008
lagi Pabrik Gula Pesantren Baru yang lebih modern. Mesin-mesin produksi yang lebih
maju dengan kapasitas produksi yang lebih banyak, sedangkan lokasi pabrik lama yang
sudah tidak dipergunakan lagi dialihfungsikan sebagai emplasement1. Bersamaan
dengan pemindahan dan pembangunan pabrik baru, pabrik juga membangun lagi
perumahan karyawan di sebelah barat kompleks pabrik gula lama, bernama Perumahan
Magersari dan di sebelah selatan pabrik gula baru, bernama Kampung Sawah.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah utama,
yaitu sebagai berikut:
1. Perkembangan permukiman
Dengan adanya perpindahan lokasi pabrik menyebabkan timbulnya tatanan
permukiman baru yang terbentuk di kawasan makro pabrik, hal ini yang sangat menarik
untuk diketahui, bagaimana perkembangan permukiman baru pasca perpindahan lokasi
pabrik gula tersebut.
2. Perkembangan tipologi bangunan
Dengan melihat adanya perkembangan yang terjadi pada lingkungan hunian
rumah-tinggal, yaitu beragamnya tipe rumah dan ciri khas arsitektur yang ada di
lingkungan perumahan karyawan. Maka, hal ini yang sangat menarik untuk diketahui,
bagaimana perkembangan tipologi rumah-tinggal pasca perpindahan lokasi pabrik gula
tersebut.
Untuk mengetahui seberapa besar permasalahan tersebut perlu dilakukan
pengkhususan pada areal lingkungan pabrik gula, dengan fokus penelitian pada tatanan
lingkungan permukiman yang terbentuk ketika awal berdirinya Pabrik Gula Pesantren
sampai sekarang. Elemen-elemen dari tatanan lingkungan permukiman yang dijadikan
variabel yang akan diamati, meliputi pengolahan lansekap/elemen-elemen ruang luar,
struktur lingkungan, jenis dan guna lahan, sedangkan mengenai perkembangan tipologi
dan historis di perumahan karyawan Pabrik Gula Pesantren Baru ini dikhususkan pada
sejumlah rumah-tinggal di kawasan Pabrik Gula Pesantren lama yang dibangun pada
masa pemerintahan kolonial Belanda (zona perumahan kolonial) dan rumah-tinggal
yang dibangun pada masa pasca kolonial (zona pasca kemerdekaan dan zona
perumahan baru). Elemen-elemen tipologi rumah-tinggal yang dijadikan variabel yang
akan diamati, meliputi: ruang, bentuk gubahan massa, gaya arsitektur, material
penyelesaian, tekstur permukaan, pengolahan lansekap juga mencakup status, jenis
dan usia bangunan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan
dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perkembangan permukiman
yang ada di Pabrik Gula Pesantren Baru? Bagaimana tipologi rumah-tinggal karyawan
di Pabrik Gula Pesantren Baru? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk
menganalisa dan mendapatkan suatu gambaran awal tentang kondisi secara umum
mengenai perkembangan pemukiman karyawan Pabrik Gula Pesantren Baru pasca
perpindahan lokasi pabrik, dengan mengidentifikasi hirarki tatanan lingkungan. Untuk
menganalisa dan mendapatkan suatu gambaran awal tentang kondisi tipologi rumah-
tinggal karyawan di Pabrik Gula Pesantren Baru.
Metode Penelitian
• Langkah awal dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder,
berupa
Karakteristik sampel yang dipergunakan untuk mengidentifikasi jumlah yang akan
diambil, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut (Tabel 1):
Langkah I: Populasi diklasifikasikan
Langgam Kolonial
Indische Empire Style
1
Emplasement ialah tempat berhentinya truk-truk pengangkut tebu yang akan masuk pabrik
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 51
Tahun 1930-an
Langgam Pasca Kolonial
Pasca kemerdekaan
Pasca orde baru
Langkah II: Hasil klasifikasi, jumlah rumah diambil 10 %
1. Indische Empire Style
1 rumah x 10% = 0,1
diambil 1 sampel.
2. Tahun 1930-an
a. De Stilj
17 rumah x 10 % = 1,7
diambil 2 sampel
b. Amsterdam School
9 rumah x 10 % = 0,9
diambil 2 sampel
3. Pasca kemerdekaan
16 rumah x 10 % = 1,6
diambil 2 sampel
4. Pasca orde baru
44 rumah x 10 % = 4,4
diambil 4 sampel
Total
Jumlah populasi = 87 rumah-tinggal
Jumlah sampel = 11 sampel rumah-tinggal
Tabel 1. Populasi dan Sampel Pengamatan di PG Pesantren Baru
Jenis Subyek Populasi Variasi Sampel
tipologis
Objek
Perumahan
• Kolonial 27 rumah-tinggal Ada 2 macam 5 sampel
• Pasca Kolonial 60 rumah-tinggal Ada 2 macam 6 sampel
Prasarana/Utilitas
lingkungan
• Jaringan air Sungai, parit dan Semua populasi Semua populasi
saluran air
• Jaringan jalan Jalan aspal, Semua populasi Semua populasi
makadam dan
railban
Sumber : Hasil Survei
Dalam menentukan jumlah sampel ini, ditentukan dahulu jumlah perumahan
karyawan dalam satu klasifikasi langgam kemudian oleh peneliti diambil sampel-sampel
yang terpilih betul menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut.
Pertimbangan pemilihan ini agar sampel memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi,
sehingga dapat dianggap cukup reseprentatif, khusus untuk pemilihan sampel
menggunakan metode Purposive sampling. Pemilihan sampel tidak melihat dari
besarnya populasi pada masing-masing zona perumahan, namun lebih melihat sisi
52 arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008
kriteria arsitektur dan variasi langgam dalam satu zona perumahan, adapun kriteria
rumah-tinggal yang akan dijadikan sampel, yaitu sebagai berikut:
a. Pemilihan pada zona perumahan memperhatikan variasi tipologis arsitektur, baik
fungsi maupun langgamnya dari semua populasi yang ada di perumahan tersebut,
sehingga sampel benar-benar dapat mewakili ciri-ciri yang esensial dari populasi
perumahan tersebut;
b. Untuk sampel rumah-tinggal pada perumahan, pemilihan rumah-tinggal mengacu
pada tata letak rumah-tinggal dalam satu blok massa, sehingga pemilihan dapat
menggali kesemua unsur-unsur arsitektur rumah-tinggal yang berada di bagian
tengah dan bagian samping dari blok massa;
c. Khusus untuk sampel bangunan kolonial, dibatasi pada bangunan-bangunan kuno
yang diperkirakan berusia minimal 50 tahun (mengacu pada UU. No. 5 tahun 1992,
tentang Benda Cagar Budaya). Usia bangunan ini untuk memastikan bangunan
tersebut didirikan pada masa kolonial Hindia Belanda;
d. Masih terawat dan mempunyai penghuni;
e. Diutamakan pada objek yang terletak di sepanjang koridor jalan-jalan utama dan
pada pusat-pusat kegiatan pabrik
Landasan Teori
Pengertian permukiman
Menurut Sujarto (1991), unsur permukiman, yaitu terdiri dari Unsur Wisma (tempat
tinggal); Karya (tempat berkarya); Suka (tempat rekreasi/bersantai/hiburan) dan
Penyempurna (peribadatan, pendidikan, kesehatan, utilitas umum) atau berintregrasi di
dalam suatu lingkungan dan hubungan satu sama lain oleh unsur Marga (jaringan jalan)
Menurut Undang-undang Permukiman nomor 4 tahun 1992, perumahan adalah
kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Lingkup pengaturan
menyangkut penataan perumahan meliputi kegiatan pembangunan baru, pemugaran,
perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatannya.
Menurut Finch dalam Wayang (1980), menjelaskan bahwa permukiman
merupakan tempat hidup manusia dan melakukan berbagai macam aktifitas, sedang
pola permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat (ruang) atau suatu daerah
tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat
untuk mempertahankan, melangsungkan dan mengembangkan hidupnya. Pengertian
pola permukiman dan persebaran permukiman mempunyai hubungan erat. Persebaran
permukiman membicarakan sebab-sebab pemencaran permukiman, sehingga pada
daerah tertentu terdapat permukiman sedang di daerah lain tidak terdapat permukiman.
Persebaran permukiman bervariasi sifatnya, dari sangat jarang sampai sangat padat,
dapat mengelompok, dapat tidak teratur, atau teratur. Pertama permukiman lebih
banyak terdapat pada tanah-tanah yang subur dengan relatif datar yang
menguntungkan untuk pertanian, kedua persebaran yang mengelompok atau tidak
teratur umumnya terdapat pada wilayah-wilayah yang topografinya tidak seragam.
Perkembangan Hunian
Dalam mengamati perkembangan morfologi hunian menggunakan kerangka Zeizel
(1981). Zeizel (1981) dalam Utomo (1990), membuat kerangka yang sangat jelas untuk
mengamati morfologi lingkungan fisik. Metoda pencarian aspek-aspek fisiknya dapat
digunakan untuk mengamati morfologi lingkungan. Ada dua hal yang dikenalkan Zeizel
(1981: 89-136), yaitu bagaimana mencari hal-hal yang berkaitan dengan fisik dan aspek
perilaku.
Dua hal yang dikenalkan Zeizel (1981) dalam Utomo (1990), merupakan hal yang
berkaitan. Keduanya menyangkut bagaimana dialog antara manusia dan
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 53
lingkungannya. Bagaimana lingkungan dimanfaatkan manusia, bagaimana
memanipulasi lingkungan untuk kepentingannya dan lain sebagainya dapat dilihat pada
dua kerangka tadi. Hal ini diperkuat oleh Ruesch & Kees dalam Utomo (1991), yang
menggunakan ekspresi, aktifitas dan fisik untuk mengetahui bagaimana manusia
berdialog dengan lingkungannya.
Menurut Zeizel (1981) dalam Utomo (1990), aspek-aspek fisik yang perlu dicari
adalah:
1. By-product of use
Ini merupakan pencarian jejak/sisa/hasil sampingan suatu kegunaan terhadap fisik
lingkungan. Jejak-jejak tersebut merupakan pencerminan tentang apa yang telah
mereka perbuat untuk kondisi semacam itu, dan yang termasuk kelompok ini adalah
erotions dan leftover.
2. Adaptations for use
Adaptasi ini menunjukkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemakai
dengan membuat lingkungannya sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan yang
diinginkannya, dan yang termasuk adaptasi ini adalah:
3. Displays of self
Ini membantu pihak luar untuk mengelompokkan ke dalam lingkungannya sesuai
dengan identitasnya. Displays of self ini terdiri dari personalisasi (unsur fisik yang
dipakai untuk menunjukkan keunikannya atau individualitasnya) dan identifikasi
(unsur yang dipakai untuk memudahkan pengenalan, identifikasi). Displays of self ini
merupakan simbolisasi untuk menunjukkan siapa dirinya kepada orang lain.
4. Public messages
Hampir sama dengan display of self, perbedaannya bahwa sasaran yang dituju oleh
public messages ini lebih luas dan lingkungannya lebih besar. Pesan-pesan atau
simbol yang disampaikan lebih membawa nama kelompok daripada perseorangan.
Tipologi Arsitektur Hunian
Dalam mengidentifikasikan tipologi arsitektur hunian digunakan parameter seperti
yang ditawarkan oleh Habraken (1988:31-41) dalam Rusdi (1993), dengan pola analisis
yang berkaitan dengan tipologinya Golgolen (t.t.:3-15) dalam Rusdi (1993), yang
bertolak dari dasar perancangan arsitektur yang dipelopori oleh Vitruvius. Parameter
tersebut adalah:
a. Sistem spasial,
Sistem spasial berhubungan dengan pola hubungan ruang, orientasi dan hirarkinya
b. Sistem fisik,
Sistem fisik dan kualitas figural berhubungan dengan wujud, pembatas ruang dan
karakter bahannya
c. Sistem stilistik,
Sistem stilistik berhubungan dengan elemen atap, kolom, bukaan dan ragam hias.
Ciri-ciri Tipologi Arsitektur Kolonial Belanda
Menurut Nix (1935) dalam pamungkas (2002: 17-20), tipe bangunan kolonial di
Indonesia terdiri dari berbagai macam langgam lainnya, disesuaikan dengan
waktu/periodesasi perkembangannya, seperti Voor 1900, NA 1900, Romantiek, gaya
tahun 1915-an dan gaya tahun 1930-an. Untuk lebih lengkapnya mengenai ciri-ciri
umum dari masing-masing corak arsitektur tersebut, yaitu sebagai berikut (Gambar1):
a. Indische Empire-Stijl
Adapun ciri-cirinya antara lain: mengarah ke ciri rumah tinggal Indis tidak
bertingkat dengan atap perisai, berkesan monumental, halaman luas, umumnya massa
bangunan terbagi atas bangunan pokok/induk dan bangunan pengapit/penunjang yang
saling dihubungkan oleh serambi atau gerbang, denah simetris, serambi muka dan
54 arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008
belakang yang terbuka dengan pilar/tiang kolom batu yang tinggi bergaya Yunani (orde
Korintis, Ionik, atau Dorik), antar serambi dihubungkan oleh koridor tengah yang
sekaligus sebagai penghubung pula ruang tidur dan ruang-ruang lainnya, round-Roman
arch pada gerbang masuk atau koridor pengikat antar massa bangunan, serta
penggunaan lisplank-lisplank batu bermotif klasik di sekitar atap.
b. Voor 1900
Corak arsitektur bangunan yang berkembang mulai pertengahan abad ke-19 ini
pada dasarnya adalah Indische Empire-Stijl dengan beberapa perubahan, khususnya
penggunaan bahan bangunan baru dari besi dan penambahan elemen-elemen yang
bertujuan untuk lebih menyesuaikan dengan iklim tropis basah Indonesia. Ciri-ciri utama
yang membedakan dengan corak sebelumnya adalah penambahan luifel-luifel/teritis-
teritis yang terbuat dari seng gelombang dengan sudut kemiringan atap yang lebih
landai dan ditopang oleh konsol besi cor yang bermotif keriting, tiang-tiang kolom batu
klasik diganti dengan kayu atau besi cor yang berdimensi lebih kecil/langsing,
penambahan balustrade/pagar besi atau batu pada serambi, serta penambahan
elemen-elemen ragam hias.
c. NA 1900
Corak arsitektur bangunan ini mulai berkembang pada akhir abad ke-19 sampai
awal tahun 1900-an dan mulai dipengaruhi oleh aliran-aliran romantis (gaya-gaya
eklektik Neoklisikisme) Eropa. Ciri-ciri utamanya adalah tampak bangunan utama yang
mulai asimetri, namun denah relatif masih simetris, serambi muka terbuka memanjang
dengan tiang-tiang kolom sudah mulai menghilang/menyempit, diganti dengan
penonjolan-penonjolan denah sampai bidang muka bangunan, tampilan fasade
bangunan yang mulai menonjolkan elemen vernakular arsitektur (Belanda) berupa
gevel/gable.
d. Romantiek
Corak arsitektur bangunan yang juga berkembang mulai awal abad ke-20 ini pada
dasarnya adalah corak arsitektur NA 1900, namun dengan pengaruh aliran-aliran/gaya-
gaya romantis Eropa yang semakin kuat. Ciri yang paling utama adalah penambahan
atau penggunaan elemen-elemen detil dekoratif yang kaya pada hampir seluruh bagian
bangunan dan elemen-elemen ruang luar (pagar, gerbang dan sebagainya). Sebagai
contoh penambahan dentils, brackets, dan/atau modilions pada bagian bawah
atap/lisplank, penambahan cresting, finial, weathervane, dan/atau balustrade pada
bagian bubungan atap, serta penambahan pada bagian bangunan lainnya (pintu,
jendela, dan sebagainya). Ciri-ciri utama lainnya adalah banyaknya penggunaan
bentuk-bentuk lengkung, serta bentuk atap tinggi (sudut kemiringan besar, antara 45°-
60°) dengan bahan penutup dari genteng.
e. Gaya tahun 1915-an
Corak arsitektur bangunan ini pada dasarnya masih dipengaruhi oleh corak-corak
arsitektur sebelumnya, terutama NA 1900 dan Romantiek, seperti adanya gevel pada
fasade, serambi muka dan penggunaan elemen-elemen detil dekoratif. Ciri-ciri utama
yang membedakan adalah mulai digunakannya atap plat beton datar pada teritis-teritis
(sebagai pengganti teritis-teritis seng gelombang) dan pada koridor-koridor penghubung
antar massa bangunan, adanya bidang ventilasi/bouvenligh di antara garis atap utama
dan badan bangunan). Penggunaan elemen-elemen yang terbuat dari bahan besi cor
sudah banyak berkurang, bentuk lebih sederhana (penggunaan elemen-elemen detil
dekoratif sudah banyak berkurang). Penggunaan variasi mahkota atap umumnya
terbatas pada bagian ujung pertemuan bubungan dan jurai, atap tinggi berpenutup
genteng, serta penambahan atau penggunaan elemen-elemen vernakular arsitektur
(Belanda).
f. Gaya tahun 1930-an
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 55
Corak arsitektur bangunan ini muncul seiring dengan pengaruh perkembangan
aliran-aliran arsitektur modern di Belanda, khususnya Amsterdam school dan De Stijl,
yang keduanya mempunyai konsepsi arsitektural yang saling berbeda. Amsterdam
school lebih menitikberatkan pada orisinalitas dan alamiah, peranan arsitektur
(vernakular) lokal masih cukup besar. Ciri-ciri umumnya adalah bangunan terbuat dari
bahan dasar alam dan menghasilkan bentukan-bentukan yang bersifat masif dan benar-
benar plastis (pengolahan bentuk berdasarkan atas garis-garis melengkung),
ornamentasi skulptural dan perbedaan warna dari material-material yang beragam
(bata, ubin dan kayu) mempunyai peran yang esensial dalam desain, serta bentuk atap
lebih runcing/tinggi (sudut kemiringan antara 45°-60°). De Stilj lebih menitikberatkan
pada fungsi. Ciri-ciri umumnya adalah, permainan volume bangunan berbentuk kubus,
dimaksudkan untuk mengekspresikan keplastisan secara keseluruhan, menggunakan
bahan-bahan dasar hasil pabrikasi (penggunaan blok-blok kubus datar dari batu bata
atau beton, baik untuk atap, teritisan dan/ badan bangunan), gevel horisontal tanpa
dekorasi serta lepas dari permainan warna (didominasi warna putih).
Gambar 2.1 Variasi bentuk corak/langgam arsitektur kolonial Belanda.
Sumber: Nix (1935) dalam Pamungkas (2002: 20)
Pembahasan
Sejarah Singkat PG. Pesantren Baru
Pada awal berdiri, yaitu pada tahun 1849, Pabrik Gula Pesantren yang
memproduksi gula merah adalah milik perseroan dari bangsa Indonesia keturunan Cina,
kemudian pada tahun 1890, perusahaan itu diambil alih oleh Pemerintah Belanda,
sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada NV. JAVASCHE CULTURE
MATSCHAPPIJ (JCM), di Indonesia diwakili oleh NV. NEDERLANDS INDISCHE
LANDBOUW MAATSCHAPPIJ.
Pabrik Gula Pesantren beberapa kali mengalami rehabilitasi yaitu, pada tahun
1911, 1928 dan 1932. Tiga tahun kemudian, yaitu pada tahun 1935 mengalami
pembaharuan dalam produksi gula merah menjadi gula putih. Pada masa
berkecamuknya Perang Dunia II, Jepang berhasil memenangkan Perang Asia Timur
Raya, yaitu pada tahun 1942 dan mengambil alih Pabrik Gula Pesantren hingga tahun
1945. Pada tahun itu pula, pihak Sekutu memenangkan pertempuran. Pada tahun 1957
Pemerintah Sekutu yang diwakili oleh Belanda mengelola Pabrik Gula Pesantren
56 arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008
dengan mengambil tenaga kerja dari Bangsa Indonesia sendiri, dan kepengurusannya
dipegang oleh Perusahaan Negara Perkebunan.
Pada tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengembalikan Irian Barat ke
wilayah Republik Indonesia, pemerintah telah mengambil alih semua perusahaan milik
Belanda yang berada di Indonesia termasuk Pabrik Gula Pesantren. Setelah diambil alih
pengelolaannya yang dilakukan oleh PPN atau Perusahaan Perkebunan Negara, pada
tahun 1960 sesuai UU. No. 9 th. 1960 dibentuk BPU-PPN gula yang mengkoordinir
pengelolaan pabrik-pabrik gula. Berdasarkan PP No. 116 tanggal 26 April 1961 Pabrik
Gula Pesantren termasuk dalam Karesidenan Kediri bersama empat Pabrik Gula
lainnya (PG. Lestari-Kertosono, PG. Meritjan-Kediri, PG. Ngadiredjo-Kediri dan PG.
Modjopanggoong-Tulungagung), dan disusul dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah No. 1 dan 2 tentang Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan
Negara (BPUPPN). Semua pabrik gula tersebut termasuk dalam Direksi Aneka Gula
yang telah Berbadan Hukum sendiri dengan sistem BPUPPN.
Pada tahun 1967 mulai diberlakukan INPRES No. 7 th. 1967 tentang Pengesahan
Pengelolaan Perusahaan Negara, sehingga pada tahun 1968 BPUPPN dibubarkan, dan
semua pabrik gula diseluruh Indonesia di bawah otoritas Departemen Pertanian dan
dibentuk Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) dimana Pabrik Gula Pesantren
termasuk di dalam lingkup PNP. XXI.
Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 th. 1973 yang berlaku tanggal 1 Januari
1974, PNP. XXI menggabungkan diri dengan PNP XXII menjadi PT. Perkebunan XXI-
XXII (Persero). Pada tanggal 19 Juli 1978 oleh Menteri Pertanian Prof. Ir. Soedarsono
Hadisaputro, pemakaian Pabrik Gula Pesantren Baru diresmikan, sedangkan Pabrik
Gula Pesantren Lama diberhentikan pengoperasiannya setahun kemudian, yaitu
tanggal 19 Juli 1979. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 15 th. 1996 tanggal 14
Februari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) mulai tanggal 11
Maret 1996 : PTP XIX, XXI-XXII, XXVI melebur menjadi satu dengan nama Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara X (persero). Dilengkapi pula dengan
akte notaris Harun Kamil, SH. No. 43 tanggal 11 Maret 1996 tentang pendirian
Perusahaan (Persero) PT. Nusantara X.
Analisis Perkembangan Permukiman Pabrik Gula
Berdasarkan gambaran awal dan sejarah, maka tahapan analisis perkembangan
permukiman Pabrik Gula Pesantren, dimulai dan diuraikan dari periode tahun 1890-
1957, 1958-1978 dan berdasarkan variabel penelitian, maka hasil analisis yang
dilakukan, yaitu sebagai berikut (Tabel 2, 3 dan 4):
Tabel 2. Tabel Tatanan Hirarki Periode Kolonial
Permukiman
PG. PESANTREN
Zona Privat Zona Semi- Zona Publik
Publik
Areal Area bangunan Area Poliklinik Perkebunan dan
pabrik dan lapangan lahan di luar area
Rumah dinas tenis peumahan dan
administratur Area garasi dan Pabrik gula
Rumah-tinggal di bengkel Pesantren
timur pabrik, Area sebelah
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 57
Rumah-tinggal barat PG
kampung pesantren lama
cemara Gudang gula
3 Rumah-tinggal dan area
di selatan pabrik sebelah
selatan PG.
Pesantren
lama
Letak Letak pabrik dan Area poliklinik Area
rumah-tinggal dan lapangan sebelah timur dan
dikelilingi oleh tennis terletak selatan Kampung
jalan sekunder di dalam Cemara
Kediri-Pare dan komplek Area
Kediri-Wates Kampung sebelah selatan
Area Kampung Cemara gudang gula
Cemara terletak Area garasi dan
di sebelah timur bengkel
pabrik & jalur terletak di
sirkulasi sebelah Utara
merupakan rumah Adm.
cabang dari Letak gudang
jalan sekunder berada di
Kediri-Pare. sebelah
selatan Pabrik
Sumber: Hasil analisa
Tabel 3. Tabel Tatanan Hirarki Periode Pasca Kemerdekaan
Permukiman
PG. PESANTREN
Zona Privat Zona Semi- Zona Publik
Publik
Areal Area bangunan Area Poliklinik Permukiman
pabrik dan lapangan penduduk,
Rumah dinas tenis perkebunan & lahan
administratur Area garasi dan di luar area
Rumah-tinggal di bengkel peumahan dan
timur & barat Area sebelah Pabrik gula
pabrik barat PG Pesantren
Rumah-tinggal pesantren lama
kampung Gudang gula
cemara dan area
3 Rumah-tinggal sebelah
di selatan pabrik selatan PG.
Rumah-tinggal Pesantren
Kampung Baru lama
Letak Letak pabrik dan Area poliklinik Area sebelah selatan
rumah-tinggal dan lapangan dan utara pabrik
58 arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008
dikelilingi oleh tennis terletak Area sebelah selatan
jalan sekunder di dalam gudang gula
Kediri-Pare dan komplek
Kediri-Wates Kampung
Area Kampung Cemara
Baru terletak di Area garasi dan
sebelah selatan bengkel
pabrik & jalur terletak di
sirkulasi sebelah Utara
merupakan rumah Adm.
cabang dari Letak gudang
jalan sekunder berada di
Kediri-Wates. sebelah
selatan Pabrik
Sumber: Hasil analisa
Tabel 4. Tatanan Hirarki Periode Pasca Orde Baru
PG. PESANTREN
LAM A
Permukiman
PG. PESANTREN BARU
Zona Privat Zona Semi-Publik Zona Publik
Areal Area bangunan pabrik Area Poliklinik dan Permukiman penduduk
Rumah dinas administratur lapangan tenis perkebunan & lahan di luar
Rumah-tinggal di timur & barat Area garasi dan area peumahan dan Pabrik
pabrik bengkel gula Pesantren
Rumah-tinggal kampung cemara Area sebelah barat Emplasement pabrik gula
3 Rumah-tinggal di selatan pabrik PG pesantren
Rumah-tinggal Kampung Baru lama
Rumah-tinggal Magersari & Gudang gula dan
Kampung Sawah area sebelah
selatan PG.
Pesantren lama
Letak Letak pabrik dan rumah-tinggal Area poliklinik dan Area sebelah selatan dan
dikelilingi oleh jalan sekunder lapangan tennis utara pabrik
Kediri-Pare dan Kediri-Wates terletak di dalam Area sebelah selatan
Area Kampung Baru terletak di komplek Kampung gudang gula
sebelah selatan pabrik & jalur Cemara Emplasement terletak di
sirkulasi merupakan cabang dari Area garasi dan lokasi Pabrik gula lama
jalan sekunder Kediri-Wates. bengkel terletak di
Area perumahan Magersari terletak sebelah Utara
di sebelah barat pabrik lama, rumah Adm.
rumah-tinggal Kampung Sawah Letak gudang
terletak di sebelah Selatan pabrik berada di sebelah
baru selatan Pabrik
Sumber: Hasil analisa
Analisis Perkembangan Tipologi Rumah-Tinggal Karyawan Pabrik Gula
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 59
Hasil analisis dari rumah-tinggal kolonial yang diambil sebagai sampel penelitian,
yaitu sebagai berikut (Tabel 5):
Tabel 5. Sampel Perkembangan Tipologi Rumah-Tinggal
Rumah-tinggal Gambar Rumah-tinggal Gambar
no 1 No 29c
Kampung Baru
(kolonial Belanda) (pasca kolonial)
no 6a no 81
Magersari
(kolonial Belanda) (pasca kolonial)
no 22c no 67
Magersari
(kolonial Belanda) (pasca kolonial)
no 10a no 80
Magersari
(kolonial Belanda) (pasca kolonial)
no 10a no 1
Kampung Sawah
(kolonial Belanda) (pasca kolonial)
no 27c
Kampung Baru
(pasca kolonial)
a. Sampel no 1
Berdasarkan hasil survey lapangan di lingkungan perumahan karyawan,
didapatkan data bahwa rumah-tinggal ini merupakan tempat tinggal kepala
pabrik/administratur, mempunyai gaya arsitektur Indische Empire-Stijl, mulai dibangun
antara tahun 1911-1932, bersamaan dengan rehabilitasi komplek Pabrik Gula
Pesantren.
b. Sampel no 2
Berdasarkan hasil survey lapangan di lingkungan perumahan karyawan,
didapatkan data bahwa rumah-tinggal ini mulai dibangun antara tahun 1911-1932,
bersamaan dengan rehabilitasi komplek Pabrik Gula Pesantren. Dengan awal
permbangunan berada di daerah timur kompleks pabrik, rumah tinggal no 6c termasuk
dalam rencana pembangunan perumahan karyawan. Rumah-tinggal ini merupakan
salah satu rumah yang mepunyai gaya arsitektur tahun 1930-an aliran De Stilj.
60 arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008
c. Sampel no 3
Berdasarkan hasil survey lapangan di lingkungan perumahan karyawan,
didapatkan data bahwa rumah-tinggal ini merupakan tempat tinggal Kepala Bagian
Instalasi, mempunyai gaya arsitektur tahun 1930-an aliran De Stilj, mulai dibangun
antara tahun 1911-1932, bersamaan dengan rehabilitasi komplek pabrik gula.
d. Sampel no 4
Berdasarkan hasil survey lapangan di lingkungan perumahan karyawan,
didapatkan data bahwa rumah-tinggal ini mempunyai gaya arsitektur tahun 1930-an
aliran Amsterdam School, mulai dibangun antara tahun 1911-1932, bersamaan dengan
rehabilitasi komplek pabrik gula.
e. Sampel no 5
Berdasarkan hasil survey lapangan di lingkungan perumahan karyawan,
didapatkan data bahwa rumah-tinggal ini mempunyai gaya arsitektur tahun 1930-an
aliran Amsterdam School, mulai dibangun antara tahun 1911-1932, bersamaan dengan
rehabilitasi komplek pabrik gula.
f. Sampel no 6
Rumah-tinggal ini merupakan salah satu rumah-tinggal karyawan di perumahan
Kampung Baru, dibangun untuk memenuhi perumahan pada masa setelah
kemerdekaan, dengan dinasionalisasikan Pabrik Gula Pesantren lama. Rumah tinggal
ini mempunyai gaya arsitektur pasca kemerdekaan.
g. Sampel no 7
Rumah tinggal ini mulai direncanakan dan dibangun sekitar tanggal 21 januari
1954 (sesuai dengan gambar ini dibuat). Waktu pembangunan bersamaan dengan
rumah tinggal no 15c1, sehingga mempunyai bentuk rumah yang mirip. Rumah tinggal
ini mempunyai gaya arsitektur pasca kemerdekaan.
h. Sampel no 8
Rumah tinggal ini mulai dibangun antara tahun 1977-1978 dan dibangun untuk
memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi kalangan pekerja. Antara tahun 1984-1993
rumah tinggal direnovasi, sehingga terdapat perubahan ruang. Rumah tinggal ini
mempunyai gaya arsitektur pasca orde baru.
i. Sampel no 9
Rumah tinggal ini termasuk dalam zona perumahan Magersari yang mulai dib
angun untuk memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi para pekerja. Antara tahun 1984-
1993 rumah tinggal direnovasi, sehingga terdapat perubahan ruang. Rumah tinggal ini
mempunyai gaya arsitektur pasca orde baru.
j. Sampel no 10
Rumah tinggal ini mulai dibangun antara tahun 1977-1978 dan dibangun untuk
memenuhi kebutuhan rumah tinggal bagi kalangan pekerja. Antara tahun 1984-1993
rumah tinggal direnovasi, sehingga terdapat perubahan ruang. Rumah tinggal ini
mempunyai gaya arsitektur pasca orde baru.
k. Sampel no 11
Rumah-tinggal ini terletak di perumahan Kampung sawah dan mulai
dibangun tahun 1993, dibangun untuk memenuhi kebutuhan rumah-tinggal bagi
kalangan staf pabrik dan letaknya berdekatan dengan lokasi Pabrik gula
Pesantren Baru. Rumah tinggal ini mempunyai gaya arsitektur pasca orde baru.
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 61
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
• Perkembangan permukiman
Aspek penting perkembangan di lingkungan permukiman Pabrik Gula Pesantren
Baru, yaitu berpindahnya lokasi pabrik gula. Perkembangan tata lingkungan di
permukiman Pabrik Gula Pesantren Baru, dapat dijelaskan dengan zonasi ruang, yaitu
sebagai berikut:
a. Zona Privat
Area privat ini dari periode ke periode, semakin bertambah luas areanya. Dari
periode tahun 1890-1957 tata lingkungan terdiri dari kompleks Pabrik lama, rumah-
tinggal Administratur, 21 rumah-tinggal karyawan, 1 wisma tamu, 1 gedung pertemuan.
Periode berikutnya tahun 1958-1978, terdapat pertambahan fasilitas hunian, yaitu
Kampung Baru. Periode tahun 1979-2005, zona privat di kompleks pabrik lama
berkurang karena lahan digunakan sebagai emplasement, rumah-tinggal Administratur,
21 rumah-tinggal karyawan, 1 wisma tamu, 1 gedung pertemuan, Kampung Baru dan
pertambahan kompleks pabrik baru dan fasilitas hunian, yaitu perumahan Magersari
dan Kampung Sawah.
b. Zona Semi Publik
Berbeda dari zona privat, area semi-publik ini dari periode ke periode, semakin
berkurang luas areanya. Dari periode tahun 1890-1957 tata lingkungan hanya terdiri dari
emplasement lori, garasi dinas, gudang gula, lapangan tennis, lahan terbuka dan
poliklinik. Periode berikutnya tahun 1958-1978, lahan emplasement lori sebagian
dialihfungsikan menjadi fasilitas hunian, yaitu Kampung Baru. Periode berikutnya tahun
1979-2005, dengan berpindahnya pabrik emplasement lori di pabrik lama sudah tidak
dipergunakan lagi, diganti dengan truk pengangkut tebu.
c. Zona publik
Area publik ini dari periode ke periode, semakin bertambah luas areanya. Dari
periode tahun 1890-1957 tata lingkungan hanya terdiri dari permukiman penduduk dan
perkebunan tebu. Periode berikutnya tahun 1958-1978, permukiman penduduk semakin
bertambah di sekitar area pabrik, dengan adanya nasionalisasi pabrik yang
membutuhkan banyak tenaga kerja. Periode berikutnya tahun 1979-2005, lahan pabrik
lama sebagian dialihfungsikan sebagai emplacement (parkir truk tebu).
• Tipologi rumah tinggal
a. Kolonial
Segi tipologi langgam mempunyai dua type langgam, yaitu Indische Empire-Stijl
dan Periode Tahun 1930-an (De Stilj dan Amsterdam School. Tatanan ruang periode
kolonial mempunyai serambi, koridor & ruang servis (bangunan penujang) yang
terpisah, perletakan dapur & kamar mandi di area servis selain aman dari bahaya
kebakaran juga sirkulasi udara & cahaya untuk KM menjadi lebih lancar. Tampak
bangunan pada rumah-tinggal periode kolonial kental dengan nuansa kebesaran dan
monumental, pemanfaatan tapak pada periode kolonial dilakukan dengan tidak
menghabiskan seluruh tapak untuk bangunan
b. Pasca kolonial
Segi tipologi langgam mempunyai dua type langgam, yaitu langgam pasca
kemerdekaan dan langgam pasca orde baru. Tatanan ruang pasca kolonial hanya terdiri
dari massa induk tanpa serambi/koridor, perletakan dapur & kamar mandi dalam satu
area rumah induk rentan dari bahaya kebakaran. Tampak bangunan pada rumah-tinggal
periode pasca kolonial di dominasi bentuk tampilan yang sederhana dan simpel.
Pemanfaatan tapak pada periode pasca kolonial dilakukan dengan menghabiskan
hampir seluruh tapak untuk bangunan.
62 arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008
Saran
• Penelitian ini terbatas lebih pada masalah fisik-deskriptif (ditinjau dari segi arsitektur
lingkungan dan bangunan), sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk melihat
dari sisi yang lain. Pada masalah fisikpun, masih diperlukan penelitian lanjutan yang
bersifat lebih detil dan spesifik, baik pada skala masing-masing unit bangunan
(dapat berupa pergeseran-pergeseran fisik tatanan ruang dalam, konstruksi dan
sebagainya) maupun elemen-elemen lingkungan (sirkulasi, akibat perpindahan
pabrik secara sosio-kultural dan sebagainya).
• Penelitian ini tidak mencakup kondisi fisik secara detil dan spesifik, namun hanya
menyoroti tinjauan umum mengenai adanya perbedaan permukiman dan tipologi
hunian berdasarkan periodesasi, sehingga perlu dikembangkan lagi penelitian
berkelanjutan pergeseran-pergeseran akibat perpindahan pabrik ditinjau dari
permukiman (sirkulasi, tata bangunan dan fasilitasnya), serta tipologi (tatanan ruang
luar dan dalam, lay out plan, konstruksi dan fasade).
• Penelitian ini tidak mencakup kondisi sosial-kultural kemasyarakatan di lingkungan
pabrik gula, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut untuk melihat kondisi
tersebut, hal ini dirasa penting karena tidak diketahui oleh peneliti, adakah dampak
yang ditimbulkan akibat perpindahan pabrik yang berpengaruh terhadap perubahan
tipologi hunian. Kesemuanya ini dimaksudkan agar hasil penelitian secara
berkelanjutan dapat lebih lengkap, berbobot dan komprehensif
Daftar Pustaka
Handinoto. 1996. Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-
1940. Diterbitkan atas Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas PETRA Surabaya dan Penerbit Andi Yogyakarta.
Handinoto & Soehargo, P. H. 1996. Perkembangan kota dan Arsitektur Kolonial Belanda
di Malang. Diterbitkan atas Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat Universitas PETRA Surabaya dan Penerbit Andi Yogyakarta.
Kano, H., Husken, F. & Surjo, D. 1996. Di Bawah Asap Pabrik Gula. Bandung: Akatiga
dan Gadjah Mada University Press.
Pamungkas, S. T. & Tjahjono, R. 2002. Tipologi-Topologi-Morfologi Arsitektur Kolonial
Belanda Di Kompleks PG. Kebon Agung Malang. Malang: Fakultas Teknik
Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan).
Pamungkas, S. T., Damayanti & Kusdiwanggo, S. 2001. Tipologi-Topologi-Morfologi
Arsitektur Kolonial Belanda Di Kompleks PG. Djatiroto, Jatiroto, Lumajang. Malang:
Fakultas Teknik Universitas Brawijaya (tidak dipublikasikan).
Sasangko, I. 2002. Trasformasi Struktur Ruang pada Permukiman Sasak. Kasus:
Permukiman Tradisional Desa Puyung. Jurnal ASPI Vol. 1, No. 2. April 2002. hlm.
117-125.
Slamet, B. U. 1990. Kajian Fenomena dan Karakteristik Pecinan di Semarang: Suatu
Telaah Morfologi Identitas Arsitektural. Tesis tidak Diterbitkan. Bandung: Institut
Teknologi Bandung, 1990.
Sumalyo, Y. 1995. Arsitektur Kolonial Belanda Di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Sumalyo, Y. 1997. Arsitektur Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Sumalyo, Y. 2001. Arsitektur Kolonial Belanda Di Kota Lama Semarang. Jurnal Teknik
Teknik. Volume VIII, No. 3.Desember 2001. hlm 40-48.
Tjahjono, R. 1993. Implikasi Perubahan Rona Lingkungan Pada Tipologi Arsitektur
Hunian Masyarakat Madura Medalungan Di Pedalaman Jawa Timur. Jurnal Fakultas
Teknik Unibraw Volume I, No. 3. April 1993. hlm 37-46.
Copyright © 2008 by antariksa
arsitektur e-Journal, Volume 1 Nomor 1, Maret 2008 63
View publication stats
Anda mungkin juga menyukai
- Buku Manajemen Konstruksi Jilid 1 PDFDokumen221 halamanBuku Manajemen Konstruksi Jilid 1 PDFWulan AgniantiBelum ada peringkat
- Proposal TesisDokumen48 halamanProposal Tesisadek solehaBelum ada peringkat
- Admin, FadylaDokumen9 halamanAdmin, Fadyla2110815210001Belum ada peringkat
- Jurnal Ars Brawijaya - Morfologi PerumahanDokumen8 halamanJurnal Ars Brawijaya - Morfologi PerumahanZILDAN RASYIDBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Sejarah (Contoh)Dokumen8 halamanProposal Penelitian Sejarah (Contoh)Belliana SukmaBelum ada peringkat
- 2663 9047 1 SMDokumen6 halaman2663 9047 1 SMGuevara AlcamiloBelum ada peringkat
- 7324-Article Text-14594-1-10-20150908 PDFDokumen8 halaman7324-Article Text-14594-1-10-20150908 PDFIrfan RahmandaBelum ada peringkat
- Pola Tata Ruang Dalam Rumah Tinggal Kolonial Di Kidul Dalem Malang-Kirim RifqiDokumen50 halamanPola Tata Ruang Dalam Rumah Tinggal Kolonial Di Kidul Dalem Malang-Kirim RifqiLathiyfahShantiPurnamasariBelum ada peringkat
- Contoh LaporanDokumen25 halamanContoh LaporanMuhammad IkhsanBelum ada peringkat
- 2-Literature ReviewDokumen11 halaman2-Literature ReviewAlifia WidyastutiBelum ada peringkat
- Muh Syahidan Prayono - Kelas ADokumen19 halamanMuh Syahidan Prayono - Kelas AI Putu Aji DeskaBelum ada peringkat
- S Sej 045789 Chapter1Dokumen12 halamanS Sej 045789 Chapter1pepekayam062Belum ada peringkat
- 3.analisa Objek Arsitektur Vernakular Jawa Joglo LambangsariDokumen13 halaman3.analisa Objek Arsitektur Vernakular Jawa Joglo LambangsariRobert Pringgo Guphito100% (3)
- Arsitektur Kolonial Kota MalangDokumen24 halamanArsitektur Kolonial Kota MalangpranggoBelum ada peringkat
- Artikel Ali KhamdhanDokumen12 halamanArtikel Ali Khamdhanali smasaBelum ada peringkat
- Mendaur Ulang Kota Tambang SawahluntoDokumen14 halamanMendaur Ulang Kota Tambang SawahluntoFitriPurwantiBelum ada peringkat
- Kera MikDokumen14 halamanKera MikJohan PerdanaBelum ada peringkat
- Materialitas Revolusi IndustriDokumen7 halamanMaterialitas Revolusi IndustriPutri Arini KusumaningtyasBelum ada peringkat
- Bab 1 Pendahuluan: Revitalisasi Bangunan Pabrik, Ginanjar Gathot Priyono, FKIP UMP, 2022Dokumen19 halamanBab 1 Pendahuluan: Revitalisasi Bangunan Pabrik, Ginanjar Gathot Priyono, FKIP UMP, 2022Bang BandolBelum ada peringkat
- Proposal L.IDokumen13 halamanProposal L.IMuhdLuqmanBelum ada peringkat
- Contoh ProposalDokumen15 halamanContoh ProposalWAN NADYA HAKIM BINTI FAHRUL HAKIM MoeBelum ada peringkat
- ID Dampak Pembangunan Industri Terhadap DivDokumen14 halamanID Dampak Pembangunan Industri Terhadap DivDave Carl KaengBelum ada peringkat
- Bab 1 Penddahuluan Dan Bab 2 Tinggal Di PrintDokumen28 halamanBab 1 Penddahuluan Dan Bab 2 Tinggal Di PrintJessica MitchellBelum ada peringkat
- Contoh Cadangan Penyelidikan SejarahDokumen14 halamanContoh Cadangan Penyelidikan SejarahArDenisJemolBelum ada peringkat
- Proposal Desain Rumah Modern TradisionalDokumen7 halamanProposal Desain Rumah Modern TradisionalMuhammad Restu WandiBelum ada peringkat
- Analisa Struktur Dan Pola RuangDokumen10 halamanAnalisa Struktur Dan Pola RuangHeidiBelum ada peringkat
- Industrialisasi Dan Penggunaan Lahan KekotaanDokumen19 halamanIndustrialisasi Dan Penggunaan Lahan KekotaanALBelum ada peringkat
- Makalah Perkembangan Arsitektur 2 (Yuliana - F22118208)Dokumen20 halamanMakalah Perkembangan Arsitektur 2 (Yuliana - F22118208)Sandi Arda PutraBelum ada peringkat
- Perubahan Lahan Di KUNINGAN JAKARTADokumen112 halamanPerubahan Lahan Di KUNINGAN JAKARTAANDIIE WONGBelum ada peringkat
- Kesimpulan Dan CadanganDokumen4 halamanKesimpulan Dan CadanganMH Abdul JabbarBelum ada peringkat
- ID Kajian Tipologi Morfologi Rumah VernakulDokumen15 halamanID Kajian Tipologi Morfologi Rumah VernakulMalghifari TeukuBelum ada peringkat
- TUGAS 1 Makalah Perancangan PemukimanDokumen11 halamanTUGAS 1 Makalah Perancangan PemukimanSupriyanto h RahmanBelum ada peringkat
- Apriroza Delaila (1706555) Met SejarahDokumen25 halamanApriroza Delaila (1706555) Met SejarahRuli Seftiana AzizaBelum ada peringkat
- Contoh KKPADokumen31 halamanContoh KKPANorsuhailah MahyidinBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen5 halamanBab I PendahuluanR buamona IdhanBelum ada peringkat
- Bab IDokumen26 halamanBab IMuamar SerajawaBelum ada peringkat
- Pengantar Bisnis Kelompok 2Dokumen7 halamanPengantar Bisnis Kelompok 2Sarah IrdayaniBelum ada peringkat
- Kelompok 4 - MK6B - SeminarKeuangan - Sejarah PG Sebelum 1942 - Tinjauan Pustaka - 9 Juni 2021Dokumen17 halamanKelompok 4 - MK6B - SeminarKeuangan - Sejarah PG Sebelum 1942 - Tinjauan Pustaka - 9 Juni 2021Alifia WidyastutiBelum ada peringkat
- Laporan LengkapDokumen34 halamanLaporan Lengkaphasnia hafidBelum ada peringkat
- Tugasan 1 HSR3033 2Dokumen17 halamanTugasan 1 HSR3033 2Sahril Ril NasSirBelum ada peringkat
- 87 EfDokumen20 halaman87 EfZarwa OfficialBelum ada peringkat
- Jurnal 1Dokumen9 halamanJurnal 1Angelin Lorin AbigaelBelum ada peringkat
- Laporan BAB I - III KP Tonasa Fix 2 Fix PRINTDokumen93 halamanLaporan BAB I - III KP Tonasa Fix 2 Fix PRINTWildan HnfBelum ada peringkat
- PoacDokumen81 halamanPoaciril hasanBelum ada peringkat
- Makalah GeotermalDokumen12 halamanMakalah GeotermalUnwanul hubbyBelum ada peringkat
- 3990 14378 1 PBDokumen11 halaman3990 14378 1 PBGuevara AlcamiloBelum ada peringkat
- PDFsam MergeDokumen192 halamanPDFsam Mergeade natashaBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen10 halaman1 SMYukio PaturusiBelum ada peringkat
- SKebudayaan UASDokumen5 halamanSKebudayaan UASnurmalisa08Belum ada peringkat
- PDGK4405Dokumen4 halamanPDGK4405al kazamaBelum ada peringkat
- Proposal Perancangan Bangunan AsramaDokumen4 halamanProposal Perancangan Bangunan AsramaGayuh WinisudaningtyasBelum ada peringkat
- Ekonomi Di Tanah Melayu Sebelum Dan Selepas PenjajahDokumen12 halamanEkonomi Di Tanah Melayu Sebelum Dan Selepas PenjajahGucci Angel100% (1)
- KOSMOLOGIDokumen7 halamanKOSMOLOGIAfifah Rabbani AfzBelum ada peringkat
- Adaptasi Arsitektur Dan Fasad Bangunan (Ekologi)Dokumen16 halamanAdaptasi Arsitektur Dan Fasad Bangunan (Ekologi)raisramdhanyBelum ada peringkat
- Hasil Penelitian Pertambangan KonselDokumen104 halamanHasil Penelitian Pertambangan KonselAdhien BinongkoBelum ada peringkat
- Makalah Penambangan BatubaraDokumen26 halamanMakalah Penambangan BatubaraDaniel DazharBelum ada peringkat
- Perkebunan Teh JamusDokumen29 halamanPerkebunan Teh Jamusali smasaBelum ada peringkat