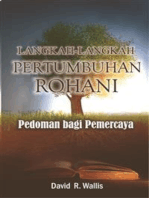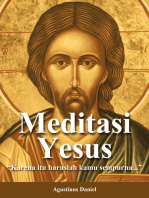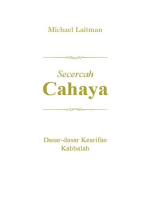Etnoreligi Dan Reka Tafsir Iman Migani - Memahami Kristus Berbasis Perspektif Kearifan Lokal
Diunggah oleh
Daniel AdrianHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Etnoreligi Dan Reka Tafsir Iman Migani - Memahami Kristus Berbasis Perspektif Kearifan Lokal
Diunggah oleh
Daniel AdrianHak Cipta:
Format Tersedia
Etnoreligi dan Reka Tafsir Iman Migani: Memahami Kristus Berbasis
Perspektif Kearifan Lokal
Kleopas Sondegau dalam Mengimani Yesus Kristus Melalui Tokoh Peagabega dalam Suku
Migani (2018) merupakan bukti dan potret kecil dari begitu banyaknya praktik keagamaan yang
didasari oleh nilai-nilai lokal. Etnoreligi (keagamaan berbasis perspektif kearifan lokal) tersebut tampil
eksotis dalam berbagai ekosistem adat di Indonesia, yang salah satunya dapat dijumpai di Bumi
Cendrawasih. Suku Migani namanya, sebuah suku di Intan Jaya, Papua. Sebelum abad ke-20, jauh
sebelum ajaran Kristiani atau kepercayaan struktural-formal masuk, masyarakat Migani menganut
kepercayaan dasar pribumi seperti animisme-dinamisme. Salah satunya berupa kepercayaan bahwa
alam adalah sumber hidup dan merupakan “Ibu” bagi mereka. Seiring meningkatnya kemampuan
berpikir yang dibarengi dengan pendewasaan iman, kepercayaan tersebut konsisten berkembang.
Selanjutnya mereka menyadari bahwa ada kuasa yang lebih tinggi daripada alam, yaitu pencipta alam
itu sendiri (Jacobs, 2002). Pengalaman iman tersebut membawa mereka kepada sosok “Emo”, yang
lahir sebelum “Allah” timbul dalam pemahaman mereka (Hesselgrave & Rommen, 1995).
Selain kepada Emo, kehidupan rohani dan sistem kepercayaan orang-orang Migani juga
dihidupi melalui sosok leluhur yang dianggap ideal. Salah satunya adalah Peagabega, tokoh yang kerap
tampil sebagai pahlawan dalam berbagai panggung legenda-kesejarahan Migani. Eksistensi
Peagabega inilah yang pada akhirnya mampu menuntun Migani untuk menemukan Kristus, Kristiani,
dan Allah Tritunggal. Kisah orang Migani tersebut memantik pertanyaan mendasar, bagaimana
paradigma tersebut dapat terlahir?
Mencari Peagabega, Menemukan Kristus
Semasa hidupnya, Peagabega kerap tampil abu-abu antara sisinya sebagai manusia dan adi-
manusia. Ia identik dengan unsur kekuatan, kecerdasan, dan kesaktian yang senantiasa digunakan
demi mewujudkan keselamatan orang-orang Migani. Masa kecilnya di Kampung Soagepa yang penuh
dengan kriminalitas menumbuhkan tekadnya saat dewasa untuk mengubah realitas tersebut.
Imbasnya, para pencuri dan perampok di desa tersebut kehabisan ruang gerak. Kesaktian lainnya
adalah berkuasanya Peagabega atas kehidupan-kematian manusia. Karakternya yang penuh dengan
rasa belas kasihan memicu Peagabega untuk menunda ajal para orang-orang tua di kampung tersebut.
Namun, niat baik yang dimiliki oleh Peagabega nyatanya tidak selalu ditafsirkan baik pula oleh
mayoritas masyarakat. Kaum-kaum kriminal yang aksinya terganggu oleh Peagabega tentu
menyimpan dendam tersendiri. Para muda-mudi yang berada dalam pemahaman “yang tua harus
mati” juga terusik dengan perilaku Pegabega yang memanjangkan umur para orang tua. Belum lagi
soal habitus Peagabega yang kontras dengan mayoritas masyarakat saat itu. Amarah yang tertimbun
selalu berbuah pada pelenyapan. Ya, itulah yang terjadi pada Peagabega selanjutnya. Dia diikat
dengan kawat berduri, dicambuk, ditusuk, dan digiring dengan cucuran darah yang mengguyur desa-
desa. Akhirnya, dia mati di sebuah desa bernama Pajebundoga. Ketika wafat, jasadnya digantung di
sebuah pohon yang diberi para-para atau yang biasa disebut Nggigibo. Keajaiban terjadi ketika kedua
kakaknya menghampiri dan menangisi jasadnya; ia bangkit dari kematian. Selanjutnya mereka bertiga
pergi ke sebuah danau di Punitigi dan menghilang.
Setelah kematiannya, mayoritas warga bersorak-sorai. Namun ada juga kaum yang menangisi
dan begitu kehilangan sososk pelindungnya. Pengikutnya berpaham bahwa kematian Peagabega
bukan sekadar angin lewat. Mereka tidak tinggal diam, mewartakan karya keselamatan Peagabega
dan terus berkembang seiring waktu. Misi pewartaan tersebut berhasil. Beberapa puluh dekade
setelahnya, Peagabega menjadi sosok yang begitu dicintai dan diimani, baik sosok atau karyanya
dalam mayoritas orang-orang Migani.
Garis besar kisah hidup Peagabega tentu sangat tidak asing dalam benak orang Kristiani. Ya,
kisahnya serupa dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Bagaimana kisah Yesus tumbuh, mati,
hingga akhirnya bangkit seolah serupa dengan riwayat Peagabega. Yesus dihukum mati karena sikap
lantangnya dalam menyuarakan kebenaran dan pengajaran Allah Bapa. Dalam pengajarannya,
perilaku Yesus kerap kali bertentangan dengan habitus masyarakat setempat. Pertentangan yang
konsisten ada tersebut tentu bermuara pada “pelenyapan”, baik diri ataupun identitas Yesus di
tengah-tengah masyarakat. Tetapi Ia tetaplah Allah yang sahih, kisahnya di dunia diakhiri dengan
kebangkitan yang mulia. Fakta tentang miripnya riwayat Yesus dan Peagabega ternyata mampu
direfleksikan dalam pertumbuhan iman orang Migani. Hal tersebut dapat dibuktikan ketika
“perjalanan iman” suku Migani berlanjut, tepatnya saat mereka mulai mengenal Yesus Kristus, Allah
Tritunggal, dan kekristenan.
Konsepsi Pendewasaan Iman
Pada tahun 1952, ajaran Katolik pertama kali menyentuh suku Migani yang dibawakan oleh
salah satu misionaris Katolik bernama Pater Carel Gotfrid. Dua tahun setelahnya, Pendeta Bills Cutts,
yang juga misionaris Kristen datang ke lingkungan Migani untuk turut menyebarkan ajaran Protestan
(Tabuni, 1999). Kedua sosok ini berperan sangat vital dalam membuka isolasi dan memperkenalkan
dunia luar kepada orang-orang Migani. Di luar itu, tentu tujuan datangnya para misionaris tersebut
adalah untuk mendatangkan identitas Kristus. Datangnya kepercayaan dan paham baru disikapi
dengan hati yang terbuka. Keterbukaan yang mampu menumbuhkan karakter, mendewasakan iman,
dan mengasah pemahaman.
Kepiawaian para misionaris, dibarengi pula dengan keterbukaan hati dalam meneroka napas
Kristiani, membuat Yesus dengan mudah diterima oleh suku Migani. Seiring berjalannya waktu,
pengetahuan dan wawasan orang Migani seputar apa, siapa, dan bagaimana Allah mulai terkonstruksi.
Sebuah kejutan tersendiri tatkala mereka menyadari bahwa riwayat Yesus serupa dengan kisah
Peagabega yang selama ini dikenal. Fakta demikian memicu adanya konsensus kepercayaan bahwa
Yesus adalah Peagabega, dan sosok Peagabega terlegitimasi dalam diri Yesus.
Situasi yang terjadi dalam suku Migani ini turut membuktikan apa yang dimaksud dalam dua
kalimat pertama tulisan ini; ber-Tuhan, beriman, dan beragama yang dipandang melalui kacamata
nilai-nilai lokal. Tentu, kondisi keimanan semacam ini tidak dapat diterima oleh semua kalangan.
Pencampuradukan antara agama dan kearifan lokal menjadi hal yang kerap kali dicap sebagai ajaran
haram, aliran sesat, dan berbagai label destruktif lainnya. Justifikasi berbasis pemikiran chauvinisme
tersebut tentu sangat berbahaya, utamanya bagi kehidupan Gereja dan keharmonisan umat. Lantas
sebagai umat beriman, bagaimana seharusnya kita memandang, memahami, dan menafsirkan
etnoreligi tersebut?
Pesan Paus, Telinga Hati, dan Eskalasi Injil
Mencari jawaban atas persoalan tersebut melempar ingatan saya terhadap apa yang
disampaikan Bapa Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sedunia ke-56. “Mendengarkan dengan
Telinga Hati” adalah tajuk yang digaungkan. Tema ini dirasa begitu relevan ketika dunia kini
bertransformasi menjadi begitu hingar-bingar. Ironi tersebut yang kembali digarisbawahi oleh Gereja
melalui pesan Bapa Paus. Dalam salah satu baris kalimatnya, Paus berucap “Di antara pancaindra,
tampaknya Tuhan mengistimewakan pendengaran, mungkin karena kurang invasif, lebih bijaksana
dari penglihatan, dan karena itu membuat manusia lebih bebas.” Dalam kalimat tersebut, seolah Paus
menegaskan seberapa vitalnya indra pendengaran. Karena nyatanya pendengaran adalah indra utama
manusia dalam proses input informasi yang menjadi rahim dari pengetahuan, gagasan, dan iman.
Artinya, dalam menyikapi sebuah permasalahan, telinga berperan esensial dalam pengumpulan
informasi yang selanjutnya akan diproduksi dalam beragam aksi-aksi. Konsep pendengaran yang
demikian pulalah yang nantinya akan mendasari bagaimana kita meneroka distingsi keimanan dalam
masyarakat Migani.
Melibatkan telinga hati dalam menafsirkan kekristenan orang-orang Migani sejatinya dapat
dimaknai dalam dua konteks dan substansi yang berbeda. Pertama, telinga hati sebagai sarana
mendengarkan secara batiniah. Definisi ini serupa dengan apa yang disampaikan Paus dalam
pesannya, yaitu mendengarkan bukan sebatas lahiriah dalam telinga, namun juga batiniah dalam hati.
Maksudnya bahwa proses mendengarkan juga perlu didasari pemikiran iman, bukan sekadar logika
pragmatis. Konsep ini menuntun kita kepada pertanyaan “bagaimana mendengar yang baik?”
Menurut Paus, mendengar yang baik adalah seperti Allah yang dengan penuh kerendahan dan
keterbukaan hati.
Filosofi tersebut yang kemudian dapat diadaptasi dalam memandang suku Migani. Namun,
kini kita kembali disadarkan bahwa proses mendengarkan tidak hanya dimaknai sebatas kata-kata
dalam suara, tetapi juga dapat dalam bentuk lain, tulisan misalnya. Tidak semua orang mampu
mendengarkan suara secara langsung, tetapi “mendengarkan” juga dapat dilakukan berbasis literatur
yang menyingkap tabir-tabir informasi. Karena pendengaran komprehensif, bagaimanapun caranya,
senantiasa berbuah pada kapitalnya iman, pemikiran, dan pemahaman. Salah satu indikasi dalam
berhasilnya “mendengarkan” adalah terciptanya rasa empati. Rasa empati akan menuntun kita ke
dalam sensibelnya perspektif yang akan bermuara kepada gagasan sahih berbasis iman.
Kedua, telinga hati sebagai pendengar primer suara hati. Suara hati pada dasarnya adalah
suara kebenaran, yang timbul sebagai bentuk keinsafan akan kewajiban. Ia dihasilkan melalui hati
nurani (conscience). Suara hati merupakan hakim yang adil, meski dapat keliru ketika konstruksi
wawasan tak lagi berpijak pada norma. Suara hati bekerja dengan menunjukkan mana yang baik dan
yang buruk, termasuk ketika terjebak dalam dilematisme gagasan. Dengan memberi pertimbangan
yang benar dan tidak, suara hati dapat sangat membantu kita dalam merumuskan pandangan dan
sikap dalam menafsirkan iman Migani. Dan hanya telinga hati-lah yang mampu memahami bisikan
tersebut. Apapun suara hati kita, itulah bisikan surgawi kepada kita. Dapat diamini, bisa juga tidak,
namun yang terpenting adalah toleransi dalam gagasan.
Berpijak dari apa yang disampaikan Paus tersebut menarik kita pada sebuah kesimpulan
bahwa etnoreligi, khususnya dalam konteks suku Migani, adalah hal yang benar adanya, karena itulah
inti dari pewartaan Injil. Bahwa pewartaan Injil dan misi Gereja selalu berpijak terhadap kultur
masyarakat setempat. Paus Paulus VI dalam Evangelii Nuntiandi menegaskan pula bahwa relevansi
Kristiani mesti digali dari berbagai titik temunya dengan kultur setempat. Maka etnoreligi tersebut
pada dasarnya adalah upaya Gereja dalam inkulturasi kearifan lokal yang didayagunakan sebagai
sarana mengenal Kristus. Mengapa? Upaya penginjilan dan mencari Kristus dengan menggali nilai lokal
juga hal-hal kontekstual selalu memiliki tujuan pragmatis berupa sustainability Kristianitas, yakni
menjamin eksistensi pengikut Kristus di dunia. Berkaca dari gagasan tersebut, nilai-nilai kultural yang
membungkus nilai Kristiani tidak selalu salah. Peagabega, atau tokoh-tokoh lain di luar sana, adalah
sarana dalam mengilhami Kristus. Pengilhaman yang komprehensif memicu mengakar kuatnya iman
akan Kristus dalam masyarakat. Menjadi salah apabila ajaran yang digaungkan justru dapat
merabunkan keimanan sesorang terhadap Allah Tritunggal. Namun, ketika kearifan lokal digunakan
sebagaimana mestinya dalam beriman, ber-Tuhan, dan beragama, maka itu baik adanya karena
menjadi bahan bakar bagi Gereja dan Injil untuk senantiasa relevan dalam berbagai kontur masyarakat
global.
Daftar Pustaka
Hesselgrave, D. J., & Rommen, E. (1995). Kontekstualisasi: Makna, Metode dan Model. Jakarta:
Gunung Mulia.
Jacobs, T. (2002). Paham Allah: Dalam Filsafat, Agama-agama, dan Teologi. Yogyakarta: Kanisius.
KWI, K. (2022, Februari 1). Pesan Paus Fransisikus dan Tata Perayaan Ekaristi Pada Hari Komunikasi
Sedunia ke-56. Mirifica.net.
No.6), P. V. (2005). Evangelii Nuntiandi (Mewartakan Injil). Jakarta.
Sondegau, K. (2017). Kristologi dalam Konteks Kebudayaan Suku Migani di Papua. Studia Philosopica
et Theologica, 60-79.
Sondegau, K. (2018). Mengimani Yesus Kristus Melalui Tokoh Peagabega dalam Suku Migani.
Bandung : Universitas katolik Parahyangan.
Tabuni, N. (1999). Relasi Orang Moni dengan "Emo". Jayapura: STFT.
Data Peserta
Nama Lengkap : Daniel Adrian Hartanto
Asal Kota : Surakarta
Kelas : Kelas X SMA
Asal Sekolah : SMA Regina Pacis Surakarta
Tanggal Lahir : 2 April 2006
NIK : 3372030204060002
NISN : 0065967555
NIS : 15879
Nomor HP : 0895377696333
Email : danieladrian0204@gmail.com
Profil singkat penulis :
Daniel Adrian Hartanto adalah seorang siswa kelas X di SMA Regina Pacis Surakarta
yang mulai terjun aktif ke dalam dunia tulis menulis semenjak 8 bulan lalu. Tulisannya
terfokus pada esai, opini, dan feature. Beberapa contoh tulisannya berjudul Parafrasa
Pandemi: Adaptasi Kebudayaan Lokal Surakarta dalam Kehidupan Saat dan Pasca
Pandemi, Guru dalam Pusaran Politik Anak Muda, dan Transfigurasi Bahasa Daerah
dalam Semesta Patron-Klien. Dalam perjalanan karir kepenulisannya, karyanya yang
berjudul Sebuah Refleksi: Mendedah Keris yang Teramat Asing dalam Wawasan
Pemuda menyabet juara pertama esai kategori pelajar tingkat nasional, dan
Transformasi Budaya Pasca Pandemi: Identitas Keindonesiaan dalam Paradigma
Indonesia yang juga berhasil meraih kategori naskah terpilih Etnika Fest 2022 Fakultas
Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
Anda mungkin juga menyukai
- Langkah-Langkah Pertumbuhan RohaniDari EverandLangkah-Langkah Pertumbuhan RohaniPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (3)
- Semua kebetulan aneh dalam hidup Anda. Peristiwa aneh kecil. Firasat. Telepati. Apakah itu terjadi pada Anda juga? Fisika kuantum dan teori sinkronisitas menjelaskan fenomena ekstrasensor.Dari EverandSemua kebetulan aneh dalam hidup Anda. Peristiwa aneh kecil. Firasat. Telepati. Apakah itu terjadi pada Anda juga? Fisika kuantum dan teori sinkronisitas menjelaskan fenomena ekstrasensor.Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (8)
- Jurnal Perspektif-Malang PDFDokumen20 halamanJurnal Perspektif-Malang PDFLike NdexBelum ada peringkat
- Opini PaskahDokumen3 halamanOpini PaskahRinggo MakingBelum ada peringkat
- Teologi Kontemporer (Pdt. DR. Apeliften)Dokumen7 halamanTeologi Kontemporer (Pdt. DR. Apeliften)Agus Rony Damanik0% (1)
- Jurnal Skripsi - Shevanya Lintuuran (201841145) TKPDokumen20 halamanJurnal Skripsi - Shevanya Lintuuran (201841145) TKPShevanya LintuuranBelum ada peringkat
- NATALDokumen4 halamanNATALhelariusBelum ada peringkat
- Analisa Tipologi BudayaDokumen14 halamanAnalisa Tipologi BudayaElysia F.HBelum ada peringkat
- Perayaan Natal - HJ Irena HandonoDokumen41 halamanPerayaan Natal - HJ Irena Handonokodok.ngorek80% (5)
- Dajjal Dan Anak Manusia Menurut InjilDokumen44 halamanDajjal Dan Anak Manusia Menurut InjilEdy Ramdan100% (1)
- Kelompok X Misiologi (Delvi Mispa)Dokumen13 halamanKelompok X Misiologi (Delvi Mispa)iston asusBelum ada peringkat
- Peran Dan Fungsi KKMK Dalam Hidup MenggerejaDokumen18 halamanPeran Dan Fungsi KKMK Dalam Hidup MenggerejaRichardus NgabutBelum ada peringkat
- Sejarah Tuhan - Karen AmstrongDokumen280 halamanSejarah Tuhan - Karen Amstrongmadjuh97% (30)
- Apologetika Biblis KatolikDokumen7 halamanApologetika Biblis KatolikSohn von LiebeBelum ada peringkat
- Pendidikan Agama - Dimensi-Dimensi - TambahanDokumen6 halamanPendidikan Agama - Dimensi-Dimensi - Tambahanerviaviot13Belum ada peringkat
- Adoc - Pub - Ketika Aku Dan Kamu Menjadi KitaDokumen14 halamanAdoc - Pub - Ketika Aku Dan Kamu Menjadi KitaHarry YunBelum ada peringkat
- 0 4 Kitab Keagamaan Theisme Dan Ilmu-CompressedDokumen48 halaman0 4 Kitab Keagamaan Theisme Dan Ilmu-CompressedPuteri SemestaBelum ada peringkat
- TugasDokumen5 halamanTugasMaria DesyBelum ada peringkat
- Pergumulan Papua Dan Protestanisme Sebuah Tantangan Bagi Gereja Protestan Di IndonesiaDokumen8 halamanPergumulan Papua Dan Protestanisme Sebuah Tantangan Bagi Gereja Protestan Di IndonesiaAngelroomBelum ada peringkat
- Teologi Manuk Si IndungDokumen5 halamanTeologi Manuk Si IndungianendaBelum ada peringkat
- Identitas Keluarga Kristiani Di Hadapan Budaya KonsumerismeDokumen18 halamanIdentitas Keluarga Kristiani Di Hadapan Budaya KonsumerismefarysBelum ada peringkat
- Tajam Ke Dalam Tumpul Ke LuarDokumen30 halamanTajam Ke Dalam Tumpul Ke LuarstefBelum ada peringkat
- Sejarah TuhanDokumen277 halamanSejarah TuhanNeptune Joo100% (3)
- Lapran TOP II Fr. AlloDokumen19 halamanLapran TOP II Fr. Alloalbertus alloBelum ada peringkat
- Tabut Perjanjian 2Dokumen313 halamanTabut Perjanjian 2Bambang TriatmokoBelum ada peringkat
- Uas AgamaDokumen3 halamanUas AgamaRhyya BriaBelum ada peringkat
- Gereja Pewarta: Fransiska Widyawati (Editor)Dokumen35 halamanGereja Pewarta: Fransiska Widyawati (Editor)scolastika leluBelum ada peringkat
- Andreas Sitepu - UTSDokumen8 halamanAndreas Sitepu - UTSsarx007 lievBelum ada peringkat
- T1 712013066 IsiDokumen39 halamanT1 712013066 Isiedwin efendi muntheBelum ada peringkat
- Pts Agama Xi Ipa-IpsDokumen4 halamanPts Agama Xi Ipa-Ips04-21128 Elizabeth Airin KallistaBelum ada peringkat
- Pendosa: Kekristenan Dan Perubahan Kebudaan Masihulan, Seram UtaraDokumen24 halamanPendosa: Kekristenan Dan Perubahan Kebudaan Masihulan, Seram UtarastarinaBelum ada peringkat
- Kristologi Bapa Abad 1 Dan 2Dokumen20 halamanKristologi Bapa Abad 1 Dan 2Fredy Raymond SiahaanBelum ada peringkat
- Spiritualitas Gereja PersahabatanDokumen11 halamanSpiritualitas Gereja Persahabatantov organizerBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian LogosDokumen16 halamanProposal Penelitian LogosBednadetus AprilyantoBelum ada peringkat
- Agama Dan Komunitas 2Dokumen15 halamanAgama Dan Komunitas 2Tri Angka RiniBelum ada peringkat
- Tesis TOPDokumen25 halamanTesis TOPGavin AkhaBelum ada peringkat
- UAS PIT (Shenly I. Titarsole)Dokumen4 halamanUAS PIT (Shenly I. Titarsole)ShenlytitrSole100% (1)
- Identitas Keagamaan Dan Lembaga KeagamaanDokumen17 halamanIdentitas Keagamaan Dan Lembaga Keagamaanzulhahaha96Belum ada peringkat
- Hakekat Gereja Dan PanggilannyaDokumen13 halamanHakekat Gereja Dan PanggilannyaGabriel MujurBelum ada peringkat
- Meditasi Yesus: "Karena itu haruslah engkau sempurna..."Dari EverandMeditasi Yesus: "Karena itu haruslah engkau sempurna..."Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (16)
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)
- Doa Mazmur Yesus: Sebuah Pembaharuan Terhadap Doa Yesus KlasikDari EverandDoa Mazmur Yesus: Sebuah Pembaharuan Terhadap Doa Yesus KlasikBelum ada peringkat
- Sejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniDari EverandSejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniBelum ada peringkat
- Menemukan Makna Hidup (The Leepers' Lessons)Dari EverandMenemukan Makna Hidup (The Leepers' Lessons)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (105)
- Parkinsons Treatment Indonesian Edition: 10 Secrets to a Happier Life 10 Rahasia Menggapai Harapan dan Hidup Lebih Bahagia dengan Penyakit ParkinsonDari EverandParkinsons Treatment Indonesian Edition: 10 Secrets to a Happier Life 10 Rahasia Menggapai Harapan dan Hidup Lebih Bahagia dengan Penyakit ParkinsonPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (8)
- Grace luar biasa Disimpan untuk TujuanDari EverandGrace luar biasa Disimpan untuk TujuanPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (2)
- Sekutu Umat Manusia - Buku Satu - ( AH1- Indonesian Edition)Dari EverandSekutu Umat Manusia - Buku Satu - ( AH1- Indonesian Edition)Penilaian: 1 dari 5 bintang1/5 (1)
- Perkuat Pelayanan Anda Dengan Berbagai Mujizat & Manifestasi Roh KudusDari EverandPerkuat Pelayanan Anda Dengan Berbagai Mujizat & Manifestasi Roh KudusBelum ada peringkat