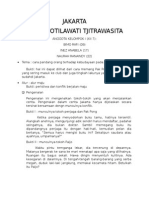Menebus Dosa Masa Lalu
Diunggah oleh
Muamal KhumaidiHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Menebus Dosa Masa Lalu
Diunggah oleh
Muamal KhumaidiHak Cipta:
Format Tersedia
Menebus Dosa Masa Lalu
Setiap tanggal 17 Agustus, aku akan datang ke tempat ini. Seperti ada kewajiban yang mengharuskanku untuk
kembali. Tak peduli panas, hujan, atau badai sekalipun. Tak akan pernah menghalangiku untuk kembali. Selama
nyawa di kandung badan dan kepikunan belum menggerogotiku.“Bapak, Bapak sudah semakin tua. Untuk apa
piknik dan piknik lagi?” tanya anak-anakku. Aku hanya tersenyum. Mereka tak akan mengerti. Ini bukan piknik,
tapi hukuman yang harus kujalani. Penjara untuk menebus kesalahanku. Hingga kini, aku belum mampu
bercerita pada mereka, kenapa aku datang ke sini setiap tahunnya. Aku menyimpannya untuk diriku sendiri.
Setiap datang aku akan memandangi benteng Van Der Wijck yang kini berdiri megah. Menabur bunga di salah
satu pintunya. Terpekur menatap ke satu titik. Mengenang cerita lara yang harus kusandang selama sisa
hidupku.”Untuk apa Bapak melakukan ini? Orang-orang melihat pada kita, Pak. Mereka mengira kita aneh.”
Kalimat itu sudah berkali-kali terlontar dari mulut anak-anakku. Mereka tidak tahu seberapa besar arti benteng
ini bagiku.
Aku mengawasinya setiap saat. Menjadi saksi sejarah segala perubahannya dari zaman ke zaman. Sejak masih
menjadi Puppilen School, berpindah ke KNIL, beralih fungsi menjadi barak TNI, lalu dibiarkan bertahun-tahun
merana, mangkrak, dan kurang terawat. Sempat menjadi sarang burung walet, dan kini bersalin rupa menjadi
gedung yang gagah, berwarna merah menyala, menjadi objek wisata sejarah kebanggaan warga. Semuanya tak
luput dari penglihatanku.
Memang sudah puluhan tahun berlalu. Namun, rekaman peristiwa itu masih melekat erat di ingatanku. Saat
sahabatku merenggang nyawa, tertembak mati di salah satu pintunya. Semua itu salahku. Aku yang paling
pantas disalahkan. Seandainya saja bisa diputar ulang, aku ingin membalikkannya kembali. Mengubahnya
menjadi cerita yang berakhir bahagia, happy ending.
Saat itu benteng Van Der Wijck masih menjadi benteng logistik, gudang pangan dan perbekalan untuk Puppilen
School atau Sekolah Calon Militer Tentara Belanda. Malam ini aku dan Parto berhasil menyusup ke areal
Benteng Van Der Wijck ini.
Parto, seorang peranakan Indo-Belanda. ibunya wanita pribumi, ayahnya serdadu Belanda tapi tak tahu
rimbanya. Fisiknya yang lebih mirip orang Belanda, membuatnya bisa bebas keluar masuk lingkungan Belanda.
Mengambil bahan makanan ataupun senjata tanpa dicurigai musuh. Sementara aku akan menunggu di luar,
bersembunyi di semak belukar. Malam itu, di tanggal yang sama seperti hari ini, 17 Agustus, Parto sudah
berhasil mengambil sekarung beras. Seharusnya itu sudah cukup. Harusnya kami kembali ke perkampungan.
Tapi, aku memaksanya masuk kembali.
“Kenapa hanya sekarung, kalau bisa membawa berkarung-karung,” kataku meyakinkannya.
“Tapi, sangat berbahaya. Mereka bisa curiga kalau aku mengambil terlalu banyak,” tolak Parto.
“Ah, kamu terlalu pengecut! Tak punya nyali!” ejekku.
Masa Agresi Milter kedua, kelaparan semakin meluas. Sejak perjanjian Renville ditandangani, penduduk di
barat sungai Kemit yang termasuk territorial Belanda kekurangan pangan. Daerah timur sungai yang menjadi
lubung padi tak bisa lagi menjual hasil panennya ke barat. Sementara di lain pihak, gudang-gudang pangan
Belanda penuh berkarung-karung makanan.
Dengan fisiknya yang seperti Belanda, kami memanfaatkannya untuk menjadi mata-mata, menyusup ke tangsi-
tangsi Belanda, mencuri bahan pangan dan persenjataan. Tapi, sepandai-pandai tupai melompat, ada kalanya
akan jatuh juga.Tiba-tiba, entah apa yang terjadi di dalam sana. Terdengar teriakan-teriakan keras dalam bahasa
Belanda. Aku terpaku.
“Je bent niet de Nederlandse!” teriak serdadu Belanda sambil menodongkan senjatanya pada Parto. Sepertinya
serdadu itu telah mencurigai Parto sebagai Belanda gadungan. “Ik ben van de Nederlandse,” jawab Parto. Ia
tetap mengaku sebagai orang Belanda.“Je bent niet de Nederlandse!” teriak Serdadu itu semakin marah.Mereka
berbantah-bantahan. Entahlah, mungkin sedang sial, tiba-tiba saja aku tak bisa menahan keinginan untuk bersin.
Haajjiin.. Serdadu itu melihatku. Menembakiku dengan berondongan peluru. Aku berlari menyelamatkan diri di
antara semak belukar. Meninggalkan sahabatku sendirian.
Itulah terakhir kalinya aku melihat Parto. Mayatnya bahkan tak pernah ditemukan. Sahabatku terjebak di
kandang musuh karena keteledoranku. Seandainya aku tak terlalu serakah. Mungkin Parto bisa ikut menikmati
perjuangannya. Menikmati kebebasan yang kami rindukan. Kita sudah merdeka. Kita sudah bebas dari
penjajahan. Berulang-ulang kuucapkan kalimat itu. Aku yakin Parto mendengarnya di atas sana.
“Eh, Maaf, Mbah! Jangan mengotori tempat ini! Tolong! Nanti saya bisa dimarahi supervisor,” kata seorang
petugas cleaning service yang melihatku hendak menabur bunga di pintu itu.“Ayolah, Pak. Jangan sampai kita
diusir dari sini karena membuang sampah sembarangan!” bisik anakku membuatku miris.Ya, zaman telah
berganti, musim terus berputar. Semuanya telah berubah. Bahkan, sekadar menaburkan bunga pun tak bisa lagi
kulakukan.
Anda mungkin juga menyukai
- Trilogi Pelelangan: Sebuah “Jane Eyre” Zaman Modern (Bahasa Indonesia)Dari EverandTrilogi Pelelangan: Sebuah “Jane Eyre” Zaman Modern (Bahasa Indonesia)Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (7)
- Laporan Jakarta Karya Totilawati TjitrawasitaDokumen8 halamanLaporan Jakarta Karya Totilawati Tjitrawasitaranaindy0% (1)
- CLARA Atawa Wanita Yang DiperkosaDokumen5 halamanCLARA Atawa Wanita Yang DiperkosasimonSapala100% (3)
- Menunggu - DazaiDokumen8 halamanMenunggu - DazaiPutri AndiniBelum ada peringkat
- Hikayat Dan CerpenDokumen6 halamanHikayat Dan CerpenAgnaBelum ada peringkat
- Analisis Kisah in Medias ResDokumen6 halamanAnalisis Kisah in Medias Reszaidan.ananda2002Belum ada peringkat
- Cerpen Menulis FiksiDokumen21 halamanCerpen Menulis FiksiGunawan SembiringBelum ada peringkat
- CerpenDokumen4 halamanCerpenApDhan B-WokeBelum ada peringkat
- Ada Monolog Kampung Kunang 24Dokumen5 halamanAda Monolog Kampung Kunang 24Mardianto HarwiBelum ada peringkat
- Peci Hitam KyaiDokumen1 halamanPeci Hitam Kyairaka151Belum ada peringkat
- Badan Saya Masih Meriang Ketika Polisi Itu DatangDokumen3 halamanBadan Saya Masih Meriang Ketika Polisi Itu DatangSharensyahBelum ada peringkat
- Bengawan SoloDokumen4 halamanBengawan SoloSAADI RISMAWAN0% (1)
- Andrea Hirata Sebelas PatriotDokumen22 halamanAndrea Hirata Sebelas PatriotIndriyani AnthonieBelum ada peringkat
- Cerita IlaDokumen34 halamanCerita IlaIla SakilaBelum ada peringkat
- Cerita IbukuDokumen3 halamanCerita IbukuSinung WidyaBelum ada peringkat
- KemarauDokumen5 halamanKemarauGenevraBelum ada peringkat
- KemarauDokumen3 halamanKemarauNur indriani SamiunBelum ada peringkat
- CerpenDokumen12 halamanCerpennecolaniceBelum ada peringkat
- Keberanian ManusiaDokumen8 halamanKeberanian ManusiaImam Al RezkiBelum ada peringkat
- Cerpen KemarauDokumen4 halamanCerpen KemarauanjelirahmiBelum ada peringkat
- Surat Tapol Kepada TKWDokumen5 halamanSurat Tapol Kepada TKWMuhammad ArifinBelum ada peringkat
- CERPENDokumen7 halamanCERPENsaptiah sindangbarang100% (1)
- Monoton - Luna 9ADokumen3 halamanMonoton - Luna 9Avanny fabiantiBelum ada peringkat
- Episode Daun KeringDokumen5 halamanEpisode Daun KeringMuhammad ArdianBelum ada peringkat
- Menjadi Diri SendiriDokumen42 halamanMenjadi Diri SendiriIndra SangianBelum ada peringkat
- Cerpen KemarauDokumen3 halamanCerpen KemarauChateria Nylan SyafaraBelum ada peringkat
- Perjalanan Sebu-WPS OfficeDokumen16 halamanPerjalanan Sebu-WPS OfficeBazgha NovanBelum ada peringkat
- Puisi-Puisi Heru EncheDokumen6 halamanPuisi-Puisi Heru EncheRiki AhmadBelum ada peringkat
- Menjelang Kedatangan Zarathustra Merancang Pencurian LenteranyaDokumen84 halamanMenjelang Kedatangan Zarathustra Merancang Pencurian LenteranyabehindthebrutalresidenceBelum ada peringkat
- KemarauDokumen3 halamanKemarausyafiq officialBelum ada peringkat
- Cerpen Andrea Hirata Kemarau 221129 101942Dokumen5 halamanCerpen Andrea Hirata Kemarau 221129 101942Ikhman AkbarBelum ada peringkat
- M.dwi Ridwan W.N - Xi-9 - 20 - Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanM.dwi Ridwan W.N - Xi-9 - 20 - Bahasa IndonesiaIrsyad Hanan r.kBelum ada peringkat
- Translate The Great ExpectationDokumen114 halamanTranslate The Great Expectationerlina nurliaBelum ada peringkat
- CerpenDokumen38 halamanCerpenAnnisa Nur FatimahBelum ada peringkat
- Cerpen JakartaDokumen11 halamanCerpen JakartaKhairunnisa ArinBelum ada peringkat
- Cerpen 1Dokumen5 halamanCerpen 1Monika LorensaBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok Cerpen Bahasa IndonesiaDokumen9 halamanTugas Kelompok Cerpen Bahasa IndonesiaHilma AyuninaBelum ada peringkat
- Si RabinDokumen5 halamanSi RabinPutri AzizahBelum ada peringkat
- Analisis Novel PeterDokumen4 halamanAnalisis Novel PeterMad Akatsuki100% (1)
- 001 - Siswandi CeriteDokumen9 halaman001 - Siswandi CeriteSISWANDIBelum ada peringkat
- Hingga Batu BerbicaraDokumen4 halamanHingga Batu BerbicaraTio AnugrahBelum ada peringkat
- Arwah - ArwahDokumen8 halamanArwah - ArwahgibransBelum ada peringkat
- KEMARAUDokumen4 halamanKEMARAUKæiBelum ada peringkat
- Pesan Dari Mereka (SFILEDokumen19 halamanPesan Dari Mereka (SFILEanofri yusbenBelum ada peringkat
- Cerpen IamsterdamDokumen19 halamanCerpen IamsterdamMaria VitaBelum ada peringkat
- Cincin KawinDokumen5 halamanCincin KawinNursita Diah AndrianiBelum ada peringkat
- Latihan Menulis Cerpen Hari Ke-9Dokumen2 halamanLatihan Menulis Cerpen Hari Ke-9보라DiahapBelum ada peringkat
- Cerpen Faisal OddangDokumen6 halamanCerpen Faisal OddangLukianBelum ada peringkat
- KemarauDokumen3 halamanKemarauGenevraBelum ada peringkat
- Bedah Kisi-Kisi UsDokumen14 halamanBedah Kisi-Kisi UsnaokoBelum ada peringkat
- Si Bongkok Dari Notre-DameDokumen114 halamanSi Bongkok Dari Notre-Damefaridze79100% (1)
- Ah, JakartaDokumen7 halamanAh, Jakartashelly nur aidaBelum ada peringkat
- Cerpen Bersambung XI MIPA GDokumen5 halamanCerpen Bersambung XI MIPA GTaufik HidayatBelum ada peringkat
- Novel Sebuah Kemurahan, Toni MorrisonDokumen195 halamanNovel Sebuah Kemurahan, Toni MorrisonJannus P. SihombingBelum ada peringkat
- Cerita Fiksi Perjuangan BangsaDokumen3 halamanCerita Fiksi Perjuangan BangsasenimanBelum ada peringkat
- CerpenDokumen38 halamanCerpenAnnisa Nur FatimahBelum ada peringkat
- Lin TangDokumen5 halamanLin TangelsaBelum ada peringkat
- Serigala Besar Jahat itu Kaya! Memoar Dongeng di ManhattanDari EverandSerigala Besar Jahat itu Kaya! Memoar Dongeng di ManhattanBelum ada peringkat