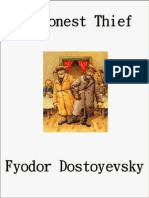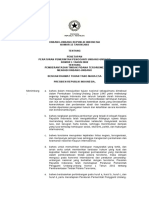Menunggu - Dazai
Diunggah oleh
Putri Andini0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
131 tayangan8 halamanMenunggu
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniMenunggu
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
131 tayangan8 halamanMenunggu - Dazai
Diunggah oleh
Putri AndiniMenunggu
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 8
Menunggu
Osamu Dazai
Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Jepang dengan judul ―Matsu‖ pada
tahun 1942
Diterjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris oleh Angus Turvill
dan diterbitkan oleh Japanese Publishing and Promotion Center pada tahun
2007
Diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh M. Al Mukhlishiddin dari versi
terjemahan bahasa Inggris pada tahun 2015
Diterbitkan di TerjemahAl pada tahun 2016
Sampul edisi ini disesuaikan dari sampul edisi bahasa Inggris
Perancang sampul: Holly Esparrago
2
Tiap hari aku pergi ke stasiun kecil untuk menemui
seseorang. Siapakah orang itu, entahlah.
Aku selalu pergi ke sana tiap kali pulang ke rumah
dari pasar. Aku duduk di bangku dingin, memangkukan
keranjang, dan memandang gerbang cek karcis. Tiap kali
sebuah kereta tiba—kereta ke hulu atau kereta ke hilir—
penumpang menghambur keluar dari pintu gerbong dan
berduyun-duyun ke gerbang. Dengan raut gusar mereka
menunjukkan kartu masuk, menyerahkan karcis. Lalu,
dengan tatapan lurus ke depan, mereka bergegas. Mereka
melewati bangkuku menuju ruang terbuka di depan
stasiun, lalu berceraiberai ke tujuannya masing-masing.
Aku cuma duduk di sini. Bagaimana kalau nanti ada
seseorang yang tersenyum dan mengajakku berbincang?
Oh, tidak, jangan! Pikiran ini membuatku sangat gugup.
Memikirkannya saja membuatku bergidik, seperti kalau
air dingin diguyurkan ke punggungku—aku merasa sesak.
3
Tapi tetap saja aku menunggu seseorang, tiap hari.
Siapakah gerangan orang yang kutunggu itu? Orangnya
macam apa? Tapi mungkin juga bukan seorang manusia.
Aku tak suka orang-orang! Lebih tepatnya, mereka
membuatku takut. Berhadapan dengan seseorang,
mengatakan hal yang sebenarnya tak kuinginkan, seperti
―apa kabar?‖ atau ―udaranya makin dingin, ya?‖—
ngomong cuma asal ngomong belaka. Aku benci itu. Aku
jadi merasa seperti seorang pembohong, seakan-akan tiada
pembohong lebih besar di dunia ini. Aku jadi ingin mati
saja. Dan orang yang berbicara denganku, karena terlalu
waspada terhadapku, memberi pujian tak jelas,
menguraikan pendapatnya padahal sebenarnya dia tak
punya pendapat. Aku mendengarkan mereka dan merasa
sedih, sedih karena kewaspadaan penuh prasangka
mereka. Itu membuatku makin makin tidak menyukai
dunia—aku tak tahan. Apakah orang-orang selalu begini
4
—seumur hidup saling menjemukan dengan obrolan kaku
penuh curiga? Aku tak suka berkumpul bersama orang-
orang! Jadi, kecuali kalau keadaannya benar-benar tidak
biasa, aku tak pernah melakukan apa pun yang seperti
mengunjungi teman. Sejak dulu aku lebih merasa nyaman
di rumah, diam merajut bersama ibuku, kami berdua saja.
Tapi lalu perang pecah dan keadaan menjadi sangat tegang
sampai-sampai aku merasa tak boleh jadi satu-satunya
orang yang tiap hari cuma diam di rumah. Aku merasa tak
nyaman. Aku tak bisa santai sama sekali. Aku jadi ingin
bekerja sekeras mungkin, berkontribusi secara langsung.
Aku jadi malu dengan cara hidupku selama ini.
Aku tak tahan duduk diam di rumah. Tapi kalaupun
aku mau bepergian, aku mesti pergi ke mana? Jadi aku
berbelanja saja, dan di jalan pulang aku pergi ke stasiun
dan duduk di bangku dingin ini. Aku ingin ―seseorang itu‖
datang: ―Ah, seolah-olah mereka memang akan tiba-tiba
5
muncul!‖ Tapi aku juga khawatir: ―Bagaimana kalau
mereka benar-benar datang? Aku mesti bagaimana?‖
Bersamaan dengan itu, aku telah memutuskan akan
pasrah: ‗Jika mereka datang aku akan mengabdikan diri
untuk mereka. Momen itu akan menentukan nasibku.‘
Perasaan-perasaan ini berkelindan dengan aneh –perasaan
ini dan khayalan memalukan. Hatiku terusik: benar-benar
membebani, nyaris menyesakkan. Dunia jadi sunyi.
Orang-orang yang datang dan pergi di stasiun tampak jauh
dan kecil, seolah-olah aku meneropongnya dengan
teleskop terbalik. Rasanya tidak nyata, seakan aku dalam
lamunan, seakan aku tak bisa memastikan aku hidup atau
mati. Oh, apakah yang kutunggu itu? Barangkali aku cuma
perek yang kotor. Segala sesuatu tentang perang dan
ketidaknyamanan, keinginan untuk bekerja sekeras
mungkin, keinginan untuk berkontribusi langsung –
mungkin semua itu cuma bohong belaka. Barangkali aku
6
cuma membuat-buat alasan yang terdengar baik.
Barangkali aku cuma berusaha mencari-cari celah untuk
mewujudkan khayalanku yang seenaknya. Aku duduk di
sini dengan wajah menatap kosong, tapi jauh di lubuk hati
aku merasa melihat suatu percik, suatu kobaran yang
keterlaluan memikat.
Lantas siapakah yang kutunggu? Aku sama sekali tak
tahu –hanya bayangan samar di tengah kabut pikiranku.
Tapi tetap saja aku menunggu. Tiap hari sejak perang
dimulai, di tengah perjalanan pulang dari belanja aku
datang ke stasiun, duduk di bangku dingin ini, dan
menunggu. Bagaimana kalau nanti ada seseorang yang
tersenyum dan mengajakku berbincang? Oh, tidak, jangan!
Bukan kamu yang kutunggu. Lantas, siapa kalau begitu?
Siapakah yang kutunggu? Seorang suami? Bukan. Seorang
kekasih? Tentu saja bukan. Seorang teman? Oh, bukan.
Uang? Konyol. Sesosok hantu? Oh, oh tidak!
7
Sesuatu yang lebih menyenangkan, cerah dan ceria,
sesuatu yang menakjubkan. Entahlah apa. Sesuatu yang
seperti musim semi. Bukan, bukan itu. Daun segar. Bulan
Mei. Air jernih dan sejuk yang mengaliri ladang gandum.
Bukan, sama sekali bukan itu. Oh, meskipun begitu, aku
tetap saja menunggu, jantungku berdegup. Orang-orang
mengalir lewat di depanku. Bukan dia. Bukan juga dia.
Sambil memeluk keranjang belanja, aku menggigil. Aku
menunggu. Dengan segenap hatiku, aku menunggu. Aku
memohon padamu, tolong, tolong jangan lupakan aku –
gadis yang datang tiap hari ke stasiun untuk menemuimu
dan lalu pulang dengan sedih. Tolong, tolong ingat aku,
dan jangan menertawakanku. Aku tak akan
memberitahukan nama stasiun kecil ini. Tak perlu: suatu
kali kau pasti pernah melihatku, bahkan kalaupun aku tak
melihatmu.
Anda mungkin juga menyukai
- Bukan Perjaka by Nuril BasriDokumen1 halamanBukan Perjaka by Nuril BasriaanBelum ada peringkat
- Light Novel - BSD-1Dokumen94 halamanLight Novel - BSD-1Hanswa50% (2)
- Subagio Sastrowardoyo-Dan Kematian Makin Akrab - Pilihan Sajak-Gramedia Widiasarana Indonesia (1995)Dokumen162 halamanSubagio Sastrowardoyo-Dan Kematian Makin Akrab - Pilihan Sajak-Gramedia Widiasarana Indonesia (1995)Nafisa DiniwatiBelum ada peringkat
- RashomonDokumen9 halamanRashomonwidya dewiBelum ada peringkat
- Kau, Aku, Dan Sepucuk Angpau MerahDokumen1 halamanKau, Aku, Dan Sepucuk Angpau Merahtimah24100% (1)
- Analisis Tokoh Utama Dalam NovelDokumen1 halamanAnalisis Tokoh Utama Dalam NovelYuris T ZegaBelum ada peringkat
- Satir Kehidupan Kelas Sosial Dalam Kita Pergi Hari IniDokumen10 halamanSatir Kehidupan Kelas Sosial Dalam Kita Pergi Hari IniHaura ZahidahBelum ada peringkat
- O Amuk Kapak: Sutardji Calzoum BachriDokumen138 halamanO Amuk Kapak: Sutardji Calzoum BachriMaman Saja100% (2)
- Supernova 6 PDFDokumen725 halamanSupernova 6 PDFIran RisiadiBelum ada peringkat
- Kucing Hitam-Edgar Allan PoeDokumen93 halamanKucing Hitam-Edgar Allan PoeRay100% (2)
- Alber Camus - The FallDokumen202 halamanAlber Camus - The FallSauqi Dzikri86% (7)
- Resensi BukuDokumen3 halamanResensi BukuBerlianaBelum ada peringkat
- Catatan Dari Bawah Tanah - Fyodor DostoyevskyDokumen83 halamanCatatan Dari Bawah Tanah - Fyodor DostoyevskysoepolenkBelum ada peringkat
- Sapardi Djoko DamonoDokumen5 halamanSapardi Djoko Damonofahri kurniawanBelum ada peringkat
- Perempuan Di Titik Nol - Nawal El - Saadawi PDFDokumen252 halamanPerempuan Di Titik Nol - Nawal El - Saadawi PDFAnamPetaniDusun100% (1)
- Perempuan Patah Hati Yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi PDFDokumen10 halamanPerempuan Patah Hati Yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi PDFFryda AyudhaBelum ada peringkat
- Artikel Tentang Sastra IndonesiaDokumen7 halamanArtikel Tentang Sastra IndonesiaSuaib S. SyamsulBelum ada peringkat
- Haruki MurakamiDokumen130 halamanHaruki MurakamiKlaudia Anastasia Deda100% (1)
- (RBE) Laksmi P - AmbaDokumen569 halaman(RBE) Laksmi P - AmbaallesandroBelum ada peringkat
- Cantik Itu LukaDokumen493 halamanCantik Itu LukaLeonaldo FirmansyahBelum ada peringkat
- Negeri 5 Menara PDFDokumen339 halamanNegeri 5 Menara PDFM Hilmi Setiawan100% (2)
- RomanDokumen4 halamanRomanLisa HendersonBelum ada peringkat
- Empat BesarDokumen218 halamanEmpat BesarPavel NevedBelum ada peringkat
- Akulah Si TelagaDokumen25 halamanAkulah Si TelagafireworkrwBelum ada peringkat
- Robohnya Surau Kami PDFDokumen14 halamanRobohnya Surau Kami PDFFie Ittue Fiandttliefde Part II100% (1)
- Kumpulan Cerpen Kompas 2007Dokumen198 halamanKumpulan Cerpen Kompas 2007Muhtar Rais100% (1)
- Dee Lestari - AkarDokumen116 halamanDee Lestari - AkarRmuchammad AliBelum ada peringkat
- Sri Men AntiDokumen2 halamanSri Men AntiNovita SariBelum ada peringkat
- Bumi Manusia by Toer, Pramoedya AnantaDokumen366 halamanBumi Manusia by Toer, Pramoedya AnantaDoni P100% (1)
- (Pramoedya Ananta Toer) Bukan Pasar MalamDokumen53 halaman(Pramoedya Ananta Toer) Bukan Pasar MalamMuhammad Isa67% (3)
- Resensi Supernova PetirDokumen7 halamanResensi Supernova PetirAkas TsubasaBelum ada peringkat
- Lelaki Harimau Eka KurniawanpdfDokumen204 halamanLelaki Harimau Eka KurniawanpdfHadi Satria GanesaBelum ada peringkat
- Booklet Kumpulan Puisi para Jenderal Marah-Marah PDFDokumen39 halamanBooklet Kumpulan Puisi para Jenderal Marah-Marah PDFSetyo PambudiBelum ada peringkat
- Maling Yang Jujur - Fyodor Mikhailovich DostoyevskyDokumen109 halamanMaling Yang Jujur - Fyodor Mikhailovich DostoyevskyRosita OktavianiBelum ada peringkat
- Ayu Utami - Cerita Cinta Enrico PDFDokumen256 halamanAyu Utami - Cerita Cinta Enrico PDFImelda TriBelum ada peringkat
- AlbertCamus Orang OrangTerbungkamDokumen212 halamanAlbertCamus Orang OrangTerbungkamAkhmad Alfan Rahadi100% (3)
- Pramoedya Ananta Tour - Dari Dekat SekaliDokumen284 halamanPramoedya Ananta Tour - Dari Dekat SekaliNaldhyRivalldhy100% (1)
- Ayu Utami: Larung Adalah Lanjutan Novel Saman. Di Penghujung MasaDokumen311 halamanAyu Utami: Larung Adalah Lanjutan Novel Saman. Di Penghujung MasaIvana Rambu Sada RewaBelum ada peringkat
- Supernova: AkarDokumen12 halamanSupernova: AkarBlue Wycherley0% (1)
- Aksi Massa - Tan Malaka (1926)Dokumen123 halamanAksi Massa - Tan Malaka (1926)Amorfati Munggaran100% (1)
- Orkes Madun IVDokumen79 halamanOrkes Madun IVPruce D. YantoBelum ada peringkat
- 1gij4rb5SRym0 BLHObllaYU Z RO7h7VDokumen85 halaman1gij4rb5SRym0 BLHObllaYU Z RO7h7VKhumaedi AbsoriBelum ada peringkat
- Maou Gakuin Vol2 RueNovelDokumen300 halamanMaou Gakuin Vol2 RueNovelPucup Subarjo100% (1)
- Dazai Osamu - WaitingDokumen5 halamanDazai Osamu - WaitingMasykur MajidBelum ada peringkat
- Malam Gelisah-NASKAH MONOLOGDokumen5 halamanMalam Gelisah-NASKAH MONOLOGDifra AldinaBelum ada peringkat
- Dokumen GuaDokumen4 halamanDokumen Guanola.mailnewBelum ada peringkat
- Dokumen CerpenDokumen4 halamanDokumen CerpenSri wildayaniBelum ada peringkat
- Cerpen Santri..Dokumen2 halamanCerpen Santri..Ubaidillah WahidBelum ada peringkat
- Di Meja KerjaDokumen4 halamanDi Meja KerjaIsmawati AhmadBelum ada peringkat
- NauraDokumen3 halamanNauraabelBelum ada peringkat
- Cerpen2 - JumiDokumen4 halamanCerpen2 - JumiJumiati Ratna SariBelum ada peringkat
- CERPEN Rhamanda LestariDokumen5 halamanCERPEN Rhamanda LestariSarjono Sendang100% (1)
- Cerpen Sebilah Pisau Roti (Un Soir Du Paris 10)Dokumen5 halamanCerpen Sebilah Pisau Roti (Un Soir Du Paris 10)lizphobeeBelum ada peringkat
- Asma Kinarya JapaDokumen5 halamanAsma Kinarya JapaUswah HasanahBelum ada peringkat
- Jilid 1 Novel SeruDokumen126 halamanJilid 1 Novel SeruMochammad Galih MaulanaBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok Cerpen Bahasa IndonesiaDokumen9 halamanTugas Kelompok Cerpen Bahasa IndonesiaHilma AyuninaBelum ada peringkat
- Cerpen Ashila Suandi 12 Mipa 6Dokumen5 halamanCerpen Ashila Suandi 12 Mipa 6Ashila SuandiBelum ada peringkat
- "Waktu Mengandung Dirimu Dulu, Ibumu Pasti NgidamnyaDokumen26 halaman"Waktu Mengandung Dirimu Dulu, Ibumu Pasti Ngidamnya2dayBelum ada peringkat
- Eiyuu To Majo No Tensei Love Comedy Vol-2 (END) (LN) Bahasa Indonesia - Reigin TLDokumen276 halamanEiyuu To Majo No Tensei Love Comedy Vol-2 (END) (LN) Bahasa Indonesia - Reigin TLRizki SyahdaniBelum ada peringkat
- Bab I PDFDokumen5 halamanBab I PDFElsasriyuliantiBelum ada peringkat
- Asal Usul Kosmos Menurut Paul Davies: Himyari Yusuf Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung AbstrakDokumen23 halamanAsal Usul Kosmos Menurut Paul Davies: Himyari Yusuf Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung AbstrakPutri AndiniBelum ada peringkat
- Silabus Kelas 6 Tema 7Dokumen20 halamanSilabus Kelas 6 Tema 7ook lebung100% (12)
- Rajinbacaebook - Pramoedya - Bumi Manusia PDFDokumen314 halamanRajinbacaebook - Pramoedya - Bumi Manusia PDFTobing89% (9)
- Menunggu - DazaiDokumen8 halamanMenunggu - DazaiPutri AndiniBelum ada peringkat
- Peristiwa Tanjung PriokDokumen6 halamanPeristiwa Tanjung PriokPutri AndiniBelum ada peringkat
- Uu No 15 Tahun 2003 Teroris PDFDokumen4 halamanUu No 15 Tahun 2003 Teroris PDFAstyr Tierta AgusBelum ada peringkat