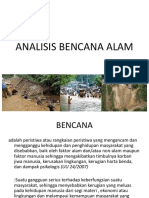Laporan Praktikum Peta Rawan Longsor 2
Laporan Praktikum Peta Rawan Longsor 2
Diunggah oleh
putrikertasmaya123Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Laporan Praktikum Peta Rawan Longsor 2
Laporan Praktikum Peta Rawan Longsor 2
Diunggah oleh
putrikertasmaya123Hak Cipta:
Format Tersedia
LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
PETA RAWAN LONGSOR
Disusun oleh:
Nama : Putri Lupita
NIM : 117210047
Plug : 01
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2021
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang secara
geografis terletak di garis khatulistiwa dan berada pada pertemuan lempengan-
lempengan tektonik utama dunia, yaitu lempeng Eurasia, India Australia, dan
Samudra Pasifik yang sangat memungkinkan untuk saling menumbuk/bertabrakan.
Tumbukan ini nantinya akan membentuk sebuah palung Samudra, lipatan,
punggungan dan patahan di busur kepulauan, sebaran gunung api, dan sebaran
sumber gempa bumi.
Terdapat sekitar 129 gunung api di Indonesia yang mana jumlah tersebut
merupakan 13% dari jumlah gunung aktif dunia, sehingga Indonesia sangat rawan
terhadap bencana letusan gunung api dan juga gempa bumi. Letusan gunung api
inilah yang menghasilkan jenis tanah pelapukan yang memiliki komposisi sebagian
besar lempung dengan sedikit pasir dan bersifat subur.
Tanah pelapukan yang berada di atas batuan kedap air pada
perbukitan/punggungan dengan kemiringan sedang hingga terjal berpotensi
mengakibatkan tanah longsor pada musim hujan dengan curah hujan yang
berkuantitas tinggi. Jika di area perbukitan tersebut tidak ada tanaman yang berakar
kuat dan dalam, maka kawasan tersebut akan rawan bencana tanah longsor.
Terlebih jika ditambah curah hujan yang tinggi dan topografi berbukit yang
memiliki tingkat kecuraman yang tinggi semakin memicu terjadinya bencana tanah
longsor.
Salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tanah longsor
yang tinggi adalah kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kondisi ini dapat dilihat dari
area pegunungan dan perbukitan kabupaten Sleman seluas 72,11% dari luas
wilayah keseluruhan (RTRW Kabupaten Sleman, 2011-2031). Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman (2011) memaparkan bahwa kabupaten
Sleman memiliki ketinggian antara 100-2.500 mdpl dengan kemiringan yang sangat
curam, yaitu di atas >40% seluas 1.526 km2 dengan total wilayah 27,01 Ha.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut:
1. Apa itu tanah longsor?
2 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2. Mengapa tanah longsor bisa terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhinya?
3. Parameter apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan peta rawan longsor?
4. Daerah mana saja di kabupaten Sleman yang memiliki potensi rawan longsor?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dari dilakukannya praktikum kali ini adalah:
1. Mengetahui pengertian dari tanah longsor.
2. Mengetahui sebab terjadinya tanah longsor dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.
3. Mengetahui parameter-parameter yang dibutuhkan dalam pembuatan peta
rawan longsor.
4. Mengetahui daerah mana saja di kabupaten Sleman yang memiliki potensi
rawan longsor.
3 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
BAB II
DASAR TEORI
2.1. Bencana Alam
Menurut Peraturan Kepala BNPB (2012) bencana merupakan suatu peristiwa
atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan
penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan/atau non-alam maupun
manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Bencana alam merupakan salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat,
dimana pun dan kapan pun sehingga menimbulkan risiko atau bahaya terhadap
kehidupan manusia, baik kerugian harta benda maupun korban jiwa (Nugroho et
al., 2009).
2.2. Tanah Longsor
Tanah longsor merupakan suatu perpindahan material pembentuk lereng
berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material tersebut yang bergerak ke
bawah atau ke luar lereng (SNI 13-7124-2005). Sedangkan menurut Bayuaji et al.,
(2016) mendefinisikan tanah longsor sebagai contoh dari suatu proses geologi yang
disebut dengan mass wasting atau sering disebut juga gerakan massa (mass
movement), merupakan perpindahan massa batuan dan tanah dari tempat yang
tinggi ke tempat yang rendah karena adanya gaya gravitasi.
Tanah longsor terjadi akibat adanya gangguan kestabilan pada tanah atau
batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng tersebut dapat dikontrol oleh
kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi tanah atau batuan
penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Secara umum,
bencana longsor ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor
pemicu. Faktor pendorong itu sendiri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi
kondisi material, sedangkan faktor pemicu merupakan faktor yang menyebabkan
bergeraknya material tersebut (Faizana et al., 2015).
Potensi terjadinya tanah longsor pada lereng tergantung pada kondisi batuan
dana tanah penyusunnya, struktur geologi, curah hujan, dan juga penggunaan lahan.
Namun, tanah longsor ini umumnya terjadi pada musim hujan dengan curah hujan
yang tinggi. Tanah yang kasar akan lebih berisiko terjadi longsor karena tanah
tersebut mempunyai kohesi agregat tanah yang rendah (Faizana et al., 2015).
4 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
2.3. Pemetaan Rawan Longsor
Perkembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu menyediakan
informasi data geospasial seperti objek di permukaan bumi secara cepat sekaligus
menyediakan sistem analisis keruangan yang akurat, sehingga dapat dilakukan
upaya mitigasi yang bertujuan mencegah risiko yang berpotensi menjadi bencana
atau mengurangi efek dari bencana ketika bencana itu terjadi (Faizana et al., 2015).
Menurut Aditya (2010) Pemetaan Risiko Bencana merupakan suatu kegiatan
pembuatan peta yang merepresentasikan dampak negatif yang dapat timbul berupa
kerugian materi dan non materi pada suatu wilayah apabila terjadi bencana.
Identifikasi daerah rawan tanah longsor penting untuk dilakukan agar dapat
mengetahui penyebab utama tanah longsor dan karakteristik dari tiap kejadian
longsor sehingga dapat menjadi sebuah rujukan dalam mitigasi bencana longsor
berikutnya. Identifikasi ini juga penting untuk mengetahui hubungan antara lokasi
kejadian longsor dengan faktor persebaran geologi (batuan) dan tata guna lahan di
daerah tersebut sehingga dapat diketahui tata guna lahan yang sesuai pada setiap
karakteristik lahan dan geologinya (Effendi, 2008).
Menurut Khoiri (2018), penentuan tingkat ancaman bencana tanah longsor
dilakukan dengan cara menggabungkan pembobotan parameter kelerengan, jenis
tanah dan batuan, curah hujan, dan tutupan lahan. Berikut merupakan rincian
pembobotan setiap parameter:
Tabel 2.1 Pembobotan Setiap Parameter
Faktor Kelas
0% - 8% 1
8% - 25% 2
Slope (Kemiringan) 30% 25% - 40% 3
40% - 100% 4
< 2000 1
Precipitation (Curah hujan) 20% 2000-3000 2
(mm/yr) > 3000 3
Bandara/Pelabuhan 1
Belukar 2
Hutan Kering Sekunder 1
Hutan Tanaman 1
Landcover (Tutupan lahan) 20% Pemukiman 1
Pertanian Lahan Kering 2
Pertanian Lahan Kering Campur 2
Sawah 1
Tanah Terbuka 1
5 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Batu Gamping Dan Batupasir 1
Napalan Formasi Sentolo
Batu Lempung Tufan Formasi 3
Semilir
Andesit 1
Batuan Vulkanik Tua (Breksi, Tuf, 1
dan Lava) Formasi Nglanggeran
Endapan Gunung Merapi Tua 1
Endapan Formasi Naggulan 1
Diorit 1
Endapan Longsoran (Ladu) Dari 3
Lithology (Jenis Tanah dan 30% Awan Panas (Muda)
Batuan) Endapan Longsoran (Ladu) Dari 3
Awan Panas (Tua)
Endapan Longsoran (Ladu) Dari 3
Awan Panas
Endapan Gunungapi Muda Merapi 1
Formasi Semilir 1
Batuan Gunung Api Tak 1
Terpisahkan
Formasi Kebobutak 1
Tabel 2.2 Indeks tanah longsor dan kerawanannya
Indeks Longsor Kerawanan
0 0.875 Rendah
0.875 1.75 Sedang
1.75 2.625 Rawan
2.625 3.5 Sangat Rawan
6 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
BAB III
METODE PRAKTIKUM
3.1. Waktu dan Tempat
Kegiatan praktikum dilaksanakan pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 26 November 2022
Pukul : 07.00 – 08.30 WIB
Tempat : Ruang Sudirman 1.1 Kampus 2 UPNYK
3.2. Alat dan Bahan
Pada kegiatan Pengenalan QGIS, terdapat perangkat dan data, di antaranya sebagai
berikut:
1. Perangkat Keras (Hardware) yang dibutuhkan:
a. Laptop
b. Mouse
2. Perangkat Lunak (Software) yang dibutuhkan:
a. Aplikasi ArcGIS 10.8
3. Data yang dibutuhkan:
a. Data SHP tutupan lahan Sleman
b. Data DEMNAS Sleman
c. Data SHP curah hujan Sleman
d. Data SHP geologi Sleman
3.3. Langkah Pengerjaan
▪ Buka software ArcGIS 10.8.
7 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Klik menu view pilih data frame properties.
▪ Ubah sistem koordinat dengan cara pilih coordinate system → WGS
1984 UTM Zone 49S.
8 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Input data curah hujan, geologi, dan juga tutupan lahan kabupaten
Sleman dengan cara klik kanan pada layers → add data → pilih data
curah hujan, geologi, dan tutupan lahan → add.
▪ Maka tampilannya akan seperti pada gambar di bawah.
▪ Input juga data DEM (Digital Elevation Model) dengan cara klik kanan
pada layers → add data → pilih data → add.
9 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka tampilannya akan seperti pada gambar di bawah.
▪ Buat peta kemiringan lahan menggunakan data DEM dengan cara klik
menu geoprocessing → Arctoolbox → 3D analyst tools → raster surface
→ slope → drag data DEMNAS ke kolom input raster. Pada kolom
output raster pilih tempat untuk menyimpan file DEMNAS tersebut. Klik
Ok
10 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka tampilannya akan seperti pada gambar di bawah.
▪ Pada Arctoolbox pilih → 3D analyst tools → raster reclass →
Reclassify. Input data DEMNAS yang sudah diolah olah kemiringannya
dengan cara drag layer DEMNAS_slope ke input raster. Pada kolom
reclass field pilih value. Selanjutnya pilih classify → method: equal
interval → classes: 5 → isi break values dengan presentase mengikuti
gambar di bawah→ kemudian klik OK
11 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
12 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka tampilannya akan seperti gambar di bawah.
▪ Pada Arctoolbox pilih → conversions tools → from raster → raster to
polygon → Drag layer reclass_DEMN1 untuk mengisi kolom input
raster → klik OK.
▪ Maka tampilannya akan seperti pada gambar di bawah.
13 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Sederhanakan poligon yang terpisah dengan cara klik layer
RasterT_Reclass1 → geoprocessing → dissolve → drag layer
RasterT_Reclass1 untuk mengisi kolom input features → centang
gridcode → OK.
▪ Klik kanan pada layer RasterT_Reclass1_Dissolve → open attribute
table → table options → add fields → pada kolom name isi keterangan
→ type: text → OK.
14 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Untuk dapat mengisi kolom keterangan dapat dilakukan dengan cara klik
editor → start editing → pilih layer RasterT_Reclass1_Dissolve →
continue → OK.
15 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Selanjutnya adalah mengisi besaran kemiringan dari kelas sesuai dengan
gambar di bawah.
▪ Setelah selesai kemudian save dengan cara pilih editor → save edits →
stop editing.
16 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka tampilannya akan seperti pada gambar di bawah.
▪ Selanjutnya adalah menyederhanakan data geologi_ar dengan cara klik
editor → start editing → klik kanan pada layer geologi_ar → open
attribute table → select data-data yang memiliki atribut yang sama →
editor → merge. Lakukan hingga semua data yang ada di layer
geologi_ar tersederhana semua.
17 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan hal yang sama pada parameter lain yang belum dilakukan
penyederhanaan data.
18 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Beri nilai pada masing-masing kelas dengan cara klik kanan pada layer
Curah_hujan_sleman → open attribute table → table options → add
field → tambahan tabel nilai, bobot, dan total.
19 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan hal yang sama pada parameter geologi.
20 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan hal yang sama pada parameter tutupan lahan.
21 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan hal yang sama pada parameter Slope.
22 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Klik kanan pada layer curah hujan → open attribute table → tambahkan
nilai dari masing-masing parameter curah hujan dengan cara pilih editor
→ start editing.
▪ Input nilai sesuai dengan gambar di bawah.
▪ Masukan juga nilai bobot hujan dengan cara klik kanan pada kolom
bbt_hujan → field calculator → tambahkan bobot berdasarkan pada
jurnal yang telah direkomendasikan yaitu sebesar 20 → OK.
23 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka nilai bobot hujan akan secara otomatis terisi.
▪ Tambahkan juga nilai total curah hujan dengan cara klik kanan pada
kolom ttl_hujan → field calculator → [c_hujan]*[bbt_hujan]*0.01 →
OK.
24 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka nilai dari total curah hujan akan terisi secara otomatis.
▪ Beri nilai pada masing-masing kelas batuan berdasarkan potensi batuan
mengalami longsor dan penyusun batuan tersebut.
25 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Masukan juga nilai bobot geologi dengan cara klik kanan pada kolom
bbt_geo → field calculator → tambahkan bobot berdasarkan pada jurnal
yang telah direkomendasikan yaitu sebesar 30 → OK.
▪ Tambahkan juga nilai total geologi dengan cara klik kanan pada kolom
ttl_hujan → field calculator → [c_geo]*[bbt_geo]*0.01 → OK.
26 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan hal yang sama pada parameter tutupan lahan untuk
menambahkan nilai kelas berdasarkan potensi longsor terhadap kelas
tersebut. Sehingga nilainya akan seperti pada gambar di bawah.
27 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
28 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan hal yang sama pada parameter slope untuk menambahkan nilai
kelas berdasarkan potensi longsor terhadap kelas tersebut. Sehingga
nilainya akan seperti pada gambar di bawah.
29 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
30 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan overlay dengan cara pilih ArcToolbox → analysis tools →
overlay.
▪ Pada input features masukkan keempat parameter yang digunakan dalam
pembuatan peta rawan longsor.
▪ Maka attribute table dari masing-masing parameter secara otomatis akan
tergabung menjadi satu layer.
31 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Tambahkan field baru untuk menjumlahkan nilai total dari seluruh
parameter.
▪ Jumlahkan nilai total dari masing-masing parameter dengan cara klik
kanan pada kolom Total → field calculator → [ttl_slope] + [ttl_tlah] +
[ttl_geo] + [ttl_hujan] → OK.
32 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka secara nilai total dari masing-masing parameter secara otomatis
akan terjumlah.
▪ Selanjutnya, untuk menambahkan kelas kerawanan pada longsor,
tambahkan field baru dengan nama Kerawanan dan dengan tipe Text.
33 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Tentukan kelas kerawanan dari nilai total yang telah dihitung dengan cara
lakukan sort dengan nilai terendah → select attribute berdasarkan nilai
yang sama pada nilai totalnya → pada field Kerawanan klik kanan →
field calculator → beri nama kelas kerawanan: “Cukup Rawan” → OK.
34 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka secara otomatis, atribut yang dipilih memiliki kelas yang terisi
pada tabel kerawanan cukup rawan.
35 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan hal yang sama untuk mengkelaskan berdasarkan nilai total pada
tabel kerawanan sebelumnya.
36 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Lakukan pewarnaan terhadap masing-masing kelas yang telah dibuat
dengan cara klik kanan pada layer Parameter_All → properties →
symbology → categories → value field: Kerawanan → add all values.
Sesuaikan warna sesuai dengan keinginan kemudian klik OK.
37 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
▪ Maka peta rawan longsor berhasil dibuat berdasarkan klasifikasi warna
yang telah ditentukan.
▪ Selanjutnya adalah melakukan layouting peta rawan longsor tersebut.
38 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
Gambar 4.1 Hasil Peta Rawan Longsor
Gambar 4.2 Nilai Koordinat Z
39 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.3 Attribute Table Reclass dan Dissolve
Gambar 4.4 Attribute Table Parameter Tutupan Lahan
40 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.5 Attribute Table Parameter Geologi
Gambar 4.6 Attribute Table Parameter Curah Hujan
41 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.7 Hasil Scoring Parameter Slope
Gambar 4.8 Rumus Menghitung Nilai Total
42 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.9 Attribute Table Overlay I-1
Gambar 4.10 Attribute Table Overlay I-2
43 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.11 Attribute Table Overlay II-1
Gambar 4.12 Attribute Table Overlay II-2
44 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.13 Attribute Table Overlay III-1
Gambar 4.14 Attribute Table Overlay III-2
45 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.15 Attribute Table Overlay IV-1
Gambar 4.16 Attribute Table Overlay IV-2
46 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.18 Attribute Table Overlay V-1
Gambar 4.17 Attribute Table Overlay V-2
47 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.19 Attribute Table Overlay VI-1
Gambar 4.20 Attribute Table Overlay VI-2
48 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
Gambar 4.21 Attribute Table Overlay VII-1
Gambar 4. 22 Attribute Table Overlay VII-2
4.2. Pembahasan
Dengan mempertimbangkan beberapa parameter seperti curah hujan,
kemiringan, geologi, dan tutupan lahan maka ada sekitar 249 area/wilayah di
kabupaten Sleman yang berpotensi terkena bencana tanah longsor. Dengan
rincian sebagai berikut: 154 area/wilayah yang cukup rawan, 89 area/wilayah
rawan tanah longsor, dan 6 area/wilayah yang sangat rawan tanah longsor.
Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat
kemiringan lereng maka semakin rawan pula area tersebut terkena tanah
longsor. Terlebih jika tingkat curah hujan di area tersebut cukup tinggi, maka
tingkat kerawanan tanah longsor juga tentunya akan semakin tinggi.
49 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
BAB V
KESIMPULAN
Dari praktikum Peta Rawan Longsor yang telah dilaksanakan ini, maka dapat dibuat
suatu kesimpulan, yaitu:
➢ Tanah longsor merupakan suatu perpindahan material pembentuk lereng
berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material tersebut yang bergerak ke
bawah atau ke luar lereng.
➢ Tanah longsor terjadi akibat adanya gangguan kestabilan pada tanah atau
batuan penyusun lereng. Gangguan kestabilan lereng tersebut dapat dikontrol
oleh kondisi morfologi (terutama kemiringan lereng), kondisi tanah atau batuan
penyusun lereng, dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Secara umum,
bencana longsor ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor pendorong dan
faktor pemicu. Faktor pendorong itu sendiri merupakan faktor-faktor yang
mempengaruhi kondisi material, sedangkan faktor pemicu merupakan faktor
yang menyebabkan bergeraknya material tersebut.
➢ Penentuan tingkat ancaman bencana tanah longsor dilakukan dengan cara
menggabungkan pembobotan parameter kelerengan, jenis tanah dan batuan,
curah hujan, dan tutupan lahan.
50 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
TEKNIK GEOMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA
DAFTAR PUSTAKA
Aditya, T. (2010). Visualisasi Risiko Bencana di Atas Peta. Yogyakarta: Fakultas
Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada.
Anwar, A. (2012). Pemetaan Daerah Rawan Longsor Di Lahan Pertanian
Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Makassar: Universitas
Hasanuddin.
Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sleman. 2011. Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sleman 2011-2031. Bappekab Sleman : DIY.
Bayuaji, D. G., Nugraha, A. L., & Sukmono, A. (2016). Analisis penentuan zonasi
risiko bencana tanah longsor berbasis sistem informasi geografis (Studi
kasus: Kabupaten Banjarnegara). Jurnal Geodesi Undip, 5(1), 326-335.
Bencana, B. N. P. (2012). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana. Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta: Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
Destriani, N., & Pamungkas, A. (2013). Identifikasi daerah kawasan rentan tanah
longsor dalam KSN Gunung Merapi di Kabupaten Sleman. Jurnal Teknik
ITS, 2(2), C134-C138.
Effendi, A. D. (2008). Identifikasi kejadian longsor dan penentuan faktor-faktor
utama penyebabnya di Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor.
Faizana, F., Nugraha, A. L., & Yuwono, B. D. (2015). Pemetaan risiko bencana
tanah longsor Kota Semarang. Jurnal Geodesi Undip, 4(1), 223-234.
Khoiri, M., Jaelani, L. M., & Widodo, A. (2018). Landslides Hazard Mapping
Using Remote Sensing Data in Ponorogo Regency, East Java. Internet J.
Soc. Soc. Manag. Syst, 11(2), 101-110.
Purba, J. O., Subiyanto, S., & Sasmito, B. (2014). Pembuatan peta zona rawan tanah
longsor di kota Semarang dengan melakukan pembobotan
parameter. Jurnal Geodesi Undip, 3(2), 40-52.
51 | Praktikum Sistem Informasi Geografis
Anda mungkin juga menyukai
- Jurnal LandslideDokumen10 halamanJurnal LandslideUpik Upiko Fitra SalehBelum ada peringkat
- 32 31 1 SMDokumen25 halaman32 31 1 SMDaffa RizkyBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen19 halaman1 PBandiaksan131Belum ada peringkat
- Tugas Metode Penelitian GeofisikaDokumen2 halamanTugas Metode Penelitian GeofisikaDelon LaleBelum ada peringkat
- Pertanyaan SkripsiDokumen22 halamanPertanyaan SkripsiSatriya PamungkasBelum ada peringkat
- KomangDokumen9 halamanKomangAnonymous RDmtjpBelum ada peringkat
- Analisis Kawasan Potensi Rawan Longsor Kabupaten Solok Provinsi Sumatera BaratDokumen6 halamanAnalisis Kawasan Potensi Rawan Longsor Kabupaten Solok Provinsi Sumatera BaratDewifkdBelum ada peringkat
- UntitledDokumen11 halamanUntitledandro valentinoBelum ada peringkat
- Laporan Peta Bencana SIGDokumen11 halamanLaporan Peta Bencana SIGhendrikaBelum ada peringkat
- 2 PBDokumen13 halaman2 PBGathon ParenzaBelum ada peringkat
- Iswandi Umar (271-278)Dokumen8 halamanIswandi Umar (271-278)FIQIH NURMANSYAHBelum ada peringkat
- Gerakan Tanah II Lanjutan MitigasiDokumen33 halamanGerakan Tanah II Lanjutan Mitigasitaufik hidayatBelum ada peringkat
- BAB 1 - Labibah (1710503001)Dokumen13 halamanBAB 1 - Labibah (1710503001)labibah basyaibanBelum ada peringkat
- Ingkat Bahaya Banjir Di Kawasan Sub Das Masamba Kabupaten Luwu UtaraDokumen12 halamanIngkat Bahaya Banjir Di Kawasan Sub Das Masamba Kabupaten Luwu Utaralarasati.syarafinaBelum ada peringkat
- Analisis Benca AlamDokumen26 halamanAnalisis Benca AlamtheresiaBelum ada peringkat
- Upaya Mitigasi Bencana Gerakan TanahDokumen23 halamanUpaya Mitigasi Bencana Gerakan TanahNoy ManikinBelum ada peringkat
- Jurnal FixDokumen10 halamanJurnal Fixandro valentinoBelum ada peringkat
- Proses Pembuatan Peta DDDTDokumen51 halamanProses Pembuatan Peta DDDTAndi BaeBelum ada peringkat
- Analisis Mitigasi Bencana LongsorDokumen8 halamanAnalisis Mitigasi Bencana LongsorDewifkdBelum ada peringkat
- Analisis Gerakan Tanah 01Dokumen10 halamanAnalisis Gerakan Tanah 01AZM ChannelBelum ada peringkat
- 288-Article Text-1518-1-10-20230321Dokumen10 halaman288-Article Text-1518-1-10-20230321Ivan SetiawanBelum ada peringkat
- Proses Pembuatan Peta DDDTDokumen51 halamanProses Pembuatan Peta DDDTNanda90% (10)
- PEMETAAN TINGKAT BAHAYA EROSI DI SUB DAS BATANG SeditANGIR DENGAN MEMAMFAATKAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFISDokumen5 halamanPEMETAAN TINGKAT BAHAYA EROSI DI SUB DAS BATANG SeditANGIR DENGAN MEMAMFAATKAN PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFISTri RistianiBelum ada peringkat
- 48 Naskah - Article JGRS 467 1 10 20211125Dokumen8 halaman48 Naskah - Article JGRS 467 1 10 20211125MOH.SUDANDIBelum ada peringkat
- Laporan Bencana BanyumasDokumen24 halamanLaporan Bencana BanyumasAditya NugrahaBelum ada peringkat
- 4 Pemetaan Daerah Rawan Longsor Dengan Metode Penginderaan Jauh Dan Operasi Berbasis Spasial TerkoreksiDokumen10 halaman4 Pemetaan Daerah Rawan Longsor Dengan Metode Penginderaan Jauh Dan Operasi Berbasis Spasial TerkoreksiEki JalaludinBelum ada peringkat
- Evi Nur cahya,+8+ARIF+RD OptDokumen11 halamanEvi Nur cahya,+8+ARIF+RD OptbayuardiyantoBelum ada peringkat
- Tanah Longsor 5Dokumen13 halamanTanah Longsor 5Kristian SimanjuntakBelum ada peringkat
- Mitigasi Tanah Longsor Berbasis MasyarakatDokumen13 halamanMitigasi Tanah Longsor Berbasis MasyarakatSENOBelum ada peringkat
- CEK PLAGIAT NEWW - Linda Elsa Wendy SilitongaDokumen55 halamanCEK PLAGIAT NEWW - Linda Elsa Wendy SilitongaSepti JohanBelum ada peringkat
- Bab 1 PendahuluanDokumen19 halamanBab 1 PendahuluanandikaBelum ada peringkat
- Tugas Paper Geologi TeknikDokumen14 halamanTugas Paper Geologi TeknikJou IndrajatiBelum ada peringkat
- Analisis Potensi Tanah Longsor Menggunakan Sistem Informasi Geografis Dan Analytical Hierarchy Process (AHP)Dokumen9 halamanAnalisis Potensi Tanah Longsor Menggunakan Sistem Informasi Geografis Dan Analytical Hierarchy Process (AHP)Ringgit Aji PamungkasBelum ada peringkat
- Analisis Tingkat Kerentanan Tanah Longsor Di Kecamatan UlujadiDokumen11 halamanAnalisis Tingkat Kerentanan Tanah Longsor Di Kecamatan Ulujadidewi rahayuBelum ada peringkat
- Kajian Bencana Geologi Di JeparaDokumen6 halamanKajian Bencana Geologi Di JeparaMarioBelum ada peringkat
- Imron Hanif Amin - 45603 - Geologi KuarterDokumen6 halamanImron Hanif Amin - 45603 - Geologi Kuarterimron hanif aminBelum ada peringkat
- Pemetaan Bencana LongsorDokumen24 halamanPemetaan Bencana LongsorIlham HabibBelum ada peringkat
- Analisa Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Di DAS Upper Brantas Menggunakan Sistem Informasi Geografi Muhammad Noorwantoro 105060400111004 PDFDokumen9 halamanAnalisa Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor Di DAS Upper Brantas Menggunakan Sistem Informasi Geografi Muhammad Noorwantoro 105060400111004 PDFsegeranBelum ada peringkat
- Analisa KAwasan Rawan Bencana PDFDokumen9 halamanAnalisa KAwasan Rawan Bencana PDFsegeranBelum ada peringkat
- LongsorDokumen18 halamanLongsorSiti Asma Hanum NasutionBelum ada peringkat
- 840-File Utama Naskah-1702-1-10-20180430Dokumen12 halaman840-File Utama Naskah-1702-1-10-20180430lailBelum ada peringkat
- Metode PemetaanDokumen66 halamanMetode PemetaanFirdaus MatasinBelum ada peringkat
- JurnalDokumen8 halamanJurnalyuyuBelum ada peringkat
- Pus Littan AkDokumen20 halamanPus Littan AkReza Muhammadi0% (1)
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik Departemen Teknik Geologi Program Studi Teknik GeologiDokumen14 halamanKementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Hasanuddin Fakultas Teknik Departemen Teknik Geologi Program Studi Teknik GeologiMuhammad Rafly PratamaBelum ada peringkat
- 654 1555 1 PBDokumen7 halaman654 1555 1 PBahmdfadillah59Belum ada peringkat
- Bab 1Dokumen9 halamanBab 1Sariati FathiyaBelum ada peringkat
- Analisis Multi-Skenario Dampak Tsunami DDokumen10 halamanAnalisis Multi-Skenario Dampak Tsunami DTimotius NugrohoBelum ada peringkat
- Upaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Selorejo Kabupaten BlitarDokumen7 halamanUpaya Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Selorejo Kabupaten BlitarLyric nabilaBelum ada peringkat
- PROPOSAL TUGAS AKHIR - Reinof Razzaqi YusyaDokumen14 halamanPROPOSAL TUGAS AKHIR - Reinof Razzaqi YusyareinofBelum ada peringkat
- Laporan UAS Mitigasi BencanaDokumen19 halamanLaporan UAS Mitigasi BencanaIlyas Fajar ZBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen15 halaman1 PBREZA DANI RYANDA S1 Teknik SipilBelum ada peringkat
- Rahajeng Shantika L. P. - Tugas MPA 1Dokumen14 halamanRahajeng Shantika L. P. - Tugas MPA 1Lintang AjengBelum ada peringkat
- Pemetaan Tingkat Bahaya Erosi Menggunakan ModelDokumen12 halamanPemetaan Tingkat Bahaya Erosi Menggunakan ModelAlfin Adi BaskoroBelum ada peringkat
- Laporan VegetasiDokumen46 halamanLaporan Vegetasitiara aurariaBelum ada peringkat
- BAB I Laporan SigDokumen5 halamanBAB I Laporan SigFREDY PALINGGIBelum ada peringkat
- Kebencanaan - MAN 9 JAKARTADokumen7 halamanKebencanaan - MAN 9 JAKARTAAdit DlyBelum ada peringkat