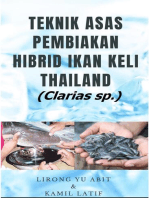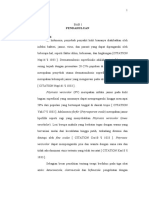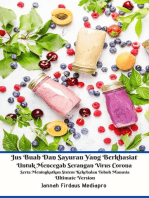1 Kunyit
1 Kunyit
Diunggah oleh
Merry ApriyaniJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
1 Kunyit
1 Kunyit
Diunggah oleh
Merry ApriyaniHak Cipta:
Format Tersedia
PELUANG PENINGKATAN KADAR KURKUMIN PADA TANAMAN KUNYIT DAN TEMULAWAK
Natalini Nova Kristina, Rita Noveriza, Siti Fatimah Syahid dan Molide Rizal Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik ABSTRAK
Produksi kurkumin menggunakan teknik budidaya secara konvensional dianggap memerlukan waktu yang sangat panjang mulai dari tanam, panen sampai proses menghasilkan simplisia/bahan aktif. Pemanfaatan bioteknologi tepatnya kultur kalus diharapkan dapat membantu mengatasi hal ini, karena dengan didapatkannya metode perbanyakan kalus, akan terbuka jalan untuk memproduksi kurkumin secara massal. Untuk meningkatkan produksi kalus dapat digunakan zat pengatur tumbuh, dan untuk meningkatkan bahan aktif (kurkumin) pada kalus dapat digunakan agen seleksi filtrat atau elisitor. Dengan teknik kultur kalus ataupun kultur suspensi dan penerapan agen seleksi filtrat atau elisitor diharapkan akan terbentuk kalus dengan kadar kurkumin tinggi sehingga dapat diproduksi dalam skala industri. Kurkumin yang terdapat pada tanaman temu-temuan, terutama kunyit dan temulawak, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti Tamiflu (antibiotik untuk penyakit flu burung). Tamiflu dinyatakan kurang efektif dalam mengatasi penyakit ini dan saat ini penyakit flu burung semakin merebak, korban terus berjatuhan. Kondisi ini merupakan tantangan bagi dunia penelitian khususnya pertanian untuk segera menghasilkan bahan tanaman yang dapat diformulasikan menjadi produk untuk meningkatkan sistim imunitas tubuh manusia. Produksi massal kurkumin dengan teknologi induksi kalus secara kultur jaringan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.
Kata kunci : kunyit, temu lawak, kurkumin, Tamiflu
PENDAHULUAN Kurkumin merupakan salah satu produk senyawa metabolit sekunder dari tanaman Zingiberaceae, khususnya
kunyit dan temulawak. Yang telah dimanfaatkan dalam industri farmasi, makanan, parfum, dan lain-lain. Ada banyak data dan literatur yang menunjukkan bahwa kunyit dan temulawak berpotensi besar dalam aktifitas farmakologi yaitu anti imflamatori, anti imunodefisiensi, anti virus (virus flu burung), anti bakteri, anti jamur, anti oksidan, anti karsinogenik dan anti infeksi (Joe et al., 2004; Chattopadhyay et al., 2004; Araujo dan Leon, 2001). Senyawa kurkumin ini, seperti juga senyawa kimia lain seperti antibiotik, alkaloid, steroid, minyak atsiri, resin, fenol dan lain-lain merupakan hasil metabolit sekunder suatu tanaman (Indrayanto, 1987). Tanaman obat dan aromatik dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder bernilai ekonomi tinggi, seperti vinblastina/vinkristina pada tanaman tapak dara (Vinca rosea), ajmalisina, digitalis (Dioscorea sp), kinina pada tanaman kina (Cinchoa sp.), kodeina, yasmin pada tanaman melati (Jasminum sambac), piretrin pada tanaman Piretrum (Pyrethrum pelargonium) dan spearmint pada tanaman mentha (Mentha sp.) (Harris, 1989). Dalam kenyataannya, produksi kurkumin untuk pabrik-pabrik industri sangat dipengaruhi oleh keberadaan dan pertumbuhan tanaman di lapang yang ditentukan oleh berbagai faktor lingkungan seperti tanah, nutrisi, iklim
serta hama dan penyakit. Salah satu upaya untuk menghasilkan kurkumin dengan jumlah yang banyak adalah dengan teknologi kultur jaringan seperti kultur kalus. Ada peluang untuk meningkatkan kadar kurkumin dalam kultur kalus tanaman kunyit dan temulawak dengan in duksi elisitor. Dilain pihak, masyarakat dunia membutuhkan kurkumin untuk obat flu burung sebagai pengganti Tamiflu. Tetapi Tamiflu terbukti tidak efektif pada suatu kasus di Vietnam dan menjadi tidak berguna selain karena mahal juga terjadi resistensi akibat sebuah mutasi yang sederhana. Tulisan ini menguraikan peluang penerapan bioteknologi tepatnya kultur kalus dengan menggunakan zat tumbuh dan elisitor sebagai bahan untuk meningkatkan produksi kurkumin pada tanaman temulawak dan kunyit yang nanti akan digunakan sebagai bahan baku obat flu burung sebagai pengganti Tamiflu. KANDUNGAN KURKUMIN DAN MANFAATNYA SEBAGAI PENGGANTI TAMIFLU Kurkuminoid adalah kelompok senyawa fenolik yang terkandung dalam rimpang tanaman famili Zingiberaceae antara lain : Curcuma longa syn. Curcuma domestica (kunyit) dan Curcuma xanthorhiza (temulawak). Kurkuminoid bermanfaat untuk mencegah timbulnya infeksi berbagai penyakit. Kandungan utama dari kurkuminoid adalah kurkumin yang berwarna kuning. Kandungan kurkumin di dalam kunyit berkisar 3 4% (Joe et al.,
2004; Eigner dan Schulz, 1999). Tiga varietas unggul kunyit yang telah dilepas Balittro memiliki kadar kurkumin cukup tinggi yaitu 8,7%. Kurkumin (C2H20O6) atau diferuloyl methane (Gambar 1) pertama kali diisolasi pada tahun 1815. Kemudian tahun 1910, kurkumin didapatkan berbentuk kristal dan bisa dilarutkan tahun 1913. Kurkumin tidak dapat larut dalam air, tetapi larut dalam etanol dan aceton (Joe et al., 2004; Chattopadhyay et al., 2004; Araujo dan Leon, 2001).
Gambar 1. Struktur kimia kurkumin Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa kurkumin aman dan tidak toksik bila dikonsumsi oleh manusia. Jumlah kurkumin yang aman dikonsumsi oleh manusia adalah 100 mg/ hari sedangkan untuk tikus 5 g/hari (Commandeur dan Vermeulen, 1996). Adapun data standar kadar kurkumin total pada rimpang kunyit tertera pada Tabel 1. Tamiflu adalah salah satu jenis antibiotik yang digunakan untuk mengatasi penyakit flu burung merupakan neuraminidase inhibitor sebuah enzim pada membran virus yang memotong partikel virus yang menyebabkan sel membran terinfeksi, sehingga virus tidak dapat berkembang biak di dalam sel atau tubuh manusia yang sudah terinfeksi virus tersebut.
Tabel 1. Hasil standarisasi kadar kurkuminoid total dari berbagai bentuk sampel umur dan asal rimpang kunyit No II Bentuk sampel/umur/asal Kunyit segar * Muda (8 bulan) eks Limbangan * Tua (11 bulan) eks Limbangan Kunyit Kering * Muda (8 bulan) eks Limbangan * Tua (11 bulan) eks Limbangan Ekstrak pekat * Eks. Produksi RG 530 A3 (SC = 21.32% b/b) * Eks Risbang RG 610 A (SC = 23.00% b/b) Sediaan jadi Alternatif formula-1 Sediaan 1 Sediaan - 2 Kisaran (% B/B) Kadar kurkuminoid Rata-rata
4,323 5,463 5,627 6,648 5,423 5,811 7,799 8,452 7,584 8,484 7,133 9,707 0,158 0,203 0,081 0,106 0,100 0,115
5,012 0,374 6,108 0,358 5,609 0,110 8,107 0,186 7,932 0,248 7,936 0,940
III
IIII
IV
0,180 0,017 0,93 0,009 0,108 0,005
Sumber : Komarawinata, 2006 (Diolah)
Dari beberapa eksperimen dinyatakan bahwa bahan obat alami seperti kurkumin, EGCG dan beberapa suplemen bisa digunakan sebagai pengganti Tamiflu untuk mengatasi infeksi virus Avian Influenza (AI). Menurut drh. CA Nidom MS, staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan yang juga Ketua Tropical Disease Diagnostic Center, Universitas Airlangga, kurkumin yang terdapat pada kunyit dan temulawak dapat berfungsi sebagai antisitokin. Seperti diketahui, bila seseorang terinfeksi virus Avian Influenza (AI) atau flu burung maka kadar sitokin dalam tubuhnya akan naik. Kenaikan
ini menjadi berbahaya karena sitokin dapat menyebabkan perubahan Oksigen (O2) menjadi peroksida (H2O2) yang meracuni sel-sel paru. Peneliti lain melaporkan bahwa dalam tubuh orang yang terinfeksi virus H5N1, terjadi reaksi badai sitokin (cytokin storm) yang berarti terjadi banjir sitokin yang mengakibatkan kerusakan sel yang parah pada sel paruparu sehingga sangat membahayakan nyawa si pasien. Untuk itu, dengan adanya antisitokin, maka jumlah sitokin dalam tubuh akan ditekan sehingga produksi peroksida juga berkurang. Dengan demikian, keru-
sakan se-sel paru dapat dicegah (Kompas, 2005a). Dalam upaya mandiri mengatasi flu burung, masyarakat telah memanfaatkan kurkumin dan temu-temuan yang dikombinasikan dengan tanaman obat lainnya sebagai jamu untuk ternak unggas mereka. Di sekitar Gunung Kidul, masyarakat memberikan ramuan ramuan jamu yang terdiri dari temu lawak, kunyit putih, temu ireng, laos, jahe, daun sereh, secang, daun salam, cengkeh, arang bathok kelapa dan ginseng pada unggas dan ayam yang disekitarnya telah terserang flu burung (Silalahi, 2005). Demikian juga dengan Sumardi dari Univ. Katolik Semarang, memberikan ramuan tradisional yang terdiri dari tepung cabe jawa, ekstrak temulawak dan ekstrak temu ireng serta tepung jahe liar yang dicampur dengan madu, gula dan air pada unggas yang terserang flu burung. Wabah flu burung akan bersifat pandemik (Verkerk et al., 2006). Walaupun sampai saat sekarang, hal ini belum terjadi. SUMBER KURKUMIN ALAMI Kunyit Kunyit (Curcuma domestica Val) merupakan salah satu tanaman obat potensial penghasil kurkumin. Selain sebagai bahan baku obat dapat juga dipakai sebagai bumbu dapur dan zat pewarna alami. Rimpangnya sangat bermanfaat sebagai antikoagulan, menurunkan tekanan darah, obat cacing, obat asma, penambah darah, mengobati sakit perut, penyakit hati, karminatif, stimulan, gatal-gatal, gigitan serangga, diare, dan rematik. Kandungan utama
didalam rimpangnya terdiri dari minyak atsiri, kurkumin, resin, oleoresin, desmetoksikurkumin, dan bidesmetoksikirkumin, damar, gom, lemak, protein, kalsium, fosfor dan besi. Zat warna kurkumin dimanfaatkan sebagai pewarna untuk makanan manusia dan ternak. Kandungan kimia minyak atsiri kunyit terdiri dari artumeron, dan tumeron, tumerol, -atlanton, -kariofilen, linalol, 1,8 sineol (Rahardjo dan Rostiana, 2004). Kunyit mengandung kurkumin dengan kadar 3 - 4%, terdiri dari kurkumin I 94%, kurkumin II 6% dan kurkumin III 0,3%. Kurkumin pertama kali diisolasi tahun 1815 (Chattopadhyay et al., 2004). Hasil eksplorasi dari berbagai sentra produksi telah diperoleh sebanyak 68 aksesi kunyit. Nomor-nomor tersebut telah diseleksi produksi dan mutunya sehingga terpilih 10 nomor harapan. Kesepuluh nomor tersebut telah diuji multilokasi di tiga lokasi selama 2 kali musim tanam. Dari hasil seleksi dan uji adaptasi di berbagai lingkungan tumbuh maka diperoleh 10 nomor harapan kunyit. Sampai tahun 2006, Balittro telah melepas tiga varietas unggul kunyit, yaitu Turina 1 dengan produksi 23,78 ton/ha, kadar kurkumin 8,36%; Turina 2 dengan produksi 23,16 ton/ha, kadar kurkumin 9,95% dan Turina 3, produksi 25,05 ton/ha dengan kadar kurkumin 8,55% (Syukur et al., 2006). Umur panen agar mendapatkan produktivitas tinggi adalah saat tanaman berumur 10 - 12 bulan setelah tanam, pada kondisi tertentu tanaman dapat dibiarkan di lapang dan
dipanen pada umur 20 24 bulan setelah tanam. Temulawak Temulawak digunakan sebagai bahan baku obat, karena dapat merangsang sekresi empedu dan pankreas. Sebagai fitofarmaka, temulawak bermanfaat untuk mengobati penyakit saluran pencernaan, kelainan hati, kandung empedu, pankreas, usus halus, tekanan darah tinggi, kontraksi usus, TBC, sariawan dan dapat digunakan sebagai tonikum. Secara tradisional temulawak banyak digunakan untuk mengobati diare, disentri, wasir, bengkak karena infeksi, eksim, cacar, jerawat, sakit kuning, sembelit, kurang nafsu makan, kejang-kejang, radang lambung, kencing darah, ayan dan kurang darah. Banyaknya ragam manfaat temulawak baik untuk obat tradisional maupun fitofarmaka karena rimpangnya mengandung protein, pati, zat warna kuning kurkuminoid dan minyak atsiri. Kandungan kimia minyak atsiri antara lain : feladren, kamfer, tumerol, tolilmetilkarbinol, arkurkumen, zingiberen, kuzerenon, germakron, -tumeron serta xanthorrizol yang mempunyai limpahan tertinggi sampai 40% (Rahardjo dan Rostiana, 2004). Senyawa xanthorizol telah dipatenkan di Korea Selatan sebagai fitofarmaka untuk mengobati kanker. Balittro memiliki 10 nomor harapan temulawak yang berpotensi produksi 20 - 40 ton/ha, kadar minyak atsiri 6,2 10,6% dengan kadar kurkumin 2,0 3,3%. Panen dapat dilakukan pada umur 9 12 bulan setelah tanaman atau daun telah menguning
dan gugur. Sebagai bahan tanaman untuk bibit digunakan tanaman yang sehat berumur 12 bulan. Perbanyakan tunas secara in vitro telah berhasil dilakukan pada tanaman ini dengan menggunakan media Murashige dan Skoog (MS) yang diperkaya dengan Benzil Adenin 1,5 mg/l + Naptheline Acetic Acid 0,5 mg/l dengan rata-rata jumlah tunas 3,65 selama 8 minggu (Syahid dan Hadipoetyanti, 2002). Perbanyakan ini tidak perlu melalui fase perakaran karena pada media tersebut telah terbentuk eksplan sempurna. Dari hasil uji analisa kimia didapatkan bahwa temulawak hasil kultur in vitro ini menghasilkan kandungan kurkumin yang lebih tinggi (Syahid dan Hadipoentyanti, 2007) dibandingkan dengan kandungan kurkumin temulawak asal koleksi plasma nutfah di kebun percobaan Sukamulia yang berkisar antara 2,11 3,24% (Setiyono dan Ajijah, 2002). KENDALA PRODUKSI KURKUMIN SECARA KONVENSIONAL Kendala yang dialami dalam produksi kurkumin secara konvensional adalah rendahnya keragaman genetik yang dimiliki. Bila dibandingkan dengan negara lain seperti India misalnya, negara kita masih jauh tertinggal dalam hal plasma nutfah kunyit Balittro baru memiliki 70 aksesi (Syukur et al., 2006). Sementara itu India telah memiliki 500 600 aksesi kunyit (Prosea, 1999), sehingga seleksi untuk mendapatkan aksesi kunyit yang memiliki kadar kurkumin tinggi, guna mendukung
untuk produksi kurkumin dalam jumlah besar juga kurang optimal. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan tanaman penghasil obat dan atsiri pada umumnya adalah merupakan tanaman musiman atau tahunan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasilnya. Berbagai kendala dijumpai dalam perbanyakan temu-temuan antara lain : budidaya, pasca panen, mutu dan fluktuasi harga. Di sisi lain, desakan penduduk dan perkembangan industri yang semakin menyempitkan ketersediaan lahan-lahan pertanian. Selain itu, produksi kurkumin secara alami dari tanaman kunyit dan temulawak memerlukan tenggang waktu yang panjang sekitar 9 bulan, mulai dari pembibitan, penanaman, panen sampai dengan prosesing. Hal ini setiap tahun terus bergulir secara kontinue. Pemecahan masalah dapat ditanggulangi dengan teknik kultur jaringan tepatnya kultur kalus secara in vitro. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syahid dan Hadipoentyanti (2002), kandungan kurkumin tanaman temulawak hasil kultur in vitro, ternyata lebih tinggi dibandingkan koleksi plasma nutfah yang diperbanyak secara konvensional. Penggunaan teknik kultur jaringan jadi lebih menarik dari pada menumbuhkan di lapangan yang mempunyai banyak hambatan (Mantel dan Smith, 1983; Sudiarto et al., 1990). Perbanyakan dan pengembangan temutemuan dengan teknik kultur jaringan mulai dilirik untuk mempercepat proses dalam mengatasi berbagai kendala tersebut di atas.
Tetapi ternyata pada penerapan teknik perbanyakan secara in vitro, juga belum dapat menjawab tantangan untuk menyediakan bahan tanaman dalam jumlah besar. Sebab walaupun dapat diperbanyak dalam jumlah besar secara in vitro, tanaman tetap harus dikeluarkan dan dibudidayakan kembali di lapang dan hal ini bahkan memperpanjang periode panen karena membutuhkan waktu yang panjang agar terbentuk rimpang yang selanjutnya dijadikan simplisia guna menghasilkan kurkumin. Penerapan bioteknologi, khususnya bioreaktor atau fermentor yang dapat memperbanyak sel tanaman yang mengandung bahan aktif dalam jumlah besar diharapkan dapat dimanfaatkan untuk produksi masal kurkumin di masa mendatang. PELUANG PENINGKATAN KURKUMIN SKALA KOMERSIAL DENGAN BIOTEKNOLOGI Penerapan bioteknologi untuk memproduksi kurkumin Pemanfaatan kultur sel untuk produksi agro industri, telah lazim digunakan saat ini, dan telah dilakukan secara komersial sejak tahun 1950, seperti perbanyakan sel tembakau dan sayur-sayuran yang telah dilakukan sejak akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an di US, Canada dan Eropa. Senyawa-senyawa seperti shikonin dan saponin ginseng sudah diproduksi dalam skala industri di Jepang, sedangkan beberapa senyawa lain juga diproduksi di Eropa (Tabel 2), (Misawa, 1994).
Tabel 2. Produksi metabolit sekunder dari sel kultur tanaman No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Senyawa Shikonin Jenis tanaman Berat kering (%) Kultur Tanaman 20 1,5 27 18 1,0 15 0,036 2 11 10 10 5,4 3,8 3,4 2,3 0,05 4,5 0,3 0,3 3 0,003 2 5-10 0,01 2-4 1,2 0,2 2,0 0,8 0,001
Lithospermum erythrorhizon Ginsenoside Panax ginseng Anthaquinones Morinda citrifolia Armalicine Canharanthus roseus Rosmarinic acid Coleus blumeii Ubiquinone-10 Nicotiana tabacum Diosgenin Dioscorea detoides Benzylisoquinoline Coptis japonica alkaloid Berberine Thalictrum minor Berberine Coptis japonica Anthraquinones Galium verum Anthraquinones Galium aparine Nicotine Nicotiana tabacum Bisoclaurine Stephania cepharantha Tripdiolide Tripteryqium wilfordii
Sumber : Misawa, (1994)
Metabolit sekunder seperti kurkumin dapat dibentuk dengan cara menginduksi jaringan tanaman pada media yang mengandung zat pengatur tumbuh untuk membentuk kalus. Kalus selanjutnya diperbanyak dengan cara kultur kalus ataupun suspensi dan dapat juga menggunakan elisitor dalam fermentor atau bioreaktor, contohnya ginseng. Keberhasilan sintesa metabolit sekunder dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kendala biologis. Faktor lingkungan dapat meliputi cahaya, penggunaan zat pengatur tumbuh, prekusor, unsur hara yang tersedia, komposisi medium, perbedaan morfologi, jaringan tanaman yang digunakan dan
aktivitas biosintesa (Tabata dalam Dalimunthe, 1987). Bahan kimia atau yang lebih dikenal sekarang dengan sebutan bahan aktif dari suatu tanaman ini, dapat diperoleh dari tanaman lengkap. Tanaman berinteraksi dengan lingkungannya memproduksi metabolit sekunder yang bermacam-macam (Harborne, 1996). Beberapa dari senyawa tersebut berperan dalam aktivitas pharmakologikal, industri dan pertanian yang mana akan meningkatkan nilai tanaman secara komersial (Paganga et al., 1999; Bingham et al., 1998). Sejak penelitian kultur jaringan berkembang dengan pesat, ditemukan bahwa sel-sel dalam kultur menghasilkan juga persenyawaan-persenyawaan
yang dibutuhkan manusia dengan tingkat produksi per unit berat kering yang setara atau bahkan lebih tinggi dari tanaman asalnya. Kultur kalus telah berhasil dilakukan pada beberapa tanaman obat seperti pada tanaman solanum (Solanum khasianum dan Solanum laciniatum) yang menghasilkan solasodin untuk bahan KB, ataupun pada tanaman Mentha (Mentha piperita) untuk menghasilkan pipperint sebagai bahan mint dalam industri (Kristina, 1992) (Tabel 2). Senyawa metabolit sekunder ini dapat dihasilkan dari kultur kalus ataupun kultur suspensi sel (Furaya, 1982). Kalus berasal dari potongan organ yang telah steril dalam media yang mengandung auksin dan kadangkala sitokinin. Kalus ini adalah sel-sel parenkim yang mempunyai ikatan yang renggang dengan sel-sel lain. Kalus berupa kumpulan sel dan selalu melakukan proses dediferensiasi. Kalus atau yang dikenal dengan kultur sel ini diharapkan dapat memperbanyak dirinya menjadi massa sel yang besar secara terus-menerus. Hal lain yang menguntungkan adalah kultur sel tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan lingkungan seperti iklim, penyakit tanaman dan peningkatan produksi dapat tersedia bila dibutuhkan sewaktu-waktu. Senyawa sekunder melalui kultur jaringan dapat diisolasi dari kalus atau sel. Kandungannya dapat ditingkatkan melalui seleksi bahan tanaman atau jaringan, tingkat pertumbuhan tanaman, pemakaian zat pengatur tumbuh dan prekusor, pemakaian mutagen baik secara fisik maupun kimia serta mani-
pulasi faktor lingkungan. Kalus sebagai bahan senyawa sekunder dan produk lainnya dapat dipacu pembentukan dan pertumbuhannya dengan pemakaian zat pengatur tumbuh 2,4-D, NAA dan sering pula dikombinasikan dengan sitokinin. Adakalanya kombinasi auksin dengan sitokinin selain dapat merangsang proses pembelahan sel juga mempengaruhi kandungan senyawa sekundernya. Hasil penelitian Marshall dan Staba (1976) mendapatkan peningkatan kandungan diosgenin dengan penggunaan 2,4-D pada tanaman Dioscorea deltoidea. Pada kultur sel, harus diperhatikan bahwa masa kultur yang panjang dalam media yang tetap, akan kehabisan unsur hara dan air, karena media menguapkan air dari waktu ke waktu. Selain kehabisan hara, sel-sel dalam kalus juga mengeluarkan persenyawaan-persenyawaan hasil metabolit sekunder. Pertumbuhan kultur kalus mirip dengan grafik pertumbuhan kultur bakteri (Dodds and Roberts dalam Gunawan. 1978), sehingga dapat dibayangkan bila proses fermentor ini diterapkan maka akan dihasilkan senyawa kurkumin dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sedangkan kultur suspensi adalah kalus yang ditumbuhkan pada media cair dan kultur suspensi ini praktis digunakan untuk produksi bahan-bahan sekunder. Dalam kultur suspensi sel dikenal dua kelompok kultur yakni kultur batch dan continuous. Dalam kultur batch, media hara dan volume tetap, tetapi konsentrasi hara berubah sesuai dengan pertumbuhan sel. pada masa
inkubasi terjadi pertambahan biomass yang mengikuti pola sigmoid. Setelah mecapai suatu masa tertentu sel berhenti membelah. Oleh karena itu kultur batch harus selalu diperbaharui. Sementara kultur continuous merupakan kultur sel jangka panjang dengan suplai hara yang konstan dalam wadah yang besar. Dalam kultur ini terdapat sistem untuk sirkulasi mengeluarkan media lama dan ditambah dengan media baru. Dalam kultur sel continuous terdapat dua tipe, yaitu tipe tertutup (close type) dan tipe terbuka (open type). Dalam tipe tertutup sel bertambah terus tanpa dipanen, hanya media yang disirkulasi. Sedangkan pada tipe terbuka, penambahan media baru disertai juga dengan panen sel dan media. Tipe kultur continuous yang terbuka dapat menggunakan chemostat atau turbidostat. Chemostat menggunakan standard konsentrasi bahan-bahan kimia tertentu yang mengatur laju pertumbuhan, misalnya konsentrasi N, P atau glukosa. Persenyawaan N, P atau glukosa diatur sedemikian rupa pada suatu level yang tetap untuk mengatur populasi sel yang tertentu. Pada kultur continuous dengan turbidostat, diatur jumlah sel tertentu, yang diatur dengan turbiditas. Kerapatan biomass yang melebihi turbiditas yang sudah ditentukan, akan dikeluarkan. Untuk tujuan komersial telah dilakukan pengembangan produksi metabolit sekunder tanaman obat dengan sistem bioreaktor. Sistem bioreaktor ini dapat digunakan untuk kultur embrionik ataupun organogenik dari berbagai
spesies tanaman (Levin et al., 1988; Preil et al., 1988). Dari salah satu hasil percobaan yang menggunakan sistem bioreaktor ini dapat dihasilkan saponin sebesar 500 mg/l/hari dari bioreaktor kultur jaringan akar ginseng (Park et al., 1992) dan produksi alkaloid ginsenoside dari kultur akar Panax ginseng dengan sistem bioreaktor berskala besar 1 10 ton (Hahn et al., 2003). Teknik kultivasi bioreaktor ini juga telah berhasil dilakukan untuk memproduksi zat anti kanker dari beberapa spesies Taxus dengan caracara konvensional dimana untuk mendapatkan 1 kg komponen aktif taxol harus menebang 1 pohon Taxus yang kira-kira telah berumur 100 tahun (Muhlbah, 1998). Sementara itu perbanyakan kunyit secara in vitro dapat juga dilakukan dengan menggunakan media Murashige dan Skoog yang diperkaya dengan Benzil Adenin 2 mg/l dan bahkan dari hasil penyimpanan pada media pertumbuhan minimal yang menggunakan manitol 1%, tunas masih mampu beregenerasi secara normal dengan rata-rata jumlah tunas 4,2 (Syahid, 2004). Peningkatan produksi bahan aktif kurkumin dengan elisitor Peningkatan produksi kalus akan semakin cepat bila menggunakan agen seleksi filtrat. Agen seleksi filtrat adalah gen-gen jasad renik atau bagian dari gen-gen jasad renik yang mampu menampung gen asing yang ditumpangkan pada struktur jasad renik tersebut dan ditransplantasikan ke sel-sel yang
harapkan mampu mengubah sifat-sifat sel. Seleksi in vitro untuk mendapatkan kalus kunyit yang mengandung kurkumin tinggi dapat dilakukan dengan menggunakan agen seleksi filtrat atau elisitor yang ditambahkan ke dalam media tumbuh. Teknik ini sudah diterapkan pada beberapa tanaman budidaya dan berhasil memperoleh varian baru yang tahan terhadap OPT. Jamur Colletotrichum lagenarum dapat menginduksi sintesa saponin (ginsengosides) pada sel kultur ginseng (Xiaojie et al., 2005). Atau Aspergillus niger menginduksi produksi hypericin pada kultur suspensi sel Hypericum perforatum (Xu et al., 2005). KESIMPULAN Peluang pengembangan bahan aktif kurkumin dari tanaman kunyit dan temulawak untuk mengatasi flu burung dapat dilakukan dengan teknik kultur jaringan yang menghasilkan kalus. Strategi untuk meningkatkan kandungan kurkumin dalam kalus dapat diberikan elisator, sehingga peluang untuk menghasilkan kurkumin dengan teknik biofermentor untuk skala industri dapat dilakukan. SARAN Penelitian ini perlu dilanjutkan untuk mendapatkan teknik untuk meningkatkan kurkumin pada kalus tanaman kunyit hasil kultur jaringan.
UCAPAN TERIMA KASIH Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ireng Darwati yang telah banyak memberi saran dalam perbaikan tulisan ini. DAFTAR PUSTAKA Araujo, C.A.C and L.L. Leon, 2001. Biological activities of Curcuma longa L. Mem. Inst. Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro 96 (5) : 723 - 728. Byron, J.R., 2006. H5N1 Avian flu virus therapy. Conventional and Herbal Options : Jrb at med-owl dot com. Version 2, February, 2006. Chattopadhyay, I., Biswas, K., Bandyopadhyay, U. and Banerjee, R.K., 2004. Tumeric and Curcumin : Biological actions ans medicinal applications. Current Science. 87 (1) : 44 - 53. Commandeur, J.N. and N.P. Vermeulen, 1996. Cytotoxicity and cytoprotective activities of natural compounds. The case of curcumin. Xenobiotica 26 : 667 - 680. Dalimonthe, S.L, 1987. Kultur jaringan sebagai sarana untuk menghasilkan metabolit sekunder. Dalam Buku Risalah Seminar Nasional Metabolit Sekunder. 1987. (Ed) Suwijiyo Pramono, D. Gunawan dan C.J. Soegihardjo, 6-9 September, Yogyakarta. PAU Bioteknologi UGM. hal. 157 162.
10
Eigner, D. And D. Schulz, 1999. Ferula asa-foetida and Curcuma longa in traditional medical treatment and diet in Nepal. J. Ethnopharmacol 67 : 1 - 6. Furaya, T., 1982. Production of pharmacologically active principles in plant tissue culture. Proc. 5th Intl. Cong. Plant Tissue and Cell Culture. Plant Tissue Culture. 269-272. Harborne, J. B., 1996. Recent advance in chemical ecology. Natural Product Reports 12 : 83 - 98. Haris, R., 1989. Tanaman Minyak Atsiri. Penebar Swadaya, Jakarta. 172 hal. IIndrayanto, G., 1987. Produksi metabolit sekunder dengan teknik kultur jaringan. Dalam buku Risalah Seminar Nasional Metabolit Sekunder 1987. (Ed.) Suwijiyo Pramono, D. Gunawan dan C.J. Soegiarto. 6-9 September. Yogyakarta. PAU Bioteknologi UGM. hal. 32 44. Joe, B.; M. Vijaykumar and B.R. Lokesh, 2004.Biological properties of curcumin-cellular and molecular mechanisms of action. Critical Review in Food Science and Nutrition 44 (2) : 97 - 112. Komarawinata, D., 2006. Budidaya dan pasca panen tanaman obat untuk meningkatkan kadar bahan aktif. Makalah pada Seminar Status Teknologi Tanaman Obat dan Aromatik. 13 Desember 2006. 8 hal. Kristina, N.N., 1992. Produksi metabolit sekunder melalui kultur in
vitro. Medkom Puslitbangtri. hal. 18 22. Levin, R., V. Gaba; B. Tal; S. Hirsch; D. De Nola; K. Vasil, 1988. Automatic plant tissue culture for max propagation. Biotechnology. 6 : 1035 - 1040. Marshall, J.O.G. and E.J. Staba, 1976. Hormonal effect on diosgenin biosynthesis and growth in Dioscorea deltoidea tissue culture Phytochem 15 : 53 - 55. Mantell, SH & H. Smith, 1983. Cultural factors that influensce secondary metabolite accumulations in plant cel and tissue culture. In : S.H. Mantell and Smith (eds.) Plant Biotechnology cambridge. Univ. Press. London. p. 75 - 108. Misawa, M., 1994. Plant tissue culture: An alternative for production of useful metabolite. FAO Agricultural services Bulletin. No. 108. Toronto-Canada. Paganga, G., N. Miller and C.A. Rice Evans, 1999. The polyphenolic content of fruit and vegetables and their anti-oxidant activities. What does a serving constitue? Free Redic. Research 30 : 153 - 162. Preil, W.; P. Florek; V. Wix, A. Beck, 1988. Toward mass propagation by use of bioreactors. Acta Horticult. 226 : 99 - 105. Park, J.M. and S.Y. Yoon, 1992. Production of sunguinarine by suspension culture of Papaver somni-
11
ferum in bioreactor. J. Ferm. Bioeng. 74 : 292 - 296. Prosea, 1999. Plant Resources of South East Asia. No. 12 (1). Medicinal and poisonous plants 1. Ed. de Padua, L.S., Bunyapraphatsara, N., and Lemmens, R.H.M.J. p. 215 216. Rahardjo, M. dan O. Rostiana, 2004. Standar prosedur Operasional Budidaya Kunyit dalam Standar Prosedur Operasional Jahe, Kencur, Kunyit dan Temulawak. Badan Litbang Pertanian. Balittro-Bogor. 46 hal. Setiyono, R.T dan N. Ajijah, 2002. Evaluasi beberapa sifat agronomi plasma nutfah temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb.). Buletin Littro XIII (2) : 7 - 12. Sudiarto, Emmyzar, S.M. Rosita, O. Rostiana, S. Affandi dan D. Sitepu, 1990. Hasil penelitian dan pengembangan tanaman obat. Dalam : Tanaman Obat (Buku VI). Seri Pengembangan No. 12. Prosiding Simposium I Hasil Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri. hal. 813 829. Syahid, S.F., 2004. Konservasi kunyit (Curcuma domestica Vahl.) melalui pertumbuhan minimal. Prosiding Simposium IV Hasil Penelitian Tanaman Perkebunan. Bogor 28 - 30 September 2004. hal. 231 236. Syahid, S.F. dan E. Hadipoentyanti, 2002. Pengaruh zat pengatur tumbuh Benzyl Adenin (BA) dan
NAA terhadap pertumbuhan temulawak (Curcuma xanthorrhiza Roxb). Buletin Penelitian Tanaman Rempah dan Obat. XIII (2): 1 - 6. Syahid, S.F. dan E. Hadipoentyanti, 2007. Respon temulawak hasil rimpang kultur in vitro genersi kedua terhadap pemupukan. Jurnal Puslitbangbun (Proses Editing). Syukur, Ch.. L. Udarno, Supriadi, O. Rostiana &. S.F. Syahid, 2006. Usulan pelepasan varietas kunyit. Balittro-Puslitbangbun. 25 hal. Verkerk, R.; D. Downing; J. Meldrum and S. Hickey, 2006. The pivotal role for natural products in countering an avian influenza pandemic. Alliance for Natural Health. p. 63. Wasito, R., 2005. Malaikat pencabut nyawa itu ternyata lalat. Harian Suara Pembaharuan. Rabu, 21 September 2005. Xiaojie, X; H. Xiangyang; S. J. Neill; F. Jianying and C. Weining, 2005. Fungal elicitor induce singlet oxygen generation, ethylene release and saponin synthesis in cultured cells of Panax ginseng. C.A. Meyer. Plant Cell Physiol. 46 (6) : 947 - 954. Zhou, L.G. and J.Y.Wu, 2006. Development and application of medicinal plant tissue cultures for production of drugs and herbal medicinals in China. Nat. Pro. Rep. 23 : 789 810.
12
Anda mungkin juga menyukai
- Teknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Dari EverandTeknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- 1kunyit 131209222604 Phpapp02 With Cover Page v2Dokumen13 halaman1kunyit 131209222604 Phpapp02 With Cover Page v2Wegen von lizbethBelum ada peringkat
- TemulawakDokumen10 halamanTemulawakselvia purwantiBelum ada peringkat
- KunyitDokumen16 halamanKunyitDhevi DwiBelum ada peringkat
- Tugas Ioat TemulawakDokumen5 halamanTugas Ioat Temulawaknindya valyaBelum ada peringkat
- Review JurnalDokumen4 halamanReview JurnalAndi nurfaidahBelum ada peringkat
- MikrobiologiDokumen14 halamanMikrobiologiMusdalifa DjurumudiBelum ada peringkat
- Analisis Senyawa KurkuminDokumen10 halamanAnalisis Senyawa KurkuminYodi SetiawanBelum ada peringkat
- Resume Kelompok 4Dokumen6 halamanResume Kelompok 4hildamaulinaBelum ada peringkat
- Vivi,+4 +JUNI+2022+ZulkifliDokumen6 halamanVivi,+4 +JUNI+2022+ZulkifliRULITA PUTRI MOHTARINSABelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen9 halamanBab I PendahuluanMandapakayaBelum ada peringkat
- Makalah Farindus UkotDokumen13 halamanMakalah Farindus UkotRizha ChaniagoBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan Dan Bab Ii Tinjauan Pustaka PDFDokumen20 halamanBab I Pendahuluan Dan Bab Ii Tinjauan Pustaka PDFMochammad RezaBelum ada peringkat
- FARMAKOGNOSIDokumen4 halamanFARMAKOGNOSIRahma WindsariBelum ada peringkat
- Materi Budidaya JamurDokumen13 halamanMateri Budidaya JamurAntoo JabrikBelum ada peringkat
- PROPOSAL RONAL PUTRA YUDHA (2018c) PDF.2Dokumen9 halamanPROPOSAL RONAL PUTRA YUDHA (2018c) PDF.2Hanaya FathihaBelum ada peringkat
- 2.1 Tanaman Yang Berpotensi Sebagai AntibakteriDokumen16 halaman2.1 Tanaman Yang Berpotensi Sebagai AntibakteriMarfida YantiBelum ada peringkat
- Kelompok 1 KunyitDokumen17 halamanKelompok 1 KunyitHaninahBelum ada peringkat
- Makalah KunyitDokumen32 halamanMakalah KunyitYeyendMustika CieCuwek UkeBelum ada peringkat
- Uji Aktivitas Anthelmintik Ekstrak Etanol Rimpang Pacing (Costus Speciosus (Koen.) SM.) Terhadap Cacing Tanah (Lubricus Rubellus)Dokumen23 halamanUji Aktivitas Anthelmintik Ekstrak Etanol Rimpang Pacing (Costus Speciosus (Koen.) SM.) Terhadap Cacing Tanah (Lubricus Rubellus)Andin TheShadowBelum ada peringkat
- Antelmentik PrintDokumen18 halamanAntelmentik PrintTaufik PrabowoBelum ada peringkat
- Serasah Daun Cengkeh Yang Masih BermanfaatDokumen5 halamanSerasah Daun Cengkeh Yang Masih BermanfaatGustiAgungKrisnaBelum ada peringkat
- Fusarium SPDokumen4 halamanFusarium SPFarah DinaBelum ada peringkat
- Makalah Tentang Manfaat Dan Khasiat Serai RomanDokumen8 halamanMakalah Tentang Manfaat Dan Khasiat Serai RomanRossalina KarubabaBelum ada peringkat
- ProposalDokumen29 halamanProposalDianita Rifqia PutriBelum ada peringkat
- Pendahuluan Aktivitas AntivirusDokumen6 halamanPendahuluan Aktivitas AntivirusPinkan NeylahBelum ada peringkat
- Artikel Ilmiah - Fransiskus Devensius Seran - 1913010024 - Kelas BDokumen15 halamanArtikel Ilmiah - Fransiskus Devensius Seran - 1913010024 - Kelas Bridwan nahakBelum ada peringkat
- Studi Kandungan Kimia Dan Aktivitas Farmakologi Tanaman KunyitDokumen6 halamanStudi Kandungan Kimia Dan Aktivitas Farmakologi Tanaman KunyitnadyaBelum ada peringkat
- Pestisida Dari Daun PepayaDokumen20 halamanPestisida Dari Daun PepayaRahmat Mozchal Redokz100% (2)
- FULL PAPER HosniyahDokumen10 halamanFULL PAPER HosniyahHosniyah HsBelum ada peringkat
- Naskah Publikasi Rima M 0404052Dokumen27 halamanNaskah Publikasi Rima M 0404052Larissa Risky AmaliaBelum ada peringkat
- Makalah Reseptir BLM FixDokumen12 halamanMakalah Reseptir BLM FixAlbert Umbu Ndjandji100% (1)
- Bab IiDokumen17 halamanBab IiAyu Atikah RamadhaniBelum ada peringkat
- Penyakit Jamur Pada Tanaman Masih Merupakan Ancaman Utama Pertanian Di IndonesiaDokumen4 halamanPenyakit Jamur Pada Tanaman Masih Merupakan Ancaman Utama Pertanian Di IndonesiaFitri ansyah82Belum ada peringkat
- Bab 1,2,3Dokumen20 halamanBab 1,2,3nurtita absariBelum ada peringkat
- ID Pengaruh Tongkol Jagung Sebagai Media Pertumbuhan Alternatif Jamur Tiram Putih PDokumen4 halamanID Pengaruh Tongkol Jagung Sebagai Media Pertumbuhan Alternatif Jamur Tiram Putih PAhusaa ToramOnlineBelum ada peringkat
- DinaDokumen5 halamanDinaDina LestariBelum ada peringkat
- Makalah Semnas Bioupi Fitri-Ammi-yanti HDokumen11 halamanMakalah Semnas Bioupi Fitri-Ammi-yanti HIndria YulandaraBelum ada peringkat
- Materi Empon-EmponDokumen4 halamanMateri Empon-EmponARDYA GALUH SEKAR NIRWANA 1Belum ada peringkat
- Laporan Praktikum Aplikasi PestisidaDokumen16 halamanLaporan Praktikum Aplikasi PestisidaHendra Setiawan PangaribuanBelum ada peringkat
- Laporan Kelompok 5Dokumen20 halamanLaporan Kelompok 5Christmas SaragihBelum ada peringkat
- Bab IDokumen21 halamanBab IPiranti HandayaniBelum ada peringkat
- Tugas Terstruktur EtnoDokumen5 halamanTugas Terstruktur EtnoYogi PamungkasBelum ada peringkat
- Bab I-Iv CobaDokumen38 halamanBab I-Iv CobaFirda AuliyaBelum ada peringkat
- Makalah KunyitDokumen32 halamanMakalah KunyitFandi M BantiBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen6 halaman1 PBArum PuspitaBelum ada peringkat
- Makalah - Alfera YusianaDokumen18 halamanMakalah - Alfera YusianaalferaBelum ada peringkat
- Jurnal ParameterDokumen47 halamanJurnal Parameteralifa mahesaBelum ada peringkat
- Identifikasi KunyitDokumen3 halamanIdentifikasi Kunyitfahri_amirullahBelum ada peringkat
- Klasifikasi KunyitDokumen20 halamanKlasifikasi KunyitNurul PaujiahBelum ada peringkat
- Hendrina R Parera 18330114 METOPEN CDokumen11 halamanHendrina R Parera 18330114 METOPEN CiinBelum ada peringkat
- 7130 - Laporan FitofarDokumen17 halaman7130 - Laporan FitofarUyunkchayunkciunkcacunkacunk Papararadiditatapradipta MamacicireverzmaciverzBelum ada peringkat
- 1 PB PDFDokumen6 halaman1 PB PDFANDYBelum ada peringkat
- Temu PutihDokumen6 halamanTemu PutihSubuhWahyuBelum ada peringkat
- Jurnal Uji EfektivitasDokumen14 halamanJurnal Uji EfektivitasTalithaRahmaNathaniaBelum ada peringkat
- Tugas Teknik Pengendalian GulmaDokumen5 halamanTugas Teknik Pengendalian GulmaBarth MakalBelum ada peringkat
- Tumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Dari EverandTumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Belum ada peringkat
- Tanaman Pepohonan Anti Hama Untuk Melindungi Padi (Oryza Sativa) Dari Berbagai Jenis Serangan Hama Penyakit Versi Bahasa IndonesiaDari EverandTanaman Pepohonan Anti Hama Untuk Melindungi Padi (Oryza Sativa) Dari Berbagai Jenis Serangan Hama Penyakit Versi Bahasa IndonesiaBelum ada peringkat
- Jus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh ManusiaDari EverandJus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh ManusiaBelum ada peringkat
- Jus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Ultimate VersionDari EverandJus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Ultimate VersionBelum ada peringkat