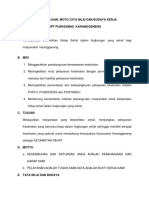Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di RS Bab 3 PDF
Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di RS Bab 3 PDF
Diunggah oleh
PranataHak Cipta:
Format Tersedia
Anda mungkin juga menyukai
- SAP Ibu Hamil Dengan Resiko TinggiDokumen4 halamanSAP Ibu Hamil Dengan Resiko TinggiRahajeng TiaBelum ada peringkat
- Alogaritma Persalinan Kompleks - Rofidah Aziz - 152191222Dokumen14 halamanAlogaritma Persalinan Kompleks - Rofidah Aziz - 152191222Rofidah azizBelum ada peringkat
- Kak Pelepasan Implant - OkDokumen3 halamanKak Pelepasan Implant - OkDian EkasariBelum ada peringkat
- Laporan Surveilans Kelompok SukabumiDokumen26 halamanLaporan Surveilans Kelompok SukabumiDhimas MuhammadBelum ada peringkat
- Makalah KP ASI YULImakalah KP AsiDokumen24 halamanMakalah KP ASI YULImakalah KP AsiAbdul AnasBelum ada peringkat
- Laporan Asuhan Kebidanan Pemberdayaan KeluargaDokumen138 halamanLaporan Asuhan Kebidanan Pemberdayaan Keluargaherysutanto.p07134322072Belum ada peringkat
- Makalah Pemberdayaan KeluargaDokumen11 halamanMakalah Pemberdayaan KeluargaHabibiBelum ada peringkat
- Uas Manajemen Pelayanan KebidananDokumen5 halamanUas Manajemen Pelayanan KebidananEchi Desnawati100% (1)
- Kewirausahaan KebidananDokumen26 halamanKewirausahaan KebidananNURUL ROMADHONBelum ada peringkat
- Manajemen LaktasiDokumen30 halamanManajemen LaktasiDewi MasithohBelum ada peringkat
- LP PrakonsepsiDokumen21 halamanLP Prakonsepsikania ambarwatiBelum ada peringkat
- BAB 1 Konseling KBDokumen18 halamanBAB 1 Konseling KBRiniez Scatzy Ciimenirr YPasBelum ada peringkat
- Konsep Keluarga GrandisnaDokumen15 halamanKonsep Keluarga GrandisnaGrandis AzhariBelum ada peringkat
- KAK Deteksi Dini Tumbang Di PosyanduDokumen4 halamanKAK Deteksi Dini Tumbang Di Posyanduirwan100% (1)
- Tugas Makalah Asuhan Kebidanan Pada Ibu NifasDokumen13 halamanTugas Makalah Asuhan Kebidanan Pada Ibu NifasNurFitryaBelum ada peringkat
- Panduan KDPKDokumen23 halamanPanduan KDPKmutmainnahBelum ada peringkat
- Bu Emi - Webinar Nasional Hut Ibi KalselDokumen37 halamanBu Emi - Webinar Nasional Hut Ibi KalselWenda JjeBelum ada peringkat
- Polindes, Poskesdes FixDokumen45 halamanPolindes, Poskesdes FixFicky A. PutriBelum ada peringkat
- KELUARGA BINAAN Tn. M DESA RAWADokumen44 halamanKELUARGA BINAAN Tn. M DESA RAWACut Melinda UfrhaBelum ada peringkat
- Notulen Evaluasi Pendataan Bayi & UCIDokumen3 halamanNotulen Evaluasi Pendataan Bayi & UCIErlina JuwitaBelum ada peringkat
- Efektifitas Pijat PayudaraDokumen7 halamanEfektifitas Pijat PayudaraDwi Fitriyana PutriBelum ada peringkat
- SAP Imunisasi DPTDokumen7 halamanSAP Imunisasi DPTIke Gusiswanti0% (1)
- Materi Lembar Balik PenyuluhanDokumen41 halamanMateri Lembar Balik PenyuluhanHidayatAsikinBelum ada peringkat
- Visi Misi Terbaru Puskesmas 2017Dokumen3 halamanVisi Misi Terbaru Puskesmas 2017Risky Novitasari50% (2)
- Klimaterium Dan MenopauseDokumen30 halamanKlimaterium Dan Menopausefary arianBelum ada peringkat
- Doula ServiceDokumen19 halamanDoula Servicefitri pitasariBelum ada peringkat
- Sap MowDokumen9 halamanSap MowAriska AyuBelum ada peringkat
- Prinsip Gizi Untuk Ibu HamilDokumen3 halamanPrinsip Gizi Untuk Ibu Hamilmashlachatul mar'ahBelum ada peringkat
- Askeb KSPRDokumen7 halamanAskeb KSPRwidyanenoBelum ada peringkat
- Rps PELAYANAN-KBDokumen10 halamanRps PELAYANAN-KBhaeraniBelum ada peringkat
- Sop Asuhan Prsalinan NormalDokumen6 halamanSop Asuhan Prsalinan NormalFara FajrinaBelum ada peringkat
- Struktur Organisasi Kelas Ibu Hamil Dan Kelas Ibu BalitaDokumen1 halamanStruktur Organisasi Kelas Ibu Hamil Dan Kelas Ibu Balitadede rusiahBelum ada peringkat
- Kelompok PendukungDokumen11 halamanKelompok Pendukunglailatulmursida87100% (1)
- Penatalaksanaan Konseling CatenDokumen1 halamanPenatalaksanaan Konseling CatenRisa Tikdia SetyowatiBelum ada peringkat
- Information Sheet Kelas Ibu Hamil PDFDokumen2 halamanInformation Sheet Kelas Ibu Hamil PDFArya Adalah KodokBelum ada peringkat
- ImplantDokumen50 halamanImplantNurul SukronBelum ada peringkat
- Sap KB Post PartumDokumen11 halamanSap KB Post PartumTantri Yunita RatnaBelum ada peringkat
- Konseling Pada Ibu MelahirkanDokumen2 halamanKonseling Pada Ibu MelahirkanNova ElviraBelum ada peringkat
- Laporan BBL KasusDokumen13 halamanLaporan BBL KasusAnindyta DewiBelum ada peringkat
- Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Cakupan Persalinan Oleh Bidan Di Desa KTI KEBIDANANDokumen5 halamanFaktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Cakupan Persalinan Oleh Bidan Di Desa KTI KEBIDANANhaidar rzBelum ada peringkat
- Makalah Pasangan Usia SuburDokumen11 halamanMakalah Pasangan Usia Suburisvara100% (1)
- Ilmu Kesehatan AnakDokumen20 halamanIlmu Kesehatan Anakrischi trysia100% (1)
- Panduan Program KiaDokumen10 halamanPanduan Program KiaWarniningsih MulyadiBelum ada peringkat
- Pengaruh Pijat Oksitosin Oleh Suami Terhadap Produksi ASI Dan Kadar Hormon Prolaktin Pada Ibu NifasDokumen22 halamanPengaruh Pijat Oksitosin Oleh Suami Terhadap Produksi ASI Dan Kadar Hormon Prolaktin Pada Ibu NifasmarianaBelum ada peringkat
- Makalah Askeb Nifas-Critical ThinkingDokumen21 halamanMakalah Askeb Nifas-Critical ThinkingPratama RzBelum ada peringkat
- Pleno MGG 5 Kel 5Dokumen22 halamanPleno MGG 5 Kel 5asri rahmayelitaBelum ada peringkat
- Pengertian ImplanDokumen19 halamanPengertian ImplanLili ErnidaBelum ada peringkat
- Pedoman Cinta HatiDokumen33 halamanPedoman Cinta HatiVeny Anggriani100% (1)
- Prinsip Dasar Dalam Mengembangkan UsahaDokumen3 halamanPrinsip Dasar Dalam Mengembangkan UsahaliaBelum ada peringkat
- LP REMAJA - Kasus AnemiaDokumen30 halamanLP REMAJA - Kasus AnemiaErfin RistianiBelum ada peringkat
- Evidence Based Masa Nifas - Mirza Aulia Cahyani - P17321183028Dokumen13 halamanEvidence Based Masa Nifas - Mirza Aulia Cahyani - P17321183028mirzaBelum ada peringkat
- LEAFLET Tanda Bahaya KehamilanDokumen2 halamanLEAFLET Tanda Bahaya KehamilanRia Aryanti Putri IIBelum ada peringkat
- Leaflet MAkanan Bergizi Untuk Ibu Hamil Dan MenyusuiDokumen2 halamanLeaflet MAkanan Bergizi Untuk Ibu Hamil Dan MenyusuiDearniBelum ada peringkat
- Leflet Tanda Bahaya BBLDokumen4 halamanLeflet Tanda Bahaya BBLfitri siregarBelum ada peringkat
- Makalah Stase 6Dokumen29 halamanMakalah Stase 6DEWI SITI NURJANAH100% (1)
- JURNAL KB - JKN RENI, (Juni 2022)Dokumen7 halamanJURNAL KB - JKN RENI, (Juni 2022)Reni SaswitaBelum ada peringkat
- Ceklist Rekom BidanDokumen4 halamanCeklist Rekom Bidanretno wahyuBelum ada peringkat
- Bidan Praktek Mandiri Asri ArsiniDokumen7 halamanBidan Praktek Mandiri Asri ArsiniDeppy DisketBelum ada peringkat
- Tuli Kongenital Pada Bayi Dan AnakDokumen16 halamanTuli Kongenital Pada Bayi Dan AnakpuspamitandaBelum ada peringkat
- Pemasangan Alat Bantu Dengar Pada AnakDokumen24 halamanPemasangan Alat Bantu Dengar Pada AnakjelitaBelum ada peringkat
Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di RS Bab 3 PDF
Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di RS Bab 3 PDF
Diunggah oleh
PranataJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di RS Bab 3 PDF
Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di RS Bab 3 PDF
Diunggah oleh
PranataHak Cipta:
Format Tersedia
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
BAB III
SKRINING BAYI BARU LAHIR
A. Deteksi Dini Gangguan Pendengaran Pada Bayi Baru Lahir
1. Gejala gangguan pendengaran pada bayi dan anak
Gejala gangguan pendengaran pada bayi sulit diketahui mengingat
ketulian tidak terlihat. Biasanya keluhan orangtua adalah bayi tidak memberi
respons terhadap bunyi. Umumnya orangtua melaporkan sebagai terlambat
bicara (delayed speech), tidak memberi respons saat dipanggil atau ada
suara/bunyi. Dapat pula sebagai keluhan perkembangan kosakata yang tidak
sesuai dengan usia anak, berbicara tidak jelas, atau meminta sesuatu dengan
isyarat.
Gangguan pendengaran dibedakan menjadi :
- tuli sebagian (hearing impaired) yaitu penurunan fungs pendengaran tetapi
masih bisa berkomunikasi dengan atau tanpa alat bantu dengar;
- tuli total (deaf) adalah gangguan fungs pendengaran yang sedemikian
terganggu sehingga tidak dapat berkomunikasi sekalipun mendapat
pengerasan bunyi.
2. Perkembangan sistem pendengaran
Pada usia gestasi 9 minggu, mulai terbentuk ketiga lapisan pada gendang
telinga, dan pada minggu ke-20 sudah terjadi pematangan koklea dengan
fungsi menyamai dewasa dan dapat memberi respons terhadap suara. Pada
saat yang sama, bentuk daun telinga sudah menyerupai daun telinga orang
dewasa walaupun masih terus berkembang sampai usia 9 tahun. Pada usia
gestasi 30 minggu terjadi pneumatisasi dari timpanum, demikian juga dengan
liang telinga luar yang terus berkembang sampai usia 7 tahun.
Perkembangan auditorik berhubungan erat dengan perkembangan otak.
Neuron dibagian korteks mengalami pematangan dalam waktu 3 tahun
pertama kehidupan dan masa 12 bulan pertama kehidupan terjadi
perkembangan otak yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, maka
upaya melakukan deteksi dini gangguan pendengaran sampai habilitasi
dapat dimulai pada saat perkembangan otak masih berlangsung.
2.a. Perkembangan mendengar
Usia
0 4 bulan
4 7 bulan
Kemampuan Auditorik
Bila diberikan stimulus bunyi, respon mendengar yang terjadi
masih bersifat refleks (behavioral responses) seperti:
- Refleks auropalpebral (mengejapkan mata)
- Heart rate meningkat
- Eye widening (melebarkan mata)
- Cessation (berhenti menyusu)
- Grimacing (mengerutkan wajah)
4 bulan : memutar kepala pada arah horizontal; masih lemah
(belum konsisten)
20
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
7 - 9 bulan
9 - 13
bulan
7 bulan : memutar kepala pada arah horizontal dengan cepat;
namun pada arah bawah masih lemah
Memutar kepala dengan cepat; mengidentifikasi sumber bunyi
dengan tepat
12 bulan : keingintahuan terhadap bunyi lebih besar; mencari
sumber bunyi yang berasal dari arah atas
13 bulan : dapat mengidentifikasi bunyi dari semua arah
dengan cepat
2.b. Perkembangan Bicara dan Bahasa
Perkembangan bicara seorang anak sejalan dengan pertambahan usianya
dan perkembangan mendengar.
Usia
Neonatus
2 - 3 bulan
4 - 6 bulan
7 - 11 bulan
12 - 18
bulan
24 - 35
bulan
36 - 47
bulan
Kemampuan
menangis ,suara mendengkur (cooing),suara berkumur
(gurgles)
tertawa dan mengoceh tanpa arti (babbling) : aaa, ooo
mengeluarkan suara kombinasi vokal dan konsonan.
- ocehan bermakna (true babling) atau lalling (pa..pa.., da..da)
- memberi respons terhadap suara marah atau bersahabat
- belajar menangis dengan suara yang bervariasi sesuai
kebutuhan
menggabungkan kata/suku kata yang tidak mengandung arti,
seperti bahasa asing (jargon); usia 10 bulan : mampu meniru
suara (echolalia)
- mengerti kata perintah sederhana : kesini
- mengerti nama obyek sederhana : sepatu, cangkir
- menjawab pertanyaan sederhana
- mengerti instruksi sederhana, menunjukkan bagian tubuh
dan nama mainan
- kata yang diucapkan antara 150 -300 kata
- volume dan pitch suara belum terkontrol
-mengenali warna, mengerti konsep besar - kecil, sekarang nanti
- jumlah kata yang diucapkan mencapai 900 1.200 kata
-memberi respons pada 2 kalimat perintah yang tidak
berhubungan seperti:ambil sepatu, letakkan gelas di atas
meja
- mulai bertanya kenapa dan bagaimana?
3. Etiologi dan Faktor Resiko
Gangguan pendengaran pada bayi dan anak dibedakan berdasarkan saat
terjadinya yaitu :
Masa Prenatal
Dibagi menjadi genetik dan nongenetik seperti gangguan/kelainan masa
kehamilan, kelainan struktur anatomi (atresia liang telinga, aplasia koklea),
dan kekurangan zat gizi (misal : defisiensi Iodium).
21
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Yang paling penting adalah trimester I kehamilan, misalnya akibat infeksi
bakteri atau virus (TORCHS). Disamping itu, beberapa jenis obat ototoksik
dan teratogenik berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran.
Masa Perinatal
Prematur , berat badan lahir rendah (< 2500 gram), hiperbilirubinemia, dan
asfiksia.
Masa Postnatal
Adanya infeksi bakteri atau virus (rubela, campak, parotitis, infeksi otak),
perdarahan telinga tengah, trauma tulang temporal yang mengakibatkan tuli
saraf atau tuli konduktif.
Gangguan pendengaran pada masa prenatal dan perinatal biasanya adalah
tuli sensorineural bilateral derajat berat/sangat berat.
Faktor faktor risiko yang perlu dipertimbangkan dan telah ditetapkan oleh
American Joint Committe on Infant Hearing pada tahun 2000 :
Usia 0 28 hari :
- Menjalani perawatan di NICU selama 48 jam
- Keadaan yang berhubungan dengan sindroma tertentu yang mempunyai
hubungan dengan tuli sensorineural atau tuli konduktif, misalnya
sindroma Rubela;
- Riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran sensorineural yang
menetap
sejak masa anak-anak;
- Kelainan kraniofasial termasuk kelainan morfologi pinna (daun telinga)
atau liang telinga;
- Infeksi intra uterin, seperti TORCHS (toksoplasma, rubella,
sitomegalovirus, herpes dan sifilis).
Usia 29 hari 2 tahun :
- Kecurigaan orangtua/pengasuh terhadap gangguan pendengaran,
keterlambatan bicara, afasia atau keterlambatan perkembangan lain;
- Riwayat keluarga dengan gangguan pendengaran yang menetap masa
anak-anak;
- Keadaan yang berhubungan dengan sindroma tertentu yang diketahui
mempunyai hubungan dengan tuli sensorineural, tuli konduktif atau
gangguan fungsi tuba Eustachius;
Infeksi
postnatal
yang
menyebabkan
gangguan
pendengaran
sensorineural, termasuk meningitis bakterialis;
- Infeksi intra uterin seperti TORCHS (toksoplasma, rubela, sitomegalovirus,
herpes, sfilis);
- Adanya faktor risiko tertentu pada masa neonatus, terutama
hiperbilirubinemia yang memerlukan transfusi tukar, hipertensi pulmonal
yang membutuhkan ventilator serta kondisi lainnya yang membutuhkan
ECMO (extra corporeal membrana oxygenation);
- Sindroma tertentu yang berhubungan dengan gangguan pendengaran yang
progresif seperti sindroma Usher, neurofibromatosis dan lain-lain;
22
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
- Adanya kelainan neurodegeneratif seperti sindroma Hunter dan kelainan
neuropati sensomotorik (Friederichs ataxia, sindroma Charcot - Marie
Tooth)
- Trauma kapitis;
- Otitis media yang berulang atau menetap disertai efusi telinga tengah
minimal 3 bulan.
Kapan kita curiga ada gangguan pendengaran ?
12 bulan -- belum dapat mengoceh (babbling) atau meniru
18 bulan -- tidak dapat menyebut 1 kata berarti
24 bulan -- perbendaharaan kata kurang dari 10 kata
30 bulan -- belum dapat merangkai 2 kata
4. Skrining gangguan pendengaran pada bayi baru lahir
4.1. Tujuan
Menemukan gangguan pendengaran sedini mungkin pada bayi baru lahir
agar dapat segera dilakukan habilitasi pendengaran yang optimal sehingga
dampak negatif cacat pendengaran dapat dibatasi.
4.2. Prinsip dasar skrining pendengaran pada bayi
Skrining pendengaran dilakukan dengan maksud membedakan populasi
bayi menjadi kelompok yang tidak mempunyai masalah gangguan
pendengaran (Pass/lulus) dengan kelompok bayi yang mungkin mengalami
gangguan pendengaran (Refer/tidak lulus).
Skrining pendengaran bukan diagnosis pasti karena selain kelompok
Pass/lulus dan kelompok Refer/tidak lulus masih ada 2 kelompok lain,
yaitu kelompok positif palsu (hasil refer namun sebenarnya pendengaran
normal) dan negatif palsu (hasil pass tetapi sebenarnya ada gangguan
pendengaran).
Hasil skrining pendengaran harus diterangkan dengan jelas kepada
pihak orangtua untuk mencegah kecemasan yang tidak perlu.
Hasil skrining pendengaran yang telah dilakukan oleh suatu
unit/kelompok masyarakat atau fasilitas kesehatan (RS, puskesmas,
praktik dokter, klinik, balai kesehatan ibu dan anak/BKIA) harus dirujuk
ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana pemeriksaan pendengaran
yang lengkap dan mampu melaksanakan habilitasi pendengaran dan
wicara.
Pemeriksaan pendengaran yang lengkap bertujuan menentukan status
pendengaran bayi dan anak berdasarkan prinsip :
Ear spesific
Frequency specific (penentuan ambang dengar pada setiap frekuensi)
23
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Berdasarkan fasilitas yang tersedia, skrining gangguan pendengaran
dapat dikelompokkan menjadi :
I. Skrining gangguan pendengaran di rumah sakit (hospital based
hearing screening)
II. Skrining gangguan pendengaran pada komunitas (community based
hearing screening)
Skrining gangguan pendengaran di rumah sakit (hospital based
hearing screening) dikelompokan menjadi :
1. Universal Newborn Hearing Screening (UNHS)
2. Targeted Newborn Hearing Screening
1.Universal Newborn Hearing Screening (UNHS)
Dilakukan pada semua bayi baru lahir (dengan atau tanpa faktor
risiko terhadap gangguan pendengaran). Skrining awal dilakukan
dengan pemeriksaan Otoacoustic Emission (OAE) sebelum bayi keluar
dari rumah sakit (usia 2 hari). Bila bayi lahir pada fasilitas kesehatan
yang tidak memiliki sarana OAE, paling lambat pada usia 1 bulan telah
melakukan pemeriksaan OAE di tempat lain. Bayi dengan hasil skrining
Pass (lulus) maupun Refer (tidak lulus) harus menjalani pemeriksaan
BERA (atau BERA otomatis) pada usia 1 3 bulan.
Pada usia 3 bulan, diagnosis harus sudah dipastikan berdasarkan
hasil pemeriksaan: OAE, BERA, timpanometri (menilai kondisi telinga
tengah). Untuk bayi yang telah dipastikan mengalami gangguan
pendengaran sensorineural, perlu dilakukan pemeriksaan ASSR
(Auditory Steady State Response) atau BERA dengan stimulus tone
burst, agar diperoleh informasi ambang dengar pada masing-masing
frekuensi; hal ini akan membantu proses pengukuran alat bantu
dengar yang optimal. Khusus untuk bayi yang tidak memiliki liang
telinga (atresia) diperlukan pemeriksaan tambahan berupa BERA
hantaran tulang (bone conduction).
Berdasarkan tahapan waktu tersebut di atas, habilitasi
pendengaran sudah harus dimulai pada usia 6 bulan.
Kriteria UNHS:
1. Mudah dikerjakan serta memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang
tinggi sehingga kejadian refer minimal.
2. Tersedia intervensi untuk habilitasi gangguan pendengaran.
3. Skrining, deteksi dan intervensi yang dilakukan secara dini akan
menghasilkan outcome yang baik.
4. Cost-effective.
Kriteria keberhasilan : cakupan (coverage) 95 %, nilai refferal : < 4 %
2.Targeted Newborn Hearing Screening
Skrining pendengaran yang dilakukan hanya pada bayi yang
mempunyai faktor risiko terhadap gangguan pendengaran (Gambar 10).
Kelemahan metode ini adalah sekitar 50 % bayi yang lahir tuli tidak
24
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
mempunyai faktor risiko. Model ini biasanya dilakukan di NICU
(Neonatal ICU) atau ruangan Perinatologi.
SKRINING
PENDENGARAN
BAYI BARU LAHIR
Hospital
based
UNIVERSAL NEWBORN
HEARING SCREENING
(UNHS)
Semua bayi
Community
based
TARGETED NEWBORN
HEARING SCREENING
Hanya bayi dengan faktor
risiko
Gambar 10. Klasifikasi skrining pendengaran bayi baru lahir
4.3. Pemeriksaan skrining pendengaran
Sampai saat ini pemeriksaan pendengaran yang terbaik adalah audiometri
karena dapat memberikan informasi ambang pendengaran yang bersifat
spesific frequency. Kelemahan pemeriksaan audiometri adalah besarnya
faktor subyektif dan membutuhkan kerja sama (pasien kooperatif) dan
membutuhkan respons yang dapat dipercaya dari pasien; akibatnya
pemeriksaan audiometri tidak dapat dilakukan pada pasien berusia
dibawah 6 bulan.
Baku emas pemeriksaan skrining pendengaran pada bayi
(1) Otoacoustic Emission(OAE)
(2) Automated ABR ( BERA Otomatik)
U.S Joint Committee on Infant Hearing Screening (JCIH 2000)
25
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Pemeriksaan objektif
(Elektrofisiologis)
Pemeriksaan subyektif
(Behavioral)
OAE (mulai 2 hari)
Behavioral Observation Test
Behavioral Observation Audiometry (0 6
bulan)
Visual Reinforcement Audiometry (7 -30
bulan)
Conditioned Play Audiometry (30 bulan
5 tahun)
BERA
Otomatis ( 3 bulan)
Click ( 3 bulan)
Tone burst ( 3 bulan)
Bone conduction
Timpanometri
ASSR
Tes Daya Dengar /TDD modifikasi
a. Pemeriksaan obyektif
a.1.Otoacoustic Emission (OAE)
Menilai integritas telinga luar dan tengah serta sel rambut luar (outer hair
cells) koklea. OAE bukan pemeriksaan pendengaran karena hanya
memberi informasi tentang sehat tidaknya koklea. Pemeriksaan ini
mudah, praktis, otomatis, noninvasif,
tidak membutuhkan ruangan
kedap suara maupun obat sedatif.
Hasil pemeriksaan mudah dibaca karena dinyatakan dengan kriteria
Pass (lulus) atau Refer (tidak lulus). Hasil Pass menunjukkan keadaan
koklea baik; sedangkan hasil Refer artinya adanya gangguan koklea
sehingga dibutuhkan pemeriksaan lanjutan berupa AABR atau BERA
pada usia 3 bulan.
Hasil OAE dipengaruhi oleh gangguan (sumbatan) liang telinga dan
kelainan pada telinga tengah (misalnya cairan).
Untuk skrining pendengaran, digunakan OAE skrining (OAE screener)
yang memberikan informasi kondisi rumah siput koklea pada 4 - 6
frekuensi. Sedangkan untuk diagnostik digunakan OAE yang mampu
memeriksa lebih banyak lagi frekuensi tinggi.
26
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Persiapan pemeriksaan OAE
1. Pemeriksaan dilakukan pada bayi baru lahir yang berusia > 24 jam.
2. Lingkungan dan bayi harus tenang.
3. Liang telinga harus bersih dari kotoran (serumen) maupun cairan.
4. Menggunakan probe yang sesuai dengan ukuran telinga bayi. Pada bayi
usia kurang dari 6 bulan digunakan probe khusus yang bergerigi (tree
tip) untuk mencegah kolaps liang telinga.
5. Posisi probe mengarah ke membran timpani.
6. Bila hasil Refer, sebaiknya diulang beberapa kali sampai dipastikan
memang hasilnya Refer.
Gambar 11.
OAE Skrining 6 frekuensi
Gambar 12. OAE Diagnostik
a.2. Brainstem Evoked Response Audiometry (BERA) atau Auditory
Brainstem Response (ABR)
BERA menilai perubahan potensial listrik di otak yang timbul setelah
pemberian stimulus suara. ABR berfungsi untuk menilai integritas saraf
sepanjang jalur pendengaran.
Pemeriksaan BERA yang dilakukan umumnya menggunakan
stimulus suara jenis click, pemeriksaan ini tidak frequency spesific artinya
hanya diketahui ambang respons pada frekuensi rata-rata (2000 - 4000
Hz). Agar dapat memperoleh ambang pada masing-masing frekuensi harus
ditambahkan pemeriksaan BERA dengan stimulus tone burst.
Pemeriksaan BERA sebaiknya dilakukan pada ruang kedap suara. Pada
27
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
bayi diperlukan sedatif untuk mencegah internal noise. Bila digunakan
BERA otomatis, karena waktunya singkat dapat dilakukan tanpa sedatif.
Respons neural terhadap stimulus bunyi yang diterima akan direkam
komputer melalui elektroda pemukaan (surface electrode) yang
ditempelkan pada kepala (dahi dan prosesus mastoid). Parameter yang
dinilai berdasarkan morfologi gelombang, amplitudo dan masa laten. Hasil
penilaian adalah intensitas stimulus terkecil (desibel/dB) yang masih
memberikan gelombang BERA. Ada 5 gelombang BERA yang dapat dibaca,
masing masing menggambarkan respons dari bagian-bagian jaras
auditorik mulai dari nervus akustikus sampai kolikulus inferior. Pada
bayi yang paling mudah diidentifikasi adalah gelombang V (kolikulus
inferior).
Perlu diperhatikan agar pemeriksaan BERA pada bayi dibawah usia
3 bulan atau bayi lahir prematur, mungkin terjadi pemanjangan masa
laten sehingga didapat kesan adanya tuli konduktif, pada kasus seperti ini
perlu dilakukan BERA ulangan pada saat usia lebih dari 3 bulan dan
dilakukan koreksi usia (pada prematur).
Pemeriksaan BERA Otomatis (Automated ABR)
Merupakan pemeriksaan BERA otomatis sehingga tidak diperlukan
analisis gelombang evoked potential karena hasil pencatatan mudah
dibaca, berdasarkan kriteria pass atau refer (tidak lulus). Pemeriksaan ini
sama dengan BERA konvensional yaitu
menggunakan elektroda
permukaan dengan pemberian stimulus click, mudah dilakukan, praktis,
tidak invasif dan hanya dapat menggunakan intensitas 30 40 dB.
Umumnya digunakan untuk keperluan skrining pendengaran.
Pemeriksaan pendengaran secara obyektif juga perlu dilakukan dan
disesuikan dengan usia anak. Apabila terdapat kelainan maka diperlukan
pemeriksaan lebih lanjut yang disesuaikan dengan alur HTA (Health
Technology Assesment) skrining pendengaran bayi 2006.
Gambar 13. BERA Click
Gambar 14.
BERA tone burst
Gambar 15.
BERA Otomatis
28
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Pemeriksaan Timpanometri
Pemeriksaan ini bertujuan untuk
menilai keadaan telinga tengah
(normal, tekanan negatif, cairan) dan
fungsi tuba Eustachius. Pada bayi
berusia kurang
dari
6 bulan
digunakan timpanometri frekuensi
tinggi
(High
Frequency
Tympanometry) dengan pertimbangan
pada
usia tersebut liang telinga
masih lentur/ kolaps
sehingga
menghalangi stimulus suara yang
masuk.
Gambar 16.Timpanogram
Auditory Steady State Response (ASSR)
Dengan ASSR dapat dibuat prediksi
atau
estimasi
audiometri
(predicting audiometry) atau evoked potential audiometry karena dapat
memberikan gambaran audiogram pada bayi dan anak. Hal ini
dimungkinkan karena ASSR memberikan informasi ambang pendengaran
pada frekuensi spesifik secara otomatis dan simultan, yaitu pada
frekuensi 500, 1.000, 2.000 dan 4.000 Hz. Bila perlu dapat di setting
untuk frekuensi lainnya.
Stimulasi berupa bunyi modulasi yang kontinu berupa AM (Amplitude
Modulation) dan FM (Frequency
Modulated) melalui insert phone.
Intensitas stimulus dapat mencapai 127 dB HL. Selain dapat memberikan
informasi ambang pendengaran, ASSR sangat bermanfaat untuk fitting
alat bantu dengar pada bayi dan menilai sisa pendengaran sebagai
pertimbangan untuk implantasi koklea.
Gambar 17. Auditory Steady State Response
29
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
b. Pemeriksaan Subyektif
Bila sarana pemeriksaan yang bersifat obyektif atau elektrofisiologis tidak
tersedia, dapat dilakukan pemeriksaan subyektif yang mengandalkan
respons behavioral sebagai reaksi bayi terhadap stimulus bunyi, antara
lain pemeriksaan Behavioral Observation Test (BOT) atau Behavioral
Observation Audiometry (BOA), Visual Reinforcement Audiometry (VRA) dan
Conditioned Play Audiometry (CPA). Namun bila memungkinkan, tetap
dianjurkan untuk mengkonfirmasi hasilnya dengan pemeriksaan obyektif.
b.1. Pemeriksaan Behavioral
Pemeriksaan pendengaran yang subyektif karena respon dari bayi dan
anak tidak konsisten. Namun demikian pemeriksaan behavioral memiliki
kemampuan frequency spesific. Tentu saja, nilai sensitivitas dan
spesifitasnya kurang dibandingkan pemeriksaan obyektif seperti OAE dan
BERA. Idealnya dilakukan di ruang kedap suara, bila tidak tersedia dapat
di ruangan biasa tetapi cukup tenang.
Bila tidak tersedia sarana pemeriksaan yang lebih obyektif, dapat
dimanfaatkan untuk bayi dibawah 6 bulan misalnya pemeriksaan
Behavioral Observation Test (BOT) atau Behavioral Observation Audiometry
(BOA).
Pada anak usia 6 bulan atau lebih pemeriksaan behavioral juga dapat
dilakukan untuk konfirmasi pemeriksaan obyektif yang telah dilakukan,
terutama bila menghadapi kendala untuk memperoleh pemeriksaan yang
bersifat frequency spesific.
Behavioral Observation Audiometry (BOA)
Tujuan : menentukan ambang pendengaran berdasarkan unconditioned
responses terhadap bunyi; misalnya refleks behavioral. Untuk menilai
bayi/anak 0 6 bulan.
Frekuensi stimulus : range speech frequency.
Persyaratan
Pemeriksaan di ruang kedap suara/cukup tenang
Respon bayi dinilai oleh 2 orang pemeriksa
Stimulus berjarak 1 meter dari dari telinga, di belakang garis lapang
pandangan
Stimulus : Audiometer + loud speaker
Intensitas stimulus dikalibrasi dengan sound level meter
Respon yang dinilai : respon behavioral /refleks( unconditioned
response):
-
mengejapkan mata (refleks auropalpebral)
ritme jantung bertambah cepat
berhenti meyusu (cessation reflex)
mengerutkan wajah (grimacing)
terkejut (refleks Moro)
30
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Prosedur Pemeriksaan BOA
Bayi dipangku dalam kondisi siap memberi respons/setengah tidur
Dapat sambil menyusu
Bila tidur nyenyak; bangunkan. Bila ketakutan : tunda.
Orangtua tidak ikut mambantu respons
Respons harus konsisten dan dapat diulang
Pada saat terjadi respons, catat intensitas
Bila respon (-) catat intensitas paling besar
Keterbatasan : tidak menentukan threshold (ambang pendengaran).
Prosedur Behavioral Obsevation Test sama dengan BOA, tetapi
menggunakan stimulus yang tidak terukur frekuensi dan intensitasnya(
misalnya bertepuk tangan).
Visual Reinforcement Audiometry (VRA)
Tujuan : Menentukan ambang pendengaran bayi 7 -30 bulan dengan
menilai conditioned response (respons yang telah dilatih terlebih dahulu).
Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menentukan ambang
pendengaran.
Keterbatasan : karena stimulus berasal dari pengeras suara (loudspeaker),
maka ambang yang diperoleh menunjukkan kondisi telinga yang lebih
baik.
Cara Pemeriksaan
Bayi dilatih terlebih dahulu untuk
memberikan respons khusus (misal
memutar kepala) terhadap stimulus
bunyi dengan
kekerasan bunyi
(intensitas)
tertentu.
Bila
bayi
memberikan respons, berikan hadiah
berupa
cahaya
lampu.
Kemudian
pemeriksaan diulang dengan intensitas
yang lebih rendah sampai tercapai
ambang dengar yaitu stimulus terkecil
yang masih menghasilkan respons.
Gambar 18. Visual Reinforcement
Audiometry (VRA)
Keterangan Gambar 8
S : Speaker; VR : Visual reinforcer;
P : Orang tua( memangku bayi);
I : Bayi; A : Pemeriksa; TA : Observer
Conditioned Play Audiometry (CPA)
Tujuan : Menilai ambang pendengaran berdasarkan respons yang telah
dilatih (conditioned) melalui kegiatan bermain terhadap stimulus bunyi.
Stimulus bunyi diberikan melalui ear phone sehingga dapat diperoleh
31
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
ambang pada masing masing frekuensi (frequency-specific) dan masingmasing telinga (ear specific). Dengan teknik ini, dapat ditentukan jenis dan
derajat ganggguan pendengaran.
Dilakukan untuk anak usia 30 bulan 5 tahun.
Prosedur Pemeriksaan
Terlebih dahulu anak dilatih memberikan respons melalui kegiatan
bermain, misalnya memasukkan sebuah balok ke dalam kotak; bila anak
mendengar suara dengan intensitas (kekerasan bunyi) tertentu.
Selanjutnya intensitas diturunkan sampai diperoleh intensitas terkecil di
mana anak masih memberikan respons terhadap bunyi. Bila suara diganti
dengan ucapan (kata-kata) dapat juga ditentukan speech reception
threshold (SRT).
b.2. Tes Daya Dengar (Modifikasi)
Merupakan pemeriksaan subyektif untuk deteksi dini gangguan
pendengaran pada bayi dan anak dengan menggunakan kuesioner
berisikan pertanyaan- pertanyaan ada tidaknya respons (daya dengar)
bayi atau anak terhadap stimulus bunyi. Pertanyaan berbeda untuk 8
kelompok usia. Untuk tiap kelompok usia, daftar pertanyaan terbagi
menjadi 3 kelompok penilaian kemampuan; (1) Ekspresif, (2) Reseptif dan
(3) Visual; masing-masing terdiri dari 3 pertanyaan dengan jawaban Ya
atau Tidak. Daftar pertanyaan Tes Daya Dengar (modifikasi) dapat
dilihat pada lampiran 2.
Cara penilaian
1. Bila semua pertanyaan (3 buah) dijawab Ya berarti tidak terdapat
kelainan daya dengar (Kode N/normal).
2. Bila terdapat minimal 1 (satu) jawaban Tidak berarti kita harus hatihati terhadap kemungkinan gangguan daya dengar (Kode HTN/Hatihati Tidak Normal). Tes harus diulang 1 (satu) bulan lagi.
3. Bila semua jawaban adalah Tidak mungkin terdapat gangguan lain
dengan atau tanpa kelainan daya dengar (ada gangguan lain dan tidak
normal).
4. Bila semua jawaban pada kemampuan ekspresif dan reseptif adalah
Tidak dengan kemampuan visual normal berarti ada kelainan pada
daya dengar (Kode TN/Tidak Normal).
Anak dengan kode HTN, GTN, dan TN dicatat pada kemampuan mana anak
tidak bisa mengerjakan; dan bila dilakukan tes dibawah kelompok usianya,
sampai usia mana anak bisa mengerjakan tes tersebut.
4.4. Tindak Lanjut setelah Skrining Pendengaran
Bayi yang tidak lulus skrining tahap kedua harus dirujuk untuk
pemeriksaan audiologi lengkap termasuk pemeriksaan OAE,ABR dan
Behavioral Audiometry, sehingga dapat dipastikan ambang pendengaran
pada kedua telinga dan lokasi lesi auditorik. Diagnosis pasti idealnya telah
selesai dikerjakan pada saat bayi berusia 3 bulan.
Berdasarkan alur skrining pendengaran bayi HTA 2006 (Lampiran 1),
bayi yang gagal pada skrining awal, dilakukan pemeriksaan timpanometri,
32
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
DPOAE dan AABR pada usia 3 bulan. Bila tetap tidak lulus, segera
dilakukan pemeriksaan BERA stimulus click + tone burst 500 Hz atau
ASSR, sedangkan BERA bone conduction diperiksa bila ada pemanjangan
masa laten (gangguan pendengaran konduktif).
Sebaiknya pemeriksaan tersebut diatas dikonfirmasi dengan
Behavioral Audiometry. Terhadap bayi yang lulus skrining awal, tetap
dilakukan pemeriksaan DPOAE dan AABR pada usia 3 bulan. Bila tidak
lulus, segera dilanjutkan dengan pemeriksaan audiologi lengkap. Untuk
bayi yang lulus skrining namun mempunyai faktor risiko terhadap
gangguan pendengaran, dianjurkan untuk follow up sampai anak bisa
berbicara.
5. Diagnosis
Ditegakkan berdasarkan anamnesis,
pemeriksaan THT, pemeriksaan
pendengaran baik secara subyektif maupun obyektif, pemeriksaan
perkembangan motorik, kemampuan berbicara serta psikologis.
6. Tatalaksana
Apabila ditemukan adanya gangguan pendengaran sensorineural harus
dilakukan habilitasi berupa amplifikasi pendengaran, misalnya dengan alat
bantu dengar (ABD). Selain itu, bayi/anak juga perlu mendapat habilitasi
wicara berupa terapi wicara atau terapi audioverbal (AVT) sehingga dapat
belajar mendeteksi suara dan memahami percakapan agar mampu
berkomunikasi dengan optimal.
Rekomendasi dari American Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) yang
ditetapkan berdasarkan banyak penelitian menyatakan bahwa bila skrining
pendengaran pada bayi telah dimulai pada usia 2 hari, kemudian diagnosis
dipastikan pada usia 3 bulan sehingga habilitasi yang optimal dapat dimulai
pada usia 6 bulan; maka pada usia 36 bulan kemampuan wicara anak tidak
berbeda jauh dengan anak yang memiliki pendengaran normal.
Dalam hal pemasangan ABD harus dilakukan seleksi ABD yang tepat dan
proses fitting yang sesuai dengan kebutuhan sehingga diperoleh amplifikasi
yang optimal.
Proses fitting ABD pada bayi/anak jauh lebih sulit dibandingkan orang
dewasa. Akhir-akhir ini ambang pendengaran yang spesifik pada bayi dapat
ditentukan melalui teknik Auditory Steady State Response (ASSR), yang
hasilnya dianggap sebagai prediksi audiogram, sehingga proses fitting ABD
bayi lebih optimal. Bila ternyata ABD tidak dapat membantu, salah satu
alternatif adalah implantasi koklea.
7. Pencegahan
Mengingat tingginya angka infeksi yang
anak maka perlu dilakukan imunisasi
pemeriksaan kehamilanpun dianjurkan
Apabila diketahui kemungkinan adanya
untuk konseling genetik.
dapat terjadi pada ibu hamil dan
misalnya untuk rubela, sehingga
untuk dilakukan secara teratur.
faktor genetik , maka dianjurkan
33
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
REKOMENDASI HTA
1. Skrining pendengaran dilakukan pada semua bayi baru lahir dengan atau
tanpa faktor risiko. (Rekomendasi B LoE IIb)
2. Skrining dilakukan sebelum bayi meninggalkan RS pada bayi yang lahir
di RS dan sebelum usia satu bulan pada bayi yang lahir selain di RS.
(Rekomendasi C LoE IV)
3. Diagnosis gangguan pendengaran ditegakkan sebelum usia tiga bulan dan
dilanjutkan dengan tatalaksana sebelum usia enam bulan.
(Rekomendasi B LoE IIb)
4. Skrining pendengaran di Indonesia dilaksanakan dengan alur sebagai
berikut: (terlampir dalam lampiran 2).
5. Departemen THT meningkatkan kerjasama dengan cabang ilmu terkait yaitu
Departemen Ilmu Kesehatan Anak (Perinatologi dan Neurologi), Kebidanan
dan Kandungan, Rehabilitasi Medik, Psikiatri, dan ahli audiologi dalam hal
penatalaksaan pasien.
6. Departemen Kesehatan RI berdasarkan asupan dari PERHATI-KL menyusun
kebijakan penyediaan fasilitas skrining pendengaran pada bayi dengan
mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.
7. Institusi pendidikan dan PERHATI-KL menyelenggarakan kursus, pelatihan,
dan bimbingan teknologi untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM
berkaitan dengan skrining pendengaran pada bayi baru lahir.
Daftar Pustaka
1. Joint Committee on infant hearing. Year 2000 Position Statement: Principles
2.
3.
4.
5.
and Guidelines for Early Hearing Detection and Intervention Programs.
Pediatrics 2000;106:789-817.
Suwento R. Zizlavsky S, Hendarmin H. Gangguan pendengaran pada bayi
dan anak. Dalam: Soepardi EA, Iskandar N, penyunting. Buku ajar ilmu
penyakit telinga hidung tenggorok. Edisi ke-6. Jakarta: Fakultas
Kedokteran Universitas Indonesia; 2007. h. 31-42
Rehm HL, Willianson RE, Keana MA, Corey DP, Korf BR. Understanding the
genetics of deafness, a guide for parents and families. Harvard Medical
School
Center
for
hereditary
deafness.
Diunduh
dari:
http://hearing.harvard.edu. Diakses tanggal 10 April 2004.
Stach BA. Causes of hearing impairment. Dalam: Stach BA. Clinical
Audiology: An introduction. San Diego: Singular Publishing Group; 1998. h.
117-61.
Fatmawaty. Peranan Tes Daya Dengar (TDD) untuk deteksi dini gangguan
pendengaran pada anak dengan keterlambatan wicara. Tesis
S2
Departemen IKA FKUI/ RSCM.2006
34
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
B. Skrining Hipotiroid Kongenital
Definisi
Hipotiroid kongenital (HK) merupakan kelainan pada bayi sejak lahir yang
disebabkan defisiensi sekresi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, dan
berkurangnya kerja hormon tiroid pada tingkat selular.1
HK merupakan salah satu penyebab terjadinya retardasi mental pada
anak. HK merupakan suatu penyakit bawaan yang dapat disembuhkan secara
total jika pengobatan dilakukan sejak dini. Di antara penyebab-penyebab
retardasi mental yang dapat dicegah yang dapat dikenali melalui uji saring
pada bayi baru lahir (BBL), HK merupakan penyebab yang tersering,
sementara penyebab lain misalnya phenylketonuria (PKU) lebih jarang.1
Epidemiologi
Angka kejadian HK di dunia adalah sekitar 1:3.500.2 Di Indonesia dengan
populasi 200 juta penduduk dan angka kelahiran 2% berarti ada 4.000.000
bayi dilahirkan setiap tahunnya. Berdasarkan data tersebut setiap tahun di
Indonesia diperkirakan lahir 1.143 bayi dengan HK. Di RSCM pada tahun
1992-2004 terdapat 93 kasus dengan perbandingan perempuan terhadap lakilaki adalah 57:36 (61%:39%). Prevalensi HK di Jawa Barat adalah 1:3.885.3
Dalam suatu penelitian deskriptif retrospektif ditemukan 30 kasus HK di Poli
Endokrinologi Anak dan Remaja FKUI/RSCM pada tahun 1992-2002 yang
terdiri dari 9 anak laki-laki (30%) dan 21 anak perempuan (70%). Pada saat
datang pertama kali didapatkan 53,3% kasus berumur 1-5 tahun. Hanya 3
kasus HK yang terdiagnosis di bawah umur 3 bulan.4
Etiologi
Etiologi yang spesifik bervariasi pada berbagai negara, yang tersering
menurut Bourgeois yaitu:5
1. Tiroid ektopik (25-50%)
2. Agenesis tiroid (20-50%)
3. Dishormogenesis (4-15%)
4. Disfungsi hipotalamus pituitari (10-15%)
Manifestasi klinis
Sebagian besar BBL dengan HK adalah asimtomatik karena adanya T4
transplasenta maternal. Pada sejumlah kasus defisiensi tiroid dapat
menunjukkan gejala yang berat yang tampak pada minggu-minggu pertama
kehidupan dan pada derajat defisiensi yang ringan gangguan baru
bermanifestasi setelah usia beberapa bulan.6
Hipotiroid kongenital memberikan menifestasi klinis sebagai berikut:
1. Gangguan makan (malas, kurang nafsu makan, dan sering tersedak pada
satu bulan pertama)
2. Jarang menangis, banyak tidur (somnolen), dan tampak lamban6
3. Konstipasi
4. Tangisan parau (hoarse cry)
5. Pucat5,7
6. Berat dan panjang lahir normal, lingkar kepala sedikit melebar
7. Ikterus fisiologis yang memanjang
8. Lidah besar (makroglosia) sehingga menimbulkan gangguan pernafasan
35
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ukuran abdomen besar dengan hernia umbilikalis
Temperatur tubuh subnormal, seringkali <35C
Kulit (terutama ekstremitas) dingin, kering dan berbercak
Miksedema kelopak mata, regio genitalia, dan ekstremitas
Frekuensi nadi lambat
Murmur, kardiomegali, dan efusi perikardium
Anemia (makrositik) yang membaik dengan terapi hematinik
Letargi
Coarse facial features
Fontanel anterior dan posterior paten dengan sutura kranialis lebar8
Retardasi perkembangan fisik dan mental
Hipotonia
Tanda ileus paralitik: hipomotilitas, distensi abdomen, dan hipertimpani
Pada usia sekitar tiga hingga enam bulan gambaran klinis telah
sepenuhnya terlihat.6
Diagnosis dan tatalaksana HK harus dilakukan sedini mungkin pada
periode neonatal yaitu untuk mencapai perkembangan otak maupun
pertumbuhan fisik yang normal, karena terapi efektif bila dimulai pada
minggu-minggu pertama kehidupan.7
Skrining
Hampir 90% kasus HK terdeteksi dengan uji saring, sedangkan selebihnya
diketahui berdasarkan pemeriksaan klinis. Sebagian kecil anak dapat saja
memiliki hasil pemeriksaan yang negatif tetapi selanjutnya ternyata
dinyatakan menderita HK. Dokter harus mampu mengenali gejala klinis dan
tanda hipotiroidisme serta riwayat gangguan tiroid pada keluarga yang
mengindikasikan perlunya dilakukan uji tiroid lengkap, apapun hasil uji
saringnya saat lahir. Pada BBL dari kehamilan multipel yang salah satunya
didiagnosis HK maka terhadap bayi lainnya juga perlu dilakukan uji saring
ulang, bahkan bila perlu dilakukan uji tambahan.7
Pemeriksaan laboratorium yang dapat dilakukan untuk mendeteksi dini
HK adalah (1) kadar TSH; (2) kadar T4 atau free T4 (FT4).
Pemeriksaan primer TSH merupakan uji fungsi tiroid yang paling sensitif.
Peningkatan kadar TSH sebagai marka hormonal, cukup akurat digunakan
untuk menapis hipotiroid kongenital primer.8
Pemeriksaan pencitraan yang dapat menunjang diagnosis hipotiroid
adalah sebagai berikut :
1. Scanning tiroid (menggunakan 99mTc atau 123I)6
2. Ultrasonografi (USG)6
3. Radiografi (Rontgen tulang/bone age)
4. Elektrokardiografi (EKG) dan ekokardiografi (ECG)5,6
5. Elektromiografi (EMG)9
6. Elektroensefalogram (EEG)6
7. Brain Evoke Response Audiometry (BERA)9
8. Proton magnetic resonance spectroscopy6
Prosedur skrining
Sampel darah dapat berupa darah kapiler dari tusukan tumit bayi (heel
stick); dari permukaan lateral atau medial dari tumit bayi (Gambar 20 dan 21).
Sebaiknya darah diambil pada hari ke-3 s/d 5 untuk menghindarkan TSH
36
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
surge;3 skrining dilakukan sebelum pemulangan dari rumah sakit atau
sebelum transfusi. Hasil false negative dapat terjadi pada bayi dengan kondisi
sakit berat atau setelah mendapat transfusi.10
Tetesan darah ditempelkan pada kertas saring Schleicher & Schuell
#903TM (S & S 903). Setelah dibiarkan kering selama 3-4 jam, dapat
dikirimkan perpos dalam amplop surat.8
Dengan demikian hasil bisa cepat diperoleh dan pada kasus positif
memungkinkan pengobatan sebelum bayi berumur 1 bulan. Pada bayi
prematur atau bayi yang sakit berat, pengambilan darah bisa ditangguhkan,
tetapi tidak melebihi umur 7 hari.8
Deteksi dini HK akan mencegah keterlambatan perkembangan neurologis
dan retardasi mental akibat HK yang tidak terdiagnosis dan tidak diobati.11
Cara pengambilan spesimen diperlihatkan dalam gambar berikut:
Gambar 19.
Lokasi tusukan tumit
Gambar 20.
Cara pengambilan
spesimen
Gambar 21.
Cara meneteskan darah
pada kertas saring
Gambar 23.
Spesimen dibungkus
dalam amplop
Gambar 22.
Spesimen dikeringkan selama
3-4 jam pada suhu kamar
Sumber: Rustama DS
37
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Kriteria skrining
Nilai TSH neonatus diperkirakan dengan metode ELISA menggunakan
peroksidase yang dilabeli dengan monoclonal antibody antiTSH ke dalam micro
well yang kemudian diukur kadarnya dengan menghitung tingkat
absorpsinya. Nilai TSH yang mencapai 10 mIU/l dianggap normal, 10-20
mIU/L dianggap sebagai nilai batas dan >20 mIU/L dianggap abrnormal.12
Nilai tersebut dapat bervariasi, tergantung pada reagen yang digunakan.
Tes uji saring dilakukan dengan pengukuran TSH IRMA, dengan double
antibody radioimmunoassay, dan pemeriksaan T4 dengan coated tube
radioimmunoassay. Reagen yang digunakan dalam bentuk kit (contoh kit
Skybio Ltd dan DPC). Bila nilai TSH <20mIU/L dianggap normal; kadar TSH
>20 mIU/L. dianggap abnormal dan perlu pemeriksaan lebih lanjut. Bila
kadar TSH > 50 IU/L perlu dilakukan pemeriksaan klinis dan pemeriksaan
TSH dan T4 serum. Bila kadar TSH tinggi, > 50 mIU/L; dan T4 rendah, < 6
g/dL, bayi diberi terapi tiroksin dan dilakukan pemeriksaan untuk
menegakkan diagnosis. Semua bayi dengan kadar TSH diatas nilai cut-off
dipanggil kembali/recall (Gambar 24).8
Mayoritas bayi hipotiroidisme primer mempunyai nilai TSH >80 IU/mL.
Beberapa kondisi hipotiroidisme nonprimer yang berhubungan dengan nilai
T4 rendah misalnya hipotiroidisme sekunder, thyroid binding globulin (TBG)
rendah, terapi maternal (dengan lithium, iodida), prematuritas, penyakit berat,
hipotiroidisme sementara yang idiopatik, dan tiroiditis maternal. Sebagian
besar kelainan ini biasanya bersifat sementara. Frekuensi hipotiroidisme
sekunder diperkirakan 1:60.000 dan sebagai akibat kelainan hipofisis atau
hipotalamus. Nilai T4 yang rendah dengan TSH normal atau sedikit meningkat
ditemukan pada bayi berat lahir rendah kemudian akan menjadi normal
setelah status nutrisinya diperbaiki.13
Gambar 24. Algoritma skrining hipotiroid kongenital8
38
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Follow up hasil skrining
Follow up jangka pendek dimulai dari hasil laboratorium (hasil positif) dan
berakhir dengan pemberian terapi hormon tiroid (tiroksin). Follow up jangka
panjang diawali sejak pemberian obat dan berlangsung seumur hidup pada
kelainan yang permanen.
Hasil tes positif membutuhkan penilaian oleh klinisi dan petugas
laboratorium yang kompeten dan menjamin diagnosis yang tepat dan akurat.
Pada bayi dengan hasil tes positif, harus segera dipanggil kembali untuk
pemeriksaan TSH dan T4 serum. Bayi dengan hasil TSH tinggi ( 50 mIU/L)
dan T4 rendah (< 6 g/dL), harus dianggap menderita HK sampai diagnosis
pasti ditegakkan.
Penatalaksanaan selanjutnya adalah sebagai berikut :
Anamnesis pada ibu, apakah ada penyakit tiroid pada ibu atau keluarga,
atau mengkonsumsi obat antitiroid;
Anamnesis tentang bayi;
Pemeriksaan fisis untuk mencari tanda dan gejala HK (Tabel 2);
Tabel 2. Daftar isian pemeriksaan fisis follow up hasil skrining8
Gejala
Letargi
Konstipasi
Kesulitan
minum (sering
tersedak)
Kulit teraba
dingin
Ya
Tidak
Tanda
Kulit burik
Ikterus
Hernia
umbilikalis
Ya
Tidak
Makroglosi
Fontanel melebar
Perut buncit
Tangisan serak
Kulit kering
Refleks lambat
Refleks lambat
Bila memungkinkan, lakukan pemeriksaan penunjang :
Sidik tiroid (dengan 123I atau TC99m).
Pencitraan, pemeriksaan pertumbuhan tulang (sendi lutut dan
panggul). Tidak tampaknya epifisis pada lutut menunjukkan derajat
hipotiroid dalam kandungan.
Pemeriksaan anti tiroid antibodi bayi dan ibu, bila ada riwayat penyakit
autoimun tiroid.
Penjelasan/penyuluhan kepada orangtua bayi mengenai :
penyebab HK dari bayi mereka,
pentingnya diagnosis dan terapi dini untuk mencegah hambatan
tumbuh kembang bayi,
cara pemberian obat tiroksin,
pentingnya pemeriksaan secara teratur sesuai jadwal yang dianjurkan
dokter.
39
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Skrining untuk fasilitas terbatas
Untuk tingkat pelayanan kesehatan dengan fasilitas terbatas, dapat
dipergunakan neonatal hipotyroid index untuk skrining HK (Tabel 3). Skrining
ini didasarkan pada penilaian terhadap klinis bayi; diagnosis HK ditentukan
jika skor
4; bayi normal jika skor <2. Seluruh bayi dengan skor > 2
kemudian diperiksa nilai FT4 & TSHs. Pemeriksaan ini tidak valid setelah bayi
berusia > 6 bulan.
Tabel 3. Neonatal hypotiroid index
0
Manifestasi klinis
Skor
1.Gangguan makan
2. Konstipasi
3. Bayi tidak aktif
4.Hipotonia
5.Hernia umbilikalis (>0.5cm)
6.Makroglosia
7.Cutis marmorata
8.Kulit kering
1.5
9.Large fontanelle (>0.5cm)
1.5
10.Typical Fascies
Total
3
13
Sumber : Letarte, Garagorri (1989)
Pengobatan
Setelah dikonfirmasi, terapi dengan hormon tiroid pada penderita HK
harus diberikan secepat mungkin. Target terapi adalah mencapai kadar T4
normal dalam 2 minggu dan TSH dalam 1 bulan.10
Bayi baru lahir biasanya membutuhkan dosis 8-15 g/kg/hari; tujuan
terapi adalah menormalisasi kadar TSH sesegera mungkin. Terapi untuk bayi
cukup bulan dimulai dengan 50 g/hari selama 1-2 minggu, kemudian dosis
diturunkan menjadi 37.5 g/hari (p.o.). Tablet levothyroxine sintetis
dilarutkan dalam 5-10 ml air dan diminumkan kepada bayi dengan spuit pada
awal menyusu untuk memastikan seluruh obatnya terminum dengan baik.11
Dianjurkan untuk memberikan selang waktu minimal 1 jam antara terapi
dengan konsumsi susu formula yang mengandung kedelai atau suplementasi
besi dan serat.10,11 Pemberian ASI dapat dilanjutkan.10
Sebagai tanda bahwa bayi mendapatkan terapi yang mencukupi, kadar T4
harus segera mencapai nilai normal. Untuk mencapai kecukupan obat,
dianjurkan selama pengobatan, nilai T4 berada diatas nilai tengah rentang
kadar T4 normal, yaitu 130-206 nmol/L (10-16 g/dL) dan nilai TSH < 5
mIU/L (0.5-2.0 mIU/L); FT4 18-30 pmol/L (1.4-2.3 ng/dL). Kondisi ini
40
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
dipertahankan terus selama terapi sampai bayi berusia 3 tahun. Dianjurkan
memberikan dosis awal tidak kurang dari 10 ug/kg/hari, agar tercapai IQ
mendekati normal.8,10
Setelah terapi, diharapkan kadar T4 meningkat mencapai > 10 g/dL; FT4
> 2 ng/dl dalam 2 minggu pascaterapi inisial. TSH diharapkan normal dalam
1 bulan pascaterapi inisial. Pemeriksaan FT4 pada 1 minggu pascaterapi
inisial dapat mengkonfirmasi peningkatan konsentrasi T4 serum. Dosis
tiroksin harus disesuaikan dengan klinis bayi, serta konsentrasi FT4 serum
dan TSH.10
Tujuan terapi adalah mencapai tumbuh kembang normal dengan
mempertahankan konsentrasi total T4 dan FT4 serum dalam nilai tengah
rentang normal sepanjang 1 tahun pertama kehidupan bayi, dengan
konsentrasi TSH serum yang optimal (0.5-2.0 mIU/L). Kegagalan mencapai
target konsentrasi FT4 serum tersebut dalam 2 minggu pascaterapi dan atau
kegagalan menurunkan nilai TSH sampai < 20 mIU/L dalam 4 minggu
pascaterapi harus dipikirkan bahwa bayi tidak mendapat dosis terapi yang
adekuat.10
Segala upaya terapi untuk mencapai target tersebut, tetap harus
mempertimbangkan efek samping dari pengobatan yang berlebihan terhadap
bayi, serta harus dilakukan pemantauan konsentrasi FT4 serum secara
berkala. Kondisi hipertiroidisme yang berkepanjangan akibat terapi, terkait
dengan kejadian premature craniosynostosis.10
Pada umumnya dosis tiroksin bervariasi tergantung berat badan dan
disesuaikan respons masing-masing anak dalam menormalkan kadar T4.
Sebagai pedoman, dosis yang umum dipergunakan adalah :
0 6 bulan
6 12 bulan
1 5 tahun
5 10 tahun
> 10 12 tahun
25-50 g/hari
50-75 g/hari
50-100 g/hari
100-150 g/hari
100-200 g/hari
atau 8-15 g/kg/hari
atau 7-10 g/kg/hari
atau 5-7 g/kg/hari
atau 3-5 g/kg/hari
atau 2-4 g/kg/hari
Pemantauan
Pemantauan fungsi tiroid dengan pemeriksaan TSH dan T4 atau FT4
dilakukan :
Setelah pemberian tiroksin
Tiap
2
T4 normal
minggu,
1-12 bulan
Tiap 2 bulan
1-2 tahun
Tiap 3 bulan
2 3 tahun
Tiap 4 bulan
> 3 tahun
Tiap 6 bulan
sampai
kadar
Sebaiknya T4 dan TSH diperiksa setelah 2 minggu perubahan dosis tiroksin.
41
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Pemantauan lainnya meliputi :
Pertumbuhan
Perkembangan
Fungsi mental dan kognitif
Gejala kekurangan/kelebihan dosis tiroksin
Tes pendengaran
Umur tulang
Gambar 25. Alur follow up hasil skrining hipotiroid kongenital
Sumber : Pedoman Umum Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital
(Pokjanas Hipotiroid Kongenital Kementrian Kesehatan)
42
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Daftar Pustaka
1. Rustama DS, Fadil MR, Harahap ER, Primadi A. Newborn screening in
Indonesia. Dalam: David-Padilla C, Abad L, Silao CL, Therell BL.
Southeast Asian J Tropical Med and Public Health 2003; 34 Suppl 3:76-9.
2. Satyawirawan FS. Penapisan hipotiroid congenital. Dalam : Suryaatmadja
M. Pendidikan berkesinambungan patologi klinik 2005. Jakarta:
Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia;
2005. H. 95-104.
3. Pulungan AB. Hipotiroid kongenital (HK). UKK Endokrinologi IDAI,
Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI Jakarta.
4. Deliana M, Batubara JR, Tridjaja B, Pulungan AB. Hipotiroidisme
kongenital di Bagian Ilmu Kesehatan Anak RSCM Jakarta, tahun 19922002. Sari Pediatri 2003; 5(2):79-84. (Level of Evidence IIB, Grade of
Recommendation B)
5. Bourgeois MJ. Congenital hypothyroidism. Department of Pediatrics,
Division of Pediatric Endocrinology and Metabolism, Texas Tech University
School of Medicine; 2004. h.1-13.
6. LaFranchi S. Thyroid function in preterm infant. Thyroid 1999; 9: 71-8
7. Newborn S. Prog
8. Komite Nasional Skrining Hipotiroid Kongenital. Pedoman Umum
Pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK). Departemen
Kesehatan; 2005.
9. (Deliana)
10. National Guideline Clearinghouse. Update of newborn screening and
therapy for congenital hypothyroidism (2006).
11. Murray MA. Primary TSH screen for congenital hypothyroidism. Summer
2009;1(2):1-5.
12. (Devi)
13. (Satyawirawan FS.)
43
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
C. Skrining Retinopathy of Prematurity
Definisi
Retinopathy of Prematurity (ROP) adalah suatu kelainan retina dari bayi
prematur berat badan lahir rendah (BBLR) yang dapat berpotensi
mengakibatkan kebutaan.
Epidemiologi
Prevalensi ROP pada studi di Panti Netra di Indonesia melaporkan
prevalensi ROP sebesar 1.1 %.1,2 Namun dengan meningkatnya harapan hidup
bayi prematur dengan berat badan lahir sangat rendah di negara berkembang
akibat kemajuan teknologi perawatan neonatus, ROP berkembang menjadi
suatu masalah yang berarti.1
Faktor risiko
Beberapa keadaan dilaporkan sebagai faktor risiko berkembangnya ROP
pada bayi prematur/BBLR. Studi yang dilakukan Karna, dkk (2004) terhadap
faktor risiko terjadinya ROP, dikatakan bahwa jenis kelamin, sindroma
distress respiratori, terapi 36 minggu usia pasca konsepsi dan penggunaan
steroid prenatal tidak menunjukkan hubungan yang bermakna terhadap ROP
berat. Kejadian ROP menurun pada usia kehamilan 26-28 minggu (OR:4.12,
95% IK: 1.0516.11) dibandingkan pada usia kehamilan 25 minggu (OR:11.27,
95% IK: 2.61 48.66). Dilaporkan juga bahwa pemberian oksigen lebih dari 2
minggu meningkatkan insidens ROP berat (OR:4.09, 95% IK: 1.5211.03).3
Shah VA (2005) menyatakan insidens ROP diantara bayi dengan berat
lahir sangat rendah sebesar 29.2%. Terdapat hubungan bermakna antara
ROP dan bayi dengan berat badan yang semakin rendah, semakin muda
(imatur), atau sakit. Usia median untuk onset ROP adalah 35 minggu (dari 3140 minggu) usia postmenstrual. Bayi dengan usia gestasi < 30 minggu dan
atau bayi dengan berat lahir < 1.000 g merupakan ambang batas risiko ROP.
Faktor risiko utama untuk terjadinya hal tersebut antara lain preeklamsia
maternal, berat lahir, dan kejadian perdarahan pulmonal, durasi ventilasi dan
ventilasi tekanan positif yang berlanjut. Untuk mencegah ROP, diperlukan
pencegahan terhadap kejadian prematuritas, mengontrol preeklamsia, serta
menggunakan ventilasi dan terapi oksigen secara bijaksana.4
Skrining
Pada bayi aterm retina berkembang sempurna, dan ROP tidak dapat
terjadi. Namun, pada bayi prematur, perkembangan retina yang berjalan dari
papil nervus optikus ke anterior selama masa gestasi berlangsung secara
tidak lengkap, dengan tingkat imaturitas retina bergantung terutama pada
derajat prematuritas saat lahir.
Perhatian dan perawatan yang efektif diperlukan, dimana bayi prematur
yang berisiko mendapatkan pemeriksaan retina yang terjadwal baik.
Pemeriksaan ini dianjurkan dilakukan oleh seorang spesialis mata yang
terlatih dalam skrining ROP pada bayi prematur. Demikian juga spesialis anak
yang merawat bayi prematur dengan risiko ini menyadari akan pengaturan
jadwal ini.
44
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
a. Tujuan skrining
Tujuan
suatu
program
skrining
yang
efektif
adalah
untuk
mengidentifikasi bayi prematur yang memerlukan terapi ROP (ROP threshold,
ROP prethreshold), tapi juga dengan meminimalisasi sejumlah pemeriksaan
yang penuh stres ini bagi si bayi sakit.
ROP merupakan kelainan yang berpotensi menyebabkan kebutaan,
namun sebetulnya kebutaannya dapat dicegah. Identifikasi dini dilanjutkan
dengan terapi yang dilakukan dalam kerangka waktu yang tepat, akan dapat
mencegah kebutaan.
Walaupun tanpa terapi, 85% kasus ROP dapat mengalami regresi
spontan, dan dari 15% yang mengalami progresi , 85% di antaranya berespon
baik dengan terapi laser ataupun krioterapi.
b. Pedoman skrining
Pedoman Skrining ROP ditetapkan pada banyak negara. Perlu diingat
bahwa parameter skrining ini dapat berbeda antar negara yang satu dengan
lainnya.
Komite/Pokja Nasional ROP yang dibentuk pada Indonesia National ROP
Workshops bulan Januari 2009 di Jakarta merekomendasikan beberapa hal
berkaitan dengan bayi prematur dan ROP, diantaranya adalah Parameter
Skrining ROP pada bayi prematur sebagai berikut:5
- Bayi dengan berat lahir <1500g atau usia gestasi <34 minggu harus
diperiksa untuk kemungkinan terjadinya ROP
- Pemeriksaan harus dimulai selama minggu ke 4 atau pada usia
postmenstrual 32-33 minggu
- Pemeriksaan terhadap bayi dengan berat lahir lebih besar atau usia gestasi
lebih tinggi daripada yang disebutkan di atas dapat dilakukan sesuai
permintaan neonatologis/spesialis anak
Data bayi yang diperiksa harus dilakukan menurut standar pelaporan
yang sudah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Komite/Pokja Nasional ROP
(lihat lampiran).6
c. Teknik Pemeriksaan
Sarana /Prasarana:
Dilatasi pupil dengan tetes mata siklopentolat 0.5% dan fenilefrin 2.5%,
paling tidak 30 menit sebelum pemeriksaan.
Oftalmoskopi indirek sebagai standar baku emas.
RetCam 120, alternatif teknik baru skrining
Penulisan dan penyimpanan data sesuai stand
Informasi untuk orang tua oleh spesialis mata, dengan didampingi seorang
staf NICU/ruang rawat intermediate
d. Pengakhiran skrining:
Skrining dilanjutkan sampai tidak mempunyai risiko lagi terhadap
berkembangnya ROP secara serius:
Regresi ROP dengan terapi
Vaskularisasi matur secara lengkap di seluruh retina
Matur sampai zona 3 tanpa ROP
Usia gestasi 45 minggu dan tanpa adanya threshold disease atau
perburukan ROP
45
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Regresi tanpa terapi dengan pemeriksaan yang stabil
e. Penundaaan skrining:
Apabila keputusan untuk melakukan penundaan skrining dibuat atas
alasan klinis, maka hal tersebut haruslah merupakan keputusan bersama
antara
dokter
mata
dengan
tim
dokter
perinatologi
dengan
mempertimbangkan risiko penundaan tersebut. Keputusan tersebut harus
ditulis dalam catatan medik bayi dengan menjelaskan secara jelas alasan
ditundanya skrining dan pemeriksaan harus dijadwalkan kembali dalam
segera setelah waktu pemeriksaan yang seharusnya.
Klasifikasi ROP
The International Classification of ROP (ICROP) mengklasifikasikan
kelainan pada ROP berdasarkan : 7
lokasi keterlibatan retina berdasarkan zona (zona 1-3);
stadium atau beratnya retinopati pada persambungan retina vaskuler dan
avaskuler (stadium 1-5);
luasnya keterlibatan retina berdasarkan arah jarum jam;
ada/tidaknya dilatasi vena serta lekukan pembuluh darah polus posterior.
(Gambar klasifikasi ROP, lihat lampiran)
Gambar 26. Klasifikasi Zona ROP
Sumber: Kuschel C, Dai S. Retinopathy of Prematurity.
Newborn Services Clinical Guideline. 2007.
Catatan penting:
- Kerjasama yang baik antara spesialis mata dan neonatologis/spesialis anak
sangat penting untuk mendapatkan hasil yang baik
- Buatlah perencanaan jadwal yang baik untuk pemeriksaan follow-up pada
saat pasien akan dipulangkan:
46
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Dokter spesialis anak (neonatologis) dan dokter spesialis mata perlu
membuat rencana follow-up pasien.
Sebaiknya tunda pemulangan pasien apabila follow-up mata belum
dijadwalkan.
Buatlah pasien menyadari tanggung jawabnya untuk membawa
bayinya pada pemeriksaan follow-up mata seperti dijadwalkan.
Tatalaksana
Observasi8
Scleral Buckle
Vitrektomi
Cryotherapy8
Laser8
Komplikasi
Katarak
Glaukoma
Kerusakan kornea
Atrofi nervus optikus
Kerusakan pigmen fovea
Miopia8
Strabismus8
Ablasi retina8
REKOMENDASI HTA
1. Bayi dengan berat lahir <1500g atau usia gestasi <34 minggu harus
diperiksa untuk kemungkinan terjadinya ROP. (Rekomendasi C LoE IV)
2. Pemeriksaan harus dimulai selama minggu ke 4
postmenstrual 32-33 minggu. (Rekomendasi C LoE IV)
atau
pada
usia
3. Pemeriksaan terhadap bayi dengan berat lahir lebih besar atau usia gestasi
lebih tinggi daripada yang disebutkan di atas dapat dilakukan sesuai
permintaan neonatologis/spesialis anak. (Rekomendasi C LoE IV)
Sumber : Komite/Pokja Nasional ROP 2009
47
HTA Indonesia_2010_Buku Panduan Tatalaksana Bayi Baru Lahir Di Rumah Sakit
Daftar pustaka
1 Sitorus RS, Abidin MS, Lorenz B, Prihartono. Prevalence of ROP in Indonesia:
results from School for the Blind studies in Java island. Acta Medica
Lithuanica 2006;13:204-6
2 Sitorus RS, Abidin MS, Prihartono J. Causes and temporal trends of childhood
blindness in Indonesia: study at schools for the blind in Java. Br J
Ophthalmol. 2007 Sep;91(9):1109-13
3 Karna P, Muttineni J, Angell L, Karmaus W. Retinopathy of prematurity and
risk factors:a prospective cohort study. BMC Pediatrics 2005, 5:18.
4 Shah VA. Incidence, Risk Factors of Retinopathy of Prematurity Among Very
Low Birth Weight Infants in Singapore. Ann Acad Med Singapore 2005;34:16978.
5 Indonesia National Committee on ROP. Report on The first National ROP
Workshops. Jakarta, 2009.
6 International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity.
The international classification of retinopathy of prematurity revisited. Arch
Ophthalmol 2005; 123(7):991-999.
7 International Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity.
The international classification of retinopathy of prematurity revisited. Arch
Ophthalmol 2005; 123(7):991-999.
8 The Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Comparative Group. The
Early Treatment for Retinopathy of Prematurity Study: structural findings at
age
2
years.
Br
J
Ophthalmology
2006;90:1378-82.doi:
10.1136/bjo.2006.098582.
48
Anda mungkin juga menyukai
- SAP Ibu Hamil Dengan Resiko TinggiDokumen4 halamanSAP Ibu Hamil Dengan Resiko TinggiRahajeng TiaBelum ada peringkat
- Alogaritma Persalinan Kompleks - Rofidah Aziz - 152191222Dokumen14 halamanAlogaritma Persalinan Kompleks - Rofidah Aziz - 152191222Rofidah azizBelum ada peringkat
- Kak Pelepasan Implant - OkDokumen3 halamanKak Pelepasan Implant - OkDian EkasariBelum ada peringkat
- Laporan Surveilans Kelompok SukabumiDokumen26 halamanLaporan Surveilans Kelompok SukabumiDhimas MuhammadBelum ada peringkat
- Makalah KP ASI YULImakalah KP AsiDokumen24 halamanMakalah KP ASI YULImakalah KP AsiAbdul AnasBelum ada peringkat
- Laporan Asuhan Kebidanan Pemberdayaan KeluargaDokumen138 halamanLaporan Asuhan Kebidanan Pemberdayaan Keluargaherysutanto.p07134322072Belum ada peringkat
- Makalah Pemberdayaan KeluargaDokumen11 halamanMakalah Pemberdayaan KeluargaHabibiBelum ada peringkat
- Uas Manajemen Pelayanan KebidananDokumen5 halamanUas Manajemen Pelayanan KebidananEchi Desnawati100% (1)
- Kewirausahaan KebidananDokumen26 halamanKewirausahaan KebidananNURUL ROMADHONBelum ada peringkat
- Manajemen LaktasiDokumen30 halamanManajemen LaktasiDewi MasithohBelum ada peringkat
- LP PrakonsepsiDokumen21 halamanLP Prakonsepsikania ambarwatiBelum ada peringkat
- BAB 1 Konseling KBDokumen18 halamanBAB 1 Konseling KBRiniez Scatzy Ciimenirr YPasBelum ada peringkat
- Konsep Keluarga GrandisnaDokumen15 halamanKonsep Keluarga GrandisnaGrandis AzhariBelum ada peringkat
- KAK Deteksi Dini Tumbang Di PosyanduDokumen4 halamanKAK Deteksi Dini Tumbang Di Posyanduirwan100% (1)
- Tugas Makalah Asuhan Kebidanan Pada Ibu NifasDokumen13 halamanTugas Makalah Asuhan Kebidanan Pada Ibu NifasNurFitryaBelum ada peringkat
- Panduan KDPKDokumen23 halamanPanduan KDPKmutmainnahBelum ada peringkat
- Bu Emi - Webinar Nasional Hut Ibi KalselDokumen37 halamanBu Emi - Webinar Nasional Hut Ibi KalselWenda JjeBelum ada peringkat
- Polindes, Poskesdes FixDokumen45 halamanPolindes, Poskesdes FixFicky A. PutriBelum ada peringkat
- KELUARGA BINAAN Tn. M DESA RAWADokumen44 halamanKELUARGA BINAAN Tn. M DESA RAWACut Melinda UfrhaBelum ada peringkat
- Notulen Evaluasi Pendataan Bayi & UCIDokumen3 halamanNotulen Evaluasi Pendataan Bayi & UCIErlina JuwitaBelum ada peringkat
- Efektifitas Pijat PayudaraDokumen7 halamanEfektifitas Pijat PayudaraDwi Fitriyana PutriBelum ada peringkat
- SAP Imunisasi DPTDokumen7 halamanSAP Imunisasi DPTIke Gusiswanti0% (1)
- Materi Lembar Balik PenyuluhanDokumen41 halamanMateri Lembar Balik PenyuluhanHidayatAsikinBelum ada peringkat
- Visi Misi Terbaru Puskesmas 2017Dokumen3 halamanVisi Misi Terbaru Puskesmas 2017Risky Novitasari50% (2)
- Klimaterium Dan MenopauseDokumen30 halamanKlimaterium Dan Menopausefary arianBelum ada peringkat
- Doula ServiceDokumen19 halamanDoula Servicefitri pitasariBelum ada peringkat
- Sap MowDokumen9 halamanSap MowAriska AyuBelum ada peringkat
- Prinsip Gizi Untuk Ibu HamilDokumen3 halamanPrinsip Gizi Untuk Ibu Hamilmashlachatul mar'ahBelum ada peringkat
- Askeb KSPRDokumen7 halamanAskeb KSPRwidyanenoBelum ada peringkat
- Rps PELAYANAN-KBDokumen10 halamanRps PELAYANAN-KBhaeraniBelum ada peringkat
- Sop Asuhan Prsalinan NormalDokumen6 halamanSop Asuhan Prsalinan NormalFara FajrinaBelum ada peringkat
- Struktur Organisasi Kelas Ibu Hamil Dan Kelas Ibu BalitaDokumen1 halamanStruktur Organisasi Kelas Ibu Hamil Dan Kelas Ibu Balitadede rusiahBelum ada peringkat
- Kelompok PendukungDokumen11 halamanKelompok Pendukunglailatulmursida87100% (1)
- Penatalaksanaan Konseling CatenDokumen1 halamanPenatalaksanaan Konseling CatenRisa Tikdia SetyowatiBelum ada peringkat
- Information Sheet Kelas Ibu Hamil PDFDokumen2 halamanInformation Sheet Kelas Ibu Hamil PDFArya Adalah KodokBelum ada peringkat
- ImplantDokumen50 halamanImplantNurul SukronBelum ada peringkat
- Sap KB Post PartumDokumen11 halamanSap KB Post PartumTantri Yunita RatnaBelum ada peringkat
- Konseling Pada Ibu MelahirkanDokumen2 halamanKonseling Pada Ibu MelahirkanNova ElviraBelum ada peringkat
- Laporan BBL KasusDokumen13 halamanLaporan BBL KasusAnindyta DewiBelum ada peringkat
- Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Cakupan Persalinan Oleh Bidan Di Desa KTI KEBIDANANDokumen5 halamanFaktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Cakupan Persalinan Oleh Bidan Di Desa KTI KEBIDANANhaidar rzBelum ada peringkat
- Makalah Pasangan Usia SuburDokumen11 halamanMakalah Pasangan Usia Suburisvara100% (1)
- Ilmu Kesehatan AnakDokumen20 halamanIlmu Kesehatan Anakrischi trysia100% (1)
- Panduan Program KiaDokumen10 halamanPanduan Program KiaWarniningsih MulyadiBelum ada peringkat
- Pengaruh Pijat Oksitosin Oleh Suami Terhadap Produksi ASI Dan Kadar Hormon Prolaktin Pada Ibu NifasDokumen22 halamanPengaruh Pijat Oksitosin Oleh Suami Terhadap Produksi ASI Dan Kadar Hormon Prolaktin Pada Ibu NifasmarianaBelum ada peringkat
- Makalah Askeb Nifas-Critical ThinkingDokumen21 halamanMakalah Askeb Nifas-Critical ThinkingPratama RzBelum ada peringkat
- Pleno MGG 5 Kel 5Dokumen22 halamanPleno MGG 5 Kel 5asri rahmayelitaBelum ada peringkat
- Pengertian ImplanDokumen19 halamanPengertian ImplanLili ErnidaBelum ada peringkat
- Pedoman Cinta HatiDokumen33 halamanPedoman Cinta HatiVeny Anggriani100% (1)
- Prinsip Dasar Dalam Mengembangkan UsahaDokumen3 halamanPrinsip Dasar Dalam Mengembangkan UsahaliaBelum ada peringkat
- LP REMAJA - Kasus AnemiaDokumen30 halamanLP REMAJA - Kasus AnemiaErfin RistianiBelum ada peringkat
- Evidence Based Masa Nifas - Mirza Aulia Cahyani - P17321183028Dokumen13 halamanEvidence Based Masa Nifas - Mirza Aulia Cahyani - P17321183028mirzaBelum ada peringkat
- LEAFLET Tanda Bahaya KehamilanDokumen2 halamanLEAFLET Tanda Bahaya KehamilanRia Aryanti Putri IIBelum ada peringkat
- Leaflet MAkanan Bergizi Untuk Ibu Hamil Dan MenyusuiDokumen2 halamanLeaflet MAkanan Bergizi Untuk Ibu Hamil Dan MenyusuiDearniBelum ada peringkat
- Leflet Tanda Bahaya BBLDokumen4 halamanLeflet Tanda Bahaya BBLfitri siregarBelum ada peringkat
- Makalah Stase 6Dokumen29 halamanMakalah Stase 6DEWI SITI NURJANAH100% (1)
- JURNAL KB - JKN RENI, (Juni 2022)Dokumen7 halamanJURNAL KB - JKN RENI, (Juni 2022)Reni SaswitaBelum ada peringkat
- Ceklist Rekom BidanDokumen4 halamanCeklist Rekom Bidanretno wahyuBelum ada peringkat
- Bidan Praktek Mandiri Asri ArsiniDokumen7 halamanBidan Praktek Mandiri Asri ArsiniDeppy DisketBelum ada peringkat
- Tuli Kongenital Pada Bayi Dan AnakDokumen16 halamanTuli Kongenital Pada Bayi Dan AnakpuspamitandaBelum ada peringkat
- Pemasangan Alat Bantu Dengar Pada AnakDokumen24 halamanPemasangan Alat Bantu Dengar Pada AnakjelitaBelum ada peringkat