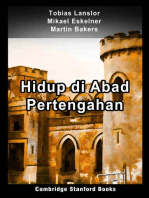Konflik Perang
Diunggah oleh
Herry HermawanJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Konflik Perang
Diunggah oleh
Herry HermawanHak Cipta:
Format Tersedia
PERANG TELUK KWAIT IRAK Perang Teluk Persia I atau Gulf War disebabkan atas Invasi Irak atas
s Kuwait 2 Agustus 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Emir Kuwait Syeikh Jaber Al Ahmed Al Sabah segera meninggalkan negaranya dan Kuwait dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Saddamiyat Al-Mitla` pada tanggal 28 Agustus 1990, sekalipun Kuwait membalasnya dengan serangan udara kecil terhadap posisi posisi Irak pada tanggal 3 Agustus 1991 dari pangkalan yang dirahasiakan.
[sunting] Latar belakang
Invasi Irak ke Kuwait disebabkan oleh kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam perang Iran-Irak. Irak sangat membutuhkan petro dolar sebagai pemasukan ekonominya sementara rendahnya harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak oleh Kuwait serta Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi serta perselisihan atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca-perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki. Akibat invasi ini, Arab Saudi meminta bantuan Amerika Serikat tanggal 7 Agustus 1990. Sebelumnya Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ekonomi pada 6 Agustus 1990. Amerika Serikat mengirimkan bantuan pasukannya ke Arab Saudi yang disusul negara-negara lain baik negara-negara Arab kecuali Syria, Libya dan Yordania serta Palestina. Kemudian datang pula bantuan militer Eropa khususnya Eropa Barat (Inggris, Perancis dan Jerman Barat), serta beberapa negara di kawasan Asia. Pasukan Amerika Serikat dan Eropa di bawah komando gabungan yang dipimpin Jenderal Norman Schwarzkopf serta Jenderal Collin Powell. Pasukan negara-negara Arab dipimpin oleh Letjen. Khalid bin Sultan. Misi diplomatik antara James Baker dengan menteri luar negeri Irak Tareq Aziz gagal (9 Januari 1991). Irak menolak permintaan PBB agar Irak menarik pasukannya dari Kuwait 15 Januari 1991. Akhirnya Presiden Amerika Serikat George H. Bush diizinkan menyatakan perang oleh Kongres Amerika Serikat tanggal 12 Januari 1991. Operasi Badai Gurun dimulai tanggal 17 Januari 1991 pukul 03:00 waktu Baghdad yang diawali serangan serangan udara atas Baghdad dan beberapa wilayah Irak lainnya serta operasi di daratan yang mengakibatkan perang darat yang dimulai tanggal 30 Januari 1991. Irak melakukan serangan balasan dengan memprovokasi Israel dengan menghujani Israel terutama Tel Aviv dan Haifa, Arab Saudi di Dhahran dengan serangan rudal Scud B buatan Sovyet rakitan Irak, serta melakukan perang lingkungan dengan membakar sumur sumur minyak di Kuwait dan menumpahkan minyak ke Teluk Persia. Sempat terjadi tawar-menawar perdamaian antara Uni Sovyet dengan Irak yang dilakukan atas diplomasi Yevgeny Primakov dan Presiden Uni Sovyet Mikhail Gorbachev namun ditolak Presiden Bush pada tanggal 19 Februari 1991. Sementara Sovyet akhirnya tidak melakukan tindakan apa pun di Dewan Keamanan PBB semisal mengambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak
mengambil serangan balasan atas Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada tanggal 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai.
Perang Teluk Pesawat tempur AS melintasi kilang minyak yang terbakar. Tanggal Lokasi Hasil Casus belli Pihak yang terlibat 2 Agustus 1990 28 Februari 1991 Teluk Persia Kemenangan mutlak koalisi, pembebasan Kuwait. Invasi Irak ke Kuwait.
Koalisi PBB
Irak
Komandan Norman Schwarzkopf Jumlah korban 378 tewas, 1.000 terluka 25.000 tewas, 75.000 terluka
Saddam Hussein Kekuatan 660.000 360.000
Pembantaian Massal di Rwanda
18 April 1984
Pada 18 April 1994 pejabat tinggi Rwanda mengumumkan terjadi pembantaian etnis di seluruh negeri. Konflik yang awalnya meletus di ibu kota Kigali itu dipicu tewasnya Presiden Juvenal Habyarimana dalam kecelakaan pesawat pada 6 April.
Sejak itu puluhan ribu orang tewas akibat konflik etnis antara suku Hutu dan Tutsi yang dituduh melancarkan serangan roket terhadap pesawat yang menewaskan Presiden Juvenal. Juru bicara Palang Merah Internasional, Jean-Luc Thevoc, mengatakan ratusan ribu warga Rwanda terpaksa mengungsi.
Sekitar 3.600 pemberontak dari Tutsi Rwanda Patriotic Front (RPF) telah mengepung ibu kota. Kelompok itu menyatakan akan terus melawan hingga pemerintah yang didominasi suku Hutu menghentikan pembantaian.
Pembantaian di Rwanda menewaskan 800.000 warga sipil suku Tutsi serta Hutu dan menempatkannya sebagai pembantaian terburuk di abad ke-20. Pembantaian berakhir pada Juli 1994, saat RPF berhasil menguasai Kigali.
Sekretaris Jenderal PBB Kofi Anan mengaku tidak cukup responsif untuk mengakhiri pembantaian di Rwanda. PBB akhirnya menggelar pengadilan internasional di Tanzania untuk menghukum pemimpin pembantaian. Selama 8 tahun pertama pengadilan itu baru berhasil menyeret 17 orang. Anggota milisi lain disidangkan di Rwanda, namun banyak yang hanya diadili melalui persidangan tradisional gacaca, sehingga ribuan tersangka dibebaskan.
Para korban yang selamat memprotes keras pembebasan para milisi tersebut. Pemerintah Rwanda menyatakan dibutuhkan 100 tahun untuk menyidangkan 120.000 orang yang ditangkap setelah pembantaian. (*)
Konflik Etnis Rwanda: Mutual-Genocide in Modern Era
Filed under: Keamanan Global by dennyprincess 1 Comment May 31, 2010
Denny L Sihombing, Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, 2010
The horror of Rwanda is too high a price to pay for a very vaporous and whimsical notion of what constitutes inviolable territorial boundaries ~Nigerian Nobel Literature Laureate Wole Soyinka, Los Angeles Times, 11 May 1994~ Ketika mendengar Rwanda dan konflik etnis yang terjadi hingga berujung pada Genosida di tahun 1994 hal pertama yang terbesit dalam benak kita adalah dua buah film yang cukup fenomenal Sometimes in April dan Hotel Rwanda, kedua film itu cukup menggambarkan situasi yang terjadi di Rwanda di tahun 1994. Akan tetapi, sebenarnya, kenyataan yang terjadi di lapangan lebih tragis dan kompleks dari apa yang kita bayangkan. Genosida[1] yang terjadi di Rwanda merupakan sebuah cerminan gagalnya negara menjamin keamanan internal dan perlindungan bagi warga negaranya. Rwanda menjadi sebuah failed state yang menjadi ancaman bagi warganegaranya sendiri, konflik Rwanda juga memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas kawasan Afrika dan menyita perhatian dunia internasional terkait dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan genosida. Konflik di Rwanda, awalnya dapat dikategorikan sebagai konflik internal, menyusul perebutan kekuasaan antara etnis Tutsi dan Hutu yang mengakibatkan perang sipil di tahun 1959. Akan tetapi konteks konflik internal dan konflik etnis di Rwanda menjadi hirauan internasional karena adanya upaya pemusnahan etnis secara besar-besaran. Rwanda merupakan salah satu negara di belahan Benua Afrika yang terdiri dari 3 kelompok etnis: Hutu (88%), Tutsi (11%), dan Twa pygmies (1%). Setidaknya ada beberapa faktor yang melatarbelakangi munculnya kebencian terhadap suku Tutsi dan akhirnya berujung pada Genosida. Pertama, fanatisme dari etnis Hutu muncul tidak lepas dari sakit hati dan reprisals methods suku Hutu yang mengalami marginalisasi dan stigmatisasi dimasa pendudukan Belgia
atas Rwanda dan perang sipil di tahun 1959. Di tahun 1961, partai gerakan emansipasi Hutu Parmehutu menang dalam referendum PBB. Pemerintahan Parmehutu, yang dibentuk sebagai hasil dari pemilihan umum tahun 1961 diberi jaminan otonomi oleh Belgia tanggal 1 Januari 1962. Juni 1962 resolusi Majelis Umum PBB mengakhiri pemerintahan Belgia dan memberikan kemerdekaan penuh atas Rwanda (dan Burundi) yang mulai berlaku sejak 1 Juli 1962. Kedua, setelah terjadi Perang Sipil di Rwanda tahun 1959, kebanyakan suku Tutsi terbang ke negara tetangga sebagai pengungsi, tekanan dan perang gerilya di negara mereka mengakibatkan mereka tidak dapat kembali ke Rwanda. Pengungsi yang tersebar di beberapa negara tetangga di Afrika ini kemudian membuat sebuah gerakan yang berpusat di Uganda dengan nama Rwandan Patriotic Front (RPF). RPF secara vocal menyerukan agar pemerintah Rwanda memperhatikan nasib jutaan pengungsi yang menjadi diaspora pasca perang sipil di tahun 1959. Gerakan pemberontak, terdiri dari etnis Tutsi yang menyalahkan pemerintah atas kegagalan demokrasi dan menyelesaikan permasalahan dari 500.000 pengungsi Tutsi yang hidup sebagai diaspora di penjuru dunia. Perang pertama muncul setelah gencatan senjata Arusha tanggal 12 juli 1992. Tanzania, melakukan upaya perundingan sebagai jalan mengakhiri pertikaian, memimpin kedamaian dan membagi kekuasaan, dan mengakuai adanya militer yang netral dalam organisasi Persatuan Afrika. Gencatan senjata efektif sejak 31 Juli 1992 dan pembicaraan politik dimulai tanggal 10 Agustus tahun 1992. Presiden Rwanda mulai melakukan perundingan Tripartite yang diadakan antara dua menteri luar negeri Rwanda dan Uganda dan perwakilan UNHCR di Kigali. Ketiga, media memainkan peranan yang signifikan dalam genosida di Rwanda, media lokal seperti surat kabar dan radio Radio Rwanda dan Radio Television Libre des Mille Collines (RTLM) dipercaya memulai pidato dan dialog-dialog yang berisi kebencian terhadap suku Tutsi, propaganda ini kemudian menjadi sangat sistematis dan berubah menjadi sebuah norma. Surat kabar yang dikuasai oleh negara Kangura memiliki peran pusat, memulai gerakan anti-Tutsi dan anti-RPF, surat kabar itu memuat artikel berisi tindakan yang harus dilakukan untuk melengkapi revolusi sosial di tahun 1959, di tahun 1990, ada artikel yang berisi The Hutus Commandments yang secara ekstrim menyatakan kebencian atas Tutsi. Keempat, operasi peacekeeping yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, United Nations Assistance Missions for Rwanda (UNAMIR), yang berusaha menjaga perdamaian pasca perundingan di tahun 1992 serta pengkondisian dan pemeliharaan wilayah Rwanda menyusul akan dipulangkannya 1 juta pengungsi Tutsi di tahun 1994 gagal, setelah Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana meninggal dalam kecelakaan pesawat di Bandara Kigali 6 April 1994. Rwanda menjadi sebuah failed state yang memiliki vacuum of power di negara itu, kendali kemudian diambil alih oleh kaum pemberontak yang akhirnya berujung pada genosida. Pembunuhan menyebar di Kigali dan seluruh pelosok negeri, genosida meluas kearah pembantaian 1 juta suku Tutsi dan Hutu moderat. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah militan Interahamwe those who attack together dan Impuzamugambi those with a single purpose. Militan genosida yang melakukan pembantaian atas Tutsi dan Hutu di tahun 1994 melanjutkan kampanye pemusnahan etnis dan mencoba memperluas operasi mereka melewati barat laut. Pemberontak bertanggung jawab atas sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk dalam membunuh siapa saja yang dianggap kontra genosida dan suku Hutu yang secara resmi menentang agenda mereka, sama halnya dengan pendeta dan para pekerja
kemanusiaan. Militan, terdiri dari sejumlah anggota bersenjata, pendiri Rwanda Armed Forces (ex-FAR) dan kelompok genosida Interahamwe, yang sering melakukan serangan terhadap kantor-kantor pemerintahan, institusi publik, seperti penjara, klinik, dan sekolah. Aksi ini meningkatkan friksi antara kekuatan keamanan dan populasi Hutu dan menimbulkan insecurity di jalanan. Bahkan masyarakat biasa dipaksa membunuh tetangga mereka oleh pemerintahan lokal yang disponsori oleh radio. Dalam kurun waktu 100 hari dari 6 April hingga 16 Juli 2004, diperkirakan 800.000 hingga 1 juta suku Tutsi dan Hutu moderat meninggal. Lebih dari 6 pria, wanita dan anak-anak dibunuh setiap menit setiap jam dalam setiap hari. Antara 250.000 dan 500.000 wanita mengalami kekerasan seksual. Sebanyak 20.000 anak-anak lahir dari tindakan itu. Lebih dari 67% wanita yang diperkosa terinfeksi HIV/AIDS. 75.000 yang selamat menjadi yatim piatu dan 40.000 lainnya tidak memiliki tempat tinggal. Rwanda tidak bisa melindungi masyarakatnya bahkan menjadi ancaman bagi warganegaranya sendiri. Genosida berakhir ketika RPF menguasai Kigali tanggal 4 Juli 1994 dan perang berakhir tanggal 16 Juli 1994. Sebanyak dua juta pengungsi terbang ke Kongo, Uganda, Tanzania, dan Burundi. Hal ini kemudian menimbulkan masalah baru bagi negara-negara perbatasan sehingga muncul krisis Danau besar dan munculnya Perang Kongo I dan II. Konflik perbatasan dan masalah pengungsi kemudian mlanda kawasan Danau Besar. Genosida yang terjadi di Rwanda merupakan tingkatan Genosida pertama dalam kategori mutual genocide karena baik Tutsi dan Hutu saling membunuh satu sama lain karena perbedaan etnis dan partai serta konflik kepentingan bebrapa pihak di negara itu. Korban yang sesungguhnya dalam kasus Genosida di Rwanda merupakan suku Tutsi, hampir 800.000 penduduk Rwanda yang terbunuh adalah suku Tutsi, mayat suku Tutsi dibuang ke sungai dan pembunuh mengatakan jika mereka akan dikirim kembali ke Ethiopia, tempat asal mereka. Negara lain juga turut andil dalam genosida yang melanda Rwanda, Perancis, disinyalir ingin mempertahankan pengaruh di Afrika, mulai menyediakan senjada dan mendukung pemerintah Rwanda, dan tentara meningkat dari 5000 menjadi 40.000 di bulan Oktober 1992. Mereka turut membantu Habyarimana untuk melakukan aksi penahanan terhadap 1000 lawan politik dan pembunuhan atas 350 Tutsi di perbatasan, bahkan melindungi pemberontak yang melakukan aksi genosida. Media internasional tidak melakukan tindakan apa-apa atas propaganda radio dan surat kabar, padahal media internasional Amerika Serikat lah yang memulai kebebasan pers dan media untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi di wilayah ini, akan tetapi tanggung jawab internasional akan masalah ini nampaknya berlawanan dengan prinsip demokrasi di satu sisi dan Hak Asasi Manusia di sisi lain. Genosida yang terjadi di Rwanda setidaknya menjadi agenda keamanan internasional karena genosida pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental manusia yang tercantum dalam piagam PBB. Genosida ini juga menjadi kejahatan kemanusiaan paling besar sepanjang abad-20 setelah Holocaust yang terjadi di Jerman. Konflik internal yang awalnya merupakan fanatisme antar suku berubah menjadi pembantaian manusia yang mengakibatkan eskalasi politik dan keamanan di kawasan juga meningkat bahkan menjadi concern dunia
internasional menyusul diadilinya para penjahat kemanusiaan di Rwanda di Pengadilan Kriminal Internasional dan perdebatan panjang akan term mutual-genocide dalam komunitas internasional. Konflik Rwanda sekaligus memberi pelajaran bagi komunitas internasional untuk mengutamakan sendi-sendi kemanusiaan dan mewaspadai mutual genocide dalam era modern. Genosida di Rwanda menjadi sebuah bukti jika moralitas, hukum internasional bahkan komunitas internasional sendiri gagal dalam melakukan upaya-upaya pencegahan terkait dengan keamanan internal suatu negara yang harusnya menjadi concern dunia internasional karena menyangkut Hak Asasi Manusia. REFERENSI Berry, J. and C Pott Berry (eds), (1999), Genocide in Rwanda: A Collective Memory, Howard Univ Press, Washington. Jeroen K. van Ginneken, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, The Hague and School of Health Systems and Public Health, Univ. of Pretoria, and Margreet Wiegers, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute
5,4 Juta Orang Tewas dalam Konflik Kongo Oleh: Rabu, 23 Januari 2008 | 03:00 WIB INILAH.COM, Nairobi - Perang, penyakit dan kekurangan gizi telah menewaskan sekitar 5,4 juta orang di Kongo sejak 1998, dan itu merupakan angka kematian tertinggi yang berkaitan dengan konflik sejak Perang Dunia II, kata sebuah kelompok kemanusiaan internasional. Komite Penyelamatan Internasional (IRC) yang berpusat di New York menyatakan, sekitar 45.000 orang tewas setiap bulan di negara Afrika tengah yang luas itu, bahkan setelah berakhirnya perang lima tahun pada 2003, dan pemulihan diri dari konflik brutal itu merupakan sebuah "proses yang berlarut-larut". "Jumlah kematian Kongo itu setara dengan seluruh penduduk Denmark atau negara bagian Colorado yang tewas dalam satu dasawarsa. Meski perang Kongo berakhir secara resmi lima tahun lalu, kekerasaan yang terus berlangsung dan kemiskinan terus merenggut jiwa," kata ketua kelompok itu, George Rupp. Mayoritas dari korban-korban itu tewas karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah dan bisa dirawat seperti malaria, diare, pneumonia dan kekurangan gizi, kata kelompok itu. Survei yang dilakukan antara Januari 2006 dan April 2007 itu berakhir segera setelah kekerasan
di provinsi bergolak North Kivu meletus, dan karenanya jumlah kematian mungkin lebih tinggi dan terus naik. Pemberontak timur dan pemerintah dijadwalkan menandatangani sebuah perjanjian perdamaian di ibukota provinsi itu Goma pada Selasa, sebuah langkah berarti untuk mengakhiri konflik yang kejam itu. Lebih dari 700.000 orang tewas akibat krisis kemanusiaan atau konflik bersenjata selama periode survei IRC itu, dan hampir separuh dari mereka anak-anak di bawah usia lima tahun. Kongo bangkit dari kekuasaan kleptokratis puluhan tahun setelah penggulingan diktator Mobutu Sese Seko oleh pemberontak pada 1997, yang membuat negara itu terjeblos ke dalam perang yang menyeret sedikitnya enam militer asing. Rakyat Kongo mengadakan pemilihan umum bersejarah pada 2006 yang mengantarkan Presiden Joseph Kabila ke tampuk kekuasaan. Namun pemerintahnya, yang dituduh melakukan korupsi, lamban menangani krisis kemanusiaan dan meski negara itu memiliki kekayaan mineral yang besar, rakyatnya tetap hidup dalam kemiskinan yang parah.
Konflik Kongo Renggut 5,4 Juta Jiwa
Kamis, 24 Januari 2008 15:45 wib
BUKAVU - Komite Penyelamatan Internasional (IRC) dalam laporannya dini hari tadi mengungkapkan konflik internal di Republik Remokrat Kongo yang terjadi sejak 1998 dilaporkan telah menewaskan 5,4 juta jiwa. IRCjuga menyatakan sebanyak 45.000 warga tewas setiap bulan. "Jumlah korban tewas di Kongo sama seperti seluruh populasi Denmark atau negara bagian Colorado di Amerika Serikat (AS). Ini merupakan salah satu bencana terburuk di dunia," tutur Presiden IRC George Rupp, Kamis (24/1/2008). Rupp menambahkan, sebagian besar korban tewas bukan karena aksi kekerasan, melainkan berbagai penyakit yang mewabah akibat krisis kemanusiaan di negeri itu.
"Konflik berkepanjangan itu menyebabkan banyak warga, terutama wanita, anak-anak, dan manula meninggal dunia karena malaria, diare, pneumonia, dan gizi buruk," jelasnya. Sementara itu, Peter Kessler dari UNHCR -badan di Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi masalah pengungsi menyatakan, dini hari tadi, pemerintah Kongo dan sejumlah kelompok bersenjata di negeri itu telah menandatangani kesepakatan damai. Perdamaian itu terwujud setelah kedua belah pihak terlibat pembicaraan selama dua pekan di Goma. "Saya belum tahu pasti detail kesepakatan damai yang dibuat pemerintah dan pemberontak. Namun, ini adalah pertanda baik untuk membangun kembali Kongo," jelas Kessler. (Sindo Sore//jri)
Anda mungkin juga menyukai
- Darvi Juliansyah (1112011095)Dokumen10 halamanDarvi Juliansyah (1112011095)Gilang Fardes PratamaBelum ada peringkat
- ,tugas Sejarah MinatDokumen29 halaman,tugas Sejarah MinatNinja ProteamBelum ada peringkat
- 38.konflik Di DuniaDokumen8 halaman38.konflik Di DuniaArisBelum ada peringkat
- Konflik RwandaDokumen4 halamanKonflik RwandaAulia FajardiniBelum ada peringkat
- Fiza Fathima Azzahra Zaky (17) Sej - MinatDokumen7 halamanFiza Fathima Azzahra Zaky (17) Sej - MinatFiza fathima AzzahraBelum ada peringkat
- Timur TengahDokumen7 halamanTimur TengahDetiran NadaBelum ada peringkat
- MAKALAH Michael SejarahDokumen20 halamanMAKALAH Michael Sejarahtheresialorens56Belum ada peringkat
- PrintDokumen15 halamanPrintMuhammad IrvanBelum ada peringkat
- Kisah Kelam Genosida RwandaDokumen9 halamanKisah Kelam Genosida RwandaSahrul rohman SahrulBelum ada peringkat
- Dinda Maylani 12 Ips 2 Perang TelukDokumen3 halamanDinda Maylani 12 Ips 2 Perang TelukHarfitrah HadjirBelum ada peringkat
- Sejarah Singkat Perang TelukDokumen3 halamanSejarah Singkat Perang Telukangelina audreyBelum ada peringkat
- Bab 8 SejarahDokumen20 halamanBab 8 SejarahTeguh RismaBelum ada peringkat
- SejarahDokumen12 halamanSejarahT Ara AgathaBelum ada peringkat
- Sejarah Kontemporer Dan PengaruhnyaDokumen36 halamanSejarah Kontemporer Dan PengaruhnyaNurani FuspawitaBelum ada peringkat
- MAKALAHDokumen10 halamanMAKALAHSATRIA BANTEN KOTA TANGERANGBelum ada peringkat
- Pelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Pada Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina (Kelompok 2)Dokumen23 halamanPelanggaran Terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Humaniter Pada Konflik Bersenjata Antara Rusia Dan Ukraina (Kelompok 2)Yosua Sihotang100% (1)
- Tugas PPT Kelompok Pa SampeDokumen20 halamanTugas PPT Kelompok Pa SampeFathia Nur100% (1)
- Konflik Rusia Vs UkrainaDokumen2 halamanKonflik Rusia Vs UkrainakamalnazhanBelum ada peringkat
- Rwanda - Hukum Pidana InternasionalDokumen14 halamanRwanda - Hukum Pidana InternasionalAyu AngreniBelum ada peringkat
- Genosida RwandaDokumen10 halamanGenosida RwandaArrol VastieBelum ada peringkat
- Tugas Individu Sejarah Peminatan (Resume)Dokumen3 halamanTugas Individu Sejarah Peminatan (Resume)Tiffany SetiawanBelum ada peringkat
- Sejm 190122Dokumen29 halamanSejm 190122ReinaldydaffaBelum ada peringkat
- Aftermid 4Dokumen11 halamanAftermid 4Salvia EmilianaBelum ada peringkat
- Tugas Analisis GenosidaDokumen8 halamanTugas Analisis GenosidaSofi SilalahiBelum ada peringkat
- Perang Teluk 2Dokumen2 halamanPerang Teluk 2Najma SyarifahBelum ada peringkat
- Sejarah Indonesia - Perkembangan Mutakhir DuniaDokumen12 halamanSejarah Indonesia - Perkembangan Mutakhir DuniaMelvianaBelum ada peringkat
- Peran Indonesia Dalam Perang DinginDokumen5 halamanPeran Indonesia Dalam Perang DinginDesmi Yunaini idBelum ada peringkat
- Makalah Perang Dunia 2Dokumen14 halamanMakalah Perang Dunia 2Mochamad Dudy WijayaBelum ada peringkat
- Konflik Di AsiaDokumen5 halamanKonflik Di AsiaRini AstutiBelum ada peringkat
- Makalah Konflik Timur TengahDokumen14 halamanMakalah Konflik Timur Tengahnayla almahyra100% (2)
- Perbudakan, Perang Saudara, Dan IndustrialisasiDokumen45 halamanPerbudakan, Perang Saudara, Dan IndustrialisasiAzzahra AfifahBelum ada peringkat
- Kisi Kisi Pts PM Sej Kls 12Dokumen5 halamanKisi Kisi Pts PM Sej Kls 12jt6qp42dcpBelum ada peringkat
- Tugas Sejarah Peminatan - Adha Cinde Balqis C F Bab 6Dokumen8 halamanTugas Sejarah Peminatan - Adha Cinde Balqis C F Bab 6vitoboy017Belum ada peringkat
- Materi Perang Teluk 2Dokumen2 halamanMateri Perang Teluk 2Azis RamadhanBelum ada peringkat
- PPTDokumen21 halamanPPTYasBelum ada peringkat
- Perang Teluk I, Ii, IiiDokumen14 halamanPerang Teluk I, Ii, IiiSalsabila Suci WibowoBelum ada peringkat
- Perang Teluk 2Dokumen2 halamanPerang Teluk 2Addhiya UlhaqBelum ada peringkat
- Sejarah BDokumen6 halamanSejarah BMGen 13Belum ada peringkat
- HAM InternasionalDokumen9 halamanHAM InternasionalAnonymous wqZcLiqBelum ada peringkat
- E-BOOK Yang Tidak Mereka Bilang PDFDokumen76 halamanE-BOOK Yang Tidak Mereka Bilang PDFKhun Ardi PatiBelum ada peringkat
- Pengaruh Perang Dunia I: KelasDokumen5 halamanPengaruh Perang Dunia I: KelasUniquestore06Belum ada peringkat
- Perkembangan Mutakhir Sejarah DuniaDokumen3 halamanPerkembangan Mutakhir Sejarah DuniaAyam Hutan HijauBelum ada peringkat
- Analisis Konflik RwandaDokumen11 halamanAnalisis Konflik RwandaMasykur Rahim100% (2)
- Perang Dunia IIDokumen4 halamanPerang Dunia IIKhoerul AmriBelum ada peringkat
- Pelanggaran Hukum Humaniter Di RwandaDokumen5 halamanPelanggaran Hukum Humaniter Di RwandaCindy Ananda100% (1)
- Materi Sejarah DuniaDokumen20 halamanMateri Sejarah DuniaEndenim EkakBelum ada peringkat
- Konflik Palestina-Israel+Revolusi MelatiDokumen32 halamanKonflik Palestina-Israel+Revolusi MelatiSindy stevanyBelum ada peringkat
- Assignmnet Perang DinginDokumen28 halamanAssignmnet Perang DinginRafie100% (3)
- Perang Dunia IiDokumen7 halamanPerang Dunia IiMuhammad Haidar HilmyBelum ada peringkat
- Sejarah Perang DinginDokumen5 halamanSejarah Perang DinginHasna RaniaBelum ada peringkat
- IsraelDokumen7 halamanIsraelHilwa Nafal MuyassarBelum ada peringkat
- Perang Dunia IIDokumen24 halamanPerang Dunia IILukas Indra Prasetio NugrohoBelum ada peringkat
- Dampak Positif Perang Dunia 1 & 2 TerhadapDokumen23 halamanDampak Positif Perang Dunia 1 & 2 Terhadaprichkyutama50% (6)
- Genosida Rwanda Terjadi Pada 7 April 1994 Sampai 15 Juli 1994Dokumen2 halamanGenosida Rwanda Terjadi Pada 7 April 1994 Sampai 15 Juli 1994Syarif HidayatullahBelum ada peringkat
- Konflik Timur Tengah1Dokumen8 halamanKonflik Timur Tengah1Suci Selva SBelum ada peringkat
- Perang Teluk IDokumen12 halamanPerang Teluk IAflah Sofa100% (1)
- Kelompok AglonemaDokumen6 halamanKelompok AglonemaFasya AdityaBelum ada peringkat
- Kel 6 S MinatDokumen14 halamanKel 6 S Minatshifameylany4Belum ada peringkat
- Anayya Nailah A - Tugas Sejarah Kontemporer DuniaDokumen5 halamanAnayya Nailah A - Tugas Sejarah Kontemporer DuniaAnayya nailahBelum ada peringkat