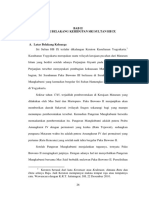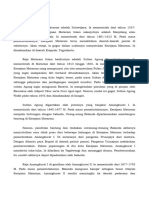Perjanjian Giyanti
Diunggah oleh
gutta21Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Perjanjian Giyanti
Diunggah oleh
gutta21Hak Cipta:
Format Tersedia
Latar belakang[sunting
| sunting sumber]
Perjanjian ini merupakan hasil utama dari Perang Takhta Jawa Ketiga pada tahun 1749–
1757. Pakubuwana II, susuhunan Mataram, telah mendukung pemberontakan Tionghoa
melawan Belanda.[4] Pada tahun 1743, sebagai pembayaran untuk pemulihan kekuasaannya,
sunan menyerahkan pantai utara Jawa dan Madura kepada Perusahaan Hindia Timur Belanda.
Pakubuwana III didukung kompeni menggantikan takhta setelah wafatnya Pakubuwana II,
namun ia harus menghadapi saingan ayahnya, Pangeran Sambernyawa, yang pernah
menduduki suatu daerah bernama Sukawati, sekarang Sragen. Pada tahun 1749 Pangeran
Mangkubumi, adik Pakubuwana II, yang tidak puas dengan kedudukannya yang lebih rendah,
bergabung dengan Pangeran Sambernyawa dalam menentang Pakubuwana III. VOC mengirim
pasukan untuk membantu Pakubuwana III, tetapi pemberontakan terus berlanjut. Baru pada
tahun 1755 Pangeran Mangkubumi melepaskan diri dari Pangeran Sambernyawa dan menerima
tawaran perdamaian di Giyanti, yang membagi Mataram menjadi dua bagian.[5] Pangeran
Sambernyawa baru menandatangani perjanjian dengan VOC pada tahun 1757
melalui Perjanjian Salatiga, yang memberinya hak untuk memiliki bagian dari timur Mataram. Ia
kemudian bergelar sebagai Mangkunegara I.
Perundingan[sunting | sunting sumber]
Lokasi penandatanganan Perjanjian Giyanti di Karanganyar, Jawa Tengah.
Menurut catatan harian Nicolaas Hartingh, Gubernur Jenderal VOC untuk Jawa Utara, pada
tanggal 10 September 1754 ia berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi.
Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terlaksana pada tanggal 22
September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan tertutup yang hanya dihadiri oleh
beberapa orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran
Natakusuma dan Tumenggung Ronggo. Hartingh sendiri didampingi oleh Breton, Kapten C.
Donkel, dan sekretarisnya, W. Fockens. Adapun yang menjadi juru bahasa adalah
pendeta Bastani.[6]
Pada pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram, Hartingh menyatakan keberatan
karena tidak mungkin ada dua pemimpin dalam satu kerajaan. Mangkubumi menyatakan bahwa
di Cirebon ada lebih dari satu sultan. Hartingh pun menawarkan Mataram sebelah timur yang
ditolak oleh Mangkubumi. Perundingan berjalan kurang lancar karena masih ada kecurigaan di
antara mereka. Akhirnya, setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka
pembicaraan dapat berjalan lancar. Hartingh kembali mengusulkan agar Mangkubumi tidak
menggunakan gelar susuhunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai olehnya.
Mangkubumi keberatan melepas gelar susuhunan karena rakyat telah mengakuinya sebagai
susuhunan sejak lima tahun sebelumnya. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai susuhunan
di daerah Kabanaran ketika Pakubuwana II wafat, bersamaan saat VOC melantik Adipati Anom
menjadi Pakubuwana III.
Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada tanggal 23 September
1754 akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai
gelar sultan dan mendapatkan setengah bagian kesultanan. Daerah pantai utara Jawa
atau daerah pesisiran yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai oleh VOC dan setengah
bagian ganti rugi atas penguasaan tersebut akan diberikan kepada Mangkubumi. Selain itu,
Mangkubumi juga akan memperoleh setengah pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman
tersebut kemudian disampaikan kepada Pakubuwana III. Pada tanggal 4 November
1754, Pakubuwana III menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob
Mossel mengenai persetujuannya tehadap hasil perundingan antara Hartingh dan Pangeran
Mangkubumi.
Berdasarkan perundingan yang dilakukan pada tanggal 22-23 September 1754 dan surat
persetujuan Pakubuwana III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatanganilah Perjanjian
di Giyanti.[7]
Anda mungkin juga menyukai
- Perjanjian Giyanti Antara VOC Dan MataramDokumen4 halamanPerjanjian Giyanti Antara VOC Dan MataramtorrackabillyBelum ada peringkat
- Buku 3 - Kala Mataram TerbelahDokumen35 halamanBuku 3 - Kala Mataram Terbelahken astrasasmitaBelum ada peringkat
- Hamengku Buwono 1Dokumen4 halamanHamengku Buwono 1Ananda Prasetia ManurungBelum ada peringkat
- Keruntuhan Mataram IslamDokumen4 halamanKeruntuhan Mataram IslamFarizca Novantia Wahyuningtyas100% (2)
- Kapitulasi TuntangDokumen4 halamanKapitulasi Tuntangfayuang0% (1)
- Perjanjian Giyanti Dan Salatiga 2013 HSMGDokumen20 halamanPerjanjian Giyanti Dan Salatiga 2013 HSMGMia Ari AndayaniBelum ada peringkat
- Sejarah IndoooooooDokumen5 halamanSejarah IndoooooooNandiya HadrayniBelum ada peringkat
- Tugas SejarahDokumen5 halamanTugas Sejarahdani msBelum ada peringkat
- Tugas Agama IslamkuDokumen14 halamanTugas Agama Islamku440 250Nurul Inas AzizahBelum ada peringkat
- Perlawanan Mangkubumi Mas SaidDokumen2 halamanPerlawanan Mangkubumi Mas SaidSyahla SalsabillaBelum ada peringkat
- Isi Perjanjian SejarahDokumen2 halamanIsi Perjanjian SejarahArek JoblengBelum ada peringkat
- Perlawanan Mangkubumi Dan Mas SaidDokumen2 halamanPerlawanan Mangkubumi Dan Mas SaidDeri SetiawanBelum ada peringkat
- Peta Politik Indonesia Pada Akhir Abad 18Dokumen3 halamanPeta Politik Indonesia Pada Akhir Abad 18Fauzul AzimBelum ada peringkat
- Perjanjian GiyantiDokumen2 halamanPerjanjian GiyantiRio BetrianBelum ada peringkat
- BCG MatriksDokumen13 halamanBCG MatriksNovia Nurassiam21Belum ada peringkat
- Sji Mataram IslamDokumen12 halamanSji Mataram IslamMuhammad Rizki Akbar RizkyakbarBelum ada peringkat
- Sri Sultan Hamengku Buwono IDokumen6 halamanSri Sultan Hamengku Buwono ILali JenengBelum ada peringkat
- PPTDokumen11 halamanPPTsoniaBelum ada peringkat
- Perlawanan Pangeran Mangkubumi Dan Mas SaidDokumen4 halamanPerlawanan Pangeran Mangkubumi Dan Mas SaidIvan Holicckzz100% (1)
- Keraton SoloDokumen13 halamanKeraton SoloHaryadi NugrohoBelum ada peringkat
- Betha Mataram IslamDokumen8 halamanBetha Mataram IslamVita Aulia RamadhaniBelum ada peringkat
- Kesultanan MataramDokumen23 halamanKesultanan MataramRangga PermadiBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Kelompok 2Dokumen6 halamanTugas Makalah Kelompok 2APRI ASTUTIBelum ada peringkat
- Sejarah Lengkap Kerajaan Mataram IslamDokumen5 halamanSejarah Lengkap Kerajaan Mataram IslamArdy JauhariBelum ada peringkat
- Sejarah L Kerajaan Mataram IslamDokumen7 halamanSejarah L Kerajaan Mataram IslamBang JemsBelum ada peringkat
- Mangku Negara 1Dokumen3 halamanMangku Negara 1Muhammad Mirza NaufalBelum ada peringkat
- Perjanjian SalatigaDokumen1 halamanPerjanjian SalatigaIrone Siburian100% (1)
- Perang Suksesi Jawa 3Dokumen5 halamanPerang Suksesi Jawa 3SalmaBelum ada peringkat
- Kasunanan SurakartaDokumen12 halamanKasunanan SurakartaNilma YolaBelum ada peringkat
- Sejarah Lengkap Kerajaan Mataram IslamDokumen11 halamanSejarah Lengkap Kerajaan Mataram IslamDyraChizuBelum ada peringkat
- Lembar Kerja Bab 2Dokumen7 halamanLembar Kerja Bab 2Nandiya HadrayniBelum ada peringkat
- Pakubuwana II - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia BebasDokumen8 halamanPakubuwana II - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia BebasFreddy PasaribuBelum ada peringkat
- Sejarah MantapDokumen15 halamanSejarah Mantap28X MIPA 6 Satrio Bagus PrakosoBelum ada peringkat
- Raja YogyaDokumen10 halamanRaja Yogyakas perbendaharaanBelum ada peringkat
- Kerajaan Mataram IslamDokumen21 halamanKerajaan Mataram IslamStephanieAgiBelum ada peringkat
- Mangkubumi Dan Mas Said + Perang Batak - TUGAS SEJARAH INDONESIADokumen11 halamanMangkubumi Dan Mas Said + Perang Batak - TUGAS SEJARAH INDONESIAIlham AningBelum ada peringkat
- Perlawanan Raden Mas SaidDokumen2 halamanPerlawanan Raden Mas SaidAlfian Silvia KrisnasariBelum ada peringkat
- Perlawanan Pangeran Mangkubumi Dan Mas Said Terhadap VOCDokumen3 halamanPerlawanan Pangeran Mangkubumi Dan Mas Said Terhadap VOCTiffanAzhimiMarseno100% (1)
- Perlawanan Pangeran Mangkubumi Dan Masaid: A. Latar Belakang Penyebab Terjadinya PerlawananDokumen3 halamanPerlawanan Pangeran Mangkubumi Dan Masaid: A. Latar Belakang Penyebab Terjadinya Perlawanannovita leliBelum ada peringkat
- Mataram IslamDokumen13 halamanMataram IslamIfhaBelum ada peringkat
- DOC-20230202-WA0027. Contoh ProposalDokumen2 halamanDOC-20230202-WA0027. Contoh ProposalDewi RahmawatiBelum ada peringkat
- Perlawanan Mangkubumi Dan Mas SaidDokumen2 halamanPerlawanan Mangkubumi Dan Mas SaidIvan HartanaBelum ada peringkat
- TUGAS SEJARAH WAJIB Perlawanan Angkubumi Dan Mas Said Terhadap VocDokumen5 halamanTUGAS SEJARAH WAJIB Perlawanan Angkubumi Dan Mas Said Terhadap Voccuman peralihanBelum ada peringkat
- Kesultanan MataramDokumen17 halamanKesultanan MataramSidiq PambudiBelum ada peringkat
- Wikipedia Kerajaan MataramDokumen5 halamanWikipedia Kerajaan MataramAFIFUDDIN F.A.DBelum ada peringkat
- Perlawanan Pangeran Mangku BmiDokumen8 halamanPerlawanan Pangeran Mangku BmiandifauzannBelum ada peringkat
- Biografi Pangeran MangkubumiDokumen3 halamanBiografi Pangeran MangkubumishintaBelum ada peringkat
- Biografi Pangeran MangkubumiDokumen3 halamanBiografi Pangeran MangkubumiAghaEppranBelum ada peringkat
- Kerajaan Mataram IslamDokumen8 halamanKerajaan Mataram Islamaradhana ghinaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen16 halamanBab Iialzaliza81Belum ada peringkat
- Endah Tugas Hukum Perjanjian InternasionalDokumen4 halamanEndah Tugas Hukum Perjanjian InternasionalEndah PurnamaBelum ada peringkat
- Perlawanan Perang Mangkubumi Dan Mas SaidDokumen2 halamanPerlawanan Perang Mangkubumi Dan Mas SaidAlLouys Kolatlena0% (1)
- Kerajaan MataramDokumen2 halamanKerajaan MataramSeha PrintingBelum ada peringkat
- Amangkurat IDokumen5 halamanAmangkurat IHan ReihanBelum ada peringkat
- Matar AmDokumen2 halamanMatar AmNabila RachmawatiBelum ada peringkat
- Tugas SiDokumen1 halamanTugas Siauliaml999Belum ada peringkat
- Kerajaan IslamDokumen19 halamanKerajaan IslamEmannuel Pratita Kharisma SaktaBelum ada peringkat
- Kutai KertanegaraDokumen8 halamanKutai KertanegaraDininrBelum ada peringkat