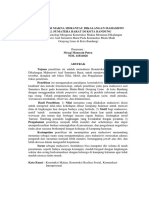Merawat Ingatan Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau
Merawat Ingatan Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau
Diunggah oleh
Adelia Aryani PutriHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Merawat Ingatan Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau
Merawat Ingatan Filosofi Marantau Di Dalam Pantun Minangkabau
Diunggah oleh
Adelia Aryani PutriHak Cipta:
Format Tersedia
SASDAYA e-ISSN: 2549-3884
e-mail: sasdayajournal.fib@ugm.ac.id
Gadjah Mada Journal of Humanities
MERAWAT INGATAN: FILOSOFI MARANTAU
DI DALAM PANTUN MINANGKABAU
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti
E-mail: sitiainim@fbs.unp.ac.id
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
ABSTRACT
Wandering for Minangkabaunese people is to go away from their
hometown to gain experience. After having successful, they have to
return to their hometown in order to develop it and lift the dignity of
their family and people. However, due to the current development, the
goals of wandering has changed. The goals are not to: 1) because of the
matrilineal system where men do not get inheritance property rights,
only the right of managing. 2) Continuing the success of previous
nomads and natural conditions. 3) Adding Life Experience (educational
factors) 4) Improving the economic and social status of families and
people, 5) marantau cino. All of these forms and reasons for wandering,
each of which has its own philosophy for the people of Minangkabau
which is conveyed through poems.
Key words: preserve memory, philosophy of wander, poem
of Minangkabau.
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
PENGANTAR
Karatau madang di hulu
Babuah babungo balun
Karantau bujang daulu
Dirumah paguno alun
Pepatah di atas bagi masyarakat Minangkabau meresap ke dalam ruang
terdalam dari dirinya (jiwanya). Bahkan pepatah di atas dapat mewakili gejolak jiwa
masyarakat Minangkabau. Pada titik tertentu, pepatah itu menjadi spirit orang
Minangkabau untuk mencari penghidupan baru yang lebih baik di negeri (rantau).
Seorang pemuda atau bujangan di kampung belumlah dibutuhkan sebagai niniak
mamak (pemimpin) dalam kaum karena keterbatasan ilmu dan pengalaman
hidupnya. Seseorang yang memimpin kaum atau keluarga harus kaya dengan
khasanah ilmu dan pengalaman, bersikap bijaksana, dan berbuat sebelum berkata.
Seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran pola perantau orang
Minang. Sebelum kemerdekaan, yang pergi merantau hanya diperuntukkan bagi
laki-laki. Hal ini mengingat dan menimbang keamanan bagi perantau perempuan
kurang baik, sebab di rantau akan menemukan medan yang berbahaya dan kondisi
keamanan yang tidak baik. Setelah kemerdekaan, kondisi daerah rantau sudah
membaik, maka para perantau sudah mulai berangsur-angsur membawa keluarga
atau saudara perempuan ke perantauan dengan berbagai alasan. Untuk itu, penulis
merasa perlu menjelaskan beberapa alasan orang Minang pergi merantau.
Istilah ‘merantau’ berarti meninggalkan kampung halaman atau
meninggalkan tanah kelahiran (Koto, 2005 :13). Filosofi rantau terkandung dari
berbagai aspek dan simbol kehidupan orang Minang. Kondisi hidup di kampung
halaman yang serba susah ikut mendorong orang Minang untuk membangun hidup
di negeri orang. Ada prinsip yang amat menarik bagi orang Minangkabau sebelum
melangkahkan kaki ke perantauan. Orang Minang tempo dulu pantang baginya
tinggal di kampung. Biarlah pergi dengan berbekal sehelai baju tanpa modal uang (jo
tulang salapan karek). Aib bagi mereka pulang dengan tangan kosong, ia takkan
pulang sebelum berhasil. Kendatipun hidup di perantauan tidur beralaskan dengan
sehelai koran.
Mereka yang merantau, memiliki kehidupan yang sama dengan kehidupan
orang lain. Di antara mereka, ada yang kaya raya, ada yang memiliki jabatan tinggi,
jadi pengusaha besar, menengah, dan kecil. Yang tidak berhasil juga banyak. Akan
tetapi bagi yang tidak berhasil ada satu kebanggaan dalam diri mereka. Ia tidak
menghabiskan segala yang dipusakai di kampung halaman dan mereka sudah
mencoba berjuang di negeri lain sebatas kemampuan yang mereka miliki.
Begitu kuat jiwa perantau bagi orang Minangkabau, sehingga tidak
mengherankan jika banyak orang Minang yang pada awalnya hanya berjualan di
kaki lima menjadi kaya raya dengan bermodalkan ketekunan dan keuletan. Oleh
sebab itulah tidak sedikit perantau asal Minang menempati posisi penting di
kawasan nusantara bahkan sampai ke Malaysia, Brunai, Thailand dan ke negara
lainnya. Dimanapun perantau Minang berada ia harus bisa menyesuaikan diri,
seperti pepatah “ dima bumi dipijak, di sinan langik di jujuang” / “dimana bumi dipijak,
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 14
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
disana langit di junjung” bajalan di tapi-tapi, mandi di baruah-baruah”/ berjalan di
pingir-pinggir, mandi di bagian bawah aliran sungai” (Hakimy. 2004). Artinya,
mereka harus mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di tempat yang
mereka tuju, menghindari semua bentuk perselisihan yang menimbulkan
perselisihan dengan penduduk setempat.
Konsep dagang yang tak mau diperintah menjadikan orang Minang untuk
mandiri. Dalam arti positif, orang Minang lebih suka hidup sederhana asalkan
jiwanya merdeka, dari pada hidup kaya tetapi jiwa terjajah. Barangkali inilah yang
melatarbelakangi banyak orang Minang yang bergerak di bidang dagang. Namun,
pergi merantau bukan berarti meninggalkan kampung halaman begitu saja atau lari
dari kehidupan, tetapi pergi untuk kembali dengan kondisi lebih baik. Hal ini
dinyatakan dalam pantun berikut ini.
Baduri-duri tabang manau
salaronyo babuang juo
Satinggi-tinggi tabang bangau
Inggoknyo kakubangan juo
Sakanyang-kanyang bantiang
rumpuik dimamahnyo juo
sajauh-jauh malantiang
suruiknyo ka ranah juo
Selaian itu, orang Minang pergi merantau adalah karena mencintai kampung
halaman. Dalam hal ini falsalah adat menyatakan,” Sayang dianak dilacuti, sayang
dikampuang ditinggakan”. Falsafah ini menganalogikan kalau sayang dengan anak,
maka ketika salah, mereka harus diingatkan agar kelak dia lebih baik, sementara
sayang dengan kampung ditinggalkan supaya suatu hari bisa memberikan yang
terbaik setelah kembali dari rantau, sebab jika tidak merantau, tentu sulit
membangun kampung halaman tempat mereka tumbuh menjadi dewasa. Aspek lain
dari merantau yang terekam dalam tradisi lisan (pantun) yang bertema “merantau”
adalah upaya masyarakat Minangkabau merawat dan mewariskan ingatan kultural-
nya sepanjang hayat. Dalam konteks itulah tulisan ini hadir dengan mengemukakan
sisi lain dari “misi” masyarakat mewariskan kebudayaannya melalui pantun. Dalam
ilmu antropologi, praktik seperti itu dinamakan dengan antropology terapan atau
dalam sastra disebut dengan sosio-linguistik.
PERAN PERANTAU DALAM MASYARAKAT
Budaya merantau mengharuskan anak-anak muda Minangkabau untuk
mengasah ilmu dan mencari pengalaman serta berhasil dulu di rantau baru bisa
menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan
demikian, merantau lebih dari sekadar migrasi penduduk dari daerah asal ke daerah
tujuan sebagaimana teori dalam demografi. (Nasroen, 1971). Sesampainya mereka di
rantau mereka harus bisa menyesuiakan diri dengan lingkungan tempat mereka
tinggal. Seperti pantun berikut.
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 15
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
Dima bumi dipijak disinan langik di junjuang
Dima sumua digali di sinan aia di sauak
Dima rantau diuni disinan adaik dipakai
(dimana bumi dipijak, di sana langit dijunjung
Dimana sumur digali, di sana air ditimba
Dimana daerah ditempati, di sana adat dipakai)
Perantau Minang tidak hanya peduli pada kelompoknya saja. Banyak di
antara mereka menjadi tokoh masyarakat setempat, berikhtiar dan berjuang bersama
dengan masyarakat sekitar. Beberapa tokoh Minang yang ikut berperan membangun
bangsa seperti Muhammada Hatta, dan Tan Malaka misalnya, (Koto, 2015). Senada
dengan itu, Rajab (1950), mengemukakan bahwa orang Minang” Kecil di kampung,
besar di rantau”. Maka boleh dikatakan secara tidak langsung budaya merantau
memiliki andil dalam melahirkan tokoh-tokoh kaliber nasional asal Minang.
Semenjak menjelang kemerdekaan Minangkabau adalah negeri yang paling banyak
mencetak tokoh-tokoh pemimpin agama dan bangsa
Pada masa sekarang, para perantau Minang telah memberikan sumbangan
yang cukup besar untuk kehidupan masyarakat di Sumatera Barat (ranah Minang)
itu sendiri. Beberapa tokoh perantau yang hidup di perantauan, mereka mendirikan
lembaga sosial yang dikenal dengan ‘Gebu Minang atau gerakan seribu Minang
pada tahun 1990 yang tetap bertahan sampai sekarang. Gerakan gebu Minang ini
memberikan sumbangan untuk pembangunan berbagai sarana umum di Ranah
Minang.
Ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan, perantau asal
Minangkabau yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dan di luar negeri,
merupakan aset terbesar daerah Provinsi Sumatera Barat. Kontribusi ekonomi
perantau Minang terhadap daerah asal mereka, cukup signifikan. Dengan kata
lain, kontribusi dan implikasi dari para perantau menjadi faktor penting bagi
pembangunan di Sumatera Barat.
BEBERAPA ALASAN UNTUK MERANTAU
Bagi pemuda Minagkabau, merantau merupakan suatu budaya yang sudah
mendarah daging. “Di saat kehidupan yang serba berkeadaan ini, dimana segalanya
ada dan cukup sesuai dengan kebutuhan manusia pada zamannya, maka kekayaan
yang ada pada dirinya hendaklah bermanfaat untuk keselamatan hidup”. seperti
falsafah, “dek ameh sagalo kameh, dek padi sagalo jadi” artinya kekayaan alam itu
bermanfaat untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan (Thamrin, 2007: 422).
Pada masa sekarang, dengan tuntutan kebutuhan yang meingkat, umumnya
mereka yang merantau memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan secara
finansial. Akan tetapi ada beberapa alasan yang berbeda, sehingga mereka
memutuskan untuk merantau meninggalkan keluarga dan karib kerabat.
Menurut Naim (1984), istilah merantau sedikitnya mengandung enam unsur
pokok yakni; (1) meninggalkan kampung halaman, (2) dengan kemauan sendiri, (3)
untuk jangka waktu lama atau tidak, (4) dengan tujuan mencari penghidupan,
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 16
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
menuntut ilmu atau mencari pengalaman, (5) biasanya dengan maksud kembali
pulang, dan (6) merantau ialah lembaga sosial yang membudaya. Apapaun alasan
tersebut akan dipaparkan pada uraian berikut.
(1) Sistem kekerabatan matrilinial
Sistem kekerabatan orang Minangkabau merupakan sebuah hubungan yang
teratur antara individu di Minangkabau sehingga membentuk satu kesatuan atau
kelompok. Matrilineal berasal dari kata ‘matri’ yang berarti ‘mother/ ibu’ dan ‘lineal’
berarti ‘line/garis’ (Saydam, 2007: 311). Istilah matrilineal merupakan ungkapan
sosiologis, yang menyatakan bahwa garis keturunan seseorang ditarik dari garis
keturunan ditarik menurut garis keturunan ibu. Ibulah yang menjadi patokan dalam
menentukan asal usul seseorang.
Adapun yang menjadi ketentuan dalam pola kekerabatan matrilineal, lebih
lanjut Saydam (2007:331) mengemukakan beberaapa ketentuan, 1) si suami yang
pulang atau datang dan tinggal di rumah keluarga istrinya. 2) si suami boleh pergi
atau ke luar dari rumah jika terjadi perceraian dalam keluarga, si istri akan tetap
tinggal bersama keluarga atau kerabatnya .3) Si Anak akan tetap tinggal dan
dibesarkan bersama ibu dan kerabat ibunya. Dengan demikian, jika terjadi
perceraian dalam suatu rumah tangga, posisi ibu/ perempuan dan anak-anak dari
perkawinan itu akan tetap aman dan terpelihara karena ia berada dalam lingkungan
keluarga. Tidak ada istilah seorang anak akan hidup bersama ibu tirinya.
Artinya, laki-laki di Minangkabau tidak memiliki hak kepemilikan harta
pusaka, baik dalam keluarga istri maupun dalam kaumnya. Seorang laki-laki di
Minangkabau, mereka tidak dimanjakan dengan harta orang tua maupun dengan
harta pusaka. Karena harta itu diwariskan kepada kaum perempuan, laki-laki hanya
sebagai pengelola. Lain halnya dengan suku-suku lain yang menganut sistem
patriakat. Hal ini bukan berarti meniadakan hak laki-laki di Minangkabau.
Dengan sistem kekerabatan matrilineal, mengharuskan mereka untuk pergi
merantau, namun mereka tidak boleh meninggalkan kampung selama-lamanya,
karena sebagai pengelola, mereka harus kembali ke kampung setelah memiliki
pengalaman, seperti ungkapan “satinggi-tinggi tabang bangau, nan pulang kakubangan
juo”.
(2) Melanjutkan kesuksesan perantau sebelumnya dan kondisi alam
Adanya cerita orang-orang terdahulu yang sukses dalam perantauan
merupakan motivasi tersendiri yang mendorong terjadinya tradisi merantau di
dalam masyarakat Minang. Kadang, ada juga saudara yang pergi merantau,lalu
sukses merantau, ketika pulang menreka mambawa saudara untuk ikut merantau
dengan harapan mereka juga ikut sukses.
Menurut Makmoer, (2004) Geografis alam Minangkabau memang cukup
potensial dalam bidang agraris, tetapi tidak semua wilayah Sumatera Barat
berpeluang subur untuk dijadikan lahan pertanian. Menurut ilmu sosilogis, semakin
sulit penghidupan suatu masyarakat maka semakin tinggi daya nalar dan kreativitas
masyarakatnya. Ini artinya apabila orang telah terbiasa hidup susah dan dibesarkan
dalam lingkungan serba sulit akan menjadikan orang berfikir dan produktif. Hal
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 17
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
inilah yang menjadi salah satu masyarakat Minangkabau sukses di perantauan.
Sebagaimana diketahui bahwa jumlah penduduk selalu bertambah dan tidak
diiringi dengan penambahan lapangan kerja. Hal tersebut juga terjadi di
Minangkabau. Di Minangkabau, kaum laki-laki akan merasa sangat malu jika tidak
bisa bekerja. Oleh sebab itu, agar tidak disebut sebagai pemalas, maka kebanyakan
kaum laki-laki yang masih bujangan bekerja membantu orang tua. Umumnya
masyarakat Minangkabau berprofesi sebagai petani dan/atau pedagang. Hasil dari
tani biasanya dijual sendiri ke pasar.
Seiiring meningkatnya kebutuhan, para kaum laki-laki merasa bahwa bekerja
di kebun atau di sawah tidak lagi bisa mencukupi kebutuhan mereka, apalagi
membantu ekonomi keluarga. Lalu Ronidin (2000) mengungkapkan bahwa kaum
laki-laki akan berpikir untuk mencari pekerjaan baru agar tidak terus-terusan
bergantung pada orang tua. awalnya pekerjaan yang dicari biasanya berkisar di
daerah tempat tinggal. Tetapi, karena permasalahan pertambahan penduduk dan
lapangan pekerjaan, maka merantau merupakan solusi satu-satunya. Dengan
merantau, diyakini bahwa permasalahn ekonomi bisa teratasi.
(3) Menambah Pengalaman Hidup (faktor pendidikan)
Merantau dalam budaya Minangkabau merupakan suatu keharusan jika ingin
dipandang mandiri dan dewasa dalam masyarakat. Seorang pemuda Minangkabau
dianggap mandiri jika sudah merantau karena mampu hidup di tempat baru tanpa
ada sanak saudara. Dianggap dewasa karena sudah mampu mencoba kehidupan
baru di daerah luar lingkungan Minang.
Seorang mamak atau laki-laki di Minangkabau diharapkan dapan mendidik
anak-anak dan kemenakannya melalui keteladanan yang dimilikinya. Tingkah laku
yang baik, disiplin, dan pengalalam dalam menghadapi orang banyak dengan segala
macam tingkah polahnya. Hal itu akan banyak diperoleh seorang laki-laki atau
mamak ketika ia berada di luar lingkangannya.
Selain itu, adanya tuntutan mencari/menambah pengetahuan dan pengalaman
hidup juga menjadi alasan bagi pemuda Minangkabau untuk pergi merantau
meninggalkan kampung halaman. Masyarakat Minang dituntut mampu menguasai
ilmu pengetahuan, namun karena keterbatasan tingkat pendidikan yang ada di
daerah Minang, memaksa mereka untuk pergi ke luar dari wilyah Minang. Hal itu
sesuai dengan pantun,
Karatau madang daulu
Babuah babungo balun
Karantau bujang daulu
Di rumah panguno balun
Artinya, para pemuda belum dianggap berguna sebelum mereka memiliki
pengalaman hidup di rantau. Sebab dengan merantau, kehidupan yang mereka
jalani di perantauan merupakan pengalaman tersendiri yang tidak akan mereka
temukan di kampung halaman. Kesusahan dan kesengsaraan di perantauan
menjadikan mereka lebih tegar dalam menjalani kehidupan pada masa yang akan
datang. Hal itu juga dapat dilihat pada pantun berikut.
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 18
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
Tanjuang Alam di Ampek Angkek
Dari Gaduik pai ka Kurai
Jauah jalan banyak diliek
Lamo hiduik banyak dirasai
Dari pantun tersebut tergambar bahwa semakin panjang perjalanan yang
ditempuh, maka semakin banyak pengalaman yang didapatkan. Selain itu, para
pemuda yang merantau juga memiliki pengalaman beriteraksi dengan masyarakat
setempat. Dengan adanya interaksi yang baik, maka akan memudahkan mereka
dalam hidup bermasyarakat, layaknya di kampung sendiri. Seperti pada pantun
berikut.
kok jadi pai ka lapau kalau jadi pergi ke lepau
hiu bali balanak bali hiu beli belanak beli
ikan panjang bali dahulu ikan panjang beli dahulu
kok jadi pai marantau kalau jadi pergi merantau
ibu cari dunsanak cari ibu cari saudara cari
induak samang cari dahulu induk semang cari dahulu
artinya, ketika seorang pemuda pergi merantau, maka mereka terlebih dahulu harus
mencari seorang majikan yang dapat menjamin kehidupannya di rantau. Setelah itu
ia juga harus memiliki keluarga atau saudara yang dapat dijadikan tempat berbagi.
Dengan adanya saudara, induk semang, maka mereka dapat hidup lebih mudah di
perantauan, sama halnya ketika merek hidup di kampung. Seperti pada pantun
berikut.
Kok dagang lai batapatan
Kok biduak lai balabuhan
Kok karakok lai bajunjungan
Kok ayam lai bainduak
Kalau perantau ada tempat saudara yang dituju
Kalau biduk ada pelabuhannya
Kalau sirih ada junjungannya
Kalau ayam ada induknya
Dengan adanya majikan dan saudara di perantauan, kehidupan di perantauan
dapat mereka jalani dengan mudah. Untuk mendapatkan itu semua tidaklah mudah.
Seorang pemuda yang merantau haruslah memiliki sifat dan akhlak yang terpuji
agar ia dapat diterima dalam suatu kelompok di tempat perantauan. Seperti falsafah
“nan kuriak kundi, nan merah sago ( nan baiak budi nan indah bahaso)” dalam arti
mereka harus pandai-pandai berinteraksi dengan orang di sekitar mereka dengan
tutur kata yang baik dan budi pekerti yang luhur. Setelah itu mereka akan dapat
hidup rukun dimanapun berada. Seperti pada pantun berikutnya.
kalau pandai bakain panjang kalau pandai berkain panjang
samo jo bakain saruang sama dengan memakai kain sarung
kalau pandai bainduak samang kalau pandai berinduk semang
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 19
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
samo jo ibu kanduang sama dengan beribu kandung
Filosofinya, pemuda yang pergi merantau tidak semata hanya mendapatkan
materi, tetapi juga menambah pengalalam dalam menjaga hubungan sosial dan
mencari saudara di daerah perantauan. Dengan demikian, jika perantau sudah
merasa cukup untuk mendapatkan pengalaman, maka mereka pulang ke kampung
untuk membangun kampung, membela kaum kerabat. Selain itu mereka mulai
membangun kehidupan yang lebih baik di masa mendatang dengan keluarga
berdasarkan pengalaman yang telah didapatkan di perantauan.
(4) Memperbaiki ekonomi dan status sosial keluarga (Kaum)
Merantau bagi masyarakat Minangkabau dianggap memberikan harapan
untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di tempat yang dituju. Seorang ibu
harus ikhlas melepas kepergian anaknya demi memperoleh kehidupan yang lebih
baik di masa mendatang. Seperti pada pantun berikut!
sikujua jo batang kapeh
kambanglah bungo parautan
jikok mujua Bundo malapeh
bak ayam pulang ka pautan
si kujua dengan batang kapas
kembanglah bunga parautan
kalau mujur bunda melepas
bagai ayam pulang ke pautan
Melalui pantun tersebut dapat diketahui jika seorang ibu melepas anaknya
pergimerantau dengan tujuan “mambangkik batang tarandam” atau menaikkan harkat
dan martabat keluarga dan kaum,baik secara ekonomi maupun dengan sosial. Ketika
seorang ibu melepas dengan iklas, maka usaha si anak juga akan lancar dan mudah.
Begitu juga dengan si anak yang merantau, sesampainya di perantauan mereka juga
harus bekerja keras tetapi tetap mejaga norma-norma yang ada atau tidak
melampaui batas kesopanan atau kepatutan. Dengan bekerja keras, para perantau
akan sukses di perantauan (Navis, 1984). Kalau mareka malas, maka kehidupan
mereka berkemungkinan akan lebih susah ketimbang hidup di kampung. Seperti
pepatah berikut.
kurai taji pakan sinanyan
urang tuo bajaga lado
capek kaki ringan tangan
namun salero lapeh juo
capek kaki indak panaruang
ringan tangan indak pamacah
Selain kerja keras, mereka juga diharapkan lebih berhati-hati dalam bersikap.
Apapun yang akan dikerjakan, maka harus dipikirkan terlebih dahulu sebelum
bertindak. Kalau bajalan paliaro kaki, kalau mangecek paliaro lidah (kalau berjalan
pelihara kaki, kalau berbicara pelihara lidah). Setiap tindakan yang merekalakukan
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 20
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
haruslah difikirkan terlibih dahulu. Naum, pada masa sekarang, Salman (1971)
menyatakan bahwa pada masa sekarang telah terjadi perubahan dalam pola
merantau terutama di kalangan generasi muda yang pergi merantau tidak menjaga
dan memelihara diri ketika berada di tempat orang lain. Sehingga ada juga
ditemukan beberapa konflik yang melibatkan perantau Minang di daerah rantau.
Seharusnya Mereka tidak boleh gegabah dalam mengambil setiap keputusan. Jika
mereka melakukan kesalahan, berkemungkinan mereka akan diusir atau tidak
diterima oleh masyarakat tempat mereka tinggal. Seperti pantun berikut.
elok-elok manyubarang
jan sampai titian patah
elok-elok di rantau urang
jan sampai babuek salah
hati-hati menyebrang
jan sampai titian patang
pandai-pandai di rantau orang
jangan sampai berbuat salah
Sebagai orang Minang yang kaya dengan filosofi hidup merantau dan sudah
terbiasa hidup dengan segala adata istiadat yang berbeda maka mereka seharusnya
dapat hidup berdampingan dengan siapapun. Sebagai salah satu suku bangsa maka
orang Minang diharapkan turut serta dalam pelestarian tatanan kehidupan yang
harmonis antar suku bangsa dimanapun ia berada. Dalam hal ini yang paling
penting sekali dijaga adalah lisan, karena lisan inilah pangkal persoalan sehingga
muncul konflik. Seperti tersirat dalam pantun.
kok pandai bakato-kato,
bak santan jotangguli.
kok ndak pandai bakato-kato,
bak cando alu pacukia duri.
Kalau pandai berkata-kata
Seumpama santan dengan tengguli
Kalau tak pandai berkata-kata
Seumpama alu pencongkel duri
Yang sering menjadi penyebab renggangnya pergaulan sesama adalah tidak
terpeliharanya kata-kata. Kata-kata yang sembarang keluar sehingga di dengar oleh
yang tidak patut mendengar menjadi pangkalrusaknya pergaulan dan bahkan tidak
jarang mendatangkan fitnah dan pertikaian. Akibatnya merusak tali kekeluargaan
yang berakhir dengan keretakan dalamkeluarga. Untuk menghindari supaya tidak
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu diresapi pantun berikut.
Batolan mangko bajalan
Bapikia mangko bakato
Kato sapatah dipikiri
Rundiang sabuah dalam bana
Pikia palito hati
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 21
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
Tanang saribu aka
Tatumbuak biduak dikelokkan
Tatumbuak aka dipikiri
Selain itu, Falsafah adat mengajarkan “jalan nan ampek” yaitu tata cara untuk
menjaga keharmonisan pergaulan dalam masyarakat, baik dari yang muda kepada
yang tua atau dari yang tua kepada yang muda, ataupun sama besar, semuanya
telah diatur dalam adat Minangkabau seperti pepatah berikut
Nan tuo dimuliakan
Nan gadang dihormati
Samo gadang kawan baiyo
Nan ketek disayangi
Yang tua dimulyakan
Yang besar dihormati
Sama besar ajak berunding
Yang kecildisayangi
Thamrin (2007) Menjelaskan bahwa falsafah ini mengandung nilai-nilai
kehidupan bersama tanpa memandang suku bangsa. Dengan menjalankan falsafah
ini,maka dimanapun perantau minang berada mereka akan akan aman dan dapat
hidup berdampingan dengan siapapun tanpa adanya konflik.
(5) Marantau Cino
Pada masa sekarang, tujuan merantau tidak saja mencari pengalaman dan
bekal yang cukup untuk membangun kampung halaman hanya tinggal pepatah.
Hanya sebagian kecil perantau yang telah sukses baik dari segi materi maupun dari
segi ilmu pengetahuan yang mau kembali ke kampung halaman dan mengamalkan
apa yang telah mereka peroleh selama di rantau untuk kemajuan kampung halaman.
Bahkan Navis (1999) menyebut mereka dengan istilah “marantau cino” yang
memperjauh daerah perantauan mereka dan tidak kembali ke kampung setelah
sukses. Dalam hal ini ungkapan “urang awak pergi kerantau bukan untuk merantau tapi
pergi bermukim di daerah orang” tak dapat di bantah lagi. Seperti pada pantun berikut.
“tinggi malanjuiklah kau batuang/ indak kaden/ tabang-tabang lai/ tingga mancanguiklah
kau kampuang/ indak ka den jalang-jalang lai (tinggi menjulanglah kau bambu/ tidakkan
saya tebang-tebang lagi/ tinggallah kau kampung/ takkan saya kunjungi lagi”
Artinya, mereka pergi merantau meninggalkan kampung agar memperoleh
penghidupan yang lebih baik, namun tidak berniat untuk kembali. Keadaan seperti
ini sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi merantau itu sendiri. Namun keadaan
seperti ini tidak dapat dielakkan. Berikut ini beberapa alasan yang berkenaan dengan
alasan perantau tidak kembali ke kampung halaman atau dengan istilah marantau
cino.
(1) Tidak memiliki ayah atau ibu serta keluarga lagi
Biasanya bagi orang Minang yang sudah tidak lagi mempunyai ayah dan ibu
serta saudara kandung di kampung halaman mereka ini sudah malas untuk pulang
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 22
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
kampung. Sebab tidak ada lagi yang mau dicari. Tidak ada lagi yang menanti
kepulangan mereka di jenjang rumah. Tidak ada lagi yang akan memasakkan
rendang untuk mereka yang pulang dari rantau. Hal ini umumnya terjadi pada laki-
laki atau perempuan Minang yang kawin dengan orang luar Minang seperti dengan
orang jawa, batak, bugis atau melayu. Mereka yang marantau cino pada hakikatnya
ingin kembali, bagi mereka masih ada kerinduan untuk pulang, namun apa dikata
yang akan dikunjungi sudah tidak ada. Seperti terlihat melalui pantun berikut.
Rang lubuak Aluang ka pasa Usang Orang Lubuk Alung ke Pasar Usang
Mambao ragi tapai jo lamang Membawa ragi, tapai, dan lemang
Manangih badan di rantau urang Menangis badan di rantau orang
Taragak badan nak pulang Rindu badan pengen pulang
(2) Malu pulang karena belum mapan
Ada juga orang Minang, walaupun masih ada sanak saudara di kampung
halaman, namun mereka enggan pulang. Mereka malu untuk pulang, karena
kehidupan mereka yang susah diperantauan. Dari pada di kampung, lebih baik
rantau diperjauh (Koto, 2015). Sebab untuk pulang ke kampung halaman sudah
tentu perlu biaya yang tidak sedikit. Bagi mereka yang malu pulang, sebenarnya
hanya faktor ekonomi yang membuat mereka belum bisa pulang, bukan karena tidak
ingin pulang. Seperti pada pantun berikut.
Pakan baru taratak buluah
Labuhan kapa dari siak
Jawek pakirim dagang jauah
Sayang bacampua jo taragak
Singkarak kotonyo tinggi
Sumaniak mandado dulang
Awan bararak den tangisi
Badan jauah di rantau urang
bukik putuih jalan ka padang
dirandang jaguang di kuali
takaik putuih nak batualang
dipandang kampuang ditangisi
Melalui pantun tersebut terlihat adanya pesan bahwa mereka yang merantau
ingin pulang ke kampung halaman. Masih ada kerinduan di hati mereka
untukberkumpul dengan keluarga yang mereka tinggalkan di kampung halaman.
Namun apa hendak dikata,kondisi mereka belum memungkinkan untukpulang.
(3) Terjadinya Perkawinan luar budaya atau beda suku.
Sistem perkawinan yang paling ideal bagi masyarakat Minangkabau dalam
Navis (1986:194) yang pertama ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti
perkawinan antara anak dan kemenakan atau dengan istilah pulang ka bako. Kedua
adalah perkawinan ambil-mengambil/timba baluak, artinya kakak beradik laki-laki dan
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 23
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan
perempuan B. Ketiga, perkawinan dengan orang sekorong, sekampung, senagari dan
sesama orang Minangkabau. Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat
Minangkabau ialah perkawinan awak samo awak.
Berdasarkan pendapat Navis tersebut, terlihat adanya perkawinan ideal bagi
orang Minangkabau yang mengutamakan perkawinan sesama orang Minang. Pola
perkawinan ini bertjuan, agar pemuda Minang tidak pergi meninggalkan kampung
halaman ketika mereka merantau. Namun seiring perkembangan zaman, terjadi
perubahan pada pola perkawinan, dimana pemuda Minang ada yang menikah
dengan pemuda luar Minang. Seperi pepatah,
Sakali aia gadang,
sakalai tapian barubah
jalan dialiah urang lalu
cupak dituka urang pangaleh
Sepertinya sudah menjadi hukum alam, bahwa perkembangan zaman juga
berdampak terhadap pola perkawinan. Adapun dampak dari perkawinan ini,
dinatara mereka ada yang ikut dengan suami atau isteri yang bukan dari Minang.
Mereka hidup menetap, bekerja, dan anak-anak mereka besar dan juga bekerja di
sana, sehingga mereka sudah sulit untuk pulang ke kampung halaman.
(4) Pertengkaran keluarga atau kaum, bahkan karena cinta ditolak
Pertengkaran keluarga atau dalam kaum misal memperebutkan tanah ulayat
dan sebagainya, juga bisa menjadi orang Minang tidak pulang-pulang. Lebih baik
berkampung bersusah-susah di negeri orang daripada dikampung halaman
bertengkar dengan saudara. Bahkan karena cinta ditolak, maka sang pemuda lebih
baik pergi meninggalkan kampung, tidak kembali lagi, atau marantau cino.
Pada masa sekarang, sudah banyak orang Minang yang telah “merantau cino”
berpuluh-puluh tahun tidak pulang. Akibatnya, mereka dan anak-anaknya tidak
paham dengan adat budaya Minang bahkan tidak menggunakan bahasa Minang.
Seiring dengan itu, mulai terkikis juga nilai rasa budaya yang mereka pakai selama
ini. Walaupun begitu, ada suatu hal yang unik dan selalu menjadi ciri khas
mereka, yaitu ikatan batin, kepedulian dan kecintaan terhadap kampung
halaman. Sejauh-jauh merantau, kampung halaman terbayang jua”. Seperti
lirik syair berikut.
Minangkabau ranah nan den cinto,
Pusako bundo nan dahulunyo,
Rumah Gadang nan sambilan ruang,
Rangkiang baririk di halamannyo,
Bilo den kana hati den taibo,
Tabayang-bayang di ruang mato,
Bilo den kana hati den taibo,
Tabayang-bayang di ruang mato.
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 24
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
(M. Fuad Nasar, Konsultan The Fatwa Center Jakarta)
Setelah ilmu di dapat dan harta diperoleh, dan usiapun telah semakin tua,
biasanya perantau Minang, batinnya berkehendak pulang ke kampung halaman dan
menghabiskan masa tuanya di lingkungan anak cucu dan kaum. keluarganya. Setiap
pribadi bahagia jika ia tua dan menutup mata dan pusaranya berada di kampung
halaman.
KESIMPULAN
Tradisi masyarakat Minangkabau, merantau, sudah mirip seperti gerakan
ideologi, terutama bagi pemuda di mana merantau merupakan suatu
keharusan/wajib. Bagaimana spirit merantau itu dirawat dan diwariskan? Ternyata
tulisan ini membuktikan bahwa filosofi merantau telah “diselipkan” dalam pantun-
pantun Minangkabau, sehingga proses pewarisannya sangat soft memasuki alam
bawah sadar orang-orang Minangkabau. Pantun-pantun Minangkabau telah menjadi
media efektif dalam merawat ingatan dan membangus spirit merantau masyarakat
Minangkabau. Dengan merantau, pemuda dan sebagian orang-orang Minang
mendapatkan pengalaman yang tidak mereka dapatkan di daerah sendiri. Pada
konteks tertentu ujian mereka adalah berada dirantau, sehingga muncul anggapan
mereka belum dikatakan dewasa atau berpengalaman jika belum pergi
mininggalkan daerah kelahirannya. Setelah sukses di rantau, mereka dapat kembali
pulang untuk memajukan kampung halaman.
Seiring perkembangan zaman, ternyata tujuan merantau bagi pemuda
Minang juga mengalami perubahan, sesuai dengan ungkapan “ sakali aia gadang,
sakali tapian barubah/ sekali ada yang datang maka akan terjadi juga perubahan” .
adapun tujuan orang Minang merantau pada masa sekarang adalah; 1) mencari
penghidupan yang lebih baik secara ekonomi, 2) Melanjutan pendidikan atau
sekolah ke luar dari kampung, 3) menaikkan derajat atau status sosial keluarga atau
kaum, dan 4) mencari pengalalam hidup agar apa yang didapatkan dapat
dimanfaatkan untuk membangun kampung halalam.
Idealnya perantau Minang selalu kembali ke kampung halaman (sirkuler),
tetapi kenyataanya mereka banyak yang tidak kembali atau menetap di perantauan
dengan istilah marantau cino. Adapun yang menjadi sebab perantau ini tidak pulang
lagi ke kampung halaman dikarenakan beberapa hal. Pertama, tidak memiliki ayah
dan ibu serta keluarga yang akan dikunjungi. Kedua, merasa malu untuk pulang
karena kondisi ekonomi yang belum mapan. Ketiga, terjadinya pernikahan dengan
orang luar Minangabau. Keempat, ada konflik dengan keluarga atau kasus cinta
ditolak. Meskipun banyak alasan yang membuat mereka tidak dapat pulang setelah
lama merantau, pada dasarnya perantau tetap merindukan ranah Minang di mana
pun mereka berada sebagai tanah kelahiran mereka.
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 25
Zulfikarni dan Siti Ainim Liusti, Merawat Memori: Filosofi Marantau dalam Pantun-Pantun Minangkabau
DAFTAR PUSTAKA
Idrus Hakimy. 2004. Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, dan Pidato Alua Pasambahan Adat di
Minangkabau. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Koto, Tsuyoshi. 2015. Adat Mianangkabau dan Marantau dalam Perspektif Sejarah. Bandung: Balai
Pustaka.
Moestamir, Makmoer. 2004. “Tanah Ulayat dan Peranannya dalam Membangun Ekonomi
Kerakyatan” Makalah.
Naim, Mochtar. 1984. Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau. Yogyakarta. Gadjah Mada
University press.
Nasroen, M. 1971. Dasar Falsafah Adat Minangkabau. Penerbit Pasaman: Jakarta.
Navis, A.A. 1999. Yang berjalan Sepanjang Jalan. Jakarta: Grasindo.
Navis, A.A. 1984. Alam Terkembang Jadi Guru. Jakarta: Grafiti Press.
Saydam, Gouzali. 2004. Kamus Lengkap Bahasa Minang. Padang: Pusat Pengkajian Islam dan
Minangkabau.
Saydam, Gouzali. 2007. Sistem Kekerabatan Matrilinieal. Bandung: Lubuk Agung
Ronidin. 2000. Minangkabau Dalam Perubahan. Padang: Yayasan Akbar.
Radjab, Muhammad. 1950. Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Padang: Center For
Minangkabau Studies Press.
Salman, Ismah. 2004. Tinjauan Kritis Terhadap Matrilinieal di dalam Adat dan Budaya
Minangkabau. Bandung: Lubuk Agung.
Thamrin. 2007. Pandangan filosofis Terhadap Alam Takambang Jadi Guru. Bandung: Lubuk
Agung.
SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Hunaities Vol. 4. No.1, 2020| 26
Anda mungkin juga menyukai
- Keminangkabauan 9Dokumen18 halamanKeminangkabauan 9ImeldarizkieBelum ada peringkat
- Makalah Bam Kelompok 8 (Budaya Merantau Orang Minangkabau)Dokumen16 halamanMakalah Bam Kelompok 8 (Budaya Merantau Orang Minangkabau)Tiara Adha Putri07Belum ada peringkat
- UNIKOM - Meygi Mansyah Putra - BAB IDokumen16 halamanUNIKOM - Meygi Mansyah Putra - BAB Iriska ramayantiBelum ada peringkat
- Makalah KLP 10 FixDokumen16 halamanMakalah KLP 10 FixSalsa NabillahBelum ada peringkat
- Makalah BAM Kelompok 7Dokumen14 halamanMakalah BAM Kelompok 7Muhammad Fizki100% (1)
- Budaya Merantau Dan Etos Kerja Suku MinangkabauDokumen9 halamanBudaya Merantau Dan Etos Kerja Suku MinangkabauRoisatin NadhirohBelum ada peringkat
- MR SmiDokumen17 halamanMR SmiLabarta Samuel NaibahoBelum ada peringkat
- RantauDokumen10 halamanRantauEmail Cad100% (1)
- 6048 9968 1 PBDokumen17 halaman6048 9968 1 PBNuryani MarshaBelum ada peringkat
- MAKALAH Islam Dan Adat Minang Kabau Kel 11Dokumen13 halamanMAKALAH Islam Dan Adat Minang Kabau Kel 11Nurul FatimahBelum ada peringkat
- Makalah KeminangkabauanDokumen16 halamanMakalah Keminangkabauanmarlina riniBelum ada peringkat
- Tugas 1 Bibliografi MinangkabauDokumen5 halamanTugas 1 Bibliografi MinangkabauLeo DikaprioBelum ada peringkat
- Skripsi PerfectDokumen124 halamanSkripsi PerfectIsmail PratamaBelum ada peringkat
- Fil Keb. Tinggal Edit. Sholeh NPM 72Dokumen10 halamanFil Keb. Tinggal Edit. Sholeh NPM 72wbahayaniBelum ada peringkat
- Resume PerkotaanDokumen5 halamanResume PerkotaanIman AryaBelum ada peringkat
- UNIKOM - Meygi Mansyah Putra - JurnalDokumen16 halamanUNIKOM - Meygi Mansyah Putra - JurnalZulfiana RahmawatiBelum ada peringkat
- Kel.10 Kons Lintas BudayaDokumen10 halamanKel.10 Kons Lintas BudayaIwan NapitupuluBelum ada peringkat
- Kebudayaan Minangkabau Dan PerantauanDokumen8 halamanKebudayaan Minangkabau Dan Perantauanafif futaqi100% (2)
- Suku MinangDokumen17 halamanSuku MinangAdo van KurBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - Psikologi UlayatDokumen11 halamanKelompok 1 - Psikologi UlayatFaiz IsmailBelum ada peringkat
- 61-Article Text-267-2-10-20200929Dokumen7 halaman61-Article Text-267-2-10-20200929Sandra Oktavia SkbBelum ada peringkat
- Uts BamDokumen3 halamanUts BamI'M IQBelum ada peringkat
- Bab 1 Gabungan 2Dokumen81 halamanBab 1 Gabungan 2Andreas PardedeBelum ada peringkat
- Suku MinangkabauDokumen6 halamanSuku MinangkabauGraceLeaBelum ada peringkat
- Esai Ulang Tahun Sabalad Ke 5 Pemuda Desa Di Desa CendekiaDokumen4 halamanEsai Ulang Tahun Sabalad Ke 5 Pemuda Desa Di Desa CendekiaIrpan IlmiBelum ada peringkat
- Tugas Uts IsbdDokumen7 halamanTugas Uts IsbdIntan juitaBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen19 halamanBab 1zivanasution6Belum ada peringkat
- Bab I PDFDokumen20 halamanBab I PDFDeniBelum ada peringkat
- Ikatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantauan Sebagai Wujud Warga NKRIDokumen3 halamanIkatan Kekerabatan Etnis Minangkabau Dalam Melestarikan Nilai Budaya Minangkabau Di Perantauan Sebagai Wujud Warga NKRIUlfa LianaBelum ada peringkat
- Pesona Rancang Bangun Ranah Minang 47-170-1-PBDokumen14 halamanPesona Rancang Bangun Ranah Minang 47-170-1-PBFadhilah TsaniBelum ada peringkat
- Suku Minangkabau Atau Minang Adalah Suku Yang Berasal Dari Provinsi Sumatera BaratDokumen36 halamanSuku Minangkabau Atau Minang Adalah Suku Yang Berasal Dari Provinsi Sumatera Baratfaerish100% (2)
- Tgs 6 Antro-Arya Afdal H.Dokumen5 halamanTgs 6 Antro-Arya Afdal H.Arya AfdalBelum ada peringkat
- Artikel - Pengantar Antropologi - (Nur Aisyah NST)Dokumen6 halamanArtikel - Pengantar Antropologi - (Nur Aisyah NST)Nur Aisyah NstAntropologiD100% (1)
- PROPOSAL MIGRASI MANDAR DI MAKASSAR 1950-80 NewDokumen20 halamanPROPOSAL MIGRASI MANDAR DI MAKASSAR 1950-80 Newaliqramadhan24Belum ada peringkat
- CERPENDokumen53 halamanCERPENtunaikiBelum ada peringkat
- Sistem Matrilineal Dan Merantau Dalam AdDokumen8 halamanSistem Matrilineal Dan Merantau Dalam AdMulki Gempi MalindoBelum ada peringkat
- Resume Masyarakat MinangkabauDokumen8 halamanResume Masyarakat MinangkabaulhcbbhBelum ada peringkat
- Etnik Minang-1Dokumen21 halamanEtnik Minang-1Reihan HidayatBelum ada peringkat
- Sejarah Islamisasi Di Kabupaten Tapanuli Utara IIDokumen15 halamanSejarah Islamisasi Di Kabupaten Tapanuli Utara IIselvi agusnia waruwuBelum ada peringkat
- Adat Dan Budaya Minangkabau KLPK 2Dokumen9 halamanAdat Dan Budaya Minangkabau KLPK 2hamlan falendaBelum ada peringkat
- MAKALAH JambiDokumen35 halamanMAKALAH Jambiyoga ratmana putraBelum ada peringkat
- BAB I Pendahuluan)Dokumen25 halamanBAB I Pendahuluan)Sanz zBelum ada peringkat
- Cerita Rakyat Sebagai Penanaman Moral Karakter BangsaDokumen6 halamanCerita Rakyat Sebagai Penanaman Moral Karakter BangsaAbang Yuda SaputraBelum ada peringkat
- Sengketa Tiada PutusDokumen20 halamanSengketa Tiada PutusDouble AZBelum ada peringkat
- Sejarah Orang JambiDokumen4 halamanSejarah Orang Jambidwi ardiahBelum ada peringkat
- MAKALAH JambiDokumen35 halamanMAKALAH Jambiadela puspitaBelum ada peringkat
- Orang Sakai Sudah Modern (Dina Amalia Susamto) 0Dokumen61 halamanOrang Sakai Sudah Modern (Dina Amalia Susamto) 0Faiz AtallahBelum ada peringkat
- Jbptunikompp GDL Restidiahn 38558 8 Unikom - R HDokumen23 halamanJbptunikompp GDL Restidiahn 38558 8 Unikom - R HAzr AororaBelum ada peringkat
- Artikel Ilmiah Tentang PendidikanDokumen4 halamanArtikel Ilmiah Tentang Pendidikanyuliva rahmawatiBelum ada peringkat
- FinalDokumen15 halamanFinalAlan MustaqimBelum ada peringkat
- 935-Production File-1890-1-10-20200202Dokumen23 halaman935-Production File-1890-1-10-20200202Panggio Restu WilujengBelum ada peringkat
- Tradisi Lisan Kalinda'Da' Nur Wajihah Anggriani Hasri-1Dokumen26 halamanTradisi Lisan Kalinda'Da' Nur Wajihah Anggriani Hasri-1HAFID ALFANDYBelum ada peringkat
- 3633-Article Text-12022-1-10-20210127Dokumen6 halaman3633-Article Text-12022-1-10-20210127Bilaa SyabillaBelum ada peringkat
- Banggalah Jadi Orang MinangDokumen12 halamanBanggalah Jadi Orang Minangendang pramanaBelum ada peringkat
- 1206 3414 1 SM PDFDokumen15 halaman1206 3414 1 SM PDFMonick AsteroidBelum ada peringkat
- Tugas Etnografi IndonesiaDokumen19 halamanTugas Etnografi IndonesiaAprodita AprilBelum ada peringkat
- Laporan Tentang Suku Anak DalamDokumen10 halamanLaporan Tentang Suku Anak DalamDiah Ayu OctavianiBelum ada peringkat