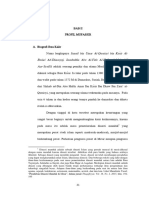Tiga Kitab dalam Satu Mushaf
Diunggah oleh
hodariJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Tiga Kitab dalam Satu Mushaf
Diunggah oleh
hodariHak Cipta:
Format Tersedia
ESAI
Bedah Manuskrip:
Tiga Kitab dalam Satu Mushaf
OLEH: HODARI MAHDAN ABDALLAH
Manuskrip di atas adalah salah satu koleksi Syaiful
Anwar, paman tiga pupu saya dari Kyai Badar (salah
seorang hafidz Qur’an keturunan Sunan Kudus yang
dijuluki Buju’ Longos) bin Abdurrahman Saudagar bin
Sayyid Mahfudz Gurang Garing. Saya memanggilnya
Le’ Toan.
Malam itu (3/5) saya berkunjung ke kediamannya, Jalan Adhirasa, No. 67 perumahan
Sumenep Regency—tak jauh dari pusat kota, sebelah timur kantor stasiun TV Madura
Channel. Di teras lantai dua, saya, dia dan seorang teman (Ra Faiq—salah satu putra kyai
ternama di Prongpong yang pesantrennya sering dikunjungi Sayyid Fadlil cicit Syekh Abdul
Qadir Jailani) berdiskusi santai sambil membedah sebagian manuskrip. Saya ambil satu dan
ternyata mengejutkan. Setelah dicermati secara serius selama kurang lebih tiga jam,
manuskrip di tangan saya itu rupanya adalah kumpulan tiga kitab.
Materi II Tadarus Esai, Mei 2021 | 1
Pertama, Aqídatu „l Ushúl karya Abu Layts Samarkandi (944-983 M). Dia merupakan
seorang ahli fikih (fáqih) bermadzhab Hanafiyah asal Samarkand, sebuah kota yang dulu
pada abad ke-10 dikenal sebagai pusat keilmuan Islam bermadzhab Sunni dan menjadi
tempat lahirnya apa yang disebut Timurid Renaissance. Sekarang, kota tersebut merupakan
kota terbesar di Negara Uzbekistan dan secara administratif menjadi ibu kota Samarqand
Region. Secara geografis, terletak di bagian selatan tenggara. Secara politik, Abu Layts ini
hidup di era transisi kejatuhan Dinasti Samanid, dinasti besar bangsa Iran yang bermadzhab
Sunni. Dalam hal kebudayaan, dinasti ini dikenal dengan proyek raksasanya dalam
menghidupkan kembali budaya Persia. Bahasa tersebutlah yang digunakan sebagai bahasa
komunikasi resmi kecuali dalam penulisan literatur keagamaan yang menggunakan Bahasa
Arab. Oleh karenanya tak heran bila kitab Aqídatu „l Ushúl yang berisi pembahasan akidah
itu ditulis dan terbit ke permukaan dengan menggunakan bahasa Arab.
Kedua, Sittín Mas-alah karya Abil „Abbas Ahmad Az-Zahid (w. 819 H/1416 M), seorang
ulama bermadzhab Sayfi‟i asal Quds, Palestina yang kelak pindah ke dan wafat di Kota
Qahirah, Mesir. Dia mendapat julukan Az-Záhid karena pilihan hidupnya yang asketis
(zuhd). Kebesaran namanya di kancah keulamaan terekam baik dalam Thabaqátu „l
Fuqahá‟ As-Syáfi‟i karya Taqiyuddin bin Shalah. Dalam kitab tersebut diceritakan dengan
cukup rinci bagaimana lakon kezuhudan yang Az-Zahid jalani. Namun sangat disayangkan,
sampai sekarang sumber biografi lengkap tentangnya masih terbatas—termasuk tahun
kelahirannya pun bahkan belum diketahui. Meski demikian, sangat jelas bahwa dia hidup di
era Dinasti Burji Mamluk (berkuasa di Mesir dari 1382-1517). Pemerintahan dinasti ini
penuh dengan gejolak politik. Perebutan kekuasan dengan cara-cara penaklukan terjadi
secara terus menerus di sepanjang periode ini. Perang antar penguasa berkecamuk. Az-
Zahid hidup pada situasi politik semacam ini. Kezuhudannya itu mungkin adalah cara dia
menyelamatkan independensi dirinya sebagai ulama sehingga otentitas keilmuan dan karya-
karyanya (seperti Sittín Masalah yang memuat bahasan fikih itu) tidak diintervensi
kepentingan politik tertentu.
Ketiga, Ummu 'l Baráhin karya Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi (1426-
1490). Dia adalah seorang ulama asal Tlemcen, sebuah kota di Al-Jazair bagian barat yang
pada abad ke-15 masih berada di bawah kekuasaan Dinasti Zayyaniyah (1235-1556) dan
menjadi pusat kerajaan. As-Sanusi hidup di era itu dan terkenal menguasai banyak disiplin
ilmu seperti akidah, ilmu logika, hadits, tasawuf, dan fikih. Buku di atas adalah salah satu
karyanya di bidang akidah. Kebanyakan orang mengenal kitab ini dengan sebutan Al-
„Aqídatu „Sanúsiyah yang memuat pembahasan terkait akidah Asy‟ariyah.
Hipotesis
Tiga kitab yang terhimpun dalam satu kesatuan manuskrip yang sedang saya amati itu
tidak tercantum tahun penulisannya. Namun kalau dilihat dari jenis kertas, tingkat
keburaman dan jenis tintanya persis dengan manuskrip satunya (berisi doa Tahlil dan
Kanzul Arasy) yang bertarikh 1327 H (1909 Masehi).
Berdasarkan temuan ini saya ingin mengajukan asumsi sementara bahwa nampaknya
pada awal abad ke-20, tiga kitab yang berasal dari penulis, negara, dan periode yang
berbeda itu telah dikenal dan dikaji oleh sebagian masyarakat di Sumenep. Mereka
mengenal kitab tersebut kemungkinan berkat adanya apa yang Azra (1994) sebut sebagai
“jaringan ulama Nusantara-Mekkah”. Hijaz (nama lain Mekkah) waktu itu merupakan
Materi II Tadarus Esai, Mei 2021 | 2
pusat keilmuan Islam di dunia. Dari berbagai negara, para sarjana Muslim datang ke sana
selain untuk menunaikan ibadah haji juga untuk menimba ilmu agama sebagai oleh-oleh
ketika pulang ke kampung halamannya nanti. Tak terkecuali mereka yang berasal dari
Sumenep.
Jauh sebelum era itu, pada paruh kedua abad ke-19, Madura sudah memiliki sejumlah
ulama jebolan Hijaz. Di Bangkalan terdapat Syaikhona Kholil. Di Pamekasan, Kyai Hamid.
Di Sumenep, Kyai Syarqawi, seorang pendatang dari Kudus yang kemudian menetap di
Guluk-guluk dan mendirikan pesantren Annuqayah—pesantren terbesar di kabupaten
tersebut. Sezaman dengan Kyai Syarqawi, di Sumenep saya mempunyai buyut bernama
Kyai Ilyasi, suami Nyai Tilam. Setelah memiliki putra bernama Hasinuddin, Kyai Ilyasi
berangkat menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama di sana. Setelah
lama menetap di Hijaz, dia tidak kunjung kembali pulang hingga kabar datang dari kyai-
kyai seangkatannya kalau Kyai Ilyasi itu telah wafat di sana.
Kisah ini mirip dengan riwayat perjalanan Kyai Gema di Prenduan yang terekam baik
dalam Handelaren en Handlangers: Ondernemerschap, Economische Ontwikkeling en
Islam op Madura karya Huub de Jonge. Saudagar religius yang terkenal kaya raya ini juga
wafat di Hijaz. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kyai Gema sempat berpesan
kepada teman akrabnya yang bernama Kyai Syarqawi itu supaya sudi menikahi istrinya di
Sumenep bilamana ajal benar-benar menjemput. Surat perjanjian pun dibuat di antara
mereka. Kejadian itu pun terjadi. Kyai Gema pergi untuk selamanya. Kyai Syarqawi datang
ke Sumenep.
Kedatangan Kyai Syarqawi di Sumenep berhasil memberi warna baru keagamaan,
terutama di bidang literatur keilmuan. Jaringan ulama Nusantara-Hijaz saat itu, memang,
salah satu dobrakan besarnya adalah berhasil membuka kran kitab kuning. Dikenalnya tiga
kitab yang saya sebut di atas (Aqídatu „l Ushúl, Sittín Mas-alah, dan Ummu „l Baráhin) pada
awal abad ke-20 itu tentu tak lepas dari pengaruh jaringan tersebut.
Wadah mempelajari kitab kuning ini berupa langgar dan pesantren. Untuk mengetahui
bagaimana hubungan kedua institusi ini dan bagaimana keduanya terbentuk, sebuah buku
Islam in Indonesian World: Ulama of Madura karya Iik Mansurnoor adalah bacaan yang
tepat. Menurut dia, kesohoran nama kyai di sebuah langgar menentukan kelak apakah
langgar tersebut akan berubah menjadi pesantren atau tidak. Pesantren terbentuk karena
banyaknya santri dari luar daerah ingin menimba ilmu di langgar tersebut yang pada
akhirnya mau tak mau harus menginap. Tempat menginap mereka disebut ponduk.
Dua bentuk institusi pendidikan tradisional ini sudah ada jauh sebelum abad ke-19.
Sejak 1871, Sumenep memiliki 49 unit pesantren (jumlah terbesar dibanding empat
kabupaten lainnya: Pamekasan mempunyai 43 unit pesantren, untuk Sampang 19 unit dan
Bangkalan 15 unit) dan 172 langgar (sumber: KV 1872, Biljage S No. 20, hlm. 6-7, 12-13, 14-
15). Dari tahun ke tahun jumlah pesantren terus meningkat. Pesatnya perkembangan
pesantren ini memancing perhatian Belanda karena dikhawatirkan menjadi kekuatan politik
seperti pemberontakan yang terjadi di Jawa pada 1825-1830 dan di Banten 1888. Oleh
karena itu, pada 1905 pemerintah kolonial Hindia-Belanda mengeluarkan sebuah
peraturan, khusus untuk mengontrol kegiatan pesantren dan langgar-langgar (baca: Social
Change in An Agrarian Society: Madura, 1850-1940 karya Kuntowijoyo). Judul
peraturannya adalah Voorschriften tot Uitvoering van de Ordonnantie van 2 November
1905 (Staatsblad no. 550) Handende Relegen Omtrent het van Bestuurwege Uit te
Materi II Tadarus Esai, Mei 2021 | 3
Oefenen Teozicht op het Mohammadaansch Godsdienstonderwijs op Java en Madoera,
met Uitzondering der Vorstenlanden.” Tiga kitab itu (yang terdapat dalam manuskrip di
atas) dipelajari pada era di mana peraturan tersebut sedang hangat-hangatnya diterapkan.
Selain itu, hal yang juga menarik di sini, di antara tiga kitab tadi terdapat satu kitab
akidah bermadzhab Hanafi: Aqídatu „l Ushúl karya Abu Layts. Ini menunjukkan bahwa
sikap mengaji para santri di Sumenep saat itu dapat dikategorikan sebagai sikap yang maju.
Mereka ternyata tidak hanya mengkaji kitab Syafi‟iyah tetapi juga Hanafiyah. Pengajian
lintas madzhab bukan sesuatu yang tabu saat itu. Oleh karenanya tak heran bila NU
menganut empat madzhab sekaligus—sebagaimana tertuang dalam dokumen Muktamar I,
1926 Surabaya—mengingat banyak guru dari para pendiri organisasi terbesar di Indonesia
(bahkan dunia) ini adalah kyai-kyai dari Madura.
Materi II Tadarus Esai, Mei 2021 | 4
Anda mungkin juga menyukai
- Biografi Sunan KudusDokumen8 halamanBiografi Sunan Kudusicpy pwrBelum ada peringkat
- Syaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masa KiniDokumen5 halamanSyaikh Yusuf Qardhawi: Guru Umat Islam Pada Masa KiniSunu WibiramaBelum ada peringkat
- Jaringan Keilmuan Mursyid Thariqah Syadziliyah di Solo RayaDokumen28 halamanJaringan Keilmuan Mursyid Thariqah Syadziliyah di Solo RayaMufid SyahlaniBelum ada peringkat
- IBNU ARABIDokumen14 halamanIBNU ARABIYanti SuryantiBelum ada peringkat
- 47-Article Text-104-1-10-20210920 PDFDokumen13 halaman47-Article Text-104-1-10-20210920 PDFAgung PrayogoBelum ada peringkat
- MANAQIB HABIB USMANDokumen7 halamanMANAQIB HABIB USMANAbdul Rahman HakimBelum ada peringkat
- Bab III Bisri MustofaDokumen22 halamanBab III Bisri Mustofaarif nurhidayatBelum ada peringkat
- Matkul Bhs IndonesiaDokumen5 halamanMatkul Bhs IndonesiaMuhammad Abrar dahlanBelum ada peringkat
- Biografi Syekh Abdur RaufDokumen9 halamanBiografi Syekh Abdur RaufSyarif AssegafBelum ada peringkat
- Syekh Abdus Shamad Al-PalimbaniDokumen17 halamanSyekh Abdus Shamad Al-Palimbaniabdul wahidBelum ada peringkat
- Biografi Syeikh Hamzah FansuriDokumen44 halamanBiografi Syeikh Hamzah FansuriManaf Èl-FazzBelum ada peringkat
- Tugas TokohDokumen27 halamanTugas Tokohrahmad100% (1)
- NASIHAT SPIRITUALDokumen121 halamanNASIHAT SPIRITUALAfiat FahmaBelum ada peringkat
- Makalah IslamDokumen12 halamanMakalah IslamteguhBelum ada peringkat
- Makalah Tugas Ibnu Khakdun Kelompok 2Dokumen13 halamanMakalah Tugas Ibnu Khakdun Kelompok 2eakun8346Belum ada peringkat
- Kel 2. Pemikiran Ulama Abad 17 Syekh Yusuf Al-MakassaryDokumen10 halamanKel 2. Pemikiran Ulama Abad 17 Syekh Yusuf Al-MakassaryAhmadnafi'uddinBelum ada peringkat
- Penyebaran Thariqah Syadziliyah Di Jawa Di Abad 19-20Dokumen16 halamanPenyebaran Thariqah Syadziliyah Di Jawa Di Abad 19-20ifet9000100% (1)
- makalah sayaDokumen14 halamanmakalah sayasitikhalimatusysyarifahBelum ada peringkat
- ULAMA PENYEBAR ISLAMDokumen6 halamanULAMA PENYEBAR ISLAMLinda Dwi WitrianingrumBelum ada peringkat
- Imam NawawiDokumen7 halamanImam NawawiMas Pion Fo YaBelum ada peringkat
- Deskripsi Kitab Senjata Mukmin Dan Risalah DoaDokumen34 halamanDeskripsi Kitab Senjata Mukmin Dan Risalah DoaMask Tiger100% (1)
- Pemikiran Tasawuf Ibn ‘AthoillahDokumen8 halamanPemikiran Tasawuf Ibn ‘AthoillahNjAapBelum ada peringkat
- JUDULDokumen19 halamanJUDULMaido HasanahBelum ada peringkat
- Bab IDokumen8 halamanBab IHilda AdeliaBelum ada peringkat
- Bab IDokumen11 halamanBab ISipiapi SipBelum ada peringkat
- JeinDokumen77 halamanJeinFadhila GueBelum ada peringkat
- Spirit Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad Xvii Dan Xviii Karya Azyumardi Azrae28099Dokumen5 halamanSpirit Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad Xvii Dan Xviii Karya Azyumardi Azrae28099Al-Ghafur ChannelBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen17 halamanBab IiInggrit L.M.Belum ada peringkat
- Peran Ulama dalam Gerakan NasionalismeDokumen31 halamanPeran Ulama dalam Gerakan NasionalismeAlfiyatun NashihahBelum ada peringkat
- 229570786Dokumen8 halaman229570786Assalaam StockBelum ada peringkat
- Ilmam Naufal - Review Tafsir An-NurDokumen21 halamanIlmam Naufal - Review Tafsir An-NurIlmam NaufalBelum ada peringkat
- Soal UASDokumen7 halamanSoal UASAhmad Sofwan HilmiBelum ada peringkat
- JEJARING ULAMA NUSANTARA DENGAN TIMUR TENGAHDokumen17 halamanJEJARING ULAMA NUSANTARA DENGAN TIMUR TENGAH7BFaiz DzulfikriBelum ada peringkat
- Kontribusi Kh. Hasyim Asy'ari Dalam Perkembangan Keilmuan HaditsDokumen10 halamanKontribusi Kh. Hasyim Asy'ari Dalam Perkembangan Keilmuan HaditsAhmad MutaqinBelum ada peringkat
- Kitab KuningDokumen349 halamanKitab KuningReni Nurlita100% (6)
- KEMATIANDokumen10 halamanKEMATIANrashidiBelum ada peringkat
- Tafsir KlasikDokumen17 halamanTafsir KlasikAufalBelum ada peringkat
- Bab Vi (2) Biografi Dan Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Perkembangan Islam Di IndonesiaDokumen17 halamanBab Vi (2) Biografi Dan Peran Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Perkembangan Islam Di IndonesiaRizki FebriantiBelum ada peringkat
- Biografi Syekh Abdurrauf AsDokumen16 halamanBiografi Syekh Abdurrauf AsCici SeptiaBelum ada peringkat
- Tarekat NaqsyabandiyahDokumen19 halamanTarekat NaqsyabandiyahlagunaBelum ada peringkat
- Tasawwuf Wal AkhlaqDokumen10 halamanTasawwuf Wal Akhlaqmafma qlateBelum ada peringkat
- Biografi Ulama IndonesiaDokumen7 halamanBiografi Ulama Indonesiaarthynay1106Belum ada peringkat
- Keteladanan para Wali AllahDokumen11 halamanKeteladanan para Wali AllahLatansa FotocopyBelum ada peringkat
- Najwa Siti SadahDokumen61 halamanNajwa Siti SadahAthenaBelum ada peringkat
- TAFSIR SINGKATDokumen10 halamanTAFSIR SINGKATDeana PutriBelum ada peringkat
- ULAMA PENYEBAR ISLAMDokumen60 halamanULAMA PENYEBAR ISLAMRezvikaAmandaBawohangBelum ada peringkat
- Tarjuman Al MustafidDokumen10 halamanTarjuman Al MustafidNyctophiliyaBelum ada peringkat
- Qintan Aghniya F. 31Dokumen4 halamanQintan Aghniya F. 31anita wahyulestariBelum ada peringkat
- Madzahib TafsirDokumen10 halamanMadzahib TafsirbuyakharismawantoBelum ada peringkat
- Tafsir KlasikDokumen15 halamanTafsir KlasikAufalBelum ada peringkat
- FalakDokumen19 halamanFalakSaha Atuh NyaBelum ada peringkat
- BAB IIDokumen15 halamanBAB IIHijrah CorporationBelum ada peringkat
- Tugas Ust TiarDokumen13 halamanTugas Ust TiarNurulBelum ada peringkat
- Modul Genesis Pemikiran Islam NusantaraDokumen22 halamanModul Genesis Pemikiran Islam Nusantarami rifaiyah dadirejoBelum ada peringkat
- Mengenal Abdul Rauf Al Singkili Dan Pemi-56018084-1Dokumen26 halamanMengenal Abdul Rauf Al Singkili Dan Pemi-56018084-1Nur OktapianiBelum ada peringkat
- SKIDokumen6 halamanSKIAhmad Basori NurtaqimBelum ada peringkat
- Terapi Maknawi Dengan Resep Qurani by Badiuzzaman Said NursiDokumen105 halamanTerapi Maknawi Dengan Resep Qurani by Badiuzzaman Said NursiYuriko AlessandroBelum ada peringkat
- Ringkasan PenelitianDokumen24 halamanRingkasan PenelitianMarsuki GaniBelum ada peringkat
- Zikir 28Dokumen1 halamanZikir 28hodijat2009Belum ada peringkat