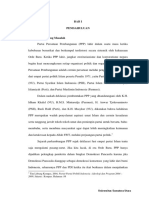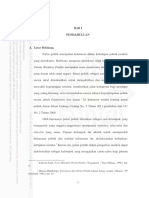Kontestasi Ideologi - Heri
Diunggah oleh
ridho dwi adinugrohoDeskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kontestasi Ideologi - Heri
Diunggah oleh
ridho dwi adinugrohoHak Cipta:
Format Tersedia
Seminar Dies XXVI Fakultas Sastra
“Peran Pendidikan Humaniora
dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat”
Kontestasi Ideologi Pasca Orde Baru
dan Peran Pendidikan Humaniora
dalam Demokratisasi Indonesia
oleh
Heri Setyawan
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta | 26 April 2019
Kontestasi Ideologi Pasca Orde Baru
dan Peran Pendidikan Humaniora dalam Demokratisasi Indonesia
Heri Setyawan
Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
hherisetya@usd.ac.id
Pasca runtuhnya kekuasaan Soeharto 21 Mei 1998, situasi kebebasan mendorong
munculnya beragam ekspresi dalam demokratisasi. Hal yang mencolok adalah
munculnya partai-partai politik, kebebasan pers, dan organisasi kemasyarakatan.
Walaupun begitu, Hadiz (2013) menyebut proses yang sedang terjadi bukanlah
demokratisasi sebagaimana diidealkan, namun berkuasanya golongan elit-elit
tertentu. Dalam konteks yang sama Tornquist (2018) mempersoalkan
demokratisasi yang tidak mewadahi kepentingan warga dan pengakuan
kewargaan, terlebih kelompok masyarakat minoritas dan kecil. Walaupun begitu,
menurut penulis, demokratisasi di Indonesia khususnya dalam kebebasan
berekspresi dan keterlibatan berpolitik menunjukkan bahwa demokratisasi di
Indonesia mengalami kemajuan besar. Partisipasi warga untuk berpolitik,
tumbuhnya budaya politik, dan terwadahinya ideologi politik menunjukkan
demokratisasi yang berhasil.
Walaupun begitu, melihat demokratisasi Indonesia dengan gejala-gejala
khusus yang akhir-akhir ini muncul, antara lain sentimen identitas yang
menyeruak di tengah demokratisasi dalam beragam bentuk, entah kekerasan,
populisme masif, politisasi identitas, maupun kesalehan individu dan komunal,
beberapa pertanyaan yang mendesak perlu dipikirkan. Pertanyaan penting
adalah apakah proses yang terjadi dalam demokratisasi Indonesia adalah
kontestasi ideologi ataukah suatu bentuk lain dari proses demokrasi yang baru?
Bagaimana perebutan dan pengaturan kekuasaan dapat menjadikan pluralitas
warga sebagai basis positif demokrasi bukan sebagai komoditas politik perebutan
kekuasaan semata?
Tulisan ini berargumen bahwa di tengah kontestasi ideologi-ideologi yang
sejalan dengan cita-cita demokrasi terselubung politik transaksionalisme yang
menjalar pada demokratisasi Indonesia. Terlebih lagi, politik transaksionalisme
merambah pada politik identitas yang membahayakan demokrasi itu sendiri.
Untuk itu, usaha untuk menguatkan demokratisasi perlu dilakukan, yakni dengan
membangun konsolidasi budaya politik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
Ketiga argumen tersebut akan dipaparkan dalam tulisan ini dengan
berusaha menelusuri gejala-gejala sosial berkaitan dengan kontestasi ideologi-
ideologi dalam demokratisasi pasca orde baru Indonesia, khususnya seputar
pemilihan umum. Untuk melihat aspek komparatif dan sisi historis, maka di sana
sini demokratisasi sekarang ini akan dibandingkan dengan demokratisasi pada
pemilu tahun 1955 yang dianggap pemilu paling demokratis sebelum pasca
reformasi. Setelah itu, tulisan akan berusaha menggali aspek pedagogis yang
dapat disumbangkan oleh pendidikan humaniora bagi demokratisasi Indonesia,
yakni memperkuat budaya politik.
Antara Kontestasi Ideologi dan Transaksionalisme Politik
Setelah terjadi fusi partai-partai politik pasca pemilu 1971, pemilu Indonesia
selalu diikuti tiga peserta, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai
Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golongan Karya (Golkar). Baru pada pasca
2 | “Peran Pendidikan Humaniora dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat”
orde baru, pemilu diikuti oleh berbagai partai politik. Euforia pasca bergantinya
orde baru ditandai dengan munculnya partai-partai politik. Pemilu pertama
pasca turunnya Soeharto, tahun 1999 diikuti 48 partai politik. Setelahnya, yakni
pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 diikuti lebih dari 12 partai.
Babak baru demokrasi Indonesia difasilitasi oleh tiga Undang-Undang yang
dikeluarkan Presiden B.J. Habibie pengganti Soeharto. Habibie mengeluarkan
undang-undang tentang Partai Politik (UU No 2 tahun 1999), undang-undang
tentang Pemilihan Umum (UU No 3 th 1999), dan tentang susunan dan kedudukan
MPR, DPR, dan DPRD (UU No 4 th 1999). Sebagai hasilnya, tahun 1999 digelar
pemilu pertama pasca reformasi untuk memilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD
II. Perubahan sistem pemilu kembali terjadi pasca amandemen UUD 1945 tahun
2002 sehingga presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu tidak hanya memilih
wakil-wakil rakyat dalam DPR, namun juga memilih presiden beserta wakilnya.
Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung membuat pemilu menjadi
semakin intens. Pemilu 2004 menghasilkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
demikian pula pemilu 2009. Pemilu 2014 menghasilkan kemenangan bagi Joko
Widodo. Dan saat ini kita masih menunggu hasil pemilu 2019.
Dilihat dari keikutsertaan partai peserta pemilu, sejak pemilu 1999
jumlah peserta pemilu cukup dinamis, begitu juga dengan hasil yang diperoleh.
Pemilu 1999 yang diikuti 48 partai politik menghasilkan lima partai dominan:
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Persatuan
Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Parta Amanat
Nasional (PAN). Sekalipun PDIP memenangkan pemilu, sidang umum MPR
memutuskan Abdurrahman Wahid dan Megawati menjadi presiden dan wakil
presiden RI. Data berikut memperlihatkan pemilu pasca orde baru:
Jumlah Partai Hasil
Pemilu Peserta Presiden
Legislatif
Pemilu dan Wakil Presiden
PDIP (33,7%), Partai Golkar
Abdurrahman
(22,44%)
1999 48 partai Wahid-Megawati
PPP (10.71%), PKB (12,61%), PAN
(dipilih MPR)
(7,12%)
Partai Golkar (21,58%), PDIP
(18,53%), PKB (10,71%), PPP Susilo Bambang
2004 24 partai (8,15%), Partai Demokrat (7,45%), Yudhoyono-Jusuf
PKS (7,34%), PAN (6,44%), PBB Kalla
(2,62%), PBR (2,44%)
Partai Demokrat (20,85%), Partai
44 partai (38 Golkar (14,45%), PDIP (14,03%), Susilo Bambang
2009 nasional, 6 PKS (7,88%), PAN (6,01%), PKB Yudhoyono-
Lokal) (4,94%), Partai Gerindra (4,46%), Boediono
Partai Hanura (3,77%)
PDIP (18,95%), Partai Golkar
(14,75%), Partai Gerindra
15 partai (12
(11,81%), Partai Demokrat Joko Widodo-Jusuf
2014 nasional, 3
(10,19%), PKB (9,04%), PAN Kalla
lokal)
(7,59%), PKS (6,79%), PPP (6,53 %),
P ND (6,72%), P Hanura (5,25%)
Menilik ideologi-ideologi partai peserta pemilu pasca orde baru, terlihat
bahwa ideologi yang tersisa di Indonesia tinggal dua, yakni nasionalis dan agama.
Dibandingkan dengan pemilu 1955, terjadi pengikisan ideologi yang signifikan.
Dies Natalis ke-26 Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | 3
Saat itu pemilu berlangsung dua tahap, yaitu untuk memilih anggota DPR dan
Konstituante yang diikuti 29 partai politik.
Bila diringkas, kontestasi ideologi pada pemilu 1955 dimainkan tiga
ideologi besar: nasionalis, agama, dan komunis. Oleh Sukarno, ketiga aliran ini
kemudian dia rangkum dalam istilah NASAKOM. Namun, pembagian tiga ideologi
tersebut juga mengandung penyederhanaan. Di balik tiga ideologi besar itu,
Herbert Feith menambahkan bahwa terdapat dua aliran lain yakni
tradisionalisme Jawa dan sosialisme demokrat (Feith dan Castles, 1988:lv). Feith
dan Castles berpendapat beberapa partai berasaskan satu atau dua ideologi.
Ideologi Marxis ditunjukkan oleh PKI, ideologi agama ditunjukkan NU, Masyumi,
dan beberapa partai Katolik dan Kristen, ideologi nasionalis ditunjukkan oleh PNI
dan Partai Indonesia Raya (PIR), dan ideologi sosialisme demokrat ditunjukkan
oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Partai Murba. Tradisionalisme Jawa
menurut Feith dan Castles juga sangat menentukan gerak partai, yakni partai NU
yang pada saat yang sama juga berasaskan Islam (Feith dan Castles, 1988:lv-lvi).
Mengerucutnya ideologi-ideologi pasca orde baru ke dalam ideologi
nasionalis dan agama membuat kedua ideologi saling berhadap-hadapan dengan
tajam. Ideologi nasionalis ditunjukkan langsung oleh partai-partai lama maupun
baru: Partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura,
Partai NasDem, dll. Sementara itu partai berbasis agama secara masif muncul
dari agama Islam: PPP, PKB, PAN, PBB, PK(S), Partai Bintang Reformasi (PBR),
dll. Partai berbasis agama Protestan dan Katolik yang pada pemilu 1955 cukup
kuat (Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik), pasca orde baru hanya muncul
dalam Partai Damai Sejahtera (PDS, pemilu 2004, 2009) dan Partai Damai Kasih
Indonesia (PDKI, pemilu 2009). PDS cukup kuat pada pemilu 2004, namun
kemudian kian merosot. Kedua partai ini sejak pemilu 2014 tidak dapat
berpartisipasi dalam pemilu karena tidak memenuhi persyaratan. Di samping
jumlah partai Islam yang lebih banyak dibanding partai Kristen dan sejak 2014
partai Kristen tidak dapat berpartisipasi lagi, maka pada akhirnya kontestasi
ideologi dalam pemilu sangat diwarnai pertarungan dua ideologi, yakni nasionalis
dan agama, secara spesifik Islam.
Ideologi Partai Nasionalis vs Partai Islam
Partai-partai berideologi nasionalis secara eksplisit menunjukkan dirinya sebagai
partai berasaskan Pancasila dan UUD 1945 sedangkan partai-partai Islam terlihat
bernegoisasi antara berasas Islam dan Pancasila. Hal ini terlihat dari visi misi
yang diusung masing-masing partai dan identitas partai yang dibangun di hadapan
massa dan pendukungnya. Konflik ideologis antara dua kelompok justru tidak
terlihat secara mencolok.
Partai nasionalis seperti PDIP dan Partai Golkar sejak awal
mendeklarasikan diri sebagai partai nasionalis. PDIP secara historis bergantung
pada identitas partai nasionalis (PNI) dan semangat nasionalis di bawah semangat
Sukarno. Jejak-jejak perjuangan PDI di bawah represi orde baru pada masa pra
reformasi semakin menyumbangkan semangat nasionalisme pada PDIP. Dalam
visinya, PDIP langsung menunjuk visi partai sebagai “alat perjuangan guna
membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni
1945”. Pada poin berikutnya PDIP memiliki visi menanamkan semangat
nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan yang ia sebut Tri Sila. Di samping itu,
sebagai Eka Sila adalah menentang individualisme dan menghidupkan semangat
gotong royong.
Identifikasi serupa juga dibuat oleh Partai Golkar, Partai Demokrat, dan
Partai Gerindra untuk menyatakan dirinya sebagai partai nasionalis. Transformasi
4 | “Peran Pendidikan Humaniora dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat”
besar-besaran dilakukan Partai Golkar untuk memperbarui diri dari identitas
Golkar pada masa orde baru di bawah Soeharto, namun juga tidak meninggalkan
ciri khas Golkar orde baru. Partai Golkar tetap menempatkan Pancasila sebagai
dasar negara dan menguatkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di
samping itu ciri khas Golkar terus dilanjutkan yakni melaksanakan pembangunan
nasional, mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan terjaminnya supremasi
hukum. Sedangkan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang
Yudhoyono meroket pada pemilu 2009 namun turun pada 2014. Visi Partai
Demokrat adalah mencapai pencerahan dalam kehidupan berbangsa. Demokrat
juga menempatkan prinsip nasionalisme, humanisme, dan internasionalisme
dalam visinya. Sementara itu Partai Gerindra lebih berbasis peningkatan
ekonomi, yakni bercita-cita menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial
dan tatanan sosial politik berdasar Pancasila dan UUD 1945.
Sementara itu identitas yang dibangun partai-partai Islam cukup dinamis
dengan terutama mengambil identitas kebangsaan dan keislaman. Sejak awal,
PKB (berdiri Juli 1998) mengenalkan diri sebagai partai berbasis Nahdhatul Ulama
(NU) dan memosisikan diri sebagai partai terbuka serta menempatkan cita-cita
Republik Indonesia dalam UUD 1945 sebagai pokok visinya. Ciri keislaman PKB
ditunjukkan secara ekplisit pada visi ketiganya, yakni “mewujudkan tatanan
politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah”.
Selain itu, prinsip perjuangan PKB didefiniskan sebagai “pengabdian kepada Allah
Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan
keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan
sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljamaah.”
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pembaruan Partai Keadilan
(berdiri Juli 1998) menempatkan visi partainya bagi terwujudnya masyarakat
madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Masyarakat madani yang
dimaksud adalah masyarakat maju berdasarkan pada nilai dan norma yang
dilandasi keimanan, demokratis dan semangat gotong-royong. Konsep
masyarakat madani bagi PKS yang perlu direalisasikannya adalah “Ukhuwwah
Islamiyyah (ikatan keislaman), Ukhuwwah Wathaniyyah (ikatan kebangsaan) dan
Ukhuwwah Basyariyyah (ikatan kemanusiaan), dalam bingkai NKRI”. Sedangkan
Partai Amanat Nasional (PAN, berdiri Agustus 1998) memosisikan agama sebagai
landasan moral dan etika berbangsa. Sekalipun begitu, PAN mendefinisikan diri
sebagai partai yang terbuka bagi semua dari berbagai latar belakang. PAN
menentukan visi sebagai partai yang ingin mewujudkan masyarakat madani yang
adil dan makmur, demokratis dan berdaulat. Partai Persatuan Pembangunan
(PPP, berdiri 1973) sebagai partai lama menyatakan visinya, “Terwujudnya
masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil,
makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum,
penghormatan terhadap HAM, serta menjunjung tinggi harkat-martabat
kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.”
Sementara itu, dalam keislaman, PPP menyatakaan perlunya penataan
masyarakat Islami dan menempatkan Islam sebagai panduan moral dan sumber
inspirasi dalam kehidupan kenegaraan. Islam dan negara, dalam pandangan PPP
perlu membangun relasi yang saling memelihara.
Melihat identifikasi partai-partai politik berhaluan Islam tersebut, terlihat
bahwa PK(S) dan PPP secara eksplisit mengidentifikasi diri sebagai partai dengan
Dies Natalis ke-26 Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | 5
platform Islam, sementara itu PKB dan PAN secara eksplisit mengidentifikasi diri
sebagai partai berplatform Islam namun menunjukkan diri sebagai partai yang
terbuka dan inklusif (Sirry, 2006:471). Dalam beberapa kasus, PK(S) juga
menyatakan diri sebagai partai terbuka, misalnya dengan menerima calon
legislatif beragama non-Islam, namun keberakaran PKS dari kader Lembaga
Dakwah Kampus yang terinspirasi dari Muslim Brotherhood di Mesir, membuatnya
sulit membentuk identitas terbuka. Dalam pengelompokan yang dilakukan
Baswedan (2004), partai Islam terbagi dalam tiga kategori, yakni Islamis, Islam-
inklusif, dan sekuler-inklusif. Islamis mengusung identitas Islam dan ingin
mengubah tata sosial kemasyarakatan dan negara berdasarkan hukum Islam,
sedangkan Islam-inklusif memandang antara negara (Pancasila) dan Islam dapat
sejalan sehingga yang perlu dilakukan adalah mendorong terbentuknya civil
society berasaskan Islam, bukan mengganti prinsip kenegaraan. Partai beraliran
sekuler-inklusif yang dimaksud Baswedan yaitu partai sekuler yang terbuka
menerima Islam dan memiliki ciri khas Islam (Baswedan, 2004:679). Namun
begitu, tipologi ketiga ini sebenarnya tidak menjelaskan partai Islam itu sendiri.
Pertentangan ideologis dalam tataran filosofis terjadi antara partai
nasionalis dengan partai Islamis, khususnya dengan partai Islamis yang
menyuarakan diterapkannya Syari’a dan dikembalikannya 7 kata dalam
pembukaan UUD 1945. Hal ini mengemuka terutama pada masa pemilu pertama
pasca orde baru (1999) dan tahun-tahun setelahnya. Gerakan ini terjadi dalam
dua bentuk baik melalui jalur formal di legislatif maupun gerakan massa. Massa
kelompok Mujahidin menyerukan diterapkannya Syari’a, misalnya dalam kongres
di Yogyakarta. “Beri kami kesempatan untuk memimpin. Kalau dalam tempo 20
tahun Indonesia tidak menjadi adil dan makmur, potong leher kami," begitu
seruan Mursalin Dahlan, salah satu tokoh Mujahidin dalam konggres Mujahidin ke
I, di Yogyakarta 7-9 Agustus 2000. Sedangkan, melalui jalur formal, pada proses
Amandemen UUD 1945 yang berlangsung 4 tahap (1999, 2000, 2001, dan 2002),
PPP dan PBB meminta pasal 29 tentang agama turut diamandemen dengan
mengembalikan 7 kata dalam UUD, yakni “...dengan kewajiban menjalankan
Syari’a Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Pada tahun 2000 seruan itu menguat,
namun tidak ditanggapi. Sidang tahunan MPR untuk amandemen tahun 2001 juga
tidak membahas tujuh kata tersebut. Saat itu usulan amandemen sudah sampai
pada ad hoc dengan tiga pilihan: dikembalikan 7 kata secara utuh, diganti
menjadi “dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing
pemeluknya”, dan tidak mengubah pasal 29 sama sekali. Pertarungan ideologis
terjadi antara fraksi reformasi dimotori PAN dan PK dengan partai mayoritas di
MPR, yaitu PDIP, Golkar, dan PKB. Sampai amandemen selesai, pasal tersebut
tidak diubah (Nursalim, 2007:147).
Kekuatan partai-partai nasionalis berhadapan dengan partai agama tidak
diragukan dilihat dari jumlah pemilihnya. Pada pemilu 1999 partai nasionalis
memenangkan pemilihan umum melebihi partai-partai berbasis agama dan Islam
(Anwar, 2009:356-357). Pemilu-pemilu selanjutnya pun kurang lebih demikian.
Presentase terbesar yang didapatkan partai agama adalah PKB yang pada tahun
1999 mendapat 10,7%. Setelahnya, ketiga partai Islam besar lainnya (PPP, PKS,
PAN) mendapat presentase antara 6-9%. Sedangkan kemenangan selalu ada pada
partai nasionalis.
Maka, praktek pertentangan ideologi-ideologi dalam demokratisasi di
Indonesia lebih merupakan sebuah konsolidasi demokrasi. Partai-partai
berideologi tertentu menyatakan identitas politiknya dan dalam alam demokrasi
mencari simpatisan untuk mendapatkan kekuasaan. Perolehan suara merupakan
6 | “Peran Pendidikan Humaniora dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat”
suara rakyat yang dipercayakan kepada partai. Namun demikian, aspirasi partai
Islamis yang berkeinginan merubah sistem negara dan sistem hukum merupakan
agenda politik agama. Dalam konteks kebangsaan, perubahan sistem negara
merupakan tindakan di luar hukum.
Politik Identitas, Matinya Ideologi, dan Politik Transaksional
Gejala kedua yang muncul dalam demokratisasi pasca odre baru adalah
menguatnya politik identitas yang dimanfaatkan oleh kepentingan politik untuk
meraih kekuasaan. Dengan demikian, yang terjadi bukan sekadar kontestasi
ideologi-ideologi, namun bersamaan dengan gejala sosial bangkitnya agama dan
politik identitas terjadi tumpang tindih kepentingan politik dan identitas hingga
kemudian memunculkan politik identitas, khususnya politik agama untuk
mencapai kekuasaan.
Pada tahap pertama pasca orde baru, politik identitas menghasilkan luka
yang berat pasca 1998 dengan terjadinya kerusuhan dan kekerasan antar entis di
Ambon, Maluku (1999), Poso, Sulawesi Tengah (2000-2001), dan Sampit,
Kalimantan Tengah (2000-2001) (Klinken, 2007). Saat itu, yang terjadi adalah
menguatnya sentimen antaretnis yang mengantarkan pada permusuhan dan
pembunuhan karena adanya pemantik konflik. Masyarakat dan pemerintah
seperti tidak memiliki daya untuk menangkal dan mengatasi konflik yang
berkepanjangan.
Memasuki dua pemilu terakhir ini, 2014 dan 2019, politik identitas
memainkan peran yang besar, ditambah lagi dengan beberapa peristiwa terkait
pilkada Jakarta saat Ahok dan Anies Baswedan memperebutkan posisi gubernur.
Yang terjadi bukan kontestasi ideologi di mana ideologi-ideologi menyampaikan
visi misi dan program bersumber dari ideologinya, namun, akumulasi identitas
untuk menyerang identitas lawan politik dengan pengerahan massa. Maka, gejala
pertama, identitas menjadi akomodasi politik untuk memperoleh kekuasaan.
Demokratisasi berjalan menegangkan karena identitas dimainkan di tempat
publik, tempat ibadah, dengan pengumpulan massa.
Tak hanya itu, pemanfaatan identitas sebagai cara akumulasi suara
semakin menggejala ketika para politikus mendekati tokoh-tokoh penyokong
identitas (tokoh agama) untuk dapat meraup suara melalui tokoh tersebut. Hal
ini terjadi dalam pemilu terakhir (2019), dan pemilukada Jakarta. Para calon
meminta restu, mendatangi tokoh agama kharismatis, bahkan mengambil tokoh
agama sebagai partnernya. Sejak pasca orde baru hal ini terjadi dengan
mengangkat beberapa tokoh agama penting (Gus Dur, Hasyim Muzadi, dll). Maka,
gejala kedua, identitas digunakan oleh tokoh-tokoh politik dengan cara
mendekati tokoh kharismatik dari penyokong identitas tersebut untuk mendapat
dukungan dari pengikutnya. Hal ini terjadi pada banyak calon yang ingin merebut
hati pemilih. Patronisme menelikung demokrasi yang harusnya lahir dari pilihan
personal sadar atas program yang akan dipilih.
Gejala ketiga, identitas menjadi penyokong politik transaksional. Tokoh
kharismatis (tokoh agama) bukan hanya didekati oleh para politikus untuk
mencari simpati massa, namun keduanya telah kehilangan ideologi masing-
masing. Ideologi telah mati (the end of ideology), bukan hanya terjadi pada
ideologi politik global, misalnya yang disampaikan Daniel Bell (1960) yang
mempertanyakan ideologi sosialis-komunis yang hancur di Soviet, namun pada
politik Indonesia, sebelum ideologi partai kuat berakar, ideologi yang dimiliki
sudah melemah bahkan mati. Ideologi politik telah melemah diganti politik
transaksional antara tokoh politik dan tokoh karismatis. Terjadi aliansi pragmatis
untuk saling memanfaatkan. Hal ini terjadi, misalnya pada pemilu terakhir (2019)
Dies Natalis ke-26 Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | 7
ketika tokoh politik Tommy Soeharto yang partainya baru saja lolos pemilu pergi
menuju Mekkah menemui Habib Rizieq. Kedua pihak saling mendukung dan setuju
untuk masuk koalisi adil makmur, padahal, sebagaimana ditunjukkan Azis (2019),
Habib Rizieq selama ini menjadi pengkritik keras orde baru dan penerapan
Pancasila yang dilakukan orde baru. Menurut Rizieq, penerapan Pancasila oleh
orde baru telah mengorbankan umat Islam. Namun, ideologi telah mati, diganti
politik transaksional berdasar identitas. Dekade sebelumnya, politik
transaksional juga telah terjadi namun bukan berdasar identitas agama, misalnya
dengan berkoalisinya Megawati dengan Prabowo Subiyanto untuk maju pada
pemilihan presiden dan wakil presiden (2004).
Peran Pendidikan Humaniora?
Gejala-gejala perubahan dalam demokrasi pasca orde baru, dengan demikian,
ditandai pergeseran dari demokrasi sentralistik kepada demokrasi kerakyatan
dan keragaman partai-partai politik. Namun, dalam perkembangannya, ideologi
partai-partai politik begitu lunak dan berubah menjadi politik transaksional yang
menunggangi politik identitas. Pengolahan politik identitas menjadi tugas besar
jangka pendek yang harus dipikirkan oleh bangsa Indonesia. Ia bisa menggerogoti
demokratisasi yang telah berjalan.
Terobosan yang dapat ditempuh untuk memperkuat demokratisasi adalah
dengan memperkuat budaya politik. Konsolidasi budaya politik, praktis dapat
terjadi di mana saja, entah dalam masyarakat maupun dalam lingkup yang lebih
sempit seperti pendidikan. Budaya politik yang dimaksud adalah segala perilaku
dan sikap yang selalu berdimensi politik namun didasari oleh sikap yang dewasa
dan beradab (Suseno, 1999:50, Hefner, 2005). Dengan demikian, politik yang
pada dirinya sendiri hadir di mana-mana menjadi sebuah kebiasaan yang dihidupi
dengan dewasa. Dengan kata lain, kesadaran manusia sebagai makhluk politik
terrealisasi dalam kehidupan sehari-harinya yang terbuka terhadap politik dan
menyikapinya dengan jujur, dan (khususnya dalam konteks pendidikan)
mendekatinya dengan daya pikir kritis.
Pendidikan humaniora yang membedakan diri dari ilmu alam dan ilmu
sosial, memiliki peluang untuk memberikan kontribusi khas bagi demokratisasi
(Sastrapratedja, 2015). Bahkan, tugas berat bagi universitas adalah membangun
humanisme baru dimana orang mengalami transformasi eksistensial dan
memunculkan kreativitas-kraetivitas baru bagi kemajuan masyarakat
(Sastrapratedja, 2013:335). Beberapa hal berikut, menurut pendapat penulis,
dapat ditempuh oleh pendidikan humaniora untuk menumbuhkan budaya politik:
1. Pendidikan Kewargaan
Pendidikan humaniora yang perlu dikembangkan dalam konteks politik demokrasi
adalah mendidik manusia sepenuhnya menjadi manusia bebas dan menjadi warga
negara, yang dalam istilah Driyarkara disebut liberalisasi (Driyarkara, 2006:705-
730). Ketika mengembangkan pendidikan humanitas, Marcus Tullius Cicero (106-
43 SM) terutama hendak mendidik para muridnya untuk menjadi orator yang
ulung, namun konsep humanitas ini kemudian disepadankan dengan konsep
paideia dalam pemikiran Yunani yang berusaha mendidik manusia untuk menjadi
manusia-yang-sepenuhnya dan menjadi warga negara (Sastrapratedja, 2015).
Pendidikan kewargaan, dengan demikian, adalah satu aspek penting
dalam pendidikan humaniora. Manusia (muda) sadar akan peran dan hak-haknya
sebagai warga negara. Pada ujungnya, manusia yang sadar akan peran dan hak-
haknya sebagai warga negara dapat terlibat dalam realitas sosial di sekitarnya.
Pendidikan kewargaan ini bukan hanya ditujukan bagi mahasiswa formal di
perguruan tinggi, namun menjadi modal dasar bagi seluruh warga negara.
8 | “Peran Pendidikan Humaniora dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat”
Pendidikan kewargaan mengajak orang dalam negara berpikir dan terlibat akan
keberadaannya sebagai warga di dalam negara. Pendidikan humaniora memiliki
tugas melakukan pendidikan kewargaan kepada masyarakat.
2. Berpikir Kritis-Solutif
Langkah metodis mengembangkan manusia (muda) dalam pendidikan adalah
menumbuhkan budaya berpikir kritis. Forum pendidikan bukanlah pertama-tama
sebagai tempat untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia (muda)
atau melatih ketrampilan-ketrampilan tertentu, namun pertama-tama adalah
tempat untuk mengembangkan daya pikir. Manusia dalam proses pendidikan
berpikir tentang hal-hal di sekitarnya dan bidang yang digeluti.
Dalam hal demokratisasi, pendidikan humaniora memiliki kekhasan untuk
melihat dan mendekati realitas secara lebih komprehensif berpijak dari unsur-
unsur humanis. Maka, beberapa aspek ini dapat menjadi ranah dan arena
pendidikan humaniora. Antara lain, kepekaan budaya (cultural sensibility),
kesadaran sejarah, dan kreativitas pendekatan masalah secara lintas ilmu
(budaya, religi, bahasa, dll).
Sumbangan pendidikan humaniora dalam masyarakat, dengan demikian,
menumbuhkan kesadaran untuk berpikir kritis dan memberi tawaran solusi bagi
permasalahan bangsa. Cara berpikir kritis dengan memberi pendasaran kuat pada
aspek kesejarahan, kebudayaan, dan cara pikir multidimensi menjadi jalan
terobosan yang diperlukan oleh demokratisasi Indonesia. Selain itu, di tengah
ideologi-ideologi atau matinya ideologi, orang diajak untuk berpikir kritis tentang
ideologi-ideologi atau tiadanya ideologi tersebut. Cara berpikir demikian, dapat
menguatkan budaya politik di tengah masyarakat. Warga, pada akhirnya, akan
mengembangkan cara berpikir politis-humanis.
3. Budaya Resolusi-Konflik
Keadaban dan sikap dewasa dalam demokratisasi semakin diuji dalam caranya
menyelesaikan konflik. Pertama-tama demokratisasi harus berada dalam koridor
demokrasi, yakni keterlibatan, kebebasan, dan kesetaraan. Perbedaan dan posisi
berlawanan tetap harus berada dalam koridor demokrasi. Bila terjadi konflik di
luar jalur demokrasi, koridor penyelesaian konflik seringkali bukanlah sekadar
soal hukum atau keamanan semata, namun juga soal kebudayaan dan aspek
multidimensional manusia. Pendidikan humaniora diperlukan untuk
mengembangkan budaya damai dan resolusi konflik.
4. Pendidikan Keragaman dan Identitas
Kesadaran pluralitas budaya sampai kapanpun mutlak menjadi kesadaran seluruh
warga negara Indonesia. Pluralitas bagi bangsa Indonesia seperti telah menjadi
akar kenegaraan. Negara Kesatuan Indonesia yang terbangun dari ribuan pulau
dengan kebudayaannya yang beragam akan menjadi potensi besar, namun pada
saat yang sama dapat menjadi sumber bahaya besar. Sejarah Indonesia telah
menunjukkan bagaimana perbedaan yang tidak terolah mengarahkan masyarakat
pada kekerasan, konflik yang berkepanjangan, dan penghancuran.
Untuk itu demokratisasi perlu dibarengi dengan pembangunan kepekaan
budaya di tengah masyarakat yang pluralis, yang berarti menghargai
multikulturalisme dalam bingkai kesatuan Indonesia. Kebhinekaan yang telah
dirajut bangsa Indonesia menjadi medan bagi ilmu humaniora untuk mengolahnya
kembali dalam konteks jaman dan kebutuhan yang baru.
Kesimpulan
Langkah maju dalam demokratisasi Indonesia pasca lengsernya Soeharto
ditunjukkan dengan kebebasan menyalurkan aspirasi politik baik dalam pemilihan
umum maupun segi kehidupan lainnya. Ideologi-ideologi bertumbuh dan
Dies Natalis ke-26 Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta | 9
berkontestasi dalam pemilihan umum. Demokrasi sentralistik bergeser kepada
demokrasi populis dan kerakyatan dengan munculnya beragam partai. Namun,
dalam perkembangannya, ideologi partai-partai politik begitu mudah melunak
demi memperoleh kekuasaan. Dibarengi dengan tumbuhnya sentimen identitas
di masyarakat, demokratisasi Indonesia masuk pada politik transaksional yang
cenderung memanfaatkan politik identitas. Politik identitas dalam politik
transaksional menurut pandangan penulis sangat berbahaya bagi kelangsungan
demokratisasi Indonesia.
Melihat gejala-gejala sosial dalam demokratisasi Indonesia pasca orde
baru tersebut, diperlukan penguatan budaya politik di masyarakat. Pendidikan
humaniora dapat memberi sumbangan khas dengan melakukan pendekatan
humanis dan lintas ilmu, memperhatikan kesadaran budaya dan kesejarahan.
Pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis menjadi kekuatan pendidikan
humaniora untuk memberikan sumbangannya bagi demokratisasi Indonesia.
Daftar Pustaka
Amir, Zaenal Abinin. Peta Islam Politik Pasca-Soeharto. Jakarta: LP3ES, 2003.
Anwar, M. "Syafi’i.“Political Islam in Post-Soeharto Indonesia: The Contest
between ‘Radical-Conservative Islam’ and ‘Progressive-Liberal Islam’.”
Southeast Asia and the Middle East: Islam, Movement and the Longue
Durée (2009): 349-385.
Baswedan, Anies Rasyid. "Political Islam in Indonesia: Present and Future
Trajectory." Asian Survey 44.5 (2004): 669-690.
Driyarkara, Nicolaus. Karya Lengkap Driyarkara: Esai-Esai Filsafat Pemikir yang
Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya. Gramedia Pustaka Utama,
2006.
Feith, Herbert, dan Lance Castle (ed.). Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965.
Jakarta: LP3ES, 1988.
Hefner, Robert W., ed. Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation,
Democratization. New Jersey: Princeton University Press, 2009.
Magnis-Suseno, Franz. “Membangun Kembali Sebuah Budaya Politik Indonesia”
dalam Sindhunata, ed. Pergulatan Intelektual Dalam Era Kegelisahan.
Yogyakarta: Kanisius, 1999, hlm. 49-64.
Nursalim, Muh. "Politik Hukum Dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945: Telaah
Terhadap Upaya Penerapan Syari'ah Islam Di Indonesia." Jurnal Fakultas
Hukum UII 30.64 (2007): 147-156.
Sastrapratedja, M. Pendidikan Multidimensional. Yogyakarta: Penerbitan
Universitas Sanata Dharma, 2015.
Sastrapratedja, M. Pendidikan Sebagai Humanisasi. Yogyakarta: Penerbitan
Universitas Sanata Dharma, 2001.
Sirry, Mun'im A. "Transformation of Political Islam in Post-Suharto Indonesia"
dalam Ibrahim M. Abu-Rabi (eds.) The Blackwell Companion to
Contemporary Islamic Thought. New York: Blackwell, 2006, hlm. 466-481.
Van Klinken, Gerry. Communal Violence and Democratization in Indonesia: Small
Town Wars. New York: Routledge, 2007.
10 | “Peran Pendidikan Humaniora dalam Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat”
Anda mungkin juga menyukai
- Strategi Komunikasi Politik Partai GerinDokumen10 halamanStrategi Komunikasi Politik Partai GerinTri SusantyBelum ada peringkat
- Urgensi Pendidikan Politik Dalam Menciptakan Pemilu Damai Di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologi Politik)Dokumen14 halamanUrgensi Pendidikan Politik Dalam Menciptakan Pemilu Damai Di Sulawesi Selatan (Pendekatan Sosiologi Politik)Kadek AdiBelum ada peringkat
- Kajian Geografi Terhadap PolitikDokumen14 halamanKajian Geografi Terhadap PolitikRezki AmaliahBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen8 halaman1 PBagan sandosBelum ada peringkat
- Sejarah Pemilihan Umum Di IndonesiaDokumen3 halamanSejarah Pemilihan Umum Di IndonesiaRyan SahputraBelum ada peringkat
- Tugas Komunikasi PolitikDokumen3 halamanTugas Komunikasi PolitikSurya SanindrataBelum ada peringkat
- Chapter IDokumen29 halamanChapter Idevi elviraBelum ada peringkat
- BUDAYA POLITIK INDONESIA (PKN)Dokumen24 halamanBUDAYA POLITIK INDONESIA (PKN)Alma SiwiBelum ada peringkat
- Sejarah Politik Indonesia Memiliki Sejarah Yang Panjang Dan KompleksDokumen4 halamanSejarah Politik Indonesia Memiliki Sejarah Yang Panjang Dan Kompleksreza dwi kurniawanBelum ada peringkat
- Diskusi 8Dokumen5 halamanDiskusi 8Ayu GhiselBelum ada peringkat
- Muhammad Falah Abdillah - Riview Jurnal SispolinDokumen3 halamanMuhammad Falah Abdillah - Riview Jurnal SispolinRheznandyaMaulanaHidayatullohBelum ada peringkat
- Modul Sistem Politik IndonesiaDokumen42 halamanModul Sistem Politik IndonesiaDila AdilaBelum ada peringkat
- SEJARAH Pemilu Dari Tahun 1955 Sampai SekarangDokumen2 halamanSEJARAH Pemilu Dari Tahun 1955 Sampai SekarangGito ManaloeBelum ada peringkat
- Sejarah PemiluDokumen4 halamanSejarah PemiluTyas WikaBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen11 halaman1 PBgearenata516Belum ada peringkat
- Resume Haikal MuhammadDokumen5 halamanResume Haikal MuhammadHaikal muhammmadBelum ada peringkat
- Memproduksi Teks Laporan Hasil Observasi-1-1Dokumen6 halamanMemproduksi Teks Laporan Hasil Observasi-1-1Rizki adityaBelum ada peringkat
- Bab IDokumen13 halamanBab IMulan SalsabilBelum ada peringkat
- Pemilu 1955Dokumen5 halamanPemilu 1955Agus susantoBelum ada peringkat
- Supra Struktur Dan Infra Struktur Politik Di IndonesiaDokumen21 halamanSupra Struktur Dan Infra Struktur Politik Di IndonesiaDwita Putri KarlitaBelum ada peringkat
- Suprastruktur Dan InfrastrukturDokumen25 halamanSuprastruktur Dan Infrastrukturnia_vet0% (1)
- Artikel Kelompok 1 (Perkembangan Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi) - 102844Dokumen6 halamanArtikel Kelompok 1 (Perkembangan Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi) - 102844Galih PratamaBelum ada peringkat
- Tinjauan Etis Kristen Tentang Gerakan Gerakan Didalam Pemilihan Presiden 2024Dokumen12 halamanTinjauan Etis Kristen Tentang Gerakan Gerakan Didalam Pemilihan Presiden 2024Billy SimbolonBelum ada peringkat
- Infrastruktur Dan Suprastruktur Politik DiDokumen9 halamanInfrastruktur Dan Suprastruktur Politik Dimonitadiah100% (1)
- PKN Bab 4 (Makalah Presentasi)Dokumen8 halamanPKN Bab 4 (Makalah Presentasi)Gung GektaBelum ada peringkat
- Muhammad Farhan Pratama Partai Politik Pada Masa ReformasiDokumen6 halamanMuhammad Farhan Pratama Partai Politik Pada Masa ReformasiMfpBelum ada peringkat
- Makalah FinalDokumen23 halamanMakalah Finalsri suparni sri suparniBelum ada peringkat
- Kelompok 8 - A 2017 - Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Dan Reformasi - Pemilu 1971 Dan 1977 Serta Peristiwa MalariDokumen13 halamanKelompok 8 - A 2017 - Sejarah Indonesia Masa Orde Baru Dan Reformasi - Pemilu 1971 Dan 1977 Serta Peristiwa MalariMuhammad Wahyudi0% (1)
- Pemilu Pada Tahun 2004Dokumen13 halamanPemilu Pada Tahun 2004IvanBelum ada peringkat
- Puad MAKALAH - PEMILU - 1955 - DI - INDONESIADokumen7 halamanPuad MAKALAH - PEMILU - 1955 - DI - INDONESIAPuad BawazerBelum ada peringkat
- Kapita Selekta PolitikDokumen8 halamanKapita Selekta PolitikCitra Puspita LubisBelum ada peringkat
- Kelompok 2 Sistem KepemiluanDokumen12 halamanKelompok 2 Sistem KepemiluanJohari GaniBelum ada peringkat
- Analisis Partai Politik Pada Masa Orde Baru Dan Pasca ReformasiDokumen5 halamanAnalisis Partai Politik Pada Masa Orde Baru Dan Pasca ReformasiRista Sanjaya63% (8)
- Latbel 2Dokumen18 halamanLatbel 2ayu baladhikaBelum ada peringkat
- 9090-Article Text-18579-2-10-20211019Dokumen10 halaman9090-Article Text-18579-2-10-20211019farrelsyafiraBelum ada peringkat
- Sistem Kepartaian Dan Sejarah Singkat Perkembangan Kepartaian Di IndonesiaDokumen17 halamanSistem Kepartaian Dan Sejarah Singkat Perkembangan Kepartaian Di IndonesiaFirman Naufal NajibBelum ada peringkat
- Sejarah PemiluDokumen11 halamanSejarah Pemilurian120Belum ada peringkat
- Esai Uas Spi Tri Panca Hendri L1a022089 CDokumen8 halamanEsai Uas Spi Tri Panca Hendri L1a022089 CIKY. 2Belum ada peringkat
- Pengetahuan KepemiluanDokumen25 halamanPengetahuan Kepemiluanbagus bachrulBelum ada peringkat
- Ksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di IndonesDokumen22 halamanKsistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di IndonesGusdediBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - Sejarah Pemilu Di IndonesiaDokumen21 halamanKelompok 1 - Sejarah Pemilu Di IndonesiaRidhwan SuriawijayaBelum ada peringkat
- Peta Politik Lokal KSBDokumen221 halamanPeta Politik Lokal KSBSyahrul Mustofa.S.H.,M.HBelum ada peringkat
- Sistem Kepartaian Dan PemiluDokumen23 halamanSistem Kepartaian Dan PemiluMaulidaaBelum ada peringkat
- Analisis Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa)Dokumen8 halamanAnalisis Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia (Studi Kasus Partai Kebangkitan Bangsa)Angga Putri Utami100% (1)
- MASA REFORMASiDokumen37 halamanMASA REFORMASiSelva TaniaBelum ada peringkat
- Paper 1Dokumen25 halamanPaper 1Suci MBelum ada peringkat
- 1635-Article Text-4154-1-10-20220601Dokumen10 halaman1635-Article Text-4154-1-10-20220601Maudy AureliaBelum ada peringkat
- OUTLINE SKRDokumen14 halamanOUTLINE SKRcover abal-abalBelum ada peringkat
- Makalah Pendidikan Pancasila 5Dokumen13 halamanMakalah Pendidikan Pancasila 5Felisa AvriliaBelum ada peringkat
- Sejarah KepemiluanDokumen5 halamanSejarah KepemiluanisarBelum ada peringkat
- Makalah AgamaDokumen23 halamanMakalah Agama08 Andrian X MIPA 3Belum ada peringkat
- Sesi 1 KekuatanDokumen19 halamanSesi 1 KekuatanFina Nur AndariBelum ada peringkat
- BangpolDokumen4 halamanBangpolFarhan Azhar FuadiBelum ada peringkat
- Esai Eksistensi Partai Politik Di Era Orde Baru Dan Pasca Reformasi - Sistem Politik Indonesia - Dinda Noveliani (20052042) PDFDokumen6 halamanEsai Eksistensi Partai Politik Di Era Orde Baru Dan Pasca Reformasi - Sistem Politik Indonesia - Dinda Noveliani (20052042) PDFDinda NovelianiBelum ada peringkat
- 2004Dokumen2 halaman2004wahyu widianingrumBelum ada peringkat
- Daftar Nama Partai PolitikDokumen40 halamanDaftar Nama Partai PolitikConsen Elia AnggenBelum ada peringkat
- 28719-Article Text-33466-1-10-20190704Dokumen8 halaman28719-Article Text-33466-1-10-20190704Zacky MaLdanyBelum ada peringkat
- Perilaku Partai Politik Dalam Pemilu 2019Dokumen6 halamanPerilaku Partai Politik Dalam Pemilu 2019Fenty Nur AiniBelum ada peringkat
- RPP 4Dokumen37 halamanRPP 4Ahmad RushanfichryBelum ada peringkat
- Perang Dingin (Kronologi)Dokumen18 halamanPerang Dingin (Kronologi)ridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Analisis Kikd XDokumen17 halamanAnalisis Kikd Xridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Kuliah 2 - Masa Pendudukan Tentara Jepang Dan Masa KemerdekaanDokumen30 halamanKuliah 2 - Masa Pendudukan Tentara Jepang Dan Masa Kemerdekaanridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- RPP 5Dokumen19 halamanRPP 5Ahmad RushanfichryBelum ada peringkat
- Geliat Kota Bandung Dari Kota Tradisional Menuju Modern (Eko Yulianto, DKK) PDFDokumen265 halamanGeliat Kota Bandung Dari Kota Tradisional Menuju Modern (Eko Yulianto, DKK) PDFridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Program Semester (Genap) IPS Kelas 7Dokumen2 halamanProgram Semester (Genap) IPS Kelas 7ridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- RPP 10Dokumen17 halamanRPP 10NikocoBelum ada peringkat
- RPP 3Dokumen14 halamanRPP 3ridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Persebaran Nenek MoyangDokumen8 halamanPersebaran Nenek Moyangridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- RPP 10Dokumen17 halamanRPP 10NikocoBelum ada peringkat
- 02 12 Sej - Indo 03 PromesDokumen1 halaman02 12 Sej - Indo 03 Promesridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- RPP 2Dokumen20 halamanRPP 2ridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- SILABUS IPS Kelas 7Dokumen4 halamanSILABUS IPS Kelas 7ridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Program Semester 2017-2018Dokumen2 halamanProgram Semester 2017-2018mahzarBelum ada peringkat
- Sejarah Teori Konflik Lewis CoserDokumen2 halamanSejarah Teori Konflik Lewis Coserridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Program Semester (Ganjil) IPS Kelas 7Dokumen2 halamanProgram Semester (Ganjil) IPS Kelas 7ridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Artikel Teori DramaturgiDokumen5 halamanArtikel Teori Dramaturgiridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Urgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi PendidikanDokumen14 halamanUrgensi Penerapan Manajemen Konflik Dalam Organisasi Pendidikanridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- MAKALAH Teori Konflik Sosial Lewis A. CoserDokumen18 halamanMAKALAH Teori Konflik Sosial Lewis A. Coserridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- 02 12 Sej - Indo 04 SilabusDokumen5 halaman02 12 Sej - Indo 04 Silabusridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- 02 12 Sej - Indo 06 RPPDokumen8 halaman02 12 Sej - Indo 06 RPPridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- 02-12-Sej - Indo-01-Ki KDDokumen3 halaman02-12-Sej - Indo-01-Ki KDridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Makalah FenomenologiDokumen18 halamanMakalah Fenomenologiridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Filsafat FenomenologiDokumen16 halamanFilsafat FenomenologiMhd RusdiBelum ada peringkat
- Dampak Dari Gerkan DiDokumen3 halamanDampak Dari Gerkan Diridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Kronologi Gerakan DITII Di JabarDokumen7 halamanKronologi Gerakan DITII Di Jabarridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat
- Latar Belakang DIDokumen5 halamanLatar Belakang DIridho dwi adinugrohoBelum ada peringkat