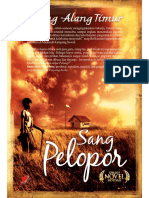PATREM, Cerpen Tentang Perempuan Dengan Pergulatan Hidup Dan Pembunuhan Yang Dilakukannya.
Diunggah oleh
Nayana MarutaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
PATREM, Cerpen Tentang Perempuan Dengan Pergulatan Hidup Dan Pembunuhan Yang Dilakukannya.
Diunggah oleh
Nayana MarutaHak Cipta:
Format Tersedia
PATREM Oleh : Nayana Maruta Bintang berpendar di langit. Rembulan bagai semangka berwarna kuning di atas kepala.
Namun, malam ini terasa begitu sunyi. Tidak ada angin yang asyik bermain dengan dedaunan. Tidak ada suara jengkerik yg menjerit meriuhkan malam. Pintu-pintu rumah juga tertutup sejak sore. Sepi. Malam seperti memberi tanda bahwa akan ada pencuri atau nyawa yang tercabut dari raga. Harum bau bunga-bunga mangga yang sedang mekar mengambang layaknya kabut. Harum itu memenuhi setiap jengkal halaman tempatku berdiri saat ini berselimut hitam jubah sang malam. Anakku, Telaga*, sudah tertidur pulas sejak sore di kamarnya. Dari arah barat lirih angin membawa suara gamelan tayup, yang membuat pikiranku dipermainkan kenangan. Menjadi perempuan itu tidak mudah. Perempuan tidak hanya harus menyusui anak, tapi juga menyusui semesta*. Berbakti pada suami. Kuat menahan semua cobaan hidup, karena semesta tercipta dengan pranata sosial yang cenderung memihak pada pria. Harus bisa mengatur segala macam emosi, adanya hanyalah rasa ikhlas, dengan begitu manusia bisa mengikuti pusaran roda nasib dan aliran sungai kehidupan. Begitu kuingat nenek dulu sering berkata padaku. Berpesan pada saat kami berdua menghabiskan sore sambil memandang merah yang menghilang perlahan berganti pekat. Nenek juga pernah bercerita bahwa ketika aku lahir disertai oleh bau harum bunga pandan. Itulah sebabnya aku diberi nama Pudhak (bunga pandan)*. Sayangnya, dua tahun setelah kuhirup pengap hawa dunia, ayah-ibuku meninggal karena kecelakaan. Hal itu baru aku ketahui begitu aku menginjak dewasa. Karena bila aku bertanya mengenai kepergian ayah-ibuku seringkali nenek hanya berkata bahwa ayah-ibuku berpergian jauh. Ke sebuah tempat yang jauh dan tinggi letaknya. Lalu nenek dengan jari tuanya menuding dua buah bintang yang ada di langit dan anehnya aku percaya. Itulah sebabnya bila rasa rindu pada ayah-ibuku menderu, aku selalu menunggu malam, berlari di halaman dan mencari dua bintang itu. Lalu kusimpan kelipnya dalam mimpi-mimpiku. Begitu banyak suara-suara berbisik, dari balik punggungku dan nenek. Suara yang tiba-tiba saja menjadi senyap dan lenyap setiap kali aku dan nenek membalikkan tubuh. Suara-suara yang tidak jelas berasal dan bersumber dari mana. Suara-suara yang lirih bercerita bahwa garis leluhurku adalah garisnya manusia yang terkena kutuk. Tidak bakal ada priya yang berumur panjang begitu masuk ke dalam lingkaran keluargaku. Bila hal ini kutanyakan pada nenek, beliau hanya tersenyum dan
1
kemudian bercerita bahwa garis keluargaku adalah garisnya dhanyang desa, orang terpilih yang pertama kali membuka lahan untuk dijadikan desa. Nenek sering mengajakku berjalan, berkenalan dengan malam dan pekat sang gelap. Melihat bintang, kunang-kunang, kodhok dan apa saja isi pekat malam. Masih kuingat jelas nenek selalu bersenandung lirih sambil berjalan. Suaranya seolah hidup merambat di batang-batang pohon, rerumputan, batu juga terbawa oleh aliran air sungai. Nenek juga guruku bercocok tanam. Membuat cok-bakal untuk di tempatkan di pojok-pojok sawah begitu padi mulai ditanam dan ketika panen tiba. Mengajari doa-doa penolak hama dan petaka. Disaksikan boneka kayu Roro Dhenok, aku menemani Sang Hyang Sri menjejak bumi. Di malam tertentu aku diajak nenek berkeliling desa, sawah dan juga perbukitan. Malam lainnya, menemaninya bersila di halaman mendengarkan suara semesta hingga dingin embun di pucukpucuk rumput terasa membasahi kaki kami. Aliran sungai kehidupanku agak berubah begitu aku menginjak dewasa. Aku mengenal Kang Marto, priya lugu, jujur yang memasuki semestaku. Seribu bunga mekar bersama kepak sayap kupukupu. Semesta meruah, indah. Aku dan Kang Marto menikah. Setahun sesudahnya beliau meninggal dunia. Sebelum meninggal nenek sempat memberiku sesuatu dan berpesan, Pudhak, jagalah barang ini seperti kamu menjaga nyawamu. Ini pusaka keluarga. Jangan pernah kamu loloskan dari sarungnya tanpa ijin semesta. Aku hanya mengangguk. Barang itu kuperhatikan. Panjangnya adalah jarak terjauh ibu jari dan jari kelingkingku*. Ukiran halus bunga tanjung, sulur-suluran dan batu mirah kecil menghiasinya*. Hanya ada getar aneh menyeruak darinya, sesuatu dingin dan senyap.* Suara-suara bisik itu terdengar begitu nenek meninggal. Namun lenyap dan senyap seperti biasanya. Setahun setelah itu, ada bintang kecil menghias semestaku. Begitu cemerlang kerlipnya. Kuberi nama Telaga, karena matanya yang bening layaknya sebuah telaga. Tangisnya menghangatkan rumah tangga kami. Semestaku terasa semakin berwarna. Telaga berumur tiga tahun saat Kang Marto mengutarakan keinginannya padaku untuk menjadi Kepala Desa. Bagiku sebuah keinginan yang terasa aneh, bagi orang selugu dia.
Pudhak, aku ingin menjadi Kepala Desa di desa ini. Apa kau setuju? kuingat benar pertanyaannya padaku kala itu. Iya, jawabku pendek. Aku setuju demi baktiku pada seorang suami. Hanya itu, tidak lebih. Kalau begitu, aku minta bantuanmu, katanya menegaskan. Aku hanya menggangguk. Di pekat malam, kudatangi sawah ganjaran untuk kepala desa. Aku duduk bersila, menutup semua pancaindraku, melebur diriku dalam semesta, mendengar suara-suaranya. Macan bumi--yang berwarna biru polos--keluar dari empat penjuru sawah. Dan aku mendapatkan ijin. Malam-malam selanjutnya kutembus pekat mengelilingi desa, tanpa peduli hujan, dingin dan suara ledakan di atas bubungan. Akhirnya Kang Marto berhasil menjadi Kepala Desa. Sepertinya aliran sungai kehidupanku berubah arah. Harus melintasi batu-batu padas, yang mulanya kecil namun tambah lama makin membesar. Setelah tiga tahun menjabat Kepala Desa tabiat Kang Marto mulai berubah. Umur Telaga menginjak enam tahun kala bapaknya jarang ada di rumah. Sawah juga tidak diperhatikannya. Benar kata nenek bahwa cobaan akan datang begitu keinginan terwujud. Suara-suara berbisik itu makin sering terdengar dan meresahkan hingga membuat Telaga ketakutan. Bu, apakah bapak punya istri lain? Kenapa bapak jadi jarang pulang? pertanyaan sama yang selalu diulang kala malam tiba. Aku hanya tersenyum, kugandeng tangan kecilnya. Kubawa ia mengenal pekat malam. Melihat bintang, kunang-kunang, kodok dan semua isi malam. Telaga mulai bisa melupakan pertanyaan-pertanyaannya juga bapaknya. Bila suara-suara bisik itu terdengar, kuajarkan pada Telaga cara membalikkan diri. Dan seketika suara itu lenyap dan senyap. Kuajarkan semua yang diajarkan nenek pada putri tunggalku. Aku sebenarnya tahu kemana perginya dan semua yang dilakukan suamiku. Aku bisa merasakan cahaya hidup suamiku kemana arah mata angin membawanya. Kemana dan dimana lirih gamelan tayub itu terdengar. Kulihat jelas semesta yang tak tampak di depan mata. Namun, tidak ada rasa sakit atau nestapa dalam hati ini. Karena aku sadar garis hidup suamiku memang harus begitu. Oleh sebab itu aku tidak pernah menyalahkannya, menyalahkan suamiku. Begitu pula pada hidup dan nasib.
Kang Marto mengajukan diri menjadi Kepala Desa untuk kedua kalinya. Kembali aku harus turun di pekat malam untuk berbakti pada suami. Kang Marto terpilih lagi. Aku masih menghormati dan berbakti padanya, meski semesta kami telah berbeda, sejauh bumi dan langit. Telaga berumur sebelas tahun kala aku mulai mengajarinya menata hati. Dan jagat sepertinya mulai ada perubahan besar. Hama dan petaka bergantian mengunjungi dan bercanda dengan desa. Datang dan berlalu semaunya, tanpa pamit, tanpa tahu waktu. Aku dan Telaga sering berada di halaman dalam pekat malam, melantunkan kidung-kidung penolak. Sekali dua kali berhasil. Namun sepertinya jagat semakin bertingkah, semakin kuat melawan. Dan kekuatan kidung-kidung itu pun musnah bersama hama dan petaka yang meruah. Jagat semakin keras bersuara bahwa ana praja salah nata lan nata salah mangsa (ada desa yang salah pemimpin dan pemimpin yang salah waktu). Embun di ujung rerumputan mulai membasahi kakiku, dinginnya terasa menusuk di jangat. Segala kenangan itu luruh bersama jatuhnya selembar daun mangga ke bumi. Aku menarik napas panjang. Kuraba patrem yang ada di gelung rambutku, kutarik dan menyebabkan rambutku jatuh terurai. Patrem yang hanya sejengkal jari itu berpendar kuning terkena cahaya bulan. Kututup seluruh panca inderaku, kulebur diri dengan semesta. Pelan kuloloskan patrem dari sarungnya. Anyir bau kematian mengambang di udara, menghapus harum bunga-bunga mangga. Malam berkubang dalam sepi tak bertepi. Kusarungkan kembali patrem ke dalam sarungnya. Kembali harum bunga-bunga mangga mengisi udara. Rembulan sedikit menyisih ke arah barat, pucat. Aku beranjak memasuki rumah, perlahan kututup pintunya. Cahaya hidup suamiku terasa semakin kecil, redup kemudian musnah. Aku tahu sebentar lagi akan terdengar suara titir kentongan ditabuh memenuhi sunyi malam, menandakan bahwa telah terjadi pembunuhan. Tarakan, 24 Desember 2011
*) ide dari kalimat di Novel Tarian Bumi Oka Rusmini.
Cerpen dewasa pertama yang saya buat. Selain cerpen dongeng yang beberapa ada dimuat di majalah anak-anak Bobo. Mohon kritik dan saran, serta like or dislike dari pembaca. Yang sangat berharga dalam mendukung perbaikan kualitas penulisan cerpen-cerpen yang mungkin akan muncul kemudian. Trmksh. E-mail : jokop96@yahoo.com
Anda mungkin juga menyukai
- Selingkuh Undercover: Lurah JasmineDari EverandSelingkuh Undercover: Lurah JasminePenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (10)
- Malam Ketika Dia Menembak Dirinya (Kumpulan Cerpen)Dari EverandMalam Ketika Dia Menembak Dirinya (Kumpulan Cerpen)Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Kumpulan Cerpen Kompas PDFDokumen150 halamanKumpulan Cerpen Kompas PDFbejokampungan100% (1)
- Puisi BaladaDokumen6 halamanPuisi BaladaRita AgustiniBelum ada peringkat
- Perempuan Penunggu MalamDokumen6 halamanPerempuan Penunggu MalamAmat JawakonoraBelum ada peringkat
- DokumenDokumen5 halamanDokumenBorutoBelum ada peringkat
- GEGURITANDokumen8 halamanGEGURITANRokhman MahfudBelum ada peringkat
- Cerpen Sandal Jepit MerahDokumen3 halamanCerpen Sandal Jepit MerahKadir JavaBelum ada peringkat
- Slide LgiiDokumen58 halamanSlide LgiiJonathan SimanulangBelum ada peringkat
- Sapardi Djoko Darmono - Ayat-Ayat ApiDokumen92 halamanSapardi Djoko Darmono - Ayat-Ayat ApiAmri DosantosBelum ada peringkat
- Ambe Masih SakitDokumen5 halamanAmbe Masih SakitDavit Banten Tandi PaloboBelum ada peringkat
- GELAPDokumen4 halamanGELAPWaluyo JatiBelum ada peringkat
- Laki-Laki Yang Kawin Dengan PeriDokumen4 halamanLaki-Laki Yang Kawin Dengan PeriJan Petra100% (1)
- Anak YatimDokumen4 halamanAnak YatimMuhammad Luthfi Az ZuhriBelum ada peringkat
- Modul Latihan Bahasa Melayu Format Baharu UPSRDokumen8 halamanModul Latihan Bahasa Melayu Format Baharu UPSRraj_pegasusBelum ada peringkat
- Cerpen Mariana Amiruddin - Kota KelaminDokumen3 halamanCerpen Mariana Amiruddin - Kota KelaminAS100% (1)
- Rok Raven - 1-16Dokumen16 halamanRok Raven - 1-16budibasahBelum ada peringkat
- Cerpen GembalaDokumen4 halamanCerpen GembalaSimple ridiBelum ada peringkat
- Perempuan Balian - Kumpulan Cerpen KompasDokumen9 halamanPerempuan Balian - Kumpulan Cerpen KompasCecilia SutantoBelum ada peringkat
- Cerpen PEREMPUAN BALIANDokumen6 halamanCerpen PEREMPUAN BALIANpermen karetBelum ada peringkat
- Legenda Puti Ampo Dan Tapian Mandi Bujang HitamDokumen5 halamanLegenda Puti Ampo Dan Tapian Mandi Bujang Hitamroland mangkuto sutanBelum ada peringkat
- La RundumaDokumen7 halamanLa RundumaAris SusantoBelum ada peringkat
- Hutan MerahDokumen19 halamanHutan MerahKarisa Safira MfBelum ada peringkat
- Sang PengembaraDokumen5 halamanSang PengembaraMuh.syahrul RamadhanBelum ada peringkat
- Bersahabat Dengan AlienDokumen130 halamanBersahabat Dengan AlienAdiBelum ada peringkat
- MajasDokumen5 halamanMajasFenny LuciaBelum ada peringkat
- CerpenDokumen38 halamanCerpenAnnisa Nur FatimahBelum ada peringkat
- TessssssssDokumen7 halamanTessssssssRyoBelum ada peringkat
- Perempuan Dan KambojaDokumen4 halamanPerempuan Dan KambojaFathul Arifin100% (1)
- Seragam - Aris Kurniawan BasukiDokumen3 halamanSeragam - Aris Kurniawan BasukikatrinaBelum ada peringkat
- MDokumen114 halamanMagung gemaBelum ada peringkat
- DataDokumen17 halamanDataAbdi PrialamBelum ada peringkat
- Soal Puisi 23-24Dokumen5 halamanSoal Puisi 23-24SyxBelum ada peringkat
- Cerpen Dewi Ria UtariDokumen24 halamanCerpen Dewi Ria UtariUdi ArtiBelum ada peringkat
- Single Reading Karya Sastra Pendek Indonesia Pilihan SRBDokumen65 halamanSingle Reading Karya Sastra Pendek Indonesia Pilihan SRBZain Nabil HaiqalBelum ada peringkat
- CerpenDokumen38 halamanCerpenAnnisa Nur FatimahBelum ada peringkat
- Langkahnya Tertatih Menuju Pojok RumahDokumen5 halamanLangkahnya Tertatih Menuju Pojok RumahArief BudhimanBelum ada peringkat
- 1 5113998743095476344 PDFDokumen355 halaman1 5113998743095476344 PDFRestu FauziBelum ada peringkat
- Air Mata Nayang Dari Ranah BetungDokumen2 halamanAir Mata Nayang Dari Ranah BetungZumrotul MaulidaturrohmahBelum ada peringkat
- Cerpen Kompas Oktober 2009Dokumen18 halamanCerpen Kompas Oktober 2009hohomBelum ada peringkat
- Sandal Jepit MerahDokumen4 halamanSandal Jepit Merahchimonblack86Belum ada peringkat
- Surti Dan Tiga UnggasDokumen14 halamanSurti Dan Tiga UnggassintyaBelum ada peringkat
- Sulaiman Pergi Ke Tanjung CinaDokumen9 halamanSulaiman Pergi Ke Tanjung Cinas zBelum ada peringkat
- BaladaSahdi MaxarifinDokumen22 halamanBaladaSahdi MaxarifinAang sajaBelum ada peringkat
- Dongeng Domba-Domba (Cerpen)Dokumen5 halamanDongeng Domba-Domba (Cerpen)Rian HarahapBelum ada peringkat
- Senopati Pamungkas Seri 8Dokumen138 halamanSenopati Pamungkas Seri 8Adi DarmawanBelum ada peringkat
- Jenis Jenis Puisi LamaDokumen11 halamanJenis Jenis Puisi Lamachey shaBelum ada peringkat
- Cerpen Ambe Masih Sakit Oleh Emil AmirDokumen5 halamanCerpen Ambe Masih Sakit Oleh Emil AmirHasan NugrohoBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen74 halamanBab 1Muhammad Andi Catur FerdiansyahBelum ada peringkat
- Di KampungkuDokumen5 halamanDi KampungkuDavit Banten Tandi PaloboBelum ada peringkat
- Cerpen SulaimanDokumen24 halamanCerpen SulaimanAfan Anas Al HakimBelum ada peringkat
- Cerpen - Ledhek - Emayama Tuntas Dana - SMAN 1 Wonosari - Gunungkidul - Daerah Istimewa YogyakartaDokumen8 halamanCerpen - Ledhek - Emayama Tuntas Dana - SMAN 1 Wonosari - Gunungkidul - Daerah Istimewa YogyakartaEMAYAMA TUNTAS DANA XII-MIPA-2 SMAN 1 WonosariBelum ada peringkat
- Remidi Bahasa JawaDokumen13 halamanRemidi Bahasa JawaIndra Rob BourdonBelum ada peringkat
- Cerpen NendraDokumen25 halamanCerpen Nendranizar rahmantoBelum ada peringkat
- Penebusan DosaDokumen3 halamanPenebusan DosaAlwi Zain ShswBelum ada peringkat
- Sandal Jepit MerahDokumen4 halamanSandal Jepit MerahFitriianah SelfiahBelum ada peringkat
- Impian Besar SumirahDokumen6 halamanImpian Besar SumirahRestu PriyantiBelum ada peringkat