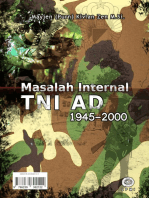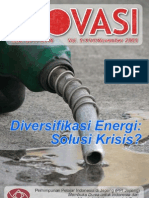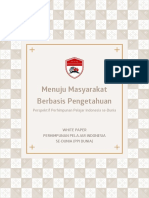Files Inovasi Vol.5 XVII November 2005 PDF
Files Inovasi Vol.5 XVII November 2005 PDF
Diunggah oleh
Bina Iqbal NugrahaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Files Inovasi Vol.5 XVII November 2005 PDF
Files Inovasi Vol.5 XVII November 2005 PDF
Diunggah oleh
Bina Iqbal NugrahaHak Cipta:
Format Tersedia
INOVASI Vol.
5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Majalah INOVASI
ISSN: 0917-8376
Volume 4 /XVII/ Agustus 2005
Daftar Isi
EDITORIAL.......1
UTAMA
1. BBM, kebijakan energi, subsidi dan kemiskinan di indonesia......................3
2. Konsumsi BBM dan Peluang Pengembangan Energi Alternatif.................11
3. Krisis Energi di Indonesia: Mengapa dan Harus Bagaimana.......18
4. Energi Nuklir dan Kebutuhan Energi Masa Depan.22
5. Diversifikasi Energi Melalui Gas Hidrat....27
6. Krisis BBM kita, belajar dari krisis Filipina..........31
INOVASI
1. Potensi pengembangan energi dari biomassa hutan di Indonesia......34
2. Rekayasa Minyak Pelumas dari bahan Botol Plastik Bekas.39
3. Campuran Bahan Bakar Waste Plastic Disposal (WPD) dan Orimulsion
sebagai Alternatif Bahan Bakar Motor Diesel..............................................41
IPTEK
1. Domestikasi laut atau restoking?...............................................................47
2. Pencemaran Udara, Suatu Pendahuluan......52
KESEHATAN
1. Kurang Gizi pada Ibu Hamil: Ancaman pada J anin.57
2. Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang.61
i
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
NASIONAL
1. Mahkamah Konstitusi unjuk gigi? Seputar Isu Impeachment dalam surat
Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden RI.65
2. Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 194570
3. Reformasi setengah hati: Refleksi atas kegagalan pemberantasan korupsi
di Indonesia..77
HUMANIORA
1. 60 Tahun J epang Pasca Perang Dunia II83
2. Bahasa dan Kognisi87
KIAT
1. Berburu Kerja di J epang90
2. Survive dengan arubaito95
FORUM
1. Keluar Dari Krisis97
TOKOH105
ii
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
EDITORIAL
Kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) sebesar 100 persen lebih pada
awal Oktober 2005 lalu telah mendorong
munculnya berbagai respons. Ada yang
positif dan ada pula yang negatif. Yang
positif adalah bersumber dari argumen
bahwa kebijakan kenaikan harga BBM
ibarat bom waktu yang suatu saat pasti
meledak. Namun dari kalangan mereka
pun terbagi menjadi dua kelompok,
masing-masing yang mendukung
kenaikan 100% dan yang tidak. Yang
mendukung berpendapat bahwa
kebijakan sekali pukul (one hit policy)
lebih baik agar rakyat hanya sekali
terkejut namun setelah itu tenang.
Sementara yang tidak mendukung
berpendapat bahwa lebih baik kenaikan
secara bertahap supaya rakyat tidak
mengalami kejutan besar. J uga, soal
waktu sebaiknya kebijakan tidak
dilakukan menjelang lebaran mengingat
masa-masa tersebut inflasi biasanya
meningkat. Serta, program kompensasi
mesti dipersiapkan dengan matang
sehingga benar-benar membantu rakyat
menghadapi kejutan kenaikan harga BBM.
Tidak seperti kenyataan bahwa untuk
kenaikan harga BBM Maret 2005, sampai
bulan September 2005 dana kompensasi
yang disalurkan belum sampai 100%.
Untuk infrastruktur pedesaan, dananya
belum cair. Sementara itu, bantuan
operasional sekolah (BOS) baru 47
persen dan untuk kesehatan, khususnya
asuransi kesehatan, mencapai 50 persen.
Artinya ada jarak waktu yang cukup lama
antara kenaikan harga BBM dan distribusi
dana kompensasi. Pada rentang itu
pulalah rakyat menderita karena tidak ada
penopang untuk menghadapi tekanan
harga barang dan jasa.
Adapun yang merespons secara negatif
umumnya lebih bersifat struktural. Artinya,
dilema kebijakan kenaikan harga BBM
sebenarnya bisa diantisipasi dengan
langkah-langkah fiskal, seperti disiplin
anggaran serta permohonan
penghapusan hutang luar negeri. Tentu
kalangan ini memahami betul bahwa
dampak kenaikan harga BBM terhadap
kemiskinan sangatlah besar dan juga sulit
dihadapi dengan mengandalkan program
kompensasi. Mengingat institutisionalisasi
program kompensasi sungguh kompleks.
Artinya kenaikan harga BBM adalah
langkah-langkah yang benar-benar akhir.
Namun, ada pula yang bersumber dari
sentimen politik yang hanya anti kebijakan
kenaikan BBM tanpa usulan solusi yang
elegan.
Diantara dua kubu di atas, ada lagi
kelompok yang tidak ingin masuk dalam
wacana pro-kontra, namun lebih pada
keinginan memberikan solusi jangka
panjang. Yakni, menawarkan diversifikasi
energi untuk mengurangi ketergantungan
pada BBM yang bersumber dari fosil.
Maklum, Cadangan minyak Indonesia
terus menurun: pada tahun 1974 sebesar
15.000 metrik barel (MB), pada tahun
2000 sekitar 5123 MB, dan tahun 2004
menjadi sekitar 4301 MB. Diversifikasi
energi dapat dilakukan melalui
pengembangan sumber-sumber energi
baru, seperti bioethanol, biodiesel, panas
bumi, mikrohidro, biomassa, tenaga surya,
tenaga angin, limbah, nuklir dan
seterusnya. Agenda diversifikasi ini tentu
tidak saja hanya pada tingkat kelayakan
teknologi, tapi juga mesti sampai pada
kelayakan sosial-ekonomi dan lingkungan.
Inilah tantangan buat para ilmuwan untuk
berkolaborasi satu sama lain dalam
mencapai ketiga kelayakan tersebut
sekaligus. Dengan harapan kita tidak lagi
tergantung pada bahan bakar fosil, bisa
terbebas dari ancaman pemanasan global,
serta relatif tenang tanpa diombang-
ambing oleh harga minya internasional
yang tak menentu.
Di tengah respons ketiga kelompok di
atas, ada lagi respons lain yang lebih
bersifat kultural, yakni gerakan hemat
energi. Gerakan ini terpaksa diinisiasi
pemerintah karena kita memang belum
sadar pentingnya hemat energi. Padahal
Di J epang hemat energi sudah
membudaya. Lihat saja kebanyakan teras
dan rumah gelap di malam hari, begitu
pula jalan-jalan. Kebiasaan berjalan kaki
berlaku sejak kecil mengingat murid
sekolah dasar diwajibkan berjalan kaki ke
sekolah. Ada juga ketentuan batas
minimal dan maksimal untuk pendingin
atau pemanas ruangan. Namun demikian
replikasi budaya hemat energi ala J epang
juga tidak mudah mengingat konteks
1
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
sosial budaya yang berbeda. Sebut saja
tingkat kepercayaan (trustworthy) sesama
warga, tingkat keamanan, tata ruang kota,
dan seterusnya.
J adi, disamping kita perlu utak-atik sisi
fiskal baik melalui disiplin anggaran,
permohonan penghapusan hutang, cari
solusi kompensasi yang tepat, juga mesti
diiringi dengan diversifikasi energi serta
gerakan hemat energi. (ARIF SATRIA)
2
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
UTAMA
BBM, Kebijakan Energi, Subsidi, dan Kemiskinan di Indonesia
Teguh Dartanto
Staf Bidang Pemikiran dan Kajian PPI J epang
Research Student Graduate School of Economics Hitotsubashi University
Staf Pengajar dan Peneliti LPEM FEUI
E-mail: tdartanto@yahoo.com
1. Pendahuluan
Kenaikan harga minyak yang mencapai
60.63 US$/Barel memberikan masalah
tersendiri bagi negara-negara pengimpor
minyak. Kenaikan harga minyak secara
langsung akan meningkatkan biaya
produksi barang dan jasa dan beban hidup
masyarakat dan pada akhirnya akan
memperlemah pertumbuhan ekonomi
dunia. Terdapat empat faktor utama yang
mempengaruhi kenaikan harga minyak
secara tajam. Pertama, invasi Amerika
Serikat ke Irak: invasi ini menyebabkan
ladang minyak di Irak tidak dapat
berproduksi secara optimal sehingga
supply minyak mengalami penurunan.
Kedua, permintaan minyak yang cukup
besar dari India dan Cina. Ketiga, badai
Katrina dan Rita yang melanda Amerika
Serikat dan merusak kegiatan produksi
minyak di Teluk Meksiko [7]. Keempat,
ketidakmampuan dari OPEC untuk
menstabilkan harga minyak dunia.
Gambar 1. Rata-rata mingguan
fluktuasi harga minya mentah OPEC
Kenaikan harga minyak menjadi petaka
tersendiri bagi pemerintah Indonesia.
Pada kenyataannya Indonesia yang saat
ini dikenal sebagai salah satu penghasil
minyak dunia sekarang merupakan salah
satu negara pengimpor minyak [6].
Kenaikan ini akan meningkatkan beban
anggaran pos subsidi BBM dan pada
akhirnya akan meningkatkan defisit APBN
dari sekitar 0.7% Produk Domestik Bruto
(PDB) menjadi 1.3% PDB [2]. Upaya
pemerintah untuk menutupi defisit APBN
adalah menaikkan BBM pada bulan Maret
2005 sebesar 29% dan disusul kenaikan
yang tidak wajar dibulan
Oktober 2005 sebesar lebih dari 100%.
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) selalu menimbulkan pro-kontra
dikalangan masyarakat dan banyak
opini/pendapat muncul tanpa diikuti oleh
data-data yang akurat sehingga
membingungkan masyarakat.
Pemahaman yang komprehensif
mengenai permasalahan BBM akan
membuka cakrawala dan pola pikir baru
terhadap permasalahan yang terjadi. Pada
tulisan ini, penulis berupaya memberikan
gambaran yang obyektif terhadap
permasalahan BBM di Indonesia baik dari
sisi produksi, kebijakan energi nasional,
alokasi pemanfaatan BBM, dampak
kenaikan BBM terhadap inflasi,
kemiskinan dan permasalahan sosial
lainnya.
2. Produksi Minyak Indonesia
1
Cadangan minyak Indonesia pada tahun
1974 sebesar 15.000 metrik barel dan
terus mengalami penurunan. Pada tahun
2000 cadangan minyak Indonesia sekitar
5123 metrik barel (MB) dan tahun 2004
menjadi sekitar 4301 MB. Penurunan
cadangan minyak disebabkan oleh dua
faktor utama yaitu eksploitasi minyak
selama bertahun-tahun dan minimnya
eksplorasi atau survei geologi untuk
menemukan cadangan minyak terbaru.
Tanpa ditemukan cadangan minyak baru,
1
Hati-hati jika mencuplik data atau pernyataan
pada bagian ini, karena dapat menimbulkan
salah persepsi.
Dunia
3
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
praktis persedian minyak di Indonesia
hanya dapat dieksploitasi sampai sekitar
30 tahunan.
Tabel 1 menunjukkan bahwa produksi
minyak di Indonesia juga mengalami
penurunan dari tahun ketahun. Produksi
minyak tertinggi di Indonesia terjadi pada
tahun 1977 yaitu 1686.2 (ribu barel/hari)
dan terus mengalami penurunan hingga
tahun 2004 yaitu sebesar 1094.4 (ribu
barel/hari). Penurunan ini disebabkan oleh
sumur-sumur yang ada sudah tua,
teknologi yang digunakan sudah
ketinggalan dan iklim investasi disektor
pertambangan minyak kurang kondusif
sehingga tidak banyak perusahaan asing
maupun nasional melakukan investasi
disektor perminyakan. Sedangkan disisi
konsumsi, konsumsi terhadap produk
minyak/Bahan Bakar Minyak terus
mengalami peningkatan seiring dengan
pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Sejak tahun 2004,
jika hasil produksi minyak Indonesia di
semua kilang dihitung, maka hasilnya
tetap tidak dapat mencukupi kebutuhan
dalam negeri. Sejak tahun 2004,
Indonesia telah mengalami defisit sebesar
49.3 ribu barel/hari.
Tabel 1. Kondisi perminyakan di Indonesia
Kondisi
perminyaka
n
Indonesia
2000 2001 2002 2003 2004
Produksi
minyak
1272.
5
1214.2 1125.4
1139.
6
1094.
4
Konsumsi
minyak
996.4 1026 1075.4
1112.
9
1143.
7
Impor
minyak
mentah
219.1 326 327.7 306.7 330.1
Ekspor
minyak
mentah
622.5 599.2 639.9 433 412.7
Kapasitas
pengilangan
1057 1057 1057 1057
1055.
5
Output
pengilangan
968.2 1006.1 1002.4 944.4
1011.
6
Cadangan
minyak
(MB)*
5123 5095 4722 4320 4301
*data ini merupakan data stock (1000
barel/hari)
Sumber: OPEC [5]
*Data ekspor dan impor minyak mentah
menunjukkan bahwa Indonesia adalah
net-eksportir, tetapi sebagian besar ekspor
dilakukan oleh Kontraktor KPS sehingga
penerimaannya tidak masuk APBN
sedangkan impor seluruhnya dilakukan
oleh Pertamina sehingga masuk pos
APBN.
Tetapi perlu diingat bahwa produksi
minyak Indonesia bukan hanya milik
Pemerintah Indonesia saja tetapi hasil
minyak produksi Indonesia tersebut harus
dibagi dengan Kontraktor perusahaan
minyak asing (Production Sharing
Contract(dikenal dengan istilah KPS))
yang beroperasi di Indonesia. Skema bagi
hasil yaitu sebesar 85% Pemerintah Pusat
dan 15% Kontraktor. Perlu diingat bahwa
pembagian 85% da 15% bukanlah hasil
produksi kotor, tapi merupakan hasil
produksi minyak bersih artinya nilai
produksi dikurangi dengan biaya ekploitasi,
pajak, land-rent, royalti,dll. Sehingga bagi
hasil minyak mentah antara pemerintah
dan KPS bisa menjadi 60% dan 40%
seperti yang ditulis Kwik Kian Gie
berikut: Tabel 1 menjelaskan bahwa
produksi minyak mentah sebanyak
1.125.000 barel per-hari yang dibagi
menjadi "Bagian Pemerintah dan
Pertamina" sebanyak 663.500 barel atau
58,98% dan "Bagian Kontraktor
Production Sharing (KPS)" sebesar
461.500 barrel atau 41,02%. Yang
dipahami oleh rakyat adalah bagian
Indonesia 85% dan bagian kontraktor
asing 15%. Bagaimana dapat dijelaskan
pembagian yang demikian signifikan
perbedaannya? [5].
Berdasarkan perhitungan diatas maka
minyak mentah yang diterima pemerintah
adalah sebesar 656.64 ribu barel/hari
(60%x1094,4) sedangkan KPS menerima
437.76 ribu barel/hari. Bagian minyak KPS
diekspor keluar negeri dan semua
hasilnya merupakan milik KPS.
Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 dan
UU No.33 tahun 2004 mengenai
Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah, maka hasil minyak yang diperoleh
pemerintah pusat harus dibagi dengan
daerah penghasil dengan proporsi 85%
dan 15%. Berdasarkan skema bagi hasil
tersebut maka pemerintah pusat
menerima bagian minyak sebesar 558.14
ribu barel/hari dan sisanya adalah miliki
pemerintah daerah penghasil. Bagian
daerah penghasil tidak diberikan dalam
bentuk minyak tetapi diberikan dalam
bentuk tunai sebesar harga minyak yang
ditetapkan dalam APBN. J adi pada
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
4
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
dasarnya pemerintah pusat mengimpor
minyak dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data diatas dapat dilakukan
perhitungan sederhana berapa harga BBM
yang dapat dijual ke masyarakat dengan
asumsi harga bagian pemerintah pusat
adalah 0. Perhitungan sederhana adalah
sebagai berikut.
Tabel 2. Perhitungan dana pembelian
BBM
Barel
Minyak
Harga
US$/Bar
el
Har
i
J umlah
Minyak
pemerinta
h
pusat
558,144 0 365 0
Minyak
pemerinta
h
daerah
98,496 45* 365
1,617,796,80
0
Impor
minyak
mentah**
330,100 60 365
7,229,190,00
0
Impor
BBM
jadi***
132,100 65 365
3,134,072,50
0
Pengilang
an,
transporta
si,dll****
1,011,6
00
5 365
1,846,170,00
0
J umlah
13,827,229,3
00
Sumber: Perhitungan Penulis, 2005
*Harga minyak asumsi APBN, **Data
impor minyak mentah Tabel 1, ***Data
impor BBM jadi adalah selisih antara
konsumsi minyak dan output pengilangan
pada Tabel 1, **** Data ini berasal dari
jumlah output yang minyak yang dikilang
J adi dana penyediaan BBM dalam
setahun adalah sebesar
13.827.229.300US$ atau setara dengan
Rp. 138 triliun rupiah. Dengan asumsi 1
barel=159 liter (1 barrelbervariasi antara
120 hingga 159 liters.www.answer.com)
maka harga jual rata-rata BBM adalah
sebesar Rp 2.360/liter (harga jual break-
even point). Tetapi konsekuensi dari
kebijakan mengasumsikan minyak milik
pemerintah pusat 0US$ berarti pos
penerimaan minyak di APBN tidak ada
dan hal ini akan
menurunkan/menghilangkan jumlah
penerimaan negara sebesar Rp. 120 triliun
dan semakin memperbesar defisit APBN.
Tetapi jika harga minyak bagian
pemerintah pusat dianggap sebagai
penerimaan negara dan dihargai sesuai
dengan harga asumsi APBN maka biaya
penyediaan BBM Rp.230 triliun rupiah dan
harga jual rata-rata BBM adalah sebesar
Rp. 3920/liter. Dengan mengasumsikan
minyak milik pemerintah pusat dianggap
sebagai penerimaan negara maka
terdapat pos penerimaan minyak di APBN,
terjadi peningkatan penerimaan APBN dan
defisit anggaran menurun. Dengan
mengasumsikan harga minyak mengikuti
harga dunia sebesar 60US$/barel maka
dana penyediaan BBM adalah sebesar Rp.
266 triliun dan harga jual rata-rata BBM
adalah sebesar Rp. 4.530/liter.
Kenaikan asumsi harga minyak akan
memberatkan APBN, selain itu kenaikan
harga BBM akan meningkatkan
penerimaan pemerintah pusat.
Konsekuensi kenaikan penerimaan dalam
APBN maka pemerintah pusat harus
meningkatkan Dana Bagi Hasil baik dalam
bentuk Dana Alokasi Umum (DAU)
maupun Dana Bagi Hasil Minyak (DBHM)
kepada daerah. Sedangkan disisi lain
kenaikan harga minyak akan
meningkatkan dana penyediaan harga
BBM. Dari perhitungan sederhana diatas
terlihat penentuan harga BBM sangat
tergantung terhadap asumsi harga BBM
dan asumsi apakah penerimaan minyak
dianggap sebagai penerimaan negara
atau bukan.
3. Kebijakan Energi Nasional
Kebijakan penentuan harga energi di
Indonesia tidak dilakukan melalui
mekanisme pasar melainkan ditetapkan
secara administrasi oleh pemerintah.
Dalam penentuan harga energi ada empat
hal yang harus dipertimbangkan yaitu :
a. tujuan efisiensi ekonomi : untuk
memenuhi kebutuhan energi dalam
negeri dengan harga
serendah-rendahnya dan memelihara
cadangan minyak untuk keperluan
ekspor, khususnya dengan
mendorong pasar domestik untuk
mensubstitusikan konsumsinya
dengan alternatif bahan bakar lain
yang persediaannya lebih melimpah
(gas dan batubara) atau sumber
energi yang nontradable seperti
tenaga air (hydropower) dan panas
bumi (geothermal),
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
5
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
b. tujuan mobilisasi dana : dengan
memaksimumkan pendapatan ekspor
dan pendapatan anggaran pemerintah
dari ekspor sumber energi yang
tradable seperti migas, dan batubara
dan memungkinkan produsen dari
sumber-sumber energi untuk
menutupi biaya-biaya ekonominya dan
memperoleh sumber-sumber dana
untuk membiayai pertumbuhan dan
pembangunan,
c. tujuan sosial (pemerataan) :
mendorong pemerataan melalui
perluasan akses bagi kebutuhan
pokok yang bergantung pada energi
seperti penerangan, memasak dan
transportasi umum, dan
d. tujuan kelestarian lingkungan:
mendorong agar pencemaran
lingkungan seminum mungkin sebagai
dampak pembakaran sumber-sumber
energi.
Keempat tujuan di atas merupakan
faktor-faktor yang perlu diperhatikan
dalam menentukan tujuan di atas,
sehingga kemungkinan bentrokan antar
tujuan dapat di atasi. Keempat tujuan di
atas tidak mungkin dicapai karena konflik
antar tujuan pasti akan terjadi. Sebagai
contoh studi yang dilakukan Pitt (1985
dalam [4]) menunjukkan tujuan untuk
mengurangi dampak lingkungan praktis
tidak tercapai.
4. Alasan Kenaikan Harga Minyak di
Indonesia
Argumen yang dilakukan pemerintah
untuk dan kalangan pendukung kenaikan
BBM adalah sebagai berikut:
a. perbedaan harga jual domestik
dengan harga luar negeri yang sangat
timpang akibat peningkatan harga
minyak bumi yang dewasa ini telah
mencapai US$ 50 per barrel, jauh di
atas harga minyak bumi yang
ditetapkan dalam asumsi harga
minyak dalam APBN 2005 sebesar
US$ 24 per barrel. Perbedaan harga
ini menimbulkan kemudian
pembengkakan subsidi,
Tabel 3. Tambahan defisit APBN 2005
akibat kenaikan harga minyak
Harga
Minya
k
$28/bb
l
$30/bb
l
$32/bb
l
$38/bb
l
$40/bb
l
Rp
(triliun)
2.9 4.3 5.7 8.5 11.4
% thd
PDB
0.1 0.2 0.2 0.3 0.4
Sumber: Estimasi Staf[4]
b. penyesuaian harga BBM telah
dilakukan oleh hampir semua negara
di dunia termasuk negara-negara
yang berpendapatan lebih rendah dari
Indonesia seperti India, Bangladesh
atau negara-negara di Afrika. Bahkan
di Timor Timur yang merupakan
salah satu negara termiskin di dunia
harga domestik BBM jauh di atas
harga BBM di Indonesia.
Germany
UK
J apan
India
Brazil
USA
Russia
China
Nigeria
Indonesia
Egypt
Grafik 2. Perbandingan harga premium di
berbagai negara
c. harga domestik yang domestik yang
terlalu rendah juga telah mendorong
pertumbuhan tingkat konsumsi yang
sangat tinggi. Sepanjang tahun 2004
lalu pertumbuhan BBM antara 5 % per
tahun. Sementara produksi minyak
mentah Indonesia terus mengalami
penurunan. Selain itu perbedaan
harga domestik dan international yang
cukup tinggi mendorong terjadinya
penyelundupan,
d. alasan lain yang menjadi dasar adalah
menyangkut masalah keadilan.
Subsidi BBM lebih banyak dinikmati
oleh kelompok 40% kelompok teratas
temasuk untuk minyak tanah
sekalipun,
0 5 100 150 0
P
r
e
m
u
r
o
c
e
n
t
s
p
e
r
l
i
i
u
m
P
e
t
r
o
l
[
E
t
e
r
]
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
6
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Tabel 4. Proporsi komsumsi BBM
berdasarkan kelompok pengeluaran
Kelompok Pengeluaran BBM
Minyak
Tanah
20% Terbawah 7 10
20% Kedua Terbawah 11 15
20% Ditengah 16 20
20% Kedua Teratas 23 24
20% Teratas 43 31
Sumber: Susenas 2002
a. penyesuaian harga BBM ini
memungkinkan pemerintah dengan
persetujuan DPR mengalokasikan
lebih banyak untuk program
penanggulangan kemiskinan dan
pembangunan pedesaan baik yang
bersifat investasi jangka panjang
(pendidikan dan kesehatan) maupun
pengurangan biaya transaksi
(infrastruktur pedesaan) dan
pengurangan beban keluarga miskin
dalam jangka pendek, dan
b. dalam jangka panjang kebijakan ini
juga akan mengoreksi kebijakan
energi yang dewasa ini tidak rasional.
Harga relatif BBM dibandingkan
dengan batubara atau gas yang lebih
murah menyebabkan insentif
penggunaan sumber energi yang lebih
murah dan sumber domestik relative
melimpah berkurang. Prasyarat utama
untuk mendorong penggunaan
sumber energi ini (termasuk yang
renewable) adalah mengoreksi harga
BBM sehingga diharapkan efisiensi
penggunaan energi akan tercapai
dalam jangka panjang.
5. Dampak Kenaikan BBM Terhadap
Inflasi
Kenaikan harga BBM secara langsung
akan mempengaruhi kenaikan harga-
harga barang lain karena BBM merupakan
bagian dari faktor input. Dengan
menggunakan model ekonomi
keseimbangan umum (CGE) LPEM-UI [4],
secara keseluruhan dampak inflasi dari
kenaikan BBM Maret 2005 adalah sebesar
0.9718%.
2
Berdasarkan kenyataan diatas
2
Hasil perhitungan ini lebih rendah dibandingkan
dengan perhitungan yang dilakukan oleh metoda
lain. Misalnya Bank Dunia memperkirakan
dampak inflasi dari kenaikan harga BBM 30% ini
mencapai 1.2%
bahwa kenaikan BBM bulan Oktober 2005
diperkirakan akan menambah kenaikan
inflasi tahun 2005 sebesar 2.8-3.0%.
Estimasi dampak inflasi diatas hanya
mencakup perhitungan yang wajar
didasarkan pada struktur konsumsi rumah
tangga dan struktur biaya produksi industri.
Dengan demikian perhitungan diatas tidak
memperhitungkan kenaikan inflasi yang
disebabkan oleh faktor lain seperti perilaku
pengusaha untuk menggeserkan beban
kenaikan harga BBM kepada konsumen
dengan menaikkan harga produk mereka
secara tidak wajar.
Inflasi yang terjadi adalah gabungan dari
inflasi murni dan inflasi psikologis. Inflasi
yang terjadi pada bulan Maret 2005
sebulan setelah kenaikan harga BBM
adalah sebesar 1,93% dan bulan
berikutnya mengalami deflasi. Inflasi
psikologis disebabkan oleh para
pengusaha yang tidak wajar dalam
menggeser beban kenaikan BBM. Salah
satu contoh upaya untuk menggeserkan
beban kenaikan BBM secara tidak wajar
adalah tuntutan sopir angkutan dan
organda untuk menaikkan tarif sebesar
30%. Perlu dicatat bahwa total biaya
angkutan tidak hanya biaya operasi tapi
juga ada biaya kapital yang sangat besar.
Kalau dihitung dari biaya total biaya
secara keseluruhan, biaya BBM di sektor
angkutan darat rata-rata mencapai 13%
pada akhir tahun 2001. Setelah kenaikan
harga BBM tahun 2002, diperkirakan
diperkirakan pengeluaran BBM tidak
mencapai 20% dari total biaya produksi.
Dengan demikian, kenaikan yang wajar
dari tarip hanya sebesar 5.8%
(29%20%=5,8%) [4].
Tabel 5. Dampak inflasi dari
kenaikan harga BBM Maret 2005
J enis Barang
Kenaikan
Harga (%)
J enis Barang
Kenaikan
Harga
(%)
Padi 0.23 Konstruksi 2.041
Sayuran 0.26 Perdagangan 1.025
Hasil Ternak 0.441 Restoran 0.821
Perikanan
Laut
0.995 Hotel 0.767
Minyak
Goreng
0.471
Angkutan
Kereta Api
2.824
Beras 0.561
Angkutan
Darat
4.117
Gula 0.65 Pelayaran 3.082
Pertambanga
n
0.798 Angkutan Air 4.21
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
7
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Pupuk 0.537
Angkutan
Udara
0.097
Industri Baja 0.916 Komunikasi 0.481
Listrik 0.08 Keuangan 0.522
Gas 0.325
J asa-J asa
Lain
0.639
Air Bersih 0.477
Sumber: Hasil Simulasi Model CGE [4]
Hal ini juga didukung oleh temuan dari
pengolahan data statistik industri.
Ternyata, dari total input industri di
Indonesia pada tahun 2003, bahan bakar
minyak merupakan input dengan porsi
sedikit. Hanya sekitar 3,68 persen dari
total input industri. Secara sederhana, jika
terjadi kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) sebesar 80 persen
sekalipun, maka implikasi peningkatan
biaya input produksi hanya sekitar 2,94
persen (Syarif Syahrial, Kompas, 1
Oktober 2005).
6. Dampak Kenaikan BBM Terhadap
Kemiskinan
Dampak kenaikan harga BBM terhadap
kemiskinan sangat tergantung terhadap
kenaikan harga BBM terhadap inflasi.
Inflasi akan mendorong peningkatan garis
kemiskinan. J ika inflasi yang ditimbulkan
oleh kenaikan BBM khususnya inflasi
bahan makanan cukup tinggi maka
dampak kenaikan BBM terhadap
kemiskinan juga tinggi. Berdasarkan hasil
simulasi data Susenas 2002 menunjukkan
bahwa kenaikan jumlah penduduk miskin
akibat kenaikan harga BBM bulan Maret
2005 (asumsi inflasi sebesar 0.9%) adalah
sebesar 0.24% (dari 16.25%-1649%) dan
jika inflasi yang terjadi semakin besar
maka angka kemiskinan juga akan
membesar. Berdasarkan kenyataan diatas
kemungkinan besar kenaikan BBM
Oktober 2005 akan meningkatkan jumlah
penduduk miskin sebesar 1% atau sekitar
2 juta orang.
Tabel 6. Dampak Kenaikan Inflasi
dan Kemiskinan di Indonesia
Initial Expected Inflation
Conditio
n
1X 2X 3X 4X
Povert
y (HCI)
16,25 16,49 16,68 16,95 17,18
Source: Working Paper [4]: The impact
study of the increasing
fuel price 2005 to the poverty incidence
Calculation from Susenas 2002
* garis kemiskinan yang digunakan adalah
garis kemiskinan BPS 2002 yaitu
perkotaan=Rp. 130.499/bulan/kapita dan
pedesaan=Rp. 96.512/bulan/kapita.
*
Data Tabel 6 merupakan angka simulasi
dan data Susenas 2002 tidak termasuk
Aceh dan Papua.
7. Dampak Kompensasi BBM Terhadap
Kemiskinan dan Problematika Sosial
Tujuan utama kebijakan dana kompensasi
BBM berupa Raskin dan Subsidi Tunai
Langsung (SLT) adalah sebagai jaring
pengaman sosial yang bersifat sementara
yaitu mengamankan orang-orang yang
berada dibawah garis kemiskinan dan
hampir miskin terhadap gejolak
perekonomian. Secara teoritis kebijakan
``Cash Transfer`` lebih baik jika
dibandingkan subsidi BBM seperti yang
terjadi selama ini dimana sebagian besar
BBM dinikmati kelompok non-miskin.
Berdasarkan teori compensating variation
(Varian, 1996 dalam Dartanto,Media
Indonesia, 2005) menunjukkan bahwa
``Cash Transfer`` akan mengembalikan
daya beli kelompok miskin pada kondisi
yang semula yaitu kondisi daya beli
sebelum adanya kenaikan harga BBB.
Dana Kompensasi BBM Raskin dan SLT
bukanlah program pengentasan
kemiskinan yang bersifat jangka panjang
dan berkelanjutan, tetapi lebih bersifat
sementara dan konsumtif. Kebijakan dana
kompensasi BBM menimbulkan berbagai
problematika sosial tersendiri. Dampak
yang sangat besar dari kebijakan ini
adalah dampak sosial. Walaupun dampak
ini tidak mudah untuk dikuantifisir, tetapi
kebijakan masif transfer menyimpan
potensi yang besar untuk menyulut
kecemburuan sosial, merusak tatanan dan
ikatan sosial dilevel bawah. Berdasarkan
pengamatan penulis pada kasus
penyaluran Raskin disebuah desa di
Kabupaten Pati, J awa Tengah,
menunjukkan bahwa ketika raskin hanya
diberikan kepada kelompok miskin
ternyata menimbulkan kecemburuan bagi
kelompok yang nyaris miskin dan tidak
miskin (Teguh Dartanto, Media Indonesia,
12 September 2005). Permasalahan lain
yang muncul belakangan ini adalah
banyak warga miskin yang tidak terdaftar
sebagai penerima dana kompensasi,
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
8
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
salah sasaran, keributan antar warga,
pengrusakan kantor pos dan gedung
kelurahan, mati berdesak-desakan saat
pengambilan SLT, ketua RT bunuh diri,
warga bunuh diri,dll.
8. Rekomendasi Kebijakan
a. Sebagai upaya untuk mengurangi
ketergantungan terhadap impor
minyak, pemerintah seharusnya
berupaya untuk meningkatkan
produksi minyak nasional dengan
perbaikan iklim investasi di sektor
pertambangan minyak sehingga
mampu menggairahkan kegiatan
eksplorasi dan eksplitasi minyak bumi.
b. Walaupun pencabutan subsidi BBM
secara teori ekonomi memiliki
argumentasi yang kuat, pemerintah
juga harus memperhatikan faktor
sosial dan politik akibat pencabutan
subsidi BBM.
c. Untuk meningkatkan kepercayaan
publik, pemerintah seharusnya
melakukan pembenahan dan audit
Pertamina
d. Upaya untuk menolong dunia usaha
yang kian terpuruk akibat kenaikan
BBM, maka pemerintah dapat
melakukan: penghapusan ekonomi
biaya tinggi, penghapusan berbagai
pungutan resmi maupun tidak resmi,
penyederhanaan rantai perijinan serta
insentif fiskal.
e. Pemerintah harus bersikap dan
bertindak tegas terhadap pengusaha
yang menggeser kenaikan harga BBM
dengan menaikkan harga secara tidak
wajar dan tidak didukung data yang
kuat.
f. Kenaikan kebutuhan bahan pokok
dapat meningkatkan kemiskinan
secara tajam, oleh karena itu
pemerintah seharusnya mampu
mengendalikan harga kebutuhan
pokok ditingkat yang wajar sehingga
tidak memberatkan kalangan
konsumen miskin dan kalangan petani
sebagai produsen.
g. Pengalihan subsidi BBM ke subsidi
langsung sebaiknya diarahkan kearah
kegiatan yang bersifat produktif,
jangka panjang, berkelanjutan dan
mampu meningkatkan kapasitas
modal manusia seperti program padat
karya, pengembangan usaha kecil
menengah, pendidikan dasar dan
kesehatan.
h. Raskin dan Subsidi Tunai Langsung
secara masif seperti saat ini harus
diposisikan sebagai J aring Pengaman
Sosial yang bersifat emergency dan
sementara.
i. Subsidi Langsung Tunai untuk
selanjutnya seharusnya diberikan
kepada kelompok usia non-produktif
diatas 60 tahun yang miskin sebagai
J aminan Sosial. Sedangkan kelompok
miskin usia produktif diarahkan untuk
berusaha dan bekerja.
9. Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan diatas dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:
a. Cadangan minyak dan produksi
minyak dunia terus mengalami
penurunan sedangkan komsumsi
minyak semakin meningkat seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk
dan perekonomian sehingga sejak
tahun 2004, Indonesia merupakan
net-importer.
b. Penentuan harga jual BBM di
Indonesia sangat ditentukan oleh
asumsi harga minyak APBN dan
asumsi apakah minyak dianggap
sebagai penerimaan negara atau
bukan.
c. Alasan kenaikan harga BBM di
Indonesia antara lain: defisit APBN,
kenaikan BBM dilakukan banyak
negara, harga BBM rendah
mendorong peningkatan konsumsi,
disparitas harga mendorong
penyelundupan, subsidi BBM banyak
dinikmati golongan kaya, realokasi
subsidi BBM ke subsidi yang bersifat
produktif, dan insentif berkembangnya
energi alternatif.
d. Dampak kenaikan BBM terhadap
kemiskinan sangat tergantung dari
dampak kenaikan BBM terhadap
inflasi khususnya inflasi bahan
makanan.
10. Daftar Pustaka
[1] Dartanto, Teguh, 2004, Is The
Economic Growth Enough for Reducing
The Poverty Incidence In Indonesia?,
Presentasi Paper: ISA 2004.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
9
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
[2] -----------------------, 2005a,
Mengkritik Kebijakan Cash Tranfer. Media
Indonesia:12/9/2005.
[5 ]Kwik Kian Gie, 2005, Minyak:
Teka-teki, manipulasi atau 'So What Gitu
Lho. Bisnis Indonesia, 12/09/2005.
[3] -----------------------, 2005b,
Kontroversi Kenaikan Harga BBM 2005.
Wacana Alumni, LPEM FEUI.
[6] OPEC, 2004, Annual Statistic
Bulletin.
[7] -------, 2005, Monthly Oil Market
Report. [4] Ikhsan, Dartanto, Usman, dan
Herman, 2005, Kajian Dampak Kenaikan
Harga BBM 2005 Terhadap Kemiskinan,
Working Paper:LPEM FEUI.
[8] Syahrial, Syarif.`` Redam
Ekspektasi Kenaikan Harga``.
Kompas,01/10/2005.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
10
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
UTAMA
Konsumsi BBM dan Peluang Pengembangan Energi Alternatif
Agus Syarip Hidayat
Mahasiswa Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC)
Hiroshima University
aa_gus@yahoo.com
1. Pendahuluan
Secara umum terjadinya peningkatan
kebutuhan energi mempunyai keterkaitan
erat dengan kian berkembang kegiatan
ekonomi dan kian bertambah jumlah
penduduk. Di Indonesia, dengan jumlah
penduduk mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun dan pertumbuhan ekonomi
terus berlangsung yang ditunjukkan oleh
kian bertambah output serta beragam
aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh
masyarakat, maka peningkatan kebutuhan
energi adalah suatu hal yang tak bisa
dihindari. Berdasarkan pemaparan Ditjen
Listrik dan Pemanfaatan Energi [4] dalam
diskusi di Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI
pada tahun 2004, dinyatakan bahwa pada
tahun 1970, konsumsi energi primer
1
hanya sebesar 50 juta SBM (Setara Barel
Minyak). Tiga puluh satu tahun kemudian,
tepatnya tahun 2001 konsumsi energi
primer telah menjadi 715 juta SBM atau
mengalami pertumbuhan yang luar biasa
yaitu sebesar 1330% atau pertumbuhan
rata-rata periode 1970-2001 sebesar
42.9%/tahun.
Di tengah cadangan energi yang kian
menipis, khususnya Bahan Bakar Minyak
(BBM), maka jelas keadaan ini sangat
mengkhawatirkan. Dalam situasi seperti ini,
maka memahami pola konsumsi energi
yang dilakukan oleh masyarakat adalah
suatu keharusan dan menjadi hal penting
bagi pemerintah sebagai regulator dan
pengendali kebijakan dalam
perekonomian khususnya dalam membuat
kebijakan dan aturan-aturan di bidang
energi. Selain itu, juga bagi masyarakat
sebagai konsumen untuk turut serta dalam
upaya menghemat dan mendiversifikasi
pemakaian energi.
1
Energi primer merupakan sumber energi yang
digali dari alam yang setelah memasuki proses
pengolahan kemudian dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan energi.
2. Konsumsi BBM, Batu Bara dan Gas
Bumi
2.1 Bahan Bakar Minyak
BBM masih merupakan energi utama yang
dikonsumsi oleh masyarakat. Persentase
konsumsinya terhadap total pemakaian
energi final merupakan yang terbesar dan
terus mengalami peningkatan. Pada tahun
1990 konsumsi BBM sebesar 169.168 ribu
SBM, angka ini adalah 40.2 % dari total
konsumsi energi final. Sepuluh tahun
kemudian, pada tahun 2000, konsumsinya
meningkat menjadi 304.142 ribu SBM,
dimana proporsi konsumsinya pun turut
meningkat menjadi 47.4 %. Proporsi
pemakaian BBM yang tinggi terkait
dengan keterlambatan upaya diversifikasi
ke energi non minyak akibat harga BBM
yang relatif murah karena masih
mendapat subsidi dari pemerintah [6].
Kebijakan pemberian subsidi BBM ini
dimulai sejak tahun anggaran 1977/1978
dengan maksud untuk menjaga stabilitas
perekonomian nasional melalui penciptaan
stabilitas harga BBM sebagai komoditas
yang strategis. Namun dalam
perjalanannya subsidi BBM ini ternyata
menimbulkan masalah tersendiri.
Masyarakat cenderung boros
menggunakan BBM dan ada indikasi
bahwa alokasi subsidi BBM lebih banyak
dinikmati oleh kelompok masyarakat
berpenghasilan tinggi yang seharusnya
tidak perlu mendapatkan subsidi.
Dilihat dari sisi pemakai BBM, sektor
transportasi merupakan pemakai BBM
terbesar dengan proporsi setiap tahun
selalu mengalami kenaikan. Kemudian di
susul oleh sektor rumah tangga, sektor
industri dan pembangkit listrik. Sedangkan,
jika dilihat ketersediaannya, selama ini
kebutuhan BBM dipasok oleh Pertamina
dan impor. Beberapa jenis energi BBM
yang sebagian penyediaannya melalui
Dunia
11
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
impor adalah avtur, minyak tanah, minyak
solar, minyak diesel, dan minyak bakar.
Tabel 1. Pangsa Konsumsi BBM Persektor
Tahun 1994-2003
Tah
un
Indu
stri
(%)
Ruma
h
Tangg
a &
Komer
sial
(%)
Transpo
rtasi
(%)
Pemba
ngkit
Listrik
(%)
199
4 23.2 21.6 45.8 9.4
199
7 21.1 19.0 47.9 12.0
199
8 21.5 20.7 48.8 9.0
200
0 21.7 22.2 47.1 9.0
200
3 24.0 18.2 47.0 10.7*
Sumber: Ditjen Migas. diolah.
*Termasuk sektor lain-lain
Satu hal yang mengkhawatirkan adalah
bahwa ada kecenderungan impor BBM
kian meningkat. maka bukan tidak
mungkin suatu saat Indonesia akan
mengimpor sepenuhnya kebutuhan BBM
bila upaya mendiversifikasi pemakaian
energi non BBM tidak dilakukan secara
serius. Pada tahun 1992 pemakaian BBM
sebagai energi final sebesar 201.577 ribu
SBM. ternyata kilang dalam negeri hanya
mampu memasok sekitar 167.944 ribu
SBM. sehingga harus mengimpor sekitar
33.633 ribu SBM atau bila dirata-ratakan
setiap harinya harus mengoimpor BBM
sebanyak 92.145 SBM. Angka impor BBM
ini terus meningkat hingga mencapai
107.935 ribu SBM pada tahun 2003 atau
sekitar 32.75 % dari total konsumsi BBM
dalam negeri.
2.2 Konsumsi Batubara
Pada tahun 1993. pemakaian batubara
mulai diperkenalkan untuk konsumsi
rumah tangga dan industri kecil yaitu
dalam bentuk briket batubara. Namun
perkembangannya kurang begitu
menggembirakan. Banyak faktor yang
menyebabkan batu bara kurang diminati
oleh masyarakat walaupun harganya
relatif murah. Menurut Indah Susilowati
PhD. ahli ekonomi sumber daya alam dari
Universitas Diponegoro menyatakan
bahwa ada tiga hal yang menyebabkan
masyarakat kurang tertarik menggunakan
energi alternatif (termasuk batubara) yaitu:
Pertama adalah masalah kebiasaan.
sudah sejak lama masyarakat terbiasa
menggunakan minyak dan sulit untuk
mengubah kebiasaan ini secara drastis.
butuh waktu yang lama. Kedua adalah
masalah kepraktisan. menggunakan
minyak lebih praktis dibandingkan dengan
bricket batu bara atau mungkin energi
altrnatif lainnya. Ketiga adalah
ketersediaan energi alternatif (briket
batubara dll) di pasar tidak terjamin secara
berkesinambungan.
Selama ini kebutuhan batubara dipasok
dari industri batubara dalam negeri dan
batubara impor. Secara kuantitas.
Indonesia dapat memenuhi kebutuhan
batubara dari sumber domestik. Kapasitas
produksi dan ketersediaan batubara dalam
negeri cukup melimpah. cadangannya
diperkirakan 36.3 milyar ton. namun 50-
85 %nya berkualitas rendah [5].
Selanjutnya. untuk mendapatkan hasil
olahan batubara yang bagus. maka perlu
ada campuran dengan batubara
berkualitas tinggi yang diimpor dari
beberapa negara. Pada tahun 1990. impor
batubara sekitar 2.930 ribu SBM atau
31.1% dari total konsumsi batubara
nasional. Secara perlahan impor batubara
ini terus mengalami penurunan. dan pada
tahun 2000 berkisar 661 ribu SBM atau
3% dari tingkat konsumsi batubara
nasional. Penurunan impor batubara ini
terjadi seiring dengan kemampuan industri
batubara dalam negeri untuk mengolah
batubara yang cukup berkualitas sesuai
dengan permintaan pasar.
2.3 Konsumsi Gas Bumi
Konsumsi gas bumi selama tahun 1990-
2000 pertumbuhannya rata-rata sekitar
4.7 % pertahun. Hingga tahun 2000.
tingkat konsumsinya hanya sebesar 5.8 %.
Selama ini pemanfaatan gas bumi lebih
banyak digunakan oleh sektor industri
untuk keperluan bahan bakar dalam
berproduksi. Pada tahun 2000. sektor
industri memanfaatkan sekitar 99 % dari
total konsumsi gas bumi dalam negeri [6].
Sementara sektor rumah tangga.
komersial. listrik dan transportasi hanya
sedikit saja menggunakan energi ini.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
12
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Gas bumi merupakan energi alternatif
yang potensial untuk dikembangkan
sebagai energi pengganti minyak bumi.
Gas bumi ini terdiri dari gas alam dan gas
kota. Total cadangannya sekitar 170
TSCF (Trillion Standard Cubic Feet).
sementara hingga saat ini yang terbukti
sebesar 95 TSCF. Dengan asumsi
produksinya konstan seperti saat ini
sebesar 2.9 TSCF dan tidak ditemukan
cadangan baru. maka jumlah ini cukup
untuk 30 tahun ke depan.
Belum optimal pemanfaatan gas bumi
selama ini lebih disebabkan oleh kurang
didukung sarana di bidang ini. Sebagai
contoh. di Palembang. Sumatra Selatan.
gas bumi dalam bentuk gas kota banyak
diminati oleh masyarakat. namun karena
keterbatasan sarana (pipa penyalur gas).
hanya sebagian kecil saja masyarakat
yang dapat terlayani.
3. Konsumsi Energi Berdasarkan
Sektor Pemakai
3.1 Konsumsi Energi Sektor Rumah
Tangga
Konsumsi energi sektor rumah tangga
adalah seluruh konsumsi energi untuk
keperluan rumah tangga tidak termasuk
konsumsi untuk kendaraan pribadi.
Konsumsi energi untuk kendaraan pribadi
dimasukkan ke dalam kelompok
penggunaan oleh sektor transportasi.
Berdasarkan data pangsa pemakaian
energi final walaupun tidak melakukan
aktivitas produksi yang bersifat komersial,
sektor rumah tangga merupakan sektor
pemakai energi final terbesar diantara
sektor lainnya [3]. Pada tahun 1990,
sektor rumah tangga mengkonsumsi
56.5 % dari total energi final. Memasuki
tahun 1995. proporsi pemakaiannya mulai
menurun menjadi 49.5% dan
kecenderungan penurunan ini terus
berlangsung, bahkan pada tahun 2000
tingkat pemakaian energi final oleh rumah
tangga menjadi 46.3 %. Kian menurun
pangsa pemakaian energi final di sektor
rumah tangga ini bukan dikarenakan
penurunan pemakaian energi di rumah
tangga. namun lebih disebabkan oleh
terjadi pertumbuhan sektor industri dan
transportasi yang pesat sehingga
menyebabkan besaran konsumsi energi
final menjadi bertambah besar.
Di kawasan ASEAN pun. pemakaian
energi oleh rumah tangga Indonesia
merupakan yang terbanyak bila
dibandingkan dengan negara anggota
ASEAN lainnya. Berdasarkan data ASEAN
Energy Review [2], pada tahun 1993
rumah tangga dan sektor komersial
Indonesia mengkonsumsi energi sebesar
52 % dari konsumsi energi total yang
dikonsumsi oleh rumah tangga dan sektor
komersial di ASEAN. Sementara konsumsi
energi negara lainnya seperti Thailand
sebesar 20.9%, Malaysia 11. 2 %,
Philipina 10.6%, Singapura 4.7%, dan
Brunei hanya 0.8%.
Berdasarkan jenis energi yang digunakan
tercatat bahwa minyak tanah merupakan
jenis energi terbesar kedua yang mereka
konsumsi setelah kayu bakar. Pangsa
konsumsi minyak tanah dari total energi
final yang dikonsumsi oleh rumah tangga
selama tahun 1990-2000 berkisar antara
16 -18 %.
3.2 Konsumsi Energi Alternatif di
Sektor Rumah Tangga
Selain minyak tanah. energi lain yang
dikonsumsi oleh rumah tangga adalah
briket. LPG. gas kota. listrik. arang dan
kayu bakar. Pangsa konsumsi sektor
rumah tangga untuk energi alternatif (non
minyak) ini mencapai kurang lebih 82%
dari total energi final yang dikonsumsi oleh
rumah tangga.
Pola konsumsi untuk energi non minyak di
sektor rumah tangga lebih terkonsentrasi
pada penggunaan kayu bakar. Sementara
batu bara yang sudah diperkenalkan untuk
konsumsi rumah tangga pada tahun 1993
ternyata tingkat penggunaan masih sangat
kecil. Hingga tahun 2000 hanya memilki
tingkat penggunaan sebesar 0.03%.
Dilihat dari pertumbuhan pun ada
kecenderungan kian menurun. Sama
halnya dengan batu bara. konsumsi LPG
dan gas kota juga tingkat penggunaannya
masih relatif kecil. Pada tahun 1990.
tingkat penggunaan LPG oleh rumah
tangga hanya 0.8 %. sementara gas kota
hanya 0.02%. Empat tahun berturut-turut
proporsi penggunaan LPG tidak
mengalami perubahan hanya sebesar
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
13
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
0.8 %. Hal yang sama terjadi pada
proporsi penggunaan gas kota. selama
delapan tahun berturut-turut tetap tidak
ada perubahan hanya sebesar 0.02%.
Beberapa faktor yang menyebabkan pola
konsumsi di sektor rumah tangga lebih
terkonsentrasi pada penggunaan minyak
tanah dan kayu bakar. yaitu: pertama,
faktor harga. Minyak tanah merupakan
energi dengan harga relatif lebih murah
dibandingkan dengan energi lain yang
digunakan untuk keperluan yang sama.
Kedua, faktor pendapatan. Sebagian
besar rumah tangga di Indonesia
merupakan kategori kelompok rumah
tangga dengan pendapatan rendah dan
menengah. Pada kelompok rumah tangga
seperti ini. energi (bahan bakar) yang
terjangkau dan umum digunakan adalah
minyak tanah dan kayu bakar. Ketiga,
alasan kepraktisan. Keempat, kurangnya
sosialisasi pemanfaatan energi non
minyak. Program pemanfaatan
diversifikasi energi yang dicanangkan oleh
pemerintah ternyata belum banyak
diketahui oleh masyarakat luas. Hingga
saat ini belum banyak masyarakat tahu
briket batubara dan cara
menggunakannya untuk keperluan rumah
tangga.
3.3 Konsumsi BBM di Sektor Industri
BBM merupakan energi dominan yang
digunakan untuk aktivitas produksi oleh
sektor industri. Selama tahun 1990-2000
tingkat konsumsi BBM sektor industri
terhadap total konsumsi BBM dalam
negeri rata-rata sebesar 21.8% setiap
tahunnya.
Konsumsi BBM oleh sektor industri
senantiasa mengalami kenaikan.
Peningkatan terbesar terutama terjadi
pada jenis minyak solar. minyak bakar dan
minyak tanah. Namun memasuki tahun
1998 konsumsi BBM sektor industri
mengalami penurunan sebesar 4.3%. Hal
ini berlanjut hingga tahun 1999 dimana
konsumsinya turun sebesar 6.2%.
Terjadinya penurunan ini merupakan efek
dari krisis ekonomi yang mulai melanda
pada pertengahan tahun 1997. Sejak
krisis ekonomi, banyak industri yang
menghentikan produksinya, sementara
yang lain walaupun tetap berproduksi
namun dengan kapasitas yang lebih
rendah dari sebelumnya. Kejadian seperti
ini banyak terjadi pada industri makanan
dan minuman, industri tekstil, pakaian jadi,
industri kulit, dan barang dari kulit.
Memasuki tahun 2000 konsumsi BBM di
sektor industri kembali meningkat, bahkan
pertumbuhan nya terbilang tinggi yaitu
23.5 %.
Dalam lingkup mikro perlu diwaspadai
bahwa peningkatan pemakaian energi di
sektor industri dalam beberapa tahun
terakhir bukan hanya terjadi karena proses
transformasi struktural yang cepat dari
pertanian ke industri saja. namun lebih
jauh dari itu diduga karena terjadi
pemborosan pemakaian energi di sektor
ini. Krisis moneter pada pertengahan
tahun 1997 telah membuat kurs rupiah
terdepresiasi sangat tajam. Keadaan ini
sangat memukul industri dalam negeri
yang selama ini masih memiliki
ketergantungan yang besar terhadap
mesin-mesin produksi impor, sehingga
banyak diantara mereka yang tak mampu
untuk mengup-grade mesin-mesin
produksinya. Sehingga banyak yang
beroperasi hanya mengandalkan mesin-
mesin tua yang tentu saja sangat boros
bahan bakar. Indikasi ini bisa dilihat dari
nilai intensitas energi pada tahun 1997
yaitu 4.196, nilai ini mengalami lonjakan
yang cukup besar dari tahun 1996 yang
hanya 2.637. Intensitas energi yang kian
besar berarti bahwa pemakaian energi
kian tidak efisien. Bila dilihat hubungan
nilai tambah sektor industri dengan
pemakaian energi, ternyata sebelum dan
sesudah krisis ekonomi mengalami
perubahan. Pada masa sebelum krisis
ekonomi. pertumbuhan nilai tambah lebih
besar dari pertumbuhan pemakaian energi.
Namun semenjak tahun 1998, yang terjadi
sebaliknya, pertumbuhan pemakaian
energi lebih besar dari pertumbuhan nilai
tambahnya. Hal ini khusus terjadi pada
industri makanan, industri tekstil, industri
kertas, dan industri kimia.
Selain itu ada dugaan bahwa pemakaian
energi di sektor industri lebih besar dari
data yang disajikan oleh departemen
energi dan sumber daya mineral. Selama
ini konsumsi energi di sektor industri
khususnya untuk BBM dicatat dengan
pendekatan dari sisi supply yaitu
berdasarkan pasokan langsung dari
Pertamina. Padahal kalau kita menyimak
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
14
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
berita di media massa. ternyata selama ini
banyak penyelewengan penggunaan BBM
oleh sektor industri yaitu berupa
pengalihan jatah BBM rumah tangga ke
sektor industri. Hal ini terjadi karena
adanya disparitas harga yang cukup besar.
dimana BBM untuk sektor industri sudah
tidak mendapat subsidi lagi dari
pemerintah. J adi sebenarnya intensitas
energi di sektor industri yang
menunjukkan tingkat efisiensi pemakaian
energi akan lebih besar dari angka yang
ada.
3.4 Konsumsi Energi Alternatif di
Sektor Industri
Energi alternatif (non minyak) yang
digunakan oleh sektor industri meliputi
batu bara, LPG gas, dan kayu bakar.
Rata-rata tingkat pemakaian energi non
minyak terhadap total energi final yang
dikonsumsi di sektor industri dalam
periode tahun 1990-2000 sekitar
47%/tahun. Tabel 2 di bawah
memperlihatkan bahwa pertumbuhan
konsumsi batubara di sektor industri cukup
tinggi dan terus meningkat. Pertumbuhan
yang negatif pada tahun 1996 lebih
disebabkan oleh terjadinya kenaikan
harga batubara untuk beberapa industri
yang menggunakan bahan bakar batubara
cukup besar. Pada tahun 1999 juga terjadi
kenaikan harga batubara untuk beberapa
industri dan lebih luas dari tahun 1996.
namun juga terjadi penurunan harga untuk
sebagian industri lainnya. maka
penurunan pemakaian batubara tidak
terlalu tajam sebesar 5.3 %.
Selanjutnya. konsumsi LPG dan gas di
sektor industri selama tahun 1990-2000
juga mengalami peningkatan yang cukup
besar. Rata-rata pertumbuhan pemakaian
LPG dan gas masing-masing sebesar
11.8 % dan 4.7 % pertahun dalam periode
tersebut. Krisis ekonomi yang dimulai
pertengahan tahun 1997 telah membuat
collapse beberapa industri. sehingga
permintaan energi pada tahun 1998
mengalami penurunan termasuk LPG dan
gas (kecuali batubara tetap meningkat).
Pertumbuhan pemakaian LPG yang
negatif pada tahun 1998 juga terjadi
karena kenaikan harga LPG untuk sektor
industri sebesar 50 %, yaitu dari Rp 1000
per kg menjadi 1500 per kg.
3.5 Konsumsi Energi Sektor
Transportasi
Sektor transportasi merupakan sektor
terbesar pengguna Bahan Bakar Minyak
diantara sektor-sektor lain. Pada tahun
1990. tingkat pemakaian BBM terhadap
pemakaian BBM total dalam negeri
sebesar 41.3 %. Angka ini terus
mengalami peningkatan hingga pada
tahun 2000 sudah mencapai 47.1 %.
Menurut studi yang pernah dilakukan oleh
Departemen Perhubungan, subsektor
perhubungan darat mengkonsumsi sekitar
80 % dari seluruh BBM yang dikonsumsi
oleh sektor perhubungan. Sementara
sektor perhubungan udara, perhubungan
laut, dan ASDP memakai sarana dengan
standar internasional, sehingga konsumsi
di sub sektor ini sudah dianggap mencapai
efisiensi yang wajar [1].
Peningkatan pemakaian BBM di sektor ini
berkaitan erat dengan pertumbuhan
jumlah kendaraan. Lebih jauh dari itu
Abdulkadir [1] menyebutkan bahwa
efisiensi dalam pemakaian BBM di sektor
transportasi sangat tergantung pada hal-
hal sebagai berikut: (1) pengaturan dan
disiplin lalu lintas yang baik, (2) kondisi
teknis mesin dan peralatan kendaraan
sebagai fungsi pemeliharaan dan
penggantian suku cadang yang tepat, (3)
cara dan teknik mengemudi, (4) kondisi
dan lebar jalan yang menentukan
kecepatan rata-rata kendaraan, (5)
banyaknya konstruksi atau cegatan
jalanan untuk pelbagai maksud, dan (6)
kepadatan lalu lintas yang berlebih-lebihan.
3.6 Konsumsi Energi Alternatif di
Sektor Transportasi
Penggunaan energi alternatif di sektor
transportasi sudah dirintis sejak 3 J anuari
1986. yaitu dengan memanfaatkan Bahan
Bakar Gas (BBG) sebagai pengganti
bensin atau solar. Program ini belumlah
dilaksanakan secara nasional, tapi masih
dalam bentuk Pilot Project yang khusus
digunakan pada taksi dan mikrolet di DKI
J akarta. Selain BBG, pada bulan Agustus
1995 ditetapkan juga pemanfaatan LPG
untuk sektor transportasi [7]. Dilihat dari
sisi harga. bahan bakar gas ini relatif lebih
murah sekitar Rp 450 per LSP (Liter
Setara Premium). Dilihat dari kegunaan
BBG lebih irit daripada premium. Bila
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
15
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
diasumsikan bahwa satu LSP BBG
memberikan manfaat yang sama dengan
satu liter premium, maka ada selisih harga
sekitar Rp 4.050 perliter, karena saat ini
premium dijual dengan harga sekitar Rp
4.500 perliter Bisa kita bayangkan berapa
besar penghematan pemakaian bahan
bakar di sektor transportasi jika upaya
diversifikasi pemakaian BBG ini berjalan
sukses.
Namun selama ini yang menjadi masalah
adalah peralatan pendukung yang relatif
mahal dan juga keamanan belum
sepenuhnya terjamin. Disamping itu,
ketersediaan stasiun BBG juga masih
terbatas. Belum lagi proses pengisian
yang butuh waktu lama. Hal ini merupakan
beberapa penyebab mengapa pemakai
BBG dan LPG di sektor transportasi masih
sedikit.
4. Peluang Pengembangan Energi
Alternatif
Kebijakan penghapusan subsidi BBM
pada tahun 2005 merupakan momentum
yang tepat bagi pemerintah untuk
mengembangkan batubara sebagai energi
alternatif yang prospeknya cukup
menjanjikan. baik dilihat dari cadangan
yang melimpah maupun dari harga yang
relatif lebih murah dibanding BBM.
Sebagai contoh bila digunakan di sektor
listrik, batubara lebih murah dibanding
BBM. Pada Pembangkit Listrik Tenaga
Diesel (PLTD) yang menggunakan solar,
harga listrik mencapai Rp 500 per KWh.
Sementara menggunakan batubara
biayanya hanya sekitar Rp 50 per KWh.
J adi bisa menghemat biaya kurang lebih
Rp 30 milyar per tahun
2
.
Bila digunakan di sektor rumah tangga
pun untuk keperluan memasak atau sektor
industri untuk bahan bakar, batubara
sangatlah hemat. Setiap satu liter minyak
tanah dapat digantikan dengan 0.6 kg
briket batubara (Soedjoko dalam Warta,
2003). Berdasarkan pada hitungan
konversi energi ini, kita dapat mengambil
contoh penghematan yang akan diperoleh.
Pada tahun 2003. harga batubara sekitar
Rp 222.27 per kg. sementara minyak
tanah Rp 700 per liter. Pada tahun 2003
2
Hasil Perhitungan Firdaus Akmal, Dirut PT.
Indonesian Power
rata-rata pemakaian minyak tanah di
sektor rumah tangga sekitar 179 liter
pertahun. maka biaya yang harus
dikeluarkan untuk membeli minyak tanah
adalah Rp 125.300 per rumah tangga.
Sedangkan, jika menggunakan batubara,
maka besarnya biaya yang harus
dikeluarkan hanya Rp 23.872. Dengan
demikian ada penghematan sebesar Rp
101.428 per rumah tangga. Dengan
merujuk pada data BPS yang
menyebutkan bahwa jumlah rumah tangga
tahun 2003 sebanyak 56.625.000. jadi
sebenarnya ada potensi penghematan
yang bisa dilakukan untuk pengeluaran
energi di sektor rumah tangga sebesar Rp
5.74 trilyun. Dengan harga minyak tanah
yang mencapai Rp 2000 perliter pada
tahun 2005. maka tentu saja
penghematan ini akan jauh lebih besar
lagi.
Tabel 2. Penghematan
Penggunaan BBM di Sektor Industri J ika
Disubstitusi Dengan Batubara dan Gas
(Milyar Rp)
MinyakTanah
Disubstitusi
dengan
Minyak Diesel
Disubstitusi
dengan
Minyak Solar
Disubstitusi
dengan
Tahun
Batu
bara
Gas
Batu
bara
Gas
Batu
bara
Gas
1996 93 99 510 540 1453 1.528
1998 75 8 724 416 2354 1.497
2002 157 158 1.268 1.271 9.752 9.773
2003 203 112 1.205 1.025 10.164 8.684
Sumber: Hasil perhitungan penulis
Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa
betapa besar penghematan yang bisa
dilakukan jika terjadi substitusi total dari
BBM ke batubara dan atau gas di sektor
industri. Pemakaian energi non minyak di
sektor industri seharusnya diintensifkan
sejak dulu. Hal ini bukan saja dilandasi
oleh alasan karena kian menipis
ketersediaan bahan bakar minyak, namun
lebih jauh dari itu juga alasan efisiensi,
baik dalam level mikro yaitu sektor industri
itu sendiri maupun dalam skala makro
perekonomian nasional.
Proses substitusi penggunaan energi ini
tentu saja harus dibarengi dengan inovasi
peralatan dan mesin-mesin industri yang
bisa mendukung digunakannya energi
alternatif tersebut dan bisa meminimalisir
efek negatif dari penggunaan energi
alternatif, seperti polusi dari hasi
pembakaran batubara. Begitupun halnya
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
16
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
dengan substitusi energi di sektor rumah
tangga. perlu ditunjang dengan
ketersediaan alat yang kompatibel dengan
harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Di sisi lain. untuk memberikan
kenyamanan pada pengguna energi
alternatif. maka pemerintah perlu
memberikan jaminan kontinuitas distribusi
energi alternatif tersebut. Mengganti BBM
dengan batubara atau gas bumi memang
terkesan hanya sebagai solusi jangka
pendek karena memang sama-sama
energi tidak terbarukan (non renewable
energy), namun hal ini akan menjadi
jembatan penting untuk pengembangan
energi alternatif lain yang dapat
diperbaharui (renewable energy).
5. Penutup
Peluang untuk mengembangkan energi
alternatif masih sangat terbuka lebar. Batu
bara dan gas bumi merupakan energi
alternatif yang bisa dikembangkan sebagai
substitusi BBM di sektor rumah tangga.
industri dan transportasi dengan prospek
menjanjikan. baik dilihat dari cadangan
yang melimpah maupun dari harga yang
relatif lebih murah dibanding BBM.
Langkah pemerintah dalam
menghapuskan subsidi BBM pada tahun
2005 merupakan momentum yang tepat
untuk menggiatkan pengembangan energi
alternatif. Untuk merangsang sektor
swasta berpartisipasi lebih jauh dalam
mengembangkan energi alternatif mulai
dari hulu sampai hilir, maka pemerintah
perlu memberikan kemudahan,
keleluasaanm, dan insentif bagi
perusahaan-perusahaan yang berminat
untuk mengembangkan energi alternatif.
Sementara untuk mendorong masyarakat
dalam menggunakan energi alternatif,
perlu dilakukan sosialisasi kepada
masyarakat secara menyeluruh dan
intensif.
6. Daftar Pustaka
[1] Abdulkadir. Ariono. 2000.
Pedoman Hitungan Dampak Kenaikan
Harga BBM dan TDL Tahun 2000. KADIN.
J akarta
[2] Asean EC. Energy Management
Training And Research Centre. Asean
Energy Review 1995.
[3] Biro Pusat Statistik. Statistik
Indonesia Tahun 2004.
[4] Ditjen Listrik dan Pemanfaatan
Energi. Pengembangan Pemanfaatan
Energi Alternatif. Makalah Disampaikan
Pada Diskusi di P2E-LIPI dengan tema
Pengembangan Sumber Daya Energi
Alternatif: Upaya Mengurangi
Ketergantungan Terhadap Minyak. 2004.
[5] Kompas. edisi 18 Agustus 2002.
Batu Bara Muda untuk Pembangkit Listrik
[6] www.esdm.go.id. Data Energi di
Sector Rumah Tangga. Sektor
Transportasi. Sektor Industri. Energi
Minyak Bumi. Energi Batubara.
[7] Warta Utama edisi J anuari 2003.
Bisnis Energi Alternatif: Pilihan-Pilihan
Yang Harus Diambil.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
17
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
UTAMA
Krisis Energi di Indonesia: Mengapa dan Harus Bagaimana
Yuli Setyo Indartono
Graduate School of Science and Technology, Kobe University, J apan
E-mail: indartono@yahoo.com
1. Pendahuluan
Lonjakan harga minyak hingga
US$ 70/barel mempengaruhi aktifitas
perekonomian di berbagai belahan dunia.
Di Indonesia, kemelut tersebut diperparah
dengan maraknya penyelundupan minyak
yang ditengarai merugian negara hingga
8.8 trilyun rupiah per tahun. Penerapan
UU Migas No 22 Tahun 2001 juga dituding
sebagai penyebab menurunnya
kemampuan Pertamina dalam
menyediakan BBM. Maka kelangkaan
BBM merupakan pemandangan yang bisa
dijumpai di berbagai daerah di tanah air.
Dari segi APBN, subsidi BBM yang
mencapai 25% dinilai sebagai sesuatu
yang tidak wajar dan memberatkan. Krisis
BBM ini disinyalir merupakan penyebab
melemahnya rupiah terhadap dolar.
Tulisan ini membahas bahaya
ketergantungan terhadap BBM dan
analisis sumber energi terbarukan yang
layak dipergunakan di Indonesia.
Untuk Indonesia, ada tiga data yang
sebenarnya bisa digunakan untuk
memprediksi kemelut BBM saat ini, yakni:
(1) Setelah mencapai puncaknya pada
tahun 1980-an, produksi minyak Indonesia
terus menurun; dari hampir 1.6 juta
barel/hari [12], saat ini hanya 1.2 juta
barel/hari [15, 6], (2) Pertumbuhan
konsumsi energi dalam negeri yang
mencapai 10% per tahun [12], dan (3)
Kecenderungan harga minyak dunia yang
terus meningkat setelah krisis moneter
yang melanda Asia pada tahun 1998 [3].
Ketergantungan terhadap bahan bakar
fosil setidaknya memiliki tiga ancaman
serius, yakni: (1) Menipisnya cadangan
minyak bumi yang diketahui (bila tanpa
temuan sumur minyak baru), (2)
Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju
permintaan yang lebih besar dari produksi
minyak, dan (3) Polusi gas rumah kaca
(terutama CO
2
) akibat pembakaran bahan
bakar fosil. Kadar CO
2
saat ini disebut
sebagai yang tertinggi selama 125,000
tahun belakangan [13]. Bila ilmuwan
masih memperdebatkan besarnya
cadangan minyak yang masih bisa
dieksplorasi, efek buruk CO
2
terhadap
pemanasan global telah disepakati hampir
oleh semua kalangan. Hal ini
menimbulkan ancaman serius bagi
kehidupan makhluk hidup di muka bumi.
Oleh karena itu, pengembangan dan
implementasi bahan bakar terbarukan
yang ramah lingkungan perlu
mendapatkan perhatian serius dari
berbagai negara.
Pemerintah sebenarnya telah menyiapkan
berbagai peraturan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap bahan bakar
fosil (misalnya: Kebijakan Umum Bidang
Energi (KUBE) tahun 1980 dan Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi No
996.K/43/MPE/1999 tentang pioritasi
penggunaan bahan bakar terbarukan
untuk produksi listrik yang hendak dibeli
PLN). Namun sayang sekali, pada tataran
implementasi belum terlihat adanya usaha
serius dan sistematik untuk menerapkan
energi terbarukan guna substitusi bahan
bakar fosil.
2. Potensi Sumber Energi Terbarukan
di Indonesia
Indonesia sesungguhnya memiliki potensi
sumber energi terbarukan dalam jumlah
besar. Beberapa diantaranya bisa segera
diterapkan di tanah air, seperti: bioethanol
sebagai pengganti bensin, biodiesel untuk
pengganti solar, tenaga panas bumi,
mikrohidro, tenaga surya, tenaga angin,
bahkan sampah/limbah pun bisa
digunakan untuk membangkitkan listrik.
Hampir semua sumber energi tersebut
sudah dicoba diterapkan dalam skala kecil
di tanah air. Momentum krisis BBM saat ini
merupakan waktu yang tepat untuk
menata dan menerapkan dengan serius
berbagai potensi tersebut. Meski saat ini
sangat sulit untuk melakukan substitusi
Dunia
18
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
total terhadap bahan bakar fosil, namun
implementasi sumber energi terbarukan
sangat penting untuk segera dimulai. Di
bawah ini dibahas secara singkat berbagai
sumber energi terbarukan tersebut.
2.1 Bioethanol
Bioethanol adalah ethanol yang diproduksi
dari tumbuhan. Brazil, dengan 320 pabrik
bioethanol, adalah negara terkemuka
dalam penggunaan serta ekspor
bioethanol saat ini [5]. Di tahun 1990-an,
bioethanol di Brazil telah menggantikan
50% kebutuhan bensin untuk keperluan
transportasi [8]; ini jelas sebuah angka
yang sangat signifikan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap bahan bakar
fosil. Bioethanol tidak saja menjadi
alternatif yang sangat menarik untuk
substitusi bensin, namun dia mampu
menurunkan emisi CO
2
hingga 18% di
Brazil. Dalam hal prestasi mesin,
bioethanol dan gasohol (kombinasi
bioethanol dan bensin) tidak kalah dengan
bensin; bahkan dalam beberapa hal,
bioethanol dan gasohol lebih baik dari
bensin. Pada dasarnya pembakaran
bioethanol tidak menciptakan CO
2
neto ke
lingkungan karena zat yang sama akan
diperlukan untuk pertumbuhan tanaman
sebagai bahan baku bioethanol.
Bioethanol bisa didapat dari tanaman
seperti tebu, jagung, singkong, ubi, dan
sagu; ini merupakan jenis tanaman yang
umum dikenal para petani di tanah air.
Efisiensi produksi bioethanol bisa
ditingkatkan dengan memanfaatkan
bagian tumbuhan yang tidak digunakan
sebagai bahan bakar yang bisa
menghasilkan listrik.
2.2 Biodiesel
Serupa dengan bioethanol, biodiesel telah
digunakan di beberapa negara, seperti
Brazil dan Amerika, sebagai pengganti
solar. Biodiesel didapatkan dari minyak
tumbuhan seperti sawit, kelapa, jarak
pagar, kapok, dsb [4]. Beberapa lembaga
riset di Indonesia telah mampu
menghasilkan dan menggunakan biodiesel
sebagai pengganti solar, misalnya BPPT
serta Pusat Penelitian Pendayagunaan
Sumber Daya Alam dan Pelestarian
Lingkungan ITB. Kandungan sulfur yang
relatif rendah serta angka cetane yang
lebih tinggi menambah daya tarik
penggunaan biodiesel dibandingkan solar.
Seperti telah diketahui, tingginya
kandungan sulfur merupakan salah satu
kendala dalam penggunaan mesin diesel,
misalnya di Amerika. Serupa dengan
produksi bioethanol, pemanfaatan bagian
tanaman yang tidak digunakan dalam
produksi biodiesel perlu mendapatkan
perhatian serius. Dengan kerjasama yang
erat antara pemerintah, industri, dan
masyarakat, bioethanol dan biodiesel
merupakan dua kandidat yang bisa segera
diimplementasikan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap bahan bakar
fosil.
2.3 Tenaga Panas Bumi
Sebagai negara yang terletak di daerah
ring of fire, Indonesia diperkirakan memiliki
cadangan tenaga panas bumi tak kurang
dari 27 GW [16]. J umlah tersebut tidak
jauh dari daya total pembangkitan listrik
nasional yang saat ini mencapai 39.5 GW
[14]. Pemanfaatan tenaga panas bumi di
Indonesia masih sangat rendah, yakni
sekitar 3% [16]. Tenaga panas bumi
berasal dari magma (yang temperaturnya
bisa mencapai ribuan derajad celcius).
Panas tersebut akan mengalir menembus
berbagai lapisan batuan di bawah tanah.
Bila panas tersebut mencapai reservoir air
bawah tanah, maka akan terbentuk air/uap
panas bertekanan tinggi. Ada dua cara
pemanfaatan air/uap panas tersebut, yakni
langsung (tanpa perubahan bentuk energi)
dan tidak langsung (dengan mengubah
bentuk energi). Untuk uap bertemperatur
tinggi, tenaga panas bumi tersebut bisa
dimanfaatkan untuk memutar turbin dan
generator yang selanjutnya menghasilkan
listrik. Sedangkan uap/air yang
bertemperatur lebih rendah (sekitar 100
o
C) bisa dimanfaatkan secara langsung
untuk sektor pariwisata, pertanian, industri,
dsb. Dengan adanya UU No 27 Tahun
2003 tentang panas bumi serta
inventarisasi data panas bumi yang telah
dilakukan Kementrian Energi dan Sumber
Daya Mineral [16], maka eksploitasi
tenaga panas bumi ini bisa segera
direalisasikan untuk mengurangi
ketergantungan Indonesia terhadap bahan
bakar fosil.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
19
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
2.4 Mikrohidro
Mikrohidro adalah pembangkit listrik
tenaga air skala kecil (bisa mencapai
beberapa ratus kW). Relatif kecilnya
energi yang dihasilkan mikrohidro
(dibandingkan dengan PLTA skala besar)
berimplikasi pada relatif sederhananya
peralatan serta kecilnya areal tanah yang
diperlukan guna instalasi dan
pengoperasian mikrohidro. Hal tersebut
merupakan salah satu keunggulan
mikrohidro, yakni tidak menimbulkan
kerusakan lingkungan. Mikrohidro cocok
diterapkan di pedesaan yang belum
terjangkau listrik dari PT PLN. Mikrohidro
mendapatkan energi dari aliran air yang
memiliki perbedaan ketinggian tertentu.
Energi tersebut dimanfaatkan untuk
memutar turbin yang dihubungkan dengan
generator listrik. Mikrohidro bisa
memanfaatkan ketinggian air yang tidak
terlalu besar, misalnya dengan ketinggian
air 2.5 m bisa dihasilkan listrik 400 W [7].
Potensi pemanfaatan mikrohidro secara
nasional diperkirakan mencapai 7,500 MW,
sedangkan yang dimanfaatkan saat ini
baru sekitar 600 MW [1]. Meski potensi
energinya tidak terlalu besar, namun
mikrohidro patut dipertimbangkan untuk
memperluas jangkauan listrik di seluruh
pelosok nusantara.
2.5 Tenaga Surya
Energi yang berasal dari radiasi matahari
merupakan potensi energi terbesar dan
terjamin keberadaannya di muka bumi.
Berbeda dengan sumber energi lainnya,
energi matahari bisa dijumpai di seluruh
permukaan bumi. Pemanfaatan radiasi
matahari sama sekali tidak menimbulkan
polusi ke atmosfer. Perlu diketahui bahwa
berbagai sumber energi seperti tenaga
angin, bio-fuel, tenaga air, dsb,
sesungguhnya juga berasal dari energi
matahari. Pemanfaatan radiasi matahari
umumnya terbagi dalam dua jenis, yakni
termal dan photovoltaic. Pada sistem
termal, radiasi matahari digunakan untuk
memanaskan fluida atau zat tertentu yang
selanjutnya fluida atau zat tersebut
dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik.
Sedangkan pada sistem photovoltaic,
radiasi matahari yang mengenai
permukaan semikonduktor akan
menyebabkan loncatan elektron yang
selanjutnya menimbulkan arus listrik.
Karena tidak memerlukan instalasi yang
rumit, sistem photovoltaic lebih banyak
digunakan. Sebagai negara tropis,
Indonesia diuntungkan dengan intensitas
radiasi matahari yang hampir sama
sepanjang tahun, yakni dengan intensitas
harian rata-rata sekitar 4.8 kWh/m
2
[2].
Meski terbilang memiliki potensi yang
sangat besar, namun pemanfaatan energi
matahari untuk menghasilkan listrik masih
dihadang oleh dua kendala serius:
rendahnya efisiensi (berkisar hanya 10%)
dan mahalnya biaya per-satuan daya
listrik. Untuk pembangkit listrik dari
photovoltaic, diperlukan biaya US $ 0.25
0.5 / kWh, bandingkan dengan tenaga
angin yang US $ 0.05 0.07 / kWh, gas
US $ 0.025 0.05 / kWh, dan batu bara
US $ 0.01 0.025 / kWh [13]. Pembangkit
lisrik tenaga surya ini sudah diterapkan di
berbagi negara maju serta terus
mendapatkan perhatian serius dari
kalangan ilmuwan untuk meminimalkan
kendala yang ada.
2.6 Tenaga Angin
Pembangkit listrik tenaga angin disinyalir
sebagai jenis pembangkitan energi
dengan laju pertumbuhan tercepat di
dunia dewasa ini. Saat ini kapasitas total
pembangkit listrik yang berasal dari
tenaga angin di seluruh dunia berkisar
17.5 GW [17]. J erman merupakan negara
dengan kapasitas pembangkit listrik
tenaga angin terbesar, yakni 6 GW,
kemudian disusul oleh Denmark dengan
kapasitas 2 GW [17]. Listrik tenaga angin
menyumbang sekitar 12% kebutuhan
energi nasional di Denmark; angka ini
hendak ditingkatkan hingga 50% pada
beberapa tahun yang akan datang.
Berdasar kapasitas pembangkitan
listriknya, turbin angin dibagi dua, yakni
skala besar (orde beberapa ratus kW) dan
skala kecil (dibawah 100 kW). Perbedaan
kapasitas tersebut mempengaruhi
kebutuhan kecepatan minimal awal (cut-in
win speed) yang diperlukan: turbin skala
besar beroperasi pada cut-in win speed 5
m/s sedangkan turbin skala kecil bisa
bekerja mulai 3 m/s. Untuk Indonesia
dengan estimasi kecepatan angin rata-rata
sekitar 3 m/s, turbin skala kecil lebih cocok
digunakan, meski tidak menutup
kemungkinan bahwa pada daerah yang
berkecepatan angin lebih tinggi (Sumatra
Selatan, J ambi, Riau [10], dsb) bisa
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
20
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
dibangun turbin skala besar. Perlu
diketahui bahwa kecepatan angin bersifat
fluktuatif, sehingga pada daerah yang
memiliki kecepatan angin rata-rata 3 m/s,
akan terdapat saat-saat dimana kecepatan
anginnya lebih besar dari 3 m/s pada
saat inilah turbin angin dengan cut-in win
speed 3 m/s akan bekerja. Selain untuk
pembangkitan listrik, turbin angin sangat
cocok untuk mendukung kegiatan
pertanian dan perikanan, seperti untuk
keperluan irigasi, aerasi tambak ikan, dsb.
[3] Anonim, GALFAD Ubah Sampah
J adi Listrik, Bali Post, 15 Februari 2005
[4] Anonim, Biodiesel, energi
alternatif, Pikiran Rakyat, 13 J uli 2005
[5] Anonim, Raja Minyak Baru itu
Bernama Brazil, Kompas, 18 Agustus
2005
[6] Anonim, Soal BBM jangan saling
menyalahkan, Pikiran Rakyat, 25 Agustus
2005
[7] Anonim, Di Mana Air Mengalir,
Listrik bisa Dihasilkan, Kompas, 15
September 2005
3. Kesimpulan
Krisis energi saat ini sekali lagi
mengajarkan kepada bangsa Indonesia
bahwa usaha serius dan sistematis untuk
mengembangkan dan menerapkan
sumber energi terbarukan guna
mengurangi ketergantungan terhadap
bahan bakar fosil perlu segera dilakukan.
Penggunaan sumber energi terbarukan
yang ramah lingkungan juga berarti
menyelamatkan lingkungan hidup dari
berbagai dampak buruk yang ditimbulkan
akibat penggunaan BBM. Terdapat
beberapa sumber energi terbarukan dan
ramah lingkungan yang bisa diterapkan
segera di tanah air, seperti bioethanol,
biodiesel, tenaga panas bumi, tenaga
surya, mikrohidro, tenaga angin, dan
sampah/limbah. Kerjasama antar
Departemen Teknis serta dukungan dari
industri dan masyarakat sangat penting
untuk mewujudkan implementasi sumber
energi terbarukan tersebut.
[8] Goldemberg, J ., Macedo, IC.,
Brazilian alcohol program: An overview,
Energy for Sustainable Development, Vol
1 No 1, May 1994
[9] Panaka, P., Technology Waste
Conversion into Energy, Integrated
Capacity Strengthening ICS-CDM/J I
Project Waste to Energy, B2TE-BPPT,
J akarta, 2004
[10] PSE-UI, INDONESIA ENERGI
Outlook & Statistics 2000, PSE-UI J akarta
2002
[11] Rahman, B., Biogas, Sumber
Energi Alternatif, Kompas, 8 Agustus 2005
[12] Sari, AP., Kehidupan tanpa
minyak: masa depan yang nyata, Pelangi,
www.pelangi.or.id
[13] Service, RF., Is it time to shoot for
the Sun?, Science Vol 309, J uly 22, 2005,
548-551
[14] Seymour, F., Sari, AP.,
Restrukturisasi di tengah reformasi,
dalam: Sari, AP., Salim, N., Elyza, R.,
Listrik Indonesia: Restrukturisasi di tengah
reformasi, Pelangi, www.pelangi.or.id
4. Daftar Pustaka
[1] Anonim, Pembangkit listrik
mikrohidro Cinta Mekar,
http://www.wwf.or.id/powerswitch/suara_k
omunitas/cinta_mekar/
[15] Tobing, M., Bencana BBM
menunggu di depan, Kompas, 11 J uli
2005
[2] Anonim, Sumber energi
terbarukan untuk antisipasi krisis BBM?,
http://www2.dw-
world.de/indonesia/wissenschaft_Technik/
1.151686.1.html
[16] Wahyuningsih, R., Potensi dan
Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi
di Indonesia, Direktorat Inventarisasi
Mineral, Energi dan Sumber Daya Mineral,
www.dim.esdm.org.id
[17] World Energy Survey, 2001
Survey of Energy Resources, WEC 2001.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
21
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
UTAMA
Energi Nuklir dan Kebutuhan Energi Masa Depan
(Era Renaisans Energi Nuklir Dunia dan Energi Nuklir Indonesia)
Sidik Permana
Research Laboratory for Nuclear Reactors, Tokyo Institute of Technology
2-12-1-N1-17, O-okayama, Meguro-ku, Tokyo 152-8550, J apan
Phone/ Fax: +81-3-5734-2955,
E-mail: 04d51469@nr.titech.ac.jp
1. Pendahuluan
Pembangunan berkelanjutan dan
kebutuhan akan energi merupakan
sebuah isu global baik isu tentang
konsumsi energi yang berkaitan dengan
kebutuhan manusia dalam menjaga
kelangsungan hidupnya maupun berkaitan
dengan keterbatasan sumber daya alam
dan efek dari penggunaan sumber energi
tersebut. Berbagai kebijakan dan
terobosan yang telah dilakukan guna
menjaga keseimbangan antara supply
energi dan demand masyarakat dunia
secara berkelanjutan, sehingga
menghasilkan sebuah kebijakan energi
mix pada level global ataupun nasional
yang tentunya mempertimbangkan aspek
ekonomis dan dampak bagi lingkungan.
Kebijakan yang diambil dalam memilih
opsi penggunakan energi nuklir tidak
hanya berkaitan secara teknologi yang
establish, komersial , dan kompetitif
secara market ekonomi, akan tetapi
sudah menjadi sebuah kebijakan negara
dan bahkan sudah menjadi sebuah
kebijakan global tingkat dunia dalam
penerapkannya.
Image yang selama ini terbangun dari
energi nuklir adalah nuklir identik dengan
senjata dan peperangan seperti halnya
bom Hiroshima dan Nagasaki, atau
berhubungan kecelakaan dan radiasi
nuklir seperti di Chernobyl (Ukraina) dan
Three Mile Island (USA) . Hal tersebut
sudah tidak relevan lagi dengan
perkembangan saat ini jika dijadikan
sebagai bayangan yang suram dari
penggunaan teknologi nuklir. Bahwa
bahan bakar yang dipakai untuk senjata
dan untuk sebuah reaktor itu bisa jadi
sama yaitu berasal dari bahan nuklir, akan
tetapi sangat berbeda antara senjata nuklir
dengan sebuah reaktor, tidak hanya tujuan
di bangunnya akan tetapi secara teknis
teknologi dan pengembangannya pun
berbeda. Energi nuklir yang dihasilkan di
sebuah reaktor nuklir dimanfaatkan
menjadi energi listrik yang bisa menjadi
kontributor kompetitif dengan sumber
energi listrik lainnya seperti batu bara,
minyak, gas, air dan lainnya. Kebijakan
energi mengharuskan pada bagaimana
optimum energy mix itu tercapai dalam
kebutuhan energi di sebuah negeri dan
yang tidak kalah pentingnya adalah
berkaitan dengan sumber daya alam dan
SDM yang ada dan juga berbagai resiko
yang akan terjadi dari berbagai sumber
energi tersebut sebagai bahan
pertimbangan. Kontribusi energi dari
berbagai aspek menjadi sebuah
keharusan yang perlu ditempuh sebagai
partner startegis yang saling
menguntungan dalam memenuhi
kebutuhan energi masa depan yang
ekonomis dan ramah lingkungan baik di
tingkat global maupun nasional.
2. Populasi Penduduk dan
Pemanfaatan Sumber Daya Alam
2.1 Populasi Penduduk Dunia.
Pada tahun 1650, populasi dunia
mencapai 0.5 milyar jiwa dan berkembang
dengan laju mendekati 0.3 persen
pertahun [7], dan di tahun 1950, populasi
dunia menjadi 2.5 milyar orang, dan
menjadi 3.6 milyar pada tahun 1970
dengan laju pertambahan 2.1 persen
pertahun [7]. Pada tahun 2001, bumi yang
cantik ini dihuni oleh 6 milyar orang dan
berdasarkan medium projectnya United
Nation Long-Range World Population
Projections, populasi dunia akan
bertambah menjadi 7.2 milyar pada tahun
2015, dan hampir 8 milyar jiwa pada tahun
2025 akan menjadi 9.3 milyar di tahun
2050 [8].
Dunia
22
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
2.2 Pemanfaatan Sumber Daya Alam
A. Sumber Daya Fosil
Efek yang penting lainnya dari
pertumbuhan penduduk dunia adalah
penyusutan dengan cepat sumber daya
alam non-renewable khususnya bahan
bakar fosil. Seperti contohnya : minyak
dengan kapasitas tersedia secara global
adalah 1195 trilyun barrel, akan terpakai
sampai 43 tahun. Batu bara, dengan
cadangan global 1316 trilyun ton dan akan
habis digunakan selama 231 tahun. Gas
alam mempunyai cadangan global 144
trilyun m
3
, dapat digunakan tidak lebih dari
62 tahun. Berhubungan dengan kontribusi
dari keseluruhan sumber energi pada total
konsumsi energi dunia, saat ini 87% untuk
supply energi dan 63% untuk supply listrik
berasal dari bahan bakar fosil. [4].
B. Pemanfaatan Bahan Bakar Nuklir
Kontribusi energi nuklir terhadap pasokan
energi sekitar 6 % dan pasokan listrik
sekitar 17 %. Densitas energi nuklir sangat
tinggi dikarenakan dalam 1 kg uranium
dapat menghasilkan 50.000 kWh
(3.500.000 kWh dengan beberapa proses)
energi, sementara 1 kg batu bara dan 1 kg
minyak dapat memhasilkan hanya 3 kWh
dan 4 kWh. Kemudian pada sebuah
reaktor berkekuatan 1000 MWe
memerlukan : 2.600.000 ton batu bara
(2000 kereta angkut dengan daya angkut
1.300 ton), atau 2,000,000 ton minyak
bumi (10 supertanker), atau 30 ton
uranium (dengan teras reaktor 10 m
3
).
Densitas energi bisa di ukur dengan areal
lahan yang diperlukan per unit produksi
energi. Fosil dan lahan reaktor nuklir
membutuhkan 1-4 km
2
. Lahan solar
thermal atau photovoltaics (PV)
memerlukan 20-50 km
2
. Areal bahan dari
sumber angin memerlukan 50-150 km
2
.
Biomass memerlukan 4.000 6.000 km
2
[4]. Dalam aspek investasi dan faktor
ekonomis, sebuah reaktor nuklir dapat
bersaing secara kompetitif dengan sumber
energi lainnya, hal ini di tunjukan pada
Gambar 1.
Gambar 1. External Costs produksi listrik
3. Limbah Bahan Bakar Fosil dan
Nuklir
Pada Sebuah pembangkit listrik 1000
MWe dengan bahan fosil menghasilkan
ribuan ton nitrous oxide(NO
x
), partikel-
partikel dan abu logam berat, dan sampah
padat berbahaya. Sekitar 500.000 ton
produksi sulfur oxida (SO
x
) dari batu bara,
lebih dari 300.000 ton dari minyak bumi,
dan 200.000 ton dari gas alam. Pada
sebuah reaktor nuklir 1000 MWe tidak
menghasilkan gas noxious atau polutan
lainnya dan akan dihasilkan 3 % sampah
hasil reaksi, yang sebagian besar adalah
produk fisi. Sekitar 96% uranium yang tak
terpakai dan menyisakan 1% plutonium.
Teknologi daur ulang sudah dapat
menjadikan bahan bekas menjadi bahan
bakar yang baru dan menyisakan kurang
dari 3% produk fisi dengan waktu paruh
100 sampai 1000 tahun dan beberapa
minor actinida. Kemudian pertimbangan
lainnya dalam berhubungan dengan
bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara
dan gas alam) adalah deteorientasi
lingkungan dengan greenhouse dari gas
keluaran. Karbon dioksida (CO
2
), metana
(CH
4
) dan NOx adalah gas-gas utama
yang meningkatkan efek greenhouse dari
aktifitas manusia. Gambar 2 menunjukan
pengaruh pemanfaatan air dan nuklir
terhadap pengurangan produksi CO
2.
Sejak perjanjian Kyoto (Kyoto protocol)
ditandatangani yang berkaitan dengan
pengurangan emisi gas buang CO
2
terutama yang menjadi faktor terjadinya
pemanasan global karena efek rumah
kaca yang ditimbulkannya.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
23
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Pada tulisan ini akan dijelaskan beberapa
jenis reactor nuklir dalam skala komersial.
Reaktor tersebut dikategorikan menjadi 2
jenis, yaitu reaktor nuklir dengan proses
reaksi fisi yang diakibatkan oleh neutron
thermal, reaktor ini disebut reaktor thermal,
dan reaktor nuklir dengan proses fisi yang
terjadi pada energi neutron yang tinggi
(fast neutron), reaktor ini disebut (fast
reactor) reaktor cepat. Reaktor cepat tidak
memerlukan moderator, sementara
reaktor thermal membutuhkan moderator
untuk mengurangi energi neutron cepat
menjadi neutron thermal. Tipe reaktor
thermal yang ada banyak sekali, seperti
reaktor berpendingin air ringan (light water
moderated reactor atau LWR), reaktor
berpendingin air berat (heavy water
moderated reactor atau HWR), reaktor
berpendingin gas (gas-cooled reactor),
dan reaktor temperature tinggi
berpendingin gas (high temperature gas-
cooled reactor atau HTGR). Ada 2 tipe
dari LWR yaitu presurrized water reactor
(PWR) dan boiling water reactor (BWR).
HWR untuk tujuan komersial ada 2 tipe
utama, kadang kala di sebut pressurized
heavy water reactor (PHWR) dan boiling
light water reactors (BLWR). Reaktor
Canadian Deuterium Uranium (CANDU)
nya Canada termasuk didalammnya dua
tipe itu dan untuk steam-generating heavy
water reactor (SGHWR) ada di Inggris
dengan versi jenis BLWR. Reaktor
FUGEN J epang bisa di kategorikan
sebagai BLWR, sejak penggunaan
moderator dari air berat (heavy water) dan
pendinginnya air ringan (light water). Gas
cooled-reactors termasuk Magnox gas
cooled reactor (GCR) dan advanced gas
cooled-reactor (AGR). Kelompok HTTR
terdiri dari HTGR dengan bahan bakar
uranium disebut HTR, dan HTGR dengan
berbahan bakar uranium dan thorium
(THTR). J enis lainnya terdapat di rusia
yaitu graphite moderated light water
reactor (RBMK) [5,1]. Sejak tidak
digunakannya moderator di reaktor jenis
reaktor cepat yaitu fast breeder reactor
(FBR), ukuran reaktor menjadi kecil,
dengan laju transfer panas yang tinggi
pada pendingin dengan logam cair (liquid
metal) sebagai pendinginnya dan dengan
peluang penggunaan gas helium
bertekanan tinggi (high-pressure helium
gas) [5,1].
Gambar 2. Pengurangan gas emisi CO
2
dengan penggunaan energi Nuklir dan Air
Gas buang tersebut berasal dari
pemanfaatan bahan bakar fosil untuk
keperluan energi saat ini. Reaktor nuklir
telah berhasil mengurangi sampai 20%
emisi CO
2
[OECD].
4. Perkembangan Pembangkit Tenaga
Nuklir (NPP, Nuclear Power Plant)
Pada periode pertama penggunaan energi
nuklir adalah untuk tujuan militer seperti
hal nya sebuah reaktor pendorong kapal
selam (submarine) [9] milik US Nautilus
dan senjata mematikan seperti bom atom
yang pernah di jatuhkan di Hiroshima dan
Nagasaki pada akhir perang dunia II.
Pengembangan energi nuklir untuk tujuan
sipil seperti reaktor nuklir untuk
pembangkit daya dimulai secara intensif
setelah konferensi Genewa On the
peaceful uses of atomic energy yang di
sponsori oleh UN (PBB) tahun 1955.
Reaktor berjenis LWR(PWR dan BWR)
memiliki kinerja yang baik, dari faktor
ekonomis dalam reaktor komersial,
reliable dan mempunyai sistem keamanan
reactor yang cukup mapan. Di dunia
sudah terdapat banyak reaktor nuklir
dibangun dan telah lama beroperasi
dengan berbagai tipe [1]. Pada tahun 2000,
sekitar 60% (256 dari 438 unit) dari
Pembangkit tenaga nuklir terdiri dari
reaktor PWR. BWR terdapat 21 % (92 dari
438 unit) pembangkit tenaga nuklir dunia.
Lebih detail, J epang mempunyai 52 NPP
(nuclear power plant) dalam operasi, 23
adalah reaktor berjenis PWR dan 28 unit
berjenis BWR. USA mempunyai 104 NPP
yang beroperasi, 69 unit NPP berjenis
PWR dan 35 berjenis BWR. Perancis
mempunyai 57 NPP dalam operasi, 56
adalah berjenis PWR. Berdasarkan
informasi di atas terlihat bahwa LWR di
dunia masih terdepan dalam abad ini.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
24
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Beberapa negara yang mempunyai NPP
telah memberikan kontribusi energi listrik
bagi kebutuhan negaranya, yang
tergambarkan pada Gambar 3.
Gambar 3. Kontribusi energi nuklir
terhadap energi nasional dibeberapa
negara didunia
Dalam hubungannya dengan cadangan
global sumber alam, untuk cadangan
global uranium diperkirakan sekitar 4.36
juta ton. Kalau mengadopsi skenario saat
ini dari daur ulang bahan bakar nuclear
(nuclear fuel cycle) Amerika Serikat (US),
yaitu dengan sistem daur ulang once
through , dimana setelah bahan bakar
yang telah digunakan di reaktor, akan
dibuang ke sebuah daerah pembuangan
khusus, oleh karenanya apabila digunakan
sistem ini maka penggunaan uranium ini
hanya dapat seluruhnya digunakan
sampai 72 tahun. Akan tetapi jika kita
mengadopsi dengan mendaur ulang atau
memproses ulang bahan bakar yang telah
digunakan, dan dengan ditambah
kontribusi FBR (Fast Breeder Reactor)
dengan jumlah yang signifikan terhadap
jumlah NPP di dunia, semua sisa uranium
dapat menjadi supply energi untuk ribuan
tahun. Kemudian juga diketahui terdapat
4 milyar ton uranium dalam konsentrasi
rendah di lautan dan terdapat thorium
sebanyak tiga kali jumlah uranium, dimana
thorium ini bisa menjadi sumber bahan
bakar nuklir yang lain di bumi ini. Oleh
karena itu, energi nuklir dapat digunakan
jutaan tahun.
5. Isu Global Teknologi Nuklir
Terdapat 3 isu global tentang
pemanfaatan energi nuklir dan kita sejak
sekarang harus mulai memikirkannya,
yaitu: isu mengenai Nuclear Safety atau
keselamatan reaktor nuklir, nuclear non-
proliferation atau pembatasan
penggunaan bahan nuklir , dan
radioactive waste management atau
pengaturan sampah radioaktif. Untuk isu
keselamatan reaktor nuklir, estimasi resiko
pada kecelakaan reaktor yang beresiko
tinggi menjadi resiko yang rendah
dibandingkan dengan semua resiko pada
kehidupan manusia umumnya. Kemajuan
dalam keselamatan reaktor ini dapat
diperoleh dengan usaha keras untuk
mempertinggi dan pemeliharaan
keselamatan reaktor, manajemen
keselamatan dan sumber daya manusia.
Nuclear non-proliferation yang berkaitan
dengan pengaturan dan pembatasan
penggunaan bakar nuklir harus dijamin
tidak hanya pengukuran dan optimasi
secara teknis tapi juga semua hal yang
berkaitan dengan politik internacional [6].
Meskipun jumlah sampah radio aktif per
unit produksi listrik dari NPP adalah relatif
sangat kecil, toxic pada sampah radio aktif
harus direduksi serendah mungkin, dalam
rangka mendapatkan penerimaan publik
secara lebih baik lagi dan mengurangi
resiko dari serangan terror.
6. Fase Renaisans Energi Nuklir
Kesadaran bersama akan pentingnya
produksi energi yang berkesinambungan
dengan bahan bakar yang terbaharukan
serta ramah pada lingkungan merupakan
tanggung jawab dan kebutuhan bersama.
Energi nuklir pada gilirannya sudah
mengalami fase regenerasi dari generasi I
ke generasi ke II sampai Sekarang dan
yang akan datang ke III dan ke IV.
Berbagai inovasi telah dilakukan sehingga
tidak hanya berkaitan pada level
keamanan reaktor yang tinggi dan berlapis,
manajemen sampah nuklir dan
reprocessing, akan tetapi berkaitan
dengan dapat digunakannya energi nuklir
untuk berbagai kebutuhan lain seperti
produksi hidrogen untuk kendaraan dan
desalinasi air untuk kebutuhan sehari hari,
hal ini bisa dilakukan dengan
memanfaatkan kelebihan panas dari
reaktor.
Pilihan energi nuklir sebagai salah satu
opsi energi yang bersih disadari oleh salah
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
25
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
seorang pendiri organisasi lingkungan
dunia greepeace Dr. Patrick Moore, PhD,
dia sampaikan pandangannya tersebut
dalam Congressional Subcommittee on
Nuclear Energy - April 28, 2005: Nuclear
energy is the only non-greenhouse gas-
emitting power source that can effectively
replace fossil fuels and satisfy global
demand.[3] . Pandangan Moore
mensiratkan adanya sebuah kesadaran
ahli lingkungan hidup akan kebutuhan
energi yang bersih dan berkesinambungan
dengan memilih opsi energi nuklir. Dua
penghargaan nobel untuk IAEA sebuah
organisasi energi nuklir dunia dan
ketuanya Muhammad Al-Baradei pada
bulan oktober 2005 juga merupakan
babak baru bagi perhatian dunia terhadap
energi nuklir untuk keperluan damai dan
keperluan sipil. Beberapa factor di atas
mengemuka dan menjadi fase baru
renaissance bagi nuklir saat ini dan yang
akan datang, hal tersebut juga terungkap
dalam sebuah konferensi internasional di
jepang GLOBAL 2005 Nuclear energy
system for future generation and global
sustainability yang dihadiri oleh 32 negara
dan lebih dari 500 peserta.
7. Kebijakan Energi Nasional
Konsep kebijakan energi mix nasional,
dengan memasukan opsi energi nuklir
terdapat dalam cetak biru energi nasional
pada departemen energi Indonesia, guna
memenuhi kebutuhan energi untuk
pemenuhan listrik nasional dalam 1 dan 2
dasawarsa kedepan. Kebijakan energi mix
untuk tahun 2025 masih di dominasi
bahan baker fosil dengan komposisi
batubara 32,7 %, Gas bumi 30.6%,
minyak bumi 26.2%, PLTA 2.4%, panas
bumi 3.8% dan lainnya 4.4%. Energi nuklir
masuk pada komposisi lainnya dengan
kontribusi 1.993% terhadap kebutuhan
energi nasional seperti dijelaskan pada
Gambar 4. Sebenarnya aplikasi energi
nuklir dalam bidang lainnya sudah lama
berkontribusi, seperti pada bidang
kesehatan, pangan, dan industri. Akan
tetapi aplikasi energi nuklir dalam
memenuhi kebutuhan listrik nasional baru
dapat di adopsi dengan tahapan
pembangunan tersebut.
Gambar 4. Kebijakan energi mix
Nasional 2025: Skenario optimalisasi
Tahapan pembangunan dibagi pada 2
periode. Rencana pembangunan awal 2
reaktor dengan daya 1000 MWe dan 2000
MWe mulai beroperasi 2016 dan 2017.
Periode kedua dengan 2 reaktor dengan
daya 3000 MWe dan 4000 MWe dengan
rencana operasi mulai 2023 dan 2024.
Total daya yang diinginkan 10 GWe
dengan harga per kWh <4 cUS$[2].
8. Daftar Pustaka
[1] ANS, 2001, World list of nuclear
power plants, Nuclear News, March 2001.
[2] Departemen Energi dan
Sumberdaya Mineral, 2005, Blue print
pengelolaan energi nasional 2005-2025,
Departemen Energi dan Sumberdaya
Mineral (www.esdm.go.id).
[3]http://www.greenspiritstrategies.com/D1
27.cfm
[4] IAEA, 1997, Sustainable Development
and Nuclear Power, IAEA, Vienna.
[5] Marshall, W., Nuclear Power
Technology, 1983, Vol. 1, Reactor
Technology, Clarendon Press, Oxford.
[6] Matsuura, S., 199, Future Perspective
of Nuclear Energy in J apan and the
OMEGA Program, Nucl. Phys. A654, 417c.
[7] Meadows, D.H.,et. al., 1972, The Limits
to Growth, New American Library, New
York.
[8] United Nation, 1998, World
Population Projections:United Nations,
New York, ESA/P/WP.xxx.
[9] West, J .M. and W.K. Davis, 2001, The
creation and beyond: Evolutions in US
nuclear power development, Nuclear
News, J une 2001.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
26
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Diversifikasi Energi Melalui Gas Hidrat
Udrekh
Peneliti pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), INDONESIA
Kandidat Doktor pada The University of Tokyo, J APAN
Email: udrekh@ori.u-tokyo.ac.jp
1. Pendahuluan
Ada sekian banyak respon orang dalam
menyikapi kenaikan harga, kelangkaan,
dan pencabutan subsidi BBM. Bagaimana
tidak, BBM adalah napas bagi bergulirnya
kehidupan, dan berputarnya roda
perekonomian. Tak heran, jika
permasalahan ini menjadi buah bibir
semua orang.
Bagi pengambil kebijakan, pelaku bisnis
maupun ilmuwan, peristiwa besar ini bisa
dipandang sebagai musibah, tetapi juga
bisa dianggap sebagai sebuah peluang.
Saat ini, kita tengah berhitung, apakah
peristiwa besar ini akan menjadi momen
munculnya gejolak perekonomian yang
akan menggoyang stabilitas politik secara
hebat, atau justru merupakan momentum
penting akan bangkitnya sebuah upaya
untuk melakukan penghematan
penggunaan energi, perbaikan sistem
pengelolaan negara yang menghapus
inefisiensi atau ekonomi biaya tinggi. Satu
hal tidak kalah pentingnya adalah
memotivasi upaya untuk menemukan
cadangan energi alternatif, maupun
menciptakan sumberdaya energi
pengganti BBM.
Keputusan untuk memilih sebuah energi
alternatif merupakan keputusan yang sulit.
Kita mungkin berangan-angan untuk
mencari energi alternatif yang dapat
diperoleh dalam jumlah yang banyak,
mampu kita buat dan kita produksi dalam
skala besar, diambil dari potensi
sumberdaya alam Indonesia, dapat
diproduksi dengan harga yang cukup
murah, dan memiliki sifat yang tidak terlalu
berbeda dengan BBM, sehingga tidak
diperlukan modifikasi yang terlalu sulit
untuk dimanfaatkan pada kendaraan
bermotor, rumah tangga maupun Industri.
2. Energi Alternatif Abad 21 dan
Perkiraan Volume Cadangan
2.1 Keunggulan Gas Hidrat
Salah satu sumber energi alternatif yang
cukup menarik perhatian para peneliti dan
industri adalah Gas Hidrat. Gas Hidrat
dianggap memiliki sekian banyak
keunggulan jika dibandingkan pilihan
sumberdaya energi yang lain.
Kelebihannya adalah: 1. volumenya yang
sangat besar di bumi, 2. letaknya yang
relatif tidak terlalu dalam sehingga
memudahkan untuk dieksplorasi dan 3.
cukup mudah untuk dimanfaatkan
2.2 Perkiraan volume cadangan gas
Hidrat Dunia
Gas hidrat diperkirakan memiliki cadangan
sebesar 10
15
- 10
17
m
3
[1] atau setara
dengan dua kali lipat besarnya cadangan
gas konvensional (2.5x10
14
m
3
) dan
hampir 2kali lebih besar daripada sumber
energi yang berasal dari fosil seperti
batubara, minyak dan gas alam (Gambar
1).
Gambar 1. Distribusi karbon organik di
bumi
UTAMA
27
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Gambar 2. Distribusi gas Hidrat di dunia.
2.3 Pemanfaatan Gas Hidrat
Gas hidrat secara alami terbentuk dalam
ikatan kristal padat berbentuk es. Oleh
karena itu, gas hidrat juga sering disebut
sebagai The Burning Ice (Gambar 3).
Strukturnya nya dibentuk dalam ikatan
molekul hidrogen. Ada banyak jenis
molekul gas yang dapat terikat untuk
membentuk hidrat. Tetapi kebanyakan
gas hidrat alam yang ditemui dibumi
adalah Methan. Oleh karena itu, bas
hidrat ini juge lebih sering disebut dengan
methan hidrat.
Gas methan sendiri sudah banyak
digunakan untuk segala jenis aktivitas
dewasa ini. Oleh karena itu, pemanfaatan
sumber daya energi ini, agaknya tidak
membutuhkan banyak modifikasi atau
penelitian yang terlalu sulit.
Gambar 3. Gas Hidrat, es yang terbakar
3. Teknologi untuk Mengetahui
Keberadaan Gas Hidrat
Sampai saat ini, seismik merupakan
teknologi yang paling banyak digunakan
orang untuk mendeteksi keberadaan gas
hidrat. Karakteristiknya yang unik,
membuat cukup mudah untuk dilihat pada
penampang seismik.
Cara kerja teknologi seismic ini pada
dasarnya mirip dengan MRI yang ada di
rumah sakit. Di mana kita bisa
mengetahui struktur lapisan bumi, seperti
kita melihat hasil penampang tulang kita
pada gambar MRI
Gambar 4 menunjukkan penampang
lapisan bumi di dasar laut. Gas hidrat
dapat dengan mudah kita lihat karena
bentuknya yang relatif sejajar dengan
dasar laut / permukaan bumi, dan
memotong struktur sedimentasi yang ada.
Garis sejajar ini biasa disebut Bottom
Simulatin Reflector (BSR), yang
merupakan dasar lapisan gas hidrat.
Umumnya, masih dapat ditemui gas
bebas di bawah lapisan gas hidrat yang
juga dapat dimanfaatkan sebagai
sumberdaya energi.
Untuk memperoleh informasi yang lebih
akurat, dilakukan pengukuran langsung
dengan menggunakan teknologi sonik
maupun pengambilan sampel secara
28
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
langsung. Negara-negara maju telah
banyak memiliki sampel serta beberapa
parameter pengukuran lainnya untuk
memperoleh infomasi yang lebih lengkap
mengenai karakteristik gas hidrat ini.
Pengukuran di beberapa titik berdasarkan
informasi yang diperoleh dari penampang
seismik, selanjutnya dibandingkan
dengan penampakan pada data seismik,
guna memperoleh informasi 3 dimensi.
Data-data seperti heatflow, atau gravitasi
juga dapat digunakan untuk memperoleh
informasi tambahan.
Sampai saat ini, terdapat korelasi yang
positif antara keberadaan BSR pada
penampakan seismik dengan adanya Gas
Hidrat pada kedalaman yang sesuai.
Hanya saja, pengetahuan yang semakin
berkembang saat ini, makin menambah
wawasan mengenai karakteristik gas
hidrat maupun gas bebas itu sendiri. Hal
yang cukup menggembirakan, sekaligus
kian menyadarkan kita, bahwa masih
banyak yang belum kita ketahui.
Gambar 4. Bottom simulating reflector
4. Potensi Gas Hidrat di Indonesia
Agaknya kita memang sangat terlambat
melakukan penelitian di bidang ini. BPP
Teknologi yang bekerjasama dengan
BGR-J erman dan J AMSTEC-J epang,
pernah mengadkan penelitian awal di
bidang gas Hidrat ini. Beberapa institusi
lain, juga pernah melakukan penelitian
serupa di beberapa perairan Timur
Indonesia. Tetapi lebih baik terlambat
daripada tidak sama sekali.
Dari 2 daerah yang telah diobservasi,
perhitungan besarnya cadangan gas
hidrat di Indonesia cukup memberikan
harapan yang menggembirakan.
Perkiraan kasar jumlah gas Hidrat yang
terdapat di daerah perairan sebelah
Selatan Sumatra Selatan, Selat Sunda
dan selatan perairan J awa Barat kurang
lebih 17.7 x 1012 m3 (625.4 triliun cubic
feet), sedangkan jumlah cadangan yang
terdapat di laut Sulawesi kurang lebih 6.6
x 1012 m3 (233.2 triliun cubic feet).
Sebagai perbandingan, besarnya
cadangan gas Alam yang terdapat di
BSR
29
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Natuna adalah sebesar 222tcf
(Penelitian tim BPPT, unpubluished).
Belakangan ini beberapa institusi
penelitian dan universitas sedang giat-
giatnya membangun kerjasama untuk
mengetahui potensi total kandungan gas
Hidrat di Indonesia.
5. Beberapa Kendala
Teknologi eksplorasi merupakan kendala
terbesar sampai saat ini, sehingga gas
hidrat belum juga bisa dimanfaatkan
sebagai energi alternatif. J epang sendiri
mentargetken 2016 sebagai awal
dimulainya eksplorasi bagi gas hidrat
yang mereka miliki.
Menilik pesat dan banyaknya kajian
mengenai gas hidrat ini, agaknya kita
boleh optimis bahwa gas hidrat dapat
digunakan dalam waktu yang mungkin
lebih cepat dari perkiraan semula. Ketika
teknologi eksplorasi ini sudah dapat
dikuasai, sehingga eksplorasi gas hidrat
menjadi cukup ekonomis, maka akan ada
pengaruh yang besar bagi dunia industri,
ekonomi maupun politik dunia.
Bagaimana dengan Indonesia?
6. Daftar Pustaka
[1] Kvenvolden, K.A, 1998, A primer on
the geological occurrence of gas hydrate,
in Henriet, J .P., and Mienert, J ., eds., Gas
hydrates: relevance to world margin
stability and climate change, Volume 137:
Special Publications: London, Geological
Society, p. 9-30. 1999, Potentioal effects
of gas hidrate on human welfare, National
Academi of Sciences, Volume 96: Irvine,
CA., National Academy of Sciences,
p.3420-3426.
[2] Mallik recearch Groups, 2003, Gas
Hydrates Research Well- Mallik NWT,
Mallik research project symposium, 2003.
[4] Morita S., Shimizu, S., Ochiai, K.,
Amano, H., Ishiyama, T., Hato, M.,
Inamori, T., Takayama, T., Baba, K.,
Tanaka, T., Unou, S., 2002, J NOCs High-
Resolution 2D and 3D Seismic Surveys
for Methane Hydrate Exploration in the
Eastern Nankai Trough, Proceedings of
the Fourth International Conference on
Gas Hydrates, Yokohama, May 19 23,
2002.
[5] Satoh, M., 2000, Distribution and
researches of marine natural gas hydrates
around japan, 2000 Western Pacific
Geophysics Meetng, Volume 81: Eos,
Transaction: Tokyo, J apan, American
Geophysical Union, p.63.
[6] Tomaru, J ., 2003. Geological and
Geochemical Studies on the Occurrence
and Stability of Natural Gas Hydrates in
Nankai Trough, Hydrate Ridge and
Mackenzie Delta, Doctoral Thesis.
30
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
UTAMA
Krisis BBM Kita, Belajar dari Krisis Filipina
Arulan Hatta
Direktur Eksekutif BBMwatch Research
1. Pendahuluan
Lonjakan harga minyak yang terjadi sejak
minggu pertama april 2005, telah
memberikan implikasi yang sangat luas
terhadap stabilitas ekonomi, politik dan
keamanan masyarakat dunia, tak
terkecuali Indonesia dan Filipina. Tulisan
ini berupaya menggambarkan kondisi
yang terjadi di Filipina, agar dapat
diperoleh benang merah yang bisa jadikan
pelajaran bagi kita dalam upaya keluar
dari krisis BBM berkepanjangan.
J auh sebelum Indonesia, pemerintah
Filipina telah mengeluarkan berbagai
kebijakaan strategis, upaya dan langkah
nyata sebagai solusi jangka pendek,
menengah dan panjang, termasuk di
dalamnya pembenahan instrumen regulasi
terkait keamanan pasokan BBM serta
penghematan dan diversifikasi energi. J adi,
gejolak harga BBM di Filipina telah
mendahului situasi krisis Energi-BBM di
Indonesia antara bulan J uli-September
2005.
2. Filipina Negara Pengimpor Migas
Filipina sebagai salah satu negara di
kawasan ASEAN dengan jumlah
penduduk sekitar 80 juta jiwa,
perekonomian negaranya sangat rentan
terhadap adanya kenaikan harga minyak
mentah yang tinggi di pasar global. Dapat
dipahami karena Filipina sudah sangat
tergantung pada impor minyak mentah
(net importer oil) , yang saat ini mencapai
sekitar 373.000 barel per hari (bph).
J umlah ini kira-kira mendekati impor untuk
minyak Indonesia tahun 2005 yaitu
400.000 bph dan ditambah dengan BBM
sebesar 330.000 bph.
Sektor Migas di Filipina telah diregulasi
melalui Oil Deregulation Law Republic Act
No. 8479 yang diberlakukan sejak tahun
1998 pada Pemerintahan Fidel V. Ramos.
Di bawah Oil Deregulation Law
pemerintah Filipina tidak boleh
mengintervensi pasar baik melalui harga,
maupun ekspor dan impor produk minyak,
atau mengembangkan retail outlets
(SPBU), depot penyimpan, fasilitas
penerimaan-laut dan pengilangan.
Undang-undang ini dirancang untuk
menekan fluktuasi atau volatilitas dari
harga minyak dan sekaligus
menghapuskan subsidi harga BBM .
Dalam kaitan ini UU Deregulasi Hilir Migas
Filipina dipersepsikan telah
menghilangkan kontrol pemerintah
terhadap harga yang ditentukan pada
industri minyak. Berdasarkan UU tersebut
harga minyak dapat naik dan turun pada
tingkat pasar (market level) atau harga
ditentukan oleh kekuatan pasar (market
forces).
Sebelum ketentuan tersebut berlaku maka
di bawah suatu Deregulasi Lingkungan
(Environment Deregulation) pemerintah
Filipina membentuk suatu mekanisme
Dana untuk Menstabilkan Harga Minyak
(oil price stabilizing fund OPSF), yang
digunakan sebagai instrumen untuk
mensubsidi harga BBM. Di samping itu
perusahaan minyak harus memiliki
persetujuan Pemerintah bila akan
menaikkan harga BBM. Berdasarkan
Memarundum No. 2001 perusahaan
minyak diwajibkan untuk melaporkan
kepada Pemerintah melalui Departemen
Energi sedikitnya sehari sebelum
diberlakukannya rencana penyesuaian
tarif.
3. Implikasi Kenaikan Harga Minyak
Merespon kenaikan harga minyak mentah
tersebut, industri minyak utama (major oil
industry) di Filipina telah menaikkan harga
BBM jenis premium, minyak diesel, dan
LPG sekitar 75-centavo. Sebagai
informasi seperti halnya Indonesia, dalam
perhitungan harga BBM di Filipina
mengacu dengan rata-rata Mean of Platts
Singapore (MOPS), namun diterapkan
secara menyeluruh tidak terbatas hanya
sektor Industri.
Dunia
31
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Kenaikan harga BBM di Filipina pada
bulan April tersebut selanjutnya telah
menimbulkan dampak berganda (multiplier
effect). Pada tanggal 18 April 2005 terjadi
pemogokan nasional sektor transporsi
umum yaitu jeepney dan bis di Filipina
dengan kekuatan sekitar 250.000
pengemudi dan operator. Untuk
memprotes kenaikan harga BBM (gasoline,
LPG, Kerosene, Diesel), sekaligus
menuntut kenaikan tarif angkutan.
Pemogokan telah mengakibatkan
kelumpuhan 70-90% transportasi umum di
beberapa kota besar, seperti Metro Manila.
Kenaikan harga BBM tersebut diikuti
dengan kenaikan harga barang-barang
dan jasa dalam jumlah yang cukup
signifikan, yang pada akhirnya
meningkatkan inflasi sekitar 0,03-0,01%
dan menghambat perkembangan ekonomi.
Momentum kenaikan harga BBM di
Filipina ini juga digunakan sebagai alat
politik oleh kelompok oposisi terhadap
kebijakan sektor migas yang telah
diregulasi melalui Oil Deregulation Law
Republic Act No. 8479, sejak tahun 1998.
UU tersebut dipersepsikan sebagai
penyebab, kenaikan harga BBM yang
sangat signifikan, dan Pemerintah
terkesan tidak mempunyai kekuatan untuk
mengendalikan harga.
Kelompok oposisi selanjutnya telah
mengumpulkan sejuta tanda tangan untuk
diserahkan ke Mahkamah Agung Filipina
dengan tuntutan agar Oil Deregulation
Law Republic Act No. 8479 tersebut
dibatalkan atau diamandemen.
Sebenarnya deregulasi sektor migas
diharapkan di satu sisi akan menciptakan
iklim kompetisi yang adil bagi para pemain
sektor perminyakan, selanjutnya dapat
menekan harga BBM agar lebih efisien.
Namun, di sisi lain ternyata pemerintah
kurang cukup kuat dalam mengelola dan
mengendalikan harga BBM.
Sementara itu upaya untuk mensubsidi
kembali harga BBM pada konsumen dinilai
kontraproduktif, dan akan semakin
memperburuk keadaan. Karena
pemberian subsidi harga BBM akan
menyebabkan jumlah pasokan kembali
meningkat seperti sebelum terjadinya
krisis.
Kenaikan harga BBM ini juga telah
menimbulkan iklim usaha yang kurang
kondusif. Karena perusahaan minyak
dituduh telah melakukan praktek kartel,
kolusi dan menaikkan harga secara
berlebihan. Akhirnya diusulkan agar
Departemen Energi dan Departemen
Kehakiman Filipina segera melakukan
audit keuangan pada perusahaan minyak
utama, melalui Commission of Audit
(COU) .
4. Upaya Filipina Keluar dari Krisis
BBM
Secara umum solusi nyata untuk
mengatasi krisis energi-BBM di Filipina
jangka pendek, menengah dan panjang
antara lain: (1) diterapkan empat hari kerja
(four-week days) sejak April 2005 yang
merupakan penghematan energi (energy-
saving) jangka pendek ; (2) tahun 2007
mengharuskan perusahaan minyak untuk
memproduksi BBM dengan 10%
kandungan etanol; (3) merubah
pembangkit listrik berbahan bakar minyak
dengan energi alternatif antara lain panas
bumi, batubara, dan energi terbarukan.
Untuk mengurangi dampak kenaikan
harga minyak dunia pemerintah Filipina
melalui program kemandirian energi
(energy independence program) akan
mengembangkan dan mengoptimalkan
penggunaan energi terbarukan seperti
solar dan angin, serta mempromosikan
energi alternatif seperti ethanol diesel ,
coco diesel , dan lain-lain.
Di samping itu, Presiden Arroyo telah
menyiapkan suatu rencana kontijensi
(contingency plan), untuk menjajaki opsi
yang harus diambil Pemerintah Filipina
terhadap kemungkinan terjadinya kembali
kenaikan harga minyak yang
berkelanjutan di pasar internasional.
Rencana kontijensi ini bertujuan untuk
menyelaraskan resiko ketergantungan
Filipina terhadap beberapa tingkat harga
minyak .
Salah satu bagian penting dari rencana
kontijensi tersebut adalah untuk
memastikan apakah tiga perusahaan
minyak terbesar di Filipina telah atau tidak
mempraktekkan kartel, dalam menentukan
kenaikan harga BBM yang terjadi pada
waktu dan besarannya relatif bersamaan.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
32
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah
upaya untuk menciptakan suatu
transparansi pasar (market transparency)
agar mekanisme harga dapat
divalidasikan oleh stakeholders . Untuk itu
diperlukan tersedianya suatu data dasar
yang akurat dan aktual, untuk digunakan
dalam menghitung kenaikan harga yang
wajar. Dalam kaitan ini kondisi yang
diharapkan adalah terjadinya kenaikan
harga BBM yang relatif lambat atau
gradual. Karena kenaikan harga minyak
yang tinggi, pada akhirnya akan
memberikan dampak langsung terhadap
kehidupan masyarakat miskin di Filipina.
Presiden Arroyo juga menghimbau agar
negara-negara Anggota OPEC dan Non-
OPEC di kawasan Asia dan Afrika bekerja
sama dalam upaya menghentikan
kenaikan harga minyak secara
berkelanjutan, yang pada akhirnya
berpotensi menciptakan dampak terburuk.
Terhadap tekanan publik yang menyorot
kebijakan sektor migas, Pemerintahan
Arroyo akan mempelajari dengan
seksama Oil Deregulation Law untuk
melihat apakah Undang-undang tersebut
masih dapat mendukung tujuan serta
kepentingan Negara Filipina. Atau
sebaliknya perlu diamandemen
sebagaimana yang saat ini digelorakan
oleh kelompok oposisi. Deregulasi industri
migas ke depan tergantung dari hasil
kajian ini.
5. Proses Belajar
Pelajaran yang dapat dipetik dari
fenomena Filipina adalah bahwa suatu
kebijakan deregulasi sektor Migas dengan
pilar untuk menciptakan iklim kompetisi
bagi para pelaku industri minyak dan
menghapuskan subsidi harga BBM yang
telah berjalan secara mulus pada kondisi
harga minyak yang wajar. Namun, pada
kondisi bervolatilitasnya harga minyak
yang tinggi, menjadi kurang mempunyai
alat pengaman. Pada saat itulah publik
mulai menyalahkan deregulasi, walaupun
sebelumnya telah berjalan, di samping itu
mereka mendambakan kembali ke era
kebijakan harga regulasi (regulated price)
melalui mekanisme subsidi harga .
Anatomi dan pengendali mekanisme
(driving force mechanism) dan solusi
jangka pendek dan panjang terhadap
krisis energi-BBM yang terjadi di Filipina
pada bulan Maret dan April 2005,
walaupun berbeda dalam sekala dan
kompleksitasnya dengan kondisi
Indonesia. Namun dapat digunakan
sebagai salah satu referensi dan proses
belajar dalam mengantisipasi krisis BBM
yang terjadi saat ini.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
33
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
INOVASI
Potensi Pengembangan Energi dari Biomassa Hutan di Indonesia
Ika Heriansyah
Peneliti pada Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam, Bogor
Mahasiswa Graduate School of Science and Technology, Kobe University. J APAN
E-mail: ika_heriansyah@yahoo.com
1. Pendahuluan
Pengembangan sumber energi dapat
diperbaharui, termasuk biomassa,
merupakan fundamental bagi
kesinambungan ketersediaan energi masa
depan. Biomassa dapat memainkan
peranan penting sebagai sumber energi
yang dapat diperbaharui, yang berfungsi
sebagai penyedia sumber karbon untuk
energi, yang dengan menggunakan
teknologi modern dalam
pengkonversiannya dapat menjaga emisi
pada tingkat yang rendah. Di samping itu,
penggunaan energi biomassa pun dapat
mendorong percepatan rehabilitasi lahan
terdegradasi dan perlindungan tata air.
Secara general, keragaman sumber
biomassa dan sifatnya yang dapat
diperbaharui dapat berperan sebagai
pengaman energi di masa mendatang
sekaligus berperan dalam konservasi
keanekaragaman hayati.
Biomassa dapat digunakan untuk
menyediakan berbagai vektor energi, baik
panas, listrik atau bahan bakar kendaraan.
Namun demikian, energi biomassa dapat
berasal dari berbagai sumber daya dan
mungkin juga rute konversi yang beragam,
sehingga dapat menimbulkan pemahaman
yang kompleks dalam implikasinya.
Sejumlah isu memerlukan klarifikasi dalam
rangka memahami potensi biomass
sebagai sumber energi yang
berkesinambungan: mengenai sumber
daya dan ketersediaannya, aspek logistik,
biaya-biaya rantai bahan baker, dan
dampaknya terhadap lingkungan. Di sisi
lain juga timbul pertanyaan berapa
kuantitas residu yang dapat digunakan
dari suatu sumber biomassa, dimana dan
bagaimana harus dikembangkan, apa dan
bagaimana kebutuhan infrastruktur harus
dipenuhi, kesemuanya memerlukan
pertimbangan yang seksama.
Tulisan singkat ini akan memaparkan
potensi pengembangan biomassa hutan
sebagai bahan substitusi minyak bumi dan
kontribusinya kepada pengurangan emisi
CO
2
di Indonesia.
2. Status Implementasi Bioenergi
Peningkatan konsumsi bahan bakar fosil
menyebabkan peningkatan emisi yang
pada gilirannya akan menimbulkan
pemanasan global yang berpengaruh
nyata terhadap pola hidup dan kehidupan
manusia. Dengan demikian penggunaan
energi yang terbarukan, dalam hal ini
bioenergi perlu terus dikembangkan.
Penggunaan biomassa untuk listrik
(bioelectricity) di Indonesia masih sangat
jarang ditemukan. Beberapa diantaranya
telah dikembangkan oleh PT. Ajiubaya di
sebagian kecil wilayah Kabupaten Sampit,
Kalimantan Timur, dengan kapasitas 4 6
MW, dan juga beberapa instalasi Bioner-1
(gasifikasi biomassa yang dikoneksikan
pada mesin diesel yang dapat digunakan
untuk power generating, pompa dan mesin
penggiling) yang dikembangkan oleh PT.
Boma Bisma Indra dengan kapasitas
sekitar 18 kW juga dimanfaatkan
dibeberapa wilayah di Kalimantan,
Sumatra dan Sulawesi Utara [5, 8].
Beberapa perusahaan industri, baik milik
pemerintah maupun swasta juga telah
memulai penggunaan bioenergi sebagai
pembangkit listrik, energi mekanik dan
energi panas. Utami (1997) dalam Boer et
al [1] melaporkan bahwa Indonesia telah
mempunyai sekitar 50 unit gasifikator
dengan kapasitas antara 15-100 kW/unit
atau total kapasitas sekitar 2.200 kW.
Sebagai tambahan, sekitar 200 unit biogas
(diproduksi dari biomassa melalui proses
fermentasi anaerobic) juga telah
dimanfaatkan dibeberapa daerah
pedesaan dengan kapasitas 4 15 m
3
.
Dunia
34
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
3. Prospek Implementasi Bioenergi
Masih banyaknya wilayah yang belum
menikmati listrik negara ataupun swasta,
dan belum optimalnya pemanfaatan
biomassa merupakan prospek yang
sangat besar dalam implementasi
bioenergi.
Sisa pemanfaatan kayu merupakan
sumber potensial bagi pembangkit listrik
tenaga biomassa. Biomassa yang belum
dimanfaatkan tersebut sebagian besar
bersumber dari sisa pembalakan, konversi
lahan hutan, maupun dari perkebunan
rakyat. Rachman [7] melaporkan bahwa
sisa pembalakan dari hutan alam sekitar
46%, yakni 8% dari tunggak, 20% dari log
yang rusak dan sisa cabang sampai
diameter 10 cm sebanyak 18%.
Berdasarkan produksi log rata-rata
tahunan dari hutan alam sebesar 22 juta
m
3
saja, dapat dihitung besaran biomassa
yang ditinggalkan di lapangan tanpa
adanya pemanfaatan. Sebagai contoh,
menurut Triono (1999) dalam Rachman [7]
jumlah sisa pembalakan di Provinsi J ambi
antara periode 1995/96-1998/99 mencapai
angka 110.000 350.000 m
3
per tahunnya.
Di samping residu biomassa dari hutan
alam, residu biomassa dari hutan tanaman
juga berpotensi besar sebagai sumber
energi, dimana program pemanfaatannya
bisa diintegrasikan dengan kegiatan lain
berbasis sosial ekonomi masyarakat
sekitar hutan. Dalam implementasi- nya,
program pengembangan bioenergi di
daerah sekitar hutan ini selain
berkontribusi dalam peningkatan taraf dan
kualitas hidup masyarakat yang umumnya
berpenghasilan rendah, juga dapat
menjadi sarana komunikasi yang efektif
untuk tujuan pengelolaan hutan
berkelanjutan.
Heriansyah dan Kanazawa [3] melaporkan
bahwa residu biomassa dari kegiatan
pemanenan akhir di hutan tanaman
jumlahnya mencapai 20% untuk hutan
tanaman yang dijarangi dan 35% dari
hutan tanaman tanpa penjarangan.
Besaran tersebut belum termasuk
biomassa cabang dan ranting, atau residu
biomassa dari kegiatan penjarangan.
Laporan lain dalam Boer et al. [1],
menyebutkan bahwa produksi biomassa
hutan tanaman adalah 8-25 ton/ha/tahun.
Dengan limpahan residu dari biomassa
hutan yang sangat besar, maka
implementasi energi biomassa memiliki
prospek yang besar. Di samping itu
pemanfaatan biomassa menjadi energi
pun dapat mengurangi emisi CO
2
baik dari
respirasi akibat dekomposisi maupun dari
kemungkinan kebakaran, serta
berkontribusi besar pada penurunan
penggunaan bahan bakar fosil yang
semakin langka dan mahal.
4. Teknologi Konversi Biomassa
Menjadi Energi
Semua material organik mempunyai
potensi untuk dikonversi menjadi energi.
Biomassa dapat secara langsung dibakar
atau dikonversi menjadi bahan padatan,
cair atau gas untuk menghasilkan panas
dan listrik (Gambar 1). Beberapa pilihan
teknologi konversinya adalah sebagai
berikut:
a. Konversi biomassa pada ketel uap
modern
Biomassa dibakar pada ketel uap modern
untuk menghasilkan panas, listrik atau
kombinasi panas dan tenaga. Sistem ini
secara komersial telah banyak digunakan
di Amerika Serikat, Australia, Finlandia
dan German, walaupun secara tipikal
hanya menghasilkan 20% energi jika
dibandingkan dengan bahan bakar fosil.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
35
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Biomass
Storage, Transport, Pre-treatment
Gambar 1. Mata rantai konversi biomassa menjadi energi panas, listrik, dan bahan bakar
kendaraan
b. Proses anaerobik
Merupakan proses biologi yang konversi
biomass baik padatan maupun cair
menjadi gas tanpa oksigen. Gas yang
dihasilkan didominasi methane dan CO
2
.
Hasil ikutan berupa kompos dan pupuk
untuk pertanian dan kehutanan. Teknologi
ini telah dikembangkan secara komersial
di Europa dan Amerika utara.
c. Gasifikasi Biomassa
Gasifikasi merupakan konversi dengan
menggunakan parsial oksidasi pada suhu
karbonisasi sehingga menghasilkan
bahan bakar gas dengan level panas
berkisar antara 0,1-0,5 dari gas alam,
tergantung proses gasifikasi yang
digunakan. Konversi ini lebih
menguntungkan secara ekonomi
dibandingkan dengan pembakaran
langsung, bersih, dan efisien dalam
pengoperasian. Produk dari gasifikasi ini
dapat juga di-reform untuk menghasilkan
methanol dan hydrogen. Teknologi ini
sedang dalam awal komersial.
d. Pyrolysis Biomassa
Pyrolysis merupakan pendegradasian
panas pada biomassa tanpa oksigen,
untuk menghilangkan komponen volatile
pada karbon. Hasil dari proses ini selalu
dalam bentuk gas, dan hasil
penguapannya dapat menghasilkan
bahan bakar cair dan padatan sisa.
Bahan bakar cair ini dapat menghasilkan
Fuel cell Engine, gas turbin Boiler
Pressing/Extract
ion
Gasificati
Pyrolysi Charcoal
production
Combustion
Fermentatio
n/
Esterificatio
Anaerobic
digestion
Thermo-chemical conversion Physico-chemical
conversion
Biological
Solid fuel Liquid fuel Gaseous fue
Heat Steam turbine
Transport fuels
Electricity
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
36
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
panas dan listrik apabila dibakar dalam
ketel uap, mesin atau turbin. Produk lain
dari proses pyrolysis ini adalah berupa
arang dan bahan kimia. Teknologi
konversi pyrolysis biomassa ini telah
demonstrasikan di Europa selama 3 tahun,
dari tahun 2002 2005.
e. Pembuatan arang
Penyiapan lahan baik pertanian maupun
HTI (Hutan Tanaman Industri) seringkali
dengan cara pembakaran, selain beresiko
kebakaran dan gangguan pernafasan,
cara inipun dapat menstimulus
pemanasan global akibat peningkatan
konsentrasi CO
2
di atmosfer. Dengan
mengkonversinya menjadi arang tentunya
dapat meminimalkan emisi, pun
menambah penghasilan masyarakat.
Selain digunakan sebagai sumber panas,
arang pun dapat digunakan sebagai
kondisioner tanah untuk mempercepat
terjadinya simbiotik antara akar dengan
mikoriza, yang berkontribusi pada
percepatan pertumbuhan tanaman dan
penyerapan emisi CO
2
di atmosfir. .
Dalam hubungannya dengan peningkatan
karbon sequestrasi, konversi biomassa
menjadi arang merupakan salah satu
pilihan bijak yang efektif dan efisien,
karena karbon pada arang dapat
disimpan dalam durasi yang lama
dibanding dengan karbon pada bentuk
kayu [6].
5. Pengembangan Energi Biomassa
Penggunaan bahan bakar biomassa atau
kayu sebagai bahan pensubstitusi bahan
bakar fosil merupakan salah satu peranan
penting hutan. FAO mengestimasi bahwa
penggunaan biomassa di negara
berkembang berkontribusi sekitar 15%
dari total biaya energi yang diperlukan [2].
Pada tahun 2000, sekitar 18,4 GW energi
biomassa telah diinstalasi di negara-
negara anggota OECD (Organization for
Economic Co-operation and
Development), yang terdiri dari negara-
negara di Amerika Utara, Europa dan
Pasifik [4]. Amerika Serikat mendominasi
7.4 GW, salah satunya dikembangkan di
Wisconsin oleh Northern States Power Co.
dengan kapasitas 75 MW.
Finlandia merupakan negara yang
memiliki instalasi energi biomassa
terbanyak dengan proporsi sekitar 8%
dari total negara-negara anggota OECD.
Dengan luas areal dan potensi hutan
yang jauh lebih besar dari Finlandia (24.4
juta ha), Indonesia memiliki prospek
pengembangan energi biomassa yang
potensial dan kompetitif.
Terkait dengan kelangkaan bahan bakar
minyak serta besarnya potensi
pengembangan energi biomassa di
Indonesia, maka dalam proses
pengembangannya perlu memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
a. Pengembangan energi dari
biomassa perlu didukung teknologi
konversi yang efektif, efisien, dan ramah
lingkungan.
b. Pasar yang kompetitif perlu
diciptakan sehingga residu biomassa dari
kehutanan dapat dimanfaatkan optimal,
tanpa berefek negatif pada keberlanjutan
eksploitasi.
c. Pengembangan bioenergi dari
biomassa harus diintegrasikan dengan
kebijakan terkait dari sektor energi,
lingkungan, pertanian, dan kehutanan,
sehingga terjadi insentif yang
merangsang pertumbuhan dari semua
sektor yang diintegrasikan.
d. Kebijakan yang dibuat harus
berjangka panjang untuk merangsang
investasi, dan pemerintah harus
menetapkan target dan ukuran kebijakan
yang menguntungkan semua pihak.
e. Kontinuitas penelitian,
pengembangan, desiminasi, dan
demonstrasi terhadap tipe/jenis biomassa,
manajemen, serta teknologi konversinya,
sehingga efektif dan efisien secara
ekonomi dan ramah lingkungan dari sisi
ekologi.
Disamping iklim usaha yang kompetitif,
pengembangan energi dari biomassa
yang berkesinambungan secara ekonomi,
lingkungan dan sosial, harus pula
memperhatikan beberapa kriteria berikut:
a. Biomassa yang digunakan harus
berasal dari sumber yang dapat
diperbaharui yang dikelola dengan
manajemen yang berkelanjutan.
b. Biaya-biaya proses harus dijaga
rendah untuk memastikan efisiensi
ekonomi.
c. Bahan input lain yang
dipergunakan dalam rantai teknologi
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
37
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
konversi yang berasal dari sumber yang
tidak dapat diperbaharui harus tetap
rendah untuk menekan tingkat emisinya
dan dengan tetap menggunakan teknologi
konversi terbaik.
d. Rancangan pengembangan
bioenergi harus bermanfaat bagi
pembangunan masyarakat secara luas.
6. Penutup
Energi berbasis biomassa berpotensi
besar dalam mendukung pasokan energi
yang berkelanjutan di masa mendatang.
Meskipun demikian, pengembangannya
harus dirancang sedemikian rupa
sehingga berefek positif terhadap
pembangunan sosial ekonomi masyarakat
dan di pihak lain juga tidak berdampak
negatif terhadap lingkungan.
Semua teknologi konversi biomassa
menjadi energi bisa diterapkan di
Indonesia, dengan pengembangan
disesuaikan dengan besaran supply
biomassa, teknologi yang telah dikuasai,
ketersediaan anggaran dan jenis produk
yang dibutuhkan pasar di masing-masing
daerah. Alternatif teknologi konversi
dalam mengantisipasi kelangkaan BBM
misalnya, akan lebih tepat bila teknologi
gasifikasi dan proses anaerobik yang
diterapkan; selain lebih efisien, produknya
pun berupa bahan bakar gas yang dapat
digunakan sebagai sumber panas, listrik
dan bahan bakar kendaraan.
Kebijakan pemerintah yang komprehensif
dan terintegrasi dengan sektor terkait juga
perlu dirancang guna merangsang iklim
investasi yang kondusif dan kompetitif.
Pengembangan energi berbasis biomassa
sebagai energi yang dapat diperbaharui
pada akhirnya akan mampu mensubstitusi
bahan bakar fosil dengan kuantitas besar,
yang pada gilirannya akan mereduksi
jumlah CO
2
yang diemisikan ke atmosfir.
Dalam konteks global, untuk mereduksi
gas rumah kaca dalam jangka panjang,
pasokan biomassa yang stabil dan
berkelanjutan merupakan tuntutan mutlak
bagi pengembangan energi biomassa.
Dengan demikian struktur insentif dalam
pengelolaan hutan yang berkelanjutan
perlu diciptakan secara kompetitif.
7. Daftar Pustaka
[1] Boer, R., Masripatin, N., J une, T.,
and Dahlan, E.N. 2001. Greenhouse Gas
mitigation Technologies in Forestry
Sector: Status, Prospects and Barries of
Their Implementation in Indonesia.
UNDP-Climate Change Enabling Activity
Project.
[2] FAO. 1999. Prevention of land
degradation, enhancement of carbon
sequestration and conservation of
biodiversity through land use change and
sustainable land management with a
focus on Latin America and The
Carribean. International Fund for
Agricultural Development, FAO, Rome.
[3] Heriansyah, I and Kanazawa, Y.
2005. Potential production of Acacia
mangium Willd. forests at harvest age
under different condition in Indonesia.
Proceeding of the 14th Indonesian
Scientific Conference in J apan.
[4] International Energy Agency.
2002. World Energy Outlook 2002. IEA
publications. France.
[5] Martono, R.W. 1998. Kajian
keekonomian pembangkit listrik gasifikasi
Bioner-1. Prosiding Konferensi Energi,
Sumberdaya Alam dan Lingkungan,
BPPT. J akarta.
[6] Pari, G., Roliadi, H., Miyakuni, K.
and Ishibashi, N. 2005. Trial on some
charcoal production methods for the
enhancement of carbon sequestration in
Indonesia. Proceeding of the 2
nd
workshop on Demonstration Study on
Carbon Fixing Forest Management in
Indonesia. Forestry Research and
Development Agency and J apan
International Cooperation Agency. Bogor.
[7] Rachman, O. 2000. Small-Log
Utilization. Proceeding of Expose of
Research Results of International
Cooperation Projects. Forestry and Estate
Crops Research and Development
Agency. J akarta.
[8] Ridlo, R., B. Sucahyo dan
Shaffriadi. 1998. Bioner-1, gasifikasi
gambut dan biomassa untuk listrikdan
pompanisasi air. Prosiding Konferensi
Energi, Sumberdaya Alam dan
Lingkungan, BPPT. J akarta.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
38
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
INOVASI
Rekayasa Minyak Pelumas dari bahan Botol Plastik Bekas
Sandri Justiana, S.Si dan Budiyanti Dwi Hardanie, S.Si
Penulis, alumni J urusan Kimia FMIPA Universitas Padjadjaran dan pegiat di Alchemist
Community
Percayakah Anda jika suatu saat nanti
botol plastik bekas dapat digunakan
sebagai bahan baku pembuatan minyak
pelumas untuk kendaraan bermotor? J ika
tidak percaya, tanyakan saja pada
Stephen J . Miller, Ph.D., seorang ilmuwan
senior dan konsultan peneliti di Chevron.
Bersama rekan-rekannya di Pusat
penelitian Chevron Energy Technology
Company, Richmond, California, Amerika
Serikat dan University of Kentucky, ia
berhasil mengubah limbah plastik menjadi
minyak pelumas. Bagaimana caranya?
Sebagian besar penduduk di dunia
memanfaatkan plastik dalam menjalankan
aktivitasnya. Berdasarkan data
Environmental Protection Agency (EPA)
Amerika Serikat, pada tahun 2001,
penduduk Amerika Serikat menggunakan
sedikitnya 25 juta ton plastik setiap
tahunnya. Belum ditambah pengguna
plastik di negara lainnya. Bukan suatu
yang mengherankan jika plastik banyak
digunakan. Plastik memiliki banyak
kelebihan dibandingkan bahan lainnya.
Secara umum, plastik memiliki densitas
yang rendah, bersifat isolasi terhadap
listrik, mempunyai kekuatan mekanik yang
bervariasi, ketahanan suhu terbatas, serta
ketahanan bahan kimia yang bervariasi.
Selain itu, plastik juga ringan, mudah
dalam perancangan, dan biaya
pembuatan murah.
Sayangnya, di balik segala kelebihannya,
limbah plastik menimbulkan masalah bagi
lingkungan. Penyebabnya tak lain sifat
plastik yang tidak dapat diuraikan dalam
tanah. Untuk mengatasinya, para pakar
lingkungan dan ilmuwan dari berbagai
disiplin ilmu telah melakukan berbagai
penelitian dan tindakan. Salah satunya
dengan cara mendaur ulang limbah plastik.
Namun, cara ini tidaklah terlalu efektif.
Hanya sekitar 4% yang dapat didaur ulang,
sisanya menggunung di tempat
penampungan sampah.
Masalah itulah yang mendasari Miller dan
rekan-rekannya melakukan penelitian ini.
Sebagian besar plastik yang digunakan
masyarakat merupakan jenis plastik
polietilena. Ada dua jenis polietilena, yaitu
high density polyethylene (HDPE) dan low
density polyethylene (LDPE). HDPE
banyak digunakan sebagai botol plastik
minuman, sedangkan LDPE untuk
kantong plastik. Dalam penelitiannya yang
akan dipublikasikan dalam J urnal
American Chemical Society bagian Energi
dan Bahan Bakar (Energy and Fuel) edisi
20 J uli 2005, Miller memanaskan
polietilena menggunakan metode pirolisis,
lalu menyelidiki zat hasil pemanasan
tersebut.
Ternyata, ketika polietilena dipanaskan
akan terbentuk suatu senyawa
hidrokarbon cair. Senyawa ini mempunyai
bentuk mirip lilin (wax). Banyaknya plastik
yang terurai adalah sekitar 60%, suatu
jumlah yang cukup banyak. Struktur kimia
yang dimiliki senyawa hidrokarbon cair
mirip lilin ini memungkinkannya untuk
diolah menjadi minyak pelumas
berkualitas tinggi. Sekedar informasi,
minyak pelumas yang saat ini beredar di
pasaran berasal dari pengolahan minyak
bumi. Minyak mentah (crude oil) hasil
pengeboran minyak bumi di dasar bumi
mengandung berbagai senyawa
hidrokarbon dengan titik didih yang
berbeda-beda. Kemudian, berbagai
senyawa hidrokarbon yang terkandung
dalam minyak mentah ini dipisahkan
menggunakan teknik distilasi bertingkat
(penyulingan) berdasarkan perbedaan titik
didihnya. Selain bahan bakar, seperti
bensin, solar, dan minyak tanah,
penyulingan minyak mentah juga
menghasilkan minyak pelumas. Sifat kimia
senyawa hidrokarbon cair dari hasil
pemanasan limbah plastik mirip dengan
senyawa hidrokarbon yang terkandung
dalam minyak mentah sehingga dapat
diolah menjadi minyak pelumas.
Pengubahan hidrokarbon cair hasil
Dunia
39
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
pirolisis limbah plastik menjadi minyak
pelumas menggunakan metode
hidroisomerisasi. Miller berharap minyak
pelumas buatan ini dapat digunakan untuk
kendaraan bermotor dengan kualitas yang
sama dengan minyak bumi hasil
penyulingan minyak mentah, ramah
lingkungan, sekaligus ekonomis.
Sebenarnya, usaha pembuatan minyak
sintetis dari senyawa hidrokarbon cair ini
bukan suatu hal baru. Pada awal 1990-an,
perusahaan Chevron telah mencoba
mengubah senyawa hidrokarbon cair
menjadi bahan bakar sintetis untuk tujuan
komersial. Hanya saja bahan baku yang
digunakan untuk menghasilkan senyawa
hidrokarbon cair berasal dari gas alam
(umumnya gas metana) melalui proses
katalitik yang dikenal dengan nama proses
Fischer-Tropsch.
Pada proses Fischer-Tropsch ini, gas
metana diubah menjadi gas sintesis
(syngas), yaitu campuran antara gas
hidrogen dan karbon monoksida, dengan
bantuan besi atau kobalt sebagai katalis.
Selanjutnya, syngas ini diubah menjadi
senyawa hidrokarbon cair, untuk
kemudian diolah menggunakan proses
hydrocracking menjadi bahan bakar dan
produk minyak bumi lainnya, termasuk
minyak pelumas. Senyawa hidrokarbon
cair hasil pengubahan dari syngas
mempunyai sifat kimia yang sama dengan
polietilena.
Gas alam yang digunakan berasal dari
Amerika Serikat. Belakangan, daerah
lepas laut Timur Tengah menjadi sumber
gas alam karena di sana harga gas alam
lebih murah. Minyak pelumas dari gas
alam ini untuk sementara dapat menjadi
alternatif minyak pelumas hasil
pengolahan minyak bumi. Pada masa
mendatang, cadangan gas alam di dunia
diperkirakan akan segera menipis. Di lain
pihak, kebutuhan akan minyak pelumas
semakin tinggi. Kini, dengan adanya
penemuan ini, pembuatan minyak
pelumas nampaknya tidak lagi
memerlukan gas alam. Cukup dengan
memanfaatkan limbah botol plastik, jadilah
minyak pelumas.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
40
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Campuran Bahan Bakar Waste Plastic Disposal (WPD) dan Orimulsion
sebagai Alternatif Bahan Bakar Motor Diesel
Agung Sudrajad
1,2
1
Mahasiswa Program Doktor pada Energy Engineering Research Laboratory, Kobe
University
2
Pengajar pada Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada J akarta
Email: 021d801n@y04.kobe-u.ac.jp , agung_sudrajad@lycos.com
1. Pendahuluan
Peningkatan jumlah produksi mesin diesel
ditambah dengan meningkatnya harga
bahan bakar minyak di seluruh dunia
memaksa kita untuk mencari bahan bakar
terbarukan sebagai bahan bakar alternatif
bagi motor diesel. Dilain sisi isu
lingkungan begitu gencar disuarakan oleh
badan-badan dunia sebagai isu utama
memasuki abad baru ini, mengingat
dampak teknologi yang sekarang sedang
kita nikmati ternyata memberi dampak
buruk terhadap lingkungan. Khususnya di
perkotaan, dampak polusi udara dari gas
buang motor/mesin sangat terasa
sehingga beberapa badan dunia
mensyaratkan tingkat emisi gas buang,
atau sering disebut ambang batas
maksimum polusi. Keadaan ini
mendorong kita untuk mengadakan
penelitian tentang penggunaan bahan
bakar alternatif yang rendah polusi dan
murah.
Saat ini, sekitar 129 juta ton plastic setiap
tahunnya diproduksi, dan 60% dari jumlah
itu diproduksi dari bahan minyak bumi.
J ika dari jumlah tersebut dapat diolah
kembali maka akan diperoleh sebesar 69
juta minyak bumi yang dapat
dimanfaatkan. J epang sendiri telah
menerapkan undang-undang pengolahan
sampah sejak 1997 dan khususnya bagi
sampah plastik sejak tahun 2000 [5]. Hasil
dari pengolahan sampah plastik (banyak
digunakan untuk pembungkus di super
market dan sisa minuman) yang diproses
pada tungku proses pada suhu 400-500
0
C
telah menghasilkan bahan bakar baru
yang diberi nama Waste Plastic Disposal
Fuel (WPD Fuel) [5]. Bahan bakar yang
disingkat WPD ini di beberapa negara
maju sedang dilakukan penelitian secara
intensif sebagai bahan bakar alternatif
pada berbagai mesin. Penelitian terdahulu
menunjukkan hasil yang memuaskan
untuk penggunaan WPD pada apliaksi
mesin diesel [1]. Pada penelitian lanjutan
ini, penulis meneliti penggunaan bahan
bakar WPD yang dicampur dengan bahan
bakar Orimulsion untuk aplikasi motor
diesel baik untuk penggunaan pada alat
transportasi darat maupun laut. Bahan
bakar Orimulsion adalah bahan bakar dari
Orinoco Tar dicampur dengan air yang
mempunyai kekentalan >10.000 cP pada
30
0
C dan mempunyai bahan campuran
hydrocarbon yang tinggi. Bahan bakar
Orinoco tar ini diproduksi di Venezuela.
Percobaan dilakukan dengan memakai
motor diesel jenis NF19SK 4 langkah yang
beroperasi konstan pada putaran mesin
2200 rpm. Tujuan utama pada penelitian
awal ini adalah mengetahui pengaruh
penggunaan WPD yang dicampur dengan
Orimulsion Fuel serta perbandingan
penurunan emisinya terhadap
penggunaan A Oil (High Speed Diesel Oil)
dan C Oil (Heavy Fuel Oil). Adapun emisi
yang di analisa adalah CH
4
, NO
2
, NO,
NOx, CO
2
, CO, SO
2
, Particulate Matter
dan Dry Soot.
2. Spesifikasi Bahan Bakar
Pada Tabel 1, 2, dan 3 dapat dilihat
spesifikasi dari bahan bakar Heavy Fuel
Oil (A Oil), WPD dan Orimulsion yang
digunakan dalam penelitian. Gambar 1
menunjukkan hasil analisa bahan bakar
dengan menggunakan LC-Mass
Spectrometer model LC-VP, Shimadzu.
Hasil penelitian laboratorium menunjukkan
pula kenaikan nilai CCAI sebesar 3% dari
858 menjadi 880, kinematic viscosity
menurun dari 500cSt menjadi 20cSt pada
20
0
C. Density dan sulfur menurun dari
0.999 menjadi 0.9853 dan 3.05 menjadi
1.98%(m/m) secara berurutan [2].
INOVASI
41
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Gambar 1. Hasil analisis Orimulsion (a), WPB
(b) dan Orimulsion 70-30% WPD (c)
dengan LC-Mass Spectometer
Tabel 1. Spesifikasi Bahan Bakar HFO
Unsur Unit J umlah
Density (15
0
C) g/cm
3
0.982
Reaction Degree Neutral
Flash Point
0
C 74.0
Kinematic viscosity
(50
0
C)
m m
2
/s
(cSt)
177.0
Pour point
0
C -10.0
Carbon Residue Wt. % 12.3
Sulfur Wt. % 2.56
Water Wt. % 0.00
Ash Wt. % 0.020
Nitrogen Wt. % 0,25
Gross Calorific Value MJ /kg 42.780
Vanadium m g/kg 58
Aluminium m g/kg 4
Magnesium m g/kg 2
Silica m g/kg 13
Tabel 2. Spesifikasi bahan bakar WPD
Unsur Satuan J umlah
Density (15
0
C) g/cm
3
0.939
Kinematic Viscosity (30
0
C)
m m
2
/s
(cSt)
1.189
Ignition Point
0
C 30.5
Styrene monomer % 63.9
Styrene dimmer % 11.5
Styrene trimer % 5.7
Toluene % 2.2
Ethyl Benzene % 1.4
Alpha methyl styrene % 2.2
K
O
M
P
O
N
E
N
Others % 13.1
Tabel 3. Spesifikasi bahan bakar Orimulsion
Unsur Satuan J umlah
Density g/cm
3
1.013
Kinematic Viscosity
(50
0
C)
mm
2
/s (cSt) 181
Carbon Residue % (m/m) 12.1
Sulfur % (m/m) 2.79
Nitrogen % (m/m) 0.39
Ash % (m/m) 0.28
Vanadium mg/kg 340
Natrium mg/kg 11
Magnesium mg/kg 410
Gross Calorific Value MJ /kg 28.3
Tabel 4. Spesifikasi motor diesel
Type Engine
Horizontal single cylinder
4 stroke diesel engine
(YANMAR NF19-SK)
Cylinder bore x stroke 110 x 106
Maximum Volume 1007 cm
3
Clearance Volume 61.78 cm
3
Maximum Power 19.0 PS / 2400 rpm
Rated Continuous
Power
16.0 PS / 2400 rpm
Compression ratio 16.3
Effect. compression
ratio
14.5
wirl ratio 2.20 0.1
Nozzle 0.33mm, 4 direction
injection
Nozzle Injection Angle 1500
Injection timing 1901 BTDC
Injection valve opening
pressure
19.620.1 Mpa (200
205 kgf/cm2)
Cooling type Radiator
Weight 192 kg
3. Langkah Percobaan
Gambar 2 menunjukkan alur penelitian
yang dilakukan. Percobaan dilaksanakan
dengan tiga bahan bakar yg berbeda,
yaitu bahan bakar WPD yg dicampur
dengan Orimulsion (WPD 30% +
Orimulsion 70%), Bahan bakar High
Speed Diesel Oil (A Oil) dan Heavy Fuel
Oil (C Oil),. Putaran mesin diatur tetap
pada 2200 rpm (dipilih karena pada
putaran ini adalah putaran kerja, MCR)
dengan beban yang berubah yaitu 25%,
50%, dan 75% beban penuh, dimana
beban penuh adalah 16 HP. Data yang
diamati adalah suhu gas buang, emisi gas
buang berupa CH
4
, NO
2
, NO, NOx, CO
2
,
CO, SO
2
, Particulate Matter dan Dry Soot
serta pemakaian bahan bakar spesifik
(Spesifik Fuel Oil Consumption). Untuk
memperoleh data emisi NOx, CO, O
2
digunakan alat chemiluminescent analyzer
(HORIBA 350), sementara CO
2
, NO
2
,
digunakan alat gas analyzer of content
potential electric type (Testo33,
Testoterm). Untuk mengetahui
kandungan SO
2
digunakan infra-rad ray
analyzer (Testo 350M) dan CH
4
dengan
CmHn analyzer (HCM-1B, Shimadzu).
Data selanjutnya yang diambil adalah PM
dan DS diperoleh dengan cara mengambil
sampel pada glass fiber filter yang
mulanya filter tersebut di keringkan pada
suhu 40
0
C selama 2 jam lalu ditimbang ,
setelah itu filter dipasang pada pipa gas
buang untuk memperoleh hasil emisi.
Setelah itu filter disimpan dalam larutan
Dichloromethane Solvent selama 24 jam,
Column: ShimpackGPC-802, GPC810Flowrate: 1.0mL/ minTemperature: 40Wavelength: 254nm
10 15 20 25
Minute
2
6
5
4
3
1
7 WPD
2
6
5
4
3
1
7
Bitumen70 vol.%
WPD30 vol.%
2
1
Bitumen
10 15 20 25 10 15 20 25
40
20
0
Column: ShimpackGPC-802, GPC810Flowrate: 1.0mL/ minTemperature: 40Wavelength: 254nm
10 15 20 25
Minute
2
6
5
4
3
1
7 WPD
2
6
5
4
3
1
7
Bitumen70 vol.%
WPD30 vol.%
2
1
Bitumen
10 15 20 25 10 15 20 25
40
20
0
10 15 20 25
Minute
2
6
5
4
3
1
7 WPD
2
6
5
4
3
1
7
Bitumen70 vol.%
WPD30 vol.%
2
1
Bitumen
10 15 20 25 10 15 20 25 10 15 20 25
Minute
2
6
5
4
3
1
7 WPD
2
6
5
4
3
1
7
Bitumen70 vol.%
WPD30 vol.%
2
1
Bitumen
10 15 20 25 10 15 20 25
40
20
0
a
c
b
42
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
dan dikeringkan lagi selama 2 jam
dengan alat yg sama dengan pertama.
Selisih berat filter sebelum diambil sampel
dengan sesudah diambil sampel itulah
yang digunakan untuk menganalisa jumlah
emisi PM dan DS. Dari data yang
diperoleh kemudian dibuat dalam bentuk
grafik seperti dapat dilihat pada bagian
Hasil dan Pembahasan.
4. Hasil dan Pembahasan
Dari hasil percobaan di laboratorium
diperoleh data yang kemudian dibuat
dalam bentuk grafik.
Gambar 3. Diagram Pressure
Gambar 3 menunjukkan diagram pressure
bahan bakar WPD-Orimulsion yang
digunakan, dimana kerja diesel relative
stabil terutama pada saat perubahan
beban kerja mesin.
Gambar 4 memperlihatkan
pemakaian bahan bakar orimulsion 70%
dan WPD 30% menghasilkan emisi CH
4
yang tertinggi namun dengan peningkatan
beban sampai 75% akan berangsur
menurun mendekati emisi CH
4
dari bahan
bakar C Oil. Pada saat beban rendah
pembakaran molekul C dan H pada
bahan bakar WPD-Orimulsion ini sedikit
tidak sempurna sehingga menghasilkan
emisi CH
4
yang tinggi, namun pada beban
tinggi pembakaran bahan bakar terlihat
kian sempurna.
9 8
7
1a
3
10
11
12 13 4 5
6
2
1b
14
Gambar 2. Diagram Ekperimen
1a WPD+Orimulsion Tank 1b DO/HFO Fuel 2 Pressure Analyzer 3 Filter 4 Diesel Engine 5 Water Hydraulic 6 Exhauts Pipe 7
EG Temperature Analyzer 8 NOx CO, O
2
Analyzer 9 SO
2
Analyzer 10 Flask 11 Water Cooler 12 Vinyl Bag 13 C
m
H
n
Analyzer 14
PM Analyzer
-40 -20 0 20 40
0
2
4
6
8
Engine load 75%
Engine load 50%
P
r
e
s
s
u
r
e
(
M
P
a
)
Crank Angle (degree)
Engine speed 2200(rpm)
Orinoco tar70%+WPD30%
Engine load 25%
-40 -20 0 20 40
0
2
4
6
8
Engine load 75%
Engine load 50%
P
r
e
s
s
u
r
e
(
M
P
a
)
Crank Angle (degree)
Engine speed 2200(rpm)
Orinoco tar70%+WPD30%
Engine load 25%
43
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
25 50 75
0
1
2
3
4
5
6
Engine Load (%)
C
H
4
(
g
r
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 4. Diagram Perubahan CH
4
25 50 75
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
Engine Load (%)
N
O
2
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 5. Diagram Perubahan NO
2
Gambar 5, 6, dan 7 menunjukkan emisi
NO
2
, NO, dan NOx meningkat linier
dengan peningkatan beban. Namun
konsentrasi emisi NOx (yg diatur dalam
Marpol 73/78 Annex 6) masih dibawah
ambang batas yang tentukan (17 gr/KwH),
dengan menggunakan bahan bakar WPD-
Orimulsion maksimum konsentrasi emisi
NO
x
yang dihasilkan adalah sebesar 7
gr/kWh pada beban 75%.
25 50 75
5
7.5
10
12.5
15
Engine Load (%)
N
O
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 6. Diagram Perubahan NO
25 50 75
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Engine Load (%)
N
O
x
(
g
/
k
W
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 7. Diagram Perubahan NO
x
25 50 75
900
1200
1500
1800
2100
2400
Engine Load (%)
C
O
2
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 8. Diagram Perubahan CO
2
25 50 75
0
5
10
15
20
25
30
35
Engine Load (%)
S
O
2
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 9. Diagram Perubahan SO
2
Gambar 8 menunjukkan konsentrasi emisi
CO
2
menurun pada beban 50% namun
meningkat kembali pada beban 75%.
Sementara untuk nilai SO
2
(Gambar 9)
menunjukkan penurunan untuk
peningkatan beban hingga mencapai rata-
rata 55,5%, nilai sulfur bahan bakar WPD-
Orimulsion menyebabkan besarnya
konsentrasi emisi SO
2
[4], namun lebih
rendah jika dibandingkan dengan nilai
konsentrasi untuk bahan bakar C Oil.
Pada temperatur tinggi dan konsentrasi
oksigen ideal bagi proses pembakaran,
sulfur berkombinasi dengan karbon,
hydrogen dan oksigen membentuk SO
2
,
SO
3
, SO, CS, CH, COS, H
2
S, S dan S
2
.
44
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Pada kondisi tersebut kandungan sulfur
bahan bakar akan dominan membentuk
SO
2
(90%) dan hanya sedikit yang
berubah menjadi SO
3
[2]. Gambar 10
memperlihatkan bahwa emisi CO bahan
bakar WPD-Orimulsion masih berada di
bawah konsentrasi CO bahan bakar HFO.
Hal ini menunjukkan bahwa proses
pembakaran yang baik, dapat mengurangi
emisi CO yang sangat berbahaya bagi
manusia dan atmosfer.
25 50 75
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
Engine Load (%)
C
O
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 10. Diagram Perubahan CO
25 50 75
250
300
350
400
450
500
550
Engine Load (%)
S
p
e
s
i
f
i
c
F
u
e
l
O
i
l
C
o
n
s
u
m
p
t
i
o
n
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 11. Diagram Perubahan SFOC
25 50 75
0
3
6
9
12
15
18
21
24
Engine Load (%)
P
M
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 12. Diagram Perubahan PM
25 50 75
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Engine Load (%)
D
S
(
g
/
k
W
.
h
)
Orimulsion 70% + WPD 30%
A Oil
C Oil
Gambar 13. Diagram Perubahan DS
Specific Fuel Oil Consumption
(SFOC) seperti yg ditunjukkan oleh
Gambar 11, dengan menggunakan bahan
bakar WPD-Orimulsion ini konsumsi
bahan bakar motor diesel dapat dikurangi
sampai 60% pada beban rendah. Proses
pembakaran yang baik dengan
menggunakan bahan bakar WPD-
Orimulsion menghasilkan konsumsi
bahan bakar yang baik pula. Gambar 12
dan 13 menunjukkan konsentrasi PM
(particulate matter) dan DS (dry soot)
yang diukur dengan menggunakan glass-
fiber filter dan electric drier pada suhu
40
0
C menunjukkan nilai terendah
dibandingkan dengan penggunaan bahan
bakar A Oil dan C Oil pada beban 25%.
Penurunan nilai PM rata-rata 45% sedang
DS adalah rata-rata 33%. Dari percobaan
yang dilakukan dapat juga diamati bahwa
kerja mesin diesel NF 19SK beroperasi
dengan stabil selama percobaan
berlangsung. Sehingga secara umum
dari hasil analisa bahwa emulsi
Orimulsion dan WPD dengan komposisi
70:30 (WPD 30% + Orimulsion 70%)
menunjukkan performa mesin diesel yang
baik dan ramah lingkungan.
5. Kesimpulan
Percobaan ini bertujuan untuk
menganalisa performa emisi mesin diesel
dengan penggunaan bahan bakar
terbarukan yaitu pencampuran antara
bahan bakar Waste Plastic Disposal
(WPD) dengan Orimulsion (Emulsified of
Orinoco Tar) yang dibandingkan dengan
penggunaan A Oil dan C Oil.
Berdasarkan hasil percobaan dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Secara teknis bahan bakar WPD-
Orimulsion dapat digunakan untuk
aplikasi pada motor diesel baik di
45
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
darat maupun di laut. Dari percobaan
diperoleh bahwa bahan bakar WPD
dapat menurunkan emisi CO
2
, CO,
SO
2
, PM dan DS. Sementara untuk
emisi CH
4
, NO
2
, NO, dan NOx
mengalami peningkatan untuk setiap
kenaikan bebannya.
2. Pencampuran bahan bakar WPD dan
Orimulsion menyebabkan penurunan
kadar sulfur bahan bakar sehingga
emisi SO
2
dapat dikurangi.
3. Selama percobaan berlangsung
motor diesel penguji NF19SK
beroperasi dengan baik dan stabil
pada suhu kerja 25.2
0
C.
4. Untuk menurunkan emisi SO
2
dan
NOx dapat digunakan teknologi
exhaust gas after treatment, seperti
exhaust gas recirculating atau
menggunakan katalis.
6. Daftar Pustaka
[1] Hai Vu, P., , et al, 2001,
Reduction of NOx and PMs from Diesel
Engines by WPD Emulsified Fuel, SAE
Conference.
[2] Luis J avier Molero de Blas.
Pollutant Formation and Interaction in the
Combustion of Heavy Liquid Fuels,
Doctoral Thesis, University of London.
[3] Nishida, O., H. Fujita, W. Harano,
T. Egashira, S. Okawa, M. Kawabata, T.
Nakatsukasa, Y. Sumitani, D. Suzuki,
1998, Proceeding of 60th Symposium of
The Marine Engineering Society in J apan,
pp.156-163.
[4] Nishida, O., Agung Sudrajad, PH. Vu,
H. Fujita, W. Harano, 2001, Exhaust
Emissions of Diesel N
2
O by various Fuel
Oil Condition. J IME Proceeding, pp. 36-43.
[5] Okaya, Y., 1997, Development of
new Technique for Reprocessing of
Waste Plastic Materials, Technical report,
pp.1-3.
46
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Domestikasi laut atau restoking?
Alimuddin
Staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB, dan
kandidat doktor dari Tokyo University of Marine Science and Technology
E-mail: alimuddin_alsani@yahoo.com
Eko Sri Wiyono
Staf pengajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB, dan
kandidat doktor dari Tokyo University of Marine Science and Technology
E-mail : eko_ipb@yahoo.com
Baru-baru ini telah dilaporkan bahwa stok
ikan laut dunia telah menurun dengan
cepat (Sargent dan Tacon,
1999). Penurunan stok ikan laut ini
diperkirakan sebagai akibat dari
kegagalan pengelolaan perikanan laut
dalam beberapa dekade terakhir di hampir
seluruh belahan dunia. Dan hal ini
menyebabkan penangkapan ikan di laut
tidak akan bertahan lebih lama lagi dan
mungkin tidak ada lagi yang tersisa untuk
bisa dikelola (Pauly et al., 2002). Kondisi
perikanan Indonesia tidak jauh berbeda
dengan kondisi perikanan dunia secara
umum. Sistem penentuan stok
sumberdaya ikan yang kurang akurat
(Wiyono, 2005) dan lemahnya penegakan
hukum di laut, telah menyebabkan
kegiatan penangkapan ikan di Indonesia
mencapai overfishing di berbagai wilayah
perair-an. Beratnya beban laut Indonesia
untuk menyediakan stok ikan semakin
diperparah dengan tingginya kejadian
illegal fishing. Bila kenyataanya stok ikan
di Indonesia juga seperti halnya kondisi
stok ikan dunia, maka apa yang
seharusnya kita lakukan untuk
memulihkan kondisi stok atau memenuhi
kebutuhan kita?
Sejak berakhirnya jaman es, dan
dimulainya revolusi industri, manusia telah
mempengaruhi evolusi organisme darat
maupun laut, dan telah menyebabkan
hilangnya beberapa jenis hewan liar
(Diamond, 2002). Manusia telah menggu-
nakan pendekatan land-based ekosistem
untuk memenuhi kebutuhannya.
Pendekatan ini, di satu sisi telah
menghasilkan keuntungan tetapi di sisi
yang lain meng-haruskan membayar cost
yang yang tidak murah, misalnya
banyaknya penyakit yang menyerang
hewan peliharaan. Hal yang mirip juga
telah terjadi di lautan, meskipun prosesnya
lebih lambat karena luasnya laut dan
ketidakramahan laut. Sejauh ini,
perubahan di laut juga menggambarkan
apa yang telah terjadi di darat seperti
perusakan habitat, perubahan utama
dalam komunitas tumbuhan dan hewan,
dan hilangnya spesies hewan ukuran
besar.
Penangkapan yang secara prinsip adalah
pengejaran ikan di laut, merupakan
penyebab langsung atau tidak langsung
perubahan-perubahan yang telah terjadi di
laut, mulai dari hilangnya mamalia laut
ukuran besar hingga kerusakan
habitat. Penangkapan yang tiada henti-
hentinya dan peningkatan kemampuan
tangkap, telah mengurangi populasi ikan
dunia dengan cepat. Penangkapan
spesies laut ukuran besar, seperti ikan
pedang (swordfish) dan tuna, telah
menurunkan 80% populasi selama 20
tahun terakhir (Myers dan Worm,
2003). Ikan cod yang secara historis
merupakan spesies utama sudah menjadi
sulit ditemukan di daerah Atlantik Utara. Di
banyak daerah, trawl-dasar (bottom trawl)
telah menyapu dasar lautan. Semua ini
hanyalah sedikit contoh dari bukti
pengejaran yang panjang dan
menyedihkan di lautan. Bila sejarah
dijadikan sebagai sebuah petunjuk,
meskipun sistem manajemen
penangkapan berbasis ekosistem atau
dengan istilah ecosystem-based fishery
management, (Pikitch, 2004) diterapkan
sekalipun, maka kemampuan laut untuk
menyuplai ikan yang dapat kita tangkap
akan segera mencapai batas
maksimumnya.
IPTEK
47
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Memburuknya perikanan tangkap dunia
dan kerusakan habitat laut membantu
menjelaskan mengapa domestikasi laut
merupakan kegiatan yang tidak dapat
dielakkan. Tetapi, kita perlu berhati-hati
mempertimbangkan bagaimana
domestikasi ini dilakukan untuk
menghindari lubang-lubang perangkap
yang bisa merusak lingkungan (Pauly et
al., 2002; Naylor et al., 2000).
Domestikasi ikan atau akuakultur secara
keseluruhan telah berperan dalam pening-
katan produksi ikan dunia yang terjadi
dalam 18 tahun terakhir ini (Naylor et al.,
2000). Peningkatan produksi ikan ini
diperoleh dengan melakukan domestikasi
di darat. Akan tetapi, hal ini kelihatannya
sudah tidak bisa ditingkatkan lagi, karena
transformasi di darat hanya menghasilkan
sedikit perubahan. Oleh karena itu, saat ini
mungkin sudah waktunya untuk
melakukan domestikasi di
laut. Domestikasi laut ini mungkin sudah
menjadi keharusan dan sesegera mungkin
untuk dilakukan, mengingat pertumbuhan
penduduk yang sangat cepat. Namun
demikian, kita juga harus mampu
menjawab bagaimana domestikasi
diterapkan, sehingga pengelolaannya
tetap memperhatikan kesehatan
lingkungan dan kesinambungannya.
Untuk mengantisipasi penurunan produksi
ikan di Amerika Serikat, baru-baru ini,
badan nasional Amerika Serikat yang
menangani laut dan atmosfir mengusulkan
peraturan untuk memperluas usaha
budidaya hingga 200 mil dari pantai dan
menambah jumlah spesies ikan yang
dibudidayakan (Marra, 2005). Berita ini
sangat mengagetkan dan menimbulkan
bermacam-macam reaksi (Dalton,
2005). Tetapi, mereka juga yakin bahwa
cara ini merupakan sesuatu yang tak
terelakkan lagi. Sementara itu, di Negara
kita, Departemen Kelautan dan Perikanan
membuat kebijakan pengembangan
spesies budidaya unggulan seperti ikan
nila untuk budidaya air tawar, dan udang
windu, kerapu dan rumput laut untuk
budidaya laut. Pemilihan jenis organisme
ini dimaksudkan untuk
mengkonsentrasikan perhatian dalam
pengem-bangan budidaya ikan yang
memiliki nilai strategis, baik secara
nasional maupun internasional.
Akuakultur dan Problematikanya
Ambruknya perikanan laut diduga akan
terjadi bersamaan dengan meningkatnya
permintaan pangan dunia, khususnya
protein hewani. Sehingga produksi
pangan dunia harus dilipat-gandakan 50
tahun ke depan untuk mengimbangi
pertumbuhan penduduk dunia (Tilman et
al., 2002), dan laut dunia harus lebih
berperan sebagai sumber pangan.
Untuk mengatasi kesenjangan kebutuhan
dan produksi protein hewani, maka
kegiatan akuakultur perlu lebih
ditingkatkan. Amerika Serikat misalnya,
dalam 20 tahun terakhir telah
meningkatkan sekitar 10% per tahun
produksi budidayanya, yang meliputi
budidaya ikan laut dan kerang-kerangan di
pinggir pantai. Sejauh ini, di Indonesia
sebagian besar perluasan akuakultur
dilakukan pada ikan air tawar, seperti nila,
ikan mas dan ikan lele-lelean di kolam
atau keramba jaring apung. Sedangkan
pada budidaya laut adalah masih
didominasi oleh udang windu. J enis
organisme budidaya laut yang
dikembangkan juga baru-baru ini adalah
udang jenis vannamei dan ikan kerapu.
Khusus untuk ikan kerapu, masih
diperlukan pengembangan teknologi
budidayanya untuk mencapai hasil yang
memuaskan, baik dari segi teknologi
produksi benih, maupun sistem
pembesarannya.
Seperti pemeliharaan hewan darat,
pemeliharaan ikan dapat merugikan
lingkungan dan ekosistem pantai dengan
berbagai cara (Pauly et al.,
2002). Pertama, budidaya laut dapat
mencemari dari segi estetika, kimiawi, dan
secara genetika. Sistem budidaya laut di
pantai merusak pemandangan di laut dan
mempengaruhi nilai pro-pertinya. Bahan
kimia yang ditambahkan dalam pakan ikan,
seperti bahan pewarna, menjadi
ditemukan di dasar laut, dari kemudian
masuk ke dalam rantai makanan di hewan
bentik. Dan untuk polusi genetika,
lepasnya ikan peliharaan dari wadahnya
dan menginfeksi gen-pool stok ikan liar
atau mengganti spesies endemik, bisa
menjadi sumber masalah. Kedua,
padatnya wadah budidaya atau tambak
dapat dengan mudah melipatkan
gandakan penyakit dan menyebarkannya
48
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
dengan cepat dibandingkan dengan yang
alami. Ketiga, marikultur ikan karnivora
memberikan tekanan tambahan yang
besar kepada stok alam yang digunakan
untuk pakan (Naylor et al., 2000), menjadi
memperburuk/mempercepat penurunan
stok populasi ikan alam.
Sampai saat ini, kebutuhan ikan pelagik
ukuran kecil, seperti anchovy atau sardine,
untuk ikan komersil budidaya (sebagai
contoh ikan salmon), adalah melebihi
produksi ikan komersil itu sendiri dalam
arti biomassa. Hal ini tidak dapat disangkal
akan mendatangkan masalah yang serius,
misal menambah penyakit-penyakit
lingkungan yang datang dari darat ke
tempat usaha pemeliharaan. Tetapi bila
kita setuju bahwa domestikasi laut baru
dimulai, kita dapat merancang agenda
penelitian untuk mengurangi masalah dan
mempertahankan kelangsungannya, baik
secara ekologis maupun ekonomis.
Domestikasi Laut Membutuhkan
Dukungan Kolektif
Penelitian untuk industri marikultur
diperlukan mulai dari penelitian dasar
hingga aplikasinya. J uga dibutuhkan
pemilihan spesies yang dapat
diadaptasikan di wadah budidaya dan
dapat didomestikasi sepanjang siklus
hidup-nya. Sistem pengelolaan kesehatan
ikan dan makanannya. Pencarian alternatif
pengganti ikan pelagik kecil yang saat ini
digunakan untuk ikan budidaya, misal
hasil tangkapan sampingan. Dengan
mempertimbangkan dina-mika laut dan
kondisi gelombang permukaan,
menentukan dimana seharusnya
marikultur dilakukan. J uga, perlu diteliti
bagaimana seharusnya konstruksi wadah
dan sistem pengelolaannya. Semua hal di
atas akan mengarahkan kita kepada
aspek peraturan dan hukum. Salah satu
jalan pemecahan untuk masalah-masalah
yang berhubungan dengan marikultur
pantai adalah memindahkan kegiatan dari
pantai ke daerah perairan lebih luar dan di
laut lepas. Secara umum, sistem lepas
pantai menyebabkan lebih sedikit polusi
pantai, tetapi akan meningkatkan biaya
secara dramastis.
Contoh Domestikasi Laut
Meskipun domestikasi laut akan
membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
tetapi dari pilot proyek yang dirancang di
Amerika mengilustrasikan sebagai suatu
solusi yang potensial. Sebagai contoh,
pemeliharaan ikan dalam pens raksasa di
pantai (volume air sekitar 100.000 m
3
)
adalah dirancang untuk tahan hempasan
dan bebas di laut. Prototipe dalam bentuk
dua cones sandwitch di dasarnya adalah
sedang diujicoba di beberapa tempat di
daerah pantai, sementara yang lainnya
ditancapkan di dasar laut.
Suatu proyek telah dicoba dengan
memelihara ikan ukuran burayak
(fingerling) menggunakan sistem pens di
Florida. Pens ini dibawa menyeberangi
Teluk Gulf Stream dan kemudian arus
Atlantic Utara akan membawa pens
tersebut menyeberangi Atlantik, dan
mendapatkan makan sepanjang
perjalanan. Dengan dirancang untuk tetap
kokoh di bawah permukaan air, gangguan
pelayaran terhadap pens menjadi
sedikit. Pens akan tiba di Eropa beberapa
bulan kemudian, dan ikan akan tumbuh
hingga mencapai ukuran pasar. Setelah
pemanenan, pens dapat diisi kembali
dengan ikan ukuran burayak dalam
perjalanan pulang. Tetapi sistem seperti
ini memiliki tantangan pengelolaan yang
tinggi: pemberian pakan,
mempertahankan kedalaman ideal dan
komunikasi lewat satelit harus dilakukan
secara otomatis, selama beberapa bulan
pada waktu tertentu.
Pengembangan lainnya adalah
penggembalaan (herding) ikan tuna di
laut. Banyak spesies ikan tuna adalah
tertarik kepada sesuatu yang berbeda
dengan kondisi di sekeliling-nya. Nelayan
dapat mengambil keuntungan dari tingkah
laku ini dengan menggunakan suatu alat
pengumpul ikan (fish aggregating device,
FAD). Secara sederhana ini dapat berupa
batang kayu terapung, atau sistem
pelampung yang lebih kompleks, atau
membuat gangguan berupa keributan
secara perlahan di permukaan air
laut. Perahu nelayan yang memancarkan
cahaya juga akan bisa menjadi sebuah
daya tarik, dan oleh karena itu dapat
menarik tuna untuk mengikuti. Tuna yang
tertarik ke FAD dapat diberi pakan,
49
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
dipertahankan, dan sebagian mungkin
dapat ditangkap. Meskipun
penggunaannya kontro-versial, FAD dapat
meningkatkan hasil. Tuna tidak akan
didomestikasi seperti sapi, tetapi apa yang
dilakukan di laut masih analog dengan
penggembalaan di daratan. Hal ini adalah
dua contoh bagaimana meningkatkan
produksi ikan laut tanpa merusak
ekosistem laut lebih parah lagi melalui
penangkapan, dan memecahkan masalah
yang disebabkan oleh marikultur di daerah
pantai.
Konsekuensi Domestikasi Laut
Beberapa konsekuensi domestikasi laut,
yaitu: pertama, nelayan mungkin akan
hilang secara besar-besaran; jumlah ikan
yang akan diambil diatur; dan jenis ikan
yang kita makan tidak banyak
bervariasi. Kita harus bisa menerima ikan
laut hasil budidaya, dan harus menerima
kenyataan bahwa kita tidak begitu bebas
di laut.
Secara internasional, domestikasi akan
memerlukan perubahan tujuan dari status
quo. Saat ini, pemerintah dan nelayan
menjadi penyebab over-eksplotasi stok
ikan dan over-kapitalisasi industri
penangkapan. Bila domestikasi laut
menjadi pilihan, negara maritim harus
melakukan negosiasi persetujuan tentang
penggunaan laut secara bersama. J uga,
pemerintah harus berperan membantu
perkembangan penelitian untuk
menemukan cara kultivasi ikan di laut
terbuka, dan budidaya ikan laut dekat
pantai yang lebih ramah
lingkungan. Tujuan utamanya diarah-kan
untuk menjaga laut sebagai sumber
pangan yang lestari, baik secara ekonomi
maupun ekologis. Seperti pada daratan,
kelangsungan suplai pangan dari laut
untuk penduduk dunia merupakan tujuan
dari domestikasi laut.
Domestikasi Tidak Mengganti
Penangkapan Bila Stok Ikan Dipulihkan
Kita telah mengetahui bahwa marikultur
bisa menjadi kontributor utama untuk
produksi pangan dunia dan sebagai
sebuah solusi dari overfishing. Dengan
kata lain bahwa perikanan dunia mungkin
seharusnya diganti dengan domestikasi
ikan di laut dalam skala besar. Kita tahu
bahwa akuakultur semakin memegang
peranan penting dalam suplai ikan
dunia. Tetapi, pemisahan secara hati-hati
harus dilakukan antara budidaya ikan air
tawar, molluska dan tanaman dengan
karakteristik teknologinya yang low-
technology dan pengaruhnya rendah (low-
impact), dan lebih banyak diarahkan untuk
membantu pangan di negara-negara
berkembang. Sementara budidaya ikan
laut menggunakan teknologi tinggi dengan
ikan target berupa ikan karnivora dan lebih
banyak diperuntukkan bagi
supermarket. Dengan demikian,
sepertinya keluarga dengan pendapatan
rendah tidak akan merasakan enaknya
ikan tuna, salmon atau cod. J uga, suplai
protein untuk masyarakat dengan
pendapatan rendah akan hilang karena
sebagian besar ikan-ikan kecil dialihkan
untuk menjadi pakan ikan
marikultur. Budidaya ikan karnivora juga
menghasilkan ketidakefisienan konversi
energi antar level tropik (tropic
level). Karena itu, usaha tuna tidak bisa
disetarakan seperti memelihara sapi,
tetapi lebih mirip mengurung serigala yang
diberi makan tikus dan rubah liar.
Salah satu alternatif pemecahan masalah
sehubungan dengan pengembangan
budidaya ikan tuna atau ikan laut secara
umum dapat dibaca dalam artikel
Memproduksi ikan dengan ikan bisa
dihilangkan? dalam INOVASI (Alimuddin,
2005) dan dalam artikel di BeritaIptek,
Teknik baru menyelamatkan ikan langka
(Alimuddin, 2005a).
Ikan hasil tangkapan dan populasi alami
untuk menyuplai kebutuhan penduduk
dunia adalah tidak berlimpah. Dengan
demikian, sudah seharusnya usaha lain
difokuskan untuk mengembalikan populasi
ikan alami yang turun drastis dengan
melakukan restoking besar-besaran dan
mengurangi total kapasitas
penangkapan. Pengelolaan yang tepat
terhadap ikan laut di alam akan
menghasilkan kemajuan yang berarti,
tetapi sayangnya, hal ini membutuhkan
pre-kondisi seperti keinginan politik untuk
mengimplementasikan perubahan-
perubahan dan membuat persetujuan
antar negara untuk penggunaan laut
secara bersama.
50
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Daftar Pustaka
[1] Alimuddin, 2005, Menghasilkan
ikan dengan ikan bisa dihilangkan?
INOVASI, 3, 47-50.
[2] Alimuddin, 2005a, Teknik baru
menye-lamatkan ikan langka, BeritaIptek;
Artikel Iptek, 14 September 2005.
[3] Dalton, J ., 2005, Bill on deep-sea
fish farms brings wave of disapproval,
Nature, 435, 1014.
[4] Diamond, J ., 2002, Evolution,
consequences and future of plant and
animal domestication, Nature, 418, 700-
707.
[5] Marra, J ., 2005, When we tame
the oceans? Nature, 436, 175-176.
[6] Myers, R.A. and B. Worm,
2003, Rapid world depletion of predatory
fish communities, Nature, 423, 280-283.
[7] Naylor, R.L., R.J .
Goldburg, J .H. Primavera, N. Kautsky,
M.C.M. Beveridge, J . Clay, C. Folke, J .
Lubchenco, H. Mooney, and M. Troell,
2000, Effect of aquaculture on world fish
supplies, Nature, 405, 1017-1024.
[8] Pauly, D., V. Christensen,
S. Guenette, T.J . Pitcher, U.R. Sumaila,
C.J . Walters, R. Watson, and D.
Zeller. 2002, Towards sustainability in
world fisheries, Nature, 418, 689-695.
[9] Pikitch, E.K., C. Santora,
E.A. Babcock, A. Bakun, R. Bonfil, D.O.
Conover, D. Dayton, P. Doukakis, D.
Fluharty, B. Heneman, E.D. Houde, J . Link,
P.A. Livingston, M. Mangel, M.K.
McAllister, J . Pope, and K.J . Sainsbury,
2004, Ecosystem-based fishery
management, Science, 305, 346-347.
[10] Sargent J R and Tacon A
(1999) Development of farmed fish: a
nutritionally necessary alternative to
meat, Proc Nutr Soc., 58, 377-383.
[11] Tilman, D., K.G. Cassman, P.A.
Matson, R. Naylor and S. Polasky, 2002,
Agricultural sustainability and intensive
production practices, Nature, 418, 671-677.
[12] Wiyono, E.S., 2005, Stok
sumberdaya ikan dan keberlanjuatan
kegiatan perikanan, INOVASI, 4, 26-30
51
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Pencemaran Udara, Suatu Pendahuluan
Agung Sudrajad
1,2
1
Mahasiswa Program Doktor Pada Laboratorium Teknik Energi Universitas Kobe
2
Staff Pengajar Fakultas Teknologi Kelautan Universitas Darma Persada J akarta
Email: 021d801n@y04.kobe-u.ac.jp , agung_sudrajad@lycos.com
1. Umum
Tulisan ini mengetengahkan sekilas
pandang mengenai pencemaran udara.
pengertian, pengaruhnya terhadap
kualitas lingkungan dan kesehatan
manusia serta teknologi terbaru untuk
menguranginya. Semakin pesatnya
kemajuan ekonomi mendorong semakin
bertambahnya kebutuhan akan
transportasi, dilain sisi lingkungan alam
yang mendukung hajat hidup manusia
semakin terancam kualitasnya, efek
negatif pencemaran udara kepada
kehidupan manusia kian hari kian
bertambah. Untuk itulah tulisan singkat ini
dipersembahkan sebagai bahan awal
untuk melangkah menciptakan lingkungan
yang sehat dan nyaman. Pencemaran
udara adalah masuknya, atau
tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke
dalam atmosfir yang dapat mengakibatkan
terjadinya kerusakan lingkungan,
gangguan pada kesehatan manusia
secara umum serta menurunkan kualitas
lingkungan. Pencemaran udara dapat
terjadi dimana-mana, misalnya di dalam
rumah, sekolah, dan kantor. Pencemaran
ini sering disebut pencemaran dalam
ruangan (indoor pollution). Sementara itu
pencemaran di luar ruangan (outdoor
pollution) berasal dari emisi kendaraan
bermotor, industri, perkapalan, dan proses
alami oleh makhluk hidup. Sumber
pencemar udara dapat diklasifikasikan
menjadi sumber diam dan sumber
bergerak. Sumber diam terdiri dari
pembangkit listrik, industri dan rumah
tangga. Sedangkan sumber bergerak
adalah aktifitas lalu lintas kendaraan
bermotor dan tranportasi laut. Dari data
BPS tahun 1999, di beberapa propinsi
terutama di kota-kota besar seperti Medan,
Surabaya dan J akarta, emisi kendaraan
bermotor merupakan kontribusi terbesar
terhadap konsentrasi NO
2
dan CO di
udara yang jumlahnya lebih dari 50%.
Penurunan kualitas udara yang terus
terjadi selama beberapa tahun terakhir
menunjukkan kita bahwa betapa
pentingnya digalakkan usaha-usaha
pengurangan emisi ini. Baik melalui
penyuluhan kepada masyarakat ataupun
dengan mengadakan penelitian bagi
penerapan teknologi pengurangan emisi.
2. Zat-zat Pencemar Udara
Emisi Karbon Monoksida (CO)
Asap kendaraan merupakan sumber
utama bagi karbon monoksida di berbagai
perkotaan. Data mengungkapkan bahwa
60% pencemaran udara di J akarta
disebabkan karena benda bergerak atau
transportasi umum yang berbahan bakar
solar terutama berasal dari Metromini [5].
Formasi CO merupakan fungsi dari rasio
kebutuhan udara dan bahan bakar dalam
proses pembakaran di dalam ruang bakar
mesin diesel. Percampuran yang baik
antara udara dan bahan bakar terutama
yang terjadi pada mesin-mesin yang
menggunakan Turbocharge merupakan
salah satu strategi untuk meminimalkan
emisi CO. Karbon monoksida yang
meningkat di berbagai perkotaan dapat
mengakibatkan turunnya berat janin dan
meningkatkan jumlah kematian bayi serta
kerusakan otak. Karena itu strategi
penurunan kadar karbon monoksida akan
tergantung pada pengendalian emisi
seperti pengggunaan bahan katalis yang
mengubah bahan karbon monoksida
menjadi karbon dioksida dan penggunaan
bahan bakar terbarukan yang rendah
polusi bagi kendaraan bermotor
Nitrogen Oksida (NOx)
Sampai tahun 1999 NOx yang berasal dari
alat transportasi laut di J epang
menyumbangkan 38% dari total emisi NOx
(25.000 ton/tahun) [4]. NOx terbentuk atas
tiga fungsi yaitu Suhu (T), Waktu Reaksi
(t), dan konsentrasi Oksigen (O
2
), NOx =f
(T, t, O
2
). Secara teoritis ada 3 teori yang
mengemukakan terbentuknya NOx, yaitu:
IPTEK
52
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
a. Thermal NOx (Extended Zeldovich
Mechanism)
Proses ini disebabkan gas nitrogen yang
beroksidasi pada suhu tinggi pada ruang
bakar (>1800 K). Thermal NOx ini
didominasi oleh emisi NO (NOx =NO +
NO
2
).
b. Prompt NOx
Formasi NOx ini akan terbentuk cepat
pada zona pembakaran.
c. Fuel NOx
NOx formasi ini terbentuk karena
kandungan N dalam bahan bakar.
Kira-kira 90% dari emisi NOx adalah
disebabkan proses thermal NOx, dan
tercatat bahwa dengan penggunaan HFO
(Heavy Fuel Oil), bahan bakar yang biasa
digunakan di kapal, menyumbangkan
emisi NOx sebesar 20-30%. Nitrogen
oksida yang ada di udara yang dihirup
oleh manusia dapat menyebabkan
kerusakan paru-paru. Setelah bereaksi
dengan atmosfir zat ini membentuk
partikel-partikel nitrat yang amat halus
yang dapat menembus bagian terdalam
paru-paru. Selain itu zat oksida ini jika
bereaksi dengan asap bensin yang tidak
terbakar dengan sempurna dan zat
hidrokarbon lain akan membentuk ozon
rendah atau smog kabut berawan coklat
kemerahan yang menyelimuti sebagian
besar kota di dunia.
SOx (Sulfur Oxide : SO
2
, SO
3
)
Emisi SOx terbentuk dari fungsi
kandungan sulfur dalam bahan bakar,
selain itu kandungan sulfur dalam pelumas,
juga menjadi penyebab terbentuknya SOx
emisi. Struktur sulfur terbentuk pada
ikatan aromatic dan alkyl. Dalam proses
pembakaran sulfur dioxide dan sulfur
trioxide terbentuk dari reaksi:
S +O
2
=SO
2
SO
2
+1/2 O
2
=SO
3
Kandungan SO
3
dalam SOx sangat kecil
sekali yaitu sekitar 1-5%. Gas yang
berbau tajam tapi tidak berwarna ini dapat
menimbulkan serangan asma, gas ini pun
jika bereaksi di atmosfir akan membentuk
zat asam. Badan WHO PBB menyatakan
bahwa pada tahun 1987 jumlah sulfur
dioksida di udara telah mencapai ambang
batas yg ditetapkan oleh WHO.
Emisi HydroCarbon (HC)
Pada mesin, emisi Hidrokarbon (HC)
terbentuk dari bermacam-macam sumber.
Tidak terbakarnya bahan bakar secara
sempurna, tidak terbakarnya minyak
pelumas silinder adalah salah satu
penyebab munculnya emisi HC. Emisi HC
pada bahan bakar HFO yang biasa
digunakan pada mesin-mesin diesel besar
akan lebih sedikit jika dibandingkan
dengan mesin diesel yang berbahan bakar
Diesel Oil (DO). Emisi HC ini berbentuk
gas methan (CH
4
). J enis emisi ini dapat
menyebabkan leukemia dan kanker.
Partikulat Matter (PM)
Partikel debu dalam emisi gas buang
terdiri dari bermacam-macam komponen.
Bukan hanya berbentuk padatan tapi juga
berbentuk cairan yang mengendap dalam
partikel debu. Pada proses pembakaran
debu terbentuk dari pemecahan unsur
hidrokarbon dan proses oksidasi
setelahnya. Dalam debu tersebut
terkandung debu sendiri dan beberapa
kandungan metal oksida. Dalam proses
ekspansi selanjutnya di atmosfir,
kandungan metal dan debu tersebut
membentuk partikulat. Beberapa unsur
kandungan partikulat adalah karbon, SOF
(Soluble Organic Fraction), debu, SO
4
,
dan H
2
O. Sebagian benda partikulat
keluar dari cerobong pabrik sebagai asap
hitam tebal, tetapi yang paling berbahaya
adalah butiran-butiran halus sehingga
dapat menembus bagian terdalam paru-
paru. Diketahui juga bahwa di beberapa
kota besar di dunia perubahan menjadi
partikel sulfat di atmosfir banyak
disebabkan karena proses oksida oleh
molekul sulfur.
3. Efek Negatif Pencemaran Udara Bagi
Kesehatan Tubuh
Tabel 1 menjelaskan tentang pengaruh
pencemaran udara terhadap makhluk
hidup. Rentang nilai menunjukkan batasan
kategori daerah sesuai tingkat kesehatan
untuk dihuni oleh manusia. Karbon
monoksida, nitrogen, ozon, sulfur dioksida
dan partikulat matter adalah beberapa
parameter polusi udara yang dominan
dihasilkan oleh sumber pencemar. Dari
pantauan lain diketahui bahwa dari
beberapa kota yang diketahui masuk
dalam kategori tidak sehat berdasarkan
ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara)
53
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
adalah J akarta (26 titik), Semarang (1 titik),
Surabaya (3 titik), Bandung (1 titik),
Medan (6 titik), Pontianak (16 titik),
Palangkaraya (4 titik), dan Pekan Baru (14
titik). Satu lokasi di J akarta yang diketahui
merupakan daerah kategori sangat tidak
sehat berdasarkan pantauan lapangan [1].
Tabel 1. Pengaruh Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)
Sumber: Bapedal [2]
Kategori Rentang
Karbon
monoksida
(CO)
Nitrogen
(NO
2
)
Ozon (O
3
)
Sulfur
dioksida
(SO
2
)
Partikulat
Baik 0-50 Tidak ada efek Sedikit berbau Luka pada
Beberapa
spesies
tumbuhan akibat
kombinasi
dengan SO
2
(Selama 4 J am)
Luka pada
Beberapa
spesies
tumbuhan
akibat
kombinasi
dengan O
3
(Selama 4
J am)
Tidak ada efek
Sedang 51 - 100 Perubahan
kimia darah tapi
tidak terdeteksi
Berbau Luka pada
Beberapa
spesies
tumbuhan
Luka pada
Beberapa
spesies
tumbuhan
Terjadi
penurunan
pada jarak
pandang
Tidak
Sehat
101 - 199 Peningkatan
pada
kardiovaskular
pada perokok
yang sakit
jantung
Bau dan
kehilangan
warna.
Peningkatan
reaktivitas
pembuluh
tenggorokan
pada penderita
asma
Penurunan
kemampuan
pada atlit yang
berlatih keras
Bau,
Meningkatnya
kerusakan
tanaman
J arak pandang
turun dan
terjadi
pengotoran
debu di mana-
mana
Sangat
Tidak
Sehat
200-299 Meningkatnya
kardiovaskular
pada orang
bukan perokok
yang
berpenyakit
J antung, dan
akan tampak
beberapa
kelemahan yang
terlihat secara
nyata
Meningkatnya
sensitivitas
pasien yang
berpenyaklt
asma dan
bronchitis
Olah raga ringan
mengakibatkan
pengaruh
parnafasan
pada pasien
yang
berpenyaklt
paru-paru kronis
Meningkatnya
sensitivitas
pada pasien
berpenyakit
asma dan
bronchitis
Meningkatnya
sensitivitas
pada pasien
berpenyakit
asma dan
bronchitis
Berbahaya 300 - lebih Tingkat yang berbahaya bagi semua populasi yang terpapar
Sumber: Bapedal [1]
Tabel 2. Sumber dan Standar Kesehatan Emisi Gas Buang
Pencemar Sumber Keterangan
Karbon monoksida
(CO)
Buangan kendaraan bermotor; beberapa
proses industri
Standar kesehatan: 10 mg/m3 (9
ppm)
Sulfur dioksida (S0
2
) Panas dan fasilitas pembangkit listrik
Standar kesehatan: 80 ug/m3 (0.03
ppm)
Partikulat Matter
Buangan kendaraan bermotor; beberapa
proses industri
Standar kesehatan: 50 ug/m3
selama 1 tahun; 150 ug/m3
Nitrogen dioksida
(N0
2
)
Buangan kendaraan bermotor; panas
dan fasilitas
Standar kesehatan: 100 pg/m3 (0.05
ppm) selama 1 jam
Ozon (0
3
) Terbentuk di atmosfir
Standar kesehatan: 235 ug/m3 (0.12
ppm) selama 1 jam
54
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia
Tabel 2 memperlihatkan sumber emisi dan
standar kesehatan yang ditetapkan oleh
pemerintah melalui keputusan Bapedal.
BPLHD Propinsi DKI J akarta pun mencatat
bahwa adanya penurunan yang signifikan
jumlah hari dalam kategori baik untuk
dihirup dari tahun ke tahun sangat
mengkhawatirkan. Dimana pada tahun
2000 kategori udara yang baik sekitar 32%
(117 hari dalam satu tahun) dan di tahun
2003 turun menjadi hanya 6.85% (25 hari
dalam satu tahun) [3]. Hal ini menandakan
Indonesia sudah seharusnya memperketat
peraturan tentang pengurangan emisi baik
sektor industri maupun sektor transportasi
darat/laut. Selain itu tentunya penemuan-
penemuan teknologi baru pengurangan
emisi dilanjutkan dengan pengaplikasiannya
di masyarakat menjadi suatu prioritas utama
bagi pengendalian polusi udara di Indonesia.
4. Tentang Teknologi Penanggulangan
Emisi dari Kendaraan
Secara sekilas teknologi penanggulangan
emisi dari mesin dapat dikategorikan
menjadi dua bagian besar yaitu
Pengurangan emisi metoda primer dan
Pengurangan emisi metoda sekunder [6].
Untuk pengurangan emisi metoda primer
adalah sebagai berikut:
Berdasarkan bahan bakar:
Penggunaan bahan bakar yang rendah
Nitrogen dan Sulfur termasuk
penggunaan non fossil fuel
Penggalangan penggunaan Non
Petroleum Liquid Fuels
Penggunaan angka cetan yang tinggi bagi
motor diesel dan angka oktan bagi
motor bensin
Penggunaan bahan bakar Gas
Penerapan teknologi emulsifikasi
(pencampuran bahan bakar dengan air
atau lainnya)
Berdasarkan Perlakuan Udara
Penggunaan teknologi Exhaust Gas
Recirculation (EGR)
Pengaturan temperature udara yang
masuk pada motor
Humidifikasi
Berdasarkan Proses Pembakaran
Modifikasi pada pompa bahan bakar dan
sistem injeksi bahan bakar
Pengaturan waktu injeksi bahan bakar
Pengaturan ukuran droplet dari bahan
bakar yang diinjeksikan
Injeksi langsung air ke dalam ruang
pembakaran
Sementara itu pengurangan emisi metoda
sekunder adalah:
Penggunaan Selective Catalytic
Reduction (SCR)
Penerapan teknologi Sea Water Scrubber
untuk aplikasi di kapal
Penggunaan katalis magnet yang
dipasang pada pipa bahan bakar
Penggunaan katalis pada pipa gas buang
kendaraan bermotor
5. Akhir
Melihat kenyataan seperti dituliskan diatas,
polusi udara merupakan salah satu
permasalahan lingkungan yang serius di
Indonesia saat ini, sejalan dengan semakin
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor
dan peningkatan ekonomi transportasi. Uji
kelayakan emisi yang sejak beberapa tahun
terakhir didengung-dengungkan oleh
pemerintah dan LSM ternyata juga tidak
berjalan dengan yang diharapkan. J umlah
kendaraan bermotor di jalan raya kian hari
semakin meningkat. Di wilayah DKI J akarta
pertambahan kendaraan tercatat 8.74% per
tahun sementara prasarana jalan meningkat
6.28% per tahun [3], menambah semakin
terpuruknya kondisi lingkungan udara kita.
Penulis berharap semoga dengan kenaikan
harga pokok bahan bakar minyak bagi
kendaraan yang ditetapkan pemerintah
dapat menjadi salah satu momentum bagi
kita semua untuk melangkah berpikir
tentang lingkungan udara yang sehat.
Kesadaran masyarakat akan pembatasan
penggunaan kendaraan pribadi dan
didukung dengan penyediaan angkutan
massal yang baik dan nyaman oleh
pemerintah akan menciptakan lingkungan
udara yang sehat bagi manusia Indonesia.
6. Daftar Pustaka
[1] Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan, 2002, Presentasi Data ISPU
J anuari 2002 hingga Desembar 2002.
[2] Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan, 2002, Sumber dan Standar
Kesehatan Emisi Gas Buang.
[3] Kementerian Lingkungan Hidup, 2002,
Status Lingkungan Hidup DKI J akarta.
[4] Nishida Osami, 2001, Actual State and
Prevention of Marine Air Pollution from
55
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk Dunia
Ships, Review of Kobe University of
Mercantile Marine No. 49, Kobe-J apan.
[5] Tempo Interaktif, 2005, Metromini
Penyebab Pencemaran Udara Terbesar di
J akarta, J anuari 2005.
(http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2
005/01/18/brk,20050118-10,id.html)
[6] Wright.A.A, 2000, Exhaust Emissions
from Combustion Machinery, IMARE-
London.
56
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
KESEHATAN
Kurang Gizi pada Ibu Hamil: Ancaman pada Janin
Wiku Andonotopo,M.D
Department of Obstetric and Gynecology,
Sveti Duh Hospital Zagreb Institute of Ultrasound
Medical School University of Zagreb.
Sveti Duh 64, Zagreb
HR 10000, CROATIA
Muhamad Thohar Arifin, M.D.
Department of Neurosurgery, Graduate School of Biomedical Science,
Hiroshima University Hospital,
Kasumi 1-2-3 Minami-Ku Hiroshima
734 8551, J APAN
Pendahuluan
Krisis energi yang berakibat menurunnya
daya beli masayarakat terutama kelompok
dibawah garis kemiskinan akan memicu
masalah yang lebih besar pada masa
depan bangsa. Ibu hamil serta janinya
rentan terhadap dampak krisis energi yang
sedang terjadi. Asupan nutrisi saat ibu
hamil akan sangat berpengaruh pada
outcome kehamilan tersebut.
Kehidupan manusia dimulai sejak masa
janin dalam rahim ibu. Sejak itu, manusia
kecil telah memasuki masa perjuangan
hidup yang salah satunya menghadapi
kemungkinan kurangnya zat gizi yang
diterima dari ibu yang mengandungnya.
J ika zat gizi yang diterima dari ibunya
tidak mencukupi maka janin tersebut akan
mempunyai konsekuensi kurang
menguntungkan dalam kehidupan
berikutnya. Sejarah klasik tentang
dampak kurang gizi selama kehamilan
terhadap outcome kehamilan telah
didokumentasikan oleh (Stein & Susser
1975). Masa paceklik di Belanda The
Dutch Fainine yang berlangsung pada
tahun 1944-1945, telah mmbawa
dampak yang cukup serius terhadap
outcome kehamilan. Fenomena the Dutch
Famine menunjukkan bahwa bayi-bayi
yang masa kandungannya (terutama
trimester 2 dan 3) jatuh pada saat-saat
paceklik mempunyai rata-rata berat badan,
panjang badan, lingkar kepala, dan berat
placenta yang lebih rendah dibandingkan
bayi-bayi yang masa kandungannya tidak
terpapar masa paceklik dan hal ini terjadi
karena adanya penurunan asupan kalori,
protein dan zat gizi essential lainnya.
(Stein & Susser 1975). Uraian di bawah
akan membahas dampak buruk
kekurangan asupan zat gizi pada
kehamilan dan bagaimana
pencegahannya.
Pembahasan
Kehamilan selalu berhubungan dengan
perubahan fisiologis yang berakibat
peningkatan volume cairan dan sel darah
merah serta penurunan konsentrasi
protein pengikat nutrisi dalam sirkulasi
darah, begitu juga dengan penurunan
nutrisi mikro. Pada kebanyakan negara
berkembang, perubahan ini dapat
diperburuk oleh kekurangan nutrisi dalam
kehamilan yang berdampak pada
defisiensi nutrisi mikro seperti anemia
yang dapat berakibat fatal pada ibu hamil
dan bayi baru lahir(Parra, B. E., L. M.
Manjarres, et al. 2005). Pada kekurangan
asupan mineral seng (zinc) dalam
kehamilan misalnya, dapat berakibat
gangguan signifikan pertumbuhan tulang.
Pemberian asam folat tidak saja berguna
untuk perkembangan otak sejak janin
berwujud embrio, tetapi menjadi kunci
penting pertumbuhan fungsi otak yang
sehat selama kehamilan (Christiansen, M.
and E. Garne 2005). Kasus-kasus
gangguan penutupan jaringan saraf tulang
belakang (spina bifida) dan kondisi dimana
otak janin tidak dapat terbentuk normal
(anencephaly) dapat dikurangi hingga
50% dan 85% jika ibu hamil mendapat
asupan cukup asam folat sebelum dia
hamil. Ibu hamil harus mendapatkan
asupan vitamin yang cukup sebelum
Dunia
57
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
terjadinya kehamilan karena pembentukan
otak janin dimulai pada minggu-mingu
pertama kehamilan, justru pada saat Sang
ibu belum menyadari dirinya telah
hamil(Obeid, R. and W. Herrmann
2005)( Wen, S. W. and M. Walker 2005).
Pada kasus-kasus dimana janin
mengalami defisiensi asam folat, sel-sel
jaringan utama (stem cells) akan
cenderung membelah lebih lambat
daripada pada janin yang dikandung ibu
hamil dengan asupan asam folat yang
cukup. Sehingga stem cells yang
dibutuhkan untuk membentuk jaringan
otak juga berkurang. Selain itu, sel-sel
yang mati juga akan bertambah, jauh lebih
besar daripada yang seharusnya (Santoso,
M. I. and M. S. Rohman (2005).
Meski dalam jumlah terminimum sekalipun,
keterbatasan nutrisi kehamilan (maternal)
pada saat terjadinya proses pembuahan
janin dapat berakibat pada kelahiran
prematur dan efek negativ jangka panjang
pada kesehatan janin. Sekitar 40 % wanita
yang melahirkan prematur disebabkan
oleh faktor yang tak diketahui (idiopatik).
Penelitian pada hewan uji kemudian
membuktikan adanya korelasi antara
kelahiran prematur dengan kekurangan
nutrisi sebelum kehamilan dimulai. Pada
kehamilan normal, janin sendiri yang akan
menentukan kapan dirinya akan memulai
proses kelahiran. Pada hewan uji, telah
diketahui kalau proses ini dimulai dari
aktivasi kelenjar adrenal untuk
memproduksi akumulasi mendadak
cortisol di dalam darah. Akibatnya,
terjadilah proses berantai yang berujung
pada proses kelahiran, dan hal yang sama
pula dianggap terjadi pada manusia.
(Challis, J. R., S. J. Lye, et al. 2001).
Problemnya adalah jika kehamilan terjadi
prematur. Pada kasus ini paru-paru dan
organ-organ penting hanya memilik
kemampuan minimum untuk berkembang
dalam rahim guna mempersiapkan
kehidupan di luar rahim nantinya. Para
peniliti mempercayai bahwa cortisol dari
kelenjar adrenal juga memacu
pematangan dari sistem organ tubuh janin
seperti paru-paru, dimana penting bagi
bayi agar dapat langsung bernafas
dengan mengembangkan paru-parunya
seketika lahir. J ika tidak terdapat cukup
cortisol untuk mematangkan paru-paru di
dalam rahim, bayi yang lahir akan
mengalami sindrom gawat nafas
(respiratory distress syndrome) dan
berlanjut pada keadaan asfiksia (lemas)
dan kemudian meninggal. Ini adalah
momok menakutkan dari kelahiran
prematur(Challis, J. R., S. J. Lye, et al.
2001).
Penelitian pada hewan uji juga
membutikan bahwa sekalipun keadaan
nutrisi yang buruk dalam kehamilan
diperbaiki dan kemungkinan dapat kembali
ke keadaan normal, janin-janin dalam
kasus di atas ternyata telah mengalami
proses percepatan pematangan kelenjar
adrenalnya yang memacu kelahiran
prematur dalam waktu rata-rata 1 minggu.
Wanita hamil harus berpikir untuk
mendapatkan diet dan asupan makanan
yang adekuat sebelum mereka tahu
dirinya hamil, karena nutrisi yang cukup
setelah kehamilan terjadi tidak dapat
mengkompensasikan ketidakcukupan
asupan nutrisi sebelum kehamilan. Meski
dalam jumlah sekecil apapun kekurangan
nutrisinya. Karena itu jika Anda
merencanakan untuk hamil, diri Anda
harus dalam kecukupan nutrisi sebelum
Anda memulai kehamilan, karena jika
tidak, bayi Anda kemungkinan besar akan
lahir prematur.
Dalam dunia medis istilah pertumbuhan
janin terhambat-PJ T (intrauterine growth
restriction) diartikan sebagai suatu kondisi
dimana janin berukuran lebih kecil dari
standar ukuran biometri normal pada usia
kehamilan. Kadang pula istilah PJ T sering
diartikan sebagai kecil untuk masa
kehamilan-KMK (small for gestational age).
Umumnya janin dengan PJ T memiliki
taksiran berat dibawah persentil ke-10.
Artinya janin memiliki berat kurang dari
90 % dari keseluruhan janin dalam usia
kehamilan yang sama. J anin dngan PJ T
pada umumnya akan lahir prematur (<37
minggu) atau dapat pula lahir cukup bulan
(at term, >37 minggu)(Gardosi, J. O. 2005).
Bayi-bayi yang dilahirkan dengan PJ T
biasanya tampak kurus, pucat, dan
berkulit keriput. Tali pusat umumnya
tampak rapuh dam layu dibanding pada
bayi normal yang tampak tebal dan kuat.
PJ T muncul sebagai akibat dari
berhentinya pertumbuhan jaringan atau
sel. Hal ini terjadi saat janin tidak
mendapatkan nutrisi dan oksigenasi yang
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
58
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
cukup untuk perkembangan dan
pertumbuhan organ dan jaringan, atau
karena infeksi. Meski pada sejumlah janin,
ukuran kecil untuk masa kehamilan bisa
diakibatkan karena faktor genetik (kedua
orangtua kecil), kebanyakan kasus PJ T
atau KMK dikarenakan karena faktor-
faktor lain. Beberapa diantaranya sbb:
Faktor ibu: Tekanan darah tinggi,
Penyakit ginjal, Kencing manis
stadium lanjut, Penyakit jantung dan
pernafasan, Malnutrisi, anemia, Infeksi,
Penyalahgunaan obat narkotika dan
alkohol dan, Perokok
Faktor sirkulasi uteroplasenta:
Penurunan aliran darah dari rahim dan
plasenta, Abrupsio plasenta (plasenta
lepas dari lokasi implantasi di rahim
sebelum waktunya), Plasenta previa
(plasenta berimplantasi di segmen
bawah rahim) dan, Infeksi di sekitar
jaringan janin
Faktor janin: J anin kembar, Infeksi,
Cacat janin dan, Kelainan kromosom
PJ T dapat terjadi kapanpun dalam
kehamilan. PJ T yang muncul sangat dini
sering berhubungan dengan kelainan
kromosom dan penyakit ibu. Sementara,
PJ T yang muncul terlambat (>32 minggu)
biasanya berhubungan dengan problem
lain. Pada kasus PJ T, pertumbuhan
seluruh tubuh dan organ janin menjadi
terbatas. Ketika aliran darah ke plasenta
tidak cukup, janin akan menerima hanya
sejumlah kecil oksigen, ini dapat berakibat
denyut jantung janin menjadi abnormal,
dan janin berisiko tinggi mengalami
kematian. Bayi-bayi yang dilahirkan
dengan PJ T akan mengalami keadaan
berikut :
Penurunan level oksigenasi
Nilai APGAR rendah (suatu penilaian
untuk menolong identifikasi adaptasi
bayi segera setelah lahir)
Aspirasi mekonium (tertelannya
faeces/tinja bayi pertama di dalam
kandungan) yang dapat berakibat
sindrom gawat nafas
Hipoglikemi (kadar gula rendah)
Kesulitan mempertahankan suhu
tubuh janin
Polisitemia (kebanyakan sel darah
merah)
Pada kasus-kasus PJ T yang sangat parah
dapat berakibat janin lahir mati (stillbirth)
atau jika bertahan hidup dapat memiliki
efek buruk jangka panjang dalam masa
kanak-kanak nantinya. Kasus-kasus PJ T
dapat muncul, sekalipun Sang ibu dalam
kondisi sehat, meskipun, faktor-faktor
kekurangan nutrisi dan perokok adalah
yang paling sering. Menghindari cara
hidup berisiko tinggi, makan makanan
bergizi, dan lakukan kontrol kehamilan
(prenatal care) secara teratur dapat
menekan risiko munculnya PJ T(Gardosi, J.
O. 2005). Perkiraan saat ini
mengindikasikan bahwa sekitar 65%
wanita pada negara sedang berkembang
paling sedikit memiliki kontrol 1 kali
selama kehamilan pada dokter, bidan,
atau perawat. Angkanya tinggi pada
negara Amerika Latin dan Karibia (83%)
sementara rendah pada negara Asia
Selatan (51%) (Piaggio, G., H. Ba'aqeel,
et al. 1998).
Penutup
Usaha untuk mencegah gizi buruk tidak
harus menunggu berhasilnya
pembangunan ekonomi sampai masalah
kemiskinan dituntaskan. Pembangunan
ekonomi rakyat dan menanggulangi
kemiskinan memakan waktu lama.
Pengalaman selama ini menunjukkan
bahwa diperlukan waktu lebih dari 20
tahun untuk mengurangi penduduk miskin
dari 40% (1976) menjadi 11% (1996).
Data empirik dari dunia menunjukkan
bahwa program perbaikan gizi dapat
dilakukan tanpa harus menunggu rakyat
menjadi makmur, tetapi perhatian pada
golongan yang beresiko kekurangan
asupan zat gizi akan membantu mengurai
peliknya masalah kemiskinan. Dan
diharapkan program perbaikan gizi
menjadi bagian yang eksplisit dari
program pembangunan untuk
memakmurkan rakyat. (edited by
T404AR)
Daftar Pustaka
Challis, J . R., S. J . Lye, et al. (2001).
"Understanding preterm labor." Ann N Y
Acad Sci 943: 225-34.
Christiansen, M. and E. Garne (2005).
"Prevention of neural tube defects with
periconceptional folic acid
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
59
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
supplementation in Europe." Ugeskr
Laeger 167(32): 2875-6.
Gardosi, J . O. (2005). "Prematurity and
fetal growth restriction." Early Hum Dev
81(1): 43-9.
Obeid, R. and W. Herrmann (2005).
"Homocysteine, folic acid and vitamin
B(12) in relation to pre- and postnatal
health aspects." Clin Chem Lab Med
43(10): 1052-7.
Parra, B. E., L. M. Manjarres, et al. (2005).
"Assessment of nutritional education and
iron supplement impact on prevention of
pregnancy anemia." Biomedica 25(2):
211-9.
Piaggio, G., H. Ba'aqeel, et al. (1998).
"The practice of antenatal care: comparing
four study sites in different parts of the
world participating in the WHO Antenatal
Care Randomised Controlled Trial."
Paediatr Perinat Epidemiol 12 Suppl 2:
116-41.
Santoso, M. I. and M. S. Rohman (2005).
"Decreased TGF-beta1 and IGF-1 protein
expression in rat embryo skull bone in folic
acid-restricted diet." J Nutr Biochem.
Stein, Z. and M. Susser (1975). "The
Dutch famine, 1944-1945, and the
reproductive process. I. Effects or six
indices at birth." Pediatr Res 9(2): 70-6.
Stein, Z. and M. Susser (1975). "The
Dutch famine, 1944-1945, and the
reproductive process. II. Interrelations of
caloric rations and six indices at birth."
Pediatr Res 9(2): 76-83.
Wen, S. W. and M. Walker (2005). "An
exploration of health effects of folic acid in
pregnancy beyond reducing neural tube
defects." J Obstet Gynaecol Can 27(1):
13-9.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
60
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Gizi Buruk, Ancaman Generasi yang Hilang
Yetty Nency, MD. DSA.
Dokter Spesialis Anak pada RS Dr. Karyadi Semarang. Sedang menempuh pendidikan
lanjutan di Dept. of Oncology Pediatrics Vrije University Medical Centrum Amsterdam
Netherlands
Muhamad Thohar Arifin, M.D.
Bagian Anatomi dan Bedah Saraf FK UNDIP, Semarang
Pendahuluan
Berita merebaknya temuan gizi buruk,
sangat mengejutkan di negara tercinta
yang terkenal subur makmur ini. Kasus ini
bisa jadi tidak hanya momok bagi para
balita namun juga bagi pemerintah.
Bahkan di era pemerintahan suharto,
pejabat daerah sangat ketakutan jika
sampai didapati kasus gizi buruk
diwilayahnya, cerminan buruknya
performa dalam menyejahterakan
raknyatnya; Bukti lemahnya infrastruktur
kesehatan dan pangan; Dan aneka
polemik mencari biang keladipun muncul
ke permukaan. Kesenjangan,
ketidakadilan, kemiskinan, kebijakan
ekonomi dan politik menjadi semakin
sering diperbincangkan. Bisa jadi hanya
sedikit yang memikirkan dampak jangka
panjang yang ditimbulkannya, jika hal ini
tidak ditangani dengan serius. Seperti
layaknya fenomena gunung es, bahwa
ancaman yang sebenarnya jauh lebih
besar dan perlu segera diambil langkah
langkah antisipasinya dari sekarang.
Karena kelainan ini menyerang anak-
anak , generasi penerus, yang sedang
dalam golden period pertumbuhan
otaknya.
Gizi buruk (severe malnutrition) adalah
suatu istilah teknis yang umumnya dipakai
oleh kalangan gizi, kesehatan dan
kedokteran. Gizi buruk adalah bentuk
terparah dari proses terjadinya
kekurangan gizi menahun. Menurut
Departemen Kesehatan (2004), pada
tahun 2003 terdapat sekitar 27,5% (5 juta
balita kurang gizi), 3,5 juta anak (19,2%)
dalam tingkat gizi kurang, dan 1,5 juta
anak gizi buruk (8,3%). WHO
(1999) mengelompokkan wilayah
berdasarkan prevalensi gizi kurang ke
dalam 4 kelompok yaitu: rendah (di bawah
10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%),
sangat tinggi (=>30%).
Status gizi anak balita secara
sederhana dapat diketahui dengan
membandingkan antara berat badan
menurut umur maupun menurut panjang
badannya dengan rujukan (standar) yang
telah ditetapkan. Apabila berat badan
menurut umur sesuai dengan standar,
anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di
bawah standar disebut gizi kurang.
Apabila jauh di bawah standar dikatakan
gizi buruk. Namun penghitungan berat
badan menurut panjang badan lebih
memberi arti klinis. Anak kurang gizi pada
tingkat ringan dan atau sedang masih
seperti anak-anak lain, beraktivitas ,
bermain dan sebagainya, tetapi bila
diamati dengan seksama badannya mulai
kurus dan staminanya mulai menurun.
Pada fase lanjut (gizi buruk) akan rentan
terhadap infeksi, terjadi pengurusan otot,
pembengkakan hati, dan berbagai
gangguan yang lain seperti misalnya
peradangan kulit, infeksi, kelainan organ
dan fungsinya (akibat atrophy / pengecilan
organ tersebut).
Diagnosis kurang gizi selain ditegakkan
melalui pemeriksaan antropometri
( penghitungan berat badan menurut
umur /panjang badan) dapat melalui
temuan klinis dijumpainya keadaan klinis
gizi buruk yang dapat dibagi menjadi
kondisi marasmus, kwasiorkor dan bentuk
campuran (marasmik kwasiorkor). Tanda
tanda marasmus adalah anak kurus,
kulitnya kering, didapatkan pengurusan
otot (atrophy) sedangkan kwasiorkor jika
didapatkan edema ( bengkak) terutama
pada punggung kaki yang tidak kembali
setelah dilakukan pemijitan (pitting edema),
marasmik kwasiorkor adalah bentuk klinis
campuran keduanya.
KESEHATAN
61
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Pengertian di masyarakat tentang Busung
Lapar adalah tidak tepat.
Sebutan Busung Lapar yang sebenarnya
adalah keadaan yang terjadi akibat
kekurangan pangan dalam kurun waktu
tertentu pada satu wilayah, sehingga
mengakibatkan kurangnya asupan zat gizi
yang diperlukan, yang pada akhirnya
berdampak pada kondisi status gizi
menjadi kurang atau buruk dan keadaan
ini terjadi pada semua golongan umur.
Tanda-tanda klinis pada Busung Lapar
pada umumnya sama dengan tanda-tanda
pada marasmus dan kwashiorkor.
Penyebab Gizi Buruk
Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor
yang saling terkait. Secara garis besar
penyebab anak kekurangan gizi
disebabkan karena asupan makanan yang
kurang atau anak sering sakit / terkena
infeksi.
Asupan yang kurang disebabkan
oleh banyak faktor antara lain:
1) Tidak tersedianya makanan secara
adekuat
Tidak tersedinya makanan yang adekuat
terkait langsung dengan kondisi sosial
ekonomi. Kadang kadang bencana alam,
perang, maupun kebijaksanaan politik
maupun ekonomi yang memberatkan
rakyat akan menyebabkan hal ini.
Kemiskinan sangat identik dengan tidak
tersedianya makan yang adekuat. Data
Indonesia dan negara lain menunjukkan
bahwa adanya hubungan timbal balik
antara kurang gizi dan kemiskinan.
Kemiskinan merupakan penyebab pokok
atau akar masalah gizi buruk. Proporsi
anak malnutrisi berbanding terbalik
dengan pendapatan. Makin kecil
pendapatan penduduk, makin tinggi
persentasi anak yang kekurangan gizi.
2) Anak tidak cukup mendapat makanan
bergizi seimbang
Makanan alamiah terbaik bagi bayi yaitu
Air Susu Ibu, dan sesudah usia 6 bulan
anak tidak mendapat Makanan
Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat,
baik jumlah dan kualitasnya akan
berkonsekuensi terhadap status gizi bayi.
MP-ASI yang baik tidak hanya cukup
mengandung energi dan protein, tetapi
juga mengandung zat besi, vitamin A,
asam folat, vitamin B serta vitamin dan
mineral lainnya. MP-ASI yang tepat dan
baik dapat disiapkan sendiri di rumah.
Pada keluarga dengan tingkat pendidikan
dan pengetahuan yang rendah seringkali
anaknya harus puas dengan makanan
seadanya yang tidak memenuhi
kebutuhan gizi balita karena ketidaktahuan.
3) Pola makan yang salah
Suatu studi positive deviance
mempelajari mengapa dari sekian banyak
bayi dan balita di suatu desa miskin hanya
sebagian kecil yang gizi buruk, padahal
orang tua mereka semuanya petani miskin.
Dari studi ini diketahui pola pengasuhan
anak berpengaruh pada timbulnya gizi
buruk. Anak yang diasuh ibunya sendiri
dengan kasih sayang, apalagi ibunya
berpendidikan, mengerti soal pentingnya
ASI, manfaat posyandu dan kebersihan,
meskipun sama-sama miskin, ternyata
anaknya lebih sehat. Unsur pendidikan
perempuan berpengaruh pada kualitas
pengasuhan anak. Sebaliknya sebagian
anak yang gizi buruk ternyata diasuh oleh
nenek atau pengasuh yang juga miskin
dan tidak berpendidikan. Banyaknya
perempuan yang meninggalkan desa
untuk mencari kerja di kota bahkan
menjadi TKI, kemungkinan juga dapat
menyebabkan anak menderita gizi buruk.
Kebiasaan, mitos ataupun kepercayaan /
adat istiadat masyarakat tertentu yang
tidak benar dalam pemberian makan akan
sangat merugikan anak . Misalnya
kebiasaan memberi minum bayi hanya
dengan air putih, memberikan makanan
padat terlalu dini, berpantang pada
makanan tertentu ( misalnya tidak
memberikan anak anak daging, telur,
santan dll) , hal ini menghilangkan
kesempatan anak untuk mendapat asupan
lemak, protein maupun kalori yang cukup
Sering sakit (frequent infection),
Menjadi penyebab terpenting kedua
kekurangan gizi, apalagi di negara negara
terbelakang dan yang sedang
berkembang seperti Indonesia, dimana
kesadaran akan kebersihan / personal
hygine yang masih kurang, serta ancaman
endemisitas penyakit tertentu, khususnya
infeksi kronik seperti misalnya tuberculosis
62
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
(TBC) masih sangat tinggi. Kaitan infeksi
dan kurang gizi seperti layaknya lingkaran
setan yang sukar diputuskan, karena
keduanya saling terkait dan saling
memperberat. Kondisi infeksi kronik akan
meyebabkan kurang gizi dan kondisi
malnutrisi sendiri akan memberikan
dampak buruk pada sistem pertahanan
sehingga memudahkan terjadinya infeksi.
Konsekuensi gizi buruk, loss
generation?
Gizi Buruk bukan hanya menjadi stigma
yang ditakuti, hal ini tentu saja terkait
dengan dampak terhadap sosial ekonomi
keluarga maupun negara, di samping
berbagai konsekuensi yang diterima anak
itu sendiri.
Kondisi gizi buruk akan mempengaruhi
banyak organ dan system, karena kondisi
gizi buruk ini juga sering disertai dengan
defisiensi ( kekurangan) asupan mikro/
makro nutien lain yang sangat diperlukan
bagi tubuh. Gizi buruk akan memporak
porandakan system pertahanan tubuh
terhadap microorganisme maupun
pertahanan mekanik sehingga mudah
sekali terkena infeksi.
Secara garis besar, dalam kondisi akut,
gizi buruk bisa mengancam jiwa karena
berberbagai disfungsi yang di alami,
ancaman yang timbul antara lain hipotermi
( mudah kedinginan) karena jaringan
lemaknya tipis, hipoglikemia (kadar gula
dalam darah yang dibawah kadar normal)
dan kekurangan elektrolit penting serta
cairan tubuh.
J ika fase akut tertangani dan namun tidak
di follow up dengan baik akibatnya anak
tidak dapat catch up dan mengejar
ketinggalannya maka dalam jangka
panjang kondisi ini berdampak buruk
terhadap pertumbuhan maupun
perkembangannya. Akibat gizi buruk
terhadap pertumbuhan sangat merugikan
performance anak, akibat kondisi stunting
(postur tubuh kecil pendek) yang
diakibatkannya. Yang lebih
memprihatinkan lagi, perkembangan anak
pun terganggu. Efek malnutrisi terhadap
perkembangan mental dan otak
tergantung dangan derajat beratnya,
lamanya dan waktu pertumbuhan otak itu
sendiri. J ika kondisi gizi buruk terjadi pada
masa golden period perkembangan otak
(0-3 tahun) , dapat dibayangkan jika otak
tidak dapat berkembang sebagaimana
anak yang sehat, dan kondisi ini akan
irreversible ( sulit untuk dapat pulih
kembali).
Dampak terhadap pertumbuhan otak ini
menjadi vital karena otak adalah salah
satu aset yang vital bagi anak untuk
dapat menjadi manusia yang berkualitas di
kemudian hari.
Beberapa penelitian menjelaskan, dampak
jangka pendek gizi buruk terhadap
perkembangan anak adalah anak menjadi
apatis, mengalami gangguan bicara dan
gangguan perkembangan yang lain.
Sedangkan dampak jangka panjang
adalah penurunan skor tes IQ, penurunan
perkembangn kognitif, penurunan integrasi
sensori, gangguan pemusatan perhatian,
gangguan penurunan rasa percaya diri
dan tentu saja merosotnya prestasi
akademik di sekolah. Kurang Gizi
berpotensi menjadi penyebab kemiskinan
melalui rendahnya kualitas sumber daya
manusia dan produktivitas. Tidak heran
jika gizi buruk yang tidak dikelola dengan
baik, pada fase akutnya akan mengancam
jiwa dan pada jangka panjang akan
menjadi ancaman hilangnya sebuah
generasi penerus bangsa
Pentingnya Deteksi Dan Intervensi Dini
Mengingat penyebabnya sangat kompleks,
pengelolaan gizi buruk memerlukan
kerjasama yang komprehensif dari semua
pihak. Bukan hanya dari dokter maupun
tenaga medis, namun juga pihak orang tua,
keluarga, pemuka masyarakat maupun
agama dan pemerintah. Langkah awal
pengelolaan gizi buruk adalah mengatasi
kegawatan yang ditimbulkannya,
dilanjutkan dengan frekuen feeding
( pemberian makan yang sering,
pemantauan akseptabilitas diet
( penerimaan tubuh terhadap diet yang
diberikan), pengelolaan infeksi dan
pemberian stimulasi. Perlunya pemberian
diet seimbang, cukup kalori dan protein
serta pentingnya edukasi pemberian
makan yang benar sesuai umur anak,
Pada daerah endemis gizi buruk perlu
distribusi makanan yang memadai.
63
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Posyandu dan puskesmas sebagai ujung
tombak dalam melakukan skrining /
deteksi dini dan pelayanan pertama
menjadi vital dalam pencegahan kasus
gizi buruk saat ini. Penggunaan kartu
menuju sehat dan pemberian makanan
tambahan di posyandu perlu digalakkan
lagi. Tindakan cepat pada balita yang 2x
berturut-turut tidak naik timbangan
berat badan untuk segera mendapat
akses pelayanan dan edukasi lebih lanjut,
dapat menjadi sarana deteksi dan
intervensi yang efektif. Termasuk juga
peningkatan cakupan imunisasi untuk
menghindari penyakit yang dapat dicegah,
serta propaganda kebersihan personal
maupun lingkungan. Pemuka masyarakat
maupun agama akan sangat efektif jika
mau membantu dalam pemberian edukasi
pada masyarakat, terutama dalam
menanggulangi kebiasaan atau mitos-
mitos yang salah pada pemberian makan
pada anak. Kasus gizi buruk mengajak
semua komponen bangsa untuk peduli,
berrsama kita selamatkan generasi
penerus ini untuk menjadi Indonesia yang
lebih baik. (edited by T404AR)
64
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
NASIONAL
Mahkamah Konstitusi unjuk gigi?
Seputar Isu Impeachment dalam surat Ketua Mahkamah Konstitusi
kepada Presiden RI
John Fresly
Program Master of Law, Niigata University,
J apanese Development Scholarship /J DS 2005
E-mail: jfresly@yahoo.com
Suhu politik di tanah air sempat memanas
ketika Ketua Mahkamah Konstitusi (MK),
J imly Asshiddiqie menyampaikan surat
kepada Presiden RI yang mengingatkan
agar pemerintah mematuhi putusan MK
terkait dikeluarkannya Peraturan Presiden
(Perpres) nomor 55 tahun 2005 tentang
harga jual bahan bakar minyak (BBM)
dalam negeri (Kompas, 10 Oktober 2005).
Surat tersebut pada intinya menyebutkan
bahwa pemerintah telah keliru
menjadikan UU nomor 22 tahun 2001
tentang Minyak dan gas bumi sebagai
dasar dalam mengeluarkan Perpres
tersebut diatas. Menurut Ketua MK, UU
nomor 22 tahun 2001 telah diujimaterilkan
(judicial review) dengan amar putusan
mengabulkan sebagian, yang menyatakan
bahwa bagian dari pasal 12 ayat 3, pasal
22 ayat 1, dan pasal 28 ayat 2 dan 3 yang
diantaranya mengatur tentang pelepasan
harga BBM mengikuti mekanisme pasar
bertentangan dengan UUD 1945 (Berita
Negara RI nomor 1 tahun 2005).
Dengan adanya putusan tersebut, MK
berpendapat bahwa penetapan harga jual
eceran BBM tidak lagi mengacu pada UU
nomor 22 tahun 2001 namun bisa saja
dijadikan rujukan sepanjang
memperhatikan perubahan sebagaimana
telah diputuskan oleh MK.
Pernyataan Ketua MK ini mendapat
tanggapan keras dari Menteri Sekretaris
Negara, Yusril Izra Mahendra, yang
mengatakan bahwa Ketua MK tidak
berhak menilai Presiden dalam
melaksanakan kebijakannya (Kompas, 11
Oktober 2005). Perdebatan ini menjadi
polemik menarik karena kedua pejabat
Negara tersebut yang sama-sama dikenal
sebagai pakar hukum tata negara
berselisih paham dalam menafsirkan
kewenangan MK.
Tindakan reaktif dari Mensesneg ini
dipandang sebagai bentuk kekhawatiran
pemerintah bahwa surat ini berimplikasi
politik dan akan berkembang kepada isu
pemberhentian kepala negara
(impeachment). Apalagi didapat informasi
bahwa surat MK tersebut keluar setelah
J imly Asshiddiqie mengadakan buka
puasa bersama dengan Ketua MPR
Hidayat Nur Wahid. Sebagian pihak
menafsirkan bahwa Ketua MPR berada di
belakang pengeluaran surat MK tersebut.
Namun demikian Ketua MK segera
mengeluarkan pernyataan bahwa tidak
ada muatan politis dari surat tersebut yang
akan mengarah kepada peluang
pemberhentian kepala negara
(impeachment). Menurutnya terbitnya
surat tersebut merupakan kewajiban dari
MK sesuai dengan kedudukannya sebagai
lembaga yudikatif.
Lalu timbul pertanyaan apakah benar
bahwa apa yang disampaikan Ketua MK
tersebut merupakan wujud dari
pelaksanaan tugas MK? Apakah MK tidak
berhak untuk menilai kebijakan
pemerintah? Lalu bagaimana kaitannya
dengan isu impeachment terhadap
Presiden? Untuk itu perlu ditelaah sejauh
mana kewenangan MK menurut peraturan
perundangan yang berlaku dan sejauh
mana putusan MK dapat dilaksanakan.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga
pemegang kekuasaan kehakiman yang
baru berdiri tanggal 17 Agustus 2003. Mk
mempunyai kedudukan yang sejajar
dengan Mahkamah Agung (MA)
sebagaimana diatur dalam UUD 1945
pasal 24 dan pasal 24 C.
Kewenangan MK diatur lebih lanjut dalam
Undang-undang nomor 24 tahun 2003,
Dunia
65
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
pasal 10 menyatakan bahwa MK
berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk :
1. Menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Memutuskan sengketa kewenangan
lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Memutus pembubaran partai politik;
dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
Kewenangan MK tersebut bersifat
limitatif hanya pada keempat hal yang
diatur dalam ketentuan tersebut diatas.
Dalam hal menyangkut kewenangan
menguji UU atau sering disebut dengan
judicial review, kewenangan ini bisa
diartikan sebagai payung hukum untuk
menguji tindakan eksekutif dan legislatif
sebagai pembuat UU. Hal ini sesuai
dengan prinsip dasar konstitusi bahwa
aturan hukum yang kedudukannya
dibawah Undang-undang Dasar
(konstitusi) tidak boleh bertentangan
dengan konstitusi. [3].
Yang menjadi masalah dalam kasus
judicial review terhadap UU nomor 22
tahun 2001 adalah bahwa hanya sebagian
dari pasal-pasal dalam Undang-undang
tersebut yang dibatalkan oleh MK. Lalu
apakah kemudian seluruh ketentuan
dalam UU tersebut menjadi gugur?
Hal ini menjadi problematik karena MK
dalam amar putusannya hanya
mengatakan bahwa permohonan judicial
review dikabulkan, tanpa ada penjelasan
lebih lanjut mengenai mekanisme
pencabutan pasal-pasal dimaksud dari UU
tersebut.
Ada pakar yang berpendapat bahwa bila
MK menyatakan suatu UU itu tidak sah,
maka segala perangkatnya langsung
gugur (Bagir Manan, kompas, 3 Agustus
2002). Sedangkan dilain pihak mekanisme
pengundangan suatu UU berada di tangan
pemerintah. Selanjutnya apakah DPR
harus mencabut atau membuat UU yang
baru untuk menggantikan UU nomor 22
tahun 2001 tersebut? Hal ini tentu saja
merupakan kelemahan yang mendasar
yang masih menjadi perdebatan dan
belum jelas jalan keluarnya.
Hal lain yang menarik untuk dikaji adalah
mekanisme pencatatan putusan MK yang
hanya pada Berita Negara bukan pada
Lembaran Negara. Hal ini merupakan
perdebatan teoritis yang sangat menarik
untuk diperdebatkan apabila hendak
dihubungkan dengan konsepsi separation
of power. Ide pencatatan putusan MK
pada Lembaran Negara akan mempunyai
implikasi yang luas sebagai sumber
hukum sekunder.
Integritas Hakim Konstitusi
Sebagaimana disebutkan diatas bahwa
MK berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir dan putusan MK
bersifat final. Artinya hanya ada satu tahap
pengadilan dengan putusan yang tidak
dapat digugat.
Dengan kekuasaan yang dominan ini
maka integritas hakim konstitusi menjadi
hal yang krusial. MK terdiri 9 orang hakim
konstitusi dengan komposisi ketua, wakil
ketua dan 7 orang anggota. Sebagaimana
diketahui, para hakim konstitusi yang
diangkat berdasarkan Keppres 147/M
tahun 2003 merupakan para pakar hukum
yang diyakini mempunyai pengetahuan
mendalam mengenai masalah konstitusi.
Paling tidak dari latar belakang pendidikan
dan pengalamannya, mereka diharapkan
mampu menyelesaikan sengketa yang
termasuk dalam jurisdiksi atau
kewenangan MK.
Menarik untuk dikaji bahwa pemilihan
hakim konstitusi mencerminkan komposisi
tiga pilar yaitu tiga hakim konstitusi pilihan
pemerintah, tiga orang usulan DPR dan
tiga orang usulan dari MA.. Sehingga tidak
dapat dipungkiri ada anggapan yang
mengatakan bahwa nuansa politis terjadi
dalam memilih para hakim konstitusi.
Menjadi ujian bagi para hakim konstitusi
untuk membuktikan bahwa lembaga MK
adalah lembaga negara yang melakukan
kekuasaan kehakiman yang merdeka
menjalankan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Hal ini sejalan
dengan visi MK untuk tegaknya konstitusi
dalam rangka mewujudkan cita-cita
negara hukum dan demokrasi.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
66
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Sebagai lembaga baru yang secara logika
tidak pernah terkontaminasi oleh penyakit
kronis lembaga negara dan lembaga
pemerintah lainnya, MK mempunyai modal
politik yang kuat untuk dapat menjadi
penjuru bagi penegakan hukum (legal
enforcement) dan ketaatan terhadap
hukum (rule of law).
Masalah integritas menjadi hal yang
prinsip bagi seorang hakim konstitusi.
Hakim konstitusi seyogyanya tidak
berafiliasi kepada aliran politik tertentu,
bersikap netral dan mempunyai sikap
yang konsisten dalam memberikan
pendapat hukum. Pendapat para hakim
konstitusi baik yang mendukung maupun
berbeda pendapat (dissenting opinion)
dalam suatu sengketa yang diajukan ke
MK akan menjadi acuan bagi publik untuk
menilai integritas dan kredibilitas hakim
konstitusi maupun MK itu sendiri.
Peluang Impeachment
Pasal 7B UUD 1945 hasil amandemen
menyebutkan bahwa proses
pemberhentian Presiden (impeachment)
terlebih dahulu harus melalui mekanisme
permintaan kepada MK untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dalam hal DPR
menganggap bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden telah melakukan
pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sedangkan dalam Undang-
undang nomor 24 tahun 2003 disebutkan
bahwa MK wajib memberikan putusan
atas permintaan impeachment tersebut
(pasal 10 ayat 2).
Perumusan norma hukum seperti tersebut
diatas menunjukkan bahwa pada
pinsipnya MK mempunyai peran strategis
dalam mekanisme impeachment terhadap
Presiden/Wakil Presiden. Namun tidaklah
memungkinkan MK secara langsung
melakukan penilaian terhadap kinerja
Presiden tanpa adanya permintaan dari
DPR. Dengan kata lain tidak terjadi
hubungan langsung antara MK dan kepala
pemerintahan dalam hal ini Presiden/Wakil
Presiden.
Mekanisme ini merupakan aplikasi dari
sistem check and balance yang dirancang
oleh pembuat undang-undang untuk
menghindari terjadinya proses
impeachment yang tendensius
sebagaimana terjadi pada era Presiden
Abdurrahman Wahid.
Dengan demikian terkait dengan suratnya,
alasan apa yang membuat Ketua MK
merasa perlu untuk menegur Presiden?
Tampaknya hal ini dilandasi oleh
keinginan untuk melakukan penyesuaian
terhadap posisi asimetral dari lembaga
yudikatif dibandingkan lembaga eksekutif
maupun legislatif.
Seperti diketahui pengaruh sistem
pemerintahan Soeharto yang mengebiri
lembaga legislatif dan lembaga yudikatif
telah dikoreksi oleh amandemen UUD
1945 yaitu salah satunya melalui
pembentukan MK sebagai lembaga
puncak kekuasaan peradilan bersama-
sama dengan MA.
Citra buruk lembaga yudikatif seperti
adanya mafia peradilan yang di
lingkungan MA perlu diperbaiki. Hal ini
tercermin dari prosedur beracara pada
pengadilan MK yang dilakukan secara
terbuka. Bahkan informasi tentang
prosedur dan putusan perkara di MK
dilakukan dengan memanfaatkan sarana
website.
Dengan demikian MK diharapkan
menghasilkan keputusan yang memenuhi
rasa keadilan masyarakat. Momentum
tersebut seputar kenaikan harga BBM
dijadikan MK untuk menyeimbangkan
posisi lembaga yudikatif terhadap lembaga
eksekutif.
Pada saat lembaga eksekutif tidak dapat
mengeluarkan kebijakan publik yang
memenuhi rasa keadilan masyarakat
maka lembaga yudikatif akan menjadi
jalan keluar yang memenuhi harapan
rakyat.
Meskipun tidak memungkinkan untuk
melakukan penilaian langsung terhadap
Presiden, MK masih berpeluang untuk
peran aktif dalam menegakkan konstitusi
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
67
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
dengan melakukan apa yang dikenal
dengan istilah judicial activism. J udicial
activism adalah suatu istilah yang
digunakan untuk menjelaskan tindakan
hakim yang aktif mencari kebenaran
dengan memberikan penafsiran dalam uji
materil UU yang merefleksikan kondisi
sosial yang berkembang di masyarakat.
Aliran ini berkembang di negara-negara
yang menganut sistem hukum Anglo-
Saxon atau Common law. Meskipun
demikian negara yang menganut sistem
hukum Eropa Kontinental juga banyak
hakimnya yang melakukan judicial
activisim.
Adapun alasan hakim untuk melakukan
judicial activism adalah karena dilandasi
oleh keyakinan bahwa suatu kasus atau
fenomena hukum harus mencermin rasa
keadilan yang berkembang di masyarakat.
Persoalannya adalah pendekatan analisis
hukum hanya berdasarkan doktrin dan
logika hukum serta kemampuan
argumentasi hipotetis yang filosofis, tidak
menggunakan tool model matematika
ataupun analisis statistik yang secara
deskriptif dan ilmiah menjelaskan suatu
fenomena baru dalam hukum [2].
Selain itu ada kekhawatiran bahwa judicial
activism ini melampaui batas dan
membawa para hakim memasuki wilayah
politik. Sulit untuk menilai apakah seorang
hakim melakukan tindakan judicial
activism karena rasa keadilan melihat
keadaan masyarakat atau sebaliknya
hakim tersebut melakukan judicial activism
karena didorong oleh motif politik tertentu.
Perdebatan ini pula yang meramaikan
pemilihan Hakim Agung di Amerika Serikat
bulan September 2005 yang lalu. Justice
J ohn Robert yang akhirnya terpilh sebagai
Ketua Mahkamah Agung AS (US Chief
Supreme Court) mengkritik penerapan
judicial activism oleh hakim agung di
Mahkamah Agung AS.
Menurut J ohn Robert tugas hakim adalah
menafsirkan Konstitusi tanpa harus
memasuki wilayah politik yang merupakan
wilayah kekuasaan eksekutif maupun
legislatif. Namun hal ini mendapatkan
tentangan dari berbagai pihak mengingat
tipisnya batas antara kepentingan publik
dan politik itu sendiri.
Kesimpulan
Tindakan proaktif yang dilakukan oleh
Ketua MK melalui surat kepada Presiden
RI merupakan preseden positif bagi
mekanisme check and balance dalam
sistem pemerintahan negara RI. Polemik
yang berkembang seputar kewenangan
MK dalam kaitannya dengan kemungkinan
impeachment tak dapat dipungkiri akan
terjadi mengingat dinamika politik yang
begitu intens.
Posisi pemerintah yang relatif tidak
sejalan dengan asipirasi masyarakat pada
umumnya berkaitan dengan kenaikan
harga BBM melalui surat Ketua MK
tersebut seolah didapatkan celah untuk
menggoyang pemerintah dibawah
Presiden SB Yudhoyono.
Namun demikian peluang impeachment
tidak dimungkinkan karena posisi MK
dalam polemik tersebut adalah dalam
rangka membangun suatu kesadaran
berkonstitusi. Pemerintah sepatutnya
memperhatikan putusan MK yang
menurut ketentuan perundangan adalah
putusan yang final dan mengikat.
Hal ini sesuai dengan semangat
konstitusionalisme, yang berintikan
sebagai ide terbatasnya pemerintahan
oleh hukum (governmental power should
be limited by law) pada akhirnya
senantiasa berujung akan perlunya
kekuasaan kehakiman yang mampu
mengontrol lembaga negara secara yuridis
[1].
Sebagai bagian dari kekuasaan
kehakiman, MK terikat dalam prinsip
konstitusionalisme tersebut. Hal ini
merupakan angin segar bagi dunia
peradilan Indonesia. Di kala krisis
kepercayaan terhadap integritas para
hakim di lingkungan MA semakin besar,
maka sepak terjang para hakim konstitusi
patut diberi acungan jempol.
Daftar Pustaka
[1] Alder, J ohn, 1989, Constitutional and
administrative law.
[2] Posner, Richard A, 1993, The problem
of jurisprudence, Harvard University
Press, Cambridge.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
68
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
[3] Vandevelde, Kenneth J , 1996,
Thinking like a lawyer, An introduction
to legal reasoning, Westview Press,
Colorado..
[5] Tap MPR RI nomor III Tahun 2000
tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Perundangan
[4] Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945
[6] Undang-undang nomor 24 tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
69
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
NASIONAL
Peranan Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Azhar
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
J SPS Fellow, Graduate School of Law, Hokkaido University., Sapporo, J apan
Email:aazhar_2000@yahoo.com
1. Pendahuluan
Reformasi nasional tahun 1998 telah
membuka peluang perubahan mendasar
atas Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
(kemudian akan kita sebut UUD RI 1945)
yang disakralkan oleh Pemerintah Orde
Baru untuk tidak direvisi. Setelah
reformasi, konstitusi Indonesia telah
mengalami perubahan dalam satu
rangkaian empat tahap, yaitu pada tahun
1999, 2000, 2001, dan 2002 (UUD RI
1945). Salah satu perubahan dari UUD RI
1945 adalah dengan telah diadopsi
prinsip-prinsip baru dalam sistem
ketatanegaraan antara lain prinsip
pemisahan kekuasaan dan checks and
balances sebagai pengganti sistem
supremasi parlemen. Dalam Pasal 24C
hasil perubahan ketiga UUD RI 1945,
dimasukkannya ide pembentukan
Mahkamah Konstitusi kedalam konstitusi
negara kita sebagai organ konstitusional
baru yang sederajat kedudukannya
dengan organ konstitusi lainnya. Fungsi
Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 24
tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
(UU No. 24, 2003), sejak tanggal 13
Agustus 2003. Hal ini disahkan dengan
adanya ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD
RI 1945 yang menentukan:
Pengangkatan dan pemberhentian Hakim
Konstitusi, hukum acara serta ketentuan
lainnya tentang Mahkamah Konstitusi
diatur dengan undang-undang. Oleh
karena itu, sebelum Mahkamah Konstitusi
dibentuk sebagai mestinya, Undang-
undang tentang Mahkamah Konstitusi
terlebih dahulu ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 13 Agustus
2003 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4316.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi telah
dilakukan dengan proses rekruitmen calon
hakim menurut tata cara yang diatur
dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 yang berbunyi
Hakim Konstitusi diajukan masing-masing
3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3
(tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang
oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
Mahkamah Konstitusi secara resmi
dibentuk dengan adanya Undang-undang
Nomor 24 tahun 2003 dan setelah
pelantikan dan pengucapan sumpah
tanggal 16 Agustus 2003, maka
kewenangan transisi Mahkamah Agung
yang dibebani tugas oleh pasal III Aturan
Peralihan UUD RI 1945, untuk
melaksanakan segala kewenangan
Mahkamah Konstitusi telah berakhir.
Untuk itu pada bagian berikut ini akan kita
bahas kewenangan mahkamah konstitusi
sebagai alat untuk melaksanakan
peranannya sebagai penjaga konstitusi
seperti yang diatur dalam UUD RI 1945.
2. Peranan Mahkamah Konstitusi
Dalam menjalankan peranannya sebagai
penjaga konstitusi, yaitu melakukan
kekuasaan kehakiman seperti diatur
dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI
1945. Sedangkan yang dimaksud dengan
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan mahkamah konstitusi diberi
beberapa kewenangan (Pasal 24 ayat (1)
UUD RI 1945). Adanya sebuah
kekuasaan kehakiman yang bebas adalah
salah satu prasyarat bagi negara hukum
disamping syarat-syarat yang lainnya.
Dunia
70
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Untuk memahami peran yang dilakukan
oleh Mahkamah Konstitusi, haruslah dikaji
dengan komprehensif kewenangan-
kewenangan yang diberikan oleh UUD RI
1945 kepada lembaga ini. Pasal 24 C ayat
(1) menyebutkan bahwa Mahkamah
Konstitusi berwenang untuk mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir dimana
putusannya bersifat final. Dari ketentuan
tersebut berarti Mahkamah Konstitusi
bersifat tunggal yang tidak mempunyai
peradilan yang berada dibawahnya dan
tidak merupakan bawahan dari lembaga
lain. Hal ini berbeda dengan Mahkamah
Agung yang mempunyai peradilan
peradilan dibawahnya dan merupakan
puncak dari peradilan-peradilan yang
berada dibawahnya. Dengan
ketunggalannya dapat dikatakan bahwa
Mahkamah Konstitusi adalam sebuah
forum khusus untuk melakukan
kewenangannya. Didalam menjalankan
perannya sebagai penjaga konstitusi,
maka Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia diberi kewenangan seperti yang
diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD RI
1945 yang kemudian dipertegas dalam
Undantg-undang No. 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi yang
menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili:
a. Menguji undang-undang terhadap
UUD RI 1945;
b. Memutus sengketa kewenangan antar
lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
RI 1945;
c. Memutus pembubaran partai politik;
d. Memutus perselisihan tentang hasil
pemilu;
e. Memberi putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat bahwa
Presiden dan/atau Wwakil Presiden
diduga telah melakukan pelanggaran
hukum berupa penghianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Ppresiden, sebagaimana
dimaksud dalam UUD RI 1945.
Pelanggaran hukum yang diduga
dilakukan presiden yang disebut dalam
pasal 10 ayat (2) UU No. 24, 2003, telah
diperjelas dalam ayat (3) dengan memberi
batasan sebagai berikut:
a. Penghianatan terhadap negara adala
tindak pidana terhadap keamanan
negara sebagaimana diatur dalam
undang-undang;
b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak
pidana korupsi atau penyuapan
sebagaimana diatur dalam undang-
undang;
c. Tindak pidana berat lainnya adalah
tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;
d. Perbuatan tercela adalah perbuatan-
perbuatan yang dapat merendahakan
martabat Presiden dan/atau Wakil
Presiden;
e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai
presiden dan/atau wakil presiden
adalah syarat sebagaimana dtentukan
dalam pasala 6 UUD RI 1945.
Dari kewenangan yang disebutkan diatas
terlihat bahwa sengketa yang
diperkarakan dan diadili Mahkamah
Konstitusi sangat banyak berkaitan
dengan proses politik, sebagian besar
merupakan perselisihan yang syarat
dengan sifat politik sebagai salah satu
karakteristik sengketa. J adi yang
dikemukakan oleh Agung Laksono, Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa
Mahkamah Konstitusi untuk tetap
memegang komitmen dalam menjalankan
tugasnya di wilayah hukum dan tidak
memasuki wilayah politik adalah kurang
begitu tepat (Kompas 11 Oktober, 2005).
Sudah barang tentu hal ini juga akan
mempunyai dampak pada pihak-pihak
yang dapat menggerakkan mekanisme
Konstitusional kontrol oleh berbagai
lembaga negara.
Diberbagai negara didunia sebanyak lebih
kurang 78 negara yang dalam
konstitusinya juga mengenal lembaga
Mahkamah Konstitusi, semenjak Hans
Kelsen merancang undang-undang dasar
Austria dan memasukkan lembaga ini
dalam konstitusi Austria. Sebagian besara
negara-negara demokrasi yang sudah
mapan kecuali J erman, tidak mengenal
lembaga Mahkamah Konstitusi yang
berdiri sendiri. Fungsinya dicakup dalam
fungsi Mahkamah Agung yang ada
disetiap negara (J imly Asshiddiqie. 2003) .
Kewenangan yang diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan
menjadi dua. Yaitu kewenangan utama,
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
71
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
dan kewenangan tambahan. Kewenangan
utama meliputi: (a) pengujian undang-
undang terhadap UUD, (b) memutus
keluhan konstitusi yang diajukan oleh
rakyat terhadap penguasa (UUD RI 1945
tidak memberikan kewenangan ini kepada
Mahkamah Konstitusi), sebaiknya
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan
utamanya yaitu untuk memutus memutus
constituional complain yang diajukan
rakyat terhadap penguasa seperti
Mahkamah konstitusi Austria, Itali, J erman
dan lainnya. Dengan diberikannya
kewenangan tersebut, Mahkamah
Konstitusi wajib menerima dan memutus
permohonan dari rakyat bilamana adanya
produk peraturan yang berada dibawah
undang-undang seperti Keputusan
Presiden, Penetapan Presiden, Instruksi
Presiden dan/atau Peraturan Presiden
untuk diajukan judicial review. Seperti kita
ketahui bahwa Peraturan Presiden no
55/2005 tentang harga BBM yang
mengacu pada Undang-undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi dimana Pasal 28 ayat (2) dan (3),
telak di dikoreksi dalam judicial review
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21
Desember 2004 karena dinilai
bertentangan dengan UUD RI 1945.
Tanpa diberi kewenangan tersebut diatas
maka Mahkamah Konstitusi belum bisa
melakukan perannya sebagai penjaga
konstitusi secara tuntas dan menyeluruh.
(c) memutus sengketa kewenangan antar
lembaga negara. Sedangkan
kewenangan tambahan dapat bervariasi
antara negara satu dengan yang lainnya.
UUD RI 1945 memberikan kewenangan
tambahan tersebut berupa; (a)
pembubaran partai politi, (b) perselisihan
hasil pemilihan umum, (d) pemberian
putusan Dewan Perwakilan Rakyat atas
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh
Presiden dan/atau wakil presiden.
Peranan yang diberikan kepada
Mahkamah Konstitusi melalui
kewenangannya sebagai sebuah lembaga
peradilan oleh UUD RI 1945,
mencerminkan semangkin kuatnya
penuangan prinsip negara hukum dalam
UUD RI 1945 setelah adanya perubahan.
Pilar yang sangat fundamental yang
diletakkan dalam UUD RI 1945 untuk
memperkuat prinsip negara hukum adalah
perumusan pada Pasal 1 ayat (2), yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada
ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar. Dengan adanya
perumusan ini, maka Indonesia yang
menganut asas demokrasi dalam
penyelenggaraan kenegaraan
menyandarkan mekanisme demokrasinya
kepada hukum, yaitu UUD RI 1945. Hak-
hak yang diakui dalam UUD RI 1945 , dan
tata cara pelaksanaan demokrasi
didalamnya menjadi rambu-rambu bagi
pelaksanaan demokrasi. Karena
demokrasi tanpa hukum akan mengarah
menjadi anarki. Pelanggaran terhadap
konstitusi dapat dilakukan dalam beberapa
bentuk. Meskipun DPR yang anggotanya
dipilih dalam pemilihan umum dan
Presiden dipilih secara langsung oleh
rakyat, yang berarti keduanya mempunyai
dasar legitimasi perwakilan aspiratif,
namun, dalam prinsip negara hukum
kedua lembaga ini tetap dapat melakukan
pelanggaran terhadap konstitusi (Harjono.
2003). Dengan ditetapkannya mekanisme
pembuatan undang-undang dalam UUD
RI 1945, yang melibatkan kedua lembaga
ini, DPR dan Presiden, maka produk
bersama dari kedua lembaga ini, yaitu
undang-undang secara potensial pun
dapat menyimpang dari UUD RI 1945.
Sebuah undang-undang dapat menjadi
objek legislative review, yang dilakukan
oleh badan legislative yang membuatnya.
Namun, haruslah diingat bahwa legislative
review masih tetap didasarkan atas
pertimbangan-pertimbangan politik karena
memang produk dari lembaga politik.
Kehadiran Mahkamah Konstitusi untuk
melakukan uji undang-undang adalah
untuk menjaga/ menegakkan konstitusi
bilamana terjadi pelanggaran konstitusi
oleh undang-undang. Dengan mekanisme
ini jelas bahwa peranan Mahkamah
Konstitusi dalam ketatanegaraan
Indonesia adalah untuk menjaga jangan
sampai terjadi pelanggaran konstitusi oleh
lembaga negara.
Mahkamah Konstitusi yang melaksanakan
fungsi peradilannya untuk melakukan uji
undang-undang harus membatasi dirinya
jangan samapai menjadi super body
dalam pembuatan undang-undang yang
terjebak untuk menjadi lembaga yang
mempunyai hak veto secara terselubung.
Dalam hal pembuatan undang-undang
harus dipahami secara kesistiman bahwa
terdapat tiga kategori substansi dalam
konstitusi; (a) pembuat undang-undang
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
72
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
diberi kewenangan penuh untuk mengatur
dan menetapkan, (b) dalam mengatur dan
menetapkan pembuat undang-undang
dengan kualifikasi atau pembatasan, (c)
pembuat undang-undang tidak diberi
kewenangan untuk mengatur dan
menetapkan karena telah ditetapkan dan
diatur sendiri oleh konstitusi.
UUD RI 1945 telah mendistribusikan
kewenangannya kepada
beberapalembaga negara. Dalam
melaksanakan kewenangan tersebut
sangat mungkin akan terjadi dimana satu
lembaga negara menggunakan
kewenangannya melampaui batas
kewenangan yang diberikan kepadanya
sehingga melanggar kewenangan
lembaga lain. Dengan adanya perubahan
UUD RI 1945, hubungan antar lembaga
negara diposisikan secara fungsional, dan
tidak secara hirarkis, maka diperlukan
sebuah lembaga yang secara final dapat
memutus perselisihan kewenangan antar
lembaga negara. Mahkamah Konstitusi
berperan sebagai lembaga peradilan yang
memutus sengketa antar kewenangan
lembaga negara. Sebelumnya peran ini
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan
Rakyat dimana sebagai sebuah lembaga
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat
yang omnipotent, yang berwenang untuk
melakukan apa saja termasuk didalamnya
untuk menmyelesaikan persengketaan
yang timbul antar lembaga negara. Dapat
diartikan bahwa peran Mahkamah
Konstitusi sebagai penjaga konstitusi
dalam sistem check and balances antar
lembaga negara. Selanjutnya kita akan
melihat bagaimana tata cara pengajuan
permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
3. Tata Cara Pengajuan Permohonan
Untuk melaksanakan peranannya
menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi
dilengkapi dengan mekanisme
constitutional control, digerakkan oleh
adanya permohonan dari pemohon yang
memiliki legal standing untuk membela
kepentingannya. Pemilihan kata pemohon
dan bukan gugatan yang diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi bilamana
dibandingkan dengan Hukum Acara
Perdata, seolah-olah perkara itu
merupakan perkara yang bersifat satu
pihak (ex parte) dan tidak ada pihak lain
yang ditarik sebagai pihak atau termohon
dan yang mempunyai hak melawan
permohonan tersebut. Hal ini tidak selalu
benar, karena dalam jenis perkara tertentu
harus ada pihak yang secara tegas
ditetapkan dan ditarik sebagai pihak, dan
yang mempunyai hak untuk menjawab
atau menanggapi permohonan tersebut
(Maruarar, Siahaan. 2003).
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.
2 tahun 2002 tentang tata cara
penyelenggaraan wewenang Mahkamah
Konstitusi oleh Mahkamah Agung dalam
Pasal 1 ayat (7) dan (8) membedakan
permohonan dan gugatan. Terhadpa
perkara:
1. Pengujian undang-undang terhadap
Undang- Undang Dasar;
2. Sengketa wewenang antar lembaga
negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang dasar
RI 1945;
3. Memeriksa, mengadili dan
memutuskan pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa presiden
dan/atau wakil presiden diduga telah
melakukan pelanggaran hukum
sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 7B ayat (1) UUD RI 1945 dan
perubahannya.
Diajukan dalam permohonan yang
merupakan permintaan untuk diputus. Di
pihak lain jika perkara yang diajukan
adalah mengenai:
1. Pembubarana partai politik;
2. Perselisihan hasil pemilihan umum.
Maka harus dengan gugatan yang
merupakan tuntutan yang diajukan secara
tertulis.
Undang-undang No. 24 tahun 2003
menyebutkan bahwa semuanya diajukan
dengan permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, ditanda tangani oleh
pemohon/ kuasa, diajukan dalam 12
rangkap dan syarat-syarat yang harus
dipenuhi disebut dalam Pasal 31 adalah
sebagai berikut:
a. Nama dan alamat pemohon;
b. Uraian mengenai perihal yang menjadi
dasar permohonan;
c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
Permohonan itu harus pula melampirkan
bukti-bukti sebagai pendukung
permohonan, yang menunjukkan
permohon bersungguh-sungguh. Dengan
kata lain, pemohon harus memuat
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
73
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
identitas piha-pihak posita dan petitum.
Tapi Undang-undang No. 24 tahun 2003
tidak mengharuskan disebut termohon.
Karena sifatnya yang lebih banyak
melibatkan lembaga-lembaga negara dan
khusus tentang pengujian undang-undang
terhadap UUD RI 1945, yang berada
dalam posisi sebagai termohon tidak
terlalu menentukan karena putusan yang
diminta adalah bersifat deklaratif terhadap
aturan yang berlaku umum juga dilain
pihak oleh karena adanya kewajiban
Mahkamah Konstitusi memanggil para
pihak yang berperkara untuk memberi
keterangan yang dibutuhkan dan/atau
meminta keterangan secara tertulis
kepada lembaga negara yang terkait
dengan termohon, maka yang
menentukan termohon itu adalah
Mahkamah Konstitusi. Meski tidak secara
tegas disebut perlu dimuat siapa yang
menjadi termohon, sebagai pihak yang
paling berwenang dan berkepentingan
menjawab gugatan tersebut, secara
praktis dengan penunjukan termohon.
Termohon dapat dipanggil untuk
memberikan keterangan. Bisa juga
dianalogikan keterangan tersebut dengan
jawaban dalam Hukum Acara Perdata.
Hal ini untuk memenuhi tenggang waktu
yang disebut Pasal 4i ayat (3) yang
menentukan paling lambat tujuh hari kerja
sejak permintaan Hakim Konstitusi
diterima, lembaga negara yang
bersangkutan wajib menyampaikan
penjelasan. Permohonan dapat disatukan
dengan panggilan sebagaimana
disebutkan dalam Acara Perdata.
Memang secara spesifik dalam perkara
pengujian undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar tidak disebut siapa
yang menjadi termohon, tapi dalam
sengketa kewenangan antar lembaga
negara, pembubaran partai politik,
impeachment, termohon harus ditulis
secara tegas. Khusus mengernai
sengketa kewenangan antar lembaga
negara, Mahkamah Konstitusi dapat
mengeluarkan penetapan yang
memerintahakan pihak pemohon dan/atau
termohon untuk menghentikan sementara
pelaksanaan kewenangan yang
dipersengketakan sampai dengan putusan
Mahkamah Konstitusi. Tanpa adanya
penyebutan termohon secara tegas dalam
penetapan yang sifatnya menghentikan
kewenangan sementara, maka putusan itu
boleh jadi tidak mempunyai arti apa-apa,
karena tidak jelas siapa yang wajib
melaksanakan perintah tersebut. Hal
yang lebih tegas lagi adalah ketika
permohonan untuk membatalkan hasil
pemilu dan pembubaran partai politik
dikabulkan, maka harus jelas siapa yang
wajib melaksanakan keputusan hakim
Mahkamah Konstitusi tersebut.
Mahkamah konstitusi memeriksa,
mengadili dan memutus dalam sidang
plenonya dengan sembilan (9) Hakim
Konstitusi, akan tetapi dalam keadaan luar
biasa dengan tujuh (7) Hakim. Itulah
sebabnya surat permohonan diajukan dua
belas (12) rangkap, karena disamping
dibagikan pada sembilan (9) Hakim, juga
harus disampaikan kepda presiden dan
DPR dalam waktu tujuh (7) hari sejak
permohonan dicatat dalam register
perkara konstitusi. Mahkamah Agung,
menurut Pasal 53 cukup diberi tahu
tentang permohona judicial review.
Namun, tidak diatur secara tegas bahwa
permohonan disampaikan ke Mahkamah
Agung, yang mempunyai arti bahwa tidak
perlu diberkanan copy surat permohonan.
Salah satu perbedaan dengan gugatan
dalam perkara perdata adalah
permohonan yang diajukan kepada
Mahkamah Konstitusi untuk dapat didaftar
harus telah menyertakan alat bukti yang
mendukung permohonan tersebut (Pasal
32 ayat (2) dan (3) UU No. 24 tahun 2003).
Karena masih ada proses untuk
memeriksa perkara dan alat-alat bukti,
maka hal ini harus ditafsirkan sebagai
bukti awal yang menunjukkan
kesungguhan permohonan tersebut dan
bukan hanya bertujuan untuk
menimbulkan sensasi atau uji coba.
Selanjutnya kita akan membahas siapa
yang dapat mengajukan permohonan
pada bagian berikut.
3. Siapa yang Dapat Mengajukan
Permohonan
Yang berhak mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi adalah setiap orang
yang memiliki kepentingan hukum atau
kewenangan yang dilanggar dan dirugikan
dengan kata lain bahwa yang
bersangkutan harus mempunya legal
standing untuk mengajukan permohonan.
Pemohon untuk setiap jenis perkara
konstitusi berbeda.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
74
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
A. Pengujian Undang-undang terhadap
UUD RI 1945
Permohonan untuk pengujian undang-
undang terhadap UUD RI 1945 dapat
dilakukan bagi yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya
sedang dan akan dirugikan dengan
berlakunya suatu undang-undang terdiri
dari:
1. Individu atau perorangan warga negara
Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-
undang;
3. Badan hukum publik atau privat; atau
4. Lembaga negara.
Keempat kategori yang disebut diatas, jika
hak dan kewenangan konstitusionalnya
dilanggar oleh berlakunya satu undang-
undang mempunyai legal standing, untuk
mengajukan permohonan.
B. Sengketa Kewenangan antar Lembaga
Negara
Pihak yang mengajukan permohonan
dalam hal ini adalah lembaga negara yang
mempunyai kepentingan langsung
terhadap kewenangan yang
dipersengketakan, akan tetapi lembaga
negara dimaksud harus secara khusus
yang kewenangannya diberikan oleh UUD
RI 1945. Kalau diteliti dalam UUD RI 1945,
secara tegas dapat disebut MPR, DPR,
DPD, Presiden, BPK, Pemerintah Daerah,
Pemerintah Provinsi yang dibagi atas
Kabupaten dan Kotamadia. Mahkamah
Agung sebagai lembaga negara yang
memperoleh kewenangan dari UUD RI
1945 tidak dapat menjadi pihak baik
pemohon maupun termohon dalam
sengketa kewenangan antar lembaga
negara (Pasal 65 UU 24/ 2003).
C. Pembubaran Parta Politik
Pemohon dalam sengketa pembubaran
partai politik adalah pemerintah dan lebih
jauh dijelaskan pemerintah pusat. Tetapi,
departemen atau lembaga dimana
ewenangnya memohon hal semacam ini
dari pemerintah pusat? Sebagai wakil
untuk mengajukan permohonan adalah
J aksa Agung. Tapi boleh jadi dalam
prakteknya nanti akan berkembang yang
akan memungkinkan mengajukan
permohanan adalah departemen-
departemen atau lembaga negara yang
mempunyai kaitan langsung dengan
alasan pembubaran partai politik. Karena
pemerintah pusat adalah kesatuan, maka
harus terlebih dahulu diperoleh izin atau
perintah atau penunjukan presiden
sebagai kepala pemerintahan.
Sedangkan alasan yang diajukan karena
ideologi, asas, tujuan, program dan
kegiatan partai politik tertentu yang
dianggap bertentangan dengan UUD RI
1945.
D. Perselisihan Hasil Pemilu
Perselisihan hasil pemilu merupakan
sengketa tentang hasil pemilu secara
nasional yang dipandang penetapan
Komisi Pemilihan Umum mempengaruhi:
a. Terpilihnya anggota DPD;
b. Penetapan pasangan calon yang masuk
pada putaran kedua pemilihan presiden
dan wakil presiden serta terpilihnya
pasangan presiden dan wakil presiden;
c. Perolehan kursi partai politik peserta
pemilu di satu daerah pemilihan.
Munculnya sengketa ini adalah karena
adanya perbedaan pendapat tentang hasil
perhitungan suara yang oleh pemohon
dipandang tidak benar dan hanya dapat
diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 X 24 (tiga kali 24 jam) sejak
Komisi Pemilihan Umum mengumumkan
penetapan hasil pemilihan umum secara
nasional. Sedangkan pemohon dalam
sengketa ini adalah:
1. Perorangan warga negara Indonesia
calon anggota DPD peserta pemilu;
2. Pasangan calon Presiden/ Wakil
Presiden peserta pemilu Presiden/ Wakil
Presiden;
3. Partai politik peserta pemilu.
E. Pendapat DPR mengenai Pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
Dalam hal ini yang dapat mengajukan ke
Mahkamah Konstitusi adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
yang dalam pengambilan sikap tentang
adanya pendapat semacam ini tentu
melalui proses pengambilan keputusan di
DPR yaitu melalui dukungan 2/3 (dua
pertiga) jumlah seluruh anggota DPR yang
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR
(Pasal 7 B ayat (3) UUD RI 1945).
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
75
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
4. Kesimpulan
Peranan Mahkamah Konstitusi dalam
menjaga Konstitusi melalui kekuasaan
kehakiman meliputi kewenangan utama
dan kewenangan tambahan.
Kewenangan utama meliputi; (a)
Pengujian undang-undang terhadap UUD
RI 1945, (b) memutus constituional
complain yang diajukan rakyat terhadap
penguasa (UUD RI 1945 tidak
memberikan kewenangan ini kepada
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
sedangkan dinegara lain diberikan kepada
mahkamah konstitusi), (c) memutus
sengketa kewenangan antar lembaga
negara. Sebagai kewenangan tambahan
dapat bervariasi antara negara satu
dengan negara lainnya. Sedangkan UUD
RI 1945 memberikan kewenangan
tambahan kepada Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia yaitu; (a) pembubaran
partai politik, (b) perselisihan hasil
pemilihan umum, (c) pemberian putusan
DPR atas dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh presiden dan/atau wakil
presiden.
Sebaiknya Mahkamah Konstitusi diberi
kewenangan utamanya yaitu untuk
memutus memutus constituional complain
yang diajukan rakyat terhadap penguasa
seperti Mahkamah konstitusi Austria, Itali,
J erman dan lainnya. Dengan sendirinya
bisa melakukan perannya sebagai
penjaga konstitusi secara tuntas.
Daftar Pustaka
[1] Harian Kompas 11 Oktober, 2005
[2] Hajono. 2003. Kedudukan dan Peran
Mahkamah Konstitusi Dalam Kekuasaan
Kehakiman dan
Ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.
[3]J imly, Asshiddiqie. 2003. Mahkamah
Konstitusi: Penomena Hukum Tata
Negara. Mahkamah
Konstitusi.
[4] Maruarar, Siahaan. 2003. Prosedur
Berperkara di Mahkamah Konstitusi dan
Perbandingan dengan Hukum Acara di
Pengadilan Umum dan TUN. Mahkamah
Konstitusi.
[2] Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah
Konstitusi.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
76
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
NASIONAL
Reformasi setengah hati :
Refleksi atas kegagalan pemberantasan korupsi di Indonesia
John Fresly
Program Master of Law, Niigata University,
J apanese Development Scholarship /J DS 2005
E-mail: jfresly@yahoo.com
Seorang pakar hukum di Indonesia
menyatakan bahwa perilaku korupsi di
Indonesia sudah seperti pedagang ikan di
pasar ikan. Tidak tercium lagi bau ikan
yang menyengat karena sudah bergumul
sepanjang hari layaknya business as
usual. Sehingga tidaklah mengherankan
ketika Transparency International (TI)
mengeluarkan laporan terbaru mengenai
indeks persepsi korupsi tahun 2005
(Transparency International Corruption
Perception Index 2005), hanya segelintir
kalangan yang memberikan komentar
bernada prihatin tentang posisi Indonesia
dalam yang berada dalam urutan ke 137
dari 158 negara atau nomor 6 paling korup
di dunia. (Kompas, 19 Oktober 2005).
Posisi tersebut hanya lebih baik dari
Myanmar, satu-satunya negara anggota
ASEAN yang masih berada dibawah junta
militer. Bahkan sejak awal dikeluarkannya
laporan TI sejak tahun 1995 Indonesia
tercatat sebagai negara yang paling korup.
(www.transparency.org/surveys/index.html
#cpi)
Lalu pelajaran apakah yang dapat ditarik
dari laporan tersebut? Benarkah korupsi
sudah sedemikian parahnya sehingga
tidak ada lagi pihak yang mampu
mengatasinya? Apakah pengaruh korupsi
ini bagi Indonesia dalam bersaing dengan
bangsa lain di era globalisasi? Mengapa
sedemikian pentingnya pemberantasan
korupsi bagi pembangunan dan ekonomi?
Atau sebaliknya kita berdalih bahwa
laporan tersebut tidak mempunyai
kredibilitas sehingga tidak dapat dijadikan
patokan untuk menilai keadaan Indonesia
saat ini.
Pertanyaan tesebut diatas menjadi
semakin krusial apabila kita
membandingkan Indonesia dengan
negara-negara lain yang posisinya lebih
baik. Berdasarkan metodologi yang
digunakan dalam laporan tersebut yang
menggunakan data dan analis dari
kalangan pengusaha dan para pakar
hubungan internasional dapat dilihat
bahwa korupsi sangat berkaitan dengan
pengelolaan pemerintahan yang
transparan dan demokratis serta iklim
kondusif untuk melakukan investasi global.
Kinerja pemerintahan SBY dalam
pemberantasan korupsi
Sebagai suatu lembaga internasional yang
diakui kredibilitasnya maka laporan TI
akan mempunyai dampak yang buruk bagi
pemulihan ekonomi di Indonesia. Sulit
membayangkan perbaikan citra Indonesia
hanya dengan retorika pemberantasan
korupsi tanpa suatu tindakan konkrit dan
menyeluruh di semua unsur pemerintahan
dan kehidupan masyarakat.
Presiden Yudhoyono menyadari bahwa
pemberantasan korupsi merupakan salah
satu agenda politik yang harus menjadi
prioritas kabinet Indonesia Bersatu. Oleh
sebab itu sejak mulainya pemerintahan
SBY tanggal 20 Oktober 2004, Presiden
menaruh perhatian dalam penanganan
kasus korupsi. Hal ini tercermin dalam
pengungkapan beberapa kasus besar
antara lain tindak lanjut pengungkapan
kasus pembobolan bank BNI 1946, kasus
korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU),
kasus illegal logging, kasus
penyelundupan BBM Pertamina dan
terakhir dugaan kasus korupsi di
Mahkamah Agung .
Namun demikian setelah satu tahun
pemerintah SBY, tampaknya upaya
pemberantasan korupsi masih terlalu
sedikit dan terkesan berjalan di tempat.
Fenomena korupsi masih menjadi
business as usual dan sudah tak asing
Dunia
77
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
lagi seperti orang membuang gas di
perutnya. Tercium baunya namun tidak
ada seorangpun yang bisa dituduh
melakukannya karena pembuktian korupsi
tidak menggunakan asas pembuktian
terbalik. Yaitu pembuktian dengan metode
pembuktian yang mendalilkan bahwa
pihak yang diduga melakukan korupsi
harus dapat memberikan bukti kekayaan
yang duimilikinya diperoleh dengan cara
yang wajar .
Metode pembuktian terbalik akan
mempermudah penyidik tindak pidana
korupsi dalam menghadapi para koruptor
yang dengan menyewa pengacara
tangguh berupaya mencari celah hukum
untuk menyatakan bahwa harta
kekayaannya diperoleh dengan tidak
melanggar hukum.
Lebih parah lagi kalau penegak hukum itu
sendiri telah tercemar korupsi. Ini
merupakan lonceng kematian bagi
pemberantasan korupsi, karena semua
pilar negara mulai dari eksekutif pusat dan
pemerintah daerah, anggota dewan atau
legislator pusat maupun daerah , dan
penegak hukum termasuk jaksa dan
hakim serta aparat keamanan tidak ada
yang immune dari korupsi.
Faktor inilah yang membuat setiap upaya
pemberantasan korupsi selalu menemui
jalan buntu karena begitu kompleksnya
permasalahan korupsi di Indonesia.
Hal yang tampak sepele namun menyolok
adalah tidak adanya perubahan di sektor
pelayanan publik. Contoh sederhana
pengurusan KTP masih dipungut biaya
dan waktunya lama. Biaya administrasi
untuk mengurus perijinan tidak seragam
dan biaya yang dikeluarkan berbeda jauh
dengan apa yang tertera pada aturan
tertulis.
Informasi tentang aturan dan pelaksanaan
selalu asimetris, sehingga ada peraturan
yang pelaksanaannya tidak seragam atau
ditutupi seperti misalnya kebijakan
pembebasan fiskal bagi pemegang
paspor RI yang mempunyai permanent
resident ataupun berdomisili di luar negeri
tidak dengan mudah dilaksanakan di
lapangan.
Tidak ada sense of crisis dari para pejabat
pemerintah, yang justru berlomba-lomba
mengejar penampilan fisik baik
kelembagaan maupun individu ketimbang
memprioritaskan penanganan pelayanan
publik.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa
fungsi pengawasan baik internal lembaga
pemerintah dalam bentuk Inspektorat
J enderal maupun eksternal berupa Badan
Pemeriksa Keuangan dan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan
hanyalah kosmetik dari sebuah sistem
pemerintahan. Bahkan ada
kecenderungan fungsi pengawasan ini
menjadi mubazir pada saat tidak ada
kewenangan eksekutorial dari putusannya.
Pembentukan berbagai komisi seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan dan
Komisi J udisial tidaklah memberikan efek
siginifikan bagi pemberantasan korupsi.
Hanya KPK yang mulai menunjukkan
kinerjanya sejak pemerintahan SBY.
Padahal lembaga pemberantas korupsi
telah ada pada masa pemerintahan
Presiden sebelumnya dengan nama
Komisi Pemeriksaan Kekayaan
Penyelenggara Negara (KPKN).
Pemberantasan korupsi menjadi semakin
kompleks karena seiring dengan
berjalannya waktu para pihak yang telah
mendapatkan kekayaan pada masa Orde
Baru dengan cara yang melawan hak
rakyat, kembali masuk ke arena publik
baik melalui lembaga formal seperti partai
politik dan lembaga sosial maupun melalui
jalur bisnis.
Sungguh ironis menyaksikan bagaimana
kota J akarta penuh dengan berbagai
kendaraan mewah dan kesibukan di
berbagai hotel berbintang lima dan tempat
hiburan kelas atas/pengunjung mal kelas
atas yang ramai, sementara lebih dari
40 % rakyat Indonesia masih hidup
dibawah garis kemiskinan.
Kondisi ini sangat rentan karena
menimbulkan permasalahan sosial yang
menjadi mudah berkembang menjadi
konflik horizontal. Merebaknya kejahatan
seperti penggunaan narkoba dan
trafficking serta kejahatan lainnya salah
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
78
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
satunya disebabkan oleh ketimpangan
ekonomi dan sosial tersebut.
Kondisi Darurat dalam Pemberantasan
Korupsi
Korupsi merupakan batu sandungan
utama untuk mencapai kemajuan besar
dalam ekonomi negara-negara di Asia dan
Afrika [5]. Lebih lanjut disebutkan bahwa
korupsi yang telah menggurita di semua
level akan membuat kebijakan publik
menjadi tidak efektif dan mengakibatkan
aktivitas ekonomi dan investasi tidak lagi
produktif karena adanya faktor non teknis
ekonomi dibawah tangan.
Dengan demikian sudah seharusnya
pemberantasan korupsi tidak lagi dilihat
hanya sebagai pekerjaan rutin namun
sudah harus menjadi prioritas utama
pemerintahan SBY.
Kesulitannya adalah bahwa korupsi di
Indonesia sudah begitu kompleks, tidak
hanya terjadi di kalangan pemerintah tepai
sudah merambah ke seluruh lapisan
masyarakat.Tidaklah mengherankan
apabila seorang tukang parkir saja sudah
menjadi agen dari korupsi struktural yang
menjadi ujung tombak dalam
pengumpulan uang parkir yang kabarnya
selalu menguap.
Aparatur pemerintah sebagai motor
penggerak pembangunan sudah
sedemikian terbebani dengan korupsi ini
sehingga tidak satupun dari institusi
negara yang mempunyai standar minimal
pelayanan publik yang memadai. Bahkan
di beberapa instansi pemerintah, prosedur
perijinan bukan menjadi bentuk pelayanan
publik tetapi menjadi ladang untuk
memungut dana secara melanggar hukum.
Etos kerja anti korupsi dalam
menghadapi era globalisasi
Lalu apakah yang dapat dilakukan untuk
keluar dari lingkaran korupsi tersebut?
Berkaca pada pengalaman negara lain,
tampaknya masalah etos kerja bangsa
Indonesia terutama para aparatur perlu
mendapatkan perhatian khusus.
Sebagai bahan perbandingan banyak
sekali kebiasaan kerja masyarakat J epang
yang dapat dijadikan bahan kajian untuk
menumbuhkan etos kerja yang anti
korupsi.
Salah satunya adalah budaya Hansei
yang terungkap dalam perilaku dan
perkataan Sumimasen dan Gomenasai.
Perkataan ini selalu diucapkan orang
J epang apabila telah melakukan suatu
tindakan yang dianggapnya merugikan
orang lain atau melakukan kesalahan.
Makna yang terkandung didalamnya suatu
bentuk self-retrospection; yang menguji
diri sendiri apakah sudah berbuat yang
sesuai dengan aturan dan diakhiri dengan
keinginan kuat untuk tidak melakukan hal
yang sama di kemudian hari.
Wujud dari budaya Hansei ini jelas
terungkap dalam kehidupan sehari-hari di
segala sektor masyarakat termasuk dalam
bidang pemerintahan. Menurut hemat
penulis budaya Hansei ini adalah salah
satu alasan mengapa pemerintahan PM
Koizumi melakukan proses reformasi
pemerintahan yang salah satunya sangat
terkenal yaitu postal privatization.
PM Koizumi konsisten dengan janji
kampanye untuk melakukan perubahan
meskipun dengan resiko terjadinya
pemutusan hubungan kerja di sektor yang
telah lama menjadi mesin uang
pemerintah. Untuk itu PM Koizumi segera
merombak kabinetnya setelah
memenangkan Pemilu yang dipercepat 11
September lalu.
Belajar dari pengalaman J epang tersebut
mungkinkah Indonesia melakukan
terobosan dengan menumbuhkan etos
kerja baru dalam menjalankan aktivitas
baik di sektor pemerintahan maupun
sektor swasta?.
Malaysia sudah lebih dahulu melakukan
hal ini dengan melalui slogan Look East
yang dipropagandakan oleh PM Mahathir
Mohamad, dengan menyuruh rakyatnya
untuk meniru etos kerja bangsa J epang
dan Korea Selatan [3].
Tak dapat dipungkiri akan ada sebagian
masyarakat yang apriori terhadap
efektifitas slogan-slogan seperti ini,
sebagaimana dulu zaman pemerintahan
Sorharto yang penuh dengan slogan
namun kenyataannya tidak sesuai dengan
praktek yang sebenarnya.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
79
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Tampaknya yang menjadi kata kunci
adalah adanya keteladanan dalam
melakukan gerakan ini. Tanpa adanya
keteladanan maka sulit untuk dapat
menggali nilai atau potensi dari
masyarakat.
Potensi masyarakat (SDM) merupakan
kunci dalam menghadapi persaingan
global dewasa ini. Sudah terbukti bahwa
kekayaan alam semata tidak cukup untuk
dapat menjadikan rakyat sejahtera dan
hidup damai. Bahkan celakanya kekayaan
alam ini menjadi bumerang yang menina
bobokkan rakyat menjadi bangsa yang
malas bekerja.
Ada obrolan ringan dengan seorang
pengamat kebudayaan yang mengatakan
bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa
pemalas karena sejak kecil kita diberi
cerita bahwa Indonesia adalah negara
yang kaya raya dan makmur sentosa.
Sedangkan di J epang sejak dari kecil
penduduknya diberitahu bahwa negeri
J epang miskin dan tidak mempunyai
kekayaan alam, sehingga sejak kecil
mereka dididik untuk bekerja keras untuk
bisa hidup.
Bahkan celakanya lagi ada pejabat di
zaman Orde Baru yang mengatakan
bahwa rakyat Indonesia belum mampu
mengurus diri sendiri, tapi tidak diberikan
pendidikan yang memadai. J adi rakyat
yang bodoh merupakan keuntungan
karena tidak akan berfikir dan mencari
kebenaran.
Pendidikan politik masyarakat dan
pemanfaatan Tekologi Informasi untuk
pemberantasan korupsi
Revolusi informasi yang ditandai dengan
konvergensi teknologi komunikasi,
komputer dan multimedia merupakan
gelombang ketiga setelah revolusi industri
di Inggris yang merubah kehidupan dunia.
Perkembangan teknologi ini memberikan
peluang kepada individu untuk
mendapatkan akses yang lebih besar
terhadap informasi, lebih cepat dalam
mengambil keputusan dan dapat
berkomunikasi dengan siapapun di
belahan dunia dalam waktu yang singkat
[2].
Tidak dapat disangkal bahwa
salah satu faktor eksternal yang
mendorong jatuhya pemerintahan
Soeharto adalah dampak dari kemajuan
teknologi informasi. Melalui internet, para
aktivis dapat menyampaikan kondisi di
Indonesia kepada masyarakat
internasional dan sebaliknya ada
dukungan dari masyarakat internasional.
Pemerintah dimanapun di dunia ini tidak
lagi mampu menutupi kemajuan atau
informasi tentang belahan dunia lain dari
rakyatnya. Seharusnya pemerintah
Soeharto saat itu menyadari bahwa
runtuhnya tembok Berlin dan jatuhnya Uni
Soviet merupakan sebagai simbol dari
runtuhnya komunis akan mempunyai efek
kepada pemerintahannya termasuk masuk
depan Indonesia paska perang dingin.
Namun tujuh tahun setelah reformasi 1998,
tampaknya belum banyak perubahan
berarti dalam reformasi birokrasi dalam
pemerintahan di Indonesia. Hal ini
terutama terlihat dalam sektor pelayanan
publik.
Terobosan untuk mendorong perubahan
yang signifikan dalam pelayanan publik
tampaknya perlu diwacanakan melalui
pemanfaatan teknologi informasi.
Otomatisasi sektor pelayanan akan
mengurangi peluang korupsi pada
institusi pelayanan publik.
Namun hal ini kembali lagi kepada etos
kerja dan political will dari pemerintah
untuk menerobos lingkaran setan korupsi.
Sebagai contoh adanya rencana
pemerintah untuk menerapkan e-
procurement perlu dijadikan momentum
untuk memulai pelayanan publik yang
bebas dari korupsi. Pembatasan akses
petugas melalui otomatisasi tidak akan
berarti banyak apabila pejabat yang
bertanggung jawab akan mencari
kelemahan dari sistem yang ada.
Penerapan Single Identification Number
untuk data kependudukan merupakan
langkah awal untuk melakukan pelayanan
kepada publik. Turunan dari kebijakan ini
akan mempunyai korelasi positif dengan
berbagai pelayanan publik mulai dari
pelayanan kartu penduduk sampai kepada
penyelidikan dan penyidikan kasus
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
80
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
kriminal maupun terorisme serta
pembayaran pajak dan lain sebagainya.
Permasalahannya adalah sampai saat ini
pemerintah masih sibuk berdebat siapa
yang akan melaksanakan pekerjaan ini.
Meminjam istilah aparatur, saat ini masih
dalam pembahasan instansi mana yang
akan menjadi leading sector dalam
melaksanakan proyek tersebut.
Keluar dari krisis yang berkepanjangan
untuk menghadapi ASEAN Free Trade
Area 2010
Globalisasi bukanlah suatu pilihan tetapi
suatu kenyataan dari tatanan baru di abad
ke-21. Thomas Friedman dalam bukunya
The Lexus and Olive Tree melukiskan hal
ini sebagai apa yang di sebutnya
Electronic Herd [1].
Pengelolaan negara di era globalisasi
bukan lagi sekedar mengelola administrasi
pemerintahan secara tradisional seperti
seorang pamongpraja yang memungut
retribusi dan membangun prasarana pasar
untuk berdagang.
Pasar bebas dan ekonomi global menjadi
pilihan yang harus disiasati karena
ekonomi dunia sudah saling terhubung
dan bisa dikatakan menjadi dunia tanpa
batas. Produk asing mulai dari peniti
sampai alat berat telah membanjiri toko-
toko di Indonesia tanpa bisa dicegah.
Sebagian masuk secara legal akibat
dampak perdagangan bebas sedangkan
sebagian masuk dengan diselundupkan .
Produk asing ini jelas mematikan industri
lokal yang memang tidak kompetitif dan
tidak efisien. Implikasinya jelas
mengurangi kesempatan atau lapangan
pekerjaan di sektor industri karena dengan
matinya industri tersebut, yang tersedia
hanya lapangan pekerjaan di sektor jasa
perdagangan bukan produksi.
Tantangan yang paling jelas ada di depan
mata adalah bagaimana Indonesia bisa
bersaing dengan negara tetangga ASEAN.
Singapura dan Malaysia sudah jauh di
depan kita. Berdasarkan angka indeks
pembangunan manusia (Human
Development Index) tahun 2005,
Singapura berada di urutan ke-25,
Malaysia di urutan ke-61, dan Thailand di
urutan ke-73. Posisi Indonesia berada di
urutan ke-110, yang bahkan dibawah
Vietnam (ke-108).
(http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pd
f).
Dengan diberlakukannya ASEAN Free
Trade Area (AFTA) yang diawali dengan
pemberlakuan Common Effective
Prefential Tariff (CEPT) sejak tahun 1992,
terlihat bahwa Indonesia tidak dapat
memanfaatkan penurunan tarif bea masuk
antar negara ASEAN tersebut. Yang
terjadi justru Indonesia menjadi sasaran
pasar dari produk negara lainnya.
Yang lebih berat lagi apabila penghapusan
hambatan tarif impor diterapkan pada
tahun 2010 pada enam negara anggota
lama ASEAN, maka lengkap sudah pasar
Indonesia menjadi lahan empuk bagi
negara lainnya.
( http://www.aseansec.org) Tak ada lagi
legal scheme yang bisa disiasati untuk
memproteksi pengusaha dan industri lokal
karena Indonesia terikat pada
kesepakatan multilateral tersebut.
Lalu bagaimana caranya agar Indonesia
bisa memenangkan persaingan dalam
AFTA? J alan keluarnya adalah membuat
Indonesia dapat menghasilkan produk
yang berkualitas dan efisien dengan harga
yang kompetitif. Hal ini tidak dapat dicapai
selama masalah ekonomi biaya tinggi
masih menjadi persoalan utama akibat
dari korupsi.
Koalisi Forum Rektor Indonesia dan
Ikatan Sarjana Lulusan Universitas di
LN
Salah satu breakthrough yang ditawarkan
oleh penulis adalah pembentukan koalisi
para intelektual yang pernah mengenyam
pendidikan di LN. Kaum intelektual
tersebut telah banyak mempelajari cara
negara maju dalam mengelola negaranya.
Best practice yang didapatkan dari
masing-masing negara itu apabila
diwacanakan secara sistematis akan
dapat memberikan pembelajaran bagi
penyelesaian persoalan bangsa Indonesia.
Untuk mendapatkan legitimasi politik yang
kuat maka kelompok ini dapat membentuk
koalisi dengan Forum Rektor, suatu
kelompok yang beranggotakan perguruan
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
81
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
tinggi di Indonesia. Melalui koalisi ini
dapat digagas terobosan yang sistematis
dan strategis untuk menembus kebuntuan
upaya pemberantasan korupsi saat ini.
Bagi pihak yang skeptis dengan ide ini
dengan mudah akan mengambil contoh
kegagalan mafia Berkeley dalam
membangun pondasi ekonomi Indonesia
di era Orde Baru.
Atau mungkin ada argumen lain yang
menyalahkan Amerika Serikat atas
rencana sitematisnya untuk hancurkan
ekonomi negara lain dengan
menggunakan tangan Economic hit men
[4].
Hal tersebut tak perlu dikhawatirkan
karena cukup banyak argument yang
dapat dikemukakan untuk mendukung
koalisi tersebut. Prospek koalisi ini
dalam konteks menjawab tantangan
bangsa Indonesia ke depan sangat
strategis dengan beberapa alasan :
1. Partai politik sebagai wadah
penampung aspirasi masyarakat tidak
mampu keluar dari perbedaan politik
yang sektoral. Praktek beberapa
negara yang telah stabil dalam
demokrasi menunjukkan bahwa
jumlah partai politik tidak banyak
bahkan hanya dua partai politik.
2. Kecenderungan untuk tidak ikut
berpolitik pada sebagian besar kaum
intelektual memperlemah pendidikan
politik masyarakat;
3. Para legislator pada umumnya lebih
mengandalkan kemampuan retorika
dalam mengkritisi pemerintah
ketimbang memanfaatkan pendekatan
ilmiah atau hasil penelitian;
4. Kalangan intelektual harus dapat
menghapus stigma buruk terhadap
integritas dan kredibilitas kaum
intelektual akibat kasus korupsi di
KPU yang melibatkan para intelektual.
5. Sudah saatnya perdebatan politik di
Indonesia dilakukan berdasarkan
pendekatan ilmiah yang didukung
oleh data dan penelitian yang
mendalam.
Kesimpulan
Agenda pemberantasan korupsi
harus menjadi prioritas utama
pemerintahan Presiden SB Yudhoyono,
mengingat persaingan global dengan
prinsip ekonomi pasar bebas sangat
kompetitif.
Penanganan korupsi yang bersifat sektoral
dan tidak tuntas akan memperlemah daya
saing Indonesia dan memperburuk citra
Indonesia dalam rangka menarik investasi
luar negeri.
Ekonomi global yang interdependesi akan
menghindari negara tujuan investasi yang
tidak efisien dan efektif dalam mengelola
pemerintahannya.
Perlu dukungan kaum intelektual secara
terorganisir untuk menerobos kebuntuan
penanganan korupsi terutama di sektor
pelayanan publik. Best practice negara
lainnya perlu dijadikan modal
pembelajaran dalam mengelola negara
terutama dalam hal penanganan sektor
publik.
Pemanfaatan teknologi informasi
merupakan salah satu tool yang terbukti
efektif mengurangi peluang untuk
melakukan korupsi.
Pembentukan koalisi masyarakat
intelektual diharapkan mampu
memberikan energi baru bagi pemerintah
untuk keluar dari krisis politik dan ekonomi
yang berkepanjangan untuk melihat ke
depan menghadapi persaingan global.
DaftarPustaka :
[1] Friedman, Thomas L, 2000, The lexus
and the olive tree, Anchor Book, New
York.
[2] Naisbitt, J ohn, 1994, Global Paradox,
Avons book, New york.
[3] Ohmae, Kenichi, 1990, The borderless
world: power and strategy in the
interlinked economy, Harper Collins
Publishers, New York.
[4] Perkins, J ohn, 2004, Confessions of
an economic hit man, Berrett-Koehler
Publishers Inc, San Francisco.
[5] Sen, Amartya, 1999, Development as
freedom, Anchor Books, New York.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
82
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
60 Tahun Jepang Pasca Perang Dunia II
Purnamawati
Fakultas Hukum
J urusan Sejarah dan Politik
Program Master semester 1
Universitas Kagoshima
Tahun 2005 ini menandai tahun ke-60
berakhirnya PD II, atau peringatan 60
tahun kekalahan J epang pada Perang
Dunia ke dua. Pada saat Perang Dunia,
J epang sebagai negara penyerang
menduduki negara Asia, terutama Cina
dan Korea. Berakhirnya PD II merupakan
kesempatan bagi mereka untuk merdeka
dan melepaskan diri dari pendudukan dan
penjajahan J epang. Pada saat yang sama,
pembentukan Persatuan Bangsa-Bangsa
di dunia yang menjadi dasar Tata Tertib
Peraturan International [6].
J epang pada saat itu memasuki periode
yang disebut periode setelah perang. Bagi
para sebagian pihak terutama pengamat
politik dan pengajar di universitas J epang,
dalam kependudukan Amerika periode
setelah perang, mulai terasa keganjilan
pada saat perubahan yang terjadi berawal
dari sebelum perang dan pada saat
perang berjalan. Perubahan yang terjadi
adalah dari kematian sampai awal
kehidupan (berjuta-juta korban yang jatuh
setelah pemboman Hiroshima dan
Nagasaki), dari negara militarisme sampai
menjadi negara Demokrasi, dari rakyat
yang lebih mencintai kesatuan national
daripada hak mereka menjadi negara
yang menghormati hak asasi manusia,
kebebasan berbicara, kebebasan berpikir,
kebersamaan kedudukan pria dan wanita.
Pengamat sejarah J epang terutama para
pengajar di universitas memandang
bahwa setelah J epang kalah dalam
perang dunia kedua masih banyak
masalah yang terjadi di dalam negeri
J epang dan sampai sekarang masih
belum terselesaikan. Bagi mereka, apa
yang terjadi sebelum dan setelah perang,
banyak orang terutama politikus lupa.
Sebelum perang sampai J epang harus
mengalami kekalahan, di dalam negeri
J epang sebenarnya terjadi kemiskinan
dan kemelaratan. J epang harus
membangun kekuatan militer untuk
menyaingi kekuatan barat, oleh karena itu
para pihak militer dibawah kekuasaan
Kaisar J epang, memaksa para rakyat
untuk bekerja dan masuk wajib militer.
Rakyat yang pada saat itu harus patuh
dengan perintah kaisar, tidak dapat
melakukan tindakan berontak. Bagi
mereka Kaisar adalah utusan Tuhan.
Pihak yang paling menderita adalah para
petani. Mereka harus bekerja di berbagai
pabrik militer dan meninggalkan tanah
pertanian, terutama para pria dan mereka
juga harus ikut wajib militer. Sebelum
J epang harus menyerah tanpa syarat di
bawah perjanjian San Frasisco, J epang
menjalani Undang-undang Meiji yaitu
semua berdasarkan perintah dan petunjuk
Kaisar J epang. Begitu juga dalam perang
[6].
J epang sebelum perang dunia berakhir
adalah negara imperialis, dengan
menjalankan paham fasisme seperti
J erman dan Undang-Undang Meiji. Pada
saat memasuki zaman modern
1
, bagi
J epang sendiri untuk sederajat dengan
kemajuan Barat harus memperluas
kekuatan di dunia. Bagi pihak J epang
yang paling dekat untuk menjalankan
paham kolonialisme adalah Taiwan.
Taiwan dapat direbut oleh J epang setelah
J epang perang dengan negara Cina
(negara kekaisaran Cina)
2
. Taiwan adalah
negara pertama dijajah J epang. Berawal
dari itu J epang terus memperluas
kekuatan militernya dengan menguasai
Korea
3
. Setelah menguasai Korea,
1
J epang sebelum masuk jaman modern,
menutup diri dengan negara asing dan
membuka diri dengan negara asing yang
disebut jaman Meiji 1860)
2
Perang Nisshin 1894-1895
3
Pada saat itu Korea yang disebut sebagai
Chosen dikuasai oleh Rusia dan Rusia harus
HUMANIORA
83
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
J epang terus berlomba dengan kekuatan
dan kemajuan negara Eropa dengan
memperebutkan negara Cina sebagai
pusat perdagangan Asia. Akhirnya J epang
terus menjadi negara penjajah dan mulai
menguasai asia timur dan selatan.
Termasuk Indonesia yang tiga tahun
diduduki oleh J epang bukan sebagai
penjajah. Dan akhirnya J epang harus
mengakui kekalahan setelah pemboman
Hiroshima dan Nagasaki. Dibawah
perjanjian San fransisco, J epang harus
mengakui (8 September 1956) dan harus
mengadakan perubahan sesuai dengan
petunjuk Amerika, terutama mengenai
Undang-undang Meiji dan menjalankan
demokrasi di dalam negeri J epang [2].
Bagi pihak militer dan pihak yang masih
menjaga kekuasaan Kaisar dan para
politikus yang masih menginginkan
kejayaan J epang kembali, apa yang terjadi
pada saat perang dan setelah perang,
tidak usah dijelaskan secara mendetil dan
mereka tidak koreksi diri dengan mawas
diri. Seperti di J erman, setelah perang
dunia kedua koreksi diri terhadap perang
yang telah terjadi merupakan kesalahan.
Oleh sebab itu J erman teguh menjaga
kedamaian dunia dan membayar ganti rugi
terhadap korban perang. Sedangkan
J epang masih dipertanyakan. Masalah
yang dihadapi J epang dan sampai
sekarang belum terselesai adalah
hubungan dengan Cina dan Korea,
permasalahan daerah militer Amerika di
Okinawa (sebagai bayaran kekalahan
J epang dan membebaskan Kaisar sebagai
penjahat perang menyerahkan Okinawa
ke Amerika), buku sejarah J epang, korban
penjajahan J epang dan korban Hiroshima
dan Nagasaki. J epang terhadap korban
penjajahan dan pendudukan di Asia timur
dan selatan tidak sesuai dengan tuntutan
para korban. Contohnya bagi pihak Cina
yang mengalami kekejaman penjajahan
J epang tidak mendapatkan ganti rugi yang
sesuai dengan kekejaman J epang
4
,
sedangkan Korea didalam bentuk
kerjasama ekonomi. Korea Utara tidak
mendapatkan ganti rugi karena belum ada
kerjasama kedua negara. Asia Tenggara
tidak mendapatkan ganti rugi tetapi dalam
mengakui kekalahan dalam perang Nichiren
1904.
4
Pada 1972 ganti rugi J epang terhadap Cina
selesai
bentuk kerjasama ekonomi. Oleh karena
itu menurut para korban kekejaman
penjajahan dan kependudukan J epang,
ganti rugi yang dibayar tidak sesuai.
Sedangkan di pihak J epang yang harus
menerima kekalahan dan korban yang
berjatuhan di pemboman di Hiroshima dan
Nagasaki masih belum diakui oleh pihak
Amerika dan harus membayar ganti rugi
ke negara-negara barat sebagai negara
yang kalah perang [3].
J epang setelah perang dunia berakhir
dengan bantuan Amerika meningkatkan
ekonominya menjadi negara industri dan
sangat maju dibandingkan negara
disekitar J epang. Sedangkan hubungan
J epang Cina dan Korea sampai pada saat
ini masih menjadi permasalahan,
khususnya di era Koizumi ini. Perdana
Menteri Koizumi ingin mengadakan
pembaharuan mengenai isi undang-
undang J epang pasal 9 yang berisikan
J epang melepaskan diri dari perang dan
menjaga perdamaian dunia dengan tidak
memiliki tentara, hanya memiliki pasukan
bela diri. Kemudian Koizumi secara
terang-terang mendatangi Shirine
Yasukuni dan berdoa di tempat tersebut
dengan memakai pakaian kebesaran
seorang perdana menteri J epang, tahun
lalu. Tindakan tersebut membuat
kemarahan bagi Cina dan Korea. Karena
Shirine Yasukuni yang dibangun kaisar
(1879) sebagai tanda penghormatan bagi
para tentara J epang yang telah berjuang
membela J epang didalam perang. Di
Shirine Yasukuni juga dikubur para
penjahat J epang yang mendapat hukuman
mati, terutama para militer yang
melakukan kejahatan dengan kekejaman
di Nanking dan Manchuria [1]. Bagi pihak
Cina dan Korea yang masih menyimpan
kemarahan atas kekejaman di Nanking
dan Manchuria, tindakan Kozumi
menghormati dan menjunjung tinggi apa
yang dilakukan para penjahat militer dan
kejayaan J epang pada saat perang.
Sedangkan didalam Undang-undang baru
J epang telah menjelaskan bahwa spritual
dan pemerintahan harus dipisahkan.
Menurut undang-undang baru J epang
menjelaskan spritual adalah kebebasan
individu untuk melakukannya [3]. Koizumi
pada tahun lalu dengan memakai pakaian
kebesaran sebagai perdana menteri telah
mencampur adukkan spiritual
(keagamaan) dengan pemerintahan. Oleh
84
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
karena itu bagi pengamat politik dan
sejarah J epang terutama para guru dan
dosen, Koizumi tidak memahami isi dari
Undang-undang Baru J epang dan mereka
sangat menentang niat Koizumi utuk
mengubah undang-undang pasal 9.
Kozumi dan para pihak liberal mulai
menekankan rasa cinta tanah air dengan
mengabdi kepada tanah air, terutama
masuk dalam militer J epang [4]. Bagi para
pengamat, negara yang kuat memiliki
tentara akan mudah melakukan tindakan
untuk menguasai seperti Amerika dengan
mudah menguasai Irak dengan dalih untuk
demokrasi. Mungkin J epang akan menjadi
negara pada saat perang dunia yang
begitu mudah menguasai negara
jajahannya dan hancurnya perdamaian
negara yang dijaga selama ini. Pihak
kozumi akan bias mengubah isi undang-
undang J epang pasal 9 tentang militer
J epang jika menguasai 60% suara di
parlemen, sedangkan hanya 40% suara
menyetujui perubahan, 40% tidak setuju
dan 20% tidak ikut suara
5
[5].
Koizumi dan para pihak liberal masih
menginginkan J epang memiliki kekuatan
militer. J epang lupa apa yang terjadi
dengan perang dunia kedua dan
berakhirnya perang. Tidak mengoreksi diri,
dengan mudah ingin mengubah isi
perdamaian dengan kekuatan militer yang
baru. Sedangkan J epang seharusnya
memperbaiki sejarah yang telah dibuat
dengan tindakan mempertahankan isi arti
perdamaian tanpa harus mengikuti
tindakan Amerika dengan mengirim
pasukannya ke Irak. Bagi pihak Cina dan
Korea sampai sekarang buku sejarah
yang diajarkan di sekolah masih terjadi
penyimpangan. Itu terjadi karena selama
ini pemerintah menyembunyikan arti dan
kejadian selama perang dan setelah
perang. Pihak J epang juga menutupi
kekejaman selama perang. Isi buku
sejarah J epang yang diajarkan di sekolah
hanya menjelaskan J epang untuk
kemajuan negara memperluas kekuatan
dengan membantu negara sekitar J epang
dengan bantuan. Oleh sebab itu bagi
pihak Korea dan Cina, J epang harus
5
terutama 20% adalah kaum muda J epang
yang masih tidak mengetahui arti perang,
perdamaian dan tidak peduli dengan masalah
politik J epang
memperbaiki buku sejarah J epang. Akan
tetapi sampai sekarang masih belum ada
perubahan. Oleh karena itu para dosen,
pengajar dan pengamat sejarah dari Cina
J epang dan Korea membuat buku sejarah
mengenai sejarah yang terjadi di ketiga
negara untuk memperbaiki hubungan dan
menjelaskan kepada masyarakat di ketiga
negara isi sejarah yang terjadi. Mulai dari
tahun 2001 sampai 2005 para pembuat
buku sejarah baru J epang Cina dan Korea
berkumpul sampai terbentuknya buku
sejarah baru yang berjudul Mirai o hiraku
rekishi (membuka masa depan melalui
sejarah). Buku ini dicetak dalam tiga
bahasa (J epang, Korea, Cina). ditujukan
untuk masyarakat umum dan pelajar.
Akan tetapi buku ini tetap tidak
diperkenalkan oleh departemen
pendidikan J epang ke sekolah. Oleh
sebab itu J epang masih mempunyai
masalah dalam buku sejarah yang harus
diajarkan dan diperkenalkan untuk di
sekolah [3].
J epang terutama politikus telah
melupakan pengalaman para tentara
J epang yang mengalami perang.
Pengalaman pahit mereka dari ikut wajib
militer sampai harus ikut berperang demi
Kaisar dilupakan. Sedikit buku yang
menjelaskan pengalaman mereka selama
perang karena mereka malu apa yang
mereka lakukan di dalam perang dan
pemerintah juga menutupi hal yang terjadi
pada mereka. Terutama apa yang terjadi
di Okinawa saat dikuasai J epang dan
akhirnnya jatuh ke pihak Amerika. Korban
yang jatuh bukan saja para tentara tetapi
rakyat Okinawa. Sehingga bagi orang
Okinawa J epang tidak ikut
mempertahankan dan membela
negaranya. Oleh sebab itu masyarakat
Okinawa sampai sekarang sangat
menentang kependudukan militer Amerika.
Tetapi masalah itu sampai sekarang
masih belum diselesaikan. Bagi orang
Okinawa, Okinawa adalah jajahan J epang.
Masalah yang dihadapi J epang adalah
para kawula muda J epang yang
memahami arti perang, perdamaian dan
korban perang sangat sedikit. Oleh karena
itu tugas para pengajar dan pengamat
sejarah untuk mempertahankan
perdamaian negara dengan kegiatan
perdamaian (seminar mengenai
perdamaian dengan mengenang
85
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
pemboman Hirsoshima dan Nagasaki).
Apakah J epang benar-benar berubah atau
kembali mau ke masa imperalisme?
Daftar Pusaka
[1] Q & A Motto Shiritai Yasukuni J inja,
Rekishi Kyoukasho Kyogikai,
Daitsukishoten,2002,6,24
[2] Owaranai 20 Seiki (Tonan Ajia Seijishi
1894-.),Ishigawa Shouji, Hirai
Kozuomi,Horitsu,Bunkasha HBB,
2004,6,10
[3] Mirai o Hiraku Rekishi, Higashi Ajia 3
Koku No chikaigenzaishi, Kobukei,
2005,6,22
[4]. Asahi Shinbun, 2005, 10, 29
[5]. Asahi Shinbun, 2005, 10, 30
[6] Sekai,Sengo 60 Nen, Tokushu,2003,9)
86
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
Bahasa dan Kognisi
Santi St.Lausia
Fakultas Hukum
Alumnus Kagoshima University
(santist@yahoo.co.jp)
Pada suatu hari, orang (yang besar di)
Kalimantan -sebutlah ia K- dan orang
(yang besar di) J awa sebut ia J - pergi
piknik ke kampung halaman si K. Lalu
tibalah mereka di tempat yang bernama
Gunung Tinggi. Kata K,Lihat J , indah
bukan gunung itu.. Lalu si J
menjawab,Itu sih bukan gunung,
melainkan bukit! . Lalu, K mengadakan
kunjungan balasan ke rumah J di daerah
pegunungan di J awa. Pada waktu makan,
J menawarkan,Mau pakai ikan apa?. K
mencari-cari menu ikan tetapi yang ada
hanya ayam, sapi dan sayur-sayuran.
Ternyata, ikan di J awa dan ikan di
Kalimantan tidak sama. Cerita lain lagi,
ketika Lebaran H-2, Amir dan Budi mudik
naik bis dari J akarta ke kampung halaman
di J awa Tengah. J alanan macet bukan
main. Ketika sampai di suatu kota, Amir
berkata, Syukurlah, tinggal 30 kilo lagi
kita akan sampai di kampung tercinta..
Namun, dengan merengut Budi
menanggapi,Apa? Masih 30 kilo lagi?
Sudah pegal badanku
Mungkin cerita di atas sudah tidak asing
lagi bagi Anda, bahwa ekspresi bahasa itu
salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan
tempat tinggal dan cara pandang. Pada
kasus pertama, bagi orang Kalimantan
yang tinggal di daerah pantai, dataran
yang tinggi dan mendaki mungkin sudah
layak disebut gunung. Akan tetapi, lain
halnya dengan orang J awa yang tinggal di
daerah yang dikelilingi dataran tinggi yang
tingginya bervariasi sehingga ada yang
dinamai gunung, dan ada yang hanya
layak menyandang gelar bukit karena
kurang tinggi. Konsep `bukit` atau
`gunung` yang ada di dalam kepala
mereka diperoleh dari lingkungan mereka
dibesarkan. Demikian juga cerita ikan
yang berarti lauk dalam bahasa J awa
yang tentu saja berbeda dengan konsep
ikan yang ada di kepala orang
Kalimantan.
Pada cerita kedua, mungkin Anda akan
mengatakan itu cerita tentang orang
optimis dan orang pesimis. Namun, tujuan
pemaparan cerita tersebut adalah untuk
menunjukkan `fokus` yang ada dalam
kepala manusia pada saat berbahasa.
Berbeda dengan Amir yang memfokuskan
perhatian pada sisa perjalanan (30 km),
Budi memfokuskan perhatian pada jarak
yang telah mereka tempuh. Fokus ini
berperan dalam pembentukan ungkapan
bahasa, dan setiap budaya mempunyai
fokus atau pandangan yang berbeda
terhadap suatu hal. Dan inilah yang
menyebabkan kejanggalan-kejanggalan
pada saat seseorang mengungkapkan
buah pikirannya dalam bahasa asing.
Contoh di atas adalah salah satu faktor
yang membuat perbedaan antara bahasa
yang satu dengan yang lain. Demikianlah
sekilas tentang kognisi berbahasa, dan
dalam kesempatan kali ini, penulis ingin
berbagi sedikit pengetahuan tentang
ungkapan yang sering salah dalam
bahasa J epang diterjemahkan oleh
penutur bahasa Indonesia.
1.
(Yuube
osoku nemashitakara, kesa
neboushiteshimaimashita.) (Ungkapan
yang salah adalah yang
digarisbawahi.)
Dalam bahasa Indonesia, kita
mengatakan, Kemarin, saya tidur
larut malam, sehingga tadi pagi
bangun kesiangan. Dalam bahasa
J epang, ungkapan tidur larut malam
tidak digunakan, karena fokus
perhatian bukan pada tidur, melainkan
kegiatan dalam kondisi bangun/terjaga.
Oleh karena itu, ungkapan yang
digunakan adalah
(yoru osoku made okiteita
HUMANIORA
87
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
kara), arti harafiahnya karena saya
terjaga sampai larut malam,.
2. Ketika ada tamu orang J epang datang,
ibu Ratna berkata,
(ocha o
tsukurimasune) Tunggu ya. Lalu,
orang J epang tersebut terkejut karena
ia membayangkan bahwa si ibu akan
mulai membersihkan daun teh dan
menjemurnya, lalu mengukusnya
wow betapa lama ia harus menunggu.
Padahal yang dimaksudkan ibu Ratna
adalah membuat teh dalam arti
menyiapkan minuman atau
(ocha o iremasu). Ungkapan
serupa juga berlaku untuk minuman
kopi.
3. Ketika ada telepon berdering, ayah
berkata, Adek, (denwa
o totte)Tolong ya Nak. . Namanya
juga anak-anak, pembelajaran bahasa
mereka lebih cepat karena melalui
proses meniru, sehingga yang
dilakukan oleh si anak, bukanlah
mengangkat telepon, tetapi membawa
telepon kepada ayahnya. Ketika sang
ayah protes setelah selesai
menelepon, sang anak
menjawab,Kalau gitu, bilangnya
(denwa ni deru) Yah. Mungkin
dalam kognisi orang J epang,
menjawab telepon sama seperti
halnya membuka pintu bagi tamu,
sehingga menggunakan kata
(deru =keluar).
4. Setelah itu ibu yang sedang
menyiapkan makan malam minta
tolong,De,
Ini ikannya udah matang.. Ade tidak
membawa piringnya ke dapur tetapi
hanya memegang piring. Ungkapan
yang benar adalah
(mottekitekudasai) yang
secara harafiah berarti =datang dan
bawa kemari.
5. Ada anak SD tiba di sekolah mengadu
kepada gurunya,
(sensei, watashi, sakki ishini
tsumazuite, ochiteshimatte . Sang
guru langsung panik karena sekolah
tersebut ada di atas bukit dan
membayangkan muridnya jatuh dari
bukit. Mengapa demikian? Sebab,
(ochiru) digunakan untuk
menyatakan jatuh dari suatu
ketinggian. Sedangkan untuk
mengungkapkan jatuh
tersandung/terjerembab digunakan
(korobu). J adi, jangan katakan
bahwa
(saifu ga eki de korobimashita) ,
karena dalam hal ini (ochiru)
lebih tepat.
6. Liburan tahun baru sebentar lagi tiba,
lalu sebagai basa-basi Ali bertanya
dengan sopan kepada senseinya
(sensei, yasumi wa doko e iku
tsumoridesuka =sensei, liburan mau
ke mana?). Sang sensei langsung
merah padam mendengar kata
tsumori. Dalam bahasa J epang,
menanyakan keinginan/rencana lawan
bicara menggunakan ungkapan ~tai
ataupun tsumori adalah kurang atau
bahkan tidak sopan terlebih lagi
terhadap orang yang lebih tua atau
yang kedudukannya lebih tinggi,
sebab tsumori mengandung nuansa
desakan. Oleh karena itu, sebagai
gantinya digunakan bentuk ~masu,
misalnya
(sensei, yasumi wa dokoka e
ikimasuka).
7. Setelah itu, Ali ingin mengatakan titip
salam untuk keluarga, maka Ali
menerjemahkannya
(sensei no
kazoku ni yoroshiku onegai shimasu.
Kali ini Sensei -yang telah sadar akan
keterbatasan bahasa J epang si Ali-
tertawa dan membetulkan
(sensei no gokazoku ni yoroshiku to
otsutaekudasai) . Ungkapan yang
hampir serupa, tapi tak sama.
8.
(Sensei, sayounara. Konnichiwa)
Ungkapan di atas seringkali diucapkan
oleh mahasiswa setelah pelajaran
selesai dan hendak meninggalkan
kelas. Dalam bahasa Indonesia,
88
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
salam seperti Selamat
pagi/siang/malam dapat digunakan
baik pada waktu bertemu maupun
berpisah dengan seseorang atau
memutuskan telepon. Namun, dalam
bahasa J epang salam hanya
digunakan pada saat bertemu.
Semoga bermanfaat dan silakan
temukan sendiri perbedaan-
perbedaan lainnya.
89
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
KIAT
Berburu Kerja di Jepang
Fachri Ghozaly
Mahasiswa S2 Tokyo Insitute of Technology
Email: fachri@gmail.com
Musim mencari kerja bagi lulusan baru
universitas di J epang sudah dimulai. Para
mahasiswa mulai mempersiapkan diri agar
proses ini dapat berjalan lancar. Namun,
terutama diantara mahasiswa asing,
banyak juga yang bertanya-tanya tentang
apa yang harus dipersiapkan agar mereka
dapat diterima di tempat yang mereka
inginkan. Tulisan kali ini ditujukan bagi
Anda yang ingin melakukan proses
perburuan kerja di J epang, berdasarkan
pengalaman pribadi penulis.
Di J epang, mahasiswa mulai melakukan
pencarian kerja sebelum lulus kuliah. Oleh
karena itu, kebanyakan dari perusahaan
perekrut tidak menitikberatkan pada tesis
ataupun penelitian yang dilakukan di
universitas, tetapi lebih kepada
kemampuan serta kepribadian seseorang.
Wajar jika seseorang mendapatkan
pekerjaan sesuai dengan pendidikan
ataupun riset yang ia lakukan, namun
banyak juga mahasiswa yang
mendapatkan pekerjaan yang sama sekali
tidak berhubungan dengan jurusan yang
diambil saat kuliah.
Yang terpenting adalah kecocokan antara
para pencari kerja dengan kriteria yang
dicari oleh perusahaan. Namun perlu
diketahui, bahwa dalam proses tersebut,
pihak perusahaan adalah pihak pembeli,
yang memiliki posisi lebih tinggi dari pihak
pelamar. Mereka memiliki hak untuk
menyeleksi apakah mereka akan
membeli para pelamar atau tidak.
Lalu, bagaimana perusahaan dapat
melihat apakah kandidat pekerjanya
sesuai dengan yang diinginkan atau tidak?
Secara umum ada dua cara, tergantung
dari jalur perekrutan yang diambil oleh
para pelamar. Apakah melalui jiyu oubo
(jalur umum) atau suisen (jalur
rekomendasi).
Bila melewati jalur rekomendasi, para
pelamar diharuskan membawa surat
rekomendasi baik dari profesornya
ataupun dari universitas tempat ia belajar.
Dengan menerima lamaran melalui jalur
ini, perusahaan menempatkan
kepercayaan mereka pada proses
pendidikan yang diterima pelamar. Lalu
untuk memastikan apakah mereka sesuai
dengan budaya perusahaan atau tidak,
diadakan proses seleksi tambahan berupa
wawancara, dan kadang-kadang juga tes
tambahan.
Di J epang, di masa lalu karena
perekonomian yang baik dan terus
berkembang, kemungkinan pelamar
diterima melalui jalur ini cukup besar.
Namun sekarang, seiring dengan
memburuknya perekonomian,
kemungkinan diterimanya pelamar melalui
jalur rekomendasi menjadi semakin
menurun.
Bila melalui jalur umum, para pelamar
tidak mempunyai pilihan lain selain
mengikuti proses seleksi yang diadakan
oleh perusahaan. Proses tersebut
mencakup seleksi melalui lamaran (entry
sheet), tes tertulis, diskusi & kerja
kelompok (group works), debat, presentasi,
maupun wawancara kelompok dan
wawancara pribadi.
Untuk menghadapi segala seleksi tersebut,
tentunya persiapan yang matang
diperlukan. Pencarian data tentang
perusahaan yang Anda inginkan, tes, dan
juga tentunya persiapan untuk lebih
mengenali diri sendiri sangat diperlukan.
Dunia
90
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Penulis akan mencoba mengupas tentang
persiapan-persiapan untuk menghadapi
beberapa tahap dalam proses mencari
kerja.
1. Tahap Pengenalan Diri
Tidak bisa disangkal bahwa tahap
pertama, dan tahap paling penting dalam
proses pencarian pekerjaan adalah tahap
pengenalan diri sendiri. Dengan
mengetahui kelebihan, kelemahan, serta
potensi diri, kita dapat dengan lebih
leluasa menyusun rencana karir ke depan,
termasuk dalam hal memilih perusahaan
dan jenis pekerjaan yang kita inginkan.
Lebih dari itu, persiapan di tahap ini akan
membuat persiapan untuk tahap lain
menjadi jauh lebih mudah, dan membuat
proses pencarian kerja secara
keseluruhan menjadi lebih lancar.
Misalnya, Anda bisa memulai dengan
menyusun daftar data-data diri. Dengan
adanya daftar itu sendiri, Anda bisa sangat
terbantu dalam mengetahui diri Anda.
Tetapi tentunya bukan hanya untuk tujuan
tersebut daftar semacam itu harus dibuat.
Tujuan terpenting adalah untuk mengatur
strategi bagaimana Anda dapat
merepresentasikan diri dengan lebih baik
kepada perusahaan yang Anda minati.
Data-data yang harus ada dalam daftar
mencakup mulai dari minat & hobi,
keahlian, pengalaman, visi dan misi
pribadi, kelebihan- kelebihan, dan
tentunya hal-hal yang patut diperbaiki alias
kelemahan-kelemahan diri. Bukan hanya
itu, Anda harus juga tahu, mengapa Anda
memiliki sifat-sifat seperti itu. Mengapa
Anda memiliki minat, misalnya hobi
membaca buku dan bukannya pergi ke
luar rumah atau outdoor activities. Atau,
mengapa Anda memilih suatu tema riset
yang populer. Apakah Anda memang
berminat pada tema itu, atau Anda adalah
orang yang efektif dan tidak mau mencari
kesulitan yang tidak perlu, sebab profesor
Anda menyarankan tema itu dan banyak
sumber literatur telah tersedia.
Dengan kata lain, dari daftar data-data
pribadi Anda, cobalah bentuk suatu
kesatuan yang sering disebut sebagai
karakter diri. Dengan mampunyai
bayangan tentang karakter diri, Anda akan
mampu mengetahui alasan-alasan tentang
tindakan yang pernah diambil. Dan Anda
akan mampu dengan mudah menjelaskan
hal-hal tersebut misalnya dalam proses
wawancara di masa depan.
Salah satu ukuran yang sering digunakan
dalam mengetahui karakter seseorang
adalah indikator tipe Myers-Briggs (Myers-
Briggs Type Indicator/ MBTI). Indikator ini
memiliki 4 macam parameter: Extraversion
/ Introversion, Sensate / iNtuitive, Thinking
/ Feeling, dan J udging / Perceiving.
Misalnya, Anda memiliki karakter
(E)xtraverted i(N)tuitive (T)hinking
(J )udging, ENTJ . Orang dengan karakter
ENTJ sering disebut sebagai the
executive. Anda memiliki kelebihan
sebagai seorang pemimpin yang mampu
berfokus pada suatu masalah dan mencari
penyelesaiannya. Anda memiliki rasa
percaya diri yang besar, serta memiliki
kemampuan verbal yang baik untuk
mengkomunikasikan pendapat Anda.
Namun Anda juga memiliki kelemahan
kurang mampu mentoleransi kekurangan
orang lain, sehingga kadang-kadang
dijauhi oleh teman Anda sendiri. Poin
inilah yang harus Anda perbaiki dalam
menyempurnakan karakter Anda.
Lebih jauh lagi, dapat disimpulkan bahwa
seorang ENTJ sangat cocok untuk
menjadi pemimpin atau pengurus
organisasi. Karena itulah, Anda dapat
merepresentasikan diri Anda sebagai
seseorang yang berpotensi menjadi
pemimpin di perusahaan manapun.
Dalam tahap-tahap berikutnya, misalnya
pada saat tes psikologi maupun
wawancara, pengetahuan seperti ini akan
sangat membantu baik dalam menjawab
pertanyaan maupun dalam menjelaskan
diri Anda kepada orang lain.
Tujuan proses mencari kerja adalah
meyakinkan pihak perusahaan untuk
mencapai kesimpulan bahwa Anda adalah
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
91
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
orang yang mereka cari. Untuk itu, perlu
juga diselidiki data-data perusahaan serta
jenis pekerjaan yang Anda cari untuk
membuat suatu argumen yang kuat dalam
meyakinkan pihak perusahaan. Biasanya,
data-data tersebut tersedia di homepage
tiap perusahaan yang dimaksud. J uga,
pada umumnya perusahaan-perusahaan
mengadakan seminar penjelasan tentang
kegiatan mereka. Ini adalah kesempatan
yang baik untuk memperoleh informasi
yang Anda butuhkan.
Penjelasan tentang MBTI dapat dilihat
misalnya di http://bsm.securesites.com/,
sedangkan tes online untuk mengetahui
career personality Anda dapat dilakukan
gratis di http://web.tickle.com/, di dalam
kategori Career. Terdapat juga tes untuk
mengetahui bakat kepemimpinan Anda.
2. Penyerahan Lamaran
Di J epang, hampir semua perusahaan
sudah mengadopsi sistem lamaran online.
Lamaran pekerjaan semacam itu disebut
sebagai entry sheet. Umumnya kita
mengisi data kita dalam kolom-kolom yang
telah disediakan. Selain data-data pribadi
seperti tanggal lahir, pendidikan, atau
pengalaman kerja, ada juga kolom-kolom
pertanyaan karangan, seperti misalnya:
apa motivasi Anda dalam memilih
perusahaan kami, atau mengapa Anda
memilih jenis pekerjaan ini, dan
sebagainya. Biasanya panjang maksimal
karangan sudah ditentukan. Walaupun
tidak ada kewajiban untuk mengisi penuh
kolom karangan, menulis terlalu sedikit
pun akan memberi kesan yang buruk pada
perusahaan.
Salah satu poin terpenting dalam menulis
karangan pada kolom semacam itu adalah
dengan memberikan jawaban yang jelas
dan lojik. Biasakan menulis kesimpulan
terlebih dahulu, setelah itu baru menulis
alasannya. Misalnya Anda diminta untuk
menuliskan appeal pribadi. J ika Anda
telah melakukan persiapan di tahap
sebelumnya denga baik, ini adalah
kesempatan untuk menjual diri dengan
baik. Anda bisa menulis bahwa Anda
adalah seorang pemimpin. Lalu
selanjutnya Anda bisa paparkan mengapa
kesimpulannya seperti itu dengan menulis
kelebihan-kelebihan dan pengalaman
Anda.
Ada perusahaan yang mengharuskan
Anda mengisi entry sheet langsung
melalui homepage mereka. Namun pada
umumnya, entry dapat dilakukan di
beberapa web site khusus untuk para
pencari kerja. Diantara yang populer
adalah situs rikunabi,
http://www.rikunabi.com/. Situs itu disebut-
sebut sebagai situs recruitment terlengkap
di seluruh J epang, dengan informasi-
informasi yang cukup detail mengenai
hampir semua perusahaan dimuat
didalamnya. Pengguna situs ini, setelah
mendaftar sebagai anggota, dapat
mencari data perusahaan yang mereka
inginkan. Dan jika perusahaan tersebut
membuka lowongan, maka pengguna
dapat dengan mudah mengirimkan
lamaran secara online. Sayangnya situs
ini hanya menyediakan tampilan dalam
Bahasa J epang. Ada situs lainnya yang
menyediakan informasi dalam Bahasa
Inggris juga, dan dapat diakses di
http://www.careerforum.net/. Selain itu,
dengan mengikuti seminar-seminar
penjelasan perusahaan, Anda dapat
memperoleh informasi tentang bagaimana
menyerahkan lamaran.
3. Tes dan Wawancara
J ika surat lamaran Anda dianggap
memenuhi syarat, maka tahap selanjutnya
yang harus Anda hadapi adalah seleksi
berupa tes dan wawancara. Tidak ada
ketentuan pasti tentang berapa kali
wawancara atau tes yang harus diambil.
Namun pada umumnya, seleksi tahap ini
terbagi menjadi 3 bagian, apakah berupa
wawancara seluruhnya, atau tes tertulis
dan wawancara.
Biasanya tes tertulis yang harus dilakukan
adalah tes jenis SPI (Synthetic Personality
Inventory). Tes ini menggabungkan
penilaian kemampuan dasar Anda dalam
berbahasa dan perhitungan matematik,
dan juga psikotes untuk mengetahui
karakter Anda. J ika Anda sudah mengerti
karakter Anda dengan baik, tidak ada
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
92
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
kesulitan dalam mengikuti psikotes.
Namun, seperti layaknya tes masuk
universitas di Indonesia, diperlukan
persiapan yang matang dalam
menghadapi tes menghitung. Soal yang
keluar tidak begitu sulit, tapi diperlukan
kecepatan untuk dapat menyelesaikan
sebagian besar atau seluruh soal.
Persiapan untuk tes SPI dapat dilakukan
dengan membeli buku-buku SPI dan
berlatih untuk menjawab soal dengan
cepat. Agar anda dapat berfokus untuk
menyiapkan wawancara dengan baik,
sangat dianjurkan untuk mulai berlatih
jauh-jauh hari. Bahkan kalau bisa, latihan
sudah dimulai dari sekarang.
Dalam seleksi wawancara, penguji akan
memberikan pertanyaan dan kita
diharapkan mampu menjawabnya dengan
baik dan jujur. Perlu ditekankan bahwa
kita tidak harus mengungkapkan seluruh
diri kita kepada mereka. Pewawancara
hanya ingin tahu apakah kita bisa
diandalkan dalam bekerja, bisa dipercaya,
mampu berpikir logis, dan mampu
menyesuaikan diri dengan kultur
perusahaan. J ika Anda ditanya dengan
pertanyaan abstrak, maka coba menjawab
dengan contoh riil. Begitu juga bila Anda
ditanya tentang pengalaman spesifik,
setelah menjawabnya, coba tarik
kesimpulan dari pengalaman Anda yang
menunjukkan bahwa Anda adalah orang
yang dapat diandalkan.
Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara
dengan perusahaan-perusahaan J epang
biasanya dimulai dengan pertanyaan
generik. Misalnya mengapa Anda tertarik
dengan perusahaan kami, atau mengapa
Anda memilih jenis pekerjaan ini, dan
sebagainya. Biasanya dalam tahap
pertama wawancara, beberapa orang
pelamar dipanggil sekaligus dalam satu
sesi. Kemudian para pelamar akan ditanya
secara bergantian. Bantu para
pewawancara dalam mencapai
kesimpulan dengan menggunakan
jawaban yang mencerminkan bahwa Anda
mengetahui diri Anda dengan baik, dan
Anda yakin bahwa Anda cocok dengan
perusahaan pewawancara. Coba untuk
selalu jujur dan menggunakan contoh-
contoh riil. Dan banyak lagi tips-tips yang
berguna dalam buku-buku tentang
wawancara yang banyak dijual saat ini,
seperti tentang mengapa memakai jam
tangan adalah penting dan sebagainya.
Semakin jauh tahap wawancara, maka
kemungkinan besar semakin tinggi jabatan
orang-orang yang mewawancarai Anda.
Mereka mungkin tidak begitu peduli
dengan kemampuan yang Anda miliki
sekarang, tetapi lebih menekankan
penilaian kepada karakter Anda. Penulis
yakin jika Anda sudah memahami diri
Anda dengan baik, maka proses
wawancara ini tidak akan menjadi proses
yang menakutkan, sebaliknya malah
menyenangkan.
Untuk berlatih dalam menyampaikan
jawaban dengan lancar, latihan
wawancara dengan teman dapat sangat
membantu. Dan coba selalu menyiapkan
jawaban sebelum wawancara bagi
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
keluar. Dengan persiapan seperti itu, Anda
bisa menilai apakah jawaban Anda nanti
cukup baik atau perlu diperbaiki lagi.
Perlu diingat, bila Anda tidak lulus dalam
proses wawancara, maka itu bukanlah
kesalahan Anda pribadi. Kemungkinan
besar hal itu disebabkan karena
pewawancara menganggap Anda tidak
cocok dengan perusahaannya. Hal itu
justru lebih baik jika dibandingkan bila
Anda diterima tapi malah kemudian anda
sadar kalau Anda tidak cocok. Percayalah,
jika Anda jujur dalam wawancara, maka
hasil yang Anda dapatkan merupakan
hasil yang baik untuk Anda.
4. Tahap Penerimaan
J ika anda telah menyelesaikan seluruh
proses dengan lancar, maka perusahaan
akan menghubungi anda baik melalui
telepon atau email bahwa Anda layak
menjadi anggota perusahaan mereka.
Umumnya di J epang, para pelamar
diterima di lebih dari satu perusahaan.
Mereka kemudian akan menentukan
perusahaan mana yang akan mereka
masuki. Biasanya pihak perusahaan akan
memberikan waktu beberapa hari/minggu
untuk memutuskan. Pikirkan dengan
masak. Tanya pendapat senior-senior
atau teman-teman Anda, dan putuskan
sesuai dengan visi Anda. Apakah Anda
mencari perusahaan dengan lingkungan
yang enak, atau jenis pekerjaan yang
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
93
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Anda inginkan adalah seperti ini, dan
sebagainya. Begitu Anda memutuskan,
maka pihak perusahaan akan meminta
Anda untuk menghentikan proses
pencarian kerja di perusahaan-
perusahaan lain. Walaupun begitu, Anda
belum terikat sampai Anda
menandatangani kontrak perjanjian, yang
biasanya diambil 6 bulan sebelum masuk
perusahaan itu.
5. Penutup
Sekian kiat tentang pencarian kerja di
J epang yang bisa penulis sampaikan kali
ini. Pesan terakhir dari penulis adalah,
berusahalah untuk jujur baik kepada diri
sendiri maupun kepada pihak perusahaan.
Dan juga selalu ingat agar melakukan
persiapan sematang mungkin sebelum
proses seleksi.
Be yourself, but BE prepared.
Selamat berjuang!
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
94
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
KIAT
Survive Dengan Arubaito
Bobsy Arief Kurniawan
Master Student (Human Information Engineering, Toyama Univeristy)
Email : bobsyfish@yahoo.com
Menjadi mahasiswa di J epang sudah
menjadi impian saya sejak dahulu.
Dengan bermodalkan nekat dan tekad
akhirnya saya berhasil menginjakkan kaki
di Toyama Prefecture ini.
Awal kedatangan saya di J epang bermula
dari keinginan untuk melanjutkan studi S-2.
Meskipun dengan kondisi ekonomi yang
terbilang pas-pasan, bukan berarti
menghalangi saya untuk nekat belajar di
Negeri Sakura ini. Pada awalnya, saya
termotivasi untuk datang di J epang berkat
mahasiswamahasiswa RRC yang datang
dengan uang pas-pasan. Saya berpikir,
mengapa mereka bisa bertahan dengan
uang yang sedikit, padahal toh kita sama-
sama makan nasi ? Oleh karena itu, saya
pun seharusnya pasti bisa !
Akhirnya saya pun memutuskan untuk
meninggalkan tanah air dan datang di
J epang dengan menggunakan visa turis.
Dengan dibantu oleh seorang kenalan
yang berada di J epang, meskipun selama
ini kami belum pernah bertatap muka,
akhirnya saya dapat tiba di Toyama
Prefecture. Dengan hanya bermodalkan
ijazah S-1 dan Bahasa J epang yang pas-
pasan, saya nekat mencari seorang
profesor pembimbing. Akhirnya saya
berhasil juga menemukan profesor yang
mau menerima saya dengan kondisi yang
hanya bermodalkan uang pas-pasan dan
visa turis.
Setelah mendapat profesor, saya
mengubah visa turis dengan visa research
student untuk 1 tahun. Dan di sinilah
menjadi awal perjuangan hidup saya di
J epang. Pada awalnya memang tidak
mudah untuk mencari pekerjaan paruh
waktu (arubaito) karena kendala Bahasa
J epang saya yang terbilang minim. Tapi
karena bantuan seorang teman, saya
akhirnya diperkenalkan kepada agen
perusahan yang menyalurkan arubaito di
pabrik makanan pada sabtu dan malam
hari. Dan yang lebih menguntungkan lagi,
perhitungan gaji diberikan tiap minggu.
Dikarenakan uang yang sudah menipis
dan tidak lagi mendapat kiriman dari orang
tua, ini merupakan suatu keberuntungan
yang sangat besar bagi saya. J adinya
saya dapat bertahan hidup dengan gaji
mingguan. Karena apa yang saya peroleh
hanya mampu untuk membayar sewa
apartemen dan makan saja, akhirnya saya
mulai dipusingkan dengan biaya kuliah
yang nilainya cukup besar.
Dengan bekerja di pabrik tersebut, saya
mendapat banyak teman baik itu orang
Cina maupun Malaysia. Dan waktu itu,
Orang Indonesia hanya dua orang yang
bekerja di sana. Karena banyak
memperoleh teman, saya mulai bertanya
bagaimana cara mendapatkan pekerjaan
yang tidak mengganggu waktu belajar ?
Dan akhirnya seorang teman Malaysia
memperkenalkan saya kepada seorang
agen koran. Kemudian, saya bekerja
sebagai loper koran setiap pagi dari jam 4
sampai sekitar jam 7. Karena bekerja di
dua pekerjaan sekaligus, yaitu pagi hari
sebagai loper koran dan malam hari di
pabrik makanan, gaji yang saya peroleh
mulai bisa ditabung Dan selama ini,
pekerjaan saya tidak mengganggu jadwal
kuliah, sehingga profesor pun tidak
mempermasalahkannya.
Satu tahun kemudian, saya lulus ujian
masuk S-2 dan masalah barupun datang,
terutama masalah uang pangkal dan biaya
kuliah yang berkisar hampir 600.000 Yen.
Saya pun mulai bingung bagaimana dapat
membayar uang sebesar itu ? Akhirnya
saya mencari pekerjaan tambahan dan
mendapatkan pekerjaan sebagai tukang
cuci piring dan membantu koki di salah
satu restoran Prancis. Karena saya
memohon untuk diberikan pekerjaan yang
gajinya lebih besar, akhirnya agen yang
mempekerjakan saya selama ini di pabrik
makanan, memperkenalkan saya kepada
perusahaan di pabrik rekanan Sony yang
memproduksi Memory Stick Duo Adapter
Dunia
95
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
sebagai operator mesin. J adi total arubaito
yang saya lakukan saat itu ada 3, yaitu di
restoran pada hari sabtu dan minggu,
loper Koran setiap pagi dan tiap malam di
pabrik elektronik. Dari hasil jerih payah ini,
selama 3 bulan saya berhasil mebayar
semua uang pangkal dan biaya kuliah.
Meskipun dalam 1 hari waktu tidur hanya
sekitar 3 jam, tetapi hasil yang saya
dapatkan sangat menggembirakan. Selain
itu, saya yang dahulu gemuk dalam 3
bulan berat badan pun turun sekitar 12 kg
tanpa harus bersusah payah untuk diet.
Dukanya dalam menjadi loper koran
adalah saat musim dingin. Toyama
Prefecture adalah salah satu kota yang
apabila musim dingin saljunya menumpuk.
Pernah suatu ketika saya mengantar
koran dari jam 4 sampai jam 12 siang
dikarenakan salju yang parah. Salju di
beberapa tempat sampai 1 meter lebih
tingginya. J adi, motor saya tinggal di jalan
yang tidak bersalju dan berjalan kaki
membelah salju yang susah untuk dilalui
meskipun dengan jalan kaki. Terlebih lagi,
dinginnya cuaca yang mencapai -5 ,
Tangan terasa sakit dan hampir tidak
dapat merasakan apa-apa karena terasa
beku meskipun sudah memakai sarung
tangan yang tebal dan terbuat dari kulit.
Waktu berlalu hampir 3 tahun, dan
sekarang saya sudah hampir lulus S-2,
selama ini saya hanya hidup dengan
penghasilan dari arubaito tanpa mendapat
beasiswa dan kiriman uang dari orang tua.
Kuliah pun selama ini tidak terganggu
meskipun badan ini terasa penat, karena
setiap hari beraktifitas dan tidak ada hari
libur bagi saya.
Berkat arubaitopun, saya dapat
mengirimkan uang untuk berobat ayah
yang sedang sakit dan juga dapat
menabung untuk pengeluaran tak terduga.
Perjuangan hidup di J epang memang
berat, tetapi saya merasa itu bukan
menjadi penghalang untuk kita semua.
Karena di mana ada kemauan dan tekad,
pasti kita akan mendapatkan hasil yang
baik.
Tahun depan saya akan melanjutkan
program S-3 di fakultas dan kampus yang
sama. Saya hanya bisa berdoa semoga
kali ini saya diberikan kemudahan dan
beasiswa, karena untuk bekerja seperti
dahulu sepertinya tidak mungkin karena
kesibukan yang ada.nanti.
Terakhir kali, apabila ada rekan-rekan
atau kerabat yang ingin menuntut ilmu di
J epang seperti saya ini, dapat
menghubungi saya via email yang tertera
di atas. Dan buat rekan-rekan senasib dan
sepenanggungan yang hidup tanpa
beasiswa dan kiriman dari orang tua, mari
kita GAMBARIMASHOU (berusaha) !
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
96
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
FORUM
Keluar dari Krisis
(Catatan Hasil Diskusi Kerjasama PPI-Komisariat Kyoto, PPI-Korda
Kansai, PPI-Japan, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia,
Osaka, JAPAN)
http://www.ppikansai.org/bincangsantai.html
Kontak Person:
Haris Syahbuddin
1)
, Arie Damayanti
2)
, Wahyu Prasetyawan
3)
,
Yuli Setyo Indartono
4)
, Sorja Koesuma
5)
, Jangkung Handoyo Mulyo
6)
,
1)
Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi, Bogor; Graduate School of Science and
Technology, Kobe University,
2)
LPEM-Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia; Kyoto
University,
3)
Peneliti di Harian Bisnis Indonesia; Center for South East Asia Study, Kyoto
University,
4)
Peneliti Grant RUTI Laboratorium Termodinamika, Institut Teknologi
Bandung; Graduate School of Science and Technology, Kobe University,
5)
J urusan Fisika,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta; Department of Geophysics, Kyoto University,
6)
Fakultas Pertanian, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; Economic Development and
Policies Department, Graduate School of International Cooperation Studies, Kobe
University
Email:
harissyahbuddin@yahoo.com, ariedamayanti@yahoo.com, wahyu@asafas.kyoto-
u.ac.jp, indartono@yahoo.com, koesuma@gmail.com, jhandoyom@yahoo.com
1. Pendahuluan
Krisis ekonomi yang berlanjut dengan
krisis politik hingga krisis multidimensi
sejak 1997 tidak kunjung tertangani hingga
kini. Sementara bangsa lain yang juga
mengalami krisis ekonomi ditahun yang
sama, telah mulai bersiap meyongsong
masa depan yang lebih terukur dan penuh
harapan. Belum usai berbagai masalah
tersebut diselesaikan, soal lain telah
menghadang: krisis energi, keamanan
nasional terkait dengan gelombang
terorisme, konflik antara golongan dan
agama diberbagai daerah, angka
kemiskinan yang terus meningkat seiring
dengan kenaikan BBM, jumlah
pengangguran yang kian besar, kasus
pencurian minyak, narkoba, sengketa
perbatasan dengan Malaysia, busung
lapar, endemik flu burung dan demam
berdarah dengu (BDB), dan lain-lain.
Begitu banyak persoalan bangsa yang
menuntut penyelesaian cepat, guna
memenuhi rasa keadilan dan mencukupi
kebutuhan setiap individu, golongan, dan
kelompok. Kondisi ini mewariskan quo
vadis yang tidak mudah dipecahkan bagi
pemerintah sebagai lembaga pelaksana
jalannya kehidupan berbangsa dan
bernegara.
Keadaan tersebut kian berat jika
dihadapkan pada isu persaingan global
dan perdagangan bebas yang harus
sudah diwujudkan pada tahun 2010.
Negara-negara Asean lainnya, terlebih
Eropa, J epang, China, dan Amerika
nampak lebih siap menghadapi AFTA
2010 nanti. Seluruh masyarakat menaruh
harapan agar multi krisis tersebut dapat
diatasi dengan cepat, memenuhi rasa
keadilan, dan tetap menjaga akurasi solusi.
Dibawah kepemimpinan SBY dan J K,
beberapa keberhasilan sesungguhnya
sudah mulai terlihat, setidaknya seperti
yang dilontarkan oleh para menteri
Kabinet Indonesia Bersatu antara lain:
perdamaian di Aceh, pertumbuhan PDB
(Produk Domestik Bruto) yang diprediksi
akan mencapai 5%, Pilkada, terungkapnya
kasus-kasus korupsi besar, penertiban
perjudian, peningkatan proporsi anggaran
pendidikan, RUU Pendidikan dengan
alokasi gaji guru/dosen yang kian besar,
terbunuh dan terkuaknya jaringan teroris
Dr. Azahari, dan lain-lain. Sebagian
Dunia
97
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
masyarakat atau partai politik masih
menganggap keberhasilan tersebut hanya
sebagai lips service atau eforia politik
untuk melanggengkan kekuasaan. Di sisi
lain, kenaikan tunjangan anggota DPR
serta anggaran kepresidenan dan
kementerian juga memicu kekecewaan
berbagai kalangan mengingat kondisi
bangsa dan negara yang sedang prihatin
akibat kenaikan BBM yang cukup tinggi.
Dampak pembangunan bagi kemakmuran
masyarakat belum dirasakan merata di
seluruh wilayah Indonesia. Cita cita
menuju masyarakat yang adil dan beradab
serta berkeadilan sosial bagi seluruh
rakyat masih jauh dari harapan. Untuk
mewujudkan cita-cita tersebut, selain
keahlian mengelola, kepercayaan, dan
mandat yang kuat dari seluruh
masyarakat pada pemerintah, juga
dibutuhkan kerjasama semua lini, keahlian,
dan kesadaran kolektif bahwa kita harus
bekerjasama mengatasi dan segera
keluar dari krisis untuk menyongsong
masa depan yang lebih baik.
Menyadari hal tersebut, PPI-Komisariat
Kyoto bekerjasama dengan PPI-Korda
Kansai, PPI-J epang dan KJ RI
mengadakan acara Bincang Santai
Ekonomi dan Politik 2005 dengan
seorang nara sumber bidang ekonomi,
Prof. Dibyo Prabowo, dan pakar bidang
politik dan demokrasi, Mochtar Pabottingi,
PhD. Prof. Dibyo Prabowo adalah seorang
Guru Besar FE UGM Agricultural and
Natural Resource Economics, the ASEAN
Economy. Direktur Pusat Studi Asia
Pasifik (Center of Asia Pacific Studies)
UGM, yang pada semester ke 2 tahun ini
sedang memberikan Special Lecture on
Development Economics: Economic
Development and Foreign Direct
Investment in ASEAN di Kobe University.
Beliau juga pernah menjabat sebagai staf
ahli Menteri Pertanian, Ir. Affandi. Mochtar
Pabottingi, Ph.D., adalah peneliti senior
pada Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), visiting professor dari
University of Wisconsin at Madison
(mengajar: Democratization in Indonesia:
Predicaments and Possibilities, 2001).
Menyelesai-
kan Pendidikan di Departemen Bahasa
Inggris UGM, Department of Sociology
University of Massachusets at Amherst,
dan Political Science Department of
Hawaii University at Manoa, USA. Sering
diundang untuk memberi kuliah tentang
Demokrasi dan Politik di berbagai
Universitas dan lembaga pemerintahan,
seperti LEMHANAS.
Acara tersebut diselenggarakan pada
tanggal 13 November 2005 di Kyoto
International Community House (Kyoto
Kokkusai Koryu Kaikan). Dari lokasi,
dimana isu global warming dengan Kyoto
Protocol nya dilahirkan, diharapkan dapat
ditelurkan sebuah "rekomendasi kecil"
untuk kemudian diteruskan ke berbagai
pihak yang berkepentingan, baik internal
PPI maupun pada pemerintah dan instansi
terkait lainnya agar memberi manfaat lebih
luas. Dialog dilakukan dalam suasana
penuh kekeluargaan dibarengi dengan
acara Halal bil Halal Korda Kansai. Acara
tersebut tidak dimaksudkan untuk
membahas secara detail teknis hingga
dilahirkannya strategis operasional untuk
keluar dari krisis, tapi lebih difokuskan
pada memahami persoalan bangsa dan
pemberian wawasan baik peserta yang
hadir (pelajar dan staf KJ RI), serta solusi
konseptual bagi dua isu cikal krisis yaitu
ekonomi dan politik. Untuk selanjutnya
pemahaman dan konsep tersebut dapat
disebarluaskan oleh rekan-rekan pelajar
sebagai agen perubahan dan
ditindaklanjuti oleh lembaga legislatif,
eksekutif, dan yudikatif sebagai pemegang
mandat untuk merancang kebijakan.
Dialog yang dihadiri oleh sekitar 125
pelajar se Kansai dan dibuka oleh Konsul
Bidang Pendidikan dan Budaya KJ RI,
Patriot Adinarto, didahului oleh pemaparan
singkat oleh kedua nara sumber secara
berurutan, dimulai dari Prof. Dibyo
Prabowo dan dilanjutkan oleh Mochtar
Pabottingi. Pada sesi berikutnya diisi
dengan tanya jawab antara peserta
dengan kedua pakar.
2. Persoalan Krusial Ekonomi
Prof. Dibyo Prabowo memulai
pembicaraannya dengan menyatakan
bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang
kritis tidak cukup terlihat dari besaran
ekonomi makro seperti pertumbuhan PDB
Dunia
98
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
(Produk Domestik Bruto), inflasi, dan nilai
tukar. Kita harus melihat kondisi ekonomi
Indonesia sesungguhnya berdasarkan
angka kemiskinan, pengangguran, dan
kesenjangan pendapatan. Berbicara
mengenai ekonomi Indonesia tidak cukup
tanpa memperhatikan ketiga hal tersebut.
Kemiskinan di Indonesia sangat tinggi.
Dimana dengan garis kemiskinan 1 dollar
per hari saja terdapat lebih dari 37 juta
penduduk miskin. Padahal garis batas
kemiskinan sebesar itu, sudah tidak
memadai lagi untuk digunakan sebagai
parameter, dan bahkan sudah tidak
digunakan oleh negara-negara ASEAN
sekalipun. Ada sekitar 40 juta penduduk
Indonesia menganggur; dan perbedaan
pendapatan antara yang kaya dan miskin
sangat besar.
Berdasarkan kondisi ekonomi di atas, Prof.
Dibyo Prabowo menyoroti kebijakan
pengurangan subsidi BBM. Menurutnya
subsidi BBM memang perlu dihapus demi
proses ekonomi yang lebih rasional. Prof.
Dibyo menekankan bahwa ekonomi yang
terbaik adalah tanpa subsidi. Harga tanpa
subsidi (harga pasar) mencerminkan
harga yang sebenarnya dan biaya
produksi perlu dihitung dengan harga yang
sebenarnya tersebut.
1
Oleh karena itu
tidak ada satupun negara di dunia, selain
Indonesia, yang memberikan subsidi pada
harga BBM. Kekeliruan yang dibuat
pemerintah dalam pengurangan subsidi
tersebut terletak pada besarnya kenaikan
harga BBM yang ditetapkan melalui
kebijakan tersebut.
2
Pemerintah dinilai
tidak atau belum benar-benar
memperhatikan kondisi sebagian besar
masyarakat seperti pendapatan rendah,
kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi,
dan distribusi pendapatan sangat timpang.
Beliau menegaskan bahwa, walaupun
1
Dalam ekonomi, biaya produksi perlu dihitung
dengan harga yang sebenarnya untuk melihat
biaya input riil (tanpa hidden cost). Dengan
demikian dapat diketahui apakah suatu produk
benar-benar kompetitif atau tidak. Produk yang
harganya murah karena ada subsidi, belum tentu
kompetitif
2
Dalam sidang Kabinet berkembang dua wacana
untuk menghapus subsidi sekaligus atau bertahap.
Bappenas mengusulkan peningkatan bertahap
sementara peserta sidang kabinet yang lain
mengusulkan peningkatan sekaligus. Opsi kedua
inilah akhirnya yang disepakati untuk dilaksanakan.
subsidi BBM tidak baik, penghapusannya
perlu dilakukan bertahap (sebaiknya
dalam tiga tahap).
3. Persoalan Politik dan Kebangsaan
Mochtar Pabottingi, Ph.D. mengungkap-
kan harapan dan impiannya tentang
Indonesia, agar suatu saat kelak akan lahir
orang-orang benar dan menjadi garda
depan bangsa; impian akan suatu masa di
mana penguasa legislatif maupun
eksekutif tidak lagi bersekongkol
merampok negeri; tentang alam Indonesia
yang senantiasa hijau; tentang pendidikan
yang kian meningkat dan generasi muda
yang unggul, berbudi pekerti, dan
berpengetahuan.
Peneliti senior LIPI ini juga mengingatkan
pentingnya memahami makna pada
Indonesia, memiliki kesadaran akan
nation, dan memahami demokrasi.
Berkaitan dengan makna Indonesia,
beliau menduga mungkin hanya sedikit
dari hadirin yang pernah membaca buku
yang ditulis oleh Bung Hatta berjudul
Indonesia Merdeka atau Indonesia
Menggugat karya Bung Karno. Padahal,
menurutnya kedua buku karya pendiri
bangsa tersebut sangat penting karena
memuat testamen politik yang menjadi
dasar negara Indonesia. Berkaitan dengan
nation, Mochtar Pabottingi menyatakan
bahwa maknanya bukan sekedar
bangsa,
3
karena nation lebih dibentuk
oleh pengalaman sejarah yang panjang,
penderitaan yang sama, perasaan senasib
dan sepenanggungan, dan cita-cita politik
yang sama.
4
Demokrasi yang memiliki
arti sama dengan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat, dipandang mempunyai
kaitan yang sangat erat dengan nation.
Menurut beliau, pemahaman atas makna
Indonesia, nation, dan demokrasi belum
banyak terlihat pada penyelenggaraan
hidup bernegara. Masih banyak peraturan
yang tidak menguntungkan bangsa; tidak
3
Nation didefinisikan sebagai kolektivisme politik
dan berbeda dengan bangsa yang lebih
merupakan kolektivisme sosiologis.
4
J epang merupakan salah satu contoh negara yang
memiliki kesadaran tentang nation, contoh
negara yang mulia, negara menyantuni bangsanya
sendiri.
Dunia
99
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
menampilkan bangsa yang mulia; tidak
mencerminkan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Tidak ada rasionalitas
politik (saling imbang, saling kontrol)
dalam penyelenggaraan hidup bernegara.
J ika dulu didominasi oleh kekuasaan
eksekutif, sekarang diwarnai oleh
dominasi kekuasaan legislatif.
5
Rasionalitas politik masih jauh dari
kenyataan di Indonesia. Walaupun sudah
ada pemilihan umum yang berdasarkan
proporsi dan distrik untuk lembaga
legislatif, namun di bawah itu masih
diberlakukan sistem nomor urut untuk
menetapkan utusan partai dalam legislatif.
Mochtar melihat gejala ini sebagai
perampasan hak-hak rakyat oleh partai
politik. Meski sudah ada terobosan baru
dengan pemilihan presiden secara
langsung, namun kabinet masih dibentuk
atas pertimbangan kepentingan partai.
6
J adi politik sekarang masih cenderung
melanggengkan kekuasaan rezim (atau
golongan yang berkuasa) daripada
mengutamakan kepentingan rakyat.
Disisi yang lain, masih banyak aturan main
yang tidak adil berlangsung. Dibutuhkan
perubaham sistem politik untuk mengubah
aturan main menjadi lebih adil.
Pemahaman mengenai Indonesia, nation,
dan demokrasi perlu sekali disebarluaskan
untuk membantu menegakkan kerakyatan,
untuk mencapai negara yang mulia.
4. Langkah Antisipasi Ekonomi dan
Politik
Berdasarkan catatan selama sesi tanya
jawab dapat disarikan berbagai langkah
antisipasi dari sudut pandang ekonomi
maupun politik. Meski tidaklah
komprehensif, namun dari jawaban dari
5
Beliau menyebutkan sumber korupsi besar dan
sistemik terdapat pada saat penentuan anggaran
(yang diajukan oleh pemerintah atau eksekutif dan
memerlukan persetujuan legislatif) yang banyak
diwarnai oleh mark-up.
6
Mochtar Pabottingi berpendapat SBY, yang
berhasil memperoleh kepercayaan dari mayoritas
rakyat, belum menggunakannya mandat tersebut
dengan sebaik-baiknya terutama dalam
membentuk kabinetnya yang masih diwarnai
dengan dagang sapi (istilah untuk membagi-bagi
jatah jabatan menteri kepada partai-partai tertentu
red).
fragmen-fragmen pertanyaan yg
berkembang dapat di uraikan sebagai
berikut.
4.1 Antisipasi Bidang Ekonomi dan
Sosial
Menjawab pertanyaan seputar
kesenjangan pendapatan antar penduduk,
Prof. Dibyo mengatakan bahwa kebijakan
pemerintah untuk mengurangi perbedaan
pendapatan antara yang kaya dan miskin
sudah ada. Ini antara lain diterapkan pada
kebijakan pajak pendapatan melalui
adanya income tax brackets (pembedaan
tarif pajak berdasarkan golongan
pendapatan red) dan batas minimum
kena pajak. Hanya masalahnya, tidak
semua rakyat membayar pajak; tax
compliance masih rendah. Selain itu juga
masih banyak yang tidak melaporkan
pendapatan yang sesunggguhnya.
Contohnya, kebanyakan dosen membayar
pajak hanya berdasarkan pendapatan dari
pekerjaan pokok, sementara pendapatan
dari pekerjaan sampingan tidak dilaporkan.
Selain itu Prof. Dibyo juga menyoroti
bahwa bangsa Indonesia masih ada yang
belum menghargai etos kerja. Contohnya,
profesionalisme kerja menteri-menteri di
kabinet saat ini kurang terasa
dibandingkan dengan profesionalisme di
jaman dulu (orde baru red). Setiap hal
lebih didasarkan oleh kepentingan partai
(bukan profesionalisme red). Kondisi ini
menyebabkan menteri menjadi tidak fokus
dalam memecahkan persolan bangsa yg
terkait pada bidang di departemen masing-
masing.
Prof Dibyo juga menyarankan agar kita
mencontoh J epang dalam hal mencintai
produk dan mengelola pasar dalam negeri
serta mengelola sumberdaya alam.
Berbagai contoh coba diungkapkan
diantarnya yang bisa dipelajari dari J epang
adalah keseriusan mereka
mengembangkan produk khas daerah
(diistilahkan dengan: one village one
product).
Terkait dengan kebijakan ekonomi
pemerintah J epang, one village one
product hal ini sebenarnya sudah coba
diterapkan oleh pemerintah Indonesia,
khususnya pada bidang pertanian.
Dunia
100
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Perbedaan karakteristik iklim spasial dan
temporal memungkinkan Indonesia untuk
memiliki produk pertanian sepanjang
tahun. Mulai dari Sabang hingga Merauke.
Wilayah potensial kesesuaian Agroekologi
telah disusun. Produk unggulan daerah
juga sudah didesiminasikan. Dan kini
dibeberapa pemerintah Kabupaten seperti
di Sragen dan Bukittinggi sedang
dikembang Agropolitan bagi produk buah-
buahan dan hortikultura. Dukungan
teknologi dan menempatkan kembali
sektor Pertanian sebagai sektor utama
harus dilakukan, didukung oleh kekayaan
sumber daya tanah, air, iklim dan
keragaan biodiversitas plasma nutfah.
Sebagian besar rakyat miskin Indonesia
hidup didaerah sentra-sentra pertanian.
Berdasarkan hal tersebut, kita masih harus
banyak belajar dari J epang dalam
kemampuannya mengembangkan produk
pertanian berkualitas tinggi seperti beras
aromatik, menjaga pasar beras mereka
dari import negara lain, pengembangan
bioteknologi untuk pertanian, dan lain-lain.
Selain itu kita juga dapat belajar dari
Thailand, yang sejak 20 tahun lalu sudah
memfokuskan produk unggulan dari hasil
pertanian. Dimana research-research
station pertanian mereka sudah sejak
lama memperhatikan permintaan pasar
dunia. Seperti penelitian dan
pengembangan tentang durian tanpa
aroma, tebu berkulit lunak, dan padi
J asmine aromatik, demikian Prof. Dibyo
menekankan.
Menjelaskan makna Indonesia kepada
orang asing misalnya orang J epang.
Dalam hal ini sudah menjadi tugas setiap
pelajar Indonesia (yang sedang belajar di
luar negeri red) bukan hanya tugas
pemerintah. Dampak yang dihasilkan akan
sangat lama bila hanya mengandalkan
pemerintah saja. Memperkenalkan
Indonesia di J epang misalnya bisa
dilakukan dengan membuat web-site
dalam bahasa J epang, tidak hanya dalam
bahasa Indonesia, agar informasi
mengenai Indonesia dapat tersebar lebih
luas di masyarakat J epang. Melalui
diskusi-diskusi dengan ahli-ahli J epang
yang mengerti tentang Indonesia. Di
J epang terdapat beberapa centre atau
institusi yang khusus mendalami hal-hal
tentang Indonesia. Atau dengan berusaha
memberi petunjuk atau informasi yang
jelas tentang Indonesia. Prinsipnya,
pelajar Indonesia di J epang perlu untuk
mengambil inisiatif mendekati orang-orang
J epang. Hal ini dapat membantu
terbentuknya identitas Indonesia.
Selain kedua hal diatas, masalah
pendidikan pun menjadi bahan diskusi
yang sangat menarik, utamanya terkait
dengan beban kurikulum pendidikan yang
sangat berat (terberat dari 50 negera yg
disurvei -red), jenjang pendidikan yang
terlalu panjang dan lama sejak SD hingga
Perguruan Tinggi. Guru besar Ekonomi itu
menyatakan persetujuannya agar
kandungan kurikulum pendidikan nasional
ditinjau kembali, jenjang pendidikan yang
dipercepat (misal: SMP dan SMA cukup 4
tahun saja sedangkan SD tetap 6 tahun
red), dan perlunya penambahan
pendidikan budi pekerti/akhlak sejak SD.
Meskipun demikian Guru Besar Ekonomi
itu juga mengatakan perlunya
dipertimbangkan lapangan kerja yang
seluas-luasnya bagi lulusan sekolah dan
perguruan tinggi sebagai akibat dari
pecepatan masa sekolah di atas.
Kemudian, persoalan pendidikan dan
solusinya tidak lah dapat di generalisir
untuk seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan di atas dapat diterapkan untuk
daerah-daerah yang sudah memiliki
fasilitas pendidikan yang baik, terjangkau
oleh semua lapisan, dan mudah di capai.
Sebab masih banyak daerah yang
memiliki keterbatasan sumberdaya alam
dan manusia, seperti halnya di Propinsi
Papua atau untuk daerah-daerah yang
baru saja mengalami musibah bencana
alam, seperti Propinsi NAD dan sekitarnya.
4.2 Antisipasi Bidang Politik
Menanggapi kritik terhadap acara-acara
dialog yang sering dilakukan berbagai
organisasi pelajar dan kepemudaan
selama ini dikaitkan dengan etos kerja,
secara bijak Mochtar Pabottingi
berpendapat bahwa acara bincang-
bincang seperti ini tidak bisa dianggap
sepele. Pergerakan kemerdekaan dimulai
dari pertemuan semacam ini (study club,
tukar pikiran - red). Selanjutnya Pak
Mochtar memandang bahwa solusi krisis
multidimensi sekarang ini bukan terletak
Dunia
101
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
pada peningkatan etos kerja. Solusi yang
ingin disampaikan bukan solusi kultural
(etos kerja merupakan soal kultur),
melainkan solusi politik. Ini dapat diartikan
dengan menegakkan aturan main, dan
membongkar yang tidak adil. Etos kerja
tidak bisa hidup dalam kondisi yang tidak
adil. Orang Indonesia telah dibuat malas
secara sistemik (oleh aturan main yang
tidak adil red) sejak jaman Belanda;
dibodohkan selama ratusan tahun.
Sehingga untuk merubah etos kerja,
dibutuhkan perubahan politik.
Sumpah Pemuda adalah sumpah yang
demokratis. Kala itu semua seperti mimpi
mempersatukan komponen bangsa,
bahwa impian kemudian perlu dimiliki, asal
benar dan berdasar, adalah sangat
penting karena bisa menjadi modal politik.
Indonesia sebenarnya berkesempatan
mengembangkan aturan main yang jelas
dan adil pada era Konstituante.
Sayangnya institusi hasil pemilihan umum
yang demokratis pada 1955 ini kemudian
dibubarkan oleh Bung Karno. J ika tidak,
aturan main di Indonesia saat ini mungkin
sudah jauh lebih maju. Pemahaman atas
konsep nation dan demokrasi mungkin
sudah jauh lebih berkembang.
Tanpa pemahaman tentang nation dan
rasionalitas ekonomi, akan banyak
kebijakan yang diambil hanya untuk
kepentingan sesaat, daerah tertentu,
segelintir orang, yang pada akhirnya
bermuara pada kerugian bangsa. Di era
otonomi daerah sudah muncul peraturan-
peraturan daerah yang bertujuan sempit
untuk memperkaya daerahnya tapi
sebenarnya merugikan kepentingan
bersama karena otonomi daerah
dijalankan tanpa ada kesadaran tentang
nation. Contohnya adalah peraturan
pungutan pajak untuk setiap kendaraan
yang lewat di daerah. Contoh lain adalah
pemberian ijin proyek di daerah hutan
lindung. Menyadarkan rakyat akan
pentingnya konsep-konsep tersebut
adalah tugas kita bersama, bukan hanya
pemerintah.
Lebih jauh Mochtar mengatakan bahwa
kita tidak perlu bingung dengan nama
Indonesia, karena yang lebih penting
adalah memaknai nama Indonesia itu
sendiri. J uga perlu kita menumbuhkan
sense of crisis masing-masing komponen
bangsa, meski ini tidaklah mudah, terlebih
untuk rejim yang masih merupakan bagian
atau berhubungan dengan orde baru.
Realitas kehidupan politik dan ekonomi
selama orde baru antara lain: menghargai
rendah produk petani untuk mensuplai
orang kota; membagi-bagi sumber daya
secara tidak adil (kepada kroni),
perbedaan perlakuan hukum dan keadilan,
dan terhentinya regenerasi kepemimpinan
pada generasi yang lebih muda.
Lebih jauh, ahli politik ini juga menegaskan
bahwa menyebarluaskan pemahaman
mengenai nation bukan dengan cara
indoktrinasi, melainkan menyebarluaskan
pandangan bahwa sistem politik yang
bersih dan sehat adalah penting. Sebagai
ilustrasi, pemilihan umum pada 1955 yang
menghasilka konstituante mampu
mengumpulkan orang-orang yang betul
merupakan pemimpin di daerahnya.
Bandingkan dengan pemilihan umum
pada masa Orde Baru.
Ahli Peneliti Utama ini juga menyatakan
keprihatinannya terhadap pendidikan. Ia
prihatin karena pendidikan tidak
dikedepankan oleh Indonesia. J abatan
pengambil keputusan untuk bidang
pendidikan saat ini masih belum diisi oleh
orang-orang yang kompeten. Secara tegas
Mochtar menghimbau partai politik untuk
mendidik kader partai untuk memahami
konsep nation dan demokrasi. Selain
tentunya pemahaman terhadap masalah
masalah sosial seperti pendidikan dan
pertanian
Ketika ada pertanyaan tentang peluang
penyebaran paham nation untuk
masyarakat kelas bawah (grass root), ia
menjelaskan bahwa memang bukan hal
yang mudah, tapi harus dilakukan, dan
perlu keberanian. Ini penting untuk
membangun karakter. Selain itu penting
untuk mengembangkan rasionalitas dalam
berpolitik melalui penerapan demokrasi
dan pendidikan politik kepada partai.
Untuk membentuk nation, dibutuhkan
orang-orang berpandangan luas,
mengayomi masyarakat luas tanpa
membedakan golongan dan agama.
Dunia
102
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
5. Rekomendasi untuk Pemerintah dan
Pihak Terkait
Berdasarkan diskusi yang berkembang
pada dialog santai seperti diuraikan di atas,
secara bulat disusunlah rekomendasi kecil
untuk ditindaklanjuti oleh pemegang
kekuasaan eksekutif dan pihak terkait.
Rekomendasi ini selanjutnya di
sebut Rekomendasi Kyoto adalah
sebagai berikut:
1. Penghapusan subsidi BBM perlu
dilakukan untuk menghadapi realitas
ekonomi, namun demikian
penghapusan subsidi tersebut perlu
mempertimbangkan daya beli
masyarakat dan dilakukan secara
bertahap. Usaha-usaha menciptakan
sumber energi terbarukan dan
penghematan energi harus mendapat
dukungan seluruh lapisan masyarakat.
2. Kondisi perekonomian tidak dapat
dinilai hanya berdasarkan parameter
makro (seperti GDP, nilai tukar rupiah,
dan inflasi), tapi harus melihat realitas
pada skala ekonomi mikro, seperti
jumlah rakyat miskin, pengangguran,
dan ketimpangan pendapatan yang
kian meningkat dan perlu ditangani
dengan segera.
3. Pendapatan negara melalui pajak
harus terus dilakukan melalui
penegakkan Institusi Pajak yang
bersih dan berwibawa, serta
penegasan kepada masyarakat untuk
taat pajak.
4. Memacu penerapan one village one
product berdasarkan keunggulan
komparatif daerah, kualitas, dan
keberlanjutan produk. Agar terjadi
perdagangan antar daerah yang pada
akhirnya akan menumbuhkan
kegairahan pelaku ekonomi.
5. Menjadikan sektor pertanian sebagai
sektor utama dalam pembangunan
ekonomi nasional berdasarkan
keunggulan sumberdaya daerah dan
didukung oleh pengembangan
teknologi dan industri pertanian.
6. Perlu dilakukan peninjauan kembali
terhadap muatan kurikulum
pendidikan Nasional pada setiap
jenjang pendidikan. Selain itu perlu
dilakukan pengkajian terhadap
pengurangan masa studi (SMP dan
SMA hanya 4 tahun) dengan
memperhatikan sarana dan prasarana
masing-masing daerah, spesialisasi,
dan ketersediaan lapangan kerja.
7. Pemerintah dan seluruh komponen
bangsa, baik individu, kelompok,
golongan atau partai diminta untuk
memahami, mengimplemetasikan dan
menumbuhkembangkan
makna nation (kolektivitas politik)
dan demokrasi (dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat) menuju
rasionalitas politik yang
berkemanusian, adil, dan beradab.
Dengan tidak mengartikan nation
sebagai indoktrinasi melainkan
sebagai perwujudan dari sistem politik
yang bersih dan sehat.
8. Percepatan implemantasi rasionalitas
politik (saling imbang dan saling
kontrol) mutlak dilakukan oleh seluruh
kekuatan sosial politik guna
menciptakan perundang-undangan
yang adil dan mengayomi kepentingan
nasional, menumbuhkan kesetaraan
hak dan kewajiban, serta
mempercepat penerapan rasionalitas
ekonomi dan menumbuhkan etos
kerja.
9. Memberi dukungan penuh pada
Presiden sebagai pemegang
kekuasaan tertinggi pemerintah untuk
menunjuk menteri yang kompeten dan
profesional. Dan meminta pada
seluruh partai politik untuk
mengedepankan kepentingan nasional
dan tidak mencampuri hak prerogratif
presiden.
10. Memberi dukungan penuh pada
upaya-upaya penghapusan aturan,
perundang-undangan yang tidak
memenuhi rasa keadilan, berpihak
pada pemilik modal dan rezim, serta
tindakan tegas dalam payung hukum
terhadap pelaku korupsi, kejahatan,
dan hal-hal lain yang merugikan
kepentingan bangsa dan negara
secara keseluruhan.
11. Perlu ditingkatkan dialog-dialog antar
pelajar di luar negeri dan antara
pemegang kekuasaan dan
masyarakat untuk memberi wawasan,
solusi, dan menumbuhkan semangat
kebersamaan dalam membangun
bangsa dan tanah air.
Dunia
103
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
12. Menyadari dengan penuh kearifan
bahwa persoalan yang sedang terjadi
di tanah air adalah tidak saja menjadi
tanggungjawab pemerintah, tetapi
juga menjadi tanggung jawab seluruh
masyarakat di dalam dan di luar
negeri dengan berbagai keahlian demi
percepatan keluar dari krisis
multidemensi saat ini.
Kyoto yang dingin dengan momiji menebar
berbagai keindahan warna daun,
menyadarkan kami bahwa sesungguhnya
kami anak bangsa yang mempunyai
kewajiban lebih besar untuk terus menerus
mencari solusi terbaik untuk negeri tercinta,
nun jauh di sana. Keragaman warna
momiji seperti juga keragaman kami
pelajar harus bersatu padu menyuarakan
Indonesia yang indah dengan segala daya
upaya dan potensi yang dimiliki.
Dunia
104
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
TOKOH
LEBIH DEKAT DENGAN RATNO NURYADI
Edisi kali ini, redaksi menampilkan tokoh
peneliti muda bidang yang menjadi kunci
perkembangan tekonologi masa depan,
yaitu nano teknologi. Karena ketekunan
riset yang dikerjakannya, tokoh kita ini
mendapatkan dana riset unggulan dari
pemerintah J epang, program J SPS.
Dimana riset yang dilakukannya termasuk
ke dalam salah satu riset unggulan
pemerintah J epang. Meskipun berasal dari
daerah terpencil, namun tidak
memupuskan semangat untuk terus
berprestasi, bersaing dengan anak-anak
perkotaan dan berkarya. Terbukti setelah
tamat SMA, dia mendapat kesempatan
untuk mengenyam pendidikan di luar
negeri, yaitu di J epang pada tahun 1993
hingga dapat menyelesaikan program
doktor dengan predikat yang sangat
memuaskan. Saat ini tokoh kita ini menjadi
peneliti di Shizuoka University yang
mendapatkan dana riset penuh oleh
pemerintah J epang untuk meneliti single
electron dan single photon. Untuk lebih
dekat dengan pejabat harian sementara
ISTECS Chapter J epang ini, tim redaksi
berhasil mewawancarai ditengah-tengah
kesibukannya. Dia adalah Dr. Ratno
Nuryadi.
Sebelumnya, kami dari rekdasi
INOVASI mengucapkan banyak terima
kasih atas waktu yang diberikan
ditengah-tengah kesibukan pak Ratno.
Bagaimana ceritanya Pak Ratno bisa
datang ke Jepang ini?
Kedatangan saya ke J epang bermula dari
keikutsertaan saya di program beasiswa
STAID III tahun 1992 setelah saya lulus
SMA. Setelah mengikuti serangkaian tes
yang panjang dan melelahkan dari ujian
tertulis sampai psikotes, alhamdulillah,
saya dinyatakan lulus dengan instansi
BPPT dan tujuan negara J epang.
Melelahkan, karena saya harus pulang
pergi J akarta-Yogya berkali-kali dan
bahkan saat itu di rumah belum ada telpon
karena kampung saya di daerah pelosok
(perbatasan Bantul dan Gunung Kidul).
Singkat cerita, setelah menjalani beberapa
tahap ujian, saya dinyatakan lulus dan
berangkat ke Tokyo-J epang bulan April
1993 untuk menjalani program belajar
bahasa J epang selama satu tahun.
Banyak pengalaman suka dan duka saya
alami sehingga sampai di J epang. Dan,
alhamdulillah, dari sini juga saya sedikit
demi sedikit bisa belajar, untuk menjadi
modal berjuang di masa-masa kritis yang
mungkin akan lebih berat lagi di masa
mendatang. Salah satu pelajaran berharga
yang saya dapatkan dalam menghadapi
masa-masa kritis adalah ketika tekad
masih kuat, tidak mudah menyerah dan
istiqomah.
Bagaimana pengalaman hidup di
Jepang selama 12 tahun lebih ?
Berbeda dengan sebagian teman-teman
seangkatan yang sejak awal sudah
diterima program S1 di perguruan tinggi
negeri, saya dan beberapa teman masih
harus belajar untuk persiapan ujian masuk
perguruan tinggi sejalan dengan program
belajar bahasa J epang. Saya mencoba
ujian di beberapa universitas, baik negeri
maupun swasta, dengan hasil ada yang
diterima dan ada yang tidak. Setelah
menimbang hasil yang ada, saya
memutuskan masuk Universitas Shizuoka
dengan mengambil program S1 di jurusan
Fisika.
Sesuai rencana, alhamdulillah, saya bisa
menyelesaikan program S1 bulan Maret
1998, dan masuk ke program S2 tanpa tes
di jurusan Electrical and Electronic
Engineering di universitas yang sama
(1998-2000). Saya pindah jurusan karena
ingin penelitian ke arah ilmu terapan
dibanding ilmu murni, di samping juga
Dunia
105
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
saya tertarik dengan elektronika material.
Selesai program S2, saya melanjutkan lagi
ke program S3 di lab sama dan selesai
Maret 2003. Berhubung beasiswa STAID
hanya sampai program S1, saya perlu
mencari beasiswa sendiri untuk kelanjutan
studi saya.
Selama program master dan doctor, saya
mencukupi hidup dari beasiswa lokal di
J epang dan part-time job (arubaito). Untuk
biaya sekolah, saya mendapatkan
keringanan tidak membayarnya baik
program S2 maupun S3. Arubaito
dilakukan karena tidak mencukupi kalau
hanya mengandalkan beasiswa saja. S2
tahun ke-1 beasiswa dari Soureihi, S3
tahun ke-1 beasiswa dari Soureihi dan S3
tahun ke-2 dan 3 beasiswa dari Sagawa.
Pada saat S2 tahun ke-2, pernah sama
sekali saya tidak mendapat beasiswa dan
mengandalkan arubaito saja. Namun,
alhamdulillah, pada saat itu, Allah justru
memudahkan saya untuk menggenapkan
dien, menikah.
Kami dengar riset yang sedang pak
Ratno kerjakan ini adalah riset
unggulan pemerintah Jepang.
Bagaimana ceritanya?
Tentang studi, ketika masih program S1,
saya merasakan bidangnya masih umum
dan sifatnya hanya penanaman ilmu-ilmu
dasar. Sejak S2, saya mulai studi/riset di
bidang yang lebih fokus, yaitu pembuatan
silicon dot untuk sub-micron transistor.
Ketertarikan saya di bidang
nanoelectronics, terus saya lanjutkan juga
saat program S3 . Di tahun ke-3 program
S3, saya mencoba mendaftar program
postdoctoral ke J apan Society for the
Promotion of Science (J SPS).
Alhamdulillah, proposal saya diterima
untuk periode program postdoctoral April
2003 Maret 2005 setelah melalui
penilaian kira-kira selang waktu 4 bulan.
Saya merasa ini kesempatan besar untuk
mendalami riset saya. Dengan program ini
juga riset saya jadi bertambah maju, dan
bisa publish baik konferensi international
maupun jurnal international. Selesai
program J SPS, saya mendapat tawaran
dari professor lagi untuk melanjutkan riset
dengan sponsor dari COE (center of
excellent) fellowship program sampai
sekarang.
Apa kiat-kiat yang Pak Ratno miliki
sehigga bisa mendapatkan fellowship
dari JSPS?
Pada awalnya saya coba-coba saja dalam
mengajukan proposal postdoct ke J SPS.
Dan alhamdulilah, saya diberi kemudahan
untuk mendapatkannya. Dalam
mengajukan proposal J SPS ini ada
beberapa point yang ingin saya tekankan
antara lain :
1. Perlunya mencari informasi terkait
dengan waktu-waktu pendaftaran.
Batas terakhir pendaftaran beserta
prosedurnya. Hal ini tentunya perlu
keaktifan kita dalam mencari tahu hal-
hal tersebut, terutama lewat
homepage J SPS dan informasi lewat
universitas.
2. Pengajuan J SPS ini tidak diajukan
secara individu. Pengajuan proposal
kita ajukan ke sensei. Kemudian
sensei selaku host-researcher akan
melengkapi dokumen-dokumen yang
kita buat dan mengirimkannya ke
J SPS melalui universitas. Karena itu,
sejak pemilihan sensei, terus
dilanjutkan dengan hubungan kita
dengan sensei, menjadi hal faktor
yang penting.
3. Yang penting juga tentu dalam
penulisan proposal. Nah, di sini
penting bagaimana kita menuangkan
ide-ide penelitian kita dengan bahasa
yang mudah di mengerti, jelas dan
gamblang. Itu perlu kita tulis sejak dari
latar belakang penelitian, tujuan,
sekejul penelitian dan prediksi hasil
akan capaian dicapai. J uga yang tak
kalah pentingnya adalah memaparkan
originalitas penelitian dan positioning
penelitian kita agar orang yang
membaca tahu keunggulan dan daya
tarik penelitian kita. Semua ini di
tuangkan dalam tulisan yang runut,
jelas dan saling berhubungan satu
dengan yang lain.
Kira-kira tiga hal tersebut yang saya
anggap penting. Selanjutnya, setelah kita
berusaha dengan sekuat daya, kita berdoa
kepada Allah swt agar lolos proposal kita.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
106
INOVASI Vol.5/XVII/November 2005
Terakhir, apakah ada pesan-pesan
untuk anggota PPI Jepang yang bisa
pak Ratno berikan ?
Menurut saya, keberhasilan studi
seseorang tidak tergantung hanya kepada
tingkat kecerdasan, namun ada yang lebih
penting lagi yakni ketekunan dan kekuatan
tekad. Setiap orang memiliki peluang
untuk berhasil dan gagal, tergantung
seberapa besar usaha untuk mencapainya.
Lalu terkait keberadaan kita di J epang,
kehidupan jepang yang cenderung
individualis, tentunya tidak menjadikan kita
sebagai pelajar yang melupakan fungsi
kita di masyarakat. Kita usahakan agar
mampu mensinergikan ilmu yang kita
dapat kepada masyarakat, baik itu yang
berada di J epang maupun di Indonesia.
Sehingga ilmu yang kita dapat bukanlah
hanya untuk diri sendiri namun memiliki
visi kemaslahatan masyaratkat. Untuk itu,
menurut saya, tugas pelajar di sini bukan
hanya menuntut ilmu, namun juga turut
aktif mensukseskan program-program
sosial masyarakat dan kemanusiaan di
Indonesia.
BIODATA
NAMA LENGKAP
Ratno Nuryadi
HOMEPAGE
http://ratnonuryadi.com
PENDIDIKAN:
Physics Shizuoka University (S1:
4/1994-2/1998),
Electrical and Electronics Engineering
Shizuoka University (S2: 4/1998-3/2000),
Electronic Materials Science Shizuoka
University (S3: 4/2000-3/2003).
KELUARGA
Isteri: Ervin Hidayati Tholib
Anak: Fatih Dzulfiqar
AFILIASI SAAT INI:
Research Institute of Electronics,
Shizuoka University
COE Postdoctoral fellow
AFILIASI DI INDONESIA
Pusat Pengkajian dan Penerapan
Teknologi Material (P3TM) - BPPT
RESEARCH SAAT INI:
- Manipulasi electron dan hole tunggal
pada struktur silikon multidot transistor.
- Single photon detector dengan material
silikon.
ORGANISASI YANG DIIKUTI SAAT INI
ISTECS J apan (www.istecs.org)
[1] Books, New York.
Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Jepang; Membuka Dunia untuk Indonesia dan Membuka Indonesia untuk
Dunia
107
SUSUNAN REDAKSI
PENANGGUNG JAWAB
Edy Marwanta
Ketua Umum PPI Jepang
Mahasiswa Tokyo University of
Agriculture and Technology (S3)
PEMIMPIN REDAKSI
Arif Satria
Dosen Departemen Sosial
Ekonomi
Perikanan FPIK IPB
REDAKTUR
Candra Dermawan
Presiden Power Media
Communication
Mahasiswa Toyohashi University of
Technology (S3)
Department of Electronic
Information Engineering,
Multimedia Communication
Laboratory.
Haris Syahbudin
Balai Penelitian Agroklimat dan
Hidrologi, Badan Litbang
Departemen Pertanian
Mahasiswa Graduate School of
Science and Technology, Kobe
University (S3)
.
108
Taruna Ikrar
Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI
Mahasiswa Niigata University (S3)
Department of Cardiology, Faculty
of Medicine
Muhamad Thohar Arifin, Dr.
Bagian Anatomi dan Bedah Saraf
FK UNDIP RS Dr. Karyadi
Semarang
Bag Bedah Saraf Rumah sakit
Universitas Hiroshima
Dodhik Kurniawan
Mahasiswa program Japan Advance
Institute of Science and Technology
(JAIST) (S2)
Muh. Zulkifli Mochtar Husein
Mahasiswa Osaka University.
Graduate School of Engineering,
Infrastructure and Transportation
Engineering.
109
Sorja Koesuma Tonang Dwi Ardyanto
Department of Geophysics Kyoto
University
Jurusan Fisika Universitas Sebelas
Maret Surakarta
Dosen Fakultas Kedokteran
Universitas
Sebelas Maret Surakarta
Mahasiswa University School of
Medicine (S3)
Department of Pathology, Tottori
TIM PRODUKSI
Muhammad Arif Kurniawan Hastari Eka Anandhita
Mahasiswa Internasional
University of Hyogo, Kobe
Fakultas Ekonomi
Mahasiswi Tokyo Institute of
Technology (S2)
Dept. of Information Processing
110
Anda mungkin juga menyukai
- Ekonomi makro menjadi sederhana, berinvestasi dengan menafsirkan pasar keuangan: Cara membaca dan memahami pasar keuangan agar dapat berinvestasi secara sadar berkat data yang disediakan oleh ekonomi makroDari EverandEkonomi makro menjadi sederhana, berinvestasi dengan menafsirkan pasar keuangan: Cara membaca dan memahami pasar keuangan agar dapat berinvestasi secara sadar berkat data yang disediakan oleh ekonomi makroBelum ada peringkat
- Pendekatan sederhana untuk keuangan perilaku: Panduan pengantar teori dan prinsip operasional keuangan perilaku untuk meningkatkan hasil investasiDari EverandPendekatan sederhana untuk keuangan perilaku: Panduan pengantar teori dan prinsip operasional keuangan perilaku untuk meningkatkan hasil investasiBelum ada peringkat
- Makalah Kenaikan BBMDokumen12 halamanMakalah Kenaikan BBMTrama Suma67% (3)
- Makalah Perekonomian IndonesiaDokumen17 halamanMakalah Perekonomian IndonesiaAsmi Nuqayah100% (8)
- Makalah Kelangkaan BBMDokumen6 halamanMakalah Kelangkaan BBMSaleh Hasyim100% (1)
- Makalah Kenaikan BBM (H1F011028)Dokumen13 halamanMakalah Kenaikan BBM (H1F011028)Prasaja Dika100% (1)
- Artikel Krisis EnergiDokumen7 halamanArtikel Krisis EnergiBrio Xyk FlatlandologyBelum ada peringkat
- MAKALAH EkonomiDokumen13 halamanMAKALAH EkonomiLuthfi SetiawanBelum ada peringkat
- Inovasi Vol.5 XVII November 2005Dokumen112 halamanInovasi Vol.5 XVII November 2005singlecrew100% (15)
- Makalah Dilema Etik Klp2Dokumen30 halamanMakalah Dilema Etik Klp2Dewi NurfadilahBelum ada peringkat
- Penyebab Terjadinya Dan Penanggulangan Krisis Angka Kebutuhan Tabung Gas Subsidi Dan Kenaikan Harga BBMDokumen11 halamanPenyebab Terjadinya Dan Penanggulangan Krisis Angka Kebutuhan Tabung Gas Subsidi Dan Kenaikan Harga BBMFarel PermanaBelum ada peringkat
- Gazel RisetDokumen17 halamanGazel Riseturang calakBelum ada peringkat
- Gazel RisetDokumen17 halamanGazel RisetYulendradinata92Belum ada peringkat
- Makalah Kelangkaan BBMDokumen15 halamanMakalah Kelangkaan BBMAndri Ocu PaslahBelum ada peringkat
- Pengaruh Kenaikan BBM Terhadap Perekonomian IndonesiaDokumen10 halamanPengaruh Kenaikan BBM Terhadap Perekonomian IndonesiaNewFreshcomBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok SosiologiDokumen14 halamanTugas Kelompok SosiologiPutra MahendraBelum ada peringkat
- Makalah Ekonomi EnergiDokumen20 halamanMakalah Ekonomi EnergiNovia ChandraBelum ada peringkat
- Perekonomian IndonesiaDokumen50 halamanPerekonomian IndonesiaJulius Arthan100% (1)
- Paper EkonomiDokumen12 halamanPaper EkonomiDidcy Mai HendriBelum ada peringkat
- Makalah - Dampak - Kenaikan - BBM AjaDokumen17 halamanMakalah - Dampak - Kenaikan - BBM AjaSuci SpenduraBelum ada peringkat
- No 2Dokumen15 halamanNo 2Bita RiaBelum ada peringkat
- Analisis Kebijakan Jokowi Terhadap Penghapusan Subsidi BBMDokumen5 halamanAnalisis Kebijakan Jokowi Terhadap Penghapusan Subsidi BBMDwi AdelianingsihBelum ada peringkat
- Analisis BBMDokumen15 halamanAnalisis BBMAnnisa PutriBelum ada peringkat
- Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak BBMDokumen21 halamanKenaikan Harga Bahan Bakar Minyak BBMShifa Nur Aulia PutriBelum ada peringkat
- Kumpulan Materi UAS EKO MAKRODokumen5 halamanKumpulan Materi UAS EKO MAKROristy aprissaBelum ada peringkat
- Ekonomi TerbaruhDokumen13 halamanEkonomi TerbaruhMardias SafriBelum ada peringkat
- Artikel Dasar Dasar SainsDokumen5 halamanArtikel Dasar Dasar SainsAyu Safitri MarzakiBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Subsidi BBMDokumen11 halamanProposal Penelitian Subsidi BBMAhmad Hazami Mabrur0% (2)
- Makalah Kenaikan BBM 2Dokumen10 halamanMakalah Kenaikan BBM 2silviayuliantiBelum ada peringkat
- PPID White Paper 2018Dokumen126 halamanPPID White Paper 2018Dhaneswara Al AmienBelum ada peringkat
- Makalah Angkatan IX Kelompok IV Sub Kelompok 2Dokumen23 halamanMakalah Angkatan IX Kelompok IV Sub Kelompok 2Hendra PrastowoBelum ada peringkat
- Artikel DandiDokumen7 halamanArtikel DandiGANDIRABelum ada peringkat
- Publish Bab I.iiDokumen41 halamanPublish Bab I.iiMayy IndahBelum ada peringkat
- Perekonomian Indonesia DocxDokumen10 halamanPerekonomian Indonesia DocxHendra ApriansyahBelum ada peringkat
- Makalah Kelangkaan BBMDokumen11 halamanMakalah Kelangkaan BBMamru haniBelum ada peringkat
- Perekonomian Indonesia 3Dokumen8 halamanPerekonomian Indonesia 3Muhammad IkromBelum ada peringkat
- Apa Itu Bio Energy PowerDokumen11 halamanApa Itu Bio Energy PowerTresna MustikasariBelum ada peringkat
- Ilyas Panaya - 221010500481 - 01SMJP004Dokumen20 halamanIlyas Panaya - 221010500481 - 01SMJP004Muhamad SadamBelum ada peringkat
- Makalah Kel 9. SpeDokumen8 halamanMakalah Kel 9. SpeElvi KurniaBelum ada peringkat
- Makalah Ocean PowerDokumen15 halamanMakalah Ocean Powerkhairu nisaBelum ada peringkat
- Makalah Pembangunan Ekonomi (Makro)Dokumen17 halamanMakalah Pembangunan Ekonomi (Makro)Cut Intan HayaturrahmiBelum ada peringkat
- Makalah Ekonomi-1Dokumen13 halamanMakalah Ekonomi-1Muhamad SadamBelum ada peringkat
- Aliran Sisi Penawaran Spe6Dokumen20 halamanAliran Sisi Penawaran Spe6Devina KasangkeBelum ada peringkat
- Makalah Ekonomi 5Dokumen11 halamanMakalah Ekonomi 5Neyzha zahraBelum ada peringkat
- Filsafat Ilmu AksiologiDokumen10 halamanFilsafat Ilmu AksiologiMr. ZBelum ada peringkat
- Kenaikan Harga BBMDokumen17 halamanKenaikan Harga BBMardi banyuasinBelum ada peringkat
- Ageng Gumelar-MKP - 3 AMP BDokumen7 halamanAgeng Gumelar-MKP - 3 AMP Bageng gumelarrBelum ada peringkat
- ANALISA KEBIJAKAN SUBSIDI THD PERTUMBUHAN EKONOMI PDFDokumen250 halamanANALISA KEBIJAKAN SUBSIDI THD PERTUMBUHAN EKONOMI PDFWasis SasmitoBelum ada peringkat
- Review Jurnal 1Dokumen10 halamanReview Jurnal 1Fuad AbrariBelum ada peringkat
- Pancasila Kelompok 4 BBMDokumen11 halamanPancasila Kelompok 4 BBMviditaimroatusBelum ada peringkat
- Anti Korupsi - 4Dokumen28 halamanAnti Korupsi - 4Tim AlineaBelum ada peringkat
- Pengaruh Kenaikan BBM Bersubsidi Terhadap Kondisi Daya Beli Masyarakat KecilDokumen39 halamanPengaruh Kenaikan BBM Bersubsidi Terhadap Kondisi Daya Beli Masyarakat KecilSyukri Muhammad100% (1)
- Bab IiiDokumen5 halamanBab IiiAlifiya nabila PurnomoBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - Konsep Dasar Ekonomi - 2018Dokumen15 halamanKelompok 1 - Konsep Dasar Ekonomi - 2018bening sekarBelum ada peringkat
- Soal Ipem4215 tmk2 22Dokumen6 halamanSoal Ipem4215 tmk2 22wanto harsomoBelum ada peringkat
- Tugas 1 Perekonomian Indonesia HafidDokumen9 halamanTugas 1 Perekonomian Indonesia HafidAbdul HafidBelum ada peringkat
- Pie Nurus SDokumen5 halamanPie Nurus SFifian LulaBelum ada peringkat
- Pendekatan sederhana terhadap krisis ekonomi di Yunani: Sebuah perjalanan untuk menemukan krisis ekonomi Yunani yang dimulai pada tahun 2008 dan menggemparkan dunia. Penyebab dan implikasinyaDari EverandPendekatan sederhana terhadap krisis ekonomi di Yunani: Sebuah perjalanan untuk menemukan krisis ekonomi Yunani yang dimulai pada tahun 2008 dan menggemparkan dunia. Penyebab dan implikasinyaBelum ada peringkat
- PKMK - 11 Its Rizal Ti Lang Lamp AromatherapyDokumen21 halamanPKMK - 11 Its Rizal Ti Lang Lamp AromatherapyRA FirmansyahBelum ada peringkat
- Perawatan Dan Perbaikan Heat Exchanger Sebagai Sistem PendinginDokumen12 halamanPerawatan Dan Perbaikan Heat Exchanger Sebagai Sistem PendinginRA Firmansyah100% (3)
- Sinta Baskoro 0910660067Dokumen39 halamanSinta Baskoro 0910660067RA FirmansyahBelum ada peringkat
- BAB 5 Sistem LubrikasiDokumen6 halamanBAB 5 Sistem LubrikasiRA FirmansyahBelum ada peringkat
- BAB 1 Konstruksi MesinDokumen26 halamanBAB 1 Konstruksi MesinRA Firmansyah100% (1)