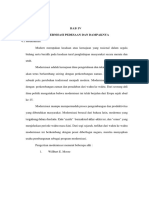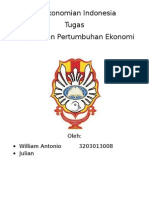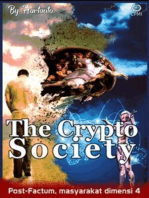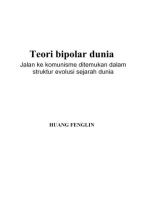Dampak Modernisasi Terhadap Masyarakat Pedesaan
Dampak Modernisasi Terhadap Masyarakat Pedesaan
Diunggah oleh
Triana WijayaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Dampak Modernisasi Terhadap Masyarakat Pedesaan
Dampak Modernisasi Terhadap Masyarakat Pedesaan
Diunggah oleh
Triana WijayaHak Cipta:
Format Tersedia
Dampak Modernisasi terhadap Masyarakat Pedesaan
8 Desember 2010 at 08:17 Filed under Sosiologi Pedesaan DAMPAK MODERNISASI TERHADAP KEHIDUPAN PETANI DI PEDESAAN MINANGKABAU Oleh Witrianto Dt. Bandaro Abstract This article tries to describe impact of modernization on life peasant on Minangkabau village that include social and culture aspects, and their orient future. Modernization which knock over farmer life in rural have caused farmer life pattern change from traditional become modern. This change is marked changedly it process agriculture farm workmanship, process processing of result of crop, fee system, mount mobility, mount education, and mount consumerism peasant. Peasant life which from the beginning tend to static, with existence modernize also turn into more dynamic. I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Persoalan pembangunan ekonomi merupakan sesuatu yang menjadi persoalan utama bagi pemimpin-pemimpin negara, terutama negara berkembang yang sedang berupaya membangun perekonomian negaranya untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Pembangunan ekonomi juga dipersoalkan oleh para pembentuk garis kebijaksanaan di negaranegara yang telah maju; dan juga sangat menarik bagi para ahli ilmu-ilmu sosial, yang mencoba menemukan faktor-faktor yang menimbulkan perubahan yang tengah merevolusikan dunia masa kini. Oleh karena ide pembangunan ekonomi ini telah menjadi sangat biasa dalam pandangan pertengahan abad keduapuluh, maka kita dengan mudah dapat menganggapnya sebagai suatu proses yang sederhana dan utuh. Akan tetapi, pembangunan ekonomi tidaklah sederhana dan utuh. Menurut Smelser dalam Weiner (1980), sekurang-kurangnya ada empat proses yang berbeda tetapi saling berhubungan yang terdapat dalam pembangunan ekonomi: (1) Dalam bidang teknologi, suatu masyarakat yang sedang berkembang sedang mengalami perubahan dari penggunaan teknik-teknik yang sederhana dan tradisional ke arah penggunaan pengetahuan ilmiah. (2) Dalam bidang pertanian, masyarakat yang sedang berkembang itu sedang beralih dari pertanian sederhana ke arah produksi hasil pertanian untuk pasaran. Ini berarti pengkhususan dalam jenis tanaman yang akan dijual hasilnya, pembelian barang-barang non-pertanian di pasaran dan sering juga kerja upahan dalam bidang pertanian. (3) Dalam bidang industri, masyarakat yang sedang berkembang sedang mengalami peralihan dari penggunaan tenaga
manusia dan binatang ke industrialisasi yang sebenarnya, atau orang-orang yang bekerja untuk upah pada mesin-mesin yang digerakkan oleh sumber tenaga, yang menghasilkan barang dagangan yang dijual diluar kalangan yang menghasilkannya. (4) Dalam susunan ekologi perkembangan masyarakat bergerak dari sawah/ladang dan desa ke pemusatan-pemusatan di kota. Pembangunan ekonomi adalah salah satu aspek saja dari serangkaian perubahan masyarakat yang dialami oleh negara-negara berkembang. Istilah modernisasi, suatu konsep yang sekeluarga dengan istilah pembangunan ekonomi, tetapi lebih luas jangkauannya, menunjukkan bahwa perubahan-perubahan teknik, ekonomi dan ekologi berlangsung dalam keseluruhan jaringan sosial dan kebudayaan. Dalam suatu negara yang sedang berkembang, menurut Smelser (Ibid.), terdapat perubahan-perubahan yang besar, (1) dalam bidang politik, sewaktu sistem kewibawaan suku dan desa yang sederhana itu digantikan dengan sistem-sistem pemilihan umum, kepartaian, perwakilan, dan birokrasi pegawai negeri; (2) dalam bidang pendidikan, sewaktu masyarakat berusaha mengurangi kebutahurufan dan meningkatkan ketrampilan-ketrampilan yang membawa hasil-hasil ekonomi; (3) dalam bidang religi, sewaktu sistem-sistem kepercayaan sekuler mulai mulai menggantikan agama-agama tradisionalistis; (4) dalam lingkungan keluarga, ketika unit-unit hubungan kekeluargaan yang meluas menghilang; (5) dalam lingkungan stratifikasi, ketika mobilitas geografis dan sosial cenderung untuk merenggangkan sistem-sistem hierarki yang sudah pasti dan turun-temurun. 1.2. Perumusan Masalah Tulisan ini memusatkan diri pada satu pertanyaan kunci mengenai masalah modernisasi pertanian. Fokus bahasan mengenai kehidupan petani dalam tulisan ini lebih ditujukan pada petani yang ada di Nagari Selayo Kecamatan Kubuang kabupaten Solok Sumatera Barat. Apakah dampak yang diberikan Modernisasi terhadap kehidupan petani di pedesaan, khususnya di Minangkabau yang sebagian besar di antaranya adalah petani sawah. Sebagai langkah-langkah dalam proses menjawab pertanyaan kunci tersebut, serentetan pertanyaan berikut perlu dijawab: Sampai berapa jauhkah modernisasi melanda kehidupan petani di daerah pedesaan? Seberapa jauh modernisasi yang terjadi mengubah pola pikir dan orientasi masa depan petani di pedesaan? Siapa sajakah yang terlibat dalam proses modernisasi ini dan siapa pula yang dirugikan dengan adanya modernisasi di pertanian? II. Kerangka Teoritis Untuk lebih memudahkan jalannya penulisan, beberapa konsep yang digunakan dalam tulisan ini perlu mendapat kejelasan. Konsep yang dimaksud adalah konsep mengenai modernisasi dan petani. Modernisasi menurut Mutakin dan Pasya (2003), menunjukkan sifat masyarakat secara umum yang dilandasi oleh sifat modern individu, karena dari individulah tumbuh modernisasi. Sementara itu Schoorl (1980), menyatakan bahwa pengertian modern dan modernisasi mengandung kaitan tertentu. Di dalamnya dapat dilihat suatu penghargaan yang positif, yaitu bahwa modern, termasuk juga modernisasi adalah baik. Di dalam kebudayaan-kebudayaan Barat biasanya terdapat penghargaan yang demikian itu, akan tetapi hal tersebut tidak harus demikian. Di dalam kebudayaan-kebudayaan lain asosiasi itu tidak harus ada. Bagaimana orang menilai pengertian-pengertian itu, sangat tergantung pada pandangan hidup dan pandangan dunianya.
Secara sangat ekstrem dapat dinyatakan bahwa suatu masyarakat dapat mengadakan modernisasi, akan tetapi bersamaan dengan itu diukur dengan nilai-nilai tertentu berkembang ke jurusan yang tidak dikehendaki; atau bersamaan dengan itu berkembang ke jurusan yang sangat kapitalistik, yang tidak dapat diterima atas dasar nilai-nilai marxis; atau bersamaan dengan itu masyarakat dapat menjadi begitu terkekang, sehingga atas dasar nilai-nilai kemanusiaan perkembangan itu harus ditolak. Penilaian terakhir atas proses modernisasi tergantung kepada pandangan dunia orang-orang yang menilainya. Konsep lainnya yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep mengenai petani. Petani adalah orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya. Secara garis besar terdapat tiga jenis petani, yaitu petani pemilik lahan, petani pemilik yang sekaligus juga menggarap lahan, dan buruh tani. Secara umum, petani bertempat tinggal di pedesaan dan sebagian besar di antaranya, terutama yang tinggal di daerah-daerah yang padat penduduk di sia enggara, hidup di bawah garis kemiskinan. Kehidupan petani identik dengan kehidupan pedesaan. Amri Marzali (1997) membedakannya menjadi peladang atau pekebun, peisan (dari bahasa Inggris Peasant), dan petani pengusaha atau farmer. Sebagian besar petani yang ada di Indonesia merupakan peisan atau petani pemilik yang sekaligus juga menggarap lahan pertanian yang mereka miliki. Petani peladang atau pekebun menurut Dobby (1954) dalam Marzali, merupakan tahap yang istimewa dalam evolusi dari berburu dan meramu sampai pada bercocok tanam yang menetap. Keistimewaan itu kelihatannya terdiri dari ciri-ciri hampa seperti tidak adanya hubungan dengan usaha pedesaan dan sangat sedikitnya produksi yang mempunyai arti penting bagi perdagangan. Gourou (1956), (Ibid.), secara garis besar menguraikan empat ciri perladangan: (1) dijalankan di tanah tropis yang kurang subur; (2) berupa teknik pertanian yang elementer tanpa menggunakan alat-alat kecuali kampak; (3) kepadatan penduduk rendah; dan (4) menyangkut tingkat konsumsi yang rendah. Pelzer (1957), (Ibid.) menyatakan bahwa petani peladang ini ciri-cirinya juga ditandai dengan tidak adanya pembajakan, sedikitnya masukan tenaga kerja dibandingkan dengan cara bercocok tanam yang lain, tidak menggunakan tenaga hewan ataupun pemupukan, dan tidak adanya konsep pemilikan tanah pribadi. Konsep mengenai peasant sekurang-kurangnya mengacu pada tiga pengertian yang berbeda. Konsep pertama mengacu pada pandangan Gillian Hart (1986), Robert Hefner (1990), dan Paul Alexander dkk (1991), (Ibid.), yang menyatakan bahwa istilah peasant ditujukan kepada semua penduduk pedesaan secara umum, tidak peduli apapun pekerjaan mereka. Konsep kedua mengacu pada pandangan James C. Scott (1976) dan Wan Hashim (1984), (Ibid.) yang menyatakan bahwa peasant tidak mencakup seluruh pedesaan, tetapi hanya terbatas kepada penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani saja. Konsep ketiga atau terakhir mengacu pada pandangan Eric Wolf yang kemudian diikuti oleh Frank Ellis (1988), (Ibid.), yang menyatakan bahwa peasant ditujukan untuk menunjukkan golongan yang lebih terbatas lagi, yaitu hanya kepada petani yang memiliki lahan pertanian, yang menggarap sendiri lahan tersebut untuk mendapatkan hasil yang digunakan untuk memenuhi keperluan hidupnya, bukan untuk dijual, atau yang di Indonesia biasa disebut sebagai petani pemilik penggarap.
Konsep mengenai farmer atau petani pengusaha adalah petani kaya yang memiliki tanah luas dan memiliki banyak buruh atau tenaga kerja yang bekerja untuk mendapatkan upah darinya. Hasil lahan pertaniannya terutama adalah untuk dijual. Pengolahan lahan sudah menggunakan peralatan teknologi modern, seperti mesin bajak, traktor, rice milling, sprayer, dan lain-lain. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah Teori Modernisasi. Menurut Suwarsono dan Alvin Y. So (2000), teori modernisasi klasik lahir sebagai akibat munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia setelah Perang Dunia II, terjadinya perluasan gerakan komunis dunia, dan lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Beberapa teori mengenai modernisasi di antaranya adalah eori Evolusi yang lahir pada awal abad ke-19 setelah Revolusi Industri dan Revolusi Perancis. Menurut Suwarsono dan So (2000), teori ini menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus, yaitu dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju, dan membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial menuju masyarakat modern. Perubahan sosial berjalan secara perlahan dan bertahap selama berabad-abad. Tradisi pemikiran lain yang banyak mempengaruhi perumusan acuan-acuan pokok teori modernisasi ialah teori fungsionalisme dari Talcott Parsons yang menyatakan bahwa, masyarakat mempunyai berbagai kelembagaan yang saling terkait dan tergantung satu sama lain dan setiap lembaga yang ada dalam masyarakat melaksanakan tugas tertentu untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tersebut. Ahli lain, Dube (1988), menyatakan bahwa modernisasi lebih banyak dihubungkan dengan kota, industri, dan masyarakat terpelajar, seperti masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Konsep modernisasi yang dikemukakan oleh Dube didasarkan pada tiga asumsi, yaitu (i) sumber kekuasaan yang mati harus selalu meningkat dibuka dengan maksud untuk memecahkan permasalahan manusia dan secara minimum diterima untuk memastikan standar hidup,yang semakin meningkat. (ii) Untuk mencapai tujuan ini dapat dicapai dengan usaha individu dan kerjasama. Dimensi kerjasama dianggap penting karena kemampuan hubungan untuk mengoperasikan organisasi yang kompleks adalah suatu prasyarat sedikitnya pertengahan dan jangkauan modernisasi yang lebih tinggi. (iii) Untuk menciptakan dan menjalankan organisasi yang kompleks perubahan kepribadian yang radikal dan perubahan yang menyertainya dalam struktur sosial dan nilai-nilai dianggap perlu. Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh ahli-ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa, (i) modernisasi merupakan proses bertahap, (ii) modernisasi dapat juga dikatakan sebagai proses homogenisasi, (iii) modernisasi terkadang mewujud dalam bentuk lahirnya sebagai proses Eropanisasi atau Amerikanisasi, (iv) modernisasi juga dilihat sebagai proses yang tidak bergerak mundur, (v) modernisasi merupakan perubahan progresif, dan (vi) modernisasi memerlukan waktu panjang. Untuk memudahkan jalannya penulisan ini, perlu disusun suatu kerangka pemikiran yang menjiwai penulisan ini. Kerangka pemikiran tersebut adalah sebagai berikut:
Anda mungkin juga menyukai
- Pengaruh Pembangunan Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat PedesaanDokumen9 halamanPengaruh Pembangunan Pertanian Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Pedesaanwahyu467% (3)
- Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan PetaniDokumen6 halamanDampak Modernisasi Terhadap Kehidupan PetanipfeifeiBelum ada peringkat
- Modernisasi PertanianDokumen10 halamanModernisasi Pertanianfebhy100% (1)
- Materi Ajar Pertemuan 11 IndustrialisasiDokumen17 halamanMateri Ajar Pertemuan 11 IndustrialisasiLediana SiskaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Sosiologi PertanianDokumen10 halamanLaporan Praktikum Sosiologi Pertanianputri limbongBelum ada peringkat
- PDF 20230801 143718 0000Dokumen13 halamanPDF 20230801 143718 0000event.kradiojemberBelum ada peringkat
- Tugas 1 LUHT4208Dokumen2 halamanTugas 1 LUHT4208Grace MonicaBelum ada peringkat
- Abigael BR BangunDokumen8 halamanAbigael BR Bangunabigael23001Belum ada peringkat
- Bab 2 - 08413244027 PDFDokumen22 halamanBab 2 - 08413244027 PDFkiki indahBelum ada peringkat
- Modernisasi Pedesaan Dan DampaknyaDokumen30 halamanModernisasi Pedesaan Dan DampaknyaDwi Nurul AnnisaBelum ada peringkat
- Perubahan Sosial Budaya Dan Globalisasi: Media Pembelajaran Syahril SahlihinDokumen8 halamanPerubahan Sosial Budaya Dan Globalisasi: Media Pembelajaran Syahril SahlihinyasrisalamatBelum ada peringkat
- Makala Perekonomian Dan Mata Pencarian MasyarakatDokumen17 halamanMakala Perekonomian Dan Mata Pencarian MasyarakatMardi TasdirBelum ada peringkat
- Sosiologi Kelompok 13Dokumen7 halamanSosiologi Kelompok 13awaltiBelum ada peringkat
- Aspek-Aspek KulturalDokumen21 halamanAspek-Aspek KulturalWandy Aguero Shut100% (2)
- Modernisasi Dan Industrialisasi Di PedesaanDokumen9 halamanModernisasi Dan Industrialisasi Di PedesaanWendi Irawan DediartaBelum ada peringkat
- ModenisasiDokumen16 halamanModenisasiPriscilla PaulBelum ada peringkat
- Tugas 2 Perubahan Sosial Dan PembangunanDokumen4 halamanTugas 2 Perubahan Sosial Dan Pembangunanestiranita897Belum ada peringkat
- Tugas Teori Buddaya Tugas Kuliah Semester 3Dokumen8 halamanTugas Teori Buddaya Tugas Kuliah Semester 3Sara DenishaBelum ada peringkat
- Teori Pertumbuhan Ekonomi LengkapDokumen28 halamanTeori Pertumbuhan Ekonomi LengkapDio PratamaBelum ada peringkat
- Draft Proposal 2Dokumen11 halamanDraft Proposal 2Alfadrik '96Belum ada peringkat
- Perubahansosialbudaya K1 9FDokumen10 halamanPerubahansosialbudaya K1 9Fmisugai579Belum ada peringkat
- Modul 2Dokumen37 halamanModul 2zainal asrofahBelum ada peringkat
- Makalah SosiologiDokumen8 halamanMakalah Sosiologipatricia tehBelum ada peringkat
- Teori ModenisasiDokumen13 halamanTeori ModenisasiQianpin Gong100% (1)
- Ips Kelompok 8 9dDokumen22 halamanIps Kelompok 8 9dberaskencur844Belum ada peringkat
- Presentasi Isbd Modul 3Dokumen12 halamanPresentasi Isbd Modul 3rraaffii098Belum ada peringkat
- Antropologi Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial PertanianDokumen6 halamanAntropologi Dampak Modernisasi Terhadap Perubahan Sosial Pertaniannia dewiBelum ada peringkat
- Kelompok 8 Manajemen Pemasaran InterDokumen6 halamanKelompok 8 Manajemen Pemasaran InterBayu Saputra 371Belum ada peringkat
- Modul 10-Globalisasi Pangan (Kelompok 6)Dokumen15 halamanModul 10-Globalisasi Pangan (Kelompok 6)dwi shafira budiartiBelum ada peringkat
- Materi 2 Kuliah Sos PembDokumen17 halamanMateri 2 Kuliah Sos PembTiara ShabiraBelum ada peringkat
- Gerakan Sosial Dan Perubahan Sosial Oleh Mustain Mashud PDFDokumen20 halamanGerakan Sosial Dan Perubahan Sosial Oleh Mustain Mashud PDFAhmad SyarifudinBelum ada peringkat
- Pengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Perubahan SosiDokumen32 halamanPengaruh Globalisasi Dan Modernisasi Terhadap Perubahan SosiAbdurraafi Maududi Dermawan86% (7)
- Bab 2 Perubahan Sosial Budaya Dan GlobalisasiDokumen7 halamanBab 2 Perubahan Sosial Budaya Dan GlobalisasiHNB BBHBelum ada peringkat
- Tugas 1 Pengantar AntropologiDokumen7 halamanTugas 1 Pengantar Antropologihaneenakira74Belum ada peringkat
- Westernisasi - ANASDokumen11 halamanWesternisasi - ANASadikBelum ada peringkat
- Materi IPS Kelas IX Tahap IIIDokumen10 halamanMateri IPS Kelas IX Tahap IIIIndri YaniBelum ada peringkat
- Bahan Ajar IPS Kelas 9 BAB 2 Perubahan SosialBudaya Dan GlobalisasiDokumen32 halamanBahan Ajar IPS Kelas 9 BAB 2 Perubahan SosialBudaya Dan GlobalisasiadhiostBelum ada peringkat
- Makalah Modernisasi Dan GlobalisasiDokumen12 halamanMakalah Modernisasi Dan GlobalisasiArifHidayatBelum ada peringkat
- Ips 3Dokumen5 halamanIps 3DEWI SINTOWATIBelum ada peringkat
- Modernisasi Diartikan Sebagai PerubahanDokumen13 halamanModernisasi Diartikan Sebagai PerubahanmarilynudingBelum ada peringkat
- Perubahan Budaya MasyarakatDokumen11 halamanPerubahan Budaya MasyarakatElina NurjannahBelum ada peringkat
- Perkembangan Sistem Ekonomi Dan Mata Pencaharian Hidup ManusiaDokumen15 halamanPerkembangan Sistem Ekonomi Dan Mata Pencaharian Hidup ManusiaPuput Eka SafitriBelum ada peringkat
- Latihan Soal Kls XII IPSDokumen6 halamanLatihan Soal Kls XII IPSYogi Trizullian0% (1)
- Pembangunan PertanianDokumen144 halamanPembangunan PertanianWahyu HidayatBelum ada peringkat
- Kajian Pertanian Di Indonesia Dari Berbagai Teori SosiologiDokumen14 halamanKajian Pertanian Di Indonesia Dari Berbagai Teori SosiologiInoki Ulma Tiara100% (1)
- Geografi Kelas Xii PertemuanDokumen5 halamanGeografi Kelas Xii PertemuanAdyan NBelum ada peringkat
- T2 Sosial Budaya Dan Budaya DasarDokumen16 halamanT2 Sosial Budaya Dan Budaya DasarYoga HernandaBelum ada peringkat
- Masyarakat Industri 1Dokumen6 halamanMasyarakat Industri 1Rizal FirdausBelum ada peringkat
- Rangkuman Pertumbuhan EkonomiDokumen12 halamanRangkuman Pertumbuhan EkonomiWilliam AntonioBelum ada peringkat
- Ketahanan Pangan ShafaDokumen5 halamanKetahanan Pangan ShafaA1-24 Shafa Salsabila LesmanaBelum ada peringkat
- Teori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaDari EverandTeori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- The Three Shades from the Past to the Present Malay VersionDari EverandThe Three Shades from the Past to the Present Malay VersionBelum ada peringkat
- The Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionDari EverandThe Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionBelum ada peringkat