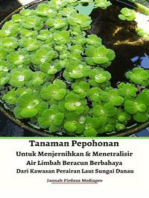BAB I, II, III, IV, V, Lampiran
BAB I, II, III, IV, V, Lampiran
Diunggah oleh
YosephLaseJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
BAB I, II, III, IV, V, Lampiran
BAB I, II, III, IV, V, Lampiran
Diunggah oleh
YosephLaseHak Cipta:
Format Tersedia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia sebagai negara berkembang memprioritaskan sektor industri
sebagai
penggerak
perekonomian
bangsa,
dengan
tujuan
akhir
untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
Perkembangan sektor industri memberikan pengaruh yang positif dalam
menunjang kehidupan masyarakat, dengan tersedianya lapangan pekerjaan,
produk industri hasil negeri sendiri, sumber devisa negara dari kegiatan ekspor
dan lain sebagainya. Namun disisi lain industri juga memiliki dampak negatif,
karena menghasilkan produk buangan yang disebut limbah, baik padat, cair
maupun gas, yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar dapat berakibat
fatal bagi kelangsungan hidup manusia pada khususnya, dan makhluk hidup pada
umumnya.
Tiap perusahaan memiliki kewajiban untuk mengolah dengan baik limbah
yang dihasilkannya, agar tidak merugikan lingkungan dan makhluk hidup
disekitarnya. Selain itu peran pemerintah sangat vital dalam mencegah dan
menanggulangi pencemaran lingkungan. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai
produk hukum yang berisikan pencegahan dan penanggulangan hasil buangan
industri, antara lain : Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air, Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup No :KEP-30/MENLH/10/2010 mengenai Baku Mutu Limbah Cair Bagi
Kegiatan Industri, Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
nomor 6 tahun 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri di
Jawa Barat dan lain sebagainya.
Setiap industri memiliki karakteristik limbah yang berbeda, oleh karena itu
diperlukan penanganan yang berbeda pula. Secara umum pengolahan limbah
dapat dilakukan secara fisika, kimia, dan biologi yang dapat dibagi ke dalam enam
tahap yaitu tahap pengolahan pendahuluan, pengolahan tingkat pertama, kedua,
ketiga,tahap desinfeksi dan tahapan lanjutan.
PT. Nalco Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
produksi bahan-bahan kimia khusus (specialty chemicals) yang digunakan untuk
pengolahan air (water teatment), pembangkit tenaga (power generator), sistem
pendingin (water cooling), industri kayu dan kertas (pulp and paper), industri
logam (metal industry), industri pengolahan, dan kilang minyak (refinery and
petroleum industry). Kegiatan produksi di PT. Nalco Indonesia, baik yang berasal
dari bagian produksi maupun bagian laboratorium, menghasilkan produk samping
berupa limbah yang berbetuk padat dan cair.
Pengolahan limbah cair hasil industrinya, PT. Nalco Indonesia telah
menerapkan sistem pengolahan limbah cair didalam perusahaannya sendiri,
sedangkan untuk limbah padat hasil industrinya, PT. Nalco Indonesia
berkerjasamadengan pihak PT. PPLI (Prasadha Pemunah Limbah Industri) untuk
diolah dengan baik dan benar. Masalah utama yang dihadapi oleh bagian Waste
Water Tretment Plan (WWTP) PT. Nalco Indonesia dalam pengolahan limbah cair
adalah tingginya nilai KOK (kebutuhan oksigen kimia) dan TDS (Total Dissolved
Solid) yang tinggi. Hal ini disebabkan karena banyaknya produk yang dihasilkan
baik dari segi jumlah maupun jenisnya. Mengatasi masalah tersebut PT. Nalco
Indonesia telah menerapkan sistem pengolahan limbah secara anaerobik, dengan
harapan dapat menurunkan nilai nilai KOK dan TDS hingga 80% sampai 90%.
1.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan :
Untuk mengetahui efisiensi dari proses pengolahan limbah cair secara
anaerobik dalam menurunkan nilai KOK dan TDS di PT. Nalco Indonesia.
1.3. Hipotesis
Proses pengolahan limbah secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia dapat
dilakukan untuk menurunkan kadar KOK dan TDS.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Air Limbah
Secara umum limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses
produksi baik industri, rumah sakit maupun domestik (rumah tangga), yang
kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan
karena tidak memiliki nilai ekonomis.
Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas limbah yaitu volume limbah,
kandungan
bahan
pencemar
dan
frekuensi
pembuangan
limbah
(http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah,2006).
Berdasarkan karakteristiknya limbah industri dibedakan menjadi 4 bagian
yaitu: limbah cair, limbah padat, limbah gas dan partikel, serta limbah B3 (Bahan
Berbahaya Beracun).
2.1.1 Pengertian Air Limbah
Menurut Sugiharto (1987), air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan
rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaaan serta
buangan lainnya. Demikian air buangan ini merupakan kotoran yang bersifat
umum. Menurut Mahida (1984), air limbah adalah buangan cairan yang berasal
dari lingkungan masyarakat dan lingkungan industri yang komponen utamanya
adalah air dan mengandung benda padat yang terdiri atas zat-zat organik dan
anorganik.
2.1.2 Penggolongan dan Komposisi Air Limbah
Menurut Sugiharto (1987), berdasarkan sumbernya air limbah dibedakan
menjadi tiga, yaitu air limbah rumah tangga, air limbah industri, air limbah
rembesan atau tambahan.
Sesuai dengan sumber asalnya, maka air limbah mempunyai komposisi
yang sangat bervariasi dari tempat dan setiap saat. Secara garis besar zat-zat yang
terdapat didalam air limbah dapat dikelompokkan seperti pada skema berikut ini.
Gambar 1. Skema pengelompokan bahan yang terkandung didalam air limbah
(Sugiharto, 1987)
2.1.3 Sifat- Sifat Air Limbah
Berdasarkan sifatnya air limbah dibedakan menjadi tiga yaitu sifat fisika,
kimia, dan biologi.
a. Sifat Fisika
Sifat fisika yang penting adalah kandungan zat padat sebagai efek
estetika, kejernihan, bau, warna dan temperatur.
Zat Padat
Berdasarkan ukuran partikelnya, padatan yang terdapat dalam air limbah
dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: zat padat terendap, zat padat yang
tercampur, serta zat padat yang terlarut. Padatan yang terdapat pada air limbah
dapat juga dibedakan menjadi padatan organik dan anorganik.
Jumlah kristal pada contoh air merupakan sisa penguapan dari contoh air
limbah pada suhu 103oC-105oC. Jumlah total endapan terdiri atas benda-benda
yang mengendap, terlarut dan tercampur (Sugiharto,1987). Analisis zat padat total
dapat ditentukan dengan menghitung berat residu dari air limbah yang telah
diuapkan dan dikeringkan dengan oven pada suhu 105oC sampai bobot konstan.
Bau
Bau dari air limbah dapat disebabkan oleh adanya bahan-bahan kimia,
ganggang, plankton, dan tumbuhan air, baik yang masih hidup atau yang sudah
mati (Fardiaz,1992).
Warna
Air yang terpolusi dapat dilihat dari warnaya yang tidak normal, warna
air yang terdapat di alam sangat bervariasi, misalnya air rawa yang berwarna
kuning, coklat atau kehijauan dan air sungai yang berwarna kuning kecoklatan
karena adanya lumpur (Fardiaz,1992). Pemeriksaan warnaditentukan dengan
membandingkan secara visual warna dari contoh dengan larutan standar yang
telah diketahui konsentrasinya. Didalam metode ini sebagai standar warna
digunakan larutan platina-kobalt dengan satuan mg/L Pt-Co.
Temperatur
Air yang telah digunakan dalam proses industri, seperti pada sistem
pendingin bila dialirkan kembali ke lingkungan akan mempunyai suhu yang lebih
tinggi dibandingkan dengan suhu asalnya. Hal ini dapat memberikan dampak
buruk bahkan kematian pada biota air seperti ikan dan mahklukhidup lainnya
(Fardiaz,1992).
b. Sifat Kimia
Kandungan bahan kimia yang ada dalam air limbah dapat merugikan
lingkungan mulai dari berbagai cara. Bahan organik terlarut dapat menghabiskan
oksigen dalam limbah serta akan menimbulkan rasa dan bau yang tidak sedap.
Bahan kimia yang penting ada didalam air limbah antara lain meliputi :
Bahan Organik
Menurut Achmad (2004), bahwa didalam lingkungan, bahan organik
dapat dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lemak. Senyawa-senyawa organik
pada umumnya tidak stabil dan mudah teroksidasi secara biologis atau kimia
menjadi senyawa stabil, antara lain menjadi CO 2 dan H2O. Proses inilah yang
menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut dalam perairan menurun. Menyatakan
kandungan bahan organik dalam perairan dilakukan dengan mengukur jumlah
oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai bahan tersebut sehingga menjadi
senyawa yang stabil.
Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)
Kebutuhan oksigen kimia (KOK) dapat diartikan sebagai banyaknya
oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang dibutuhkan dalam kondisi khusus
untuk menguraikan benda organik secara kimia (Sugiharto, 1987). KOK
digunakan sebagai ukuran dari oksigen serta senyawa organik yang terdapat
dalam contoh yang peka terhadap oksidator kuat. Contoh dari sumber khusus,
KOK dapat dihubungkan secara empiris dengan BOD, karbon organik, dan zat
organik.
Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)
KOB menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh
organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan
didalam air. Konsumsi oksigen dapat diketahui dengan mengoksidasi air pada
suhu 20o selama 5 hari, dan nilai KOB yang menunjukan jumlah oksigen yang
dikonsumsi dapat diketahui dengan menghitung selisih konsentrasi oksigen
terlarut sebelum dan sesudah inkubasi (Fardiaz,1992).
Penentuan nilai KOB dapat dilakukan dengan menghitung perbedaan
tekanan dalam sebuah sistem tertutup yang dinamakan oxidirect. Nilai KOB dapat
ditentukan di dalam botol tersebut tanpa dilarutkan terlebih dahulu. Unit KOB ini
terdiri dari botol sampel dan KOB sensor udara. Selama pengukuran KOB
bakteri-bakteri mengkonsumsi oksigen terlarut dalam sampel, CO 2 yang terlepas
pada saat yang sama diikat oleh kalium hidroksida secara kimia di dalam seal
gasket. Adanya seal gasket ini akan membuat tekanan bertambah dalam sistem,
tekanan ini diukur oleh BOD sensor dan di display sebagai nilai KOB dalam mg/L
O2.
Derajat Keasaman (pH)
pH menunjukan kadar asam atau basa dalam suatu larutan, melalui
konsentrasi ion hidrogen. Air yang mempunyai nilai pH antara 6,7-8,6
mendukung populasi hewan dan tumbuhan dalam air. Jangkauan pH itu
pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan di air tidak terganggu.
Pengukuran pH dapat dilakukan dengan metode potensiometri menggunakan pH
meter, dengan kertas universal atau dapat juga dengan titrasi asam basa.
Minyak dan Lemak
Minyak dan lemak yang terdapat dalam air limbah terdapat sebagai
padatan yang mengapung diatas permukaan air, dan ada juga yang mengendap
terbawa lumpur. Apabila lemak tidak dihilangkan sebelum dibuang ke saluran air
limbah dapat mempengaruhi kehidupan yang ada dipermukaan air dan
menimbulkan lapisan tipis dipermukaan sehingga membentuk selaput.
Pencemaran
air
oleh
minyak
sangat
merugikan
karena
dapat
menyebabkan hal-hal sebagai berikut :
Konsentrasi oksigen terlarut menurun dengan adanya minyak karena lapisan
film minyak menghambat pengambilan oksigen oleh air.
Penetrasi sinar dan oksigen yang menurun dengan adanya minyak dapat
mengganggu kehidupan tanaman air (Fardiaz, 1992).
Logam Berat
Logam berat seperti arsen, kadmium, timbal, dan merkuri bila terdapat
dalam konsentrasi melebihi ambang batas dapat bersifat toksik bagi makhluk
hidup yang berada di sekitar daerah perairan yang tercemar.
Arsen dihasilkan antara lain dari pembakaran batu bara dan hasil akhir
pertambangan tembaga dan emas. Arsen sangat berbahaya karena
bersifat
karsinogenik.
Kadmium dalam air berasal dari pembuangan limbah industri dan limbah
pertambangan, kadmium secara luas digunakan dalam industri pelapisan logam.
Kadmium dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, kerusakan ginjal dan
kerusakan dari sel-sel darah merah.
Timbal dapat berasal dari bahan bakar bertimbal, batuan kapur dan
galena. Timbal banyak digunakan sebagai bahan untuk solder dan untuk
menyambung pipa air. Timbal dapat menyebabkan kerusakan parah pada ginjal,
sistem reproduksi, hati dan otak, serta sistem syaraf sentral dan bisa menyebabkan
kematian.
Merkuri dapat masuk secara langsung keperairan alami dari buangan
industri juga dapat masuk melalui air hujan dan pencucian tanah. Merkuri banyak
digunakan dalam peralatan vakum di laboratorium dan juga sebagai pestisida.
Merkuri dapat menyebabkan kerusakan syaraf, kebutaan dan cacat bayi dalam
kandungan (Achmad, 2004).
c. Sifat Biologis
Mikroorganisme yang terdapat dalam air limbah berasal dari berbagai
sumber seperti udara, tanah, sampah, lumpur, hewan, dan tanaman baik yang
hidup maupun yang mati, kotoran manusia dan sebagainya. Sifat biologis air
limbah ditentukan dengan ada tidaknya bakteri patogen yang terkandung dalam
air limbah. Bakteri patogen yang sering ditemukan didalam air terutama adalah
bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan seperti Vibrio cholerae, shigella
dysentriae, salmonella typhosa, salmonella paratyphi dan sebagainya (Fardiaz,
1992).
2.1.4 Proses Pengolahan Air Limbah
Menurut Sugiharto (1987), tujuan utama pengolahan air limbah adalah
untuk mengurangi KOB, partikel tercampur serta membunuh organisme patogen.
Selain itu, diperlukan juga tambahan pengolahan untuk menghilangkan bahan
nutrisi, komponen beracun serta bahan yang tidak dapat didegradasikan agar
konsentrasi yang ada menjadi rendah.
Secara garis besar kegiatan pengolahan air limbah dapat dikelompokan
menjadi enam bagian, yaitu pengolahan pendahuluan, pengolahan pertama,
pengolahan kedua, pengolahan ketiga, tahap desinfeksi, pengolahan tingkat
lanjutan.
a. Pengolahan Pendahuluan
Tujuan pengolahan pendahuluan adalah untuk mensortir kerikil, lumpur,
menghilangkan
zat
padat,
dan
memisahkan
lemak.
Adapun
kegiatan
tersebutberupa pengambilan benda terapung dan pengambilan benda yang
mengendapan seperti pasir.
b. Pengolahan tahap pertama
Pengolahan tahap pertama bertujuan untuk menghilangkan zat padat
tercampur melalui pengendapan atau pengapungan. Pengendapan adalah kegiatan
utama pada tahap ini dan pengendapan yang dihasilkan terjadi karena adanya
kondisi yang sangat tenang. Bahan kimia dapat juga ditambahkan untuk
menetralkan keadaan atau meningkatkan pengurangan dari partikel-partikel
kecilyang tercampur. Dengan adanya pengendapan dapat mengurangi kebutuhan
oksigen pada pengolahan biologis selanjutnya dan pengendapan yang terjadi
adalah pengendapan secara gravitasi.
c. Pengolahan tahap kedua
Pengolahan tahap kedua umumnya mencakup proses biologis untuk
mengurangi bahan-bahan organik melalui mikroorganisme yang ada didalamnya.
Pada tahap ini biasanya menggunakan reaktor untuk mengolah lumpur aktif dan
saringan penjernih.
d. Pengolahan tahap ketiga
Menurut Sugiharto (1987), Pengolahan tahap ketiga adalah kelanjutan
dari pengolahan-pengolahan sebelumnya. Oleh karena itu pengolahan jenis ini
baru akan dipergunakan apabila pada pengolahan pertama dan kedua masih
banyak zat tertentu yang masih berbahaya bagi masyarakat umum. Pengolahan
tahap ketiga ini merupakan pengolahan khusus, sesuai dengan kandungan
terbanyak dalam air limbah. Beberapa jenis pengolahan yang sering dipergunakan
antara lain saringan pasir yang terdiri atas saringan pasir cepat dan saringan pasir
lambat, peubahan CN-, dan osmosis bolak-balik.
e. Tahap Desinfeksi
Pembunuhan bakteri bertujuan untuk mengurangi atau membunuh
mikroorganisme patogen yang ada dalam air limbah. Pengurangan atau
pembunuhan mikroorganisme patogen dilakukan dengan cara penambahan bahan
kimia seperti klorin oksida, bromin, rodin, permanganat, logam berat, asam dan
basa kuat. Ada dua macam mekanisme desinfeksi, yaitu :
Dengan cara merusak atau meninaktifkan enzim utama sehingga terjadi
kerusakan sel.
Dengan merusak langsung dinding sel seperti yang dilakukan apabila
menggunakan bahan radiasi ataupun panas.
f. Pengolahan tingkat lanjutan
Pengolahan tingkat lanjutan merupakan pengolahan lumpur yang
dihasilkan dari setiap tahap pengolahan, lumpur tersebut diolah secara khusus agar
dapat dimanfaatkan kembali.
2.2 Pengolahan Limbah Cair Secara Anaerobik
10
Pengolahan secara anaerobik biasa digunakan untuk pengolahan limbah cair,
seperti halnya pada pencemaran lumpur. Hasil akhir dari degradasi anaerobik
adalah gas, dimana hampir sebagian besar dihasilkan gas metana, karbon dioksida,
dan dalam jumlah kecil dihasilkan gas hidrogen dan hidrogen sulfida
(Ramalho,1977).
Proses pengolahan air limbah secara anaerobik termasuk kedalam proses
biologis yang tidak memerlukan kehadiran oksigen serta dalam prosesnya
melibatkan mikroorganisme.
2.2.1 Pengertian Fermentasi
Fermentasi berasal dari bahasa latin fervere yang berarti mendidihkan.
Seiring perkembangan teknologi, definisi fermentasi meluas, menjadi semua
proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang
disebut metabolit primer dan sekunder dalam suatu lingkungan yang
dikendalikan.Fermentasi anaerobik adalah proses pemecahan senyawa organik
menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan melibatkan mikroorganisme dalam
keadaan tanpa oksigen.
Bakteri yang berperan dalam proses fermentasi adalah bakteri anaerobik
baik yang bersifat fakultatif maupun obligat. Bakteri anaerobik tidak
membutuhkan oksigen dan kadang kala oksigen molekuler sangat toksik
terhadapnya (Achmad,2004).
2.2.2 Tahapan Degradasi Anaerobik
Tahapan degradasi anaerobik terdiri atas tiga tahap, yaitu : tahap hidrolisis,
asetogenesis dan metanogenesis. Tahapan degradasi dari bahan-bahan organik
menjadi metana dalam bak anaerobik disajikan pada Gambar 2.
11
Gambar 2. Diagram degradasi bahan-bahan organik (Horan, 1993).
a. Tahap Hidrolisis
Pada tahap hidrolisis, senyawa organik kompleks dipecah kedalam
bentuk gula sederhana, asam amino dan asam lemak. Bahan organik yang terdiri
atas polisakarida, protein dan lemak tidak dapat didegradasi oleh bakteri metan
secara langsung, karena bakteri tersebut hanya mengkonsumsi asam asetat,
hidrogen dan karbon dioksida sebagai subtrat. Degradasi senyawa organik polimer
memerlukan beberapa macam bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik
obligat (Indriyati, 2002).
b. Tahap Asetogenesis
Pada tahap kedua senyawa organik yang dihasilkan pada tahap
sebelumnya dipecah lagi menjadi karbon dioksida, hidrogen, dan sejumlah besar
asam asetat, setelah itu dihasilkan pula asam butirat, asam propionat serta asam
laktat.
12
Menurut Ramalho (1977), pada tahap fermentasi asam, zat-zat organik
dipecah menjadi asam-asam organik. Pada tahap ini dihasilkan sebagian besar
asam asetat (CH3COOH), asam propionat (CH3CH2COOH) dan asam butirat
(CH3CH2CH2COOH).
c. Tahap Metanogenesis
Tahap metanogenesis merupakan tahap terakhir dari proses degradasi
anaerobik, pada tahap ini dihasilkan gas metana dan karbon dioksida.Menurut
Ramalho (1977), pada tahap metanogenesis bakteri metanogenik mengubah asam
dengan rantai karbon panjang menjadi metana, karbondioksida dan asam yang
memiliki rantai karbon yang lebih pendek. Molekul asam dipecah secara berulang
kali dengan cara yang sama. Asam asetat dikonversi secara langsung menjadi
karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4) .
CH3COOH CH4 + CO2
Biogas yang dihasilkan dari proses pengolahan secara anaerobik adalah
berupa gas metana sebesar 50% hingga 80%, karbon dioksida sebesar 20% hingga
50%, dan sisanya berupa gas hidrogen, karbon monoksida nitrogen, oksigen, dan
hidrogen sulfida. Persentasi masing-masing komponen gas relatif tergantung pada
bahan
material
dan
proses
pada
saat
pembakaran
(http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah,2006).
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Degradasi Anaerobik
a. Suhu
Untuk hasil yang optimal, reaktor pencerna harus dijaga pada suhu yang
tetap. Bakteri metan aktifitasnya akan berkurang pada suhu dibawah 10OC, namun
aktivitasnya akan meningkat apabila suhu dinaikan. Bakteri metan dapat tumbuh
optimal pada suhu sekitar 30OC-35OC. Kondisi alam indonesia yang beriklim
tropis sangat cocok untuk mendukung pertumbuhannya.
b. Derajat Keasaman (pH)
Konsentrasi ion hidrogen adalah ukurun kualitas dari air maupun air
limbah. Adapun kadar yang baik adalah dimana masih memungkinkan kehidupan
biologis didalam air berjalan dengan baik (Sugiharto, 1987). pH yang sesuai untuk
pertumbuhan bakteri dalam reaktor anaerob adalah pada kisaran 6,8 sampai 7,4
(Jorgensen, 1979). Pada pH dibawah 6 atau diatas 8 fase metanorgenik tidak dapat
berjalan. Pada awal degradasi anaerobik yaitu pada saat terjadi pembentukan asam
13
pH turun dengan tajam namun pada tahap selajutnya pada saat asam-asam tersebut
dipecah oleh bakteri metan, pH akan kembali naik. Jika jumlah asam lemak volatil
yang terbentuk lebih besar dibandingkan dengan asam lemak volatil yang telah
dipecah oleh bakteri metan maka nilai pH akan jatuh dan dapat mengakibatkan
kematian pada bakteri tersebut.
c. Nutrisi
Untuk pertumbuhan mikroorganisme membutuhkan nutrisi yang cukup.
Air limbah harus mengandung nutrisi seimbang dengan perbandingan KOK,
nitrogen dan fosfat atau disingkat C : N : P = 800 : 5 : 1. Untuk pertumbuhan
bakteri membutuhkan sumber energi berupa senyawa karbon selain itu dibutuhkan
sumber energi berupa senyawa karbon selain itu dibutuhkan pula nitrogen sebagai
pembentuk sitoplasma juga berperan dalam dintesis protein serta penyusun ATP
(Adenosin Tri Fosfat) dan ADP (Adenosin Di Fosfat).
d. Waktu Tinggal
Waktu tinggal (retention time) adalah waktu yang diperlukan oleh suatu
tahap pengolahan agar tujuan pengolahan dapat dicapai secara optimal. Setiap
bangunan pengolah mempunyai waktu tinggal yang berbeda-beda (Sugiharto,
1987). Berdasarkan data hasil percobaan waktu retensi bervariasi yaitu antara 2
hingga 20 hari. Untuk waktu retensi yang panjang, hampir semua asam volatil
diubah menjadi metana dan karbondioksida.
e. Zat Beracun
Logam berat seperti tembaga, perak, timbal, krom arsen dan boron adalah
zat yang beracun terhadap mikroorganisme, begitu juga bila terdapat antibiotik
pada air limbah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu
sebelum memasuki proses biologis zat-zat tersebut harus dihilangkan terlebih
dahulu karena dapat mempengaruhi terhadap jumlah biogas yang dihasilkan
(Sugiharto,1987).
2.2.4 Model Reaktor Anaerob
Reaktor anaerobik terbuat dari beton, baja, plastik atau batu bata dapat
berbentuk seperti silos, kolam atau palung yang dapat ditempatkan dibawah tanah
atau dipermukaan. Semua model mempunyai komponen dasar yang sama, terdiri
atas tangki pre-mixing, digester vessel, sistem untuk penggunaan biogas, dan
14
sistem untuk mendistribusikan atau menyebarkan effluent (U.S. Departement of
Energy, 2004).
Ada dua tipe dasar model reaktor anaerob yaitu tipe batch dan tipe kontinyu.
Tipe batch merupakan tipe yang paling sederhana, bahan organik ditambahkan ke
dalam reaktor pada saat proses akan dimulai dan reaktor ditutup selama proses
berjalan (http://en.wikipedia.org/wiki/Anaerobik_digestion, 2006).
Pada tipe kontinyu, bahan organik dimasukkan ke dalam reaktor secara
teratur dan tetap. Bahan organik yang telah dicerna dikeluarkan dari reaktor
menggunakan mesin atau oleh kekuatan bahan masukkan baru yang mendorong
keluar bahan yang telah dicerna (U.S. Departemen of Energi, 2003).
2.2.5 Kelebihan dan kekurangan Pengolahan Limbah Cair secara Anaerobik
Kelebihan dari pengolahan secara anaerobik adalah sebagai berikut:
Proses pengolahan limbah secara anaerobik relatif lebih murah
dibandingkan dengan pengolahan secara aerobik, sebab pada pengolahan
secara anaerobik tidak perlu mengeluarkan biaya untuk aerasi.
Hasil akhir berupa biogas dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik,
menggerakan mesin, dan sebagai pemanas.
Selain memiliki beberapa kelebihan, pengolahan anaerobik juga mempunyai
beberapa kekurangan :
Proses anaerobik menghasilkan bau yang tidak sedap, terutama pada saat
produksi hidrogen sulfida.
Proses anaerobik membutuhkan waktu tinggal yang lebih panjang
dibandingkan dengan proses aerobik.
Proses anaerobik mempunyai kontribusi dalam menambah beban air
limbah, sebab dapat menghasilkan kadar nitrit yang cukup tinggi.
Sehingga diperlukan proses pengolahan lanjutan, sebelum dialirkan ke
saluran pembuangan.
2.3
Limbah PT Nalco Indonesia
PT Nalco Indonesia menghasilkan limbah berupa limbah padat dan limbah
cair. Limbah cair dikelola sendiri oleh PT Nalco Indonesia dan dimanfaatkan
untuk proses pencucian drum, kontainer dan lain sebagainya. Sedangkan untuk
limbah padat dan minyak dikelola oleh PPLI.
15
2.3.1 Karakteristik Limbah Cair PT Nalco Indonesia
Jenis kandungan utama limbah cair PT Nalco Indonesia terdiri atas: polimer,
campuran nitrogen, campuran fosfat dan minyak. Volume limbah cair PT Nalco
Indonesia setiap harinya mencapai angka 6 m3, dengan rincian yang tercantum
pada Tabel 1.
Tabel 1. Asal Limbah PT Nalco Indonesia
Debit
Asal
Cucian blending dari pabrik
Cucian kontainer dan drum berkas pakai
Cucian laboratorium dan dapur
TOTAL
Sumber: Data perusahan, 2003
Jumlah (%)
(m3/hari)
2
3
1
6
33,33
50,00
16,67
100,00
2.3.2 Pengolahan Limbah Cair PT Nalco Indonesia
Tujuan utama dari kegiatan pengolahan limbah di PT Nalco Indonesia
adalah untuk mengolah limbah cair dari proses produksi sehingga hasil akhir air
dapat dipergunakan kembali atau air dapat dibuang ke badan sungai yang
memenuhi persyaratan baku mutu libah cair.
a. Tahap Pendahuluan
Limbah yang berasal dari pabrik, laboratorium dan dapur disatukan pada
bak penampung atau disebut juga sum pit yang berukuran 20 m3. Selain untuk
menampung air limbah, bak ini juga digunakan untuk membuat kondisi air limbah
yang selalu homogen, karena dalam kenyataannya air limbah yang datang sifatnya
selalu berubah, tergantung dari proses pengujian, untuk menjaga agar air limbah
selalu sama kondisinya maka sebaiknya pada bak penampungan harus selalu terisi
air (Susanto et al., 1997).
Selanjutnya limbah melewati scrubber, dimana pada tahap ini limbah
yang berupa minyak dan polimer dipisahkan dan limbah yang cair lainnya masuk
ke dalam proses sedimentasi.
b. Tahap Sedimentasi
Limbah cair sisa
penyaringan
masuk
ke
dalam
tangki
koagulator/flokulator yang berukuran 30 m3, pada tangki ini terjadi proses
koagulasi dengan penambahan PAC dan proses flokulasi dengan penambahan
produk N9905, tujuan dari penambahan koagulan dan flokulan adalah untuk
16
menghilangkan zat padat tercampur dan mengubah partikel-partikel kecil menjadi
partikel-partikel besar sehingga lebih mudah mengendap.
Pada proses ini menghasilkan lumpur yang selanjutnya ditampung pada
bak sludge Thickener menuju filter press dimana air yang terkandung dalam
lumpur dikeluarkan. Selanjutnya lumpur yang telah bebentuk lempengan
dicampur dengan senyawa polimer, agar dihasilkan lumpur yang lebih padat dan
stabil, kemudian dikeringkan dalam dryer container.
c. Pengolahan Secara Biologi
Tahap selanjutnya limbah cair melewati proses biologi. Menurut Susanto
et,al. (1997). Proses biologi dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan
bakteri dan penambahan oksigen ke dalam air limbah. Secara umum reaksi yang
terjadi pada proses aerobik adalah sebagai berikut:
bakteri
Bahan organik + Oksigen
sel bakteri baru + H2O + CO2
Pada proses biologi masih dapat dibedakan menjadi dua cara yakni:
aerobik dan anerobik, untuk limbah cair dengan kandungan bahan organik yang
sangat tinggi sebaiknya melalui proses anaerobik sebelum dilakukan proses
aerobik.
Pada pengolahan secara anaerobik, proses berjalan tanpa adanya oksigen
dan melibatkan mikroorganisme dalam menguraikan bahan-bahan organik yang
terkandung dalam air limbah. Proses ini dimaksudkan untuk menurunkan nilai
KOK yang tinggi (>2000 mg/L).
Proses selanjutnya berlangsung secara aerobik, pada bak aerob proses
penguraian bahan organik berjalan dengan kehadiran oksigen. Oksigen
ditambahkan ke dalam air limbah dengan cara mengontakkan air limbah dengan
oksigen melalui pemutaran baling-baling yang diletakkan pada permukaan air
limbah (Sugiharto, 1987). Bak aerasi adalah bak yang berfungsi untuk melarutkan
oksigen yang digunakan untuk mengoksidasi bahan cemaran yang masih ada dan
untuk membantu bakteri dalam memecah bahan organik yang ada dalam air
(Susanto et al., 1997). Selain itu bak aerob merupakan tempat untuk
menambahkan lumpur aktif dan kapur dengan tujuan untuk mengendapkan fosfat
dan menghilangkan amonia.
d. Pengolahan Tahap Lanjut
17
Limbah yang telah melewati proses biologi selanjutnya memasuki bak
flokulasi (floculant pond), pada tahap ini air limbah ditambahkan senyawa
polimer dengan tujuan untuk mengendapkan bahan organik terlarut dan bakteri
berbahaya. Bak pengendapan adalah bak yang digunakan untuk mengendapkan
bahan cemaran yang telah direaksikan dengan bahan kimia ataupun tanpa bahan
kimia. Bak pengedapan memegang peranan penting, sebab pada bak pengendapan
dibutuhkan waktu yang cukup untuk mengedapkan bahan cemaran. Faktor yang
mempengaruhinya antara lain debit air dan waktu tinggal yang dibutuhkan bahan
cemaran untuk mengendapkan (Susanto et al., 1997). Partikel yang memiliki berat
jenis lebih dari satu akan terendapkan pada setlement pond sedangkan partikel
yang memiliki berat jenis kurang dari satu akan mengalir menuju stabilizer pond
yang selanjutnya menuju bak penyerapan nitrogen dan fosfor.
Limbah cair yang telah melewati proses pengolahan dimanfaatkan untuk
pembilasan awal dalam pencucian kemasan, pencucian lantai produksi dan apabila
telah dipastikan sesuai dengan parameter baku mutu air buangan limbah hasil
pengolahan dibuang ke badan sungai.Langkah-langkah pengolahan limbah di
WWTP PT Nalco Indonesia di sajikan pada Lampiran 3.
2.4 Parameter Pengolahan Limbah Cair Secara Anaerobik PT. Nalco
Indonesia.
2.4.1 Suhu
Pengukuran suhu air limbah dapat dilakukan dengan termometer, salah
satunya termometer air raksa dalam gelas yang merupakan termometer yang
dibuat dari air raksa yang ditempatkan pada suatu tabung kaca. Tanda yang
dikalibrasi pada tabung membuat temperatur dapat dibaca sesuai panjang air raksa
di dalam gelas, bervariasi sesuai suhu. Untuk meningkatkan ketelitian, biasanya
ada bohlam air raksa pada ujung termometer yang berisi sebagian besar air raksa;
pemuaian dan penyempitan volume air raksa kemudian dilanjutkan ke bagian
tabung yang lebih sempit.
2.4.2 pH (derajat keasaman)
Pengukuran pH dapat dilakukan dengan teknik klorimetri dan
potensiometri (elektrometri). Teknik kolorimetri menggunakan indikator (celupan)
18
selama suatu titrasi asam basa, teknik potensiometri menggunakan pH-meter
bersama elektrodanya. Pengukuran pH secara potensiometri dilakukan melalui
pembacaan potensial melalui elektrodanya. Pengukuran pH secara potensiometri
dilakukan melalui pembacaan potensial dari elektroda dengan referensi (sensitif
terhadap suhu) dan pH-meter harus dikalibrasi ulang sebelum digunakan
2.4.3 Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)
Penetapan KOK dapat ditentukan dengan metode refluks terbuka
titrimetri, metode refluks tertutup-titrimetri atau metode refluks tertutup
spektrofotometri. Contoh direfluks selama 2 jam dengan larutan kalium dikromat
dalam keadaan asam mendidih. Perak sulfat ditambahkan sebagai katalisator,
sedangkan merkuri sulfat ditambahkan untuk menghilangkan gangguan klorida.
Sisa kalium dikromat yang tersisa, dapat ditentukan dengan metode titrasi
menggunakan amonium sulfat serta digunakan indikator feroin untuk menentukan
titik akhir titrasi yaitu di saat warna hijau-biru larutan berubah menjadi coklatmerah. Selain dengan metode titrasi, nilai KOK dapat juga ditentukan dengan
metode spektrofotometri visible pada panjang gelombang 600 nm.
Pada metode ini digunakan oksidator kuat kalium dikromat sebagai
sumber oksigen. Sebagian besar zat organik dioksidasi oleh larutan dikromat
dalam keadaaan asam mendidih.
Reaksi :
AgSO4
CaHbOc + Cr2O72- + H+
CO2 + H2O + Cr3+
Reaksi berlangsung selama dua jam dalam alat refluks agar zat organik
yang mudah menguap tidak keluar. Perak sulfat ditambahkan sebagai katalis
untuk mempercepat reaksi.
2.4.4 Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)
Menurut Fardiaz (1992), Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB) atau
Biochemical Oksygen Demand (BOD) menunjukan jumlah oksigen terlarut yang
dibutuhkan organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan
19
buangan di dalam air. Jadi, nilai oksigen kebutuhan oksigen biologis (KOB) tidak
menunjukan bahan organik sebenarnya, tetapi hanya mengukur secara relatif
jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan buangan
tersebut.
2.4.5 TDS (Total Dissolved Solid)
Padatan terlarut (Dissolved Solid) adalah padatan yang mempunyai
ukuran lebih kecil dari pada padatan tersuspensi. Padatan terdiri atas senyawasenyawa anorganik dan organik yang terlarut di dalamnya. Kualitas air limbah
dapat ditunjukan oleh jumlah dan jenis zat- zat yang terlarut. Besarnya nilai TDS
pada saat >2000 mg/L ditentukan oleh banyaknya bahan buangan padat yang
padat yang larut. Pada batasan tertentu, air yang mengandung TDS >2000 mg/L
akan memberikan rasa tidak enak dan timbul rasa mual (Fardiaz,1992).
Penetapan TDS (Total Dissolved Solid) dilakukan berdasarkan metode
konversi. Prinsip metode ini, nilai TDS (perkiraan) diperoleh dari konversi
pengukuran DHL (daya hantar listrik) dengan menggunakan rasio (TDS/DHL)
yang ditetapkan.
2.4.6 F/M (Food to Microorganisme Ratio)
F/M (Food to Microorganisme Ratio) merupakan perbandingan antara
ketersediaan bahan organik sebagai bahan makanan (BOD) dengan jumlah
miksoorganisme lumpur aktif di dalam tangki anaerob. Nilai F/M ini dikontrol
oleh kegiatan wasting, yaitu kegiatan pembuangan bagian dari massa mikroba dari
anaerob atau dari bak pengendapan kedua. Nilai F/M sebaiknya berkisar antara
0,1-1,0, nilai ini menunjukan bahwa terjadinya penggumpalan lumpur dan
pengendapan dalam tangki sedimen yang disebabkan oleh metabolisme bahan
organik berjalan sederhana (Metcalf dan Eddy,Icn,1981).
Perhitungan=
Food
BOD
=
Microorganisme MLSS
2.4.7 MLSS (Mixed Liquor Suspended Solid)
Mixed Liquor Suspended Solids (MLSS) merupakan kandungan padatan
tersuspensi yang terdapat di dalam bak anaerobik. Padatan ini tersaring pada fibre
20
glass filter yang berpori-pori 1. Nilai MLSS yang baik dalam proses lumpur aktif
di bak anaerob adalah 2000-3500 mg/L (Metcalf dan Eddy,Icn,1981).
2.5 Spektrofotometri
Spektrofotometri merupakan suatu metode yang digunakan untuk
menganalisis suatu zat kimia baik kuantitatif maupun kualitatif atau dapat juga
digunakan untuk menentukan rumus bangun dari suatu senyawa kimia yang
belum diketahui. Alat yang digunakan disebut spektrofotometer.
2.5.1 Spektrofotometri Sinar Tampak (Visible)
Radiasi sinar tampak bila diabsorbsi oleh suatu senyawa, hasilnya adalah
transisi elektron dari keadaan dasar (energi terendah) kekeadaan energi yang lebih
tinggi karena adanya rangsangan. Spektrofotometri sinar tampak atau visible
banyak digunakan untuk analisis kuantitatif suatu zat dan memancarkan energi
radiasi pada daerah dengan panjang gelombang antara 400-800 nm. Panjang
gelombang dari sinar tampak diukur dalam nanometer dimana 1 nm = 10 -9 m dan
dapat juga dinyatakan dalam satuan angstrom, dimana 1A = 10 -10 m atau satuan
milimikron (m), dimana 1 m = 1 nm (Fesenden & Fesenden, 1997).
Jika suatu berkas sinar melalui suatu medium yang serba sama, sebagian
dari cahaya datang (Io) akan diabsorpsi sebanyak (Ia), sebagian dapat dipantulkan
(Ir) dan sisanya akan diteruskan (It). Hubungan di atas dapat dituliskan sebagai
berikut :
Io = Ia + Ir + It
Keterangan :
Io = sinar yang masuk
Ia = sinar yang diserap
Ir = sinar yang dipantulkan
It = sinar yang diteruskan
Pada tahun 1760, Lambert menyelidiki hubungan antara absorpsi radiasi dan
panjang jalan melaui medium yang menyerap. Bunyi dari hukum Lambert adalah
bila suatu cahaya monokromatis dialirkan melalui suatu media maka turunnya
intensitas cahaya berbanding lurus dengan panjang media penyerap .
21
Pada tahun 1830, Beer merumuskan hubungan antara konsentrasi zat
penyerap dan besarnya absorpsi. Bunyi hukum Beer adalah bila suatu cahaya
monokromatis dialirkan melalui suatu medium turunnya intensitas cahaya
berbanding lurus dengan naiknya kepekatan.
Dari kedua hukum diatas dapat diketahui hubungan antara transmitan, tebal
cuplikan, dan konsentrasi sebagai dasar pengukuran spektrofotometri, hubungan
tersebut dikenal dengan hukum Lambert-Beer dan dapat dinyatakan sebagai
berikut :
log It
Io = a. b. c = A
Keteranagan :
Io = sinar yang masuk
It = sinar yang diteruskan
a = Absorbtivitas
b = tebal media
c = konsentrasi
A = Absorbansi
2.5.2 Instrumentasi Spektrofotometer
Suatu spektrofotometer tersusun dari sumber cahaya, monokromator sel
penyerap, detektor, penguat arus dan penampil data. Gambar 3. merupakan
diagram dari komponen spektrofotometer jenis single beam.
22
.
Gambar 3. Diagram komponen spektrofotometer single beam.
a. Sumber Cahaya
Sumber energi radiasi yang biasa digunakan pada daerah tampak
adalah lampu wolfram. Lampu walfram dapat memancarkan cahaya
tampak pada kisaran panjang gelombang 400 nm hingga 800 nm.
Kelebihan dari lampu walfram adalah energi radiasi yang dibebaskan
tidak bervariasi pada berbagai panjang gelombang. Arus cahaya yang
dipancarkan tergantung dari tegangan lampu, untuk memperoleh
tegangan yang stabil dapat digunakan transformator sebab jika potensial
tidak
stabil,
akan
didapatkan
energi
yang
bervariasi,
untuk
mengkompensasi hal ini maka dilakukan pengukuran transmitan larutan
sampel selalu disertai larutan pembanding (Khopkar, 1990).
b. Monokromator
Monokromator berfungsi sebagai pengubah cahaya polikromatik
menjadi cahaya monokromatik. Alat yang digunakan dapat berupa prisma
atau
grating.
Sumber
cahaya
dari
wolfram
dilewatkan
pada
monokromator menjadi berbagai sinar yang monokromatis dan
mempunyai panjang gelombang tertentu. Selanjutnya, kita dapat
mengisolasi salah satu panjang gelombang yang diperlukan pada suatu
pengukuran.
c. Sel Penyerap
23
Sel penyerap merupakan suatu wadah untuk menyimpan larutan
contoh yang akan dianalisis atau lebih dikenal dengan sebutan kuvet.
Pada umumnya kuvet mempunyai tebal sebesar 10 mm, dan berbentuk
slinder ataupun persegi (Khopkar, 1990).
d. Detektor
Detektor berfungsi sebagai pemberi respon terhadap cahaya pada
berbagai panjang gelombang. Detektor berkerja dengan cara mengubah
energi cahaya menjadi energi listrik, dimana cahaya yang ditransmitasikan,
selanjutnya diubah menjadi besaran-besaran yang dapat dibaca.
e. Penguat Arus ( Amplifier )
Fungsi utama dari amplifier adalah untuk memperkuat arus listrik
yang berasal dari detektor menjadi suatu potensial yang cukup besar untuk
menggerakan alat pencatat. Amplifier berkerja dengan cara menangkap
isyarat masuk (input) dari rangkaian detektor dan melalui proses elektronik
tertentu menghasilkan suatu isyarat keluar (output), dan secara langsung
dicatat dalam unit transmisi atau absorban.
f. Penampil data (display)
Penampil data adalah suatu bagian yang memonitor output dari
detektor dan menampilkan dalam besaran-besaran tertentu baik absorban,
transmitan dan konsentrasi.
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Laboratorium PT. Nalco Indonesia yang
beralamat jalan Pahlawan no.25, Ds. Karang Asem Timur, Citeureup, Kab. Bogor.
Dilaksanakan mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012.
3.2.
Bahan dan Alat
3.2.1. Bahan
24
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan uji dan
bahan kimia. Bahan uji meliputi contoh air limbah yaitu air limbah hasil proses
koagulasi flokulasi sebagai inlet, air limbah yang berada pada bak anaerobik
sebagai proses serta air limbah hasil proses pengolahan anaerobik sebagai outlet.
Bahan kimia larutan perak sulfat 0,0324 M, larutan pencerna (kalium dikromat,
asam perak sulfat, merkuri sulfat), larutan asam sulfat 4 N, tablet NaOH, larutan
buffer pH 4, 7, dan 10, air demin.
3.2.2. Alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabung HACH
lengkap dengan tutup plastik, HACH COD Reactor, Nalco pH-meter,
konduktometer, termometer, membran filter steril dengan pori berukuran 0,45 m,
kertas Whatman, Vacum Flask, kompresor, labu ukur 50 mL dan 100 mL, pipet
volumetric 1 mL, 6 mL, dan 10 mL, Spektrofotometer Visibel merek Nalco seri
DR-2800, kuvet 10 mL,eksikator, pipet tetes, pipet Mohr 5 mL, Hot plate merek
Thermolyne, bulb, gelas ukur 250 mL, labu semprot.
3.3. Metode
Penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu, pengambilan sampel, dan
pengujian.
3.3.1. Pengambilan sampel
Pengambilan contoh air limbah (sampel)
dilakukan sebanyak 3 kali
ulangan dalam satu unit pengolahan limbah cair, yaitu diambil dari tangki
keluaran flokulasi/koagulasi (inlet), bak proses anaerob, dan bak hasil proses
anaerob (outlet). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan derigen
(polyethylene) dengan ukuran 1 liter.
25
Gambar 4. Skema Pengambilan Sampel
Pengambilan sampel inlet
dilakukan pada hari pertama dimana air
limbah baru akan masuk ke tangki anaerob. Pengambilan sampel proses dilakukan
pada hari pertama proses sampai dengan hari terakhir proses yaitu pada hari
keenam. Pengambilan sampel outlet dilakukan pada hari keenam dimana air
limbah baru akan masuk ke tangki aerob.
3.3.2. Perlakuan
Sebelum pengolahan limbah secara anaerobik PT. Nalco Indonesia,
dilakukan pengamatan terhadap suhu, pH, KOK, KOB5 dan TDS sebagai
pengamatan inlet pada limbah cair keluaran dari flokulan tank. Limbah cair ini
diumpankan ke dalam tangki anerobik yang telah berisi mikroorganisme
anaerobik. pengolahan secara anaerobik dilakukan untuk memecahan senyawa
organik
menjadi
senyawa
yang
lebih
sederhana
dengan
melibatkan
mikroorganisme anaerobik dalam keadaan tanpa oksigen. Pengolahan limbah
secara anerobik diharapkan bisa mengurangi senyawa organik yang terkandung
dalam limbah cair sebelum mengalami proses pengolahan limbah selanjutnya.
Limbah cair akan mengalami proses anaerobik selama 6 hari, dimana
dalam waktu tinggal tersebut tangki proses pengolahan limbah tidak boleh
terkontaminasi oleh oksigen. Dalam proses ini mikroorganisme diberikan nutrisi
pada hari pertama dengan tujuan untuk menjaga kualitas nutrisi dalam limbah cair
yang dibutuhkan oleh mikroorganisme anaerobik. Selama proses pengolahan
26
berlangsung mikroorganisme dalam tangki anaerob akan terkumpul satu sama lain
dan membentuk flok miksroorganisme yang akibat gaya beratnya sendiri akan
turun secara gravitasi ke bagian bawah tangki sebagai sludge atau lumpur
biomassa. Selama waktu tersebut dilakukan pengamatan Suhu, pH, KOK, KOB5,
MLSS dan perhitungan jumlah nutrisi F/M sebagai pengamatan proses. Setelah
proses anaerobik selesai, lumpur biomassa akan dipisahkan mengunakan
penyaring dan limbah cair dialirkan kepengolahan limbah secara aerob di aerobik
pond. Limbah cair yang keluar dari anaerobik pond dilakukan pengamatan suhu,
pH, KOK, KOB5 dan TDS sebagai pengamatan outlet.
3.3.3.
Pengujian
Pengujian pada sampel dilakukan dalam beberapa parameter, yaitu suhu,
pH, pengukuran KOK, KOB5, TDS, pengamatan MLSS dan perhitungan F/M
Ratio.
3.3.3.1.
Pengukuran Suhu
Pengukuran suhu dilakukan di tangki anaerob pada hari ke-1 sampai hari
ke-6 dengan menggunakan termometer raksa. Dicatat suhu suhu yang tertera pada
termometer.
3.3.3.2.
Pengukuran pH
Pada pengukuran pH dilakukan pada sampel air limbah tangki anaerob
pada hari ke-1 sampai hari ke-6. Sebelum dilakukan pengukuran pH, pH-meter
dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan buffer 4, buffer 7, buffer 10.
Elektroda dibersihkan dengan cara membilasnya menggunakan air demin dan
mengeringkannya dengan tisu. Setelah itu elektroda dicelupkan ke dalam larutan
contoh sampai angka yang tertera pada layar stabil. Nilai yang tertera pada layar
merupakan pH dari larutan contoh.
3.3.3.3.
Pengukuran KOK (Kebutuhan Oksigen Kimia)
Penetapan KOK dilakukan pada sampel air limbah tangki anaerob pada
hari ke-1 sampai hari ke-6. Sampel dipipet 2,5 mL ke dalam tabung HACH yang
telah dicuci bersih dan dikeringkan lengkap dengan tutupnya, kemudian berturutturut ditambahkan 1,5 mL larutan pencerna 3,5 mL larutan perak sulfat 0,0324 M.
Contoh direfluks pada HACH COD Reactor dengan suhu 105oC selama dua jam
lalu contoh didinginkan pada suhu kamar dengan spektrifotometer DR-2800 pada
27
600 nm. Kadar KOK yang terdapat dalam contoh dihitung.Penetpan blanko
dilakukan dengan menggunakan air demin dan diperlakukan sama dengan contoh.
3.3.3.4.
Pengukuran KOB5 (Kebutuhan Oksigen Biologi)
Penetapan KOB dilakukan pada sampel air limbah tangki anaerob pada
hari ke-1 sampai hari ke-6. Pengukuran KOB dilakukan dengan menggunakan
metode respirometeri. Mula-mula sampel air limbah cair di masukan ke botol
KOB yang kemudian dimasukan magnetic stirrer ke botol dan karet ke leher
botol. Di isikan 1-2 tablet NaOH untuk menjaga agar nilai pH dapat tetap terjaga
antara 6-9. Botol KOB ditutup dengan hati-hati. Dinyalakan alat dan sampel KOB
disimpan selama 5 hari pada suhu 20 oC. Pengukuran selesai setelah 5 hari dan
dicatat pembacaan nilai KOB pada alat dalam satuan mg O2/L.
3.3.3.5.
Pengukuran TDS
Pengukuran TDS dilakukan pada sampel air limbah keluaran tangki
flokulan (inlet) dan sampel air limbah keluaran tangki anaerobik (outlet). Jumlah
padatan terlarut (TDS) ditetapkan dengan menggunakan alat konduktometer
dengan prinsip mengukur daya hantar listrik dari aktifitas ion yang terdapat pada
larutan. Konduktometer yang digunakan adalah Nalco-HACH Conductivity. Alat
dihidupkan dengan menekan tombol On. Sebelum dan sesudah digunakan
elektroda harus dibilas dengan menggunakan air demin dan dikeringkan dengan
tisu. Dicelupkan elektroda ke dalam larutan contoh yang diambil dari instalasi
pengolahan. Elektroda digoyang-goyangkan dan didiamkan sejenak hingga angka
pada display stabil. Dicatat angka yang ditunjukan alat.
3.3.3.6.
Penetapan MLSS
Penetapan MLSS dilakukan pada sampel air limbah tangki anaerob pada
hari ke-1 sampai hari ke-6. Sampel air limbah dikocok sampai homogen dan
dipipet 50 ml, lalu saring dengan kertas saring Whatman yang telah diketahui
beratnya (w0 0,001 g) pada Vacum Flask. Kemudian di keringkan di dalam oven
pada suhu 110-120oC selama 1 jam. Dimasukan kedalam eksikator selama 20
menit. Selanjutnya di timbang kembali sampai diperoleh berat yang tetap. (w 1
0,001 g).
Perhitungan :
MLSS (mg/L) = (w1-w0) x 1000 x 20
28
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengolahan limbah di PT. Nalco Indonesia dilakukan dengan lumpur
aktif dan menggunakan mikroorganisme secara anaerobik. Pengujian dilakukan
terhadap air limbah pada keluaran tangki flokulan (inlet), tangki anaerobik
(proses) dan keluaran tangki anaerobik (outlet).
4.1.
Pengujian Limbah Cair
Hasil analisis yang diperoleh dari pengukuran pH, KOB 5, KOK, dan TDS
tangki inlet dan outlet, dibandingkan dengan standar baku mutu yang telah
ditetapkan Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No:
KEP-
03/MENLH/1995 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri.
4.1.1. Hasil Pengukuran Suhu
Nilai suhu yang terukur menunjukan kondisi temperatur limbah dalam
tangki anaerobik. Kondisi suhu berperan penting dalam mendukung aktifitas
mikroorganisme pencerna di dalam pengolahan limbah cair secara anaerobik.
Adapun hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Data pengukuran suhu limbah cair selama tiga kali pengolahan
Hari
Ke-
Suhu
Pengolahan
Suhu
Pengolahan
Suhu
Pengolahan
29
1
2
3
4
5
6
Ulangan ke-1
(oC)
28
29
31
30
31
29
Ulangan ke-2
(oC)
28
28
30
31
33
30
Ulangan ke-3
(oC)
27
28
30
32
33
29
Berdasarkan Tabel 2. secara keseluruhan nilai kondisi suhu baik pada air
limbah selama proses anaerobik ulangan ke-1, ke-2 dan ke-3 pada kondisi normal,
yaitu berkisar 28 oC -33oC. Nilai suhu ini tidak mengganggu aktifitas biologis
yang terdapat pada tangki anaerob mengingat bakteri pencerna aktifitasnya akan
berkurang pada suhu di bawah 10oC.
4.1.2. Hasil Pengukuran pH
Nilai pH yang terukur menunjukkan derajat keasaman atau kebasaan dari
suatu limbah cair. Adapun hasil pengukurannya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Data pengukuran pH limbah cair selama tiga kali pengolahan.
Hari
Ke1
2
3
4
5
6
pH Pengolahan
Ulangan ke-1
8,02
7,50
5,06
5,72
6,71
6,78
pH Pengolahan
Ulangan ke-2
7,62
6,81
4,94
5,42
6,01
6,38
pH Pengolahan
Ulangan ke-3
7, 54
6,44
5,34
5,92
7,01
6,98
Baku Mutu
Maksimum
6-9
6-9
6-9
6-9
6-9
6-9
Berdasarkan Tabel 3. dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan nilai
kondisi pH limbah cair baik pada air limbah selama proses anaerobik ulangan ke1, ke-2 sampai pengolahan ulangan ke-3 bersifat fluktuatif dan untuk pH outlet
telah memenuhi baku mutu. Dimana pada proses anaerobik ulangan ke-1 pH
berkisar antara 5,06-8,02, pada proses anaerobik ulangan ke-2 pH berkisar antara
30
4,94-7,62, pada proses anaerobik ulangan ke-3 pH berkisar antara 4,34-7,54.
Secara keseluruhan pada hari k-3 pH turun tajam pada suasana asam, ini dapat
disebabkan fase asetogenik yang berlangsung di anaerobik pond. Hal ini harus
dikaji ulang karena memungkinkan kehidupan biologis dalam limbah cair tersebut
tidak berjalan dengan baik ataupun bisa mengakibatkan kematian pada bakteri
anaerobik. Bakteri anaerobik membutuhkan lingkungan dengan pH antara 6,8-7,4.
Pada pH di bawah 6 atau di atas 8 fase metanogenik tidak dapat berjalan dengan
baik. pH air limbah yang tidak netral akan menyulitkan proses biologis, bahkan
akan mengakibatkan kematian pada mikroorganisme dalam air.
4.1.3. Hasil Pengukuran KOK (Kebutuhan Oksigen Kimia)
Nilai KOK merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik
yang
secara
alamiah
dapat
dioksidasikan
melalui
proses
kimia,
dan
mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut dalam air (Alaerts & Santika,
1984). Adapun hasil pengukuran KOK yang menunjukan efisiensi dari proses
pengolahan limbah secara anaerobik dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Data pengukuran KOK inlet dan outlet selama tiga kali pengolahan
Pengolahan
limbah
anaerobik
KOK inlet
(mg O2/L)
KOK
outlet
(mg O2/L)
Efisiensi
Pengolahan
(%)
Ulangan ke-1
Ulangan ke-2
Ulangan ke-3
6203,06
8170,32
4072,59
2240,60
3026,86
1386,46
63,87
62,95
66,06
Baku
Mutu
Maksimu
m (mg
O2/L)
300
300
300
Berdasarkan Tabel 4, kisaran efisiensi dari pengolahan limbah secara
anaerobik selama tiga kali ulangan dalam menurunkan KOK pada air limbah
berkisar antara 62,95% sampai dengan 66,06%. Nilai efisiensi tersebut belum
sesuai dengan harapan SOP perusahan yang berkisar antara 80%-90%. Nilai KOK
outlet yang bervariasi disebabkan oleh beban air limbah yang masuk (KOK inlet)
yang bervariasi pula. Berdasarkan hasil pengukuran KOK outlet hasil pengolahan
31
limbah secara anaerobik diperoleh hasil konsentrasi yang belum memenuhi baku
mutu, sehingga air limbah outlet dari pengolahan limbah belum bisa langsung
dibuang ke lingkungan. Untuk lebih jelasnya ditampilkan grafik perbandingan
yang mendeskripsikan penurunan konsentrasi KOK selama waktu tinggal proses
pengolahan limbah secara anaerobik yang dapat dilihat pada Gambar 5, 6, dan 7.
6203.06
5101.87
f(x)
= 6545.72 x^-0.63
R = 0.94
2911.32541.3
2353.78
konse ntras i KOK proses (mgO2/L)
baku mutu maksimum
Ulangan ke-1
Power (Ulangan2240.6
ke-1)
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
waktu tinggal (hari)
Gambar 5. Grafik Penurunan nilai KOK Proses pada pengolahan limbah ulangan
ke-1 Selama Waktu Tinggal.
10000 8170.32
konsentrasi KOK proses (mgO2/L)
baku mutu maksimum
5000
5953.96
f(x)
= 8307.93 x^-0.59
4104.83
R = 0.98
3504.11
3108.21
Ulangan ke-2
Power (Ulangan3026.86
ke-2)
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
waktu tinggal (hari)
Gambar 6. Grafik Penurunan nilai KOK Proses pada pengolahan limbah ulangan
ke-2 Selama Waktu Tinggal.
32
5000 4072.59
4000
3000
konse ntrasi KOK prose s (mgO2/L)
baku mutu maksimum
3033.3
f(x)
= 4177.13 x^-0.64
R = 0.96
1813.03
1702.45
1449.88
1386.46
2000
Ulangan ke-3
1000
Power (Ulangan ke-3)
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
waktu tinggal (hari)
Gambar 7. Grafik Penurunan nilai KOK Proses pada pengolahan limbah ulangan
ke-3 Selama Waktu Tinggal.
Berdasarkan Gambar 5, 6, dan 7, dapat dilihat penurunan konsentrasi
KOK selama 6 hari berlangsung baik pada ulangan ke-1, ke-2 dan ke-3. Ini
mendeskripsikan kondisi bahan-bahan organik yang telah didegradasi oleh bakteri
anaerobik. Penurunan konsentrasi KOK selama 6 hari belum mencapai titik
optimal, dimana KOK outlet masih jauh dari baku mutu yang ditentukan. Secara
keseluruhan diperkirakan waktu tinggal pengolahan limbah yang dibutuhkan
untuk menurunan konsentrasi KOK agar mencapai titik optimal yang sesuai, baik
SOP perusahaan sebesar 80-90% maupun baku mutu maksimum Berdasarkan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: KEP-03/MENLH/1995 Tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri masih yaitu sebesar 814,51 mg/L
memerlukan waktu tinggal diatas 12 hari (Lampiran 15). Untuk menambahan
waktu tinggal menjadi 12 hari dalam satu kali proses pengolahan limbah cair
secara anaerobik memungkinkan penurunan akan lebih kecil dari pada konsentrasi
KOK yang didapat sekarang ini. Tapi hal ini kurang begitu efisien, karena
mengingat setelah proses pengolahan limbah cair secara anaerob masih dilakukan
proses pengolahan limbah lanjutan.
4.1.4. Hasil Pengukuran KOB5 (Kebutuhan Oksigen Biologi)
KOB merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan bakteri untuk
menguraikan (mengoksidasi) hampir semua zat organik yang terlarut dan sebagian
33
zat- zat yang tersuspensi dalam air. Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada
Tabel 5.
Tabel 5. Efisiensi penurunan nilai KOB5.
Pengolahan limbah
anaerobik
Ulangan ke-1
Ulangan ke-2
Ulangan ke-3
KOB5
inlet
(mg
O2/L)
723
719
735
KOB5
outlet
(mg
O2 /L)
280
307
265
Efisiensi
(%)
Baku Mutu
(mg O2/L)
61,3
57,3
63,9
150
150
150
Berdasarkan Tabel 5, kisaran efisiensi dari tiga kali ulangan pengolahan
limbah secara anaerobik dalam menurunkan KOB5 pada air limbah berkisar antara
57,3% sampai dengan 63,9%. Nilai efisiensi tersebut belum sesuai dengan SOP
perusahan yang berkisar antara 80%-90%. Berdasarkan hasil pengukuran KOB 5
outlet hasil pengolahan limbah secara anaerobik diperoleh hasil konsentrasi yang
belum memenuhi baku mutu, sehingga air limbah outlet dari pengolahan limbah
secara anaerobik belum bisa langsung dibuang ke lingkungan. Untuk lebih
jelasnya ditampilkan grafik perbandingan yang mendeskripsikan penurunan
konsentrasi KOB5 selama waktu tinggal proses pengolahan limbah secara
anaerobik yang dapat dilihat pada Gambar 8, 9, dan 10.
konse ntras i KOB5 prose s (mgO2/L)
Ulangan ke-1
723
611
f(x)
= 786.99 x^-0.52
R = 0.94
447 421
342
Power ( Ulangan ke-1)
280
Baku mutu maksimum
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
waktu tinggal (hari)
Gambar 8. Grafik Penurunan nilai KOB5 Proses pada pengolahan limbah ulangan
ke-1 Selama Waktu Tinggal
34
719
636
f(x) = 783.59 x^-0.46
475 433
R = 0.93
379
konse ntrasi KOB5 prose s (mgO2/L)
Ulangan ke-2
Power (Ulangan ke-2)
307
Baku mutu maksimum
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
waktu tinggal (hari)
Gambar 9.
Grafik Penurunan nilai KOB5 Proses pada pengolahan limbah
ulangan ke-2 Selama Waktu Tinggal
735
641
f(x) = 825.17 x^-0.57
456
R = 0.93
398
320
konse ntras i KOB5 proses (mgO2/L)
Ulangan ke-3
Power (Ulangan ke-3)
265
Baku mutu maksimum
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
waktu tinggal (hari)
Gambar 10. Grafik Penurunan nilai KOB5 Proses pada pengolahan limbah
ulangan ke-3 Selama Waktu Tinggal.
Berdasarkan Gambar 8, 9, dan 10, dapat dilihat penurunan konsentrasi
KOB5 selama 6 hari berlangsung baik pada ulangan ke-1, ke-2 dan ke-3. Ini
mendeskripsikan kondisi bahan-bahan organik yang telah didegradasi oleh bakteri
anaerobik. Penurunan konsentrasi KOB5 selama 6 hari belum mencapai titik
optimal, dimana KOB5 outlet masih jauh dari baku mutu yang ditentukan.
Diperkirakan waktu tinggal pengolahan limbah yang dibutuhkan untuk
menurunan konsentrasi KOB5 agar mencapai titik optimal yang sesuai baik SOP
perusahaan sebesar 80-90% maupun baku mutu maksimum Berdasarkan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No: KEP-03/MENLH/1995 Tentang Baku
Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri sebesar 150 mg/L masih diatas 15 hari
(Lampiran 15). Untuk menambahan waktu tinggal menjadi 15 hari dalam satu
kali proses pengolahan limbah cair secara anaerobik memungkinkan penurunan
35
yang lebih kecil untuk konsentrasi KOB5 yang didapat sekarang ini. Hal ini
kurang begitu efisien, karena mengingat limbah yang dihasilkan oleh PT. Nalco
Indonesia baik dari segi jenis maupun jumlahnya, dan dalam menghasilkan
produk tidak selalu sama dalam setiap waktu maka penambahan waktu tinggal
menjadi 15 hari terlalu lama. Tapi hal ini tidak begitu berpengaruh, karena setelah
proses pengolahan limbah cair secara anaerob masih dilakukan proses pengolahan
limbah lanjutan.
4.1.5. Hasil Pengukuran TDS (Total Dissolved Solid).
Kualitas air limbah dapat ditunjukkan oleh jumlah dan jenis zat- zat yang
terlarut. Pengukuran TDS dilakukan untuk mengetahui efisiensi pengolahan
limbah secara anaerobik dalam menurunkan nilai TDS. Berdasarkan hasil analisis
untuk pengukuran TDS dapat dilihat pada Tabel 6.
Tabel 6. Efisiensi penurunan nilai TDS.
TDS
TDS
Efisiensi
Baku Mutu
(%)
Maksimum
inlet
outlet
(mg /L)
(mg
(mg /L)
/L)
Ulangan ke-1
11078
6890
37,8
4000
Ulangan ke-2
15200
9465
37,7
4000
Ulangan ke-3
8735
4065
53,4
4000
Data pada Tabel 6 menujukan selama tiga kali ulangan proses pengolahan
Pengolahan
limbah
anaerobik
limbah secara anaerobik didapat efisiensi pengolahan limbah secara anaerobik
dalam menurunkan nilai TDS sebesar 37,7% sampai dengan 53,4%. Nilai TDS
outlet dari hasil pengolahan limbah belum bisa dibuang ke lingkungan mengingat
baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus <4000 mg/L. Akan tetapi
nilai ini cukup bagus untuk mengurangi nilai TDS yang terkandung di dalam
limbah cair yang akan diolah kembali pada pengolahan limbah selanjutnya.
4.2. Hasil Pengamatan MLSS (Mixed Liquor Suspended Solids).
Bak anaerobik bahan-bahan organik terlarut akan diuraikan oleh mikroba
dan proses perombakan senyawa organik tersebut berlangsung secara anaerobik.
36
Kandungan air di bak anaerobik dalam sistem ini disebut mixed liquor. Jumlah
padatan tersuspensi, termasuk mikroorganisme dalam bak anaerobik dinyatakan
MLSS. MLSS digunakan untuk memastikan bahwa ada jumlah yang cukup aktif
biomassa tersedia untuk mengkonsumsi kuantitas diterapkan polutan organik
setiap saat. Keseimbangan antara nutrisi dengan bakteri anaerobik yang terdapat
pada proses pengolahan limbah cair bisa diketahui dengan MLSS (Mixed Liquor
Suspended Solids). MLSS sebagian besar terdiri dari mikroorganisme dan nonbiodegradable padatan tersuspensi. Kadar MLSS pada tangki pengolahan limbah
cair secara anaerobik selama proses pengolahan limbah anaerobik dapat dilihat
pada Tabel 7.
Tabel 7. Data pengukuran MLSS selama tiga kali pengolahan.
Hari
Ke1
2
3
4
5
6
MLSS Ulangan ke-1
(mg/L)
3120
2820
2680
2590
2480
2140
Tabel 7. Menunjukan
MLSS Ulangan ke-2
(mg/L)
3680
3200
2860
2740
2590
2420
MLSS Ulangan ke-3
(mg/L)
3260
3020
2700
2570
2320
2080
kondisi MLSS baik pada air limbah selama
ulangan ke-1, ke-2 dan ke-3 yang bersifat fluktuatif. Jika nilai MLSS lebih besar
dari 5000 mg/L menandakan bahwa mikroorganisme yang ada di dalam bak
anaerob kekurangan nutrisi sehingga terjadi kanibalisme, sedangkan nilai MLSS
lebih kecil dari 2000 mg/L, menandakan pengolahan limbah kurang baik, karena
kekurangan mikroorganisme untuk mengurai bahan-bahan organik. Pada hari ke4 rata-rata mengalami penurunan nilai MLSS yang menandakan bahwa
pengolahan limbah kurang baik. Hal ini dapat disebabkan proses asetogenik
sedang berlangsung tinggi yang mengakibatkan kondisi limbah cair menjadi asam,
sehingga banyak bakteri anaerob yang mati sebelum mengurai bahan-bahan
organik yang terkandung dalam limbah. Hal ini dapat mengakibatkan
ketidakseimbangan jumlah bakteri pencerna dengan nutrisi yang terkandung
dalam air limbah.
37
4.3. Hasil Perhitungan F/M Ratio (Food to Microorganisme)
Perhitungan F/M Ratio
kontrol proses yang digunakan untuk
mengevaluasi jumlah makanan (KOK dan KOB) yang tersedia per satuan MLSS.
Kondisi F/M Ratio pada tangki pengolahan limbah cair secara anaerobik dapat
diketahui pada akhir proses pengolahan limbah anaerobik. Nilai F/M Ratio yang
diperoleh dapat dilihat pada Gambar 11, 12, dan 13.
0.23
0.21
0.16
0.16
0.14
0.13
F/M Ratio (KOB/Kg)
0.5
1.5 Ratio
2 2.5
3 ke-1
3.5 4 4.5
F/M
Ulangan
Waktu tinggal (Hari)
5.5
6.5
Gambar 11. Grafik kondisi F/M Ratio pada tangki pengolahan minggu ke-1.
0.19
F/M Ratio (KOB/Kg)
0.5
0.19
0.16
0.15
0.14
1 F/M
1.5 Ratio
2 Ulangan
2.5 3 ke-2
3.5 4 4.5
Waktu tinggal (Hari)
0.12
5.5
6.5
Gambar 12. Grafik kondisi F/M Ratio pada tangki pengolahan minggu ke-2.
0.22
0.21
0.16
0.15
0.13
0.12
F/M Ratio (KOB/kg)
0.5
1 F/M
1.5 Ratio
2 2.5
3 3.5
Ulangan
ke-3 4
4.5
5.5
6.5
Waktu tinggal (Hari)
Gambar 13. Grafik kondisi F/M Ratio pada tangki pengolahan minggu ke-3.
Gambar 4, 5, 6. menunjukan nilai F/M Ratio selama tiga kali pengolahan
limbah cair secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia. Ulangan ke-1 F/M Ratio
berkisar antara 0,13 sampai 0,23 KOB/kg, ulangan ke-2 F/M Ratio berkisar antara
0,12 sampai 0,19 KOB/kg, dan ulangan ke-3 F/M Ratio berkisar antara 0,12
sampai 0,22 KOB/kg. Kisaran F/M Ratio yang diharapkan sebesar 0,1-0,2
KOB/kg. Nilai yang didapat menunjukkan bahwa F/M ratio pada proses
pengolahan limbah secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia masih pada kondisi
normal. Nilai ini menunjukkan proses penggumpalan lumpur dan pengendapan
38
dalam tangki anaerob yang disebabkan oleh metabolisme bakteri anaerob terhadap
bahan organik berjalan lancar. Semakin tinggi F/M Ratio menandakan semakin
tinggi jumlah makanan yang terkandung dalam air limbah atau makin sedikit
jumlah bakteri pencerna. Parameter ini penting karena kondisi ideal dapat tercapai
jika kebutuhan nutrisi bagi bakteri terpenuhi (Metcalf dan Eddy, Icn,1981).
4.4. Evaluasi Efisiensi Pengolahan Limbah Secara Anaerobik.
Pengolahan limbah cair secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia selama
tiga kali tahap pengolahan menghasilkan rata-rata efisiensi terhadap penurunan
KOK sebesar 64,3%, KOB5 sebesar 60,8%, dan TDS sebesar 42,9%. Efisiensi
tertinggi terlihat pada parameter KOK, sedangkan terendah pada parameter TDS.
Penurunan ini sangat bergantung pada karakteristik dan jumlah air limbah yang
diolah dan kondisi proses anaerobik yang dilakukan. Hal ini menujukkan bahwa
pengolahan limbah cair secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia dapat
menurunkan KOK, KOB5, dan TDS yang terkandung dalam limbah cair. Hasil
dari pengolahan limbah secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia masih belum
sesuai harapan SOP perusahaan maupun ketetapan Berdasarkan Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup No: KEP-03/MENLH/2010 Tentang Baku Mutu Air
Limbah Bagi Kawasan Industri (lampiran). Hasil efisiensi dari Pengolahan limbah
cair secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Rata-Rata Efisiensi Dari Berbagai Parameter
Parameter
KOK
KOB5
TDS (mg /L)
Efisiensi
Ulangan ke-1
(%)
63,87
61,3
37,8
Efisiensi
Ulangan ke-2
(%)
62,95
57,3
37,7
Efisiensi
Ulangan ke-3
(%)
66,06
63,9
53,4
RataRata
(%)
64,3
60,8
42,9
Pengolahan limbah cair secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia
berfokus pada penurunan nilai KOK dan TDS untuk penstabilan kondisi dari
limbah cairnya, sehingga libah cair bisa diolah ke pengolahan limbah selanjutnya.
Dari data yang ada dapat dilihat bahwa kosentrasi KOK inlet yang terkandung air
39
limbah dari tiap ulangan tidak sama yang berarti jumlah kandungan pencemar
dalam limbah cair pada saat akan diolah bervariasi. Nilai konsenterasi yang tidak
sama tersebut mempengaruhi nilai beban yang ingin diolah dengan jumlah bakteri
pencerna tidak seimbang, sehingga ada kemungkinan nilai hasil pengolahan pun
tidak maksimal.
Faktor lainnya yang turut berperan dalam penguraian limbah yaitu
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biodegradasi selama proses pengolahan
limbah berlangsung, diantaranya nutrisi, suhu dan pH. Keadaan nutrisi pada saat
pengolahan limbah kadangkala tidak sesuai dengan yang ditentukan yaitu kurang
dari seharusnya. Akibatnya bakteri pencerna yang membutuhkan nutrisi pun
aktifitas pertumbuhannya terhambat dan penguraian tidak optimal. Dari tiga kali
ulangan pengolahan limbah dilakukan perhitungan F/M Ratio kontrol proses. Hal
ini digunakan untuk mengevaluasi jumlah makanan atau nutrisi (KOK dan KOB)
yang tersedia per satuan MLSS. Walaupun dari data yang diperoleh bersifat
fluktuatif, tapi hasilnya nilai kisaran F/M Ratio masih pada kisaran yang
diharapkan sebesar 0,1-0,2 KOB/kg (Metcalf dan Eddy,Icn,1981).
Kondisi faktor pendukung sangat berpengaruh, yang diantaranya suhu
dan pH. Kondisi suhu pada tiga kali ulangan pengolahan limbah juga masih pada
kondisi normal atau pada kondisi mendukung aktifitas biologis. Pengontrolan
suhu sangat penting dalam proses anaerob yang bertujuan untuk mengontrol
keadaan suhu pada saat proses pengolahan berlangsung tidak jatuh dibawah 10 OC,
sebab sebagian bakteri pencerna aktifitasnya akan berkurang pada suhu dibawah
10oC. Faktor yang berpengaruh sebenarnya adalah pH sistem. pH sistem yang
optimal untuk proses anaerob adalah mendekati 7 atau netral. Keseimbangan
pertumbuhan asetogenisis dan metanogenisis perlu dijaga. Bila asetogenisis lebih
cepat, maka terjadi akumulasi asam-asam volatil, yang mengakibatkan pH sistem
menjadi rendah (kondisi asam). Pada pH asam yang rendah, metanogenesis akan
terhambat, akibatnya penguraian menjadi tidak sempurna. Data pH pada tiga kali
ulangan pengolahan limbah terjadi penurunan pH maksimum pada hari ke tiga, ini
40
menujukkan tidak stabilnya pH sistem yang dapat mempengaruhi jalannya proses
pengolahan limbah secara anaerob.
Tabel 9 dibawah merupakan hasil evaluasi efisiensi dari pengolahan limbah cair
secara anaerobik di PT.Nalco Indonesia untuk setiap parameter.
Tabel 9. Perbandingan Hasil Pengolahan Limbah Cair Secara Anaerobik dengan
Ketetapan Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
No.3/MENLH/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Lingkungan.
Parameter
Suhu (oC)
pH
KOK (mg O2/L)
KOB5 (mg
O2/L)
TDS (mg/L)
Outlet
Ulangan
ke-1
29
6,78
2240,60
280
6890
Outlet
Ulangan
ke-2
30
6,38
3026,86
307
9465
BAB V
Outlet
Ulangan
ke-3
29
6,98
1386,46
265
Baku Mutu
Maksimum
4065
4000
40
6,0-9,0
300
150
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Efisiensi pengolahan limbah cair secara anaerobik di PT. Nalco Indonesia
selama tiga kali tahap pengolahan dalam menurunkan kadar KOK mencapai
62,95% sampai dengan 66,06%, dan menurunkan kadar TDS mencapai 37,7%53,4%. Kualitas parameter pengolahan limbah cair secara anaerobik di PT. Nalco
perlu dijaga yaitu suhu, pH, KOK, KOB 5, dan TDS agar sesuai dengan SOP PT.
Nalco Indonesia sebesar 80-90% dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor : KEP-03/MENLH/2010 Tentang Baku Mutu Air limbah Bagi Kawasan
Industri.
5.2. Saran
a. Perlu adanya penanganan lebih terhadap pengolahan limbah cair secara
anaerobik di PT. Nalco indonesia mengingat belum tercapainya efisiensi
41
yang sesuai dengan SOP perusahaan sebesar 80-90%, seperti penambahan
waktu tinggal pada proses pengolahan limbah cair secara anaeobik atau
menambah tangki bak anaerobik sehingga proses pengolahan limbah lebih
efektif.
b. Perlunya penelitian lebih lanjut tentang zat-zat yang bersifat racun bagi
bakteri pencerna (bakteri anerobik) yang terkandung dalam limbah,
mengingat zat beracun merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi
tahap degradasi anaerobik.
DAFTAR PUSTAKA
Achmad, R. 2004. Kimia Lingkungan. ANDI, Yogyakarta,
Alaerts, G. dan Santika S., 1984. Metode Penelitian Air. Usaha Nasional,
Surabaya,
APHA. 1989. Standard Methods For The Examination Of Water AND Watewater.
17th edition, Washington DC.
Fardiaz, S., 1992. Polusi Air dan Udara. Kanisius, Yogyakarta.
Fessenden, R., Joan, S. F., Penerjemah Maun S., Karmianti, A., Tilda, S. S., 1997.
Dasar-Dasar Kimia Organik. Binarupa Aksara, Jakarta.
HACH company, 1997. HACH Water Analysis Handbook. 3rd, Colorado.
Horan, N. J., 1993. Biological wastewater treatment system. Jhon Wiley and Sons
Ltd, England.
http://en.wikipedia.org, 2006. Anaerobic Digestion, 27/9/2006
http://id.wikipedia.org/wiki/Limbah, 27/9/2006
Indriyanti, 2002. Pengaruh Waktu Tinggal Substrat Terhadap Efisiensi Reaktor
Tipe Totally Mix. Jurnal Sains dan Teknologi BPPT : v4.n4.07 : 27/9/2006.
42
Jorgensen, Stven, E., 1979. Industrial Wate Water Mangement. Elsevier Scientific
Publishing Company, Amsterdam.
Khopkar, S. M., Penerjemah Saptoharjo, A., 1990. Konsep Dasar Kimia Analitik.
Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Mahida, U. N., 1984. Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri, C. V.
Rajawali, Jakarta.
Manahan, E. S., 2005. Enverironmental Chemistry. 8th edition, CRC Press Boca
Raton, London.
Ramalho R. S., 1977. Introduction To Wastewater Treatment Processes, Academic
Press, London.
Setyowati, A. R., 2000. Pengolahan Air Limbah Secara Anaerobik. PT Nusantara
Waterr Centre, Jakarta.
Soeprijatna, E., Eva, S., 2003. Penuntun Praktikum Teknologi Analisis Air. ST.
MIPA Bogor, Bogor.
Sugiharto, 1987. Dasar-Dasar Pengolahan Air Limbah. Universitas Indonesia
Press, Jakarta.
Susanto, E., A. Moestafa Gazali, Sri Harjanto, Nasyirudin, 1997. Perencanaan
Instalasi Pengolahan Air Limbah Laboratorium, Balai Besar Penelitian Dan
Pengembangan Industri Hail Pertanian, Bogor.
U.S. Departement of Energy, 2003. Methane (Biogas) from Anaerobic Digestres,
29/7/2006.
Underwood, A. L., R. A., Day J. R., 1990. Analisis Kimia Kuantitatif. Edisi ke-5,
Erlangga, Jakarta.
43
Lampiran 1. Baku Mutu Air Limbah
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 3/MENLH/1995
Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri.
Parameter
Kadar Maksimum
BOD5
COD
TDS
PH
Kekeruhan
TSS
Minyak dan Lemak
Fosfat
Detergen/ MBAS
Amonia
Nitrit
Nitrat
50-150 mg/L
100-300 mg/L
2000-4000 mg/L
6.0-9.0
5-20 NTU
60-100 mg/L
25 mg/L
3 mg/L
5 mg/L
10-150 mg/L
0.03-0.27 mg/L
2-9 mg/L
44
Lampiran 2. Diagram Unit Pengolahan Limbah di PT. Nalco Indonesia
Gambar 3. Diagram unit pengolahan limbah di PT. Nalco Indonesia.
45
keterangan : floculan tank, Anaerobic pond,dan clear watter adalah
tempat pengambilan limbah contoh
Lampiran 3. Diagram Alir Analisis Penelitian
PT. Nalco Indonesia
Limbah Padat
Limbah Gas
Limbah Cair
PT. PPLI
Sump pit
20 M3
Flokulan Tank
Waste water treatment PT.
Nalco indonesia
Pengukuran :
KOK inlet
30 M
TDS inlet
Pengukuran :
Anaerobik Pond
Suhu
120 M3
pH
KOK proses
Aerobik Pond
3
120 M
KOB5 proses
Pengukuran :
MLLSS
KOK outlet
TDS outlet
46
Lampiran 4. Pengukuran Suhu
Termometer raksa dibilas dengan air
demin dan dibersihkan dengan tisu
Termometer dicelupkan ke dalam sampel limbah cair
Dicatat nilai suhu yang tertera pada termometer
47
Lampiran 5. Pengukuran pH
pH meter dikalibrasi dengan Buffer
4,7,dan 10
Dibilas dengan air demin
Elektroda dicelupkan ke dalam sampel limbah cair
Dibaca nilai pH
48
Lampiran 6. Pengukuran KOK
Dipipet 2,5 mL limbah cair ke dalam
tabung HACH yang telah dicuci bersih
Ditambahkan secara berturut-turut 1,5 mL larutan pencerna dan 3,5
mL larutan perak sulfat 0,0324 M
Direfluks pada HACH COD reactor
pada suhu 105oC selama 2 jam
Didinginkan dan diukur dengan spektrofotometer
DR-2800
49
Lampiran 7. Pengukuran KOB5
Sampel limbah cair dimasukkan ke botol KOB yang kemudian
dimasukkan magnetic stirrer
Diisikan 1-2 butir NaOH
Sampel KOB disimpan pada alat selama 5 hari pada suhu 20oC
Pengukuran selesai 5 hari dan
pembacaan nilai KOB pada alat
dalam satuan mg O2/L
50
Lampiran 8. Pengukuran TDS
TDS meter dikalibrasi dengan larutan
standar
Dibilas dengan air demin
Elektroda dicelupkan kedalam sampel limbah cair
Dicatat nilai TDS
51
Lampiran 9. Pengukuran MLSS
Sampel limbah cair dikocok sampai
homogen dan di pipet 50 mL
Ditimbang kertas saring Whatman (w0)
Dipipet 50 mL dan disaring dengan kertas saring Whatman
Dikeringkan di dalam oven pada suhu 110-120oC selama satu jam
Dimasukan ke dalam eksikator
Ditimbang kembali (w1)
52
Lampiran 10. Tabel Data Konsentrasi KOK Dan Perhitungan Efisiensi
Pengolahan
limbah anaerobik
Ulangan ke-1
Ulangan ke-2
Ulangan ke-3
Hari
Ke-
1
2
3
4
5
6
KOK inlet
(mg O2/L)
6203,06
8170,32
4072,59
Rata-Rata
KOK proses
Pengolahan
Ulangan ke-1
(mg O2/L)
6203,06
5101,87
2911,30
2541,30
2353,78
2240,60
Rumus :
Efisiensi=
KOK outlet
(mg O2/L)
2240,60
3026,86
1386,46
Efisiensi
(%)
63,87
62,95
66,06
64,3%
KOK proses
Pengolahan
Ulangan ke-2
(mg O2/L)
8170,32
5953,96
4104,83
3504,11
3108,21
3026,86
KOK awalKOK akhir
x 100
KOK awal
b. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-2
8170,323026,86
Efisiensi=
x 100
= 62,95 %
8170,32
c. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-3
4.071,481.381,65
x 100
4. 071,48
= 66,06 %
100-300 mg/L
100-300 mg/L
100-300 mg/L
KOK proses
Pengolahan
Ulangan ke-3
(mg O2/L)
4072,59
3033,30
2579,03
1702,45
1449,88
1386,46
Contoh perhitungan :
a. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-1
6203,062240,60
Efisiensi=
x 100
= 63,87 %
6203,06
Efisiensi=
Baku Mutu
53
Lampiran 11. . Tabel data konsentrasi KOB5 dan perhitungan efisiensi
KOB5
KOB5
Pengolahan limbah
Efisiensi
anaerobik
(%)
inlet
outlet
Har
KOB5
KOB5(mg /L) KOB5
(mg /L)
i keUlanganUlangan
ke-1
723
Ulangan ke280 Ulangan
61,3
Ulangan ke-2
719
307
57,3
ke-1
2
ke-3
Ulangan
ke-3
735
265
(mg O2/L)
(mg O2/L)
(mg O63,9
2/L)
Rata-Rata
60,8%
1
723
719
735
2
611
636
651
3
487
512
486
4
421
433
398
5
342
379
320
6
280
307
265
Baku Mutu
Baku Mutu
(mg
O2/L)
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
50-150
Rumus :
Efisiensi=
KOB 5 awalKOB 5 akhir
x 100
KOB 5 awal
Contoh perhitungan :
a. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-1
723280
Efisiensi=
x 100
= 61,3%
723
b. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-2
719307
Efisiensi=
x 100
= 57,3%
719
c. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-3
Efisiensi=
735265
x 100
735
= 63,9%
Lampiran 12. Perhitungan Efisiensi TDS
TDS
inlet
(mg
/L)
Ulangan ke-1
11078
Ulangan ke-2
15200
Ulangan ke-3
8735
Rata-Rata
Pengolahan
limbah
anaerobik
TDS
outlet
(mg /L)
Efisiensi
(%)
Baku Mutu
6890
9465
4065
37,8
37,7
53,4
42,9%
2000-4000
2000-4000
2000-4000
54
Rumus :
Efisiensi=
TDS awalTDS akhir
x 100
TDS awal
Contoh perhitungan :
a. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-1
110786890
Efisiensi=
x 100
= 37,8%
11078
b. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-2
152009465
Efisiensi=
x 100
= 37,7%
15200
c. Perhitungan Efisiensi Proses Pengolahan Limbah Ulangan ke-3
Efisiensi=
87354065
x 100
8735
= 53,4%
Lampiran 13. Tabel Dan Perhitungan Pengukuran MLSS
Hari
Ke1
2
3
4
5
6
MLSS Ulangan Ke-1
(mg/L)
3120
2820
2680
2590
2480
2140
MLSS Ulangan Ke-2
(mg/L)
3680
3200
2860
2740
2590
2420
MLSS Ulangan Ke-3
(mg/L)
3260
3020
2700
2570
2320
2080
Perhitungan Pengukuran MLSS :
Persamaan : MLSS (mg/L) = (w1-w0) x 1000x 20
55
Contoh perhitungan :
a. Perhitungan MLSS Hari ke-1, Ulangan ke-1
MLSS (mg/L) = (0,156-0,001) x 1000x 20 = 3120 mg/L
b. Perhitungan MLSS Hari ke-1, Ulangan ke-2
MLSS (mg/L) = (0,185-0,001) x 1000x 20 = 3680 mg/L
c. Perhitungan MLSS Hari ke-1, Ulangan ke-3
MLSS (mg/L) = (0,164-0,001) x 1000x 20 = 3260 mg/L
Lampiran 14. Tabel Dan Perhitungan Pengukuran F/M Ratio
Hari
Ke1
2
3
4
5
6
MLSS Ulangan Ke-1
(mg/L)
0,23
0,21
0,16
0,16
0,14
0,13
Persamaan :
Perhitungan=
MLSS Ulangan Ke-2
(mg/L)
0,19
0,19
0,16
0,15
0,14
0,12
Food
KOB
=
Microorganisme MLSS
Contoh perhitungan :
1. Perhitungan pengukuran F/M Hari ke-1, Ulangan ke-1 :
Hari ke-1 =
Food
723
=
Microorganisme 3120
= 0,23
2. Perhitungan pengukuran F/M Hari ke-1, Ulangan ke-2 :
MLSS Ulangan Ke-3
(mg/L)
0,22
0,21
0,16
0,15
0,13
0,12
56
Hari ke-1 =
Food
719
=
Microorganisme 3680 = 0,19
3. Perhitungan pengukuran F/M Hari ke-1, Ulangan ke-3 :
Hari ke-1 =
Food
735
=
Microorganisme 3260
= 0,22
Lampiran 15. Tabel Dan Perhitungan Penentuan Titik Optimal Waktu
Tinggal
Parameter
KOK
SOP (80%)
Baku Mutu Maksimum
(300 ppm)
Hari Optimal
Ulangan ke-1
14 hari
134 hari
Hari Optimal
Ulangan ke-2
58 hari
268 hari
Hari Optimal
Ulangan ke-3
12 hari
58 hari
Parameter
KOB5
SOP (80%)
Baku Mutu Maksimum
(150 ppm)
Hari Optimal
Ulangan ke-1
27 hari
15 hari
Hari Optimal
Ulangan ke-2
49 hari
40 hari
Hari Optimal
Ulangan ke-3
18 hari
20 hari
Persamaan :
y = 4177 . x -0,64
ln y = ln 4177 + (-0,64) . ln x
(y)
(a)
(b) .
(x)
57
ln y = ln a + b ln x
ln x=
ln yln a
b
Perhitungan Penentuan penurunan KOK terhadap Titik Optimal Waktu Tinggal
Pada Ulangan ke-3.
6000
4000
konsentrasi KOK proses (mgO2/L)
baku mutu maks imum
2000
0
4072.59
3033.3
f(x) = 4177.13
x^-0.64
1813.03
1702.45
1449.88
1386.46
R = 0.96
Ulangan ke-3
Power (Ulangan ke-3)
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
waktu tinggal (hari)
Contoh perhitungan :
ln 300ln 4177
ln x=
0,64
ln x=
5,78,3
0,64
x = Anti ln 4,1
x = 58 hari
Anda mungkin juga menyukai
- Karakteristik Air Limbah Industri Pulp Dan KertasDokumen3 halamanKarakteristik Air Limbah Industri Pulp Dan Kertasgioldingl0% (1)
- Kualitas Lindi TPST PiyunganDokumen18 halamanKualitas Lindi TPST PiyunganErshaBelum ada peringkat
- P3 Ipal Revisi Terakhir 3Dokumen45 halamanP3 Ipal Revisi Terakhir 3fajarBelum ada peringkat
- Bab 1,2,3 OdDokumen41 halamanBab 1,2,3 OdChairi Abdillah100% (1)
- Tugas 2 PDFDokumen23 halamanTugas 2 PDFmuhammad rahmanBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum 4Dokumen26 halamanLaporan Praktikum 4Indah Ayuningtyas WardaniBelum ada peringkat
- BAB 3 Tinjauan Pustaka HahaDokumen10 halamanBAB 3 Tinjauan Pustaka HahaTuanku Muhammad Azzam FarisBelum ada peringkat
- Prosedur Penanganan LimbahDokumen8 halamanProsedur Penanganan LimbahfridayantiBelum ada peringkat
- Ppab Bab Iii 100219Dokumen37 halamanPpab Bab Iii 100219rizkiah safitriBelum ada peringkat
- Kerugian Air LaundryDokumen10 halamanKerugian Air LaundryIda Fitria RahmawatiBelum ada peringkat
- Bab Ii PKL GMSDokumen30 halamanBab Ii PKL GMSnitaBelum ada peringkat
- Bab Ii PlaDokumen24 halamanBab Ii PlaFadli Maulana FikriBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen32 halamanBab 2gitadwi zakiahBelum ada peringkat
- Sistem Pengolahan Limbah Cair Pada Industri Tekstil Dan Produk TekstilDokumen18 halamanSistem Pengolahan Limbah Cair Pada Industri Tekstil Dan Produk TekstilSigitBelum ada peringkat
- Pegolahan Limbah Cair Industri Tahu MengDokumen8 halamanPegolahan Limbah Cair Industri Tahu MengZaini Tri EfendiBelum ada peringkat
- Bab 2 CoretcoretDokumen6 halamanBab 2 CoretcoretAmmatul FirdausaBelum ada peringkat
- ProposalDokumen31 halamanProposalSagita DewiBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen19 halamanBab IiAnonymous HL8fHKqsBelum ada peringkat
- Makalah PbpabDokumen6 halamanMakalah PbpabFebrianta LenggogeniBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTIKUM Cek Lagi KesimpulannyaDokumen14 halamanLAPORAN PRAKTIKUM Cek Lagi KesimpulannyaChrisa Meila PratamaBelum ada peringkat
- 691 2402 1 PBDokumen8 halaman691 2402 1 PBNurul Hidayah Eka SetiawatyBelum ada peringkat
- ProposalDokumen5 halamanProposalannekeBelum ada peringkat
- Limbah Cair Industri TekstilDokumen6 halamanLimbah Cair Industri Tekstilrahayu_handayaniBelum ada peringkat
- Proposal Limbah Air TahuDokumen33 halamanProposal Limbah Air TahuKholisotul HikmahBelum ada peringkat
- 1 Karakteristik LimbahDokumen34 halaman1 Karakteristik LimbahHabib Faisal YahyaBelum ada peringkat
- Makalah Pengolahan Limbah (Limbah Domestik)Dokumen16 halamanMakalah Pengolahan Limbah (Limbah Domestik)Sherina TaniaBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Pabrik KertasDokumen13 halamanTugas Makalah Pabrik KertasCandra Napoleon100% (1)
- Proposal 1-3 Revisi 3Dokumen19 halamanProposal 1-3 Revisi 3tegar khartapatiBelum ada peringkat
- Proposal BiofilmDokumen12 halamanProposal BiofilmmariaBelum ada peringkat
- Bab 2 KEGIATAN INDUSTRI DAN DAMPAKNYA BAGI LINGKUNGANDokumen10 halamanBab 2 KEGIATAN INDUSTRI DAN DAMPAKNYA BAGI LINGKUNGANFatimah QurratuBelum ada peringkat
- Proposal 1-3Dokumen16 halamanProposal 1-3tegar khartapatiBelum ada peringkat
- Tugas Antonius Doan PalandaDokumen11 halamanTugas Antonius Doan PalandaAldy BaralingBelum ada peringkat
- Definisi Air LimbahDokumen22 halamanDefinisi Air LimbahAndrizal KotoBelum ada peringkat
- Limbah Sem 5Dokumen14 halamanLimbah Sem 5faridaBelum ada peringkat
- Kel2 Pencemaran LingkunganDokumen11 halamanKel2 Pencemaran Lingkunganhesti SyafiBelum ada peringkat
- Limbah Cair SIERDokumen26 halamanLimbah Cair SIERKokoro No Tomo100% (4)
- Tugas 2 - Studi KasusDokumen31 halamanTugas 2 - Studi KasusPavitaSalsabilaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen5 halamanBab IiFaisal AmrullohBelum ada peringkat
- Makalah Ipal Industri Tahu SumantikaDokumen23 halamanMakalah Ipal Industri Tahu SumantikaLaisah JamalaBelum ada peringkat
- Laporan RESPONSI PBPLCDokumen83 halamanLaporan RESPONSI PBPLCdesyaaasfBelum ada peringkat
- BAB I ItdcDokumen21 halamanBAB I ItdcAngga Setia100% (1)
- Analisis Kandungan DOBODCODTSTDSTSSdan Analisis Karakteristik Fisikokimia Limbah Cair Industri Tahudi UMKMDaerah Imogiri Barat YogyakartaDokumen13 halamanAnalisis Kandungan DOBODCODTSTDSTSSdan Analisis Karakteristik Fisikokimia Limbah Cair Industri Tahudi UMKMDaerah Imogiri Barat YogyakartaALIKA MAHARANIBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen30 halamanBab IinurmayaBelum ada peringkat
- Modul IpalDokumen103 halamanModul IpaljusnelliBelum ada peringkat
- Air LimbahDokumen6 halamanAir LimbahNurul AiniBelum ada peringkat
- Skrip AsikDokumen9 halamanSkrip AsikHikmah UnnesBelum ada peringkat
- Tanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauDari EverandTanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauBelum ada peringkat