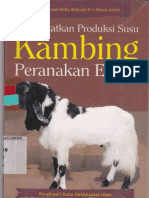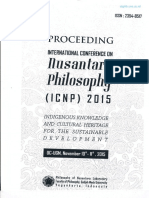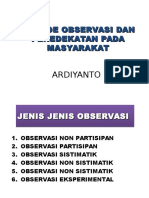Kopikir Susah Mu PDF
Kopikir Susah Mu PDF
Diunggah oleh
VhanJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kopikir Susah Mu PDF
Kopikir Susah Mu PDF
Diunggah oleh
VhanHak Cipta:
Format Tersedia
POLA PEMBIAYAAN USAHA KECIL (PPUK)
PERKEBUNAN KOPI ARABIKA
BANK INDONESIA
Direktorat Kredit, BPR dan UMKM
Telepon : (021) 3818043 Fax: (021) 3518951, Email : tbtlkm@bi.go.id
DAFTAR ISI
1. Pendahuluan ................................ ................................ ............... 2
a. Latar Belakang ................................ ................................ ........... 2
b. Tujuan ................................ ................................ ...................... 3
2. Kemitraan Terpadu ................................ ................................ ..... 4
a. Organisasi ................................ ................................ ................. 4
b. Pola Kerjasama ................................ ................................ .......... 6
c. Penyiapan Proyek................................ ................................ ........ 7
d. Mekanisme Proyek ................................ ................................ ...... 8
e. Perjanjian Kerjasama ................................ ................................ .. 9
3. Aspek Pemasaran................................ ................................ ....... 11
a. Peluang Pasar ................................ ................................ .......... 11
b. Produksi Kopi ................................ ................................ ........... 13
c. Situasi Persaingan ................................ ................................ ..... 14
4. Aspek Produksi ................................ ................................ .......... 17
a. Kesesuaian Lingkungan ................................ .............................. 17
b. Pembukaan Lahan................................ ................................ ..... 18
c. Penanaman dan Penaungan ................................ ........................ 18
d. Pemupukan................................ ................................ .............. 19
e. Pengendalian Hama................................ ................................ ... 19
f. Pemanenan ................................ ................................ .............. 20
g. Pasca Panen................................ ................................ ............. 21
5. Aspek Keuangan ................................ ................................ ........ 23
a. Umum................................ ................................ ..................... 23
b. Kebutuhan Biaya Investasi ................................ ......................... 24
c. Proyeksi Laba Rugi ................................ ................................ .... 25
d. Neraca ................................ ................................ .................... 26
e. Proyeksi Arus Kas ................................ ................................ ..... 27
f. Analisis Sensitivitas ................................ ................................ ... 28
6. Aspek Sosial Ekonomi dan Dampak Lingkungan .......................... 29
a. Aspek Sosial Ekonomi ................................ ................................ 29
b. Dampak Lingkungan ................................ ................................ .. 29
7. Kesimpulan ................................ ................................ ................ 31
LAMPIRAN ................................ ................................ ..................... 32
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 1
1. Pendahuluan
a. Latar Belakang
Pembangunan pertanian yang berbasis agribisnis dalam pengembangannya
memerlukan keterpaduan unsur-unsur sub sistem, mulai dari penyediaan
input produksi, budidaya, sampai ke pemasaran hasil. Keterpaduan tersebut
memungkinkan terbentuknya suatu kemitraan usaha yang ideal antara usaha
besar (inti) dengan petani (plasma).
Sektor usaha perkebunan di Indonesia telah tumbuh dan berkembang
melalui usaha perkebunan rakyat, perkebunan besar milik pemerintah dan
milik swasta nasional atau asing. Perkebunan rakyat bercirikan usaha skala
kecil, pengelolaan secara tradisional, produktivitas rendah dan tidak
mempunyai kekuatan menghadapi pasar. Di lain pihak, perkebunan besar
yang memiliki skala usaha yang besar, mengelola usahanya secara modern
dengan teknologi tinggi, sehingga produktivitasnya tinggi dan mempunyai
kekuatan untuk menghadapi pasar. Kesenjangan tersebut dapat diperkecil
dengan melakukan kemitraan antara perkebunan besar dengan perkebunan
rakyat. Salah satu komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan melalui
kemitraan usaha tersebut adalah kopi.
Tanaman kopi sudah lama dibudidayakan baik oleh rakyat maupun
perkebunan besar. Luas lahan perkebunan kopi di Indonesia cenderung
berkurang. Jika pada tahun 1992 luas lahan 1.333.898 ha, maka pada tahun
1997, berkurang 154.055 ha menjadi 1.179.843 ha. Namun demikian,
produksinya meningkat dari 463.930 ton pada tahun 1992 menjadi 485.889
ton pada tahun 1997. Pada tahun 1992 ekspor kopi Indonesia mencapai
259.349 ton atau 59% dari total produksi dan nilai yang didapatkan adalah
US$ 236.775.000. Sedangkan volume ekspor sampai dengan September
1997 mencapai 372.958 ton atau 77% dari total produksi dengan nilai US$
577.914. Peningkatan persentase volume kopi yang di ekspor ini cenderung
meningkatkan dengan harga kopi pasaran dunia yang dinilai dengan US$. Hal
ini juga menyebabkan harga kopi arabika di beberapa daerah meningkat dari
Rp. 15.000/kg pada bulan Desember 1997 menjadi Rp. 31.000/kg pada
minggu I bulan Agustus 1998. Hal ini juga terjadi pada kopi robusta,
walaupun peningkatannya tidak sebesar kopi arabika, yaitu dari Rp. 5.250
pada bulan Desember 1997 menjadi Rp. 22.000/kg pada minggu I bulan
Agustus 1998. Harga kopi robusta tersebut adalah harga untuk kualitas I.
Melihat prospek pasar komoditas kopi tersebut, diperlukan usaha-usaha
untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi, baik melalui usaha
intensifikasi maupun ekstensifikasi kebun. Usaha pengembangan tersebut
akan lebih berdaya guna jika melibatkan perkebunan besar dan perkebunan
rakyat yang terikat dalam suatu kemitraan usaha. Untuk itulah dalam
laporan ini akan dibahas pola kemitraan terpadu dengan melihat aspek
kelayakan usaha, yang terdiri dari aspek pemasaran, teknis budidaya,
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 2
finansial, Aspek Sosial Ekonomi serta bagaimana pola kemitraan terpadu
yang sesuai untuk dikembangkan dalam komoditas ekspor.
b. Tujuan
Tujuan penulisan Model Kelayakan Proyek Kemitraan Terpadu (KM-PKT)
komoditas kopi adalah untuk :
1. Memberikan informasi kepada perbankan tentang model kemitraan
terpadu yang sesuai dan layak dibiayai dengan kredit perbankan untuk
komoditas kopi;
2. Dipergunakan oleh para mitra usaha petani yang bermitra dalam
pengembangan kemitraan usaha komoditas kopi;
3. Mendorong pengembangan komoditas kopi sebagai komoditas
penghasil devisa negara.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 3
2. Kemitraan Terpadu
a. Organisasi
Proyek Kemitraan Terpadu (PKT) adalah suatu program kemitraan terpadu
yang melibatkan usaha besar (inti), usaha kecil (plasma) dengan melibatkan
bank sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan
dalam nota kesepakatan. Tujuan PKT antara lain adalah untuk meningkatkan
kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling
menguntungkan antara inti dan plasma, serta membantu bank dalam
meningkatkan kredit usaha kecil secara lebih aman dan efisien.
Dalam melakukan kemitraan hubunga kemitraan, perusahaan inti (Industri
Pengolahan atau Eksportir) dan petani plasma/usaha kecil mempunyai
kedudukan hukum yang setara. Kemitraan dilaksanakan dengan disertai
pembinaan oleh perusahaan inti, dimulai dari penyediaan sarana produksi,
bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi.
Proyek Kemitraan Terpadu ini merupakan kerjasama kemitraan dalam bidang
usaha melibatkan tiga unsur, yaitu (1) Petani/Kelompok Tani atau usaha
kecil, (2) Pengusaha Besar atau eksportir, dan (3) Bank pemberi KKPA.
Masing-masing pihak memiliki peranan di dalam PKT yang sesuai dengan
bidang usahanya. Hubungan kerjasama antara kelompok petani/usaha kecil
dengan Pengusaha Pengolahan atau eksportir dalam PKT, dibuat seperti
halnya hubungan antara Plasma dengan Inti di dalam Pola Perusahaan Inti
Rakyat (PIR). Petani/usaha kecil merupakan plasma dan Perusahaan
Pengelolaan/Eksportir sebagai Inti. Kerjasama kemitraan ini kemudian
menjadi terpadu dengan keikut sertaan pihak bank yang memberi bantuan
pinjaman bagi pembiayaan usaha petani plasma. Proyek ini kemudian dikenal
sebagai PKT yang disiapkan dengan mendasarkan pada adanya saling
berkepentingan diantara semua pihak yang bermitra.
1. Petani Plasma
Sesuai keperluan, petani yang dapat ikut dalam proyek ini bisa terdiri atas
(a) Petani yang akan menggunakan lahan usaha pertaniannya untuk
penanaman dan perkebunan atau usaha kecil lain, (b) Petani /usaha kecil
yang telah memiliki usaha tetapi dalam keadaan yang perlu ditingkatkan
dalam untuk itu memerlukan bantuan modal.
Untuk kelompok (a), kegiatan proyek dimulai dari penyiapan lahan dan
penanaman atau penyiapan usaha, sedangkan untuk kelompok (b), kegiatan
dimulai dari telah adanya kebun atau usaha yang berjalan, dalam batas
masih bisa ditingkatkan produktivitasnya dengan perbaikan pada aspek
usaha.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 4
Luas lahan atau skala usaha bisa bervariasi sesuai luasan atau skala yang
dimiliki oleh masing-masing petani/usaha kecil. Pada setiap kelompok
tani/kelompok usaha, ditunjuk seorang Ketua dan Sekretaris merangkap
Bendahara. Tugas Ketua dan Sekretaris Kelompok adalah mengadakan
koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan oleh para
petani anggotanya, didalam mengadakan hubungan dengan pihak Koperasi
dan instansi lainnya yang perlu, sesuai hasil kesepakatan anggota. Ketua
kelompok wajib menyelenggarakan pertemuan kelompok secara rutin yang
waktunya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok.
2. Koperasi
Parapetani/usaha kecil plasma sebagai peserta suatu PKT, sebaiknya menjadi
anggota suata koperasi primer di tempatnya. Koperasi bisa melakukan
kegiatan-kegiatan untuk membantu plasma di dalam pembangunan
kebun/usaha sesuai keperluannya. Fasilitas KKPA hanya bisa diperoleh
melalui keanggotaan koperasi. Koperasi yang mengusahakan KKPA harus
sudah berbadan hukum dan memiliki kemampuan serta fasilitas yang cukup
baik untuk keperluan pengelolaan administrasi pinjaman KKPA para
anggotanya. Jika menggunakan skim Kredit Usaha Kecil (KUK), kehadiran
koperasi primer tidak merupakan keharusan
3. Perusahaan Besar dan Pengelola/Eksportir
Suatu Perusahaan dan Pengelola/Eksportir yang bersedia menjalin kerjasama
sebagai inti dalam Proyek Kemitraan terpadu ini, harus memiliki kemampuan
dan fasilitas pengolahan untuk bisa menlakukan ekspor, serta bersedia
membeli seluruh produksi dari plasma untuk selanjutnya diolah di pabrik dan
atau diekspor. Disamping ini, perusahaan inti perlu memberikan bimbingan
teknis usaha dan membantu dalam pengadaan sarana produksi untuk
keperluan petani plasma/usaha kecil.
Apabila Perusahaan Mitra tidak memiliki kemampuan cukup untuk
mengadakan pembinaan teknis usaha, PKT tetap akan bisa dikembangkan
dengan sekurang-kurangnya pihak Inti memiliki fasilitas pengolahan untuk
diekspor, hal ini penting untuk memastikan adanya pemasaran bagi produksi
petani atau plasma. Meskipun demikian petani plasma/usaha kecil
dimungkinkan untuk mengolah hasil panennya, yang kemudian harus dijual
kepada Perusahaan Inti.
Dalam hal perusahaan inti tidak bisa melakukan pembinaan teknis, kegiatan
pembibingan harus dapat diadakan oleh Koperasi dengan memanfaatkan
bantuan tenaga pihak Dinas Perkebunan atau lainnya yang dikoordinasikan
oleh Koperasi. Apabila koperasi menggunakan tenaga Penyuluh Pertanian
Lapangan (PPL), perlu mendapatkan persetujuan Dinas Perkebunan setempat
dan koperasi memberikan bantuan biaya yang diperlukan.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 5
Koperasi juga bisa memperkerjakan langsung tenaga-tenaga teknis yang
memiliki keterampilan dibidang perkebunan/usaha untuk membimbing
petani/usaha kecil dengan dibiayai sendiri oleh Koperasi. Tenaga-tenaga ini
bisa diberi honorarium oleh Koperasi yang bisa kemudian dibebankan kepada
petani, dari hasil penjualan secara proposional menurut besarnya produksi.
Sehingga makin tinggi produksi kebun petani/usaha kecil, akan semakin
besar pula honor yang diterimanya.
4. Bank
Bank berdasarkan adanya kelayakan usaha dalam kemitraan antara pihak
Petani Plasma dengan Perusahaan Perkebunan dan Pengolahan/Eksportir
sebagai inti, dapat kemudian melibatkan diri untuk biaya investasi dan modal
kerja pembangunan atau perbaikan kebun.
Disamping mengadakan pengamatan terhadap kelayakan aspek-aspek
budidaya/produksi yang diperlukan, termasuk kelayakan keuangan. Pihak
bank di dalam mengadakan evaluasi, juga harus memastikan bagaimana
pengelolaan kredit dan persyaratan lainnya yang diperlukan sehingga dapat
menunjang keberhasilan proyek. Skim kredit yang akan digunakan untuk
pembiayaan ini, bisa dipilih berdasarkan besarnya tingkat bunga yang sesuai
dengan bentuk usaha tani ini, sehingga mengarah pada perolehannya
pendapatan bersih petani yang paling besar.
Dalam pelaksanaanya, Bank harus dapat mengatur cara petani plasma akan
mencairkan kredit dan mempergunakannya untuk keperluan operasional
lapangan, dan bagaimana petani akan membayar angsuran pengembalian
pokok pinjaman beserta bunganya. Untuk ini, bank agar membuat perjanjian
kerjasama dengan pihak perusahaan inti, berdasarkan kesepakatan pihak
petani/kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan memotong uang hasil
penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang disepakati bersama
untuk dibayarkan langsung kepada bank. Besarnya potongan disesuaikan
dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada waktu perjanjian kredit
dibuat oleh pihak petani/Kelompok tani/koperasi. Perusahaan inti akan
memotong uang hasil penjualan petani plasma/usaha kecil sejumlah yang
disepakati bersama untuk dibayarkan langsung kepada Bank. Besarnya
potongan disesuaikan dengan rencana angsuran yang telah dibuat pada
waktu perjanjian kredit dibuat oleh pihak petani plasma dengan bank.
b. Pola Kerjasama
Kemitraan antara petani/kelompok tani/koperasi dengan perusahaan mitra,
dapat dibuat menurut dua pola yaitu :
a. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani mengadakan
perjanjian kerjasama langsung kepada Perusahaan Perkebunan/
Pengolahan Eksportir.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 6
Dengan bentuk kerja sama seperti ini, pemberian kredit yang berupa KKPA
kepada petani plasma dilakukan dengan kedudukan Koperasi sebagai
Channeling Agent, dan pengelolaannya langsung ditangani oleh Kelompok
tani. Sedangkan masalah pembinaan harus bisa diberikan oleh Perusahaan
Mitra.
b. Petani yang tergabung dalam kelompok-kelompok tani, melalui
koperasinya mengadakan perjanjian yang dibuat antara Koperasi
(mewakili anggotanya) dengan perusahaan perkebunan/
pengolahan/eksportir.
Dalam bentuk kerjasama seperti ini, pemberian KKPA kepada petani plasma
dilakukan dengan kedudukan koperasi sebagai Executing Agent. Masalah
pembinaan teknis budidaya tanaman/pengelolaan usaha, apabila tidak dapat
dilaksanakan oleh pihak Perusahaan Mitra, akan menjadi tanggung jawab
koperasi.
c. Penyiapan Proyek
Untuk melihat bahwa PKT ini dikembangkan dengan sebaiknya dan dalam
proses kegiatannya nanti memperoleh kelancaran dan keberhasilan, minimal
dapat dilihat dari bagaimana PKT ini disiapkan. Kalau PKT ini akan
mempergunakan KKPA untuk modal usaha plasma, perintisannya dimulai
dari :
a. Adanya petani/pengusaha kecil yang telah menjadi anggota koperasi
dan lahan pemilikannya akan dijadikan kebun/tempat usaha atau
lahan kebun/usahanya sudah ada tetapi akan ditingkatkan
produktivitasnya. Petani/usaha kecil tersebut harus menghimpun diri
dalam kelompok dengan anggota sekitar 25 petani/kelompok usaha.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 7
Berdasarkan persetujuan bersama, yang didapatkan melalui
pertemuan anggota kelompok, mereka bersedia atau berkeinginan
untuk bekerja sama dengan perusahaan perkebunan/
pengolahan/eksportir dan bersedia mengajukan permohonan kredit
(KKPA) untuk keperluan peningkatan usaha;
b. Adanya perusahaan perkebunan/pengolahan dan eksportir, yang
bersedia menjadi mitra petani/usaha kecil, dan dapat membantu
memberikan pembinaan teknik budidaya/produksi serta proses
pemasarannya;
c. Dipertemukannya kelompok tani/usaha kecil dan pengusaha
perkebunan/pengolahan dan eksportir tersebut, untuk memperoleh
kesepakatan di antara keduanya untuk bermitra. Prakarsa bisa dimulai
dari salah satu pihak untuk mengadakan pendekatan, atau ada pihak
yang akan membantu sebagai mediator, peran konsultan bisa
dimanfaatkan untuk mengadakan identifikasi dan menghubungkan
pihak kelompok tani/usaha kecil yang potensial dengan perusahaan
yang dipilih memiliki kemampuan tinggi memberikan fasilitas yang
diperlukan oleh pihak petani/usaha kecil;
d. Diperoleh dukungan untuk kemitraan yang melibatkan para
anggotanya oleh pihak koperasi. Koperasi harus memiliki kemampuan
di dalam mengorganisasikan dan mengelola administrasi yang
berkaitan dengan PKT ini. Apabila keterampilan koperasi kurang, untuk
peningkatannya dapat diharapkan nantinya mendapat pembinaan dari
perusahaan mitra. Koperasi kemudian mengadakan langkah-langkah
yang berkaitan dengan formalitas PKT sesuai fungsinya. Dalam
kaitannya dengan penggunaan KKPA, Koperasi harus mendapatkan
persetujuan dari para anggotanya, apakah akan beritndak sebagai
badan pelaksana (executing agent) atau badan penyalur (channeling
agent);
e. Diperolehnya rekomendasi tentang pengembangan PKT ini oleh pihak
instansi pemerintah setempat yang berkaitan (Dinas Perkebunan,
Dinas Koperasi, Kantor Badan Pertanahan, dan Pemda);
f. Lahan yang akan digunakan untuk perkebunan/usaha dalam PKT ini,
harus jelas statusnya kepemilikannya bahwa sudah/atau akan bisa
diberikan sertifikat dan buka merupakan lahan yang masih belum jelas
statusnya yang benar ditanami/tempat usaha. Untuk itu perlu adanya
kejelasan dari pihak Kantor Badan Pertanahan dan pihak Departemen
Kehutanan dan Perkebunan.
d. Mekanisme Proyek
Mekanisme Proyek Kemitraan Terpadu dapat dilihat pada skema berikut ini :
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 8
Bank pelaksana akan menilai kelayakan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip
bank teknis. Jika proyek layak untuk dikembangkan, perlu dibuat suatu nota
kesepakatan (Memorandum of Understanding = MoU) yang mengikat hak
dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra (inti, Plasma/Koperasi
dan Bank). Sesuai dengan nota kesepakatan, atas kuasa koperasi atau
plasma, kredit perbankan dapat dialihkan dari rekening koperasi/plasma ke
rekening inti untuk selanjutnya disalurkan ke plasma dalam bentuk sarana
produksi, dana pekerjaan fisik, dan lain-lain. Dengan demikian plasma tidak
akan menerima uang tunai dari perbankan, tetapi yang diterima adalah
sarana produksi pertanian yang penyalurannya dapat melalui inti atau
koperasi. Petani plasma melaksanakan proses produksi. Hasil tanaman
plasma dijual ke inti dengan harga yang telah disepakati dalam MoU.
Perusahaan inti akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk
diserahkan kepada bank sebagai angsuran pinjaman dan sisanya
dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.
e. Perjanjian Kerjasama
Untuk meresmikan kerja sama kemitraan ini, perlu dikukuhkan dalam suatu
surat perjanjian kerjasama yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak
yang bekerjasama berdasarkan kesepakatan mereka. Dalam perjanjian
kerjasama itu dicantumkan kesepakatan apa yang akan menjadi kewajiban
dan hak dari masing-masing pihak yang menjalin kerja sama kemitraan itu.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 9
Perjanjian tersebut memuat ketentuan yang menyangkut kewajiban pihak
Mitra Perusahaan (Inti) dan petani/usaha kecil (plasma) antara lain sebagai
berikut :
1. Kewajiban Perusahaan Perkebunan/Pengolahan/Eksportir sebagai mitra
(inti)
a. Memberikan bantuan pembinaan budidaya/produksi dan penaganan
hasil;
b. Membantu petani di dalam menyiapkan kebun, pengadaan sarana
produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), penanaman serta
pemeliharaan kebun/usaha;
c. Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca
panen untuk mencapai mutu yang tinggi;
d. Melakukan pembelian produksi petani plasma; dan
e. Membantu petani plasma dan bank di dalam masalah pelunasan kredit
bank (KKPA) dan bunganya, serta bertindak sebagai avalis dalam
rangka pemberian kredit bank untuk petani plasma.
2. Kewajiban petani peserta sebagai plasma
a. Menyediakan lahan pemilikannya untuk budidaya;;
b. Menghimpun diri secara berkelompok dengan petani tetangganya yang
lahan usahanya berdekatan dan sama-sama ditanami;
c. Melakukan pengawasan terhadap cara panen dan pengelolaan pasca-
panen untuk mencapai mutu hasil yang diharapkan;
d. Menggunakan sarana produksi dengan sepenuhnya seperti yang
disediakan dalam rencana pada waktu mengajukan permintaan kredit;
e. Menyediakan sarana produksi lainnya, sesuai rekomendasi budidaya
oleh pihak Dinas Perkebunan/instansi terkait setempat yang tidak
termasuk di dalam rencana waktu mengajukan permintaan kredit;
f. Melaksanakan pemungutan hasil (panen) dan mengadakan perawatan
sesuai petunjuk Perusahaan Mitra untuk kemudian seluruh hasil panen
dijual kepada Perusahaan Mitra ; dan
g. Pada saat pernjualan hasil petani akan menerima pembayaran harga
produk sesuai kesepakatan dalam perjanjian dengan terlebih dahulu
dipotong sejumlah kewajiban petani melunasi angsuran kredit bank
dan pembayaran bunganya.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 10
3. Aspek Pemasaran
a. Peluang Pasar
Hal-hal yang dipaparkan dalam aspek pemasaran ini, terdiri dari peluang
pasar, produksi (sebagai pendekatan sisi penawaran) dan situasi persaingan.
Dalam hal ini, perlu dijelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang perlu
mendapat perhatian.
Harga jual kopi yang diterima pelaku pasar kopi dalam jangka panjang
terbukti fluktuatif disebabkan kondisi permintaan dan penawaran di pasar
internasional. Khusus untuk Indonesia saat ini, harga yang diterima oleh
para produsen sangat dipengaruhi oleh depresiasi rupiah terhadap dollar
Amerika, sehingga perhitungan kelayakannya perlu mempertimbangkan
kemungkinan penurunan harga sehubungan dengan apresiasi rupiah di masa
depan.
Selama ini, kekhawatiran terhadap produksi kopi yang melimpah lebih
mengarah pada jenis Kopi Robusta. Produksi Kopi Arabika di Indonesia hanya
sekitar 5% dari produksi total, sehingga jenis kopi ini masih mempunyai
peluang pasar yang tinggi, karena sekitar 70% permintaan kopi dunia adalah
untuk Kopi Arabika.
Volume ekspor kopi Indonesia tahun 1990 - 1997 cenderung menurun,
namun nilai ekspornya cenderung meningkat. Dari Tabel 1. Terlihat bahwa
pada tahun 1990, volume ekspor kopi mencapai 422.161 dan berkurang
menjadi 372.958 ton pada tahun 1997. Dalam periode tersebut terjadi
penurunan volume ekspor 69.203 ton.
Tabel 1.
Realisasi Ekspor Kopi dari Indonesia
Tahun Volume / Nilai Ekspor
Volume (ton) 442.161
1990
Nilai (ribu US $) 377.201
Volume (ton) 380.656
1991
Nilai (ribu US $) 372.416
Volume (ton) 259.349
1992
Nilai (ribu US $) 236.775
Volume (ton) 349.916
1993
Nilai (ribu US $) 344.208
Volume (ton) 289.303
1994
Nilai (ribu US $) 745.803
Volume (ton) 230.199
1995
Nilai (ribu US $) 606.469
Volume (ton) 366.602
1996
Nilai (ribu US $) 595.268
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 11
Volume (ton) 372.958
1997 s/d Sept
Nilai (ribu US $) 577.914
Sumber : *BPS
Namun demikian, dalam kurun waktu yang sama nilai ekspornya meningkat
dari US$ 377.201.000 pada tahun 1990, menjadi US$ 577.914.000 pada
tahun 1997. Suatu peningkatan US$ 200.713 dalam kurun waktu 7 tahun.
Peningkatan nilai ekspor ini disebabkan oleh peningkatan harga kopi (lihat
Tabel 2) kualitas kopi yang diekspor dan adanya suatu usaha pengolahan
kopi mentah (green beans) menjadi kopi masak (roasted beans) dan kopi
bubuk.
Permintaan biji kopi di pasaran dunia cukup tinggi, yaitu sekitar 5,5 juta ton,
tetapi 70% kopi yang diminta adalah dari jenis arabika dan kopi jenis ini
hanya 5% dari produksi kopi di Indonesia. Kopi Arabika selain banyak
diminta pasar luar negeri, juga harganya lebih tinggi dari kopi robusta,
bahkan pada tahun 1997, harga kopi tersebut lebih tinggi US$ 2,54 (lihat
Tabel 2). Melihat potensi tersebut pemerintah berupaya untuk meningkatkan
pangsa produksi kopi arabika sampai 30%. Untuk itu pemerintah, melalui
Dirjenbun telah melakukan usaha-usaha peningkatan produktivitas dan
ekstensifikasi kebun kopi.
Tabel 2. Perkembangan Harga Kopi Ekspor (FOB dalam US $/kg)
No Jenis Kopi 1993 1994 1995 1996 1997
1. Kopi Arabika 2,19 3,73 3,31 2,58 4,18
2. Kopi Robusta 1,04 2,15 3,06 2,07 1,64
Sumber : Deperindag 1998
Tabel 3.
Perkembangan Rata-rata Bulanan Harga Kopi
di Beberapa Kota di Indonesia
(dalam Rp/kg)
Jenis 1997 1998
Kota
Mutu Des Jan Mar Apr Mei Jun Jul Agt
Medan 4.900 4.900 - 4.900 - - - -
Arabika
U. Pandang 11.353 16.841 23.417 25.417 30.000 30.000 30.667 31.000
Medan 3.100 3.100 - - - - - -
Robusta
Surabaya U. 7.589 9.402 15.700 17.125 18.042 18.042 22.000 22.750
Mutu I
Pandang 3.875 6.563 16.000 19.333 19.000 19.000 22.000 22.000
Bdr Lampung 5.520 6.508 11.700 12.050 15.500 15.500 20.067 16.500
Mutu IV
Surabaya 5.692 6.767 9.875 11.323 13.125 13.125 17.917 18.250
Mutu VI Bdr Lampung 5.413 6.438 10.800 12.200 13.600 13.600 19.067 16.100
Palembang 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 15.500 15.500
Asalan
Bdr Lampung 4.867 5.953 9.500 10.800 11.783 11.783 13.533 13.250
Sumber : Badan Agribisnis Deptan www.fintrac.com/indag/,11/08/1998
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 12
Dengan mengingat bahwa kenaikan harga belakangan ini lebih disebabkan
oleh depresi nilai rupiah dan agar studi ini lebih adaptif terhadap
kemungkinan penurunan harga, maka harga jual rata-rata yang digunakan
dalam studi ini adalah masih dalam bentuk biji gelondong basah, dengan
komposisi biji berwarna merah, kuning dan hijau dengan perbandingan 7 : 2
: 1. Harga untuk kondisi tersebut diasumsikan Rp. 3.500/kg
b. Produksi Kopi
Di Indonesia, tanaman kopi dibudidayakan oleh rakyat dan perkebunan besar
di beberapa tempat, antara lain DI Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan,
NTT dan Timor-Timur. Dari keseluruhan sentra produksi tersebut, produksi
kopinya mencapai 88,37% dari total produksi Indonesia. Pada tahun 1997,
luas areal perkebunan kopi diperkirakan 1.179.843 ha dengan produksi
485.889 ton. Nilai tersebut lebih tinggi 1.480 ha dan 7.038 ton dari tahun
sebelumnya. Potensi lahan yang masih dapat dikembangkan untuk
perkebunan kopi diperkirakan sekitar 790.676 ha. Pada Tabel 4 dapat dilihat
perkembangan luas areal produksi kopi di Indonesia.
Tabel 4.
Luas Areal Dan Produksi Kopi di Indonesia
Tahun Keterangan Nilai
Luas Areal (ha) 1.069.848
1990
Produksi (ton) 412.767
Luas Areal (ha) 1.119.854
1991
Produksi (ton) 428.305
Luas Areal (ha) 1.133.898
1992
Produksi (ton) 436.930
Luas Areal (ha) 1.147.567
1993
Produksi (ton) 438.868
Luas Areal (ha) 1.140.385
1994
Produksi (ton) 450.191
Luas Areal (ha) 1.167.511
1995
Produksi (ton) 457.801
Luas Areal (ha) 1.178.363
1996*)
Produksi (ton) 478.851
Luas Areal (ha) 1.179.843
1997**)
roduksi (ton) 485.889
Keterangan : *) Angka sementara **) Angka estimasi per 11 Maret 1998.
Sumber : Website Deptan www.deptan.go.id
Menurut FAO, pada tahun 1997, diantara negara-negara penghasil kopi di
dunia, luas panen kopi di Indonesia berada ditingkat keempat sesudah Brazil,
Cote d' Ivoire dan Colombia (lihat Tabel 5). Walaupun demikian,
produktivitas perkebunan kopi di Indonesia masih rendah dan berada di
urutan ke -53 (yaitu 375 kg/ha) dari 80 negara penghasil kopi dunia.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 13
Produktivitas perkebunan kopi yang tertinggi adalah negara Martineque (2,5
ton/ha), kemudian disusun oleh China dan Vietnam, masing-masing 2, 0 dan
1,8 ton/ha.
Tabel 5.
Luas Panen Perkebunan Kopi di Beberapa Negara (ha)
Tahun Brazil Cote 'd Colombia Indonesia Mexico Dunia
Ivoire
1990 2.905.818 1.323.900 1.000.000 746.759 587.235 11.308.960
1991 2.767.439 1.215.000 1.020.000 760.308 643.264 11.169.320
1992 2.498.489 1.220.000 1.085.000 793.000 686.222 10.968.100
1993 2.257.197 1.225.000 955.000 810.000 697.839 10.570.840
1994 2.097.650 1.385.000 926.000 797.000 741.311 10.521.870
1995 1.868.027 1.415.000 1.042.541 810.000 724.974 10.572.160
1996 1.989.890 1.405.000 965.000 810.000 745.386 10.677.660
1997 2.036.460 1.405.000 1.041.480 800.000 750.541 10.748.880
Sumber : FAO, http://www.fao.org
c. Situasi Persaingan
Produksi kopi dunia pada tahun 1998/1999 diperkirakan akan mencapai 6,45
juta ton (107, 5 ribu karung), lebih tinggi 14% dari angka yang diperbarui
untuk tahun 1997/1998. Dari jumlah tersebut, diperkirakan 2,14 juta ton
berasal dari Brasilia dan 396 ribu ton (6.600 ribu karung) dari Indonesia
(lihat Tabel 6). Kopi yang diekspor oleh negara-negara penghasil kopi
diperkirakan akan mencapai 4,87 juta ton atau meningkat 7% dari tahun
sebelumnya.
Ditinjau dari aspek pasar, peningkatan produksi dan ekspor dari negara
penghasil kopi tersebut akan menurunkan harga kopi di pasaran dunia.
Harga kopi arabika dari Brasilia di pasar (spot market) New York pada bulan
mei 1998 adalah US$ 1,25/lb (US$ 2,5/kg), lebih rendah 12% dari bulan
sebelumnya dan turun 41% dibandingkan bulan Mei 1997.
Tabel 6.
Perkiraan Produksi Kopi Dunia (green beans)
oleh USDA (satuan dalam ribuan karung @ 60 kg)
Wilayah dan
1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
Negara
NORTH
19.387 19.265 18.693 18.410
AMERIKA
SOUTH
34.712 43.250 38.390 51.375
AMERKA
AFRIKA 18.491 20.274 17.563 18.257
ASIA
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 14
India 3.717 3.417 3.800 3.500
Indonesia 5.800 7.900 7.000 6.600
Laos 150 150 150 150
Malaysia 158 160 160 160
New Caledonia 5 5 5 5
Papua New
1.000 1.075 900 1.000
Guinea
Philppines 876 980 700 725
Sri Langka 60 60 60 60
Thailand 1.300 1.400 1.300 1.300
Vietnam 3.937 5.783 5.450 5.800
Yemen 150 175 150 150
ASIA total 17.153 21.105 19.675 19.450
WORLD TOTAL 89.743 103.894 94.321 107.492
Sumber : Coffe new : http:/www.vinews.com, Last updated 7/21/98
Peningkatan produksi dunia tersebut tidak sejalan dengan yang terjadi di
Indonesia. Produksi kopi di Indonesia pada tahun 1998/99 diperkirakan 396
ribu ton, berkurang 5,7% dari tahun sebelumnya. Hal ini antara lain
disebabkan oleh pengaruh kekeringan akibat El NiNo. Namun demikian
konsumsi kopi di Indonesia diperkirakan akan meningkat dari 124 ton pada
tahun 1997/1998 menjadi 125,4 ribu ton pada tahun 1998/99. Peningkatan
yang tidak terlalu tinggi ini disebabkan oleh tingkat konsumsi per kapita yang
masih rendah, yaitu sekitar 629 gram pada tahun 1996/97 dan harga kopi
yang diperkirakan akan meningkat sesuai dengan peningkatan kurs dollar.
Kondisi tersebut akan berpeluang untuk lebih memacu usaha ekspor kopi
keluar negeri. Di Amerika Serikat, Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari
35 negara pengekspor kopi ke negara tersebut (Tabel 7).
Tabel 7.
Nilai Ekspor Kopi Mentah (raw coffee) dari 35 Negara Pengekspor Kopi ke
Amerika Serikat Sampai Bulan Mei 1998 (ribu US$)
CALENDER YEARS (JAN-DEC) JANUARY - MAY
1997 COMPARISONS
1997
IMPOR MARKET RANK 1997 1998
LEADING 35 COUNTRY SUPPLIER
COLOMBIA 1 656.539 222.909 254.100
MEXICO 2 545.814 365.244 309.768
BRAZIL 3 450.081 162.379 102.429
GUATEMALA 4 393.688 203.239 186.327
PERU 5 168.191 9.964 21.785
INDONESIA 6 139.684 36.442 36.945
COSTA RICA 7 126.013 45.158 83.304
VIETNAM 8 104.031 69.342 76.726
EL SAVADOR 9 100.433 41.480 66.954
HONDURAS 10 67.772 46.395 101.854
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 15
ETHIOPIA 11 60.279 19.607 25.529
ECUADOR 12 60.157 8.295 9.485
THAILAND 13 45.949 34.049 34.102
INDIA 14 36.632 4.216 11.203
DOMINICAN REPUBLIK 15 34.031 16.341 29.503
UGANDA 16 33.551 9.753 6.179
SWITZERLAND 17 25.489 9.684 1.425
KENYA 18 18.802 6.153 7.318
NICARAGUA 19 16.683 9.962 18.896
PAPUA NEW GUINEA 20 15.606 2.911 1.568
PANAMA 21 14.770 7.456 13.264
BURUNDI 22 13.171 0 3.347
COTE D' IVOIRE 23 13.729 1.510 19.795
VENEZUELA 24 11.964 9.391 900
SINGAPORE 25 6.075 3.620 786
UNITED KINGDOM 26 5.647 305 906
GUINEA 27 3.596 3.017 1.330
LEEWARD-WINDWARD ISLAND 28 3.469 371 81
YEMEN 29 3.180 1.248 1.380
MADAGASKAR 30 3.000 1.182 5.414
JAMAICA & DEP 31 2.872 1.185 507
FRANCE 32 2.868 1.208 803
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 33 2.798 617 161
TANZANIA 34 2.692 1.296 1.263
GERMANY 35 2.572 1.125 2.235
REST OF WORLD - 15.127 4.906 5.239
Sources : US Bureau Of The Census Trade Data in Cofee News.
www.binews.com, Last Updated 7/21/98
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 16
4. Aspek Produksi
a. Kesesuaian Lingkungan
Tanaman kopi (coffea. sp) yang ditanam di perkebunan rakyat pada
umumnya adalah kopi jenis Arabica (Coffea Arabica), Robusta (Coffea
Canephora), Liberika (Coffea liberica) dan hibrida (hasil persilangan antara 2
varietas kopi unggul). Beberapa klon kopi unggul, khususnya untuk kopi
arabika telah disebarkan luaskan di sentra-sentra penghasil kopi. Klon-klon
tersebut antara lain adalah Kartika 1 dan 3 , USDA 762, lini S 795, $ 1934
dari India dan hibrido de timor dari Timor-Timur. Kedua klon yang terakhir
masih dikembangkan di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Jember. Sedangkan
untuk jenis robusta, klon-klon unggul yang telah dikembangkan antara lain
adalah BP 409, BP 358, SA 237, BP 234, BP 42 dan BP 288.
Dalam aspek produksi ini, hal-hal yang dibahas menyangkut kesesuaian
lingkungan ; pembukaan lahan ; penanaman dan penaungan; pemupukan;
pengendalian hama ; penyakit dan gulma; pemangkasan; pemanenan ; serta
pasca panen dan mutu kopi.
Dalam aspek ini hal yang perlu diperhatikan antara lain pengadaan bibit yang
harus menggunakan bibit bersetifikat, terutama apabila proyek membutukan
bibit dalam jumlah besar. Untuk itu perlu kerja sama dengan Dinas
Perkebunan setempat atau langsung menghubungi Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao di Jember. Demikian juga dalam hal kerawanan menghadapi serangan
penyakit. Selain itu, karena kopi Arabika mensyaratkan ketinggian lokasi
tertentu disamping persyaratan teknis lainnya, maka penentuan lokasi
proyek harus dikaji secara cermat.
Dalam hal pengolahan, kemungkinan tidak setiap lokasi pengembangan
(ekstensifikasi, intensifikasi) terdapat usaha besar yang mempunyai fasilitas
pengolahan kopi basah (wet processing) menjadi kopi biji (kopi beras).
Dalam hal ini, petani kopi bisa menjual kepada eksportir kopi dalam bentuk
biji kopi beras. Karena itu, dalam rancangan proyek perlu ditambahkan
fasilitas pengolahan untuk menghasilkan biji kering tersebut.
Faktor-faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap tanaman kopi
antara lain adalah ketinggian tempat tumbuh, curah hujan, sinar matahari,
angin dan tanah. Kopi robusta tumbuh optimal pada ketinggian 400 - 700 m
dpl, tetapi beberapa jenis diantaranya masih dapat tumbuh baik dan
mempunyai nilai ekonomis pada ketinggian di bawah 400 m dpl. Sedangkan
kopi arabika menghendaki tempat tumbuh yang lebih tinggi dari lokasinya
dari pada kopi robusta, yaitu antara 500 - 1.700 m dpl.
Curah hujan yang optimum untuk kopi (arabika dan robusta) adalah pada
daerah-daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata 2.000 - 3.000 mm
per tahun, mempunyai bulan kering (curah hujan <100 mm per bulan)
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 17
selama 3 - 4 bulan dan diantara bulan kering tersebut ada periode kering
sama sekali (tidak ada hujan) selama 2 minggu - 1,5 bulan.
Tanaman kopi umumnya menghendaki sinar matahari dalam jumlah banyak
pada awal musim kemarau atau akhir musim hujan. Hal ini diperlukan untuk
merangsang pertumbuhan kuncup bunga.
Angin berperan dalam membantu proses perpindahan serbuk sari bunga kopi
dari tanaman kopi yang satu ke lainnya. Kondisi ini sangat diperlukan
terutama untuk jenis kopi yang self steril.
Secara umum tanaman kopi menghendaki tanah yang gembur, subur dan
kaya bahan organik. Selain itu, tanaman kopi juga menghendaki tanah yang
agak masam, yaitu dengan pH 4,5 - 6 untuk robusta dan pH 5,0 - 6,5 untuk
kopi arabica.
b. Pembukaan Lahan
Lahan yang digunakan untuk penanaman kopi dapat berasal dari lahan
alang-alang dan semak belukar, lahan primer atau lahan konversi.
Pada lahan alang-alang dan semak belukar, cara pembukaan lahan dilakukan
dengan pembabatan secara manual atau dengan menggunakan herbisida.
Pada lahan primer dilakukan dengan cara menebang pohon-pohon,
sedangkan yang dari lahan konversi dilakukan dengan menebang atau
membersihkan tanaman yang terdahulu.
c. Penanaman dan Penaungan
Penanaman bibit kopi sebaiknya dilakukan pada awal atau pertengahan
musim hujan, sebab tanaman kopi yang baru ditanam pada umumnya tidak
tahan kekeringan.
Tanaman kopi robusta dianjurkan untuk ditanam dengan jarak 2,5 x 2, 5 m
atau 2, 75 x 2, 75 m, sedangkan untuk jenis arabika jarak tanamnya adalah
2,5 x 2,5 m, dengan demikian jumlah pohon kopi yang diperlukan sekitar
1.600 pohon/ha. Untuk penyulaman, sebaiknya dicadangkan lagi 400
pohon/ha. Sebelum tanaman kopi ditanam, harus terlebih dahulu ditanam
tanaman pelindung, seperti lamtoro gung, sengon laut atau dadap yang
berfungsi selain untuk melindungi tanaman muda dari sinar matahari
langsung, juga meningkatkan penyerapan N (Nitrogen) dari udara pada
tanaman-tanaman pelindung yang mengandung bintil akar.
Tanaman kopi sering ditanam di lahan yang berlereng. Untuk menghindari
erosi dan menekan pertumbuhan gulma dapat ditanam penutup lahan
(cover crop) seperti colopogonium muconoides, Vigna hesei atau
Indigovera hendecaphila.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 18
d. Pemupukan
Pupuk yang digunakan pada umumnya harus mengandung unsur-unsur
Nitrogen, Phospat dan Kalium dalam jumlah yang cukup banyak dan unsur-
unsur mikro lainnya yang diberikan dalam jumlah kecil. Ketiga jenis tersebut
di pasaran dijual sebagai pupuk Urea atau Za (Sumber N), Triple Super
Phospat (TSP) dan KCl. Selain penggunaan pupuk tunggal, di pasaran juga
tersedia penggunaan pupuk majemuk. Pupuk tersebut berbentuk tablet atau
briket di dalamnya, selain mengandung unsur NPK, juga unsur-unsur mikro.
Selain pupuk an organik tersebut, tanaman kopi sebaiknya juga dipupuk
dengan pupuk organik seperti pupuk kandang atau kompos.
Tabel 8.
Dosis Pemupukan Tanaman Kopi (gram/poho/tahun)
Tahun ke Urea TSP KCl
1 2 x 25 2 x 20 2 x 20
2 2 x 50 2 x 40 2 x 40
3 2 x 75 2 x 60 2 x 40
4 2 x 100 2 x 80 2 x 40
5 - 10 2 x 150 2 x 120 2 x 60
> 10 2 x 200 2 x 160 2 x 80
Sumber : Buku Kegiatan Teknis Operasional Budidaya Kopi, Dit Jen
Perkebunan,1996
Pemberian pupuk buatan dilakukan 2 kali per tahun yaitu pada awal dan
akhir musim hujan, dengan meletakkan pupuk tersebut di dalam tanah
(sekitar 10 - 20 cm dari permukaan tanah) dan disebarkan di sekeliling
tanaman. Dosis pemupukan mulai dari tahun pertama sampai tanaman
berumur lebih dari 10 tahun dapat dilihat pada Tabel 1. Adapun pemberian
pupuk kandang hanya dilakukan Tahun 0 (penanaman pertama).
e. Pengendalian Hama
Hama yang sering menyerang tanaman kopi, adalah penggerek buah kopi
(Stephanoderes hampei), penggerek cabang coklat dan hitam (Cylobarus
morigerus dan Compactus), kutu dompolan (Pseudococcus citri), kutu
lamtoro (Ferrisia virgata), kutu loncat (Heteropsylla, sp) dan kutu hijau
(Coccus viridis).
Sedangkan penyakit yang sering ditemukan adalah penyakit karat daun
(Hemileia vastantrix), jamur upas (Corticium salmonicolor), penyakit
akar hitam dan coklat (Rosellina bunodes dan R. arcuata), penyakit
bercak coklat dan hitam pada daun (Cercospora cafeicola), penyakit mati
ujung (Rhizoctonia), penyakit embum jelaga dan penyakit bercak hitam dan
buah (Chephaleuros coffea).
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 19
Adapun jenis gulma yang sering menganggu tanaman kopi antara lain adalah
alang-alang (Imperata Cylindrica), teki (cyperus rotudus), cyanodon
dactylon, Salvia sp, Digitaria sp, Oxalis sp, dan Micania cordata.
f. Pemanenan
Tanaman kopi jika dibiarkan tumbuh terus dapat mencapai ketinggian 12 m
dengan pencabangan yang rimbum dan tidak teratur. Hal ini akan
menyebabkan tanaman terserang penyakit, tidak banyak menghasilkan buah
dan sulit dipanen buahnya. Untuk mengatasi hal itu, perlu dilakukan
pemangkasan pohon kopi terhadap cabang-cabang dan batang-batangnya
secara teratur.
Ada empat tahap pemangkasan tanaman kopi yang sering dilakukan, yaitu
pemangkasan pembentukan tajuk, pemangkasan pemeliharaan,
pemangkasan cabang primer dan pemangkasan peremajaan.
Panen
Tanaman kopi yang terawat dengan baik dapat mulai berproduksi pada umur
2,5 - 3 tahun tergantung dari lingkungan dan jenisnya. Tanaman kopi
robusta dapat berproduksi mulai dari 2,5 tahun, sedangkan arabika pada
umur 2,5 - 3 tahun.
Jumlah kopi yang dipetik pada panen pertama relatif masih sedikit dan
semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya umur tanaman sampai
mencapai puncaknya pada umur 7 - 9 tahun. Pada umur puncak tersebut
produksi kopi dapat mencapai 9 - 15 kuintal kopi beras/ha/tahun untuk kopi
robusta dan 5 - 7 kuintal kopi beras/ha/tahun untuk kopi arabika. Namun
demikian, bila tanaman kopi dipelihara secara intensif dapat mencapai hasil
20 kuintal kopi beras/ha/tahun.
Berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam satu siklus
produksi (dapat berlangsung hingga tahun ke-21), studi ini membuat asumsi
produktivitasnya tanaman seperti terlihat pada Tabel 9. Rata-rata
produktiitas dalam 21 tahun adalah 441 kg/ha.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 20
Tabel 9.
Perkiraan Produktivitas Biji Kopi Kering 14% (kg/ha)
Tahun ke Asumsi (kg/ha)
3 350
4 400
5 450
6 550
7 600
8 650
9 650
10 600
11 550
12 500
13 500
14 450
15 450
16 400
17 400
18 400
19 350
20 350
21 300
22 300
g. Pasca Panen
Tanaman kopi ditanam untuk menghasilkan buah kopi yang fungsi utamanya
digunakan sebagai bahan minuman penyegar. Dengan demikian penanganan
pasca panen yang baik akan menentukan kualitas biji kopi yang dihasilkan.
Pengolahan biji kopi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara basah (wet
process) dan cara kering (dry process). Pengolahan cara basah (mutu WIB)
memerlukan proses yang cukup memakan waktu dan tenaga, antara lain
dengan melakukan proses fermentasi biji, sehingga hanya dilakukan di
perkebunan besar. Sedangkan cara kering (mutu OIB) untuk perkebunan dan
GB untuk rakyat), umumnya dilakukan oleh petani karena prosesnya yang
lebih sederhana dari pada proses basah. Kedua cara tersebut akan
menentukan kualitas kulit tanduk dan kulit arinya, baik yang diproses
dengan cara kering dan cara basah dapat dilihat pada Tabel 10 dan 11.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 21
Tabel 10.
Syarat Mutu Ekspor Kopi GB atau OIB
Lolos
Triaga Kadar Kotoran Bau
Ayakan
% Air% % w/w Apek Permukaan
Jenis Mutu 8
w/w w/w, max Dan Biji
Mesh,%
max max max bulukan
w/w,
EK - I (GB 3/5% ) 5 14,5 2 0,5 Bebas -
EK - II (GB 5/7%) 7 14,5 2 0,5 Bebas -
EK - III (GB 10/12%) 12 14,5 2 1 Bebas -
ROB 20 -25 (GB
23 14,5 2 2 Bebas -
20/25%)
Halus dan
AP - I 5 14,5 2 0 Bebas
Mengkilap
Halus dan
AP - II 7 14,5 2 0 Bebas
Mengkilap
AP - III 12 14,5 2 1 Bebas Halus dan
AP - 15 15 14,5 2 1 Bebas Mengkilap
Sumatera Arabica DP 2 14,5 2 0 Bebas -
Arabica Kalosi DP 2 14,5 2 0 Bebas -
Arabica Ratepao 2 14,5 2 0 Bebas -
Arabica Bali DP 3 14,5 2 0 Bebas -
Arabica Bali Sp 3 14,5 2 0 Bebas -
Sumber : Amir M.S . 1993, Seluk beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri
PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
Tabel 11.
Syarat Mutu Ekspor Kopi Biji WIB untuk jenis Robusta
Triaga% Ukuran
W/w max Dimakan Kadar Biji
Kotoran
bubuk Air, < 5,5 Bintik
Jenis % Bau
Biji 1 lubang % mm Bintik
Mutu Biji Biji w/w, busuk
ter %, w/w w/w % (spot)
Hitam Pecah max
bakar max max w/w,
max
WIB I 0,25 0,25 0,25 5 14 2,5 0,5 Bebas Bebas
WIB II 1 5 - 14 - 0,5 Bebas -
Sumber : Seluk beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri
PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 22
5. Aspek Keuangan
a. Umum
Analisa ini diharapkan akan dapat menjawab apakah para petani plasma
akan mendapatkan nilai tambah dari proyek ini, serta mampu
mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank dalam jangka waktu yang
wajar.
Perhitungan ini didasarkan pada kelayakan usaha setiap petani dengan luas
lahan 2 ha yang akan melakukan ekstensifikasi ataupun intensifikasi kebun
kopinya.
a. Untuk kegiatan ekstensifikasi Perusahaan inti akan terlibat kegiatan
sejak awal, mulai kegiatan pembukaan lahan sampai tanaman
menghasilkan. Pemberian kredit, dengan demikian meliputi semua
kegiatan pembangunan tanaman dan non-tanaman, serta telah
memasukkan bunga masa konstruksi (IDC) selama 3 tahun;
b. Untuk kegiatan intensifikasi diasumsikan petani sudah mempunyai
kebun kopi yang sudah berbuah (umur 5 - 10 tahun), dengan sumber
dananya sendiri. Mengikat pada umumnya kebun petani kurang
terpelihara, maka asset petani berupa kebun dinilai 75% dari nilai
investasi standar. Angka 75% ini, dalam aplikasinya harus disesuaikan
dengan kondisi kebun petani. Dengan demikian, pemberian kredit
hanya digunakan untuk pembelian beberapa peralatan pertanian kecil
(non-tanaman) dan sebagian besar biaya tanaman menghasilkan
tahun ke-1.
Skim kredit yang digunakan dalam analisa keuangan ini adalah skim Kredit
Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) dengan bunga 16% per tahun.
Untuk ekstensifikasi, selama tanaman belum menghasilkan plasma diberikan
masa tenggang (grace period) dengan bunga pinjaman 14% per tahun.
Pembayaran angsuran kredit (bunga dan pokok) untuk proyek ekstensifikasi
dimulai pada waktu tanaman petani sudah menghasilkan, yaitu pada tahun
ketiga; sedangkan untuk proyek intensifikasi angsuran kredit (bunga dan
pokok) dilakukan pada tahun itu juga (pada saat panen).
Parameter teknis untuk perhitungan analisa keuangan proyek ekstensifikasi
dapat dilihat pada Lampiran A-17, dengan asumsi harga tetap pada tahun
ini; sedangkan hasil perhitungannya secara terinci dapat dilihat pada
Lampiran A-01 - A16. Selanjutnya dengan mempertimbangkan kemungkinan
penurunan harga jual, maka dilakukan analisa sensitifitas, dengan berbagai
variabel perubahan harga (Lampiran A-18).
Adapun para meter teknis untuk memperhitungkan analisa keuangan proyek
intensifikasi dapat dilihat pada Lampiran B-17; sedangkan hasil
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 23
perhitungannya secara terinci dapat dilihat pada Lampiran B01-B16.
Selanjutnya dengan mempertimbangkan kemungkinan penurunan harga jual,
maka dilakukan analisa sensitifitas, dengan berbagai variabel perubahan
harga (Lampiran B-18). Jenis kopi yang digunakan sebagai dasar
perhitungan kelayakan usaha ini adalah untuk jenis kopi arabika.
b. Kebutuhan Biaya Investasi
Biaya investasi untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi kebun kopi rakyat
digunakan untuk biaya investasi tanaman dan non tanaman. Perincian biaya
investasi untuk 2 ha kebun kopi arabika dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12.
Kebutuhan Biaya Kebun Kopi Arabika
Nilai (Rp per 2 Ha)
Kebutuhan Biaya
Ekstensifikasi Intensifikasi
A. INVESTASI TANAMAN
- Tahun 0 (TBM 0) 13.667.580 10.160.610
- Tahun 1 (TBM 1) 2.664.600 1.998.450
- Tahun 2 (TBM 2) 2.509.200 1.881.900
Jumlah Investasi Tanaman 18.841.280 14.040.960
B. INVESTASI NON TANAMAN 1.680.800 1.770.200
Total Investasi Tan + Non 23.022.080 15.811.160
Tanaman
Biaya Umum 600.000 176.739
JUMLAH INVESTASI 20.522.080 15.987.899
Bunga masa Konstruski (IDC) 6.631.304 0
JUMLAH KESELURUHAN 27.753.384 15.987.899
Biaya investasi ekstensifikasi tanaman kopi pada Tahun ke-0 (TBM 0)
digunakan untuk pembukaan lahan (land clearing), pembuatan lubang,
penanaman tanaman pelindung dan tanaman kopi, serta pembuatan teras.
Sedangkan biaya Tahun Ke-1 (TBM-1) dan ke 2 (TBM-2) digunakan untuk
perawatan tanaman, seperti penyulaman, pemupukan dan pencegahan hama
dan penyakit.
Investasi non tanaman digunakan untuk pembangunan prasarana kebun,
seperti jalan kebun, dan juga digunakan untuk pembayaran jaminan kredit
ini dijaminkan ke perusahaan penjamin kredit seperti Perum PKK, Askrindo
atau PKPI. Selain itu dimasukkan juga dalam komponen biaya tersebut
adalah biaya umum (management fee) yang besarnya maksimum 5% dan
harus jelas perincian penggunaannya.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 24
Untuk intensifikasi kebun kopi, biaya yang diperlukan adalah pembelian
sarana produksi, peralatan pertanian kecil dan biaya tenaga kerja. Bantuan
kredit perbankan diberikan untuk pembelian sarana produksi pertanian,
peralatan pertanian dan biaya tenaga kerja untuk pemangkasan. Jumlah
kebutuhan biaya untuk intensifikasi tersebut adalah seperti yang terlihat
pada Tabel 13.
Tabel 13.
Kebutuhan Dana untuk Intensifikasi Kebun Kopi Arabika
Nilai Sumber Dana (Rp/ha)
Kebutuhan Biaya
(Rp/ha) Perbankan Sendiri
Sarana Produksi
- Pukuk 668.800 668.800 0
- Pestisida + 218.250 218.250 0
angkutan
Peralatan pertanian 885.100 885.100 0
Investasi Lainnya 88.370 88.370 0
Tenaga kerja 678.400 217.600 460.800
Jumlah 2.538.920 2.078.120 460.800
c. Proyeksi Laba Rugi
Proyeksi laba/rugi memberikan gambaran tentang keuntungan atau kerugian
usaha perkebunan kopi arabika di masa mendatang. Asumsi dasar yang
digunakan untuk perhitungan laba atau rugi ini adalah menyangkut kualitas
biji kopi yang dijual oleh petani. Petani dapat menjual kopinya kepada
Perusahaan Inti dalam bentuk glondongan basah atau kopi tanduk kering.
Produktivitas lahan (selama tahun ke-3) sampai akhir tahun ke-11.
Sedangkan untuk pola intensifikasi tanaman menghasilkan dianggap mulai
tahun ke-1 (sekalipun sebelumnya sudah menghasilkan dengan produktivitas
relatif rendah) hingga tahun ke-9. Lihat Tabel 14.
a. Pada pola ekstensifikasi, pada tahun pertama kopi berbuah (tahun ke
3) keuntungan petani hanya 3,5 juta/tahun (profit margin 28,9%),
maka pada tahun berikutnya, keuntungannya meningkat sejalan
dengan peningkatan produktivitas kebun. Keuntungan tersebut
mencapai puncaknya pada tahun ke -8 dan ke-9, yaitu Rp. 15,7
juta/tahun (profit margin 69,1%). Pada tahun ke-11, keuntungan
bersih petani sebesar Rp. 12,5 juta/tahun (profit margin 61,9%).
Secara rinci proyeksi laba-rugi tersebut terdapat pada Lampiran A-02;
b. Pada pola intensifikasi, pada tanaman kopi berbuah, keuntungan
petani hanya Rp. 7,1 juta/tahun (profit margin 57,7%), maka pada
tahun ke-6 dan ke-7, keuntungan menjadi Rp. 15,1 juta/tahun (profit
margin 66,2%). Pada tahun ke 9, keuntungan bersih petani sebesar
Rp. 11,9 juta/tahun (profit) margin 64,9%). Secara rinci proyeksi
laba-rugi tersebut terdapat pada lampiran B-02.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 25
Tabel 14.
Proyeksi Laba-Rugi Tahun ke-3 dan Tahun ke-11 Kebun Kopi Arabika
Nilai (Rp/2 Ha)
Ekstensifikasi Intensifikasi
Uraian
Tahun ke- Tahun ke - Tahun ke-
Tahun ke-3
11 3 9
Hasil Penjualan 12.250.000 19.250.000 12.250.000 19.250.000
Jumlah Biaya 8.309.727 5.288.169 4.395.753 6.043.895
Usaha
Pajak dan lain-lain 394.027 1.396.183 785.425 1.320.611
Laba bersih 3.546.246 12.565.648 7.068.822 11.855.495
d. Neraca
Proyeksi Neraca (dihitung pada akhir tahun) terus menunjukkan peningkatan
seperti tampak pada Tabel 15.
a. Untuk proyek Ekstensifikasi , kekayaan petani meningkat dari Rp. 0
pada awal tahun menjadi Rp. 97,3 juta pada akhir tahun ke -11 jika
perolehan hasil usaha tersebut ditanamkan kembali kedalam proyek
ini. Pada tahun tersebut, nilai sisa aktiva tetap adalah Rp. 16,1 juta
dan tidak memiliki hutang ke bank, demikian juga akumulasi
Tabungan Hari Depan (THD) telah mencapai Rp. 9,7 juta. Dengan
posisi tersebut, petani sudah mampu mandiri untuk melanjutkan
usahanya. Secara rinci, proyeksi Neraca tersebut dapat dilihat pada
Lampiran A-01;
b. Untuk proyek Intensifikasi, kekayaan petani meningkat dari Rp. 0 pada
awal tahun menjadi Rp. 120,6 juta pada akhir tahun ke 9 jika
perolehan hasil usaha tersebut ditanamkan kembali ke dalam proyek
ini. Pada tahun tersebut, nilai sisa aktiva tetap adalah Rp. 9,1 juta dan
tidak memiliki hutang ke bank, demikian juga akumulasi Tabungan
Hari Depan telah mencapai Rp. 10,7 juta. Dengan posisi tersebut
petani sudah mampu mandiri untuk melanjutkan usahanya. Secara
rinci proyeksi tersebut dapat dilihat pada Lampiran B-01.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 26
Tabel 15.
Proyeksi Neraca Kebun Kopi Arabika
Nilai (Rp/2 Ha)
Ekstensifikasi Intensifikasi
Uraian
Tahun ke- Tahun ke - Tahun ke-
Tahun ke-3
11 1 9
Akiva lancar 364.129 81.271.613 8.769.700 111.512.135
Tabungan Hari 354.625 9.734.371 706.882 10.656.423
Depan
Hutang Bank 27.753.384 0 2.970.640 0
Laba Ditahan (489.356) 97.343.708 7.068.822 106.564.230
Total Asset 27.264.028 96.701.468 24.080.422 120.605.190
e. Proyeksi Arus Kas
Dengan mengatur seluruh dana pembiayaan dari bank dan adanya grace
period selama 2 tahun (untuk proyek Ekstensifikasi), maka selama masa
proyek berlangsung tidak terjadi defisit anggaran. Petani dapat
mengembalikan pokok dan bunga pinjaman dalam waktu yang telah
ditentukan yaitu selama 5 tahun, dimulai pada tahun ke-3 hingga tahun ke-
7. Setelah tahun ke-8 petani sudah dapat mandiri, artinya dari tabungan
mereka dapat membiayai sendiri usahanya. Secara rinci proyeksi Arus Kas
tersebut dapat dilihat pada Lampiran A-03.
Demikian pula, untuk proyek Intensifikasi, selama masa proyek berlangsung
tidak terjadi defisit anggaran. Petani dapat mengembalikan pokok dan bunga
pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan, yaitu selama 3 tahun, dimulai
pada tahun ke-1 hingga tahun ke-3. Setelah tahun ke-4 petani sudah dapat
mandiri, artinya dari tabungan mereka, petani dapat membiayai sendiri
usahanya. Secara rinci, proyeksi Arus Kas tersebut dapat dilihat pada
Lampiran B-03.
Untuk menilai kelayakan proyek ini digunakan kriteria Net Present Value
(NPV), Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (B/C), Break Even
Point (BEP) dan Pay-back Period, seperti tampak pada Tabel 16.
Tabel 16.
Kriteria Kelayakan Usaha Kebun Kopi Rakyat
Kriteria Kelayakan Ekstensifikasi Intensifikasi
NPV (df = 16%) Rp. 10,36 juta Rp. 35,67 juta
Net B/C 5,03 7,8
IRR 28,27% 63,67%
BEP 1,927 kg 427 kg
Pay back Period 4 tahun 8 bulan 2 tahun 8 bulan
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 27
Untuk melihat perbandingan analisa kelayakan tersebut selengkapnya dapat
dilihat pada Lampiran A-04 (proyek Ekstensifikasi) dan Lampiran B-04
(proyek Intensifikasi).
f. Analisis Sensitivitas
Dengan pertimbangan bahwa harga jual kopi arabika cenderung fluktuatif
dalam pasar internasional, serta harga-harga saat ini lebih banyak
dipengaruhi deprisiasi rupiah terhadap dollar Amerika, maka studi ini
mencoba mengkaji sejauh mana penurunan harga dari asumsi yang
dikemukakan berpengaruh terhadap kelayakan proyek yang diukur dengan
perubahan Internal Rate of Return (IRR), Benefit Cost Ratio (B/C), dan
Pay-back Period.
Hasilnya untuk proyek Ekstensifikasi dapat dilihat pada Tabel 17, sedangkan
untuk proyek Intensifikasi dapat dilihat pada Tabel 18.
Tabel 17.
Analisa Sensitivitas untuk Proyek Ekstensifikasi
No Harga Jual Kopi B/C IRR Payback Period
1. Normal (sesuai asumsi) 5,03 28,27% 4 tahun 8 bulan
2. Harga jual Rp. 3.250 -/kg 4,65 26,34% 5 tahun 1 bulan
3. Harga jual Rp. 2.750-/kg 3,87 22,17% 5 tahun 7 bulan
4. Harga jual Rp. 2.250,-/kg 3,09 17,45% 6 tahun 10 bulan
Tabel 18.
Analisa Sensitivitas Untuk Proyek Intensifikasi
No Harga Jual Kopi B/C IRR Payback Period
1. Normal (sesuai asumsi) 7,8 63,67% 2 tahun 8 bulan
2. Harga jual Rp. 3.250,-/kg 7,11 58,22% 3 tahun
3. Harga jual Rp. 3.000,-/kg 6,42 52,69% 3 tahun 2 bulan
4. Harga jual Rp. 2.500,-/kg 5,05 41,23% 4 tahun 9 bulan
5. Harga jual Rp. 2. 050-/kg 3,81 30,25% 5 tahun 8 bulan
6. Harga jual Rp. 1.500,-/kg 2,30 15,34% 7 tahun 7 bulan
Seperti tampak pada Tabel 6 dan Tabel 7, agar usaha ini layak secara
finansial, maka tingkat harga jual kopi (biji basah) minimal Rp. 2.250/kg
untuk Proyek Ekstensifikasi dan Rp. 1.500/kg untuk Proyek Intensifikasi.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 28
6. Aspek Sosial Ekonomi dan Dampak Lingkungan
a. Aspek Sosial Ekonomi
Pembangunan perkebunan kopi rakyat dalam skala besar akan mampu
menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, mulai dari tahap persiapan,
konstruksi sampai pasca konstruksi. Dengan demikian aktivitas
pembangunan perkebunan ini akan berdampak positif terhadap penduduk di
sekitar lokasi proyek maupun para petani peserta proyek.
Pengembangan usaha perkebunan ini akan memberikan contoh positif bagi
sistem usaha tani yang intensif dan lebih maju kepada masyarakat sekitar
lokasi proyek, yang bersifat praktis yaitu melalui learning by doing dan
seeing is be leaving.
Sebagaimana diuraikan dalam analisis finansial, pengembangan proyek
perkebunan kopi rakyat ini akan meningkatkan pendapatan petani, yang
pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Secara lebih luas proyek perkebunan ini akan memberikan dampak positif
terhadap peningkatan aktivitas perekonomian daerah setempat, seperti
peningkatan jasa transportasi, jasa perdagangan dan aktivitas ekonomi
lainnya, serta peningkatan perolehan devisa negara, karena komoditas kopi
ini termasuk salah satu komoditas ekspor.
Terbukanya hutan atau termanfaatkan 'lahan tidur' yang dikembangkan
menjadi areal produktif yang diiringi berkembangnya pemukiman dan pusat
perekonomian, serta semakin baiknya aksebilitas akan berdampak positif
terhadap pengembangan wilayah dan tata ruang wilayah tersebut.
b. Dampak Lingkungan
Pembukaan kawasan untuk proyek perkebunan dengan pola kemitraan
terpadu, dimana plasmanya berasal dari masyarakat petani setempat akan
menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan setempat,
baik lingkungan fisik, hayati maupun sosial ekonomi.
Secara ekologis dampak dari proyek perkebunan ini akan berpengaruh
terhadap keseimbangan ekosistem hutan keterkaitannya dengan ekosistem
atau sub-ekosistem lainnya. Perubahan ini akan terus berlanjut pada
komponen-komponen lingkungan laiinya, antara lain satwa liar, hama dan
penyakit tanaman, air, udara , transportasi dan akhirnya berdampak pula
pada komponen sosial, ekonomi, budaya, serta komponen kesehatan
lingkungan.
Untuk itu perlu adanya telaah lingkungan yang berguna memberikan
informasi lingkungan, mengidentifikasi permasalahan lingkungan, kemudian
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 29
mengevaluasi dampak penting yang timbul untuk kemudian disusun suatu
alternatif tindakan pengelolaannya untuk penanggulangan dampak negatif
dan mengoptimalkan dampak positif.
Telaah Amdal yang berkaitan dengan pembangunan proyek perkebunan ini,
yang harus dilakukan antara lain, identifikasi permasalahan lingkungan, yaitu
telaah 'holistik' terhadap seluruh komponen lingkungan yang diperkirakan
akan mengalami perubahan mendasar akibat pengembangan proyek
perkebunan ini, seperti perubahan tata guna lahan, iklim mikro, tanah,
vegetasi, satwa, hama dan penyakit tanaman, sosial ekonomi, sosial budaya,
kesehatan lingkungan dan sebagainya.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 30
7. Kesimpulan
1. Analisa permintaan dan penawaran menunjukkan bahwa sampai saat
ini komoditas kopi merupakan komoditas andalan ekspor non-migas
2. Kopi adalah komoditas yang bebas dijual belikan, sehingga dalam
menerapkan pola kemitraan untuk komoditas tersebut perlu dibuat
nota kesepakatan yang mengikat setiap pihak, serta saling
menguntungkan antara petani dan mitra usaha besar.
3. Pola kemitraan yang dikembangkan adalah Proyek Kemitraan Terpadu
(PKT) dengan mekanisme closed system yang dapat menguntungkan
pihak-pihak yang bermitra, yaitu petani (plasma) mitra usaha besar
dan perbankan.
4. Dengan unit usaha 2 ha/petani, maka kebutuhan biaya untuk
ekstensifikasi kebun kopi arabika adalah 27.753.384/2 ha (termasuk
IDC). Biaya tersebut digunakan untuk investasi tanaman, non
tanaman, management fee dan asuransi kredit.
Sedangkan kebutuhan biaya untuk intensifikasi adalah Rp.
15.259.649/2ha. Dengan mempertimbangkan asset petani, maka
kredit yang diberikan adalah Rp. 2.078.639/ha. Kredit tersebut
digunakan untuk sarana produksi pada TM-1 dan beberapa kebutuhan
investasi non tanaman.
5. Sesuai dengan proyek aliran kas untuk Proyek Ekstensifikasi kredit ini
akan dapat dilunasi oleh petani dalam waktu 7 tahun dengan grace
period selama 2 tahun, yaitu selama tanaman belum menghasilkan.
Dari proyek tersebut juga terlihat bahwa sejak tanaman mulai
menghasilkan petani mendapatkan keuntungan yang wajar dan kas
usahanya tidak pernah mengalami defisit. Untuk proyek intensifikasi
kredit akan dapat dilunasi oleh petani dalam waktu 3 tahun, tanpa
grace period. Dari proyeksi tersebut juga terlihat bahwa petani
mendapatkan keuntungan yang wajar dan kas usahanya tidak pernah
mengalami defisit.
6. Hasil analisa keuntungan menunjukkan untuk Proyek Ekstensifikasi,
dengan skim KKPA yang berbunga 16% per tahun usaha ini
menguntungkan. IRR 28,27% dan B/C nya sebesar 5,03. Untuk proyek
Intensifikasi, IRR 63,67% dan B/C 7,8.
7. Berdasarkan analisa sensitifitas, agar memenuhi kelayakan finansial
untuk proyek Ekstensifikasi harga jual minimal kopi adalah Rp.
2.250/kg, sedangkan untuk proyek Intensifikasi Rp. 1.500/kg
8. Dilihat dari aspek pemasaran, teknis budidaya dan finansial, usaha
pengembangan kebun kopi arabika ini layak untuk dikembangkan
dengan kredit perbankan.
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 31
LAMPIRAN
Bank Indonesia – Perkebunan Kopi Arabika 32
Anda mungkin juga menyukai
- Proposal Bisnis Budidaya Tanaman MelonDokumen53 halamanProposal Bisnis Budidaya Tanaman Melonismanda meisaBelum ada peringkat
- Perkebunan Kopi ArabikaDokumen33 halamanPerkebunan Kopi ArabikaOnri0% (1)
- Proposal Magang Di MGLDokumen13 halamanProposal Magang Di MGLPSHT UMBYBelum ada peringkat
- Strategi Pemberdayaan Dan Penataan PasarDokumen146 halamanStrategi Pemberdayaan Dan Penataan PasarSUFIBelum ada peringkat
- Zat Aktif Tanaman ObatDokumen25 halamanZat Aktif Tanaman Obatshevmyr100% (1)
- Jenis Kambing Dan SapiDokumen19 halamanJenis Kambing Dan SapiDidaBelum ada peringkat
- Meningkatkan Produksi Susu Kambing PEDokumen68 halamanMeningkatkan Produksi Susu Kambing PEFajar HidayatBelum ada peringkat
- Eco Enzyme Menyelamatkan Bumi PDFDokumen3 halamanEco Enzyme Menyelamatkan Bumi PDFPandu Imam Sudibyo AdibBelum ada peringkat
- Serat WedhatamaDokumen12 halamanSerat WedhatamaImamBelum ada peringkat
- Artikel Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Pusat Peradaban - M Dafandra Dimas ADokumen21 halamanArtikel Optimalisasi Peran Masjid Sebagai Pusat Peradaban - M Dafandra Dimas ADafandra DimasBelum ada peringkat
- 2016 Pengantar Pelestarian Pusaka 1Dokumen25 halaman2016 Pengantar Pelestarian Pusaka 1RayBelum ada peringkat
- Proposal Usaha Ternak KambingDokumen8 halamanProposal Usaha Ternak KambingArie Hendarta SeptianBelum ada peringkat
- Tradisi Orang JaWaDokumen33 halamanTradisi Orang JaWaNur Fajrina TamimiBelum ada peringkat
- Pancakai Ati (Edisi Baru) - 2019Dokumen110 halamanPancakai Ati (Edisi Baru) - 2019budi100% (2)
- Pertanian Dan Islam - Perkembangan Ilmu Pertanian Dalam IslamDokumen9 halamanPertanian Dan Islam - Perkembangan Ilmu Pertanian Dalam Islamfazlulrahman85Belum ada peringkat
- Arti Simbol Sesaji SuraDokumen5 halamanArti Simbol Sesaji SuraBahrun MunawirBelum ada peringkat
- AgrisetaDokumen10 halamanAgrisetaLovina SutedjaBelum ada peringkat
- Lap Pelatihan Pemandu SL Pengelolaan Das Esp SolokDokumen149 halamanLap Pelatihan Pemandu SL Pengelolaan Das Esp SolokMuharruddinBelum ada peringkat
- Ski Pangeran Demang 2Dokumen17 halamanSki Pangeran Demang 2Annas Fathoni100% (1)
- Fungsi Titik Atau Area Pijat RefleksiDokumen21 halamanFungsi Titik Atau Area Pijat RefleksiM Kosim AlbanjariBelum ada peringkat
- Buku Pedoman Pendidikan 2016 2017 Fakultas PeternakanDokumen74 halamanBuku Pedoman Pendidikan 2016 2017 Fakultas PeternakanadeBelum ada peringkat
- Laku RitualDokumen28 halamanLaku RitualWahyudi FendyBelum ada peringkat
- ProbiotikDokumen10 halamanProbiotikBagus Ahmad100% (2)
- Usaha TaniDokumen6 halamanUsaha TaniTyas IyasBelum ada peringkat
- SOP Pembuatan PUPUK Super Bokasi N P K Pestisida Rev 5Dokumen4 halamanSOP Pembuatan PUPUK Super Bokasi N P K Pestisida Rev 5Dedi Mulyadi R.Belum ada peringkat
- Analisis Biaya Penggilingan Padi Oleh KeDokumen29 halamanAnalisis Biaya Penggilingan Padi Oleh Keadolkulam100% (1)
- Domba GarutDokumen8 halamanDomba GarutSandra Nugroho100% (1)
- Koperasi PertanianDokumen14 halamanKoperasi PertanianDes MuharBelum ada peringkat
- Makalah Epg - Kelompok 07 - Sayur Dan Buah PDFDokumen20 halamanMakalah Epg - Kelompok 07 - Sayur Dan Buah PDFlintameyla100% (1)
- Laporan Pembuatan PakasamDokumen2 halamanLaporan Pembuatan PakasamMuhammad RafiqBelum ada peringkat
- Setting NFSU2Dokumen4 halamanSetting NFSU2Asmara Putra100% (1)
- Sejarah Keraton SoloDokumen28 halamanSejarah Keraton Solobayu aryantoBelum ada peringkat
- Tugas Kandang KambingDokumen6 halamanTugas Kandang KambingWayan WidyastawanBelum ada peringkat
- Presentasi Tanaman Musiman Dan Tahunan Dea Candra Kirana Xmipa4.Dokumen4 halamanPresentasi Tanaman Musiman Dan Tahunan Dea Candra Kirana Xmipa4.Dea Candra Kirana100% (1)
- Jamu TernakDokumen2 halamanJamu TernakaslandrwBelum ada peringkat
- BAB 14 Analisa Kelayakan UsahaDokumen34 halamanBAB 14 Analisa Kelayakan UsahaReza Alfitra MutiaraBelum ada peringkat
- Ba Kesepakatan PencaiaranDokumen4 halamanBa Kesepakatan PencaiaranGilang AdiyasaBelum ada peringkat
- Kembang SetamanDokumen7 halamanKembang SetamanBambang SatrioBelum ada peringkat
- Cara Budidaya Pare, Cabe Dan GambasDokumen16 halamanCara Budidaya Pare, Cabe Dan Gambassuprihadi estiBelum ada peringkat
- Cara Penggilingan Padi Yang BaikDokumen18 halamanCara Penggilingan Padi Yang BaikLian Siahaan100% (1)
- Pamuksan Prabu AnomDokumen9 halamanPamuksan Prabu AnomLeonyNauraBelum ada peringkat
- Tanggulangi CVPD Pada Tanaman JerukDokumen21 halamanTanggulangi CVPD Pada Tanaman JerukWiwik Septiani0% (1)
- Upja PDFDokumen27 halamanUpja PDFDita Wahyuningtyas TutyBelum ada peringkat
- Tinjauan Umum Tentang Tanaman OkraDokumen9 halamanTinjauan Umum Tentang Tanaman OkraghinaBelum ada peringkat
- Arti Weton Tanggal KelahiranDokumen26 halamanArti Weton Tanggal KelahiranBambang Setiyo Prayitno100% (1)
- Mantra Pengobatan 2Dokumen24 halamanMantra Pengobatan 2Derys SaputraBelum ada peringkat
- Jono Guide Book PDFDokumen36 halamanJono Guide Book PDFIntan PramudyaBelum ada peringkat
- Metode Observasi Dan Pendekatan Pada MasyarakatDokumen49 halamanMetode Observasi Dan Pendekatan Pada MasyarakatZhrahfzah Audilla100% (1)
- Makalah Kelompok I Studi Integrasi Ilmu Al-Qur'anDokumen23 halamanMakalah Kelompok I Studi Integrasi Ilmu Al-Qur'anFittoBelum ada peringkat
- Visi Kelompok Tani RUKUN MAKMUR IV Desa SELOKGONDANG Kecamatan SUKODONO Sejalan Dengan Mayoritas Anggota Kelompok TaniDokumen1 halamanVisi Kelompok Tani RUKUN MAKMUR IV Desa SELOKGONDANG Kecamatan SUKODONO Sejalan Dengan Mayoritas Anggota Kelompok TaniRino PeterPan100% (1)
- Makalah Analisis ProduktivitasDokumen13 halamanMakalah Analisis Produktivitaslevina pridyBelum ada peringkat
- Shalat KejawenDokumen19 halamanShalat Kejawendyah utamiBelum ada peringkat
- KentangDokumen21 halamanKentangrahm24_0567% (3)
- Islam NusantaraDokumen18 halamanIslam NusantaraDody Redaks100% (1)
- Proposal Tasyakuran PSHT 2019Dokumen10 halamanProposal Tasyakuran PSHT 2019nadia eggaBelum ada peringkat
- Terjemahan Dan Makna Surat 114 An-Nas (Umat Manusia) The Mankind Edisi BilingualDari EverandTerjemahan Dan Makna Surat 114 An-Nas (Umat Manusia) The Mankind Edisi BilingualBelum ada peringkat
- Budidaya Ulat Suteradan Produksi Kokon 1Dokumen32 halamanBudidaya Ulat Suteradan Produksi Kokon 1Windrio Indra SampurnoBelum ada peringkat
- Lending Model Budidaya Tanaman JerukDokumen36 halamanLending Model Budidaya Tanaman Jerukwani_singalBelum ada peringkat
- EmpingMelinjo PDFDokumen66 halamanEmpingMelinjo PDFPopo YuppyBelum ada peringkat
- IbM PENGRAJIN TAHU DI KAMPUNG 2Dokumen42 halamanIbM PENGRAJIN TAHU DI KAMPUNG 2Aguyus RiniBelum ada peringkat
- Pola Pembiayaan Usaha Kecil (Ppuk) Usaha Industri RotiDokumen27 halamanPola Pembiayaan Usaha Kecil (Ppuk) Usaha Industri RotiM.Maulana Iskandar ZulkarnainBelum ada peringkat
- Kelayakan Agroindustri Kopi Luwak Di Kabupaten Lampung BaratDokumen10 halamanKelayakan Agroindustri Kopi Luwak Di Kabupaten Lampung BaratOnriBelum ada peringkat
- Perkebunan Budidaya KopiDokumen75 halamanPerkebunan Budidaya KopiOnri100% (1)
- Konversi Koordinat TM3Dokumen6 halamanKonversi Koordinat TM3OnriBelum ada peringkat