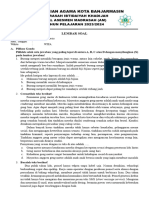Kolom Dea Anugrah
Diunggah oleh
taufik barli0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
272 tayangan38 halamanKumpulan kolom Dea Anugrah di situs asumsi.co
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniKumpulan kolom Dea Anugrah di situs asumsi.co
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
272 tayangan38 halamanKolom Dea Anugrah
Diunggah oleh
taufik barliKumpulan kolom Dea Anugrah di situs asumsi.co
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 38
Keberanian Menghadapi Kebaruan
May 13th, 2019
Kita hadir setelah begitu banyak hal terjadi, selama lebih dari ratusan ribu tahun,
di dunia ini. Dan untuk memahami hal-hal baru, yang ada di hadapan, alangkah
penting mempelajari peristiwa-peristiwa dari masa sebelum kita lahir.
Itu nasihat Umberto Eco kepada cucunya dalam sebuah surat Natal. Dia bukan
kakek saya, tentu, namun saya senang membayangkannya bicara kepada
semua orang, seperti pak tua bijaksana dalam masyarakat pemburu-peramu.
Sebagaimana umumnya orang tua, Eco punya kekhawatiran besar terhadap
generasi kiwari. Ia cemas, misalnya, kemudahan memperoleh informasi di
internet pelan-pelan menggembosi daya ingat kita. "Yang berbahaya dari
anggapan bahwa komputer bisa memberitahumu kapan saja adalah hilangnya
kebiasaan menyimpan informasi di otak," tulisnya.
Namun, berbeda dari kakek saya, yang percaya bahwa dia harus
mengencangkan urat leher saban kami bercakap-cakap lewat telepon ("Kau kan
di Jawa," katanya. "Kalau tidak berteriak, nanti suaraku tidak sampai"),
kekhawatiran Eco dilandasi pemahaman yang memadai atas teknologi.
"Setelah beberapa tahun, komputer di mejamu bakal melambat dan harus
diganti," ujarnya. "Tetapi otakmu sanggup bertahan hingga 90 tahun. Bila kau
terus membuatnya sibuk, kelak ia akan jauh lebih kaya ketimbang sekarang. Dan
itu fitur gratis."
Seandainya sejak kecil saya mendengarkan Eco, yang bijaksana dan caranya
menasihati begitu memikat, akankah saya lebih berani menghadapi kebaruan?
Kebaruan, masa depan, serbaneka yang belum terjadi, terasa menakutkan
karena diselubungi misteri. Sebagian orang, mungkin karena kepalanya penuh
wawasan (atau malah tak berisi apa-apa), menerobos selubung itu secara
gagah berani. Sebagian lainnya memilih bercokol di sudut terjauh, gemetar,
sampai kebaruan yang terus meluas tak terhindarkan lagi.
Dalam lebih dari sepuluh tahun pertama hidup saya, pekerjaan Ayah menuntut
keluarga kami berpindah-pindah tempat tinggal. Tak seperti Ibu yang
pembawaannya mudah disenangi orang, atau adik saya, yang masih balita
sehingga dipandang pantas-pantas saja menancapkan gigi-giginya yang runcing
dan beracun pada apa pun yang bergerak, saya cemas setengah mati setiap kali
kami harus pindah.
Saya takut ditolak. Saya takut dianggap kampungan karena logat saya berbeda.
Apa jadinya kalau di sekolah baru tak ada murid Tionghoa, sehingga saya jadi
dua kali lipat lebih menggiurkan bagi para perundung? Atau bagaimana kalau
sebaliknya, kebanyakan murid di sana adalah Kevin dan David dan Sean, anak-
anak Tionghoa totok, padahal saya hanya seperempat thong ngin dan punya
satu lidah Melayu utuh, yang terkenal berduri dan panjangnya lebih dari 2 meter?
Saat kami bersiap-siap pindah dari Muntok, Kabupaten Bangka Barat, ke
Sungailiat, Kabupaten Bangka, saya memohon agar rencana itu dibatalkan saja.
Alasannya, kata saya, orang-orang di sana terkenal sombong. Kedua orangtua
saya cuma tertawa. Dan saya, yang waktu itu hendak naik ke kelas 3 SMP,
kecewa berat karena merasa mereka telah mengabaikan kebenaran.
Di kemudian hari saya sadar bahwa pernyataan itu bukanlah kebenaran. Ia cuma
persepsi, yang terbentuk dari pengalaman menumpang di kota itu selama tiga
bulan ditambah beberapa kali kunjungan singkat beberapa tahun
sebelumnya. Tak cukup untuk menyimpulkan apa pun, tentu saja.
Kini saya telah berpindah-pindah lebih sering ketimbang orangtua saya. Namun,
terlepas dari berbagai pengalaman kurang sedap, toh saya berhasil keluar hidup-
hidup dan menemukan teman di semua tempat yang pernah saya singgahi.
Sebagian besar ketakutan saya tak terjadi. Dan sebagian kecil yang terjadi
rupanya tak seseram khayalan saya.
Ada berapa banyak pasangan yang mempertahankan hubungan beracun karena
takut tak mendapat ganti, atau malah mendapat ganti yang lebih payah? Ada
berapa banyak buku cemerlang yang batal ditulis karena calon pengarangnya
takut menghasilkan karya buruk? Ada berapa banyak calon pebisnis yang
mencekik impiannya sendiri karena takut gagal? Para kekasih meyakini bahwa
mereka tak bisa hidup tanpa satu sama lain, pengarang yang tak kunjung
menulis merasa kurang berbakat, dan si pengusaha pemula mengira tak ada
yang berminat pada inovasinya. Daftar ini bisa berlanjut, tetapi intinya:
ketidaktahuan dan paranoia yang mengiringinya kerap menciptakan ilusi
kebenaran yang mengelabui kita.
Dari mulut seorang anak yang tidak ingin pindah rumah, hal itu barangkali cuma
terdengar seperti kerewelan sepele. Namun, di tengah masyarakat, ilusi
kebenaran melahirkan hoaks dan teori konspirasi. Jika sudah begitu, tanggapan
yang patut tentu bukan sekadar ketawa.
Menurut Karl Popper dalam sebuah esai di Conjectures and Refutations: The
Growth of Scientific Knowledge(1963), teori konspirasi lebih kuno dibandingkan
kebanyakan agama. Ia bahkan bisa dilacak hingga Homer, penyair Yunani Kuno
yang memberitahu kita bahwa kehancuran Troya adalah hasil persekongkolan
dewa-dewa di puncak Olimpus.
"Teori konspirasi adalah versi lain teisme yang sama, di mana dewa-dewa yang
berkuasa atas segalanya digantikan oleh orang-orang jahat yang luar biasa kuat
dan bertujuan menyengsarakan kita," tulis Popper.
Belakangan ini, seberapa sering kita mendengar, misalnya, tuduhan bahwa
seorang calon presiden bakal membiarkan negara ini diserbu tenaga kerja asing,
sementara calon presiden saingannya dikabarkan hendak membangun fondasi
bagi kekhalifahan?
Sebagian dari kita menelan informasi-informasi tersebut bulat-bulat dan
meyakininya sebagai kebenaran. Maka, saat kedua kubu meninggikan status
coblos-mencoblos calon presiden menjadi peperangan hitam lawan putih, atau
batil lawan suci, atau setan lawan Tuhan, atau omprengan lawan becak motor,
sambil terus mengeksploitasi hoaks dan teori konspirasi, kita terseret-seret
belaka. Padahal, boleh jadi ganti presiden merupakan penyegaran yang
dibutuhkan bangsa ini. Atau, sebaliknya, periode pemerintahan kedua untuk
presiden yang kini berkuasa mungkin saja membawa bangsa kita kepada
kemenangan.
Umberto Eco, yang lahir satu dekade setelah kebangkitan fasisme di Italia,
semasa kecilnya dididik untuk mengingat bahwa bangsa Inggris, Yahudi, dan
para kapitalis bersekutu menindas rakyat Italia. "Hitler menjual narasi yang sama.
Dan Berlusconi menghabiskan jadwal kampanye untuk membicarakan konspirasi
ganda para hakim dan orang-orang komunis. Padahal tidak ada lagi orang
komunis, sekalipun kau mencarinya pakai lampu," kata Eco.
AS Laksana, seorang pak tua lain yang saya senangi, mengatakan bahwa jalan
terbaik bagi masyarakat untuk menangkal narasi-narasi penuh kebohongan itu
ialah dengan menumbuhkan perangai ilmiah alias scientific temper.
Dan memang teori konspirasi bertentangan dengan sains. Jika ilmu-ilmu sosial
bertujuan memahami dan menjelaskan konsekuensi-konsekuensi terencana dan,
terutama, yang tak terencana dari suatu situasi sosial, agar keburukan yang
pernah terjadi tak terulang, teori konspirasi justru mengabaikan konsekuensi tak
terencana. Teori-teori konspirasi senantiasa berangkat dari keyakinan bahwa
segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat merupakan hasil rancangan yang
disengaja. Artinya, alih-alih memberikan pemahaman objektif, teori-teori
konspirasi hanya menyediakan jawaban sekenanya bagi pikiran-pikiran yang
takut dan tidak tahu.
"Dengan menumbuhkan scientific temper, kita mendorong masyarakat untuk
bergairah melakukan pencarian kebenaran dan pengetahuan baru, berpikir kritis,
dan selalu bersandar pada fakta yang teramati, bukan prakonsepsi, apalagi
sekadar otak-atik gatuk," tulis AS Laksana.
Rasa takut terhadap kebaruan, apa pun bentuknya, mungkin takkan pernah
benar-benar meninggalkan kita. Atau, meminjam istilah Eco tentang paranoia
universal yang melahirkan teori-teori konspirasi: ia senantiasa jadi rayuan
psikologis yang tak dapat kita tolak. Namun, laku ilmiah dapat membantu kita
menyiapkan diri. Mengantungi sedikit pengetahuan yang tepat jelas lebih
berharga ketimbang menggendong ransel penuh kesalahpahaman.
Sepekan yang lalu, saya datang ke kantor Asumsi untuk pertama kali. Meski
telah berupaya mencari tahu dan mengingat sebanyak mungkin tentang media
ini, saya tetap takut. Bagaimana kalau, misalnya, Pangeran Siahaan tidak
seasyik dalam video-video Pangeran, Mingguan? Apa jadinya jika Lisa Siregar
ternyata suka mengancam anak-anak buahnya dengan pentungan? Aduh, seram
sekali.
Namun, pada akhirnya, saya kira, satu-satunya cara untuk benar-benar
menyingkap kebaruan adalah dengan mengalaminya secara langsung. Sehari-
hari saya bertugas sebagai editor, dan setiap senin saya akan menerbitkan satu
kolom. Saya harap kesempatan menjalankan rutin ini, juga kerja-kerja lain yang
saya lakukan buat Asumsi, menjadi kebaruan yang menggembirakan bagi
pembaca sekalian.
Api dan Takhta Daenerys Targaryen
May 20th, 2019
Api! Api! Kapal-kapal perang remuk dan tenggelam, barisan tentara bayaran
termahal di dunia kocar-kacir, tembok dan ballista porak-poranda. Puing dan abu
dan kematian di mana-mana. Dan setelah jeda yang terasa seperti selamanya,
lonceng-lonceng berdentangan. Cersei Lannister meneteskan air mata. Rakyat
King's Landing, yang cemas dan barangkali tahu bahwa mereka dimanfaatkan
sang ratu sebagai perisai hidup, memutuskan untuk menyerah.
Bagi banyak karakter Game of Thrones, juga banyak penonton,
amukan Daenerys Targaryen semestinya cukup. Dia sudah menang. Hore!
Selamat! Panjang umur Mama Naga! Pemindahan kekuasaan dan lain-lain dapat
diselenggarakan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Namun, Drogon
mengepakkan sayap dan kamera disentakkan. Tiba-tiba kita hanya dapat melihat
Daenerys dan naganya dari jauh, dari ketinggian atau dari jalanan di bawah,
sebagai pembinasa tak berwajah. Tak berwajah seperti puing dan abu. Seperti
Robert Oppenheimer yang berkata, "Kini akulah maut, pemusnah dunia," saat
menyaksikan bom atom ciptaannya bekerja.
Api! Api!
Tyrion Lannister termangu-mangu. Barangkali dia memikirkan nasib rakyat King's
Landing, terutama anak-anak, dan kegagalannya melindungi mereka. Arya Stark,
yang belakangan ini meraih banyak keberhasilan pribadi tetapi cuma terlunta-
lunta di medan perang terakhir, mungkin menambahkan Daenerys ke daftar
orang yang hendak dibunuhnya. Oberyn Martell dan Petyr Littlefinger, karakter-
karakter kesukaan saya, sudah lama mati. Yang satu kepalanya dipencet sampai
lembek dan yang lain disembelih seperti ayam. Maka, berbeda dari banyak
penonton yang memusatkan perhatian pada "kegilaan" Daenerys (Aaron Bady
menulis esai yang bagus tentang kewarasan "Mad Queen" di LA Review of
Books), saya malah memikirkan King's Landing itu sendiri, kota terbesar
sekaligus pusat pemerintahan Seven Kingdoms.
"Red Keep tak pernah tumbang, dan takkan tumbang hari ini," kata Cersei
kepada Qyburn, Dr Frankenstein sekaligus Zhuge Liang privatnya, menjelaskan
keputusannya menonton amukan Daenerys dari jendela kastil.
Selain merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya, Cersei jelas tak tahu diri
dalam banyak hal lain. Ya ampun, bukankah kedudukannya sebagai ratu jelas-
jelas dihubungkan rantai kausalitas dengan kejatuhan Red Keep 24 tahun
sebelumnya?
Memang, sepanjang Game of Thrones, kita tak pernah melihat Cersei membaca
buku sejarah. Tetapi agak mengejutkan bahwa ia tak mempertimbangkan
Harrenhal, kastil terkuat dan terbesar di Westeros, sebagai pengingat bahwa
musuh yang datang menunggangi naga sebaiknya dituruti, bukan malah
dipancing-pancing supaya mengamuk.
"Harrenhal sanggup membendung gempuran sejuta prajurit," kata Tywin
Lannister, ayah Cersei, suatu kali. Jenderal dan politikus cemerlang itu tentu
membicarakan serbuan darat. Adapun semburan naga, semua orang selain
Cersei tahu, ialah perkara berbeda. Tiga abad sebelumnya, Aegon I Targaryen,
leluhur Daenerys sekaligus orang pertama yang menaklukkan seluruh Westeros,
memanggang Harrenhal beserta seluruh anggota dinasti Hoare yang
bersembunyi di dalamnya.
Dibandingkan Harrenhal, King's Landing jauh lebih rentan. Tak perlu sejuta
prajurit, lebih-lebih naga, untuk menaklukannya. Ada banyak celah, termasuk
yang dipakai Davos Seaworth untuk menyelundupkan Jaime Lannister, buat
menyusup dan merebut kota dari dalam sebagaimana di Yunkai dan Meereen.
Sial bagi penduduk Westeros, Daenerys menyeberangi Narrow Sea bukan untuk
membebaskan kelas terperintah, melainkan merebut takhta, meski harus dengan
api dan darah. Adapun rakyat Westeros, yang menurutnya sudah membusuk
karena tirani, bukan persoalan penting. Api dan darah adalah wujud belas
kasihnya kepada generasi mendatang, kata Daenerys, agar mereka terbebas
dari derita yang sama.
"Terdengar seperti Nazi," kata sejarawan Barry Strauss dalam sebuah
wawancara di The Atlantic.
Hari ini, dalam episode terakhir Game of Thrones, kita akan mengetahui apa-apa
yang akan dilakukan oleh (dan terjadi kepada) Daenerys. Mungkin persis mimpi
yang ia alami di House of the Undying, mungkin lain. Barangkali kita akan
mengingat serial ini sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah, atau
justru kecewa, dengan banyak kata-kata, setidaknya di media sosial.
Yang tak bisa lain adalah situasi King's Landing.
Tyrion Lannister, dalam upayanya membujuk Daenerys agar tak menjalankan
siasat bumi hangus, mengatakan ada sejuta orang di kota itu. Namun, menurut
Steve Doig, pengajar jurnalisme data di Arizona State University, populasi King's
Landing jauh lebih sedikit jika dinilai berdasarkan pemandangan dari jendela Red
Keep. Jumlahnya lebih dekat ke 500 ribu jiwa, seperti perkataan Tyrion beberapa
tahun sebelum itu.
Untuk memperkirakan jumlah korban serangan Daenerys, Matt Wynn dari USA
Today membandingkannya dengan beberapa peristiwa historis. Yang pertama
adalah pemboman Dresden oleh pasukan Sekutu pada 1945, di mana 4.500 ton
bom api dijatuhkan ke area seluas 13 mil persegi. Berdasarkan kepadatan
penduduk Dresden kala itu, hampir 5 ribu jiwa per mil persegi, serangan tersebut
diduga menggempur 65 ribu penduduk, dengan tingkat kematian mencapai 28%.
Perbandingan lainnya adalah dengan pemboman Tokyo pada tahun yang sama.
Serangan pertama Angkatan Udara Amerika Serikat di Jepang itu menyasar
wilayah 15,8 mil persegi, yang sebagian besarnya pemukiman, selama tiga jam.
Dengan kepadatan sekitar 16 ribu orang per mil persegi, populasi terdampak
mencapai 254 ribu jiwa.
"Jika serangan fiksional Drogon semematikan di Dresden, ada sekitar 140 ribu
warga Westeros terbunuh. Kalau setara Pemboman Tokyo, jumlah korban jiwa
mencapai 39% penduduk atau sekitar 200 ribu orang," tulis Wynn.
George R.R. Martin pernah mengatakan bahwa Westeros kurang lebih seluas
Amerika Selatan. Pertanyaannya, bagaimana memerintah sebuah benua, yang
terdiri dari tujuh kerajaan vassal, dari ibu kota yang telah kehilangan hampir
separuh penduduk dan nyaris seluruh infrastrukturnya, ditambah catatan si
penguasa baru dan penyebab kehancuran adalah orang yang sama?
Dalam kenyataan, ada banyak kota yang berhasil bangkit dari kehancuran
mutlak. Dresden dan Tokyo lahir kembali dari abu peperangan, demikian pula
Berlin dan Hiroshima. Lisbon dan San Fransisco, meski pernah hancur-lebur
digulung gempa, kini tergolong kota-kota terbesar dan termaju di negara masing-
masing. Namun, dalam konteks Westeros, Daenerys tak punya banyak sumber
daya. Jangankan memulihkan seluruh kota, untuk membangun ulang Red Keep
saja dananya belum tentu memadai, mengingat pemborosan Cersei dan utang-
piutang takhta Seven Kingdoms kepada Iron Bank of Braavos.
Pada Abad ke-12, Raja Henry II Inggris menghabiskan hingga 40% pemasukan
tahunannya untuk membangun dan merawat kastil-kastilnya. Seabad kemudian,
di tangan Raja Edward I, kerajaan nyaris bangkrut membiayai benteng-benteng
di Wales. Dari segi waktu, pembangunan kastil Abad Pertengahan--yang paling
menyerupai dunia Game of Thrones--berlangsung selama dua hingga 10 tahun.
Sampai hari ini, saya baru membayangkan dua opsi bagi Daenerys dalam
penutupan Game of Thrones, dengan catatan ia tak kena tikam Jon Snow atau
Arya Stark atau siapalah dan cerita berakhir konyol dengan Bran Stark duduk di
Iron Throne. Pertama, kembali ke Dragonstone sembari pelan-pelan membangun
King's Landing, seperti yang pernah dilakukan Aegon I. Namun, perlu diingat
bahwa Dragonstone diciptakan untuk perang, bukan memerintah atau
mengumpulkan kekayaan, dan letaknya yang terpencil jelas akan mempersulit
kendali atas Seven Kingdoms. Kedua, yang lebih baik, ialah memindahkan pusat
pemerintahan ke kota besar lain yang lebih stabil dan mempunyai kedudukan
strategis serta infrastruktur lengkap, seperti Oldtown, Highgarden, atau Casterly
Rock.
Jika menjalankan rencana itu, Daenerys tak perlu memikirkan ketersediaan air,
risiko bencana alam, serta dampak terhadap hutan lindung, kan? Apalagi
keadaannya darurat. Tetapi bagaimana jika, katakanlah, tetap ada penolakan
dari kota yang hendak dijadikan pusat pemerintahan baru? Bagaimana dengan
kepentingan politik elite Westeros, yang mungkin terusik? Seingat saya, King's
Landing penuh penolakan dan politik, dan kini ia rata dengan tanah.
Valar morghulis.
Tentang 22 Mei: Harapan, dari Dekat Sekali
May 27th, 2019
Kalau kota ini terbakar, saya ingin berada di sebuah tempat yang bersih dan
terang, dan--jika boleh meminta lebih banyak--berciuman dengan orang yang
saya cintai. Bukan buat melepaskan diri dari kenyataan yang berantakan,
melainkan untuk merayakan bahwa hidup tak bisa sepenuhnya hancur-lebur.
Bahwa selalu ada harapan, betapa pun kecilnya.
22 Mei 2019, menjelang malam, saya tiba di gedung Bawaslu bersama empat
orang simpatisan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno: dua perempuan seusia ibu
saya dari Bandung dan Ancol; seorang laki-laki paruh baya dari Banten; dan
seorang laki-laki muda dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kami berkenalan di
depan rumah Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada hari yang
sama. Saya bilang saya berasal dari Pulau Bangka, dan berkat baju koko putih
yang saya kenakan, mereka mengira saya seorang mualaf yang datang jauh-
jauh untuk memprotes hasil pemilu.
Saya menanggung ongkos taksi, Ibu dari Ancol membelikan kami makanan dan
minuman untuk berbuka puasa, pria dari Banten berjalan paling depan, dan laki-
laki dari Tarakan--yang mengenakan cincin dan jam emas--mengatakan kami
berlima jangan sampai terpisah. "Kita dari daerah ini kan tidak tahu medan,"
ujarnya. Saya manggut-manggut, tetapi sepuluh menit kemudian meninggalkan
mereka untuk bergabung dengan rekan-rekan Asumsi di Artotel Sarinah.
Karena pemerintah membatasi akses internet, ditambah koneksi yang
sewajarnya buruk di tempat banyak orang berhimpun, saya hanya bisa mencari
tahu letak tujuan saya dengan cara bertanya ke orang-orang. Mula-mula,
berdasarkan informasi dari beberapa demonstran, saya berjalan ke timur. Tak
ketemu, saya menanyai beberapa orang lain dan diberitahu bahwa saya
seharusnya berjalan ke barat. Deritanya mungkin tidak sebanding dengan Ti Pat-
kay dalam serial televisi Journey to the West yang mondar-mandir di gurun
karena diperintahkan berjalan mengikuti matahari, tetapi saya merasa kami sama
konyolnya.
"Masya Allah, kalau berjodoh, Allah pasti mempertemukan!"
Kata-kata itu keluar dari mulut Ismail, yang saya kenal sehari sebelumnya, juga
di Kertanegara, saat kami berpapasan. Dia berasal dari Medan, pernah bekerja
di Jakarta Timur, dan sudah berhari-hari menginap di tenda di luar rumah
Prabowo. "Peci merah loreng Abang kelihatan dari jauh," kata saya. Dia tertawa
dan mengajak saya berbuka puasa bersama. Saya bilang harus mencari hotel
tempat rekan-rekan saya berkumpul.
Sekitar 100 meter dari tempat bertemu Ismail, saya berhenti lagi karena massa
hendak salat berjamaah. Takut mengganggu, saya bersila di dekat sekelompok
pemuda dan remaja berkaus hitam (beberapa di antara mereka mengenakan ikat
kepala dengan tulisan Arab) yang duduk-duduk sambil merokok. Kelak, begitu
kerusuhan terjadi, saya langsung teringat rombongan ini.
Saya jelas tidak relijius, tetapi rasa-rasanya ada semacam keharuan yang
membuai ketika menyaksikan ribuan orang rukuk dan sujud bersama-sama. Alih-
alih amarah dan penolakan, saya hanya melihat mereka memasrahkan diri
kepada yang mereka yakini berkuasa atas segalanya. Kelak, dari berbagai foto,
saya tahu bahwa di balik kawat berduri, para polisi pun meletakkan dahi di atas
aspal untuk Tuhan yang sama, dengan cara yang sama, pada saat yang sama.
Selepas Magrib, para pemandu aksi 22 Mei meminta para demonstran
membubarkan barisan sembari mengemasi sampah masing-masing. "Jangan
tolah-toleh ke polisi. Pulang, keluarga menunggu di rumah!" kata salah seorang
di antaranya. "Perjuangan kita belum selesai. Kami akan mengirimkan undangan
untuk saudara-saudara sekalian kalau waktu untuk bergerak sudah tiba."
Saya terus berjalan ke barat, melewati beberapa ambulans. Artotel belum
kelihatan dan jaringan internet tetap buruk. Saya terpikir untuk menulis tentang
pembatasan akses internet. Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak
Sipil dan Politik (ICCPR), kebebasan menerima dan menyebarkan informasi
memang tergolong sebagai hak-hak yang boleh dibatasi negara dalam keadaan
darurat. Namun, apakah situasi Indonesia darurat? Jika ya, mengapa tak ada
penetapan resminya? Mengapa pula pembatasan itu diumumkan setelah
diberlakukan, bukan sebaliknya?
Kemudian, gara-gara melihat Holiday Inn Express, pertanyaan-pertanyaan itu
berubah jadi lamunan: suatu tengah malam, sehabis dari Jaya Pub--yang terletak
di seberangnya, saya terlampau teler baik untuk pulang ke indekos di Kemang
maupun menyadari bahwa harga sewa kamar di hotel itu semalam akan
menghukum saya selama sepekan. Ini bukan ingatan yang menarik, tetapi saya
kira ia jauh lebih menyenangkan ketimbang apa-apa yang terjadi dan mengisi
kepala saya setelahnya.
Tiba-tiba saya mendengar suara orang berteriak-teriak dari arah belakang.
Merasa ada yang tak beres, saya mempercepat langkah dan menyelinap ke
sebuah warung makan di samping Holiday Inn Express. Namanya Warteg
Kharisma Bahari. Tak sampai lima menit, warung itu ditinggalkan semua
pengunjungnya kecuali saya, yang tak tahu harus ke mana lagi. Kursi-kursi
ditumpuk, kaca dilapik gorden, pintu dikunci, dan lampu-lampu dimatikan.
Bersama para pegawai warung, sesekali saya mengintip ke jalanan dari jendela
atau ventilasi. Orang-orang marah dan berlarian. Api menyala dan letupan
mercon bergaung tak putus-putus.
Saya tak suka kegelapan karena ia selalu merawankan saya, membuat saya
mudah takut. Padahal takut bukan perasaan yang saya inginkan saat itu. Saya
ingin keluar, berdiri di dekat api unggun, dan melaporkan segalanya. Tapi, kata
satu suara dalam kepala saya, baterai ponselmu belum penuh. Dan berturut-
turut: Tapi kau Cina. Tapi para perusuh di luar sana bukan orang-orang yang
datang bersamamu. Tapi mereka tak bakal menyambutmu seperti saudara. Tapi,
kalau kau terjebak, polisi belum tentu percaya bahwa kau--yang tak punya kartu
pers karena baru pindah kantor--adalah seorang jurnalis, dan bisa saja mereka
menyadari bahwa tubuhmu bertato dan malah menghajarmu sebab mengira kau
seorang perusuh. Tapi...
Saya kira pegawai-pegawai warteg memadamkan lampu agar tak terkesan
mengundang penjarah. Mungkin malam sebelumnya mereka melakukan hal yang
sama dan baik-baik saja meskipun polisi dan pengacau saling tumbuk. Namun,
kemungkinan kena serbu tetap berseliweran dalam benak saya. Empat laki-laki
dewasa, tiga perempuan, dan satu anak perempuan. Kira-kira, berapa lama kami
bisa bertahan? Meski pernah belajar karate dan tinju, saya sangat jarang
berkelahi dan tak pernah ikut tawuran. Maka, kecuali para pengacau itu--yang
sebagian besarnya berbadan kurus dan melengkung seperti udang rebon--punya
adab (ini oksimoron, tentu saja) untuk baku pukul satu lawan satu dan bersikap
ksatria saat saya mematahkan lengan mereka sesuai giliran, tak banyak yang
bisa saya harapkan.
Kalau saya sampai mati, saya akan jadi hantu yang menjaili Wiranto setiap hari.
Sesekali jaringan internet membaik dan saya dapat berkomunikasi lewat ponsel.
"Bro, tarik diri sekarang dari lokasi," kata Pangeran Siahaan dalam pesan pendek
yang tertunda beberapa menit. Kalau selamat, pikir saya waktu itu, saya akan
memberitahunya bahwa saya tidak suka dipanggil "Bro." Sementara itu, pacar
saya bilang ia sangat cemas dan mengomel kenapa saya mau-maunya
meletakkan diri di tengah "orang-orang barbar.
Sambil berusaha menenangkannya, saya menjawab bahwa massa aksi dan
kelompok yang sedang berantam dengan polisi tidak sepenuhnya sama.
Sebagian demonstran mungkin terpancing dan ikut-ikutan menyerang, tetapi
kelompok inti perusuh, saya yakin, terdiri dari para pengacau profesional. Dan
para profesional ini semestinya lebih mudah dikendalikan. Kelak, beberapa di
antara mereka yang tertangkap polisi mengaku bahwa mereka memang dibayar.
Saya bilang saya justru mengkhawatirkan para simpatisan sungguhan, yang
sama rentannya dengan saya dalam kekacauan ini. Apakah si Ibu dari Ancol,
yang berkata, "Alhamdulillah, masih ada orang baik di Jakarta" ketika saya
membayar ongkos taksi kami, dapat pulang dengan selamat ke rumahnya?
Apakah Ismail, yang mengaku bahwa nuraninya diketuk oleh Tuhan agar tak
diam saja, ikut berkelahi? Apakah dua pemuda Lampung yang saya temui,
seorang petani dan seorang kasir minimarket, benar-benar memilih "kabur kalau
berhadapan dengan polisi" seperti niat mereka?
Pilihan politik orang-orang tersebut, sebagaimana gagasan mereka tentang
Indonesia yang lebih baik, jelas berbeda dari saya. Mereka bicara banyak dalam
pertemuan-pertemuan kami yang singkat, dan meski tak sepakat, saya tidak mau
merasa lebih benar dari mereka. Saya kira kesediaan untuk mendengarkan
pandangan lain, juga kesiapan untuk memeriksa (kalau perlu, menyesuaikan)
pendapat sendiri, wajib dimiliki semua orang. Dan dalam politik, tentu akan
sangat mengerikan jika hanya boleh ada satu cara memandang.
"Indonesia tidak mungkin tanpa sayap konservatif," kata politikus Budiman
Sudjatmiko. Menurutnya, harus ada dialog yang ajek antara kelompok progresif
dan kelompok konservatif dalam politik, agar--salah satunya--kemajuan dapat
dijaga oleh nilai-nilai yang telah mapan.
Yang menyedihkan, kita tahu, pemilihan presiden kali ini telah mengubah ruang
untuk bercakap-cakap dan berdebat menjadi medan perang.
Hasil penghitungan suara menunjukkan bahwa Jokowi menguasai daerah-
daerah berpenduduk mayoritas Islam nominal dan tradisional atau agama-agama
lain, serta daerah-daerah yang kebanyakan penduduknya beretnis Jawa. Di sisi
lain, Prabowo menang di daerah-daerah yang komposisi etnis dan corak
keagamannya berbeda, seperti Aceh dan Sumatera Barat.
Menurut ilmuwan politik Made Tony Supriatma, penyebabnya ialah penggunaan
sentimen identitas besar-besaran oleh kedua kubu dalam musim kampanye
yang berkepanjangan, ditambah penyebaran hoaks, berita palsu, dan
penyesatan lewat media sosial. Siasat itu mempertebal perbatasan sekaligus
menjadikan para anggota tiap-tiap kubu menganggap pihak lawan sebagai
pembawa kehancuran.
"Jika Anda pendukung Prabowo, berita-berita palsu dibikin untuk menguatkan
keyakinan Anda bahwa pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan represif yang
akan menindas Anda. Jika Anda pendukung Jokowi, Anda akan dipaksa untuk
melihat Prabowo sebagai ancaman eksistensial," tulisnya.
Memang, pada dasarnya, tak ada kelompok yang tidak memiliki musuh. Musuh
diperlukan untuk mendefinisikan diri serta menguji sistem nilai setiap kelompok.
Pertarungan melawan musuh ialah upaya meyakinkan diri bahwa kelompok
masing-masing sungguh-sungguh hebat dan benar.
"Akan jadi apa kita tanpa orang-orang biadab?" tanya seorang warga Byzantium
dalam baris-baris penutup puisi "Waiting for Barbarians" karya C.P. Cavafy,
"mereka menyelesaikan masalah kita." Hanya dengan kabar kedatangannya,
orang-orang itu jadi penyeimbang kehidupan di Byzantium. Selain mengukuhkan
kehebatan kekaisaran, ia mencegah kemutlakan yang melenakan dan
menggerakkan kembali apa-apa yang mandek dalam politik.
Namun, permusuhan antarkelompok berbasis identitas dalam sebuah bangsa,
sebagaimana terjadi di Indonesia kini, hanya menghasilkan gerak yang sia-sia.
Permusuhan ideologis yang mematuhi aturan main memang menyehatkan
demokrasi dan memperbaiki kehidupan, tetapi apa yang mungkin kita harapkan
bila yang dipandang berbeda dan dibela hanyalah keutamaan hal-hal yang
terberi dan biasanya tak dapat diutak-atik, seperti ras dan keyakinan?
Made mengaku tak yakin kita bisa pulih dari keterbelahan akibat pemilihan
presiden kali ini. Pada satu sisi, kubu Prabowo sibuk mendelegitimasi hasil
pemilu (sejauh ini belum ada bukti kuat tentang kecurangan terorganisasi seperti
tuduhan mereka), sementara pendukung Jokowi sama sekali tidak
mengendurkan permusuhan. "Kita berhadapan dengan polarisasi yang tidak
pernah selesai," tulisnya. Dan Made menuntut kedua tokoh yang bertarung itu
bertanggungjawab "menyembuhkan bangsa ini."
Meski sama sekali tidak percaya Prabowo dan Jokowi bakal memenuhi tugas itu,
saya yakin bangsa kita akan pulih. Made Supriatma, selaku seorang ilmuwan
politik, tentu punya dasar untuk berharap kepada perilaku politikus dan partai-
partai politik selepas pemilihan. Namun, sebagai orang yang bersembunyi di
tempat gelap ketika api menyala, terpisah dari semua orang yang saya kenal,
saya menaruh harapan kepada orang pertama yang mengajak saya bicara.
Namanya Anis, anak perempuan berumur sembilan atau sepuluh tahun. Mungkin
ia putri atau keponakan salah satu pegawai Warteg Kharisma Bahari. Sekitar
sejam setelah kerusuhan dimulai, ia mendekati saya dan bertanya: "Kakak mau
di sini sampai kapan?" Suaranya tak mengesankan ketakutan.
"Kalau sampai sepi, boleh?"
"Kemarin, sih, jam tujuh baru sepi," katanya sambil mengaduk teh manis dalam
gelas plastik.
"Tujuh pagi?"
"Iya, tapi nggak apa-apa. Kakak tidur di sini saja," katanya. "Nggak apa-apa. Di
luar berbahaya."
Pada 22 Mei 2019, api menyala di sebagian kecil Jakarta, dan saya menemukan
harapan, keindahan kecil dalam kekacauan itu, dalam bentuk belas kasih
seorang anak. Tidak sesuai khayalan, memang, tetapi toh saya bukan karakter
dalam novel Haruki Murakami atau puisi Aan Mansyur. Saya bisa makan
gorengan dingin atau minum kopi saset sambil melihat api bekerja, dari balik
jendela.
Rumah = Nostalgi + Fantasi
June 03th, 2019
Pada hari kedatangan saya di Mexico City, ibu saya mengirimkan sebuah pesan
pendek. "Bagaimana cara mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Spanyol?"
katanya. Saya menjawab dan kami mengobrol sebentar soal jet lag dan
perbedaan waktu antara Indonesia dan Meksiko. Esoknya, begitu membuka
mata, saya menemukan satu pesan baru:
"Buenos Aires, Nak."
"Caracas, Mama."
Obrolan itu saya ceritakan kepada Tania sekitar sebulan kemudian. "Manis
sekali," katanya sambil menyeka air mata yang keluar saat ia terbahak-bahak.
"Aku tidak paham kenapa kau menampik rumah, tempat ibu semanis itu
menunggumu, dan malah menginginkan tempat celaka ini," katanya.
Saya tidak tahu apakah waktu itu saya paham tetapi tidak cukup artikulatif untuk
menjelaskan ataukah sebenarnya sama bingungnya dengan dia. Yang bisa saya
katakan hanya: "Kita tidak bisa memilih asal-usul, kan? Lagi pula, kautahu, yang
menungguku di sana tidak semuanya manis," lalu menumpahkan keluhan demi
keluhan tentang masa kecil dan remaja dan urusan percintaan dan seterusnya
dan seterusnya, yang serba morat-marit dan tentu saja sudah didengarnya.
"Mexico City lumayan, kok," kata saya sambil meraih gelas berisi mezcal di meja.
"Pertengahan tahun depan aku bisa kembali dan menjalani hidup yang
kuinginkan, bersama orang-orang yang menerimaku apa adanya."
Dia mendengus. "Satu lagi," katanya, dengan mimik serius. "Aku heran kenapa
orang sepintar kau bisa tolol sekali."
"Kenapa tidak bilang, 'dasar bocah tidak tahu apa-apa,' kayak biasanya?" tanya
saya.
Dia tak mengatakannya, tetapi sore itu kami berhenti membicarakan rumah.
Sebenarnya, kami berhenti membahas apa pun setiap kali dia, yang lebih tua 14
tahun (Halo, Vargas Llosa!), bersikap menggurui atau kebiasaannya itu saya
ungkit-ungkit. "Aku cukup tua untuk jadi ibumu," katanya kadang-kadang. Lama-
kelamaan saya terbiasa dengan lagak itu dan hubungan kami justru selesai
ketika dia mengatakan tak hendak menunggu, tidak seperti ibu saya.
Rumah bukan cuma perkara ruang, tetapi juga waktu. Hari-hari itu saya
membayangkannya selalu sebagai cita-cita, yakni sesuatu yang ada di depan,
yang kelak, sambil menampik segala yang ada di belakang dan telah berlalu.
Dengan kata lain: fantasi. Saban mengingat rumah tempat saya tumbuh besar,
yang melintas di pikiran cuma perkataan Asrul Sani dalam sebuah cerpen di
buku Dari Suatu Masa dari Suatu Tempat, "Tiada lagi. Telah punah hubunganku
dengannya."
Hanya setelah fantasi itu pecah berkeping-keping saya sanggup
menyadari bahwa gagasan saya tentang rumah harus dibongkar kembali.
Bertahun-tahun sebelumnya, pernah juga saya membayangkan rumah sebagai
tempat asal, udik atau hulu dari mana saya berangkat. Seperti karakter-karakter
rekaan Umar Kayam, waktu itu saya mengira: terlepas dari apa-apa yang terjadi,
asal-usul adalah sesuatu yang tetap dan sebagiannya selalu terbawa dalam diri.
Lihat bagaimana, misalnya, Lantip dalam Para Priyayi dan Jalan
Menikung memastikan semua anggota keluarganya insaf bahwa pada intinya
mereka adalah Orang Jawa, dan selapis kemudian barulah tentara atau
simpatisan partai komunis atau pegawai negeri.
"Jangan jadi kacang lupa kulit," tulis saya di buku harian, dengan perasaan
compang-camping, ketika berangkat kuliah ke Yogyakarta. Catatan itu saya bikin
dengan huruf besar-besar, tegak mendampingi sepasang nasihat orangtua saya
yang tak kalah dramatis: "kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana
saja" dan "jangan lupa salat."
Entah kapan pikiran itu berubah. Hanya, rasa-rasanya pulang, lebih-lebih mudik
yang riuh setiap tahun, semakin lama semakin kehilangan daya gugahnya. Saya
pernah berkeras melewatkan malam lebaran dengan mengetik saja di kantor
meski ibu saya merajuk dan mengancam untuk tak memasak raya kalau anak-
anaknya tak lengkap.
Mungkin sebabnya adalah kemarahan. Saya marah karena pernah terpaksa
menumpang tinggal di rumah orang lain, terpisah dari semua anggota keluarga.
Saya marah karena orang yang hanya dapat saya pandangi punggungnya selagi
saya tumbuh dewasa, pemberi teladan utama tentang menjadi laki-laki, pernah
menelepon saya dan menceritakan sebuah pengkhianatan sambil terisak-isak.
Saya marah karena banyak hal yang, anehnya, terasa biasa-biasa saja saat
terjadi.
Saya membayangkan rumah hanya sebagai kenang-kenangan, yang ada di
belakang dan mesti terjaga kemurniannya. Dengan kata lain: nostalgi. Dan
seperti fantasi, nostalgi pun terpisah jauh dari kenyataan. Jarak itulah yang,
tanpa saya sadari, memungkinkan saya merasa patut menghakimi rumah secara
keras dan semena-mena.
"Kautahu puisi Khalil Gibran yang mengatakan 'anakmu bukan anakmu'?" kata
AS Laksana pada suatu tengah malam, menanggapi ocehan saya.
Saya menggeleng dan mulai mengetik. Pencarian singkat di internet
menghadirkan baris-baris berikutnya: "Mereka putra-putri kehidupan. Mereka
datang lewat engkau tetapi bukan darimu. Dan meski bersamamu, mereka bukan
milikmu."
"Caraku memahami puisi itu berubah setelah punya anak," katanya.
Pendapat serupa pernah dikatakan ayah saya dalam satu dari sekian banyak
pertengkaran kami. Dia bilang dia mengerti perasaan saya karena ia pun
seorang anak, tetapi saya, yang belum pernah menjadi orangtua, mungkin tak
mengerti perasaannya.
Saya baru tahu betapa sedih kata-kata itu sebenarnya, dan betapa lembut ia
sebagai cara menanggapi kekurangajaran saya ketika menolak diatur, bertahun-
tahun kemudian. "Meski punya jutaan kata-kata indah," kata Maxwell Perkins
kepada Tom Wolfe dalam film Genius, "kau sama sekali tak mengerti hidup, tak
mengerti bagaimana rasanya menatap mata seseorang dan merasa sakit karena
kesedihannya." Saya menonton adegan itu dengan air mata berderai-derai. Ayah
saya jelas tak mirip Colin Firth, tetapi potongan dialog itu mengingatkan saya
kepada perbantahan kami.
Sepotong dialog lain, mungkin dari sebuah film atau buku lain: "Tanganmu bakal
terikat terus kalau kau tak memaafkan."
"Tapi mereka belum meminta maaf."
"Apa perlunya? Kau melakukannya untuk dirimu, bukan buat mereka."
Tentu saya bukan satu-satunya orang yang dijerat kerumitan saat berusaha
memahami rumah. Beberapa bulan lalu saya membaca novel grafis Fun
Home karya Alison Bechdel. Dalam karya otobiografis itu, Bechdel
membayangkan kehidupannya semasa kanak dan hubungannya dengan
keluarga, terutama ayahnya, sebagai pantulan kisah-kisah fiksional yang mereka
baca. Ia memahami keputusan sang ayah untuk bunuh diri lewat buku-buku
Albert Camus; mengenal sifatnya dari Stephen Dedalus, yang penuh keraguan
serta berjarak dari orang-orang lain dan dunia; dan menyamakan nasibnya
dengan Icarus, yang celaka karena terbang kelewat dekat dengan matahari.
Kata Bechdel di akhir cerita, ayahnya jatuh ke laut seperti Icarus, tetapi ia
percaya laki-laki itu menunggu di sana, bersiap menangkapnya jika suatu saat ia
memutuskan untuk melompat.
David Sedaris juga banyak membicarakan rumah dalam kumpulan esai
terbarunya, Calypso. Dalam "Now We Are Five", misalnya, ia menyandingkan
pengalamannya berlibur bersama keluarga semasa kecil, yang penuh
keterbatasan, dengan pengalamannya kini, ketika dia punya segalanya namun
telah kehilangan ibu dan seorang adik. Cita-cita Sedaris untuk memiliki hunian
lapang dengan banyak kamar, juga rumah liburan di tepi pantai, sudah terpenuhi,
tetapi mengapa ia baru dapat merasa lengkap setelah merelakan ketidakutuhan
keluarganya?
Saat merencanakan tulisan ini beberapa hari lalu, perut saya mulas berat. Saya
tiba-tiba menyadari sebuah kekeliruan: tak semestinya saya memilih rumah
hanya sebagai kenang-kenangan atau cita-cita, semata nostalgi atau fantasi,
sembari membantah yang lainnya.
Kedua orangtua saya, sebagai bagian dari asal-usul, tak pernah melarang saya
menghasratkan kehidupan yang saya anggap lebih baik. Demikian pula
sebaliknya Nadya, pasangan saya, bagian dari hari depan, malah tak putus-
putus mengingatkan agar saya selalu memperhatikan orangtua. Saya terlambat
memahami bahwa rumah tak seharusnya hanya dibayangkan sebagai salah satu
di antara kemarin dan besok. Gagasan tentang rumah semestinya mengatasi
dulu, kini, dan nanti, sebab ia terus bergerak bersama diri saya dan orang-orang
yang saya anggap sebagai bagiannya.
Saya merasa beruntung karena menyadari itu sekarang. Beruntung sekali. Nanti
siang, ketika tulisan ini terbit, barangkali saya sedang meletakkan oleh-oleh
titipan pacar di meja makan, lalu memeluk kedua orangtua saya sambil
berbisik, "Buenas tardes, Mama."
Dia mungkin akan menjawab, "Guatemala", dan saya akan mensyukuri semua
yang saya miliki hari ini, merayakan yang lengkap dan yang tidak dalam hidup,
dengan kegembiraan tak terkira.
Jakarta, Kenapa Kita Tidak Berdansa?
Author : Dea Anugrah
June 25th, 2019
Berapakah penghasilan minimum untuk hidup layak di Jakarta? Kalau Anda
melajang, kata penulis Ika Natassa dalam sebuah twit, 10 juta rupiah saja. Pada
twit berikutnya, dia menyampaikan anggaran kasar, mulai dari biaya sewa tempat
tinggal hingga alokasi tabungan. Kalau mau tinggal di tempat eksklusif, katanya,
harus punya gaji 20 juta supaya lega. Rangkaian twit itu mewabah dan orang
beramai-ramai menanggapi Ika: sebagian mengejek kemampuannya berhitung,
sebagian lagi menghakimi gaya hidupnya.
Berkisar dari komentar ke komentar, saya menemukan seseorang
mengatakan,"Gaji saya cuma 4 juta. Hidup saya nggak layak, dong." Saya
menekan tombol like dua kali untuk orang itu dan kecemasannya. Seandainya
ontran-ontran itu terjadi lima tahun lalu, kata-kata sedih tersebut mungkin saja
berasal dari saya.
Lima tahun lalu, saya menjalani pekerjaan tetap pertama di Jakarta dengan gaji 4
juta rupiah per bulan. Di luar pajak dan kewajiban lain-lain, perusahaan
memberikan diskon 500 ribu rupiah karena hampir setiap hari saya
menempelkan jari di mesin pencatat kehadiran pada waktu paling mustajab untuk
berdoa, yakni sepertiga terakhir malam, alih-alih pagi dan sore.
Apa istilah untuk menyebut orang yang memiliki uang berjuta-juta? Jutawan,
tentu saja. Dan selaku jutawan, saya bisa menyewa sebuah kamar yang
jendelanya tidak bisa ditutup, makan tiga kali sehari, dan membeli sekaleng
Bintang buat menyempurnakan me time--artinya duduk-duduk sambil
mendengarkan lagu "Indonesia Pusaka" yang disetel berulang-ulang oleh
tetangga saya--setiap malam. Hidup terasa cukup dan satu-satunya yang tidak
saya miliki cuma harapan.
E.B. White, dalam esainya yang terkenal, "Here is New York", mengatakan
bahwa ada tiga New York. Satu milik orang-orang yang bercokol di dalamnya
sejak lahir atau kanak-kanak, satu buat para pekerja yang umumnya datang dari
kawasan-kawasan satelit, dan satu lagi milik para perantau. Saya kira begitu pula
kota-kota raksasa lain di seluruh dunia, termasuk Jakarta. Warga asli memberi
Jakarta identitas, rombongan pekerja ulang-alik memberinya kesibukan, dan para
perantau memberinya gairah. Semuanya, meminjam istilah Seno Gumira
Ajidarma, adalah Homo jakartensis.
Saya seorang pendatang, tetapi tak ingin selamanya begitu. Saya hendak
menetap sebagaimana urusan-urusan penting dan kesempatan-kesempatan
terbaik menetap di kota ini. Namun, rencana itu memerlukan harapan besar, dan
harapan, pada titik tertentu, menuntut keleluasaan finansial.
Berita buruknya: hari-hari ini, rata-rata orang di seluruh dunia menggunakan
49,3% penghasilan untuk mencicil rumah, jauh lebih berat dibandingkan 17,5%
pada 1996, misalnya. Dan dalam lima tahun terakhir, menurut Real Estate
Indonesia (REI), harga rumah di perkotaan naik 10 hingga 30% meski rata-rata
inflasi hanya sebesar 5%. Maka, hasil survei Kompas pada 2017 wajar belaka:
61% warga berumur 25-35 tahun di tujuh kota besar Indonesia belum memiliki
rumah.
Khusus di Jakarta, yang akan menjadi salah satu kota dengan penduduk
terbanyak di dunia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, hampir
separuh penduduk tak punya rumah, dengan backlog alias kekurangan tempat
tinggal sebanyak 1,3 juta hunian.
Lima tahun lalu, saya tak sanggup membayangkan masa depan yang aman di
Jakarta. Dan kalau saya saja, yang tumbuh besar dalam keluarga kelas
menengah, belajar di salah satu universitas terbaik di negeri ini, dan punya
pekerjaan dengan gaji di atas upah minimum merasa terancam, bagaimana
dengan orang-orang miskin?
Oh, mereka terperosok makin dalam.
Menurut BPS, ketimpangan ekonomi telah banyak berkurang dibandingkan pada
2014, tetapi di sisi lain, saya--yang kini berpenghasilan sesuai standar minimum
Ika Natassa--bahkan mulai merasa hanya sanggup membeli rumah bersubsidi,
seperti banyak orang dengan kemampuan ekonomi setingkat. Pertama, aturan
soal batas penghasilan bisa disiasati dengan memisahkan gaji dalam dua
rekening. Kedua, saya tak sanggup mengejar kenaikan harga di perumahan-
perumahan biasa, yang diperlekas oleh kebiasaan orang-orang berduit
untuk menjadikan rumah sebagai instrumen investasi.
Jadi, di manakah orang-orang miskin semestinya tinggal? Bagi kelas menengah-
atas Jakarta pada umumnya, jawaban untuk pertanyaan itu terang-benderang: di
mana saja asalkan tak dekat-dekat sini.
Ian Wilson, dalam "Pengalihan Isu Ketimpangan & Kemiskinan di Pilgub Jakarta",
mengatakan: "Hasrat memperoleh keamanan, gaya hidup mewah, dan
kenyamanan berarti perluasan pemisahan hidup dari orang-orang miskin. Mereka
mengurung diri di dalam rumah-rumah mewah berpagar, bangunan-bangunan
apartemen yang menjulang, pusat-pusat perbelanjaan, dan kendaraan pribadi."
Wilson juga menulis bahwa penataan ulang kota semasa pemerintahan Basuki
Tjahaja Purnama--yang melibatkan penggusuran sejumlah pemukiman liar--
populer di kalangan kelas menengah karena, salah satunya, mewakili hasrat
mereka untuk bebas dari kekumuhan.
Salah satu konsekuensi terburuk pemisahan ruang hidup adalah distribusi air.
Kita tahu mayoritas penduduk Jakarta, kaya maupun miskin, mengandalkan air
tanah alih-alih jaringan PAM. Dari 1 miliar meter kubik konsumsi air per tahun di
Jakarta, sekitar 630 juta meter kubiknya didapat dari sumur-sumur. Masalahnya,
menurut riset Michelle Kooy dan Kathryn Furlong, pompa-pompa berkekuatan
tinggi di lingkungan-lingkungan bisnis dan pemukiman warga kaya mengisap
sebagian besar air tanah dalam. Itu menyebabkan penurunan permukaan tanah
sekaligus meningkatkan risiko banjir.
Dan kalau banjir terjadi, cadangan air tanah yang tercemar pertama kali jelas di
daerah-daerah kumuh, terutama di pesisir yang rendah. Coba tebak siapa yang
tinggal di sana? Petunjuknya: jangankan alat-alat pengolahan air, membeli air
minum dalam kemasan saja mereka sering tak sanggup.
Kerawanan ekonomi, bayangan berembun tentang masa depan, penyingkiran
dari ruang-ruang hidup yang melekat dengan mata pencarian, ditambah
ancaman kesehatan karena terpaksa minum air beracun, saya kira, lebih dari
cukup buat menjepit saraf siapa saja. Dan dalam keputusasaan, sebagaimana
ditunjukkan olehbanyak sekali lagu pop kita, yang tersisa tinggal "mengapa."
"Mengapa kami menderita?" misalnya, adalah pertanyaan bertenaga besar yang
gampang dimanfaatkan secara politis.
Semasa Orde Baru, pemerintah menjawab dengan cara menunjuk orang-orang
Tionghoa. Belum lama ini, siasat serupa dipakai kembali. Menurut Wilson,
jaringan pendukung Anies Baswedan pada pemilihan gubernur yang lalu "tidak
segan-segan mengeksploitasi kecemasan dan penderitaan kaum papa dengan
ceramah-ceramah yang mencampurkan kritik terhadap neoliberalisme dan
demokrasi dengan kebencian terhadap 'asing.'"
Sewaktu gelombang kemarahan itu bangkit ke permukaan sebagai hasil politik
identitas yang brutal, berapa banyak di antara kita yang malah mengoceh soal
keberagaman sampai berbusa-busa atau, lebih buruk lagi, menggoblok-
goblokkan mereka?
Dua hari lalu, Jakarta berulang tahun ke-492. Saya mendatangi puncak
perayaannya di Bundaran HI. Ramai sekali. Orang-orang berdesakan di sekitar
panggung buat menyaksikan penampilan grup-grup musik terkenal dan
pertunjukan lain-lain. Di sepanjang Jalan MH Thamrin, gelombang manusia tak
putus-putus mendekati atau menjauhi pusat kerumunan. Namun, suasana yang
saya rasakan sama sekali tak mengesankan pesta. Dalam pesta, orang
membaur dan berdansa, bukannya sibuk dengan ponsel atau otopet masing-
masing. Dalam pesta, lampu-lampu bersinar terang. Dalam pesta, kegembiraan
menyala-nyala.
Saya kehilangan minat, lalu buru-buru mengambil sepeda motor yang terparkir di
belakang bioskop Djakarta XXI. Sepanjang jalan, saya berpikir apakah orang-
orang tidak berpesta sebagaimana mestinya karena merasa berbeda satu sama
lain? Atau semata-mata karena memang tak ada pencapaian yang patut
dirayakan dalam setahun terakhir?
Begitu tiba di kamar, saya membuka pintu balkon lebar-lebar dan menuang Jose
Cuervo Especial ke dalam dua gelas. Langit bersih dan terang. Hampir dua
tahun lalu, juga ketika langit bersih dan terang, saya bertanya kenapa orang-
orang di Mexico City bisa berpesta kapan dan, sepertinya, untuk alasan apa saja.
Teman saya Abraham Lobillo bilang bahwa saya beruntung datang ke kota itu
beberapa pekan setelah gempa. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat.
"Gempa, Bung. Gempa keparat itu mengeluarkan sisi terbaik kami," katanya.
Saya menelan isi gelas pertama untuk Jakarta, sambil berharap ia senantiasa
aman dari bencana. Kemudian gelas kedua, diiringi harapan lain, untuk diri
sendiri. Lima tahun lalu, belum ada satu pun buku saya yang diterbitkan dan
teman saya Sabda Armandio mirip sekali dengan Sujiwo Tedjo. Apa susahnya,
sih, mencari sesuatu buat dirayakan? Kalau saja ada musik, asalkan bukan
"Indonesia Pusaka", dan dua atau tiga orang lain, asalkan bukan Pak
Gubernur, saya tak berkeberatan menunjukkan joget T-Rex andalan saya.
Kalau Nasi Sudah Jadi Bubur
June 17th, 2019
Beberapa hari lalu Vice Indonesia menerbitkan berita tentang seorang bos geng
pelajar di Tangerang yang diburu polisi karena perkelahian antara kelompoknya
dan kelompok lain pada Minggu, 9 Juni 2019, mengakibatkan kematian.
Redaktur pelaksana media tersebut, Ardyan M. Erlangga, menikah kemarin
(selamat, Bung!) dan kecil kemungkinan dia mengucapkan ijab kabul sambil
membayangkan gir motor yang diikat sabuk taekwondo dan diputar-putarkan.
Tetapi saya memikirkan berita itu sampai hari ini. Bukan perkara tawurannya,
yang tak pernah saya alami, melainkan: si buron, remaja 16 tahun bernama Dea
Imut, mungkin akan masuk penjara, tempat yang jelas tak menyimpan keimutan
jenis apa pun. Berapa lama ia bakal dikurung? Apakah dia akan kehilangan
tahun-tahun terbaiknya?
Para orangtua, atau setidaknya orangtua saya sendiri, sering menggunakan
cerita-cerita seperti itu buat mengantarkan nasihat. "Kalau nasi sudah jadi bubur,
cuma bisa menyesal," kata ibu saya. Tetapi apakah orang yang dihukum karena
bersalah pasti menyesal? Dan apa yang disesalinya? Hukuman atau
kesalahannya?
Saya ingin percaya bahwa setiap orang, kecuali segelintir saja yang punya
masalah kimiawi tertentu di otak mereka, sanggup menyesali kesalahan--dengan
atau tanpa hukuman. Dasarnya ialah kenyataan bahwa diribukanlah sesuatu
yang beku. Ia bisa berubah, berkembang, membaik, seiring laju hidup.
Dua pekan lagi, saya bakal berumur 28 tahun. Kadang saya mendengar orang
mengatakan bahwa mencapai usia itu adalah sebuah kemenangan, meski saya
tak pernah tahu terhadap apa. Beberapa teman sebaya bilang: tahun ke-27,
kalau bukan yang terberat, merupakan salah satu yang paling menentukan,
dalam hidup mereka. Tetapi saya hanya tahu: sepanjang tahun ini saya gembira
dan kecewa karena banyak hal, menangis dan tertawa karena banyak peristiwa.
Secara umum sama dengan yang sudah-sudah. Bedanya, tentang tahun-tahun
yang lebih lampau, mata saya lebih awas menilai, juga lidah saya lebih luwes
bicara.
Kata George Saunders dalam pidatonya saat melepas wisudawan Syracuse
University pada 2013 (pidato itu kemudian dibukukan dengan
judul Congratulations, By the Way), ada tiga manfaat orang-orang tua bagi anak
muda: meminjamkan duit, menjadi bahan tertawaan, dan memberitahukan hal-
hal yang disesalinya dalam hidup. Tentang yang terakhir, kata Saunders,
"Kadang, seperti yang kalian tahu, orang-orang tua bercerita meski tidak ditanya.
Dan kadang mereka tetap bercerita walaupun kalian sudah bilang jangan."
Sebulan lalu, seorang rekan saya di Asumsi, yang sebelas tahun lebih muda,
memanggil saya "Om." Mungkin ini waktu yang tepat untuk menceburkan diri ke
kolam pemandian air panas dan mulai bicara soal penyesalan, meski tidak
ditanya....
Sebelas tahun lalu, saya tinggal di rumah kontrakan yang pada atapnya terpacak
sebuah tiang besi, dan pada tiang itu bendera Partai Keadilan Sejahtera
berkibar-kibar. Kamar yang saya tempati tak kalah hebat: pada salah satu
temboknya ada poster Intifada Palestina berukuran besar, dan pada sisi lainnya
ada lubang akhir zaman yang bisa mengeluarkan kecoa terbang kapan saja.
Tetapi ongkos sewa kamar itu murah dan itulah satu-satunya tempat yang
ditawarkan oleh pemandu saya, seorang tetangga yang lebih dulu kuliah di
Jogja.
"Insyaallah hanif," kata si pemandu saat memperkenalkan saya kepada kawan-
kawannya. Saya menanyakan apa arti hanif. "Orang yang lurus. Lurus di jalan
Allah," katanya. Dan hanya dalam beberapa hari, latihan para penghuni baru
rumah itu, mahasiswa-mahasiswa semester pertama di UGM dan UNY, untuk
menjadi kader-kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
dimulai.
Pemuda Islam yang baik adalah yang sedikit tidurnya, kata
seorang murabbi alias pembimbing. Maka kami mengikuti liqa atau pengajian
dalam kelompok-kelompok kecil di kampus, di masjid-masjid, dan di rumah, juga
berbagai pelatihan kepepimpinan dan kegiatan organisasi. Saya pernah
merayap-rayap seperti biawak di sebuah kali dangkal berbatu di daerah
Kaliurang, ikut membakar baliho bergambar George Bush dalam demonstrasi,
dan menancapkan bendera-bendera PKS di sepanjang Jalan Affandi pada jam
tiga pagi.
Sampai sekarang, teman-teman sekelas di kampus senang menceritakan
sebuah adegan dari masa ospek setiap kali kami berkumpul. Waktu itu kakak-
kakak tingkat menyuruh kami maju bergiliran buat memperkenalkan diri. Itu
bukan pengalaman biasa buat saya, yang seumur hidup hanya menggunakan
bahasa Melayu dialek Bangka, termasuk di sekolah, dan tidak pernah berbicara
di depan umum. Tekanan itu bertemu sifat berterus-terang yang tak kenal
tempat, dan hasilnya ialah bunyi-bunyian berikut: "Saya Dea Anugrah. Saya Cina
tapi Islam, dan saya gemar membaca teori-teori konspirasi."
Minyak rambut saya meleleh bersama keringat.
"Terus, terus, ingat nggak kelen tasnya Dea?" kata Chandra Siagian, salah satu
kawan kuliah yang paling akrab dengan saya, seorang peranakan campuran
Batak-jet pump, yang keahlian utamanya ialah mengisap apa-apa yang terkubur
jauh di dalam tanah lalu menyemburkannya kencang-kencang.
"Ada patch bendera Palestinanya, oi!" katanya, lalu tertawa memakai jatah
empat orang.
Namun, kelurusan di jalan tarbiyah itu cuma bertahan sebentar. Semester
berikutnya, meski tetap tinggal di rumah itu karena sudah membayar sewa buat
setahun, saya tak pernah lagi mengikuti kegiatan para penghuni lain. Saban
waktu salat subuh tiba, misalnya, pintu kamar saya digedor-gedor. Dan saya,
yang biasanya tidur pagi, cengengesan saja sambil menyumpal kuping dengan
headset. Saya menukar majalahSabili dan Eramuslim Digest dengan buku-buku
Islam Pembebasan, terutama karya-karya Ashgar Ali Engineer dan Ali Shariati,
kemudian menukarnya lagi dengan buku-buku yang membicarakan ide-ide
pembebasan, tanpa Islam, dan seterusnya, dan seterusnya.
Suatu kali, sepulang kuliah, saya menemukan kertas bertuliskan "KALAU
SAMPAI TERCIUM ASAP ROKOK, JANGAN SALAHKAN KAMI" tertempel di
dinding lorong depan kamar saya. Ancaman itu hadir tanpa aba-aba, seperti
saya yang melintas di depan beberapa murabbi saat mereka menggosipkan
bokong Agnes Monica di depan televisi, hanya tak mengejutkan.
Para penghuni rumah itu kemudian pergi satu demi satu. Beberapa orang lulus
kuliah. Sisanya, termasuk kawan-kawan yang sebaya saya, mungkin hijrah ke
kontrakan baru bersama-sama. Suatu malam, selain lampu meja di kamar saya,
semua lampu di rumah itu tak bisa dinyalakan, dan barulah saya menyadari
bahwa saya sendirian di bangunan lapuk dua lantai itu. Bau bangkai tikus
menguar ke mana-mana dan berhari-hari saya tidak berhasil menemukan
sumbernya.
Uang kiriman dari orangtua saya waktu itu Rp500 ribu per bulan, dan lebih dari
separuhnya sudah saya tukar dengan buku-buku. Maka, jangankan buat
menyewa tempat tinggal baru, urusan makan pun kadang saya mesti memakai
siasat 1:1, yaitu sehari makan dan besoknya cuma minum air galon, berselang-
seling. Kadang, saya menumpang makan di kos-kosan teman saya Rozi
Kembara, yang hampir sama miskinnya dengan saya.
Banyak pengalaman waktu itu, juga keputusan-keputusan yang saya ambil di
dalamnya, kini terasa keliru. Memperkenalkan diri dengan ucapan "saya Cina
tapi Islam" di fakultas filsafat, misalnya, tentu akan selamanya jadi salah satu
perbuatan paling memalukan dalam hidup saya. Demikian pula soal keterlibatan
saya di KAMMI. Tetapi saya tak menyesal, juga tidak kepengin mengubah apa-
apa, sekalipun dapat kembali ke hari-hari itu. Di sisi lain, terlepas dari
kekecewaan terhadap satu-dua orang, saya menyesal karena telah memutus
pertemanan dengan orang-orang pertama yang menyambut saya di perantauan.
Saya menyesali urusan itu sebagaimana saya menyesal kerap ikut tertawa ketika
seorang teman sekelas saya di sekolah dasar dihina karena rambutnya berbau
sampah setiap hari. Atau dua tahun kemudian, di sekolah yang sama, ketika
saya mengatakan, "Eit, eit, lihat ke mana sih?" kepada seorang teman yang
bermata juling.
Tak ada hukuman yang saya terima untuk perbuatan-perbuatan jahat itu, tetapi
saya tak pernah bisa melupakannya. Mungkin karena secara alamiah, seperti
kata Saunders, usia menumbuhkan belas kasih. "Selagi menua, kita menyadari
bahwa bersikap egois tak ada gunanya, bahkan tak masuk akal," katanya.
Perubahan itu membuat orang menilai kembali apa-apa yang sudah
dilakukannya.
Gagasan-gagasan moral Saunders agaknya banyak dipengaruhi Buddhisme
dan, hingga taraf tertentu, Katolikisme. Saya tidak paham keduanya, tetapi saya
pernah membaca soal pentingnya belas kasih dalam karya-karya Arthur
Schopenhauer.
Immanuel Kant, dalam Groundwork of the Metaphysic of Morals, mengatakan
bahwa sebuah tindakan dapat dikatakan bermoral hanya jika orang yang menjadi
sasaran perbuatan itu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat. Dengan
kata lain, tindakan tersebut harus steril dari kepentingan pelakunya.
Dan ia memperkenalkan imperatif kategoris, gagasan bahwa setiap manusia
terlahir membawa semacam perintah Tuhan yang membuatnya rela bersusah-
payah, bahkan berkorban, demi keselamatan dan kebaikan orang lain. Namun,
karena didasari "perintah dari atas", sistem itu secara otomatis mengandaikan
sebuah hukum universal, di mana setiap orang dituntut memperlakukan orang
lain sebagaimana ia ingin orang lain memperlakukannya.
Dan dari sisi mana pun, kata Schopenhauer dalam esainya "On the Basis of
Morality", sistem macam begitu jelas egoistik. Dia mengatakan ada satu nasib
yang mengganduli bahu setiap orang di dunia, yaitu kehidupan, yang tidak
bertujuan, dan karenanya merupakan rangkaian penderitaan tak kunjung padam.
Selama puluhan tahun orang bisa mengumpulkan harta, tahta, cinta, popularitas,
dan macam-macam lagi, tetapi yang menunggu sama belaka: kematian, tanpa
makna lebih. Situasi itu melahirkan "Fenomena belas kasih (mitleid), yaitu
keterlibatan langsung seseorang--tanpa kepentingan terpendam--dalam
kubangan penderitaan pihak lain, dan berujung kepada bantuan simpatik untuk
mencegah atau mengurangi penderitaan itu."
Hanya tindakan-tindakan yang didasari belas kasih, kata Schopenhauer, yang
mempunyai nilai moral. Sebab ia murni, bebas dari keakuan orang yang
mengerjakannya. Namun, mungkinkah belas kasih menjadi landasan moralitas
kita semua, dan kemudian menjadi jalan keluar untuk persoalan-persoalan orang
banyak, mulai dari, katakanlah, kebiasaan tawuran antarpelajar hingga
keterbelahan bangsa akibat pemilihan presiden?
Tentu saja tidak.
Menyesali perbuatan-perbuatan jahat, atau tepatnya ketidaksanggupan bertindak
dengan dasar belas kasih, bukanlah urusan sulit. Bahkan sekalipun penyesalan
itu amat besar sampai-sampai saya merasa harus menyembunyikannya di akhir
tulisan: sebelum merantau, saya sering mengatakan bahwa semua orang Jawa
harus diusir dari kampung halaman saya, karena mereka culas dan
senang merebut kesempatan kerja para pribumi, dan seterusnya, dan
seterusnya....
Yang luar biasa sulit ialah perkara setelahnya.
Arti Sebuah Nama
June 10th, 2019
Setiap kali berkenalan dengan seseorang, hal pertama yang saya lakukan
adalah menunggu. Lima, empat, tiga ... kalau matanya mendelik atau mengerjap-
ngerjap dengan cepat, kemungkinan besar obrolan kami akan diawali dengan
pertanyaan. Tiga, dua, satu, "Kok namamu Dea?"
Beberapa teman saya merahasiakan nama asli mereka yang feminin dan
memilih panggilan yang lebih umum buat laki-laki. Dalam sebuah
wawancara, Linda Raharja menanyakan apakah saya pernah terpikir untuk
menggunakan pseudonim. Pilihan-pilihan itu tersedia, tetapi saya menyukai
nama saya sebagaimana adanya. Ia mudah diingat, bunyinya sedap, dan, kata
ayah saya, mengandung harapan agar saya senantiasa menghormati
perempuan seperti saya menghormati diri sendiri.
Selama ini, tanpa malu-malu, saya mengira sudah memenuhi harapan tersebut.
Memang saya tidak pernah memperlakukan perempuan secara kurang ajar, juga
tak pernah berpikir "sALah sEnDiri paKai RoK pEnDek" atau semacamnya
tentang korban kekerasan seksual, misalnya, tetapi apakah itu sudah cukup
untuk disebut menghormati?
Seorang teman pernah memberitahu saya bahwa ada kenalannya yang tak
menyukai Bakat Menggonggong dan penulisnya, yaitu saya sendiri, karena
cerita-cerita di dalam buku itu "terlalu maskulin." Waktu itu saya membela diri,
juga tanpa malu-malu, dengan argumen pinjaman dari novelis Jim Harrison
dalam wawancaranya dengan Paris Review: "Masak orang disalahkan hanya
karena menulis tentang apa-apa yang dia alami dan ketahui?"
Namun, ketika membaca ulang buku itu untuk keperluan penerjemahannya baru-
baru ini, saya merasa penilaian yang disampaikan teman saya kelewat halus.
Mungkin, sebelum mengatakannya, dia sudah menyaringnya bolak-balik. Semua
narator dan tokoh utama cerita-cerita saya laki-laki, sedangkan karakter-karakter
perempuannya cuma kebagian peran cerewet, sulit diajak bicara, khianat, dan
selalu memperkeruh keadaan meski sekadar berjongkok di pinggiran cerita.
"Sejarah mencatat terlalu banyak lelaki hebat yang tumpas karena gagal
menjinakkan perempuan," kata narator cerpen "Sebuah Cerita Sedih, Gempa
Waktu, dan Omong Kosong yang Harus Ada." Seorang pembaca berkomentar di
Twitter: "Kenapa pula perempuan harus dijinakkan?" Kita memang bisa bicara
berbuih-buih bahwa narator atau tokoh utama tidak sama dengan pengarang,
bahwa pendapat yang satu belum tentu mencerminkan yang lain, tetapi
bagaimana menjelaskan keseragaman cara pandang 14 cerita di buku itu selain
mengakui betapa sempit penglihatan penulisnya?
Setiap pengarang, kata Intan Paramaditha dalam esainya "Jalur Feminis pada
Pengaruh Sastra", mesti mencari jejak-jejak suara, pikiran, dan cerita para
pendahulu perempuan dalam karya masing-masing, dan mencari tahu sebabnya
apabila jejak itu tak ketemu. Saya senang mempelajari puisi-puisi Wislawa
Szymborska, Gabriela Mistral, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, dan banyak
penyair perempuan lain. Kalau harus membuat daftar pengaruh atau
rekomendasi dadakan, satu atau dua dari nama-nama itu bakal saya cantumkan
di tiga besar. Namun, sebagai penulis cerita pendek dan esai, urusan serupa
menjadi pelik. Selain Lydia Davis, mungkin semua penulis prosa yang saya
anggap hebat dan hendak saya ikuti adalah laki-laki.
Bagaimana dengan penulis perempuan Indonesia? Mungkin, saya bahkan tak
bakal membaca Habis Gelap Terbitlah Terang seandainya tak kepepet. Pada
2013, Ubud Writers and Readers Festival menjadikan judul kumpulan surat
Kartini itu sebagai tema pokok. Saya tidak pernah tahu mengapa panitia
mendudukkan saya, bukan emerging writer lain, di samping Joost Cote,
penerjemah dan pakar Kartini dari Monash University, Australia, dan Ayu Utami
dalam diskusi berjudul Kartini's Letters. Panitia mungkin tidak menyangka bahwa
saya bakal mempermalukan diri saya dan semua orang hanya beberapa menit
setelah pidato pembuka festival oleh Goenawan Mohamad.
Setelah membaca buku itu dalam sekali duduk, saya pikir surat-surat Kartini
adalah sumbangan besar pertama Indonesia untuk Global Whining.
"Siapa, sih, orang itu?" tanya Goenawan kepada Zunifah, teman seangkatan
saya di kampus yang menjadi relawan festival dan kebetulan berdiri di
sampingnya. Zunifah menceritakan itu selepas diskusi. "Keningnya berkerut dan
jarinya nunjuk-nunjuk kamu, lho," katanya, lalu tertawa kencang sekali. Saya
kabur sebelum bunyi-bunyian itu reda.
Orang-orang mengatakan bahwa selera bacaan tak pernah murni. Ia bukan
sekadar mengikuti pengetahuan dan pandangan si pembaca, melainkan juga
membimbingnya. Ia berjalan di belakang sekaligus di depan. Dan ketika berjalan
di depan pembaca, selera itu sebenarnya mengikuti jalur yang telah disiapkan
pihak-pihak lain lewat, misalnya, kanonisasi dan politik kebudayaan. Jika tulisan-
tulisan saya yang menampakkan kesempitan pandangan tentang perempuan
merupakan akibat kekotoran saya sebagai pembaca, saya kira cara terbaik untuk
mengubahnya ialah dengan memperluas bacaan, tanpa memedulikan arahan
selera.
Mudah saja, pikir saya beberapa bulan lalu, sewaktu mengambil dua novel tipis
karya pengarang perempuan, Clarice Lispector dan Sayaka Murata, dari rak toko
buku. Satu atau dua halaman, tidur, dan sampai sekarang saya belum beres
membaca keduanya. Teman saya Sabda Armandio berkali-kali
merekomendasikan, bahkan mau meminjamkan, novel Homegoing karya Yaa
Gyasi. Tapi saban kami mengobrol, yang saya tanyakan cuma penyakit tukak
lambungnya. Di sisi lain, buku-buku George Saunders dan Yuri Herrera yang
saya beli belakangan malah rampung dalam sekali baca.
Siasat berikutnya adalah membaca novel-novel grafis yang dibuat seniman dan
penulis perempuan. Berhasil. Saya menikmati Anya's Ghost karya Vera
Brosgol, This One Summer karya Mariko dan Jillian Tamaki, dan lain-lain.
Memang sebagian besar merupakan kisah-kisah coming-of-age, yang cenderung
mudah dibaca, tapi setidaknya saya jadi bisa menghibur diri: kesulitan membaca
cerita-cerita perempuan pasti bisa terobati.
Dan dua hari lalu, nenek saya dari pihak ibu, yang biasanya selalu kelihatan
sibuk bekerja, bercerita tentang ayahnya. Saya pernah mendengar cerita
sepotong-sepotong dari Ibu dan Bibi bahwa kakek buyut saya, namanya Tjhia
Tjung, datang dari Taipei. Rupanya cerita itu keliru. Kata nenek saya, ayahnya
berasal dari provinsi Guangdong di Cina Daratan, dan melarikan diri dari wajib
militer--kemungkinan besar untuk Perang Cina-Jepang Kedua (1937-1945) atau
Revolusi Komunis Cina (1945-1949).
Dia tiba di Pulau Bangka dan memutuskan untuk beranak-pinak. Pada akhir
1950-an, Tjung sekeluarga hendak kembali ke Cina tetapi batal karena nenek
buyut saya hamil dan takut melahirkan di kapal. Dan kapal tak pernah datang
lagi.
Setelah cerita singkat tentang keterampilan kungfu kakek buyut, pelan-pelan
minat saya bergeser. Saya jadi lebih banyak bertanya tentang riwayat si juru
cerita, nenek saya. Namanya Tjhia Jun Lan dan ia bilang ia disayangi
ayahnya karena gesit mengerjakan apa saja, mulai dari menganyam pukat
sampai mengangkut kayu-kayu untuk membangun rumah. Sementara itu, ibunya
gila judi dan agak sedeng. Ketika Jun Lan berumur 16 tahun, ibunya, yang
didorong cemburu buta, mengancam: "Kalau bukan dia, aku yang keluar dari
rumah." Maka Jun Lan mengalah.
Dia memulai hidupnya di kota asing, sebatang kara, sebagai pembantu rumah
tangga yang cuma dibayar makanan. Kalau pekerjaan sudah beres, dia mencari
uang tambahan dengan menjahit. Lama-kelamaan, koleksi keahliannya
menumpuk: mengobras, memasak, membuat kue, memangkas rambut,
memelihara segalanya. Dua tahun kemudian ia kawin dengan kakek saya,
seorang Melayu, dan memilih untuk menjadi mualaf. Hubungannya dengan ayah
dan ibunya putus. Namun, tentu saja tidak ada penderitaan terakhir. Kakek saya
senang main perempuan dan, kata nenek saya, ia menanggung derita itu
sendirian selama 17 tahun.
"Mau cerita ke siapa? Adik-adikku paling cuma akan bilang, 'siapa suruh kawin
sama Melayu?'" katanya. "Jadilah aku menangis sambil menguleni adonan kue.
Entah sudah berapa banyak orang yang makan air mataku," katanya.
Kapan-kapan, saya ingin menceritakan kisah hidupnya secara lebih rinci. Namun,
kembali ke urusan jejak suara, cerita, dan pikiran perempuan, kini saya punya
satu riwayat yang bakal saya dekap erat-erat sampai kapan pun. Lisan saja, tapi
berapa banyak di antara kita yang mula-mula berminat kepada cerita berkat
kelisanan? Berkat kisah ini, yang bekasnya pada saya tak kalah dalam
ketimbang The Old Man and the Sea, misalnya, saya merasa mendapat
tambahan rasa percaya diri untuk mendengarkan lebih banyak cerita dan pikiran
perempuan, untuk membaca buku-buku mereka, meski mungkin tetap tak
mudah.
Menghormati seseorang, saya kira, mencakup keinginan untuk
mendengarkannya, mengetahui pendapat-pendapatnya, mempertimbangkan
perasaannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bukan sekadar tak berbuat jahat
kepadanya. "Tapi," kata Nadya Noor, yang pertama membaca rancangan tulisan
ini, "kenapa kamu merasa harus menghormati perempuan?"
Bukan agar lebih memahami perempuan, juga bukan supaya bisa menulis lebih
baik tentang mereka. Itu jelas tak masuk akal, sebab perempuan bukan sekadar
konsep atau cangkir di atas meja, yang kedudukannya tetap dan tinggal diraih.
Setiap orang adalah pribadi, bukan setumpuk kopi yang identik dari selembar
kertas.
"Atau, masak cuma untuk memenuhi harapan dalam namamu?"
Saya mengatakan sesuatu kepadanya, yang tak hendak saya tuliskan di sini.
Tetapi tentu saja bukan perkara nama. Lagi pula, seperti kata Juliet Capulet
dalam lakon Shakespeare yang judulnya diketahui semua orang: apa, sih, arti
sebuah nama?
Asal-usul Penderitaan
Author : Dea Anugrah
July 15th, 2019
Beberapa jam setelah tulisan pertama saya untuk Asumsi terbit, saya menerima
pesan WhatsApp dari Zen RS. Katanya, kalau saya berhasil menulis kolom
mingguan selama setahun tanpa ada yang terlewat, dia bakal
membelikan sesuatu. Sesuatu, kata yang dipilihnya, mungkin saja berarti obat
nyamuk bakar, maka saya tak merasa terbebani. Yang mengganggu pikiran saya
adalah kalimat berikutnya. "Aku pernah dikoyak-koyak deadline seminggu satu
tulisan," kata Zen.
Kesempatan memperoleh obat nyamuk bakar itu menguap pada pekan
kedelapan alias dua minggu lalu. Saya berada di Luwuk, sebuah kota kecil yang
indah di ujung timur Sulawesi, untuk mengoceh tentang kepenulisan di depan
banyak orang, tetapi benar-benar tidak tahu harus menulis apa untuk ruang yang
dipercayakan sepenuhnya kepada saya. Sehari, dua hari--kembali ke Jakarta--
seminggu... beban makin menumpuk, saya tetap tak kuasa. Hari ini, pekan
kesepuluh, ada tiga draf tulisan terbuka di layar dan semuanya mampat. Langit
makin terang dan pandangan makin buram.
Segenap tulang, otot, dan saraf pada jari-jari kita sudah lebih dari cukup untuk
menulis apa saja, kata Wislawa Szymborska dalam sebuah puisinya. Saya
pernah mengutip kata-kata itu, dengan kepercayaan diri berlimpah, untuk
menjawab pertanyaan tentang writer's block dalam sebuah wawancara. "Seperti
dosa," kata saya waktu itu, "ia hanya ada kalau kita memikirkannya."
Tak ada yang berubah dalam cara saya bekerja. Setiap tulisan berangkat dari
ikhtisar. Saya memecah pokok pembicaraan menjadi balok-balok kecil,
membayangkan pilar dan kamar, lalu mengatur penempatan setiap balok agar
kelak ia menjadi bangunan yang kokoh, molek, sekaligus nyaman.
Saya mengawali rancangan tulisan yang pertama, tentang kekuatan cerita, lewat
sebuah peribahasa populer "satu gambar bernilai setara seribu kata." Kita sering
mendengar bahwa kata-kata itu berasal dari Konfusius, atau siapalah orang bijak
lain dari Cina Kuno, kan? Saya mengira atribusi itu wajar, sebab memang
ungkapan tersebut terasa antik: ia ringkas, gampang dipahami, dan
menggunakan kata "seribu" semau-maunya--seperti Lawang Sewu, Candi Sewu,
dan lagu Didi Kempot "Sewu Kuto."
Rupanya, menurut Burton Stevenson dalam buku The Home Book of Proverbs,
Maxims, and Familiar Phrases, ungkapan itu mula-mula digunakan sebagai trik
pemasaran iklan bergambar pada awal abad ke-20, tak lama setelah kamera-
kamera murah menyerbu pasar dan fotografi jadi bisa diakses semua orang.
Sampai di situ uraian mandek karena saya tak kunjung menemukan cara yang
pas untuk mengaitkannya dengan pokok pembicaraan.
Untuk tulisan kedua, tentang kesempatan para penulis mendapat penghasilan
dari luar industri buku, saya benar-benar menjumput bahan dari Cina Kuno,
tepatnya dari abad ke-3 SM: Perdana Menteri Lü Buwei dari kerajaan Qin
menghimpun ribuan sarjana untuk menuliskan kitab berisi "segala urusan Langit
dan Bumi, hal-hal tak tepermanai, masa lalu dan kini" alias semacam kombo
maut buku RPUL, pengantar ilmu pemerintahan, dan astrologi.
Hasil proyek ambisius itu sewajarnya sempurna. Dan buat membuktikannya,
Perdana Menteri Lü menawarkan seribu keping emas kepada siapa pun yang
sanggup menyunting Lüsi Chunqiu, meski hanya menambahkan atau
mengurangi satu huruf.
Untuk menciptakan kontras, saya iseng-iseng menghitung waktu yang diperlukan
teman saya Safar Banggai buat mengumpulkan seribu keping emas dengan
pekerjaannya sebagai editor lepas di Yogyakarta. Begitu hasilnya keluar, yaitu
308 tahun saja, segenap rancangan yang terpacak dalam kepala saya roboh.
Mungkin Safar membuat saya jadi agak putus asa, tetapi mungkin juga tak ada
hubungan apa-apa di antara keduanya. Satu-satunya yang terang ialah saya tak
sanggup meneruskan cerita.
Kebuntuan demi kebuntuan itu membuat saya merasa gagal sebagai penulis.
Namun, seperti mata yang dapat membedakan terang dari gelap, menyadari
kegagalan berarti menyadari pula bahwa di sisi yang berlawanan, di seberang
sana, ada keberhasilan. Keberhasilan, kata orang, ialah kesanggupan memenuhi
tujuan. Tetapi apa, sih, tujuan orang menulis?
Saya senang membayangkan bahwa saya menulis untuk meneruskan kebaikan
buku-buku yang pernah saya baca. Ada harapan kelak, entah di mana, tulisan-
tulisan saya menyentuh seseorang dan mengubah caranya memandang dunia,
sebagaimana novel-novel Hemingway dan Camus, misalnya, pernah
menyadarkan saya bahwa dalam hidup ini orang harus bertahan meski tahu
pada akhirnya akan kalah.
Namun, kalau benar-benar menginginkan hal itu, semestinya saya lebih giat
mencari pembaca, sebanyak-banyaknya. Beberapa teman penulis menyarankan
agar saya mencari penerjemah, mengirimkan karya ke media-media berbahasa
asing, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tak berminat menjalani urusan-
urusan itu karena tahu tak bakal menderita seandainya harapan itu tidak
terwujud. Ada banyak sekali buku hebat di dunia ini, dan kalau itu tak cukup
untuk menyentuh dan mengubah cara orang memandang dunia, atas dasar apa
saya merasa dapat memperbaiki keadaan?
Lagi pula, kata Schopenhauer dalam "The Art of Being Right", kalau seseorang
menyadari bahwa pendapatnya berbeda dari orang lain, hal pertama yang ia
lakukan bukanlah mencari kesalahan dalam proses berpikirnya sendiri,
melainkan menganggap lawan bicaranya keliru. Sebaliknya, kalau menemukan
pandangan yang sejalan dengan miliknya, meski melenceng, orang akan dengan
senang hati turut memeluknya.
"Pada dasarnya," kata Schopenhauer, "kita ini keras kepala." Tetapi dia, juga
saya, percaya bahwa orang dapat berubah. Jika Schopenhauer yakin bahwa
filsafat membukakan jalan bagi belas kasih, dan belas kasih melahirkan
penerimaan, saya percaya bahwa hasil yang sama dapat dilahirkan oleh tulisan-
tulisan yang baik.
Tetapi tulisan tak sepatutnya dibuat dengan tujuan mengubah orang. Saya baru
menyadari bahwa itulah sumber penderitaan saya dalam tiga pekan belakangan.
Kelewat ingin menyampaikan bermacam-macam urusan, saya lupa bahwa
aturan utama dalam menulis bukanlah menanamkan ide di kepala orang.
Kata George Saunders, yang tulisan-tulisannya senantiasa penuh empati dan
memancarkan harapan dalam situasi segelap apa pun, selagi menulis dia cuma
berpikir untuk mengurangi keburukan tulisannya. Kalau ada kalimat sembrono, ia
membuatnya lebih kaya. Kalau ada karakter yang terkesan cuma seperti setan,
ia memberinya kepribadian dan latar belakang. Begitu terus, kata Saunders,
sampai alat ukur imajiner dalam kepalanya menunjukkan bahwa ia sudah
menulis sebaik yang ia bisa.
Bukan kali ini saja kata-kata Saunders menyentuh dan mengubah cara berpikir
saya. Kalau suatu hari nanti kami bertemu, saya hendak mengucapkan terima
kasih dan memberinya oleh-oleh, tapi tentu bukan obat nyamuk bakar.
Lahir seorang Rich Brian, Tenggelam Beratus Ribu
July 23th, 2019
Rich Brian menyebut "Kids" lagu istimewa saat mengumumkan peluncurannya
lewat Twitter. Tak bisa lain, memang. Musiknya sedap, boom bap dengan cita
rasa kiwari, dan sang MC bukan lagi badut dalam "Dat $tick" atau pecundang
dalam "History."
Kali ini Brian berbicara tentang diri yang gagah sekaligus rawan, yang siap
menaklukkan dunia tetapi penuh hormat terhadap segala yang menaunginya:
keluarga, kultur hip hop, Indonesia, Asia, dan tradisi diaspora. Kedalaman
membuat lagu ini terasa tulus, dan ketulusan itu menggugah.
"Fuck bein' one of the greatest, I'm tryna be the greatest one," ujarnya. Dan pada
baris lain, dia mengatakan: "Everyone can make it, don't matter where you're
from."
Sebagaimana Presiden Jokowi yang tersenyum kebapakan saat lagu itu
diputarkan untuknya di istana, saya tentu berharap cita-cita Brian terwujud. Saya
juga senang membayangkan bahwa pencapaian demi pencapaiannya
menyalakan api dalam diri orang-orang lain. Namun, pada saat yang sama,
hasrat Brian yang meluap-luap terhadap kesuksesan dalam "Kids" mengingatkan
saya kepada sebuah perkara sedih.
"Umur kita hampir 30 tahun, dan aku belum jadi apa-apa," kata seorang teman
baik saya suatu kali. "Such a failure."
"Memangnya situ mau jadi apa, Bung?" tanya saya.
"Setidaknya di umur 30 sudah bikin album musik atau apalah," katanya.
Pengantar daftar tahunan "30 Under 30" Forbes pada 2014 menyatakan bahwa
anak-anak muda masa kini beruntung, sebab dunia digital yang dinamis
memungkinkan kita untuk langsung menguber tujuan-tujuan besar tanpa
berlama-lama mematangkan diri seperti angkatan terdahulu. Namun, yang tak
dikatakan catatan tersebut, kesempatan menggapai cita-cita yang terbuka lebar
hadir bersama tuntutan semena-mena: sukses dalam tempo sesingkat-
singkatnya.
Usia 30, seperti yang dikhawatirkan teman saya, memang telah jadi semacam
simpang di mana orang-orang sukses dan gagal berpisah. Menurut Paul
Graham, seorang venture capitalist ternama, para pendiri perusahaan yang
berusia di atas 32 tahun cenderung lebih sulit mendapatkan pendanaan.
Kita, ujar Chairil Anwar dalam puisinya "Catetan Th. 1946," bagai anjing diburu.
Dan hari-hari ini, lebih dari 70 tahun kemudian, sama saja. Teman saya tentu
bukan satu-satunya yang cemas mendapati bahwa hidupnya tak sesuai dengan
naratif kesuksesan. Padahal, tak peduli seberapa erat kita memeluk keyakinan
bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama, kesuksesan, lebih-lebih di
usia muda, menuntut bakat, akses, daya tahan, ambisi, dan mungkin hal-hal lain
lagi. Tentu sedikit saja orang yang memiliki semuanya.
"Lahir seorang besar dan tenggelam beratus ribu," kata Chairil dalam puisi yang
sama. "Keduanya harus dicatat, keduanya dapat tempat." Jika si besar hari-hari
ini adalah orang yang memenuhi tuntutan kesuksesan, katakanlah seperti Rich
Brian, tempat macam apa yang patut diberikan kepada mereka yang
tenggelam?
Saya berharap kita bisa lebih relaks. Orang yang belum jadi apa-apa saat
berumur 30 tahun mungkin saja mekar di kemudian hari, seperti Paul Cézanne
atau Mark Twain. Dan yang terpenting, saya kira, kita mesti bertanya: kenapa,
sih, orang harus sukses?
"Masyarakat kita tak pernah puas menelan cerita-cerita tentang kekayaan dan
kesuksesan," kata Paul Dolan, Kepala Departemen Psychological and
Behavioural Science di London School of Economics. "Tanpa keduanya, kita
gelisah dan menderita."
Naratif-naratif sosial itu memandu hidup kita, menyediakan jalan. Namun, ujung-
ujungnya, "lebih dari ingin memastikan diri selalu berada di jalan itu, kita bahkan
memarahi orang-orang yang melenceng," kata Dolan. Di titik inilah pikiran kita
terperangkap: hanya ada satu cara.
Hanya dengan berpikir demikian kita menganggap yang tak sukses, yang tak
menjadi apa-apa, sebagai kesia-siaan.
Kita terbiasa mengira akan semakin bahagia bila semakin banyak harta dan
kesuksesan bertumpuk, bila terus-terusan meraih lebih. Padahal, sebagaimana
ditunjukkan riset American Time Use Survey (ATUS), orang-orang
berpenghasilan di atas US$100 ribu tak lebih bahagia ketimbang yang mendapat
kurang dari US$25 ribu. Bahkan, orang-orang dari kelompok berpenghasilan
paling tinggi justru paling sering mengaku merasa hidupnya hampa.
Menurut Penelitian City & Guilds pada 2012, 87% floris dan tukang kebun di
Inggris merasa bahagia. Jumlah itu jauh lebih tinggi ketimbang bankir (44%) dan
pengacara (64%), sekalipun kelompok profesi yang terakhir jelas lebih makmur.
Orang-orang yang berbahagia, saya kira, mengerti bahwa kesuksesan bukanlah
harga mati.
Kalau ada kesempatan, saya ingin mengatakan kepada teman saya bahwa tak
peduli sukses atau tidak, menjadi besar atau tidak, dia tetaplah salah satu orang
paling menyenangkan yang saya kenal. Dan atas dasar itu saja, hidupnya patut
dirayakan.
"Jauh di dasar jiwamu bertampuk suatu dunia," kata Chairil dalam sebuah puisi
untuk sahabatnya, penyair LK Bohang. Dan pada baris lain, ia memuji sepenuh
hati, "Duka juga menengadah melihat gayamu melangkah." Tak ada satu pun
karya Bohang yang saya ingat. Mungkin karena memang tak ada yang istimewa.
Bagi saya, ia cuma satu dari ribuan nama yang tenggelam dalam sejarah sastra
Indonesia, tetapi Chairil Anwar merayakannya.
Di Balik #AsumsiDistrik: Mengurai Manggarai
Sejauh yang saya ingat, kakek saya selalu tinggal di Kampung Katak, sebuah
kampung kota di belakang Jalan Sudirman, Pangkal Pinang. Rumahnya sesak
dan bobrok dan berimpitan dengan bangunan-bangunan lain. Beberapa tahun
sebelum meninggal dunia, dia pindah ke rumah yang lebih patut di lingkungan
yang sama.
Gang-gang di sana sempit, apak, gelap, dan umumnya tergenang air buangan
rumah tangga. Kakek saya beruntung karena jalan menuju rumahnya dilengkapi
pelimbahan, dan saya senantiasa berhati-hati agar tak menginjak terali penutup
lubang tersebut. Bukan soal merawat fasilitas umum, cuma tak mau belepotan
tahi anak tetangga.
Tak jauh dari rumah kakek saya, sepanjang jalan utama kampung, ada selokan
mati selebar lima meter. Airnya meluap saban hujan deras. Kalau cuaca cerah
dan hari sudah malam, kadang ada orang dewasa berjongkok di atas pipa besar
yang melintang di atasnya—tentu buat berak juga.
Kata ibu saya, dia pernah tercebur ke selokan itu saat belajar mengendarai
sepeda.
Di Yogyakarta, saya dan dua kawan baik tinggal di tepi Kali Winongo, Kricak Lor,
selama setahun. Menurut kami rumah itu bagus dan sewanya terjangkau.
Meskipun beberapa teman asli Yogya mengingatkan supaya kami selalu
waspada (“Banyak gentho dan maling,” kata salah seorang di antara mereka),
saya pikir kehidupan di Kricak wajar-wajar saja.
Sesekali memang saya terbangun tengah malam, dikejutkan oleh bunyi slopok-
slopok dari rumah tetangga, lalu memindahkan bantak ke ujung lain kasur sambil
menggerutu. Tapi itu bukan masalah. Pengalaman paling menjengkelkan buat
saya justru datang dari luar kampung: suatu hari rumah kami disemprot racun
serangga pagi-pagi, tanpa pemberitahuan, atas nama pemberantasan demam
berdarah.
Kota yang saya tempati selama hampir enam tahun belakangan, Jakarta, jelas
menyembunyikan banyak sekali kampung kota di belakang jalan-jalan besar,
pencakar langit, dan pusat-pusat perbelanjaannya. Menurut catatan Badan
Pertanahan Nasional dan Bank Dunia, hampir 49% wilayah Jakarta, 118 dari 267
kelurahannya, memiliki pemukiman kumuh, termasuk Kelurahan Bangka tempat
saya tinggal dan bekerja sekarang.
Namun, terus terang saja, saya tak pernah memikirkan perkara tersebut hingga
setahun terakhir. Saya bahkan tak mengingat-ngingat Kampung Katak sejak
kakek saya wafat, dan baru tadi malam mengetahui Kricak masuk daftar prioritas
program pengentasan kekumuhan. Dengan kata lain, terlepas dari kedekatan
fisik yang pernah dan sedang saya alami dengan kampung-kampung kota
beserta para penghuninya, pikiran saya selalu berjarak dari mereka.
Dan jarak itu pernah mengelabui pikiran saya.
Pada 2017, ketika jaringan pendukung salah satu pasangan calon gubernur
Jakarta mengeksploitasi kecemasan dan penderitaan orang-orang di
perkampungan kota, yang mula-mula saya lihat hanya rasisme gila-gilaan.
Maka berbuih-buihlah mulut saya mengucapkan kata toleransi. Mencuplik contoh
dari sana-sini, termasuk kampung halaman saya—di mana masyarakat yang
heterogen hidup secara harmonis—saya bertingkah seolah-olah paling mengerti
apa artinya menjadi beradab.
Kalau saat itu ada yang mengatakan kaum miskin kota bodoh dan gampang
dihasut, saya mengangguk. Ketika ada yang marah-marah, menuduh mereka
telah mengkhianati pemimpin serbamulia yang muncul hanya sekali dalam 348
tahun, saya jadi ikut sebal dan kecewa. Itulah pikiran yang tak adil. Bagaimana
mungkin seseorang beradab tanpa terlebih dahulu berusaha menjadi manusia
yang seadil-adilnya?
Anda mungkin juga menyukai
- Surabaya - Agam WispiDokumen10 halamanSurabaya - Agam WispiBudi SetiyonoBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi (Lokal & Nasional)Dokumen101 halamanKumpulan Puisi (Lokal & Nasional)Fadil ApriyantoBelum ada peringkat
- Annemarie SchimmelDokumen2 halamanAnnemarie SchimmelKartikaningtyas KusumastutiBelum ada peringkat
- Isi Wacana Kritis Foucaldian Terhadap HukumDokumen70 halamanIsi Wacana Kritis Foucaldian Terhadap HukumbumdesaguyubrukunlpkBelum ada peringkat
- Alih Aksara Hikayat Abdullah - Yuke Alfi - 1185020141Dokumen40 halamanAlih Aksara Hikayat Abdullah - Yuke Alfi - 1185020141AfraBelum ada peringkat
- UntitledDokumen34 halamanUntitledIqbal PutraBelum ada peringkat
- Sastra Melayu Riau, Yang Kuno Dan Yang KiniDokumen114 halamanSastra Melayu Riau, Yang Kuno Dan Yang KiniJOHN KEVIN APUTRA LANGURBelum ada peringkat
- BM Part 2Dokumen74 halamanBM Part 2Abdul Rahman AsrulBelum ada peringkat
- Senikini#17Dokumen40 halamanSenikini#17senikiniBelum ada peringkat
- Buku Masyarakat Dan Kesenian IndonesiaDokumen225 halamanBuku Masyarakat Dan Kesenian IndonesiaAbanNk DanNyBelum ada peringkat
- Serat Centhini-1 PDFDokumen8 halamanSerat Centhini-1 PDFAnlisa LailanBelum ada peringkat
- A.latiff MohidinDokumen6 halamanA.latiff MohidinSyue HadaBelum ada peringkat
- Bahasa IndonesiaDokumen21 halamanBahasa IndonesiaIsnadiarBelum ada peringkat
- Kritik Sastra Dalam Minggu Pagi, Masa Kini, Dan SemangatDokumen107 halamanKritik Sastra Dalam Minggu Pagi, Masa Kini, Dan SemangatTirto SuwondoBelum ada peringkat
- Hamka Pokok-Pokok Kepertjajaan Islam - 001Dokumen70 halamanHamka Pokok-Pokok Kepertjajaan Islam - 001BUDI SAPUTRABelum ada peringkat
- Tintabahasasiri3 EbookDokumen196 halamanTintabahasasiri3 EbookKang SolBelum ada peringkat
- Dialektologi Sebuah PengantarDokumen77 halamanDialektologi Sebuah PengantarSatriani BgaBelum ada peringkat
- Daeng Kanduruan Ardiwinata Sastrawan Sunda (1979) PDFDokumen123 halamanDaeng Kanduruan Ardiwinata Sastrawan Sunda (1979) PDF022 Najla Afifah NailaBelum ada peringkat
- Adoc - Pub Cerita Pendek IndonesiaDokumen90 halamanAdoc - Pub Cerita Pendek IndonesiaFebbyBelum ada peringkat
- Yuhana Sastrawan Sunda (1979)Dokumen97 halamanYuhana Sastrawan Sunda (1979)Louie BuanaBelum ada peringkat
- MEMENTO Buku Puisi Arif Bagus PrasetyoDokumen63 halamanMEMENTO Buku Puisi Arif Bagus PrasetyoHesti DamaraBelum ada peringkat
- Sastra Keagamaan Dalam Perkembangan Sastra Indonesia Puisi 1946-1965Dokumen146 halamanSastra Keagamaan Dalam Perkembangan Sastra Indonesia Puisi 1946-1965Meri Az-zahraBelum ada peringkat
- Pengantar Dan Metode Penelitian Budaya Indra TjahyadiDokumen172 halamanPengantar Dan Metode Penelitian Budaya Indra TjahyadiMuhammad TuwahBelum ada peringkat
- 10 11 PBDokumen100 halaman10 11 PBAsra TillahBelum ada peringkat
- Terombang AmbingDokumen137 halamanTerombang AmbingAstar SiregarBelum ada peringkat
- Ebook Agama Seni Dan Budaya IndonesiaDokumen410 halamanEbook Agama Seni Dan Budaya IndonesiaNathan NathanBelum ada peringkat
- Abdul Hadi - 1911008014 - Dramaturgi LLLDokumen4 halamanAbdul Hadi - 1911008014 - Dramaturgi LLLJansen GoldyBelum ada peringkat
- Ironi Rasionalitas Dan ModernitasDokumen6 halamanIroni Rasionalitas Dan ModernitasRalip AlipuBelum ada peringkat
- Opini. Matinya Kertas, Matinya Kepakaran. Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus. FPPsi UMDokumen3 halamanOpini. Matinya Kertas, Matinya Kepakaran. Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus. FPPsi UMMuhammad Iqbal Fakhrul FirdausBelum ada peringkat
- Gede PramaDokumen65 halamanGede PramaTri Yulianto100% (1)
- 2 B.indonesia Kelas 10Dokumen50 halaman2 B.indonesia Kelas 10Chichi FauziyahBelum ada peringkat
- Dunia Yang MembosankanDokumen100 halamanDunia Yang MembosankanReva WiratamaBelum ada peringkat
- Umberto Eco Dan Iman Oleh Goenawan MohamadDokumen11 halamanUmberto Eco Dan Iman Oleh Goenawan MohamadNasruddin HamidBelum ada peringkat
- Alber Camus - The FallDokumen202 halamanAlber Camus - The FallSauqi Dzikri86% (7)
- Pendapat 2016Dokumen339 halamanPendapat 2016ekho109Belum ada peringkat
- FrankensteinDokumen13 halamanFrankensteinAnisa KhoiriyaniBelum ada peringkat
- Resensi NovelDokumen23 halamanResensi NovelSmagz Majalah Anak LembangBelum ada peringkat
- Makalah Novel SejarahDokumen11 halamanMakalah Novel Sejarahsjnetclient90% (20)
- FILSAFAT SEBAGAI PELIPUR LARA The Consolations of PhilosophyDokumen4 halamanFILSAFAT SEBAGAI PELIPUR LARA The Consolations of PhilosophyithakBelum ada peringkat
- Bin To Bimbel 2Dokumen12 halamanBin To Bimbel 2dimas aweBelum ada peringkat
- Resensi NovelDokumen4 halamanResensi NovelGeorge SimanjuntakBelum ada peringkat
- 1 Pramoedyaanantatoer BoemimaneosiaDokumen5 halaman1 Pramoedyaanantatoer Boemimaneosiaabcde12345Belum ada peringkat
- The OthersDokumen95 halamanThe OthersMyRepublic BobbyBelum ada peringkat
- Novel EdensorDokumen2 halamanNovel EdensorDilla ElysBelum ada peringkat
- Bab 4 Mengasihi Dan Menghasilkan PerubahanDokumen10 halamanBab 4 Mengasihi Dan Menghasilkan PerubahanCicilia NonieBelum ada peringkat
- 901 AlbertcamusDokumen385 halaman901 AlbertcamusosternpriyambodoBelum ada peringkat
- Yennie Hardiwidjaja - Hantu Jeruk Purut (Bag 01)Dokumen43 halamanYennie Hardiwidjaja - Hantu Jeruk Purut (Bag 01)iqbalsyariefBelum ada peringkat
- Leila Chudori - Malam TerakhirDokumen132 halamanLeila Chudori - Malam TerakhiramelBelum ada peringkat
- Bind Tgs TeksDokumen3 halamanBind Tgs TeksAl Fatih wahyu BasalamahBelum ada peringkat
- Hayalan Di Warung KopiDokumen4 halamanHayalan Di Warung KopiKonstantinus MokoBelum ada peringkat
- Kelas 12Dokumen6 halamanKelas 12Anggi purnama0% (1)
- Babebo Zine #1Dokumen32 halamanBabebo Zine #1Dieqy Hasbi WidhanaBelum ada peringkat
- Euforia Merah Saga ApriliyantinoDokumen155 halamanEuforia Merah Saga ApriliyantinoJonizarBelum ada peringkat
- Achdiat K. Mihardja - Atheis @PenalaranITSDokumen575 halamanAchdiat K. Mihardja - Atheis @PenalaranITSrisnakhoerunnisa12gBelum ada peringkat
- Angka TanDokumen5 halamanAngka TanYudha Nugraha PrakosaBelum ada peringkat
- Soal Asesmen B.Indo TP 2023-2024Dokumen10 halamanSoal Asesmen B.Indo TP 2023-2024ppg.litasarisaputri99328Belum ada peringkat
- God Delusion Bahasa Indonesia PDFDokumen3 halamanGod Delusion Bahasa Indonesia PDFLeeBelum ada peringkat
- Di Bawah Bayang-Bayang Kapitalisme Global PDFDokumen38 halamanDi Bawah Bayang-Bayang Kapitalisme Global PDFIga AbdillahBelum ada peringkat
- Soal BHS - Indonesia DinasDokumen13 halamanSoal BHS - Indonesia DinasregyanaBelum ada peringkat
- No Game No Life Volume 1 Bahasa Indonesia Upload by IsekaipantsuDokumen324 halamanNo Game No Life Volume 1 Bahasa Indonesia Upload by Isekaipantsuisekaipantsu100% (6)