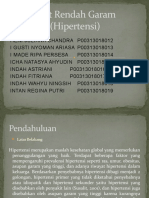Gout 8 PDF
Gout 8 PDF
Diunggah oleh
Jessica Adhyka0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
20 tayangan5 halamanJudul Asli
Gout 8.pdf
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
20 tayangan5 halamanGout 8 PDF
Gout 8 PDF
Diunggah oleh
Jessica AdhykaHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Artritis gout merupakan suatu penyakit peradangan pada persendian yang
dapat diakibatkan oleh gangguan metabolisme (peningkatan produksi) maupun
gangguan ekskresi dari asam urat yang merupakan produk akhir dari metabolisme
purin, sehingga terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darah. Peningkatan
kadar asam urat dalam darah disebut hiperurisemia (Mandell, 2008). Acuan untuk
menyatakan keadaan hiperurisemia adalah kadar asam urat >7 mg% pada laki -
laki dan >5,6 mg% pada perempuan (Longo, 2008). Asam urat akan terakumulasi
pada persendian dan jaringan lunak, sehingga akan terjadi hipersaturasi asam urat
dan terjadi kristalisasi asam urat menjadi kristal monosodium urat (Cecil
Medicine, 2012).
Prevalensi artritis gout di dunia berkisar 1 - 2% dan mengalami peningkatan
dua kali lipat dibandingkan dua dekade sebelumnya (Hamijoyo,Perhimpunan
Reumatologi Indonesia, 2010). Artritis gout merupakan penyakit peradangan
sendi ke-3 yang paling sering terjadi pada golongan usia lanjut yaitu sekitar 6 - 7
% di Indonesia (Muchid, 2006).
Data dari poli reumatologi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung selama
Januari - Desember 2010, menunjukan kurang lebih sekitar 3,3% mengalami nyeri
sendi disebabkan oleh peningkatan kadar asam urat atau dikenal sebagai artritis
gout (Hamijoyo, 2010). Di Indonesia prevalensi artritis gout belum diketahui
secara pasti dan cukup bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain.
Sebuah penelitian di Jawa Tengah mendapatkan prevalensi artritis gout sebesar
1,7% sementara di Bali didapatkan prevalensi hiperurisemia mencapai 8,5%
(Hamijoyo, 2010).
Pada satu studi serangan berulang terjadi pada 62% pasien dalam 1 tahun, dan
78% dalam 2 tahun, serta 84% pada tahun ke empat (Underwood, 2006).
Universitas Kristen Maranatha
Penderita paling banyak pada golongan usia 30 - 50 tahun yang tergolong usia
produktif (Diah Krisnatuti & Rina, 2006). Berdasarkan jurnal penelitian Best
Practice & Research Clinical Rheumatology pada tahun 2010, terhadap 4683
orang dewasa menunjukkan bahwa angka prevalensi gout dan hiperurisemia di
Indonesia pada pria adalah masing-masing 1,7 dan 24,3% (E.U.R Smith, 2010).
Prevalensi Gout di kota Semarang mencapai 165,375 penderita, pada penderita
laki-laki lebih banyak dibandingkan pada penderita perempuan dengan proposi
puncaknya pada usia 50 tahun (Susenas, 2010).
Artritis gout bila berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan
komplikasi deformitas pada sendi yang terkena artritis gout. Melihat cukup
banyaknya angka kejadian dan angka kekambuhan serta komplikasi artritis gout
yang mungkin terjadi maka saya merasa tertarik dan perlu untuk mengetahui
gambaran penderia artritis gout.
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan identifikasi masalah
penelitian sebagai berikut :
1. Berapa jumlah kasus penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di Rumah
Sakit Immanuel Bandung periode 2012 – 2014.
2. Bagaimana gambaran penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Immanuel Bandung berdasarkan usia.
3. Bagaimana gambaran penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Immanuel Bandung berdasarkan jenis kelamin.
4. Bagaimana gambaran penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Immanuel Bandung berdasarkan kekambuhan (Kedatangan
Kembali ke Rumah Sakit).
5. Bagaimana gambaran penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Immanuel Bandung berdasarkan keluhan utama.
Universitas Kristen Maranatha
6. Bagaimana gambaran penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Immanuel Bandung berdasarkan ada tidaknya podagra dan
tofus.
7. Bagaimana gambaran penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Immanuel Bandung berdasarkan kadar asam urat darah.
8. Bagaimana gambaran penderita artritis gout pada pasien rawat jalan di
Rumah Sakit Immanuel Bandung berdasarkan cara penatalaksanaan.
1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui gambaran penderita artritis gout berdasarkan usia, jenis
kelamin, kekambuhan (kedatangan kembali ke Rumah Sakit), manifestasi klinik,
ada tidaknya podagra, ada tidaknya tofus, kadar asam urat darah, dan cara
penatalaksanaan di Rumah Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2012 - 31
Desember 2014.
1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah
1.4.1 Manfaat Akademis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar hasil yang didapat dapat
dijadikan acuan informasi mengenai gambaran penderita artritis gout di Rumah
Sakit Immanuel Bandung periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2014.
1.4.2 Manfaat Praktis
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi dan menambah
wawasan yang lebih luas bagi masyarakat maupun petugas medis mengenai
penyakit artritis gout.
1.5 Landasan Teori
Artritis gout dapat disebabkan oleh peningkatan produksi metabolisme asam
urat dan kurangnya ekskresi dari asam urat yang merupakan produk akhir dari
Universitas Kristen Maranatha
metabolisme purin, sehingga terjadi peningkatan kadar asam urat dalam darah.
Peningkatan kadar asam urat dalam darah disebut hiperurisemia, pada laki - laki
>7 mg% dan pada perempuan > 5,6 mg%. Peningkatan kadar asam urat darah
dapat menyebabkan suasana jenuh pada tempat terjadinya akumulasi dari asam
urat tersebut, sehingga terjadi hipersaturasi asam urat yaitu pada kondisi kadar
asam urat darah 6,8 mg/dL (408 µmol/L) dengan pH 7,40 dan suhu tubuh normal
yang berakibat terbentuknya kristal monosodium urat (Longo, 2008).
Kristal monosodium urat telah terbentuk sebelum timbulnya gejala klinik dari
artritis gout. Kristal monosodium urat terbentuk dalam bentuk struktur kecil yang
disebut mikrotofi pada permukaan kartilago dan lapisan synovial. Pada keadaan
yang berlangsung lama dengan kondisi yang mendukung untuk terbentuknya
kristal monosodium urat maka kristal monosodium urat akan tertimbun.
Semakin lama penimbunan dari kristal monosodium urat, maka akan terjadi
perubahan suasana lingkungan pada persendian yang menyebabkan terpecahnya
kristal ini menjadi struktur - struktur yang lebih kecil dan akan mengaktifkan
reseptor makrofag pada persendian sehingga terjadi reaksi inflamasi pada
persendian. Dikarenakan terjadinya proses peradangan maka timbul manifestasi
klinik yaitu podagra, tofus, kemerahan, rasa nyeri sendi (monoartikular pada
serangan awal, poliartikular pada serangan berulang, panas, bengkak,
berkurangnya fungsi organ yang terkena (Goldman, 2012).
Pui et al juga menemukan bahwa estrogen berperan dalam regulasi kadar asam
urat, dimana estrogen dapat meningkatkan ekskresi asam urat melalui ginjal (Jill
McClory, 2009). Sebaliknya pada laki - laki kadar asaam urat serum tidak berbeda
secara signifikan pada usia pertengahan dan yang lebih tua (A. Elisabeth Hak,
2010). Pada laki - laki usia pertengahan gout biasa terjadi pada usia sekitar 40
tahun, dimana laki - laki pada usia ini memiliki faktor risiko seperti obese,
hipertensi, peningkatan kolesterol, dan suka meminum alkohol. Pada usia yang
lebih tua gout biasa terjadi karena penyakit ginjal (Simon, 2013).
Terapi untuk artritis gout Secara umum, inhibitor xantin oksidase diindikasikan
pada pasien dengan peningkatan produksi asam urat (overproducers), dan obat
urikosurik pada mereka dengan ekskresi urat yang rendah (underexcretors)
Universitas Kristen Maranatha
(Mutoharoh, 2012). NSAID adalah terapi utama untuk serangan akut gouty
arthritis. Mekanisme aksi NSAID menghambat enzim cyclooxygenase-1 dan 2
sehingga mengurangi pembentukan prekusor prostaglandin yang merupakan
mediator inflamasi. Mekanisme aksi dari kolkisin adalah mengurangi motilitas
leukosit sehingga mengurangi fagositosis pada sendi serta mengurangi produksi
asam laktat dengan cara mengurangi deposit kristal asam urat yang berperan
dalam respon inflamasi. Kolkisin hanya digunakan pada pasien yang mengalami
intoleransi, kontraindikasi, atau ketidakefektifan dengan NSAID (Mutoharoh,
2012).
Kortikosteroid dapat digunakan dalam terapi gout akut pada kasus resistensi
atau pada pasien yang kontraindikasi atau tidak berespon terhadap NSAID dan
kolkisin, serta pasien dengan nyeri gout yang melibatkan banyak sendi.
Mekanisme kerja kortikosteroid adalah dengan menekan migrasi leukosit PMN
dan menurunkan permeabilitas kapiler (Mutoharoh, 2012).
Universitas Kristen Maranatha
Anda mungkin juga menyukai
- Jurnal Asam UratDokumen15 halamanJurnal Asam Uratsuci wahyu bustaBelum ada peringkat
- Sumber AntioksidanDokumen5 halamanSumber AntioksidanTriastuti DarmayantiBelum ada peringkat
- LANSIADokumen64 halamanLANSIAKia AgusputraBelum ada peringkat
- Satuan Acara Penyuluhan DifteriDokumen11 halamanSatuan Acara Penyuluhan DifteriDhwwi YovanaBelum ada peringkat
- MTBS Untuk TB AnakDokumen33 halamanMTBS Untuk TB Anakamroel acehBelum ada peringkat
- Modul Home Visit PDFDokumen30 halamanModul Home Visit PDFNur khasanahBelum ada peringkat
- Proposal Karya Tulis IlmiahDokumen29 halamanProposal Karya Tulis IlmiahIndah PuspitaBelum ada peringkat
- Laporan Hasil ProgramDokumen38 halamanLaporan Hasil ProgramMathilda DerekBelum ada peringkat
- Kesehatan Gigi Ibu HamilDokumen12 halamanKesehatan Gigi Ibu HamilErfiadi Nur Fahmi0% (1)
- Dampak Narkoba Pada RemajaDokumen27 halamanDampak Narkoba Pada RemajaHerjuno DarpitoBelum ada peringkat
- BAB 1 Hipertensi WAEDokumen6 halamanBAB 1 Hipertensi WAEWae Muk MukBelum ada peringkat
- TUGAS EBM SkenarioDokumen3 halamanTUGAS EBM SkenarioSuci RahayuBelum ada peringkat
- MAKALAH Kelompok 4 HIVDokumen16 halamanMAKALAH Kelompok 4 HIVMuhammadRadhistaBelum ada peringkat
- Leaflet Hipertensi NoviDokumen2 halamanLeaflet Hipertensi NoviNovi Kemala SariBelum ada peringkat
- Kuesioner Survey Mawas Diri (SMD)Dokumen6 halamanKuesioner Survey Mawas Diri (SMD)dheaBelum ada peringkat
- Proposal VCTDokumen3 halamanProposal VCTAnggi Setia NingrumBelum ada peringkat
- Jenis ObatDokumen12 halamanJenis ObatnovitaBelum ada peringkat
- Analisis Pico ViaDokumen6 halamanAnalisis Pico ViaNawawiBelum ada peringkat
- Makalah DMDokumen19 halamanMakalah DMYori Susmitra50% (2)
- Sugar Withdrawal SyndromeDokumen20 halamanSugar Withdrawal SyndromeHenindita Anggra SwastikaBelum ada peringkat
- Gambaran Penyakit Rematik Pada LansiaDokumen99 halamanGambaran Penyakit Rematik Pada LansiaRiska HanumBelum ada peringkat
- Ketoasidosis DiabetikumDokumen24 halamanKetoasidosis DiabetikumRoehan FirdausBelum ada peringkat
- Sap DiareDokumen16 halamanSap Diaretantya putriBelum ada peringkat
- Obat DM Untuk SirosisDokumen9 halamanObat DM Untuk SirosisMuhammad NazliBelum ada peringkat
- Makalah KLB (Fix)Dokumen32 halamanMakalah KLB (Fix)Aprillia AngellinaBelum ada peringkat
- Tips Menjaga Kesehatan Di Musim PancarobaDokumen4 halamanTips Menjaga Kesehatan Di Musim Pancarobafarhan assegafBelum ada peringkat
- Lampiran 5 Dummy TabelDokumen5 halamanLampiran 5 Dummy TabelOsinBelum ada peringkat
- Maya Rahmayana 1801032074Dokumen100 halamanMaya Rahmayana 1801032074Brosch IchankBelum ada peringkat
- Sap KBDokumen12 halamanSap KBSri Widi AstutiBelum ada peringkat
- Askep KeluargaDokumen14 halamanAskep KeluargaAzrizal MrJacBelum ada peringkat
- Kuliah IDI MerokokDokumen39 halamanKuliah IDI Merokokkurniati azizaBelum ada peringkat
- Tentang RokokDokumen13 halamanTentang RokokAkbar Cilew-cilew SuKmaragaBelum ada peringkat
- Meningkatkan Mutu Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai PDCADokumen11 halamanMeningkatkan Mutu Pelayanan Bayi Baru Lahir Sesuai PDCAFitri Handayani100% (1)
- Materi Anemia Pada RemajaDokumen3 halamanMateri Anemia Pada RemajaNuri noerliana0% (1)
- Jejak Langkah Soeko Werdi Menapaki DharmaisDokumen5 halamanJejak Langkah Soeko Werdi Menapaki DharmaisDonna LaurenBelum ada peringkat
- Lpim Poli Mtbs 2022Dokumen3 halamanLpim Poli Mtbs 2022mardiyahBelum ada peringkat
- Proposal Penyuluhan HivDokumen13 halamanProposal Penyuluhan HivudhinadBelum ada peringkat
- Obesitas Pada LansiaDokumen39 halamanObesitas Pada LansiaLestari Anjani DewiBelum ada peringkat
- Askep AlzheimerDokumen33 halamanAskep AlzheimerAnti khoirunnissaBelum ada peringkat
- PKPR Power PointDokumen7 halamanPKPR Power PointDhitaBelum ada peringkat
- Buku Saku Stunting PDFDokumen36 halamanBuku Saku Stunting PDFNettyBelum ada peringkat
- Buletin Stunting 2018Dokumen73 halamanBuletin Stunting 2018Daday Rahmat HidayatBelum ada peringkat
- Anemia Pada Neonatus RevDokumen13 halamanAnemia Pada Neonatus RevhwelpBelum ada peringkat
- INSTRUMEN P3G (Lansia)Dokumen12 halamanINSTRUMEN P3G (Lansia)Vera Viviana Deo GraciaBelum ada peringkat
- Proposal Kegiatan Donor DarahDokumen2 halamanProposal Kegiatan Donor DarahRuben JupandiBelum ada peringkat
- Diet Rendah Garam (Hipertensi)Dokumen22 halamanDiet Rendah Garam (Hipertensi)Indah AstrianiBelum ada peringkat
- Sap Puskesmas KolesterolDokumen10 halamanSap Puskesmas KolesteroladeBelum ada peringkat
- Contoh PPT Proposal SkripsiDokumen14 halamanContoh PPT Proposal SkripsiAbdul Aziz RBelum ada peringkat
- Bahaya Prilaku Seks Bebas Pada RemajaDokumen26 halamanBahaya Prilaku Seks Bebas Pada Remajaazizah100% (1)
- JurnalDokumen18 halamanJurnalrambutan27Belum ada peringkat
- Kespro Dan Bahaya Seks BebasDokumen97 halamanKespro Dan Bahaya Seks BebaslordaponkBelum ada peringkat
- SkripsiDokumen23 halamanSkripsiMike FandriBelum ada peringkat
- LP Jiwa Lansia 1Dokumen10 halamanLP Jiwa Lansia 1wheikapBelum ada peringkat
- Management Diet Untuk Pasien Dengan Gagal GinjalDokumen14 halamanManagement Diet Untuk Pasien Dengan Gagal GinjalRio Jati Kusuma93% (14)
- ASKEP Syndrom NefrotikDokumen16 halamanASKEP Syndrom NefrotikNurul FauzhiyahBelum ada peringkat
- GOUTDokumen25 halamanGOUTUtami Murti PratiwiBelum ada peringkat
- USULAN TOPIK PENELITIAN (F. 01) - DikonversiDokumen2 halamanUSULAN TOPIK PENELITIAN (F. 01) - DikonversiKurniawan Dwi UtomoBelum ada peringkat
- Makalah Flat Foot Mau Di Frint LalalaDokumen30 halamanMakalah Flat Foot Mau Di Frint LalalaRirin NaibahoBelum ada peringkat
- Proposal Kti PriscillaDokumen23 halamanProposal Kti PriscillaAdi prastiyoBelum ada peringkat
- Jurnal GoutDokumen16 halamanJurnal GoutFumika VenayaBelum ada peringkat