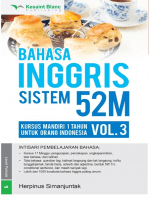Anti Toksin
Anti Toksin
Diunggah oleh
Dhanar AdhityaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Anti Toksin
Anti Toksin
Diunggah oleh
Dhanar AdhityaHak Cipta:
Format Tersedia
BAHAN AJAR
ANTINUTRISI DAN HIJAUAN PAKAN
BERACUN PADA TERNAK
PROF. DR. IR. I GST. NYM. GDE BIDURA, MS
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2017
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 i
PRAKATA
Banyak spesies tumbuhan di dunia tidak dapat dimakan karena
kandungan racun yang dikandung atau dihasilkannya. Proses domestikasi atau
pembudidayaan secara berangsur-angsur dapat menurunkan kadar zat racun
yang dikandung oleh suatu tanaman, sehingga tanaman pakan yang
dikonsumsi ternak mengandung racun dengan kadar yang jauh lebih rendah
daripada kerabatnya yang bertipe liar (wild type).
Penurunan kadar senyawa racun atau antinutrisi pada tanaman yang
telah dibudidaya, antara lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat
tumbuhnya. Karena racun yang dihasilkan oleh tanaman merupakan salah satu
cara untuk melawan predator, maka tidak mengherankan bila tanaman pakan
modern jauh lebih rentan terhadap penyakit. Beberapa kelompok racun yang
ditemukan pada tanaman yang biasa di konsumsi ternak, adalah ada beberapa
yang larut dalam lemak dan dapat bersifat bioakumulatif. Ini berarti, bila
tanaman tersebut dikonsumsi, maka racun tersebut akan tersimpan pada
jaringan tubuh, misalnya solanin pada kentang.
Dalam buku ajar ini, dikupas mengenai antinutrisi pada beberapa bahan
pakan ternak, serta senyawa-senyawa yang bersifat toksik pada hijauan
makanan ternak. Buku ajar ini akan sangat berguna dan membantu sekali
dalam pemahaman mengenai pakan ternak. Sasaran utama pengguna buku
ajar ini, adalah mahasiswa peternakan tingkat sarjana maupun pascasarjana
bidang peternakan dan yang terkait dengannya. Selain itu, buku ini juga akan
bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung atau setidaknya menaruh minat di
bidang usaha peternakan.
Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada
kepada Bapak Dekan Fakultas Peternakan, Unud, atas waktu dan dorongan
yang diberikan sehingga penyusunan buku ajar ini dapat terselesaikan.
Penerbitan buku ini pun akan sulit terwujud bila tidak ada kesempatan dan
bimbingan dari para guru besar dan teman sejawat di lingkungan Fakultas
Peternakan, Unud. Karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan
terimakasih yang tulus kepada beliau.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 ii
Akhirnya, penulis berharap semoga buku ini berguna untuk menambah
pengetahuan dan menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, dengan memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga
produktivitas ternak dapat ditingkatkan. Buku ajar yang sederhana ini, tidak
akan sempurna bila tidak ada kritik saran dari pembaca. Oleh karena itu,
segala kritik dan saran untuk kesempurnaan buku ajar ini, sangat kami
harapkan.
Denpasar, Juni 2007
Hormat kami,
Penyusun
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 iii
DAFTAR ISI
halaman
HALAMAN JUDUL ..................................................................................................... i
PRAKATA ..................................................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ........................................................................................................ vi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... vii
I. PENDAHULUAN .......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1
1.2 Prospek Masa Depan .................................................................... 2
1.3 Kerja dan Efek Toksik .................................................................... 3
II. RACUN ALAMI PADA TANAMAN PANGAN DAN PENCEGAHAN 6
KERACUNANNYA ...............................................................................
2.1 2.1 Kacang merah (Phaseolus vulgaris) ...................................... 6
2.2 2.2 Singkong ................................................................................ 6
2.3 2.3 Pucuk bambu (rebung) ........................................................... 7
2.4 2.4 Biji buah-buahan .................................................................... 7
2.5 2.5 Kentang .................................................................................. 7
2.6 2.6. Tomat Hijau ........................................................................... 8
2.7 2.7. Parsnip (semacam wortel) ..................................................... 8
2.8 2.8. Seledri .................................................................................. 8
2.9 2.9. Zucchini (semacam ketimun) ................................................ 9
2.10 2.10. Bayam ................................................................................. 9
III. TOKSIKOLOGI TUMBUHAN .............................................................. 11
3.1 Senyawa Racun pada Tanaman ................................................... 11
3.2 Absorpsi Tokson ............................................................................ 12
3.3 Mekanisme Kerja Efek Toksik ....................................................... 15
IV FAKTOR YANG PENENTU RESIKO TOKSISITAS ............................ 18
4.1 4.1 Faktor Penentu Resiko pada Fase Eksposisi .......................... 18
4.1.1. Dosis ................................................................................... 18
4.1.2. Dosis .................................................................................. 18
4.1.3. Dosis .................................................................................. 18
4.1.3. Keadaan Fungsi Organ yang Kontak .................................. 19
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 iv
4.2 4.2 Metabolisme ............................................................................ 19
4.3 Toksin Alami ............................................................................ 21
V. TOKSIKOLOGI DAN FAKTOR PENENTU TOKSISITAS .................. 23
5.1 Efek Toksik ................................................................................... 23
5.2 Hubungan Dosis-Respon ............................................................. 24
5.2.1. Frekuensi Respon Kumulatif .............................................. 24
5.2.2. Konsep statistika dan besaran aktivitas 50% ...................... 25
VI ZAT ANTI NUTRISI ............................................................................... 29
6.1 Zat Antinutrisi ................................................................................. 29
6.2 Berbagai Antinutrisi dalam Bahan Pakan ..................................... 29
6.3 Leguminosa ................................................................................... 30
6.4 Singkong (Ubi Kayu) ..................................................................... 32
6.5 Biji Kapas ..................................................................................... 33
6.6 Senyawa Racun Alkaloid .............................................................. 34
VII SENYAWA RACUN PROTEIN DAN ASAM AMINO ........................... 46
7.1 Antitripsin ...................................................................................... 46
7.2 Papain .......................................................................................... 47
7.3 Lectin (Hemaglutinin) .................................................................... 49
7.4 Mimosin ......................................................................................... 50
7.5 Latirogen ....................................................................................... 50
7.6 Linatin, Indospecine dan Canavanin ............................................. 51
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................. 53
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 v
DAFTAR TABEL
No teks halaman
2.1 Contoh racun yang terkandung pada tanaman pangan dan gejala 9
keracunannya .....................................................................................
5.1 Kriteria Ketoksikan akut xenobiotika ................................................... 27
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 vi
DAFTAR GAMBAR
No teks halaman
3.1 Pembentukan emulsi oleh senyawa aktif permukaan ”surfaktan” (a) 12
emulsi minyak dalam air dengan perantara surfaktan, zat lipofil
(misal Vit A /lingkaran hitam) larut dalam bagian lipofil dari surfaktan,
dengan cara ini zat yang mudah disolubilisasi di dalam air; (b)
Emulsi air-minyak tetesan air terperangkap dalam emulgator
surfaktan dan terdispersikan di dalam minyak (Ariens et al., 1985) ..
3.2 Difusi bentuk non-ion senyawa asam dan basa melalui membran 16
biologic ................................................................................................
4.1 Diagram sistematis membran biologi. Bulatan menggambarkan 19
kelompok kepala lipid (fosfatidilkolin), dan baris zig-zag
menunjukkan bagian ekornya. Bulatan hitam, putih, dan berbintil
menunjukkan jenis lipid yang berbeda. Benda-benda besar
menggabarkan protein, yang sebagian terletak di permukaan, dan
sebagian lain di dalam membran. .......................................................
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 vii
1
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengetahuan tentang kandungan antinutrisi dalam berbagai bahan
pakan perlu perlu dimiliki oleh formulator pakan, termasuk para peternak yang
mencampur pakan sendiri. Langkah ini sangat penting sebagai strategi untuk
meminimalkan pengaruh-pengaruh yang merugikan dari antinutrisi. Telah
dikembangkan metode-metode prosesing, baik secara fisik, mekanik maupun
kimiawi yang mungkin dapat diterapkan guna memerangi dan menghilangkan
antinutrisi dalam bahan pakan.
Toksikologi dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan
mekanisme efek berbahaya (efek toksik) berbagai bahan kimia terhadap
makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Ia dapat juga membahas penilaian
kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut sehubungan dengan
terpejannya (exposed) makhluk tadi. Toksikologi dapat didefinisikan sebagai
kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya (efek toksik) berbagai
bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya.
Apabila zat kimia dikatakan beracun (toksik), maka kebanyakan diartikan
sebagai zat yang berpotensial memberikan efek berbahaya terhadap
mekanisme biologi tertentu pada suatu organisme. Sifat toksik dari suatu
senyawa ditentukan oleh: dosis, konsentrasi racun di reseptor “tempat kerja”,
sifat zat tersebut, kondisi bioorganisme atau sistem bioorganisme, paparan
terhadap organisme dan bentuk efek yang ditimbulkan. Sehingga apabila
menggunakan istilahtoksik atautoksisitas, maka perlu untuk mengidentifikasi
mekanisme biologi di mana efek berbahaya itu timbul. Sedangkan toksisitas
merupakan sifat relatif dari suatu zat kimia, dalam kemampuannya
menimbulkan efek berbahaya atau penyimpangan mekanisme biologi pada
suatu organisme.
Aplikasinya toksikologi dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yakni:
toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi dan toksikologi forensic. Toksikologi
lingkungan lebih memfokuskan telaah racun pada lingkungan, seperti
pencemaran lingkungan, dampak negatif dari akumulasi residu senyawa kimia
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 1
2
pada lingkungan, kesehatan lingkungan kerja. Toksikologi ekonomi membahas
segi manfaat dan nilai ekonomis dari xenobiotika. Tosikologi forensik
menekunkan diri pada aplikasi ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan.
Kerja utama dari toksikologi forensik adalah analisis racun baik kualitatif
maupun kuantitatif sebagai bukti dalam tindak kriminal (forensik) di pengadilan.
1.2. Prospek Masa Depan
Kemajuan di bidang bioteknologi pertanian, telah terbukti memberikan
bebagai kemajuan jika dibandingkan pertanian konvensional. Melalui rekayasa
genetika pada tanaman pertanian telah terbukti diperoleh bibit unggul, yang
dibandingkan dengan pertanian konvensional sangat sedikit membutuhkan
tanah, merupakan andalan dalam meningkatkan pasokan makanan kita.
Keamanan makanan semacam ini membutuhkan evaluasi keamanan yang
memadai.
Bersama dengan ilmu-ilmu lain, toksikologi dapat menyediakan bahan
kimia alternatif yang lebih aman untuk pertanian, industri, dan kebutuhan
konsumen melalui penentuan hubungan strukturtoksisitas. Pengurangan sifat
toksik mungkin dapat dicapai dengan mengubah toksisitas sasaran atau
dengan mengubah sifat toksokinetiknya. Toksikologi juga berperan dalam
pengembangan obat baru, sudah menjadi prasat dalam pengembangan obat
baru harus dibarengi baik uji toksisitas akut maupun toksisitas krinis, dengan
persyaratan uji yang ketat. Penilaian tentang keamanannya merupakan
tantangan dan tunggung jawab toksikologi.
1.3 Kerja dan Efek Toksik
Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan
proses fisika, biokimia, dan biologik yang sangat rumit dan komplek. Proses ini
umumnya dikelompokkan ke dalam tiga fase yaitu: fase eksposisi, toksokinetik
dan fase toksodinamik. Dalam menelaah interaksi xenobiotika/tokson dengan
organisme hidup terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu: kerja
xenobiotika pada organisme dan pengaruh organisme terhadap xenobiotika.
Yang dimaksud dengan kerja tokson pada organisme adalah sebagai suatu
senyawa kimia yang aktif secara biologik pada organisme tersebut (aspek
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 2
3
toksodinamik). Sedangkan reaksi organism terhadap xenobiotika/tokson
umumnya dikenal dengan fase toksokinetik.
Fase eksposisi merupakan kontak suatu organisme dengan
xenobiotika, pada umumnya, kecuali radioaktif, hanya dapat terjadi efek
toksik/farmakologi setelah xenobiotika terabsorpsi. Umumnya hanya
tokson yang berada dalam bentuk terlarut, terdispersi molekular dapat
terabsorpsi menuju sistem sistemik. Dalam konstek pembahasan efek
obat, fase ini umumnya dikenal dengan fase farmaseutika. Fase
farmaseutika meliputi hancurnya bentuk sediaan obat, kemudian zat aktif
melarut, terdispersi molekular di tempat kontaknya. Sehingga zat aktif
berada dalam keadaan siap terabsorpsi menuju sistem sistemik. Fase ini
sangat ditentukan oleh faktor-faktor farmseutika dari sediaan farmasi.
Fase toksikinetik disebut juga dengan fase farmakokinetik. Setelah
xenobiotika berada dalam ketersediaan farmasetika, pada mana
keadaan xenobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau
pembuluh limfe, maka xenobiotika tersebut akan bersama aliran darah
atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik
(reseptor). Pada saat yang bersamaan sebagian molekul xenobitika akan
termetabolisme, atau tereksresi bersama urin melalui ginjal, melalui
empedu menuju saluran cerna, atau sistem eksresi lainnya.
Fase toksodinamik adalah interaksi antara tokson dengan reseptor
(tempat kerja toksik) dan juga proses-proses yang terkait dimana pada
akhirnya muncul efek toksik/farmakologik. Interaksi tokson-reseptor
umumnya merupakan interaksi yang bolak-balik (reversibel). Hal ini
mengakibatkan perubahan fungsional, yang lazim hilang, bila xenobiotika
tereliminasi dari tempat kerjanya (reseptor).
Efek toksik/farmakologik suatu xenobiotika tidak hanya ditentukan oleh
sifat toksokinetik xenobiotika, akan tetapi juga tergantung kepada faktor yang
lain seperti:
bentuk farmasetika dan bahan tambahan yang digunakan,
jenis dan tempat eksposisi,
keterabsorpsian dan kecepatan absorpsi,
distribusi xenobiotika dalam organisme,
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 3
4
ikatan dan lokalisasi dalam jaringan,
biotransformasi (proses metabolisme), dan
keterekskresian dan kecepatan ekskresi, dimana semua faktor di atas
dapat dirangkum ke dalam parameter farmaseutika dan toksokinetika
(farmakokinetika).
Selain interaksi reversibel, terkadang terjadi pula interaksi tak bolak-balik
(irreversibel) antara xenobiotika dengan subtrat biologik. Interaksi ini didasari
oleh interaksi kimia antara xenobiotika dengan subtrat biologi dimana terjadi
ikatan kimia kovalen yang bersbersifat irreversibel atau berdasarkan perubahan
kimia dari subtrat biologi akibat dari suatu perubaran kimia dari xenobiotika,
seperti pembentukan peroksida. Terbentuknya peroksida ini mengakibatkan
luka kimia pada substrat biologi.
Eksposisi (pemejanan) yang palung mudah dan paling lazim terhadap
manusia atau hewan dengan segala xenobiotika, seperti misalnya kosmetik,
produk rumah tangga, obat topikal, cemaran lingkungan, atau cemaran industri
di tempat kerja, ialah pemejanan sengaja atau tidak sengaja pada kulit. Kulit
terdiri atas epidermis (bagian paling luar) dan dermis, yang terletak di atas
jaringan subkutan. Tebal lapisan epidermis adalah relative tipis, yaitu rata-rata
sekitar 0,1-0,2 mm, sedangkan dermis sekitar 2 mm. Dua lapisan ini dipisahkan
oleh suatu membran basal.
Lapisan epidermis terdiri atas lapisan sel basal (stratum germinativum),
yang memberikan sel baru bagi lapisan yang lebih luar. Sel baru ini menjadi sel
duri (stratum spinosum) dan, natinya menjadi sel granuler (stratum
granulosum). Selain itu sel ini juga menghasilkan keratohidrin yang nantinya
menjadi keratin dalam stratum corneum terluar, yakni lapisan tanduk. Epidermis
juga mengandung melanosit yang mengasilkan pigmen dan juga sel langerhans
yang bertindak sebagai makrofag dan limfosit. Dua sel ini belakangan diketahui
yang terlibat dalam berbagai respon imun.
Dermis terutama terdiri atas kolagen dan elastin yang merupakan
struktur penting untuk mengokong kulit. Dalam lapisan ini ada beberapa jenis
sel, yang paling banyak adalah fibroblast,yang terlibat dalam biosintesis protein
berserat, dan zat-zat dasar, misalnya asam hialuronat, kondroitin sulfat, dan
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 4
5
mukopolisakarida. Disamping sel-sel tersebut, terdapat juga sel lainnya antara
lain sel lemak, makrofag, histosit, dan mastosit. Di bawah dermis terdapat
jaringan subkutan. Selain itu, ada beberapa struktur lain misalnya folikel
rambut, kelenjar keringan, kelenjar sebasea, kapiler pembuluh darah dan unsur
syaraf. Pejanan kulit terhadap tokson sering mengakibatkan berbagai lesi
(luka), namun tidak jarang tokson dapat juga terabsorpsi dari permukaan kulit
menuju sistem sistemik.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 5
6
BAB II.
RACUN ALAMI PADA TANAMAN PANGAN DAN PENCEGAHAN
KERACUNANNYA
2.1 Kacang merah (Phaseolus vulgaris)
Racun alami yang dikandung oleh kacang merah disebut dengan
fitohemaglutinin (phytohaemagglutinin), yang termasuk golongan lektin.
Keracunan makanan oleh racun ini biasanya disebabkan karena konsumsi
kacang merah dalam keadaan mentah atau yang dimasak kurang sempurna.
Gejala keracunan yang ditimbulkan antara lain adalah mual, muntah, dan nyeri
perut yang diikuti oleh diare. Telah dilaporkan bahwa pemasakan yang kurang
sempurna dapat meningkatkan toksisitas sehingga jenis pangan ini menjadi
lebih toksik daripada jika dimakan mentah. Untuk mengurangi kemungkinan
terjadinya keracunan akibat konsumsi kacang merah, sebaiknya kacang merah
mentah direndam dalam air bersih selama minimal 5 jam, air rendamannya
dibuang, lalu direbus dalam air bersih sampai mendidih selama 10 menit, lalu
didiamkan selama 45-60 menit sampai teksturnya lembut.
2.2 Singkong
Singkong mengandung senyawa yang berpotensi racun yaitu linamarin
dan lotaustralin. Keduanya termasuk golongan glikosida sianogenik. Linamarin
terdapat pada semua bagian tanaman, terutama terakumulasi pada akar dan
daun. Singkong dibedakan atas dua tipe, yaitu pahit dan manis. Singkong tipe
pahit mengandung kadar racun yang lebih tinggi daripada tipe manis. Jika
singkong mentah atau yang dimasak kurang sempurna dikonsumsi, maka racun
tersebut akan berubah menjadi senyawa kimia yang dinamakan hidrogen
sianida, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Singkong manis
mengandung sianida kurang dari 50 mg per kilogram, sedangkan yang pahit
mengandung sianida lebih dari 50 mg per kilogram. Meskipun sejumlah kecil
sianida masih dapat ditoleransi oleh tubuh, jumlah sianida yang masuk ke tubuh
tidak boleh melebihi 1 mg per kilogram berat badan per hari. Gejala keracunan
sianida antara lain meliputi penyempitan saluran nafas, mual, muntah, sakit
kepala, bahkan pada kasus berat dapat menimbulkan kematian. Untuk
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 6
7
mencegah keracunan singkong, sebelum dikonsumsi sebaiknya singkong dicuci
untuk menghilangkan tanah yang menempel, kulitnya dikupas, dipotong-potong,
direndam dalam air bersih yang hangat selama beberapa hari, dicuci, lalu
dimasak sempurna, baik itu dibakar atau direbus. Singkong tipe manis hanya
memerlukan pengupasan dan pemasakan untuk mengurangi kadar sianida ke
tingkat non toksik. Singkong yang umum dijual di pasaran adalah singkong tipe
manis.
2.3 Pucuk bambu (rebung)
Racun alami pada pucuk bambu termasuk dalam golongan glikosida
sianogenik. Untuk mencegah keracunan akibat mengkonsumsi pucuk bambu,
maka sebaiknya pucuk bambu yang akan dimasak terlebih dahulu dibuang
daun terluarnya, diiris tipis, lalu direbus dalam air mendidih dengan
penambahan sedikit garam selama 8-10 menit. Gejala keracunannya mirip
dengan gejala keracunan singkong, antara lain meliputi penyempitan saluran
nafas, mual, muntah, dan sakit kepala.
2.4 Biji buah-buahan
Biji buah-buahan yang mengandung racun glikosida sianogenik adalah
apel, aprikot, pir, plum, ceri, dan peach. Walaupun bijinya mengandung racun,
tetapi daging buahnya tidak beracun. Secara normal, kehadiran glikosida
sianogenik itu sendiri tidak membahayakan. Namun, ketika biji segar buah-
buahan tersebut terkunyah, maka zat tersebut dapat berubah menjadi hidrogen
sianida, yang bersifat racun. Gejala keracunannya mirip dengan gejala
keracunan singkong dan pucuk bambu. Dosis letal sianida berkisar antara 0,5-
3,0 mg per kilogram berat badan. Sebaiknya tidak dibiasakan mengkonsumsi
biji dari buah-buahan tersebut di atas. Bila anak-anak menelan sejumlah kecil
saja biji buah-buahan tersebut, maka dapat timbul gejala keracunan dan pada
sejumlah kasus dapat berakibat fatal.
2.5 Kentang
Racun alami yang dikandung oleh kentang termasuk dalam golongan
glikoalkaloid, dengan dua macam racun utamanya, yaitu solanin dan
chaconine. Biasanya racun yang dikandung oleh kentang berkadar rendah dan
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 7
8
tidak menimbulkan efek yang merugikan bagi manusia. Meskipun demikian,
kentang yang berwarna hijau, bertunas, dan secara fisik telah rusak atau
membusuk dapat mengandung kadar glikoalkaloid dalam kadar yang tinggi.
Racun tersebut terutama terdapat pada daerah yang berwarna hijau, kulit, atau
daerah di bawah kulit. Kadar glikoalkaloid yang tinggi dapat menimbulkan rasa
pahit dan gejala keracunan berupa rasa seperti terbakar di mulut, sakit perut,
mual, dan muntah. Sebaiknya kentang disimpan di tempat yang sejuk, gelap,
dan kering, serta dihindarkan dari paparan sinar matahari atau sinar lampu.
Untuk mencegah terjadinya keracunan, sebaiknya kentang dikupas kulitnya dan
dimasak sebelum dikonsumsi.
2.6. Tomat Hijau
Tomat mengandung racun alami yang termasuk golongan glikoalkaloid.
Racun ini menyebabkan tomat hijau berasa pahit saat dikonsumsi. Untuk
mencegah terjadinya keracunan, sebaiknya hindari mengkonsumsi tomat hijau
dan jangan pernah mengkonsumsi daun dan batang tanaman tomat.
2.7. Parsnip
Parsnip mengandung racun alami yang disebut furokumarin
(furocoumarin). Senyawa ini dihasilkan sebagai salah satu cara tanaman
mempertahankan diri dari hama serangga. Kadar racun tertinggi biasanya
terdapat pada kulit atau lapisan permukaan tanaman atau di sekitar area yang
rusak. Racun tersebut antara lain dapat menyebabkan sakit perut dan nyeri
pada kulit jika terkena sinar matahari. Kadar racun dapat berkurang karena
proses pemanggangan atau perebusan. Lebih baik bila sebelum dimasak,
parsnip dikupas terlebih dahulu.
2.8. Seledri
Seledri mengandung senyawa psoralen, yang termasuk ke dalam
golongan kumarin. Senyawa ini dapat menimbulkan sensitivitas pada kulit jika
terkena sinar matahari. Untuk menghindari efek toksik psoralen, sebaiknya
hindari terlalu banyak mengkonsumsi seledri mentah, dan akan lebih aman jika
seledri dimasak sebelum dikonsumsi karena psoralen dapat terurai melalui
proses pemasakan.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 8
9
2.9. Zucchini (semacam ketimun)
Zucchini mengandung racun alami yang disebut kukurbitasin
(cucurbitacin) dan racun ini menyebabkan zucchini berasa pahit. Namun,
zucchini yang telah dibudidayakan (bukan wild type) jarang yang berasa pahit.
Gejala keracunan zucchini meliputi muntah, kram perut, diare, dan pingsan.
Sebaiknya hindari mengkonsumsi zucchini yang berbau tajam dan berasa pahit.
2.10. Bayam
Asam oksalat secara alami terkandung dalam kebanyakan tumbuhan,
termasuk bayam. Namun, karena asam oksalat dapat mengikat nutrien yang
penting bagi tubuh, maka konsumsi makanan yang banyak mengandung asam
oksalat dalam jumlah besar dapat mengakibatkan defisiensi nutrien, terutama
kalsium. Asam oksalat merupakan asam kuat sehingga dapat mengiritasi
saluran pencernaan, terutama lambung. Asam oksalat juga berperan dalam
pembentukan batu ginjal. Untuk menghindari pengaruh buruk akibat asam
oksalat, sebaiknya kita tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung
senyawa ini terlalu banyak.
Tabel 2.1. Contoh racun yang terkandung pada tanaman pangan dan gejala
keracunannya
Racun Terdapat pada tanaman Gejala keracunan
Fitohemaglutinin Kacang merah Mual, muntah, nyeri
perut,diare.
Glikosida Singkong, rebung, biji buah- Penyempitan saluran
sianogenik buahan(apel, aprikot, nafas,mual, muntah, sakit
pir,plum, ceri, peach) kepala.
Glikoalkaloid Kentang, tomat hijau Rasa terbakar di mulut,
sakitperut, mual,muntah.
Kumarin Parsnip, seledri Sakit perut, nyeri pada kulitjika
terkena sinar matahari.
Kukurbitasin Zucchini Muntah, kram perut,
diare,pingsan.
Asam oksalat Bayam, rhubarb, teh Kram, mual, muntah, sakit
kepala.
Fitoaleksin adalah zat toksin yang dihasilkan oleh tanaman dalam jumlah
yang cukup hanya setelah dirangsang oleh berbagai mikroorganisme patogenik
atau oleh kerusakan mekanis dan kimia. Fitoaleksin dihasilkan oleh sel sehat
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 9
10
yang berdekatan dengan sel-sel rusak dan nekrotik sebagai jawaban terhadap
zat yang berdifusi dari sel yang rusak. Fitoaleksin terakumulasi mengelilingi
jaringan nekrosis yang rentan dan resisten. Ketahanan terjadi apabila satu jenis
fitoaleksin atau lebih mencapai konsentrasi yang cukup untuk mencegah
patogen berkembang
Fitoaleksin adalah zat toksin yang dihasilkan oleh tanaman dalam jumlah
yang cukup hanya setelah dirangsang oleh berbagai mikroorganisme patogenik
atau oleh kerusakan mekanis dan kimia. Fitoaleksin dihasilkan oleh sel sehat
yang berdekatan dengan sel-sel rusak dan nekrotik sebagai jawaban terhadap
zat yang berdifusi dari sel yang rusak. Fitoaleksin terakumulasi mengelilingi
jaringan nekrosis yang rentan dan resisten. Ketahanan terjadi apabila satu jenis
fitoaleksin atau lebih mencapai konsentrasi yang cukup untuk mencegah
patogen berkembang
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 10
11
BAB III.
TOKSIKOLOGI TUMBUHAN
3.1 Senyawa Racun pada Tanaman
Banyak spesies tumbuhan di dunia tidak dapat dimakan karena
kandungan racun yang dihasilkannya. Proses domestikasi atau pembudidayaan
secara berangsur-angsur dapat menurunkan kadar zat racun yang dikandung
oleh suatu tanaman, sehingga tanaman pakan yang dikonsumsi ternak
mengandung racun dengan kadar yang jauh lebih rendah daripada kerabatnya
yang bertipe liar (wild type).
Penurunan kadar senyawa racun pada tanaman yang telah dibudidaya,
antara lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat tumbuhnya. Karena
racun yang dihasilkan oleh tanaman merupakan salah satu cara untuk melawan
predator, maka tidak mengherankan bila tanaman pakan modern jauh lebih
rentan terhadap penyakit. Beberapa kelompok racun yang ditemukan pada
tanaman yang biasa di konsumsi ternak, ada beberapa yang larut lemak dan
dapat bersifat bioakumulatif. Ini berarti bila tanaman tersebut dikonsumsi, maka
racun tersebut akan tersimpan pada jaringan tubuh, misalnya solanin pada
kentang.
Kadar racun pada tanaman dapat sangat bervariasi. Hal itu dipengaruhi
antara lain oleh keadaan lingkungan tempat tanaman itu tumbuh (kekeringan,
suhu, kadar mineral, dan lain lain) serta penyakit. Varietas yang berbeda dari
spesies tanaman yang sama juga mempengaruhi kadar racun dan nutrien yang
dikandungnya.
Namun dengan demikian bukan berarti senyawa yang sangat lipofil tidak
akan terserap ke dalam tubuh. Senyawa seperti ini, misal Vitamin A atau
insektisida DTT yang praktis tidak larut dalam air, terlebih dahulu harus
diperlarutkan atau disolubilisasikan. Solubilisasi senyawa seperti ini dapat
berlangsung di usus halus, terutama dengan bantuan garam empedu.
Xenobiotika yang luar biasa lipofil dapat diabsorpsi bersama lemak (seperti
kolesterin) sebagai kilomikron ke dalam sistem limfa. Dalam hal ini juga ikut
mengambil bagian garam asam empedu yang bersifat aktif permukaan. Bagian
lipofil dari asam empedu akan berikatan dengan xenobiotika lipofil dan
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 11
12
membungkusnya, selanjutnya membentuk misel (lihat Gambar 3.1).
Permukaan ion dari garam empedu akan mengarah ke larutan hidrofil ”air”.
Dengan demikian xenobiotika ini dapat tersolubilisasi dalam lapisan air,
sehingga absorpsi pun dapat berlangsung.
Gambar 3.1. Pembentukan emulsi oleh senyawa aktif permukaan ”surfaktan”
(a) emulsi minyak dalam air dengan perantara surfaktan, zat lipofil
(misal Vit A /lingkaran hitam) larut dalam bagian lipofil dari surfaktan,
dengan cara ini zat yang mudah disolubilisasi di dalam air; (b) Emulsi
air-minyak tetesan air terperangkap dalam emulgator surfaktan dan
terdispersikan di dalam minyak (Ariens et al., 1985)
3.2 Absorpsi tokson melalui saluran pencernaan
Kebanyakan studi toksisitas suatu xenobiotika dilakukan melalui rute
oral, oleh sebab itu dalam bahasan ini absorpsi melalui saluran pencernaan
didahulukan, dan diikuti oleh rute eksposisi yang lain.
Pada umumnya produk farmaseutik mengalami absorpsi sistemik melalui
suatu rangkaian proses. Proses tersebut meliputi: (1) disintegrasi bentuk
farmaseutik yang diikuti oleh pelepasan xenobiotika, (2) pelarutan xenobiotika
dalam media ”aqueous” , (3) absorpsi melalui membrane sel menuju sirkulasi
sistemik. Dalam suatu proses kinetik, laju keseluruhan proses ditentukan oleh
tahap yang paling lambat (rate limiting step). Pada umumnya bentuk sediaan
padat, kecuali sediaan “sustained release” atau “prolongedaction”, waktu
hancur sediaan akan lebih cepat daripada pelarutan dan absorpsi obat. Untuk
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 12
13
xenobiotika yang mempunyai kelarutan kecil dalam air, laju pelarutan seringkali
merupakan tahap yang paling lambat, oleh sebab itu akan menjadi faktor
penentu kecepatan ketersediaan hayati obat. Tetapi sebaliknya, untuk
xenobiotika yang mempunyai kelarutan besar dalam air, laju pelarutannya cepat
sedangkan laju lintas xenobiotika melewati membran sel merupakan tahap
paling lambat atau merupakan tahap penentu kecepatan.
Pada pemakaian oral (misal sediaan dalam bentuk padat), maka terlebih
dahulu kapsul/tablet akan terdisintegrasi, sehingga xenobiotika akan
terdisolusi/terlarut di dalam cairan saluran pencernaan (lumen). Tokson yang
terlarut ini akan terabsorpsi secara normal dalam duodenal dari usus halus dan
ditranspor melalui pembuluh kapiler mesenterika menuju vena porta hepatica
menuju hati sebelum ke sirkulasi sistemik.
Umumnya absorpsi ditentukan oleh pH cairan lumen serta pKa dan laju
pelarutan dari suatu xenobiotika. Pariabel biologi lainnya, seperti ada tidaknya
makanan, waktu pengosongan lambung, waktu transit di saluran cerna, dan
mikro-flora usus, mungkin juga dapat mempengaruhi laju absorpsi dan jumlah
xenobiotika yang akan terabsorpsi. Telah dilaporkan bahwa, selama di dalam
saluran cerna mungkin terjadi penguraian kimia baik yang terjadi akibat proses
kimia (misalnya hidrolisis ester) atau akibat penguraian oleh mikro flora usus,
seperti reduksi senyawa azo menjadi amina aromatik yang lebih bersifat toksik
dari senyawa induknya.
Beberapa faktor yang mungkin berpengaruh pada jumlah xenobiotika
yang mampu mencapai system sirkulasi sistemik dalam bentuk bebasnya
setelah pemberian oral (ketersediaan hayati) adalah:
1. pH yang extrim, dimana mungkin berpengaruh pada stabilitas
xenobiotika. Seperti telah diketahui pH lambung adalah sangat asam dan
pH lambung bervariasi untuk spesies yang berbeda, seperti pada tikus
pH labungnya berkisar 3,8 - 5,0, dan pada kelinci berkisar 3,9.
sedangkan pH lambung manusia berkisar 1 - 2. Telah dilaporkan
terdapat beberapa senyawa obat yang stabilitasnya menurun dalam pH
asam. Sebagai contoh, obat eritromisin memiliki sifat kestabilan yang
bergantung pada pH. Dalam suatu media yang bersifat asam, seperti
cairan lambung, peruraian terjadi secara cepat, sedangkan pada pH
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 13
14
netral atau alkali eritromisin relative stabil. Sehingga obat-obat seperti itu
tidak diharapkan mengalami kontak dengan cairan asam lambung. Oleh
sebab itu pada perencanaan formulasi sediaan farmaseutika
kebanyakan obat seperti ini dibuat missal dalam bentuk tablet salut
enterik, sehingga tablet tersebut tidak akan pecah di dalam cairan
lambung melainkan di dalam usus halus.
2. Enzim-enzim hidrolisis, saluran cerna kaya terhadap berbagai enzim
hidrolisis non spesifik, seperti: enzim lipase, protease, amilase. Enzim-
enzim ini mungkin juga dapat menguraikan xenobiotika selama berada di
saluran cerna.
3. Mikroflora usus, telah dilaporkan bahwa mikroflora usus dapat
menguraikan molekul xenobiotika menjadi produk metabolik yang
mungkin tidak mempunyai aktifitas farmakologik dibandingkan dengan
senyawa induknya atau bahkan justru membentuk produk metabolik
dengan toksisitas yang lebih tinggi. Umumnya mikroflora usus hidup di
saluran pencernaan bagian bawah dan di saluran cerna bagian atas
umumnya steril karena pH lambung yang relatif asam. Namun
belakangan telah ditemukan juga bahwa terdapat mikroba yang sanggup
hidup di dalam cairan lambung, yaitu heriobakter vilori .
4. Metabolisme di dinding usus, dinding usus dengan bantuan enzim-enzim
katalisis mempunyai kemampuan untuk melakukan metabolisme (reaksi
biokimia) bagi senyawa tertentu sebelum mencapai pembuluh darah
vena hepatika. Enzim-enzim yang banyak dijumpai pada dinding saluran
cerna seperti umumnya enzim yang mengkatalisis reaksi hidrolisis dan
konjugasi (seperti reaksi kunjugasi glukuronat), reaksi monoamine
oksidase, dan beberapa enzim yang mengkatalisis reaksi oksidatif
lainnya seperti CYP3A4/5 (sitokrom3A4/5).
5. Metabolisme di hati. Setelah xenobiotika diabsorpsi dari saluran cerna
maka dari pembuluh-pembuluh kapiler darah di mikrovili usus melalui
pembuluh vena hepatika menuju hati. Hati adalah tempat utama
terjadinya reaksi meabolisme. Telah banyak dilaporkan, bahwa sebagian
dari xenobiotika telah mengalami reaksi metabolisme di hati sebelum
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 14
15
menuju tempat kerjanya atau sebelum didistribusikan ke seluruh tubuh.
Reaksi metabolisme ini dikenal dengan firstpass-effect.
6. Makanan yang terdapat di lumen saluran cerna, mungkin juga
memberikan pengaruh pada absorpsi xenobiotika dari saluran cerna,
karena jenis makanan juga mempengaruhi gerakan peristaltik usus, pH
lambung, dan waktu pengosongan lambung. Kadang kala jenis makanan
tertentu akan berinteraksi dengan xenobiotika tertentu yang
mengakibatkan gagalnya absorpsi xenobiotika tersebut. Seperti pada
pengobatan antibiotika turunan tetrasiklin dianjurkan pada saat
mengkonsumsi obat tidak berbarengan dengan makanan yang banyak
mengandung logam-logam kalsium, (seperti susu, pisang), karena
tetrasiklin dengan logam kalsium akan membentuk komplek yang
mengendap, komplek ini sangat susah diabsorpsi dari saluran cerna.
7. P-Glykoprotein, terdapat banyak pada permukaan lumen epitelium
saluran cerna. Protein ini dapat bertindak sebagai pompa pendorong
bagi beberapa xenobiotika untuk memasuki sistem sistemik.
3.3 Mekanisme Kerja Efek Toksik
Fase toksodinamik adalah interaksi antara tokson dengan reseptor
(tempat kerja toksik) dan juga proses-proses yang terkait dimana pada akhirnya
muncul efek toksik/farmakologik. Farmakolog menggolongkan efek yang
mencul berdasarkan manfaat dari efek tersebut, seperti:
1. efek terapeutis, efek hasil interaksi xenobiotika dan reseptor yang
diinginkan untuk tujuan terapeutis (keperluan pengobatan),
2. efek obat yang tidak diinginkan, yaitu semua efek / khasiat obat yang
tidak diinginkan untuk tujuan terapi yang dimaksudkan pada dosis yang
dianjurkan, dan
3. efek toksik, pengertian efek toksik sangatlah bervariasi, namun pada
umumnya dapat dimengerti sebagai suatu efek yang membahayakan
atau merugikan organisme itu sendiri.
Bila memperhatikan kerumiatan sistem biologi, baik kerumitan kimia
maupun fisika, maka jumlah mekanisme kerja yang mungkin, praktis tidak
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 15
16
terbatas, terutama sejauh ditimbulkan efek toksik. Dalam sub bahasan ini akan
dibicarakan beberapa mekanisme utama yang penting.
Gambar 3.2. Difusi bentuk non-ion senyawa asam dan basa melalui membran
biologik
Gambar 3.1 menggambarkan ilustrasi difusi senyawa asam dan basa
melintasi membrane dipengaruhi oleh ionisasi di kedua daerah membran.
Disamping faktor-faktor diatas, laju aliran darah di pembuluh-pembuluh kapiler
di tempat absorpsi juga merupakan salah satu factor berpengaruh pada laju
absorpsi suatu xenobiotika. Laju aliran darah akan berpengaruh pada
perbedaan konsentrasi xenobiotika di kedua sisi membran. Pada awal absorpsi
umumnya konsentrasi xenobiotika di tempat absorpsi jauh lebih tinggi
ketimbang di sisi dalam membrane (sebut saja dalam kapiler darah periper).
Apabila laju aliran pada pembuluh darah kapiler tersebut relatif cepat, maka
xenobiotika akan dengan cepat terbawa menuju seluruh tubuh, sehingga pada
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 16
17
tempat absorpsi, sehingga kesetimbangan konsentrasi antara tempat absorpsi
dan kapiler darah akan lebih lama tercapai dan terdapat perbedaan konsentrasi
antar dua sisi yang relative besar. Difusi akan tetap berlangsung selama
terdapat berbedaan konsentrasi antara kedua sisi membran.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 17
18
BAB IV.
FAKTOR YANG PENENTU RESIKO TOKSISITAS
4.1 Faktor Penentu Resiko pada Fase Eksposisi
Zat toksik adalah merupakan zat yang dapat menimbulkan kerja yang
merusak dan berbahaya bagi kesehatan. Zat toksik ini lebih dikenal dengan
sebutan racun. Dalam prakteknya, senyawa dikatakan sebagai racun bila
resiko yang ditimbulkan relatif besar. Ada beberapa factor yang menentukan.
Faktor-faktor tersebut akan dibahas dalam hubungannya dengan tiga fase
toksik, yaitu fase eksposisi, fase toksokinetika, dan fase toksodinamika.
4.1.1. Dosis
Semua zat adalah racun dantidak ada zat yang bukan racun; hanya
dosislah yang membuat suatu zat bukan racun. Hal ini berarti zat yang
potensial belum tentu menyebabkan keracunan. Hampir tiap individu dapat
dideteksi sejumlah tertentu zat seperti DDT dan timbal, tetapi zat-zat tersebut
tidak menimbulkan reaksi keracunan karena dosis yang ada masih berad
dibawah konsentrasi toksik. Setelah dosis berada pada dosis toksik maka zat
tersebut dapat menimbulkan kercunan. Hal yang sebaliknya, jika zat yang
digunakan dalam jumlah yang besar maka dapat menimbulkan kerusakan atau
keracunan bagi tubuh, bahkan air sekalipun. Karenanya perlunya pengetahuan
yang mendasari tentang resiko toksisitas suatu zat.
Dosis terutama ditentukan oleh konsentrasi dan lamanya ekposisi zat.
Racun pada konsentrasi yang rendah tetapi terdapat kontak yang lama dapat
menimbulkan efek Tosik yang sama dengan zat yang terpapar pada
konsentrasi tinggi dengan waktu kontak yang singkat.
4.1.2. Keadaan dan kebersihan tempat kerja dan perorangan
Hal yang penting antara lain adalah penyimpanan zat yang berbahaya
seperti zat kimia, termasuk yang digunakan dalam rumah tangga, contohnya
deterjen, kosmetika, dan obat. Zat –zat tersebut sebaiknya disimpan ditempat
yang aman dan jauh dari jangkauan anak. Karena keteledoran dalam
penyimpanan sering menimbulkan keracunan pada anak – anak. Hal yang
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 18
19
penting adalah pakaian yang tercemar dibersihkan secara teratur dan ditangani
secara terpisah dari pakaian atau benda yang lain. Higiene kerja seseorang
penting artinya terutama dalam hal pembatasan pembentukan debu atau
pemaparan zat kimia, meminimalkan kontak antara bahan berbahaya dengan
kulit, ataupun anggota tubuh yang lain. Untuk perlunya pengetahuan dan
peraturan tentang penggunaan alat-alat kerja, sarung tangan, dan lain secara
benar.
4.1.3. Keadaan Fungsi Organ yang Kontak
Keaadaan fungsi organ yang kontak dengan zat toksik akan
mempengaruhi eksposisi zat tersebut. Contohnya pada: Kulit, Absorbsi melalui
kulit dipengaruhi oleh kandungan kelembaban, peredaran darah kulit, dan
keadaan setiap lapisan kulit. Apabila lapisan permukaan kulit rusak maka fungsi
kulit sebagai barier (penghambat) terhadap zat-zat yang masuk ke tubuh
menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan zat-zat (tidak hanya yang lipofil saja
yang bisa masuk tapi juga yang hidrofil) atau bahkan bakteri dan virus akan
lebih mudah masuk.
Saluran pernapasan, Adanya Industrialisai, menyebabkan terjadi polusi
terhadap udara. Hal ini menyebabkan saluran pernapsan menjadi terpejan oleh
zat toksik yang berada pada udara. Kondisi saluran napas dan paru-paru yang
telah mengalami eksposisi sebelumnya dapat mempengaruhi keadaan organ
tersebut pada pajanan berikutnya atau pajanan yang lebih lama. Contoh:
apabila paru-paru telah terkena Arsen maka dapat terjadi iritasi local pada
organ tersebut, apabila pajanan terjadi lebih lama maka dapat menyebabkan
kanker paru-paru
Laju absorpsi suatu xenobiotika ditentukan juga oleh sifat membran
biologi dan aliran kapiler darah tempat kontak. Suatu xenobiotika, agar dapat
diserap/diabsorpsi di tempat kontak, maka harus melewati membran sel di
tempat kontak. Suatu membran sel biasanya terdiri atas lapisan biomolekular
yang dibentuk oleh molekul lipid dengan molekul protein yang tersebar
diseluruh membran (Gambar 4.1).
Jalur utama bagi penyerapan xenobiotika adalah saluran pencernaan,
paru-paru, dan kulit. Namun pada keracunan aksidential, atau penelitian
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 19
20
toksikologi, paparan xenobiotika dapat terjadi melalui jalur injeksi, seperti injeksi
intravena, intramuskular, subkutan, intraperitoneal, dan jalur injeksi lainnya.
Gambar 4.1. Diagram sistematis membran biologi. Bulatan menggambarkan
kelompok kepala lipid (fosfatidilkolin), dan baris zig-zag menunjukkan
bagian ekornya. Bulatan hitam, putih, dan berbintil menunjukkan jenis
lipid yang berbeda. Benda-benda besar menggabarkan protein, yang
sebagian terletak di permukaan, dan sebagian lain di dalam membran.
4.2 Metabolisme
Xenobiotika yang masuk ke dalam tubuh akan diperlakukan oleh sistem
enzim tubuh, sehingga senyawa tersebut akan mengalami perubahan struktur
kimia dan pada akhirnya dapat dieksresi dari dalam tubuh. Proses biokimia
yang dialami oleh ”xenobiotika” dikenal dengan reaksi biotransformasi yang
juga dikenal dengan reaksi metabolisme. Biotransformasi atau metabolism
pada umumnya berlangsung di hati dan sebagian kecil di organ-organ lain
seperti: ginjal, paru-paru, saluran pencernaan, kelenjar susu, otot, kulit atau di
darah.
Secara umum proses biotransformasi dapat dibagi menjadi dua fase,
yaitu fase I (reaksi fungsionalisasi) dan fase II (reaksi konjugasi). Dalam fase
pertama ini tokson akan mengalami pemasukan gugus fungsi baru,
pengubahan gugus fungsi yang ada atau reaksi penguraian melalui reaksi
oksidasi (dehalogenasi, dealkilasi, deaminasi, desulfurisasi, pembentukan
oksida, hidroksilasi, oksidasi alkohol dan oksidasi aldehida); rekasi reduksi
(reduksi azo, reduksi nitro reduksi aldehid atau keton) dan hidrolisis (hidrolisis
dari ester amida). Pada fase II ini tokson yang telah siap atau termetabolisme
melalui fase I akan terkopel (membentuk konjugat) atau melalui proses sintesis
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 20
21
dengan senyawa endogen tubuh, seperti: Konjugasi dengan asam glukuronida
asam amino, asam sulfat, metilasi, alkilasi, dan pembentukan asam
merkaptofurat.
Enzim-enzim yang terlibat dalam biotransformasi pada umumnya tidak
spesifik terhadap substrat. Enzim ini (seperti monooksigenase, glukuronidase)
umumnya terikat pada membran dari retikulum endoplasmik dan sebagian
terlokalisasi juga pada mitokondria, disamping itu ada bentuk terikat sebagai
enzim terlarut (seperti esterase, amidase, sulfoterase). Sistem enzim yang
terlibat pada reaksi fase I umumnya terdapat di dalam retikulum endoplasmik
halus, sedangkan system enzim yang terlibat pada reaksi fase II sebagian
besar ditemukan di sitosol. Disamping memetabolisme xenobiotika, sistem
enzim ini juga terlibat dalam reaksi biotransformasi senyawa endogen (seperti:
hormon steroid, biliribun, asam urat, dll). Selain organ-organ tubuh, bakteri flora
usus juga dapat melakukan reaksi metabolisme, khususnya reaksi reduksi dan
hidrolisis.
4.3 Toksin Alami
Berupa kelompok toksin yang secara alamiah ada dalam makanan
termasuk dalam kelompok ini adalah phenol, glikosida sianogen, glukosinolat,
inhibitor asetilcholinesterase, amina biogenik, dan stimulan sentral.
Kelompok fenol yang biasa dijumpai dalam proses produksi makanan
dan minuman kelompok ini merupakan kelompok racun yang jarang
menyebabkan keracunan akut; beberapa diantaranya adalah: asam fenolat
seperti asam kafeat, asam ferulat, asam galat, flavonoid, lignin, tanin yang
dapat terhidolisis, dan tanin terkondensasi dan turunannya. kelompok fenol
yang lebih heterogen umumnya memiliki tingkat racun yang lebih tinggi,
beberapa diantaranya adalah kumarin, safrol, miristisin, dan fenolat-fenolat
amin.
Kelompok glikosida sianogen merupakan glikosida yang mampu
menghasilkan sianida akibat proses aktifitas enzim hidrolitik. racun sianida
bersifat mematikan dengan dosis 0.5 sampai3.5 mg/kg berat badan. Bebrapa
jenis tanaman yang mengandung glikosida sianogen diantaranya adalah, ketela
pohon, sorgum, biji karet, gadung dan pucong.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 21
22
glukosinolat. hirolisis glukosinolat menghasilkan isotiosianat dan nitril. Beberapa
isotiosianat menunjukkan efek racun pada embrio tikus sedang beberapa
diantaranya menyebabkan sitotoksik dan mutagenik. glukosinolat dapat
dijumpai pada sayur-sayuran seperti kol dan brokoli.
Inhibitor asetilkolinesterase; kelompok ini diantaranya adalah kelompok
alkaloid, salah satu umbi yang cukup berpotensi menghasilkan inhibitor adalah
kentang. kentang mengandung glikoalkaloid solanin. Umbi kentang komersial
mengandung solanin 2 – 15 mg per 100 gr. Umbi kentang yang berwarna hijau
memiliki kandungan solanin yang lebih tinggi dan terkonsentrasi pada bagian
kulit yang berwarna hijau. Keracunan solanin dapat mengganggu sistem
pencernaan dan simtom syaraf.
Amino biogenik terdapat dalam beberapa tanaman tertentu seperti, buah
apokat, pisang, kurma, nanas, dan tomat. Beberapa amino biogenik yang cukup
beresiko yaitu phenethylamines, dopamine, norepinephrine, dan tyramine yang
menyebabkan hipertensi. Jenis yang terakhir adalah stimulan, termasuk
didalamnya adalah kafein teofilin dan teobromin.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 22
23
BAB V.
TOKSIKOLOGI DAN FAKTOR PENENTU TOKSISITAS
5.1 Efek Toksik
Respons biologis “efek farmakologis/toksik” ditentukan oleh afinitas
xenobiotika terhadap reseptor dan juga jumlah xenobiotika yang menduduki
reseptor (konsentrasi xenobiotika pada reseptor). Kemampuan suatu
xenobiotika untuk mencapai reseptor dan factor yang berpengaruh, telah
dibahas pada sub bahasan fase toksikenetik, ditentukan oleh beberapa faktor
seperti: sifat fisikokimia, bentuk farmaseutika, tempat kontak dan faktor
psiologik organisme. Dalam prakteknya diperlukan suatu sistem yang ideal,
yang dapat menggambarkan kekerabatan antara respon dan dosis (konsentrasi
xenobiotika), dosis dan kerja ”afinitas intrinsik”, serta hubungan antara waktu
dan kerja. Sistem ini dapat dijadikan dasar oleh seorang toksikolog dalam
menentukan ambang batas minimal konsentrasi toksikan dinyatakan berbahaya
atau oleh seorang dokter dalam memilih obat dan memberi dosis yang tepat,
guna mendapatkan suatu keputusan terapeutik yang rasional.
Bila dapat dianggap bahwa efek akhir dari suatu paparan diwujudkan
sebagai ada respon menyeluruh atau sama sekali tidak ada respon, maka
haruslah terdapat suatu kisaran konsentrasi xenobiotika yang akan memberikan
suatu respon ”efek” bertingkat pada suatu tempat diantara dua titik ekstrim
tersebut. Percobaan penetapan kisaran kadar ”dosis” ini merupakan dasar
kekerabatan atara dosis dan respon.
Dalam praktisnya, pada suatu penelitian biologis sering sekelompok
sampel, seperti sel tunggal ”bakteri”, atau sekelompok hewan percobaan, dapat
dianggap sebagai suatu populasi mekanisme biologi yang seragam, dan karena
itu mungkin dapat dipejankan dengan suatu kadar atau dosis dari xenobiotika
tertentu yang telah diseleksi secara tepat. Namun anggapan ini tidak selalu
tepat dimana perbedaan individual turut memberikan perbedaan respon pada
jumlah pejanan xenobiotika yang sama.
Bila suatu xenobiotika mampu menimbulkan efek yang dapat diamati,
seperti kematian, perubahan mekanisme biologi, maka dosis xenobiotika itu
dapat dipilih agar dapat menimbulkan efek tersebut. Dan lagi, bila efek tersebut
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 23
24
dapat dikuantitatifkan, maka percobaannya akan menunjukkan bahwa tidak
seluruh anggota kelompok memberi respon yang secara kuantitatif identik
terhadap sejumlah dosis yang sama. Kiranya beberapa hewan percobaan akan
memberikan respon yang hebat, sedangkan yang lain bahkan sama sekali tidak
menunjukkan respon. Jadi apa yang telah dianggap sebagai ”sama sekali ada
atau sama sekali tak ada respon” hanya berlaku untuk suatu anggota tunggal
dari kelompok uji tersebut, dan ternyata respons merupakan hubungan yang
benar-benar bertingkat bila dilihat dari keseluruhan kelompok hewan uji.
Dalam sub bahasan berikut ini kita akan mengulas bagaimana cara
memperoleh hubungan antara dosis-respon, dosis-kerja, dan kerja dan waktu,
serta makna dari kekerabatan tersebut dan pada akhir bagian akan diulas
faktor-faktor yang bepengaruh atau menentukan resiko dalam lingkungan zat
berbahaya.
5.2. Hubungan Dosis-Respon
Hubungan dosis-respon menggambarkan suatu distribusi frekuensi
individu yang memberikan respons pada rentang dosis tertentu (gambar 5.1).
Bila distribusi frekuensi tersebut dibuat kumulatif maka akan diperoleh kurva
berbentuk sigmoid yang umumnya disebut kurva dosis-persen responder
(gambar 5.2). Pada dasarnya kurva hubungan dosis-respon menunjukkan
variasi individual dari dosis yang diperlukan untuk minimbulkan suatu efek
tertentu.
5.2.1. Frekuensi respon - respon kumulatif
Dalam percobaan toksikologi menggunakan hewan uji, biasanya
digunakan hewan dalam satu seri anggota spesies tertentu yang dianggap
seragam bila diberikan suatu dosis xenobiotika uji guna menimbulkan suatu
respon yang identik. Data yang diperoleh dari suatu percobaan seperti itu diplot
dalam suatu bentuk kurva distribusi atau kurva frekuensi-respon.
Dimaksud respon bersifat kuantal (all or none) adalah ada atau tidak
sama sekali respon pada hewan uji. Kurva frekuensi-respon menunjukkan
bahwa persentase atau jumlah dari hewan uji yang memberikan respon secara
kuantitatif identik pada pemberian sejumlah dosis tertentu. Dari kurva tersebut
terlihat, dimana beberapa hewan akan memperlihatkan respon yang sama pada
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 24
25
dosis yang rendah sedangkan yang lainnya memerlukan dosis yang lebih tinggi.
Kurva seperti di atas, mengikuti pola distribusi Gaussian, namun berbeda dalam
praktisnya distribusi suatu frekuensi respon tidak selalu memenuhi pola
distribusi Gaussian.
Pada prakteknya baik uji toksikologi maupun farmakologi, dimana
percobaan invivo tidak semudah pada percobaan invitro. Karena secara invivo,
terdapat sejumlah reaksi umpan balik yang dapat terjadi, sebagai contoh:
misalnya zat yang bekerja mengubah tekanan darah. Dengan bertambahnya
perubahan tekanan darah maka mekanisme homeostasis juga akan mengubah
lebih banyak hubungan antara dosis dan efek. Kenaikan dosis biasanya akan
menyebabkan lebih banyak sistem organ yang dikenai dan akan memberikan
efek kerja yang jauh berbeda. Pada efek toksik akan menimbulkan kematian,
berbagai sistem organ akan banyak mengalami kegagalan satu persatu.
Sebaliknya, jumlah individu yang menunjukkan efek toksik atau efek terapetik
tergantung dari dosisnya.
Dalam toksikologi, kurva frekuensi-respon biasanya tidak dipergunakan.
Melainkan, adalah lazim mengeplot data dalam bentuk kurva yang
menghubungkan dosis suatu xenobiotika uji dengan persentase kumulatif
hewan uji yang memperlihatkan respon. Kurva semacam itu biasanya dikenal
sebagai kurva dosis-respon.
Hanya melalui suatu percobaan maka kita dapat memilih dosis dimana
seluruh hewan akan memberikan respon (misalnya mati) atau seluruh hewan uji
tidak memberikan respon. Dosis awal mungkin saja dosis yang demikian kecil
sehingga tidak ada efek ”mati” yang dapat diwujudkan oleh hewan uji. Pada
kelompok hewan berikutnya, dosisnya ditingkatkan dengan suatu perkalian
tetap, misal dua atau berdasarkan hitungan logaritma, sampai pada akhirnya
ditemukan suatu dosis yang cukup tinggi yang bila diberikan, akan mematikan
seluruh hewan dalam kelompk itu.
5.2.2. Konsep statistika dan besaran aktivitas 50%
Gambar 4.2 menjelaskan suatu konsep, dimana dosis suatu xenobiotika
mungkin cukup kecil sehingga tidak menimbulkan efek kematian, namun bila
dosis dinaikkan, hingga diperoleh suatu kurva sigmoid, sehingga pada dosis
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 25
26
yang cukup tinggi, 100% hewan uji mati sebagai akibat pemejanan xenobiotika
uji. Hubungan ini menggambarkan bahwa respon yang timbul langsung
berkaitan dengan kadar/dosis dari suatu senyawa yang ada. Sehingga tidak
dapat disangkal bahwa bahaya atau amannya suatu senyawa kimia itu
tergantung pada dosis yang diberikan.
Kurva pada gambar 4.2 menggambarkan bagaimana diperoleh suatu
dosis dimana 50% dari populasi menunjukkan respon. Dalam toksikologi,
jumlah dosis yang menyebabkan 50% individu memberikan reaksi (respon)
digunakan sebagai besaran aktivitas (seperti, ED50 = effective dose 50% atau
LD50 = lethal dose 50%) dari xenobiotika uji. Besaran aktivitas 50% adalah
suatu harga sebenarnya yang diperoleh secara statistika. Ini merupakan suatu
harga perhitungan yang menggambarkan estimasi yang paling baik dari dosis
yang diperlukan untuk menimbulkan respon pada 50% individu uji, karenanya
selalu disertai dengan suatu rataan estimasi dari harga kesalahannya, seperti
probabilitas kisaran nilainya. Terdapat beberapa metode untuk melakukan
perhitungan tersebut. Metode yang paling lazim digunakan ialah metode grafik
Litchifield dan Wilcoxon (1949), metode kertas probit logaritma dari Miller dan
Tainter (1944), dan tatacara menemukan kisaran dari Weil (1952).
Penentuan LD50 dilakukan dengan cara yang serupa, yaitu menarik
garis mendatar dari titik angka kematian 50% pada ordinat sampai titik tertentu
yang memotong kurva tersebut selanjutnya dari titik potong tersebut, ditarik
garis vertikal sehingga memotong sumbu absis. Sehubungan dengan
ketoksikan racun, bentuk kurva bagian awal kekerabatan dosis-respon lebih
relevan untuk dikaji daripada keseluruhan kurva. Hal ini berkaitan dengan nilai
ambang pemejanan racun, yaitu takaran pemejanan dimana individu tidak
menunjukkan efek atau respons toksik yang dapat terukur atau teramati.
Takaran ambang ini merupakan batas aman-ketoksikan racun, yang lazimnya
disebut Kadar Efek-toksik yang Tidak Teramati (KETT) atau no observed effect
level (NOEL).
No observed effect level (NOEL) menggambarkan takaran pemejanan
tertinggi yang tidak menyebabkan timbulnya efek toksik atau kematian pada diri
subyek uji. Nilai ambang batas ini digunakan untuk menentukan nilai batas
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 26
27
aman suatu toksikan dapat terserap oleh organisme tanpa menimmbulkan efek
toksik.
Konsep NOEL pada umumnya dapat diterima untuk sebagian besar jenis
wujud efek toksik, tetapi untuk beberapa efek toksik seperti karsinogennik yang
diperantrai oleh mekanisme genotoksik, konsep itu merupakan masalah yang
masih diberdebatkan. Dalam karsinogenesis, bila kurva takaran-respons
diekstrapolasi ke arah basis, bisanya melintas titik nol (Gambar 4.3) Artinya:
dengan teknik analisa yang ada, tidak terlihat NOEL, sehingga tidak dapat
disimpulkan batas aman pemejanan, karena semua peringkat takaran
pemejanan yang diuji merupakan efek toksik.
Jadi dari kasus takaran pemejanan tunggal (pemejanan akut) pada
hubungan dosis dan respon, terdapat parameter kuantitatif utama ketoksikan
racun, yaitu: LD50 dan NOEL.
Harga LD50 merupakan tolak ukur toksisitas akut racun. Semakin kecil
harga LD50 , racun berarti semakin besar potensi toksik atau toksisitas akut
racun, yang kriterian tersaji pada Tabel 5.1. Harga NOEL merupakan parameter
batas aman dosis pemejanan racun yakni: takaran tertinggi yang tidak
menimbulkan efek toksik atau kematian subjek uji
Tabel 5.1. Kriteria Ketoksikan akut xenobiotika
NO KRITERIA LD50 (mg/kg)
1 Luar biasa toksik 1 atau kurang
2 Sangat toksik 1 – 50
3 Cukup toksik 50 – 500
4 Sedikit toksik 500 – 5000
5 Praktis tidak toksik 5000 – 15000
6 Relatif Kurang berbahaya Lebih dari 15000
LD50 hanya menggambarkan potensi racun relative terhadap racun yang
lain (potensi realtif). Jadi kedua parameter tersebut tidak menggambarkan
batas aman dosis pemejanan. Parameter yang bisa menggambarkan hal
tersebut adalah NOEL. Artinya, meskipun LD50 racun (A) lebih besar daripada
LD50 racun (B) atau ketoksikan akut (A) lebih besar daripada (B), tidak berarti
racun (A ) lebih aman daripada racun (B). Hal ini tergantung dari nilai NOEL.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 27
28
Misal harga NOEL (A) lebih kecil dibanding dengan (B), maka batas aman dosis
pemejanan racun (B) lebih besar daripada (A), meskipun toksisitas akut (B)
lebih besar daripada (A). Hal dapat terjadi, terutama bila kurva kekerabatan
dosis-respons yang dibandingkan tidak sejajar (Gambar 4.4, a), misal pada
mekanisme dan wujud toksik A dan B berbeda. Tapi bila kurva yang
dibandingkan adalah sejajar (gambar 4.4.b.) mungkin perbedaan toksisitas akut
berbanding lurus dengan perbedaan batas aman dosis pemejanan.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 28
29
BAB VI.
ZAT ANTI NUTRISI
6.1 Zat anti nutrisi
Zat anti nutrisi dapat mempengaruhi senyawa makanan sebelum
dimakan, selama pencernaan dalam saluran pencernaan dan setelah
penyerapan oleh tubuh. Pengaruh negatif dari zat anti nutrisi tidak segera
nampak sebagaimana senyawa toksik pada makanan. Pengaruh yang nampak
dari konsumsi zat anti nutrisi adalah kekurangan gizi atau keadaan nutrisi
marginal. Zat anti gizi dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: anti protein
termsuk diantaranya adalah protease inhibitor, terdapat pada kacang-
kacangan. Anti mineral termasuk didalamnya adalah asam fitat, asam oksalat,
glukosinolat, serat pangan, dan gosipol. Kelompok anti nutrisi berikutnya adalah
anti vitamin, termasuk didalamnya asam askorbat oksidase, anti tiamin,
antipiridoksin
Pada dasarnya banyak bahan pakan secara potensial mengandung satu
atau beberapa jenis antinutrisi. Hal ini berakibat terjadinya gangguan
pertumbuhan, bahkan gangguan kesehatan, apabila kandungan antinutrisi
dalam bahan pakan yang dikonsumsinya cukup tinggi.
Pengetahuan tentang kandungan antinutrisi dalam berbagai bahan
pakan perlu perlu dimiliki oleh formulator pakan, termasuk para peternak yang
mencampur pakan sendiri. Langkah ini sangat penting sebagai strategi untuk
meminimalkan pengaruh-pengaruh yang merugikan dari antinutrisi. Telah
dikembangkan metode-metode prosesing, baik secara fisik, mekanik maupun
kimiawi yang mungkin dapat diterapkan guna memerangi dan menghilangkan
antinutrisi dalam bahan pakan.
6.2 Berbagai Antinutrisi dalam Bahan Pakan
Berbagai jenis tanaman pangan memiliki potensi untuk mensintesis
substansi kimia tertentu sebagai mekanisme untuk mempertahankan diri dari
gangguan infeksi oleh jamur, bakteri dan insekta. Banyak di antara substansi
kimia ini ternyata dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 29
30
maupun ternak yang mengkonsumsinya. Gangguan tersebut dapat berupa
gangguan pertumbuhan, seperti : penurunan Pertambahan Bobot Badan Harian
(PBBH), oleh karena dihambatnya enzim pencernaan tertentu. Gangguan yang
lain berupa gangguan kesehatan, seperti gangguan pernapasan bahkan
kematian. Selanjutnya senyawa-senyawa tersebut dikenal dengan istilah
antinutrisi.
Macam antinutrisi pada berbagai bahan pakan berlainan. Senyawa
antinutrisi yang sering ditemukan, antara lain: Protein inhibitor (penghambat
protease), goitrogen, nekaloid, oksalat, fitat, tannin, HCN dan gossipol.
Antinutrisi tersebut seringkali mengikat protein, zat-zat mineral, sehingga
pemanfaatan gizi dalam bahan pakan oleh ternak menjadi berkurang. Sebagai
akibatnya akan menimbulkan gangguan pertumbuhan pada ternak atau
gangguan kesehatan yang lain.
Antinutrisi dalam bahan pakan kadang-kadang dihasilkan oleh
metabolisme jamur atau mikroba dalam bahan pakan, atau oleh tumbuhan itu
sendiri sebagai mekanisme untuk mempertahankan diri dari gangguan infeksi
atau kelukaan. Hasil samping atau sisa pengolahan bahan pakan seringkali
menimbulkan efek toksik pada ternak, hal ini diduga adanya kandungan nutrisi
dalam bahan limbah atau sisa pengolahan tersebut. Berikut ini disajikan
beberapa bahan pakan dengan kemungkinan zat-zat antinutrisi yang
terkandung di dalamnya.
6.3 Leguminosa
Leguminosa, seperti kedelai dan kacang tanah merupakan sumber gizi
penting bagi ternak. Namun penggunaannya harus dibatasi, karena leguminosa
mengandung zat-zat antinutrisi, antara lain: Protein inhibitor (penghambat
protease), phytphaemagluttin (Lectin), urease, hypoxygenase, glukoside-
sianogenik dan faktor-faktor antivitamin. Hampir semua leguminosa
mengandung unsur penghambat tripsin, dan akan mengikat tripsin sehingga
terbentuk suatu kompleks yang inaktif. Sebagai akibatnya tripsin tidak dapat
berfungsi. Keadaan ini menyerupai dengan kejadian gangguan sintesis tripsin
oleh pankreas. Sebagai konsekuensinya, pankreas akan mengalami hipertrofi
untuk mensintesis tripsin secara berlebih. Hipertrofi pankreas akan diikuti
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 30
31
hambatan pertumbuhan dan menurunnya efisiensi pakan. Protein inhibitor
ternyata mudah diinaktifkan oelh panas.
Antinutrisi lain yang hampir selalu ditemukan dalam leguminosa adalah
phytohaemagluttin atau lectin, yang memegang peran penting dalam simbiosis
antara legum dengan bakteri pengikat nitrogen. Lectin terikat secara reversibel
dengan gula-gula yang berkombinasi dengan protein (glikoprotein) pada
permukaan mikrovilli usus halus, dan menimbulkan lesi-lesi serta perkmbangan
mikrovilli yang tidak no9rmal serta gangguan absorbsi nutrisi lewat dinding
intestinum. Gangguan absorbsi (malabsorbsi) dapat terjadi terhadap vitamin
B12, glukosa dan asam-asam amino. Gangguan transport ion lewat intestinum,
tidak tercernanya karbohidrat dan protein bisa terjadi.
Adanya lectin pada epithelium intestinum yang reseptornya terdapat di
glikoprotein antara intestinum dengan permukaan bakteri enterik, merupakan
perekat antara intestinum dengan bakteri. Pertumbuhan berlebih bakteri
coliform telah dilaporkan terjadi pada ayam yang ransumnya mengandung
kedelai tanpa perlakuan (prosesing) sebelum penggunaannya sebagai bahan
pakan. Lectin menimbulkan lesi-lesi pada ephitelium intestinum yang diikuti
dengan dikeluarkannya endotoksin bakteri yang masuk ke peredaran darah dan
menggangu kesehatan ternak. Ayam muda sangat sensitif terhadap lectin.
Kedelai juga mengandung urease, yaitu suatu enzim yang berperan
untuk menghidrolisis urea menjadi ammoniak dan CO2. Goitrogen juga
dihasilkan oleh kedelai dan kacang tanah. Goitrogen merupakan senyawa
yang berhubungan dengan aktivitas fungsi kelenjar thyroid. Alipoxidase
ditemukan pada kulit kedelai yang akan menurunkan vitamin A dengan cara
merusak karoten.
Cyanogenic-glukoides merupakan senyawa yang membebaskan HCN
pada proses hidrolisis, terdapat pada semua leguminosa.
Faktor antivitamin mungkin ditemukan pada leguminosa, yaitu
antivitamin E, sehingga berakibat terjadinya penurunan tocoferol yang
menimbulkan dystrophia otot pada ayam.
Protease inhibitor, lectin, urease dan faktor-faktor antivitamin serta
lipoxygenase dapat dirusak oleh panas. Besarnya tingkat kerusakan tergantung
kepada tinggi rendahnya temperatur pemanasan, lama pemanasan, ukuran
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 31
32
partikel dan kondisi-kondisi penguapan. Fermentasi merupakan suatu metode
untuk menurunkan level tripsin inhibitor. Germinasi juga merupakan cara untuk
memperbaiki nilai gizi pada kedelai.
Karbohidrat yang sulit dicerna juga merupakan antinutrisi. Kira-kira 40%
dari tepung kedelai disusun oleh serat kasar, polisakarida serta oligosakarida
yang bervariasi. Diketahui sekitar 15 -22% polisakarida dibentuk oleh acidic
polisakarida sebesar 8 – 10%, arabinogalaktan sebesar 5%, selulosa 1,2% dan
starch 0,5%. Senyawa terakhir tidak dapat dicerna oleh ayam. Starch dan
mannan tidak sensitif terhadap pemanasan dan merupakan antinutrisi bagi
ayam. Oligosakarida dalam kedelai merupakan karbohidrat yang mudah
dicerna, akan tetapi menghasilkan TMEn (Energi termetabolisme
sesungguhnya) yang rendah. Sebagai bahan makanan unggas, biji kedelai
memang tidak digunakan dalam bentuk mentah, akan tetapi dalam bentuk
bungkil kacang kedelai yang merupakan limbah dari proses pembuatan minyak
kedelai, dan digunakan sebagi pendamping tepung ikan, sehingga penggunaan
tepung ikan tidak berlebihan.
Penggunaan bungkil kacang tanah untuk unggas kira-kira 0-25%.
Penggunaannya untuk membantu menggantikan jagung kuning dan minyak
nabati guna memenuhi kebutuhan energi. Kelemahan penggunaan bungkil
kacang tanah adalah ketersediaannya yang terbatas, hanya ada di daerah-
daerah yang memiliki pabrik pengolah kacang tanah serta penyimpanan
bungkilnya yang sulit, karena mudah tercemar oleh Aspergillus flavus, yaitu
jamur yang menghasilkan racun berbahaya bagi ayam.
6.4 Singkong (ubi kayu)
Singkong (ubi kayu) sebagai bahan makanan memang tidak pernah
dimakan dalam bentuk mentah sebagaimana ubi manis. Secara fisik, apabila
ubi kayu dibuka kulitnya dan dibiarkan, tidak segera digoreng atau direbus,
maka akan berubah warna menjadi kebiru-biruan. Hal ini menunjukkan adanya
sesuatu zat yang perlu diperhatikan secara serius. Namun apabila ubi kayu t
digoreng, dibakar atau direbus, maka zat yang kebiru-biruan tersebut akan
punah. Oleh karena itu diperlukan proses tertentu sebelum ubi kayu digunakan.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 32
33
Kandungan energi ubi kayu ± 2970 Kkal/kg, mengalahkan energi dalam
dedak, kacang kedelai dan bungkil kelapa. Oleh karena itu ubi kayu banyak
diberikan kepada unggas pedaging yang memang memerlukan energi tinggi,
seperti : ayam broiler, bebek, angsa dan sejenisnya, tetapi tidak diperlukan
untuk anggas petelur.
Cyanogenic-glucosides merupakan senyawa toksik yang terkandung
dalam ubi kayu dan merupakan mekanisme pertahanan tubuh bagi tumbuhan
ubi kayu untuk melindungi dirinya dari serangan insekta. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka ubi kayu mentah tidak dapat digunakan untuk ternak.
Linamarin termasuk dalam Cyanogenic-glucoside. Adanya enzim
hidrolitik berupa ß-glycosidase, linamarin akan terurai dan menghasilkan
aseton, glukosa dan HCN. Terbebasnya HCN inilah yang menyebabkan
keracunan pada ternak. Enzim ß-glycosidase merupakan protein yang mudah
rusak selama pemanasan. Jika enzim tersebut rusak, maka tidak mampu
mengkatalisis pembebasan HCN yang toksik tadi. Pemanasan di bawah
matahari terbuka, direbus atau dipanaskan dalam oven dalam temperatur 70 0C
hingga 800C dapat mengurangi pengaruh racun HCN dalam ubi kayu. Ubi kayu
juga mengandung tripsin inhibitor dan khemotripsin inhibitor, meskipun dalam
kadar rendah. Antinutrisi ini bisa dirusak dengan cara pemanasan.
6.5 Biji Kapas
Biji kapas sebagai bahan pakan ternak dibatasi penggunaannya, karena
mengandung zat antinutrisi yang dikenal dengan sebutan ”gossipol”. Gossipol
merupakan senyawa polifenol dan menyebabkan pucatnya kuning telur pada
ayam atau unggas petelur. Bagi tumbuhan kapas, gossipol merupakan
senyawa yang berperan penting dalam mekanisme pertahanan diri terhadap
serangan insekta.
Gossipol bersifat sangat toksik bagi ruminansia maupun monogastrik
muda. Lesi-lesi pada jantung, saluran reproduksi, paru-paru dan hati terjadi
pada ayam dan ruminansia. Oleh adanya gossipol, jika biji kapas digunakan
pada ayam petelur, maka akan terjadi kepucatan pada warna kuning telur.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 33
34
6.6 Senyawa racun alkaloid
Piperidin Alkaloid: Piperidin alkaloid diidentifikan dari lingkaran
heterosiklik jenuh yang dimilikinya, sebagai contoh adalah inti piperidin.
Senyawa terpenting dari piperidin alkaloid adalah coniin yang di jumpai
pada tanaman conium maculatum atau lebih dikenal dengan nama
tanaman hemlock beracun. Racun ini mudah menyebar karena mudah
menguap sehingga dapat terhirup alat pernafasan.
Hemlock beracun ini dapat menyebabkan kacanduan pada ternak.
Apabila alkaloid diberikan secara oral dan dalam tempo 30-40 menit
pada kuda betina dan sekitar 1.5 – 2 jam setelah pemberian pada sapid
an domba betina, maka ternak mulai terlihat nervous, di ikuti dengan
gemetaran dan atasia. Gejala tersebut berakhir setelah 4-5 jam pada
kuda betina dan 6-7 jam pada sapi dan domba betina. Di antara
ketiganya, sapi merupakan ternak yang paling sensitive terhadap
alkaloid. Sapi-sapi mengalami gejala keracunan pada dosis 3.3 miligram
coniin per kilogram berat badan, kuda pada dosis 15.5 mg/kg dan domba
baru akan menampakan gejala keracunan yang sama pada dosis coniin
44 mg/kg.
Pencegahan terhadap keracunan hemlock beracun sebaiknya dilakukan
dengan cara memonitor kandang, terutama kandang babi karena babi
akan siap mengkonsumsi tanaman tersebut bila ada. Hemlock beracun
tidak palatable pada sapi, kuda dan domba dan jarang ternak tersebut
akan mengkonsumsi jika ada pakan ternak lainnya. Oleh karena conium
alkaloid mempunyai efek teratogenik pada sapi, perhatian sebaiknya di
curahkan pada sapi yang sedang bunting tiga bulan, diusahakan jangan
sampai merumput pada pasture yang terdapat hemlock beracun. Biji-
bijian mengandung konsentrasi toksikan yang tinggi, lagi pula biji-bijian
dapat secara potensial terkontaminasi tanaman hemlock beracun
sehingga berbahaya apabila diberikan pada ternak. Meskipun herbisida
dan kultivasi rutin dapat mengurangi jumlah tanaman hemlock beracun,
tetapi biji-bijian yang terkontaminasi masih potensial berbahaya.
Indol Alkaloid: Indol alkaloid adalah turunan dari asam-asam amino
triptofan yang mudah diamati oleh perbandingan kandungan inti nitrogen
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 34
35
pada struktur zat kimia triptofan. Kelas tanaman yang penting dari indol
alkaloid adalah ergotalkoloid (ergotamine, ergokristin, dll), fescue
alkaloid (ergovalin, ergosin, ergonin, amida asam lisergat), 3-metilindol
(diproduksi oleh fermentasi triptofan dalam rumen dan b-karbolin.
Indol alkaloid beracun pada ternak yang paling penting adalah alkaloid
ergot yang diproduksi oleh jamur parasit pada biji jenis rumput-rumputan
dan biji padi-padian. Istilah ergot umumnya digunakan untuk jenis jamur
Claviceps. Tiga jenis Claviceps yang utama adalah Claviceps Purpurea,
Claviceps paspali, dan Claviceps cinerea.
Ketiga jenis jamur Claviceps tersebut terdapat pada tanaman gandum
dan beberapa rumput liar. Claviceps paspali tumbuh pada rumput
spesies paspalum (seperti Dallis dan Bahia) dan Claviceps cinerea
merupakan parasit pada beberapa rumput lainnya (seperti tobasa grass).
Ergot secara khusus menunjuk pada sclerotium yang dibentuk oleh
claviceps purporea pada saat tumbuh pada gandum (secale cereale).
Ergot digunakan untuk tujuan medis seperti pengontrol perdarahan pada
saat kelahiran.
Ergotalkaloid mengandung asam lisergat sebagai komponen dasar
(Lysergic acid diethylamide/LSD) yaitu obat halusinasi yang merupakan
perubahan pada ergot. Kelompok racun pada ergot alkaloid adalah
ergotamine, ergonovin, dan ergotoxin. Ergotamine dan ergotoxin
merupakan turunan polipeptida dari asam lysergic. Ergotoxin merupakan
campuran dari tiga alkaloid. Ergot alkaloid berpengaruh langsung pada
system stimulus pada otot halus, menyebabkan vasokontriksi dan
meningkatkan tekanan darah. Selama trisemester ketiga kehamilan,
ergot berakibat seperti oxitocin, otot rahim pada tingkat ini lebih sensitive
terhadap ergot dari pada otot halus lainnya.
Penyebaran ergot pada manusia adalah masalah besar di prancis sejak
abad 9-14. Ciri-ciri terjangkitnya ergot diperlihatkan dengan adanya
gatal-gatal, mati rasa, kram otot, kejang dan sakit yang teramat sangat.
Telapak kaki, kaki, dan kadang-kadang tangan akan dipengaruhi oleh
sugesti perasaan dingin diselingi dengan rasa terbakar (st. Anthony fire).
Mati rasa dan rasa lemas akan mengikuti, dengan kehilangan rasa pada
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 35
36
jari tangan dan telapak kaki bahkan seluruh anggota badan. Wabah
tersebut berkurang karena perubahan aktivitas perkebunan. Gandum
putih menggantikan gandum hitam sebagai hasil panen yang terbesar
dan lebih kecil kemungkinan terinfeksi ergot. Pembajakan yang dalam
menghasilkan sclerotia terkubur dan mereka tidak dapat berkecambah
dan membentuk spora.
Akibat umum dari ergot pada mahluk hidup dapat di kategorikan dalam
empat kelompok yaitu pertama adalah efek behavioral yang meliputi
kejang, terganggunya koordinasi tubuh, kepincangan, kesulitan
bernapas, terlalu banyak air liur dan diare. Kedua adalah kehilangan
anggota tubuh. Ketiga adalah efek reproduksi yang terdiri dari aborsi,
tingginya angka kematian kelahiran, penurunan produksi susu dan
keempat adalah pengurangan konsumsi pakan dan bobot badan. Akibat-
akibat tersebut tidak terlihat seluruhnya pada setiap jenis mahluk hidup,
tergantung pada jenis spesiesnya dan tergantung pada sumber ergot,
jumlah yang dikonsumsi, lama penyebaran dan usia serta tingkat
produksi dari hewan.
Sapi dapat terkena wabah ergotisme berupa kejang dan gangrene.
Kekejangan terutama oleh infeksi Claviceps pasapali pada rumput-
rumputan paspalus spp (seperti rumput dallis) dan bukan oleh ergot
Claviceps purpurea. Masalah ergot penting pada peternakan di AS,
dikarenakan sapi mengkonsumsi rumput Dallis yang mengandung Ergot.
Ciri-ciri klinisnya adalah mudah terkejut, terganggunya koordinasi tubuh
dan sawan. Perpindahan sapi dari padang rumput yang terinfeksi
membutuhkan waktu 3-10hari. Ergot menyebabkan gangrene pada sapi
disebabkan oleh ergot dari claviceps paspali dan claviceps purpurea.
Gangren dapat terjadi pada ujung telinga dan ekor, tapi umumnya yang
terinfeksi adalah telapak kaki. Ciri-ciri umum termasuk kaki belakang
yang halus dengan perkembangan gangrene dan pengelupasan kuku.
Ada efek kecil pada reproduksi, dengan aborsi dan agalactia (yang
terlihat pada babi) tidak terdeteksi.
Domba yang mengkonsumsi ergot Claviceps purpurea kelihatan sulit
bernafas, pernafasan terlalu cepat, diare dan pendarahan dalam saluran
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 36
37
pencernaan. Domba cenderung untuk tidak makan bunga rerumputan
dan karenanya lebih sedikit terinfeksi daripada sapi karena kebiasaan
makan yang berbeda. Kuda yang memakan rumput yang terinfeksi
Claviceps paspali bias terjangkit gejala kejang karena ergotisme.
Pertumbuhan padi-padian yang tahan terhadap ergot (wheat, barley,
atau oat) lebih di anjurkan dari pada rye atau triticale pada area dimana
ergot menjadi masalah.
Sclerotia dapat dipindahkan dari biji padi dengan tehnik pembersihan biji
padi-padian yang mengandung ergot tidak boleh digunakan untuk
makanan. Biji padi-padian yang terinfeksi dapat di campur dengan biji
padi-padian yang bersih untuk mengurangi konsentrasi ergot pada
tingkat yang tidak beracun. Tingkat toleransi ergot pada biji padi-padian
di AS adalah 0.3% ergot alkaloid mentah. Tingkat 0.15 ergot pada pakan
dapat merugikan pada kualitas peternakan.
Indolizidin alkaloid: Indolizidin alkaloid merupakan salah satu senyawa
yang merupakan golongan dari alkaloid. Dalam tanaman, senyawa
indolizidin alkaloid ini mempunyai sifat racun dan dapat membahayakan
bagi ternak, terutama bila dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu jenis
keracunan dari indolizidin alkaloid yang terjadi adalah locoisme.
Sedangkan salah satu dari kelompok indolizidin alkaloid yang terpenting
adalah swainsonin, sedangkan lainnya adalah slaframin dan
castanospermin. Jenis-jenis tanaman yang mengandung indolizidin
alkaloid swainsonin adalah Astragalus dan Oxytropis. Tanaman ini
biasanya ditemukan di daerah Australia barat.
Ternak yang biasanya mengkonsumsi tanaman ini adalah sapi, kuda dan
domba, namun kadang-kadang diberikan juga pada unggas. Tanaman
ini telah dikenal lebih dari 75 tahun mempunyai kesamaan fisiologis
dengan Swainsona spp. Yang pernah meracuni hewan ternak di
Australia Barat. Factor-faktor yang menjadi penyebab keracunan pada
ternak dari tanaman tersebut sulit dipahami sampai tahun 1979 ketika di
teliti di Universitas Murdoch Australia Barat yang diidentifikasi sebagai
indolizidin Alkaloid.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 37
38
Keracunan tanaman ini pada ternak dapat mengakibatkan timbulnya
infeksi, seperti pneumonia, footrot, dan pink aye, dan pengobatan yang
disarankan adalah dengan menggunakan system kekebalan. Hasil
penelitian yang dilakukan, hewan yang mengkonsumsi tanaman ini akan
mengalami penurunan leukosit dan limfosit dengan indikasi efek selektif
pada respon kekebalan sel-sel perantara. Mengkonsumsi tanaman ini
juga dapat membawa efek terhadap tingkat mortalitas. Selain itu tanda-
tanda keracunan pada ternak sapi adalah pada saat hewan berjalan
kakinya terlihat kaku, kepala menggeleng-geleng dan matanya sayu.
Sedangkan tanda pada domba adalah kepala gemetar, mata sayu,
gangguan penglihatan dan tidak terkoordinasi.
Beberapa solanum spp menyebabkan degenerasi cerebellar pada sapi
yang sama kejadiannya seperti pada tanaman swainsona dan Astragalus
spp. Sejumlah alkaloid yang terlibat dalam tanaman solanum spp
menyebabkan kekacauan yang dikarakteristikkan oleh timbulnya
serangan tiba-tiba secara berulang dengan berkurangnya keseimbangan
, opisthotonus, pergerakan mata yang cepat dan jatuh kesamping atau
kebelakang. Tanda-tanda patologis yang utama adalah vakuolasi,
degenerasi, dan kehilangan sel-sel purkinje. Factor-faktor keracunan
dalam tanaman solanum tidak dapat diidentifikasikan, namun mungkin
adalah inhibitor dalam hidrolase.
Efek biologis pada sindrom slafamarin yang terjadi adalah disebabkan
oleh slafamarin. Tanda-tanda klinis keracunan pada hewan ternak
adalah bertambahnya air liur yang luar biasa, lakrimasi (mata kosong),
kembung, terjadi kencing yang berkali-kali, dan feses yang cair (diare).
Salvias yang jumlahnya luar biasa dapat muncul segera setelah
mengkonsumsi tanaman yang mengandung salfamarin dan mungkin
akan berlanjut untuk beberapa hari setelah pengkonsumsian pada racun
itu berhenti.
Efek keracunan yang lain selain salvias adalah terjadinya peningkatan
aliran produk pancreas, aliran cairan empedu, dan asam lambung,
penurunan rataan hati, output kardiak, rataan respirasi, suhu tubuh, dan
rataan metabolism dan pendarahan rahim serta aborsi fetus. Disana
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 38
39
tidak dapat dibedakan kerusakan atau akibat-akibat yang lain yang
disebabkan dari keracunan slafamarin. Penyambunan akan berlangsung
dengan sendirinya dan akan sempurna dalam jangka waktu 2-3 hari.
Atropine dan antihistamin tertentu cukup efektif dalam meredakan
beberapa tanda-tanda klinis pada keracunan.
Senyawa racun glukosida-Glukosida sianogenik: Bagi tanaman,
senyawa ini diperlukan dalam mekanisme pertahanan diri terhadap
predator dan dalam proses metabolism untuk membentuk protein dan
karbohidrat. Umumnya senyawa tersebut disintesis dari asam amino
yang merupakan homolognya. Sebagai contoh beberapa senyawa yang
strukturnya hampir sama dengan asam amino prekursornya. Nampak
bahwa linamarin dan lotaustarin yang masing-masing berasal dari asam
amino L-Valin dan L-Isoleusin.
Gagasan mengenai pola umum biosintesa glikosida sianogenik
berkembang cepat setelah ditemukan bahwa asam-asam amino adalah
precursor dari glikosida sianogenik dari studi isotop radioaktif 14C15N
menunjukkan bahwa ikatan karbon nitrogen pada asam amino
menjadikan penggabungan yang lengkap. Jalur biosintesa glikosida
sianogenik dimulai dari asam amino yang di ubah ke dalam bentuk
aldoxime, kemudian terbentuk menjadi sianohidrin yang sebelumnya
melalui (dapat dua cara) pembentukan nitril atau hidroksi aldomin.
Sianohidrin dikatalis oleh β-glikosil-transferase menjadi glikosida
sianogenik. Pada tanaman yang tumbuh tanpa kerusakan, glikosida
sianogenik dimetabolisme menjadi asam amino, tetapi apabila tanaman
tersebut luka atau dipotong maka glikosida sianogenik akan terdegradasi
dan akan membebaskan asam sianida. Tahap pertama proses degradasi
(katabolisme) adalah pelepasan gula dan terbentuk sianohidrin oleh
enzim β-D-glukosidase. Sianohidrin dapat memisahkan diri menjadi
aldehida atau keton dan asam sianida dengan enzim oxynitrilase atau
hydroksi nitrilase.
Emulsin, suatu system enzim yang di dapat pada biji almond (prunus
amygdalus, Rosaceae) akan mengkatalisis baik hidrolisis gula maupun
pembentukan asam sianida. Pada amigdalin, gentibiosa mula-mula
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 39
40
terhidrolisa menjadi glukosa (membentuk prunasin), kemudian molekul
glukosa kedua lepas. Emulsion spesifik untuk glikosida sianogenik
aromatic, sedangkan linamarinase (9 glukosidase) yang terdapat pada
biji flax, white clover dan ubi kayu akan mengkatalisa hidrolisis baik
glikosida alifatik maupun aromatic tapi tidak mengkatalisis hidrolisis baik
glikosida alifatik maupun aromatic tapi tidak mengkatalisis diglukosida.
Secara lebih rinci, dua contoh antinutrisi dari senyawa glukosida
sianogenik (linamarin dan lotaustralin) serta derivatnya (asam sianida).
Linamarin: Linamarin merupakan senyawa turunan dari glikosida
sianogenik. System metabolism dalam tanaman meyebabkan salah satu
hasil dari degradasi asam amino L-valin adalah linamarin. Linamarin
terdapat dalam tanaman linum usitatissinum (linseed), phaseolus lunatus
(java bean), trifolium repens (white clover), lotus spp. (lotus),
dimorphoteca spp (cape marigolds) dan manihot spp. (ubi kayu). Namun
linamarin diberikan karena serupa dengan yang diketemukan dalam
tanaman rami (linum spp). Phaseolus lunatus sebagai salah satu
tanaman yang mengandung linamarin. Bagian distal ubi (mengarah ke
ujung) mengandung lebih banyak linamarin dibandingkan dengan bagian
proksimal (mengarah ke batang ubi). Linamarin larut dalam air dan
hanya dapat hancur oleh panas di atas suhu 150°C. daun ubi kayu
mengandung linamarin sebesar 93 persen dari glikosida.
Lotaustralin: Lotaustralin merupakan senyawa turunan dari glikosida
sianogenik. System metabolism dalam tanaman menyebabkan salah
satu dari degradasi asam amino L-isoleusin adalah lotaustralin.
Lotaustralin terdapat bersama linamarin dalam tanaman yang sama,
tetapi berbeda jumlahnya. Lotaustralin jauh lebih sedikit dibandingkan
dengan linamarin. Perbandingannya berkisar dari 3 sampai dengan 7
persen lotaustralin berbanding 93 sampai dengan 97 persen linamarin.
Lotaustralin antara lain terdapat dalam tanaman linum utilissinum
(linseed), phaselous lunatus (java bean), trifolium repens (white clover),
lotus spp. (lotus), dimorphoteca spp. (cape marigolds) dan manihot spp.
(ubi kayu). Lotaustralin larut dalam air dan hanya dapat hancur oleh
panas di atas suhu 150°C. daun ubi kayu mengandung lotaustralin
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 40
41
sebesar 7 persen dari glikosida. Bila senyawa ini dihidrolisa oleh asam
atau enzim maka akan menghasilkan methyl ethyl keton + glukosa +
asam sianida.
Asam sianida (HCN): Lebih dari 100 jenis tanaman mempunyai
kemampuan untuk memproduksi asam sianida. Jenis tanaman tersebut
antara lain family rosaceae, possifloraceae, leguminosae, sapindaceae,
dan graminae. Manihot utilissima sebagai salah satu tanaman yang
mengandung asam sianida. Asam sianida merupakan anti nutrisi yang
diperoleh dari hasil hidrolisis senyawa glikosida sianogenik seperti
linamarin, luteustralin, dan durin. Salah satu contoh hasil hidrolisis
adalah pada linamarin dengan hasil hidrolisisnya berupa D-glukosa +
HCN + aceton dengan bantuan enzim linamerase tanaman terhadap
gangguan/kerusakan. Asam sianida hanya dilepaskan apabila tanaman
terluka. Tahap pertama dari proses degradasi adalah lepasnya molekul
gula (glukosa) yang dikatalis oleh enzim glukosidase. Sianohidrin yang
dihasilkan bias berdissosiasi secara nonenzimatis untuk melepaskan
asam sianida dan sebuah aldehid atau keton, namun pada tanaman
reaksi ini biasanya dikatalis oleh enzim.
Jika sianida masuk dalam tubuh, efek negatifnya sukar diatasi. Kejadian
kronis akibat adanya sianida terjadi karena ternyata tidak semua SCN
(tiosianat) terbuang bersama-sama dengan urin, walaupun SCN dapat
melewati glomerulus dengan baik, tetapi sesampainya di tubuli di
sebagian akan diserap ulang, seperti halnya klorida. Selain itu,
kendatipun system peroksidase kelenjar tiroid dapat mengubah tiosianat
menjadi sulfat dan sianida, tetapi hal ini berarti sel-sel tetap berenang
dalam konsentrasi sianida di atas nilai ambang. Jelaslah bahwa sianida
dapat merugikan utilisasi protein terutama asam-asam amino yang
mengandung sulfur seperti metionin, sistein, sistin, vitamin B12, mineral
besi, tembaga, yodium, dan produksi tiroksin.
Inhibisi sitokrom oksidase akan menekan transport electron dalam siklus
krebs yang menghasilkan energy, sehingga gejala keracunan pertama
adalah hewan tampak lesu, tak bergairah seolah-olah tidak mempunyai
banyak tenaga untuk bergerak, nafsu makannya juga sangat menurun.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 41
42
Karena tubuh kekurangan oksigen, tubuh tampak kebiru-biruan
(cyanosis) dan dengan sorot mata yang tidak bersinar. Terjadi pula
disfungsi pada system syaraf pusat, sehingga menimbulkan gejala
mengantuk yang sulit dihindarkan. Keracunan yang berlanjut akan
menyebabkan kehilangan keseimbangan, hewan tidak dapat berdiri
tegak, sempoyongan, nafas tersengal-sengal, muntah, kejang-kejang,
lumpuh, dan dalam beberapa detik akhirnya hewan mengalami
kematian. Langkah yang dapat dilakukan untuk menghilangkan atau
mengurangi efek negative sianida, yaitu pertama adalah menghilangkan
sebanyak mungkin sianida sebelum suatu bahan makanan yang
mengandung sianida yang tersisa agar dapat dikeluarkan bersama-sama
dengan feses.
Asam sianida dapat dinetralisasikan dengan beberapa macam
perlakuan. Beberapa studi tentang mekanisme penurunan anti nutrisi
sianida dan peningkatan reduksinya dapat dilakukan dengan
suplementasi sulfur anorganik maupun organic. Suplementasi sulfur
akan menghasilkan tiosianat, reaksi ini akan dibantu oleh rodanase.
Tiosianat, akan dikeluarkan melalui urin. Pemberian garam ferosulfat
dapat mengikat asam sianida dalam pakan sehingga hilang sifat
racunnya. Pemberian garam ferosulfat 12,7 kali kandungan asam sianida
pakan menunjukkan efek yang paling baik. Pakan dapat disuplementasi
dengan asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin, sistein
supaya menghasilkan penampilan yang baik bagi unggas. Apabila
unggas keracunan asam sianida, langkah yang dapat dilakukan adalah
menginjeksi dengan Na-Nitrit. Telah dijelaskan bahwa keracunan sianida
terjadi akibat timbulnya ikatan yang kuat antara enzim sitokrom oksidase
dengan ion sianida. Mengobati keracunan dilakukan untuk mencegah
terjadinya ikatan tersebut.
Telah diketahui bahwa ion sianida berikatan dengan Fe3+, tetapi tidak
dengan Fe2+. Dalam tubuh Na-Nitrit akan merubah ion Fe2+ pada
hemoglobin menjadi ion Fe3+ (Methemoglobin). Methemoglobin ini dapat
berikatan dengan CN membentuk sian-mathemoglobin. Ikatan CN-
methemoglobin ini tidak menimbulkan keracunan. Terjadi kompetisi
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 42
43
antara mathemoglobin dan sitokrom oksidase untuk mengikat CN,
dengan demikian pengikatan CN oleh sitokrom oksidase menjadi
minimal. CN dalam ikatan CN-methemoglobin ini selanjutnya dikeluarkan
dengan member injeksi Na-sulfat. CN bersenyawa dengan Na-tiosulfat
membentuk tiosianat yang tidak beracun dan mudah dikeluarkan urin.
Solanin: Solanin merupakan senyawa golongan glikosida yang diketahui
sebagai antienzim, yaitu penghambat enzim akholinesterase. Solanin
yang ditemukan pada tanaman yang tergolong dalam suku solanaceae
yang kebanyakan berupa terna berbatang basah, jarang berupa semak
atau pohon, atau umumnya pada kentang-kentangan, dengan
spesiesnya adalah: Solanum dulcamara L, Solanum ningrum L, dan
Solanum tuberosum L.
Sebagaimana senyawa golongan glikosida yang merupakan hasil dari
proses esterifikasi atau kondensasi hydrogen dari gugus hidroksil, yang
terikat pada atom karbon pertama dari glukosa dengan alcohol atau
fenol. Glikosida ini berbahaya jika terhidrolisis lebih dahulu, yang dapat
terjadi lebih cepat oleh adanya enzim yang biasanya terdapat pada
tanaman. Jika enzim di inaktifkan maka tanaman dapat dimakan tanpa
bahaya. Bila kadar glukosa tinggi, tanaman harus direbus dulu sebelum
diberikan pada ternak, karena umumnya panas dapat menginaktifkan
enzim.
Dua dampak mendasar dari solanin yang umumnya terdapat dalam
kentang ini adalah iritasi terhadap bagian usus halus yang menyebabkan
penyerapan terganggu, disamping terjadinya ketegangan system syaraf.
Kandungan solanin dalam tubuh yang terlalu banyak setidaknya
menyebabkan penurunan penyerapan oleh alat pencernaan dalam
tubuh, solanin yang terhidrolisa akan menyebabkan terbentuknya
solanidin yang merupakan racun. Dari berbagai uraian di atas dapat
diketahui bahwa untuk meminimalkan kandungan solanin dalam bahan
pangan sehingga dapat dikonsumsi dengan aman oleh M.H. adalah
dengan jalan pemanasan terlebih dahulu agar enzim dalam kentang
tidak aktif sehingga tidak sampai terjadi hidrolisa pada senyawa yang
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 43
44
tergolong glikosida ini. Di samping itu pemilihan kentang yang tidak
terlalu muda juga menghindari dampak keracunan.
Fitoestrogen (Isoflavon dan Coumestan): Fitoestrogen adalah
estrogen tanaman. Dua senyawa yang merupakan fitoestrogen adalah
isoflavon dan coumestan yaitu zat yang berasal dari kelas fenilpropanoid
dan merupakan penggabungan decumarol (3.3 metyhylenebis atau 4-OH
coumarin) melalui posisi ketiga. Isoflavon adalah senyawa yang dibentuk
sebagai reaksi kondensasi antara gula dan gugus hidroksil dari senyawa
kedua yang dapat tidak dapat merupakan gula yang lain. Dalam
senyawa ini, residu karbohidrat terikat oleh suatu ikatan asetal pada
atom karbon yang anomer dengan gula atau bahan gula senyawa kedua
atau aglikon. Kelompok ini, misalnya genistein, biochaunyin A. Eqoul,
Phaseollin, pisatin, meditagol, coumestrol, lucernal, trifolin dan epensol
dan banyak terdapat pada leguminosa.
Fitoestrogen terkandung dalam tanaman sub clover, red clover (trifolium
pretense), dan alfalfa (medicago sativa). Secara umum estrogen dalam
clover adalah isoflavon, sedangkan pada alfalfa adalah coumestan.
Isoflavon di sintesis tanaman dari fenilalanin sedangkan coumestan
disintesis dari asam sinamat. Subterranean clover (trifalin subteraneum),
red clover (trivalium protense), dan Lucerne (medicago sativa),
mempunyai kadar senyawa estrogenic yang tinggi, sehingga beberapa
leguminosa tersebut dapat menyebabkan infertilitas dan gangguan
reproduksi yang lain. Masalah estrogenic dari subterranean clover
disebabkan oleh isoflavon, sedangkan gejalanya disebut clover disease.
Kadar asam estrogenic pada alfalfa dan clover tergantung pada
serangan penyakit terhadap daun dan cekaman pada tanaman. Belum
diketahui apakah produksi zat estrogenic tersebut sebagai mekanisme
proteksi atau efek khusus apa dari zat tersebut terhadap penyakit.
Pengaruh kerja isoflavon adalah melemahkan penetrasi sperma pada
oviduct sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Cairan serviks sudah
dirusak konsistensinya yang menyebabkan penyimpanan sperma di
serviks terganggu. Akibat clover disease meliputi distokia maternal,
prolapsus uteri, kematian induk dan mortalitas pasca lahir. Gejala
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 44
45
patologis dapat dihindari dengan usaha menurunkan pengaruh clover
disease antara lain dengan penggunaan kultivar yang berkadar
estrogenic rendah. Disamping itu isoflavon dapat menyebabkan
kematian karena dalam waktu singkat terjadi hiperglisemia, diikuti oleh
hilanganya glukosa yang cepat dalam darah dan glikogen dari jaringan.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 45
46
BAB VII.
SENYAWA RACUN PROTEIN DAN ASAM AMINO
7.1 Anti tripsin
Anti tripsin atau inhibitor tripsin adalah senyawa penghambat kerja tripsin
yang secara alami terdapat pada kedelai, lima bean (kara), gandum, ubi jalar,
kentang, kecipir, kacang polong, umbi leguminosa, alfalfa, sorgum, kacang
fava, beras dan ovomucoid. Kesemuanya tanaman tersebut mempunyai
antitrypsin dengan protein berberat molekul rendah, keculi anti tripsin yang
terdapat pada ovomucoid yang terdiri dari 75% asam amino dan 25%
karbohidrat.
Dalam kacang kedelai, anti tripsin mempunyai dua macam tipe yang
kunitz inhibitor dan Bowman-Birk inhibitor (BBI). Kunitz inhibitor mempunyai
ukuran molekul 20.000 sampai 25.000 dengan aktivitas yang spesifik pada
tripsin, terdiri dari 181 residu asam amino dengan 2 ikatan disulfide dan 63
asam amino yang aktif. Kunitz inhibitor menunjukkan sebagai penghambat
reaksi tripsin dengan cara yang sama yaitu reaksi dengan pencernaan protein
lain, tetapi sejumlah ikatan non kovalen dibentuk pada tempat aktif dalam
sebuah ikatan kompleks yang tidak dapat dirubah.
Anti tripsin akan memacu pembentukan dan sekaligus pelepasan zat
seperti panckreozimin yang bersifat seperti hormone dari dinding usus. Zat ini
akan merangsang pengeluaran enzim dari pancreas. Seperti diketahui
pengeluaran enzim dari pancreas diatur oleh mekanisme umpan balik karena
adanya tripsin dan kimotripsin dalam usus akan merangsang pengeluaran
enzim-enzim pancreas dengan jalan mengikat tripsin dan kimotripsin aktif
dalam usus halus. Dengan demikian dengan adanya anti tripsin, pancreas akan
mengeluarkan enzim secara berlebihan.
Karena enzim itu sendiri adalah protein, maka ternak yang diberi pakan
yang mengandung anti tripsin tidak saja tidak dapat menggunakan protein yang
terdapat dalam pakan tersebut, melainkan juga kehilangan protein tubuh lewat
enzim yang dikeluarkan berlebihan. Akibatnya ternak yang mengkonsumsi
pakan yang mengandung anti tripsin akan mengalami beberapa gejala seperti
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 46
47
kesulitan mengkonsumsi pakan, hipertropi pankreatik dengan adanya
peningkatan jumlah sel-sel jaringan pancreas, gangguan pencernaan protein,
gangguan absorpsi lemak, pengurangan sulfur asam amino dan terhambatnya
pertumbuhan.
Pakan unggas yang mengandung anti tripsin cenderung akan
membentuk pembesaran pancreas. Pembesaran pancreas akan memperbesar
sekresi tripsin. Tripsin yang berlimpah dari pembesaran pancreas
menyebabkan kekurangan sulfur asam amino. Efek yang paling akhir terjadi
adalah terhambatnya pertumbuhan karena tingginya sulfur asam amino dari
dalam yang hilang karena hasil tripsin yang berlebihan. Pada binatang seperti
babi, anak sapid dan ayam muda (konsidi hipertropik pancreas umumnya
lambat) maka akan terjadi penghambatan pencernaan protein karena jumlah
anti tripsin yang berlebihan melebihi produksi tripsin. Pada anak ayam yang
diberi bahan pakan yang mengandung anti nutrisi mengalami problem dalam
hal ukuiran pancreas, pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan. Pada
ayam dewasa lebih tahan terhadap penggunaan kedelai mentah dari pada
ayam muda.
Hampir semua anti tripsin dalam tanaman dapat dirusak oleh panas.
Lebih dari 95% aktivitas dirusak dengan perlakuan panas dalam waktu 15 menit
pada suhu 100°C. penggilingan pakan yang menggunakan esktruder sangat
efektif dalam menghancurkan anti tripsin. Factor penting dalam mengontrol
perusakan anti tripsin adalah suhu, lama pemanasan, ukuran partikel dan
kandungan air. Pemanasan yang berlebihan akan merusak zat makanan yang
lain seperti asam amino dan vitamin.
7.2 Papain
Papain adalah suatu enzim pemecah protein (enzim proteolitik) yang
terdalam dalam getah papaya yang memiliki aktifitas proteolitik minimal 20
unit/gram preparat dan tergolong ke dalam senyawa oraganik komplek yang
tersusun dari gugusan asam amino. Papain adalah protease sulfilhidril karena
memiliki gugusan sulfilhidril (SH) pada bagian aktifnya. Papain kali pertama
ditemukan pada tahun 1975 oleh graffiti Huges.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 47
48
Papain termasuk enzim hidrolisa karena menggiatkan berlangsungnya
proses hidrolisa protein, dengan demikian papain juga merupakan enzim
protease dank arena mengandung sulfilhirdil (SH) pada bagian aktifnya maka
dikatakan protease sulfilhidril, sedangkan aktivitas enzim dihambat oleh adanya
logam berat dan oksidator. Berdasarkan tempat pemutusan ikatan peptidanya
maka papain tergolong enzim endopeptidase yaitu enzim yang dapat
memutuskan ikatan peptide pada bagian dalam rantai, hasil hidrolisanya berupa
penggalan rantai peptide asam-asam amino.
Adanya kandungan enzim papain pada papaya yang berperan sebagai
pencerna karena sifat katalis merupakan suatu enzim proteolitik yang mampu
merusak protein tubuh cacing dalam saluran pencernaan. Reaksi yang terjadi
pada enzim proteolitik papain adalah hidrolisis menjadi polipeptida dan peptide,
kemudian selanjutnya menjadi asam amino. Mekanisme kerja enzim papain
khusus terhadap cacing dewasa yang terdapat pada saluran pencernaan
hewan adalah di duga enzim papain akan berperan dalam merusak enzim-
enzim yang dibutuhkan cacing yang ada di dalam saluran pencernaan sehingga
suplai nutrisi bagi cacing terproteksi. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan
pencernaan untuk keperluan tubuh cacing akan terhambat. Selain itu pula
papain dimungkinkan akan merusak protein dan glikoprotein yang berperan
dalam transport hasil metabolism tubuh cacing sehingga akan berefek pada
kematian cacing dewasa. Pada akhirnya hal tersebut mempengaruhi
produktivitas induk semang cacing yantu nutrisi yang dikandung oleh pakan
yang dikonsumsi dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup pokok
maupun kebutuhan berproduksi sehingga secara nyata efek yang diperoleh
terjadi peningkatan konsumsi dan konversi pakan.
Berdsarkan hasil penelitian Murcof (1998), menyatakan bahwa pada
kadar konsentrat 20% getah papaya efektif dalam pengendalian infeksi
Ascaridia galli pada ayam petelur. Adapun pengobatan dengan getah papaya
20% pada ayam yang terifeksi Ascaridia galli menyebabkan kenaikan produksi
telur ayam setingkat dengan berat telur dari ayam yang bebas dari infeksi
cacing tersebut. Disarankan penggunaan papain sebagai obat cacing pada
konsentrasi 20% dengan dosis 0.5 kg BB ayam dalam 2.5 ml air memberikan
hasil yang baik untuk membasmi cacing pada ternak unggas.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 48
49
7.3 Lectin (Hemaglutinin)
Lektin adalah glikoprotein yang mempunyai bobot molekul 60.000-
100.000 yang dikenal untuk kemampuannya menggumpalkan eritrosit.
Tanaman yang mengandung lectin dijumpai dalam banyak kelompok botani
meliputi monokotiledon dan dikotiledon, jamur, dan lumut. Tetapi yang paling
banyak terdapat pada leguminoseae dan euphobiaceae. Lectin berada dalam
berbagai jaringan pada tanaman yang sama dan mempunyai lokasi seluler dan
sifat molekuler yang berbeda.
Lektin menggumpalkan sel-sel darah merah yang terdapat pada ternak.
Lektin dapat disebut agglutinin atau biasa juga di sebut phitohemaglutinin.
Dilihat dari namanya maka lectin memang berfungsi menggumpalkan sel-sel
darah merah. Lektin dapat juga mematikan ternak karena bersifat racun
dikarenakan terdapat pepsin. Lektin adalah protein yang mempunyai ketinggian
afinitas untuk molekul gula tertentu. Lektin pertama-tama diisolasi dari kacang
castor, dengan kandungan lektin yang biasa disebut ricin. Jadi, lektin adalah
protein yang sangat mempengaruhi gula dan gabungan gliko dengan pengaruh
yang tinggi. Lektin berinteraksi dengan karbohidrat tertentu yang sangat spesifik
enzim-substrat, atau interaksi antigen-antibodi. Lektin berikatan dengan gula
bebas atau residu gula polisakarada, glikoprotein, atau glikolipid yang dapat
dibebaskan atau diikat dalam membrane sel.
Lektin ini banyak terdapat dipakan ternak. Jadi dalam pemberian pakan
harus dilihat dahulu apakah pakan itu berbahaya bagi ternak atau
menguntungkan bagi ternak. Oleh karena itu pakan yang diberikan pada ternak
haruslah diolah lebih dulu agar tidak terjadi kesalahan metabolism pada ternak
sangatlah kompleks. Racun dari lektin akan tumbuh dan diserap oleh zat gizi
pakan, dengan adanya penyerapan ini maka akan terjadi infeksi bakteri. Lektin
ini mengganggu sel-sel darah, kemudian di dalam sel darah merah tersebut
terjadi penggumpalan pada sel darah merah. Lecithin juga merugikan system
dalam infeksi bakteri, lectin mengacaukan garis batas sel vili duodenum dan
jejunum dan abnormalitas dengan tingginya katabolisme di jaringan protein.
Disamping itu juga terjadi perkembangbiakan dramatis dari Escherichia coli
diusus halus. Lektin dapat dihancurkan dengan pemanasan basah, sementara
sangat tahan terhadap pemanasan kering.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 49
50
7.4 Mimosin
Mimosin merupakan zat racun atau zat anti nutrisi yang berasal dari
lamtoro atau leguminosa. Mimosin merupakan racun yang berasal dari turunan
asam amino. Mimosin merupakan racun yang berasal dari turunan asam amino
heterosiklik, yaitu asam amino yang mempunyai rantai karbob melingkar
dengan gugus berbeda. Mimosin mempunyai gugus keton dan hidroksil pada
inti pirimidinnya, yang diketahui bersifat toksik. Mimosin sering disebut
leusenina, dengan rumus molekul C8H10O4N2.
Penelitian mendalam mengenai senyawa ini belum banyak dilakukan,
beberapa ahli mendapatkan gejala keracunan. Percobaan pada tikus dengan
memberikan mimosin sebanyak 1% menyebabkan gejala toksik dengan
terjadinya alopecia, penghambatan pertumbuhan dan gejala memperpendek
umur tikus. Percobaan lain dengan ekstrak lamtoro pada makanan tikus
ternyata menyebabkan kerusakan pada folikel rambut, sehingga merusak
rambut tikus. Ternyata beberapa pengamat mensinyalir adanya gejala rontok
rambut pada manusia jika makan bahan senyawa ini.
Pencegahan dapat dilakukan dengan membatasi pemberian bahan
pakan yang mengandung senyawa tersebut dalam ransum yaitu kurang dari
5%. Mimosin diketahui stabil dan sedikit larut dalam air. Kelarutannya adalah
500 (1 gram dalam 500 cc air) sehingga apabila senyawa tersebut dilarutkan
lebih 500 CC air maka senyawa tersebut akan berkurang sifar toksiknya.
Mimosin merupakan senyawa yang tidak mudah rusak pada pemanasan biasa,
kadar kerusakannya mulai terjadi jika dilakukan pemanasan tinggi, sekitar 227 -
228°C, hal ini dapat digunakan sebagai pencegahan keracunan dengan
pemanasan terlebih dahulu bahan pakan yang mengandung senyawa tersebut
sebelum diberikan pada unggas.
7.5 Latirogen
Latirogen adalah racun yang ditemukan dalam chick pea dan vetch yaitu
sejenis kacang polong. Latirogen merupakan derivate asam amino yang
bekerja melawan metabolism asam glutamate, sebagai neurotransmitter di
otak. Ketika latirogen terkonsumsi dalam jumlah banyak oleh ternak, maka akan
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 50
51
terjadi kelumpuhan. Penyakit yang disebabkan oleh racun latirogen dinamakan
latirisme.
Biji-bijian L. sativus dapat diperlakukan untuk membatasi toksisitas.
Perendaman dan perebusan di dalam air panas dapat menghilangkan
neurotoksin. Biji-bijian dipergunakan biasanya berupa bahan mentah seperti
bentuk bola pasta, agar toksikan dapat tertahan. Sehingga dengan sedikit
penyiapan pakan biji-bijian, kecunan dapat dihindari. Pemecahan yang paling
ideal adalah dengan cara mengembangkan penanaman tanaman L. sativus
bebas racun, karena setiap tanaman hijauan memiliki ciri agronomi tersendiri
yang akan menjadikannya sebuah tanaman pakan yang baik jika tidak beracun.
7.6 Linatin, indospecinedan canavanin
Bungkil biji rami (Linum Usitatissimum) mengandung sebuah zat
antagonis dari piridoksin yaitu asam amino 1-amino-D-prolin. Pada bungkil biji
rami, zat yang apabila dihidrolisis akan mengahasilkan dipeptida 1-amino-D-
prolin dan asam glutamate dikenal sebagai linatin. 1-amino-D-prolin bereaksi
dengan piridoksal fosfat membentuk hidrazona dan akan menghalangi fungsi
sebagai kofaktor di metabolism asam amino. Produksi piridoksal fosfat
dimasukkan pada transaminasi, dekarboksilasi dan reaksi metabolism asam
amino lainnya. Gejala defisiensi piridoksal meliputi depresi nafsu makan,
pertumbuhan lambat, dan konvulasi pada ayam yang mengkonsumsi bungkil
biji rami. Pemanasan dan ekstraksi air serta suplementasi piridoksi pada
bungkil biji rami akan menanggulangi efek antipiridoksin.
Racun indospecine mengahambat penggabungan arginin menuju protein
jaringan dan menyebabkan kerusakan hati pada sapi dan domba yang
mengkonsumsi tanaman ini. Gejala yang terjadi adalah nekrosis dan sirosis
nodular. Canavarin seperti indospecine adalah analog dari arginin. Hal tersebut
terjadi pada konsentasi tinggi (diatas 5%) pada jack bean (canavalia ensiformis)
dan sejumlah leguminosa lainnya. Tunas alfalfa mengandung canavanin sekitar
1.5% dari berat bersih. Pada beberapa lupus erythematosus-like syndrome
terjadi ketika tunas alfalfa dikonsumsi oleh monyet.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 51
52
DAFTAR PUSTAKA
Adams, C. A., 2000. Enzim komponen penting dalam pakan bebas antibiotika.
Feed Mix Special. http ://www.alabio.cbn.net. (20 Agustus 2003).
Afwan. 1992. Pengaruh Sari Bawang Putih Terhadap Penurunan Kadar
Glukosa Darah Kelinci Dibandingkan Dengan Metformin Hidroksida.
Laporan Penelitian, Jurusan Farmasi, FMIPA USU, Medan
Anderson, H. l994. Effect of carbohydrates on the exretion of biles acids,
cholesterol and fat from the small bowel. Am. J. Clin. Nutr. 59 : 785
Anggorodi, R. l979. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT. Gramedia, Jakarta
Anggorodi, R. l985. Kemajuan Mutakhir dalam Ilmu Makanan Ternak Unggas.
Universitas Indonesia Press., Jakarta.
Anonymous. l992. Wawasan lingkungan dan bioteknologi. Infovet no. 004,
Agustus-Oktober l992, Hal : 24-26
Annison, G. 1993. The role of wheat non starch polysaccharides in broiler
diets. Aust. J. Agric. Res. 44 : 405 – 422
Arafa, A. S., R. J. Bloomer, H. R. Wilson, C. F. Simpson and R. H. Harms.
1981. Susceptibility of various poultry species to dietary aflatoxin. Brit.
Poult. Sci. 22 : 431-436.
Arsyad, M. H. Syam, dan R. Islamiyati. 2001. Kandungan kalsium dan fosfor
buah kakao yang difermentasi dengan EM-4 pada berbagai lama
penyimpanan. Buletin Nutrisi dan Makanan Ternak, Fapet Unhas 2 (1) :
1 – 10.
Asplin, F. D., and R. B. A. Carnaghan. 1961. The toxicity of certain groundnut
meals for poultry with special reference to their effects on ducklings and
chickens. The Veterinary Record 73 : 1215-1219.
Atkinson, D. 1995. Effect of temperature on the size of aquatic exothermic:
Exemption to the general rule. J. of Thermal Biol. 20: 61-74.
Bahri, S. R. Maryam, R. Widiastuti dan P. Zahari. 1995. Aflatoksikosis dan
cemaran aflatoksin pada pakan serta produk ternak. Prosiding Seminar
Nasional Peternakan dan Veteriner. Cisarua, Bogor. 7-8
November1995. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. p:
95-106.
Bangun, A. P., dan B. Sarwono. 2002. Khasiat dan Manfaat Mengkudu. Agro
Media Pustaka, Jakarta
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 52
53
Bidura, I.G. N. G. 2007. Aplikasi Produk Bioteknologi Pakan Ternak. Udayana
University Press, Universitas Udayana, Denpasar.
Bidura, I.G. N. G., I. B. Gaga Partama, dan T. G. O. Susila. 2008. Limbah,
Pakan Ternak Alternatif dan Aplikasi Teknologi. Udayana University
Press, Universitas Udayana, Denpasar.
Bidura, I.G. N. G. dan I. K. Ramia. 2004. Pengaruh pemberian rumput laut
sebagai sumber serat terlarut dalam ransum terhadap penampilan dan
akumulasi lemak tubuh Itik Bali. Laporan Penelitian, Fakultas
Peternakan, Universitas Udayana, Denpasar.
Bidura, I.G. N. G. dan I. K. Ramia. 2004. Pengaruh penggunaan agar dalam
ransum terhadap penampilan, karkas, perlemakan, dan kolesterol darah
itik Bali jantan umur 2-8 minggu. Laporan Penelitian, Fakultas
Peternakan, Universitas Udayana, Denpasar.
Bidura, I.G. N. G., dan I N. Suwidjayana. l997. Pemanfaatan Tepung Daun
Bawang Putih (Allium sativum) dan Serbuk Gergaji Kayu dalam Ransum
Terhadap Produksi dan Kadar Kolesterol Telur Ayam. Laporan
Penelitian. Fapet. Unud.-Ditbinlitabmas, Dikti., Jakarta.
Bidura, I.G. N. G. dan A. W. Puger. 2003. Pengaruh penggunaan tepung daun
duckweed dalam ransum terhadap penampilan itik Bali jantan umur 0-8
minggu. Laporan Penelitian, Fakultas Peternakan, Universitas Udayana,
Denpasar.
Bidura, I.G. N. G. dan N. N. Candraasih, K. 2004. Pengaruh pemberian ekstrak
daun asem dan ekstrak daun katuk melalui air minum terhadap
pertambahan berat badan, abdominal-fat, dan kolesterol total plasma
ayam broiler umur 2-6 minggu. Laporan Penelitian, Fakultas Peternakan,
Universitas Udayana, Denpasar
Bidura, I.G. N. G. dan I. N. Suwidjayana. 1998. Khasiat Tepung Jerami
Bawang Putih (Allium sativum) Menurunkan Kandungan Lemak dan
kolesterol Karkas Itik. Laporan Penelitian BBI, Dirjen Dikti, Fapet. Unud.,
Denpasar
Bidura, I G. N. G., dan I N. Suwidjayana. l997. Pemanfaatan Tepung Daun
Bawang Putih (Allium sativum) dan Serbuk Gergaji Kayu dalam Ransum
Terhadap Produksi dan Kadar Kolesterol Telur Ayam. Laporan
Penelitian. Fapet. Unud.-Ditbinlitabmas, Dikti., Jakarta.
Block, E. l985. The Chemistry of Garlic and Onions. Scientific America 252 : 94-
l00
Bradshaw, A. D. 1965. Evolutionary significance phenotypic plasticity in
plants. Adv. Genet. 13: 115 - 155.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 53
54
Brakefield, P. M. and Reitsma. 1991. Phenotypic plasticity, seasonal climate
and the population biology of Bacillus butterflies (Satiradie) in Malawi.
Ecol. Entomology 16: 291-303.
Bumpuss, J. A. and S. D. Aust. 1987. Biodegradation of Environmental
Pollutans by The White Rot Fungus Phanerochaete chrysosporium :
Involvement of The Lignin Degrading System. Biossyas 6 : 166 – 170
Bodwell, C. E., and J. H. Erdman. 1988. Nutrient Interaction. Marcel Dekker,
Inc., Madison Avenue, New York.
Cavallito, C. J., J.B. Bailey and J. Buck. l959. American Chemistry. W. H.
Freeman and Co., San Francisco
Cheeke, P. R. and R. S. Lee. 1985. Natural Toxicant in Feed and Poisoning
Plants. The Avi Publishing Inc. Westport, Connecticut.
Chen, D. 2001. Biotechnologies for improving metabolism and growth, A review.
Asian-Aust. J. Anim. Sci. 14 (12) : 1794 – 1802
Chen, C., A. M. Pearson, T. H. Coleman, J. J. Pestka and S. D. Aust. 1984.
Tissue deposition and clearance of aflatoxin from broiler chikens fed a
contaminated diet. Food Chem. Toxic. 22: 447-451.
Chin, D. T. F. and R. I. Hutagalung. 1985. Incidence of aflatoxin contaminated
feed and its effects in animal production in tropics. Proc. The 3rd AAAP
Anim. Sci. Congress 2: 680-682.
Choct, M. 1997. Feed enzymes; current and future aplication. In: 11th annual
Asia Pacific Lecture Tour. 73-82.
Cieglar, A., S. Kadis and J. A. Samuel. 1971. Microbial Toxic. Vol. VI.
Academic Press. New York.
Coombs, J. 1995. Dictionary of Biotechnology. Elsevier, New York.
Culvenor, C. C. J. 1974. The hazard from toxic fungi in Australia. Aust. Vet.
J. 50: 69-78.
Diener, V. L. and Davis, N. D. 1969. Aflatoxin Formation by Aspergillus flavus
in : L. A. Golded. Aflatoxin. Academic Press. New York.
Dixon, R. C., L. A. Nelson and P. B. Hamilton. 1982. Dose response
relationship during aflatoxicosis in young chickens. Toxicol. Appl.
Pharmacol 64 : 1-9.
Elfawati. 2006. Pengaruh pemakaian tepung umbi talas (Xanthosoma
sagittifolium) dan penambahan metionin dalam ransum puyuh periode
pertumbuhan. Jurnal Peternakan Vol. 3 No. 1 : 10 – 18
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 54
55
Ensminger, M. E., J. E. Oldfield and W. W. Heinemann. 1990. Feeds and
Nutrition. The Ensminger Publ. Co. California.
Ensminger, A. H., M. C. Ensminger, J.E . Konlande and J. R. K. Robson. 1983.
Foods and Nutrition Encyclopedia. Vol. 2. Pegus Press, Clovis,
California, USA.
Fahn, A. 1982. Anatomi Tumbuhan. Diterjemahkan oleh Soediareta, A. Edisi
Ke Tiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Ferket, P. R., and T. Middelton. 1999. Antinutritive in feedstuffs. Poultry
International, March, 1999. 38 (3) : 46 – 55
Fischer, J. R., A. V. Jain. D. A. Shipes, and J. S. Osborne. 1995. Aflatoxin
contamination of corn used as bait for deer in the Southeastern United
States. J. of Wildlife Disease 31: 570-572.
Garlich, J. D., H. T. Tung and P. B. Hamilton. 1973. The effect of short term
feeding of aflatoxin on egg production and some plasma constituents of
the laying hen. Poult. Sci. 52: 2206-2211.
Ghosh, S. P., T. Romanujan, J. S. Jos, S. N. Moorthy and R. G. Nair. 1988.
Tuber Crops. Oxpord & IBH Publishing Co. PVT, New Delhi.
Giambrone, J. J., U. L. Diener, N. D. Davis, V. S. Panangala and F. J. Hoerr.
1985. Effects of purified aflatoxin on broiler chickens. Poult. Sci. 64: 852-
858.
Gillespie, J. H. and M. Turrelli. 1989. Genotype-environment interaction and
the maintenance of polygenic variation. Genetics, 121: 129-138.
Ginting, N.G. 1983. Sumber aflatoksin dan pengaruhnya pada pertumbuhan
ayam pedaging. Laporan kedua. Balai Penelitian Veteriner. Bogor.
Golblatt, L. A. 1969. Aflatoxin: Scientific Background, Control and Implications.
Academic Press. New York.
Han, I. K., J. H. Lee, X. S. Piao, and D. Li. 2001. Feeding and management
system to reduce environmental pollution in swine production. Asian-
Aust. J. Anim. Sci. 14 : 432 – 444
Harbone, J.B. 1987. Metode Fitokimia. Edisi Kedua, Diterjemahkan Oleh K.
Padmawinata dan I. Soediro. Penerbit ITB, Bandung.
Harianto. l996. Manfaat serat makanan. Sadar Pangan dan Gizi Vol. 5 (2) : 4-5
Heathcote, J. and J. R. Hibbert. 1978. Aflatoxin : Chemical and Biological
Aspect. Elsevier. Amsterdam.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 55
56
Hegazy, S. M., A. Azzam, and M. A. Gabal. 1991. Interaction of naturally
occurring aflatoxins in poultry feed and immunization against fowl
cholera. Poult. Sci. 70: 2425-2428.
Hernaman, I., T. Toharman, W. Manalu, dan P. I., Pudjiono. 2007. Efektivitas
asam asetat dalam ekstraksi asam fitat pollard. Media Peternakan.
Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Peternakan 30 (2) : 114 – 118
Hetzel, D. J. S., dan Irawan. 1979. The effect of aflatoxin on growing ducks.
Laporan Seminar Ilmu dan Industri Perunggasan II. Pusat Penelitian dan
Pengembangan Ternak, Ciawi. Bogor.
Huff, E. W., L. F. Kubena, R. B. Harvey, D. E. Corrier and H. H. Mollenhaver.
1986. Onset of aflatoxin in broiler chickens. Poult. Sci. 65: 60.
Idouraine, A., M. J. Khan and C. W. weber. 1996. In Vitro binding capacity of
wheat bran, rice bran, and oat fiber for Ca, Mg, Cu, and Zn alone and in
different combinations. J. Agric. Food Chem. 44 : 206 – 2072.
Iji, P. A. 1999. The Impact of Cereal Non-Starch Polysaccharides on Intestinal
Development and Function in Broiler Chickens. Worlds Poult. Sci.
Journal 55 (4) : 375 – 387
Jain, R. G., and D. B. Konar. l98l. Blood Sugar Lowering Activity of Garlic
(Allium sativum). Medikon l977, VI : 3-l5
Jhori, T. S., and P. N. Sharma. 1979. Studies on utilization of dried Duckweed
(Lemna minor) in chicks. Indian Journal Poult. Sci. 14 : 14 – 18
Jones, F. T., W. H. Hagler and P. B. Hamilton. 1982. Association of low levels
of aflatoxin in feed with productivity losses in commercial broiler
operation. Poult. Sci. 61: 861-868.
Jufri, S. M. 1987. Pengaruh ekstrak Umbi Bawang Merah (Allium cepa)
Takaran 250 mg/kg Berat Badan Terhadap Penurunan Kadar Gula
Darah Normal Kelinci. Laporan Penelitian, Jurusan Farmasi FMIPA,
UNHAS, Ujung Pandang
Kamal, M. Dan M. Murdhika. 1983. Kemungkinan Pemanfaatan Eceng
Gondok sebagai Sumber konsentrat protein daun (Leaf Protein
Concentrate) untuk Pengganti kedelai dalam Ransum Ayam. Laporan
penelitian, Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Karyadi, E. l997. Khasiat fitokimia bagi kesehatan. Harian Kompas, Minggu, 20
Juli l997. Hal : l5, Kol : 1-7, PT. Gramedia, Jakarta.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 56
57
Kriswiyanti, E., N. M. Puspawati, N. N. Darsini, N. W. Bogoriani, dan I.G.M.O.
Nurjaya. 1997. Identifikasi, Struktur Anatomi dan Studi Pendahuluan
Golongan Senyawa Kimia Daun Pelengkap Bumbu Lawar dan Betutu.
Laporan Penelitian, FMIPA, UNUD, Denpasar
Leng, R. A., J. H. Stambolie and R. Bell. 1995. Duckweed a potential high
protein feed resource for domestic animals and fish. In: Livestock
Research For Rural Development Vol. 7 No. 1.
Linder, M. C. 1985. Biokimia Nutrisi dan Metabolisme. Ed. II. Penterjemah A.
Parakkasi. Penerbit UI., Jakarta.
Littlefield, L. H. 1976. Mycotoxins in poultry feed. Poultry Nutrition Short
Course Proceeding. 13-20.
Lloyd, L. E., B. E. McDonald and E. W. Crampton. l978. The Carbohidrates
and Their Metabolism. In : Fundamental of Nutrition. 2 nd Ed. W.H.
Freman and Co., San Francisco.
Mahmilia, F. 2005. Perubahan nilai gizi tepung eceng gondok fermentasi dan
pemanfaatannya sebagai ransum ayam Pedaging. JITV 10 (2) : 90 – 95
Maksudi. 2000. Quantitative oxidation on nutrients in broiler treated with -
agonist L-644,969. Bulletin of Animal Sci. 24 (3) : 94 – 102
Malik, Z.A. and S. Siddique. l98l. Hypotensive effect of freeze dried garlic
(Allium sativum). SAP. In : Dog. JPMA. 31 : 12-13
McDonald, P., R.A. Edwards, J. F. D. Greenhalgh, and C.A. Morgan. 1995.
Animal Nutrition. Jhon Wiley and Sons, New York.
Men, B.X., B. Ogle, and J.E. Linberg. 2001. Use of duckweed as a protein
supplement for growing ducks. Asian-Aust. J. Anim. Sci.14 (12) : 1741-
1746
Nurhayati, Nelwida, dan Marsadayanti. 2005. Pengaruh penggunaan tepung
buah engkudu dalam ransum terhadap bobot karkas broiler. Jurnal
Pengembangan Peternakan Tropis Vol. 3 No. 2 : 96 – 101
Nye, A. R. l990. Garlic and Health. Medical Progress No. : l7, August : 7-l0.
Ochetim, S. 1993. The Effects of partial replacement of soybean meal with
boiled fether meal on the performance of broiler chickens. AJAS. 6 (4) :
597 – 600
Parakkasi, A. 1983. Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik. Penerbit
Angkasa, Bandung.
Parry, J. W. 1969. Spices. Vol. II. Publishing Co. Inc. New York.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 57
58
Piliang, W. G. 1997. Strategi Penyediaan Pakan Ternak Berkelanjutan Melalui
Pemanfaatan Energi Alternatif. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu
Nutrisi, Fapet IPB, Bogor
Plummer, D. T. l977. An Introduction to Practical Biochemestry. McGraw-Hill
Book Co., Ltd. New Delhi.
Radjiman, D. A., T. Sutardi, dan L. E. Aboenawan. 1999. Efek Substitusi
Rumput Gadjah dengan Eceng Gondok dalam Ransum Domba terhadap
Kinerja proses Nutrisi dan Pertumbuhan. Laporan Penelitian, Fakultas
Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
Richardson, C. R. 2005. Quality Control in Feed Production. The Center for
Feed Industry Research and Education. Dept. Animal Science and Food
Technology,Texas Tech University. Lubbock, Texas.
www.asft.ttu.edu/cfire/reserc.htm
Santoso. 1993. Fisiologi Tumbuhan. Fakultas Biologi. Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Santoso, U. 2000. Mengenal daun katuk sebagai feed additive pada broiler.
Poultry Indonesia, Juni/Nomor 242 : 59 – 60
Santoso, U. 2000. Pengaruh pemberian ekstrak daun keji beling (Strobilanthes
crispus BL.) terhadap performans dan akumulasi lemak pada broiler.
Jurnal Peternakan dan Lingkungan 6 (2) : 10 – 14
Santoso, U. 2005. Pengaruh pemberian ekstrak daun katuk dalam ransum
terhadap produksi, kadar nitrogen dan fosfor, dan jumlah koloni mikrobia
pada feses ayam petelur. Jurnal Pengembangan Peternakan Tropis Vol.
30 (4) : 237-241
Sikder, A. C., S. D. Chowdhuri, M. H. Rashid, A. K. Sarker and S. C. Das. 1998.
Use of dried carrot meal (DCM) in laying hens diets for egg yolk
pigmentation. Asia-Aust. J. Anim. Sci. 11 (3) : 239 – 244
Smith, J. W. and P. B. Hamilton. 1970. Aflatoxicosis in the broiler chickens.
Poult. Sci. 49: 207-215.
Sobetra, I. 1991. Pemanfaatan tepung umbi talas (Xanthosoma sp.) sebagai
makanan broiler. Tesis, Fakultas Peternakan, Universitas Andalas,
Padang.
Soekarman dan S. Riswan. 1992. Status Pengetahuan Etnobotani di
Indonesia. Perpustakaan Nasional RI dan Litbang Botani, Puslitbang
LIPI, Bogor, dalam Prosiding Seminar dan Lokakarya Nasional
Etnobotani, Cisarua, Bogor, 19 – 20 Februari LIPI dan Lembaga
Perpustakaan Nasional RI. Hal : 1 – 7
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 58
59
Speedy A. 2005. Animal Feed Safety. www.fao.org/DOCREP/005/AC801E
Sumiati. 2006. Rasio Molar asam fitat : Zn untuk Menentukan Suplementasi
ZNn dan Enzym Phytase dalam Ransum Berkadar Asam Fitat Tinggi.
Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian, Bogor
Sudibia, I M. l997. Kandungan zat kimia pada bawang merah (Allium cepa) dan
bawang putih (Allium sativum). Majalah Ilmiah UNUD. No. l5l/September
: 15-16
Sobetra, I. 1991. Pemanfaatan tepung umbi talas (Xanthosoma sp.) sebagai
makanan Broiler. Tesis, Fakultas Peternakan, Universitas Andalas,
Padang.
Sumarno. 1992. Petunjuk Laboratorium Analisis Metabolit Sekunder dengan
HPLC. PAU-Bioteknologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Syamsuhaidi. 1997. Penggunaan Duckweed (Family Lemnaceae) sebagai
Pakan Serat Sumber Protein dalam Ransum Ayam Pedaging. Thesis,
Program Pascasarjana, IPB, Bogor.
Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo dan S.
Lebdosoekojo. 1986. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada
University Press, Yogyakarta.
Trotter, D. C. 1990. Biotechnology in The Pulp Paper Industry. A Review Part
1. J. Tappi. 198 – 202
Vranjes, V. And C. Wenk. 1995. The Influences of Extruded vs Untreated
Barley in The Feed with and without dietary Enzyme Supplement on
Broiler Performance. Anim. Feed Sci. And tech. 54 : 21 – 32.
Wahyu, J. 1992. Ilmu Nutrisi Unggas. Gajah Mada University Press.
Yogyakarta.
Widiyanto, E. Pangestu, Surahmanto, F. Wahyono, dan B.I.M. Tampoebolon.
1994. Teknologi Pengolahan Pucuk Tebu Untuk Merningkatkan Daya
Gunanya Sebagai Pakan Ruminansia. Laporan Penelitian, Fapet, Undip,
Semarang.
Widodo, W. 2005. Tanaman Beracun dalam Kehidupan Ternak. UMM press,
Malang.
Wijaya, C. H. l997. Mengoptimalkan Khasiat Bawang. Harian Kompas, Minggu,
25 Mei l997, Ha : l5, Kol : 6-9. PT. Gramedia, Jakarta.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 59
60
Winarno, F. G. 1979. Fermented vegetable protein and related foods of south-
east Asia with Special reference to Indonesia. J.Anim. Oil. Chem. 56 :
363 – 366
Zahari, P. dan Tarmudji. 1995. Aflatoksikosis pada ternak itik Alabio di
Kalimantan Selatan. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Veteriner
untuk Meningkatkan Kesehatan Hewan dan Pengamanan Bahan
Pangan Asal Ternak. Cisarua, Bogor. 22-24 Maret 1994. Balai
Penelitian Veteriner. p: 408-411.
AntiNutrisi dan Hijauan Pakan Beracun pada Ternak-2017 60
Anda mungkin juga menyukai
- Bahasa Inggris Sistem 52M Volume 3Dari EverandBahasa Inggris Sistem 52M Volume 3Penilaian: 3 dari 5 bintang3/5 (3)
- Everyday IndonesianDari EverandEveryday IndonesianPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (2)
- Ikan NilaDokumen70 halamanIkan NilaMahatmakresnhaBelum ada peringkat
- Integrated Farming PDFDokumen116 halamanIntegrated Farming PDFPratama El'bantany100% (1)
- Penilaian Yang Dilakukan Oleh Guru Seharusnya Bersifat KomprehensifDokumen1 halamanPenilaian Yang Dilakukan Oleh Guru Seharusnya Bersifat KomprehensifalfanBelum ada peringkat
- Hasil Riskesdas Jabar 2018Dokumen640 halamanHasil Riskesdas Jabar 2018Puji NurulBelum ada peringkat
- Daftar IsiDokumen4 halamanDaftar IsiFebri YandiBelum ada peringkat
- Daftar Isi Buku Saku Interaksi Obat Dan MakananDokumen3 halamanDaftar Isi Buku Saku Interaksi Obat Dan MakananZulfa Ulfa FhaBelum ada peringkat
- Daftar Isi Buku Saku Interaksi Obat Dan Makanan PDFDokumen3 halamanDaftar Isi Buku Saku Interaksi Obat Dan Makanan PDFPina DeliBelum ada peringkat
- Laporan Prak PHPT Satya Panca Yudha 1904290181Dokumen40 halamanLaporan Prak PHPT Satya Panca Yudha 1904290181Satya Panca YudhaBelum ada peringkat
- Skripsi ArniasihDokumen89 halamanSkripsi ArniasihI Made Astawa Ari Putra 245Belum ada peringkat
- (LAPORAN) Aspek Biologi Ikan MasDokumen87 halaman(LAPORAN) Aspek Biologi Ikan MasMohammad Syarifudin67% (3)
- Kelompok 5 Karotenoid RevisiDokumen28 halamanKelompok 5 Karotenoid RevisiRianBelum ada peringkat
- REV 9 Pengaruh Lama Pencahayaan Dan Level Protein WendiDokumen39 halamanREV 9 Pengaruh Lama Pencahayaan Dan Level Protein WendiAhmad DanielBelum ada peringkat
- Fisiolgi Pasca Panen PDFDokumen179 halamanFisiolgi Pasca Panen PDFDevi SarvikaBelum ada peringkat
- Up - Hidroponik - Razaky Wahyu Putranto - 1610631090128 - Kelas 7DDokumen36 halamanUp - Hidroponik - Razaky Wahyu Putranto - 1610631090128 - Kelas 7DRafid RakeriBelum ada peringkat
- Farid Aswan (Pengaruh Frekuensi Penyiraman Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Kacang Tunggak)Dokumen46 halamanFarid Aswan (Pengaruh Frekuensi Penyiraman Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Kacang Tunggak)fareed_84100% (2)
- Studi Literatur Efek Farmakologi Ekstrak Daun JAMBU AIR (Syzygium Samarangense)Dokumen45 halamanStudi Literatur Efek Farmakologi Ekstrak Daun JAMBU AIR (Syzygium Samarangense)Ardina Mariana PakpahanBelum ada peringkat
- CoverDokumen13 halamanCoverOvViq ThecyberBelum ada peringkat
- Proposal ELSI TERBARUDokumen71 halamanProposal ELSI TERBARUelsi isneini runandaBelum ada peringkat
- PDF Daun Bunga KertasDokumen43 halamanPDF Daun Bunga KertasAugia Hernita pasaribuBelum ada peringkat
- Buku Jamur Patogen Terbawa Tanah PDFDokumen238 halamanBuku Jamur Patogen Terbawa Tanah PDFJonoSoeparjonoBelum ada peringkat
- Sampul Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kentang G-2 (Solanum Tuberosum L.) Terhadap Dosis Pupuk Kotoran Ayam Dan Kotoran Sapi Hasil FermentasiDokumen11 halamanSampul Respon Pertumbuhan Dan Produksi Tanaman Kentang G-2 (Solanum Tuberosum L.) Terhadap Dosis Pupuk Kotoran Ayam Dan Kotoran Sapi Hasil FermentasiAli HussainBelum ada peringkat
- Keracunan Alergi Dan Intoleran Makanan 230801 215611Dokumen7 halamanKeracunan Alergi Dan Intoleran Makanan 230801 215611Rina PratiwiBelum ada peringkat
- Juknis Pestisida NabatiDokumen75 halamanJuknis Pestisida NabatiDevi Citra RastutiBelum ada peringkat
- KAJIAN SENYAWA BIOAKTIF EKSTRAK BULU BABI (Diadema Setosum) Sebagai Anti Bakteri Terhadap Bakteri Escherichia Coli Dan Bacillus CereusDokumen39 halamanKAJIAN SENYAWA BIOAKTIF EKSTRAK BULU BABI (Diadema Setosum) Sebagai Anti Bakteri Terhadap Bakteri Escherichia Coli Dan Bacillus CereusNindya Riesmania PratiwiBelum ada peringkat
- Kelompok 2 MAKALAH BOTFAR RevisiDokumen79 halamanKelompok 2 MAKALAH BOTFAR RevisiSunani AldehidaBelum ada peringkat
- Proposal Devi FixDokumen97 halamanProposal Devi FixAfif PusamaniaBelum ada peringkat
- Daftra Isi NugrohoDokumen3 halamanDaftra Isi NugrohoAnnisha WidyasariBelum ada peringkat
- Modul Variasi Menu Balita StuntingDokumen42 halamanModul Variasi Menu Balita StuntingAnitaBelum ada peringkat
- Buku GulmaDokumen8 halamanBuku GulmaDerry Bunga TulipBelum ada peringkat
- Maju Kalo BeraniDokumen42 halamanMaju Kalo BeraniEster LusianaBelum ada peringkat
- Skripsi IstiDokumen67 halamanSkripsi Istisiti istiqomahBelum ada peringkat
- Laprak Agroekologi A2 Sm1 Kel b4Dokumen30 halamanLaprak Agroekologi A2 Sm1 Kel b4Rizqi RizalddinBelum ada peringkat
- Daftar Isi SkripsiDokumen7 halamanDaftar Isi Skripsisepri yadiBelum ada peringkat
- Fix Rezti Laporan Akhir Praktikum TptorDokumen40 halamanFix Rezti Laporan Akhir Praktikum TptorZandra AndraBelum ada peringkat
- Rahmidyahp 1 2Dokumen8 halamanRahmidyahp 1 2pokja madinaBelum ada peringkat
- Laporan PKPA BMG PDFDokumen42 halamanLaporan PKPA BMG PDFMax KwangminBelum ada peringkat
- PDF of Mikroba Potensial Dalam Pengendalian Biologi Patogen Tumbuhan Mengenal Mikroba Sahabat Petani I Ketut Suada Full Chapter EbookDokumen69 halamanPDF of Mikroba Potensial Dalam Pengendalian Biologi Patogen Tumbuhan Mengenal Mikroba Sahabat Petani I Ketut Suada Full Chapter Ebookaueyturkmen728100% (5)
- Laporan Ilmu Nutrisi Ternak HabibDokumen41 halamanLaporan Ilmu Nutrisi Ternak HabibMoh ikbal Dwi PutraBelum ada peringkat
- Daftar Isi - BAB IDokumen11 halamanDaftar Isi - BAB IHady Saeful RaillahBelum ada peringkat
- Karya TulisDokumen25 halamanKarya TuliskristianaendangpalupiBelum ada peringkat
- Ikan Ekor KuningDokumen68 halamanIkan Ekor Kuningnanda_rizkyBelum ada peringkat
- Laporan Individu PKL TB 1Dokumen37 halamanLaporan Individu PKL TB 1doctor TailsBelum ada peringkat
- BAB I-BAB II-BAB III Rani Lengkap Daftar IsiDokumen31 halamanBAB I-BAB II-BAB III Rani Lengkap Daftar IsiAfikah ChikaBelum ada peringkat
- 6 Des SETELAH SEMPRODokumen44 halaman6 Des SETELAH SEMPROOvyana Nur QoriahBelum ada peringkat
- RAMA 54321 05041381520034 0005037303 0019068502 01 Front RefDokumen18 halamanRAMA 54321 05041381520034 0005037303 0019068502 01 Front RefSesar FajarBelum ada peringkat
- Konservasi - Hijauan - Pakan UGMDokumen17 halamanKonservasi - Hijauan - Pakan UGMJaya Wilastra NasrizalBelum ada peringkat
- BAHAN BAGUS DOSIS TEPAT DAUN SALAM-dikonversiDokumen95 halamanBAHAN BAGUS DOSIS TEPAT DAUN SALAM-dikonversiNurdiana Tandi PareBelum ada peringkat
- Parasit Dan Penyakit Pada IkanDokumen19 halamanParasit Dan Penyakit Pada Ikansiti zahra riandiBelum ada peringkat
- Uji Aktivitas Sediaan Gel Facial Wash Ekstrak Daun Kemangi Terhadap Bakteri P. AcneDokumen52 halamanUji Aktivitas Sediaan Gel Facial Wash Ekstrak Daun Kemangi Terhadap Bakteri P. AcneEustas D PickBelum ada peringkat
- Laporan ArkhanDokumen23 halamanLaporan ArkhanFikri HaikalBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Ipit Revisi NewDokumen47 halamanProposal Penelitian Ipit Revisi NewDara PonselBelum ada peringkat
- Proposal Uji KesukaanDokumen40 halamanProposal Uji KesukaanSitifatimah rahmaBelum ada peringkat
- Proposal Tiara ZahrahDokumen45 halamanProposal Tiara Zahrahvadvad0044Belum ada peringkat
- ANALISIS ASPEK BIOLOGI IKAN KembungDokumen63 halamanANALISIS ASPEK BIOLOGI IKAN KembungheldiBelum ada peringkat
- Proposal Irene Tanod FiXDokumen37 halamanProposal Irene Tanod FiXShort Movie TVBelum ada peringkat
- Cover Makalah FarmasiDokumen4 halamanCover Makalah Farmasisistri ajeng gmBelum ada peringkat
- Kimia Proyek Nutrisi Ab Mix Pasti Fix BangetDokumen39 halamanKimia Proyek Nutrisi Ab Mix Pasti Fix BangetnurmalaniBelum ada peringkat
- PendahuluanDokumen22 halamanPendahuluanaditya speedBelum ada peringkat
- LAPORAN KASUS ILMU PENYAKIT MULUT RAS - Sildha 160112190099 - Rev1Dokumen70 halamanLAPORAN KASUS ILMU PENYAKIT MULUT RAS - Sildha 160112190099 - Rev1puspita witriaBelum ada peringkat
- DikonversiDokumen5 halamanDikonversialfanBelum ada peringkat
- PROMES Fiqih Kelas 9 Semt 1Dokumen2 halamanPROMES Fiqih Kelas 9 Semt 1alfanBelum ada peringkat
- DikonversiDokumen19 halamanDikonversialfanBelum ada peringkat
- Rencana Pelaksanaan Pembelajaran: Menyimpulkan Hasil Analisis Data Percobaan Termokima Pada Tekanan TetapDokumen4 halamanRencana Pelaksanaan Pembelajaran: Menyimpulkan Hasil Analisis Data Percobaan Termokima Pada Tekanan TetapalfanBelum ada peringkat
- LKPD Laju Reaksi 11 PDF Free DikonversiDokumen9 halamanLKPD Laju Reaksi 11 PDF Free DikonversialfanBelum ada peringkat
- RPP 10 MenitDokumen1 halamanRPP 10 MenitalfanBelum ada peringkat
- Penerapan Sekolah AdiwiyataDokumen11 halamanPenerapan Sekolah AdiwiyataalfanBelum ada peringkat
- 2315201005-Master Thesis PDFDokumen100 halaman2315201005-Master Thesis PDFalfanBelum ada peringkat
- Pemanfaatan Limbah Ampas KopiDokumen16 halamanPemanfaatan Limbah Ampas Kopialfan100% (1)
- RPP Praktikum Kimia Anorganik2Dokumen12 halamanRPP Praktikum Kimia Anorganik2alfanBelum ada peringkat