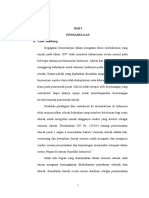Penataan Daerah Sebagai Penataan Institusi Laila Nova 2007-With-cover-page-V2
Diunggah oleh
Fauzia HoerunnisaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Penataan Daerah Sebagai Penataan Institusi Laila Nova 2007-With-cover-page-V2
Diunggah oleh
Fauzia HoerunnisaHak Cipta:
Format Tersedia
Accelerat ing t he world's research.
Penataan Daerah sebagai Penataan
Institusi ( July 2007)
Laila Alfirdaus
Related papers Download a PDF Pack of t he best relat ed papers
Penat aan daerah sebagai penat aan inst it usi
Laila Kholid Alfirdaus, Longgina N Bayo
Polit ik Hukum Pemekaran Daerah
Bilal Dewansyah
Ot onomi Daerah Unt uk Penguat an NKRI
Kardiansyah Afkar
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
Penataan Daerah sebagai Penataan Institusi
Laila Kholid Alfirdaus
Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro
Longgina Novadona Bayo
Dosen Jurusan Politik & Pemerintahan, FISIPOL Universitas Gadjah Mada
Abstrak
Pengertian territorial reform tidak hanya terbatas pada pemekaran, pemecahan,
maupun penggabungan wilayah. Ada aspek yang lebih penting pada territorial reform
dari yang sekedar berurusan dengan batas wilayah, yaitu penguatan kapasitas
institusi. Ini penting untuk menjadi substansi reform itu sendiri karena pada dasarnya
setiap perubahan teritori dan batas wilayah selalu memiliki konsekuensi institusional,
baik yang menyangkut administrasi publik–government, maupun konstituen. Oleh
karena itu, penguatan kapasitas governance di daerah yang baru terbentuk menjadi
sangat krusial, dengan cara membangun sinergi dan konsolidasi antar elemen dalam
governance–government, market, civil society. Kapasitas governance menjadi
penting bagi daerah baru, bukan saja diorientasikan bagi kepentingan lokal, tetapi
lebih jauh dalam interaksinya dengan institusi nasional dan internasional, meski
disadari, seringkali gerakan pemekaran pada awalnya bersifat penegasan identitas
dan didorong oleh nilai-nilai kelokalan.
Kata kunci: territorial reform, batas wilayah, konsekuensi institutional, penguatan kapasitas
governance, sinergi, konsolidasi.
Latar Belakang
Territorial reform atau penataan wilayah, dalam pengertian yang sempit mencakup
pemekaran daerah (USAID, 2006, p. 5), yaitu pembentukan, penggabungan, maupun pemecahan
suatu wilayah menjadi wilayah-wilayah baru yang berdiri sendiri dalam sebuah wilayah negara.
Terkait erat dengan pengertian ini adalah political geography dan politics of land ownership. Tetapi,
pada dasarnya terdapat pengertian yang lebih luas dari sekedar pemekaran yang fokusnya terletak
pada garis batas wilayah (border), yaitu penataan kelembagaan pemerintahan, mencakup struktur
dan sumberdaya, serta penataan hubungan lembaga pemerintahan dengan institusi-institusi non-
pemerintah, yang terdiri dari market dan civil society dalam kerangka governance. Pengertian
territorial reform sebagai institutional bulding and reform menjadi begitu penting karena setiap
pembentukan, pemisahan dan penggabungan wilayah baru selalu memiliki konsekuensi
institusional.
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 1
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
Dengan demikian, pemekaran sebagai salah satu pengertian dari territorial reform hanya
menjadi jembatan bagi penataan (reform) yang lebih jauh. Dalam pengertian inilah daerah-daerah
yang tidak memekarkan diri juga dapat dikatakan bisa melakukan territorial reform. Pertanyaan
penting yang kemudian mengikuti pengertian territorial reform sebagai institutional building and
reform adalah dengan cara bagaimana menata ulang lembaga pemerintahan? Akan mencakup apa
saja? Adakah perbedaan mendasar pola penataan (reform pattern) antara daerah yang
memekarkan diri dan yang tidak? Bagaimana mensinergikan hubungan antara lembaga
pemerintahan, civil society dan atau lembaga non-pemerintah lainnya di tengah rapuhnya lembaga
pemerintah dalam payung governance? Apakah mungkin? Apakah tidak terdengar sangat ambisius?
Sederet pertanyaan tersebut memang akan memancing sederet jawaban yang sangat
normatif. Tetapi, lesson-learning dan lesson-drawing dengan segala kelebihan dan kekurangannya
tetap menjadi bagian yang penting bagi penata-ulangan pemerintahan. Makalah ini mencoba
berbicara tentang territorial reform dalam pengertian tersebut dengan mendasarkan diri pada
kajian Chalmer Johnson, Amartya Sen, dan beberapa pengkaji yang lain. Bagian-bagian dalam
makalah ini kurang lebih mencakup: (i) Territorial reform: secession, partitionism dan
amalgamation; (ii) Territorial reform: lebih dari sekedar pemekaran wilayah; (iii) Institutional
building and reform: penataan struktur dan sumberdaya (resources); (iv) Menata daerah yang baru
dan yang lama; (v) Mensinergikan hubungan lembaga pemerintahan dan non-pemerintah.
Territorial reform untuk menguatkan kapasitas daerah dalam menjawab tantangan global
dan lokal. Dengan demikian, bidikan utama dari reform adalah untuk membangun struktur dan
sumberdaya pemerintahan yang efektif sehingga bisa lebih akomodatif terhadap aspirasi dan
partisipasi civil society, pressure groups, pelaku-pelaku usaha dan lain-lain. Local governance, di
tengah menguatnya keinginan untuk memberdayakan potensi dan identitas masyarakat lokal juga
mesti peduli (aware) dengan kondisi, perkembangan dan tantangan masyarakat global. Untuk
itulah, mereformasi institusi dalam rangka mereformasi daerah menjadi sangat penting.
Territorial Reform: Secession, Partitionism, dan Amalgamation
Territorial reform dalam pengertiannya dengan batas wilayah berhubungan dengan
pemodifikasian luas dan pembentukan daerah baru sebagai sub dalam sebuah negara.
Penjabarannya mencakup secession, partitionism, dan amalgamation yang berkaitan erat dengan
pemekaran, pemecahan, dan penggabungan wilayah. Penjelasan territorial reform sebagai hal yang
berkaitan dengan batas wilayah, adalah sebagai berikut.
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 2
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
Seccession
Perhatian terhadap teori-teori tentang secession berkembang pada tahun 1990-an. Dalam
literatur ilmu politik, secession didefinisikan sebagai wilayah teritorial sebuah komunitas yang
memisahkan diri (bekas) dari sebuah negara dan membangun wilayahnya sendiri menjadi entitas
yang mempunyai kedaulatan politik sendiri (Caney 1998 dalam Conversi, 2000, h. 334). Secession
dalam pengertian asalnya ini merupakan sebuah gerakan yang berkembang di tingkat lokal untuk
melawan (baca: memisahkan diri) pusat, dan biasanya bertujuan membentuk sebuah negara
sendiri. Seperti analogi “perceraian”, secession diamini sebagai tindakan akhir dari alienasi
(Premdas 1990 dalam Conversi, 2000, h. 334).
Ada 3 faktor pendorong mengapa suatu wilayah atau komunitas mengambil jalan secession
(Erlingsson, 2005, hal. 145-146), yakni: (1) Economic driven, the seccesion of the rich: suatu daerah
yang memiliki income per kapita yang tinggi memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan
pemisahan demi menjamin pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. (2) Cultural
driven, the borders were inappropriately drawn. (3) Political driven, relative partisan power. Sedangkan
Conversi membagi alasan secession menjadi 2, yakni ethnically driven dan territorial driven (Conversi,
2000, h. 334).
Dalam perjalanan sejarah negara bangsa modern di dunia, ethnically driven, atau lebih luas
lagi identity driven, lebih sering dijadikan rujukan alasan untuk secession, sebagaimana dijelaskan
oleh Keating (2001, hal. 49-76). Analisis yang sering muncul lebih terbatas pada kasus kemunculan
etno-nasionalism yang menjadi dorongan kemudian untuk melakukan secession. Ethnic secessionism
kemudian menjadi tren politik dan tujuan dari secession itu sendiri. Disinilah nampak kegagalan
negara mengembangkan civic-nationalism. Gagasan akan secession ini dimaknai sebagai sebuah
respon politik terhadap penguatan identitas yang terjadi pada aras lokal. Dengan kata lain, gagasan
tentang secession hanya merupakan bagian dari politik pengelolaan dan penataan teritorial
(territorial reform).
Sebagai sebuah tren politik, sedikitnya ada 4 aspek yang menjadi basis kriteria dalam
melakukan secession, antara lain sebagai berikut (Conversi, 2000, h. 334): (i) Antagonist atau
oppositional legitimacy, berupa serangan terhadap legitimasi akan keberadaan negara, dengan
mengambil sikap berdiri diluar struktur Negara; (ii) Anti-constitutionalism, berupa dorongan
radikal untuk mengubah tatanan konstitusi negara yang bersangkutan; (iii) Ethnicism, merupakan
pandangan yang menganggap kesatuan etnis sebagai nilai tertinggi, superoritas adalah nilai dari
sebuah Negara; (iv) Irredentism, berupa tekanan terhadap territorial reunification bagi satu etnis
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 3
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
tertentu dalam satu homeland. Keempat faktor diatas menjadi embrio dan senjata politik bagi
kelahiran secession. Semuanya dapat ditemui di hampir setiap gerakan separtisme.
Semua argumen yang dibangun diatas mengasumsikan bahwa hasrat untuk mengambil
jalan secession berasal dari aras lokal (peripheral seccession. Tapi secession juga bisa karena
rekayasa negara. Dalam teori tentang seceesion sendiri, ada 3 pendekatan yang dipakai dalam
menjelaskan kelahiran sebuah negara baru (Conversi, 2000, h. 335), yaitu: (1) dissolution, meliputi
pecahnya sebuah kerajaan dan adanya proses de-colonisation. (2) peripheral secessionism, misal
Bangladesh, Eritrea. (3) secessionism by the centre, misal Serbia, dengan atau tanpa Montenegro.
Ketiganya bisa terjadi secara simultan, tetapi ketiganya akan lebih berguna jika dibedakan. Tapi
yang patut menjadi perhatian adalah pada darimana ide inisiasi untuk melakukan disintegratif
tersebut muncul. Jika dissolution dapat terjadi dalam keadaan dimana ada keabsenan nasionalisme,
maka sebaliknya secession, khususnya ethnic secession, baik itu karena peripheral driven maupun
central driven, justru terjadi karena dorongan etno-nasionalisme dan tidak dapat bekerja tanpa
ruang primordialisme tersebut.
Partitionism
Dalam kaitannya dengan politik, political partitions diartikan sebagai pembagian kesatuan
teritorial ke dalam dua atau lebih bagian-bagian, yang ditandai dengan garis batas (border),
terkodifikasi dalam peta baru, dan dapat dioperasionalisasikan, misal ada garis pembatas, dan
kemungkinan tanda pembatas tersebut bisa berupa pagar, dinding, dan kawat berduri, dimana
untuk memasuki wilayah tersebut dibutuhkan surat ijin bahkan paspor (O’Leary, 2006). Secara
khusus lagi, political partition didefinisikan sebagai pemotongan garis batas wilayah pada
sedikitnya satu komunitas nasional homeland yang kemudian menciptakan pemisahan menjadi
paling sedikit dua unit politik dibawah kedaulatan atau kewenangan yang berbeda (O’Leary, 2001,
h. 54). Tujuan dari political partition ini adalah untuk mengatur dan menyelesaikan konflik baik
konflik nasional, etnik, maupun konflik komunal.
Di kalangan ilmuwan politik sendiri istilah partition dan secession masih menjadi
perdebatan. Ada yang membedakan antara partition dengan secession, seperti Nicholas Sambanis,
namun ada juga yang mempertukarkan kedua istilah tersebut. Mendasarkan pada data dari
keseluruhan perang sipil yang terjadi sejak tahun 1944, Sambanis sendiri mendefinisikan partition
sebagai dampak dari perang yang meliputi border adjustment dan demographic changes (Sambanis
dalam oleh O’Leary, 2006, h. 7). Border adjustment terjadi dalam partition karena menghadirkan
sesuatu yang baru, border yang baru. Tetapi dalam secession yang terjadi hanyalah border
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 4
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
transformation, perpecahan pada kedaulatan entitas yang mengubah kesepakatan (internal) border
sebelumnya menjadi sovereign demarcation (O’Leary, 2006, h. 7). Sedangkan demographic changes
yang diprasyaratkan oleh Sambanis ditunjukkan dengan adanya new border sebagai outcome dari
perang tersebut.
Definisi yang dikemukakan oleh Sambanis ini sekaligus bertujuan untuk mengoreksi
kalangan ilmuwan lainnya yang masih sering mempertukarkan kedua istilah (partition &secession)
tersebut. Ilmuwan geo-politik seperti Peter Taylor misalnya, mendefinisikan partition sebagai
pembagian negara menjadi dua atau lebih teritori yang membentuk negara baru. Sementara
secession dia definisikan sebagai gerakan pemisahan teritorial dari negara (Taylor dalam oleh
O’Leary, 2006, h. 8). Namun justru definisi Taylor inilah yang banyak diadopsi oleh kalangan
ilmuwan politik.
Berbeda dengan Taylor, Alexis Heraclides mendefinisikan partition sebagai pembentukan
dua atau lebih state yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Sedangkan secession dia artikan
sebagai gerakan sepihak yang tiba-tiba menuntut kebebasan salah satu daerah yang merupakan
wilayah metropolitan, lambang kedaulatan negara, oleh karena itu bertentangan dengan negara
(Heraclides dalam O’Leary, 2006, h. 8). Dalam pandangan Heraclides ini, proses secession bisa
didahului melalui partition.
Sementara itu dari sisi dimensi sejarah, Robert Schaeffer mencoba untuk memetakan
partition yang terjadi di abad ke-20, sebagai berikut (O’Leary, 2006, h. 15): (i) partition yang terjadi
sebagai bagian dari proses dekolonisasi, seperti Irlandia, India, Palestina; (ii) partition yang terjadi
sebagai dampak dari perang dingin, seperti Jerman, Korea, Vietnam, Cina, Taiwan; (iii) partition
yang terjadi hasil keputusan kekuasaan negara tetangga, seperti Turki di Cyprus, dan di Kurdistan);
(iv) partition yang mengambil bagian pada saat sekarang sebagai hasil dari proses demokratisasi di
plurinational states, seperti pembentukan negara USSR, pembentukan negara Czechoslovakia,
Yugoslavia, dan Eithopia.
Dari beberapa paparan diatas, maka penting untuk membedakan partition dengan secession
maupun recognitition of a secession by political centre. Setidaknya ada kata kunci yang menjadi
esensi dari partition, yakni fresh border yang memotong melintasi national homeland, guna
mengatur dan menyelesaikan konflik etnik, nasional maupun konflik komunal di daerah tersebut.
Amalgamation
Berbeda dengan secession dan partitionism yang hasil akhirnya membentuk sebuah daerah
baru sehingga menghasilkan sejumlah daerah baru, amalgamation justru merupakan sebuah
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 5
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
instrumen menata daerah yang mencoba untuk melakukan penggabungan beberapa wilayah
administrasi teritorial (baik itu kabupaten/kota atau provinsi atau yang setingkat) menjadi satu.
Meskipun yang terjadi kemudian daerah yang bersangkutan secara teritori menjadi lebih luas
daripada sebelumnya sehingga beban pemerintah lokal dalam menjalankan fungsinya menjadi dua
kali lipat lebih besar, tetapi asumsi yang coba dibangun oleh kebijakan amalgamation ini adalah
bahwa proses amalgamation justru akan membawa implikasi pada efisiensi sumberdaya dan
efisiensi kinerja pemerintah lokal.
Tawaran konsep amalgamation ini banyak diterapkan di negara-negara Scandinavia
dimana tradisi communitarianism masyarakatnya masih tinggi. Kasus di Scandinavia menunjukkan
bahwa proses amalgamation telah mampu memadatkan jumlah wilayah administrasi teritorial dari
2.500 menjadi 277 (Erlingsson, 2005, p. 145). Latvia, juga merupakan salah satu negara yang
menerapkan kebijakan amalgamation. Local government reform yang diberlakukan di negara
tersebut sejak 28 September 1993 pada dasarnya meliputi 2 hal yakni penguatan demokrasi dan
peningkatan efektivitas & efisiensi kinerja pemerintah daerah. Dan inti dari local government
reform di Latvia adalah penataan administratif melalui territorial reorganization melalui proses
amalgamation1.
Hal yang hampir serupa terjadi juga di Jepang. Sejarah negara ini tidak lepas dari sejarah
amalgamation itu sendiri. Proses amalgamation di negara itu telah berlangsung sejak tahun 1883.
Proses amalagamation tahap pertama di negara ini dari tahun 1883 sampai dengan 1898 telah
berhasil memadatkan jumlah wilayah administrasi teritorial di negara tersebut dari 71.497 menjadi
14.298. Kebijakan amalgamation ini kemudian dilanjutkan kembali dari akhir abad tersebut hingga
tahun 1950 meskipun hasilnya tidak luar biasa. Justru pada periode tahun 1950 sampai 1960
kebijakan amalgamation ini mendapatkan hasil yang signifikan, yakni dari 10.443 wilayah
administrasi teritorial mengerucut menjadi 3.526 . Hingga saat ini proses amalgamation masih
terus berlangsung di negara Tirai Bambu tersebut. Data tahun 1995 menunjukkan bahwa jumlah
wilayah administrasi teritorial di negara tersebut tercatat 3.234 (Mabuchi, 2001:1-2).
Territorial Reform: Lebih dari Sekedar “Pemekaran Wilayah”
Namun demikian, territorial reform pada dasarnya bukan hanya sekedar perkara
perubahan garis batas wilayah administrasi sebuah daerah. Tetapi, esensi penting dari territorial
reform itu sendiri adalah pada penataan institusi daerah lama maupun daerah baru hasil territorial
reform. Setidaknya territorial reform yang dilakukan sebenarnya mencoba untuk memenuhi 3
permintaan, yaitu: (1) sebagai instrumen resolusi konflik, (2) dalam rangka penyesuaian teritorial
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 6
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
untuk mendukung daya tarik ekonomi, (3) dalam rangka perbaikan serta peningkatan efektivitas
pemerintah lokal. Pola penataan daerah yang ditawarkan yakni: secession, partitionism, dan
amalgamation merupakan alternatif instrumen untuk memenuhi ketiga hal diatas.
Begitu juga dengan territorial reform dalam konteks Indonesia, sebagaimana sering disebut
sebagai pemekaran wilayah. Kebijakan pemekaran wilayah yang diterapkan di Indonesia
sebenarnya diharapkan mampu menjadi panacea untuk menjawab persoalan nasional seperti
disparitas pembangunan ekonomi dan sosial, kerapuhan identitas ke-Indonesiaan, dan kerapuhan
penjagaan kewilayahan aktif (Lay dan Santoso 2006:8). Namun, yang terjadi justru pemekaran
menjadi instrumen penguatan identitas lokal. Dengan kata lain, territorial reform kemudian
dijadikan salah satu prerequisite untuk transformasi konflik dan menjamin kelangsungan
perdamaian dalam internal negara yang bersangkutan oleh negara.
Perdebatan tentang pemekaran wilayah memang belum menjadi discourse internasional
karena pengalaman pemekaran wilayah secara masif baru dialami di Indonesia2. Untuk kasus
Indonesia sendiri, pemekaran wilayah yang terjadi lebih dimaknai sebagai instrumen untuk
mengelola konflik. Berbeda dengan negara-negara lain di dunia yang lebih cenderung melakukan
amalgation dalam terriorial reform mereka, pengalaman Indonesia justru menunjukkan sebaliknya.
Pemekaran tersebut bukan merupakan pemisahan diri (self-secession) dengan state untuk
kemudian membentuk sebuah negara baru, tetapi pemisahan diri (baca: wilayah) atau self-secession
yang terjadi berada pada level pemerintah lokal, masih dalam border administratif internal negara
yang bersangkutan.
Dengan kata lain, pemekaran wilayah bukan melahirkan negara baru, melainkan daerah
otonom baru yang masih berada dalam wilayah negara tersebut. Dalam literatur ilmu politik
sendiri, kata “pemekaran” ini belum menemukan istilahnya dalam bahasa Inggris. Untuk konteks
Indonesia, kebijakan politik desentralisasi yang difasilitasi dalam UU No.22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No.32/2004 telah menjadi basis untuk
melahirkan pembentukan daerah-daerah otonom baru yang disebut dengan “pemekaran wilayah”.
Secara yuridis, landasan untuk melakukan pemekaran tersebut dimungkinkan melalui PP
No.129/2000 Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan
Daerah. Dalam regulasi itu disebutkan bahwa sebuah daerah bila ingin dimekarkan harus
memenuhi beberapa prasyarat yang merupakan indikator kesiapan daerah. Syarat-syarat tersebut
mencakup syarat administrasi3, syarat teknis4 dan syarat teknis kewilayahan. Inisiatif untuk
melakukan pemekaran itu sendiri berangkat dari kegelisahan terhadap berbagai persoalan nasional
mulai dari isu ketimpangan pembangunan hingga isu separatisme. Pengalaman Timor-Timur yang
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 7
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
lepas dari Indonesia, serta Aceh dan Papua yang menuntut otonomi khusus, dapat dijadikan
pengalaman berharga bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam mengelola dan menata
kembali teritorialnya. Oleh karena itu, pemekaran wilayah lebih sering dimaknai sebagai sarana
negosiasi untuk mengakomodasi kepentingan lokal baik yang terkait dengan isu penguatan
identitas di ranah lokal maupun isu incapacity pemerintah daerah setempat dalam memberikan
pelayanan publik bagi masyarakat lokal.
Namun, pada tataran praksis kebijakan pemekaran daerah tersebut mengalami kegagalan,
antara lain karena5: (1) adanya politik uang dalam proses inisiasi pemekaran sebagai akibat dari
panjangnya prosedur dan proses pemekaran; (2) menguatnya politik identitas, sentimen-sentimen
primordialisme sering digunakan sebagai basis untuk pemekaran; (3) free-rider, anggapan bahwa
pemekaran adalah investasi politik dan ekonomi memicu hadirnya aktor lokal yang menjadi free
rider yang bersedia mengalokasikan sumber daya keuangannya, baik dana privat maupun
pemerintah. Diluar kegagalan yang menghantui pemekaran wilayah ini, bagi Indonesia kebijakan
pemekaran wilayah tetap dipandang efektif sebagai instrumen bagi territorial reform yang paling
strategis untuk menjembatani berbagai persoalan nasional.
Institutional Building and Reform: Penataan Struktur dan Sumberdaya
Tantangan baru yang dihadapi sebagai konsekuensi dari kebijakan territorial reform adalah
penataan institusi baik bagi daerah baru maupun daerah lama. Penataan institusi tersebut akan
sangat terkait pada bagaimana daerah yang bersangkut membangun sinergi dan konsolidasi antar
aktor dalam kerangka governance. Asumsinya proses penataan daerah yang tidak dibarengi dengan
penataan institusi justru akan menyebabkan kegagalan bagi daerah tersebut, atau bahkan lebih
jauh lagi justru memberi kontribusi bagi proses kegagalan negara (failed state6). Dalam konteks
yang lebih luas, institutional reform dimaknai sebagai point kritis dalam proses rekonstruksi dan
pembangunan demokrasi bagi negara yang gagal. Dalam kaitan dengan institutional reform tersebut
setidaknya ada 5 arena yang harus menjadi fokus perhatian, yaitu: (1) reform konstitusi, (2)
pengaturan pembagian kekuasaan, (4) melindungi minoritas, (5) rule of the law, (6) hak azazi
manusia7.
Sementara itu secara general berbicara tentang institusi, setidaknya ada beberapa elemen
penting yang harus diperhatikan dalam rangka institutional building yaitu kepemimpinan, doctrine,
program, sumberdaya dan struktur internal (Eaton, 1972, hal. 22-24). Faktor kepemimpinan
merujuk pada sekelompok orang yang yang secara aktif terlibat dalam proses formulasi kebijakan
institusi serta yang memberikan pengarahan dalam operasionalisasi dan tata hubungan dengan
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 8
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
lingkungan. Jika doctrine merujuk pada spesifikasi nilai-nilai, tujuan, dan metode operasional yang
melandasi tindakan sosial; program lebih merujuk pada tindakan-tindakan yang terkait dengan
fungsi dan pemberian pelayanan sebagai output dari institusi.
Sementara itu sumberdaya sendiri lebih terkait dengan input finansial, fisik, human,
teknologi dan informasi yang dimiliki institusi. Sedangkan struktur internal akan sangat
berhubungan dengan struktur dan proses dibangun dalam rangka operasional institusi dan
pemeliharaan akan institusi tersebut. Pembagian peran internal organisasi, pola pembagian
kewenangan, sistem komunikasi dan komitmen terhadap organisasi akan sangat mempengaruhi
kapasitas sebuah institusi dalam mencapai tujuannya. Disamping kelima elemen yang melekat pada
institusi, faktor linkages juga menjadi kunci penting dalam dalam penataan institusi karena menjadi
jembatan antara insitusi dengan masyarakat.
Dalam kaitannya dengan pemekaran wilayah, penataan institusi bagi daerah hasil
pemekaran maupun bagi daerah lama akan menjadi titik krusial bagi daerah yang bersangkutan
untuk dapat menjalankan fungsi dasarnya memberikan pelayanan bagi masyarakat. Penataan
struktur internal yang berhubungan dengan persiapan perangkat-perangkat administrasi di daerah
dan sumberdaya yang lebih berhubungan erat dengan ketidakmampuan daerah dalam membangun
sumber-sumber ekonominya. Kedua elemen tersebut menjadi kunci penting dalam penataan
institusi daerah-daerah tersebut. Pangalaman pemekaran wilayah di Indoensia selama ini
menunjukkan fakta yang terjadi sebaliknya karena ada indikasi kegagalan daerah baru produk
pemekaran, adanya problem incapacity daerah dalam menata institusi baru mereka8. Dengan
demikian, disamping berkaitan dengan border, penting juga untuk memberikan tekanan yang besar
pada penguatan kapasitas institusi sebagai pengejawantahan dari territorial reform.
Menata daerah yang baru dan yang lama
Jika kita berpijak pada pengertian territorial reform sebagai penguatan institusi dan
struktur, pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara mereformasi daerah baru dan
daerah lama. Karena, inti dari reform tetap sama, menata (kembali) institusi pemerintahan lokal.
Hanya saja, ada aspek-aspek yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara
keduanya, terutama karena reform di daerah baru lebih terkait dengan konsekuensi perubahan
batas wilayah, sedang di daerah lama, tidak. Kelebihan tersebut penting untuk dielaborasi lebih
jauh, sementara persoalan kekurangannya penting untuk dipikirkan pemecahannya. Daerah baru
dan daerah lama sama-sama memiliki kesulitan dan kelebihannya masing-masing untuk melakukan
reformasi.
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 9
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
Beberapa kelebihan menjadi daerah baru dalam kerangka territorial reform adalah
setidaknya ia terlepas dari sejarah patologi birokrasi yang menjadi tipikal institusi pemerintahan di
Indonesia. Menjadi baru, dengan demikian berarti kesempatan yang lebih besar untuk memberi
corak yang lebih progresif pada institusi yang akan dibentuk. Hanya saja, ada prasyaratnya, yaitu
adanya political will yang kuat, dan bahwa pemekaran diasumsikan untuk memajukan kehidupan
bersama, bukan sebagai penegasan identitas primordial. Bagi Erlingsson, masih lemahnya
sumberdaya politik di daerah baru, baik mencakup pengaruh (influence) dan sumberdaya keuangan
(money) justru bisa dijadikan pemicu bagi perubahan kelembagaan (institutional change) sebagai
bentuk political struggle.
Menjadi baru, juga merupakan kesempatan bagi terciptanya ruang dan tatanan
berdemokrasi yang baru, yang lebih luas. Karena, pada umumnya alasan utama pemekaran adalah
sempitnya ruang berapresiasi di kabupaten atau propinsi yang sebelumnya cakupannya lebih luas,
maka pembentukan daerah baru adalah merupakan pelepasan atas segala sempitnya partisipasi,
baik secara politik, ekonomi dan budaya (Erlingsson, 2005, 144-6). Hanya saja, jika menjadi daerah
baru justru memicu munculnya konflik, terutama berkaitan dengan perebutan sumberdaya dengan
daerah lama, tentu keinginan dan kebijakan pemekaran menstimulasi tanda tanya besar atas
efektivitasnya dan justifikasi untuk memekarkan diri justru menjadi lemah (h. 153). Dengan
demikian, konflik sebisa mungkin harus dihindari, atau, jikapun tidak, mestinya bisa dibangun
instrumen untuk mengatasinya.
Meskipun demikian, di sisi yang lain terdapat tantangan besar dalam hal kekuasaan
(power), ideologi, dan strategi antar aktor yang berkepentingan dengan pemekaran wilayah
(Erlingsson, 2005, h. 142). Daerah baru sangat rentan dengan konflik, karena institusi yang belum
tertata mapan. Jika terdapat lebih banyak aktor yang berkepentingan, kontestasi kekuasaan akan
lebih terasa karena seperti memperebutkan lahan kosong. Perkara lain yang juga krusial adalah
pembentukan ideologi dan identitas politik. Bagaimana karakter masyarakat akan terbentuk, akan
sangat tergantung pada bagaimana elit membangun opini, menata institusi dan berinteraksi satu
sama lain. Ini adalah perkara psikologi politik massa yang harus dijaga dan diperlakukan secara
hati-hati. Jika tidak, kemunculan sebagai daerah baru melalui pemekaran hanya akan menjadi
pemicu konflik berbasiskan identitas sempit. Demikian juga dengan perkara strategi. Karena
tatanan, lembaga dan aturan belum berdiri secara mapan, kesadaran tinggi akan konsensus dan
deliberative democracy adalah mutlak untuk menghindari pemekaran yang bersifat
kontraproduktif. Dalam hal ini, kehadiran pemerintah yang mampu mendisiplinkan antar aktor
sangat krusial.
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 10
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
Sementara itu, bagi daerah lama, territorial reform lebih ditekankan pada penguatan
institusi-institusi yang sudah established tapi tidak berfungsi secara baik. Dengan demikian,
identifikasi permasalahan dan upaya prioritisasinya lebih mudah dibandingkan dengan daerah
baru. Daerah lama juga relatif tidak terlalu mengalami disorientasi dan kekosongan politik
identitas. Akan tetapi, masalah menjadi berbeda jika ternyata patologi birokrasi sudah sedemikian
parah, sementara struktur politik, sosial dan budaya tidak kondusif.
Merujuk pada The World Development Report tahun 2002 tentang “Building Institutions for
Market”, meski terdengar sangat ambisius untuk konteks pemerintahan daerah di Indonesia, ide
tentang mensinergikan tatatan dengan para pelaku dalam melakukan reform tetap relevan, karena
keduanya saling mengisi (The World Bank, 2002, h. 6). Territorial reform di daerah lama fokus pada
penguatan jaringan internal, antara institusi formal dan non-formal, dan jaringan eksternal, baik
antara daerah yang satu dengan daerah lain melalui kerjasama antar wilayah, dengan pemerintah
pusat, maupun dengan lembaga-lembaga internasional (NGOs) bagi pemberdayaan masyarakat.
Mensinergikan hubungan lembaga pemerintah dan non-pemerintah sebagai core dari
territorial reform dalam kerangka governance
Ketika daerah baru telah terbentuk melalui kebijakan pemekaran, maka batas wilayah pun
berubah, disertai dengan jumlah dan karakter konstituen yang berubah pula. Perubahan ini
membawa konsekuensi pada penataan kelembagaan daerah yang tujuannya adalah untuk
membangun dan mengatur struktur dan tatanannya. Sinergi kemudian menjadi kata kunci disini.
Jika kita merujuk pada Rhodes, yang berusaha menyempurnakan pengertian politik teritori yang
diargumentasikan oleh Bulpitt, maka politik teritori mesti dipahami secara lebih komprehensif,
bukan saja pada lembaga pemerintahan yang erat kaitannya dengan administrasi publik, baik
dalam hubungannya dengan pemerintah pusat maupun intergovernmental interaction dalam batas
wilayah negara, tetapi juga pada komunitas dan kepentingan (Bradbury, 2006, h. 563) yang mengisi
ruang-ruang aktivitas sosial, ekonomi dan politik dalam asosiasi yang bernama civil society dan
market.
Territorial reform, dengan demikian, tidak hanya terpaku pada penataan kelembagaan
pemerintahan lokal sebagai sub-negara yang baru, akan tetapi, juga pada pembentukan dan
penguatan jaring-jaring masyarakat lokal dan pasar sebagai kesatuan yang utuh dalam lingkaran
governance. Di sini, pembentukan pemerintahan yang efektif adalah bidikan utamanya untuk
memungkinkan bekerjanya roda politik, sosial, dan ekonomi antar aktor dan institusi yang baru
saja terbentuk. Dalam kontenks ini, sinergi adalah salah satu jawaban bagi pertanyaan besar
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 11
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
tentang konsolidasi di daerah yang baru saja memekarkan diri. Sebagaimana Boudreau dan Keil
(2001, h. 1703), pemekaran merupakan reaksi atas kuatnya tekanan-tekanan politik baik secara
eksternal maupun internal yang membutuhkan strategi-strategi inovatif dan terintegrasi, setelah
proses perdebatan politik yang panjang tentang perlu tidaknya pemekaran dilalui.
Evans dalam tulisannya tentang embedded autonomy kiranya bisa menjadi lecutan awal bagi
pemikiran konsolidasi governance dalam reformasi teritorial, yaitu dengan penguatan kapasitas
pemerintah supaya secara efektif mampu melakukan fungsi pengaturan tetapi juga mampu
merengkuh market, struktur sosial dan civil society untuk berpartisipasi dalam pembangunan
negara dan masyarakat (1995, hal. 47-60). Ide ini sejalan dengan Johnson yang menggambarkan
pola pembangunan partisipatif di Jepang, dimana pemerintah mampu melakukan sinkronisasi
kebutuhan pasar dan masyarakat, melalui pengaturan yang efektif, tanpa perlu secara signifikan
mengorbankan satu demi yang lainnya (1999, p. 37-9), misalnya mengorbankan komunitas
masyarakat lokal demi pasar dan industri, atau sebaliknya memperioritaskan civil society tapi tidak
berorientasi pada pembangunan ekonomi. Sementara itu, Sen juga secara gamblang menekankan
sinergi antara pemerintah, market dan civil society (2000, h. 30-5) dalam penyelenggaran
kehidupan ekonomi, sosial dan politik yang partisipatif melalui penguatan network dan trust serta
penyediaan kesempatan yang merata bagi tiap-tiap elemen masyarakat untuk berpartisipasi
didalamnya. Pemikiran-pemikiran Evans, Johnson, dan Sen merupakan satu dari beberapa
alternatif mengkonsolidasikan governance dan mereformasi lembaga pemerintahan lokal dalam
kaitannya dengan territorial reform.
Dalam konteks territorial reform di Indonesia, utamanya yang tertuangkan dalam kebijakan
pemekaran daerah baru, penguatan political community dan social territoriality menjadi penting
karena pemekaran bukan sekedar reaksi atas persoalan ketidakpuasan pada kebijakan pemerintah
pusat, tetapi lebih sering pada masalah identitas, sehingga permasalahan menjadi amat dinamis. Ini
sebagaimana juga dijelaskan oleh Boudreau ketika menganalisis gerakan pemekaran di Los Angeles
(2001, h. 1710). Kompetisi identitas telah mendorong pencipataan ruang-ruang sosial budaya dan
politik yang baru, yang menariknya, dikerangkai didalam wadah struktur demokrasi regional dan
localised governance. Untuk itu, konsolidasi dalam tipikal masyarakat yang terfragmentasi dan
terbuka adalah penting untuk membangun koherensi sosial, dan local governance reform
merupakan cara untuk menemukan dan menyediakan wadah yang demokratis dan fleksibel bagi
solidaritas sosial.
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 12
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
Territorial reform untuk menguatkan kapasitas daerah dalam menjawab tantangan global
dan lokal.
Mengingat yang terjadi pada fenomena pemekaran di Indonesia sebagian besar berkaitan
dengan identitas politik dan perkara pemerataan sumberdaya antar komunitas, sehingga ia lebih
bersifat sentrifugal, maka, bidikan utama konsolidasi dan sinergi dalam lingkaran governance
adalah untuk menguatkan kapasitas masing-masing institusi di masing-masing daerah. Ini
berkebalikan dengan fenomena yang terjadi di Uni-Eropa yang bersifat sentripetal, dimana negara-
negara berusaha mengintegrasikan dirinya di salam satu sistem ekonomi, sosial dan politik. Proses
integrasi negara dan pemerintah ini pun memaksa civil society dan pressure groups yang
sebelumnya terfragmentasi atas wilayah-wialayah dan berkonsentrasi pada isu-isu di lembaga
pemerintahan masing-masing untuk membangun networks yang sifatnya lebih global. Luasnya
cakupan policy dalam uni memerlukan energi yang lebih besar bagi konsolidasi gerakan, memaksa
elemen-elemen gerakan untuk berpikir deduktif.
Melihat bahwa pola gerakan pemekaran yang bersifat segregatif di Indonesia ini berbeda
dengan pola aglomerasi di negara-negara Uni-Eropa, maka didalamnya memerlukan analisis yang
bersifat individualis, sehingga reform di wilayah governance pun terpusat pada satuan-satuan yang
lebih kecil dan kontekstual. Dengan demikian, pada dasarnya, apakah wilayah-wilayah politik akan
bergerak secara sentripetal maupun sentrifugal, tidaklah signifikan, karena ini hanya berkaitan
pada pilihan untuk menjadi komunitarian atau individual. Dua-duanya memiliki justifikasi dengan
kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga judgement atas mana yang lebih baik tentu
kurang sesuai.
Hanya saja, yang lebih penting dari sekedar bergerak secara sentripetal atau sentrifugal,
adalah apakah pada paska pembentukan wilayah baru, lembaga pemerintahan yang ada siap
melakukan reform pada ranah governance sehingga mampu mewadahi kelonpok-kelompok sosial,
ekonomi, dan politik yang baru untuk saling berinteraksi dalam lingkaran governance dan policy
interaction. Penguatan kapasitas governance kemudian menjadi krusial supaya daerah memiliki
keuntungan komparatif yang menguntungkan ketika ia bergerak keluar dalam kerangka
intergovernmental interaction, baik dalam bentuk kooperasi maupun kompetisi di ranah lokal,
nasional, maupun internasional (global). Lagi-lagi, konsolidasi dan sinergi terasa amat krusial. Jika
the World Bank dalam program Road to Recovery berusaha memberikan tekanan yang besar pada
governance, civil society dan social capital, serta safety net, maka, kiranya untuk konteks
pemerintahan lokal di Indonesia, kiranya pemikiran untuk menata institusi yang mengakomodasi
dan mengatur juga signifikan. Penguatan tiga pilar awal adalah untuk mengimbangi eksesifnya
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 13
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
market di ranah governance. Keseimbangan antar pilar adalah untuk mengakomodasi market yang
lebih friendly -bersahabat, sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Sen ketika menjelaskan
development dan social exclusion.
Penguatan kapasitas pada ranah governance di antaranya adalah dengan menegaskan
kembali fungsi pengaturan government terhadap aspek-aspek non-government. Bahwa dalam
territorial reform, fungsi government harus diakui dan kembali ditegaskan sehingga menjadi efektif.
Government, tetap menjadi salah satu unsur penting dalam public policy, policy interaction dan
deliberative democracy. Tentu saja pengakuan pentingnya government tidak untuk menegasi
pentingnya aktor dan institusi di luar government. Mengingat konteks pemerintahan Indonesia
yang masih sangat kental diwarnai oleh patologi birokratis, kiranya upaya pemberdayaan penting
untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kapasitas managerial dan
sumberdaya manusia yang duduk dalam jajaran birokrasi. Kapasitas government juga diperlukan
untuk mengatur interaksi public dan private dalam penyelenggaraan kehidupan sosial, ekonomi
dan politik (Jayasuriya dan Rosser, 2001, hl. 388). Ketidaksempurnaan lembaga pemerintah diatasi
dengan pembenahan, bukan dengan pemarginalannya di ranah governance. Karena, lembaga
government lah yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk membatasi eksesifnya penetrasi pasar
untuk mendorong keterlibatan civil society yang lebih luas didalamnya.
Penguatan kapasitas civil society dan social capital adalah dengan menyediakan ruang-
ruang partisipasi yang luas. Penguatan civil society menjadi penting karena ia berdiri di antara
negara dan pasar (Jayasuriya, 2001, h. 391). Civil society mesti diberi kebebasan untuk
mengaktualisasikan dirinya sebagai wadah aktivitas sosial yang otonom. Ini tidak saja menjadi
penting dalam kaitannya dengan penguatan demokrasi, tetapi juga dengan penguatan social capital,
karena civil society adalah tempat bagi terbangunnya trust dan network sebagai inti dari social
capital. Dengan ini, maka, segala bentuk segregasi sosial melalui konflik dan kecemburuan sosial
dapat diatasi secara deliberatif dan demokratis. Oleh karena itu, institusi pemerintah lokal harus
memiliki kemampuan memobilisasi sosial capital karena ia bersifat konstruktif melalui perluasan
partispasi dan partnership.
Penguatan safety net adalah dengan mendukung social policy yang memungkinkan
masyarakat menikmati fasilitas-fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Setidaknya social policy akan memudahkan masyarakat memenuhi syarat konstitutif untuk
berpartisipasi dalam pembangunan daerah, sebagaimana Sen menjelaskan konsep development-
nya. Safety net menjadi penting karena lembaga ekonomi dan sosial pada masyarakat di daerah
yang terbentuk pada umumnya belum mapan, dan safety net adalah untuk mengamankan masa-
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 14
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
masa transisi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan fasilitas sosial mereka. Lebih jauh, safety net
memiliki peran untuk membangun kohesi sosial dan social capital bagi lembaga kemasyarakatan
yang masih infant (Jayasuriya dan Rosser, 2001, h. 392).
Penguatan kapasitas market adalah dengan mendorongnya untuk berperan secara aktif dan
positif dalam pembangunan daerah dengan cara yang bersahabat, atau dalam istilah Sen disebut
dengan friendly. Meski pengalaman ekonomi menunjukkan bahwa market lebih sering bersifat
predatory, terutama di negara-negara berkembang, yang instrument pengaturannya belum
sempurna, akan tetapi, ini tidak berarti bahwa kita harus meniadakan eksistensi market di daerah.
Namun demikian, ada prasyarat penting untk bisa mempersilahkan market masuk ke ranah lokal,
yaitu dengan menyiapkan instrument dan aturan bermain yang jelas sehingga ia tidak merugikan
civil society.
Dengan demikian, penguatan kapasitas governance dalam kerangka territorial reform
adalah untuk menyiapkan amunisi, bukan saja pada ranah lokal dan nasional, tetapi juga ranah
global. Pemerintahan di daerah baru, meskipun dalam konteks sejarah pemekarannya lebih sering
didorong oleh faktor penguatan identitas bersama, untuk kepentingan ke depan tetap mesti
memikirkan bagaimana membentuk daerah yang memiliki keuntungan komparatif. Berbagai
tuduhan primordialis yang banyak ditujukan pada gerakan-gerakan pemekaran di daerah, kiranya
perlu dijawab dengan langkah konkret elemen-elemen governance di daerah dengan mendesain
daerah yang responsif terhadap demokrasi dan pembangunan pada aspek ekonomi, sosial, dan
politik. Karena, tantangan bukan saja ada di sekitar lokalitas daerah baru, tetapi lebih luas,
mencakup arena global.
Kesimpulan
Dari pembahasan di atas, sinergi dan konsolidasi local governance merupakan elemen kunci
dalam territorial reform yang merupakan kerangka bagi penguatan kelembagaan (institutions
building). Daerah yang baru terbentuk sangat rentan dengan lembaga pemerintahan yang masih
belum mapan, juga komunitas yang masih segmented dan bersifat sangat terbuka. Penguatan
kapasitas lembaga pemerintah dengan menguatkan fungsi regulasinya menjadi prasyarat awal
reform untuk memungkinkan terkonsolidasikannya civil society yang kaya dengan social capital dan
terfasilitasinya safety net untuk menjaga kohesi sosial pada masa transisi. Local governance reform
juga penting ditujukan untuk pengorientasian identitas komunitas yang lebih positif, juga untuk
mendorong peran market yang konstruktif. Pentingnya penguatan institusi governance dalam
territorial reform adalah untuk memperkuat kapasitas di dalam menjawab permasalahan baik pada
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 15
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
level lokal, nasional, dan global, meskipun pemekaran, pada awalnya, sebagian besar dipicu oleh
fenomena penguatan identitas primordial yang bersifat kedaerahan.
1 Local government reform di Latvia meliputi: membuat aturan baru tentang pemilu di tingkat lokal; membuat aturan baru
tentang pemerintah daerah; penataan administrasi melalui territorial reorganization; perbaikan sistem penganggaran daerah;
menciptakan sistem informasi teritorial; membangun institusi untuk training bagi staff pemerintah lokal; membangun sistem
organisasi dan komunikasi diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk lebih detail lihat Edvin Vanags,
“Development of Local Government Reforms in Latvia”, Viesoji Politika Ir Administravimas, 2005.
2 Data yang dikeluarkan Kompas, 16 Maret 2007 menunjukkan bahwa dalam jangka waktu antara tahun 1999-2006 tercatat
sekitar kurang lebih 153 daerah baru, baik daerah provinsi maupun daerah kota/kabupaten yang sudah terbentuk, sehingga saat
ini jumlah kabupaten/kota di Indonesia mengalami peningkatan hingga mencapai 450 kabupaten/kota.
3 Syarat administrasi untuk pembentukan Kabupaten/ Kota mencakup adanya: (1) Keputusan DPRD kabupaten/kota Induk
tentang persetujuan pembentukan calon daerah kabupaten/kota; (2) Keputusan bupati/walikota Induk persetujuan
pembentukan calon daerah kabupaten/kota; (3) Keputusan DPRD Provinsi Induk tentang persetujuan pembentukan calon
daerah kabupaten/kota; (4) Keputusan gubernur persetujuan pembentukan calon daerah kabupaten/kota; (5) Rekomendasi
Mendagri. Sedangkan syarat administrasi pembentukan Provinsi mencakup adanya: (1) Keputusan masing-masing DPRD
kabupaten/kota yag akan menjadi cakupan wilayah calon Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Provinsi
beradasrkan Hasil Rapat Paripurna; (2) Keputusan bupati/walikota diteatapkan dengan keputusan bersama bupati/walikota
wilayah calon Provinsi tentang persetujuan pembentukan calon Provinsi; (3) Keputusan DPRD Provinsi Induk tentang
persetujuan pembentukan calon Provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna; (4) Keputusan Gubernur tentang persetujuan
pembentukan calon Provinsi; (5) Rekomendasi Mendagri.
4 Syarat teknis mencakup 11 indikator, yaitu: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik; jumlah
penduduk, luas daerah, pertahanan, keamanan, pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan
rentang kendali pelaksanaan pemerintahan daerah.
5 Untuk lebih lanjut lihat Cornelis Lay dan Purwo Santoso (Eds.), Perjuangan Menuju Puncak: Kajian Akademik Rencana
Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua, PLOD UGM, Yogyakarta, 2006.
6 Failed state (Rotberg, 2004) adalah salah satu fenomena negara yang memiliki kapsitas governability rendah. Biasanya ditandai
dengan rendahnya kapasitas negara dalam menyediakan political goods. Kewajiban negara untuk untuk memenuhi kebutuhan
political goods terdelegasikan secara terpisah-pisah. Negara justru menyerahkan fungsi mereka sebagai penyedia barang-barang
politik kepada pemimpin-pemimpin perang atau aktor non negara lainnya (misalnya HAMAS di palestina). Keamanan hanya
tersedia di kota-kota utama. Infrastruktur ekonomi jatuh, sistem perawatan kesehatan mengalami penurunan dan sistem
pendidikan berada dalam ketidakjelasan. Failed states biasanya mempunyai kaum minoritas kaya raya yang selalu mengambil
keuntungan dari failed system yang ada. Ciri-ciri Failed state antara lain: (1) Selalu diwarnai dengan adanya disharmoni antar
komunitas; Tidak bisa menyediakan barang politik “keamanan” –yang merupakan barang politik yang paling utama- kepada
seluruh domain mereka. Negara gagal menciptakan atmosfir keamanan di seluruh wilayah nasional. (2) Negara hanya bisa
menjamin keamanan pada ibukota negara saja. (3) Memiliki institusi yang lemah, hanya institusi eksekutif yang berfungsi
sedangkan keberadaan legislatif tidak lebih dari tukang stempel semata. (4) Tidak ada debat-debat yang demokratis di ranah
publik. (5) Lembaga yudikatif tidak independen dan lebih sekedar kepanjangtanganan eksekutif. Masyrakat pun tidak
mendapatkan keadilan di sistem pengadillan , apalagi bila berhadapan dengan negara. (6) Birokrasi dalam waktu yang sudah
cukup lama kehilangan tanggungjawab profesionalitas mereka. Mereka hanya mementingkan kepentingan eksekutif semata dan
dengan cara yang halus menekan warganya. (7) Militer masih memungkinkan menjadi satu-satunya institusi yang memiliki
integritas, namun punya kecenderungan terpolitisasi secara kuat (highly politized). Aparat keamanan cenderung menjadi negara
dalam negara (State within a State) (8) Menyediakan kesempatan ekonomi yang tidak pararel hanya bagi segelitir orang yang
punya hak privilege. (9) Tanggungjawab negara untuk memaksimlisasikan kesejahteraan warganya sama sekali tidak ada.(10)
Korupsi menggurita dengan skala yang sangat luas. (11) Pada beberapa kasus, chaos ekonomi yang dikombinasikan dengan
bencana kemudian menimbulkan adanya bencana kelangkaan makanan dan keleparan yang meluas. (12) Negara kehilangan
legitimasi dasar mereka di saat batas wilayah mereka menjadi tidak relevan lagi dan sekelompok kekuatan mencoba menggalang
kekuatan. (13) Warga justru semakin menguat loyalitas komunitasnya dan menjadikannya sebagai sumber keamanan dan
kesempatan ekonomi.
7 Untuk lebih lanjut lihat http://www.berghof-handbook.net.
8 Data yang dipublikasikan Litbang Kompas tanggal 10 Maret 2007 menunjukkan bahwa dari 143 daerah yang dievaluasi, potensi
perkembangan pembangunan di 69 daerah (45%) sangat rendah. Bukan saja daerah baru yang mengalami dampak dari
pemekaran daerah tersebut, tetapi daerah lama (daerah induk) juga mengalami problem yang hampir sama, yakni sekitar 34%.
Sedangkan data yang dipublikasikan Kompas pada 03 Maret 2007 juga menggambarkan fenomena serupa dimana dari hasil
evaluasi yang dilakukan Depdagri setidaknya ada 104 daerah pemekaran (5 provinsi dan 97 kabupaten) yang berlangsung
selama periode 2000 sampai 2004, ada 76 daerah yang dianggap bermasalah.
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 16
Seminar Internasional VIII “Dinamika Politik Lokal di Indonesia: Territorial Reform & Dinamikanya”
Yayasan PERCIK Salatiga & Ford Foundation
DAFTAR PUSTAKA
Boudreau, J & Keil, R 2001, ‘Seceding from responsibility? secession movements in Los Angeles’,
Urban Studies, vol. 38, no. 10, hal. 1701-1731.
Boudreau, Julie-Anne, 2003, ‘The politics of territorialization: regionalism, localism, and other
Isms…the case of Montreal’, Journal of Urban Affair, vol. 25, no.2, h. 179-99.
Bradbury, J 2006, ‘Territory and power revisited: theorising territorial politics in the United
Kingdom after Devolution’, Political Studies, vol. 54, hal. 559-582.
Conversi, D 2000, ‘Central secession: towards a new analytical concept? the case of former
Yugoslavia’, Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 26, no.2, h.333-55.
Eaton, JW 1972, Institutional building and development: from concepts to application, Sage
Publication, London.
Erlingsson, GÓ, 2005, ‘Modelling secessions from municipalities’, Scandinavian Political Studies, vol.
28, no. 2, hal. 141-59.
Evans, P 1995, Embedded autonomy: states and industrial transformation, Princeton University
Press, New Jersey.
Jayasuriya, K & Rosser, A 2001, ‘Economic orthodoxy and the East Asian crisis’, Third World
Quarterly, vol. 22, no. 3, hal. 381-96.
Johnson, C 1999, ‘The developmental state: odyssey of a concept’, in Woo-Chumings, M (ed.), The
developmental state, Cornell University Press, London.
Keating, M 2001, Nations against the state: the new politics of nationalism in Quebec, Catalonia and
Scotland, Palgrave, Canada.
Mabuchi, M 2001, Municipal amalgamation in Japan, The World Bank Institute, The World Bank,
Washington, h.1-18.
O’Leary, B 2006, ‘Analyzing partition: definition, classification and explanation’, Working Paper
No.27 dalam ‘Mapping frontiers, plotting pathways, routes to North-South cooperation and divided
island’, h.1-27.
Sen, A 2000, ‘Social exclusion: concept, application, and scrutiny’, Social Development Papers, No. 1,
Asian Development Bank, Manila.
The World Bank 2002, World Development Report 2002: building institutions for market, Oxford
University Press, New York.
Vanags, E 2005, ‘Development of local government reform in Latvia’, Viesoji Politika Ir
Administravimas, no. 13, Latvia, h. 15-24.
Kampung Percik, Salatiga, Jawa Tengah, 17- 20 Juli 2007 17
Anda mungkin juga menyukai
- Rahmat - 044359126 - Tugas 3 Pendidikan KewarganegaraanDokumen11 halamanRahmat - 044359126 - Tugas 3 Pendidikan KewarganegaraanTata Usaha SMPK HIDUP BARU80% (10)
- Tugas Review Jurnal Politik Lokal Dan Otonomi DaerahDokumen6 halamanTugas Review Jurnal Politik Lokal Dan Otonomi DaerahSyahrul MaulanaBelum ada peringkat
- Makalah Otonomi DaerahDokumen13 halamanMakalah Otonomi DaerahMilsa SolvadianaBelum ada peringkat
- Desentralisasi Pendidikan Dalam PDFDokumen30 halamanDesentralisasi Pendidikan Dalam PDFIra MahartikaBelum ada peringkat
- MAKALAH UTS (Kelompok I)Dokumen8 halamanMAKALAH UTS (Kelompok I)neidjiBelum ada peringkat
- Tugas 3 Pendidikan Pancasila - Della Putri SariDokumen9 halamanTugas 3 Pendidikan Pancasila - Della Putri SariMuflih TivendoBelum ada peringkat
- Tugas 3 Hasna Afifah PKN 04790857Dokumen16 halamanTugas 3 Hasna Afifah PKN 04790857Hasna AfifahBelum ada peringkat
- Tugas Tutorial Iii Pendidikan Kewarganegaraan Febi Ferediawan 2023Dokumen8 halamanTugas Tutorial Iii Pendidikan Kewarganegaraan Febi Ferediawan 2023SEPUTAR BANTENBelum ada peringkat
- PKNDokumen14 halamanPKNEndang EstiyatiBelum ada peringkat
- 1 Ignatius IsmantoDokumen8 halaman1 Ignatius IsmantoFara AjahBelum ada peringkat
- ArtikelDokumen4 halamanArtikelOktavianaBelum ada peringkat
- TGZ 2 Filsafat Admstrsi Muslim M KarimDokumen16 halamanTGZ 2 Filsafat Admstrsi Muslim M KarimAcim M KarimBelum ada peringkat
- 10Dokumen11 halaman10jayadimirandaBelum ada peringkat
- Pembangunan Dan Perkembangan Praktek Perencanaan Dan Hukum Administrasi WilayahDokumen25 halamanPembangunan Dan Perkembangan Praktek Perencanaan Dan Hukum Administrasi WilayahLisa Christie Gosal100% (1)
- 1644-File Utama Naskah-4491-1-10-20181229Dokumen9 halaman1644-File Utama Naskah-4491-1-10-20181229banu banaBelum ada peringkat
- Atin Irmaya (201FK03010) - KWN10Dokumen16 halamanAtin Irmaya (201FK03010) - KWN10atin irmayaBelum ada peringkat
- Tugas 2 Hukum Agraria 19Dokumen4 halamanTugas 2 Hukum Agraria 19Ahmad FuadiBelum ada peringkat
- Bab1 2 3Dokumen39 halamanBab1 2 3Putra SuaBelum ada peringkat
- Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State/societyDokumen20 halamanDesentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State/societypaulaBelum ada peringkat
- Otonomi DaerahDokumen16 halamanOtonomi DaerahdwiBelum ada peringkat
- Jurnal Skripsi Dian PDFDokumen18 halamanJurnal Skripsi Dian PDFnaruse10Belum ada peringkat
- RegionalismeDokumen5 halamanRegionalismerisaBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah Perkembangan AdministrasiDokumen14 halamanMakalah Sejarah Perkembangan AdministrasiYulisa FebrianiBelum ada peringkat
- Dimensi LingkunganDokumen14 halamanDimensi Lingkungandoni100% (2)
- Bab IiDokumen8 halamanBab IiRif'ah S. PdBelum ada peringkat
- Tugas Dimensi FilsafatDokumen4 halamanTugas Dimensi FilsafatDiivaaBelum ada peringkat
- Tiara Nuralinda 2019280023 - Manajemen PembangunanDokumen13 halamanTiara Nuralinda 2019280023 - Manajemen PembangunanRana ZahputBelum ada peringkat
- Pengertian Desentralisasi Dekonsentrasi Medebewind Definisi Asas Pemerintahan Daerah Menurut para AhliDokumen6 halamanPengertian Desentralisasi Dekonsentrasi Medebewind Definisi Asas Pemerintahan Daerah Menurut para AhliNafrizal KamalBelum ada peringkat
- Penerapan Learning OrganizationDokumen15 halamanPenerapan Learning Organizationmuhammad da'i100% (6)
- Makalah Peran Budaya Dalam Membangun PolitikDokumen21 halamanMakalah Peran Budaya Dalam Membangun PolitikslampackBelum ada peringkat
- Makalah Reformasi AdministrasiDokumen15 halamanMakalah Reformasi Administrasifarras fadhillah100% (1)
- Administrasi NegaraDokumen25 halamanAdministrasi NegaraFaisyah Rahayu RustamBelum ada peringkat
- Pidato Pengukuhan Prof. Wihana Kirana Jaya M.soc - Sc. PH.DDokumen21 halamanPidato Pengukuhan Prof. Wihana Kirana Jaya M.soc - Sc. PH.DParlinBelum ada peringkat
- Teori OmpDokumen14 halamanTeori OmpDedy NgonthelagiBelum ada peringkat
- Bab 5Dokumen4 halamanBab 5Kevin DasBelum ada peringkat
- Linda 042381301 - T3 Sistem Politik IndonesiaDokumen7 halamanLinda 042381301 - T3 Sistem Politik IndonesiaLin-LinBelum ada peringkat
- Politik Desentralisasi Dari Tahun 1974 Sampai 2014Dokumen17 halamanPolitik Desentralisasi Dari Tahun 1974 Sampai 2014Kuy JasainBelum ada peringkat
- Politik PendidikanDokumen90 halamanPolitik PendidikanHestyBelum ada peringkat
- Makalah Studi Kasus Intervensi Dalam PembangunanDokumen10 halamanMakalah Studi Kasus Intervensi Dalam PembangunanKhaira UmmatinBelum ada peringkat
- ARHAN D10122877 - Resume DesentralisasiDokumen7 halamanARHAN D10122877 - Resume Desentralisasihae xBelum ada peringkat
- Tugas RemedialDokumen8 halamanTugas RemedialPrasetya AlifBelum ada peringkat
- Nofal Arifin - Pemberian Wewenang Dan Pelaksanaan Otonomi Daerah - B5Dokumen13 halamanNofal Arifin - Pemberian Wewenang Dan Pelaksanaan Otonomi Daerah - B5Nofal ArifinBelum ada peringkat
- Administrasi Pembangunan Nasional Sejak Era Orde Lama Hingga ReformasiDokumen8 halamanAdministrasi Pembangunan Nasional Sejak Era Orde Lama Hingga ReformasiKhaidir Wijaya0% (1)
- Aspek Yg Mempengaruhi Adm PembangunanDokumen7 halamanAspek Yg Mempengaruhi Adm Pembangunancitra rantikaBelum ada peringkat
- Administrasi KeuanganDokumen5 halamanAdministrasi Keuangansaniy29fasyabasirBelum ada peringkat
- Reformasi Adm Publik Bangun Daya Saing Daerah - Perspektif Resource BasedDokumen26 halamanReformasi Adm Publik Bangun Daya Saing Daerah - Perspektif Resource BasedDoniSuryoAjiBelum ada peringkat
- An Otonomi Daerah Di PalutaDokumen12 halamanAn Otonomi Daerah Di PalutaAkmal KodirBelum ada peringkat
- Desentralisasi & Globalisasi.3Dokumen21 halamanDesentralisasi & Globalisasi.3Ardian HavidaniBelum ada peringkat
- Pengertian ReformasiDokumen26 halamanPengertian ReformasiIntan Nurjanah100% (1)
- BUKU JAWABAN 4111 - PKNDokumen6 halamanBUKU JAWABAN 4111 - PKNJulian AndryantoBelum ada peringkat
- Kel 1 - Konteks Dan Urgensi Kelembagaan Dalam PerencanaanDokumen21 halamanKel 1 - Konteks Dan Urgensi Kelembagaan Dalam PerencanaanHukma ZulfinandaBelum ada peringkat
- Politik Desentralisasi Di IndonesiaDokumen42 halamanPolitik Desentralisasi Di IndonesiaputriBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen19 halaman1 SMBrizzie IkarisBelum ada peringkat
- Aan Zulyanto - Implikasi Pelaksanaan Otonomi DaerahDokumen19 halamanAan Zulyanto - Implikasi Pelaksanaan Otonomi DaerahAan Zulyanto100% (1)
- Arikel TANTANGAN OTONOMI DAERAH TUGAS 3 PKN Nur AiniDokumen10 halamanArikel TANTANGAN OTONOMI DAERAH TUGAS 3 PKN Nur Aininuraini01909Belum ada peringkat
- 04 - Bab 4 - Izin Tanah - LADokumen30 halaman04 - Bab 4 - Izin Tanah - LAYose Ra Abdul AzisBelum ada peringkat
- Makalah Pempolin Kel VickiDokumen19 halamanMakalah Pempolin Kel VickiRiza MuhammadBelum ada peringkat
- The Three Shades from the Past to the Present Malay VersionDari EverandThe Three Shades from the Past to the Present Malay VersionBelum ada peringkat
- Bab IIDokumen16 halamanBab IIFauzia HoerunnisaBelum ada peringkat
- CoverDokumen1 halamanCoverFauzia HoerunnisaBelum ada peringkat
- Bab IIIDokumen12 halamanBab IIIFauzia HoerunnisaBelum ada peringkat
- Efektivitas Komunikasi Dan Negosiasi Dalam Bisnis PDFDokumen4 halamanEfektivitas Komunikasi Dan Negosiasi Dalam Bisnis PDFNur LaeliahBelum ada peringkat
- Efektivitas Komunikasi Dan Negosiasi Dalam Bisnis PDFDokumen4 halamanEfektivitas Komunikasi Dan Negosiasi Dalam Bisnis PDFNur LaeliahBelum ada peringkat
- Ok Pedoman Skripsi Tesis Disertasi - Final - A5Dokumen82 halamanOk Pedoman Skripsi Tesis Disertasi - Final - A5Fauzia HoerunnisaBelum ada peringkat
- Pengantar Manajemen by PriyonoDokumen140 halamanPengantar Manajemen by PriyonoNurul uyunkBelum ada peringkat
- Kelompok 3 Makalah Komunikasi Bisnis Tentang Negosiasi Bisnis-1 PDFDokumen19 halamanKelompok 3 Makalah Komunikasi Bisnis Tentang Negosiasi Bisnis-1 PDFRatnasariBelum ada peringkat
- ID Pengaruh Perumusan Dan Implementasi StraDokumen13 halamanID Pengaruh Perumusan Dan Implementasi StraFauzia HoerunnisaBelum ada peringkat
- Kelompok 3 Makalah Komunikasi Bisnis Tentang Negosiasi Bisnis-1 PDFDokumen19 halamanKelompok 3 Makalah Komunikasi Bisnis Tentang Negosiasi Bisnis-1 PDFRatnasariBelum ada peringkat