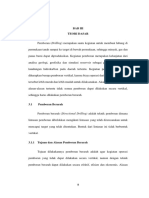Materi KP
Materi KP
Diunggah oleh
IkhaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Materi KP
Materi KP
Diunggah oleh
IkhaHak Cipta:
Format Tersedia
4.
METODE KONSTRUKSI DAN DINDING PENAHAN TANAH
(RETAINING WALL)
4.1. Pendahuluan
Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan basement adalah penentuan
metode konstruksi galian dan penggunaan retaining wall serta sistem dewatering.
Ada tiga hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode konstruksi dan
penggunaan retaining wall, yakni lokasi galian, jenis tanah dan kedalaman galian
basement. Sedangkan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan
sistem dewatering dapat dilihat pada bab 5.
Lokasi galian basement
Pemilihan Metode Konstruksi
dan Jenis tanah
Penggunaan Retaining Wall
Kedalaman Galian
Gambar 4.1. Pertimbangan dalam pelaksanaan basement
4.2.Metode Konstruksi
Beberapa metode konstruksi yang biasa dikenal adalah metode open-cut,
metode cut and cover dan metode top-down. Perbedaan mendasar dari metode-
metode tersebut terletak pada penggunaan retaining wall. Pada metode cut and
cover dan metode top-down, dilakukan pemasangan retaining wall terlebih dahulu
sebelum dilakukan penggalian. Sedangkan pada metode open-cut, tidak
menggunakan retaining wall.
Oleh karena itu, sebelum melakukan pemilihan metode konstruksi yang
akan dipakai, dilakukan analisa pertimbangan mengenai lokasi galian basement,
jenis tanah dan kedalaman galian, guna menentukan terlebih dahulu apakah perlu
menggunakan retaining wall atau tidak. Jika memerlukan retaining wall, maka
27 Universitas Kristen Petra
metode konstruksi yang digunakan adalah metode cut and cover atau metode top-
down. Sebaliknya jika tidak menggunakan retaining wall, maka digunakan adalah
metode open-cut.
4.2.1. Metode Open-Cut
Metode ini biasa disebut juga metode konvensional, merupakan metode
yang paling sederhana. Pada metode ini, dilakukan penggalian dari permukaan
tanah hingga ke dasar galian dengan sudut lereng galian tertentu (slope angle) dan
tanpa menggunakan retaining wall. Selanjutnya pekerjaan konstruksi basement
akan dikerjakan dari dasar galian berlanjut ke atas (bottom-up). Setelah pekerjaan
basement selesai, maka lubang galian dapat ditimbun atau diurug kembali.
Metode ini biasanya digunakan pada proyek yang mempunyai lahan cukup
luas, dimana galian basement terletak di tengah-tengah site, sehingga tidak
berbatasan langsung dengan bangunan tetangga (existing building) dan jumlah
lantai basement kurang dari dua lantai atau semi-basement. Metode ini juga tidak
disarankan untuk dilakukan di wilayah perkotaan atau galian basement yang
berbatasan langsung dengan bangunan tetangga.
Gambar 4.2. Metode open-cut
Sumber : Chew (2009, p. 63)
28 Universitas Kristen Petra
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan metode
konstruksi ini adalah jenis tanah, sudut kemiringan lereng galian (slope angle),
kondisi muka air tanah dan surcharge load yang bekerja di sekitar galian. Hal-hal
tersebut perlu diperhatikan untuk menjaga kestabilan lereng dan mencegah
terjadinya longsor. Adapun identifikasi, klasifikasi dan deskripsi dari jenis-jenis
tanah, dapat dilihat pada bab 3. Kaitan antara jenis tanah dan sudut kemiringan
lereng dapat dilihat pada beberapa tabel dibawah ini.
Tabel 4.1. Temporary Slope Angle
Sumber : Ahlvin, Smoots (1988, p. 24)
Tabel 4.2. Slope Angle untuk Granular Soil
Temporary Slope Permanent Slope
Jenis Tanah
β , deg Tan β β, deg Tan β
Gravel with boulder 53 1 : 0,75
Sand gravel or angular sand 39 1 : 1,25 34 1 : 1,5
Rounded coarse sand 34 1 : 1,5 30 1 : 1,75
Rounded fine sand 30 1 : 1,75 27 1:2
Sand with water emerging on slope 22-16 1 : 2,5-3,5
Sumber : Koerner (1985, p. 61)
29 Universitas Kristen Petra
Tabel 4.3. Slope Angle untuk Cohesive Soil
Soil Type PI Depth (m) β , deg Tan β
Clayey silt Less 0-3 39 1 : 1,25
than 10 3-6 32 1 : 1,6
6-9 30 1 : 1,75
Silty clay 10 – 20 0-3 39 1 : 1,25
3-6 39 1 : 1,25
6-9 35 1 : 1,4
Plastic clay More 0-3 39 1 : 1,25
than 20 3-6 39 1 : 1,25
6-9 39 1 : 1,25
Sumber : Koerner (1985, p. 77)
Tabel 4.4. OSHA Soil and Rock Classification
Sumber : Nunnally (2004, p. 85)
30 Universitas Kristen Petra
Tabel 4.5. OSHA Maximum Allowable Slope
Sumber : Nunnally (2004, p. 86)
Metode ini cocok digunakan apabila kondisi muka air tanah tidak lebih
tinggi dari dasar galian, namun hal tersebut dapat dikendalikan dengan sistem
dewatering yang benar. Pada tanah granular, metode ini dapat diaplikasikan
dengan metode dewatering sistem ground-water lowering. Pada tanah kohesif,
metode ini dapat diaplikasikan dengan metode dewatering sistem open pumping.
Adapun penjelasan lebih rinci mengenai sistem dewatering akan dibahas lebih
lanjut pada bab 5.
Pada tanah kohesif, sudut kemiringan lereng dapat lebih besar dan lebih
stabil dibandingkan tanah granular. Tetapi kelongsoran rawan terjadi pada musim
hujan, karena pada jenis tanah kohesif (yang dominan lempung), tanahnya akan
mengembang, menjadi ekspansif, meleleh, menjadi lumpur ketika terkena air
hujan dalam jumlah tertentu. Pada saat hujan akan terjadi penambahan tegangan
air tanah yang dapat mengganggu stabilitas lereng galian.
Kelongsoran juga bisa disebabkan akibat getaran dari kendaraan berat
yang lewat di tepi lereng galian (surcharge load). Oleh karena itu perlu adanya
jarak aman dari tepi lereng galian, sehingga tidak mengganggu kestabilan lereng.
Selain itu, pada metode ini rawan terjadi heave pada dasar galian akibat
kehilangan beban tanah selama penggalian, sehingga tanah di samping galian
akan menjadi suatu beban tambahan pada dasar galian.
Pada kondisi tertentu, untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan pada
lereng galian akibat pengaruh cuaca (hujan), maka lereng galian diproteksi dengan
shot-crete atau gunniting (beton cair yang disemprotkan pada lereng galian) atau
dapat pula ditutupi dengan terpal. Beberapa upaya perkuatan lereng galian yang
31 Universitas Kristen Petra
dapat dilakukan, antara lain memberi susunan anyaman kawat berisi batu
(bronjong) pada lereng galian atau dengan memasang susunan karung berisi pasir
kering atau mortar semen pada lereng galian. Selain itu, dapat juga memperkuat
lereng galian dengan shot-crete yang diperkuat dengan menggunakan nail,
sehingga biasa disebut soil nailing.
4.2.1.1. Soil Nailing
Soil nailing merupakan metode untuk memperkuat tanah dengan cara
memasang nail dengan kedalaman dan jarak tertentu untuk memperkuat
kestabilan tanah dengan meningkatkan kekuatan geser tanah secara keseluruhan
serta menahan kemungkinan terjadinya gejala pergerakan tanah atau
displacement, sehingga stabilitas lereng terjaga.
Nail yang digunakan terbuat dari tulangan baja atau bahan lainnya yang
dapat menahan tegangan tarik, geser maupun momen lentur. Tulangan baja ini
dimasukkan ke dalam lubang lalu dilakukan grouting dengan cairan semen. Jarak
antar nail sekitar 1-3 meter dan pada permukaan tanah lereng dilapis dengan beton
cair tipis, sekitar 7-20 sentimeter (shotcrete). Pada bagian ujung nail dipasang plat
baja tipis yang diikat dengan sekrup baja.
Adapun beberapa keuntungan dari pemakaian soil nailing sebagai berikut :
Teknik pelaksanaan lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan
retaining wall.
Sudut kemiringan lereng (slope angle) dapat dimodifikasi, sehingga dapat
menghemat penggunaan lahan.
Peralatan konstruksi yang digunakan lebih sederhana.
Dapat dipakai sebagai struktur permanen maupun sementara.
Selama pelaksanaan tidak terlalu bising dan bergetar.
Selain beberapa keuntungan di atas, soil nailing memiliki beberapa
keterbatasan atau kekurangan, antara lain :
Nail dipasang menembus ke luar galian, sehingga lahan di sekitar lereng tidak
dianjurkan untuk digali atau dipancang atau dibor karena pemasangan,
khususnya untuk nail yang permanen.
32 Universitas Kristen Petra
Kurang tepat digunakan pada tanah yang lunak atau loose, karena ikatan nail
dengan tanah akan menjadi tidak cukup kuat.
Aspek ketahanan dan kekuatan (service period) masih sukar diprediksi karena
kemungkinan terhadap korosi pada tulangan di dalam tanah sukar
perhitungkan.
Kesulitan mengontrol bila terjadi pembengkokan tulangan khususnya
pemasangan dengan sistem driven nail.
Gambar 4.3. Tahap-tahap pelaksanaan soil nailing
Sumber : Chew (2009, p. 74)
33 Universitas Kristen Petra
Dalam pelaksanaan soil nailling melalui 3 tahapan, yakni penggalian,
nailing, drainase dan perkuatan permukaan dengan shotcrete.
1. Penggalian
Penggalian bisa dilakukan dengan konvensional atau dengan berat.
Penggalian dilakukan secara bertahap dalam tingkatan tertentu. Kedalaman pada
tiap tingkat dibatasi tidak lebih dari 10 ft, dengan memperhatikan jenis tanah pada
saat digali. Pemotongan slope atau lereng galian harus dilakukan dengan hati-hati
untuk memastikan kerusakan permukaan tanah lereng cukup minimum.
2. Nailing
Proses nailing dilakukan secepat mungkin setelah penggalian dalam satu
tingkat, untuk mengantisipasi kerusakan permukaan lereng akibat cuaca. Adapun
proses pemasangan nail dapat dilakukan dengan beberapa teknik antara lain :
Driven nail
Nail yang digunakan menggunakan tulangan diameter 15 sampai 46
milimeter atau profil logam lainnya seperti baja dengan tegangan leleh 350
MPa, dipasang cukup rapat ( 2-4 batang per meter persegi ). Tulangan atau
profil baja langsung dimasukkan ke dalam tanah dengan Vibro-Percussion
Pneumatic atau Hydraulic Hammer, tanpa dilakukan pengeboran terlebih
dahulu. Untuk melakukan grouting, dipakai silinder baja (batang baja khusus
yang berongga di tengahnya). Teknik ini cukup ekonomis dan cepat, sekitar
4-6 batang per jam dan cocok untuk tanah yang lunak atau loose. Hal yang
perlu diantisipasi adalah tulangan dapat bengkok ketika dimasukkan ke dalam
tanah.
Drilled nail
Nail menggunakan tulangan ulir, baja mutu tinggi, berdiameter 15 sampai 46
milimeter. Grouting cairan semen dilakukan dengan cara gravitasi
(mengandalkan berat sendirinya) atau dengan dipompa dengan tekanan
rendah. Pada jenis tanah lepas (loose) lubang bor di-grouting dengan
bentonite slurry, untuk menjaga kestabilan lubang bor.
34 Universitas Kristen Petra
Jadi pertama-tama, lubang nail dibor terlebih dahulu, selanjutnya cairan grout
dimasukkan ke dalam lubang bor. Setelah lubang bor terisi penuh, tulangan-
tulangan dengan centering ring atau spacer segera di masukkan ke dalam
lubang bor, sebelum cairan grouting mulai mengeras. Jarak antara spacer
sekitar 1-2 m.
Pada tanah yang loose, bisa juga dilakukan dengan Hollow Stem Continous
Flight Auger. Pertama-tama, dilakukan pengeboran hingga kedalaman yang
diinginkan, lalu tulangan diletakkan pada batang bor. Cairan grout dipompa
masuk ke dalam lubang melalui batang bor, sementara itu batang bor ditarik
perlahan-lahan keluar, sedangkan tulangan tetap tertinggal. Cairan grouting
akan mengisi lubang bor, mengikat tulangan dan tanah.
Untuk lubang nail yang horizontal dan permanen, maka dapat dipasang
selubung atau casing untuk mempertahankan kestabilan lubang bor pada saat
pengerjaan dan dapat pula mencegah korosi.
3. Drainase
Sistem drainase diperlukan untuk mengendalikan air permukaan (surface
drainage) dan air tanah, apabila level muka air tanah lebih tinggi dari dasar
galian. Ada 2 sistem drainase pada soil nailing, antara lain :
Drainase dalam, dengan menempatkan pipa-pipa yang lebih panjang dari nail,
untuk menjaga kestabilan lereng, menjaga kadar air dalam tanah sehingga
mengurangi tegangan air tanah. Pipa yang digunakan bisa dari pvc,
berdiameter 2 inchi dan dipasang miring dengan sudut 50-100 terhadap garis
horizontal.
Drainase dangkal, dengan menempatkan pipa kecil, panjang sekitar 12 inchi
untuk mencegah pengumpulan air di belakang permukaan lereng. Jumlah pipa
yang dipasang kurang lebih sama dengan jumlah nail.
4. Perkuatan Permukaan dengan Shot-crete
Shot-crete merupakan beton cair yang disemprot pada permukaan lereng
galian, digunakan untuk menutupi lapisan permukaan lereng galian, guna menjaga
sudut kemiringan lereng dari erosi maupun cuaca, juga untuk membatasi
35 Universitas Kristen Petra
kehilangan tekanan udara (decompression) segera setelah penggalian. Ukuran
agregat pada shotcrete dibatasi, sekitar 10-15 milimeter dan tebal lapisan sekitar
7-20 cm. Pelaksanaan shot-crete dapat dilakukan setelah penggalian tiap tingkat
selesai atau ketika keseluruhan galian selesai, tergantung jenis tanahnya.
Ada 2 macam metode pelaksanaan shot-crete, antara lain:
Metode kering
Pada metode ini, semen kering dan agregat (pasir dan kerikil) dicampur
terlebih dahulu, kemudian disemprot dengan tekanan udara melalui pipa dan
air ditambahkan pada nozzle (bagian akhir pipa).
Metode basah
Pada metode ini, campuran beton segar (semen, agregat dan air)
disemprotkan langsung dengan tekanan udara dari concrete pump melalui
pipa-pipa.
Lapisan shotcrete dapat pula diperkuat dengan wiremesh berdiameter 5-10
mm yang dipasang pada tenga-tengah lapisan shot-crete. Wiremesh diikatkan pada
paku pendek yang ditancapkan pada permukaan tanah.
Berdasarkan ketahanannya terhadap korosi, soil nailing bisa diaplikasikan
sebagai struktur penahan tanah sementara (temporary) maupun permanen.
Temporary nail diperkirakan waktu pemakaiannya (service period) kurang dari
dua tahun, sedangkan permanent nail direncanakan untuk waktu pemakaian lebih
dari dua tahun.
1. Temporary Nail
Pada temporary nail, tulangan yang dipakai tidak dilindungi terhadap
korosi, sehingga service period cukup terbatas, kurang dari dua tahun. Grouting
pada tulangan dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan lekatan antara
tulangan dengan tanah dan melindungi tulangan selama service period.
Diameter tulangan yang digunakan sekitar 20-32 mm, tebal grouting
minimum 15 mm, sehingga diameter lubang bor ditentukan dari diameter tulangan
baja ditambah tebal grouting. Tulangan diletakkan di tengah-tengah lubang
sehingga ketebalan grouting seragam.
36 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.4. Temporary nail standar Jerman
Sumber : Bauer (1998, p. 5)
2. Permanent Nail
Pada permanent nail, service period direncanakan lebih lama daripada
temporary nail, lebih dari 2 tahun. Oleh karena itu, untuk melindungi tulangan
dari korosi, maka dipasang selubung dari bahan plastik seperti pvc, untuk
menyelubungi nail. Cara ini cukup efektif dan ekonomis untuk mencegah korosi
dalam jangka waktu yang cukup lama.
Gambar 4.5. Permanent nail standar Jerman
Sumber : Bauer (1998, p. 5)
Adapun beberapa kegagalan soil nailing, karena diakibatkan panjang
penembusan nail tidak cukup dalam sehingga tidak mampu menahan kelongsoran
tanah, seperti pada gambar 4.6.
37 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.6. Beberapa contoh kegagalan soil nailing
Sumber : Chew (2009, p. 96)
4.2.2. Metode Cut and Cover
Berbeda dengan metode open cut, pada metode ini sebelum dilakukan
pekerjaan penggalian, di sekeliling lahan galian dipasang dinding penahan tanah
(retaining wall) terlebih dahulu. Setelah dinding penahan tanah terpasang, maka
dilakukan penggalian dari tanah permukaan (ground level) hingga ke dasar galian
dan pekerjaan konstruksi basement akan dikerjakan dari dasar galian dilanjutkan
ke atas (bottom up).
Gambar 4.7. Metode cut and cover
Sumber : Chew (2009, p. 68)
Dinding penahan tanah ini berguna untuk menghindari terjadinya
longsoran akibat tekanan tanah dari sisi luar ketika dilakukan penggalian. Tanpa
mengesampingkan pelaksanaan sistem dewatering yang tepat, dengan adanya
38 Universitas Kristen Petra
dinding penahan tanah juga dapat mencegah resiko terjadinya piping dan
meminimalkan terjadinya penurunan pada lahan di sekeliling galian. Pada
beberapa kasus, untuk memperkuat dan menjaga kestabilan dinding penahan
tanah, maka dapat dipasang suatu support system, seperti strutting atau anchor.
Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai dinding penahan tanah (retaining wall)
dan support system akan dibahas pada bab 4.3 dan 4.4.
Metode ini cocok untuk pekerjaan penggalian yang cukup dalam (deep
basement) dengan lokasi lahan yang cukup sempit dan terletak di kawasan yang
padat. Selain itu, metode ini cocok dipakai untuk jenis tanah galian granular.
Namun, jika jenis tanah pada lahan proyek bersifat ekspansif (dominan lempung
atau lempung murni), maka metode ini juga cukup efektif untuk digunakan,
dengan pertimbangan tidak perlu perawatan atau penanganan khusus untuk
mencegah tanah tersebut mengembang (swell), karena ada dinding penahan tanah
(retaining wall) yang menahan.
Metode ini juga cocok digunakan apabila kondisi muka air tanah cukup
tinggi (lebih tinggi dari dasar galian) dan cocok untuk diaplikasikan bersama
dengan menggunakan metode dewatering sistem open pumping. Penjelasan lebih
rinci mengenai sistem dewatering akan dibahas pada bab 5.
Sama seperti metode open-cut, yang perlu diantisipasi pada metode ini
adalah heave pada dasar galian. Selama tanah digali, terjadi pengurangan beban di
atas galian, sedangkan tanah di samping galian akan menjadi suatu beban
tambahan terhadap tanah dasar galian. Tanah di samping galian akan menekan ke
bawah dan menyebabkan gerakan tanah naik ke atas (bottom heave), seperti pada
gambar di bawah ini.
Gambar 4.8. Heave pada dasar galian
Sumber : Tschebotariof (1982, p. 103)
39 Universitas Kristen Petra
Oleh karena itu, salah satu solusi untuk mencegah terjadinya heave adalah
melakukan galian secara bertahap dan segera melakukan pengerjaan konstruksi
sub-structure. Selain itu, penggunaan retaining wall secara tepat juga dapat
menghambat terjadinya heave pada dasar galian.
4.2.3. Metode Top-Down
Hampir sama dengan metode cut and cover, pada metode ini sebelum
dilakukan penggalian dan pelaksanaan konstruksi basement, dipasang dinding
penahan tanah (retaining wall) terlebih dahulu. Pada metode open cut maupun
metode cut and cover, pelaksanaan konstruksi basement dilakukan dari dasar
galian berlanjut ke atas. Sedangkan pada metode top-down, pelaksanaan
konstruksi basement dimulai dari level permukaan tanah (ground level) berlanjut
hingga ke lantai dasar basement terdalam. Dengan penggunaan metode konstruksi
top-down, maka pekerjaan struktur bawah bisa dilakukan secara bersamaan
dengan struktur atas (upper structure). Pekerjaan struktur bawah yang dimaksud
seperti penggalian, penulangan dan pengecoran plat lantai basement, kolom
basement, pile cap serta sloof.
Adapun tahap-tahap pelaksanaan konstruksi basement dengan metode top-
down sebagai berikut :
Dilakukan pelaksanaan pekerjaan pondasi terlebih dahulu. Jika menggunakan
metode top-down, maka pondasi yang biasa digunakan adalah bored-pile.
Dilakukan pengeboran lubang-lubang tiang pondasi sekaligus lubang bagi
king-post. Lubang bor diberi slurry untuk mencegah terjadi longsoran pada
lubang yang dibor. Pada kasus tertentu, pada lubang bor bisa diberi casing
untuk mencegah terjadinya kelongsoran.
Setelah lubang-lubang pondasi siap, maka dilakukan pengecoran dengan
menggunakan tremi. Beberapa diantara lubang bor yang disiapkan, selain
berfungsi sebagai pondasi juga dapat berfungsi sebagai king-post. King-post
merupakan kolom penopang selama dilakukan penggalian, yang nantinya
akan dijadikan sebagai kolom basement itu sendiri. King-post bisa terbuat
dari pondasi yang diteruskan, dicor hingga mencapai level permukaan tanah
atau terbuat dari baja WF tertanam sedalam tertentu pada bored-pile. Yang
40 Universitas Kristen Petra
harus diperhatikan dalam pemasangan king-post batang baja WF adalah
batang ini harus dipasang vertikal dan tegak lurus. Adapun pemasangan baja
WF sebagai king-post, dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni baja WF
dimasukkan sesaat setelah pengecoran pondasi (post-concreting method) dan
baja WF dimasukkan sebelum pengecoran pondasi (pre-concreting method)
seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.9. Pemasangan king-post baja WF dengan post-concreting method
Sumber : Thasnanipan, Maung (2000, p. 6)
Gambar 4.10. Pemasangan king-post baja WF dengan pre-concreting method
Sumber : Thasnanipan, Maung (2000, p. 8)
Untuk lubang bor yang hanya berfungsi sebagai pondasi, maka dicor sampai
kedalaman yang direncanakan (sampai kedalaman lantai basement terdalam).
41 Universitas Kristen Petra
Sedangkan untuk lubang yang juga difungsikan sebagai king-post, maka
dapat dicor seluruhnya, penuh, hingga ke level permukaan tanah.
Setelah tiang-tiang pondasi dan king-post selesai dikerjakan, maka dilakukan
pekerjaan penulangan dan pengecoran plat lantai dan balok serta kolom mulai
dari level permukaan tanah (ground level). Yang perlu diperhatikan adalah
harus ada lubang yang cukup untuk akses masuk-keluar alat gali yang akan
menggali basement di bawahnya.
Alat gali akan masuk menggali basement pertama, kemudian dilakukan
pekerjaan penulangan dan pengecoran tulangan plat dan balok basement
pertama. Demikian seterusnya basement di bawahnya, hingga dilakukan
penulangan dan pengecoran sloof dan poer pondasi. Adapun skema sederhana
pelaksanaan penggalian metode top-down, dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.
Gambar 4.11. Tahap pelaksanaan metode top-down
Sumber : Apartemen Trilium (2007, p. 31)
42 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.11. Tahap pelaksanaan metode top-down (sambungan)
Sumber : Apartemen Trilium (2007, p. 31)
Di samping memiliki tingkat kerumitan pelaksanaan yang cukup tinggi,
metode ini memiliki beberapa keuntungan yang dapat menjadi pertimbangan
antara lain :
Cocok untuk pelaksanaan konstruksi basement yang terletak di kawasan
perkotaan yang padat, yang berbatasan langsung dengan existing building
maupun utilitas lainnya.
Relatif lebih hemat waktu, karena upper structure dapat dikerjakan tanpa
menunggu basement selesai dikerjakan. Berbeda dengan metode lainnya,
dimana pekerjaan konstruksi dilakukan dari bawah ke atas (bottom-up).
Tetapi tentu saja ada batasan, struktur atas tidak melampaui ketinggian
tertentu yang telah diperhitungkan sebelum keseluruhan struktur basement
(struting dan pile cap) selesai dibangun.
Tidak membutuhkan anchor, bracing atau struting sementara untuk menahan
retaining wall, karena penggalian dilakukan bertahap dari atas ke bawah dan
balok-balok basement dapat berfungsi sebagai struting.
Galian tanah dilakukan secara bertahap, sehingga resiko terjadi heave dapat
terkurangi, terutama pada jenis tanah highly over-consolidated.
43 Universitas Kristen Petra
4.3.Dinding Penahan Tanah (Retaining Wall)
Apapun metode yang digunakan untuk pengerjaan basement, dinding
penahan tanah mutlak diperlukan, kecuali jika menggunakan metode konstruksi
open-cut. Oleh karena itu, salah satu komponen utama dalam pelaksanaan
konstruksi basement adalah dinding penahan tanah atau retaining wall.
Adapun fungsi utama dari dinding penahan tanah atau retaining wall
adalah untuk mencegah displacement dan sliding di sekitar galian, yang dapat
menyebabkan terjadinya kelongsoran serta mencegah terjadinya penurunan tanah
di sekitar lahan proyek akibat heave pada dasar galian. Selain itu, kedalaman
retaining wall yang tepat dapat mencegah terjadinya piping akibat rembesan air
(seepage) ke dalam galian dan mengurangi terjadinya penurunan tanah di sekitar
lahan proyek akibat dewatering, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab 5.
Gambar 4.12. Piping pada dasar galian
Sumber : Tschebotariof (1982, p. 94)
44 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.13. Perkiraan kedalaman retaining wall
Sumber : Tschebotariof (1982, p. 107)
Beberapa pertimbangan dalam pemilihan tipe dinding penahan tanah yang
akan digunakan antara lain :
Jenis tanah.
Level muka air tanah dan sistem dewatering yang digunakan.
Lokasi dan kondisi lingkungan sekitar.
Ketersediaan alat yang digunakan.
Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka dikenal beberapa jenis
dinding penahan tanah (retaining wall), antara lain sheet piles wall, diaphragm
wall, secant piles wall, contigous bored piles wall dan soldier pile wall.
4.3.1. Sheet Piles Wall
Sheet piles wall merupakan sejumlah sheet pile yang disusun sebaris,
saling mengunci satu sama lain sehingga membentuk suatu konstruksi dinding
penahan tanah sementara maupun permanen, yang mampu menahan beban akibat
tekanan tanah dan air dari sebelah luar galian. Adapun pada bagian atas sheet pile
45 Universitas Kristen Petra
diberi capping beam, untuk mengikat sheet pile tersebut agar lebih kaku dan solid.
Pada saat pemasangan sheet pile, perlu dibuat guide wall agar
dapat tersambung dengan rapi dan lurus.
Sheet pile yang digunakan bisa terbuat dari kayu, baja maupun beton
bertulang. Pemilihan jenis sheet pile yang digunakan tergantung jenis tanah,
kedalaman galian, lokasi galian dan tujuan dari penggunaan sheet pile itu sendiri.
Penggunaan sheet pile dari kayu sudah jarang digunakan, karena hanya
cocok untuk galian yang tidak terlalu dalam (maksimal 2 meter) dan mudah patah
serta harganya cukup mahal.
Sheet pile khususnya yang terbuat dari baja (steel sheet pile), bernilai
ekonomis karena pile bisa digunakan berkali-kali dan cocok digunakan pada lahan
yang memiliki level muka air tanah cukup tinggi karena mampu menahan
rembesan air tanah. Berbeda dengan sheet pile yang terbuat dari beton (concrete
sheet pile), biasanya digunakan sebagai dinding penahan tanah permanen dan
pada umumnya tidak kedap air. Namun hal ini tidak menjadi masalah apabila
dilakukan sistem dewatering ground-water lowering.
Sheet pile bisa digunakan pada tanah berpasir maupun tanah lempung. Jika
tanah dasar memiliki kohesi yang besar, maka sebaliknya adhesi tanah akan kecil,
sehingga sheet pile mudah dipancang atau dicabut kembali. Tetapi, jika tanah
dasar merupakan tanah granular, maka akan friksi atau gesekan pada sekeling
sheet pile akan menyebabkan perlambatan ketika pemancangan atau pencabutan
kembali.
Sheet pile yang terbuat dari baja, memiliki panjang 12 meter dan tidak
cocok untuk pekerjaan galian yang cukup dalam, karena mempertimbangkan
faktor kelangsingan steel sheet pile. Berbeda dengan sheet pile yang terbuat dari
beton, maka ukuran dan panjangnya dapat disesuaikan dengan perencanaan dan
lebih kuat dibandingkan steel sheet pile, sehingga cocok untuk pekerjaan galian
yang cukup dalam.
Steel sheet pile dimasukkan ke dalam tanah dengan cara digetarkan
menggunakan hydraulic vibro hammer. Getaran ini cukup berdampak pada
lingkungan sekitar dan dapat menyebabkan retak-retak pada bangunan tetangga.
46 Universitas Kristen Petra
Oleh karena itu, tidak disarankan untuk digunakan pada lokasi yang berbatasan
langsung dengan bangunan tetangga.
Sedangkan concrete sheet pile, dapat dimasukkan ke dalam tanah dengan
cara ditekan atau diinjeksi, sehingga getaran yang terjadi akan lebih kecil
dibandingkan steel sheet pile. Oleh karena itu, concrete sheet pile lebih cocok
digunakan sebagai struktur penahan tanah di kawasan yang padat. Walaupun
demikian, pada kawasan yang cukup padat, yang jaraknya cukup rapat, resiko
retak pada bangunan tetangga sangat sulit dihindarkan, karena pemancangan sheet
pile akan membuat desakan di dalam tanah, sehingga resiko terjadi retak tetap
masih ada.
Sheet pile dari baja terdiri dari steel section atau potongan-potongan baja
yang dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan ketebalannya kurang
lebih 10 mm dan panjangnya 12 meter. Apabila menginginkan pile lebih panjang,
maka dapat disambung dengan mengelas. Umumnya steel sheet pile yang
digunakan di Surabaya adalah sheet pile yang terbuat dari baja tipe “U”.
Gambar 4.14. Steel Sheet Pile Tipe U yang Umum Digunakan
Sumber : Chew (2009, p. 61)
Secara garis besar steel sheet pile atau turap baja berdasarkan pada
bentuknya dibedakan menjadi 5 bentuk dasar yaitu :
a) Tipe U (U-type) dikembangkan oleh Larssen.
b) Tipe Z (Z-type) dikembangkan oleh Hoesch.
c) Tipe S (S-type) dikembangkan oleh Terre Rouge.
d) Tipe I (I-type) dikembangkan oleh Peine.
e) Tipe Straight Web dikembangkan oleh Lackawana.
47 Universitas Kristen Petra
(a)
(b) (c)
(d) (e)
Gambar 4.15. Steel sheet pile : (a) tipe U, (b) tipe Z, (c) tipe S, (d) tipe I, (e) Straight Web
Sumber : Bazant (1982, p. 14)
Sheet pile dari beton atau biasa disebut concrete sheet pile, terbuat batang
beton bertulang yang dibuat dengan ukuran penampang dan panjang tertentu,
sesuai dengan perencanaan. Bila dituntut untuk kedap air, maka dapat dilakukan
grouting pada daerah sambungan. Pada saat pemancangan concrete sheet pile,
massa tanah yang dipindahkan cukup besar, sehingga akan menimbulkan desakan
tanah di dalam tanah dan perlawanan akibat gaya gesek tanah sepanjang pile. Oleh
karena itu resiko retak pada bangunan sekitar tetap masih ada.
48 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.16. Concrete sheet pile
Sumber : Teng (1982, p. 28)
Untuk galian tanah yang tidak terlalu dalam, maka sheet pile ditanam
begitu saja (cantilever sheet pile), sehingga kestabilan sheet pile sepenuhnya
ditahan oleh tekanan tanah pasif yang timbul di bawah permukaan tanah galian.
Tetapi bila galian cukup dalam dan tekanan tanah serta air tanah cukup besar
maka perlu dipasang support system seperti anchor, bracing atau strutting pada
sheet pile tersebut. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai support system dapat
dilihat pada bab 4.4.
4.3.2. Soldier Pile Wall
Soldier pile cocok digunakan pada tanah jenis tanah berbutir kasar maupun
tanah berbutir halus dan dapat digunakan untuk galian yang cukup dalam. Soldier
pile menggunakan baja WF yang dipancang ke dalam tanah, dengan posisi sayap
baja WF sejajar dengan tepi galian pada jarak tertentu. Selama dilakukan
penggalian, dipasang lagging (papan kayu atau lembaran baja) di antara baja WF,
secara bertahap sesuai dengan kedalaman galian untuk menahan tanah.
Stabilitas dari soldier pile didapat dari jepitan kaki tiang sedalam tertentu
di bawah galian atau dari struting maupun anchor. Baja WF yang biasa digunakan
adalah WF 250 – 400, yang diletakkan berjajar dengan jarak sekitar 1,5 – 3 meter
dengan papan kayu setebal 100 milimeter atau lembaran baja yang biasanya
disisipkan di antara sayap baja WF. Adapun kedalaman baja WF, jarak antar baja
WF dan penggunaan lagging serta struting tergantung dari perencanaannya.
49 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.17. Soldier pile dengan lagging dipasang : (a) di dalam sayap
WF, (b) di sebelah luar galian, (c) diberi grouting, (d) di sebelah dalam galian
Sumber : Teng (1982, p. 47)
4.3.3. Diaphragm Wall
Diaphgram wall mulai dikenal sejak Perang Dunia ke-2 usai, merupakan
suatu dinding penahan tanah yang berupa dinding-dinding beton yang
digabungkan menjadi satu. Diaphgram wall cocok dipakai pada kondisi tanah
yang cukup baik (sedang). Tanpa mengesampingkan biaya pelaksanaan
diaphragma wall yang cukup mahal, terdapat beberapa keunggulan dari
diaphragma wall yang dapat dijadikan pertimbangan, antara lain :
Dapat digunakan pada saat struktur penahan tanah lainnya tidak dapat
digunakan, seperti galian terlalu dalam.
Tidak menimbulkan kebisingan dan getaran pada saat pelaksanaan.
Dapat digunakan sebagai dinding basement itu sendiri (permanent retaining
wall).
Mampu menahan tekanan tanah lateral dan tekanan air yang besar.
Mencegah terjadinya lateral movement pada tanah sekitar galian.
Cocok untuk sistem cut-off dewatering.
50 Universitas Kristen Petra
Secara garis besar, tahap-tahap pelaksanaan diaphragma wall sebagai
berikut:
a) Pembuatan guide wall.
Untuk memastikan dimensi dan kelurusan dari dinding diafragma, maka perlu
dibuat suatu balok beton pengarah di kedua sisi, sejajar sehingga membentuk
suatu parit, yang nantinya akan menjadi digali untuk dinding diafragma.
Balok beton pengarah inilah yang dinamakan guide wall. Adapun contoh-
contoh bentuk guide wall, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.18. Contoh bentuk-bentuk guide wall
Sumber : Hajton, Regele (1984, p. 52)
51 Universitas Kristen Petra
b) Penggalian lubang dinding diafragma.
Setelah guide wall dibuat, maka penggalian lubang dinding panel diafragma
dapat dilakukan dengan menggunakan clamshell atau hydrofraise. Fungsi alat
ini sama dengan back-hoe, yaitu untuk menggali, namun keunggulannya
adalah mampu menggali hingga kedalaman yang cukup jauh dibandingkan
back-hoe. Penggalian dilakukan sedalam tinggi diaphragm wall dan
sepanjang jarak tertentu yang telah direncanakan. Selama dilakukan
penggalian, untuk mencegah longsor di dalam lubang galian, maka dapat
dimasukkan bentonite slurry. Adapun skema penggalian dapat dilihat pada
gambar di bawah ini
Gambar 4.19. Skema penggalian dinding diafragma
Sumber : Gambin, Devis (1991, p. 27)
c) Pemasangan elemen joint.
Setelah mencapai kedalaman dan lebar yang direncanakan serta panjang
tertentu, maka dipasang suatu batang panjang pada kedua sisi galian yang
dinamakan stop-end joint with waterstop atau dikenal CWS joint. Tujuan
penggunaan CWS joint adalah untuk membentuk interlocking joint dan
memasang waterstop pada dinding diafragma. Waterstop berfungsi untuk
mencegah terjadinya rembesan air pada sambungan antar dinding diafragma.
Selain menggunakan CWS joint, dapat pula menggunakan tabung baja bulat
untuk membentuk interlocking joint dinding panel.
52 Universitas Kristen Petra
Gambar 4.20. Stop-End Joint with Single Waterstop
Sumber : Chew (2009, p. 89)
d) Penulangan dan pengecoran.
Bersamaan dengan pemasangan stop-end joint, tulangan yang sudah dirakit
dimasukkan ke dalam galian. Setelah tulangan dan stop-end joint siap, maka
beton cair akan dipompa ke dalam lubang galian dengan menggunakan pipa
tremi. Berat volume beton yang lebih besar akan mendesak bentonite slurry
mengalir keluar dari lubang dinding diafragma. Adapun, bentonite slurry
yang mengalir keluar akan ditampung dan dipakai untuk lubang berikutnya.
Ketika dinding diafragma mulai mengeras, maka akan mengikat waterstop
yang dipasang pada CWS joint, sehingga pada saat CWS joint dicabut, maka
waterstop akan tertinggal.
Gambar 4.21. Penulangan dan pengecoran panel dinding diafragma
Sumber : Gambin, Devis (1991, p. 28)
53 Universitas Kristen Petra
Dua belas jam setelah pengecoran panel dinding pertama selesai, maka
penggalian untuk panel dinding berikutnya siap dilakukan, dimulai dari sisi
terjauh stop-end joint. Dua puluh empat jam setelah pengecoran panel dinding
pertama, maka penggalian sisi yang berbatasan dengan stop-end joint baru boleh
dilakukan. Lubang galian kedua siap, maka stop-end joint dapat dicabut dan
waterstop akan tertinggal, mengeras, menjadi satu dengan panel dinding pertama.
Lalu tulangan dinding yang sudah dirakit dimasukkan ke dalam lubang dinding
kedua, bersamaan dengan dipasangnya stop-end joint pada sisi sebelahnya.
Setelah selesai dipasang maka pengecoran siap dilakukan lagi, demikian
seterusnya hingga terbentuk rangkaian dinding penahan tanah yang disebut
diaphgram wall.
Gambar 4.22. Skema pelaksanaan penggalian diaphragm wall
Sumber : Chew (2009, p. 87)
54 Universitas Kristen Petra
Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin panjang sebuah panel
dinding diafragma, maka akan semakin menguntungkan, karena mengurangi
pemakaian waterstop dan mengontrol rembesan pada sambungan (jika tidak
menggunakan waterstop). Tetapi, ada beberapa pertimbangan yang juga perlu
diperhatikan terkait dengan panjangnya panel dinding diafragma, yakni :
Stabilitas tanah pada lubang panel yang lebih pendek lebih terjamin.
Panel dinding yang pendek, lebih memperkecil kemungkinan terjadinya
slurry loss pada jenis tanah yang sangat permeable.
Seluruh pekerjaan pengecoran untuk satu panel dinding harus sudah selesai
sebelum terjadi pengerasan yang cukup berarti pada beton (initial set). Dalam
prakteknya proses pengecoran satu buah panel dinding tidak boleh lebih dari
empat jam.
Panjang panel dan tempat joint antar panel harus disesuaikan dengan denah
struting ataupun anchor, apabila digunakan.
Pada saat pre-eleminary design, ditentukan terlebih dahulu kedalaman
dinding berdasarkan pertimbangan strukutral kestabilan galian, selanjutnya baru
dipertimbangkan panjang dan lebar atau tebal dinding panel berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas.
Adapun lebar atau tebal dinding panel juga dipengaruhi ketersediaan alat
di lapangan. Clamshell dapat membuat lubang selebar 45 cm hingga 150 cm,
sedangkan rotary drill dapat membuat lubang selebar 40 cm hingga 120 cm.
Disarankan tebal minimum dinding adalah 45 cm, agar memudahkan pipa tremi
keluar masuk dan kemudahan pengerjaan di lapangan.
Untuk mempercepat pelaksanaan diaphragma wall, maka sejak tahun
1970 telah dikenal dinding panel pre-cast. Selain pemasangan yang cepat dan
mudah, penggunaan dinding panel pre-cast mempunyai beberapa keuntungan
yakni kualitas dinding beton lebih terjamin dan dinding panel mempunyai
permukaan yang halus sehingga cocok digunakan sebagai dinding basement itu
sendiri.
Proses penyiapan lubang galian sama dengan metode konvensional, tetap
digali dengan clamshell atau hydrofraise, lalu diberi slurry untuk menjaga
kestabilan lubang. Tetapi tidak perlu menggunakan tremi untuk pengecoran,
55 Universitas Kristen Petra
diganti dengan memasukkan panel-panel pre-cast ke dalam lubang dengan
menggunakan crane.
(a) (b)
Gambar 4.23. Pre-cast diaphragm wall
Sumber : Hajton, Regele (1984, p. 58)
Pada gambar 4.23.(a) menunjukkan panel dinding pre-cast dikombinasi
dengan batang beton yang menjadi tumpuan dari panel dinding yang menahan
tanah. Tebal batang beton ini minimum dua kali lipat dari tebal panel. Adapun
tebal standar batang balok adalah 50 cm dan tebal panel dinding adalah 25 cm.
Metode ini digunakan pada tanah yang cukup lunak atau loose.
Pada gambar 4.23.(b) menunjukkan panel dinding pre-cast yang tipikal,
yang dihubungkan satu sama lainnya dengan interlocking joint, hampir sama
dengan concrete sheet pile wall. Metode ini cocok digunakan pada tanah yang
cukup kaku, medium hingga sangat padat.
4.3.4. Contigous Bored Piles Wall
Contigous Bored Piles Wall merupakan sekumpulan bored pile yang
disusun segaris, dan diantara bored pile akan disisipkan dengan bored pile lainnya
atau dengan bentonite yang dicampur dengan semen atau bisa pula dengan
56 Universitas Kristen Petra
lagging, sehingga membentuk suatu dinding penahan. Contigous Bored Piles Wall
dapat digolongkan dinding penahan tanah permanen, hampir cocok digunakan
untuk semua jenis tanah. Contigous Bored Piles Wall biasa dipakai bila konstruksi
terletak pada lahan yang padat dan ramai, karena selain amat kuat, juga
pengerjaannya tidak menimbulkan getaran yang keras dan tidak terlalu bising. Di
samping beberapa kelebihan bored-pile wall, juga terdapat beberapa kekurangan
seperti rembesan air tanah sukar dihindari dan pendetailan joint dengan balok atau
pelat lebih rumit.
Gambar 4.24. Contigous Bored Piles Wall yang tersusun dari bored piles
Sumber : Tan, Gue (1998, p. 102)
Gambar 4.25. Contigous Bored Piles Wall dengan menggunakan lagging
Sumber : Xanthakos (1994, p. 62)
Gambar 4.26. Contigous Bored Piles Wall dengan menggunakan campuran
bentonite dengan semen
Sumber : Xanthakos (1994, p. 62)
57 Universitas Kristen Petra
Proses pelaksanaannya sama seperti bored pile pada umumnya. Pertama-
tama dilakukan pengeboran, disertai dengan memasukkan bentonite slurry ke
dalam lubang bor untuk menjaga kestabilan lubang bor. Pada kasus-kasus tertentu,
lubang bor dapat dipasang temporary casing. Selanjutnya beton cair dimasukkan
dengan tremi ke dalam lubang bor menggantikan bentonite slurry, demikian
seterusnya. Adapun selanjutnya dilakukan pengeboran lubang ketiga terlebih
dahulu lalu kelima dan ketujuh. Selang 24 jam, akan dikerjakan lubang kedua,
keempat dan seterusnya.
4.3.5. Secant Pile Wall
Secant Pile Wall pada prinsipnya hampir sama dengan Contiguos Bored
Pile Wall, merupakan bored pile yang disusun segaris, saling memotong satu
sama lain, sehingga membentuk dinding penahan yang kedap air dan lebih kuat
dibandingkan sheet pile wall.
Secant Pile Wall terdiri dari 2 bagian pile, yaitu primary pile (female pile)
dan secondary pile (male pile).
a. Primary pile (female pile), merupakan bored pile tanpa tulangan, yang dibuat
dengan diameter yang lebih kecil daripada secondary pile. Pada pile ini diberi
aditif retarder untuk memperpanjang waktu setting beton, sehingga pile ini
masih cukup lunak atau lemah pada saat dilakukan pengeboran secondary
pile. Tujuan pile ini dibuat lunak karena pada bagian tertentu dari pile ini akan
hancur digantikan dengan secondary pile.
b. Secondary pile (male pile), merupakan bored pile yang dibuat dengan
diameter yang lebih besar daripada primary pile dan diberi tulangan. Pada
proses pengerjaan dinding, pile ini akan disisipkan diantara primary pile.
Pengeboran secondary pile akan memotong sebagian primary pile (sekitar 10
cm), sehingga ketika dicor akan menghasilkan interlocking joint antara pile
yang satu dengan lainnya.
Secant pile wall yang dibuat haruslah lurus dan kaku. Oleh karena itu
sebelum dilakukan pengeboran pile, dapat dibuat guide wall sebagai acuan.
Setelah guide wall dibuat maka, pertama dilakukan pengeboran untuk membuat
primary pile. Pelaksanaan pengeboran sama dengan bored-pile wall. Hanya saja,
58 Universitas Kristen Petra
antara primary pile yang satu dengan lainnya dipisahkan pada jarak tertentu dan
tidak melebihi diameter secondary pile. Setelah primary pile mengeras maka,
dilakukan pengerjaan untuk secondary pile yang letaknya diantara primary pile,
sehingga terbentuk dinding penahan.
Gambar 4.27. Secant Pile Wall
Sumber : Tan, Gue (1998, p. 103)
4.4. Support System pada Retaining Wall
Support System yang dimaksud adalah penahan atau penopang yang
digunakan pada retaining wall yang membantu untuk menahan tekanan dari sisi
bagian luar dinding, sehingga lebih stabil. Ada 3 kategori support system pada
dinding penahan, antara lain strutting (bracing), anchored dan soil bern.
Sedangkan untuk dinding tanpa menggunakan support system dikenal dengan
cantilever wall (no-support).
Gambar 4.28. Support system pada retaining wall
Sumber : Nunnnally (2004, p. 73)
Cantilever Wall biasa digunakan apabila galian tidak terlalu dalam.
Kestabilan dinding sepenuhnya ditahan oleh tekanan tanah pasif yang berada di
59 Universitas Kristen Petra
muka dindingnya. Jadi pada sistem ini tidak menggunakan penopang seperti
strutting.
Strutted Wall dan Anchored Wall digunakan pada galian tanah yang dalam
dan lebar. Strutted Wall merupakan kondisi dimana dinding penahan tanah
diperkuat dengan menggunakan horizontal strutting atau inclined bracing (raker),
seperti pada gambar 4.29. Sedangkan pada anchored wall, dinding penahan
diperkuat dengan menggunakan angker yang dijangkar ke dalam tanah yang
ditahan. Ada 2 jenis angker yang digunakan yakni tie-back anchor dan grouting
pre-stress anchor, seperti pada gambar 4.30.
Gambar 4.29. (a) Horizontal strutting, (b) Inclined bracing
Sumber : Ahlvin, Smoots (1988, p. 87)
Gambar 4.30. (a) Tie-back anchor, (b) Grouting pre-stress anchor
Sumber : Ahlvin, Smoots (1988, p. 87)
Horizontal strutting biasanya terbuat dari baja WF atau rangka batang
baja. Support system ini cocok digunakan pada lahan yang luas dan dalam. Pada
bagian sudut, strutting yang digunakan dipasang diagonal menahan pada kedua
sisi dinding, seperti pada gambar 4.33.
60 Universitas Kristen Petra
Inclined bracing biasa terbuat dari baja atau balok beton, dengan sudut
kemiringan yang aman sekitar 300 hingga 400. Reaksi pada batang diteruskan ke
tanah melalui kicker block. Pada inclined bracing, perlu diperhatikan adanya gaya
aksial yang bekerja pada batang, sehingga dapat mengakibatkan gaya angkat ke
atas (up-lift) pada retaining wall. Oleh karena itu berat sendiri dan kedalaman
penembusan retaining wall harus cukup dalam, untuk melawan gaya up-lift ini.
Anchor biasa digunakan pada lahan yang sempit, galian dalam tetapi
galian terletak di tengah-tengah lahan proyek. Anchor tidak dapat digunakan
apabila galian berbatasan langsung dengan existing building. Untuk proyek yang
membutuhkan ruang gerak yang luas, maka anchor dapat digunakan. Selain itu
anchor juga dapat digunakan pada tempat yang tidak bisa menggunakan strutting
atau tidak terjangkau oleh strutting. Adapun instalasi angker dapat dilihat pada
gambar di bawah ini.
Gambar 4.31. Tahapan pembuatan anchor
Sumber : Chew (2009, p. 82)
61 Universitas Kristen Petra
Lokasi angker harus diperhatikan oleh perencana struktur, supaya angker
dapat memberikan fungsi maksimum. Lokasi angker harus melewati daerah
sliding surface yang aktif (active wedge) dan mencapai daerah pasif (passive
wedge) sehingga dapat memberi kapasitas tahanan penuh, seperti pada contoh
gambar 4.32.
Gambar 4.32. Contoh penempatan lokasi angker yang baik
Sumber : Ahlvin, Smoots (1988, p. 57)
Gambar 4.33. Contoh skema dinding penahan tanah dengan strutting dan anchor
Sumber : Chew (2009, p. 86)
62 Universitas Kristen Petra
Adapun beberapa macam kemungkinan kegagalan retaining wall dengan
angker (anchor), antara lain:
Keruntuhan sistem angker.
Hal ini disebabkan karena sistem angkernya tidak memadai, seperti
pengikatan baut pada retaining wall tidak cukup kuat, tie-rod putus karena
mengalami korosi atau terjadi penambahan beban (surcharge load) yang
melebihi rencana.
Gambar 4.34. Keruntuhan pada sistem angker
Sumber : Fang (1982, p. 47)
Gerakan tanah di dasar retaining wall.
Hal ini terjadi karena penembusan retaining wall tidak cukup dalam atau
karena terjadinya pengikisan tanah oleh aliran air (piping) atau karena
penggalian dilakukan melebihi kedalaman rencana.
Gambar 4.35. Gerakan tanah pada dasar galian
Sumber : Fang (1982, p. 48)
63 Universitas Kristen Petra
Keruntuhan akibat momen lentur.
Hal ini terjadi karena kesalahan memperkirakan besarnya tekanan tanah
lateral yang terjadi, ada tambahan tekanan dari luar retaining wall atau karena
pemilihan jenis retaining wall yang tidak tepat.
Gambar 4.36. Keruntuhan karena momen lentur
Sumber : Fang (1982, p. 48)
Sliding pada tanah
Hal ini biasa terjadi pada tanah kohesif, disebabkan angker kurang panjang
dan retaining wall kurang dalam dan disertai penambahan kadar air dalam
tanah.
Gambar 4.37. Sliding pada tanah
Sumber Fang (1982, p.49)
64 Universitas Kristen Petra
Anchor dan struting yang digunakan biasanya dipasang pada semacam
balok horisontal yang dipasang pada retaining wall atau disebut juga waller,
terbuat dari baja WF, kanal C atau balok beton, seperti pada gambar di bawah ini.
Gambar 4.38. Contoh penggunaan waller
Sumber : Teng (1982, p. 69)
Gambar 4.39. Contoh sambungan antara strutting dengan waller
Sumber : Tschebotariof (1982, p. 94)
65 Universitas Kristen Petra
Anda mungkin juga menyukai
- Jurnal Ma 2 Tie in RararDokumen15 halamanJurnal Ma 2 Tie in RararniraBelum ada peringkat
- 8.bahan Peledak Dan Teknik Peledakan (Persiapan Peledakan)Dokumen40 halaman8.bahan Peledak Dan Teknik Peledakan (Persiapan Peledakan)weldy kurniawanBelum ada peringkat
- DEWATERINGDokumen26 halamanDEWATERINGeddy batunaBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Peledakan Geometri PeledakanDokumen18 halamanLaporan Akhir Peledakan Geometri PeledakanIqbal Firman Pranata100% (1)
- JurnalDokumen15 halamanJurnalniraBelum ada peringkat
- Pola Dan Arah Pemboran SurfaceDokumen11 halamanPola Dan Arah Pemboran SurfaceFaisal SaleBelum ada peringkat
- Pola PeledakanDokumen18 halamanPola PeledakanrisalBelum ada peringkat
- Shrink and Fill Stoping Method RevisiDokumen9 halamanShrink and Fill Stoping Method RevisiUtuh Jamping100% (1)
- Jurnal Ma 3 Iga MawarniiDokumen12 halamanJurnal Ma 3 Iga MawarniiAsfikar 0072Belum ada peringkat
- Jurnal Praktikum Simulasi Tie In: Arya Dhipa Sakti 09320200182 C3Dokumen11 halamanJurnal Praktikum Simulasi Tie In: Arya Dhipa Sakti 09320200182 C3ollapsBelum ada peringkat
- Bab 4Dokumen16 halamanBab 4Ridho Muhammad AfifBelum ada peringkat
- Pola Pemboran Dan Pola Peledakan SurfaceDokumen7 halamanPola Pemboran Dan Pola Peledakan SurfaceIbro Retno SugiartoBelum ada peringkat
- Arya Dhipa Sakti 2Dokumen11 halamanArya Dhipa Sakti 2AndinugiBelum ada peringkat
- Laporan Awal Pola Pemboran Dan Pola PeledakanDokumen16 halamanLaporan Awal Pola Pemboran Dan Pola PeledakanFaisal SaleBelum ada peringkat
- Presentasi PGMT Kelompok 4Dokumen28 halamanPresentasi PGMT Kelompok 4Abid HabibiBelum ada peringkat
- Materi Kelompok 2 TBT Cut and Fill StopingDokumen9 halamanMateri Kelompok 2 TBT Cut and Fill Stopingzalsa vionathaBelum ada peringkat
- Jurnal Simulasi Tie inDokumen11 halamanJurnal Simulasi Tie inCaturRahmad SBelum ada peringkat
- Bab III Peledakan TBTDokumen9 halamanBab III Peledakan TBTyozialwanBelum ada peringkat
- Materi Tambang Bawah Tanah Karisma N R KalutiDokumen26 halamanMateri Tambang Bawah Tanah Karisma N R KalutiGeryBelum ada peringkat
- Pola PemboranDokumen51 halamanPola Pemborananon_456587083Belum ada peringkat
- Modul Praktikum Pemboran Dan Peledakan: Bab Iii: Persiapan PeledakanDokumen18 halamanModul Praktikum Pemboran Dan Peledakan: Bab Iii: Persiapan PeledakanandreBelum ada peringkat
- #E Bab VDokumen6 halaman#E Bab VSyafrullahBelum ada peringkat
- Teknik PeledakanDokumen31 halamanTeknik PeledakanMila karmilaBelum ada peringkat
- Tugas 4 Perbaikan TanahDokumen45 halamanTugas 4 Perbaikan Tanahryadi pratama RyadiBelum ada peringkat
- Bab Ix Organisasi Dan Tenaga KerjaDokumen10 halamanBab Ix Organisasi Dan Tenaga KerjaMuhammad Rizki KojaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen56 halamanBab IiEfa OctaviaBelum ada peringkat
- Jurnal Ma 2Dokumen16 halamanJurnal Ma 2ollapsBelum ada peringkat
- Bab 2 Landasan TeoriDokumen12 halamanBab 2 Landasan Teori8172 Nanang ZulkarnaenBelum ada peringkat
- Bab V Rencana PenambanganDokumen36 halamanBab V Rencana PenambanganEko PoernomoBelum ada peringkat
- Laporan PeledakanDokumen22 halamanLaporan PeledakanzehanfahmiBelum ada peringkat
- JURNAL MA 3 SIMULASI TIE AsfikarDokumen11 halamanJURNAL MA 3 SIMULASI TIE AsfikarAsfikar 0072Belum ada peringkat
- Cristian SimanullangDokumen33 halamanCristian Simanullangmawar lehaBelum ada peringkat
- Metode Dewatering Pada Pekerjaan SIPILDokumen14 halamanMetode Dewatering Pada Pekerjaan SIPILPungge Prima HuwaBelum ada peringkat
- Kaison Dan Tiang BorDokumen19 halamanKaison Dan Tiang BorStw 33Belum ada peringkat
- Bore PileDokumen8 halamanBore PileCakra Wisma Cipta MandiriBelum ada peringkat
- PP Perbaikan TanahDokumen57 halamanPP Perbaikan TanahPieter KristiantoBelum ada peringkat
- 2017 TA TM 071001300100 Bab-3Dokumen28 halaman2017 TA TM 071001300100 Bab-3rama kasim05Belum ada peringkat
- METODE PENAMBANGAN Tambang Bawah TanahDokumen17 halamanMETODE PENAMBANGAN Tambang Bawah TanahMuh Fachrie Anggriawan100% (1)
- Metode Block CavingDokumen7 halamanMetode Block CavingChristina TambunanBelum ada peringkat
- Pola Peledakan Underground BlastingDokumen12 halamanPola Peledakan Underground BlastingmochwidyBelum ada peringkat
- Analisis Fragmentasi Batuan Hasil PeledakanDokumen13 halamanAnalisis Fragmentasi Batuan Hasil PeledakanKaisan Shoope100% (4)
- Bore PileDokumen4 halamanBore PileBeny NainggolanBelum ada peringkat
- LERENGDokumen35 halamanLERENGNiamBelum ada peringkat
- BAB 9 Pola Pemboran UndergroundDokumen14 halamanBAB 9 Pola Pemboran UndergroundMoh. Iqbal Luthfi HidayatBelum ada peringkat
- Perencanaan PeledakanDokumen30 halamanPerencanaan PeledakanSoni Silalahi HalohoBelum ada peringkat
- Seputar Tambang BawahDokumen18 halamanSeputar Tambang BawahSitorus BintangBelum ada peringkat
- Faktor Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemilihan Metode PenambanganDokumen24 halamanFaktor Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemilihan Metode PenambanganToto Susilo QuaressmaBelum ada peringkat
- Tugas Perbaikan Tanah 22Dokumen9 halamanTugas Perbaikan Tanah 22riamurdani09Belum ada peringkat
- PerkerasanDokumen9 halamanPerkerasanriamurdani09Belum ada peringkat
- Makalah Proctor Modified NadyaDokumen15 halamanMakalah Proctor Modified NadyaNadya Rizki UmamiBelum ada peringkat
- Bench BlastingDokumen16 halamanBench BlastingHasrul Asrori0% (1)