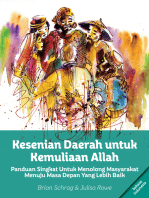1068-Article Text-1722-1-10-20201105
1068-Article Text-1722-1-10-20201105
Diunggah oleh
Sultan RizzaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
1068-Article Text-1722-1-10-20201105
1068-Article Text-1722-1-10-20201105
Diunggah oleh
Sultan RizzaHak Cipta:
Format Tersedia
Vidya Wertta Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020
p-ISSN 0852-7776-e-ISSN 2655-7282
https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta
AKTUALISASI PANCASILA DALAM
BUDAYA MASYARAKAT BALI AGA
(Studi di Desa Cempaga dan Pedawa, Buleleng, Bali)
I Gusti Agung Paramita
paramita@unhi.ac.id
Prodi Ilmu Filsafat Hindu
Fakultas Ilmu Agama, Seni dan Budaya
Universitas Hindu Indonesia Denpasar
ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang aktualisasi Pancasila dalam budaya
masyarakat Bali Aga khususnya di dua desa yakni Desa Cempaga dan
Pedawa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik
pengumpulan data dibagi menjadi tiga yakni observasi, wawancara
mendalam dengan para tokoh adat dan agama, dan studi dokumen yang
berhubungan dengan penelitian. Setelah data terkumpul akan dilakukan
analisis secara deskriptif kualitatif, lalu dituliskan menjadi laporan
penelitian. Berdasarkan penelitian di lapangan, didapatkan hasil yakni
bahwa budaya masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga dan Pedawa sangat
relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi dua sila dari Pancasila
dalam masyarakat di Desa Cempaga yakni sila tentang kerakyatan dan
keadilan sosial. Masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga menerjemahkan
prinsip kerakyatan dalam kehidupan keseharian. Bentuk aktualisasi nilai
Pancasila dalam budaya masyarakat Desa Pedawa juga tidak jauh berbeda
dengan Desa Cempaga. Khususnya yang berhubungan dengan
musyawarah mufakat dan sikap gotong royong yang merupakan wujud
dari Eka Sila Bung Karno. Dalam kehidupan sosio-kultural di Desa
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 1
Pedawa, prinsip-prinsip pemusyawaratan dijunjung tinggi. Mereka akan
bermusyawarah ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan
keagamaan—apalagi berhubungan dengan pengambilan keputusan
penting di desanya.
Kata kunci: Aktualisasi, Nilai, Pancasila
ABSTRACT
This article discusses the actualization of Pancasila in the culture of the
Bali Aga people, especially in two villages, namely Cempaga and Pedawa
Villages. This research is a qualitative research. Data collection techniques
are divided into three, namely observation, in-depth interviews with
traditional and religious leaders, and study of documents related to
research. After the data is collected, a qualitative descriptive analysis will
be carried out, then written into a research report. Based on research in the
field, the results obtained are that the culture of the Bali Aga community
in Cempaga and Pedawa villages is very relevant to the values of
Pancasila. Actualization of the two principles of Pancasila in the
community in Cempaga Village, namely the principles of populist and
social justice. The people of Bali Aga in Cempaga Village interpret the
principles of democracy in their daily life. The actualization form of
Pancasila values in the culture of the Pedawa Village community is also
not much different from Cempaga Village. Especially those related to
consensus agreement and mutual cooperation which is the manifestation
of Eka Sila Bung Karno. In the socio-cultural life in Pedawa Village, the
principles of deliberation are upheld. They will hold meetings when there
are social, cultural and religious activities — especially when it comes to
making important decisions in their village.
Keywords: Actualization, Value, Pancasila
I. PENDAHULUAN
Sejak beberapa tahun terakhir isu-isu tentang Pancasila mengemuka
menjadi isu publik. Hal ini didasari atas munculnya gerakan-gerakan yang
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 2
dianggap anti Pancasila. Memang, selama ini pembudayaan nilai Pancasila
belum begitu banyak dilakukan. Banyak masyarakat Indonesia yang hafal
tentang Pancasila, namun tidak melaksanakan nilai yang terkandung dalam
Pancasila dengan baik. Begitu juga sebaliknya, anak-anak muda—
jangankan mengaktualisasikan nilai Pancasila, sila-sila yang terkandung
dalam Pancasila pun mereka tidak hafal. Ini problem serius yang dihadapi
bangsa Indonesia.
Studi-studi tentang Pancasila selama ini juga lebih banyak
menempatkan Negara sebagai subyek Pancasila, sementara masyarakat,
termasuk masyarakat adat sebagai obyek yang mesti di Pancasilakan.
Padahal, masyarakat adat sudah ada sebelum bangsa Indonesia ini
terbentuk. Masyarakat adat memiliki sistem nilai dan kulturalnya sendiri.
Jika ditelusuri historis dari pemikiran Pancasila, memang perlu digali dari
kedalaman adat dan budaya masyarakat Indonesia.
Masyarakat Indonesia sudah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila
dalam budaya, religi dan kearifan lokal mereka jauh sebelum rumusan
Pancasila menjadi dasar negara. Hal ini sejalan dengan pandangan
Notonagoro (dalam Sutrisno, 2006:6) bahwa bangsa Indonesia
berpancasila dalam “Tripakara”, yakni dalam adat istiadat, dalam budaya,
keagamaan dan dalam kenegaraan.
Sebagaimana diafirmasi Riyanto (2015: 13) dalam Buku Kearifan
Lokal dan Pancasila, kearifan lokal bangsa adalah “akar” dari Pancasila,
sekaligus pohon yang kokoh rimbun penuh dengan dahan-dahan dan
dedaunan lebat yang di dalamnya berlindung kupu-kupu indah dan aneka
burung rupawan. Jadi kearifan lokal tersembunyi dalam tradisi hidup
sehari-hari, dalam mitologi, dalam sastra yang indah, dalam bentuk-bentuk
ritual penghormatan, atau upacara adat, dalam wujud nilai-nilai simbolik
wujud rumah, dalam bahasa dan kebudayaan kesenian, dan dalam tata
kehidupan masyarakat.
Dalam artikel ini penulis berupaya menelusuri “akar” Pancasila dengan
melihat pada aktivitas budaya, adat dan agama masyarakat Bali Aga di dua
Desa yakni Desa Cempaga dan Pedawa. Asumsinya adalah bahwa
sebenarnya masyarakat di dua desa ini sudah mengaktualisasikan nilai-
nilai Pancasila—dalam arti yang luas—dalam kehidupan keseharian
mereka, sebelum mereka mengenal rumusan tentang Pancasila sebagai
dasar pembentukan bangsa Indonesia. Studi ini penting dilakukan untuk
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 3
melihat korelasi nilai Pancasila dengan keberadaan masyarakat adat dan
sistem nilainya khususnya di Bali.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif yang secara umum didefinisikan sebagai
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, simbol, dan
perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini dilakukan di daerah Bali,
khususnya di dua desa yakni Desa Cempaga dan Pedawa. Penulis sudah
pernah menjajagi dan membaca refesensi tentang dua desa ini, menggali
kearifan lokal dan pandangan hidup masyarakat yang sangat relevan
dengan nilai Pancasila.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yakni obervasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Observasi
dilakukan untuk dapat mengamati secara langsung aktivitas masyarakat di
lokasi penelitian. Dengan melakukan pengamatan di lapangan dalam
waktu yang cukup lama diharapkan dapat diperoleh data yang lebih
bersifat natural artinya, data atau perilaku yang tidak dibuat-buat karena
diketahui ada kegiatan penelitian.
Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dilakukan dengan
cara menentukan terlebih dahulu informan. Melalui wawancara mendalam
diharapkan perolehan data terutama menyangkut world-view masyarakat
terkait dengan Pancasila. Untuk menuntun wawancara dibuatkan pedoman
wawancara. Studi dokumen dalam hal ini difokuskan pada dokumen baik
berupa foto maupun dokumen-dokumen lain serta tulisan-tulisan terkait
dengan aktualisasi nilai Pancasila.
III. PEMBAHASAN
3.1 Bentuk Aktualisasi Pancasila dalam Budaya Masyarakat Desa
Cempaga
Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa peneliti berupaya
memotret aktivitas sosio-kultural dan religi masyarakat Bali Aga di
Cempaga yang memang sarat akan nilai Pancasila. Setidaknya ini
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 4
menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia khususnya di Desa Bali Aga,
sudah mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam ranah
adat, agama dan budaya mereka. Bisa dikatakan, mereka mengamalkan
nilai Pancasila jauh sebelum Pancasila menjadi dasar Negara Indonesia.
Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai Pancasila bisa digali di dalam
kearifan lokal dan budaya masyarakat di Indonesia. Dalam konteks ini,
peneliti berupaya memaparkan aktualisasi dua sila dari Pancasila dalam
masyarakat di Desa Cempaga yakni sila tentang kerakyatan dan keadilan
sosial.
Menurut Riyanto (2015: 38), dalam kearifan lokal, konsep
kerakyatan lebih cenderung pada subyek kehidupan yang arif dan
bijaksana. Dalam pengertian kerakyatan tersembunyi pula makna
kebijaksanaan dan kearifan. Konsep kerakyatan juga berhubungan dengan
“tata damai” hidup masyarakat, bukan dengan hal-hal yang berhubungan
dengan keputusan rakyat. Tata damai dalam kearifan lokal masyarakat
Indonesia merupakan produk dari relasi sehari-hari.
Begitu juga musyawarah dan mufakat dalam kearifan lokal tidak
hanya berdiskusi atau perjumpaan formal dalam rapat penentuan kebijakan
publik. Nilai musyawarah dan mufakat merupakan mili kehidupan
keseharian masyarakat. Artinya prinsip musyawarah mufakat bukan hanya
berada pada tatanan verbal semata, melainkan juga kehidupan nyata dan
faktual untuk masa depan yang lebih baik.
Berangkat dari penjelasan tersebut bisa dikatakan bahwa
masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga menerjemahkan prinsip kerakyatan
dalam kehidupan keseharian. Di dalam kerakyatan ini, terkandung juga
prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan-
keputusan yang berhubungan dengan tata kehidupan adat, budaya, dan
agama di Desa Cempaga. Hal ini teraktual ketika masyarakat Cempaga
melakukan sangkepan—pertemuan dalam skala kecil yang dilakukan
setiap bulan.
Biasanya sangkepan ini dilakukan dengan beberapa topik
pertemuan seperti misalnya kegiatan masyarakat mayah dedosan—
berhubungan dengan iuran desa yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial,
budaya dan keagamaan. Tidak hanya itu, kegiatan sangkep juga dilakukan
ketika desa akan mengadakan kegiatan Saba atau upacara keagamaan.
Sangkepan ini dipimpin oleh seorang Ulun Desa yang terdiri dari 1) baan
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 5
kenawan, 2) baan kekehe, 3) takin kenawan, 4) takin kekehe, 5)
keban/pangenter, dan 6) panglunduan/juru getek.
Dalam proses sangkepan yang dipimpin oleh Ulun Desa,
pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak, atau hanya
mengikuti keinginan subyektif Ulun Desa, melain berdasarkan
musyawarah dan mufakat antara krama desa. Misalnya saja sebelum
mengawali upacara Saba, Ulun Desa biasanya melaksanakan tugasnya
melakukan pengecekan terkait keberadaan pura di Desa Cempaga.
Ketika dalam proses pengecekan pura ada bangunan yang mesti
diperbaiki atau direhab, maka keputusan perehaban bangunan itu
dilakukan secara musyawarah dan mufakat dalam sangkepan desa. Krama
desa diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah dan dialog
untuk menemukan satu keputusan yang akan dijalankan bersama. Hal ini
disampaikan seorang narasumber dari Cempaga yang bernama I Putu
Mangku sebagai berikut:
”Kami di Desa Cempaga melaksanakan kegiatan berdasarkan
musyawarah mufakat. Apalagi yang berhubungan dengan
pengambilan kebijakan dan keputusan di tingkat desa. Biasanya
kegiatan musyawarah dilakukan menjelang akan melaksanakan
kegiatan Saba, diawali dengan Ulu melaksanakan tugasnya untuk
melihat bangunan pura kemudian apabila hal-hal yang harus
diperbaiki maka dalam pelaksanaan musyawarah dicetuskan
biasanya dicetusan dalam sangkep. Ketika musyawarah dalam
sangkep sudah diputuskan untuk melakukan perehaban dan
disetujui oleh masyarakat, baru akan dilaksanakan perehaban. Jadi
pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat
bersama”. (Wawancara 19/07/2020).
Perihal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain, yakni I
Gede Budiarta tokoh masyarakat di Desa Cempaga sebagai berikut:
“Musyawarah tentunya dilakukan setiap bulan yang disebut dengan
sangkep. Biasanya ini dilakukan berkaitan dengan kegiatan
kemasyarakatan seperti mayah dedosan, atau bayar iuran tetapi
kalau untuk kegiatan yadnya biasanya dilakukan paruman yang
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 6
dipimpin oleh Ulu yang dilaksanakan setiap akan melaksanakan
upacara atau nemu gelang tadi. Kalau sangkep insidential juga
dilakukan jika ada kegiatan yang sifatnya mendesak dan terpaksa
(Wawancara 19/07/2020).
Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa
pengambilan keputusan dalam tata sosial dan keagamaan di Desa
Cempaga didasarkan pada pertemuan atau sangkepan. Meskipun di dalam
sistem pemerintahan desa dipimpin oleh Ulun Desa, namun dalam setiap
pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan sosial
kemasyarakatan dan agama, mereka tetap melakukan musyawarah untuk
mencapai sebuah kesepakatan.
Mereka selalu dituntun oleh spirit bernama “kebijaksanaan” dalam
menjalankan kewajiban-kewajiban sosial dan keagamaan. Karena tujuan
mereka melakukan sangkepan—khususnya untuk kegiatan Saba—adalah
untuk harmonisasi baik itu antara manusia, Tuhan maupun alam semesta.
Hal ini bisa kita lihat dari pelaksanaan aktivitas Saba di Desa Cempaga. Di
sini antara prinsip kerakyatan, ketuhanan, dan keadilan sosial mewujud
dalam rentetan upacara Saba tersebut. Kerakyatan dalam konteks
pengelolaan kekuatan masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan,
sementara Ketuhanan ditunjukkan dalam wujud sradha dan bhakti mereka,
dan keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk kesesuaian antara hak dan
kewajiban yang mereka dapatkan.
Pandangan tentang keadilan di Desa Cempaga bisa dilihat dari
kepemimpinan di dalam sistem pemerintahan desa adat. Kepengurusan di
dalam sistem pemerintahan desa adat ditentukan berdasarkan ririgan
(urutan) dan senioritas perkawinan atau di dalam bahasa mereka sebagai
ulu apad. Artinya struktur kepemimpinan desa pakraman ditentukan atas
dasar keseniorannya berdasarkan atas catatan waktu perkawinan mereka.
Setiap anggota masyarakat yang telah menikah, secara berjenjang nantinya
pasti akan sampai pada struktur kepengurusan desa pakraman. Setiap
masyarakat akan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk
menempati posisi di dalam struktur pemerintahan desa adat ini. Ini
menarik jika dilihat dari prinsip atau nilai-nilai keadilan. Artinya
”keadilan” bagi masyarakat Cempaga ketika semua masyarakat memiliki
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 7
kesempatan yang sama untuk ngayah—perbuatan yang dilakukan dengan
tulus ikhlas—di dalam keprajuruan desa mereka.
Selain itu, prinsip kerakyatan dan keadilan sosial bisa dilihat dalam
kegiatan atau rentetan upacara Saba Kuningan di Desa Cempaga. Rentetan
Sabha Kuningan ini meliputi persiapan upacara, puncak upacara dan
penutup. Pada persiapan upacara Saba Kuningan ini seluruh kekuatan
masyarakat digunakan, termasuk sekaa teruna atau anak-anak muda di
desa tersebut. Mereka mengawali kegiatan dengan ngayah, membersihkan
lingkungan pura dan desa, setelah itu berburu binatang Kijang, selanjutnya
mengerahkan masyarakat untuk mebat (mengolah daging buruan yang
digunakan untuk keperluan upacara ritual).
Bila memperoleh kijang betina diolah menjadi berabagai jenis
makanan seperti jajeruk, gagecok, urab putih, timbungan. Bila yang
diperoleh kijang jantan diolah sebagaimana jenis olahan kijang betina,
namun ditambah dengan olahan berupa sate. Olahan dimaksud
ditempatkan di samping olahan makanan yang berbahan babi. Bila
memperoleh kijang jantan dalam perburuan, upacara kuningan tersebut
diperpanjang perayaannya yang disebut dengan Naksuin.
Setelah mengolah hasil buruan, mereka dikoordinir oleh seorang
yang bernama sayan desa—seorang yang bertugas mengkoordinir
masyarakat untuk segala aktivitas dalam Saba Kuningan. Cara sayan desa
menyebar informasi pun menarik, yakni dengan memegang tampul bale
gede lalu mengeluarkan kata-kata yang bernada ajakan untuk gotong
royong. Misalnya desa pesu jaja nasi, desa pesu mebat yang artinya desa
mengeluarkan jajanan dan nasi, desa keluar untuk membuat olahan daging
buruan. Menariknya, masyarakat dengan penuh kegairahan mengikuti
apapun komando yang dikeluarkan oleh sayan desa ini.
Setelah selesai membuat olahan, mereka akan membersihkan alat-
alat yang digunakan untuk menabuh dan membersihkan segala jenis
peralatan yang digunakan untuk upacara ritual Saba Kuningan. Para
seniman seperti penabuh dan penari dibeirkan kesempatan untuk latihan
untuk menyambut para dewa yang akan turun ketika upacara dilaksanakan.
Selanjutnya, setelah olahan makanan sudah tersedia, maka sayan desa
kembali memanggil krama desa dan krama teruna untuk mengambil hak
mereka berupa lawar atanding.
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 8
Di sini ada yang menarik bahwa dalam rangkaian persiapan upacara
Saba Kuningan, masyarakat di Desa Cempaga diminta untuk menjalankan
kewajiban dan dipenuhi hak-haknya setelah selesai melaksanakan
kewajiban tersebut. Tidak hanya lawar atanding, masyarakat juga
dipersilakan mengambil makanan yang sudah disediakan. Pada puncak
upacara dan penutup, mereka benar-benar guyub memuja para dewa
melalui tarian dan tetabuhan, begitu juga upacara ritual.
Jika dicermati rentetan upacara Saba di atas, kita bisa melihat
sebuah rangkaian kegiatan yang terpola dengan memberdayakan seluruh
kekuatan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kerakyatan
bagi masyarakat Desa Cempaga adalah sikap gotong royong dalam setiap
pelaksanaan kegiatan sosial dan religi. Mereka dikoordinir oleh sayan desa
untuk melaksanakan setiap rentetan upacara. Setelah masyarakat di Desa
Cempaga melaksanakan kewajiban mereka, maka mereka dipersilakan
untuk mengambil haknya berupa makanan. Ini tidak hanya berlaku bagi
kaum dewasa saja, melainkan juga untuk generasi muda di Desa Cempaga
yang mereka sebut sebagai krama taruna. Berangkat dari pengamatan
tersebut, bisa dijelaskan bahwa masyarakat Cempaga memiliki prinsip dan
nilai Pancasila dalam tata kehidupan sosial dan keagamaan mereka.
3.2 Bentuk Aktualisasi Pancasila dalam Budaya Masyarakat Desa
Pedawa
Bentuk aktualisasi nilai Pancasila dalam budaya masyarakat Desa
Pedawa juga tidak jauh berbeda dengan Desa Cempaga. Khususnya yang
berhubungan dengan musyawarah mufakat dan sikap gotong royong yang
merupakan wujud dari Eka Sila Bung Karno. Dalam kehidupan sosio-
kultural di Desa Pedawa, prinsip-prinsip pemusyawaratan dijunjung
tinggi. Mereka akan bermusyawarah ketika ada kegiatan-kegiatan sosial,
budaya dan keagamaan—apalagi berhubungan dengan pengambilan
keputusan penting di desanya.
Sebagaimana disampaikan tokoh masyarakat Pedawa yakni I Ketut
Belgi bahwa musyawarah dilakukan setiap akan melaksanakan kegiatan di
desa. Kegiatan bermusyawarah ini disebut dengan istilah sangkep. Ada
berbagai jenis sangkep, ada yang sudah terjadwal, ada juga yang
incidental. Biasanya sangkep yang tidak terjadwal ini dilakukan apabila
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 9
ada kejadian-kejadian mendadak dan desa harus memutuskan sesuatu.
Berikut kutipan wawancaranya.
“Di Desa Pedawa prinsip pemusyawaratan memang dijunjung
tinggi. Keputusan desa diambil dengan jalan bermusyawarah
agar mencapai kata mufakat. Kegiatan musyawarah di sini
disebut sangkep. Ada sangkep yang terjadwal, tetapi ada juga
yang tidak dijadwalkan, atau ketika ada persoalan yang menuntut
segera ada solusi. Di sini peran Ulun Desa, Tugu, yakni pimpinan
desa sangat penting dalam upaya bermusyawarah dengan
masyarakat. Sangkep yang bersifat incidental dilakukan ketika
terjadi mara bahaya di desa dan bencana. Apapun yang menjadi
keputusan desa tetap ditempuh dengan jalan musyawarah”.
(Wawancara 20/07/2020).
Berdasarkan kutipan wawancara di atas bisa dijelaskan bahwa
pengambilan keputusan penting di desa, meskipun dalam konteks
kebencanaan yang sifatnya mendadak, tetap diputuskan berdasarkan
prinsip permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Di sini
peran Ulun Desa sebagai pimpinan tradisional sangat penting karena
dianggap mewakili “kebijaksanaan” dalam kepemimpinannya. Ulun Desa
akan mengambil keputusan berdasarkan hasil dari sangkepan tersebut.
Tidak hanya berhubungan dengan persoalan insidental kebencanaan,
dalam kegiatan-kegiatan agama dan budaya pun, kegiatan sangkep tetap
dilakukan.
Menurut tokoh Desa Pedawa yang lain seperti I Kadek Satria,
pengambilan keputusan di Desa Pedawa didasarkan pada semangat
bermusyawarah. Banyak jenis kegiatan bermusyawarah di Desa Pedawa
yang didasarkan pada runtutan kegiatan. Ada yang namanya sangkep desa
(musyawarah yang diadakan di tingkat desa), ada sangkep Bungan tahun,
sangkep sari, sangkep ketipat yang dilakukan dengan lelintih nemu gelang
yakni sebuah siklus lima tahunan yang berisi aktivitas keagamaan.
Sangkep Bungan tahun ini berhubungan dengan rapat karma ngarep
yang dalam setiap pertemuannya setiap karma membawa sarin tahun.
Krama di sini dibagi dalam nomor tata lungguh atau nomor induk
perkawinan. Dalam rapat ini mereka membahas tentang rangkaian upacara
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 10
ritual yang disebut Sabha, peraturan desa yang disebut awig-awig yang
perlu disempurnakan. Sementara sangkep ketipat adalah rapat yang
dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan upacara ritual.
Apabila ada persoalan yang harus diselesaikan secara darurat, maka
seorang Tugu atau Bendesa, sejenis pimpinan desa, dan sangket (kepala
desa) akan mengeluarkan pakebah atau musyawarah darurat yang
dilakukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Desa. Artinya
dalam keadaan darurat pun masyarakat di Desa Pedawa tetap
mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
Berikut kutipan wawancara dengan Kadek Satria, tokoh agama di Desa
Pedawa.
“Musyawarah dilakukan dalam setiap pengambilan keputusan.
Artinya ketika akan ada keputusan yang berhubungan dengan sosial,
budaya dan agama di Desa, selalu dikerjakan dengan mengambil
sikap musyawarah terlebih dahulu di antaranya ada yang disebut
dengan sangkep desa, sangkep Bungan taun, sangkep sari, sangkep
ketipat dilakukan dengan lelintih nemu gelang (yaitu siklus 5
tahunan), jika berjalan dengan baik, jika tidak maka dilaksanakan
dengan 6 tahun sekali. Apabila dalam situasi darurat berdasarkan
keputusan tugu (bendesa) dan sangket (kepala desa) dengan
mengeluarkan pekebah darurat. (Wawancara 19/07/2020).
Berdasarkan kutipan wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa
prinsip musyawarah mufakat menjadi basis dalam pengambilan keputusan
di tingkat desa. Mereka menganggap bahwa keputusan yang menyangkut
situasi dan kondisi di desa, mesti diambil melalui kesepakatan bersama.
Meskipun ada jajaran kepemimpinan di desa, baik itu kepemimpinan
tradisional maupun administratif, fungsinya mempertahankan kehidupan
bersama yang harmonis di desa, baik itu secara sekala maupun niskala.
Kebijakan di tingkat desa diambil dengan pola komunikasi komunal, tidak
hanya di bidang sosial dan budaya saja, melainkan juga keagamaan.
Hal ini juga tercermin dalam pelaksanaan siklus yang mereka sebut
Lelintih Nemu Gelang. Wayan Sukrata seorang tokoh intelektual di
Pedawa menjelaskan bahwa Lelintih Nemu Gelang ini adalah peredaran
waktu sampai kembali lagi pada saat semula. Hal ini berhubungan dengan
rangkaian kegiatan di Desa Adat Pedawa, dari awal sampai akhir dan
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 11
kembali lagi seperti semula. Adapun kegiatan tersebut meliputi sabha,
sangkep, muga. Sabha di sini dimaksudkan untuk upacara ritual yang
dilaksanakan di pura atau tempat suci yang ada di Pedawa, sementara
sangkep adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan, dan terakhir Muga
adalah sebuah ritus mempersembahkan makanan kepada para dewa atau
bhatara di Desa Pedawa.
Siklus Lelintih Nemu Gelang ini menjadi ciri khas tradisi
masyarakat Pedawa. Dalam siklus ini terdapat kegiatan sosial, budaya dan
keagamaan yang sangat guyub dan komunal. Semua masyarakat terlibat
dalam aktivitas ini, termasuk para generasi muda. Rangkaian upacara
Sabha misalnya, dilakukan dengan pola gotong royong dan pembagian
tugas kepada masyarakat.
Mereka akan dikoordinir oleh pimpinan desa untuk melaksanakan
setiap kegiatan tersebut. Bisa dikatakan, prinsip gotong royong sangat
kentara dalam pelaksanaan sabha. Peran lembaga adat sangat kuat di sini
untuk memobilisasi karma atau anggotanya. Bahkan kekuatan pimpinan
adat lebih kuat dalam memobilisasi masyarakat daripada pimpinan di
lembaga-lembaga dinas atau lembaga formal.
Berdasarkan wawancara dengan Ketut Rostika, semangat gotong
royong di Desa Pedawa diwarisi secara turun temurun. Mereka memegang
teguh nilai Tri Hita Karanga yakni hubungan yang harmonis antara Tuhan,
Lingkungan alam dan sesama manusia. Harmonisasi baik secara makro
dan mikro menjadi cita-cita masyarakat di Desa Pedawa. Apabila ada yang
tidak harmonis, mereka akan berupaya membuat keadaan menjadi stabil
dan seimbang baik melalui kegiatan sosial maupun keagamaan.
Semangat gotong royong dalam kesosialan masyarakat di Desa
Cempaga juga bisa dilihat dari pembentukan sub kelompok sosial yang
mereka sebut dengan istilah sekaa. Sekaa ini memiliki hak dan kewajiban
berdasarkan pembagian wilayah tugas mereka. Ada yang namanya sekaa
sambangan yang memiliki wilayah tugas di parahyangan, sedangkan
gotong royong di tingkat pawongan dan palemahan dilakukan berdasarkan
Yos—yakni kelompok keluarga, tempek dan kamling.
Tidak hanya itu, di Desa Pedawa juga terdapat kelompok sekaa yang
berhubungan dengan aktivitas kesenian seperti sekaa tabuh, sekaa gegitan,
dan sekaa-sekaa yang lain. Ini menunjukkan bahwa tipologi masyarakat di
Pedawa bersifat komunal dengan prinsip gotong royong dan menyama
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 12
braya yang cukup kuat. Mereka selalu menjaga hubungan yang harmonis
antar sesama/pawongan. Segala jenis pelaksanaan kegiatan di tingkat desa
pun diselesaikan dengan semangat gotong royong tersebut. Artinya,
masyarakat Pedawa sudah menerapkan Eka Sila jauh sebelum mereka
mengenal dan memahami nilai-nilai Pancasila. Semangat gotong royong
bahkan telah dilaksanakan sampai saat ini, meskipun Desa Pedawa terkena
dampak perkembangan teknologi dan informasi sebagai konsekuensi
modernitas.
3.3 Respon Masyarakat Desa Cempaga dan Pedawa Terhadap
Pancasila
Masyarakat di dua Desa Bali Aga baik itu Desa Cempaga maupun
Pedawa meyakini bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila
masih relevan dengan tradisi, adat dan budaya yang telah diwarisi secara
turun-temurun. Antara Pancasila dan pandangan dunia masyarakat dua
desa ini pun dianggap saling berkorelasi, karena memang Pancasila
merupakan nilai yang digali dari kedalaman budaya dan adat masyarakat
di Indonesia. Bahkan masyarakat meyakini, tidak ada perbedaan signifikan
antara tradisi dan kehidupan religius mereka dengan nilai Pancasila yang
selama ini menjadi dasar dan falsafah bernegara.
Sebagaimana disampaikan oleh tokoh di Desa Pedawa bernama I
Ketut Belgi, bahwa tidak ada pertentangan antara nilai yang terkandung di
dalam Pancasila dan budaya yang selama ini dijalankan di Desa Pedawa—
aturan berupa awig-awig yang mengikat krama desa Pedawa pun dibuat
sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini artinya, Pancasila memang
digali dari tradisi dan budaya yang hidup di tanah Indonesia sehingga
pelaksanaannya sangat relevan dengan budaya masyarakat di Desa
Pedawa.
Respon tentang hubungan Pancasila, adat dan tradisi di Desa Bali
Aga juga disampaikan oleh tokoh sekaligus akademisi dari Desa Pedawa
yakni di Kadek Satria. Menurutnya, Pancasila di Desa Pedawa tidak hanya
dipahami oleh masyarakatnya, melainkan juga dilaksanakan. Pancasila
tidak menjadi doktrin, tetapi sudah menjadi sebuah laku hidup yang tetap
dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Pedawa. Berikut kutipan
wawancaranya.
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 13
“Pancasila di Desa Pedawa tidak dipahami akan tetapi dilaksanakan.
Pancasila tidak menjadi doktrin tetapi menjadi sebuah perilaku yang
dilaksanakan oleh masyarakat Pedawa karena Pancasila merupakan
laku hidup bagi masyarakat Pedawa sendiri. Pandangan hidup dan
keyakinan masyarakat di Desa Pedawa pun sangat relevan dengan
nilai-nilai Pancasila. Saya rasa relevansi ini menunjukkan bahwa
Pancasila memang digali dari kehidupan masyarakat di Indonesia.
Ini ajaran yang original dari masyarakat Indonesia”. (Wawancara
19/07/2020).
Respon yang sama juga disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat
di Desa Cempaga, salah satunya adalah I Putu Mangku. Dirinya bahkan
menyampaikan selama ini nilai Pancasila masih sangat cocok dengan
tradisi, adat dan budaya masyarakat di Desa Cempaga. Tidak ada
pertentangan nilai di dalamnya, karena apa yang terkandung di dalam
Pancasila, juga kami laksanakan di Cempaga, meskipun masyarakat
Cempaga tidak semua paham dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka sudah
melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini artinya, masyarakat di
Desa Cempaga sudah berpancasila di dalam adat dan budaya mereka.
Pandangan hidup mereka juga merepresentasikan dan mengaktualisasikan
nilai dari Pancasila tersebut.
Bahkan I Putu Mangku menyatakan, kalau nilai Pancasila diganti
dengan ideologi yang lain, bisa jadi justru tidak relevan dengan nilai dan
budaya yang selama ini dijalankan di Desa Cempaga. Berikut kutipan
wawancaranya.
“Saat ini Pancasila masih cocok dengan adat, budaya yang kami
laksanakan di Desa Cempaga. Meskipun adat dan budaya kami
tergolong kuno dan warisan leluhur, tapi ternyata memiliki
kesamaan dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya kami sudah
menerapkan Pancasila jauh sebelum dijadikan dasar Negara. Justru
seandainya ideologi itu diganti dengan yang lain, belum tentu cocok
dengan kehidupan dan budaya kami di Cempaga. Saya rasa
Pancasila sudah mewakili adat, budaya dan religi kami di Desa
Cempaga”. (Wawancara 19/07/2020).
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 14
Tidak hanya I Putu Mangku saja, tokoh Desa Cempaga yang lain
yakni I Gede Budiarta menyampaikan hal yang sama bahwasannya nilai-
nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat cocok dengan pandangan
hidup masyarakat di Desa Cempaga. Misalnya saja sila persatuan sangat
melekat di dalam kehidupan sosial masyarakat di Cempaga. Mereka
mengedepankan persatuan sosial untuk keharmonisan baik itu bhuana alit
maupun bhuana agung. Dalam setiap aktivitas baik itu sosial, budaya dan
keagamaan mereka mengedepankan persatuan untuk melaksanakan
kegiatan atau aktivitas tersebut. Berangkat dari sinilah, masyarakat
Cempaga meyakini jika Pancasila menjadi bagian dari kehidupan mereka.
Tidak hanya itu, masyarakat Cempaga juga mengedepankan gotong
royong dalam setiap pelaksanaan upacara agama. Mereka menyadari
dengan gotong royong semua persoalan dan kegiatan di Desa Cempaga
bisa terlaksana dengan baik. Melalui gotong royong pula solidaritas sosial
akan terus terjaga dengan baik.
IV. PENUTUP
Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa budaya
masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga dan Pedawa sangat relevan dengan
nilai-nilai Pancasila. Aktualisasi dua sila dari Pancasila dalam masyarakat
di Desa Cempaga yakni sila tentang kerakyatan dan keadilan sosial.
Masyarakat Bali Aga di Desa Cempaga menerjemahkan prinsip
kerakyatan dalam kehidupan keseharian. Bentuk aktualisasi nilai Pancasila
dalam budaya masyarakat Desa Pedawa juga tidak jauh berbeda dengan
Desa Cempaga. Khususnya yang berhubungan dengan musyawarah
mufakat dan sikap gotong royong yang merupakan wujud dari Eka Sila
Bung Karno. Dalam kehidupan sosio-kultural di Desa Pedawa, prinsip-
prinsip pemusyawaratan dijunjung tinggi. Mereka akan bermusyawarah
ketika ada kegiatan-kegiatan sosial, budaya dan keagamaan—apalagi
berhubungan dengan pengambilan keputusan penting di desanya.
DAFTAR PUSTAKA
Abdulah, Irwan. 2006. Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 15
Astra, Semadi I Gde. 1997. Birokrasi Pemerintahan Bali Kuno Abad XII-
XIII. Disertasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Bakker, SJ. 1984. Filsafat Kebudayaan, Sebuah Pengantar. Yogyakarta:
Kanisius.
Budi Utama, I Wayan. 2011. Adaptasi budaya Masyarakat Bali Aga di
desa Cempaga Kabupaten Buleleng dalam Merespon Regulasi Negara
dalam Bidang Agama. Disertasi: Denpasar: Universitas Udayana.
Dwipayana, AA GN Ari. Melewati Benteng Ajeg Bali. Pengantar untuk
Buku Henk Schulte Nordholt, Bali: Benteng Terbuka 1955-2005,
2010.
--------------------, 2005. Globalism. Pergulatan politik Representasi atas
Bali. Uluangkep.
Notonagoro. 1980. Pancasila Secara Ilmiah Populer. Dhakarta: Patjuran
Tudjuh.
Nordholt, Henk Schulte. 2010. Bali Benteng Terbuka. Denpasar: Pustaka
Larasan.
Paramita, I Gusti Agung. 2015. Wacana Kebudayaan dalam Dinamika
Pers di Arena Politik Lokal. Tesis di Program Studi Magister
Ilmu Agama dan Kebudayaan Universitas Hindu Indonesia.
Paramita, I Gusti Agung. 2016. Air, Puisi dan Industri, terbit dalam Buku
Air, Tradisi dan Industri (ed) I Wayan Budi Utama. Denpasar:
Pustaka Ekspresi bekerjasama dengan Pascasarjana Unhi
Denpasar.
Pranarka, A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila. Jakarta:
Yayasan Proklramasi CSIS.
Riyanto, Armada dkk. 2015. Kearifan Lokal-Pancasila: Butir Filsafat
Keindonesiaan. Yogyakarta: PT Kanisius.
Sudiarja, A. dkk. 2006. Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat
Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya.
Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 16
Suharja, Arya. 2017. Bali Mandara: Estafeta untuk Generasi Muda.
Denpasar: Bappeda Litbang Provinsi Bali
Suryawan, I Ngurah. 2010. Genealogi Kekerasan dan Pergilakan
Subaltern. Jakarta: Predana.
Sutrisno, Slamet. 2006. Filsafat dan Ideologi Pancasila. Yogyakarta:
Penerbit Andi.
JURNAL ILMIAH
http://www.dharmasmrti.com/index.php/jurnal_agama/article/view/
96
WIDYA WERTTA Volume 3 Nomor 2 Tahun 2020 17
Anda mungkin juga menyukai
- Faktor Pendorong Dan Penghambat Modernisasi: Desa PakramanDokumen21 halamanFaktor Pendorong Dan Penghambat Modernisasi: Desa PakramanOjiBelum ada peringkat
- 2321 4854 1 SMDokumen9 halaman2321 4854 1 SMAyu LestariBelum ada peringkat
- 10.+40757 102136 1 PB - 109 117Dokumen9 halaman10.+40757 102136 1 PB - 109 117Arjuna Heri PrasetyoBelum ada peringkat
- Luh Nugrahini RahayuDokumen16 halamanLuh Nugrahini RahayuSyafroyy SyafroyyBelum ada peringkat
- 345-Article Text-801-1-10-20210409Dokumen14 halaman345-Article Text-801-1-10-20210409mrido297Belum ada peringkat
- J1A022027 - Review JurnalDokumen9 halamanJ1A022027 - Review JurnalBintang AndromedaBelum ada peringkat
- Kajian Nilai-Nilai Karakter Kearifan Lokal Masyarakat Sunda Dalam Membentuk Sikap Moral KewarganegaraanDokumen11 halamanKajian Nilai-Nilai Karakter Kearifan Lokal Masyarakat Sunda Dalam Membentuk Sikap Moral Kewarganegaraanraprakoso2Belum ada peringkat
- Admin Jko,+8.+Muh.+Ali+JennahDokumen14 halamanAdmin Jko,+8.+Muh.+Ali+JennahAlyatri AgustinaBelum ada peringkat
- Artikel Bodo Contong.Dokumen11 halamanArtikel Bodo Contong.mazaziz08Belum ada peringkat
- Hubungan Tradisi Munjung Dengan Sikap Ke d768d11dDokumen13 halamanHubungan Tradisi Munjung Dengan Sikap Ke d768d11dDevia UtamiBelum ada peringkat
- Artikel BaduyDokumen12 halamanArtikel BaduySiti BarkahBelum ada peringkat
- IcrhdDokumen20 halamanIcrhdwildananmillahmashyarBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 3-3Dokumen9 halamanMakalah Kelompok 3-3Oktavia SilitongaBelum ada peringkat
- Baimppkn, 081. Analisis Rasionalisasi Nilai-Nilai Mitos Tradisi Bepapas Pada Masyarakat Melayu Sambas Di Desa Tempapan Hulu Kabupaten-3Dokumen15 halamanBaimppkn, 081. Analisis Rasionalisasi Nilai-Nilai Mitos Tradisi Bepapas Pada Masyarakat Melayu Sambas Di Desa Tempapan Hulu Kabupaten-3anis zulaifahBelum ada peringkat
- Novalsiregar, 1. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 129 - 138Dokumen10 halamanNovalsiregar, 1. Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 129 - 138rafiqialvanBelum ada peringkat
- None 6327341fDokumen8 halamanNone 6327341fXun BaoBelum ada peringkat
- 3800 9612 3 PBDokumen18 halaman3800 9612 3 PBFradilahBelum ada peringkat
- Tradisi Di HinduDokumen10 halamanTradisi Di HinduDevia UtamiBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen9 halaman1 SMMuhammad ihwanul usliminBelum ada peringkat
- 2857 11273 1 PBDokumen15 halaman2857 11273 1 PBAyu Widya ArtiniBelum ada peringkat
- 853-Article Text-2139-1-10-20221101Dokumen8 halaman853-Article Text-2139-1-10-20221101Tasya RosaBelum ada peringkat
- 06 - Kekerabatan Dan SoldaritasDokumen5 halaman06 - Kekerabatan Dan SoldaritasWinda FitrianaBelum ada peringkat
- Mochamd Edo Syaaf Jafar 20105028 Tugas Penelitihan Sosial Keagamaan-1Dokumen13 halamanMochamd Edo Syaaf Jafar 20105028 Tugas Penelitihan Sosial Keagamaan-1kreatif bangetBelum ada peringkat
- PROPOSAL PenelitianDokumen13 halamanPROPOSAL PenelitianMasyanita SinagaBelum ada peringkat
- 30445-Article Text-35718-1-10-20190821Dokumen16 halaman30445-Article Text-35718-1-10-20190821luckymalvinoBelum ada peringkat
- Review Jurnal IBDDokumen3 halamanReview Jurnal IBDDek OnatBelum ada peringkat
- Diyah Pujining (Sripsi)Dokumen87 halamanDiyah Pujining (Sripsi)Dewa Putu TagelBelum ada peringkat
- Hani Fajrah Tugas SainsDokumen6 halamanHani Fajrah Tugas SainsHANI FAJRAHBelum ada peringkat
- Caroline FebryliaDokumen20 halamanCaroline FebryliaCaroline FebryliaBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - Kekentalan Adat BatakDokumen23 halamanKelompok 1 - Kekentalan Adat BatakDiah AdawiahBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen15 halaman1 SMClarita SimangunsongBelum ada peringkat
- 49 300 1 PBDokumen14 halaman49 300 1 PBLusi Rahma YantiBelum ada peringkat
- Jurnal Lampuhyang Lembaga Penjaminan Mutu Stkip Agama Hindu Amlapura Volume 13 Nomor 1 Januari 2022 p-ISSN: 2087-0760 e-ISSN: 2745-5661Dokumen14 halamanJurnal Lampuhyang Lembaga Penjaminan Mutu Stkip Agama Hindu Amlapura Volume 13 Nomor 1 Januari 2022 p-ISSN: 2087-0760 e-ISSN: 2745-5661Lard KardBelum ada peringkat
- 612-Research Results-1446-1-10-20190817Dokumen8 halaman612-Research Results-1446-1-10-20190817Wilda Dwi Ilsa PutriBelum ada peringkat
- MID (METODE PENELITIAN SENI) Bungadiyati TodingDokumen7 halamanMID (METODE PENELITIAN SENI) Bungadiyati Todingbungadiyati todingBelum ada peringkat
- 4 Bab1Dokumen17 halaman4 Bab1mujahidinmaruf47Belum ada peringkat
- 1761 3543 1 SMDokumen10 halaman1761 3543 1 SMMilati HimatunaBelum ada peringkat
- Budaya KulkulDokumen14 halamanBudaya KulkulIntan Tri DamayanthieBelum ada peringkat
- Template-Jurnal-Sosbud (AutoRecovered)Dokumen6 halamanTemplate-Jurnal-Sosbud (AutoRecovered)Budriyon BudriyonBelum ada peringkat
- Makalah Etnis Bugis MakassarDokumen41 halamanMakalah Etnis Bugis MakassarMNM MahmuddinBelum ada peringkat
- 4045 11693 1 PB PDFDokumen8 halaman4045 11693 1 PB PDFMuhammad RaflyBelum ada peringkat
- Article TextDokumen8 halamanArticle TextHadit Zulqi RezaBelum ada peringkat
- 3 PBDokumen9 halaman3 PBRein SiraitBelum ada peringkat
- Firdani Annisa Dhika Sahari - I3401201057 - Praktikum Minggu Ke 4Dokumen6 halamanFirdani Annisa Dhika Sahari - I3401201057 - Praktikum Minggu Ke 4Firdani Annisa Dhika SahariBelum ada peringkat
- 958-Article Text-4106-1-10-20220801Dokumen11 halaman958-Article Text-4106-1-10-20220801Erik Aria winataBelum ada peringkat
- Shermawan,+7.+artikel WarthaDokumen8 halamanShermawan,+7.+artikel WarthaperpustakaansundakecilBelum ada peringkat
- Bab IDokumen19 halamanBab Ievoshaykal.ex0Belum ada peringkat
- 219-Article Text-855-3-10-20180305Dokumen10 halaman219-Article Text-855-3-10-20180305Luh Putu AnggrenyBelum ada peringkat
- Siska Ariyanti - 152210026 - Tugas Paparan PancasilaDokumen3 halamanSiska Ariyanti - 152210026 - Tugas Paparan PancasilaSiska AriyantiBelum ada peringkat
- 146-Article Text-202-1-10-20210312Dokumen9 halaman146-Article Text-202-1-10-2021031229Ni Made Sri Suartini XI MIPA 7Belum ada peringkat
- Kampung Naga - IndraP2KM - 2017Dokumen17 halamanKampung Naga - IndraP2KM - 2017Indra KWBelum ada peringkat
- A.fahrul Islami F031181003Dokumen18 halamanA.fahrul Islami F031181003Andi Fahrul IslamiBelum ada peringkat
- Skripsi Imelda Piri 1-5Dokumen50 halamanSkripsi Imelda Piri 1-5emilBelum ada peringkat
- 1347-Article Text-4704-1-10-20211217Dokumen5 halaman1347-Article Text-4704-1-10-20211217Jisal qaarBelum ada peringkat
- 12 Published TeologiAgama Agama - JurnalHARMONIDokumen28 halaman12 Published TeologiAgama Agama - JurnalHARMONIImo AndersonBelum ada peringkat
- Bolong KopingDokumen14 halamanBolong Kopingsahidin_iBelum ada peringkat
- 8419 Gotong-Royong+sbg+implementasi+pancasilaDokumen11 halaman8419 Gotong-Royong+sbg+implementasi+pancasilagantengbangetpro1Belum ada peringkat
- Makalah Bahasa Indonesia Rani MardeswanDokumen11 halamanMakalah Bahasa Indonesia Rani MardeswanRani MardeswanBelum ada peringkat
- RESUME JURNAL KEWARGANEGARAAN FixDokumen5 halamanRESUME JURNAL KEWARGANEGARAAN FixRegita IbrahimBelum ada peringkat
- Kesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikDari EverandKesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikBelum ada peringkat