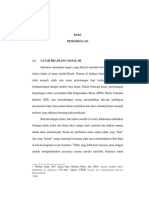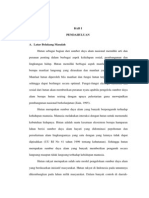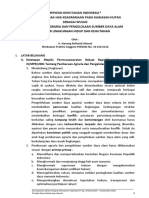Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia
Diunggah oleh
Kemas Bedi0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
3 tayangan5 halamanJudul Asli
Sejarah hukum pengelolaan hutan di indonesia
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
3 tayangan5 halamanSejarah Hukum Pengelolaan Hutan Di Indonesia
Diunggah oleh
Kemas BediHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
Kemas Muhammad Ardian
05 / 189624 / hk / 17071
Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia
Kehutanan ada suatu praktek untuk membuat, mengelola, menggunakan, dan
melestarikan hutan untuk kepentingan manusia.
Undang-Undang republik Indonesia No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan,
definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
Belum lama ini ada sebuah publikasi yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai
Negara perusak hutan nomor 1 (satu) di dunia. Sangat ironis sekali karena sebenarnya
dikenal sebagai Negara yang memiliki kawasan hutan tropis basah (tropical rain forest)
terluas kedua di dunia setelah Brazilia. Namun demikian, sejak tiga dekade terakhir ini
kawasan hutan di Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius dari segi kuantitas
maupun kualitasnya. Ini disebabkan karena jumlah penduduk yang mengandalkan hutan
sebagai sumber penghidupan terus bertambah dari tahun ke tahun, juga disebabkan
karena pemerintah secara sadar telah mengeksploitasi sumber daya hutan sebagai sumber
pendapatan dan devisa Negara yang paling diandalkan setelah sumber daya alam minyak
dan gas bumi.
Memang secara nyata, eksploitasi sumber daya hutan yang dilakukan pemerintah
telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan
pemberian konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan
(HPHH), atau konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) pemerintah mampu mendongkrak
pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menyerap
tenaga kerja, menggerakan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah.
Hal ini juga menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan sumber daya hutan akibat
eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi selain menimbulkan kerugian ekologi
(ecological cost) yang tak terhitung nilainya, juga menimbulkan kerusakan social dan
budaya termasuk pembatasan akses dan penggusuran hak-hak masyarakat atas sumber
daya hutan (social and cultural cost).
Degradasi kuantitas dan kualitas sumber daya hutan di Indonesia terjadi bukan
semata-mata karena faktor kepadatan penduduk, rendahnya tingkat kesejahteraan
ekonomi masyarakat, yang cenderung dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di dan
sekitar hutan yang memiliki tradisi perladangan gilir balik (shifting cultivation). Tetapi,
kerusakan sumber daya hutan justru terjadi karena pilihan paradigma pembangunan yang
berbasis Negara (state-based resource development), penggunaan manajemen
pembangunan yang bercorak sentralistik dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan
ekonomi, yang didukung dengan instrument hukum dan kebijakan yang bercorak represif
(repressive law).
Sejarah hukum pengelolaan hutan di Indonesia selama ini sudah mengalami tiga
jaman. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, kemudian pemerintahan bala tentara
Dai Nippon Jepang, sampai instrument hukum produk pada masa pasca kemerdekaan
Indonesia, termasuk pada masa pemerintahan orde lama, orde baru, dan masa
pemerintahan orde reformasi.
Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dipelopori oleh Herman Willem
Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, tugas yang dibebankan adalah
merehabilitasi kawasan hutan melalui kegiatan reforestasi pada lahan-lahan hutan yang
mengalami degradasi serius. Banyak hal yang telah dilakukan, antara lain, membuat
ordonansi-ordonansi tentang reforestasi, kemudian membentuk Jawatan Kehutanan yang
diberikan wewenang mengelola hutan di Jawa dan Madura.Dalam perkembangannya,
peraturan-peraturan hukum tersebut pada dasarnya mengandung banyak kelemahan,
tumpang tindih, dan terutama tidak memperoleh dukungan konsolidasi sosial dan budaya
masyarakat setempat, sehingga tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk
mengoperasikan pemangkuan dan pengusahaan hutan seperti yang diharapkan
pemerintah Hindia Belanda.
Selama masa pendudukan tentara Jepang pengelolaan hutan di Jawa mengalami
kegoncangan, dalam arti tidak berjalan seperti pada masa pemerintahan kolonial Belanda,
selain karena sedikit dari bekas pegawai Jawatan Kehutanan Belanda yang mau bekerja
untuk kepentingan pemerintah Dai Nippon, juga karena keadaan chaos akibat perang
gerilya rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan tidak memungkinkan pengelolaan
hutan berlangsung seperti yang diharapkan pemerintah Dai Nippon. Karena itu, sampai
menjelang jatuhnya kekuasaan Jepang, urusan kehutanan yang menjadi sumber keuangan
untuk membiayai perang tentara Jepang di Asia dimasukkan ke dalam urusan
Departemen Produksi Kebutuhan Perang.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus
1945, maka dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah mulai menata
pengaturan hukum pengelolaan hutan yang sesuai dengan kondisi Indonesia sebagai suatu
Negara yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perkembangannya, pemerintah
Indonesia telah banyak membuat peraturan-peraturan mengenai pengolahan sumber daya
alam. Untuk merealisasikan asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan Negara, dan
mengakomodasi kepentingan pemerintah daerah dalam pengeloalaan sumber daya alam,
untuk pertama kali pemerintah mengeluarkan PP No. 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan
Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan, Laut, Kehutanan, dan
Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I.
Usaha untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan tugas dan
kewajiban pengelolaan hutan di seluruh wilayah Indonesia, maka pada bulan November
1963 di Bogor diselenggarakan Konferensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan. Ini
menjadi konferensi dinas yang pertama setelah diberlakukannya desentralisasi urusan
kehutanan dan perusahaan-perusahaan kehutanan Negara. Setelah Kabinet Dwikora
dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964, maka dari sisi kelembagaan
pengelolaan hutan di Indonesia, untuk pertama kalinya pemerintah membentuk
Departemen Kehutanan sebagai institusi Negara yang diberi wewenang mengelola dan
mnegusahakan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri
Kehutanan No.1 Tahun 1964 ditegaskan bahwa salah satu tugas Departemen Kehutanan
adalah merencanakan, membimbing, mengawasi, dan melaksanakan usaha-usaha
pemanfaatan hutan dan kehutanan, terutama produksi dalam arti yang luas di bidang
kehutanan, untuk meninggikan derajat kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan Negara
secara kekal.
Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, dibentuk cabinet pemerintahan yang
dinamakan Kabinet Ampera (Amanat Pemerintahan Rakyat). Kabinet Ampera
membubarkan Departemen Kehutanan yang selanjutnya urusan kehutanan dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Kehutanan yang secara kelembagaan berada di dalam
Departemen Pertanian. Era Kabinet Ampera dilaksanakan oleh Pemerintah orde baru
melalui pembangunan ekonomi nasional yang diorientasikan semata-mata untuk
mengejar pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi
secara cepat dan kilat maka pemerintahan orde baru (1) membuka peluang ekonomi dan
kesempatan berusaha dengan mengundang sebanyak mungkin pemilikmodal di dalam
maupun di luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia , dan (2) dengan
secara sadar pemerintah mengeksploitasi sumber daya dan kekayaan alam di Indonesia,
terutama minyak dan gas bumi.
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang bercorak kapital
dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah membangun instrument
hukum yang dimulai dengan UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(PMA), kemudian disusul dengan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam negeri (PMDN).
Dalam rangka peningatan PMA maupun PMDN di bidang pengusahaan sumber
daya hutan, maka pemerintah membangun instrument hukum yang dimulai dengan
pembentukan UU No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengusahaan hutan yang mendasari
kebijakan pemeberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan, maka dikeluarkan PP
No.21 tahun 1970 jo. PP No.18 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak
Pemungutan hasil Hutan (HPH dan HPHH). Segera setelah PP mengenai HPH dan
HPHH ini dikeluarkan, mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-
besaran dilakukan pemerintah, melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada
pemilik modal asing maupun dalam negeri dalam bentuk Badan Usaha Milik Swasta
(BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dari segi ekonomi pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada BUMS dan BMN
memang secara nyata memberi kontribusi yang positif bagi peningkatan pertumbuhan
ekonomi Indonesia. Tetapi, dari sesilain kebijakan pemberian konsesi pengusahaan hutan
yang tidak terbuka dan tidak selektif, karena mengandung unsure KKN sehingga konsesi
dikuasai oleh orang-orang atau yayasan-yayasan tertentu yang memilikiakses kuat pada
elit penguasa, ditambah lagi dengan lemahnya aspek pengawasan dan penegakkan hukum
di Indonesia, maka terjadilah eksploitasi sumber daya hutan yang tak terkendali, tak
terkontrol, dan tak tersentuh oleh hukum para pemegang konsesi HPH dan HPHH.
Konsekuensi yang muncul kemudian adalah: (1) dari segi ekologi terjadi degradasi
kuantitas dan kualitas hutan tropis di berbagai kawasan di Indonesia, dan (2) dari segi
social dan budaya muncul kelompok-kelompok masyarakat, terutama masyarakat yang
secara turun temurun hidup dan tinggal did an sekitar hutan, sebagai korban-korban
pembangunan (victims of development), yang tergusur dan terabaikan serta terbekukan
akses dan hak-hak mereka atas sumber daya hutan.
Banyak kejanggalan yuridis dalam konteks produk hukum yang dikeluarkan
pemerintah Orde baru untuk mendukung kebijakan pengusahaan hutan di Indonesia,
maka secara idiologis produk hukum pengelolaan hutan terutama yang berbentuk UU
mencerminkan idiologi pengelolaan hutan yang berbasis Negara (state based Forest
Management), yang kemudian diinterprestasikan secara tunggal dan sempit atau
dianalogikan pemerintah sebagai pengelolaan hutan yang berbasis Pemerintah
(Government based Forest Management). Instrumen pengelolaan hutan yang diproduk
pemerintah juga lebih merupakan hukum pemerintah (government law), atau lebih
konkrit sebagai hukum birokrasi (bureaucratic law), bukan hukum Negara (state law)
seperti yang diamanatkan UUD 1945. Hukum birokrasi cenderung dengan muatan
penekanan, pengabaian, penggusuran, dan bahkan pembekuan akses serta hak-hak
masyarakat atas sumber daya hutan. Model produk seperti ini dikenal sebagai produk
hukum yang bercorak represif (repressive law) seperti dimaksud Nonnet & Selzniek
(1978).
Pada era reformasi di bawah pemerintahan B.J. Habibie secara idiologis tidak
mengalami perubahan. Produk hukum dalam bentuk PP No. 6 tahun 1999 tentang
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan Produksi mengandung muatan jiwa,
semangat, dan substansi yang secar prinsip tidak berbeda dengan PP No. 21 tahun 1970
tentang HPH dan HPHH, alias tidak mencerminkan semangat reformasi.
Lebih ironis lagi, produk hukum pada era reformasi dalam bentuk UU No. 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan secara idiologis dan substansial sama dan sebangun
dengan UU No. 5 Tahun 1967 sebagai produk hukum orde baru.
Paradigma manajemen pembangunan yang berbasis Negara, bercorak sentralistik
dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi harus dirubah. Pemerintah
harus segera mengakaji ulang dan mereorientasi serta mengganti idiologi pembangunan
yang berbasis pemerintah (government based forest management) ke pembangunan
sumber daya hutan yang berbasis masyarakat (community based forest management).
Selain itu, pemerintah harus melakukan kajian ulang dan restrukturisasi atas pilihan
instrument hukum yang dibangun dan diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan
kebijakan pengelolaan sumber daya hutan, dari bangunan hukum pengelolaan sumber
daya hutan yang lebih bercorak represif (repressive law) ke instrument hukum yang lebih
bersifat responsive (responsive law).
Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Konsepsi kehutanan masyarakat
(community forestry/CF) sebenarnya relatif baru karena muncul sebagai tanggapan dari
kegagalan konsep industrialisasi kehutanan yang populer pada sekitar tahun 1960-an.
Yang menarik, penggagas CF justru ekonom kehutanan yang merasa bersalah karena
terlibat dalam inisiatif industrialisasi kehutanan. Orang itu bernama Jack Westoby
(Munggoro, 1998). Ia kemudian tercatat sebagai salah seorang yang banyak terlibat
dalam gagasan tema pokok Kongres Kehutanan Dunia VII yang diselenggarakan pada
tahun 1978 di Jakarta: Forest for People. Kristalisasi pikiran – pikirannya tentang CF ini
kemudian banyak dipublikasikan FAO. Dan kemudian pada tahun 1983, secara resmi
FAO mendefinisikan CF sebagai : “konsep radikal kehutanan yang berintikan pastisipasi
rakyat, artinya rakyat diberi wewenang merencanakan dan memutuskan sendiri apa yang
mereka kehendaki“. Hal ini berarti memfasilitasi mereka dengan saran dan masukan yang
diperlukan untuk menumbuhkan bibit, menanam, mengelola, dan melindungi sumberdaya
hutan milik mereka dan memperoleh keuntungan maksimal dari sumberdaya itu dan
memanennya secara maksimum. CF didedikasikan sebagai gagasan untuk meningkatkan
keuntungan langsung sumber daya hutan kepada masyarakat pedesaan yang miskin.
Beberapa tahun terakhir ini konsepsi kehutanan masyarakat (CF) sering dikonfrontasikan
dengan konsep perhutanan sosial yang merupakan terjemahan dari social forestry (SF).
Konsepsi SF lebih dikonotasikan sebagai bentuk pengusahaan kehutanan yang
dimodifikasi supaya keuntungan yang diperoleh dari pembalakan kayu didistribusikan
kepada masyarakat lokal. Dan kemudian di Indonesia Perum Perhutani – sebagai salah
satu pelopor SF di Indonesia – mendefenisikan bahwa SF adalah: “Suatu sistem di mana
masyarakat lokal berpartisipasi dalam manajemen hutan dengan tekanan pada pembuatan
hutan tanaman“. Tujuan sistem SF adalah reforestasi yang jika berhasil akan
meningkatkan fungsi hutan, dan pada saat yang bersamaan meningkatkan kesejahteraan
sosial.
Dalam perubahan idiologi tersebut yang menjadi halangan adalah:
1. dari sisi kelembagaan ekonomi masyarakat belum terbentuk
2. dari social-politik, dalam kebijakan pembangunan masyarakat belum memiliki
posisi sebagai subyek secara utuh.
3. keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan,
maupun peningkatan pendapatan negara, jelas meminimalkan semangat
ekologis.
Anda mungkin juga menyukai
- Resensi Relasi Negara Dan Masyarakat AdatDokumen6 halamanResensi Relasi Negara Dan Masyarakat AdatCaca nadyaBelum ada peringkat
- Paper Kehutanan Kelompok 2Dokumen15 halamanPaper Kehutanan Kelompok 2Muhammad A VitoBelum ada peringkat
- Pengembangan Kawasan Hutan RakyatDokumen8 halamanPengembangan Kawasan Hutan RakyatFitri WulandariBelum ada peringkat
- Jiptummpp GDL Nataliaint 31142 2 Bab1Dokumen24 halamanJiptummpp GDL Nataliaint 31142 2 Bab1Muhammad SyafiiBelum ada peringkat
- Persentasi Hutan Dan Pengentasan KemiskinanDokumen4 halamanPersentasi Hutan Dan Pengentasan KemiskinanJharz Nagh SmataygcalucheerfuleverydayBelum ada peringkat
- SKRIPSI Wawan BAB I - BAB VDokumen69 halamanSKRIPSI Wawan BAB I - BAB Vtuanwanda712Belum ada peringkat
- Tugas Essai Kehutanan MasyarakatDokumen7 halamanTugas Essai Kehutanan MasyarakatThe P-ManBelum ada peringkat
- Bab IDokumen17 halamanBab IJuli AndiniBelum ada peringkat
- Makalah Hukum KehutananDokumen22 halamanMakalah Hukum KehutananRicky Ricardo100% (1)
- Tugas KelompokDokumen7 halamanTugas KelompokFahmi MimiBelum ada peringkat
- Hukum KehutananDokumen3 halamanHukum KehutananpakdheugengBelum ada peringkat
- Foresty LawDokumen4 halamanForesty LawRyan ChocolatosBelum ada peringkat
- Contoh Makalah Manajemen Hutan - Fakultas Kehutanan Universitas Lambung MangkuratDokumen12 halamanContoh Makalah Manajemen Hutan - Fakultas Kehutanan Universitas Lambung MangkuratAnindyaMustikaBelum ada peringkat
- 1714101054-Bab 1 PendahuluanDokumen11 halaman1714101054-Bab 1 PendahuluanfatihaBelum ada peringkat
- 199-Article Text-387-1-10-20151004Dokumen16 halaman199-Article Text-387-1-10-20151004Nindya SafiraBelum ada peringkat
- Hukum KehutananDokumen30 halamanHukum KehutananyurikeBelum ada peringkat
- UU Nomor 18 Tahun 2013 (P3H) 2Dokumen92 halamanUU Nomor 18 Tahun 2013 (P3H) 2Nurhikmah RnBelum ada peringkat
- Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten MarosDokumen21 halamanSistem Pengelolaan Hutan Rakyat Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Tangkuli Kecamatan Camba Kabupaten MarosHajar Bsc100% (1)
- Tugas Ekonomi Sumber Daya HutanDokumen4 halamanTugas Ekonomi Sumber Daya HutanUmmu AthiyyahBelum ada peringkat
- Penerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Di Provinsi RiauDokumen7 halamanPenerapan Hukum Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Di Provinsi RiauBunga Soraya ApefhaBelum ada peringkat
- 1 PDFDokumen14 halaman1 PDFRamnah RamnahBelum ada peringkat
- Tugas Resume Biokonserfasi Ahmad Migi Fatoni 193030903032Dokumen8 halamanTugas Resume Biokonserfasi Ahmad Migi Fatoni 193030903032Ahmad MigifatoniBelum ada peringkat
- Sosiologi KehutananDokumen11 halamanSosiologi KehutananNur IlhamBelum ada peringkat
- Skripsi (Bab 3)Dokumen86 halamanSkripsi (Bab 3)ZainBelum ada peringkat
- Makalah Perhutanan Sosial (2) - CompressedDokumen7 halamanMakalah Perhutanan Sosial (2) - Compressedfarras nflBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen17 halamanBab Iidzafif rktBelum ada peringkat
- Bab IDokumen10 halamanBab IFahril KunBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen14 halaman1 SMwilly.susantoBelum ada peringkat
- File 4 Bab IDokumen12 halamanFile 4 Bab IIsra Al-KautsarBelum ada peringkat
- Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah Ditinjau Dari Hak Masyarakat Hukum AdatDokumen12 halamanPerlindungan Hukum Terhadap Kawasan Hutan Adat Di Kalimantan Tengah Ditinjau Dari Hak Masyarakat Hukum AdatBennedictus ShBelum ada peringkat
- Elis Rusnita - 10040021207 - HK Adat eDokumen2 halamanElis Rusnita - 10040021207 - HK Adat earif budiman hrBelum ada peringkat
- Makalah Bab 1Dokumen6 halamanMakalah Bab 1hanafuadah04Belum ada peringkat
- Prosiding Lokakarya Penerapan Multisistem Silvikultur-12Dokumen20 halamanProsiding Lokakarya Penerapan Multisistem Silvikultur-12OkiHerliBelum ada peringkat
- Dimas Adijaya Nugraha - 2007511244 SalinanDokumen2 halamanDimas Adijaya Nugraha - 2007511244 SalinanSie Keamanan Dimas adijaya nugrahaBelum ada peringkat
- Reposisi KehutananDokumen9 halamanReposisi KehutananUsmanBelum ada peringkat
- Tugas 1 Botani Pertamanan I Widya SafitriDokumen3 halamanTugas 1 Botani Pertamanan I Widya Safitriwidyasafitri162325Belum ada peringkat
- Kebijakan Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan RakyatDokumen9 halamanKebijakan Perhutanan Sosial Untuk Kesejahteraan Rakyatsri rahayuBelum ada peringkat
- L1A119066 - Syarli Febryanti - Perencanaan HutanDokumen12 halamanL1A119066 - Syarli Febryanti - Perencanaan HutanSyarliBelum ada peringkat
- Keteknikan Dan Pembukaan Wilayah HutanDokumen9 halamanKeteknikan Dan Pembukaan Wilayah HutanIcukSugiartoBelum ada peringkat
- Makalah Putra Judul Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan KotaDokumen14 halamanMakalah Putra Judul Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Hutan KotaSona Zisekhi HalawaBelum ada peringkat
- RESUME Implikasi Konsep UtilitarianismeDokumen4 halamanRESUME Implikasi Konsep Utilitarianismeasrullah uad18Belum ada peringkat
- Hutan Desa1Dokumen14 halamanHutan Desa1Elok Ponco MulyoutamiBelum ada peringkat
- Kerusakan HutanDokumen4 halamanKerusakan HutanRahma WatiBelum ada peringkat
- 2997d Hukum Kehutanan 1Dokumen14 halaman2997d Hukum Kehutanan 1Brillianto PutraBelum ada peringkat
- 22-049 Ester Deviana SitorusDokumen5 halaman22-049 Ester Deviana Sitorus22-049 Ester Deviana SitorusBelum ada peringkat
- Uu Kehutanan IsiDokumen21 halamanUu Kehutanan IsiZahra AmaliaBelum ada peringkat
- Ringkasan Seminar Fakultas Kehutanan UntanDokumen15 halamanRingkasan Seminar Fakultas Kehutanan Untantridonibudianto00Belum ada peringkat
- Kehutanan SosialDokumen18 halamanKehutanan SosialCheipuetlyy Yhudhey MuethiaraBelum ada peringkat
- Kelompok Hukum AdatDokumen33 halamanKelompok Hukum Adatarjunalaode20Belum ada peringkat
- Tugas KonservasiDokumen15 halamanTugas KonservasiIsma RiskianiBelum ada peringkat
- LILI CANTIKA (M011171309) BAB1-6 Revisi 1Dokumen47 halamanLILI CANTIKA (M011171309) BAB1-6 Revisi 1liyBelum ada peringkat
- Analisis Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Ni Putu SekarDokumen10 halamanAnalisis Kebijakan Hutan Kemasyarakatan Ni Putu SekarSekarTrisnaningBelum ada peringkat
- Amadoni Makalah-Hutan-Dan-Pengelolaan-KehutananDokumen15 halamanAmadoni Makalah-Hutan-Dan-Pengelolaan-KehutananJoko CahyonoBelum ada peringkat
- Deforestasi & Pengelolaan KehutananDokumen16 halamanDeforestasi & Pengelolaan KehutananCindy HosianiBelum ada peringkat
- Essay Hukum KehutananDokumen5 halamanEssay Hukum KehutananRum PurpleBelum ada peringkat
- Manajemen Penggelolaan Hutan RakyatDokumen18 halamanManajemen Penggelolaan Hutan RakyatzllvyBelum ada peringkat