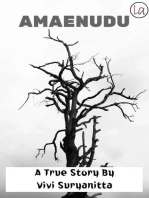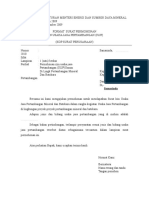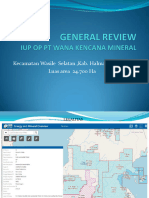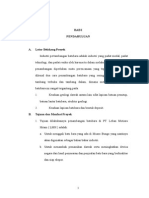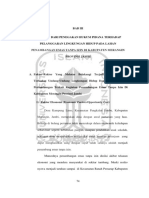Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat
Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat
Diunggah oleh
Dhi ManHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat
Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat
Diunggah oleh
Dhi ManHak Cipta:
Format Tersedia
1
KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DI KENAGARIAN MUNDAM SAKTI KECAMATAN IV NAGARI, KABUPATEN SIJUNJUNG
ARTIKEL
Disusun Oleh : REFLES 0921202052
Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
2012
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pada wilayah Propinsi Sumatera Barat terkandung Potensi sumber daya mineral seperti emas dan mangani. Menurut laporan Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumbar (2004), emas terdapat pada wilayah daerah Kabupaten Sijunjung, 50 Kota, Pasaman, dan Pesisir Selatan. Pada wilayah Kabupaten Sijunjung, deposit emas diperkirakan terdapat di sejumlah lokasi seperti; Bukit Kabun, Batu Manjulur, Silokek, Tanjung Ampalu, Palangki, Mundam Sakti, Muaro Sijunjung dan Lubuk Karia. Pada lokasi-lokasi yang memiliki kandungan emas ini, secara tradisional sudah sejak lama diexploitasi oleh masyarakat dengan menggunakan cara dan teknis sangat sederhana yang dikenal dengan mendulang emas. Pendulangan emas dilakukan pada aliran sungai yaitu dengan cara melakukan penyaringan pasir yang terdapat disepanjang aliran sungai, menggunakan dulang yang dibuat khusus dari kayu. Mendulang emas secara tradisional dilakukan pada umumnya oleh kaum perempuan sebagai pekerjaan sampingan/sambilan pada saat tidak melakukan kegiatan usaha pertanian seperti kesawah, ladang atau pun kebun. Dengan cara dan peralatan yang sederhana tersebut pendulang tidak mendapatkan kepastian akan mendapatkan hasil dan kalau pun didapat hasil hanya dalam jumlah rata-rata yang sangat kecil, tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan keluarga.
Di Kabupaten Sijunjung mendulang emas dilakukan sepanjang aliran batang ombilin, batang Sukam dan batang Palangki atau pada beberapa anak sungai lainnya. Sejumlah Nagari yang dilalui aliran sungai - sungai tersebut, penduduknya memiliki pengetahuan dan pengalaman panjang mendulang emas, salah satunya adalah penduduk Nagari Mundam Sakti, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung yang dilalui oleh batang Palangki. Beranjak dari pengalaman tradisonal tersebut, sejak 1990an, exploitasi emas tidak lagi dilakukan dengan cara mendulang pasir yang ada dipinggiran batang Palangki, tetapi sejumlah penduduk Mundam Sakti sudah melakukan penggalian pasir pada aliran sungai dan dilakukan penyaringan secara mekanis dengan menggunakan tenaga mesin pompa dan sedot. Melalui metoda demikian, volume pasir yang mampu disaring jauh lebih banyak dan lebih cepat sehingga jumlah emas yang didapatkan juga lebih banyak. Pada dekade ini, exploitasi emas di aliran sungai Palangki tidak lagi dilakukan oleh kaum perempuan sebagai pekerjaan sampingan, tetapi sudah dijadikan usaha dengan membutuhkan modal usaha yang relative besar. Exploitasi emas di batang Palangki sudah melibatkan berbagai pihak diluar penduduk nagari yang besangkutan khususnya yang bertindak sebagai investor pencarian emas. Dengan pola yang demikian, pencarian emas dilakukan lebih intensif sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih fokus, lebih banyak dan juga lebih kuat. Kondisi yang demikian menyebabkan tenaga kerja yang terlibat tidak lagi hanya berasal dari penduduk setempat, tetapi sudah melibatkan sejumlah tenaga kerja yang berasal dari luar daerah terutama dari daerah-daerah tertentu di Pulau Kalimantan
yang sudah berpengalaman melakukan explorasi dan exploitasi bahan galian berupa tambang emas rakyat. Dalam perkembangannya, tambang emas rakyat tidak lagi hanya dilakukan pada aliran Batang Palangki di Kenagarian Mundam Sakti, tetapi juga sudah dilakukan pada pinggiran/tebing sungai, berlanjut ke lokasi-lokasi lainnya termasuk pada lokasi sawah, kebun, ladang dan bahkan pekarangan. Pendulangan sudah berganti dengan penambangan yang menggunakan alat mekanis penggalian dan penyaringan/pengayakan. Untuk penggalian sudah dilakukan dengan menggunakan alat berat traktor maupun escavator. Hasil kunjungan lapangan pada bulan November 2010 didapatkan informasi bahwa diperkirakan lebih dari setengah dari jumlah penduduk pada kenagarian Mundam Sakti terlibat pada usaha Exploitasi emas. Kehadiran tambang emas rakyat di nagari Mundam Sakti mempengaruhi berbagai aspek dan dinamika kehidupan masyarakat. Penambangan yang dilakukan pada lahan persawahan menyebabkan berkurangnya potensi produksi padi pada nagari ini sehingga ketergantungan kepada daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat tidak bisa dihindari. Selanjutnya produktifitas tenaga kerja petani semakin menurun apabila ia tidak memiliki alternative lain untuk usaha diluar usahatani yang sudah sejak lama digelutinya. Selanjutnya kecendrungan masyarakat untuk melakukan explorasi emas pada sejumlah lahan yang dimiliki keluarga tidak jarang menghadapi pro dan kontra didalam keluarga sendiri yang pada gilirannya menyebabkan sering terjadi konflik didalam keluarga sendiri.
Exploitasi sumberdaya mineral di Indonesia diatur dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batu bara. Di Kabupaten Sijunjung, untuk pertambangan skala kecil di kenal dengan tambang Rakyat diatur melalui Peraturan Bupati No 19 tahun 2007 tentang prosedur dan mekanisme pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR). Bagaimana sesungguhnya probahan itu terjadi sejauh ini belum diketahui berdasarkan bukti empiris. Sehubungan dengan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka sudah dilakukan penelitian dengan judul Kegiatan Pertambangan Emas Rakyat dan Implikasinya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.
Berkembangnya usaha tambang rakyat berimplikasi kepada berbagai aspek, diantaranya adalah pemanfaatan lahan pertanian untuk lokasi penambangan yang menyebabkan berkurangnya luas garapan bagi petani. Selanjutnya tenaga kerja di sektor pertanin lebih memilih melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian, termasuk sebagai tenaga kerja pada usaha tambang. Perpindahan tenaga kerja disektor pertanian ke non-pertanian diperkirakan akan menghadapi sejumlah persoalan, baik jangka pendek maupun dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka
pendek,pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki petani sering kurang dan bahkan tidak relevan dengan jenis pekerjaan diluar sektor pertanian. Oleh sebab itu, tingkat produktivitasnya sebagai tenaga kerja cenderung rendah sehingga gaji/upah yang
diterima relative kecil. Petani sering hanya menjadi tenaga kerja/buruh untuk berbagai jenis pekerjaan, dan mempunyai kedudukan sangat rapuh terhadap pekerjaannya. Perkembangan usaha tambang juga menyebabkan kedatangan tenaga kerja migrant dari berbagai daerah di Indonesia. Tenaga kerja/pekerja tambang yang seluruhnya adalah laki-laki, jumlahnya ratusan orang membawa berbagai kebiasaan dan budaya yang berbeda dari kebiasaan dan budaya masyarakat. Dalam kesehariannya interaksi antara pekerja migrant dengan masyarakat tempatan memungkinkan terjadinya pergeseran-pergeseran prilaku dari masyarakat tempatan. Adapun rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana realitas Kegiatan Penambangan Emas Masyarakat di Kanagarian Mundam Sakti ?. 2. Bagaimana Implikasi Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Kanagarian Mundam Sakti dan konversi lahan pertanian yang sudah terjadi, bagaimana antisipasi yang dilakukan setelah lahan pertanian tidak produktif.
LANDASAN TEORI
2.1. Pertambangan di Indonesia. Pertambangan di Indonesia telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah besar bangsa ini. Menurut Mancayo A.S (2008), seberapa tua pemakaian besi dan mineral lainnya dalam kehidupan, setua itulah umur pertambangan dilakukan rakyat. Pertambangan dilakukan oleh masyarakat secara tradisional dengan alat-alat sederhana. Ia mengemukakan bahwa sejarah pertambangan di Indonesia dapat dirunut dari wilayah Minang Kabau. Pada tahun 1651 emas dapat diperoleh secara resmi dari tangan VOC di pantai Pariaman. Perdagangan emas ini berlangsung atas perjanjian bilateral antar Bandaharo di Sungai Tarab yang mengusai distribusi pengangkutan emas dari Saruaso, pedalaman Minangkabau . Dua orang Bandaharo yaitu Bandaharo Putih dan Bandaharo Kuning mengendalikan ekspor emas dari pedalaman Minangkabau, sampai pada akhir abad XVIII, bangsa eropa yang pertama yang menyelidiki sumberdaya alam di Tanah Datar, menyebutkan emas mulai habis didaerah tersebut . Panjangnya lintasan sejarah yang dilalui oleh pertambangan dalam kehidupan rakyat, dapat dilihat pada aturan-aturan lokal (adat) dibanyak tempat , mengatur tentang pengelolaan sumberdaya alam, termasuk pertambangan. Di Minang kabau (Sumbar) terdapat aturan tentang pengelolaan ulayat termasuk pertambangan yang
harus dipatuhi oleh orang-orang yang ingin memanfaatkan ulayat-sumberdaya tambang. Aturan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam (SDA) tersebut berbunyi: Karimbo Babungo Kayu, ka Sungai Babungo Pasia, Kaladang Babungo Ampiang, Katanah babungo ameh . Pepatah adat ini menggariskan bahwa setiap pemanfaatan SDA dalam territorial Minang kabau harus memberikan kontribusi kepada masyarakat adat setempat. Dalam konteks pertambangan, fee untuk masyarakat adat inilah yang disebut dengan Bunga Emas. Data-data diatas menunjukkan bahwa pertambangan telah menjadi satu bentuk usaha yang sangat tua, dikelola secara mandiri dengan alat-alat sederhana dan diselenggarakan oleh komunitas-komunitas masyarakat mandiri dan telah berkembang jauh sebelum republik ini ada. Uraian-urain singkat diatas juga menunjukkan terdapat masyarakat-masyarakat didaerah yang karena mata pencaharian dan interaksi dengan pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus, melahirkan budaya pertambangan, meskipun pada saat ini dinamai dengan penambangan tradisional, penambang rakyat atau bahkan penambang tanpa izin (PETI).
2.2. Pengertian Pertambangan Rakyat
Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf n, UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahanbahan galian dari semua golongan a, b dan c yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Golongan A ( bahan galian strategis, seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, nikel, kobalt dan timah), Golongan B ( bahan galian vital, seperti besi, mangan, tembaga, timbale, emas, perak, intan, zircon, Kristal kuarsa dan belerang ) dan golongan C ( bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, seperti marmer, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata ) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Kegiatan pertambangan rakyat dilakukan pada wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat ( WPR ).
2.3.Realitas Lapangan Pertambangan Rakyat Dari semua peraturan yang ada, dapat ditarik catatan penting yaitu : 1) Berbagai pengaturan pertambangan rakyat dalam berbagai paraturan perundangan memberikan pembatasan keleluasaan rakyat menambang, 2) Ketidak pastian usaha pertambangan rakyat karena kalau ada pemegang Kontrak Karya atau kontrak pertambangan lain, maka penambang rakyat harus menyingkir, 3) Sedangkan untuk diareal yang ada Kontrak
10
Pertambangannya tetap dibuka kemungkinan pertambangan rakyat, dengan syarat adanya ijin pemegang kontrak pertambangan dan 4) Penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh Negara lebih merupakan tindakan yang reaktif dan tidak terencana dan cendrung dimaksudkan untuk mematikan pertambangan rakyat. Karena itu sebagai akibat dari berbagai kebijakan terhadap pertambangan rakyat tersebut, banyak pertambangan-pertambangan dilakukan tanpa ijin (PETI). PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) adalah cap yang diberikan negara pada pelaku pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasasi negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambang adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, atau pun mereka yang hanya berjudi nasib dari bahan tambang, tetap akan menyandang label PETI jika tak mendapat izin. Stigma PETI berkonotasi liar, merusak, dan tak menguntungkan. Oleh karena itu perlu ditertibkan.
2.4. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Pertambangan Rakyat Menurut Tim Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin ( PETI ) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ( 2000 ), Faktor-faktor timbulnya kegiatan pertambangan rakyat diantaranya adalah kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai pemodal. Salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk keluar dari kemiskinan dan memperoleh pendapatan yang layak adalah dengan memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, diantaranya adalah bahan galian (Bahan tambang ) dan mudah dijual
11
dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi, salah satunya adalah penambangan emas dan bahan galian lainnya seperti batu bara dan timah.
Keterbatasan Lapangan Kerja Sebagai konsekwensi dari laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dalam dasa warsa tahun 1960-an da 1970-an, terkonsentrasinya pemusatan pembangunan, kuatnya arus investasi antar tempat dan ruang serta bervariasinya laju pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan arus mobilisasi orang dan jasa menjadi semakin deras. Selanjutnya lapangan pekerjaan disuatu sisi tersedia seiring dengan semangkin
besarnya derived demand terhadap tenaga kerja menurut keahlian dan spesifikasi bidang tertentu. Disisi lain, pencari kerja yang baru serta yang lama akumulasinya semangkin membesar. Tidak disangka bahwa dalam interaksi tersebut telah pula menghasilkan jenis lapangan kerja yang semangkin beragam dan kompleks, baik formal maupun tidak formal ( Elfindri, 2004 ).
Adanya Pemodal Keberadaan pihak ketiga ( penyandang dana ) yang memanfaatkan kemiskinan masyarakat tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mangkin maraknya kegiatan pertambangn oleh rakyat yang sudah mengarah kepada kegiatan Pertambangan Tanpa Izin ( PETI ) sebagai mana
12
disinyalir oleh tim penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dalam publikasi yang diterbitkan dalam tahun 2000. Pada umumnya masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan rakyat adalah berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Para penambang ini sering kali menjadi korban atau sapi perahan dari penyandang dana dengan memberikan pinjaman modal terlebih dahulu dan dikembalikan dengan cara menjual hasil tambangnya kepada pemodal tersebut dengan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga dipasaran ( Tim Terpadu Penanggulangan Pertambangan Tanpa Izin, 2000 ).
2.5 Dampak Pertambangan Rakyat Sebagai mana dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa pertambangan rakyat yang pada masa krisis ekonomi berkepanjangan dan munculnya era reformasi yang terjadi di Indonesia, mengalami peningkatan luar biasa baik secara kuantitas maupun kualitas dan sebagian besar telah bergeser kepada kategori pertambangan tanpa izin ( PETI ). Menurut tim terpadu pusat pertambangan masalah pertambangan tanpa izin Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral dalam publikasi mengenai penanggulangan masalah Pertambangan Tanpa Izin tahun 2000, kegiatan
pertambangan yang masuk kepada kategori PETI pada umumnya tidak memenuhi berbagai kriteria yang dapat diterima baik dari aspek ekonomi, konservasi, pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesejahteraan kerja. Hal ini menimbulkan danpak negatif yang banyak disoroti dari kegiatan pertambangan rakyat seperti :
13
a. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, berupa terjadinya pengundulan hutan menjadi padang pasir yang berjumlah ribuan hektar, dan pencemaran air sungai terutama oleh unsure merkuri yang jauh diatas ambang batas b. Kecelakaan tambang yang menyebabkan hilangnya nyawa pelaku tambang rakyat c. Pemborosan sumberdaya mineral, berupa tertinggalnya cadangan berkadar rendah yang tidak ekonomis lagi untuk ditambang baik karena pertambangan rakyat yang hanya menambang cadangan berkadar tingi maupun akibat recovery pengolahan yang rendah d. Kawasan sosial antara lain terjadinya kerusuhan di wilayah-wilayah pertambangan rakyat menyusul berkembangnya budaya premanisme, perjudian, prostitusi, dan kemerosotan moral lainnya.
Disamping dampak negatif tersebut, kegiatan pertambangan rakyat juga memberikan danpak positif, khususnya bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pertambangan itu sendiri, yaitu sebagai lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan utama bagi penambang dan keluarganya.
2.6 Konsep Pertambangan Skala Kecil ( PSK ) Salah satu bentuk usaha pertambangan yang dinyatakan legal di indonesia adalah pertambangan yang dilakukan masyarakat melalui pertambangan skala kecil ( Small Scale Mining ), yang telah berjalan sejak tahun 1990, sebagai salah satu upaya pemberdayaan usaha kecil/menengah dalam bentuk Badan Usaha Koperasi/KUD.
14
Menurut Wiriosudarmo (1999), Pertambangan Skala Kecil ( PSK ) diartikan sebagai operasi dan investasi pertambangan dimana investor maupun operatornya adalah rakyat kecil atau masyarakat secara bersama-sama ( kolektif ). Jadi, suatu operasi pertambangan yang secara fisik kecil, namun kalau dimiliki oleh pengusaha besar, maka pertambangan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai PSK. Masalah utama yang banyak dihadapi dalam proses pengelolaan usaha pertambangan skala kecil diantaranya adalah : a. Masalah kewilayahan, seringkali wilayah yang dimohonkan untuk wilayah pertambangan skala kecil lokasinya tumpang tindih dengan kegiatan lain, sehingga proses perizinannya terkendala b. Masalah permodalan, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penambangan skala kecil atau koperasi/KUD kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan pengakses perbankan/lembaga keuangan lainnya dalam rangka memperoleh pinjaman modal untuk usaha pertambangan skala kecil c. Masalah manajemen, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan penambangan skala kecil atau koperasi/KUD kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai manajemen usaha/perkoperasian d. Kekurangmampuan dalam penguasaan teknologi dan penggunaan peralatan semi mekanis serta perawatannya, sehingga peralatan yang dimiliki cepat rusak e. Ketidaktahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan pertambangan.
15
Pengusahaan pertambangan skala kecil yang ada di Indonesia saat ini dapat digolongkan atas beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut didasarkan pada klasifikasi yang digunakan dalam pedoman pengembangan pengusahaan penambangan skala kecil yang dibuat oleh Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral ( 2004 ), yaitu : a. Penambangan skala kecil pemula b. Penambangan skala kecil utama c. Penambangan skala kecil mantap 2.7 Konsep Ketenagakerjaan di Sektor UMKM Beberapa pengertian yang berhubungan dengan ketenagakerjaan menurut Subri ( 2003 ), yaitu : Tenaga kerja ( manpower ) adalah penduduk dalam usia kerja ( berusia 15-64 tahun ) atau jumlah penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Angkatan kerja ( labor force ) adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif, yaitu produksi barang dan jasa. Lapangan pekerjaan utama seseorang adalah bidang utama pekerjaan tersebut. Lapangan pekerjaan utama digolongkan atas : ( a ). Pertanian, perburuan, kehutanan, perikanan, ( b ). Pertambangan dan galian, ( C ). Industri pengolahan, ( d ). Listrik gas dan air, ( e ). Bangunan, ( f ). Perdagangan besar, enceran dan rumah makan, ( g ). Angkutan, pergudangan dan komunikasi, ( I ). Dan jasa kemasyarakatan.
16
Jenis pekerjaan utama seseorang adalah macam pekerjaan yang dilakukan pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan utama biasanya digolongkan atas : ( a ). Tenaga professional, teknisi dan sejenisnya, (b). Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanana, ( c ). Tenaga tata usaha dan tenaga yang sejenis ( d ). Tenaga usaha penjualan, ( e ), Tenaga usaha jasa, ( f ). Tenaga usaha pertanian, perburuan dan perikanan, ( g ). Dan tenaga produksi, operator alat-alat angkut, dan pekerja kasar. 2.8 Konsep Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Menurut ilmu antropologi, masyarakat berasal dari kata arab, yaitu syaraka yang berarti Ikut serta berpartisipasi ( Koentjaraningrat, 2000 ). Jadi masyarakat berarti sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dalam istilah ilmiah saling berintegrasi antara warga-warganya, adat istiadat, norma-norma, hukum dan aturanaturan khusus yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga Negara, kota dan desa atau suatu komuditas,dalam suatu waktu dan suatu rasa identitas kuat yang mengikat semua warganya ( Koentjaraningrat, 2000 ). Masyarakat dalam kegiatan pertambangan emas adalah masyarakat yang terlibat dalam aktifitas pertambangan rakyat ( skala kecil ), yaitu masyarakat pedesaan yang merupakan suatu komuditas penduduk yang umumnya memiliki keterkaitan erat dengan usaha pertambangan emas rakyat yang ada di daerah tersebut. Konsep perubahan sosial umumnya diartikan dengan sangat biasa. Menurut Moore ( 1967 ) dalam Lauer ( 1993 ), perubahan sosial didefinisikan sebagai
perubahan penting dari struktur sosial dalam hal ini dimaksudkan sebagai pola-pola
17
prilaku dan interaksi sosial. Ekspresi tentang struktur adalah norma, nilai dan fenomena kultural.
Faktor-faktor penyebab timbulnya perubahan sosial budaya menurut Murdock ( 1960 ) dalam Manan ( 1977 ), adalah : a. Pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk b. Perubahan lingkungan geografis c. Perpindahan kelingkungan baru d. Kontak dengan orang yang berlainan kebudayaan e. Malapetaka alam dan sosial seperti banjir, kegagalan panen, epidemic, perang dan depresi ekonomi f. Kelahiran atau kematian seseorang pemimpin 2.9 Hubungan Kegiatan Pertambangan Rakyat Dengan Perubahan Sosial Ekonomi Setiap aktivitas pembangunan akan berpengaruh terhadap sosial masyarakat, termasuk kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Spengler dan Harington dalam Lauer ( 1993 ), yang menekankan bahwa pada kenyataan manusia mampu mengendalikan perubahan dan memberikan tanggapan kepadanya, dan apabila manusia tidak berjuang mengendalikan jalannya perkembangan, manusia akan menjadi budak sendiri. Untuk menganalisis hubungan suatu pembangunan dengan perubahan sosial, dimulai oleh pandangan Steward dalam Lauer ( 1993 ) dengan pendekatan evolusi,
18
yaitu gagasan mengenai evolusi menurut garis lurus banyak ( multilinier ), yang merupakan salah satu pendekatan utama untuk memahami perkembangan kebudayaan yang berhubungan dengan pembangunan. Steward dalam Gama ( 1992 ) menyatakan bahwa pendekatan multilinier ini merupakan kritik teori garis lurus menyatu ( Unilinier ), yang mencakup hal-hal umum, dan bahwa perubahan sosial itu bergerak ketahapan masyarakat yang lebih tinggi, baik dan matang. Teori ini merupakan suatu upaya untuk mempelajari bagai mana faktor-faktor dalam suatu situasi tertentu akan membentuk perkembangan suatu jenis masyarakt, yang berarti Steward memberikan penekanan bahwa adanya perubahan budaya yang khas untuk masing-masing masyarakat. Febriamansyah ( 2003 ) menyatakan bahwa dalam suatu upaya pembangunan, kebutuhan suatu perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal adalah suatu yang tidak dapat dihindari. Pada saat perkembangan masyarakat berintegrasi dengan masyarakat lainnya terjadi suatu perubahan yang menuntut peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi lokal lebih dari yang biasanya, yang dibutuhkan tidak hanya konsumsi lokal, tetapi juga untuk kebutuhan konsumsi masyarakat lainnya. 3.0 Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh kantor wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 1988 dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat tahun 2010, diketahui bahwa kegiatan pertambangan emas oleh masyarakat di Kabupaten Sijunjung telah dimulai jauh sebelum masa
19
penjajahan Belanda secara turun temurun, umumnya dilakukan dengan mendulang emas alluvial disungai-sungai. Selain pendulang emas alluvial di sungai, pada beberapa lokasi juga dilakukan penambangan emas primer di daerah perbukitan sekitar Batang malandu., Mudiak Simpang, Tanjung Bungo dan Padang Bubus. Penambangan emas primer dilakukan dengan peralatan sederhana
diantaranya linggis, pahat, palu, sekop dan cangkul. Dibeberapa tempat penggalian telah membentuk lubang bukaan menyerupai bentuk goa dengan kedalaman 3-25 meter dan diameter lubang bukaan antara 1-1,5 meter mengikuti urat ( Vein ) batuan kuarsa yang mengandung logam emas Biji emas diolah dengan cara memecah batu yang mengandung emas hingga berukuran split ( diameter kira-kira 2,5 cm ), lalu ditumbuk hingga menjadi halus ( seperti pasir hingga tepung ). Batu yang telah dihaluskan tersebut selanjutnya dimasukkan kedalam gerondong ( sejenis rod mill ) dan dicampur dengan air raksa dengan perbandingan berat antara batu dan air raksa berkisar antara 10 : 1 hingga 25 : 1. Gerondong untuk pengolahan biji emas ada yang digerakan oleh tenaga kincir air dan ada juga yang menggunakan mesin disel yang berkekuatan 25 PK. Implikasi positif penambangan emas terhadap ketahanan sosial budaya masyarakat mandor, pada aspek ekonomi, secara fisik berupa berkembangnya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Sedangkan secara non fisik berupa meningkatnya penghasilan masyarakat dan menguatnya daya beli masyarakat yang berakibat pada mendorong lancarnya roda perekonomian masyarakat.
20
Penelitian-penelitian tersebut sebagaimana diuraikan diatas masing-masing membahas dampak pertambangan rakyat terhadap lingkungan fisik, sosial budaya dan ekonomi secara parsial, sebelum terfokus pada aspek sosial ekonomi penambang secara terpadu. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai pengaruh sosial ekonomi secara terpadu guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai pengaruh positif kegiatan pertambangn emas rakyat.
21
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Nagari Mundam Sakti, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung. Penelitian dilakukan selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2011. 3.2 Metode Penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Survey. Dengan demikian hasil dari yang didapatkan berdasarkan penelitian ini tidak serta merta dapat digeneralisasikan pada semua nagari yang ada. Namun demikian, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi nagari-nagari lainnya yang memiliki karakteristik hampir sama dengan Nagari Mundam Sakti yang dijadikan sebagai kasus penelitian ini. a. Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Adapun sumber data sekunder yang digunakan meliputi: dokumen, laporan dan publikasi dari kantor Wali Nagari, dokumen dan laporan dari SKPD yang relevan di tingkat Kabupaten dan dokumen serta arsip pada pelaku tambang. Sedangkan sumber data primer adalah Informan kunci (key informan) yang terdiri dari : Wali Nagari, pemuka masyarakat di nagari, pelaku usaha dan tenaga kerja yang berasal dari penduduk Nagai Mundam Sakti. Teknik Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: (1). Merekam dokumen dan arsip
22
(2) Wawancara mendalam dengan menggunakan pertanyaan terbuka terhadap informan (3). Observasi lapangan
3.3 Analisa Data Sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang digunakan maka analisa data yang akan digunakan adalah analisas kualitatif. Sedangkan analisis kulitatif akan dilkukan dengan menggunakan bentuk-bentuk analisis dominan seperti yang dikemukakan Yin K.R. (1996) yaitu : Perjodohan pola, Penjelasan tandingan dan analisis Deret Waktu Logika perjodohan pola dilkukan dengan memperbandingkan kondisi empiris dengan kondisi yang diprediksikan. Jika keduanya didapatkan persamaan maka akan dikatakan bahwa terdapat validitas internal dari apa yang ingin disimpulkan. Penjelasan tandingan akan dilakukan dengan melakukan komparasi dengan teori dan temuan-temuan penelitian lain untuk kasus yang sama. Sedangkan analisis deret waktu dilakukan untuk mendiskripsikan fenomena yang di analisis dalam rentetan waktu tertentu guna mendapatkan pemahaman tentang perkembangan dan proses yang terjadi dalam periode waktu tertentu.
23
4.1. Kondisi Umum Nagari Mundam Sakti Berdasarkan cerita rakyat yang dituturkan dari generasi ke generasi, nama Mundam Sakti diambil dari nama bukit yang terdapat dalam wilayah ini yatu bukit Mundam. Di kisahkan bahwa pada wilayah ini konon dahulu kala ada dua orang kuat (penguasa) yaitu Datuak Bagindo Saik dan Datuak Sati. Dengan dua orang penguasa ini, maka wilayah dan masyarakatnya terbelah menjadi dua yaitu : Pertama dinamakan Tungku Nan Tigo yang dikuasai oleh Datuak Bagindo Saik sebagai Rajo Adat. Kedua dinamakan Tungku Nan Ampek yang dikuasai oleh Datuak Sati sebagai Rajo Ibadat.
4.1.1. Penduduk Berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari kantor Wali Nagari, Jumlah penduduk Nagari Mundam Sakti adalah 2.560 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 610 KK, yang terdiri dari laki-laki 1.257 jiwa dan perempuan sebanyak 1303 jiwa.
4.1.2. Kondisi Sosial Budaya
24
Sebagaimana halnya orang Minang Kabau, semua penduduk Nagari Mundam Sakti adalah pemeluk agama Islam. Nuansa dan pola kehidupan keseharian mereka diwarnai oleh ajaran - ajaran agama islam. Kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual keagamaan dan aktifitas keagamaan seperti pengajian dan majlis taklim sudah menjadi melekat dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan wirid-wirid pengajian senantiasa dilaksanakan di Mesjid maupun Surau/Mushalla pada malam hari yang dapat diikuti oleh semua kalangan. Selain itu kaum ibu juga melaksnakan pengajian rutin pada pagi hari. 4.1.3. Mata Pencaharian Berdasarkan data profil Nagari diketahui bahwa pada umumnya masyarakat Mundam Sakti (91 %) mempunyai ketergantungan ekonomi terhadap sektor pertanian secara umum. Yang bekerja diluar sektor pertanian hanya segelintir saja diantaranya perdagangan (3,3 %), Tukang bangunan (3,2 %) PNS/Polri 1.8% dan sopir (0.2 %). 4.2. Kegiatan Penambangan Emas Rakyat dan Implikasi Sosial Ekonominya. 4.2.1. Fenomena Penambangan Rakyat Secara Umum. Tonggak awal bagi penguasaan sumberdaya pertambangan setelah
kemerdekaan adalah pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut merupakan deklarasi fundamental pengambilalihan penguasaan sumberdaya alam (termasuk tambang) dari tangan rakyat pada bangunan kekuasaan yang lebih besar yaitu negara. Negara menegaskan diri sebagai penguasa tunggal dari seluruh sumberdaya alam dengan maksud digunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Model pengusaan
25
begini kemudian popular disebut dengan Hak Mengusai Negara (HMN). Inilah yang menjadi idiologi penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia. 4.2.2. Fenomena Tambang Rakyat di Kabupaten Sijunjung
Di Kabupaten Sijunjung penambangan emas sebenarnya sudah dimulai sejak lama. Sebelum menggunakan peralatan berat dan kapal bermesin dompeng, dulu warga hanya menambang dengan menggaruk pasir demi pasir di dasar sungai menggunakan dulang kayu sederhana. Tapi sejak munculnya dompeng dan alat berat lainnya, persolan mulai muncul. Tanah yang tidak direklamasi, air sungai yang berubah warna, dan perebutan wilayah tambang, menjadi sorotan bagi pemerintah daerah dan pihak kepolisian (Padang Expres, 24 Juli 2010).
Perebutan wilayah tambang diantara anggota masyarakat juga sering terjadi dan menimbulkan konflik horizontal. Namun demikian, usaha penambangan emas juga memberikan berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat didaearh ini. Sebagaimana yang dikatakan Bupati Sijunjung Kami sadar, sejak adanya pertambangan emas dengan menggunakan alat canggih berupa alat berat di wilayah ini, berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Dapat kita lihat pesatnya pembangunan rumah permanen dan penambahan kendaraan roda empat di daerah kita ini sangat berkembang pesat. Namun di balik itu, sawah, ladang, serta sungai yang kita jaga selama ini menjadi hilang dan tercemar (dikutip dari Padang Express, 11/12/2011).
26
Selanjutnya Bupati Sijunjung menambahkan Kerugian yang diakibatkan penambangan liar akan dirasakan oleh masyarakat sendiri. Walaupun perekonomian sebagian masyarakat menjadi lebih baik, namun itu bukanlah masyarakat kelas menengah ke bawah. Melainkan yang memiliki modal untuk menambang dengan menggunakan alat berat. Sementara, hutan lindung dan lingkungan hidup menjadi korban karena tidak adanya reklamasi tanah kembali, tutur nya. Dalam dua tahun belakangan, tambang emas menjadi persoalan yang paling fenomenal di Kabupaten Sijunjung. Mulai dari persoalan perizinan, penambang meninggal, konflik antara warga dengan pemerintah daerah, hingga demo besarbesaran warga ke DPRD. Tidak tanggung-tanggung, masalah ini melibatkan berbagai pihak. Berangkat dari kondisi demikian, maka Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban karena dinilai sudah berimplikasi negative yang besar terhadap berbagai aspek baik sosial, ekonomi, budaya maupun terhadap lingkungan alam. Kebijakan inilah yang menyebabkan sekitar 4.000 pekerja PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin) Nagari yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Rakyat Anak Nagari (PERAN) melakukan aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Sijunjung, pada tanga 15/6 2011. Para buruh dari kecamatan Sijunjung, Kupitan, Koto VII dan Koto IV itu menuntut agar pemda setempat membuka kembali pertambangan. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pengaturan penambangan rakyat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan
27
Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010. UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu bara (minerba). Pada produk hukum ini dijelaskan peraturan Bupati No 23 tahun 2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Usaha pertambangan pada wilayah pertambangan rakyat di kabupaten Sijunjung dapat dilakukan apabila telah mengantongi IPR. Setiap penambang, baik perorangan maupun kelompok dapat melaksankan usaha pertambangan pada WPR setelah mendapatkan IPR. 4.3. Fenomena Penambangan Emas Rakyat di Kenagarian Mundam Sakti Pencarian emas yang dilakukan masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti sudah menjadi kegiatan yang turun temurun. Dalam cerita lisan yang disampaikan informan (GF, Ketua KAN Nagari Mundam Sakti,) ada kisah bahwa suatu ketika dulu terjadi banjir di wilayah nagari ini. Setelah bajir surut, dijalan-jalan penduduk dapat memungut butiran-butiran emas yang muncul bersamaan dengan pasir setelah lapisan tanah terkikis oleh aliran air yang bajir. Cerita lisan ini setidaknya memberikan gambaran bahwa masyarakat kenagarian Mundam Sakti mempunyai persepsi bahwa tanah yang ada dinagari ini mempunyai kandungan emas yang banyak. Pencarian emas dimulai dengan cara mendulang emas dari pasir yang terdapat dipinggiran sungai Palangki menggunakan alat sederhana terbuat dari kayu.
28
Gambar 2. Dulang emas terbuat dari kayu, alat mengayak pasir untuk mencari aliran sungai Palangki.
emas di
Pesatnya penambahan jumlah kelompok penambang emas di sungai palangki menyebabkan lokasi penambangan sudah semakin menyempit. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, pada wilayah kenagarian Mundam Sakti didapatkan sebanyak 19 kelompok penambang dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sebanyak 240 orang. Adapun diskripsi pelaku penambangan emas di aliran batang Palangki dalam kenagarian Mundam Sakti seperti terlihat pada Lampiran L3.
Usaha penambangan emas pada aliran sungai Palangki tersebar pada 2 jorong yang ada dalam kenagarian Mundam Sakti. Terdapat sebanyak 19 kelompok usaha dengan menggunakan 30 unit mesin dompeng yang melibatkan sebanyak 240 orang pekerja yang sehari-hari melakukan pengerukan pasir sungai. Pengerukan pasir
29
dilakukan sampai ke lapisan Napar yang berkedalaman 8-10 m dari dasar sungai. Untuk itu tenaga kerja/pekerja melakukan keterampilan khusus. 4.4. Implikasi Sosial Ekonomi Dari Penambangan Emas Rakyat di Nagari Mundam Sakti. kenagarian Mundam Sakti yang dipandang sebagai implikasi dari adanya usaha penambangan emas yang dilakukan di dalam wilayah Kanagariannya. Untuk lebih fokusnya pembahasan, maka implikasi sosial ekonomi dibatasi untuk 5 (lima) hal yaitu : (1) Etos Kerja masyarakat sebagai dasar untuk peningkatan produktifitas; dan (2) Partisipasi dan aktifitas Sosial dalam Kenagarian Mundam Sakti; (3) Penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung; (4) Perekonomian dan Ekonomi Ekonomi masyarakat. 4.4.1. Penambagan Emas Rakyat dan Implikasibya Masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti Terhadap Etos Kerja Perilaku penyelaman yang memerlukan
Dalam perjalanan waktu, nilai-nilai etis tertentu, yang tadinya tidak menonjol atau biasa-biasa saja bisa menjadi karakter yang menonjol pada masyarakat atau bangsa tertentu. Muncullah etos kerja Miyamoto Musashi, etos kerja Jerman, etos kerja Barat, etos kerja Korea Selatan dan etos kerja bangsa-bangsa maju lainnya. Bahkan prinsip yang sama bisa ditemukan pada pada etos kerja yang berbeda sekalipun pengertian etos kerja relatif sama. Sebut saja misalnya berdisiplin, bekerja keras, berhemat, dan menabung. Nilai-nilai ini ditemukan dalam etos kerja Korea
30
Selatan dan etos kerja Jerman atau etos kerja Barat (Wilkipedia, diunduh Desember 2011). 4.4.2. Penambangan Emas Rakyat dan Implikasinya Tehadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Aktifitas sosial di Kenagarian Mundam Sakti. Pengertian tentang partisipasi masyarakat dikemukakan oleh para penulis dan pakar dalam berbagai bentuk. Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. 4.4.3. Penambangan Emas Rakyat dan Implikasinya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Nagari Mundam Sakti Secara umum di Indonesia terdapat sejumlah persoalan lapangan kerja yang sifatnya mendasar. Adapun persoalan-persoalan tersebut diantaranya adalah ; Pertama adalah ketidakseimbangan secara umum antara penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan lapangan kerja. Jumlah yang dibutuhkan melebihi jumlah yang dapat disediakan. Kedua adalah kekurangseimbangan struktur dalam lapangan kerja. Ketiga adalah kekurangseimbangan antara kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dengan penyediaan tenaga terdidik. Keempat adalah adanya kecenderungan semakin meningkatnya peranan dan aspirasi angkatan kerja wanita dalam seluruh struktur angkatan kerja Indonesia. Kelima adalah adanya kekurang seimbangan antar daerah dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja
31
Indonesia. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Nagari Mundam Sakti untuk usia 20 -50 tahun lebih kurang 1.500 orang, dan separohnya adalah laki-laki maka dapat dikatakan bahwa seluruh penduduk laki-laki yang berusia antara 20 -50 tahun di nagari Mundam Sakti terserap pada usaha penambangan emas rakyat. Dengan demikian secara sederhana dapat dikemukakan bahwa kegiatan penambangan emas berimplikasi positif terhadap penyerapan tenaga keraja khususnya di kenagarian Mundam Sakti. Fenomena yang menarik dikemukakan oleh informan berkenaan dengan tenaga kerja ini. Menurutnya, berbeda dari daerah lain, di kanagarian Mundam Sakti penambangan pada suatu lokasi biasanya dilakukan oleh keluarga dan kerabat dekatnya. Sangat jarang tenaga kerja yang berasal dari luar nagari Mundam Sakti dipekerjakan pada usaha penambangan. Kalaupun ada biasanya tidak terlibat langsung dalam lobang penambangan atau hanya pada penambangan yang dilakukan dialiran sungai Palangki karena harus dilakukan penyelaman kedalam air. Untuk melakukan pekerjaan pada penambangan emas rakyat, kekuatan dan ketahan fisik serta keberanian menghadapi resiko sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, usaha penambangan rakyat secara langsung hanya menyerap tenaga kerja laki-laki dan berusia antara 20 - 50 tahun. Sangat jarang ditemukan tenaga kerja yang berusia lanjut terlibat dalam pekerjaan penambangan emas yang dilakukan di Nagari
32
Mundam Sakti. Sebaliknya pencarian emas dengan cara mendulang pada umumnya dilakukan oleh perempuan dan angkatan kerja berusia muda. Namun demikian, secara tidak langsung keberadaan usaha tambang rakyat berimplikasi terhadap terbukanya lapang usaha yang mendukung aktifitas pekerja tambang. 4.4.4. Panambangan Emas Rakyat dan Implikasinya Terhadap Perekonomian dan Perilaku Ekonomi Masyarakat di Kenagarian Mundam Sakti. Secara umum, pemerintah Kabupaten Sijunjung mengklaim bahwa penduduk miskin pada daerah sudah menurun dan kesejahteraan meningkat. Hal ini dapat dibaca dari pernyataan pemerintah pada Website Kabupaten Sijunjung yang selengkapnya sebagai berikut : Akhir-akhir ini kesejahteaan masyarakat sudah semakin meningkat. Peningkatan kesejahteraan dapat dari banyaknya rumah penduduk yang kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Disamping itu, di era sekarang, hampir tidak ada rumah yang penghuninya tidak memiliki sepeda motor. Terlepas dari dikredit atau dibeli kesnya sepeda motor itu, yang pasti memiliki sepeda motor sudah merupakan bukti bahwa tingkat ekonomi dan kesejahtraan rakyat sudah lebih baik dari sebelumnya. Namun bukan berarti penduduk miskin tidak ada lagi di kabupaten ini. Masih banyak, sehingga masih diperlukan upaya dan kerja keras Pemkab dan DPRD untuk mengatasinya.
33
Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan IV Nagari, dalam 5 (lima) tahun terakhir perkembangan jumlah keluarga miskin pada nagari ini seperti terlihat pada grafik berikut ini.
140 120 100 80 60 40 20 0 Thn 2005 Thn 2006 Thn 2007 Thn 2008 Thn 2009 Thn 2010 Keluarga Miskin
Gambar 6. Grafik perkembangan KK miskin di Nagari Mundam Sakti Grafik diatas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin memperlihatkan trend yang menurun dalam periode 2005 - 2010. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penurunan jumlah kk miskin di nagari Mundam Sakti dapat diduga salah satunya sebagai implikasi dari banyaknya penduduk yang melakukan dan bekerja pada usaha penambangan emas, secara langsung maupun multiflier effect dari ekonomi penambangan emas. Selain itu, juga diduga berimplikasi terhadap perilaku ekonominya. 4.5. Konversi Lahan Pertanian dan Antisipasi Setelah Lahan Tidak Produktif.
34
Hasil penelitian di kenagarian Mundam Sakti memperlihatkan bahwa sejauh ini sudah dilakukan penambangan emas pada lahan sawah seluas 18 dan pada lahan kebun seluas 17 Ha. Bila dibandingkan dengan lahan sawah yang ada pada kenagarian ini yaitu seluas 483 Ha (Tabel 4.3.), maka berarti tambang emas rakyat sudah mengalihkan fungsi sawah 4 % dari luas sawah yang ada. Selain alih fungsi untuk lokasi penambangan, perkembangan penambangan emas juga berimplikasi terhadap peningkatan jumlah pembangunan rumah yang diataranya dilakukan pada lahan sawah. Disisi lain, pada kenagarian ini dalam periode 20 tahun terakhir tidak pernah dilakukan pencetakan sawah baru untuk menambah luas areal persawahan rakyat. Selain sawah, alih fungsi lahan perkebunan juga terjadi pada kenagarian ini. Pada umumnya lokasi penambangan dilakukan pada lahan perkebunan khusunya kebun karet yang sebelumnya menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Banyak penambangan tidak melakukan reklamasi lahan kembali setelah panambangan dilakukan. Pada usaha tambang yang tidak menghasilkan emas dalam jumlah yang memadai, maka lahan pada umumnya ditinggalkan begitu saja sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk usaha pertanian. Pada lahan yang direklamasi, untuk mengembalikan lagi fungsinya sebagai sawah merupakan sesuatu yang sangat sulit. Dengan demikian keberadaan usaha penambangan emas pada lahan sawah jelas akan berimplikasi negative terhadap
35
produksi padi. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang usaha penambangan emas rakyat jika tetap dilakukan tanpa pembatasan yang jelas maka akan dapat mengancam swasembada pangan pada nagari ini.
36
DAFTAR PUSTAKA
Chambers, Robert, 1993. Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang, LP3ES Jakarta. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat, 2004. Potensi Bahan Galian Sumatera Barat, Padang. Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batubara, Direktoral Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, 2004. Pedoman Pengembangan Pengusahaan Pertambanagan Skala Kecil, Jakarta. Elfindri,. Bachtiar, Nasri, . 2004. Ekonomi Ketenaga Kerjaan, Andalas University Press, Padang. Exploitasi Sumberdaya Mineral di Indonesia diatur dengan Undang-undang nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Fadillah T. 2010. Tambang Rakyat dan Dilema Kemanusiaan. Teknik Tambang ITB. Bandung Haryono, 1999. Analisis Bandingan Perolehan Penambangan Emas dan Budidaya Tanaman (Kopi dan Cengkeh) di Desa Tobongan, Bolaang Mongondow Sulawesi Utara. Herianto, 2008. Studi Identifikasi Dampak Lingkungan Pertambangan Emas Skala Kecil di Kabupaten Garut (Studi kasus di Desa Mulyajaya), Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung. Koentjaradiningrat, 2000,. Pembangunan Masyarakat Tinjauan Aspek : Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan, Liberty, Yogyakarta. Kustiwan I .1997., Fenomena Konversi atau Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Penggunaan Non Pertanian. Lauer, R. H. 1993, Perspektif tentang Perubahan Sosial, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
37
Mahdi, Marsuki ., 1998, Laporan monitoring penambangan / pendulangan emas rakyat di Kabupaten Pasaman, Kanwil Dep. Pertambanagan dan Energi Provinsi Sumatera Barat, Padang. M.Rasyid Manggis Dt. Radjo Panghulu. 1971. Minangkabau. Sejarah Ringkas dan Adatnja Pertambangan Rakyat. Sridharma, Padang. Manan,Imran,1997, Perubahan Sosial, Budaya dan Pendidikan, Dalam Forum Pendidikan, Tahun II No. 2, Padang. Mantra, I. B. 1985, Pengantar Kependudukan Demografi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Ngadiman, 2000. Dampak Sosial Penambangan Emas di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, Program Studi Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana University Gajah mada, Yogyakarta. Pemerintah Nagari Mundam Sakti 2010, Buku Data Dasar Profil Nagari Mundam Sakti Tahun 2010, Kantor Nagari Mundam Sakti. Peraturan Bupati No 19 tahun 2007, tentang Mekanisme Pengurusan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) Pudjiastuti N.T. 2009. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bombana. Lapoan Penelitian. Dept.ESDM. Jakarta. Ramelan R (1994). Konsepsi Dan Strategi Peningkatan Produktivitas Nasional . paper disampaikan pada Seminar Gerakan Produktivitas Nasional" pada tanggal 13 Juli 1994 di Departemen Tenaga Kerja RI, Jakarta Soemitro R, Sutyastie, dan Tjiptoherjanto,. 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia (Suatu Analisis Awal), Rineka Cipta, Jakarta. Subri, M., 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudradjat, A., 1999. Teknologi & Manajemen Sumber Daya Mineral, Penerbit ITB, Bandung.
38
Sugihen dan Bahrein, T. 1997, Sosiologi Pedesaan (suatu pengantar), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-undang No 11 Pertambangan tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Utomo, M., Eddy Rifai dan Abdulmutalib Thahir. 1992. Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan. Lampung: Universitas Lampung. Tim Terpadu Pusat Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), 2000, Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Inplementasi Inpres No. 3 Tahun 2000, Jakarta. Tim Terpadu Pusat Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), 2001. Laporan Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Inplementasi Inpres No. 3 Tahun 2000, Jakarta. Tim Inventarisasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat, 2001. Wiriosudarmo, R. 1999. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Pertambangan Skala Kecil, Yayasan Ecomine NL, Makalah pada Seminar Kebijakan dan Manajemen Pertambangan Berskala Kecil, Jakarta. Wooda,M. 1975. Culture Change, WM.C. Brown Company Publishers, Lowa. Yin. K.R. 1996. Analisas Kualitatif dan Kuantitatif, yaitu : Perjodohan pola, Penjelasan tandingan dan analisis Deret Waktu.
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Seminar Air Asam Tambang Di Indonesia Ke 4 Tahun 2012Dokumen106 halamanMakalah Seminar Air Asam Tambang Di Indonesia Ke 4 Tahun 2012Irsani FeniliaBelum ada peringkat
- Preentase Tambang Terbaru Oktober 2012 Final Fix (Compatibility Mode)Dokumen153 halamanPreentase Tambang Terbaru Oktober 2012 Final Fix (Compatibility Mode)zultriBelum ada peringkat
- Emas AluvialDokumen6 halamanEmas AluvialEdAjabbarBelum ada peringkat
- RPT PT Mas Rev 2 TH 2020 (20-09)Dokumen194 halamanRPT PT Mas Rev 2 TH 2020 (20-09)Dana SuardanaBelum ada peringkat
- Formulir Iujp Permen 28Dokumen6 halamanFormulir Iujp Permen 28lionchadBelum ada peringkat
- Proposal KP Surya PT SatuiDokumen31 halamanProposal KP Surya PT SatuisuryanaBelum ada peringkat
- Zirkon KendawanganDokumen15 halamanZirkon Kendawangandani bayu0% (1)
- KCMI Tambang 28jan2015a PDFDokumen28 halamanKCMI Tambang 28jan2015a PDFFahriBelum ada peringkat
- Proposal Kparif - Nitha LatarbelakangDokumen8 halamanProposal Kparif - Nitha LatarbelakangRobby Caur100% (1)
- Perkembangan Industri Perkapalan Atau Maritim IndonesiaDokumen4 halamanPerkembangan Industri Perkapalan Atau Maritim IndonesiaAdam WBelum ada peringkat
- Proposal Invest RDokumen9 halamanProposal Invest Rilo3thBelum ada peringkat
- Profil PT - Jgi Site Tanjung MangkaliatDokumen36 halamanProfil PT - Jgi Site Tanjung MangkaliatAchmad DjunaidiBelum ada peringkat
- Bab II PAMA Rev 5Dokumen10 halamanBab II PAMA Rev 5Lawrenza Jeriko SiburianBelum ada peringkat
- Rancangan Pabrik SingkatDokumen71 halamanRancangan Pabrik Singkatzultri100% (10)
- Adaro - Coking Coal InfoDokumen14 halamanAdaro - Coking Coal InfoMaruli TobingBelum ada peringkat
- Eksploras SBHM Sungai DanauDokumen13 halamanEksploras SBHM Sungai Danauvorda buaymadangBelum ada peringkat
- Laporan Pli Chintia Tri PutriDokumen88 halamanLaporan Pli Chintia Tri PutriAf RiBelum ada peringkat
- Eksplorasi Aryoseno Arutmin Indonesia TPTXXIIDokumen7 halamanEksplorasi Aryoseno Arutmin Indonesia TPTXXIIFakhrur RaziBelum ada peringkat
- Bab IV Hasil Dan PembahasanDokumen23 halamanBab IV Hasil Dan PembahasanIsmail Andi BasoBelum ada peringkat
- Kunjungan Ke Perusahaan PT Nusa Alam LestariDokumen3 halamanKunjungan Ke Perusahaan PT Nusa Alam LestariShulhan Fasya WibawaBelum ada peringkat
- KAJIAN MINERAL IKUTAN PT TIMAH TBKDokumen32 halamanKAJIAN MINERAL IKUTAN PT TIMAH TBKkejawakBelum ada peringkat
- Bab IiiDokumen19 halamanBab Iiidimar agusriawanBelum ada peringkat
- Proses Penambangan Timah Di Bangka BelitungDokumen9 halamanProses Penambangan Timah Di Bangka BelitungtikolikBelum ada peringkat
- PROPOSAL TUGAS AKHIR Adam PT BRAMDokumen30 halamanPROPOSAL TUGAS AKHIR Adam PT BRAMAdam SatriaBelum ada peringkat
- COMPRO Sinar Mutiara Megalitindo New PDFDokumen9 halamanCOMPRO Sinar Mutiara Megalitindo New PDFEnergi Alam BorneoBelum ada peringkat
- Proposal TaDokumen17 halamanProposal TaAnonymous yU8hVBuBelum ada peringkat
- Bench Blasting PresentasiDokumen10 halamanBench Blasting PresentasiAfdha SyahqiBelum ada peringkat
- Contoh Laporan Ekskursi Tambang UnhasDokumen29 halamanContoh Laporan Ekskursi Tambang UnhasMuh Mizanul HaqBelum ada peringkat
- Resume PertambanganDokumen13 halamanResume PertambanganMochamadWidyBelum ada peringkat
- Lampiran ESDMDokumen116 halamanLampiran ESDMUmar AlfaruqBelum ada peringkat
- Perusahaan Tambang Di Kota Palangka RayaDokumen1 halamanPerusahaan Tambang Di Kota Palangka RayaAriantossgBelum ada peringkat
- Tambang Batubara Daerah TenggarongTenggarong (Hartono)Dokumen13 halamanTambang Batubara Daerah TenggarongTenggarong (Hartono)sandro0112Belum ada peringkat
- Tugas Tambang BatubaraDokumen35 halamanTugas Tambang Batubarayongky_andre_jocom17Belum ada peringkat
- Bayan Prima Coal Ka Zul TADokumen191 halamanBayan Prima Coal Ka Zul TADirman Eka SyaputraBelum ada peringkat
- Tugas Perencanaan TambangDokumen11 halamanTugas Perencanaan TambangAtlas Asy SyuraBelum ada peringkat
- 103479Dokumen10 halaman103479des mawitaBelum ada peringkat
- GENERAL REVIEW Wana Kencana MineralDokumen11 halamanGENERAL REVIEW Wana Kencana MineralSETIOBelum ada peringkat
- Ventilasi TambangDokumen14 halamanVentilasi TambangMiftah FaridBelum ada peringkat
- PerhitunganDokumen35 halamanPerhitunganAndi MercuryBelum ada peringkat
- Ekskursi TambangDokumen31 halamanEkskursi TambangRiiiiianBelum ada peringkat
- Pt. Bbun RabDokumen2 halamanPt. Bbun RabDPD BARA JP KALTENGBelum ada peringkat
- Bab IiiDokumen18 halamanBab Iiimonalisa ariosBelum ada peringkat
- Laporan Batubara Cv. Bara Mitra KencanaDokumen8 halamanLaporan Batubara Cv. Bara Mitra KencanaJo DiliaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Pengantar Teknologi PertanianDokumen25 halamanLaporan Praktikum Pengantar Teknologi PertanianAry SaputraBelum ada peringkat
- Kajian Teknis Penanganan Air Asam Tambang Pada Pit Satu PT Baturona Adimulya BaruDokumen20 halamanKajian Teknis Penanganan Air Asam Tambang Pada Pit Satu PT Baturona Adimulya BaruanisaBelum ada peringkat
- Perijinan TambangDokumen19 halamanPerijinan TambangJab ChoyBelum ada peringkat
- Pt. Bukit AsemDokumen3 halamanPt. Bukit AsemDeden MaryadinBelum ada peringkat
- Laporan Survey Tinjau PT. SambasDokumen14 halamanLaporan Survey Tinjau PT. SambasBayu MaranaiBelum ada peringkat
- PT. Mahakam Sumber JayaDokumen2 halamanPT. Mahakam Sumber JayarisalBelum ada peringkat
- S SOS 1106012 Chapter1Dokumen6 halamanS SOS 1106012 Chapter1HariyonoBelum ada peringkat
- Laporan Pembagunan BerkelanjutanDokumen7 halamanLaporan Pembagunan BerkelanjutanJuhari JuhariBelum ada peringkat
- Model Pertambangan Emas Rakyat Dan Pengelolaan Lingkungan Tambang Di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa TengahDokumen9 halamanModel Pertambangan Emas Rakyat Dan Pengelolaan Lingkungan Tambang Di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa TengahDian Fernando SiregarBelum ada peringkat
- Artikel Isbd Kelompok 8 Penambang EmasDokumen5 halamanArtikel Isbd Kelompok 8 Penambang EmasNaomi OctavinBelum ada peringkat
- Potensi PertambanganDokumen32 halamanPotensi Pertambanganyevi kristiawanBelum ada peringkat
- Dampak Pertambangan Emas Illegal Di Aliran Sungai Batanghari Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat PDFDokumen13 halamanDampak Pertambangan Emas Illegal Di Aliran Sungai Batanghari Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat PDFNizaBelum ada peringkat
- Anggi Diah Lestari - 207032051 - Perencanaan K3 - SMK3Dokumen11 halamanAnggi Diah Lestari - 207032051 - Perencanaan K3 - SMK3Anggi Diah LestariBelum ada peringkat
- Laporan KLHDokumen6 halamanLaporan KLHReni EniBelum ada peringkat
- 05.3 Bab 3Dokumen28 halaman05.3 Bab 3AllieBelum ada peringkat
- Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Terhadap Ekologi Sosial Masyarakat - Outline ProposalDokumen16 halamanDampak Aktivitas Pertambangan Emas Ilegal Terhadap Ekologi Sosial Masyarakat - Outline ProposalMUHAMMAD RIKHO A A ABelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen8 halamanBab I Pendahuluanrezapurba581Belum ada peringkat
- Bencana LongsorDokumen1 halamanBencana LongsorzultriBelum ada peringkat
- Rekap Verivikasi Data Miskin TeomokoleDokumen7 halamanRekap Verivikasi Data Miskin TeomokolezultriBelum ada peringkat
- Anjab Kasubag PrasaranaDokumen7 halamanAnjab Kasubag PrasaranazultriBelum ada peringkat
- Khotbah Seragam Idul Fitri 1443 HDokumen9 halamanKhotbah Seragam Idul Fitri 1443 HzultriBelum ada peringkat
- PBT Baubau28-01-2022-142821Dokumen1 halamanPBT Baubau28-01-2022-142821zultriBelum ada peringkat
- Sejarah Benteng KabaenaDokumen3 halamanSejarah Benteng KabaenazultriBelum ada peringkat
- Struktur Pemerintahan Kerajaan Kabaena FixDokumen3 halamanStruktur Pemerintahan Kerajaan Kabaena FixzultriBelum ada peringkat
- Laporan Bulanan AidsDokumen6 halamanLaporan Bulanan AidszultriBelum ada peringkat
- Bahasa Indonesia01Dokumen13 halamanBahasa Indonesia01zultriBelum ada peringkat
- 13.tindak Pidana Pornografi PDFDokumen85 halaman13.tindak Pidana Pornografi PDFzultriBelum ada peringkat
- Berita Acara Penggunaan PelabuhanDokumen1 halamanBerita Acara Penggunaan PelabuhanzultriBelum ada peringkat
- Jenis-Jenis Kerajinan Tekstil Dan Gambarnya LengkapDokumen9 halamanJenis-Jenis Kerajinan Tekstil Dan Gambarnya Lengkapzultri100% (1)
- FDSFSDFDokumen190 halamanFDSFSDFBm X BreakerBelum ada peringkat
- BOQ PatarakiDokumen7 halamanBOQ PatarakizultriBelum ada peringkat