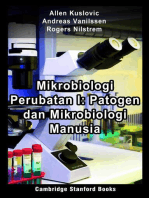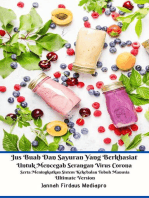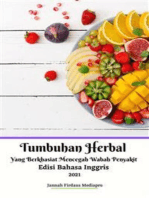Demam Tifoid
Demam Tifoid
Diunggah oleh
fitrianugrahJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Demam Tifoid
Demam Tifoid
Diunggah oleh
fitrianugrahHak Cipta:
Format Tersedia
DEMAM TIFOID
I. PENDAHULUAN Demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh Salmonella Thypi (S. Typhi) dengan gejala demam yang lebih dari satu minggu, gangguan saluran pencernaan dan gangguan kesadaran.1 Demam tifoid banyak terjadi di Negara-negara berkembang. Demam tifoid merupakan suatu penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh S. Thypi yang masih dijumpai secara luas di berbagai Negara berkembang yang terutama terletak di daerah tropis dan subtropis. Penyakit ini juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting karena penyebarannya berkaitan erat dengan urbanisasi, kepadatan penduduk, kesehatan lingkungan, sumber air dan sanitasi yang buruk serta standar higiene industri pengolahan makanan yang masih rendah.2,3,4 Perbedaan antara demam tifoid anak dan dewasa adalah mortalitas (kematian) demam tifoid pada anak lebih rendah bila dibandingkan dengan dewasa. Resiko terjadinya komplikasi fatal terutama dijumpai pada anak besar dengan gejala klinis berat, yang mempunyai kasus dewasa. Demam tifoid pada anak terbanyak terjadi pada umur 5 tahun atau lebih dan mempunyai gejala klinis ringan.5
II.
EPIDEMIOLOGI Besarnya angka pasti kasus demam tifoid di dunia sangat sulit ditentukan
karena penyakit ini mempunyai gejala dengan spektrum klinis yang sangat luas. Data World Health Organization (WHO) tahun 2003 memperkirakan terdapat sekitar 17 juta kasus demam tifoid di seluruh dunia dengan insidensi 600.000 kasus kematian tiap tahun. Di Negara berkembang, kasus demam tifoid dilapokan sebagai penyakit endemis dimana 95% merupakan kasus rawat jalan sehingga insidensi yang sebenaranya adalah 15-25 kali lebih besar dari laporan rawat inap di rumah sakit.[3] Demam tifoid pada anak umur 5-15 tahun di Indonesia terjadi 180,3/100.000 kasus pertahun dan dengan prevalensi mencapai 61,4/1000 kasus pertahun. Menurut data Hasil Riset Dasar Kesehatan (RISKESDAS) tahun 2007, demam tifoid menyebabkan 1,6% kematian penduduk Indonesia untuk semua umur. Insidensi demam tifoid berbeda pada tiap daerah.4
III. ETIOLOGI Demam tifoid disebabkan oleh Salmonella Enterica serovar Typhi (S. Typhi), basil gram negatif, bergerak dengan rambut getar, berkapsul, tidak berspora, dan bersifat fakulatif anaerob. Demam tifoid mempunyai 3 macam antigen yaitu antigen 0 (somatik, terdiri dari zat kompleks lipopolisakarida), antigen H (flagella), dan antigen Vi.1 Antigen Vi didapatkan pada 90% salmonella typhi yang diisolasi. Antigen ini berperan sebagai proteksi terhadap baktersidal dari antibody serum penderita.
Sementara demam paratiroid yang gejalanya mirip dengan demam tifoid namun lebih ringan, disebabkan oleh Salmonella paratyphi A, B, atau C. bakteri ini hanya menginfeksi manusia. Penyebaran demam tifoid terjadi melalui makanan dan air yang telah tercemar oleh tinja atau urin penderita demam tifoid dan meraka yang diketahui sebagai carrier (pembawa) demam tifoid.2
IV. PATOFISIOLOGI Penyakit ini terjadi melalui ingesti dari S. Typhi melalui kontaminasi secara feko-oral melalui makanan ataupun melalui air yang tercemar. Masuknya kuman Salmonella typhi ke dalam tubuh manusia terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh kuman. Sebagian kuman dimusnahkan di dalam lambung (pH<2), sebagian lolos masuk ke dalam lumen usus, yang selanjutnya berkembang biak. Jika respons imun humoral usus kurang baik, kuman akan menembus epitel, terutama sel-M, dan selanjutnya di lamina propria kuman berkembang biak serta difagosit, terutama oleh makrofag. Kuman dapat hidup dan berkembang biak di dalam makrofag, dan selanjutnya dibawa ke plaque Peyeri ileum distal kemudian ke kelenjar getah bening mesenterika. Selanjutnya melalui duktus torasikus, kuman yang terdapat di dalam makrofag ini masuk ke dalam sirkulasi darah (menyebabkan bakteremia pertama yang asimtomatik) dan menyebar ke seluruh organ retikuloendotelial tubuh terutama hati dan limpa. Di organ-organ ini kuman meninggalkan sel fagosit dan kemudian berkembang biak di luar sel, selanjutnya
masuk ke dalam sirkulasi darah lagi, menimbulkan bakteremia kedua yang disertai tanda dan gejala penyakit sistemik.6 Di dalam hati, kuman masuk ke dalam kandung empedu, berkembang biak, dan bersama cairan empedu di ekskresikan secara intermittent ke dalam lumen usus. Proses yang sama terulang kembali, berhubungan makrofag telah tereksitasi dan hiperaktifmaka saat fagositosis kuman S. Typhi terjadi pelepasan beberapa mediator inflamasi uang selanjutnya akan menimbulkan gejala reaksi inflamasi sistemik seperti demam, malaise, mialgia, sakit kepala, sakit perut, instabilitas vaskuler, gangguan mental, dan koagulasi7
V.
DIAGNOSIS Diagnosis demam tifoid dapat ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan
fisis, dan pemeriksaan penunjang yang dilakukan.1,2
A. Gejala Klinis Masa inkubasi dari Demam Tifoid biasanya 7-14 hari tetapi juga bergantung pada infeksi yang terjadi, umumnya 3-30 hari. Manifestasi klinis bervariasi mulai dari sakit ringan dan demam yang tidak terlalu tinggi, malaise, sampai keadaan klinis yang berat dengan gangguan pencernaan dan komplikasi yang berat. Banyak faktor yang mempengaruhi berat ringannya penyakit pada demam tifoid. Hal ini mencakup lama berlangsungnya penyakit sebelum dilakukannya terapi, pemilihan antibiotic yang sesusai, umur, riwayat vaksinasi, strain bakteri, dan faktor imunitas seseorang.2 Gejala klinis pada anak umumnya tidak khas.Umumnya perjalanan penyakit berlangsung dalam jangka waktu yang pendek dan jarang menetap lebih dari 2 minggu.5 Gejala klinis demam tifoid umumnya demam tinggi (95%), lidah kotor (76%), anoreksia (70%), muntah (39%), hapatomegali (37%), diare (36%), toksik (29%), nyeri abdomen (21%), pucat (20%), splenomegali (17%), konstipasi (7%), sakit kepala (4%), ikterus (2%), ileus (1%), dan perforasi usus (0,5%).2 1. Demam Demam atau panas merupakan gejala utama demam tifoid. Awalnya demam hanya samar-samar saja, selanjutnya suhu tubuh turun naik yakni pada pagi hari lebih rendah atau normal, sementara sore dan malam hari lebih tinggi. Pada kasus-kasus yang khas umumnya demam berlangsung selama 3
minggu. Demam dapat mencapai 39-40 C yang sifatnya remitten. Intensitas demam akan makin tinggi disertai gejala lain seperti sakit kepala, diare, nyeri otot, pegal, insomnia, anoreksia, mual, dan muntah. Selama minggu pertama, suhu tubuh berlangsung meningkat setiap hari, pada minggu kedua, intensitas demam makin tinggi kadan terus menerus. Bila pasien membaik maka pada minggu ketiga, suhu tubuh berangsur turun dan dapat normal pada akhir minggu ketiga.1,5,7 2. Gangguan Saluran Pencernaan Sering ditemukan bau mulut yang tidak sedap karena demam yang lama. Bibir kering dan kadang pecah-pecah (ragaden). Lidah terlihat kotor dan ditutupi selaput putih kotor, ujung dan tepinya kemerahan. Umumnya penderita sering mengeluh nyeri perut, teutama nyeri ulu hati, disertai mual dan muntah. Penderita anak lebih sering mengalami diare, sementara dewasa cenderung mengalami konstipasi.1,5,7 3. Gangguan Kesadaran Umumnya terdapat gangguan kesadaran berupa penurunan kesadaran ringan. Sering ditemui kesadaran apatis. Bila gejala klinis berat, tak jarang penderita sampai samnolen dan koma atau dengan gejala-gejala psikosis. Pada penderita dengan toksik, gejala delirium (mengigau) lebih menonjol.1,5,7 4. Hepatosplenomegali Pada penderita demam tifoid, hati dan atau limpa sering ditemukan membesar. Hati terasa kenyal dan nyeri bila ditekan.5,7
5. Bradikardi Relatif Bradikardi relatif adalah peningkatan suhu tubuh yang tidak diikuti oleh peningkatan frekuensi nadi.Patokan yang sering dipakai adalah peningkatan suhu 1C tidak diikuti peningkatan frekuensi nadi 8 denyut dalam 1 menit. Bradikardi relative tidak sering ditemukan, mungkin karena teknis pemeriksaan yang sulit dilakukan. Gejala-gejala lain yang dapat ditemukan pada demam tifoid adalah rose spot (bintik kemerahan pada kulit) yang biasanya ditemukan di perut bagian atas, serta gejala klinis yang berhubungan dengan komplikasi yang terjadi. Rose spot pada anak sangat jarang ditemukan.5,7 B. Pemeriksaan Penunjang Pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosi demam tifoid yaitu 1. Pemeriksaan Darah Tepi Pada penderita demam tifoid bisa didapatkan anemia, jumlah leukosit normal, bisa menurun datau meningkat, mungkin didapatkan
trombositopenia dan hitung jenis biasanya normal atau sedikit bergeser ke kiri, mungkin didapatkan aneosinofilia dan limfositosis relative, terutama pada fase lanjut. Penelitian oleh beberapa ilmuwan mendapatkan bahwa hitung jumlah dan jenis leukosit serta laju endap darah tidak mempunyai nilai sensitivitas, spesifisitas, dan nilai ramal yang cukup tinggi untuk dipakai dalam membedakan antara penderita demam tiofid atau bukan, akan tetapi adanya leucopenia dan limfositosis relative dugaan diagnosis demam tifoid.3
2. Pemeriksaan Bakteriologis dengan Isolasi dan Biakan Diagnosis pasti demam tifoid dapat ditegakkan bila ditemukan bakteri S.Typhi dalam biakan darah, urine, feses, sumsum tulang, cairan duodenum atau dari rose spots. Berkaitan dengan pathogenesis penyakit, maka bakteri akan lebih mudah ditemukan dalam darah dan sumsum tulang pada awal penyakit sedangkan pada stadium berikutnya di dalam urine dan feses. Hasil biakan yang positif memastikan demam tifoid akan tetapi hasil negative tidak dapat menyingkirkan demam tifoid karena hasilnya tergantung beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil biakan : Jumlah darah yang diambil Perbandingan volume darah dari media empedu Waktu pengambilan darah Volume darah yang dianjurkan untuk anak besar 10-15 mL sedangkan untuk anak kecil dibutuhkan 2-4 mL. Volume sumsum tulang yang dibutuhkan untuk kultur hanya sekitar 0,5-1 mL. bakteri dalam sumsum tulang juga sedikit dipengaruhi oleh antibiotika daripada bakteri dalam darah. Hal ini dapat menjelaskan teori bahwa kultur sumsum tulang lebih tinggi hasil positifnya bila dibandingkan dengan darah walaupun dengan volume sampel yang lebih sedikit dan sudah mendapatkan terapi antibiotika sebelumnya. Media pembiakan yang dianjurkan untuk S. Typhi adalah media empedu (gall) dari sapi dimana dikatakan media gall ini dapat meningkatkan
positivitas hasil karena hanya S.Typhi dan S.Paratyphi yang dapat tumbuh pada media tersebut. Biakan darah terhadap Salmonella juga tergantung dari saat pengambilan pada perjalanan penyakit, beberapa peneliti melaporkan biakan darah positif 40-80% atau 70-90%dari penderita pada minggu pertama sakit dan positif 10-50% pada akhir minggu ketiga. Sensitivitasnya akan menurun pada sampel penderita yang telah mendapatkan antibiotika dan meningkat sesuai dengan volume darah dan rasio darah dengan media kultur yang dipakai. Bakteri dalam feses ditemukan meningkat dari minggu pertama (10-15%) hingga minggu ketiga(75%) dan turun secara perlahan. Biakan urinpositif setelah minggu ketiga. Biakan sumsum tulang merupakan metode baku emas karena mempunyai sensitivitas paling tinggi dengan hasil positif didapat pada 80-95% kasus dan sering tetap positif selama perjalanan penyakit dan menghilang pada fase penyembuhan. Metode ini terutama bermanfaat pada penderita yang sudah mendapat terapi atau dengan kultur darah negatif. Prosedur terakhir ini sangat invasive sehingga tidak dipakai dalam praktek sehari-hari. Pada keadaan tertentudapat dilakukan kultur pada specimen empedu yang
diambil dari duodenum dan memberikan hasil yang cukup baik akan tetapi tidak digunakan secara luas karena adanya resiko aspirasi pada anak-anak. Salah satu penelitian pada anak menunjukan bahwa sensitivitas kombinasi kultur darah dan duodenum hampir sama dengan kultur sumsum tulang.
Kegagalan dalam isolasi atau biakan dapat disebabkan oleh keterbatasan media yang digunakan, adanya penggunaan antibiotika, jumlah bakteri yang sangat minimal dalam darah, volume specimen yang tidak mencukupi, dan waktu pengambilan specimen yang rendah dan adanya kendala berupa lamanya waktu yang dibutuhkan (5-7 hari) serta peralatan yang lebih canggih untuk identifikasi bakteri sehingga tidak praktis dan tidak tepat untuk dipakai sebagai metode diagnosi baku dalam pelayanan penderita.3 3. Uji serologis Uji serologis digunakan untuk membantu menegakkan diagnosis demam tifoid dengan mendeteksi antibody spesifik terhadap komponen antigen S.Typhi maupun mendeteksi antigen itu sendiri. Volume darah yang diperlukan untuk uji serologis ini adalah 1-3 mL yang diinokulasikan ke dalam tabung tanpa antikoagulan. Metode pemeriksaan serologis imunologis ini dikatakan mempunyai nilai penting dalam proses diagnostic demam tifoid Akan tetapi, masih didapatkan adanya variasi yang luas dalam sensitivitas dan spesifisitas pada deteksi antigen spesifik S.Typhi oleh karena tergantung jenis antigen, specimen yang diperiksa, teknik yang dipakai untuk melacak antigen tersebut, jenis antibody yang digunakan dalam uji (poliklonal atau monoclonal) dan waktu pengambilan specimen (stadium dini atau lanjut dalam perjalanan penyakti).3
Uji Widal Suatu metode serologis yang digunakan sejak tahun 1896. Prinsip uji widal adalah memeriksa reaksi antara antibody agglutinin dalam serum penderita yang telah mengalami pengenceran berbeda-beda terhadap antoigen somatic (O) dan flagella (H) yang ditambahkan dalam jumlah yang samasehingga terjadi aglutinasi. Pengenceran tertinggi yang masih menimbulkan aglutinasi menunjukkan titer antibody dalam serum. Teknik aglutinasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji hapusan (slide test) atau uji tabung (tube test). Uji hapusan dapat dilakukan secara cepat dan digunakan dalam prosedur penapisan sedangkan uji tabung membutuhkan teknik yang lebih rumit tetapi dapat digunakan utnuk konfirmasi dari uji hapusan. Interpretasi dari uji widal ini harus memperhatikan beberapa faktor antara lain sensitivitas, spesifisitas, stadium penyakit, factor penderita seperti status imunitas dan status gizi yang dapat mempengaruhi pembentukan antibody, gambaran imunologis dari masyarakat setempat (daerah endemis atau non-endemis), factor antigen, teknik serta reagen yang digunakan. Kelemahan tes in adalah rendahnya sensitivitas dan spesifisitas serta sulitnya melakukan interpretasi hasil akan tetapi hasil uji widal yang positif akan memperkuat dugaan pada tersangka penderita demam tifoid (penanda infeksi). Saat ini walupun telah digunakan secara luas di seluruh dunia, manfaatnya masih diperdebatkan dan sulit dijadikan
pegangan karena belum ada kesepakatan akan nilai standar aglutinasi (cut-off point). Untuk ,encari standar uji widal seharusnya ditentukan titer dasar (baseline titer) oada anak sehat di populasi dimana pada daerah endemis seperti di Indonesia akan didapatkan peningkatan titer antibody O dan H pada anak-anak sehat.3 Tes TUBEX Merupakan tes aglutinasi kompetiti semi kuantitatifyang sederhana dan cepat (kurang lebih 2 menit) dengan menggunakan partikel yang berwarna untuk meningkatkan sensitivitas, spesifisitas dengan
menggunakan antigen O9 yang benar-benar spesifik yang hanya ditemukan pada Salmonella serogrup D. Tes ini sangat akurat dalam diagnosis infeksi akut karena hanya mendeteksi antibody igG dalam waktu beberapa menit. Walaupun belum banyak penelitian yang menggunakan tes TUBEX ini, beberapa penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa tes ini mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik dari uji Widal. Penelitian oleh Lim dkk (2002) mendapatkan hasil sensitivitas 100% dan spesifisitas 100%. Penelitian lain mendapatkan sensitivitas sebesar 78% dan spesifisitas 89%. Tes ini dapat menjadi pemeriksaan yang ideal, dapat digunakan untuk pemeriksaan secara rutin karena cepat, mudah, dan sederhana terutama di Negara berkembang.3
Metode Enzyme Immunoassay (EIA) DOT Uji didasarkan pada metode untuk melacak antibody spesifik IgM dan IgG terhadap antigen OMP 50 kD S.Typhi. Deteksi terhadap IgM menunjukkan fase awal infeksi pada demam tifoid akut sedangkan deteksi terhadap IgM dan IgG menunjukkan demam tifoid pada fase pertengahan infeksi. Pada daerah endemis dimana didapatkan tingkat transmisi demam tifoid yang tinggi akan terjadi peningkatan deteksi IgGspesifik akan tetapi tidak dapat membedakan antara kasus akut, konvalesen, dan reinfeksi. Pada metode Typhidot-M yang merupakan modifikasi dari metode Typhidot telah dilakukan inaktivasi dari IgG total sehingga menghilangkan pengikatan antigen terhadap antigen terhadap IgM spesifik. Metode Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) Dilakukan untuk melacak antibody IgG, IgM, dan IgA terhadapa antigen LPS O9, antibody IgG terhadap antigen flagella d (Hd) dan antibody terhadap antigen Vi S. Typhi. Uji ELISA yang sering dipakai untuk mendeteksi adanya antigen S. Typhi dalam specimen klinis adalah double antibody sandwich ELISA.3 Pemeriksaan Dipstik Pemeriksaan ini dikembangkan di Belanda dimana dapat mendeteksi antibody IgM spesifik terhadap antigen LPS S. Typhi dengan menggunakan membrane Nitoselulosa yang mengandung antigen S. Typhi sebagai pita pendeteksi dan antibody IgM antihuman Immobilized
sebagai reagen control. Pemeriksaan ini menggunakan komponen yang sudah distabilkan, tidak memerlukan alat yang spesifik dan dapat digunakan di tempat yang tidak mempunyai fasilitas laboratorium yang lengkap.3 4. Pemeriksaan Bakteriologis secara molekuler Metode lain yang akurat adalah mendeteksi DNA (asam nukleat) gen flagellin bakteri S. Typhi dalam darah dengan teknik hibridasi asam nukleat atau amplifikasi DNA dengan cara polymerase chain Reaction (PCR) melalui identifikasi antigen Vi yang spesifik untuk S. Typhi.3
VI. DIAGNOSIS BANDING Pada daerah endemik, demam tifoid merupakan penyebab tersering dari kejadian demam tanpa disertaitanda local. Demam yang terjadi pada anak pada keadaan awal terkadang memberikan gambaran seperti gastroenteritis, bronchitis, atau bronkopneumonia. Secara umum diagnosis banding dari demam tifoid yaitu malaria, sepsis dengan infeksi bakteri yang lain, infeksi karena mikroorganisme intraseluller seperti tuberculosis, brusellosis, leptospirosis, dan penyakit akibat infeksi virus seperti demam berdarah dengue, hepatitis akut, dan infeksi mononukleosis juga dapat dipikirkan.3
VII. PENATALAKSANAAN Penatalaksanaan pada penderita demam tifoid mempunyai tujuan untuk mencegah kmplikasi, mencegah relaps, dan mempercepat penyembuhan. Oleh karena itu penatalaksanaan demam tifoid meliputi : A. Simtomatis 1. Istirahat Mutlak (Tirah baring) Anak baring terus ditempat tidur dan letak baring harus sering diubah. Lamanya istirahat baring berlangsung sampai 5 hari bebas demam, dilanjutkan dengan mobilisasi secara bertahap sebagai berikut : Hari 1 duduk 2 x 15 menit Hari 2 duduk 2 x 30 menit Hari 3 jalan dan pulang Seandainya selama mobilisasi bertahap ada kecenderungan suhu meningkat, maka istirahat mutlak diulagi kembali.8 2. Dietik Diet harus mengandung kalori dan protein yang cukup. Sebaiknya rendah selulosa (Rendah serat) untuk menceah perdarahan dan perforasi. Diet untuk penderita demam tifoid, basanya diklsifikasikan atas diet cair, bubur lunak, tim, dan nasi biasa.5 IVFD bila ada dehidrasi berat, keadaan toksik, dan komplikasi berat. Maksud pemasangan IVFD pada keadaan ini adalah untuk : Menanggulangi gangguan sirkulasi Menjamin intake (keseimbangan cairan dan elektrolit)
Pemberian obat-obatan intravena Menanggulangi sirkulasi Renjatan RL : 20-30 cc/kgBB/jam renjatan berat RL diguyur samapai tekanan darah terukur dan nadi teraba, kemudian jumlah cairan yang diberikan disesuaikan dengan keadaan penderita. Diare dehidrasi sesuai dengan protocol gastroenterologi B. Kausal 1. Kloramfenikol Dosis : 7-100 mg/kgBB/hari, dibagi dalam 3 atau 4 dosis peroral atau paenteral, sesuai keadaan penderita. Lama pemberian : 10 hari untuk demam tifoid ringan 14 hari untuk demam tifoid berat (keadaan tokdik, bronchitis, pneumonia, dan komplikasi berat) serta masih demam setelah 10 hari pemberan kloramfenikol. 2. Obat Pilihan Diberikan bila ada tanda-tanda resistensi atau intoksikasi kloramfenikol Kotrimoksasol, Dosis : Trimetoprim 6 mg/kgBB/hari dan lama pemberian 10 hari. Tiamfenikol, Dosis : 30-50 mg/kbBB/hari Ceftriaxone, Dosis : 80 mg/kgBB/hari pemberian selama 5 hari.
Amoksisilin, Dosis : 100 mg/kgBB/hari dibagi dalam 3 atau 4 dosis dan lama pemberian 10 hari
C. Kortikosteroid 1. Keadaan toksik 2. Komplikasi berat (perdarahan usus / perforasi usus, ensefalitis). Untuk ini diberikan deksametason 1 mg/kgBB/hari intravena selama 2-3 hari, kemudian dilanjutkan dengan prednisone 2 mg/kgBB/hari sampai dengan 2 minggu. Khusus renjatan septik mempunyai penanganan tersendiri. D. Tindakan khusus 1. Perforasi / perdarahan Stop intake oral IFVD (koreksi gangguan sirkulasi, keseimbangan elektrolit, dan menjamin intake) Transfusi darah ( untuk atasi anemi pasca perdarahan dan renjatan/syok hemoragik) diberikan 10-20 cc/kgBB, dapat diulangi sesuai keadaan penderita. Kloramfenikol 100mg/kgBB/hari iv Deksametason 1 mg/kgBB/hari iv Konsul bedah Perdarahan >72 jam perlu petimbangan pemberin hemostatik (carbazochrome sodium sulfonate 50 mg bolus iv. Kemudian dilanjutkan dengan 100 mg/24 jam secara drips.
2. Renjatan septik IVFD (penanggulangan gangguan sirkulasi) Kloramfenikol 100 mg/kgBB/hari iv Dimulai dengan deksametason 3 mg/kgBB 1 dosis, setelah 6 jam diikuti 8 dosis 1 mg/kgBB/6 jam Setiap kali pemberian kortikosteroiddilarutkan didalam 50 cc dekstrose 5% dan diberikan selama 30 menit. Dapat dipertimbangkan obat-obatan inotropik : dopaminn dengan dosis 5-20 g/kgBB/menit secara drips Bila perlu diberikan plasma ekspander untuk mempertahankan tekanan koloid Bila ada tanda-tanda anoksia diberikan oksigen 2-4 liter/menit.8
VIII. KOMPLIKASI Komplikasi yang sering terjadi pada demam tifoid adalah a. Perndarahan usus dan perforasi Merupakan komplikasi yang serius dan perlu diwaspadai dari demam tifoid yang muncul pada minggu ketiga. Sekitar 5% penderita demam tiofid mengalami komplikasi ini. Perdarahan usus pada umumnya ditandai keluhan nyeri perut, perut membesar nyeri pada perabaan, seringkali ditandai dengan penurunan tekanan darah dan terjadinya shock, diikuti dengan perdarahan saluran cerna sehingga tampak darah kehitaman yang keluar bersama tinja.
Perdarahan usus muncul ketika ada luka di usus halus sehinggan membuat gejala seperti sakit perut, mual, muntah, dan terjadi infeksi pada selaput perut (peritonitis). Jika hal ini terjadi maka diperluka perawatan medis yang segera. Komplikasi yang lebih jarang a. Pembengkakan dan peradangan pada otot jantung. b. Pneumonia. c. Peradangan pankreas (pankreatitis). d. Infeksi ginjal atau kandung kemih. e. Infeksi dan pembengkakan selaput otak Masalah psikiatri seperti mengigau, halusinasi, dan paranoid psikosis. Merupakan komplikasi yang serius dan perlu diwaspadai dari demam tifoid yang muncul pada minggu ketiga. Sekitar 5% penderita demam tiofid mengalami komplikasi ini. Perdarahan usus pada umumnya ditandai keluhan nyeri perut, perut membesar nyeri pada perabaan, seringkali ditandai dengan penurunan tekanan darah dan terjadinya shock, diikuti dengan perdarahan saluran cerna sehingga tampak darah kehitaman yang keluar bersama tinja.
IX. PROGNOSIS Prognosis tergantung dari diagnosi tepat yang dilakukan secara dini dan pemberian antibiotic sebagai terpai dari penyakit ini. Umumnya prognosis baik jika penderita cepat mendapatkan pengobatan. Faktor lain yang berperan yaitu umur pasien, keadaan umum, dan status nutrisi yaitu prognosis buruk jika keadaan
fisik yang lemah dan status nutrisi yang buruk, serotype Salmonella typhi, dan komplikasi yang terjadi. Dengan terapi yang adekuat, biasanya 2-4% relaps, mortalitas pada penderita yang dirawat mencapai 6%.1,2
Anda mungkin juga menyukai
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Merawat penyakit kencing manis tanpa ubatDari EverandMerawat penyakit kencing manis tanpa ubatPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Jus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh ManusiaDari EverandJus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh ManusiaBelum ada peringkat
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Referat Demam TifoidDokumen30 halamanReferat Demam TifoidYani Pukari Sweet86% (7)
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaDari EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Jus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Standar VersionDari EverandJus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Standar VersionPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)
- Jus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Ultimate VersionDari EverandJus Buah Dan Sayuran Yang Berkhasiat Untuk Mencegah Serangan Virus Corona Serta Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Ultimate VersionBelum ada peringkat
- Demam Thypoid Dalam KehamilanDokumen12 halamanDemam Thypoid Dalam KehamilanAlexandra Niken Larasati100% (2)
- Tumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Dari EverandTumbuhan Herbal Yang Berkhasiat Mencegah Wabah Penyakit Edisi Bahasa Inggris 2021Belum ada peringkat
- SK Panduan High Alert MedicationDokumen4 halamanSK Panduan High Alert MedicationSrhi NurhayatiiBelum ada peringkat
- Demam Tifoid ReferatDokumen17 halamanDemam Tifoid Referatnisrinakl67% (3)
- Referat Demam TifoidDokumen21 halamanReferat Demam TifoidIche Juwice100% (3)
- Sop Lasa & High AlertDokumen3 halamanSop Lasa & High AlertSrhi Nurhayatii100% (1)
- Referat-Demam Tifoid-AnakDokumen16 halamanReferat-Demam Tifoid-AnakBambang Aditya100% (1)
- Asuhan Keperawatan Demam ThypoidDokumen19 halamanAsuhan Keperawatan Demam Thypoidenda anggrayneeBelum ada peringkat
- Check List Dokumen HPK BaruDokumen3 halamanCheck List Dokumen HPK BaruSrhi NurhayatiiBelum ada peringkat
- Demam Tifoid FarmakoDokumen15 halamanDemam Tifoid FarmakoNicky SeptianaBelum ada peringkat
- TyphoidDokumen23 halamanTyphoidMario Hendry WongsoBelum ada peringkat
- Demam Tifoid Pada Anak: ReferatDokumen21 halamanDemam Tifoid Pada Anak: ReferatWendy ErikBelum ada peringkat
- Ringkasan - Agnes Nur Mileniawati - 24185565ADokumen7 halamanRingkasan - Agnes Nur Mileniawati - 24185565AAgnes Milenia2Belum ada peringkat
- BAB 1 Referat TifoidDokumen30 halamanBAB 1 Referat TifoidInggrid GraciaBelum ada peringkat
- Bahan Tifoid 2Dokumen12 halamanBahan Tifoid 2Rio Eka SaputraBelum ada peringkat
- Bangsal AnakDokumen48 halamanBangsal AnakRizqy AnugrahBelum ada peringkat
- LP Demam TypoidDokumen19 halamanLP Demam Typoiddewi murdiantyBelum ada peringkat
- (Fix) Lapsus Demam TifoidDokumen29 halaman(Fix) Lapsus Demam TifoidFauqi RamadhanBelum ada peringkat
- Demam TifoidDokumen19 halamanDemam TifoidFany LainamaBelum ada peringkat
- Demam Tifoid - Astri.2016Dokumen28 halamanDemam Tifoid - Astri.2016MonaBelum ada peringkat
- Makalah Demam Thypoid - Docx PatologiDokumen27 halamanMakalah Demam Thypoid - Docx PatologiMuhamad NurholisBelum ada peringkat
- Referat Demam TifoidDokumen11 halamanReferat Demam TifoidYoana AngelineBelum ada peringkat
- Salmonella ParatyphiDokumen6 halamanSalmonella ParatyphiSyifa FadyaBelum ada peringkat
- Referat Demam Tifoid Lolita Lorentia 112019155Dokumen13 halamanReferat Demam Tifoid Lolita Lorentia 112019155vioBelum ada peringkat
- Demam TifoidDokumen13 halamanDemam Tifoiddr nuriel anwarBelum ada peringkat
- CBD Syifa DwiDokumen33 halamanCBD Syifa DwiSyifa dwi N RBelum ada peringkat
- Typhoid - Kel 4Dokumen26 halamanTyphoid - Kel 4Herry PrasetyoBelum ada peringkat
- Referat Demam TifoidDokumen19 halamanReferat Demam Tifoidsri wulanBelum ada peringkat
- TyfoidDokumen17 halamanTyfoidprahastaBelum ada peringkat
- Demam TifoidDokumen14 halamanDemam Tifoid082292095743Belum ada peringkat
- Gejala Dan Penanganan Demam Tifoid PDFDokumen11 halamanGejala Dan Penanganan Demam Tifoid PDFDaniel Bryant100% (1)
- REFERAT Gangguan Fungsi Hati Pada Demam Tifoid AILADokumen24 halamanREFERAT Gangguan Fungsi Hati Pada Demam Tifoid AILAIda LailaBelum ada peringkat
- Referat Demam Tifoid Pada KehamilanDokumen13 halamanReferat Demam Tifoid Pada KehamilanFauziaEvaLatifahSBelum ada peringkat
- Simulasi Kasus Demam TifoidDokumen34 halamanSimulasi Kasus Demam TifoidnkesumawatiBelum ada peringkat
- LP Demam ThypoidDokumen17 halamanLP Demam ThypoidAyu RahmatiaBelum ada peringkat
- Lidahku KotorDokumen48 halamanLidahku Kotorrosa litaBelum ada peringkat
- Askep Keluarga Typoid EndangDokumen46 halamanAskep Keluarga Typoid Endangsrihariati100% (1)
- Demam ThypoidDokumen13 halamanDemam Thypoidnabilamaharani12100% (1)
- Lp-Tifoid ST KMBDokumen11 halamanLp-Tifoid ST KMBkisya purnomoBelum ada peringkat
- Demam Typhoid Dan GastritisDokumen30 halamanDemam Typhoid Dan Gastritisabdul halimBelum ada peringkat
- TifoidDokumen17 halamanTifoidIlhami RamadentaBelum ada peringkat
- CSS Demam TifoidDokumen35 halamanCSS Demam TifoidAida Fitriyane HamdaniBelum ada peringkat
- Demam TifoidDokumen15 halamanDemam Tifoidbangarsiagian100% (1)
- Demam TifoidDokumen23 halamanDemam Tifoidferdich100% (1)
- Ikm Edit (Demam Tipes)Dokumen19 halamanIkm Edit (Demam Tipes)Marlina LinaBelum ada peringkat
- MAKALAH CASE III (Typhoid Dan Disentri) TUTORIAL C2Dokumen22 halamanMAKALAH CASE III (Typhoid Dan Disentri) TUTORIAL C2Qara Syifa FBelum ada peringkat
- Askep Demam TifoidDokumen10 halamanAskep Demam TifoidHerrySetiawanBelum ada peringkat
- Materi TyphoidDokumen11 halamanMateri Typhoidsri wahyuniBelum ada peringkat
- Fix Revisi Dokter Armon OkDokumen66 halamanFix Revisi Dokter Armon Okyulita kesumaBelum ada peringkat
- LP KMB I (Thypoid Abdominalis)Dokumen30 halamanLP KMB I (Thypoid Abdominalis)Riska YantiBelum ada peringkat
- Pedoman Pelayanan PasienDokumen11 halamanPedoman Pelayanan PasienSrhi NurhayatiiBelum ada peringkat
- Daftar Obat High AlertDokumen3 halamanDaftar Obat High AlertSrhi NurhayatiiBelum ada peringkat
- Akreditasi RS. Stella Maris Tahun 2015: Yos Immanuel J., SKM, M.KesDokumen15 halamanAkreditasi RS. Stella Maris Tahun 2015: Yos Immanuel J., SKM, M.KesSrhi NurhayatiiBelum ada peringkat