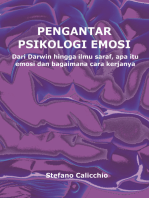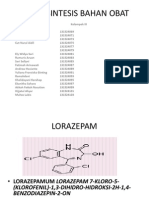Jurnal SSP Perb1
Jurnal SSP Perb1
Diunggah oleh
Chichi2406Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Jurnal SSP Perb1
Jurnal SSP Perb1
Diunggah oleh
Chichi2406Hak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Makin tinggi makhluk hidup berkembang, makin besar kebutuhan akan
system penghantar informasi, system koordinasi, dan sistem pengaturan,
disamping kebutuhan akan organ pemasok dan organ ekskresi. Pada hewan dan
manusia terdapat sistem saraf dan kelenjar endokrin yang membentuk
hormon.Pada manusia, sistem saraf, khususnya otak, mempunyai kemampuan
berfungsi yang jauh lebih berkembang daripada sistem saraf makhluk hidup lain.
Sistem saraf berfungsi:
- Menerima rangsang dari lingkungan atau rangsang yangterjadi dalam tubuh,
- Mengubah rangsang ini dalam perangsangan saraf , menghantar
memprosesnya, serta
- Mengkoordinasi dan mengatur fungsi tubuh melalui impuls-impuls yang
dibebaskan dari pusat ke perifer (Mutschler,1991).
Unsur penyusun system saraf adalah neuron. Disamping suatu badan sel
dengan inti sel, neuron kebanyakan mempunyai banyak cabang sel.Cabang yang
lebih panjang yang disebut neurit atau serabut saraf selalu ada.Kebanyakan sel
saraf menunjukkan cabang-cabang pendek yang banyak yaitu dendrite
(Mutschler,1991).
Sifat pokok makhluk hidup adalah dapat terangsang, yaitu kemampuan sel-
sel tertentu untuk bereaksi terhadap suatu rangsang fisika atau kimia dengan suatu
reaksi spesifik, yaita eksitasi.Disini, disamping sel saraf, terhadap pengkhususan
sel reseptor dan sel saraf.Rangsang dihantarkan ke sel-sel lain melalui neurit.Pada
dendrit, tempat berakhirnya sebagian serabut saraf neuron lain, terjadi pengalihan
rangsang (Mutschler, 1991).
Potensial aksi (impuls saraf) yang dihantarkan terus melalui serabut saraf
berfungsi untuk pengalihan informasi dalam organism.KArena potensial aksi pada
kondisi yang identik memiliki amplitudo dan lama yang sama (Mutschler, 1991).
2
1.2 Tujuan Percobaan
- Untuk mengamati dan memahami stimulan susunan saraf pusat pada
makhluk hidup secara berlebihan.
- Untuk mengetahui efek pemberian Isoniazid pada susunan saraf pusat.
- Untuk mengetahui efek pemberian diazepam pada rangsangan isoniazid.
- Untuk membandingkan antikonvulsi dari diazepam pada dosis yang
berbeda.
3
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sistem saraf Pusat
Sistem saraf pusat berfungsi untuk menerima, memperoses,
menginterpretasikan, dan menyimpan informasi sensoris yang datang seperti
informasi mengenai mengenai rasa, suara, bau, warna tekanan pada kulit, kondisi
organ internal, dan lain lain. Sistem saraf pusat juga mengirimkan pesan untuk
otot, kelenjar, dan organ internal. Secara konseptual, sistem saraf pusat dapat
dikatakan memiliki dua komponen : otak dan saraf tulang belakang. Sebenarnya
saraf tulang belakang merupakan perpanjangan dari otak. Saraf tulang belakang
bermula dari dasar otak, kemudian menjulur di sepanjang bagian tengah punggung
dan dilindungi oleh tulang punggung. Saraf tulang belakang berfungsi sebagai
jembatan yang menghubungkan otak dengan bagian bagian dari tubuh yang
terletak di bawah leher (wade,C & Tavris, C,2008)
Susunan saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan
urat-urat saraf atau saraf cabang yang tumbuh dari otak dan sumsum tulang
belakang yang disebut urat saraf periferi (urat saraf tepi). Jaringan saraf
membentuk salah satu dari empat kelompok jaringan utama pada tubuh
(Evelyn.C, 2009).
Sel-sel saraf berpadu dan membentuk apa yang disebut substansi kelabu
dalam sistem ini, seperti yang dijumpai dalam korteks otak, dan pada bagian
dalam sumsum tulang belakang. Serabut saraf atau akson membentuk substansi
putih. Perbedaan warna ini terjadi karena akson atau serabut penghantar diselimuti
sejenis sarung yang terbentuk dari bahan seperti lemak, yang mempunyai fungsi
melindungi, memberi makan, dan memisahkan serabut serabut yang satu dari
yang lainnya. Sebuah sel saraf berikut aksonnya dan proses lainnya membentuk
sebuah neuron. Pada saat pembentukan batang saraf, serabut serabut saraf
disusun menjadi berkas berkas yang disebut fasikuli. Sebuah serabut saraf
mempunyai konduktivitas (penghantar) dan excitabilitas (dapat dirangsang)
(Evelyn.C, 2009).
4
Sistem saraf mempunyai sifat-sifat unik berkaitan dengan proses berfikir
dan fungsi pengaturan yang sangat kompleks yang dapat dilakukannya. Sistem ini
setiap menit menerima berjuta-juta rangsangan informasi yang berasal dari
bermacam-macam saraf sensorik dan organ sensorik, kemudian menyatukan
semuanya untukj menentukan respons apa yang akan diberikan oleh tubuh
(Guyton, 2007).
Susunan saraf:
1. Saraf sadar
- Saraf pusat
Saraf pusat terdiri dari otak dan sumsung tulang belakang.
- Otak
Otak manusia terdiri dari belahan kiri dan kanan. Kedua belahan tersebut
dihubungkan oleh balok otak yang berongga (ventrikel) yang berisi cairan
getah bening (cerebrospinal)
- Sumsum tulang belakang
Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat dari gerak reflex,
pengantar impuls sensori dari kulit atau otot ke otak, dan pembawa impuls
motor dari otak ke otot tubuh.
- Saraf tepi
Saraf tepi teridiri dari system saraf sadar dan system saraf tak sadar
(Izzudin, 2008).
SSP adalah dibentuk oleh ventral segmental ganglia dan otak, dan
biasanya mengontrol reproduksi, metamorfosis, pertumbuhan, metabolisme, dan
perilaku serangga secara langsung. serangga memiliki menyediakan sistem model
penting untuk analisis jaringan saraf yang mendasari semua macam perilaku.
Diptera seperti Drosophila melanogaster, telah lama digunakan untuk studi
tentang sistem saraf (Mora. S, 2011).
Jaringan otak system saraf pusat (SSP) sangat peka terhadap berbagai
cedera seperti sangat peka terhadap berbagai cedera seperti trauma mekanik,
ischemia, dan stress oksidatif. Baik cedera SSP maupun penyakit
neurodegenerative dapat mengakibatkan berbagai tingkat kematian neuron dan
neuroinflamasi serta kelemahan memori. Selama lebih dari satu decade diyakini
5
bahwa jaringan otak yang mengalami kerusakan tidak dapat mengalami
regenerasi, karenanya kerusakan pada SSP dapat bersifat permanen. Namun
kemudian, diketahui bahwa didalam jaringan SSP masih terdapat populasi neural
system cells ataupun neural progenitor cells (Djuwita, dkk. 2012).
Sistem saraf pusat mengandung lebih dari 100 juta neuron.
Memperlihatkan jenis neuron yang khas yang ditemukan di korteks motorik otak.
Sinyal yang datang memasuki neuron melalui sinaps yang lokasinya kebanyakan
pada neuron dendrit, namaun juga pada badan sel. Untuk berbagai jenis neuron,
mungkin hanya terdapat beberapa ratus atau sampai 200.000 sambungan sinaptik
dari serabut yang masuk. Sebaliknya, sinyal yang keluar berjalan melalui jalur
akson tunggal meninggalkan neuron. Kemudian, akson ini memiliki banyak
cabang yang berbeda kebagian-bagian lain sistem saraf atau tubuh bagian perifer
(Guyton, 2007).
Aktivitas penekan system saraf pusat dipengaruhi oleh sifat lipofilik,
elektronik, dan sterik. Sifat lipofilik terutama mempengaruhi kemampuan
senyawa dalam menembus membrane biologis, sifat elektronik terutama
mempengaruhi proses interaksi obat reseptor selain juga meningkatkan
penembusan senyawa ke dalam membrane biologis, sedangkan sifat sterik
menentukan keserasian interaksi senyawa dengan reseptor dalam sel. Peningkatan
sifat lipofilik dapat dilakukan dengan memasukkan gugus atau subtituen nonpolar,
sedangkan peningkatan sifat elektronik dilakukan dengan memasukkan substituent
yang bersifat elektronegatif, seperti halogen, ke dalam cincin aromatic. Kelarutan
meksimum golongan sedative hipnotik terjadi pada koefisien partisi antara fase
lipid dan air mendekati 100 (Guyton, 2007).
Fungsi sistem saraf pusat
Sistem saraf mempunyai kemampuan fungsional khusus yang diturunkan
pada setiap tahap perkembangan evolusi manusia. Dari sifat-sifat yang diwariskan
ini, tiga tingkat utama sistem saraf pusat mempunyai sifat-sifat fungsional yang
khas, yakni:
1. Tingkat medula spinalis
Suatu saluran untuk menyalurkan sinyal yang berasal dari perifer tubuh ke
otak atau dengan arah yang berlawanan dari otak kembaliu ketubuh. Hal ini
6
sebenarnya jauh dari keadaan yang sebenarnya. Biarpun medula spinalis itu telah
dipotong setinggi darerah leher atas, banyak fungsi medula spinalis itu masih tetap
ada. Contohnya, sirkuit neorol dalam medula spinalis dapat menyebabkan gerakan
berjalan, refleks yang menarik bagian tubuh dari suatu objek, refleks yang
mengeraskan kaki guna menunjang tubuh terhadap gravitasi, dan refleks yang
dipakai untuk mengatur pembuluh-pembuluh darah setempat, gerakan
gastrointestinal atau ekskresi urin.
2. Tingkat otak bagian bawah,atau subkortikal
Aktivitas bawah sadar dari tubuh diatur oleh bagian bawah otak pada
medula oblongata, pons, mesensefalon, hipotalamus, talamus, serebelum, dan
ganglia basalis. Sebagai contoh, pengaturan bawah sadar dari tekanan arteri dan
pernapasan terutama dicapai didalam medula dan pons.
3. Tingkat otak bagian atas atau tingkat korteks.
Korteks selebri merupakan gudang memori yang sangat besar. Koterks itu
tidak pernah berfungsi sendiri tetapi slalu berhungan dengan pusat-pusat bagian
bawah sistem saraf. Tanpa adanya korteks serebri, fungsi pusat-pusat otak bagian
bawah sangat tidak teliti lagi.Tempat penyimpanan atau gudang informasi yang
luas dalam korteks biasanya akan mengubah fungsi-fungsi ini menjadi tindakan
yang lebih tepat dan tertentu. Akhirnya, korteks selebri berguna untuk sebagian
Sinaps saraf pusat
Informasi yang dijalarkan sistem saraf pusat terutama dalam bentuk
potensial aksi saraf, disebut impuls saraf, yang melewati serangkaian neuron
neuron, darisatu neuron satu ke neuron berikutnya. Namun, selain itu, setiap
impuls itu mungkin dihambat suatu dijalarkan dari satu neuron ke neuron
berikutnya, mungkin diubah dari impuls tunggal menjadi impuls yang datangnya
beruntun, atau mungkin digabungkan dengan impuls yang datang dari neuron-
neuron lainnya untuk membentuk pola impuls yang sangat ruwet yang melewati
serangkaian neuron (Guyton, 2007).
Terdapat 2 macam sinaps, yaitu:
1. Sinaps kimia
Pada sinaps kimia ini, neuron pertama menyekskresikan pada sinaps ujung
sarafnya suatu bahan kimia yang disebut neurotransmiter (atau sering disebut
7
bahan transmiter), dan bahan transmiter ini sebaliknya bekerja pada protein
reseptor dalam membran neuron berikutnya sehingga neuron tersebut akan
terangsang, menghambatnya, atau mengubah sensitivitasnya dalam berbagai cara.
Beberapa diantaranya adalah astikolin, norepinefrin, epinefrin, histamin, asam
gamma amino butirat (GABA), glisin, serotonin, dan glutamat.
2. Sinaps listrik
Ditandai adanya kanal cairan terbuka langsung yang menjalarkan aliran
listrik dari sartu sel ke sel berikutnya. Kebanyakan saluran ini terdiri atas struktur
tubular protein kecil yang disebut gapjunctions yang memudahkan pergerakan
ion-ion secara bebas dari bagian dalam suatu sel kebagian dalam sel berikutnya
(Guyton, 2007).
Transmisi rangsang
Impuls yang keluar dari SSP dikirim ke ganglia parasimpatik, lalu
ditempatkan tersebut, asetilkolin meneruskan impuls ke serat serat
pascaganglion. Rangsangan pada ujung ujung saraf parasimpatik mengakibatkan
curahan asetilkolin dari dalam vesikel. Pada organ sasaran, asetilkolin
menyebabkan perangsangan reseprot reseptor khusus (Schmitz, 2009).
Striknin merupakan alkaloid tanaman nux vomica, yang tidak bermanfaat
untuk pengobatan, tetapi berguna untuk menjelaskan fisiologi dan farmakologi
susunan saraf pusat dan merupkan obat utama diantara obat-obat yang bekerja
menstimulasi susunan saraf pusat (Schmitz, 2009).
Striknin merupakan senyawa yang bekerja dengan mengadakan
antagonisme secara kompetitif terhadap transmitor di daerah pasca sinap.
Pemberian striknin dalam dosis tinggi menyebabkan kejangan tonik dan klonik,
kematian terjadi bila kejangan tonik yang meliputi keseluruhan otot rangka
termasuk otot pernafasan berlangsung terlampau lama (Schmitz, 2009).
Pada hewan percobaan umumnya konvulsi ini berupa ekstensi tonik dari
badan dan semua anggota gerak, maka kejang/konvulsi oleh striknin berbeda
dengan yang diakibatkan oleh obat yang langsung merangsang neuron pusat,
kejang oleh striknin terjadi suatu gerakan yang berupa kontraksi ekstensor yang
8
simetris, kontraksi ini diperkuat oleh rangsangan sensorik, baik penglihatan,
pendengaran, maupun perabaan (Schmitz, 2009).
2.2 Obat-Obat untuk susunan saraf pusat
Obat-obat yang bekerja untuk sistem saraf pusat (SSP) merupakan salah
satu yang pertama ditemukan manusia primitif dan masih digunakan secara luas
sebagai zat farmakologi sampai sekarang. Disamping penggunaannya dalam
terapi, obat-obat sistem saraf pusat dipakai untuk meningkatkan kesehatan tanpa
resep. Kopi, alcohol, dan nikotin digunakan masyarakat diperbagai Negara,
hampir merata diseluruh dunia. Karena beberapa obat-obat golongan bersifat
adiktif dan menyebabkan disfungsi berat baik bagi pribadi, social maupun
ekonomi, maka masyarakat merasa perlu member batasan penggunaan dan
penyediannya (Katzung, 1997).
Cara kerja berbagai obat pada sistem saraf pusat (SSP) belum begitu jelas.
Karena penyebab penyakit-penyakit yang disembuhkannya (skizofren, ansietas,
dan lain-lain). Dalam dua puluh tahun terakhir, banyak kemajuan yang diperoleh
dalam farmakologi sistem saraf pusat (SSP). Informasi yang diperoleh dalam studi
ini merupakan dasar dari beberapa perkembangan penelitian SSP (Katzung, 1997).
Pertama, jelas semua obat-obat sistem saraf pusat bekerja pada reseptor
khusus yang mengatur transmisi sinaps. Beberapa obat seperti anastetik umum
dan alcohol dapat bekerja secara nonspesifik pada membran (meskipun
pengecualian ini tidak sepenuhnya diterima) tetapi kerja tanpa melalui reseptor ini
mengakibatkan perubahan-perubahan yang mencolok pada transmisi sinaps
(Katzung, 1997).
Kedua obat-obatan merupakan alat paling penting untuk mempelajari
aspek fisiologi sistem saraf pusat (SSP) mulai dari terjadinya bangkitan sampai
pada penyimpanan memori jangka panjang. Seperti akan diterangkan dibawah,
agonis yang menyerupai transmitter alamiah (dalam beberapa kasus lebih selektif
dari zat endogen) dan antagonis sangat berguna dalam penelitian (Katzung, 1997).
Ketiga, kerja obat dengan manfaat klinik yang nyata telah membawa
hipotesa yang sangat menguntungkan mengenai mekanisme penyakit. Misalnya,
informasi tentang obat antipsikotik pada reseptor memberikan dasar hipotesa
9
tentang patologi skizopren. Kajian beberapa efek agonis dan antagonis respetor
asam gamma aminobutirat (GABA) memberikan konsep baru tentang patofisologi
penyakit-penyakit yang berhubungan dengan obat-obatan sistem saraf pusat
termasuk penyakit ansietas dan epilepsy (Katzung, 1997).
Diazepam
Diazepam dapat merupakan relaksan otot yang bekerja sentral dan
berpengaruh selektif terhadap refleks polisinaptik disumsum tulang belakang,
maka diazepam dapat digunakan untuk mengatasi kejangan yang diakibatkan
striknin. digunakan sebagai obat referensi (kontrol positif) untuk anxiolytic,
sedatif, relaksan otot dan aktivitas antikonvulsan. fluoxetine digunakan sebagai
standar obat untuk efek antidepresan dan sodium pentobarbital digunakan untuk
menginduksi hypnosis (Zhang. DKK, 2012).
2.3 Tempat kerja obat sistem saraf pusat (SSP)
Obat- obat yang bekerja di sistem saraf pusat sebagian besar menimbulkan
efek dengan mengubah beberapa tahapan transmisi sinaps kimia. Kegiatan obat-
bat sistem saraf pusat dalam mengubah tahapan transmisi sinaps kimia dapat
dibagi dalam katagori presinaptik dan pascasinaptik (Katzung, 1997).
Dalam katagori presinaptik termasuk obat-obat yang bekerja untuk
sintesis, penyimpanan, metabolisme dan penglepasan neurotransmitter. Transmisi
sinaptik dapat ditekan dengan penghambatan sintesis atau penyimpanan
transmitter. Contohnya -klorofenilalanin menghambat sintesis serotonin, dan
reserpin menguras monoamine dari sinaps dengan mengganggu simpanan
intraseluler. Penghambatan katabolisme transmitter dapat meningkatkan
konsentrasi transmitter dan juga jumlah transmitter yang dilepaskan per impuls.
Obat-obatan juga dapat mengubah jumlah pelepasan transmitter (Katzung, 1997).
Didaerah pascasinaptik, reseptor transmitter merupakan tempat pertama
obat bekerja. Obat-obat dapat berfungsi sebagai agonis neurotransmitter, seperti
opiate, bekerja seperti enkefalin atau menghambat fungsi reseptor. Antagonis pada
reseptor. Antagonis pada reseptor merupakan mekanisme yang biasa dari obat-
obat sistem saraf pusat. Contohnya penghambatan striknin pada reseptor
penghambat transmitter glisin. Hambatan ini merupakan dasar terjadinya kejang
10
striknin, menggambarkan bagaimana proses hambatan inhibisi dan akan
menimbulkan eksitasi. Umumnya reseptor tergabung pada satu atau dua macam
mekanisme transduksi (Katzung, 1997).
Reseptor yang terdapat pada sebagian besar sinaps si sistem saraf pusat
terikat pada saluran ion, dan reaktivasi reseptor yang khusus akan menyebabkan
pembukaan saluran dalam dalam periode yang periode yang sangat cepat. Obat-
obatan ini juga dapat mempengaruhi ion secara langsung, sebagai contoh
barbiturat masuk dan menghambat saluran yang tergabung pada reseptor
neurotransmitter eksitatif (Katzung, 1997).
2.4 Perangsang Sistem saraf pusat
Efek perangsangan susunan saraf pusat (SSP) baik oleh obat yang berasal
dari alam atau sintetik dapat diperlihatkan pada hewan dan manusia. Beberapa
obat memerlihatkan efek perangsangan yang nyata dalam dosis toksik, sedangkan
obat lain memperlihatkan efek perangsangan system saraf pusat (SSP) sebagai
efek samping (Tanu, 1995).
Dahulu beberapa sintetik analeptik digunakan untuk mengatasi intoksikasi
berat obat penekan SSP umum, sekarang tindakan ini tersisih karena dengan
tindakan konservatif berupa perawatan intensif hasil-hasilnya jauh lebih baik.
Dalam dosis yang cukup, semua analeptik menimbulkan kejang secara umum dan
sayangnya sebagai obat perangsang pusat nafas memperhatikan batas keamanan
yang sangat sempit dan sulit diramalkan. Pada saat ini belum ada obat yang
perangsang yang aman dan selektif sehingga penggunaan obat analeptik amat
dibatasi (Tanu, 1995).
Perangsang SSP oleh obat pada umumnya melalui dua mekanisme yaitu :
1. Mengadakan blokade sistem penghambat
2. Meningkatkan perangsangan sinaps Dalam SSP dikenal sistem penghambatan
pascasinaps dan penghambatan prasinaps. Stiknin merupakan prototip obat yang
mengadakan blokade selektif terhadap sistem penghambatan ptrasinaps, dan
kedua obat ini penting dalam bidang penelitian untuk mempelajari berbagai
macam jenis reseptor dan antagonisnya. Analeptik lain tidak berpengaruh
11
terhadap sistem penghambatan dan mungkin bekerja dengan meninggikan
perangsangan sinaps (Tanu, 1995).
2.5 Susunan Sistem Saraf Pusat (SSP)
Semua anastetik lokal merangsang SSP, menyebabkan kegelisahan dan
tremor yang mungkin berubah menjadi kejang klonik. Secara umum makin kuat
suatu anatetik mekin mudah menimbulkan kejang. Perangsangan iniu akan diikuti
depresi, dan kematiannya biasa terjadi karena kelumpuhan nafas. Disini pada
penggunaan nafas tidak efektif sebab anastetik lokal sendiri merangsang
pernafasan, depresi nafas timbul karena perangsangan SSP berlebihan.
Perangsangan yang di susul oleh depresi pada pemakaian anastetik lokal itu hanya
disebabkan oleh depresi pada aktivitas neuron. Perangsangan ini terjadi karena
adanya depresin selektif pada neuron penghambat. Pada keracunan lanjut,
disamping memperbaiki pernafasan, penting juga menggunakan hipnot
menggunakan hipnotik untuk mencegah dan mengobati kejang. Dalam hal ini
pemberian diazepam merupakan obat terpilih, untuk mencegah atau menghentikan
kejang (Katzung, 2004).
2.7 Isoniazid (INH)
Isoniazid yang diperkenalkan pada tahun 1953, merupakan obat paling
aktif dalam pengobatan pada penderita yang dapat mentoleransi obat tersebut atau
pada mikobakterianya rentan. Isoniazid adalah asam isonikotinat hidrazid, yang
sering disebut INH. Obat ini merupakan molekul sederhana yang kecil (BM 137)
dan bebas larut dalam air. Struktur kimia obat ini mirip piridoksin (Katzung,
1997).
Bentuk isoniazid yang diaktifkan menghasilkan efek mematikan dengan
membentuk sebuah kompleks kovalen dengan sebuah protein pembawa (AcpM)
dan KasA, suatu pembawa beta-ketoacyl protein synthesase yang menyatakan
sintesis myocolic acid. Resistensi terhadap terhadap isoniazid telah di asosiasikan
dengan mutasi yang menghasilkan overekspresi dari ahpC sebuah gen virulence
dugaan yang terlibat dalam proteksi sel dari stress oksidatif dan mutasi pada kasA
(Katzung, 2004).
12
BAB III
METODE PERCOBAAN
3.1 Alat
- Timbangan elektrik
- Spuit skala 40
- Stopwatch
- Alat suntik 1 ml
- Kandang metabolit
3.2 Bahan
- Akuades
- Diazepam 0,5%
- INH 1%
3.3 Hewan percobaan
Hewan uji yang digunakan adalah mencit
3.4 Prosedur percobaan
1. Ditimbang dan ditandai diekor
2. Dihitung dosis dengan pemberian
Pemberian dosis
- Mencit 1 : Kontrol akuades dosis 1% BB secara i.p
- Mencit 2 : Diazepam 0,5% dosis 20 mg/kgBB secara i.p
- Mencit 3 : Diazepam 0,5% dosis 25 mg/kgBB secara i.p
- Setelah 45 menit masing-masing mencit diberi INH 1% dosis 250
mg/kgBB secara i.p
3. Diamati gejala yang terjadi pada mencit
4. Disuntikkan masing-masing mencit dengan INH 1% dosis 250 mg/kgBB
secara i.p setelah 45 menit
5. Diamati gejala dan kejang yang terjadi selama 45 menit dengan selang waktu
5 menit
13
3.5 Perhitungan Dosis
1. Mencit 1:
Kontrol akuades dosis 1% /BB secara i.p
BB mencit = 29,8 g
Skala =
Jumlah obat =
Jumlah obat yang diberikan =
INH 1% dosis 250 mg/kgBB
INH 1% =
= 10 mg/ml
Jumlah obat =
5 mg
Jumlah obat yang diberikan =
Skala yang diberikan =
2. Mencit 2:
Diazepam 0,5% dosis 20 mg /kgBB secara i.p
BB mencit = 24,8 g
Skala =
Diazepam 0,5 % =
= 5 mg/ml
Jumlah obat =
mg
Jumlah obat yang diberikan =
Skala yang diberikan =
INH 1% dosis 250 mg/kgBB
INH 1% =
= 10 mg/ml
Jumlah obat =
mg
Jumlah obat yang diberikan =
Skala yang diberikan =
14
3. Mencit 3:
Diazepam 0,5% dosis 25 mg /kgBB secara i.p
BB mencit = 28,8 g
Skala =
Diazepam 0,5 % =
= 5 mg/ml
Jumlah obat =
mg
Jumlah obat yang diberikan =
Skala yang diberikan =
INH 1% dosis 250 mg/kgBB
INH 1% =
= 10 mg/ml
Jumlah obat =
mg
Jumlah obat yang diberikan =
Skala yang diberikan =
15
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil
A. Sebelum Pemberiaan INH
No
Waktu
(Menit)
Dosis
Kontrol (Aquadest)
Diazepam dosis
20 mg/kg BB
Diazepam dosis
25 mg/kg BB
1 5 1.1 1.3 1.3
2 10 1.1 1.3 1.3
3 15 1.1 1.3 1.3
4 20 1.1 1.3 1.3
5 25 1.1 1.3 1.3
6 30 1.1 1.3 1.4
7 35 1.1 1.4 1.4
8 40 1.1 1.4 1.4
9 45 1.1 1.4 1.4
B. Setelah Pemberian Isoniazid
No
Waktu
(Menit)
Dosis
Kontrol (Aquadest)
Diazepam dosis
20 mg/kg BB
Diazepam dosis
25 mg/kg BB
1 5 1.1 1.3 1.3
2 10 1.1 1.3 1.3
3 15 1.2 1.3 1.3
4 20 1.2 1.3 1.3
5 25 1.2 1.3 1.3
6 30 1.2 1.3 1.4
7 35 1.2 1.4 1.4
8 40 1.2 1.3 1.4
16
9 45 1.2 1.3 1.4
10 50 1.5 1.3 1.4
11 55 1.2 1.3 1.4
12 60 1.2 1.3 1.4
4.2 Pembahasan
Sebelum pemberian isoniazid, mencit pertama dengan berat 32 kg yang
diberikan kontrol aquadest 1% BB memberikan reaksi normal, dari pengamatan
menit ke-5 hingga pada menit ke-50. Setelah diinjeksikan isoniazid 0,025%
dengan dosis 1,5 mg/kg BB, mencit pertama menunjukkan reaksi yang reaktif dari
menit ke-15 hingga menit ke-45 dan kejang pada menit ke-50 kemudian kembali
reaktif lagi hingga menit ke-60.
Kejang yang terjadi pada mencit pertama karena efek samping dari dosis
toksik yang diberikan oleh isoniazid yaitu polyneuritis yakni radang saraf dengan
gejala kejang dan gangguan penglihatan yang disebabkan oleh persaingannya
dengan piridoksin yang rumus kimianya mirip INH (Tjay, 2007).
Mencit kedua dengan berat 39,8 kg yang diberikan Diazepam 0,5%
dengan dosis 20 mg/kgBB langsung menunjukkan reaksi berupa gerak lambat dari
menit ke-5 hingga menit ke-30 dan tidur pada menit ke-35 hingga menit ke-45.
Setelah diinjeksikan isoniazid 0,025% dengan dosis 1,5 mg/kg BB, mencit kedua
menunjukkan reaksi berupa gerak lambat dari menit ke-5 hingga menit ke-30,
tidur pada menit ke-35, dan kembali gerak lambat pada menit ke-40 hingga menit
ke-60.
Pada mencit ketiga dengan berat 25,2 kg yang diberikan Diazepam 0,5%
dengan dosis lebih tinggi, yaitu 25mg/kgBB. Berdasarkan hasil pengamatan pada
menit ke-5, menit ke-10, menit ke-15, menit ke-20 dan menit ke-25 menunjukkan
respon gerakan lambat. sedangkan pada menit ke-30 hingga menit ke-45 mencit
menunjukkan respon tidur, walaupun mencit sudah diberikan rangsangan dari
luar. Setelah disuntikkan isoniazid 0,025% dengan dosis 1,5 mg/kgBB, mencit
menunjukkan respon gerak lambat pada menit ke-5 dan pada menit ke-10,
sedangkan pada menit ke-15 hingga menit ke-60 mencit menunjukkan respon
tidur.
17
Pada mencit ke-2 dan ke-3 tidak menimbulkan kejang dibandingkan
dengan kontrol, hal ini dikarenakan mencit ke-2 dan ke-3 telah diinjeksikan
terlebih dahulu dengan diazepam sebagai antikejang dengan dosis 20 mg/Kg BB
dan 25 mg/Kg BB, sedangkan pada mencit control hanya diberikan enjeksi
aquades 1% BB. Diazepam yang diberikan sangat efektif untuk menghentikan
aktivitas kejang kontinu, terutama status epileptikus umum tonik-klonik.
diazepam bekerja pada sinaps GABA
A
, dan sebagian kerjanya dalam mengurangi
spastisitas setidaknya diperentarai di medulla spinalis karena obat ini sangat
efektif pada pasien yang mengalami transeksi medulla spinalis, diazepam
menghasilkan sedasi pada dosis yang diperlukan untuk menurunkan tonus otot
(Katzung, 2007).
18
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
- Stimulan yang berlebihan pada susunan saraf pusat dapat menyebabkan
kejang pada hewan percobaan
- Pemberian INH secara berlebihan menyebabkan kejangan tonik dan klonik
bahkan kematian akibat kejangan tonik.
- Diazepam mempunyai efek sebagai anti-konvulsan yang dapat mengatasi
kejang yang diakibatkan oleh INH.
- Semakin tinggi dosis diazepam yang diberikan semakin besar memberikan
efek antikonvulsi pada hewan percobaan.
5.2 Saran
- Sebaiknya pada durasi percobaan dilakukan lebih dari 2 jam untuk melihat
efek maksimal dari obat antikonvulsi tersebut.
- Sebaiknya percobaan dilakukan menggunakan obat lain yang juga dapat
menyebabkan kejang.
- Sebaiknya percobaan dilakukan pada hewan percobaan lain.
19
DAFTAR PUSTAKA
Djuwita, Ita., dkk. (2012). Pertumbuhan Sekresi Protein Hasil Kultur Primer Sel-
sel Sereberum Anak Tikus. Jurnal Veteriner Juni 2012 Vol. 13 No.2.
(http://ojs.unud.ac.id/index.php/jvet/article/view/5994)
Pearce, E.C, (2009). Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis. Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama.
Guyton, A.C., Hall, J.E. (2007). Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Katzung, B. G. (2007). Farmakologi Dasar dan Klinik. Jakarta: Salemba
Medika.
Katzung, Bertram, G. (1997). Farmakologi Dasar dan Klinik , Edisi Ke 6. Jakarta:
Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Katzung, Bertram, G. (2004). Farmakologi Dasar dan Klinik , Edisi Ke 8. Jakarta:
Penerbit Salemba Empat.
Mutschler, E. (1991). Dinamika Obat. Bandung: ITB.
Mora, S. (2011). Central nervous system activity of the hydroalcoholic ekxtract of
casimiroa eduils in rats and mice.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874104005604
Tjay, T.H, dan Rahardja, Kirana. (2007). Obat-Obat Penting. Jakarta: PT Elex
Media Komputindo.
Wade.C & Tavris.C., (2008), Psikologi. Edisi 9. Jilid 1. Jakarta: Penerbit
Erlangga
Zhang, Zhengyi, dkk. (2012). Identification Of Representative genes Of The
Central Nervous System Of The Locust, Locusta migratoria manilensis bu
Deep Sqeuencing. Journal of Insect Science: Vol.12.
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23421689) diakses tanggal 5 April
2014.
Tanu, I., (1995), Farmakologi dan Terapi, Edisi Keempat, Fakutas Kedokteran
Universitas Indonesia, Jakarta.
Anda mungkin juga menyukai
- Bab 1 AnfisDokumen25 halamanBab 1 AnfisPache ChristyoBelum ada peringkat
- Kelompok 1 PersyarafanDokumen12 halamanKelompok 1 Persyarafan베띠땀바Belum ada peringkat
- Fiswan Saraf FixDokumen21 halamanFiswan Saraf FixNaning Dwi LestariBelum ada peringkat
- Anatomi Dan Fisiologi Sistem PersarafanDokumen25 halamanAnatomi Dan Fisiologi Sistem PersarafanAgstri Dwi MarselaBelum ada peringkat
- Kel 1Dokumen12 halamanKel 1베띠땀바Belum ada peringkat
- Biomedik Dasar Anatomi Dan FisiologiDokumen18 halamanBiomedik Dasar Anatomi Dan FisiologiZairul AshariBelum ada peringkat
- Makalah PsikologiDokumen12 halamanMakalah PsikologiFatih BasmalahBelum ada peringkat
- Anatomi FIsiologi SIstem NeurologiDokumen34 halamanAnatomi FIsiologi SIstem NeurologiNikmah El-husna HusainBelum ada peringkat
- Sistem Koordinasi Pada ManusiaDokumen19 halamanSistem Koordinasi Pada ManusiasalsaBelum ada peringkat
- SISTEM SARAF NEUROLOGI (Nining)Dokumen19 halamanSISTEM SARAF NEUROLOGI (Nining)AsrikimalahaBelum ada peringkat
- Pembagian Sistem SarafDokumen22 halamanPembagian Sistem SarafMWBelum ada peringkat
- Fisiologi Olahraga (Sistem Saraf)Dokumen8 halamanFisiologi Olahraga (Sistem Saraf)KriztianBelum ada peringkat
- Makalah Sistem RegulasiDokumen26 halamanMakalah Sistem RegulasiprechelBelum ada peringkat
- Bab 3 Sistem Saraf Dan Indera ManusiaDokumen42 halamanBab 3 Sistem Saraf Dan Indera ManusiaMariama RestiBelum ada peringkat
- Sistem Saraf Pada Manusia NaveDokumen27 halamanSistem Saraf Pada Manusia NaveNatasia TanaumaBelum ada peringkat
- Anatomi & Fisiologi Sistem SarafDokumen18 halamanAnatomi & Fisiologi Sistem SarafFitri EgaBelum ada peringkat
- LP Epilepsi AnakDokumen28 halamanLP Epilepsi Anakyvs552kcfqBelum ada peringkat
- Jaringan SarafDokumen6 halamanJaringan SarafVyan BagusBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan EpilepsiDokumen39 halamanLaporan Pendahuluan EpilepsiReza SimbeBelum ada peringkat
- Kata PengantarDokumen19 halamanKata PengantarbuyagolazoBelum ada peringkat
- Sistem Saraf Pada ManusiaDokumen28 halamanSistem Saraf Pada ManusiaSeptiana Putrining Suci AdiBelum ada peringkat
- LP Epilepsi AnakDokumen25 halamanLP Epilepsi Anakyvs552kcfqBelum ada peringkat
- Sistem Saraf & Sistem KoordinasiDokumen6 halamanSistem Saraf & Sistem KoordinasiErfanBelum ada peringkat
- Sistem Saraf Dan Pusat InformasiDokumen14 halamanSistem Saraf Dan Pusat InformasiLutfiana FaridaBelum ada peringkat
- Bahan Ajar KoordinasiDokumen15 halamanBahan Ajar KoordinasiSyavira AzzahraBelum ada peringkat
- Proses Pembentukan Sistem Saraf PusatDokumen22 halamanProses Pembentukan Sistem Saraf Pusatriskamanda94Belum ada peringkat
- Tugas Praktikum NeuroDokumen5 halamanTugas Praktikum NeuroN.F AbdillahBelum ada peringkat
- Sistem Saraf Dan Sistem EndokrinDokumen11 halamanSistem Saraf Dan Sistem EndokrinselviBelum ada peringkat
- Makalah Anatomi Fisiologi Sistem SyarafDokumen172 halamanMakalah Anatomi Fisiologi Sistem Syarafyolaengla28Belum ada peringkat
- Makalah Jaringan SarafDokumen41 halamanMakalah Jaringan SarafGiovanni TakeneBelum ada peringkat
- Sistem KoordinasiDokumen31 halamanSistem KoordinasiRiski AmalludinBelum ada peringkat
- Resume Anfis Sistem PersarafanDokumen20 halamanResume Anfis Sistem PersarafanHusna ArdianaBelum ada peringkat
- Sistem RegulasiDokumen27 halamanSistem RegulasiDickyBelum ada peringkat
- Sistem Saraf PusatDokumen14 halamanSistem Saraf Pusatmaghfirah jailaniBelum ada peringkat
- Sistem Saraf Pada ManusiaDokumen19 halamanSistem Saraf Pada ManusiaaprilBelum ada peringkat
- Sistem PersyarafanDokumen18 halamanSistem PersyarafanFeby YuniarBelum ada peringkat
- LP FebrisDokumen17 halamanLP FebrisEriyan Pratama LutfiBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan VertigoDokumen25 halamanLaporan Pendahuluan VertigoMarioDalthonBelum ada peringkat
- Makalah Jaringan SarafDokumen17 halamanMakalah Jaringan SarafAnche Poe0% (1)
- Ipa Sistem SarafDokumen19 halamanIpa Sistem SarafSaniya jauharBelum ada peringkat
- Resume Materi Sistem Saraf Dan Special SenseDokumen21 halamanResume Materi Sistem Saraf Dan Special SenseFrensi Arynanti TangkiBelum ada peringkat
- Histologi Saraf Dan EndokrinDokumen16 halamanHistologi Saraf Dan EndokrinNabillah HazimahBelum ada peringkat
- Farmakologi 2018Dokumen64 halamanFarmakologi 2018Surya RamadhanBelum ada peringkat
- Hernia Nukleus PulposusDokumen61 halamanHernia Nukleus Pulposuseuis salsabila izzatiBelum ada peringkat
- Resume Sistem Persyarafan Kel 4Dokumen21 halamanResume Sistem Persyarafan Kel 4Intan Fatria YulianiBelum ada peringkat
- Makalah Sistem SarafDokumen13 halamanMakalah Sistem SarafyanuarBelum ada peringkat
- Makalah Sistem Saraf Manusia (1) ARSENNNDokumen32 halamanMakalah Sistem Saraf Manusia (1) ARSENNNetris angkutBelum ada peringkat
- Potensial AksiDokumen15 halamanPotensial AksiRipiani Yanditri0% (1)
- Sistem Saraf Pusat Dan PeriferDokumen24 halamanSistem Saraf Pusat Dan PeriferErwanda Eka PrastikaBelum ada peringkat
- Patman Penyakit SyarafDokumen12 halamanPatman Penyakit SyarafMedyarina KurniasihBelum ada peringkat
- Sistem Regulasi Pada Manusia 2Dokumen23 halamanSistem Regulasi Pada Manusia 2Ayu Laila MuflihaBelum ada peringkat
- Jaringan Epitel NinyDokumen16 halamanJaringan Epitel NinyEster MangeroBelum ada peringkat
- Revisi Logbook Stroke KMBDokumen46 halamanRevisi Logbook Stroke KMBSiti Alifah PutriBelum ada peringkat
- Toaz - Info Makalah Konsep Kekritisan Neurologi PR DikonversiDokumen73 halamanToaz - Info Makalah Konsep Kekritisan Neurologi PR DikonversiDesti NopitaBelum ada peringkat
- Makalah FisiologiDokumen12 halamanMakalah FisiologifarizdiaulhaqBelum ada peringkat
- Laprak Sistem SarafDokumen13 halamanLaprak Sistem SarafRaden Ayu RantyBelum ada peringkat
- Sel SarafDokumen10 halamanSel SarafArni LajuluBelum ada peringkat
- Struktur Neuron Beserta FungsinyaDokumen21 halamanStruktur Neuron Beserta FungsinyaRima DwiBelum ada peringkat
- Pengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPengantar psikologi emosi: Dari Darwin hingga ilmu saraf, apa itu emosi dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Identifikasi AmylumDokumen6 halamanIdentifikasi AmylumChichi2406100% (1)
- Tes Urine MultidrugDokumen7 halamanTes Urine MultidrugChichi2406Belum ada peringkat
- Tugas Sintesis Bahan ObatDokumen17 halamanTugas Sintesis Bahan ObatChichi2406Belum ada peringkat
- Skrining Fitokimia Golongan Senyawa Kimia SaponinDokumen2 halamanSkrining Fitokimia Golongan Senyawa Kimia SaponinChichi2406Belum ada peringkat
- Anatomi RambutDokumen1 halamanAnatomi RambutChichi2406Belum ada peringkat
- Pemeriksaan Psikotropika Dan NarkotikaDokumen16 halamanPemeriksaan Psikotropika Dan NarkotikaChichi2406Belum ada peringkat
- Sulfaguanidin BaruDokumen8 halamanSulfaguanidin BaruChichi2406Belum ada peringkat
- Asma Pada Ibu HamilDokumen10 halamanAsma Pada Ibu HamilChichi2406Belum ada peringkat