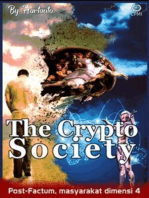Pemikian Gus Dur Budaya
Diunggah oleh
Fadilla Muhammad CcifpHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Pemikian Gus Dur Budaya
Diunggah oleh
Fadilla Muhammad CcifpHak Cipta:
Format Tersedia
Agama Di TV Dan Dalam Kehidupan Oleh: Abdurrahman
Wahid
Pada suatu hari yang cerah, penulis memasuki ruang tunggu lapangan terbang Cengkareng, jam 5.30 wib pagi. Sambil menunggu saat penerbangan pertama ke Yogyakarta, penulis mendengarkan siaran TV di ruang tunggu itu. Seorang penceramah agama sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para pemirsa melalui telepon, ketika dihadapkan pada masalah-masalah hukum Islam (figh), di saat menjalankan ibadah haji. Salah seorang pemirsa menanyakan; apakah sebuah tindakan yang dilakukan jamaah haji dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan yang merusak ihram atau tidak. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, sang penceramah melakukan pembedaan, antara hal-hal yang merusak sarat-sarat ibadah haji, merusak kewajiban-kewajiban haji dan merusak ihram itu sendiri. Hal elementer seperti ini dengan akibat hukum-hukum agama (canon law) sendiri pula yang biasa dipelajari dari kitab-kitab agama di pesantren, terpaksa dijelaskan di layar televisi itu oleh sang penceramah. Ini tentu karena sang penanya diandaikan tidak tahu masalahnya, karena mereka hanya berkomunikasi melalui telepon. Sekaligus, pertanyaan itu menunjukkan perhatian sang pemirsa tersebut pada segi-segi ibadah, ketika menunaikan perjalanan ibadah haji. Mungkin itu juga disertai oleh pandangan tertentu mengenai perjalanan haji: peribadatan yang menyenangkan, menjengkelkan atau yang tidak berguna sama sekali. Sudah tentu sang jamaah haji memiliki wewenang bertanya tentang sesuatu hal yang oleh jamaah lain dianggap soal kecil. Bukankah ia telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk melakukan perjalanan tersebut, bahkan mungkin saja ia sampai menabung uang seumur hidup untuk itu. Karenanya, ia berhak bertanya apa saja , karena perjalanan tersebut merupakan sebuah obsesi dalam hidupnya. Hak ini adalah sesuatu yang sangat inherent dalam hidup sang penanya, dan sangat menyedihkan bahwa Departemen Agama Republik Indonesia (Depag-RI) yang menjadi penyelenggara ibadah haji tersebut tidak pemah mengumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam sebuah buku yang dapat dijadikan pegangan bagi para calon jamaah haji. Maka terpaksalah mereka bertanya melalui TV karena tidak ada saluran lain. Ketika memasuki lapangan terbang itu, penulis juga berjumpa dengan Jajang dan Debra Yatim, keduanya seorang aktivis perempuan yang, juga sama-sama akan menuju Yogyakarta, untuk menayangkan film tentang perjuangan kaum perempuan di negeri kita. Tentu saja pertunjukkan film tersebut akan disertai tanya jawab antara para pemirsa dan kedua aktifis terebut. Dan dapat diperkirakan , mereka akan berbeda mengenai tema makro yaitu tentang perjuangan menegakkan hak-hak wanita di negeri kita. Ini adalah hal yang wajar, bahkan kalau tidak dibicarakan, kita bertanya-tanya dalam hati, kedua orang aktifis itu untuk apa datang ke Yogyakarta? Kalau hanya untuk memutar film itu dapat dilakukan oleh para petugas setempat. Bahwa orang lain dapat saja menganggap pembicaraan mereka itu sesuatu yang bersifat setengah makro, karena membahas
kurang lebih separuh warga masyarakat, yaitu kaum perempuan, tentu saja merupakan hal yang wajar pula. Pembahasan baru dianggap makro, menurut pandangan ketiga dalam pembedaan pandangan masyarakat tentang negara, karena mereka berpendapat bahwa bahasan yang tidak menyangkut struktur masyarakat, belumlah dianggap sebagai pembahasan yang serius. Bahwa pembahasan mengenai nasib perempuan, termasuk apakah poligami (beristri banyak) selayaknya dilarang atau tidak, juga menyangkut posisi dan harkat tiga milyard jiwa lebih kaum perempuan di seluruh dunia saat ini, dalam pandangan ini tidak otomatis menjadikan masalah gender sebagai masalah makro. Memang ini adalah masalah yang sangat besar dan menyangkut jumlah manusia yang sangat besar pula. Tapi, ia tidak terkait dengan masalah struktur masyarakat. Karena itu pula ia tetap diperlakukan sebagai masalah mikro. Di tambah dengan ketidakpedulian mayoritas jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak memperhatikan masalah ini, dengan sendirinya masalah gender ini tidak berkembang menjadi masalah struktural. Memang para aktifis di berbagai bidang di lingkungan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari jenis hawa, selalu meneriakkan dengan lantang bahwa masalah perempuan/gender adalah masalah struktural, tetapi tetap saja masalah itu diperlakukan dalam dunia LSM intemasional dan domestik sebagai masalah non-struktural. Ini memang menyakitkan, tapi dalam kenyataan hal ini memang terjadi, dan kita tidak usah meratapinya. Perjuangan memang masih panjang, dan hal itu tidak perlu diperlakukan secara emosional. Paham ketiga tidak pemah mempersoalkan struktur masyarakat, dan menganggap semua struktur masyarakat yang ada dalam sejarah sebagai sesuatu yang benar. Masalah pokok yang dihadapi umat manusia, menurut pandangan ini, adalah bagaimana menegakkan keadilan dan kemakmuran yang, dalam ajaran agama Islam disebut dengan istilah kesejahteraan. Jadi, menurut pandangan ini, masalah utamanya adalah penegakkan hukum dan perumusan kebijakan serta pelaksanaan di bidang ekonomi, terlepas dari jenis dan watak struktur itu sendiri. Inilah pandangan yang sering disebut sebagai pandangan non-struktural, juga dikenal dengan pandangan developmentalist. Dalam pandangan ini, Islam atau agama-agama lain dapat berperan memerangi meterialisme dan sebagainya, tanpa terpengaruh oleh struktur masyarakat. Dengan demikian, masalah yang dihadapi terkait sepenuhnya dengan keahlian dan pengorganisasian sumber daya manusia yang dimiliki. Pandangan non-struktural ini, antara lain diikuti oleh para tehnokrat kita, yang selama ini menentukan kebijakan pembangunan yang kita ikuti sebagai bangsa. Dan, temyata para tehnokrat tersebut telah menemui kegagalan, karena keadilan dan kemakmuran temyata tidak kunjung tercapai, yang menikmati hanyalah sejumlah konglomerat belaka. Karenanya, pembahasan mengenai hubungan antara agama dan idiologi negara, sebaiknya dibatasi pada pandangan-pandangan agama yang ada mengenai struktur sosial yang adil bagi seluruh warga
masyarakat, dan menuju pada kemakmuran bangsa. Pendekatan struktural ini diperlukan, karena memang semua agama menghendaki masyarakat yang adil, menuju pencapaian kemakmuran. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafuur (negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun) adalah semboyan upaya kaum muslimin dalam menciptakan masyarakat yang demikian itu, sesuai dengan ajaran Islam sendiri. Karenanya, membahas hubungan antara Islam dengan negara, tanpa membahas struktur masyarakat yang hendak didirikan adalah sesuatu yang secara inherent menyangkut keadilan, dan dengan demikian merupakan struktur masyarakat yang benar. Dalam hubungan inilah, pembahasan kaitan antara Islam dan idiologi negara, sebaiknya benar-benar menjadi pusat perhatian kita.
Akademi Betawi Oleh:
Abdurrahman
Wahid
R. Soeprapto mulai dikenal sebagai gubemur yang memiliki visi unik diantara deretan gubemur dan walikota daerah ibukota kita ini. Visinya sangat sederhana: berpegang pada fungsi pemerintahan sebagai pemerintah daerah. Tidak seperti Ali Sadikin yang sering tidak ambil pusing dengan reaksi atau status pemerintah pusat Orang dapat bertanya, tidakkah berbahaya bersikap terlalu menganggap diri hanya berfungsi kedaerahan seperti itumengingat kekhususan Jakarta sebagai daerah ibukota negara dengan keragaman etnis, budaya, agama, dan politik? Negara yang agraris tapi maritime, yang tradisional tapi dinamis? Semua itu menghendaki peranan tersendiri bagi DKI Jakarta. Australia yang lebih homogen masih memberikan kekhususan penuh kepada ibukotanya, Canberra, yang didudukkan dalam sebuah daerah administrasi bergelar ACT, Australia Capital Territory. Yang jelas pendirian "mempersempit jangkauan DKI" itu tercermin juga dalam sikapnya mengenai pengelolaan kehidupan seni di lingkungan Taman Ismail Marzuki tempo hari. Dalam sebuah pertemuan dengan pimpinan harian Dewan Kesenian Jakarta, waktu itu Gubemur Soeprapto mengemukakan pentingnya dalam bidang itu. "Kami hanya menyediakan sarana dan presarana, tidak lebih dari itu." Itu berarti, pembinaan kegiatan seni pada tingkat nasional bukan tanggung jawab masing-masing. Ketoprak urusan Pemda Jawa Tengah dan DIY. Ludruk urusan Pemda Jawa Timur, begitu seterusnya. Atau pemerintah pusat. Pihak DKI hanya menyediakan sarana dan prasarana. Taman Ismail Marzuki boleh dipakai siapa saja, tetapi pembinaannya oleh pemerintah DKI terbatas. Dimensi nasional kegiatan seni di Taman Ismail Marzuki, mau tidak mau lalu harus dikaitkan dengan "pihak pendamping" lain di luar pemerintah daerah. Direktorat Jenderal Kebudayaan? Sudah tentu. Begitu juga pihak pariwisata dan lembagalembaga yang mampu menyerap kegiatan seni. Ini harus selalu diingat, kalau mengikuti jalan pikiran Gubemur. Apalagi oleh Dewan Kesenian Jakarta: harus jelas pembinaan dan pengelolaan kegiatan seni mana yang harus ditangani DKJ dalam kapasitas pengelola seni kebudayaan daerah, dan mana yang harus dimasukkan dalam kategori pengelolaan kesenian nasional. Dimensi local dan nasional itu membutuhkan penanganan berbedadan sudah tentu sponsor yang berlainan. Inilah kenyataan yang tidak dapat diabaikan DKJjuga lembaga-lembaga lain yang menangani kehidupan seni di lingkungan TIM, seperti Institut Kesenian Jakarta. Orientasi pendidikan seni lebih "mendaerah" tentu saja memerlukan pemikiran kembali semua jenis kegiatan yang dikerjakan selama ini. Apakah hanya lenong, topeng Betawi, dan sebangsanya yang boleh diajarkan? Kalau mengikuti pendirian Gubemur Soeprapto memang demikian, kalau menyangkut subsidi Pemerintah DKI. Lain-lainnya harus cari dari sumber lain.
Memang mungkin tidak sampai sedrastis itu, tetapi, bagaimanapun memerlukan pemikiran ulang. Pendirian yang demikian jelas landasannya itu dating dari seorang pejabat yang tadinya terbiasa mengelola daerah-daerah dari pusat, sebagai sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri. "Terbiasa" dalam arti selalu harus menerapkan wewenang pemerintah daerah hanya pada daerahnya, karena menyimpang dari itu dapat membuat ia menjadi pejabat yang pilih kasih. Seorang pengatur lalu lintas antar daerah akan selalu menumbuhkan sikap demikian. Bahwa sikap seperti itu lalu membawa perubahan mendasar dalam penetapan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam "penyediaan sarana dan prasarana" kegiatan seni di lingkungan TIM adalah soal lain lagi. Masalahnya adalah bagaimana halnya dengan Akademi Jakarta yang diisi "manusia-manusia bionik" yang sudah tidak kenal batas geografis, paham, dan lain-lain? Apakah mereka juga diharuskan hanya memikirkan kehidupan seni dan budaya di lingkungan DKI? Padahal, mereka sudah terbiasa dengan wawasan universal, dengan jarak jelajah yang tidak lagi antarbenua, melainkan antarplanet! Kalau mereka tidak diharuskan menciutkan bidang perhatian, lalu siapa yang harus memikirkan pengembangan kebudayaan asli Jakarta atau kehidupan seni dan budaya (macam-macam) dengan dimensi Jakarta? Akan diserahkan kepada lembaga lain? Kalau memang demikian, mengapa tidak dibentuk juga sebuah Akademi Betawi, diisi para dedengkot, seperti S.M. Ardan, Bokir, Anen dan Zahid? Karena, bagaimanapun sudah terasa keperluan itu. Mungkin namanya yang sulit diterima, gagasannya bisa mudah dicema.
Arafat, Israel, dan Palestina Oleh: Abdurrahman Wahid Akhimya, yang paling ditakuti terjadi juga. Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, mengumumkan keadaan bahaya bagi Israel, mengurung Yasser Arafat di Ramallah dan membiarkan penangkapan besar-besaran-terhadap apa yang disebutnya sebagai "para teroris Palestina". Dengan langkah itu, Sharon secara praktis menutup jalan bagi penyelesaian damai masalah Israel-Palestina. Hal itu telah dimulai dari larangan atas Arafat untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Beirut, dan disudahi dengan pengurungan atas dirinya oleh serdaduserdadu Israel di Ramallah. Karena situasi seperti itu, Gedung Putih di Washington DC terpaksa meminta agar Sharon tetap membuka jalan bagi tercapainya perdamaian permanen di kawasan itu. Benarkah pemyataan itu membuktikan Amerika Serikat tidak turut merencanakan tindakan Sharon tersebut, ataukah justru kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney ke kawasan itu justru untuk mempersiapkannya, sejarahlah yang akan menjawab. Seperti kebanyakan kejadian sejarah, baru belakangan dapat diketahui secara pasti sampai di mana peranan pemerintahan Bush dalam masalah ini: menipu dunia ataukah ditipu Israel? Tindakan Sharon itu juga tidak jelas bagi kita: benarkah ia secara logis berani menindak secara tegas semua orang Palestina militan yang disebutnya "kaum teroris?" Ataukah pada gilirannya, ia juga akan bersikap separuh hati, karena biaya ekonomis dan keuangannya akan menjadi sangat besar. Belum lagi kalau diingat biaya politik yang ditanggung Pemerintah Israel dengan kebijaksanaan "garis keras"-nya itu. Dengan kata lain, kekerasan Sharon dan kelemahan Arafat, yang tidak mau menghentikan kaum militan dan radikal Palestina selama ini, merupakan saham yang hampir bersamaan dalam menciptakan keadaan seperti sekarang ini. Memang, Sharon benar dalam satu hal: kelembutan yang terlalu jauh justru akan lebih memicu tindakan-tindakan radikal dan konfrontatif dari pihak Palestina. Akan tetapi sebaliknya, tindakan kekerasan saja seperti yang dilakukan Sharon, tidaklah menyelesaikan masalah. Sikap menghormati kedaulatan Israel sebagai negara merdeka dan berdaulat harus juga diimbangi dengan sikap yang sama terhadap Palestina. Inilah yang diperjuangkan sejak dahulu oleh negara-negara Arab, yang tidak bersikap konfrontatif terhadap Israel. KTT Arab di Beirut, justru membuktikan hal ini. Bahwa di kalangan negara-negara Arab ada sikap radikal, seperti ditunjukkan Suriah dan Irak, sama wajamya dengan sikap kaum kanan dalam Partai Likud, yang dipimpin oleh Ariel Sharon sendiri. *** JADI tidak realistiklah untuk mengharapkan dukungan penuh dari kedua belah pihak atas gagasan penyelesaian damai yang permanen dengan saling pengakuan antara Israel dan Palestina akan wujud lawan mereka sebagai negara berdaulat. Dengan ungkapan lain, penyelesaian damai yang permanen bagi kawasan itu, hanya dapat dicapai melalui sikap saling mempercayai antara pimpinan Israel dan
Palestina. Tanpa sikap saling mempercayai itu, kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai perdamaian permanen di kawasan itu, akan menjadi hampa belaka. Sekali lagi, tanpa sikap kepercayaan pimpinan kedua bangsa itu, maka krisis Timur Tengah dengan segala akibatnya, akan tetap ada dan-mau tidak mau kita sebagai bangsa bermayoritas Muslim juga akan terkena akibat-akibat tersebut. Pokok persoalannya, dengan demikian dapat disederhanakan: akan munculkah kepemimpinan baru yang saling mempercayai di kalangan kedua belah pihak? Akan adakah Anwar Sadar dan Menachen Begin yang baru; yang satu bekas opsir tentara Arab dan yang lain telah melakukan tindakan yang dapat dinamakan "tindakan teror" terhadap pemerintah jajahan Inggris itu, kalau digunakan istilah Sharon. Gerakan teroris Hagana yang diikuti Begin semenjak sebelum Perang Dunia Kedua, sama halnya dalam pengaturan, prinsip-prinsip yang digunakan dan tujuan yang dimiliki gerakan Intifadah yang dilaksanakan bangsa Palestina sekarang. Dengan demikian, persoalannya menjadi jelas bagi kita sekarang: akan digantikan siapakah Arafat dan Sharon? Hal ini akan membawakan pemyataan berikut; dengan cara apakah kepemimpinan kedua bangsa itu akan dibentuk? Di Israel pemilihan umum atau pembentukan pemerintahan baru melalui Knesset (parlemen) adalah jalan untuk itu. Di kalangan bangsa Palestina, masalahnya menjadi lebih ruwet. Cara Israel, yang didasarkan pada demokrasi model Barat tidak berlaku bagi orang-orang Palestina, karena di kalangan kebanyakan bangsabangsa Arab, demokrasi masih lebih merupakan impian dari pada suatu kenyataan. Karenanya, kedua cara yang digunakan untuk menggantikan kepemimpinan kedua belah pihak, adalah kunci permasalahan yang harus dicari pada saat ini. Kegagalan mendapatkannya hanya akan membuat keadaan lebih parah, yang akan menyeret kepentingan semua bangsa di dunia, karena pertimbangan-pertimbangan geopolitik. Karenanya, tindakan-tindakan luar biasa memang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina itu. Kegagalan mengganti kepemimpinan kedua bangsa itu, secara realistik akan membuat lebih sulit tercapainya dunia yang aman bagi semua pihak. Kalau keadaan itu dibiarkan, maka hanya ada satu jalan bagi kita: penggunaan kekerasan oleh negara adikuasa, dalam hal ini Amerika Serikat. Bukankah ini yang ditolak oleh pimpinan Republik Rakyat Cina (RRC) di zaman Mao Zedong, dengan prinsip non-hegemonik dalam percaturan intemasional? Bukankah membiarkan kekuasaan hegemonik manapun untuk melakukan tindakan unilateral dengan menggunakan kekerasan, adalah sebuah ekstremitas tersendiri? Karenanya, jika para pemimpin Arab dan mayoritas bangsa Palestina tidak segera mengganti kepemimpinan Arafat di kalangan mereka, berarti kita merelakan tindak kekerasan oleh Israel? Dan kalau di Israel tidak ada proses politik yang berujung pada penggantian Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri, berarti juga tidak ada kemampuan kaum pecinta damai untuk mencari perdamaian melalui berunding? Jelaslah dengan demikian. Kita semua berada pada titik sensitif untuk membiarkan
eskalasi kekerasan atau menyelesaikan sengketa dengan berunding, suatu hal yang dirasakan di seluruh dunia dan bukannya di kawasan Timur Tengah saja. Arti seorang Raja Tradisional Sri Susuhunan Pakubuwono XII telah meninggalkan kita dalam usia lanjut (80 tahun menurut hitungan almanak Jawa mendekati 81 tahun) sebabnya adalah ketuaan. Kekosongan itu tidak dapat kita rumuskan dengan baik karena beliau adalah seorang Raja (dalam bahasa Jawa juga disebut: Ratu) yang oleh sebagian orang beliau dianggap sebagai penguasa yang sesungguhnya. Karena kita tidak mampu merumuskan dengan baik, maka kita cukupkan dengan istilah Raja Tradisional. Gelar itu tidak hanya menunjukkan arti kultural/simbolik belaka, melainkan juga menunjuk kepada beberapa aspek kekuasaan formal di tingkat daerah, propinsi maupun pusat. Di sinilah terdapat kontradiksi antara wewenang penuh seorang Raja Tradisonal dan penguasa pemerintahan yang efektif. Penggantian beliau sangat, ditentukan oleh kenyataan bahwa beliau tidak meninggalkan Permaisuri (Garwo Padhmi), yang ada hanyalah istri selir (Garwo Ampil) dengan sekian orang putra-putri, tanpa seorang Putra Mahkota yang memperoleh penunjukkan untuk menggantikan beliau di atas tahta kerajaan, untuk menjalankan sisa-sisa kewenangan efektif yang masih ada. Karena sebab itu mungkin akan ada sedikit banyak pertentangan intemal antara beberapa orang putra beliau yang bergelar Gusti. Namun tentu saja pertentangan intemal itu tidak akan dilakukan dengan kasar, karena hal itu bukanlah budaya kraton. Justru Kraton tradsional akan menampakkan wajah keutuhan keluar, walaupun pertentangan intemal itu berjalan sangat sengit. Semenjak beberapa tahun terakhir ini disiplin pribadi yang sangat kuat, membatasi ruang gerak para putra beliau, dengan semakin lanjutnya usia beliau. Di tutupi oleh kesopanan yang sangat tinggi dan tata pergaulan yang dipersatukan oleh Sang Raja, tidak pemah pertentangan itu (kalaupun ada) terdengar di luar Kraton. Ini tentu saja sangat berbeda dari pertentangan intemal dalam partai-partai politik, yang memang kalau perlu diperagakan di muka umum, terutama dengan menggunakan media massa. Kenyataan seperti inilah yang sering membuat orang tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, lalu menciptakan kebingungan tersendiri. Dalam kerangka ini kita harus melihat apa yang terjadi pada lingkungan Kraton Tradisional yang masih ada dan berfungsi di negeri kita. Ada fungsi ekonomis, karena beberapa buah kraton masih memiliki tanah-tanah dan bangunanbangunan yang terletak di beberapa tempat dalam lingkungannya. Demikian juga, ada fungsi politis yang tersisa dari masa lampau seperti di daerah DI Yogyakarta. Karena kemampuanya , Sri Sultan Hamengkubuwono IX dapat melestarikan wewenang efektif bagi para pengganti beliau, untuk juga menjadi Kepala Daerah di wilayah tersebut, yang saat ini bergelar Gubemur dan saat ini dijabat oleh putra beliau Sri Sultan Hamengkubuwono X. Raja Tradisional merangkap Gubemur inilah yang menarik untuk diperhatikan. Persolaan utama yang dihadapi oleh para Raja Tradisonal, di luar hubungan
dengan pejabat negara yang memiliki wewenang efektif, adalah masalah keuangan dan masalah tugas-tugas apa yang dapat diberikan kepada warga Kraton yang semakin lama berjumlah semakin besar. Dalam hal ini, kekuatan moral saja tidak cukup untuk memperkokoh kedudukan beliau itu. Juga diperlukan kekuatan ekonomi dan finansial, yang umumnya jarang digerakkan oleh para pengusaha di kawasan para raja itu. Para pengusaha itu hanya menyumbangkan sebagaian kecil saja dari keuntungan yang diperoleh dari usaha-usaha yang dilakukan, karena sebagian besar diambil oleh para pejabat yang memiliki wewenang efektif yang bersandar kepada wewenang melalui KKN, karena pendapatan resmi mereka sangat kecil. Akhimya para Raja Tradisional itupun harus juga mengalami apa yang oleh Clifford Geertz dinamai kemiskinan bersama (shared poverty). Karena itulah, jumlah negara-negara tradisional yang mampu menghidupi kratonkraton mereka, semakin lama berjumlah semakin kecil. Bahkan ada seorang Raja Tradisional di sebuah daerah yang tidak lagi mampu membayar langganan listrik pada PLN bagi Istana yang beliau tinggali. Ketika salah seorang beliau itu ada yang membiayai bepergian ke tanah suci untuk melakukan ibadah haji, beliau pun bertemu dengan penulis. Karena sebab itu, dengan sendirinya kekuatan moral beliau menjadi sangat kecil, bahkan tampaknya beliau tidak mampu membiayai pendidikan putra-putri yang ada. Tentu saja kenyataan ini terkait sangat erat dengan situasi keuangan beliau-beliau itu. Semakin kecil kemampuan itu, semakin kecil pula kekuatan moral beliau-beliau itu. Karena itu, kemampuan finansial/keuangan yang tidak sama antara beliau-beliau, membuat kekuatan moral yang dimiliki juga berbeda-beda. Ini juga, lalu membuat para pejabat dengan kekuasaan efektif memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada para beliau itu. Apalagi, kalau di sebuah kawasan terdapat lebih dari seorang Raja Tradisional, seperti di kota madya dan Kabupaten Cirebon dengan empat buah Kratonnya. Karena itu lah, hanya diberikan pelayanan minimal kepada dua orang Raja Tradisonal saja di sana, yaitu kepada Kraton Kesepuhan dan Kraton Kanoman. Perlakuan itu juga tidak sama, sesuai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Karenanya, kunci pokok bagi pelayanan nyata kepada kraton-kraton tersebut, sangat tergantung kepada kekayaan daerah yang bersangkutan. Jelaslah dari uraian di atas, bahwa faktor utama bagi perbaikan layanan kepada para beliau, yang sering dianggap sebagai kekuatan moral yang mempunyai fungsi kultural, sangat bergantung kepada kemampuan keuangan pemerintah daerah setempat. Seperti apa yang terjadi pada Kraton Kutai di Kalimantan Timur, yang sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah daerah Tenggarong Kertanegara, yang kaya raya dengan sumber-sumber alamnya. Dalam hal ini, otonomi daerah (Otda) memegang peranan sangat penting dalam menghidupkan kembali tradisi dari Kraton Tradisional yang ada di sebuah daerah. Namun hal ini tidak dapat di generalisisr (disamaratakan) kraton-kraton tradisional di Maluku Utara. Tinggal tiga buah saja yang masih didukung oleh keadaan dan pengaruh pemerintah daerah propinsi, yaitu di Temate, Tidore dan Bacan. Faktor terakhir yang tidak dapat dianggap ringan dalam mendukung kekuatan
moral kraton-kraton tradisional itu adalah faktor keamanan setempat. Apa yang terjadi di Kraton Langkat pada saat revolusi kemerdekaan di paruh kedua tahun 40-an, dengan terbunuhnya hampir seluruh keluarga raja setempat, termasuk penyair Amir Hamzah, sekarang terulang dalam porsi dan versi lain di tempattempat yang berbeda. Dengan sendirinya, posisi peran kekuatan moral para beliau itu juga berbeda dari satu ke lain tempat. Seperti terjadi pada Kraton Pakubuanan dan Kraton Kadipaten Mangkunegaran dalam kaitannya dengan eksistensi Pesantren Al-Mukmin di Ngruki di Solo. Tentu saja kita berkeinginan agar kedua Kraton tradisional itu dapat turut berperan mengembangkan kemampuan masyarakat dan pemerintah di daerah di Solo, untuk menangani dengan baik kecenderungan militan dari pesantren tersebut. Hal ini mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan, bukan?
Bagaimana Membaca NU? Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Sejak kemerdekaan kita, perdebatan masalah-masalah kemasyarakatan kita senantiasa di dominasi oleh pertukar-pikiran antara kaum elitis melawan kaum populis. Memang ada suara-suara tentang Islam, seperti yang dikembangkan oleh Bung Kamo dan lain-lain, tetapi itu semua hanyalah meramaikan situasi yang tidak menjadi isu utama. Masalah pokok yang dihadapi adalah bagaimana selanjutnya Indonesia harus dibangun yang, dalam bahasa agung disebut mengisi kemerdekaan. Kalangan elitis, selalu menggunakan rasio/akal dan argumentasi mereka senantiasa bemada monopoli kebenaran. Mereka merasa sebagai yang paling tahu, rakyat hanyalah orang kebanyakan yang tidak mengerti persoalan sebenamya. Kalau rakyat mengikuti pendapat kaum elitis ini, tentu mereka akan pandai pada waktunya kelak. Sebaliknya, kaum populis senantiasa mengulangi semangat kebangsaan yang dibawakan para pemimpin, seperti Bung Kamo, selalu mempertentangkan pendekatan empirik dengan perjuangan ideologis. Tentu saja, cara berdialog semacam ini tidak memperhitungkan bagaimana kaum Muslim tradisionalis seperti warga NU (Nahdlatul Ulama)-, menyusun pendapat dan pandangan dan mendasarkan hal itu pada asumsi yang tidak dimengerti, baik yang oleh golongan elitis maupun oleh golongan populis. Demikianlah, dengan alasan-alasaan keagamaan yang mereka susun sendiri, kaum Muslimin yang hadir dalam Muktamar NU di Banjarmasin (Bomeo Selatan) tahun1935 memutuskan kawasan ini tidak memerlukan Negara Islam. Keputusan Muktamar NU ini menjadi dasar, mengapa kemudian para pemimpin berbagai gerakan di negeri ini kemudian mengeluarkan Piagam Jakarta dari Undang-Undang Dasar (UUD) kita. Jadilah negeri kita sebuah Negara Pancasila dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang tetap lestari hingga hari ini. Dan, kelihatannya tidak akan berubah seterusnya. Pada tanggal 22 Oktober 1945, PBNU (hoofdbestuur NU), yang waktu itu berkedudukan di Surabaya mengeluarkan Resolusi Jihad, berisikan untuk mempertahankan dan memperjuangkan Republik Indonesia (RI) adalah kewajiban agama atau disebut sebagai jihad, walaupun NKRI bukanlah sebuah Negara Islam atau lebih tepatnya sebuah Negara agama. Di sini tampak, bahwa kaum muslimin trasidional dalam dua hal ini mengembangkan jalan pikiran sendiri, yang tidak turut serta dalam perdebatan antara kaum elitis dan populis. Namun, mereka tidak menguasai media khalayak (massa) dalam perdebatan di kalangan ilmuwan. Karena itulah, mereka dianggap tidak menyumbangkan sesuatu kepada debat publik tentang dasar-dasar negara kita. ***** Dalam sebuah harian (Kompas, Senin 8/9/2003) , seorang sejarawan membantah tulisan penulis yang mengatakan Sekarmadji M. Kartosoewirjo adalah asisten/staf ahli Jenderal Besar Soedirman di bidang militer. Dengan keahliannya sebagai politisi bukankah lebih tepat kalau ia menjadi staf ahli beliau di bidang sosialpolitik? Pengamat tersebut lupa bahwa asisten/staf ahli beliau saat itu dijabat oleh
ayahanda penulis sendiri, KH. A. Wahid Hasjim, dan Kartosoewirjo sendiri memang berpangkat tentara/militer sebagai akibat dari integrasi Hizbullah ke dalam APRI (Angkatan Perang Republik Indonesia). Jenderal Besar Soedirman sendiri juga tidak pemah menjabat pangkat militer apapun sebelum bala tentara Jepang datang kemari dan menduduki kawasan yang kemudian disebut sebagai NKRI. Dari penjelasan di atas menjadi nyata bagi kita, bahwa layak-layak saja S.M. Kartosoewirjo menjadi asisten/staf ahli Panglima APRI di bidang militer. Bahwa ia kemudian mempergunakan DI/TII sebagai alat pemberontakan, adalah sesuatu yang lain sama sekali. Dan sang sejarawan lupa bahwa penulusuran sejarah tidak hanya harus didapat dalam sumber-sumber tertulis, tapi juga sumber-sumber lisan. Dari kasus NII dapat kita lihat, bahwa di masa lampau -pejabat-pejabat negarajuga ada yang membaca secara salah hal-hal yang ada di luar diri mereka dengan cara berpikir yang lain dari ketentuan dan kesepakatan berdirinya negara kita. Ini disebabkan oleh adanya perbedaan cara memandang persoalan, apalagi yang berkenaan dengan ambisi politik pribadi atau karena pertimbangan-pertimbangan lain. Dalam hal ini, yang paling mencolok adalah jalan pikiran NU yang tidak memandang perlu adanya Negara Islam. Kalau ditinjau dari adanya peristiwa itu sendiri, jelas bahwa perbedaan pemahaman itu timbul dari cara berpikir keagamaan yang kita lakukan. Bagi NU, hukum agama timbul dari sumber-sumber tertulis otentik (adillah naqliyyah) yang diproyeksikan terhadap kebutuhan aktual masyarakat. Sedangkan gerakan-gerakan Islam lainnya langsung mengambil hukum tertulis itu dalam bentuk awal, yaitu berpegang secara letterlijk (harfiyah) dan tentu saja tidak akan sama hasilnya. Bahkan,diantara para ulama NU sendiri sering terjadi perbedaan paham, karena anutan dalil masing-masing saling berbeda. Sebagai contoh dapat digambarkan bahwa hampir seluruh ulama NU menggunakan ruyah (penglihatan bulan) untuk menetapkan permulaan hari Idul Fitri. Tetapi, alm. KH. Thuraikhan dari Kudus justru menggunakan hisab (perhitungan sesuai almanak) untuk hal yang sama. Sedangkan diantara para ahli ruyah sendiri, terdapat perbedaan paham. Seperti antara alm. KH.M Hasjim Asjari Rais Akbar NU dengan KH. M. Bisri Sjansuri, -wakil Khatib Aam/wakil sekretaris Syuriyah PBNU-, yang bersama-sama melakukan ruyah di Bukit Tunggorono, Jombang namun temyata yang satu melihat dan yang lain tidak. Hasilnya, yang seorang menyatakan hari raya Idul Fitri keesokan harinya, sedangkan yang lain menyatakan hari berikutnya. Jadi, walaupun sama-sama mengikuti jalan pikiran ushul-fiqh (teori hukum Islam), namun dapat mencapai hasil yang saling berbeda. Karena Perbedaan pendapat memang diperkenankan dalam pandangan fiqh, yang tidak diperkenankan adalah terpecah-belah. Ayat al-quran jelas dalam hal ini; Berpeganglah kalian pada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan terpecah-belah (Watashimu bi Habli Allahi Jamian wa la Tafarraqu). **** Nah, dalam soal-soal bertarap kebangsaan dan kenegaraan, -seperti penetapan orientasi bangsa,- jelas bahwa kita harus menerima perbedaan pandangan, karena
semuanya di dasarkan oleh argumentasi masing-masing. Karena itu ketika ada pendirian berbeda antara pihak seperti NU dengan kaum muslimin lainnya, maka kata akhimya bukanlah dari pihak yang mengemudikan negara (pemerintah), melainkan hasil pemilihan umum yang menjadi acuan. Kalau ini tidak dipahami dengan baik, tentu akan ada usulan-usulan yang ditolak atau ditunda oleh partaipartai, para aktifis, para wakil organisasi Islam di satu pihak dengan elemen bangsa lain yang tidak secara resmi mendukung atau menolak gagasan kenegaraan yang diajukan. Inilah yang senantiasa harus kita ingat setiap kali membahas kesempitan pandangan dari beberapa agama yang besar, seperti serunya perbedaan antara pihak yang mengharuskan dengan pihak yang tidak pemah melihat pentingnya keterwakilan rakyat. Karena Partai Kebangkitan Bangsa yang memiliki ikatan historis dengan NUbukanlah sebuah partai Islam, maka tidak perlu terlalu mementingkan ajaran formal Islam dalam setiap penagambilan keputusan. Cukuplah kalau lembaga yang menetapkan Undang-Undang (UU) itu bergerak mengikuti prosedur kelembagaan yang ditopang oleh UU, pakar hukum agama dan segenap pemikiran masyarakat. Pendapat para pakar hukum agama ini menjadi pertimbangan pembuatan hukum bukan pelaksanaannya. Di sinilah diperlukan kearifan dunia hukum nasional kita, untuk juga memperhitungkan pendapat yang dilontarkan masyarakat dan berasal dari para pakar hukum agama. Dengan demikian, kita sampai kepada hal-hal yang berkenaan dengan pandangan kaum Muslimin Sunni tradisional dalam kehidupan bangsa kita. Dalam hal-hal yang sifatnya fundamental bagi kehidupan agama di negeri kita, jelas hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama tidak dapat ditolerir, umpamanya saja, mengenai keyakinan akan ke-Esaan Tuhan (tauhid). Hal-hal semacam ini tidak dapat dibiarkan dan harus diperjuangkan sehabis daya oleh kaum Muslimin sendiri. Sebaliknya, hal-hal yang tidak bersifat fundamental bagi keyakinan agama seseorang, tentu saja masih diperlukan telaahan lebih jauh dan dapat ditolerir perubahan-perubahannya. Bukankah al-quran sendiri yang justru menyatakan dan Ku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal . Dari hal ini dapat diharapkan, di masa depan produk-produk hukum kita akan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pengetahuan kita.
Yang Terbaik Ada Di Tengah Oleh :
KH.Abdurrahman
Wahid
Judul diatas diilhami oleh sabda Nabi Muhammad SAW: Sebaik-baik persoalan adalah yang berada ditengah (Khairu Al-Umur Ausathuha). Ia juga mencerminkan Pandangan agama Budha tentang jalan tengah yang dicari dan diwujudkan oleh penganut agama tersebut. Walaupun demikian, judul itu dimaksudkan untuk mengupas sebuah buku karya, tokoh Syiah terkemuka Dr. Musa Al Asyari, Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Darul Ulum Jombang, beberapa waktu lalu, katakanlah sebagai sebuah resensi, yang juga menunjukan kecenderungan umum mengambil jalan tengah yang dimiliki bangsa kita, dan mempengaruhi kehidupan di negeri ini. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sikap mencari jalan tengah ini, akhimya berujung pada sikap mencari jalan sendiri di tengah-tengah tawaran penyelesaian berbagai persoalan yang masuk ke kawasan ini. Namun, sebelum menyimpulkan hal itu, terlebih dahulu penulis ingin melihat buku itu dari kacamata sejarah yang menjadi jalan hidup banyak peradaban dunia. Kalau kita tidak pahami masalah tersebut dari sudut ini, kita akan mudah menggangap jalan tengah sebagai sesuatu yang khas dari bangsa kita, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Bahwa bangsa kita cenderung untuk mencari sesuatu yang independen dari bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mr. Muhammad Yamin, umpamanya menggangap kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat dan menguasai kawasan antara pulau Madagaskar di lautan Hindia/Samudra Indonesia di Barat dan pulau Tahiti di tengah-tengah lautan Pasifik, dengan benderanya yang terkenal Merah Putih. Padahal, angkatan laut kerajaan tersebut hanyalah fatsal (pengikut) belaka dari Angkatan Laut Tiongkok yang menguasai kawasan perairan tersebut selama berabad-abad. Kita tentu tidak senang dengan klaim tersebut karena mengartikan kita lemah, tetapi kenyataan sejarah berbunyi lain, Australia yang menjadi dominion Inggris, secara hukum dan tata negara, memiliki indenpendensi sendiri terlepas dari negara induk. ***** Penulis melihat, bahwa sejarah dunia penuh dengan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Umpamanya saja, seperti di tunjukan oleh Oswald Spengler dalam Die Untergang des Abendlandes"(The Decline Of The West). Buku yang menggambarkan kejayaan peradaban Barat dalam abad ke 20 ini temyata mulai mengalami keruntuhan (Untergang) . Filosof Spanyol Kenamaan, Ortega Y Gasset, justru menunjuk kepada tantangan dari massa rakyat kebanyakan dalam peradaban moderen terhadap karya-karya dan produk kaum elit, seperti tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal Rebellion of the Masses (Pemberontakan Rakyat Kebanyakan). Kemudian itu semua, disederhanakan oleh Amold Jacob Toynbee dalam karya
momentumnya yang terdiri dari 2 jilid, A Study of History. Toynbee mengemukakan sebuah mekanisme sejarah dalam peradaban manusia, yaitu tantangan (challenges) dan jawaban (responses). Kalau tantangan terlalu berat, seperti tantangan alam di kawasan Kutub Utara, seperti yang dialami bangsa Eskimo, maka manusia tidak dapat memberikan jawaban memadai, jadi hanya mampu bertahan hidup saja. Sebaliknya, kalau tantangan harus dapat diatasi dengan kreatifitas, seperti tantangan banjir sungai yang merusak untuk beberapa bulan dan kemudian membawa kemakmuran melalui kesuburan tanah untuk masa selanjutnya, akan melahirkan peradaban tepi sungai yang sangat besar, seperti di tepian Nil, Tigris, Eupharat, Gangga, Huang Ho, Yang Tse Kiang, Musi dan Brantas. Lahimya Pusat-pusat peradaban dunia ditepian sungai-sungai itu, merupakan bukti kesejahteraan yang tidak terbantah. Jan Romein, seorang sejarawan Belanda, menulis bukunya Aera Eropa ia menggambarkan adanya PKU I (Pola Kemanusiaan Umum pertama, Eerste Algemeene menselijk Patron). PKU I itu, menurut karya Romein tersebut memperlihatkan diri dalam tradisionalisme yang dianut oleh peradaban dunia dan kerajaan-kerajaan besar waktu itu, berupa masyarakat agraris, birokrasi kuat dibawah kekuasaan raja yang moralitas yang sama di mana-mana. Dalam abad ke6 sebelum masehi, terjadi krisis moral besar-besaran yang ditandai dengan munculnya nama-nama Lao Tze dan Konghucu, Budha Gautama, Zarathustra di Persia dan Akhnaton di Mesir. Mereka para moralis hebat ini mengembalikan dunia kepada tradisionalismenya, karena memperkuat keseimbangan. Sebaliknya, para filsuf Yunani Kuno, membuat penimpangan pertama terhadap PKU kesatu itu, dengan mengemukakan rasionalitas sebagai ukuran perbuatan manusia yang terbaik. Penyimpangan-penyimpangan PKU I ini di ikuti oleh penyimpanganpenyimpangan lain oleh Eropa seperti kedaulatan hukum Romawi (Lex Romanum) pengorganisasian kinerja, Renaissance (Abad kebangkitan), Abad pencerahan (Aufklarung), Abad Industri dan Abad Ideologi. Dengan adanya penyimpangan itu, Eropa memaksa dunia untuk menemukan PKU II (Tweede Algemeene menselijk Patron), yang belum kita kenal bentuk finalnya. **** Nah, kita menolak Theokrasi (negara agama) dan Sekularisme, dengan mengajukan altematif ketiga berupa Pancasila. Kompromi politik yang dikembangkan kemudian (dan sampai sekarang belum juga berhasil) sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi Agama maupun kekuasaan Anti Agama dalam kehidupan bemegara kita. Karena sekularisme di pandang sebagai penolakan kepada agama -dan bukannya sebagai pemisahan agama dari negara-, maka kita merasakan perlunya mempercayai Pancasila yang menggabungkan Sila pertama (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak penulis dianggap sebagai penolakan atas agama. Buku yang ditinjau penulis ini, sebenamya adalah upaya dari jenis yang berupaya menyatukan kebenaran Agama dan illmu pengetahuan sekuler (dirumuskan sebagai kemerdekaan berpikir oleh pengarangnya). Jelas yang dimaksudkan
adalah sebuah sintensa baru yang terbaik bagi kita dari dua hal yang saling bertentangan. Apakah ini merupakan sesuatu yang berharga, ataukah hanya berujung kepada sebuah masyarakat (dan negara) yang bukan-bukan. Sederhana saja masalahnya, bukan?
Yang Umum dan Yang Khusus Oleh Abdurrahman
Wahid
Sebagaimana umumnya dosen angkatan lama, Pak Hasan lemah lembut dalam segala hal. Ketika berbicara suaranya tidak begitu keras, nadanya datar. Kalau mengemukakan sesuatu tidak begitu menggebu-gebu, melainkan teratur dan sistematis. Istilah yang digunakan sudah baku; dan dipahami sama oleh para pendengamya, karena jelas yang dimaksud. Tidak banyak memerlukan ilustrasi deskriptif, apalagi yang bersifat gambaran fisik. Prinsip-prinsip dan kategorikategori lebih penting dari deskripsinya sendiri. la terlibat dalam kegiatan 'turun ke bawah' yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tempat ia bekerja sudah tentu dalam kerjasama dengan lembagalembaga lain. Pekerjaannya memperkenalkan teknologi yang sederhana dan lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari rakyat pedesaan, seperti juga banyak 'aktivis pedesaan' yang berkiprah ke bawah. Namun temyata ia melakukan sesuatu yang besar sekali artinya bagi kita semua,tidak seperti yang dilakukan teman-teman sesama aktivis. Yang dilakukannya adalah menyiapkan lahan kemasyarakatan' bagi teknologi yang ditawarkannyaberupa penumbuhan kesadaran dan kebutuhan akan teknologi tersebut. la berarti menciptakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang akan mengembangkan teknologi yang bersangkutan. "Kami mencoba memperkenalkan bio-mass sebagai bahan bakar pengganti kayu, untuk keperluan dapur. Temyata tidak mudah. Karena ibu rumah tangga yang menjadi sasaran kami bukan hanya seorang individu. Ia juga anggota keluarga, dan setelah itu warga masyarakat. Untuk membuat ia menerima bio-mass, keluarga dan masyarakat harus dibuat menerimanya. Dan itu berarti kami harus mendorong munculnya sarana tempat memutuskan sikap, menerima atau menolak gagasan yang ditawarkan. Juga mengelola penggunaan teknologi yang dijajakan itu." Bekerja sama dengan para pamong desa setempat, melalui izin pemerintah daerah, Pak Hasan dan kawan-kawan berhasil merintis sejumlah proyek penumbuhan kebutuhan dan keinginan tersebut. Sebuah 'proyek penawaran teknologi' yang dimulai di sebuah desa, dengan segera berhasil melipatgandakan diri, menjadi kegiatan yang mencakup dua puluh desa lain dalam waktu cepat. Kiai Madun lain lagi. la 'menawarkan' pesantren asuhannya kepada masyarakat, dengan melakukan sesuatu yang fundamental bagi pesantrennya: menjadikan lembaga pendidikan yang dikelolanya 'pusat pengembangan masyarakat'. Para santri asuhannya berlatih cara-cara mendorong masyarakat, melalui kegiatan ekonomi secara pra-kooperatif (dengan merk'Usaha Bersama') dan kemudian kooperatif. Juga membawa teknologi baru yang sederhana. Memperkenalkan kesadaran bergizi dan KB. Sibuk dengan urusan pelestarian lingkungan.Walhasil menampilkan pesantren sebagai salah satu 'pangkalan' mengubah wajah hidup masyarakat secara total. Menawarkan agama sebagai 'mendorong motivasi
keagamaan
bagi
pembangunan'.
Ada pos obat di lingkungan pesantrennya, ada karang kitri dan apotek hidup untuk masyarakat. Ada latihan keterampilan 'yang sudah disempumakan'. Berbagai kegiatan teknis untuk memperbaiki pola kerja dimulai, baik dibidang pertanian atau kerajinan tangan maupun kesehatan masyarakat. Sementara itu Isha adalah seorang intelektual kelas berat.Jidatnya lebar, menerbitkan kesan banyak berfikir. Kalau berbicara senang istilah asing, biar dikira orang pandai. Banyak teori dilontarkannya. Namun iajauh lebih baik dari sejumlah intelektual lain, yang senang hanya dengan retorika melambung dan pikiran ideal, tanpa mampu menerjemahkannya ke dalam kegiatan operasional yang berangkai. Yang menarik adalah komentamya tentang apa yang dilakukan Pak Hasan dan Kiai Madun tadi. Pak Hasan katanya memakai pendekatan 'tawaran' umum dalam pembangunan di pedesaan. Jalumya adalah kebutuhan umum masyarakat sendiri. Kebutuban itu disentuh, melalui kelembagaan biasa seperti arisan, paguyuban RT/RK dan sebagainya. Sebaliknya Kiai Masdun. la mengajak kepada hal sama melalui keunikan, kekhususan pesantren. Pada pendekatan umum itu ada kelebihan penting.Yakni mudahnya replikasi atau penggandaan. Sekali gagasan dasamya diterima baik, seterusnya jalan sudah licin, kata intelektual kota yang spesialisasi urusan pedesaan itu. Namun sering terjadi, justru penerimaan gagasan dasar itu sangat lama berlangsung. Sebaliknya pendekatan khusus untuk menawarkan pembangunan melalui paham, ideologi, agama atau lembaga tertentu yang memiliki keunikan, sangat cepat diterima. Yaitu kalau pimpinannya sudah 'tersentuh'. Tokoh seperti Isha ini temyata mampu memaparkan jalinan dua pendekatan yang komplementer dan sama pentingnya, dengan kelebihan dan kekurangan masingmasing. Banyakkah di antara kita yang memahami keadaan secara terpadu seperti si Isha?
Bagaimana Mengelola Garuda? Oleh:
Abdurrahman
Wahid*
Jika paparan dalam buku Peter L. Berger, The Heretical Imperative diadopsi ke dalam konteks Indonesia, dapat diceritakan tentang seorang petani jawa ditengah sawahnya, berhenti mencangkul karena ia melihat ke atas kepada sebuah benda logam berkilat terkena cahaya matahari, dengan suara mesin menderu-deru di angkasa. Petani itu memandang dengan takjub kepada benda logam itu, yang dari bawah tidak terbaca tulisan disamping badannya: tulisan Garuda Indonesia Airways. Namun petani itu tahu hal tersebut bahwa benda tersebut adalah pesawat terbang nan jauh disana, karena tiap kali menerbangi kawasan tersebut. Ia juga tahu bahwa ada burung besar bemama Garuda, yang menurut cerita adalah burung yang dikendarai Batara Wisnu, Tuhan kebaikan dalam mithologi pra Islam yang sampai saat ini masih berkembang di beberapa tempat. Heretical Imperative bermakna keharusan munafik artinya harus memilih antara dua hal yang tidak dapat dicerai. Kalau kita berpegang pada mithologi lama yang tidak menggunakan rasio, maka berarti kita menafikan rasio itu sendiri dan percaya pada hal-hal supranatural. Dengan demikian kita berpegang kepada mithologi Garudanya Dewa Wisnu dan tidak mementingkan lagi perusahaan penerbangan nasional dengan nama yang sama itu. Padahal Garuda Indonesia Airways (GIA) adalah lambang alih teknologi, dan jika kita mampu mengelola perusahaan penerbangan nasional itu maka akan dapat mengejar ketertinggalan kita. Karena belum tentu kita menguasai industri pembuatan pesawat-pesawat terbangnya, karena sudah terlanjur dimonopoli bangsa-bangsa maju dunia, kita hanya mampu menguasai perusahaan penerbangannya dan bukan teknologi pembuatan pesawat terbang itu sendiri. Pengelolaan perusahaan penerbangan nasional itu harus pula dipecah antara pengusahaan penerbangan dalam negeri, dan pengelolaan penerbangan luar negeri. Bedanya yang terbesar adalah pada jenis pesawat terbang yang digunakan, dan dengan demikian pengelolanya sendiri, nyata-nyata sangat berbeda satu dari yang lain. Jika pengelolaan penerbangan Intemasional/luar negeri menggunakan pesawat-pesawat berbadan lebar (wide body jet) seperti B-747 (dan sekarang juga B-777) dan A-300, yang berharga sangat mahal tiap unitnya, maka penerbangan dalam negeri cukup menggunakan pesawat-pesawat berbadan sempit seperti B737 dan A-319 saja. Tentu banyak sekali variasi pesawat terbang jet berbadan sempit yang digunakan, tetapi dominasi kedua pesawat diatas tampaknya sulit lagi ditembus oleh lain-lainnya. ***** Kita hampir tujuh tahun berada dalam krisis ekonomi (dan sudah barang tentu
krisis finansial) sejak 1997. sekarang pun, ketika tulisan ini dibuat kita belum lagi mampu mengatasi krisis multi-dimensional itu. Seolah-olah, krisis yang kita hadapi sama panjang dan krisis di Mesir yang dihadapi Nabi Yusuf, yaitu 7 tahun. Namun mudah-mudahan krisis itu tidak memerlukan waktu selama itu untuk menyelesaikannya. Sudah wajar jika dalam krisis itu lalu perusahaan penerbangan Garuda juga mengalami kemunduran karena terpaksa membatalkan rute eksploitasinya, baik domestik maupun Intemasional. Sampai hari inipun Route penerbangan dari/ ke luar negeri itu masih banyak yang yang ditutup. Apalagi harus dihilangkannya sekian banyak rute penerbangan keluar negeri. Yang tinggal hanyalah sangat kecil jumlah penerbangan, umpamanya saja dari/ ke Amsterdam (Schipol). Akibat dari hal ini maka terlepas sejumlah pesawat terbang dari tangan Garuda. Karena umumnya masih hutang, maka pesawat-pesawat tersebut dilepas, baik dikembalikan kepada pemilik sebelumnya ataupun dijual. Sebab di lepasnya sejumlah pesawat, karena Garuda menggunakan pesawat milik luar negeri, atau memang dimiliki Garuda tetapi dalam bentuk pinjaman uang/kontrak. Karena proses itu, maka Garuda terpaksa mendasarkan diri kepada pesawat-pesawatnya sendiri dan rute penerbangan yang masih diteruskan hanyalah yang menggunakan pesawat-pesawat yang sudah lama dimiliki Garuda. Karena lamanya ia digunakan tanpa diperbaharui interiomya, tentu saja ia terasa sangat kuno. Bukan itu saja, bahkan bencel-bencel (terkelupas) pada tangantangan kursinya sampai hari ini masih dibiarkan, mungkin karena tidak ada dana untuk memperbaikinya. Semua dana yang ada dihabiskan untuk biaya pengelolaan dan manajemen penerbangan, dan hampir-hampir tidak ada tersedia dana untuk perbaikan pesawat. Kalau kita mengerti hal ini, tentu kita membenarkan sikap yang diambil untuk menunggu kucuran dana dari pemerintah kepada Garuda. Salah urus di masa lampau, termasuk pemberian uang dalam jumlah sangat besar pada akhir tiap periode keuangan kepada pihak-pihak diluar kebutuhan perusahaan tersebut (katakanlah), sebagai iuran wajib kepada pihak-pihak tertentu yang dekat dengan penguasa, akhimya membuat Garuda berantakan sebagai sebuah badan usaha. Karena itu, GIA tidak dapat membeli pesawat-pesawat baru dan justru mengurangi penerbangan-penerbangan yang dimilikinya sebelum krisis multidimensi yang kita alami sekitar 7 tahun yang lalu. ***** Dalam mengahadapi tantangan demi tantangan di masa krisis itu, terjadi sebuah orientasi baru dalam usaha penerbangan milik pemerintah itu. Garuda lalu mengalihkan titik perhatiannya kepada penerbangan dalam negeri. Masih harus dikaji apa saja yang menjadi pendorong bagi munculnya orientasi baru itu, tetapi kemungkinan besar karena lebih mudah/murah mencari pesawat-pesawat terbang baru bagi rute penerbangan dalam negeri dari pada biaya perbaikan pesawat-pesawat terbang untuk rute perjalanan luar negeri. Bahkan, perjalanan ke Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura (yang notabene berada ke Luar Negeri), juga menggunakan pesawat-pesawat terbang lebih kecil daripada sebelumnya.
Demikianlah, secara salah Garuda terpaksa menerapkan prinsip yang dikemukakan EF Schumacher, small is beautiful (kecil itu indah). Nah, dalam hal ini penulis berpendapat Garuda harus memperoleh kucuran dana dari pemerintah sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memperbaiki pesawatpesawatnya yang berbadan lebar yang dimilikinya, serta membayar jumlah pertama untuk pembelian pesawat-pesawat terbang baru guna menghidupkan rute-rute penerbangan intemasional yang sudah ada, maupun membuka rute-rute penerbangan yang baru. Dalam upaya menciutkan penerbangan dalam negerinya Kalau perlu rute-rute penerbangan dalam negeri dialihkan kepada maskapaimaskapai penerbangan lain. Karena sudah pasti maskapai-maskapai penerbangan milik swasta akan membeli saham-sahamnya. Maka harus disediakan jumlah saham tertentu untuk disediakan bagi dan dijual kepada maskapai-maskapai penerbangan dalam negeri seperti Merpati. Dengan demikian, dijaga keseimbangan antara penguasaan pemerintah di satu sisi dan modal swasta disisi lain atas dunia penerbangan, yaitu perpaduan antara kapitalisme (privatisasi/swastanisasinya) dengan orientasi kepemilikan negara dengan demikian, kita mengikuti arus privatisasi tanpa melanggar Undang-undang Dasar 1945. Yang ada (yang patut dibanggakan) para penerbang Garuda terkenal sangat halus dan tepat waktu (punctual) dalam kerja mereka, dan kalau ini dikombinasikan dengan kemampuan memperbesar usaha penerbangannya tentu dalam waktu sebentar saja akan merajai dunia penerbangan. Tentu saja hal itu harus dikombinasikan dengan tingkatan kesejahteraan para karyawannya, pembersihan besar-besaran dalam tubuh maskapai itu, dan melanjutkan perbaikan-perbaikan fasilitas pemeliharaan (maintenance). Maka dengan diversifikasi rute-rute penerbangan yang lebih baik di dalam negeri (antara lain dengan menghilangkan Jakarta sebagai titik pusat penerbangan dalam negeri, melainkan dengan membuka Manado, Banjarmasin, Denpasar, Medan dan Ambon sebagai titik Pusat yang baru bagi penerbangan dalam negeri), maka penerbangan dalam negeri kita akan mengalami pengembangan luar biasa secara cepat. Nah, kalau Garuda mampu menjadikan titik baru itu sebagai pangkalan bagi penerbangan intemasionalnya, tentu Garuda juga akan berkembang secara intemasional dengan cepat. Memang mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan, bukan?
Baik Belum Tentu Bermanfaat Oleh Abdurrahman
Wahid
Tertawa senantiasa dilakukannya sepenuh hati. Raut mukanya seperti menyimpan tawa dalam kadar sangat besar. Sedikit alasan saja sudah cukup membuatnya tergelak-gelak. Sering kali orang sekitamya terbawa kepada suasana penuh tawa seperti itu. Hanya kesopanan bersikap di depan seorang kiai sajalah yang menahan mereka dari turut tertawa tergelak-gelak. Seperti kecenderungannya yang begitu besar untuk tertawa sepenuh hati itu, Kiai Ali Krapyak memiliki pandangan serba optimistis tentang kehidupan dan tentang tempatnya sendiri dalam kehidupan itu. Begitu optimistis ia memandang peranannya dalam kehidupan, sehingga ia sering bagaikan bertindak semau-maunya. Menasehati menteri, menyindir orang lain dan membuat lelucon bahkan hingga tentang soal-soal keagamaan yang terdalam sekalipun (seperti kepercayaan kepada para wali). la sendiri yang menetapkan hak berbuat demikian, dan ia tidak bertanya kepada orang lain tentang tepat atau tidaknya tindakan seperti itu. Pokoknya ia yakin tentang penting atau benamya suatu hal, langsung dilakukannya. Walaupun bergaul dekat dengan banyak pejabat pemerintahan dari tingkat teras di pusat dan daerah, sering kali ia mengambil sikap melawan dan menyanggah. Kasus RUU Perkawinan dalam tahun 1973-74. Kasus tanda gambar Ka'bah menjelang Pemilu 1977. Kasus aliran kepercayaan dalam SU- MPR yang lalu. Kasus liburan puasa. Mengapakah Kiai yang begitu luas dan bersifat akomodatif dalam pergaulan dapat mengambil sikap 'keras' dalam kasus-kasus di atas? Bukankah itu berarti adanya inkonsistensi antara pola umum hidupnya yang serba akomodatif dan kekerasan kepala dalam beberapa hal? Jawabannya terletak pada kemampuan Kiai Ali untuk menentukan pilihan antara hal-hal esensial agama dari hal-hal yang dianggapnya bukan persoalan utama. Kemampuan untuk melakukan penyesuaian dengan tuntutan zaman, tanpa kehilangan identitas semula yang bersumber pada nilai-nilai keagamaan yang paling dalam. Ini terbukti dari keseluruhan pola kehidupan kiai yang baik ini. Sebagai kiai yang mendalam pengetahuan agamanya.sebenamya ia cukup mengikuti sistem pendidikan tradisional yang sudah berjalan begitu lama, untuk memperoleh tempat terhormat dalam barisan ulama 'tangguh'. ltu tak dilakukannya. Sebaliknya, ia membuka sekolah agama yang 'aneh': di samping kitab-kitab kuno agama, para santrinya dirangsang untuk membaca literatur baru dari Timur Tengah. Di samping mempelajari gramatika Arab kuno, para santri itu dirangsang untuk mempelajari literatur bahasa kontemporer.
Di samping mendalami hukum agama dari buku-buku fiqh kuno, mereka didorong untuk mendalami juga literatur studi perbandingan dengan hukum-hukum lain yang dianut di Barat dan Timur. "Mengapa Kiai menyuruh mereka membaca bukubukunya Abduh, apakah tidak khawatir para santri 'lepas' dari NU?" Kiai Ali menjawab dengan tertawanya yang khas: "Kalau membaca buku yang macam-macam nanti akan menjadi NU yang matang". "Mengapa Kiai begitu gandrung mengajar di IAIN, mengapa justru tidak membuka sendiri pengajian agama lanjutan khusus untuk kitab-kitab mazbab Syafi'i? " Sambil tertawa lagi, Kiai Ali menjawab: "Di IAIN mereka akan memperoleh tambahan pengetahuan di samping kitab-kitab mazhab tersebut". Di sini kita bertemu dengan pribadi yang mencari pemecahan pragmatis bagi masalah-masalah keagamaan yang rumit. Pragmatisme yang dihasilkan lalu memiliki perpaduan antara sikap rasionalistis dan keyakinan yang teguh akan kebenaran ajaran agama. Apa yang harus dipelihara sekuat tenaga dari warisan masa lampau, dan apa yang harus diambil dari kehidupan kontemporer bagi kepentingan penyesuaian dengan kebutuhan. Dalam kerangka seperti inilah dapat dipahami 'penafsiran' Kiai All ini atas sebuah pendapat Imam Ghazali dalam karya utamanya lhya'. Imam Ghazali berpendapat, para remaja yang sedang menuntut ilmu harus tirakat. Antara lain dengan jalan memakan hanya daun-daunan dan sedikit buah-buahan, dan menjauhi 'makanan keras' (solid food) seperti nasi jagung dan sebagainya apalagi daging, ikan dan ayam. Hanya mencemakan makanan 'serba prihatin' seperti itu sangat baik dan bermanfaat untuk mencapai kedalaman ilmu agama. Pendapat seperti ini sudah tentu berlawanan dengan sebutan gizi para remaja yang sedang membutuhkan semua jenis makanan yang akan mengembangkan bentuk fisik tubuh mereka. Ketika ditanya pendapatnya tentang seruan Imam Ghazali untuk melakukan tirakat ngrowot seperti di atas, jawab Kiai Ali adalah 'baik, tetapi belum tentu bermanfaat'. Kemampuan memberikan klasifikasi berdasarkan kategorisasi adalah kunci dari kemampuan adaptasi yang dilakukan Kiai Mengaku kebaikan pendapat yang dirumuskan di masa lalu, manfaat yang baru, adalah salah satu bentuk yang kompleks Ali Krapyak ini. sambil mencari adaptasi ini.
Tanpa tercabut dari akar masa lalunya, adaptasi Kiai Ali cukup dinamis, bukan?
Bangsa Kita dan Pembiaran Kekerasan Oleh: Abdurrahman Wahid Yogya TV (YTV) secara rutin menayangkan siaran tunda acara Kongkow Bareng Gus Dur (KBGD). Acara yang disiarkan langsung tiap Sabtu pagi jam 10 oleh Radio 68H dari Kedai Tempo, Utan Kayu, ini juga ditayangkan 13 stasiun televisi lokal. Nah, minggu lalu YTV mendapatkan telpon dari orang yang mengaku sebagai Pengurus Front Pembela Islam (FPI) dan Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) daerah Yogyakarta. Orang itu mengatakan kepada YTV agar tidak menayangkan lagi KBGD. Alasan yang digunakan, karena dalam salah satu siaran itu, penulis bergurau dengan menyatakan sebab terjadinya gempa bumi di daerah Bantul adalah karena Nyai Ratu Kidul dipaksa mengenakan jilbab oleh Ketua FPI Habib Riziq. Ini berarti, menurut penelpon tadi, Habib Riziq telah dihina oleh Gus Dur dengan lelucon tersebut. Itulah sebab munculnya permintaan berbentuk ancaman dari pengikut Habib Riziq itu. Mengapa penulis menyampaikan hal tersebut? Karena penulis sudah muak dengan sikap main hakim sendiri dari tokoh tersebut dan anggotanya. Karena ketidakberanian pemerintah untuk menindak FPI dan tokoh tersebut, maka sikap mereka semakin menjadi kurang ajar. Main ancam dan tindakan main hakim sendiri adalah ciri pokok mereka yang harus kita hadapi sebagai bangsa. Padahal FPI itu melanggar undang-undang, yang jelas menyatakan bahwa membawa senjata di muka umum dan merusak milik orang lain adalah pelanggaran hukum. Karena itulah kejengkelan pun semakin lama semakin bertumpuk. Itulah penyebab sindiran yang dimaksudkan oleh penulis. Tapi bukannya mencari maksud sindiran penulis, FPI malah dengan arogan mengeluarkan ancaman kepada YTV. Sikap yang buruk itu masih diikuti oleh penilaian seorang pimpinan lokal FPI Yogyakarta, yang menyatakan bahwa penulis hanya diikuti satu persen saja dari keseluruhan kaum muslimin di negeri ini. Sisanya mengikuti jalan pikiran FPI. Penulis sendiri terheran-heran dengan pemyataan tersebut. Dengan demikian, mereka menganggap kaum muslimin di negeri ini begitu tololnya. Ini adalah mispersepsi yang timbul dari kurangnya pengetahuan akan kenyataankenyataan obyektif perkembangan sejarah Islam di negeri ini. Mereka mengulangulang bahwa Islam lebih maju daripada agama-agama lain, padahal penulis artikel ini yakin akan kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW bahwa al-islamu yalu wa la yula alaih (Islam itu unggul dan tidak terungguli). Namun karena keyakinan itu maka penulis tidak perlu meremehkan agama-agama lain. Karena sikap terbuka itu maka penulis artikel ini dengan santai menunjukkan penghormatan kepada penganut agama lain yang ada di negeri kita. Sebagai mayoritas kaum beragama, kaum muslimin di negeri ini sebaiknya melindungi agama lain itu. Hal ini yang justru menunjukkan kekuatan Islam yang sebenamya. Umat Islam seperti inilah yang patut disebut umat yang dewasa. Seorang dewasa akan memuji dan melindungi si anak dan tidak akan memaksanya untuk menjadi seorang dewasa. Dengan tidak menghardik si anak, orang justru akan dinilai bijaksana dan menunjukkan kedewasaan. Kelembutan dianggap jauh lebih bemilai.
Dan orang yang berbudi luhur dikenal karena memiliki kekuatan tapi tidak pemah digunakan untuk kekerasan. Seperti dua orang pesilat Cina, yang berputar-putar di atas kotak gelangang. Begitu keduanya beradu kekuatan, maka yang lebih besar tenaga dalamnya, tanpa memforsir tenaga fisiknya, yang akan menang. Dari teriakan masing-masing sudah dapat diketahui siapa yang memiliki tenaga dalam (lweekang) paling tinggi. Inilah cara yang diperlihatkan seorang pandai, berbeda dengan seorang bodoh dan lemah. Masalah yang sangat mendasar dalam hal ini adalah, apa yang harus diperbuat oleh seorang muslim yang cinta kepada agamanya? Haruskah ia menyatakan dengan jelas dan terbuka akan kelebihan Islam? Bagi mereka yang tidak benarbenar yakin kelebihan Islam atas agama-agama lain tentu kelebihan itu haruslah dinyatakan secara berulang-ulang. Dengan berbuat demikian, berarti ia memposisikan Islam sebagai altematif bagi agama-agama lain itu. Sebaliknya mereka yang benar-benar memahami kebesaran Islam tentu akan bersikap lebih menghargai agama lain dan tidak takut bergaul dengan penganut agama lain. **** Ketika kemudian FPI Yogyakarta meyampaikan permintaan kedua kepada manajemen YTV yang meminta supaya permintaan pertama itu dianggap tidak ada, maka jelas ini adalah koreksi atas sikap pertama yang meminta acara KBGD dihentikan. Ini masih lumayan, karena menunjukkan kemampuan menggambil sebuah tindakan korektif di kalangan kedua organisasi tersebut. Ataukah karena peringatan halus dari Kapolri agar aksi kelompok itu tidak merugikan siapapun, termasuk dengan pihak penulis artikel ini. Bukankah ini menujukkan sikap setengah-setengah dari pihak Kapolri yang segan membubarkan kelompokkelompok yang gemar menebar kekerasan dan ketakutan? Jika memang demikian hal itu, berarti benar anggapan orang bahwa kepolisian di masa lalu ada kaitannya dengan pendirian FPI? Kenyataan-kenyataan inilah yang terjadi dalam sejarah obyektif bangsa kita. Jika kita tidak melakukan koreksi, berarti kita mengorbankan obyektifitas sejarah kita sebagai bangsa? Entahlah, penulis artikel ini sendiri takut akan konsekuensi sikap mengemukakan obyektifitas sejarah bangsa itu. Berat konsekuensi sikap benar seperti itu, bukan?
Benarkah Diperlukan Sebuah Jaringan? Oleh
Abdurrahman
Wahid
Sehari setelah pulang dari Muktamar Ke-31 NU di Boyolali, saya berangkat dari Cengkareng siang hari menuju India, sampai di New Delhi pukul 7 malam waktu setempat. Sesampai di sana, saya dibawa oleh teman-teman ke Hotel Grand Hyatt di dekat lapangan terbang Indira Gandhi. Setelah malam itu tidur di hotel tersebut, sekitar pukul 11
keesokan harinya, saya diajak ke sebuah rumah di kompleks para menteri dekat gedung parlemen, yaitu tempat tinggal Ghulam Nabi Azad, menteri urusan parlemen dalam kabinet yang dibentuk Sonia Gandhi. Sebagaimana biasa, tokoh muslim tersebut berusaha menguasai pembicaraan. Ghulam Nabi Azad seorang Kashmir muslim, yang menjadi orang ketiga di India sekarang setelah Sonia Gandhi dan Perdana Menteri Manmohan Singh. Jadi, dia adalah politikus yang sangat bepengaruh dan, menurut seorang teman saya, ada kemungkinan di kemudian hari dia akan menjadi perdana menteri. Tetapi, saya agak ragu terhadap hal itu karena dia adalah seorang muslim dan bukannya beragama Hindu. Dalam pandangan saya, di kemudian hari, dia dapat menjadi presiden seperti almarhum Zakir Husain. Karena India mengangkat presiden sebagai kepala negara, maka peranannya lebih bersifat protokoler dan bukannya menjadi kepala pemerintahan. Walaupun tidak menjadi orang pertama di negeri itu, presiden India bukannya tidak berpengaruh, seperti halnya Maulana Abdul Kalam Azad, pemimpin India yang sekarang sudah meninggal dunia dan dulunya adalah seorang pejuang kemerdekaan yang gigih (dan teman mendiang Mahatma Gandhi), yang juga adalah pengarang tafsir berjudul Tarjuman Al Quran berbahasa Urdu. Ghulam Nabi Azad sekarang ini menjadi muslim pertama di negeri tersebut. Sebab, apa yang dia perbuat dan putuskan mempunyai pengaruh besar terhadap 120 juta jiwa kaum muslimin di negeri itu. Dia kini menjadi menteri yang sangat penting akibat terbawa oleh Partai Kongres yang memerintah, karena meraih kemenangan besar dalam pemilu yang lalu. Walaupun di saat berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP) di bawah pimpinan Vajpayee, membuat India mencapai peningkatan cukup besar dalam perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya angka Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product/GDP), temyata dia kalah dalam pemilu tahun ini. Sebabnya ialah peningkatan itu tidak dinikmati masyarakat bawah. Peningkatan kemakmuran itu hanya dirasakan kalangan atas, seperti pegawai negeri dan pengusaha. Sebagai suara protes, para pemilih pun meninggalkan BJP dan pindah mencoblos Partai Kongres. Tetapi, karena pemimpin Partai Kongres, Sonia Gandhi, lahir di Italia, oleh parlemen dia dilarang menjadi perdana menteri alias orang pertama di negeri itu. Maka, Sonia menunjuk Manmohan Singh menjadi perdana menteri dan Ghulam Nabi Azad menjadi menteri urusan parlemen/minister of parliamentary affairs, yang menjadikannya langsung sebagai orang ketiga yang berkuasa setelah Sonia Gandhi dan Perdana Menteri Singh. Sebagai seorang muslim yang sangat berkuasa, dia berpandangan bahwa Islam tidak mengenal kekerasan dan -seperti dalam bahasa politik AS saat ini- dia adalah seorang muslim moderat. Apalagi, dia tinggal dan bekerja (dan dengan sendirinya
aktif) sebagai politikus di sebuah negara sekuler seperti India, maka tampak sikap moderatnya itu justru membuat dia bertambah penting. Hal inilah yang menarik perhatian penulis. Dan dengan tokoh tersebut, penulis terus melakukan komunikasi. *** Kemudian timbul pertanyaan, mengapakah saya menemuinya? Apalagi, saya datang ke New Delhi hanya semalam karena keesokan harinya saya harus pulang ke Jakarta? Saya diberi waktu untuk bertemu dengannya pada Sabtu pagi itu. Tadinya, ada keinginan untuk berjumpa dengan beberapa tokoh seperti imam masjid di New Delhi dan pimpinan Universitas Millia (lembaga pendidikan milik kaum muslimin yang paling berpengaruh di India), namun kedatangan Vladimir Putin dari Rusia pada hari yang sama, untuk kunjungan selama tiga hari ke ibu kota India itu, membuat ruang hotel sangat sulit didapatkan. Sudah untung mendapatkan kamar untuk semalam saja sehingga penulis tidak dapat berlama-lama berada di kota tersebut. Karena itu, penulis memutuskan untuk kembali ke Jakarta malam Minggu (5 Desember 2004). Mengapakah sejauh itu saya berjalan? Karena ingin segera menciptakan jaringan dan hubungan komunikasi dengan para pemimpin muslim moderat di mana pun mereka berada. Orang-orang seperti Anwar Ibrahim dari Malaysia, Ghulam Azad dari India, Dr M. Khalid Masud dari Pakistan, Khatami yang menjadi presiden Iran saat ini, M. Rajab Erdogan (baca:Ridwan) dari Turki, Muhammad Al-Sammak di Lebanon, dan beberapa orang lainnya yang banyak melahirkan pemikiran dan pandangan moderat mereka di dunia Islam, patutlah membuat jaringan seperti itu. Ini minimal untuk menampilkan sejumlah pemimpin moderat muslim ke permukaan dan untuk menandingi kaum garis keras yang mengajukan pendapat bahwa harus ada negara Islam di tempat masing-masing untuk dapat membuat agama tersebut berjaya dalam hubungan intemasional. Langkah membentuk jaringan tadi lebih konstruktif daripada berdebat melawan kaum garis keras baik terbuka maupun tertutup. Jika hal ini tercapai, langkah selanjutnya adalah melakukan inventarisasi pendapat dan pandangan orang-orang moderat tersebut. Memang selama ini inventarisasi yang dilakukan hanyalah bersifat terbatas, dan itu pun lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti rakyat. Tidak ada yang memikirkan cara "mencapai rakyat" dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sebagai akibat adanya "sentuhan intelektual" dari para pemikir dan aktivis tersebut, tidak heranlah jika kemudian komunikasi antara orang-orang itu dan masyarakat ditanggapi emosional dan berisi kecurigaan yang sangat berlebih-lebihan, bahkan dianggap menghadapkan Islam kepada dunia Barat. Hal ini tertulis di mana-mana. Memang sebagian kecil karena arogansi pihak Barat itu, tetapi sebagian besar karena kegagalan komunikasi intem di kalangan kaum muslimin sendiri.
Karena alasan di atas, penulis pada hari-hari ini sibuk menciptakan kontak-kontak baru dengan para pemikir moderat yang berada di negara-negara lain. Katakanlah, sebagai permulaan dari upaya serius untuk menampilkan agama Islam dengan ajaran-ajarannya yang manusiawi. Diakui atau tidak, citra Islam identik dengan kekerasan, sekarang terpulang kepada kaum muslimin sendiri untuk memperbaiki citra yang sudah telanjur salah itu. Saya merasa pantas melakukan peranan itu karena perjuangan saya selama lebih dari 30 tahun untuk membela hak-hak asasi manusia (HAM) sekarang diterima luas tidak hanya kaum muslimin, tetapi juga aktivis HAM. Baik di negeri ini maupun di negeri-negeri lain, apa yang dilakukan penulis itu telah menimbulkan reaksi positif. Memang diperlukan penciptaan jaringan untuk itu. Dalam seminar di Belanda beberapa waktu silam, seorang wanita Turki, Fadime Orgu, menyatakan bahwa dia lahir di Eropa. Karena itu, dia mengamalkan ajaran Islam yang tentu saja tidak sama dengan apa yang diamalkan orang tuanya di Turki. Tapi, dia juga tidak akan dapat menjadi seperti orang-orang Eropa lainnya yang nonmuslim. Dia tidak pemah melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Dia juga tidak pemah minum setetes alkohol, dan dia juga tidak pemah makan daging babi. Dengan demikian, dia berdiri di tengah-tengah antara orang muslim kuno dari tanah leluhur dan orang Eropa modem yang tidak beragama Islam. Orang-orang seperti inilah yang harus kita hubungi dalam sebuah komunikasi yang sehat. Fadime Orgu, yang sekarang terpilih menjadi anggota parlemen Belanda (tweede kamer), adalah contoh dari pemimpin-pemimpin muslim yang baru timbul di manamana. Mereka mengalami proses mengambil dan membuang dari ajaran-ajaran mereka, sesuatu yang lazim terjadi dalam sejarah manusia, bukan?
Beri Jalan Orang Cina Oleh: Abdurrahman
Wahid
Jadi orang Cina di negeri ini, di masa ini pula, memang serba salah. Walaupun sudah ganti nama, masih juga ditanyakan nama aslinya kalau mendaftarkan anak ke sekolah atau jika membuat paspor. Mungkin, karena memang nama yang digunakan terasa tidak pas bagi orang lain, seperti nama Nagaria. Biasanya naga menggambarkan kemarahan dan keganasan. Apakah si naga yang riang gembira ini tertawa-tawa? Hartadinata, terasa lucu, karena tidak klop antara kekayaan dan keanggunan jabatan, antara harta dan nata. Temyata bukan hanya karena nama baru orang-orang Cina terasa tidak sreg di telinga orang lain. Tetapi karena keputusan politik, untuk membedakan orang Cina dari pribumi. Memang tidak ada peraturan tertulis, melainkan dalam bentuk kesepakatan memperlakukan orang Cina tersendiri. Mengapa? Karena mereka kuat, punya kemampuan terlebih, sehingga dikhawatirkan akan meninggalkan suku-suku bangsa lainnya. Apalagi mereka terkenal dalam hal kewiraswastaan. Kombinasi kemampuan finansial yang kuat, dan kemampuan lain yang juga tinggi, dikhawatirkan akan membuat mereka jauh melebihi orang lain dalam waktu singkat. Secara terasa, "kesepakatan" meluas itu akhimya mengambil bentuk pembatasan bagi ruang gerak orang Cina. Mau jadi tentara? Boleh masuk AKABRI, lulus jadi perwira. Tetapi harus siap menerima kenyataan, tidak akan dapat naik pangkat lebih dari kolonel. Mau jadi dokter? Silakan, namun jangan mimpi dapat meniti karier hingga menjadi kepala rumah sakit umum. Mau masuk dunia politik? Bagus, tetapi jangan menduduki jabatan kunci. Di birokrasi? Jadi pejabat urusan teknis sajalah, jangan jadi eselon satu. Apalagi jadi menteri. Sialnya lagi, jalan buntu itu temyata tidak membawakan altematif yang memuaskan. Jalan terbuka satu-satunya adalah mencari uang. Dan itu sesuai pula dengan kecenderungan sosiologis mereka sejak masa lampau, karena di masa kolonial pun mereka hanya boleh cari uang. Usaha berhasil, uang masuk berlimpah-limpah, kekayaan makin bertambah. Celakanya, justru karena itu mereka disalahkan pula: penyebab kesenjangan sosial. Akumulasi modal dan bertambahnya kekayaan temyata tidak membawa keberuntungan. Cara mereka menggunakan uang dinilai sebagai penyebab kecenderungan hedonistik di kalangan generasi muda kita, padahal permasalahannya sangat kompleks. Kekayaan mereka dianggap diperoleh melalui pengisapan si kecil, padahal orang Cina hanyalah satu saja dari sekian banyak faktor kemiskinan. Dengan kata lain, orang Cina dipersalahkan bagi kebanyakan hal yang dirasakan tidak benar dalam kehidupan kita. Salah satu kemampuan hukum kehidupan masyarakat bertahan. adalah pentingnya
Potensi untuk survive ini dimiliki orang Cina, di manapun mereka berada dan potensi itu diwujudkan di negeri kita oleh mereka, dengan memanfaatkan satusatunya jalur kolektif yang masih terbuka bidang ekonomi. Segala tenaga dan daya dicurahkan untuk mencari kekayaan. Perkecualiannya hanyalah sedikit orang Cina yang menjadi intelektual, akademisi, tenaga profesi, politisi dan sebagainya. Kemampuan bertahan demikian tinggi bila dimampatkan ke dalam sebuah sasaran kolektif mencari kekayaan, sudah tentu sangat besar hasilnya. Apa pula dibantu oleh kemudahan di segenap faktor produksi dan sektor usaha. Karenanya wajar-wajar saja bila mereka berhasil, tidak perlu dikembalikan kepada sifat serakah, atau direferensikan kepada rujukan akan licin dan sejenisnya. Bahwa banyak sekali orang Cina melakukan hal-hal seperti itu, tetapi tentunya tidak dapat dianggap sebagai watak rasial atau sifat etnis dari orang Cina. Orang lain juga berbuat sama. Dengan demikian, persoalannya bukanlah bagaimana orang Cina itu bisa dibuktikan bersalah, melainkan bagaimana mereka dapat ditarik ke dalam alur umum (mainstream) kehidupan bangsa. Bagaimana kepada mereka dapat diberikan perlakuan yang benar-benar sama di segala bidang kehidupan. Tanpa perlu ditakutkan bahwa sikap seperti itu akan memperkokoh posisi kolektif mereka dalam kehidupan bangsa, karena hal-hal seperti itu dalam jangka panjang temyata hanyalah sesuatu yang berupa mitos belaka. Keperkasaan orang putih temyata dapat disaingi oleh keperkasaan orang hitam di Amerika Serikat. Orang Melayu di Singapura juga menyimpan kemampuan sama maju dengan orang Cina, seperti semakin banyak terbukti saat ini. Begitu pula bangsa-bangsa lain, baik yang menjadi minoritas maupun mayoritas. Tesis pokoknya di sini adalah: dapatkah kelebihan kekayaan orang Cina dimanfaatkan bagi usaha lebih memeratakan lagi tingkat pendapatan segala lapisan masyarakat bangsa kita di masa depan? Jawabnya, menurut penulis, adalah positif. Orang Cina, sebagaimana orang-orang lain juga, dapat diappeal untuk berkorban bagi kepentingan masa depan bangsa dan negara. Tentu dengan tetap menghormati hal-hal mendasar yang mereka yakini, seperti kesucian hak-milik dari campur-tangan orang lain. Pemindahan kekayaan secara masif bukanlah barang baru bagi orang Cina, karena mereka pun baru saja melakukan hal itu, dalam bentuk merampungkan upaya akumulasi modal yang bukan main besamya. Salah satu instink untuk tetap bertahan hidup bagi orang Cina adalah realisme sangat besar yang mereka miliki. Akal mereka akan mendiktekan keputusan pemindahan kekayaan secara masif kepada mereka yang lebih lemah, dalam upaya mendukung pihak lemah itu agar juga menjadi kuat. Tetapi itu semua harus dilakukan dengan menghormati kesucian hak-milik mereka, bukan dengan cara paksaan atau keroyokan. Kalau begitu duduk perkaranya, jelas akses orang Cina kepada semua bidang kehidupan harus dibuka, tanpa pembatasan apa pun. Kalau sekarang ada tiga orang Arab menjadi menteri, tanpa ada pertanyaan atau kaitan apa pun dengan asal-usul etnis atau rasial mereka, hal yang sama juga harus diberlakukan bagi
orang Cina kepada semua bidang kehidupan harus dibuka, tanpa pembatasan apa pun. Kalau prestasi para dokter orang Cina sama baiknya dengan yang lain-lain, mereka pun berhak menjadi kepala rumah sakit umum. Begitu juga menjadi jenderal, dan demikian seterusnya. Cerita gurau yang luas beredar menyebutkan perbedaan orang Jawa dari orang Cina. Orang Jawa, kata cerita itu, akan senantiasa menanyakan kesehatan kita kalau bertemu: sampean waras? Bagi orang Jawa yang mudah masuk angin dan sebagainya, kesehatan adalah perhatian utama. Ini berbeda dengan orang Cina. Kalau berjumpa dengan orang lain, pertanyaan yang diajukan: sampean apa sudah cia? alias apakah sudah makan atau belum. Mengapa? Karena mereka dahulu datang kemari akibat bahaya kelaparan di daratan Cina, negeri asal mereka. Keanehan seperti itu adalah karakteristik etnis, yang tidak boleh mengganggu keserasiah hidup sebuah bangsa. Apalagi bagi bangsa yang pada dasamya sudah sangat heterogen, seperti bangsa kita. Kita sudah harus dapat melihat karakteristik khusus orang Cina seperti juga keanehan suku-suku bangsa kita yang lain. Ini berarti kita harus mengubah cara pandang kita kepada orang Cina. Mereka harus dipandang sebagai unit etnis. Bukan unit rasial. Kalau kita bisa menerima kehadiran orang Flores, Maluku dan Irian sebagai satuan etnis - padahal mereka bukan dari stok Melayu (karena stok mereka adalah Astromelanesia), maka secara jujur kita harus melakukan hal yang sama kepada stok Cina. Juga stok Arab. Mereka bukan orang luar, melainkan kita-kita juga.
Mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Itulah reaksi pertama pada ajakan menyatukan dengan orang Cina". Akan banyak alasan dikemukakan dan argumentasi diajukan. Karena, memang, dalam diri kita telah ada keengganan mendasar untuk menerima kehadiran orang Cina sebagai orang sendiri. Kita sudah terbiasa mau menerima uang mereka tanpa merasakan kehadiran mereka. Boleh saja keengganan bahkan ketakutan seperti itu kita beri sofistikasi sangat canggih. Tetapi, ia tetap saja merupakan keengganan dan ketakutan. Sesuatu yang irasional. Justru itulah yang harus kita perangi, kita jauhi sejauh mungkin. Mengapakah hal itu menjadi keharusan? Karena hanya dengan perlakuan wajar, jujur dan fair dari kita sebagai bangsa kepada orang Cina sajalah yang dapat mendorong timbulnya rasa berkewajiban berbagi kekayaan dan nasib antara mereka dan pengusaha kecil kita. Ini kalau kita benar-benar jujur, lain halnya kalau tidak...
Bersatu dalam Menuntut llmu Oleh Abdurrahman
Wahid
Kiai Fatah dan Kiai Masduki adalah dua orang di antara sekian orang kiai yang hidup di desa Tambakberas. Bersama-sama, kesemua kiai itu menghidupkan kegiatan keagamaan dan mengelola pesantren di desa tersebut, sebagai amanat Kiai Wahab Chasbullah. Kiai Fatah tinggal di kompleks utama Bahrul Ulum itu, di sebelah timur sungai yang membelah dua desa yang terletak dua kilometer di utara kota Jombang itu. Kiai Masduki tinggal di sebelah barat sungai. Kiai Fatah jadi pemimpin formal kompleks utama dengan ratusan santri yang tinggal, termasuk mengelola semua jenis pendidikan di lingkungan tersebut, Kiai Masduki hanya mengurusi beberapa belas santri saja, itu pun di waktu mereka tidak bersekolah di kompleks utama. Kiai Fatah menjadi agamawan penuh, dalam artian tidak memiliki pekerjaan apa pun selain menjadi kiai di pesantrennya. Kiai Masduki adalah petani yang mengerjakan sawahnya sendiri dengan susah payah, dan mengusahakan pekarangan rumah yang di tanaminya dengan tanaman kebun. Kiai Fatah mengajar di madrasah, menggunakan peralatan sekolah dengan jam pelajaran teratur. Balaghah (retorika) adalah mata pelajaran kesayangannya,juga usul fiqh. Lain dari itu, tidak mau ia mengajarkannya di sekolah. Paling-paling di luar jam sekolah, sebagai pengajian weton yang diikuti para santri tanpa memandang kelas sekolah masing-masing. Semacam kuliah umum atau courses menurut bahasa program puma sarjana di universitas modem. Kiai Masduki sebaliknya tidak mengajar di kelas. la mengajar di suraunya sendiri, menunggu santri yang akan mengaji kepadanya. Seperti dokter praktek yang menunggu kedatangan pasien. Lima kali sehari ia buka praktek. Sehabis salat subuh pada dini hari, sehabis salat zuhur di tengah hari, sehabis salat 'asar di sore hari, sehabis salat magrib di senja hari dan sehabis salat 'isya di malam hari. Siklus kehidupan ini tidak mengenal nilai waktu secara modem, tidak dibatasi oleh pagaran waktu yang umum digunakan di luar. Pengajian siang terhenti kalau kereta api kejurusan kota Babat melalui desa Tambakberas. Kalau peluit kereta tidak kunjung terdengar pengajian tidak selesai secara cepat. Tiap santri yang mengaji menunggu giliran masing-masing. Kalau tiba gilirannya, akan meletakkan teks yang ingin di pelajarinya di atas meja yang terletak di muka sang kiai. Kiai Masduki akan membaca halaman yang di buka oleh santri, walaupun teks itu di letakan secara terbalik, sang kiai membaca teks itu dari atas, santrinya memberikan catatan di bawab baris yang dibaca. Habis sebuah subyek dibacakan dan diterangkan, sang kiai beralih kepada santri
yang lain. Lagi-lagi seperti dokter yang berpraktek. Kalau dokter tidak menampik pasien yang berpenyakit apapun, Kiai Masduki tidak pemah menolak santri yang membawa kitab teks apapun. Kiai Fatah pandai berpidato, bahkan termasuk orator yang memikat hati. Bermacam-macann ilustrasi sejarah dikemukan untuk menggambarkan pesan yang disampaikan secara hidup. Banyak lelucon diceritakannya untuk mencegah datangnya kantuk para hadirin, dan banyak hafalan ayat AI-Qur'an dan hadith dan syair-syair Arab dilontarkannya untuk meyakinkan orang banyak. Kiai Masduki, sebaliknya, mungkin tidak pemah berpidato di muka umum seumur hidupnya. Kalaupun 'berperan' dalam majelis-majelis keagamaan di muka umum, paling-paling hanya untuk membacakan doa penutup atau memimpin tahlil. Kiai Fatah sering menggoda dan mempersilakan Kiai Masduki memberikan sambutan. Dan Kiai Masduki akan selamanya menjawab nanti saja, sehabis sampeyan memimpin tahlilan. Maklumlah Kiai Fatah sebagai orang yang tidak pemah urut dan runtut kalau memimpin tahlil. Perbedaan gaya, cara hidup dan pola pembagian kegiatan antara keduanya tidak menutupi kenyataan akan persamaan yang mendasar antara keduanya: keteguhan hati untuk mengabdikan diri kepada tugas hidup mengajarkan ilmu-ilmu agama di lingkungan pesantren. Kiai Fatah dalam bahasa kini dapat dikatakan 'kiai full timer', sedangkan Kiai Masduki 'kiai part timer' ( karena merangkap bertani) . Tetapi keduanya mengkhususkan pengabdian mereka kepada upaya 'menuntut ilmu'. Tidak heran kalau keduanya lalu diarahkan jalan pikiran mereka oleh tugas hidup 'menuntut ilmu *itu, watak mereka dibentuk oleh kecintaan kepada ilmu-ilmu agama , dan sikap hidup mereka sepenuhnya ditentukan oleh kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh ilmu-ilmu agama itu sendiri . Mereka menjadi orang yang tulus dalam mengarungi lautan hidup tulus kepada panggilan hidupnya, tulus kepada orang lain (tidak pemah mengemukakan buruk sangka mereka kepada orang lain) dan tulus kepada kebenaran yang datang dari keputusan yang diambil bersama. Tidak heranlah jika mereka tidak pemah menyerang pihak lain, berusaha sejauh mungkin tidak menyakiti hati golongan lain, dan lebih-lebih lagi bersikap toleran dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum. Ya, kebersamaan yang datang dari kesannaan tata nilai dan sikap hidup yang bersumber pada kecintaan mereka kepada ilmu-ilmu agama. Mereka menganggap kesemuanya itu sebagai bagian dari upaya 'menuntut ilmu' yang mereka yakini kebenarannya. Kiai Fatah telah tiada. Kiai Masduki sudah tua renta (tetapi tetap mengajar, walaupun tidak lagi ke sawah). Dapatkah mereka wariskan pola kehidupan saling berbeda tetapi sama-sama semangat 'menuntut ilmu' itu?
Bila Kiai Berdebat Oleh
Abdurrahman
Wahid
Banyak kiai memiliki sifat aneh, tetapi yang paling sering didapati adalah sikap egosentris mereka. Mungkin ini adalah kompensasi kejiwaan untuk mengimbangi keharusan berpola hidup serba konformistis dengan sesama kiai. Juga untuk mengimbangi 'larutnya kepribadian' dalam tugas pelayanan mereka yang begitu total kepada kehidupan masyarakat. Taruhlah ini semacam 'kemewahan' sikap dalam deretan mendatamya pola hidup mereka sendiri: mengajar,beribadat ritual,konsultasi kepada masyarakat, memimpin beberapa jenis upacara keagamaan yang berdimensi sosial (kelahiran, khitanan,perkawinan dan kematian) dan sebagainya. Justru dalam forum musyawarah hukum agama antara sesama kiai terletak 'katup pelepas' untuk menunjukkan arti diri mereka dalam rutinitas lalu muncul dalam bentuknya yang paling sedikit berakibat negatif. Memang cukup banyak yang memperagakan eksentrisitas watak hanya untuk sekadar tampak aneh saja, sering dirupakan secara kongkrit dalam bentuk pembicaraan berkepanjangan tentang definisi suatu hal tanpa mampu mencari kerangka sosial yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup masa kini. Seolah-olah dominasi pemikiran skolastik menutupi munculnya kesadaran sosial yang sedang mencari jalannya sendiri memasuki lingkup pemikiran keagamaan. Di luar forum musyawarah hukum agama, sedikit sekali tampak perbedaan pendirian dan pendekatan antara semua kiai itu, karena fungsi ritual mereka lakukan kurang lebih dalam pola yang hampir bersamaan. Hanya dalam fungsi mendidik masyarakat melalui dakwah oral, para kiai telah mulai menunjukkan perbedaan cara berpikir. Ada yang menekankan pesan-pesan mereka pada penguatan nilai-nilai moral melalui penolakan atas segala yang bercap modem,tetapi cukup banyak pula yang memusatkan perhatian pada masalahmasalah dasar dalam kehidupan masyarakat, seperti penumbuhan toleransi dan pengembangan sikap perhitungan (rechenhaftigkeit, kalau meminjam istilahnya Jan Romein) Dalam musyawarah hukum agama yang berlangsung ribuan kali banyaknya di seluruh penjuru tanah air setiap tahunnya,berlangsung perdebatan sengit antara mereka yang hanya berkepentingan untuk membatasi diri pada rumusan-rumusan harfiah yang sesuai dengan landasan berpikir skolastik, dan mereka yang mencoba mencari relenvansi skolastisisme itu sendiri dalam perkembangan sosial berlangsung cepat. Perdebatan antara mereka yang setuju KB sebagai gagasan dan yang tidak setuju, yang dapat menerima pemindahan kuburan untuk membuat jalan dan yang tidak dapat menerimanya dan seribu kasus lainnya. Variasi sangat besar tampak dalam argumentasi yang digunakan dalam forumforum tersebut, untuk menunjang pendapat yang saling berbeda itu. Kaidah yang dipergunakan aplikasi kaidah yang digunakan atas persoalan yang menjadi pokok
pembahasan. Tidak kurang juga argumentasi murahan dipergunakan, seperti ucapan almarhum Kiai Wahab Chasbullah kepada almarhum Kiai Abdul Jalil Kudus ketika membahas validitas DPR-GR dari sudut hukum agama dua puluhan tahun yang lampau: "Kitab yang sampeyan gunakan 'kan cuma cetakan Kudus, kalau kitab yang menunjang pendapat saya ini cetakan luar negeri!" Ada sesuatu yang lebih berharga yang sebenamya tersimpan dalam mengemukakan argumentasi langsung seperti itu. Keinginan untuk memasukkan unsur-unsur kehidupan aktual ke dalam proses perumusan pendapat agama atas sesuatu persoalan. Keinginan agar ada perubahan kriteria, betapa halus dan kecilnya sekalipun, dalam penyusunan postulat-postulat(faradhiyat) logika agama. Tidak heranlah jika upaya seperti itu pemah membawa pada suatu kejadian yang berakibat positif, walaupun menggelikan. Masalahnya menyangkut diktum mazhab Syafi'i tentang larangan menyelenggarakan dua rombongan sembabyang Jumat di kampung yang sama. Di kota Jember timbul persoalan dengan diktum ini, tatkala guru agama sebuah SMP yang berdekatan dengan Masjid Agung bermaksud menyelenggarakan sembahyang Jumat sebagai peragaan praktek di sekolah tersebut. Para kiai pun segera ribut, terlibat dalam perdebatan antara yang membolehkan dan yang tidak memperkenankan. Perdebatan segera memasuki definisi kampung, yang dalam bahasa arab kuno disebut balad,dan aplikasinya bagi masa modem dengan pemisahan wilayah secara administratif. Kelurahankah, atau pedukuhan? Dalam suasana demikian Kiai Rahmat mengemukakan pendapat yang 'nyentrik' juga: "Boleh saja dilakukan. Antara SMP dan Masjid Agung 'kan sudah berlainan kampung, tidak sama balad-nya.Bukankah RK-nya berlainan?". Dangdut, Sebuah Pemberontakan Massal? Oleh: Abdurrahman
Wahid
Pada suatu pagi penulis naik kendaraan ke Surabaya, untuk menghadiri rapat umum perkenalan Partai Pelopor, yang dipimpin Rahmawati Soekamoputri. Temyata, penulis tidak dapat menemukan di mana tempat pertemuan itu berlangsung. Dalam perjalanan ke Cengkareng itu, penulis mendengarkan siaran sebuah stasiun radio FM dari Tanggerang, yang menamakan diri Bandar Dangdut Indonesia. Dengan cermat, penulis mula-mula mendengarkan sebuah lagu yang bemada nasehat moral untuk tidak ikut masyarakat yang sudah gila. Ini disusul oleh sebuah gambaran sepasang pengantin yang duduk di pelaminan. Kemudian disusul dengan penceritaan tentang keadaan kini yang penuh dengan pemberontakan anak muda. Akhimya, sebelum dibacakan warta berita, disodorkan sebuah lagu lama dari masa ketika Oma Irama baru mulai menyimpang ke dunia dangdut. Penulis lalu teringat, bahwa Oma Irama berangkat dari dunia musik pop Indonesia. Entah karena apa, ia lalu meyimpang ke dunia dangdut, di mana ia menjadi raja, relatif hingga saat ini. Namanya
ditambah dengan singkatan Raden Haji sehingga lengkapnya berbunyi Rhoma Irama. Mula-mula, lagu-lagunya tidak memperoleh bentuk yang pasti. Cinta kasih, penolakan pada materialisme, kebanggaan akan bagian budaya Indonesia dan sebagainya, menjadi tema-tema yang digarapnya dengan serius. Kemudian ia beralih kepada nasehat yang diperlukan orang muda dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu, ia mendendangkan demokrasi, yang kala itu masih menjadi impian saja. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, ia mengumandangkan tematema keagamaan dalam nyanyian-nyanyiannya. Bahwa hal itu lalu diikuti oleh sejumlah penyanyi-penyanyi lain dapatlah dipahami. Tetapi kemudian, ia menjadi marah besar ketika Inul Daratista membuat goyangan ngebor dalam nyanyiannyanyian dangdutnya, dapatlah dipahami. Namun ia lupa, konstitusi memberikan peluang kepada Inul untuk berbuat demikian. Penulis membela hak konstitusional Inul, tetapi tetap khawatir akan proses demoralisasi yang menjadi akibatnya, tepat seperti Bang Haji (panggilan penulis untuk Rhoma Irama). Dari penyimpangan Bang Haji ke musik dangdut itu, penulis yakin, bahawa sebuah pemberontakan massal tengah terjadi dalam blantika musik di negeri kita. Bukan hanya pemusik kawakan seperti Bang Haji, dengan tatanan musiknya yang apik dan liriknya yang memukau, tetapi juga dengan biramanya yang menyentuh hati kita yang sedikit demi sedikit ditariknya ke langgam dangdut yang ditampilkannya. Ia menyanyi tidak asal menyanyi, tetapi penuh dengan perasaan yang ditampilkan oleh jiwa raganya. Beberapa orang penyanyi dangdut sanggup mengikutinya, namun pada umumnya kata-kata yang mereka kemukakan hanya bersifat vulgar, dan permainan musik yang ditampilkan terdengar berantakan. Erotika nafsu seksual yang bermutu rendah menjadi isi utama dari lagu-lagu dangdut yang mereka sodorkan. Inilah yang membuat penulis jarang mendengarkan lagu-lagu dangdut belakanngan ini: seleranya terlalu rendah. Lagu-lagu dangdut yang bermutu tinggi, memang mengasikkan untuk didengar. Kita harus pandai memilih mana lagu-lagu dangdut yang patut didengar, dan mana yang tidak. Karena itu, musik dangdut bagi penulis masih merupakan penyimpangan dari sebuah garis umum yang memerlukan lyric yang baik kepada musik yang mengesankan dan langgam yang mengasikkan. Selain Bang Haji dan beberapa orang pemusik lain, penulis masih mencatat bahwa sebagian besar penyanyi dangdut belum mencapai tingkat kesenimanan yang dewasa dan hanya sekedar mencari uang dan ketenaran melalui goyangan-goyangan erotis belaka. Mereka belum mencapai (atau mungkin tidak) tingkat kesenimanan yang matang untuk menghidupi budaya bangsa. Kenyataan ini tidak terbantahkan oleh siapapun, termasuk oleh para dedengkot musik itu sendiri. Sejarahlah yang akan membuktikan benar atau tidaknya perkiraan ini. ***** Ortega Y Gasett filosof sosial Spanyol yang terkenal itu, dalam karyanya berjudul Rebellion de las massas (Pemberontakan Massa) mengemukakan bahwa massa rakyat di masyarakat-masyarakat modem ini, akan menampilkan rasa seni yang
memberontak terhadap kemapanan yang ada. Pemberontakan seni itu akan diikuti oleh pemberontakan moral dan seterusnya. Seperti sekarang yang sering kita dengar bahwa dinegeri-negeri maju, hukum memperkenankan perkawinan lesbi (sesama perempuan) maupun perkawinan gay (antara sesama lelaki). Dalam bacaan-pun, terjadi pemberontakan selera, dengan semakin banyaknya orang menikmati berbagai komik dan novel mata-mata. Perubahan nilai itu lebih dirangsang lagi oleh semakin menguatnya dunia pariwisata. Jadilah dunia merupakan gado-gado yang berlainan dengan versi yang selama ini dianut. Sebenamya pemberontakan kultural itu dalam beberapa hal seringkali justru dapat mengatasi pembatasan terhadap tingginya ekspresi kesenian yang dibuat pada masa sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam perjalanan ludruk, yang menggunakan para pemain pria untuk memainkan peran sebagai wanita. Contoh paling tepat dalam hal ini adalah Tessy dalam pagelaran yang dipertunjukkan oleh perkumpulan Srimulat. Ini jelas adalah pembelokan peran, yang di tempat lain dimainkan oleh wanita sendiri. Sebab karena kuatnya pengaruh agama yang tidak memperkenankan pemain wanita muncul di atas panggung, pada waktu itu. Sekarang, setelah munculnya wanita menjadi biasa di atas panggung, maka pemberontakan budaya sebenamya sudah tidak perlu lagi. Namun, karena hal itu telah dibiasakan oleh publik yang menikmatinya, maka kebutuhan untuk itu lalu menjadi sesuatu yang khas. Pemberontakan lalu menjadi kemapanan. Halnya sama dengan lagu dangdut. Ia bermula dari respon terhadap lagu pop, yang kemudian dengan perbaikan terus-menerus akhimya menjadi sesuatu yang umum dan bisa bermutu tinggi. Upaya manusia yang bemama Rhoma Irama sangat menentukan dalam hal ini. Tentu saja perlawanan kultural tidak selamanya dapat menghasilkan mutu tinggi dalam produk-produk yang ditawarkan pada publik. Kekurangan yang sekarang dirasakan oleh sejumlah penyanyi dangdut, dengan, dapat dilihat sebagai upaya untuk menampilkan substitusi (penggantian) melalui goyangan-goyangan erotis, kaibat ketidakmampuan menyajikan persembahan lagu dangdut bermutu tinggi. Maka terjadilah pemberontakan dalam pemberontakan, yang lahir dari ketidakmampuan memberikan persembahan bermutu tinggi. Jika dilihat dari sudut pandang ini, maka telah terjadi kesenjangan kultural di lingkungan lagu-lagu dangdut juga, padahal ia tadinya adalah pemberontak kultural terhadap kemapanan lagu-lagu pop dan seriosa. Kemapanan kultural yang dialami oleh lagulagu dangdut itu adalah perjalanan yang lumrah di bidang budaya. Tak ada yang perlu ditangisi, dan tidak pula diperlukan upaya khusus untuk menolong perkembangan sebuah bentuk budaya. ***** Justru hal-hal lumrah tersebut yang kini memerlukan perhatian khusus dari para perancang budaya. Lalu-lagu keroncong dan pagelaran musik daerah (seperti gamelan) justru harus dipikirkan eksistensinya. Jika tak ada pagelaran wayang, tentu musik gamelan sudah lenyap dari budaya Jawa. Begitu juga keroncong, yang sekarang sudah menjadi sesuatu yang kuno dalam pandangan publik. Film-film dengan ceritera-ceritera yang menampilkan kekerasan dan kejantanan fisik, kini
boleh dikata sudah menjadi umum, sedangkan ceritera-ceritera yang dahulunya dianggap umum, sekarang sudah menjadi langka. Walaupun dahulu tokoh-tokoh keras seperti Alan Ladd, Burt Lancaster dan Gary Cooper menampilkan sosok tubuh koboy jagoan, namun dalam peragaan mereka tidak diperlihatkan secara spesifik penggunaan kekerasan secara berlebihan. Namun sekarang, figur biasa justru menggelar tindak-tindak kekerasan yang berlebih-lebihan. Jadi, kita melihat bahwa perlawanan kultural terhadap kemapanan yang ada, mengambil bentuk yang sangat mengerikan bagi para pendidik atau orang tua yang konvensional, karena terasa sekarang ini telah terjadi perkembangan baru: penggunaan erotisme dan kekerasan secara berlebih-lebihan. Sampai dimanakah perkembangan nilai-nilai baru itu akan berlangsung, belum ada orang yang mampu memetakan landscape-nya dengan baik, seperti yang dilakukan Gasett di atas. Inilah sebabnya mengapa mereka yang merasa prihatin atas nilai-nilai seksual dan kekerasan yang baru, akhimya menggunakan bahasa defensive (bertahan) melalui khotbah agama dan penjelasan moral seperti banyak terjadi dewasa ini. Bahwa tempat-tempat peribadatan menjadi ajang dialog mengenai kepatutan seni dan budaya, menunjukkan dengan jelas adanya krisis budaya tersebut. Ini berarti terjadinya disfungsi (salah-peran) yang harus dikembalikan ke jalan yang benar. Tentu saja ini hal hal mudah untuk dikatakan, namun sulit dilaksanakan, bukan? Dicari: Keunggulan Budaya Oleh:
Abdurrahman
Wahid*
Ada sebuah prinsip yang selalu dikumandangkan oleh mereka yang meneriakkan kebesaran Islam: Islam itu unggul, dan tidak dapat diungguli (Al-Islam Yaiu wala Yula Alahi). Dengan pemahaman mereka sendiri, lalu mereka menolak apa yang dianggap sebagai kekerdilan Islam dan kejayaan orang lain. Mereka lalu menolak peradaban-peradaban lain dan menyerukan sikap mengunggulkan Islam secara doktriner. Pendekatan doktriner seperti itu berarti pemujaan Islam terhadap keunggulan teknis peradaban-peradaban lain. Dari sinilah lahir semacam klaim kebesaran Islam dan kerendahan peradaban lain, karena memandang Islam secara berlebihan dan memandang peradaban lain lebih rendah. Dari keangkuhan budaya seperti itu, lahirlah sikap otoriter yang hanya membenarkan diri sendiri dan menggangap orang atau peradaban lain sebagai yang bersalah atas kemunduran peradaban lain. Akibat dari pandangan itu, segala macam cara dapat dipergunakan kaum muslim untuk mempertahankan keunggulan Islam. Kemudian lahir semacam sikap yang melihat kekerasaan sebagai satu-satunya cara mempertahankan Islam. Dan lahirlah terorisme dan sikap radikal demi kepentingan Islam. Mereka tidak mengenal ketentuan hukum Islam/ Fiqh, bahwa orang Islam diperkenankan menggunakan kekerasan hanya jika diusir dari kediaman mereka (Idza ukhriju min diyarihim). Selain alasan tersebut itu tidak diperkenankan menggunakan kekerasan terhadap siapa pun, walau atas dasar keunggulan pandangan Islam. Sesuai dengan ungkapan di atas maka jelas mereka salah
memahami Islam, yang dipahami bahwa kaum Muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan atas kaum lain. Inilah yang dimaksudkan oleh kitab suci Al-Quran dengan ungkapan Tiap kelompok bersikap bangga atas milik sendiri (Kullu hizbin bima ladaihim farihun). Kalau sikap itu dicerca oleh Al-Quran sendiri, berarti juga dicerca oleh Rasul-Nya. ***** Jelaslah sikap Islam dalam hal ini, tidak menggangap rendah peradaban orang lain. Bahkan Islam mengajukan untuk mencari keunggulan dari orang lain sebagai bagian dari pengembangannya. Untuk mencapai keunggulan itu Nabi bersabda carilah Ilmu hingga ke tanah Tiongkok (Utlubu al-ilma walau fi al-shin), bukankah hingga saat ini pun ilmu-ilmu kajian keagamaan Islam telah berkembang luas di kawasan tersebut? Dengan demikian, Nabi mengharuskan kita mencarinya ke mana-mana. Ini berarti kita tidak boleh apriori terhadap siapa pun, karena ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang terdapat di mana-mana. Bahkan teknologi maju adalah hasil ikutan (spend off) dari teknologi ruang angkasa yang dirintis dan dibuat di bumi ini. Dengan demikian, teknologi antariksa juga menghasilkan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Pengertian longgar seperi inilah yang dikehendaki kitab suci Al-Quran dan Al-Hadist. Lalu adakah kelebihan teknis orang-orang lain atas kaum Muslimin dapat dianggap sebagai kekalahan umat Islam? Tidak, karena awal perbuatan kaum muslimin yang ikhlas kepada agama mereka memiliki sebuah nilai lebih dalam pandangan Islam. Hal itu dinyatakan sendiri oleh Al-Quran: Dan orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama, tak akan diterima amal perbuatannya di akhirat. Dan ia adalah orang yang merugi (Wa man yabtaghi qhaira Al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin). Dari kitab suci ini dapat diartikan Allah tidak akan menerima amal perbuatan seseorang non-Muslim, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh memandang rendah kerja siapa pun. Sebenamya pengertian kata diterima di akhirat berkaitan dengan keyakinan agama dan dengan demikian memiliki kualitas tersendiri. Sedangkan pada tataran duniawi perbuatan itu tidak tersangkut dengan keyakinan agama, melainkan secara teknis membawa manfaat bagi manusia lain. Jadi manfaat secara teknis dari setiap perbuatan dilepaskan oleh Islam dari keyakinan agama dan sesuatu yang secara teknis memiliki kegunaan bagi manusia diakui oleh Islam. Namun, dimensi penerimaan dari sudut keyakinan agama memiliki nilainya sendiri. PengIslamnya perbuatan kita justru tidak tergantung dari nilai perbuatan teknis semata, karena antara dunia dan akhirat memiliki dua dimensi yang berbeda satu dari yang lain. ***** Dengan demikian, jelas peradaban Islam memiliki keunggulan budaya dari sudut pengelihatan Islam sendiri, karena ada kaitannya dengan keyakinan keagamaan. Kita diharuskan mengembangkan dua sikap hidup yang berlainan. Di satu pihak, kaum muslimin harus mengusahakan agar supaya Islam- -sebagai agama langit yang terakhir tidak tertinggal, minimal secara teoritik. Tetapi di pihak lain kaum
Muslimin diingatkan untuk melihat juga dimensi keyakinan agama dalam menilai hasil budaya sendiri. Dengan demikian keunggulan atau ketertinggalan budaya Islam tidak terkait dengan penguasaan kekuatan politis, melainkan dari kemampuan budaya sebuah masyarakat Muslim untuk memelihara kekuatan pendorong ke arah kemajuan, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, kita tidak perlu berkecil hati melihat kelebihan orang lain, karena hal itu hanya akibat belaka dari kemampuan budaya untuk mendorong munculnya hal-hal yang bersifat teknis seperti dikemukakan di atas. Ini juga berarti penolakan Islam atas tindak kekerasan untuk mengejar ketertinggalan teknis tadi. Walaupun kita menggunakan kekerasan berlipat-lipat kalau memang secara budaya kita tidak memiliki pendorong ke arah kemajuan, kaum Muslimin akan tetap tertinggal di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sinilah letak penting dari apa yang oleh Samuel Hutington di sebut sebagai pembenturan budaya (clash of civilizations) perbenturan ini secara positif harus dilihat sebagai perlombaan antar budaya, jadi bukanlah sesuatu yang harus dihindari. ***** Beberapa tahun lalu penulis diminta oleh Yomiuri Shinbun, harian berbahasa Jepang terbitan Tokyo dan terbesar di dunia dengan oplah 11 juta lembar tiap hari, untuk berdiskusi dengan Profesor Huntington, bersama-sama dengan Chan Heng Chee (dulu Direktur Lembaga Kajian Asia-Tenggara di Singapura dan sekarang Dubes negeri itu untuk Amerika Serikat) dan Profesor Aoki dari Universitas Osaka. Dalam diskusi di Tokyo itu, penulis menyatakan kenyataan yang terjadi justru bertentangan dengan teori perbenturan budaya yang dikemukakan Huntington. Justru sebaliknya ratusan ribu warga Muslimin dari seluruh dunia belajar ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri-negeri barat tiap tahunnya, yang berarti di kedua bidang itu kaum Muslim saat ini tengah mengadopsi (mengambil) dari budaya barat.
Nah, keyakinan agama Islam mengarahkan mereka agar menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mereka kembangkan dari negeri-negeri barat untuk kepentingan kemanusiaan, bukannya untuk kepentingan diri sendiri. Pada waktunya nanti, sikap ini akan melahirkan kelebihan budaya Islam yang mungkin tidak dimiliki orang lain, kebudayaan yang tetap berorientasi melestarikan perikemanusiaan, dan tetap melanjutkan misi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Kalau perlu harus kita tambahkan pelestarian akhlak yang sekarang merupakan kesulitan terbesar yang dihadapi umat manusia di masa depan, seperti terbukti dengan penyebaran AIDS di seluruh dunia (termasuk di negeri-negeri Muslim). Mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan.
Dimensi Kehalusan Budi dan Rasa Oleh Abdurrahman
Wahid
Di tengah kecenderungan memanasnya suhu politik, terutama menjelang dilaksanakannya Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998 ada baiknya kita menengok salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting namun sering kali diabaikan, yakni unsur kehalusan budi dan rasa. Kalau kita hanya terlalu banyak memberikan perhatian kepada dimensi keyakinan dan kebenaran, maka kehidupan kita akan terasa kering. Kehidupan akan menjadi sangat ideologis, sangat formal, dan sangat sarat dilingkupi oleh aturan-aturan. Padahal tidak tertutup kemungkinan aturan-aturan itu justru akan menjerat manusia dalam pola kehidupan menghadapkan satu dengan yang lain. Apabila manusia terlalu banyak memberikan tempat kepada rasio, kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kepada sikap memperhitungkan segala sesuatu an sich, maka dengan sendirinya manusia juga akan mengalami kekeringan batin. Manusia akan mengalami kegalauan perasaan. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi pada analisis para pakar terakhir temyata tidak mampu memecahkan segala masalah yang ada. Bahkan kemungkinan ia menjadi tambahan masalah yang baru. Setiap kali kita menemukan penemuan ilmiah yang baru, muncul pula dampak negatifnya bagi kehidupan manusia. Penemuan plastik, misalnya, semula sangat menggembirakan, karena mampu memberi fungsi yang lebih efektif, ringan, dan murah. Tetapi temyata ujung-ujungnya mendatangkan malapetaka. Antara lain dapat menjadi penyebab tersumbatnya saluran-saluran air dan pada akhimya menjadi penyebab banjir di kota-kota. Terakhir, teknologi kloning, dari segi iptek merupakan penemuan luar biasa, tapi temyata sekarang mendatangkan kecemasan jika diterapkan pada manusia. Maka jika kita hanya berbangga-bangga dengan iptek semata, kita akan kehilangan dimensi kehidupan yang paling berharga,yakni adanya pengertian dalam keseimbangan hidup. Kehidupan akan timpang manakala kita mengabaikan kehalusan budi dan rasa, jika kita mengabaikan apresiasi yang benar terhadap kehidupan. Sekalipun terkadang apresiasi itu tidak sejalan dengan ideologi dan keyakinan rohani. Sebagai contoh, seorang sahabat saya, K.H. Mustofa Bisri memberi nama mushalla di belakang rumahnya dengan Pasujudan. Nama itu diprotes dan diributkan orang. Gus Mus dianggap terlalu kejawen dan abangan. Padahal yang dilakukannya adalah dengan kehalusan rasa ingin mencari makna kata lain yang lebih halus dan mushalla, yakni pasujudan, yang berarti bersujud kepada Allah SWT, meletakkan muka di lantai dengan menelungkupkan badan, dan merasakan diri sebagai makhluk yang paling hina di hadapan kemahakuasaan Allah SWT. Mereka yang memprotes sebenamya dilatarbelakangi oleh minimnya rasa halus yang mereka miliki. Mereka hanya berpegang pada aturan-aturan dan kelaziman-kelaziman. Di sinilah arti penting rasa halus. Jika kita tidak memiliki kehalusan rasa terlalu gampang terlanda kesalahpahaman. Satu contoh lagi, sekitar sepuluh tahun lalu saya merasakan kehalusan, getaran yang sangat dalam dan luar biasa, yaitu saat Muslimat NU mengadakan rapat kerja
nasional di Tegal, Jawa Tengah. Pada pembukaan rakemas itu tampil ibu-ibu Muslimat dengan pakaian hijau-hijau muda, tampak asri dan anggun. Bayangan saya seperti biasanya mereka akan mengalunkan Shalawat Badr. Tetapi yang terjadi ibu-ibu itu melantunkan tembang Jawa Ilir-ilir. Apa yang dilakukan Muslimat itu di luar tradisi NU, namun memberikan kesejukan yang luar biasa. Bukan hanya pada saya, tetapi pada ibu Menteri Urusan Peranan Wanita dan Gubemur Jawa Tengah pada waktu itu. Di sinilah kita mendapati hal-hal yang halus merupakan sesuatu yang esensial dari kehidupan kita. Temyata kehidupan itu memerlukan dimensi-dimensi yang lain. Kehidupan kita juga tidak hanya diarahkan oleh kepastian-kepastian kebenaran ideologis, kebenaran yang formal. Kita temyata juga memerlukan ketidakpastian, kebimbangan, kegalauan, dan kesenduan. Dalam sebuah novel berbahasa Prancis dalam bahasa Indonesia berjudul Gerbang yang Tertutup dikisahkan seorang gadis bemama Allisa. Dia mencintai sepupunya. Kegalauan gadis Allisa terombangambing oleh rasa dnta, rasa takut, dan rasa bimbang, yang akhimya justru menghaluskan perasaannya. Membawa diri kepada kesadaran bahwa di balik semua itu yang mengacaukan, membingungkan, dan menggalaukan, tampak yang abadi, yaitu Tuhan. Karena itulah hanya orang-orang yang mendapati kebesaran Tuhan dalam konteks ini, maka bagi merekalah jalan untuk membuka gerbang yang tertutup itu menjadi sangat luas. Sedemikian besar pengaruh ketokohan dan sosok Allisa dalam diri saya, sehingga nama itu saya berikan untuk putri pertama saya. Dari sini kita dapat memahami seni dan budaya berfungsi agar hidup kita tidak terlalu serba pasti dan tidak serba benar. Dokter Idealis, Kiai Formalis Oleh: Abdurrahman
Wahid
Prototipe dokter masa lampau adalah seorang idealis. Pekerja social yang mengabdi kepada kemanusiaan. Tiang susila masyarakat. Tidak hanya menyembuhkan orang sakit, tetapi juga memimpin masyarakatnya. Tidak hanya menyehatkan manusia di segi fisik, tetapi juga mengobati situasi kejiwaan masyarakatnya. Tidak heran kalau dari kelompok itu lahir pejuang-pejuang yang tangguh, seperti dokter Soetomo. Pantas pula kalau profesi dokter idam-idaman tertinggi para remaja kita hingga belasan tahun yang lalu. Kini keadaan sudah berubah. Banyak dokter yang lebih memikirkan mencari kekayaan secepat mungkin melalui praktek medis dan melalaikan aspek kemanusiaan. Sikap pribadi mereka juga terlihat dalam sikap rumah-rumah sakit tempat mereka bekerja. Ada yang tega menolak pasien yang sudah gawat hanya karena tidak mampu membayar uang muka biaya perawatan sepuluh hari sekaligus. "Perjuangan" dokter-dokter yang baru lulus ke puskesmas punya motif pemerataan pelayanan kesehatan. Di samping itu, juga membawa sebuah hasil positif: para dokter muda terpaksa menumbuhkan orientasi pengabdian, minimal kalau mereka mau mengerti. Walaupun tidak semua memiliki sikap mental seperti itu, bagi
kebanyakan dokter muda bekas mendalam terasa di hati dari "masa pembuangan" itu. Memang masih ada juga yang sudah mulai sombong dan main bentak pasien di beberapa puskesmas, apalagi yang terletak di pedesaan. Seolah para pasien orang kecil itu, yang sering hanya bisa menghargai kerja dokter dengan imbalan in natura, harus dijadikan sasaran kekesalan hati menjalani "masa pembuangan" di tempat terpencil. Apalagi kalau sampai akhir "masa pembuangan" tetap belum terbayang tempat penempatan yang "gemuk pasien". Untunglah, tidak semua dokter bersikap seperti itu. Dan kepuasan yang diperoleh para dokter jenis ini bersifat rohaniah: berhasil menunuaikan pengabdian dan menunjukkan kebolehan profesional, sering menghadapi tantangan penyakit berat yang harus diatasi dengan obat-obatan sangat minim dan peralatan yang tidak mencukupi. Tetapi, justru para dokter muda idealis itulah yang sering harus menjumpai kepahitan setelah kembali ke "dunia normal". Di rumah sakit metropolitan, misalnya, dengan kehidupan serbamaterialistis dan berorientasi sangat finansial, belum lagi kalau "dilengkapi" situasi birokratis yang memuakkan. Juga di rumah sakit di kota kecil, menjadi "dokabu" alias dokter kabupaten yang kepala dinasnya sering menuntut diperlakukan sebagai dewa. Birokrasi memiliki hukumnya sendiriterutama kejelusan antarlembaga dan kekakuan sikap institusional. Kalau sudah dijatahkan, hal ini atau itu harus dilakukan, tidak boleh ada penyimpangan sedikitpun. Tidak peduli keadaanmedan yang dihadapi atau manusia yang harus rugi. Pembagian wilayah kerja antara berbagai lembaga yang menimbulkan pengkotakannya sendiri, dengan akibat dengki atau iri sebuah lembaga pemerintah jika lembaga lain "menjarah" wilayahnya. Seorang dokter muda di sebuah kota kecil di pantai utara Jawa, misalnya. Pikiranpikirannya yang jemih tidak memperoleh sambutan positif dari semua koleganya, apalagi atasan. Sikap ugal-ugalannya juga membuat dicurigai jajaran pemerintah daerah. Jelas sekali, promosi tidak akan diperolehnya, kenaikan gaji berkala tidak akan datang dengan sendirinya, dan konduite kepegawaiannya akan terus menurun. Sehingga nanti tinggal dicari alasan tepat untuk membuangnya ke daerah lain. Pada tumpukan prospek gelap itu, ia masih harus terbentur pada kasus tambahan ini: sikap seorang kiai tarekat yang kukuh pada sikap hidupnya. Anaknya menderita penyakit paru-paru, akibat pecahan bibir atassejak lahirhingga ke rongga hidung. Udara tidak tersaring lagi. Dengan demikian, segala gengguan paru-paru dapat terjadi dengan mudah. Kesimpulannya, belahan bibir atas harus ditutup dengan transplantasi kulit. Kesulitan bermula: sang kiai berkeberatan kalau diambilkan kulit orang lain. Bagaimana pertanggungjawaban di akhirat kelak, memakai hak milik yang ditentukan Allah bagi orang lain? Dijawab: justru harus diambilkan dari kulit sendiri, menjadi persoalan pula. Darimana? Dokter
menyatakan, dari pantat. Sang kiai menjawab, tidak mungkin. Kulit pantat adalah bagian aurat seseorang. Berarti harus ditutup kalau akan bersembahyang Apa harus menggunakan tutup muka seperti Zorro? Dokter menjawab, kulit menjadi aurat hanya ketika berada di bagian yang dinamakan aurat. Begitu dipindahkan, ia sudah bukan aurat lagi. Sang Kiai, yang setia pada metode berpikir normal legalitasnya, belum puas. Kalau "anu"nya seorang pria dipasang di mukanya dan temyata bias bergerak kalau ada rangsangan, apakah juga bukan aurat? Sang dokter terpana. Ada birokrasi. Ada kesemrawutan pencanangan pembangunan di tingkat daerah. Dan sekarang, dengan hanya satu contoh formalisme, akan lunturkan idealismenya?
Dunia Nyata Kiai Zainal Oleh
Abdurrahman
Wahid
Wajahnya mencerminkan kekerasan hati, kesan yang timbul dari tekukan rahangnya yang tampak sangat nyata. Mirip wajah Jack Palance yang sedang menggertakkan gigi menghadapi Alan Ladd dalam film Shane dari masa dua puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada sedikit kesan kebengisan pada wajahnya itu, tetapi yang bercampur dengan ketampanan yang masih tersisa dari masa mudanya. Wajah keren dari masa muda itu kini membayangkan kewibawaan di masa tua. Tindak tanduknya (dedeg, kata orang Jawa) mencerminkan, juga hati yang penuh ketetapan pendirian, ucapannya menunjukkan keyakinan pendapat, dan caranya mengemukakan pendiriannya juga lugas penuh kepercayaan kepada diri sendiri. Bagaikan eksekutif dinamis masa kini yang temyata tidak memerlukan Brisk dan tidak butuh Supradin serta berbagai jenis deodorant untuk menjaga kepercayaan diri itu. Penampilan bagaikan eksekutif temyata hanya terhenti pada raut wajah dan kesan yang ditimbulkannya belaka, karena Kiai Zainal Abidin Usman membawa penampilan lain pada sisa tubuhnya: kain sarung polekat yang sudah berumur lama,baju panjang abu-abu dengan sebuah kancing yang hampir lepas,sandal plastik yang begitu murah harganya sehingga tidak akan dicuri orang dari halaman masjid atau langgar, dan seterusnya. Pendeknya, penampilan utuh dari seorang kiai 'di tingkat lokal'. Kesemua manifestasi lahiriyah di atas merupakan hasil dari hidup Kiai Zainal yang penuh kesukaran. Harus mengikuti pola belajar yang penuh disiplin dan sanksi fisik (termasuk dilecut) kalau tidak menunjukkan 'jatah' hafalan yang sudah ditetapkan sang guru semenjak usia sangat muda, enam tahun.Tidak diperkenankan menikmati masa muda yang penuh kesenangan inderawi, melainkan harus
mengikuti pola hidup yang diselaraskan dengan hukum-hukum fiqh dan tata cara belajar (adabut ta'allum) yang diletakkan kitab-kitab kuno agama. Lebih jauh lagi, ia kemudian harus belajar lama di Mekkah: jauh dari sanak saudara, sering dihadapkan dengan kekurangan belanja 'kebutuhan pokok', dan harus banyak menjalani tirakat untuk memperoleh ilmu-ilmu agama yang diharapkan. Tidak heran jika seandainya Kiai Zainal kemudian mengembangkan kepribadian yang 'berlajur tunggal', di mana dominasi hukum agama dan bentuknya yang paling kaku dan 'harfiah' atas pandangan hidupnya. Orang tidak akan tercengang kalau Kiai Zainal kemudian menumbuhkan sikap untuk menerapkan hukum agama secara apa adanya, secara apa yang tertulis dalam kitab-kitab fiqih kuno. Bukankah semua kiai yang berpola pendidikan dan kemudian pola hidup seperti Kiai Zainal juga berbuat demikian? Pantaslah kalau Kiai Zainal juga diperkirakan akan mengikuti 'jalur umum ke-kiai-an' seperti itu. Temyata tidak demikian kenyataannya. Kiai Zainal temyata menumbuhkan pola berpikir yang lain, mengembangkan pandangan hidup dari 'jalur umum' di atas. la mengikuti 'jalur umum' hanya pada pola hidup lahiriyahnya sebagai kiai belaka, seperti digambarkan pada penampilan fisik di atas. la temyata melakukan dialog dengan kenyataan-kenyataan hidup yang dihadapinya yang sering kali jauh berbeda dari kondisi ideal yang melahirkan hukum-hukum agama yang dikodifikasikan dalam kitab-kitab fiqh kuno. la melakukan peninjauan kembali atas hukum-hukum agama itu, walaupun dengan caranya sendiri dan melalui pendekatan persoalan yang dirumuskannya sendiri. Perbedaan dari 'jalur umum ke-kiai-an' itu tampak nyata dalam sebuah forum penataran mubaligh dan khatib baru-baru ini, ketika berlangsung debat tentang penyelenggaraan zakat. Kalau zakat ingin diterapkan secara organisatoris dan dikembangkan melalui perluasan jenis-jenis 'wajib zakat', sehingga meliputi upah, honorarium dan gaji tetap dari bermacam-macam profesi,tentu ada kesulitan. Mazhab-mazhab fiqh sudah menentukan kategori kewajiban zakat hanya jatuh pada keuntungan berdagang, basil panenan tanaman utama (padi dan sebagainya), harta benda tetap, dan logam mulia emas perak. Lainnya tidak terkena zakat. Lalu bagaimana mungkin gaji tetap, honorarium dan upah dikenakan zakat? Belum lagi pelaksanaannya, yang dikehendaki sementara pihak harus diorganisasi secara efisien dan administratif. Diberikannya pun juga harus dalam bentuk tidak melulu konsumtif, melainkan dalam bentuk pinjaman dan pemberian alat, Belum lagi kalau dijadikan biaya penataran dan latihan-latihan keterampilan. Apakah tidak menyalahi ajaran-ajaran mazhab-mazhab fiqh? Persoalannya bukan demikian, kata Kiai Zainal berapi-api. Apa yang dirumuskan kitab-kitab fiqh itu 'kan hanya dalam negara Islam saja dapat diterapkan sepenuhnya! Di zaman Rasulullah ada sanksi kalau orang tidak menyerahkan zakat
karena yang dipergunakan adalah perundang-undangan Islam secara total. Jadi tidak perlu ada panitia zakat dan lain-lain kelengkapan administratif lagi. Negara bertanggungjawab atas kesejahteraan masing-masing warga negara, jadi tidak usah kita berpayah-payah mencari dana untuk melatih orang bekerja atau membeikan modal kerja kepadanya. Tetapi kita 'kan tidak hidup dalam negara Islam, karena itu kondisi yang dihadapi pula berlainan. Kalau tidak ada sanksi otomatis bagi orang yang enggan menyerahkan zakat, apakah justru tidak diperlukan panitia zakat yang akan menyelenggarakannya ? Kalau kaum Muslim masih lemah ekonominya, apakah seluruh perolehan zakat harus dihabiskan sekaligus secara konsumtif dan tidak digunakan sebagian untuk kepentingan produktif? Kalau kita ingin mengembangkan zakat itu sendiri secara kuantitatif, apakah justru tidak perlu diciptakan wajib zakat baru? Temyata dibalik bentuk lahiriyah yang kuno, Kiai Zainal memilliki daya tanggap yang cukup relevan dengan kebutuhan masa dan keadaan ummatnya. Patutlah kalau ia dianggap berorientasi kepada dunia nyata. Tetapi patut juga dipertanyakan anggapan bahwa ia menyimpang dari 'jalur umum ke-kiai -an' dalam orientasinya kepada dunia nyata ini.Mengingat bahwa ia dibenarkan dan tidak ditentang oleh kiai-kiai lain, apakah bukannya sebaliknya yang terjadi? Bukan tidak mungkin bahwa justu orientasi 'jalur umum ke-kiai-an' memang ditunjukan kepada dunia nyata, di kala mereka harus melakukan peninjauan kepada hukum-hukum agama yang ada dalam kitab-kitab fiqh kuno. Fundamentelisme Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kata fundamentalisme sebenamya telah berkembang dan artinya semula. Berangkat dan pengertian Kristen, ia berhenti pada pengertian untuk semua agama. Dalam pengertian semula, kata itu berarti gerakan-gerakan yang menunjukkan fanatisme agama dan militansi terhadap ajaran-ajaran kitab suci. Kalau kaum Kristen mengatur kehidupan mereka berdasarkan fundamen-fundamen (dasar-dasar) yang disebutkan dalam Kitab Suci, maka jadinya adalah kaum yang lemah. Bukankah mereka yang memberikan pipi kanan kalau dipukul pipi kiri, mereka adalah kaum lemah secara rasional? Karenanya, mereka yang tidak setuju dengan semua yang dirumuskan kitab suci, lalu mencari fundamen-fundamen agama. Lahirlah apa yang dinamakan fundamentalisme agama, yaitu pencarian prinsipprinsip yang mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama dalam pandangan mereka. Ini, harus dibedakan dan keinginan untuk mendasarkan kehidupan secara inspiratif dalam, kehidupan bermasyarakat. Dari ajaran-ajaran formal agama, dicari prinsip-prinsip pengaturan kehidupan bermasyarakat, bukan dari pengertian harafiahnya.
Dari uraian di atas jelaslah bahwa dengan pendirian inspiratif seperti yang dimaksudkan tadi, merupakan pencarian prinsip-prinsip pengaturan hidup masyarakat dari agama yang dipeluk seseorang. Jadi, bukanlah dengan mengemukakan dalil-dalil formal agama melalui kutipan kitab-kitab suci. Nah, dari pengertian fundamentalisme seperti inilah arti kata itu digunakan bagi agamaagama lain. Maka, lahirlah kata fundamentalisme Islam yang berarti pemahaman kata tersebut secara harafiah dari Kitab Suci Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Karenanya, istilah tersebut menimbulkan ketakutan yang sangat pada fenomena penerapan hukum Islam secara harafiah. Seolah-olah dengan demikian, setiap tindakan menegakkan semangat Islam adalah penerapan hukum agama secara formal. Tidaklah terlihat adanya kemungkinan lain bagi fundamentalisme Islam. Karenanya, istilah itu menjadi kata kotor dalam mengenali Islam sebagai proses kemasyarakatan. Bulu kuduk kita berdiri setiap kali mendengar istilah tersebut, tanpa ada kemungkinan memahaminya secara lain. Dalam sebuah pertemuan antara Pengurus Besar Nahdiatui Ulama (PBNU) dan Ketua UNICEF (Dana Darurat PBB untuk Anak-Anak), kepala perwakilannya yang ada di sini, membawa serta seorang bekas Menteri Perhubungan Ethiopia. Dikatakan bekas, karena ia baru saja berhenti dari kabinet dan kini tinggal di London. Mengapakah ia pilih mengungsi di negara lain? Karena ada masalah pribadi yang bisa membuatnya "mati". Penduduk Ethiopia 55 persen beragama Islam. Dengan demikian, ia dimasukkan dalani kabinet pada waktu itu guna mewakili kelompok yang besar, walaupun mayoritas muslim itu tidak diakui oleh dunia politik Ethiopia, la bersedia duduk di kabinet, walaupun di luamya ada pihak garis keras yang menolak hal itu. Mereka justru menuntut agar Ethiopia diperintah oleh kabinet yang mencerminkan keadaan kaum muslimin sebagai kaum mayoritas. Karena menteri yang satu ini justru tidak mengindahkan tuntutan ini, maka ia lalu diserang sebagai pihak yang mengacaukan tuntutan. Karena itu, ia pemah diserang sebanyak tujuh kali upaya pembunuhan, yang kesemuanya berasal dari gerakan Islam berhaluan keras. Bukankah hal itu berarti ada orang Islam yang tunduk pada kekuasaan kaum bukan muslimin, yang berarti penyimpangan dari Alqur'an? Karenanya, bukankah orang yang demikian wajib dibunuh? Bukankah kabinet Ethiopia sekarang yang dipimpin presiden tidak beragama Islam, termasuk dala apa yang dimaksudkan Al-qur'an itu? Maka alangkah terkejutnya para anggota PBNU yang hadir dalam pertemuan itu ketika sang bekas menteri itu menjawab pertanyaan termasuk golongan apakah ia? "Saya adalah termasuk fundamentalisme muslim". Temyata istilah itu di Ethiopia mempunyai konotasi lain, yang berbeda dari pengertian yang biasa kita pahami. Dalam percakapan selanjutnya menjadi jelas, sang bekas menteri itu mempunyai pandangan keagamaan yang sama dengan
pendirian NU. Di negara orang berkulit hitam itu, kata "fundamentalisme Islam", berarti orang-orang yang berpegang pada makna inspiratif agama tersebut, yaitu kelonggaran pada pihak lain, selama prinsip-prinsip Islam dihargai oleh setiap orang. Dengan menggunakan istilah tersebut, sang bekas menteri bermaksud menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diambil dari inspirasi keagamaan adalah penentu kehidupannya. Sama dengan pemimpin Islam, sama dengan NU, yang menggunakan Islam dengan pengertian demikian dalam hidup ber-Pancasila di negeri ini. Bukankah dengan demikian, para pemimpin itu menggunakan fundamen-fundamen Islam dan bukannya kutipan-kutipan formalnya belaka? Bukankah dengan demikian, sang bekas menteri dari Ethiopia itu lebih mendekati pengertian harafiahnya dari kata "fundamentalisme Islam" daripada yang kita kenal selama ini? Lain kalau kita gunakan pengertian bekas menteri dari Ethiopia tersebut, apakah istilah yang lebih tepat untuk kaum perusuh yang memaksakan kehendak atas nama Islam di negeri mi? Jawabnya, mudah saja, kaum muslim radikal, atau istilah apa pun yang mengandung arti seperti itu.
Gus Miek: Wajah Sebuah Kerinduan Oleh Abdurrahman
Wahid
Tiga tahun lalu, di beranda sebuah surau di Tambak, desa Ploso, Kediri saya berhasil mengejamya. Mobil yang saya tumpangi menelusuri kota Kediri sebelum melihat mobil Gus Miek di sebuah gang, tengah meninggalkan tempat itu. Dalam kecepatan tinggi mobilnya menuju ke arah selatan dan hanya kami bayangi dari kejauhan. Setelah membelok ke barat dan kemudian ke utara melalui jalan paralel, akhimya mobil itu berhenti di depan surau tersebut. Gus Miek sudah meninggalkan mobilnya menuju ke surau itu, ketika mobil tumpangan saya sampai. la terkejut melihat kedatangan saya, karena dikiranya saya adalah adiknya, Gus Huda. Rupanya mobil tumpangan saya sama wama dan merek dengan mobil adiknya itu. Dari beranda itu ia menunjuk sebidang tanah yang baru saja disambungkan ke pekarangan surau dan berkata kepada saya, "Di situ nanti Kiai Achmad akan dimakamkan. Deinikian juga saya. Dan nantinya sampeyan. Dikatakan, tanah itu sengaja dibelinya untuk tempat penguburan para penghafal AI-Qur'an. Saya katakan kepadanya, bahwa saya bukan penghafal AI-Qur'an. Dijawabnya bahwa bagaimanapun saya harus dikuburkan di situ. Setahun kemudian, ketika KH Achmad Siddiq wafat, beliau pun di kuburkan di tempat itu atas permintaan Gus Miek. Baru saya sadari bahwa Kiai Achmad yang dimaksudkannya setahun sebelum itu adalah KH Achmad Siddiq. Hal-hal seperti inilah yang seringkali dijadikan bukti oleh orang banyak,bahwa KH Hamim Jazuli alias Gus Miek adalah seorang dengan kemampuan supematural. Sesuai dengan "tradisi" penyempitan makna lstilah,orang awam menyebutnya dengan istilah wali (Saint). Kemampuan supematural KH Hamiem alias Gus Miek itu, dalam istilah eskatologi orang pesantren, dinamakan khoriqul'adah, alias keanehan-keanehan. Dengan bennacam-macam keanehan yang dimilikinya, Gus Miek lalu memperoleh status orang keramat. Banyak "kesaktian" ditempelkan pada reputasinya. Mau banyak rezeki, harus memperoleh berkahnya. Ingin naik pangkat, harus didukung olehnya. Mau beribadah haji, harus dimakelarinya. Mau gampang jodoh, minta pasangan kepadanya. Dan demikian seterusnya. Reputasi sebagai orang keramat ini, dinilai sebagai pendorong mengapa banyak orang berbondong-bondong memadati acara keagamaan yang dilangsungkan oleh Gus Miek. Sema'an (bersama-sama mendengarkan bacaan AI-Qur'an oleh para penghafalnya) yang diselenggarakannya di mana-mana, selalu penuh sesak oleh rakyat banyak. Dari pagi orang bersabar mendengarkan bacaan AI-Qur'an, untuk mengamini doa yang dibacakan Gus Miek seusai menamatkan bacaan AI-Qur'an secara utuh, biasanya sekitar jam delapan malam. Bersabar mereka menanti sepanjang hari, untuk memperoleh siraman jiwa berupa mauizah hasanah (petuah yang baik) dari tokoh kiai kharismatik ini. Padahal, sepagian itu ia masih tidur, setelah begadang semalam suntuk. Itulah acara rutinnya, di mana pun ia berada. Baru belakangan orang menyadari, bahwa Gus Miek menempuh dua pola kehidupan sekaligus. Kehidupan tradisional orang pesantren, tertuang dalam
rutinitas semaan, dan gebyamya kehidupan dunia hiburan modem. Gebyar, karena dia selamanya berada di tengah diskotik, night club, coffee shop dan "arena persinggahan perkampungan" orang-orang tuna susila. Tidak tanggung-tanggung, ia akrab dengan seluruh penghuni dan aktor kehidupan tempat tersebut. Yang ditenggaknya adalah bir hitam, yang setiap malam ia nikmati berbotol-botol. Rokoknya Wismilak bungkus hitam, yang ramuannya diakui berat. Kontradiktif? Temyata tidak, karena di kedua tempat itu ia berperan sama. Memberi kesejukan kepada jiwa yang gersang, memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, menghibur mereka yang bersedih, menyantuni mereka yang lemah dan mengajak semua kepada kebaikan. Apakah itu peluah di pengajian sesuai semaan, sewaktu konsultasi pribadi dengan pejabat dan kaum elite lainnya, atau pun ketika meladeni bisikan kepedihan yang disampaikan dengan suara lirih ke telinganya oleh wanita-wanita penghibur, esensinya tetap sama. Manusia mempunyai potensi untuk memperbaiki keadaannya sendiri. Dua tahun yang lalu, Gus Miek mengatakan kepada saya, bahwa saya harus mundur dari NU. Saya baca hal itu sebagai himbauan, agar saya teruskan perjuangan menegakkan demokrasi di negeri kita, tetapi dengan tidak "merugikan" kepentingan organisasi yang saat ini sedang saya pimpin. Dikatakan, sebaiknya saya mengikuti jejaknya berkiprah secara individual melayani semua lapisan masyarakat. Saya tolak ajakan itu dua tahun yang lalu, karena saya beranggapan perjuangan melalui NU masih tetap aktif. Baru sekarang saya sadari, menjelang saat kepulangan Gus Miek ke haribaan Tuhan, bahwa ia membaca tanda zaman lebih jeli dari pada saya. Bahwa dengan "menggendong" beban NU, upaya menegakkan demokrasi tidak menjadi semakin mudah. Karena para pemimpin NU yang lain justru tidak ingin kemapanan yang ada diusik orang. Dari tokoh inilah saya belajar untuk membedakan apa yang menjadi pokok persoalan, dan apa yang sekadar ranting. Tetapi, Gus Miek juga hanyalah manusia biasa. Manusia yang memiliki kekuatan dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan. Keseimbangan hidupnya tidak bertahan lama oleh ketimpangan pendekatan yang diambilnya. la menjadi terlalu memperhatikan kepentingan orang-orang besar dan para pemimpin tingkat nasional. Ia juga tidak menjadi imun terhadap kenikmatan dunia hidup gebyar. Untuk beberapa bulan hubungan saya dengan Gus Miek secara batin menjadi sangat terganggu karena hal-hal itu. Saya menolak untuk mendukung jagonya untuk jabatan Wapres, dan ini membuat ia tidak enak perasan kepada saya. Mungkin, tidak dipahaminya keinginan saya agar agama tidak dimanipulasikan dengan politik negara. Tugas pemimpin agama adalah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dan berupaya agar kebenaran dapat ditegakkan. Sedang kebenaran itu akan terjelma melalui kedaulatan rakyat yang sesungguhnya, kedaulatan hukum, kebebasan dan persamaan perlakuan di muka undang-undang.
Tetapi, sejauh apa pun hubungan kami berdua, saya sendiri tetap rindu kepada Gus Miek. Bukan kepada gebyamya dunia hiburan. Tetapi bahwa kalau malam, menjelang pagi, ia tidur beralaskan kertas koran di rumah Pak Syafi'i Ampel di kota Surabaya, atau Pak Hamid di Kediri. Yang dimiliki Pak Hamid hanyalah sebuah kursi plastik jebol dan dua buah gelas serta teko logam. ltulah dunia Gus Miek yang sebenamya, yang ditinggalkannya untuk beberapa bulan mungkin hanya sebagai sebuah kelengkapan lakonnya yang panjang. Agar ia tetap masih menjadi manusia, bukan malaikat. Yang selalu saya kenang adalah kerinduannya kepada upaya perbaikan dalam diri manusia. Karena itu, ulama idolanya pun adalah yang membunyikan lonceng harapan dan genta kebaikan, bukan hardikan dan kemarahan kepada hal-hal yang buruk. Tiap 40 hari sekali ia mengaji di makam Kiai lhsanJampes, yang terletak di tepi Brantas di dukuh Mutih, pinggiran kota Kediri. la gandrung kepada Mbah Mesir yang dimakamkan di Trenggalek, pembawa tarekat Sadziliyah dua ratus tahun yang lalu ke Jawa Timur. Tarekat itu adalah tarekatnya orang kecil, dan membimbing rakyat awam yang penuh kehausan rasa kasih dan sapaan yang santun. Gus Miek inilah yang melalui transendensi keimanannya tidak lagi melihat "kesalahan" keyakinan orang beragama atau berkepercayaan lain. Ayu Wedayanti yang Hindu diperlakukannya sama dengan Neno Warisman yang muslimah, karena ia yakin kebaikan sama berada pada dua orang penyanyi tersebut. Banyak oring Katolik menjadi pendengar setia wejangan Gus Miek seusai semaan. Kerinduannya kepada realisasi potensi kebaikkan pada diri manusia inilah yang menurut saya supematural. Bukan karena ia menyalahi ketentuan bukum-hukum alam. Super karena ia mampu mengatasi segala macam jurang pemisah dan tembok penyekat antara sesama manusia. Natural, karena yang ia harapkan hanyalah kebaikan bagi manusia. Kalau ia dianggap nyleneh (khoriqul'adah) , maka dalam artian inilah ia harus dipahami demikian. Bukankah nyleneh, orang yang tidak peduli batasan agama, etnis dan profesi dan tidak hirau apa yang dinamakan baik dan buruk di mata kebanyakan manusia, sementara manusia saling menghancurkan dan membunuh? Haruskah Inul Diberangus? Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Semula penulis hanya tertawa saja mendengar nama Inul, wanita muda yang menjadi anggota Fatayat Nahdlatul Ulama di anak cabang (Ancab) Japanan, (Pasuruan), memang terdengar lucu. Antara lain karena istilah yang digunakan orang atas dirinya ngebor . Karena itulah penulis pemah mengatakan di muka umum bahwa salah satu jalan beraspal di kota Pasuruan berlubang-lubang karena sering dibor Inul. Bahkan sebelumnya, di muka ratusan ribu orang saat berceramah di Tuban pada upacara peringatan kewafatan (Haul) Sunan Bonang, di tengah-tengah hujan lebat penulis mengucapkan selamat kepada hadirin atas datangnya lebaran, haji tahun ini, dengan ucapan Selamat ber Inul Adha.
Gurauan itu berubah menjadi keheranan ketika Rois Syuriah NU cabang Pasuruan, melarang para warganya untuk tidak menyaksikan pagelaran Inul. Hal itu, di perkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan keputusan yang sama. Penulis heran, karena selama ini apa yang dilakukan Inul, masih jauh di bawah erotika berbagai goyangan orang lain. Mengapakah mereka nampaknya kita sibuk dengan urusan Inul? Sementara purapura tidak tahu atas berbagai pelanggaran hak azasi manusia di negeri ini, KKN yang semakin menghebat, lebih lebih jauh lagi pelanggaran konstitusi lainnya, dibiarkan saja oleh lembaga keagamaan itu. Sedangkan sikap sebaliknya diarahkan pada Inul dengan pagelarannya, yang tidak melanggar Undang-Undang apapun di negeri ini. Keheranan penulis itu berubah menjadi sesuatu yang lain, ketika sang teman sangat baik, H. Rhoma Irama melarang Inul untuk tidak mengelar hal-hal yang merusak moral bangsa. Dari ucapan-ucapannya melalui berbagai media kepada Inul, penulis mendapati sebuah sikap Bang Rhoma Irama, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita yaitu melarang Inul melakukan pagelaran. Betapa jauhnya sikap Bang Rhoma dengan penulis, sekalipun perasaan penulis hampir bersamaan dengan perasaan Bang Haji. Walaupun mengikuti perasaan, namun kita tidak boleh melanggar undang-undang, apalagi kalau memang temyata tidak undang-undang dilanggar Inul. Dan yang menyatakan pelanggaran inipun bukanlah kita sendiri sebagai warga masyarakat melainkan Mahkamah Agung. ***** Sebagai orang yang menghargai alasan berdirinya sebuah bangsa (raisson detre du nation), seperti ucapan seorang intelek Prancis yang dikutip Bung Kamo, kebhinekaan lah yang justru menjadi pegikat kita dalam membentuk bangsa Indonesia. Justru kebhinekaan atau pluralitas bangsa kita yang sangat tinggi itu merupakan kekayaan yang menghimpun, hingga menjadi sebuah wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi UUD 45 dan peraturan lah yang menjadi panutan kita, seperti diputuskan oleh Mahkamah Agung, dan bukanya pemimpin manapun dalam kehidupan bangsa kita. Ketika Mr. AA Maramis mengajukan keberataan atas Piagam Jakarta, karena akan mengakibatkan dua kelas warga negara di Indonesia (Muslim dan Non Muslim), maka para pendiri negara ini setuju seluruhnya untuk mengeluarkan piagam tersebut dari pembukaan UUD 45. Berarti kita bukan lagi negara agama negara Islam-, dan dengan demikian penafsiran Mahkamah Agung atas UUD 45 menjadi satu-satunya penafsiran legal atas hukum di negeri ini. Kalau pun ada warga negara tidak menyetujui suatu tindakan, maka tindakan yang diperbolehkan hanyalah mengajak kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal itu (amar maruf). Dengan kata lain melalui kesadaran masyarakat hal-hal seperti itu dapat dicegah bukannya melalui tindakan langsung perorangan.
Sama halnya ketika ada penilaian, apakah yang dilakukan para mahasiswa dengan berdemo di jalan Teuku Umar, dapat dianggap sebagai gangguan atas ketertiban umum? Penulis segera menyatakan reaksinya, bukannya Polri (termasuk Kapolri) yang berhak mengemukakan penilaian seperti itu, melainkan Mahkamah Agung. Dengan sistem hukum yang dijalankan seperti itu barulah seluruh warga negara bebas dari ketakutan terhadap aparat negara mereka sendiri. Kasus lainnya yaitu saat Kapolda Jateng menyatakan akan membubarkan Pesatren Al-Mukmin di Ngrungki Solo, segera penulis membuat pemyataan menolak hal itu. Karena negara tidak boleh campur tangan dalam masalah ajaran agama apapun, termasuk pembubaran sebuah pondok pesantren. Biarkan masyarakat saja melakukan hal itu, sesuai dengan ketentuan UUD 1945. ***** Karena keyakinan itulah penulis menolak tindakan apapun atas pagelaran Inul. Tentu saja penulis menghimbau secara pribadi kepada Inul agar menghilangkan gerakan-gerakan erotis dalam pagelaran tersebut, kalau memang sudah melewati batas moralitas. Menurut cerita teman-teman penulis sendiri, yang menyaksikan pagelaran tersebut, gerakan-gerakan ngebor Inul sendiri sudah cukup untuk mengikat penonton pemirsa-. Memang garis batas antara hal-hal erotis dan moralitas sangatlah samar, tetapi justru kita sendirilah yang harus pandai-pandai menjaga garis batas itu secara suka rela, karena reaksi masyarakat seperti apa yang dilakukan Bang Haji Rhoma Irama merupakan sirine (tanda peringatan) yang harus diperhatikan. Sikap tidak memperdulikan peringatan moral dari masyarakat, apabila diabaikan akan menyulut reaksi-reaksi dalam bentuk yang lain. Tentu saja kita tidak ingin hal itu terjadi, karenanya kita harus bersikap hati-hati tanpa melanggar ketentuanketentuan atau undang-undang. Namun begitu banyak KKN dan pelanggaran hukum yang dilakukan tanpa ada sanksi apapun, sehingga masyarakat tidak lagi percaya kepada sistem politik kita dewasa ini Sebuah sikap dewasa yang diterima masyarakat adalah kejujuran. Karenanya, kejujuran Inul untuk mengatakan ia melakukan pagelaran ngebor hanya untuk mencari makan tanpa embel-embel bohong seperti sok untuk memajukan seni dan sebagainya-, merupakan hal yang menyegarkan. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat itu, dengan menjaga agar batas-batas halus antara yang diperkenankan dan yang tidak hendaklah jangan dilanggar. Dengan menyatakan hal tadi, penulis ingin bersikap jujur, baik terhadap Inul maupun terhadap Bang Haji Rhoma Irama. Terlebih jelas lagi, penulis ingin bersikap jujur kepada masyarakat. Demikian pula ketika ketua panitia mukemas partai yang diikuti penulis menyatakan akan mengundang Inul dalam acara pembukaan forum tersebut, namun tanpa memintanya melakukan pagelaran, segera penulis menyetujui gagasan tersebut. Bukankah ia selebriti? Seperti selebriti lainnya yang diundang. Karena itu adalah tanggung jawab panitia, maka penulis tidak ikut campur tangan.
Hasil Sebuah Pendekatan Budaya Oleh: Abdurrahman
Wahid
Beberapa hari yang lalu, penulis berziarah ke makam Kebo Kanigoro dan Syekh Maulana Maghribi, di pantai dekat Ampel dan Sukoharjo. Ziarah itu untuk menunjukkan penghormatan kepada leluhur penulis, yang ia yakini dikubur di sana. Baik Kebo Kanigoro maupun Kebo Kenongo, menurut legenda adalah putra Brawijaya V di Majapahit. Setelah ia dongkolan (menjadi mantan) raja/prabu di Majapahit menurut legenda ia lalu menjadi Sunan Lawu. Kedua anak itu lalu dititipkannya kepada Ki Pengging Sepuh, yang menjadi panglima angkatan perang di bawah Sultan Trenggono dari Demak. Ki Pengging Sepuh itu adalah Habib Abdurrahman Al-Basaibani, yang dikuburkan di Segapara, desa Pemantren Jero (Rejoso, Pasuruan). Ini adalah legenda yang penulis dengar,dan menurut legenda itu pula penulis adalah keturunan Kebo Kanigoro melalui anaknya, Maulana Maghribi. Apa yang menarik hati penulis, adalah kenyataan bahwa para penduduk dan juru kunci kedua makam itu menggunakan istilah Allah dalam doa-doanya yang menggunakan bahasa Jawa. Ini berarti tidak benamya anggapan bahwa (orang kejawen/kebatinan semuanya bukan santri). Generalisasi dalam hal ini menjadikan kita salah pandang, dan menumbuhkan anggapan tidak benar dalam pandangan kita. Jadi kita sekarang memiliki 3 macam penganut Islam : kejawen/kebatinan yang tidak menjadi santri, kejawen/kebatinan yang merupakan santri, tetapi tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam (Syariah) dan santri yang lengkap karena melaksanakan syariah secara utuh . Pengenalan seperti ini tentu saja masih kontroversial dan ditentang orang. Penelitian akan hal ini, tentu saja sangat diperlukan dalam kehidupan bangsa yang memiliki banyak keragaman dan pluralitas yang sagat tinggi. Kita harus berani melihat kenyataan sebagaimana adanya, dan memisahkan hal itu dari keyakinan kita akan kebenaran. Kemampuan membedakan yang salah dari yang benar dalam keyakinan kita itu, dan tidak melarang kedua-duanya adalah sari pandangan beragam dan pluralitas. Kitab suci Al-Quran telah pula membenarkan sikap ini: tiap kelompok dengan dengan apa yang dimilikinya selalu berbangga/bersenangsenang hati (kullu hizbin bina ladaihi farihun) sebagai fanatisme sempit yang ditolak oleh Allah. Sikap seperti ini diperlukan, karena kita bukanlah bangga yang membenarkan diri sendiri belaka, melainkan, sanggup menghargai pandapat orang lain, yang terkadang betentangan dengan pendirian kita sendiri. Pandangan ini memang perlu ditekankan karena pluralitas kita sangat tinggi dari sudut agama, budaya, bahasa, ada kebiasaan maupun politik. Ini terbawa oleh pendidikan, letak geografis maupun cara hidup kita yang sangat berbeda dari satu dengan lain. Proses sejarah telah menjadikan kita bangsa yang satu, ini berarti keharusan menerima kenyataan sebagaimana apa adanya, dan menjadikan perbedaan-perbedaan sebagai kekayaan bangsa bukanya sebagai penghambat bagi sebuah kebenaran yang kita yakini masing-masing.
Dalam hal ini, sikap untuk memahami orang lain sangat diperlukan, guna menjaga keutuhan bangsa. Jika ini diganggu sedikit saja, maka hal itu akan menimbulkan reaksi balik yang tidak tahu kita akan lari kemana. Karenanya, kita harus sangat berhati-hati dan tidak membuat hal-hal yang akan menganggu keutuhan bangsa kita. Peristiwa yang terjadi di Universitas Trisakti dan Semanggi beberapa tahun yang lalu, menunjukkan kepada kita bahwa cita-cita menegakkan pluralitas dan demokrasi akan diperjuangkan bangsa ini, dengan irama yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Setiap kejadian yang menimpa bangsa kita, haruslah dilihat dari perspektif seperti ini, dan kegagalan untuk memahaminya dapat mengakibatkan reaksi balik yang tadinya kita tidak perhitungkan. Kekerasan yang terjadi itu, akan menimbulkan reaksi baru, dengan akibat-akibat traumatiknya. Peritistiwa penjarahan dan perkosaan yang terjadi di Jakarta pada Mei 1998, mau tidak mau memperlihatkan hubungan kesejarahan yang ada dari dua kejadian sebelumnya. Omong kosong jika pemerintah kita berbicara tentang perlindungan kepada seluruh warga negara di negeri ini, sesuai dengan tuntutan undangundang dasar kita sendiri, dan rasa kesejarahan yang kita miliki bersama. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Bagaimana mungkin, bangsa yang tampaknya begitu damai dan saling tenggang rasa, dalam waktu sekejap saja dapat menjadi bangsa yang buas mengandalkan diri kepada kekerasan. Akibat dari kejadian yang sampai sekarangpun masih terasa, kita harus menyusun kembali kehidupan sebagai bangsa dan kembali ke jalan semula. Hal seperti inilah yang untungnya membuat kita sadar akan keutuhan diri sebagai bangsa. Manipulasi dan kecurangan yang terjadi dalam pemilu legislatif tahun 2004 juga sangat terkait erat dengan hal itu. Bahwa sikap kita bersama untuk menerima hasil-hasil itu tanpa kekerasan, tidak berarti bahwa kekesalan dan kejengkelan mengenai hal itu tidak tumbuh dalam masyarakat. Di mana-mana penulis mendapati sikap yang berbeda dari sikap resmi pemerintah, sehingga tidak bijaksana untuk menganggap apa yang terjadi itu sudah benar. Penulis dan aliansi parpol-parpol yang berjumlah belasan itu mencoba menerima damai atas hasil-hasil pemilu legislatif dan pemilihan umum Presiden pada tahun yang sama. Jelaslah dari apa yang diuraikan diatas, bahwa oleh sejarah kita harus bersikap hati-hati dalam urusan yang menyangkut keutuhan bangsa. Adagium ini sudah terbukti berkali-kali dalam kehidupan bangsa kita semenjak mencapai kemerdekaan dalam tahun 1945. Kenyataan sejarah ini harus selalu diingat oleh siapapun, berarti kita tidak boleh bersikap asal menang belaka: apa yang terjadi dipermukaan, belum tentu berlangsung pula dibawahnya. Kesadaran seperti ini sangat diperlukan, dan inilah yang menentukan kualitas kepemimpinan yang dimiliki bangsa kita di suatu saat. Kalau hal ini kita lupakan, dan lalu kita menyesal atas apa yang terjadi selengkapnya, tentu merupakan kemunduran yang harusa kita pikul bersama. Namun pendekatan budaya menentukan lain, berdasarkan pendekatan ini justru kita harus memacu sebagai bangsa untuk tidak selalu mengandalkan diri kepada pendekatan politis yang senantiasa berdasar kepada kalah menang, dalam
percaturan kekuatan maupun melalui proses-proses lain seperti pemilu. Karena itulah kemenangan physic (semu) yang dicapai dapat saja sewaktu-waktu menjadi kekalahan sebagai kesalahan langkah dalam sejarah yang tidak kita ingini bersama. Akankah kita berulang-ulang harus mengalami hal-hal seperti itu? Apakah tidak lebih baik kita mengambil sikap seperti apa yang dilakukan Vajpayee di India saat ini, yang menerima kekalahan dalam pemilu secara jantan, demi keutuhan India sendiri? Sikap mengalah kepada lawan seperti itu, untuk menjaga esensi demokrasi, adalah sesuatu yang mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan, bukan? Islam Dan McLuhan Di Surabaya Oleh: Abdurrahman
Wahid
Penulis diundang oleh harian Memorandum di Surabaya untuk memberikan ceramah maulid Nabi Muhammad saw, beberapa waktu yang lalu, yang di hadiri ribuan massa, diantaranya para habaib yang datang dari berbagai penjuru Jawa Timur. Penulis sendiri disertai Prof. Dr. Mona Abaza dari Mesir, Maria Pakpahan dan dr. Sugiat (DPP PKB Jakarta). H. Moh. Aqiel Ali, selaku pemimpin umum harian ini, menyatakan peredaran opplaag harian tersebut kini sudah mencapai 120 ribu exemplar per hari, yang menjadikannya koran besar dengan pembaca yang rata di Jawa Timur. Maksud penulis mengajak Prof. Dr. Mona Abaza dan Maria Pakpahan tercapai, ketika digelar pembacaan shalawat Nabi dari Habib Al-Haddad dan sajak burdah dari Imam Al-Busyairi, sesuatu yang belum pemah mereka saksikan. Ketika memberikan ceramah, penulis mempertanyakan adakah para peraga kedua jenis peragaan agama itu berlatih atas kehendak sendiri sepanjang tahun, ataukah ada yang membiayai? Jawaban gemuruh tidak, berarti mereka tidak pemah mengkaitkan latihan sepanjang tahun dari pembiayaan acara. Dengan kata lain, mereka berlatih atas inisiatif sendiri dan dibiayai oleh keinginan keras mengabdi pada agama. Inisiatif sendiri tanpa ada yang menyuruh inilah yang oleh George McLuhan, seorang pakar komunikasi, sebagai happening (kejadian). Dicontohkan penulis dalam ceramah itu -seperti yang terjadi di Masjid Raya Pasuruan, setiap tahun dua kali. Para pemain rebana datang dari seluruh penjuru Jawa Timur, setiap kelompok bermain sekitar 5-10 menit. Mereka datang sendiri dengan menyewa truk, memakai pakaian dan tanda pengenal serta makanan sendiri. Begitu juga kendaraan yang mereka pakai, umumnya truk, disewa sendiri oleh tiap kelompok. Apa yang disebutkan sebagai happening oleh McLuhan itu, juga terjadi pada acara haul atau peringatan upacara kematian Sunan Bonang di Tuban. Acara itu tidak memerlukan undangan dari panitia, kecuali hanya berupa pemberitahuan yang sangat terbatas, tidak lebih dari 300 orang saja, untuk mereka yang disediakan tempat duduk. Sedangkan untuk puluhan ribu pengunjung lainnya, mereka membawa sendiri tikar/koran bekas sebagai alas duduk serta botol air untuk mereka minum sendiri, tanpa mendapat undangan untuk hadir. Selama 43 tahun,
muballigh kondang alm. KH. Yasin Yusuf dari Blitar, berpidato dalam acara haul tersebut, tanpa mendapatkan undangan dari panitia. Yang penting, ia dan rakyat pengunjung tahu hari dan tanggal acara haul tersebut, dan mereka datang atas dasar kesadaran mereka sendiri. Temyata, dalam hal-hal yang terjadi tanpa disiapkan matang-matang terlebih dahulu, pengamatan George McLuhan itu terjadi. Happening itu terdapat di seluruh dunia dalam bentuk dan ragam yang beraneka wama. Apakah implikasi dari hal tersebut? Mudah saja pertanyaan itu untuk dapat dijawab: selama hal-hal itu dapat dianggap membawa berkah Tuhan, dan hal itu dibuktikan oleh hal-hal di atas, maka selama itu pula kesuka-relaan akan menjadi pendorongnya. Ini terjadi, dalam banyak bidang kehidupan yang memperagakan kekayaan kultural suatu kelompok, tanpa ada yang dapat melarangnya. Dengan kata lain, kesuka-relaan atas dasar keagamaan itu, adalah sesuatu yang menghidupi masyarakat kita. Apa yang tidak diuraikan penulis dalam acara peringatan maulid Nabi saw itu, karena keterbatasan waktu, adalah keharusan bagi kita untuk menerapkan secara lebih luas prinsip kesuka-relaan di atas. Terutama dalam kehidupan politik kita, perlu dipikirkan adanya sebuah sistem politik yang sesuai dengan ajaran agama tentang keikhlasan, kejujuran, ketulusan dan keterbukaan. Menjadi nyata bagi kita, bahwa bentukan sebuah sistem politik yang memiliki kandungan sangat beragam, benar-benar diperlukan saat ini. Jelaslah bahwa, aspek kesuka-relaan dan keterbukaan sistem politik itu sangat diperlukan dalam sikap dan landscape kehidupan kita sebagai bangsa. Sementara itu, happening sebagaimana yang diajarkan McLuhan itu temyata memiliki arti yang mendalam bagi peneropongan akan fungsi ajaran agama tersebut. Pengingkaran terhadap kesuka-relaan di bidang politik, hanya akan menghasilkan sistem politik yang memungkinkan seseorang berbohong kepada rakyat. 'Islam Kaset dengan Kebisingannya Oleh: Abdurrahman
Wahid
Suara bising yang keluar dari kaset biasanya dihubungkan dengan musik kaum remaja. Rock ataupun soul, iringan musiknya dianggap tidak bonafide kalau tidak ramai. Kalaupun ada unsure keagamaan dalam kaset, biasanya justru dalam bentuk yang lembut. Sekian buah baladanya Trio Bimbo atau lagu-lagu rohani dari kalangan gereja. Sudah tentu tidak ada yang mau membeli kalau ada kaset berisikan musik agama yang berdentang-dentang, dengan teriakan yang tidak mudah dimengerti apa maksudnya. Tetapi, temyata ada "persembahan" berirama yang menampilkan suara lantang. Bukan musik keagamaan, tetapi justru bagian integral dari upacara keagamaan; berjenis-jenis seruan untuk beribadat dilontarkan dari menara-menara masjid dan atap surau. Apalagi malam hari, lepas tengah malam di saat orang sedang tidur lelap. Dari
tarhim (anjuran bangun malam untuk menyongsong saat shalat subuh) hingga bacaan Alquran dalam volume yang diatur setinggi mungkin. Barangkali saja agar lebih "terasa" akibatnya: Kalau sudah tidak dapat terus tidur karena hiruk pikuk itu. Bukankah memang lebih baik bangun, mengambil air sembahyang dan langsung ke masjid? Bacaan Alquran, tarhim, dan sederet pengumuman muncul dari keinginan meninsafkan kaum muslimim agar berperilaku keagamaan lebih baik. Bukankah shalat subuh adalah kewajiban? Bukankah kalau dibiarkan tidur orang lalu meninggalkan kewajiban? Bukankah meninggalkan kewajiban termasuk dosa? Bukankah membiarkan dosa berlangsung tanpa koreksi adalah dosa juga? Kalau memang suara lantang yang menggganggu tidur itu tidak dapat diterima sebagai seruan kebajikan (amar maruf), bukankah minimal ia berfungsi mencegah kesalahan (nahi munkar)? Sepintas lalu memang dapat diterima argumentasi skolastik seperti itu. Ia bertolak dari beberapa dasar yang sudah diterima sebagai kebenaran: kewajiban bersembahyang, kewajiban menegur kesalahan, dan menyerukan kebaikan. Kalau ada yang keberatan, tentu orang itu tidak mengerti kebenaran agama. Atau justru mungkin meragukan kebenaran Islam? Undang-undang negara tidak melarang. Perintah agama justru menjadi motifnya. Apalagi yang harus dipersoalkan? Kebutuhan manusiawi, bagaimanapun, harus mengalah kepada kebenaran Ilahi. Padahal mempersoalkan hal itu sebenamya juga menyangkut masalah agama sendiri. Mengapa diganggu? Nabi Muhammad mengatakan, kewajiban (agama) terhapus dari tiga macam manusia: mereka yang gila (hingga sembuh), mereka yang mabuk (hingga sadar), dan mereka yang tidur (hingga bangun). Selama ia masih tidur, seseorang tidak terbebani kewajiban apa pun. Allah sendiri telah menyediakan "mekanisme" pengaturan bangun dan tidumya manusia dalam bentuk metabolisme badan kita sendiri. Jadi, tidak ada alas an untuk membangunkan orang yang sedang tidur agar bersembahyang- kecuali ada sebab yang sah menurut agama, dikenal dengan illat. Ada kiai yang merokok di pintu tiap kamar di pesantrennya untuk membangunkan para santri. Illat-nya: menumbuhkan kebiasaan baik bangun pagi, selama mereka masih di bawah tanggung jawabnya. Istri membangunkan suaminya untuk hal yang sama, karena memang ada Illat: bukankah sangu suami harus menjadi teladan anak-anak dan isterinya di lingkungan rumah tangganya sendiri. Tetapi Illat tidak dapat dipukul rata. Harus ada penjagaan untuk mereka yang tidak terkena kewajiban: orang jompo yang memerlukan kepulasan tidur jangan sampai tersentak. Wanita haid jelas tidak terkena wajib sembahyang. Tetapi mengapa mereka harus diganggu? Juga anak-anak yang belum akil balig (atau tamyiz, sekitar umur tujuh delapan tahunan, menurut sebagian ahli fiqh Mazhab Syafii) Tidak bergunalah rasanya memperpanjang illustrasi seperti itu: akal sehat cukup
sebagai landasan peninjauan kembali "kebijaksanaan" suara lantang di tengah malam- apalagi kalau didahului tarhim dan bacaan Alquran yang berkepanjangan. Apalagi, kalau teknologi seruan bersuara lantang di malam buta itu hanya menggunakan kaset! Sedangkan pengurus masjidnya sendiri tenteram tidur di rumah. Kasidah Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Ketika ia memperkenalkan diri melalui telepon, saya belum tahu apa yang dirisukannya. Ia minta waktu untuk bertemu. Langsung saya katakana sebaiknya dilakukan sore itu juga. Temyata, orangnya sudah setengah baya, sudah menemukan arti dirinya dalam hidup. Menjadi pemimpin sebuah kursus musik, melukis dan bahasa di bilangan Kebayoran. Ia telah mapan dan mulai mencari sesuatu yang bemilai lebih tinggi dari sekadar "menjalankan profesi". Dan itu ditemukannya dalam agama. Temyata yang dipersoalkannya adalah kaitan antara profesinya sebagai musikus dan penghayatan agamanya. Kepada saya mula-mula ditanyakannya: Apakah yang akan dikenakan Nabi Muhammad "seandainya beluai hidup di masa ini?" Tetap berjubah sajakah, seperti orang Arab dari pedalaman semenanjung bergurun luas itu? Ataukah justru mengenakan pakaian "lebih universal", seperti celana, dasi, dan jas. Ini cara unik juga untuk memulai sebuah pembicaraan serius. Tapi diteruskannya dengan pengamatan bahwa setiap hari Jumat TVRI menyiarkan acara yang bemada Islam. Nah, yang menggelisahkan adalah seringnya lagu-lagu gambus Arab, atau juga kasidah modem, dibawakan di layar TVRI. "Ini mengganggu saya sebagai orang yang berkecimpung di dunia musik," katanya. Sudah benarkah "kebijaksanaan" menjadikan kasidah sebagai "perwakilan musik Islam" di layar TV, dalam suatu rangkaian dengan uraian keagamaan dan pengajian Alquran? Benarkah yang dituju adalah seni "musik agama" yang akan membawa kepada kebesaran Tuhan? Kalau memang benar itu yang dituju, dengan kualitas acara yang disajikan sekarang, apa bukan sebaliknya yang terjadi? Saya balik bertanya kepadanya: Apakah yang sepatutnya dianggap sebagai musik yang mewakili Islam? Jawabannya mengejutkan juga bagi saya :" Ya, yang universal, diakui di manamana, seperti lagu pop dan musik klasik. Asal jelas diisi pesan keagamaan, dan bermutu tinggi, dihargai orang dimana-mana." ? Tertegun saya mendengar uraiannya. Teringat saya akan cerita Bung Syubah Asa: ada seorang pelukis yang menyebutkan ciptaan Beethoven sebagai "musik yang paling dekat dengan Tuhan".
Saya sendiri dapat merasakan bagaimana pelukis tersebut sampai kepada kesimpulan itu. Kelembutan dan keaslian alami Simfoni Pastoral Beethoven memang dapat mengantarkan kita kepada kebesaran alam, apalagi pencipta alam itu sendiri. Tetapi benarkah universalitas yang dituntut dari medium musik yang "mewakili Islam" itu harus lepas dari wama local tempat lahir Islam sendiri, tanah Arabia? Memang benar, penyajian vulgar dari "tari-tarian Arab" yang mengiringi musik kasidah di sini bermutu rendah dan tidak bisa diterima sebagai "citra Islam". Juga lirik Arabnya, yang tidak dimengerti bangsa kita, salah informasi. Belum lagi diingat mutu suara penyanyinya yang tampak tak pemah dibekali pengetahuan teoritis tentang musik dan latihan menyanyi di tangan ahli. Tetapi, cukupkah deretan kelemahan itu, yang lebih bersifat teknis daripada substansial, untuk "menghukum mati" siaran kasidah di layar TV? Bagaimana kalau yang dimunculkan justru rekaman biduanita Fairuz dari Lebanon membawakan ciptaan suaminya (dengan lirik penyair Arab kaliber dunia, Khalil Gibran Khalil) berjudul Atni an-Naya? Saya sendiri tidak pemah dapat lepas dari pengaruh lagu ini, yang judul Indonesianya berbunyi Berikan Padaku Seruling sudah berusia lebih dua dasa warsa. Seperti saya juga tak dapat lepas dari karya Beethoven dan Bach yang terasa membawakan keagungan dan kebesaran Tuhan. Yang jelas, penyajian cara kasidahan sebagai representasi "musik Islam" dalam bentuknya sekarang memang harus ditolak. Kawan baruku ini benar seluruhnya dalam hal ini. Masalahnya lalu kembali pada pihak TVRI: mau berfungsi edukatif yang benarkah atau sekadar memperkirakan kesenangan kelompok formal keagamaan belaka? Kasus Terjemahan H. B. Jassin Oleh Abdurrahman
Wahid
Akhimya, terjemahan Al Qur'an yang dilakukan H.B Jassin jadi juga terbit cetakan keduanya."Bacaan Mulia", penerbit Yayasan 23 januari 1942, Jakarta, 1982, xxxviii +891 halaman. Cetakan kedua itu terbit di sekitar hari ulang tahun Jassin yang ke-65, menjadi semacam hadiah ulang tahun baginya. Mungkin sebagai persiapan memasuki 'masa pensiun' - walaupun dalam kenyataan tidak akan pemah ada masa seperti itu bagi orang seperti penerjemah yang satu ini. Tentu saja suara yang menentang dan tidak menyetujui kerja Jassin itu juga akan berkumandang lagi. Walaupun mungkin tidak akan seramai dulu. Argumentasi demi argumentasi akan dilancarkan, mungkin sebagian besar pengulangan apa yang telah dilontarkan di masa lalu. Tetapi masih belum jelas apakah akan mampu semua serangan atas 'Bacaan Mulia' itu menahan beredamya karya terjemahan itu di tengah-tengah masyarakat.
Yang menarik perhatian dalam kasus ini adalah konteksnya: penolakan lembagalembaga agama yang telah mapan atas dasar alasan keagamaan yang bersifat formal, temyata tidak mampu menghentikan beredamya sebuah karya yang dianggap tidak memenuhi kriteria sebagai 'karya agama'. Dengan kata lain, sesuatu yang secara keagamaan formal dinilai 'mbeling', temyata dapat merebut hati masyarakat. Adapun keberadaan yang diajukan terhadap terjemahan Jassin itu menyangkut hal-hal yang prinsipiil, dipandang dari sudut ajaran Islam. Secara umum, serangan dan keberatan dapat dibagi dua. Pertama serangan yang meragukan kompetensi Jassin sebagai penerjemah. Khususnya menyangkut kemampuannya memahami Al Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab Klassik. Jika kemampuan itu tak cukup sahkah hasil terjemahannya sebagai sesuatu yang secara formal tidak - dididik untuk menguasai ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam, melakukan kerja penerjemahan kitab suci Al Qur'an? Di sini masuk pula sejumlah tuduhan yang menolak kepatutan moral (moral fitness) Jassin pribadi untuk melakukan 'kerja keagamaan' tersebut. Tadinya diharapkan akan terjadi perdebatan terbuka. Sejumlah forum yang akan melakukan dialog seperti itu bahkan telah dipersiapkan. Bahkan penulis kolom inipun pemah diminta oleh Koordinator Dakwah Islamiyah (KODI) DKI Jakarta Raya untuk mempersiapkan sebuah makalah tentang masalah di atas. Sayang, semua harapan itu tidak terpenuhi sama sekali. Sebab pertama adalah karena tidak adanya perkenan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, lembaga pemerintahan yang diserahi menyelesaikan masalah penerjemahan Al Qur'an oleh Jassin itu. Alasan yang dibisik-bisikan ialah: kasus ini terlalu sensitif, bisa menimbulkan gejolak di masyarakat'. Masalahnya lalu diserahkan kepada sebuah team peneliti, tanpa diketahui apa yang diperdebatkan di dalamnya. Padahal masalah yang dipersoalkan sebenamya menyangkut sejumlah hal yang sangat menarik untuk diketahui kejelasannya. Misalnya, bagaimana sesuatu yang indah secara manusiawi harus dihadapkan kepada sikap formal agama? Apakah persyaratan formal yang harus dimiliki seorang penerjemah Al Qur'an menentukan keabsahan setiap karya terjemahan. Kitab Suci itu? Dapatkah dilakukan terjemahan tidak langsung atas Al Qur'an tanpa penguasaan mendalam atas bahasa Arab? Adakah pengaruh moralitas dan perilaku pribadi seseorang penerjemah terhadap sah tidaknya karyanya - terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan yang dilancarkan terhadap Jassin? Sayang, lepaslah sudah peluang untuk memahami hal-hal tersebut secara mendalam. Padahal secara keseluruhan hal-hal itu dapat juga ditelusuri adanya dalam banyak 'kasus-kasus' lain di bidang keagamaan. Sebagaimana setiap kasus yang dipecahkan secara institusional belaka, tanpa perhatian cukup kepada aspek
intelektualnya, penanganan 'di bawah tangan' atau 'Bacaan Mulia'-nya H.B.Jassin sebenamya hanya menunda persoalan belaka. Kemudian hari, toh masih akan ada orang melakukan kerja penerjemahan Al Qur'an, bukan? Kata Pengantar Buku "Aku Bangga Menjadi Anak PKI" Orientasi Adalah Bagian Oleh: Abdurrahman
Dari
Idiologi Wahid
Pengantar ini hanya membicarakan Bab I dari tulisan dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati (selanjutnya, ditulis dr. Ribka, penulis), berjudul "Aku Bangga Menjadi Anak PKI". Ada dua alasan mengapa kata pengantar buku ini ditulis hanya mengenai Bab I, dan tidak mencakup bab II dan bab III. Pertama, dalam pembahasan bab II dan III, tanpa membahas tindakan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Megawati Soekamoputri, dkk, adalah merupakan kekurangan yang sangat besar, bahkan- boleh dikatakan penggelapan sejarah. Kedua, memang keseluruhan isi buku ini diberi kata pengantar berkenaan dengan orientasi dari ideologi yang dibawakan oleh institusi/lembaga bemama Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyak cara untuk meninjau idiologi tersebut, tetapi buku ini hanya membicarakan orientasi partai tersebut. Pembicaraan tentang orientasi PKI ini menunjukkan pembelaannya terhadap kepentingan rakyat kecil, yang oleh Karl Marx dan Friederich Angels disebut sebagai kaum proletar. Tetapi, komunisme dapat dilihat dari berbagai sudut yang tidak seluruhnya sesuai dengan azas peri-kemanusiaan. Ketika Mao Zedong mengalahkan Chiang Kai -Sek tahun 1949 dari Beijing, ia segera memerintahkan pengadilan rakyat atas kaum borjuis dengan korban dua belas juta jiwa manusia ditembak mati di seluruh daratan China. Gerakannya untuk melakukan revolusi besar kebudayaan proletar memakan belasan juta jiwa, semua itu dilakukan untuk kemumian budaya kaum proletar. Bagaimana kita harus menjelaskan hal ini secara kemanusiaan? Inilah yang membuat mengapa kata pengantar buku ini hanya dibatasi pada bab I belakang saja. Bahwa, penulis buku ini memiliki orientasi yang benar- hal itu tidak perlu diragukan lagi. Bahkan, orientasi itu sangat jelas berjalan seiring dengan orientasi penulisnya, yaitu rasa perikemanusiaan yang tinggi. Dalam hal ini, penulis buku ini memiliki orientasi yang bersamaan dengan apa yang dimiliki oleh penulis pengantar buku ini. Ayah penulis pengantar buku ini adalah seorang pejuang gerakan Islam yang militan, tapi memiliki orientasi perikemanusiaan yang tinggi. Karenanya, ia selalu bersikap simpati kepada kepentingan rakyat kecil, sebagaimana ia dipahami dan dilihat sehari-hari. Kalau ayah dari dr. Ribka adalah seorang ningrat dengan kakayaan besar sebagai konglomerat waktu itu, orientasinya jelas berpihak kepada kepentingan rakyat. Ayah penulis pengantar buku ini- pun seorang putera Kyai besar yang
diistimewakan oleh para pengikutnya dalam segala hal, tetapi ia membela kepentingan rakyat banyak dan ia tidak menjadi aktivis partai komunis, melainkan menjadi penggerak idiologi agama. Namun ia menentang negara agama, karena hal itu akan membedakannya dari kedudukan warga negara non-muslim. Sangatlah menarik untuk berspekulasi, bersediakah ayah dr.Ribka menerima gagasan DN Aidit tentang sebuah negara komunis? Bisakah ia menjadi seorang Boris Pastemak yang kecewa pada komunis? Dapatkah ia menjadi Milovan Djilas, yang menganggap para fungsionaris partai komunis Yugoslavia sebagai kaum apparatchik penindas rakyat dengan demikan menjadi "kelas baru"? Karena alasan di atas, penulis kata pengantar buku ini lebih mengutamakan aspek peri-kemanusiaan dari aspek-aspek yang lain. Dari buku ini, tampak sekali generasi muda banyak memiliki orientasi kerakyatan dan mereka menyatakan berpegang pada sebuah idiologi. Sikap ini sekaligus mengungkapkan kelemahan dan kekuatan pendekatan orientatif yang mereka miliki. Kelemahannya, dengan tidak berpegang pada "sisi keras" idiologi seperti ini, tidak satupun idiologi yang berhasil diterapkan secara menyeluruh di dalam kehidupan masyarakat bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita menjadi apa yang dikatakan Gunnar Myrdal sebagai "bangsa lunak" (soft nation). Kekuatannya, orientasi kerakyatan tersebut akan tetap menjadi panduan kita sebagai bangsa dan kita tidak akan pemah terpecah-pecah secara serius. Saudara dr.Ribka yang komunis dan penulis kata pengantar buku ini yang Islamis dapat bergaul dengan mudah karena kami berdua penganut asas peri-kemanusiaan. Idiologi adalah perambah jalan bagi kita berdua. (Ketika mendiktekan kata pengantar buku ini, penulis kata pengantar buku ini (Abdurrahman Wahid red) baru saja mendapat pesan dari mantan Presiden Soeharto, diajak melepas Tommy Soeharto dari penjara Cipinang ke Nusa Kambangan. Walaupun Tommy Soeharto pemah mengeluarkan uang belasan milyar rupiah untuk demo melengserkan penulis kata pengantar buku ini dari kursi kepresidenan, dengan langsung ia menjawab bersedia). Bukankah Tommy Soeharto berada dalam kedudukan sebagai narapidana, dan mantan Presiden Soeharto menunjukkan penghormatan yang besar pada kedaulatan hukum? Bahwa nama Soeharto, atau dirinya sekalipun, pemah digunakan untuk menindas orang lain, bagi seseorang seperti penulis kata pengantar ini, mengharuskannya menghormati mantan Presiden tersebut. Inilah konsekuensi terjauh dari sikap berperikemanusiaan yang dianut oleh penulis kata pengantar buku ini. Karena sikap seperti inilah, lalu penulis kata pengantar buku ini dihujat oleh sementara aktivis gerakan Islam yang disebut "muslim garis keras", karena mengusulkan dicabutnya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) No. XXV tahun 1966, yang melarang penyebaran Marxisme-Leninisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai sesuatu yang tidak demokratis. Sikap menolak TAP MPRS tersebut, karena atas dasar perikemanusisan. Dalam bahasa
komunisme, sikap ini membuat penulis pengantar buku ini sebagai "sesama pejalan" (fellow traveler), karena rasa peri-kemanusiaan yang tinggi. Memang sikap seperti ini sering dianggap sebagai sesuatu yang bersifat tanggungtanggung, dan tidak akan pemah menghasilkan negara yang benar-benar komunis, nasionalis ataupun Islam. Tapi, bukankah ini jauh lebih baik dari pembantaian dan penjagalan manusia secara besar-besaran, seperti yang terjadi di tempat-tempat lain? Dalam sejarah umat manusia, hal ini sering kita jumpai- misalnya, Akhnaton dalam sejarah Mesir kuno, Gramsci di lingkungan kaum komunis pada tahun-tahun 60-an, adalah contoh dari sikap ini. Panglima besar Jenderal Sudirman yang memimpin Amgkatan Perang kita dari tahun 1945 hingga 1949, adalah contoh yang sangat baik dalam hal ini. Kalau mengingat hal ini, maka kita harus bersyukur memiliki ribuan orang pencipta idiologi yang memiliki rasa peri-kemanusiaan yang tinggi. Ini yang menerangkan mengapa dr.Ribka- yang berasal dari keluarga ningrat dan golongan borjuis menjadi anggota PKI. Ini juga yang menerangkan mengapa Megawati Soekamoputri yang berasal dari keluarga rakyat kemudian mengikuti aspirasi borjuis yang ada. Intinya, karena dalam masyarakat kita sangat kecil jumlahnya orang-orang yang benar-benar memiliki idiologi seperti di negeri-negeri lain-seperti dikatakan di atas. Hal ini menjadi kelemahan dan sekaligus kekuatan kita sebagai bangsa. Dikatakan kekuatan, kalau rasa perikemanusiaan itu dapat diterjemahkan dalam usaha-usaha yang luas untuk mewujudkan prinsip peri-kemanusiaan. Kalau tidak, akan menjadi kelemahan yang dapat menggerogoti capaian-capaian yang diraihnya di masa lampau. Sumpah serapah dan maki-makian atas tidak idiologisnya perjuangan yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh kelompokkelompok Islam kanan yang berhaluan keras terhadap "perjuangan kaum tradisional", menggambarkan kenyataan yang sangat memilukan akan munculnya gerakan Islam dari kaum kanan dalam upaya idiologisasi yang mereka lakukan. Ini adalah sebuah kenyataan yang harus diterima sungguh-sungguh, apabila diinginkan upaya penyebaran Islam secara idiologis. Kalau tidak demikian, satusatunya cara adalah perjuangan kultural. Pengingkaran atas kenyataan ini hanya akan menghasilkan sikap sok pahlawan, yang justru tidak mencerminkan sikap bangsa kita yang menginginkan salah satu dari pendekatan ini: pendekatan kultural, yang sama sekali tidak didasarkan pada upaya kemasyarakatan. "Keaslian" Karya Slamet Gundono
Oleh: Abdurrahman Wahid Penulis memperoleh sebuah kaset dari KH A. Mustofa Bisri, Rembang. Kaset itu berupa nyanyian-nyanyian mistiskus ciptaan Slamet Gundono, budayawan/seniman kita yang berasal dari daerah. Nyanyian-nyanyian itu berisikan jeritan hati seseorang yang memiliki mistik daerah tertentu, yang terkadang tidak dipahami orang latar belakangnya. Tulisan ini bermaksud sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai
asal-usul mistik daerah itu . Walaupun ini bukan satu-satunya penjelasan yang dapat dikemukakan, jika kita ingin mengetahui perkembangan historis/kesejarahan yang terjadi. Namun dalam hal ini, keterangan tersebut dapat dianggap berguna sehingga penulis tergugah untuk turut memberikan semacam penjelasan melalui tulisan ini. Slamet Gundono, dengan keluguan yang sangat kental, menampilkan sejumlah lagu mistik, dengan berbagai judul yang merangsang, antara lain nyanyian Mabuk Gusti dan Urip Dhewekan. Nyanyian-nyanyiannya itu dilagukan dari mistik lokal dari Tegal. Dengan berkembangnya mistik santri/ tasawuf yang menjadi tanda kesantrian yang umum muncul di kalangan kaum muslimin kawasan itu, dengan sendirinya mistik lokal yang ada lalu menjadi terancam. Dengan demikian, munculah upaya untuk melestarikannya melalui nyanyian-nyanyian orang seperti Slamet Gundono. Tidak jelas, adakah Slamet Gundono merasa bahwa nyanyian-nyanyian itu justru membuktikan ke-Islaman mistik lokal itu sendiri. Menjadi jelas bagi kita, bahwa mistik lokal yang sarat dengan nilai-nilai agama Islam, dikenal sebagai sesuatu yang berbeda dari tasawuf, yang merupakan penampilan kaum santri. Jadi, perbenturan yang terjadi antara mistik lokal di satu pihak, dan tasawuf santri di pihak lain, dianggap mewakili perbedaan antara dua wujud/entitas dari dua buah masyarakat yang saling berbeda, padahal sebenamya berasal dari sebuah masyarakat yang boleh dikata sama. Ini dapat diketahui dari nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam nyanyian-nyanyian Slamet Gundono itu. Ia selalu mengetengahkan nilai-nilai yang berasal dari dua buah kecenderungan yang tadinya berasal dari sumber yang sama : ajaran Islam dalam keluasannya. Hanya saja, dalam mistik lokal nilai-nilai itu muncul ke permukaan dengan menggunakan bahasa Jawa lokal. Sedangkan tasawuf santri dimunculkan dengan bahasa Arab, seperti Qodrat Allah, nasib dan sebagainya. Sedangkan Slamet Gundono menggunakan bahasa lokal, seperti dengan mengajukan pertanyaan: bersediakah engkau hidup sendiri, tanpa saudara? Kedua macam nilai itu, dengan menggunakan bahasa yang berbeda, sebenamya mengetengahkan persamaan yang mendasar. Hanya saja, mistik lokal itu tidak berkembang menjadi anutan penduduk setempat dan hanya menjadi mistik lokal yang sangat sedikit penganutnya. Dengan demikian, seolah-olah terjadi perkembangan sejarah yang saling berbeda antara keduanya. Dan seolah-olah mistik lokal dikalahkan dan ditindas oleh tasawuf santri. Padahal, yang terjadi adalah meluasnya pengaruh tasawuf santri dalam kehidupan kaum musliminnya dengan manifestasi mistik lokal di kawasan tersebut. Karenannya, dapat dimengerti mengapa Slamet Gundono lalu menjadi seperti orang yang kalah dalam sebuah perbenturan budaya. Padahal, yang terjadi adalah meluasnya peristilahan bahasa Arab dari tasawuf santri ,seperti terdapat dalam berbagai bentuk wirid/ kata-kata doa. Adalah sesuatu yang mengherankan, bentuk doa berbahasa lokal dapat dikalahkan oleh wirid/doa yang menggunakan bahasa luar/Arab. Karena itu, lalu timbul anggapan diatas, yang sebenamya merupakan rekonstruksi budaya yang belum tentu benar.
Sebagai akibat, munculah anggapan dan perasaan, seolah-olah terjadi perbenturan budaya antara mistik lokal dan tasawuf santri. Padahal yang terjadi, adalah munculnya dua buah varian dari mistik tasawuf kaum muslimin, yang sama-sama berhadapan dengan perbenturan melawan arus modemisasi. Ini juga terlihat pada pagelaran wayang oleh dalamg Ki Entus Susmono yang serba lucu, dan melawan konvensi/cerita pakem yang telah dibakukan oleh para dalang tradisional. Hal ini lagi-lagi menunjukkan responsi berbeda terhadap tantangan modemisasi di kalangan budaya Jawa pinggiran. Sesuatu yang sebenamya normal-normal saja dan menunjukkan daya tanggap yang sehat dari kawasan budaya tersebut. Yang menarik, justru untuk melihat bagaimana sebuah kawasan budaya lokal dapat menemukan/menampilkan jawaban yang kreatif dari situasinya sendiri. Ini menunjukkan besamya vitalitas/daya hidup dari kalangan budaya lokal itu, atau terdapat kreatifitas yang sangat besar dari masyarakat kawasan itu sendiri. Inilah yang perlu kita kenali, untuk dikembangkan lebih jauh sebagai bagian dari responsi umum budaya kawasan nusantara. Untuk dapat mengenal responsi itu, kita harus mampu memahami perkembangan sebenamya dari berbagai aspek budaya yang ada dalam sebuah kawasan dengan tepat, agar supaya responsi yang diberikan juga memadai kebutuhan. Namun sebuah upaya untuk menghidupkan kembali tradisi lama yang ada, tentu saja membawa hasil yang tidak optimal, seperti berbagai upaya menghidupkan kembali budaya Jawa klasik yang akhimya memunculkan budaya tontonan (kitsch) saja, yang pada analisa terakhir akan melahirkan komersialisasi berbagai penampilan tradisional untuk kepentingan kaum turis asing/wisman belaka. Hal ini tampak di India, ketika lagu-lagu pemusik Zakir Hussain dan Ravi Shankar yang penuh berbagai tanggapan budaya, sangat berbeda dari sejumlah kuburan dan istana lama yang menarik hati para wisman itu. Semua hal tentu ada pos anggarannya sendiri, seperti halnya dunia pariwisata untuk menghasilkan devisa bagi pembangunan bidang-bidang lain. Karena itu, sahsah saja mengembangkan dunia pariwisata di negeri kita. Tetapi ini tidak berarti kita harus mengembangkan hal-hal komersial belaka. Jika ini yang kita lakukan, bidang-bidang lain tidak akan memperoleh hal-hal yang akan menimbulkan kemampuan memberikan jawaban positif terhadap tantangan modemisasi. Karenanya, hasil-hasil karya seperti rekaman nyanyian Slamet Gundono perlu dilakukan, guna menampilkan keragaman budaya kita, sebagai pengembangan budaya berisi banyak, yang kita perlukan dewasa ini. Jadi, sekaligus kita memperoleh dua hal: menampilkan varian-varian/budaya yang berkembang dalam masyarakat kita, disamping penyimpanan warisan budaya beragam itu untuk kepentingan masa depan kita sendiri. Proses penyimpanan dan perekaman budaya kita yang serba bagai itu, merupakan sesuatu hal yang perlu memperoleh perhatian kita sendiri, dan harus dilakukan dalam jangka panjang. Ia adalah bagian tak terelakan bagi kebutuhan kita di masa depan. Sebagai sebuah tahapan penting, minimal bagi kehidupan kita bersama. Ia merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari kita semua. Jika benda-benda bersejarah harus disimpan, guna menunjukkan masa lampau kita sendiri, sama saja upaya rekam dan menyimpan manivestasi budaya
dan seni dari mistik lokal serta tasawuf santri, merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali. Jika Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) merekam dan menyimpan nyanyian-nyanyian Slamet Gundono, maka itu adalah sebuah hal yang patut kita hargai. Ia adalah bagian dari proses melestarikan dan membuang yang biasa terjadi dalam sejarah peradaban manusia, bukan? Ciganjur, 18 Mei 2005
Kebenaran dan Penolakan Atasnya
Oleh: Abdurrahman Wahid Pada suatu ketika, penulis dihadapkan pada sebuah pertanyaan yang terus menerus mengganjal hubungan mesra antara dirinya dengan orang beragama lain. Pertanyaan itu adalah: apakah batas dan hubungan antara kebenaran sebuah keyakinan dengan pergaulan antara sesama penganut agama dalam konteks negara Republik Indonesia? Pertanyaan ini haruslah memperoleh jawaban yang jujur, karena sendi-sendi kenegaraan kita sangat tergantung kepada jawaban itu. Jika kita menggunakan kerangka penuh sebagai seorang muslim saja, kita akan menjawab: persetan dengan semua hubungan antara diri kita sendiri dengan para penganut agama-agama lainnya. Kita hanya akan melihat pentingnya pencapaian hubungan dalam pola sempit, yaitu antara seorang muslim dan akidahnya. Sikap sebagai seorang muslim, lalu menjadi sangat arogan dalam negara kita hidup. Akhimya, kita hanya mau tahu kebenaran agama sendiri, dan menjadi puas ketika mengalahkan agama lain. Arogansi seperti inilah yang menjadikan kita berstandar ganda dalam bemegara. Di satu pihak, kita memerlukan negara untuk tetap hidup. Di pihak lain, kita acuh tak acuh terhadap eksistensi/wujud negara ini. Padahal, salah satu cara untuk mempertahankannya adalah memahami watak kemajemukan hidup beragama di negeri itu, yaitu dengan bersikap toleransi/tenggang rasa antara sesama agama yang hidup di negara tersebut. Karenanya, pluralisme yang ditolak oleh Munas ke7 Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini, justru memperlihatkan adanya sikap yang tidak mau tahu dengan toleransi, yang sebenamya menjadi inti dari kehidupan beragama yang serba majemuk dalam kehidupan negara kita. Sebagai pemimpin formal Rebuplik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam percakapan dengan penulis baru-baru ini bertanya: Kalau saya mengambil sikap hanya berpegang pada ajaran Islam yang resmi, bukankah saya akan dipersalahkan jika hadir dalam sebuah peringatan Hari Natal? Bukankah lalu saya harus mau menghapus tradisi baik yang sudah berjalan puluhan tahun? Dan bukankah saya lalu menyalahkan sikap para Presiden setelah kita merdeka, yang selalu hadir dalam acara-acara seperti itu? Bukankah dari dulu hingga sekarang, saya tidak mengikuti acara peribadatan Kristen? Penulis tidak menjawab deretan pertanyaan tersebut, karena jawaban kekanak-kanakan akan merusak tradisi
sangat baik yang dihadirkan oleh hubungan mesra antara sesama agama yang hidup di negeri kita. Jawabannya sudah jelas, tidak perlu penulis ulangi di sini. Bahkan baru-baru ini Presiden Bush dari Amerika Serikat, menghadiri perayaan yang dilakukan kaum muslimin di negaranya. Bukankah ini kebalikan dari negara kita? Sesuatu yang justru harus diabadikan di negara kita, malah dijauhi dengan keputusan yang dangkal oleh sebuah forum semulia Munas MUI. Seharusnya tradisi baik ini dikembangkan lebih jauh tanpa harus melemahkan akidah kita sendiri. Penulis yakin bahwa sikapnya untuk hadir dalam berbagai upacara keagamaan oleh agama-agama yang berlainan, tidak akan mematahkan keyakinannya sendiri sebagai seorang muslim. Di sinilah terletak saripati sikap beragama yang benar, seperti saat kita melaksanakan firman Allah dalam kitab suci Al-Quran Mudah-mudahan kedamaian menyertainya, di hari kelahirannya (salamunalayhi yauma mulida). Siapapun juga akan tahu, ayat suci tersebut ditujukan kepada Nabi Isa AS, terlepas dari kenyataan bahwa ia dinyatakan sebagai Anak Tuhan atau bahkan Tuhan oleh orang-orang Kristen jauh sebelum Islam sendiri lahir di dunia ini. Keyakinan bahwa Nabi Isa adalah Anak Tuhan atau Tuhan, bukanlah urusan kita. Justru sikap untuk memaksakan tafsiran sepihak akan hakikat diri tokoh tersebut, akan meracuni hubungan mesra antara kaum muslimin dan kaum nasrani. Penghargaan kepada kaum non-muslim oleh kaum muslimin, tidak berarti menunjukkan kita telah meninggalkan akidah kita sendiri, melainkan justru menunjukkan kedewasaan pandangan kita di mata mereka. Kenyataan sekecil ini saja, menunjukkan bahwa pandangan terlalu formal tanpa memperhatikan perasaan orang lain, adalah sikap kekanak-kanakan yang perlu dikikis habis. Harus diakui umat Islam terbagi menjadi dua dalam bersikap terhadap agama lain. Jika pimpinan MUI tetap terbuai oleh sikap harus menyatakan kebenaran sendiri, maka kaum muslimin akan terjebak dalam formalisasi sikap yang tidak dikehendaki. Itulah sebabnya, mengapa para pendiri Republik Indonesia berkeras mengatakan bahwa negara ini bukanlah sebuah negara agama. Lalu apakah para pemimpin Islam waktu itu seperti: Ki Bagus Hadikusumo dan KH. Kahar Muzakir dari Muhammadiyah, AbikusnoTjokrosuyoso dari Serikat Islam, Achmad Subarjo dari Masyumi, AR. Baswedan dari Partai Arab Indonesia, KH. Wahid Hasjim dari Nahdlatul Ulama dan H. Agus Salim, adalah tokoh-tokoh gadungan yang tidak mewakili golongan Islam? Jelaslah, kaum muslim pendiri Indonesia berpandangan luas mengenai hubungan timbal balik dengan para pengikut dan pimpinan agama-agama lain. Selama lebih dari empat dasawarsa, kita hidup dalam tradisi saling menghormati. Mengapakah kita lalu harus meninggalkan sikap tersebut, padahal tidak ada keharusan untuk melakukannya? Bukankah sikap apriori, yang dalam hal ini tidak mau mengakui kehadiran agama-agama lain dalam kehidupan bemegara kita, adalah buah dari kesombongan? Mengapakah kita harus menerima pandangan kaku seperti itu, yang dimulai oleh segelintir orang yang menggunakan MUI secara tidak wajar? Bukankah itu adalah sikap tergesa-gesa dari mereka yang menggangap diri sendiri sebagai pihak paling berhak menafsirkan kebenaran ajaran Islam?
Sebuah sikap untuk mencuri-curi ajaran Islam dari lingkupnya yang sehat, menunjukkan sikap arogan yang harus ditentang habis. Tindakan sembunyisembunyi itu dilakukan untuk mempertahankan sebuah versi kebenaran, karena belum tentu dimaui oleh mayoritas bangsa. Siapapun orangnya dan darimana pun asalnya, tidak lagi menjadi penting bagi kitas semua.Penulis sendiri yakin, jika hal itu dibuat dalam sebuah referendum, mayoritas kaum muslimin akan menolaknya. Di sinilah kita memerlukan demokrasi dalam artian sebenamya, dalam kehidupan kelompok besar seperti bangsa kita. Pemyataan Din Syamsuddin dalam siaran radio niaga Elshinta, minggu lalu, bahwa ia akan mencoba melerai/menjembatani perbedaan antara yang menyetujui dan menolak fatwa MUI itu, adalah sesuatu yang sebenamya tidak diperlukan. Sebab arogansi yang sudah diperlihatkan MUI telah menyadarkan kita, agar tidak mudah tertipu terhadap sikap yang seolah-olah mewakili umat Islam. Sebenamya, dari peristiwa-peristiwa itu hanya ingin menunjukkan bahwa telah terjadi sebuah proses lain yang tidak kalah penting, yaitu proses melestarikan dan membuang, yang sering terjadi dalam sejarah umat manusia, bukan?
Keberagaman Spiritualitas Kita Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Penulis teringat mendiang Soedjatmoko, mantan Dubes kita di PBB, mantan Rektor Universitas PBB di Tokyo dan salah seorang intelektual kita yang dihormati orang. Ia menyatakan melihat tiga jenis kerohanian/sufisme yang ada di tanah air kita. Pertama, sufisme kaum Katolik yang berujung kepada aneka Ordo yang disahkan oleh Gereja. Ada yang menggabungkan spiritualitas dan ilmu, seperti kaum Jesuit; adapula yang mengemukakan pentingnya tindak langsung untuk menolong mereka yang miskin dan menderita, seperti kaum Fransiskan. Bahkan adapula yang bertapa bisu tidak pemah berbicara kepada orang lain, mereka hanya mendengar saja apa yang dikatakan orang tanpa menjawab. Semua macam sufisme itu oleh DR. Soedjatmoko dinamakan kebon raya (botanical garden), yang pohon-pohonya dibentuk begitu rupa oleh tukang kebon hingga berbentuk macammacam. Karena itulah, orang senang dengan kebon raya, karena pohon-pohonnya sangat teratur dan terpelihara rapi. Kerohanian kedua, menurut DR. Soedjatmoko adalah Sufisme Islam. Bermacammacam gerakan sufi muncul dari satu mata air yaitu keyakinan mutlak akan kebenaran Allah SWT dan Rasullulah SAW. Sufisme Islam diibaratkannya seperti air yang mengalir dari sebuah sumber mata air di gunung, yang terus mengaliri jenjang-jenjang sawah hingga ke laut. Karenanya ia menyamakan sekian banyak gerakan sufi itu sebagai bidang-bidang sawah yang mendapatkan air dari satu petak ke petak lain, tetapi berasal dari satu sumber. Pemetakan (teras siring) itu memang membuat sekian banyak sawah itu terairi dengan baik, dan jika dilihat dari jauh jenjang-jenjang sawah itu tampak indah. Karenanya, keseluruhan gerakan tarekat memang mengagumkan tetapi ketika sebuah tarekat diteliti gerak-
geraknya, banyak juga pertanyaan muncul tanpa ada jawaban yang pasti. Bahkan Nahdlatul Ulama yang didirikan di tahun 1926, dan dianggap merupakan wakil dari salah satu gerakan penyebar ajaran Islam, memberikan imprimatur (pengesahan) atas 45 buah ajaran-ajaran sufi. Gerakan tarekat yang diakui Al-Thariqoh AlMutabarah itu berkumpul dalam sebuah organisasi bemama Jam'iyyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah yang kini dipimpin oleh Habib Luthfi dari Pekalongan, tanpa ada larangan bergerak sendiri-sendiri bagi masing-masing tarekat itu. Sementara itu, DR Soedjatmoko mengibaratkan aliran kepercayaan kejawen bagaikan semak-semak bertanaman perdu yang tidak dapat tumbuh tinggi dan juga tidak beraturan. Ada semak-semak yang tebal dan rapat tanamannya, dan ada pula semak-semak yang bertanaman jarang. Itu semua karena tidak ada yang mengatur. Tetapi diantara kumpulan demi kumpulan semak-semak itu, tumbuh menjulang tinggi di sana-sini pohon-pohon yang tinggi. Nah, pohon demi pohon tinggi yang tidak beraturan tempatnya itu, melambangkan guru-guru atau para bikhu yang memimpin berbagai gerakan kepercayaan kejawen tersebut. Ketiga gambaran di atas itu melukiskan dengan tepat berbagai gerakan kerohanian yang ada dan hidup di negeri kita. Memang masih banyak gerakan kerohanian yang tidak masuk dalam pembidangan yang dibuat mendiang Soedjatmoko itu, namun jelas bahwa ia mencoba memahami berbagai corak gerakan kerohanian yang ada di negeri kita. Orang boleh berbeda dengan mendiang Soedjatmoko, tapi mereka harus mengakui kategorisasi yang dilakukannya atas berbagai gerakan kerohanian yang kita miliki dewasa ini. Kurang atau lebihnya, tentu saja tokoh intelektual kita itu tidak berkeberatan akan kehadiran pandangan-pandangan lain, asal dapat dipertanggung jawabkan/dipertahankan secara argumentatif. Di sinilah terletak sumbangan pemikiran mendiang tokoh tersebut, yang tidak lain adalah ipar Sutan Sjahrir, yang beberapa kali menjadi Perdana Menteri kita dan merupakan salah seorang pendiri negara ini. Kedua tokoh itu justru berprinsip dari perbedaanlah akan muncul kebenaran. ***** Kita sekarang berada pada era baru dari keberagaman spiritualitas yang kita miliki. Ada kerohanian yang menuntut kesetiaan untuk melaksanakan ajaran-ajaran formal agama. Dari mereka juga lahir organisasi-organisasi agama yang menuntut dilaksanakannya ajaran-ajaran agama secara resmi/formal oleh negara. Tuntutan demi tuntutan dari mereka, pada akhimya akan berujung pada pemberlakuan ajaran agama tertentu dalam kehidupan bemegara kita. Dengan kata lain, tuntutan pemberlakuan syariah (hukum agama) dalam kehidupan bersama yang kita miliki ini bukan tuntutan main-main, karena hal itu dikemukakan oleh orang-orang yang menurut penilaian kalangannya- hidup jujur dan ikhlas untuk kepentingan agama Islam yang mereka cintai. Hal ini sudah berjalan begitu jauh, sehingga beberapa DPRD dan pemerintah daerah melakukan adopsi atasnya. Pemerintah atau pihak eksekutif telah membahasnya dengan seksama dalam Sidang Kabinet kira-kira sebulan sebelum penulis dilengserkan. Dalam sidang itu,
kabinet memutuskan bahwa peraturan demi peraturan kearah syariatisasi itu dianggap tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan-ketentuan UndangUndang Dasar. Hanya saja siapakah yang berhak memberikan tafsiran seperti itu? Tentunya -seperti juga terjadi di negeri-negeri lain, Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi di bidang yudikatif yang berwenang untuk itu. Tetapi bagaimana halnya dengan MA yang kita miliki sekarang ini ? Penulis menilai mereka tidak mempunyai pendirian pasti mengenai apa yang benar dan tidak menurut Undang-Undang Dasar. Jika mengambil keputusan saja tidak berani, bagaimana pula memberikan penafsiran? Karena itu kita sekarang berada dalam persimpangan jalan yang tidak jelas, yang pada akhimya mengakibatkan ketakutan di berbagai pihak, termasuk dari golongan minoritas etnis dan agama. Ketidakpastian hukum itu, juga menjadi sebab utama bagi langkanya investasi modal asing di negeri kita. Kita berharap pemilu legislatif dan pemilu Presiden di tahun akan datang, akan menyudahi ketidakpastian seperti ini, sehingga kita dapat kembali bekerja seperti dahulu, dengan semangat dan tekad baru yang diperlukan untuk mengatasi krisis multi-dimensi yang menghinggapi kita saat ini. Tentu saja, harus ada kejelasan siapa yang akan memimpin tahap mengatasi berbagai macam krisis tersebut, karena rakyat sudah demikian jauh terpuruk kehidupan mereka. ***** Dari gambaran seperti dicontohkan mendiang DR. Soedjatmoko di atas, dapat disimpulkan bahwa model hidup seragam, seperti yang diajarkan pemerintahan Orde Baru tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Sikap penyeragaman seperti itu, sangat berlawanan dengan spiritualitas/kerohanian yang kita miliki. Justru keberagamanlah yang kita perlukan. Karena itulah, penulis lalu menekankan perlunya pemisahan antara agama dan negara, itupulah yang membuat penulis menentang pemberlakuan pendidikan agama oleh negara. Kalaupun negara harus membantu pendidikan salah satu agama melalui sekolah-sekolah, itu pun hanya sebagai bantuan yang tidak mengikat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Negara tidak wajib menyelenggarakan pendidikan agama, karena akhimya hanya akan mementingkan versi ajaran yang disetujui negara. Akibat dari itu, maka akan timbul bukannya keberagaman yang seperti kita kehendaki. Memang sulit memahami dan merasakan kebutuhan akan keberagaman, selama kita sendiri tidak menyakini dengan sesungguhnya maksud Undang-Undang Dasar kita sendiri. Sulit menegakan kebenaran di tengah-tengah keberagaman pendapat seperti di negeri kita saat ini, bukan?
Kepergian Setelah Mengabdi
Oleh: Abdurrahman Wahid Seorang lagi dari deretan tokoh-tokoh kita telah meninggalkan lingkungan, setelah lama menderita sakit: Dr. Nurcholish Madjid. Banyak sekali orang yang merasa kehilangan dengan kepergiannya pada usia 66 tahun itu. Padahal, itu adalah usia yang mencerminkan kematangan hidup, terlebih-lebih pada masa penuh kesalahpahaman dan salah pengertian satu sama lain, terkadang diwamai oleh ledakan bom dan lemparan granat. Ada perbedaan faham yang fundamental antarsesama warga gerakan Islam dan hampir selalu berakhir pada hilangnya toleransi dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Nurcholish Madjid atau Cak Nur tetap konsisten dengan gaya hidupnya di tengahtengah masyarakat. Ia tetap mempergunakan cara-cara menolak pemakaian kekerasan. Ia dimaki-maki oleh begitu banyak orang, sehingga sangat lucu melihat bagaimana ia dimaki-maki dan diumpat-umpat untuk berbagai dosa yang tidak pemah dilakukannya. Bahkan, setelah ia meninggal pun, masih ada orang yang menganggapnya ia melakukan hal-hal yang tidak pemah dikerjakannya selama hidup. Cercaan dan umpatan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa di telinganya sewaktu ia hidup. Bahkan, setelah meninggal, masih ada yangkarena kekerdilan jiwamengatakan secara lisan bahwa ia seharusnya sudah bertobat. Padahal, yang seharusnya melakukan hal itu bukanlah Cak Nur, melainkan orang itu sendiri. Bukankah kitab suci Al Quran memuat salah satu sifat yang mulia adalah kemampuan memberikan maaf kepada siapa pun untuk kesalahan apa pun. Di sinilah terletak kebesaran Cak Nur. Ia berhasil mendidik kaum Muslimin pada umumnya bahwa sifat yang seperti itulah yang harus dikembangkan terus dalam kehidupan mereka. Apakah artinya ini? Artinya, bahwa kita semua harus mengikuti teladan yang diperlihatkannya itu. Bahwa hampir seluruh kaum Muslimin di negeri ini bersikap demikian, itu adalah bukti bahwa Cak Nur telah berhasil dengan pendidikannya itu. Ia yang lahir di Desa Mojoduwur, Kecamatan Bareng, di Jombang, Jawa Timur, itu akhimya menjadi contoh bagi semua warga bangsa yang berjumlah lebih dari 210 juta jiwa itu (menurut hitungan Prof Dr Prijono Tjiptoherijanto) Kita belum lagi berbicara tentang Islam sebagai bidang kajian, tempat Cak Nur menghabiskan umur. Sebagai ilmuwan, ia tidak mau berkompromi dengan politik sama sekali. Orang boleh berbicara di sinilah terletak kekuatan Cak Nur, atau sebaliknya menganggap itulah titik lemahnya.
Bagi penulis, hal itu tidak penting benar karena ia tidak menjadi besar atau kecil dalam hal ini. Ia akan tetap diakui sebagai salah satu pemegang otoritas studi keislaman (Islamic studies) di negeri kita. Tentu saja ia punya sederet kesalahan karena ia adalah seorang anak manusia, tetapi kesalahan-kesalahan itu tidaklah memudarkan namanya (atau menurunkan nilai dirinya). Ia adalah orang besar, karena ia memang demikian. Kini ia telah tiada, dan menjadi kewajiban kita untuk mengembangkan Nurcholish-Nurcholish baru. Hanya dengan cara demikian kita patut disebut pengikut Cak Nur di masa hidupnya. Orang-orang lain, termasuk mereka dari garis kekerasan, adalah orang yang ditinggalkan oleh perkembangan Islam, dan akan pudar dengan sendirinya ditelan masa. Jakarta, 29 Agustus 2005
| Islam | Demokrasi | Dunia | Budaya | Isuaktual |
Kerudung dan Kesadaran Beragama Oleh Abdurrahman
Wahid
Kerudung adalah 'pemandangan' biasa di kalangan kaum muslimin yang taat beragama.Tidak semua wanita muslim dikenal dengan sebutan muslimat, menggunakannya. Namun porsi pemakainya cukup besar guna melekatkan predikat 'biasa' di atas. Ke pasar, rumah sakit, masjid maupun pesta dan upacara, pendeknya ke semua keperluan di luar rumah , kerudung selalu di pakai, begitu juga dirumah, kalau sedang ada tamu. Ada yang berwama-wami, terkadang dihiasi renda dan sulaman indah: ada juga yang polos, hanya pinggimya saja yang disentuh benang jahitan. Ada yang memang dipakai menutup rambut seluruhnya, namun tidak kurang pula yang hanya disangkutkan pada bahu, tidak sampai menghalangi pandangan mata keseluruh sanggul di 'sasak' lebar-lebar, dengan diameter tidak kurang dari ban sekuter Vespa atau Bajaj! Biasanya yang begini adalah tanda krisis identitas: tidak
berani meninggalkan identitas diri sebagai muslimat, tetapi enggan disebut kampungan. Tidak disangka tidak dinyana, penggunaan kerudung dapat juga menimbulkan pertentangan pendapat, antara mereka yang menentang dan yang mempertahankan. Tidak terduga sebelumnya kerudung dapat menjadi titik sengketa, fokus sebuah konflik sosial. Padahal, tadinya masalah penggunaan kerudung dianggap masalah sepele saja. Yang masih kuat bertahan pada identitas 'kesantrian' terus memakainya, yang sudah tidak merasa perlu sudah meninggalkannya. Juga ada peragu yang menggunakannya di atas bahu sewaktu ada pesta atau upacara. Apakah gerangan yang membuat pemakaian kerudung menjadi masalah peka, padahal sekian lama ia 'dibiarkan' pada keputusan pribadi masing-masing di kalangan kaum muslimat? Masalahnya berkisar pada munculnya kerudung itu sendiri sebagai simbol. Selama ini , simbol tersebut, yaitu simbol ketaatan beragama bagi yang memakai dan simbol 'kekampungan' bagi yang tidak mengenakannya, hidup berdampingan secara damai. Masing-masing berkembang didunianya sendiri, bagaikan polisi dan pencuri, seirama dengan pelapisan masyarakat begitu ruwet dan kompleks. Tidak pemah ada pertentangan terbuka, tidak pemah didiskusikan perlu atau tidaknya menggunakan kerudung. Apalagi dilokakaryakan atau di seminarkan. Masalahnya menjadi berbeda, ketika berkembang sebuah kesadaran baru di kalangan kaum remaja muslim. Mereka adalah generasi yang serius melihat segala sesuatu dalam hidup ini, dari jerawat di pipi hingga pandangan hidup yang diidealkan masing-masing. Begitulah, ketika seorang anutan yang dianggap memiliki wewenang penuh merumuskan 'kebenaran agama' memerintahkan remaja asuhannya untuk memelihara 'aurat' berdasarkan ketentuan Islam. Dengan serta merta anjuran itu diikuti, termasuk oleh siswi SMA lalu mengenakan kerudung dilingkungan sekolah. Sudah tentu ini 'pemandangan' tidak , jauh dari 'kebiasaan' berseragam sekolah tanpa tutup kepala sama sekali. Dua hal 'dilanggar' oleh perbuatan itu. Pertama, 'konsensus' selama ini, yang juga tidak begitu didasari dahulu, bahwa kerudung bukanlah pakaian yang 'layak' untuk siswi-siswi sekolah nonagama. Kedua, kecenderungan kepada uniformitas sikap dan perilaku, yang dicoba untuk 'ditegakkan' oleh lingkungan pendidikan nasional kita. Dari pesuruh sekolah sampai Menteri P dan K, besar sekali nampaknya kecenderungan untuk menyeragamkan pandangan sikap dan perilaku 'keluarga besar pendidikan nasional' Sudah tentu 'konsensus' dan kecenderungan di atas segera mengeluarkan reaksi balik atas prakarsa siswi SMA yang menggunakan kerudung pergi ke sekolah itu. Dapat di terka, senjata utama yang digunakan pihak pimpinan sekolah adalah 'pelanggaran disiplin'. Benar saja, atas dalih itu sang siswi itu dikeluarkan dari sekolahnya.
Pemecatan dapat dilakukan, selama ada kesamaan pandangan antara pihak 'penegak disiplin' dan pihak-pihak lain di luar. Berarti dalam kasus-kasus di mana ada kejelasan bahwa si 'pelanggar disiplin' memang bersalah atas persetujuan universal semua pihak. Kesulitannya adalah kalau cukup banyak jumlah orang yang tidak sependapat, seperti dalam kasus kerudung di Bandung baru-baru ini. Lalu disebutkanlah hal-hal yang meragukan kebenaran tindakan disipliner yang dijatuhkan atas diri 'siswi berkerudung' itu. Pelanggaran hak pribadi sang siswi untuk mengenakan pakaian yang disenanginya, tuduhan pimpinan sekolah bersikap 'memusuhi Islam' dan lainlain tuduhn lagi dilemparkan seenaknya. Apa yang dilupakan kebanyakan orang adalah penglihatan global terhadap masalah kerudung itu. Ia tidak lain adalah pencerminan dari kuatnya tuntutan di kalangan remaja muslim, agar ajaran Islam dilaksanakan secara tuntas dan konsekuen. Ia adalah bagian dari ketekunan yang semakin bertambah untuk meramaikan masjid, merumuskan 'sikap Islam' terhadap berbagai masalah, dan keberangan terhadap apa yang digeneralisasi sebagai 'pandangan-pandangan sekularistis' di kalangan kaum muslimin sendiri. Kasus kerudung itu adalah bagian dari meningkatnya kesadaran beragama di kalangan kaum remaja muslim dewasa ini. Kesadaran itu muncul dari banyak sebab. Diantaranya adalah kekecewaan terhadap kebangkrutan teknologi dan ilmu pengetahuan modem , yang diredusir kedudukannya menjadi hamba kekuasaan modal saja, tanpa membawa perubahan mendasar atas tingkat kehidupan manusia. Juga kekecewaan melihat terbatasnya kemampuan umat manusia untuk mencari pemecahan hakiki atas peroalanpersoalan utama yang dihadapinya. Tidak kurang pentingnya adalah juga kekecewaan mereka terhadap kegagalan elite kaum muslimin di seluruh dunia, yang tidak mampu mengangkat derajat agama mereka di hadapan tantangan 'pihak luar' terhadap Islam. Dapat di mengerti kalau kesadaran itu juga mempunyai imbas fisiknya atas perilaku para remaja muslim di mana-mana termasuk mereka lalu memelihara jenggot dan memakai kerudung. Perilaku seperti itu tidak sepatutnya diremehkan dan disepelekan, karena ia merupakan bagian dari kesadaran untuk menegakkan Islam sebagai 'jalan hidup'. Boleh kita tidak setuju dengan aspirasi holistik seperti itu, namun dihargai sebagai upaya untuk menemukan Islam dalam kebulatan dan keutuhan, jadi motifnya berwatak transendental. Kalau tidak diperhitungkan 'tindakan disipliner' atas 'pelanggaran gadis berkerudung' di salah satu SMA di Bandung itu dari sudut kesadaran beragama ini, terlepas dari keputusan apa yang akan diambil, maka sebenamya tindakan itu tidak memecahkan masalah. Ia hanya menunda atau memindahkan persoalannya saja. Kasus-kasus serupa akan tetap muncul, dengan intensitas dan implikasi yang mungkin semakin gawat bagi masa depan kita semua sebagai bangsa.
Ketat Tetapi Longgar Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kiai pantai utara Jawa ini terkenal keras sikapnya, kaku pikirannya, dan ketat dalam perumusan pendirian keagamaannya. Entah di sebelah barat, seperti di daerah Cirebon, entah pula di timur. Keyakinan agama para kiai pesisir itu kokoh, sekokoh batu karang yang sesekali menghiasi lepas pantai mereka yang dangkal. Hukum agama yang mereka rumuskan berwatak tegar, sedikit sekali mempertimbangkan keadaan mannusiawi masyarakat di mana mereka hidup. Tidak heranlah jika Kiai Wahab Sulang dari Rembang sempat membuat heboh di kalangan yang sedemikian tangguh keyakinan dan ketat perumusan hukum agamanya. Bagaimana tidak heboh, kalau istrinya yang anggota DPRD itu termasuk yang paling asyik dan getol mengikuti acara non-santri di pendopo kabupaten. Sudah fraksinya F-PP, masih campur baur lagi dengan nyonya-nyonya Golkar dan Kopri dalam acara 'maksiyat' yang berupa tarian-tarianJawa gendingan. Bagaimana tidak geger kalau istrinya kian kemari tanpa 'mahram' yang mengawal, sering dalam rombongan yang berisi para pria saja. Pola tingkah laku 'non-santri' seperti itu tidak heran sebenamya kalau datang dari Kiai Wahab Sulang. Karena memang ia tidak pemah konvensional. Tindakannya sering kali timbul dari spontanitas sendiri saja. Sewaktu istrinya baru mendapat pembagian sepeda motor (dengan pembayaran kembali secara diangsur, tentunya), kiai kita ini segera menggunakannya. Sebagai akibat ia menabrak sebuah rumah. Sepeda motor rusak dan ia sendiri luka-luka. Penjelasan kiai: "Habis saya pakai rem kaki". "Lho, rem kaki 'kan memang harus dipakai dalam hal ini, Kiai."
"Ya, tetapi maksud saya bukan begitu: saya mengerem hanya pakai kaki saja. Karena belum tahu bagaimana dan di mana remnya." Menarik untuk dikaji, bagaimana kiai tidak konvensional seperti ini masih diikuti orang. Mengapa ia masih di terima di lingkungan sesama kiai? Mengapa ia tidak diserang dan 'disensor' oleh klai-kiai lain? Mengapa dibiarkan saja ia memberikan pengajian umum, memberikan fatwa hukum agama kepada yang datang memintanya, dan melakukan fungsi ke-kiai-an secara penuh? Apakah hanya karena ketenarannya sebagai orang 'jaduk' yang kebal senjata tajam dan tidak mempan peluru? Kemampuannya mengobati orang dengan do'anya yang mustajab? Temyata tidak demikian persoalannya. Ada sebuah jawaban yang menunjukan
lentumya hubungan antara sesama kiai di pedesaan Jawa. Sebabnya terletak pada kesanggupan Kiai Wahab yang eksentrik itu untuk secara minimal mengikuti garis bersama, sedangkan pada saat yang sama mengikuti pola berpikir tidak konvensional itu. Dalam forum yang merumuskan hukum agama, Kiai Wahab terkenal sama keras pendiriannya dengan para kiai lainnya. Sama ketat perumusan hukumnya. Sikap begini terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut dogma keagamaan: ia mengikuti konsensus dalam hal yang sudah ditetapkan, dan dengan demikian ia mengikuti pola umum sikap para kiai secara nominal. Tetapi sikap di atas tidak dapat membatasi Kiai Wahab Sulang hanya pada pendekatan legal-formalitis belaka, tanpa mampu mengembangkan sikap adaptif terhadap kebutuhan masa. Dan kehebatan kiai yang ini justru terletak dalam kemampuannya mencari landasan keagamaan bagi sikap yang longgar terhadap kebutuhan manusiawi. Anda butuh transfusi darah, tetapi takut hukum agamanya haram menerima donasi darah orang lain? Sikap yang salah, menurut Kiai Wahab. Orang Islam harus bertolong-tolongan, bukan? Allah 'kan berfirman 'bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan!' "Ya, kiai, memang demikian, tetapi bukankah donor darah menyangkut soal hubungan kekeluargaan dan sebagainya?" "Sampeyan ini tidak ingat firman 'permudahlah oleh kalian, jangan persulit' (yassiru wa la tu'assiru)! Asal tujuannya baik, dan untuk menolong manusia lain, apa salahnya?" Untuk manusia kosmopolitan, sikap seperti ini bukanlah barang baru. Tapi pentingnya sikap ini baru dapat dirasakan dalam situasi di mana pendidikan nonagama masih dilihat dengan penuh kecurigaan; dan di mana segala sesuatu justru ditinjau dari rumusan legal-formalistik hukum agama. Dan justru di sinilah letak nilai penting dari sikap Kiai Wahab tersebut: sikap untuk merumuskan kembali hukum agama dengan mempertimbangkan kebutuhan manusiawi masyarakat. Jadi, sikap untuk meninjau kembali keseluruhan wawasan legal - formalistik itu sendiri. Bukankah ini titik tolak pandangan hidup serba humanistik yang kini begitu dipuja orang? Tetapi Kiai Wahab memiliki kelebihan atas semua orang humanistik dan kosmopolitan, yaitu bahwa benih-benih humanistisnya secara kongkrit dilandaskannya pada keyakinan agama dan kebenaran firman Allah; sedangkan kita justru sering mempertentangkan antara keduanya. Kelebihan ini harus diakuinya lebih-lebih karena ia dimiliki oleh kiai desa yang tidak dapat menggunakan rem sepeda motor.
Ketika Santri 'Mengikuti' Rekaman Wayang Oleh:
Abdurrahman
Wahid*
Semasa mengikuti pendidikan SMEP di Growongan Lor (Yogyakarta), penulis indekost di rumah H. Djunaidi di Kauman Jogyakarta untuk 3 tahun lamanya. Tokoh yang kemudian menjadi anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu adalah penjahit terkenal di kotanya. Penulis sendiri yang baru berusia belasan tahun waktu itu, pada pertengahan 1954 hingga pertengahan 1957, sering kali menimba ilmu fiqh dari beliau. Juga cara hidup beliau yang penuh degan kesederhanaan, di samping penghormatan tulus kepada para ulama baik dari lingkungan organisasinya, maupun dari Nahdalayul Ulama (NU), terasa sangat mengesankan bagi penulis pada usia formatif (pembentukan kepribadian) tersebut. Salah satu kegemaran beliau adalah memperdengarkan rekaman radio dari pagelaran Ketoprak, yang disiarkan Radio Republik Indonesia (RRI) stasiun Yogyakarta. Baru-baru ini, saat 2 hari 2 malam penulis mengulangi pengobatan matanya di sebuah tempat, penulis membawa rekaman pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Timbul Hadiprayitno, dengan lakon/cerita Kamo Tanding. Selama masa pengobatan itu, rekaman pagelaran wayang kulit yang terdiri dari 8 buah kaset itu diselesaikan oleh penulis. Kaset terakhir, penulis dengarkan dalam cassette player yang ada dalam sistem suara (sound system) mobil. Terjadi dialog antara diri penulis, sistem nilai yang dianutnya dengan sistem nilai yang digunakan dalam kisah epic karya seorang sarjana India itu, yang penulis baca puluhan tahun yang lalu. Segitiga nilai itulah yang ingin penulis kemukakan dalam artikel ini. Dalam hal ini perbenturan nilai-nilai itu menjadi sangat penting bagi penulis, dan ia ingin berbagi rasa dalam proses tersebut. Dahulu, seorang santri (penganut ajaran Islam yang taat pada angamanya), tidak akan menonton wayang kulit. Ini dialami KH. Ahmad Mutamakkin (Kajen, Pati), yang memimpin sebuah tarekat, diadili oleh Menteri Agama (Khatib Anom) cucu/turunan Sunan Kudus, Jafar Shadiq. Dalam proses pengadilan di jaman Amangkurat IV itu, seperti diceritakan oleh Serat Cebolek ditinjau ulang dan dijadikan disertasi doktor oleh R. Subardi pada Monash University di Melboume (Australia), Khatib Anom membela pendirian para ahli fiqh di paruh kedua abad ke18 Masehi itu. Serat Cebolek itu bercerita tentang dialog dalam proses itu, yang mengemukakan bahwa KH. Mutamakkin (disebut sebagai Kyai Mutamakkin), yang menurut versi keraton/penguasa akhimya kalah dan minta ampun. Dalam versi lain, yaitu Kidung yang beberapa tahun lalu dibacakan dalam Khaul/peringatan kematian beliau tiap tahun di Kajen, dihadiri oleh sekitar 100.000 orang Kyai Mutamakkin justru memenangkan atas Raja Pakubuwono II dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Dalam hal ini, Raja tersebut justru mengikuti Suluk
(teks doa-doa) dalam tarekat yang dipimpin Kyai kita itu. Salah satu tuduhan yang diarahkan kepadanya oleh para ahli Fiqh, adalah kegemarannya untuk menonton wayang kulit, terutama dengan lakon Bima Sakti/ Dewa Ruci, seperi penulis yang telah dua kali mengundang dua orang dalang (termasuk Ki Entus dari Tegal) untuk mengelar wayang kulit di dekat rumahnya, di Ciganjur Jakarta-Selatan . Dalam rekaman Kamo Tanding itu, dalang mengemukan bagaimana perang tanding menggunakan jemparing (panah) antara Adipati Kamo dan Arjuna. Yang menarik versi Jawa itu mengemukakan, bagaimana Prabu Salya (mertua Adipati Kamo) menghentakan kuda penarik kereta yang dikusirinya, sehingga sang Adipati Kamo yang sudah meluncurkan panah Kuntawijayadanu, terpaksa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana senjata pusaka itu hanya mengenai rambut atau mahkota Arjuna, Raja Amarta. Pada saat itu, Raja Krisna dari negara Dwarwati, menjadi kusir kereta (chariote) yang digunakan Arjuna. Ia pada saat itu meminta Prabu Arjuna, untuk melepaskan anak panahnya, senjata pusaka Pasopati. Anak panah mengenai Adipati Kama, dan ia mati seketika. Buku mengenai tokoh-tokoh Mahabarata yang ditulis orang India itu, menggambarkan Krisna sebagai tokoh licik (master of deceit) yang penuh dengan tipu daya dalam menghadapi lawan. Dalam rekaman lakon yang diceritakan Ki Timbul itu, Prabu Krisna adalah seorang tokoh setia yang jujurjujur saja. Kalau perbedaan dua versi ini menggambarkan bagaimana obyek dapat di lihat oleh dua pendekatan budaya yang berbeda (dalam hal ini antara India dan Jawa), maka dapat dimengerti jika penulis artikel ini juga mempunyai pandangannya sendiri mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di mata penulis, KPU melakukan kecerobohan dalam persiapan pemilu tahun ini, memihak kepada peserta tertentu dan melakukan manipulasi penghitungan suara. Di mata orang lain, KPU adalah lembaga formal/resmi yang tidak dapat diganggu gugat. Hal lain, yang sangat menarik perhatian penulis, adalah pesan abadi yang dibawakan Ki Timbul. Dalang bercerita, Arjuna menolak untuk menjadi senopati/ panglima perang kaum Pandawa. Ini berarti, ia harus bertempur sampai mati melawan kakak lain ayah, yaitu Adipati Kamo Raja Muda (viceroy) Awangga, yang menjadi Senopati Agung dari pihak Kurawa. Ada persamaan antara sikapnya itu dengan ucapan Nabi SAW: Bukan golongan kita, orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua (Laissa minna mallam yarham saghiranaa, walaa yuwaqqir kabiirana). Baru setelah ada laporan, bahwa Adipati Kamo mempermalukan dirinya dengan melepas senjata pusaka berupa anak panah bukan untuk membunuh Wara Srikandi (istri Arjuna), melainkan hanya untuk membuat terlihat payudaranya, maka Prabu Arjuna pun langsung meminta diangkat menjadi senopati/ panglima perang kaum Pandawa. Episode di atas menunjukkan, bahwa kakuatan saja tidak cukup untuk digunakan menopang sebuah pemerintahan melainkan ada aspek lain yang harus dimiliki juga, yaitu batas-batas moral dalam penyelenggaraan kekuasaan. Tanpa moralitas yang kokoh, kekuasaan hanya akan membawa kasulitan dan keboborokan hidup
bersama belaka. Kembali ingatan penulis melayang ke KPU lagi. Pelanggarannya atas 5 buah Undang-Undang menunjukkan tidak adanya kedaulatan hukum di negeri kita saat ini. Apalagi dijalankan dengan sikap sangat arogan/sombong, yang justru sepi dari wawasan moral tersebut. Dalam hal ini, penulis ingat kepada firman Allah Swt Dan jangan kalian campur adukan kebenaran dengan kebathilan, serta jangan kalian tutup-tutupi kebenaran, jika kalian ketahui (Wa la talbisu alhaqqa bi al-bathil wa taktumu al-haqqa wa antum talamu). Demikianlah dua buah pelajaran penting yang penulis ambil dari rekaman pagelaran wayang dengan dalam Ki Timbul Hadiprajitno tersebut. Yaitu bahwa setiap masalah dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan dan bahwa moralitas adalah pesan abadi yang harus terus menerus diperjuangkan dalam kehidupan, termasuk kehidupan kita bersama selaku bangsa dan negara. Jika ini kita lupakan, jadilah kita orang-orang yang hanya bersandar pada kekuasaan belaka, sedangkan sebenamya ia hanyalah alat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur menurut pembukaan undang-undang dasar kita sebagai sebuah proses jangka panjang, yang dituangkan dalam perjuangan menegakkan demokrasi. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan? Kiai Dollar Berdakwah Oleh
Abdurrahman
Wahid
Gerak-geriknya memang mirip wanita. Serba luwes,termasuk caranya berbicara dan tertawa yang tampak seakan-akan manja. Belum lagi kegemarannya memukulkan tangan pada orang lain yang diajaknya berbicara untuk menekankan suatu ungkapan yang juga sangat luwes, 'Ah masak begitu, Mas!' Gaya kewanitaan itu lebih-lebih terlihat dalam ketelitiannya memilih barang, dan kepandaiannya untuk tawar-menawar dalam apapun, dengan menunjukkan hal-hal kecil sebagai poin untuk tawarannya sendiri. Dan terakhir, kepandaiannya memasak yang sudah legendaris: sewaktu menjadi mahasiswa Universitas AI-Azhar di Kairo, ia adalah sandaran kaum ibu-ibu Kedutaan besar Rl dalam keperluan masak-memasak dan hidangan untuk resepsi dan sebagainya. Pantaslah kalau ia sering diselorohi dengan panggilan 'tante'. Penampilan itu temyata bukan datang dari penampilan seorang eks pria yang kemudian menjadi wanita 'penuh' dengan cara berganti kelamin, seperti Vivian Rubianti beberapa tahun lalu. Ia muncul dari seorang kiai yang memiliki ilmu agama yang cukup dalam dan lama sekali hidup di lingkungan pesantren. Sejak masa kanak-kanak, ia sudah bergumul dengan kitab-kitab kuno keagamaan, yang sejak semula masa pertumbuhannya sudah terikat dengan norma-norma keagamaan dengan nilainya yang menetap. Sebagai murid Kiai ldris selama bertahun-tahun di Tebuireng semasa usia belasan tahun, ia telah terlatih dalam ilmu-ilmu keagamaan tradisional, bahkan sebelum ia berangkat meneruskan pendidikan dalam hukum agama (syari'ah) Islam di Timur Tengah.
Sepenuhnya identitas ke-kiai-annya memiliki kredibilitas penuh, didukung oleh peranannya sebagai salah seorang mubaligh di ibu kota dewasa ini. Lebih di kenal dengan gelar Ustadz karena penampilannya yang membawakan vitalitas orang muda (walaupun sedikit banyak sudah di'rasuki' gaya jadi orangtua),ia merupakan sasaran kajian yang menarik untuk diperhatikan. Bukan karena gaya kewanitaannya itu, bukan karena vitalitas usia muda yang diperlihatkannya, dan bukan karena ia kini sudah mulai mengarah kepada sikap orang tua. Yang membuat kiai ini menarik adalah pandangan dunia yang dikembangkannya, yang sepenuhnya berlandaskan keyakinan kepada kebenaran ajaran-ajaran agama yang dihayatinya sejak kecil. Pandangan dunia yang sering diharapkan akan memunculkan ke'khusuk'an (asketisme) hidup yang jauh dari perhatian kepada masalah-masalah duniawi. Diharapkan dari seorang kiai hasil didikan Kiai ldris Tebuireng, tak akan menyimpang dari acara lama amar makruf nahi munkar yang biasa dikumandangkan para muballigh dalam uraian-uraian mereka. Atau kalau tidak begitu, akan mengambil sikap agresif, menyerang tanda-tanda kerusakan moral, terutama di kalangan muda, sebagai bukti dari kerusakan akibat kehidupan modem yang sedang merayap ke bumi Indonesia juga. Temyata bukan itu yang muncul dari Kiai Masyburi Syahid. Ia justru memberikan perhatian sangat besar kepada soal-soal duniawi, terutama perdagangan. Maklum ia dulu juga senang berdagang di kalangan masyarakat Indonesia di Kairo. la senang dengan isu-isu kemasyarakatan, karena ia terlibat dalam bebagai usaha sosial. Di samping menjadi sekretaris Yayasan lkatan Alumni Timur Tengah di Jakarta, ia juga aktif dalam sebuah lembaga penganjur transmigrasi dan sebuah organisasi antar pedagang kecil. Bahkan ia memotori penataran teknis elementer di bidang pengetahuan usaha bagi para anggota ikatannya, pedagang kecil dari berbagai sudut Jakarta, bekerjasama dengan PPN (Pusat Produktivitas Nasional). Sorban yang tersampir di bahunya tidak menghalanginya untuk melakukan transaksi dagang dengan siapa pun. Tidak heranlah kalau muncul mutiara keagamaan tidak sedikit, yang menggambarkan kecenderungan dan pandangan hidupnya itu. Seperti penafsiran 'kontemporer'-nya atas ayat AI-Qur'an "Jika kalian mendapat teguran (baik), balaslah dengan tegur sapa yang lebih baik (wa idza huyyitum bitahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha).
Tahiyyah, menurut Kiai Masyhuri, bukan hanya tegur sapa secara vokal atau oral belaka. la memiliki arti lebih ajuh, hingga mencapai semua perbuatan yang menunjukkan penghargaan dan kepercayaan kepada kita. Kalau orang membeli barang yang kita produksikan, itu berarti tahiyyah, tegur sapa dalam arti paling dalam, Nah, kita wajib menjawabnya dengan tahiyyah lebih baik, tegur sapa nonoral lebih baik: peningkatan kualitas barang yang kita tawarkan kepada pembeli.
Ini adalah esensi perbuatan membalas tahiyyah yang baik dengan tahiyyah yang lebih baik. "Ini menurut saya adalah ayat advertensi ," demikian Kiai Masyhuri dalam salah satu acara tabilgh-nya. Herankah kita kalau ada penamaan pada kiai yang satu ini, dengan pesan agamanya yang begitu kontemporer, sebagai kiai dollar? Kiai Ikhlas dan Ko-edukasi Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kyai Sobari sudah berusia lebih dari tujuh puluh tahun. Tidak lagi kuat berpergian jauh-jauh dari rumah. Terkena angin sedikit bisa kumat asmanya yang sudah menahun. Sudah hampir dua tahun ia berhenti mengajar di Pesantren Tebuireng, yang terletak 5 kilometer dari desanya. Selama 33 tahun jarak sekian itu ditempuhnya hampir setiap hari, untukmenunaikan tugas mengajar, yang dirumuskannya sebagai "membayar utang ilmu kepada Hadratus Syaikh Kiai Hasyim Asy'ari." la tidak meminta jabatan formal apapun di pesantren itu, tak mengharapkan imbalan apapun. Corak kiai yang begini disebut oleh kalangan pesantren sebagai orang yang ikhias, tulus tanpa pamrih dalam pengabdiannya. Mungkin karena ikhlasnya itulah do'anya lebih diterima Allah, begitu komentar orang banyak. Karena itu pantas kalau khalayak ramai banyak meminta dido'akan agar sembuh dan penyakit atau lepas dari gangguan bermacam-macam, dari yang bersumber dari makhluk halus hingga ke persoalan kasar. Guraunya yang lembut dan menunjukkan kerendahan hati. Dan dengan keteguhan jiwa orang telah menemukan dirinya sendiri, Kiai yang satu ini dihormati semua orang, dicintai murid-muridnya dan disegani mereka yang mendapat perintah atasan untuk mengimbangi pengaruhnya dengan berbagai macam cara. Kesederhanaan hidupnya menjadi contoh bagi rakyat kecil untuk menanamkan derita yang timbul dari berbagai macam cobaan dalam hidup. Tetapi, tidak semua begitu cerah seperti digambarkan di atas. Pendiriannya yang sekokoh karang penghadang hempasan ombak di laut lepas, sering kali membuat sulit orang lain. la memang tidak sengaja membuat sulit, tetapi toh kesulitan lah yang muncul dari kiai ini. Pejabat yang harus mensukseskan program KB bisa pusing tujuh keliling mendengar permintaannya kepada rakyat agar berbanyak-banyak anak. 'Himbauan'-nya agar santri hanya mengurusi 'ilmu agama' membuat repot guru aljabar yang mengajar di kelas sebelah. Moralitasnya yang utuh dan bulat tetapi berjalan tunggal, sering membingungkan anak-anak muda yang lagi gandrung sesuatu yang sedang menjadi mode. Walhasil, gambaran kiai yang ikhlas tetapi kolot. Pergaulannya luwes, tetapi
pendiriannya
kaku.
Sudah tentu menjadi kejutan bagi penulis ini, ketika ia menyanjung SMP-SMA yang sudah tiga tahun berdiri di Pesantren Tebuireng. Ketika penulis ini berkunjung ke rumahnya beberapa bulan lalu, kiai tua ini menyatakan persetujuan atas tegaknya disiplin dan peraturan di kedua sekolah tersebut. Tidak seperti Madrasah Aliyah, katanya, semuanya belum sadar kepada peraturan. Apakah kiai ini tidak tahu bahwa kedua sekolah ini mencampurkan sisvva dan siswi dalam satu kelas, atau dengan kata lain mengadopsi ko-edukasi? "Tahu", katanya, "anak saya sendiri sekolah di situ. Karena itu saya tahu betul di situ peraturan dijaga dan ditegakkan", lanjutnya. Apa kiai tidak keberatan dari sudut pandangan hukum agama atas sistem koedukasi? "Tidak", jawabnya, "karena jelas tujuannya. Larangan bercampur aduk antara pria dan wanita 'kan ditujukan untuk menjaga moralitas dalam pergaulan, untuk menjaga keamanan dalam pergaulan. Jangan sampai ada penyelewengan. Itu saja tujuannya. Lha kalau mau aman-amanan, mana ada yang lebih aman dari ruang kelas?" Apa ada sekolah mengajarkan keburukan, ia balik bertanya. Di sinilah pentingnya peraturan ditegakkan. Peraturan sekolah menetapkan pergaulan antara sesama siswa harus berlangsung secara tertib dan menjaga tata kesopanan. Kalau peraturan ditegakkan, dari yang menyangkut absensi hingga kepada aturan pergaulan, sudah tentu tercapai tujuan menjaga moralitas dalam sistem ko-edukasi itu. Bagaimana dengan pakainan anak putri, yang menggunakan yurk? Berangsurangsur ditata yang baik,nanti akan diusulkan agar dianjurkan pakai yurk maksi, atau dalam istilah kiai kita rok landung, suatu istilah Belanda Jawa. Fleksibilitas kiai 'kolot' yang satu ini cukup menarik perhatian, kerena ia membawa implikasi bermacam-macam. Yang jelas, tidak benar anggapan kiai-kiai 'kolot' tidak memiliki rasionalitas dalam berpendapat, hanya mampu mengoper saja dari literatur fiqh kuno tanpa dikembangkan. Kiai kolot seperti Kiai Sobari ini memiliki logika dan rasionalitas mereka sendiri, walaupun mungkin tidak sama dengan dasar-dasar berpikir modem. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan keagamaan atas kasus-kasus kongkrit, sesuai dengan apa yang mereka anggap sebagai kebutuhan masa. Kalau rasionalitas seperti ini tidak membawa kepada pandangan rasional dalam pendapat Kiai Sobari tentang KB, bukankah anak-anaknya nanti yang akan berpikir seperti itu, tanpa harus terputus akar mereka dengan prinsip-prinsip keagamaan yang mereka warisi dari ayah mereka? Bukankah cukup banyak kiai yang menerima gagasan KB, walaupun ayah mereka dahulu tentu tidak setuju?
Kiai Khasbullah dan Musuhnya Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kiai Khasbullah Salim almarhum memang prang luar biasa. Orang Sedan (Rembang) yang kemudian tinggal di Jombang ini senang dengan keterusterangan sikap dan ucapan. Lugas dalam berbicara, teguh dalam sikap, berani melawan yang dianggap tidak benar. Sering kali hanya pakai "celana kiai" (celana dalam 'midi' hanya sampai sedikit di bawah lutut, biasanya dibuat dari kain belacu) sonder kaus dalam, kiai yang satu ini menganggap penegakan bukum agama sebagai inti perjuangan hidupnya. Keseluruhan hidupnya diabdikan untuk mengajar orang banyak di kampungnya yang akan banyak aspek kehidupan individual dan masyarakat yang belum sesuai dengan perintah Islam. Pendekatanya langsung ke pokok persoalan. Tidak selesal dengan adu argumentasi, kalau perlu adu jotosan. Mula-mula mendirikan ranting NU di Desa Denanyar, harus berkelahi fisik karena diejek terus-menerus oleh 'orang abangan' di tempat itu.Tidak heranlah sewaktu dia pindah ke desa Rejosari (delapan kilometer ke barat daya), segeralah ia terlibat dengan kasus baru yang dihadapinya. Di desa yang bersebelahan dengan Gadingmangu, muncul gerakan baru bemama Darul Hadith. Di bawah pimpinan 'Amirul Muloninin' Abu Hasan Ubaidah, gerakan itu kini memiliki nama lain, Islam Jama'ah, yang sempat membuat heboh beberapa waktu yang lalu. Di tahun-tahun limapuluhan belum ada Majelis Ulama Indonesia, jadi Kiai Khasbullah harus berjuang sendirian melawan 'bahaya dari timur' desanya itu. Sesuai dengan kelugasan seorang agamawan yang berpegang teguh pada keyakinan agama yang dianggapnya benar, ia segera mengajukan tantangan berdebat. Diceritakan pada penulis, perdebatan berjalan dua kali, di muka umum dalam rapat terbuka di atas mimbar. Pertama kali Kiai Khasbullah tidak berhasil mematahkan argumentasi lawan, ia langsung berteriak 'Siapa yang benar?', dan publik langsung membenarkan dia. 'Satu nol untuk pihak saya,' katanya. Kali dua, pihak Darul Hadith tidak mau dengan syarat begitu itu. Kembali adu argumentasi berlangsungsecara bertele-tele. Saling menyalahkan.'Setelah capek saya berdebat dan dia kelihatan tidak akan menyerah, langsung saya pukul dia. Saya menang lagi, dua nol untuk golongan saya, 'ucap kiai kita ini dengan polosnya. Sudah tentu perkembangan gerakan Ubaidah itu tidak terhenti hanya dengan skor dua nol itu. Homogenitas paguyubannya dan kohesi masyarakatnya membuat Darul Hadith semakin kokoh di Gadingmangu. Bagaimana halnya dengan Kiai Khasbullah? Beliau mengatakan kepada penulis beberapa waktu sebelum wafatnya beberapa tahun yang lalu: "Biar saja. Gurunya Ubaidah dulu, almarhum Kiai Zaid Semelo, pemah bilang kalau kenakalan Ubaidah tidak usah digubris. Nanti 'kan hilang sendiri kenakalan itu kalau dia mati. Ini
omongannya wali lho! Lagi pula sudah ada saling pengertian saya dengan pengikutnya di Gadingmangu. Tidak kita apa-apakan, asal mereka tidak tabligh ke desa lain di sekitamya, serta tidak membeli tanah di desa saya ini. Biar saja, becik ketitik ala ketara. Tampak kiai yang sepintas lalu tampak kasar sikapnya ini, karena kelugasannya dalam berbicara dan bersikap, menyimpan kearifannya sendiri. Pertentangan pendapat tidak semuanya diselesaikan; dan lebih-lebih tidak akan terselesaikan dengan melarang begini atau begitu. Adakalanya toleransi lebih memberikan hasil, sebagai upaya menahan perluasan pengaruh lawan. Dalam bahasa politik luar negerinya mendiang Dulles, sikap menahan perluasan pengaruh ini dilstilahkan sebagai containment policy. Cuma saja,Dulles tidak toleran kepada pihak lawan, main kepung saja dengan fakta-fakta pertahanan. Karena ini tidak searif Kiai Khasbullah. Mungkin Majelis Ulama Indonesia, yang pemah mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk melarang Islam Jama'ah, dapat belajar banyak dari 'strategi perjuangan' model Kiai Khasbullah ini. Setidak-tidaknya, toleransi kepada gerakangerakan 'sempalan' (splinter group) dalam Islam harus diperhitungkan sebagai salah satu jalan terbaik untuk mendewasakan sikap hidup umat secara keseluruhan. Bukankah kasihan umat yang harus melihat musuh di setiap pojok jalan dan seluruh penjuru angin? Kiai lskandar dan Pak Damin Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kiai Iskandar masih muda walaupun sering dituakan oleh orang-orang di sekitamya. Dalam umur belum tiga puluh tahun sudah jadi 'lurah pondok' di Pesantren Lirboyo. Ini tanda kepercayaan almarhum Kiai Marzuki dan Kiai Makhrus kepadanya. Bersekolah SMP Muhammadiyah semasa menjadi santri di pesantren tersebut, sedikit banyak ia menyatukan dalam dirinya dua jenis 'budaya santri': budaya akhlak pribadi serba tasawuf, yang menjadi 'merk' para kiai NU, dan budaya senang bekerja dalam jalur organisatoris untuk menangani masalahmasalah kemasyarakatan, yang menjadi 'cap'nya orang Muhammadiyah. Berkembangnya pola tunjang-menunjang antara kedua 'budaya santri' tersebut tambah diperkuat lagi oleh statusnya sebagai pegawai negeri, dus anggota kopri. Ke-kiai-an pesantren harus difungsikan seiring dengan tugas sebagai direktur di sebuah sekolah agama negeri, plus keterlibatan sebagai wakil ketua Majelis Ulama di kabupatennya. Pendekatan manusiawi yang sarat dengan kepemimpinan yang sanggup menyantuni masyarakat agraris di desanya, harus diimbangi oleh pola hubungan dengan guru-guru negeri yang menjadi anak buahnya. Akhlak ke-kiai-an yang mampu menyantuni segenap lapisan masyarakat, yang dikembangkan oleh gemblengan yang diterimanya di Pesantren Lirboyo,
membawanya juga kepada kemampuan mengelola harta masyarakat dengan penuh tanggungjawab. Maka pada usia muda ia terkenal dengan kejujuran finansialnya. Wakaf, infak dan sadaqah adalah harta masyarakat yang sering diamanatkan kepadanya. Juga titipan uang orang banyak untuk diusahakan, dengan cara ia menitipkan kembali kepada para petani dan pengusaha lokal. Selain fungsi bermacam-macam itu, ia punya Fungsi yang unik: menjadi clearing house bagi informasi soal perjodohan. Soal menghubungkan pihak-pihak yang akan berjodoh adalah spesialisasinya. Ini didukung oleh reputasinya sebagai orang yang berhasil mencarikan jodoh yang sesuai dan serasi. Ini tentu berkat ketajaman penglihatannya akan watak manusia, status sosial masing-masing dan lain-lain faktor yang harus diperhitungkan dalam soal perjodohan yang sukses. Sang kiai juga jadi wasit dalam sengketa harta di kalangan masyarakat, ditambah fungsi kerohanian untuk menolong mereka yang menderita di sekitamya. Bukan tanpa pengorbanan Kiai lskandar dapat melakukan fungsi seperti itu dengan penuh. la harus mampu menyesuaikan diri sepenuhnya dengan aspirasi kiai lain di daerahnya. la harus mampu mempelopori penerapan nilai-nilai keagamaan konvensional dalam kehidupan masyarakat. la tidak boleh menyimpang dari 'aturan permainan' tersebut. Bila ada orang kawin, ia harus memberikan sambutan standar yang sudah berumur ratusan tahun. Bila ada pengajian, ia harus mencanangkan pentingnya berakhlak konvensional, seperti menganjurkan salat secara tetap, melarang orang berjudi dan seterusnya. Di antara nilai yang harus dituntutnya adalah pembagian tugas antara 'kita orang santri' dan 'mereka yang bukan santri'. Tidak usah memusuhi, tetapi tidak pula boleh menggauli mereka secara akrab. Tidak boleh menyantuni dalam soal yang berada di luar persamaan sebagai penduduk yang sama-sama tinggal di satu desa. Di hari lebaran, tidak usah bertandang ke rumahnya. Kalau mereka sakit tidak usah dijenguk. Kalau mereka berpesta, tidak usah datang membantu persiapannya cukup datang sebagai undangan pada waktunya saja. Dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, Kiai lskandar harus mengikuti pola hubungan monolotis kaum santri di pedesaan Jawa: kucilkan mereka yang bukan santri dari pola paguyuban ke-santri-an sejauh mungkin. Belasan tahun Kiai lskandar menjalani pola kehidupan seperti ini, hingga secara kebetulan ia menghadapi kejadian yang tidak diduganya sama sekali. Bulan puasa yang lalu, salah satu tetangga yang baru berpindah ke desa itu, meninggal dunia karena sakit. Pendatang baru itu belum pemah bertandang ke rumah Kiai lskandar, sehingga sang kiai tidak tahu dengan tepat apa 'identitas kultural' sang tetangga. Miskomunikasi wajar dalam kehidupan yang semakin kompleks.
Karena sang tetangga meninggal dunia malam Jumat bulan puasa, secara spontan Kiai lskandar memasukannya dalam kategori orang baik, yang kepulangannya ke rahmatullah akan di terima dengan baik di sisi Tuhan. Prasangka baik yang dibawakan oleb kepercayaan akan sabda Nabi Muhammad ini mendorong Kiai lskandar untuk segera memerlukan datang ke rumah tetangga itu. Kiai lskandar menjadi heran ketika dilihatnya hanya sedikit orang berada di tempat Pak Damin, tetangga baru yang meninggal dunia. Tidak ada 'tokoh pengurus jenazah, seperti kebiasaannya. Tidak ada rakyat yang memotong batang bambu, membelah-belahnya untuk dijadikan peralatan mengubur jenazah nanti. Tanpa kecurigaan apapun, Kiai lskandar segera 'menggerakkan' rakyat sekitar untuk mengurusi jenazah Pak Damin, dari memandikan hingga ke upacara penguburan keesokan paginya. La memberikan kesaksian jenazah tersebut sebagai orang baik, karena kematian Pak Damin terjadi malam Jumat di bulan puasa. Ketika ia meminta pengokohan orang banyak atas kesaksiannya itu, mereka menjawab secara bermalas-malasan, tidak antusias, menurut bahasa orang kota. Kiai lskandar tidak menyangka jauh-jauh apa sebab keengganan itu. Temyata Pak Damin bukan santri. la orang kebatinan, alias Kejawen. Pak Damin diidentifisir sebagai orang luar yang tidak perlu disantuni, menurut tata nilai dan pola hubungan serba monolit di pedesaan. Segera Kiai lskandar melancarkan jawabannya sendiri atas kejadian tersebut. Untuk menghilangkan salah pengertian orang banyak, demikian tutumya. Di mana-mana ia jelaskan perlunya orang kebatinan seperti Pak Damin juga disantuni kalau meninggal dunia.Orang yang bukan santri juga harus diberlakukan dengan baik dan terhormat dalam pergaulan hidup, kalau mereka memerlukan santunan. Kalau kaum santri dapat berbuat begitu, kalaupun orang bukan santri tetap pada keadaan semula, anak cucunya toh akan merasakan pentingnya arti santunan tersebut dan akan melihat kegunaan menjadi orang santri. Entah karena perhitungan praktis bahwa ia toh dapat menggerakkan orang banyak untuk berbuat demikian, entah karena sudah terlanjur melakukan hal yang sama, Kiai lskandar lalu mengambil sikap menyimpang dari sikap monolit kaum santri di desanya. Yang jelas, perubahan sikap yang bersumber pada prasangka baik dan kepercayaan akan 'status baik' jenazah yang meninggal dunia malam Jumat bulan puasa itu telah membawakan pola hubungan baru di desa tersebut. Ini mungkin tidak disadari sejauh itu oleh Kiai lskandar sendiri. Bagaimanapun juga, kejadian ini menunjuk kepada salah satu landasan kehidupan para kiai: rasionalitas tersendiri, yang tumbuh dari kepercayaan keagamaan mereka.
Kiai Nyetrik Membela Pemerintah Oleh Abdurrahman
Wahid
Orangnya peramah tetapi lucu. Raut wajahnya sepenuhnya membayangkan kekiai-an yang sudah mengalami akulturasi dengan "dunia luar". Pandangan matanya penuh selidik, tetapi kewaspadaan itu dilembutkan oleh senyum yang khas. Gaya hidupnya juga begitu. Walaupun sudah tinggal di kompleks universitas negeri, masih bemafaskan moralitas keagamaan. Gaya bicaranya juga ada dua macam. Di hadapan "orang luar" ia sedikit berbicara dan lebih banyak "meladeni". Tetapi di tengah "rakyatnya" sendiri, ia memakai gaya pengajian seratus persen. ltulah Kiai Muchit (yang ejaannya belum disesuaikan EYD) yang mampu berbicara tentang real politik lokal dengan bupati di wilayahnya ketika ia menjadi wakil ketua DPRD, tetapi yang dengan santainya membuka pengajian umum dengan humor. Apakah tipe kiai begini yangjadi citra "ulama - intelek" yang begitu didambakan orang-orang Departemen Agama, kita tidak tahu persis. Bagaimanapun juga, kredibilitasnya untuk itu cukup kuat: ia kiai populer berilmu agama mendalam, sekaligus ia jadi dosen universitas (walaupun hanya untuk mata kuliah agama). Setidak-tidaknya ia tipe yang lebih realistis, dan lebih memikat hati, daripada sejumlah sarjana dari disiplin non-agama, tetapi yang mengajarkan agama, dengan kegalakan dan militansi yang terasa menakutkan wakil dari tipe "intelekulama". Menghadapkan jenis silang "ulama-inteiek" dan "intelek-ulama" memang kerja mengasyikkan. Di satu segi, jenis pertama banyak dimodali keakraban hubungan bermacam-macam lapisan masyarakat, karena kelonggaran pendekatan yang dilakukannya. Jenis kedua justru lebih sering didorong oleh semangat menyala untuk membuktikan kebenaran agama melalui argumentasi dan dalil-dalil ilmiah, yang sudah tentu sering menghasilkan polemik dengan "orang luar". Pada segi lain, jenis "ulama-inteiek" menekankan pesan mereka pada ajakan perbaikan akhlak pribadi. Sedangkan jenis "intelek-ulama" lebih senang menawarkan tema besarmisalnya superioritas peradaban Islam, dsb. Keberanian Moral Kedua pendekatan yang tampak saling berbalik punggung itu sepenuhnva tergantung kepada keberanian moral untuk mempertahankan pendirian dan keyakinan. Pada jenis "intelek-ulama" hal itu tampakjelas, bahwa ada sarjana disiplin nonagama berbicara soal-soal keagamaan,jelas dibutuhkan keberanian moral untuk itu sejak semula. Paling tidak di hadapan yang tadinya bingung, melihat adanya insinyur fisika inti yang bersusah payah menghafalkan AI-Qur'an, ada profesor seni rupa sibukdengan konsep-konsep dasar kemasyarakatan Islam, dan ada dokter yang giat bertabligh (sudah tentu dihadapkan ejekan tentang prakteknya yang
mungkin
tidak
laku).
Yang lebih sulit adalah mengetahui keberanian moral apa yang dibutuhkan untuk menjadi "ulama-intelek". Sejak semula jenis ini telah membatasi diri jadi pengikut yang mencoba berpikir secara disiplin non-agama, tetapi tidak pemah mengajukan klaim jadi pelopor dalam disiplin yang bersangkutan. Tidak perlu ada keberanian moral dari sudut penglihatan ini. Bahkan rakyat awam yang menjadi pemujanya sudah kagum sekali, dengan sekedar satu dua contoh dari dunia disiplin non-agama yang mereka paparkan dalam pengajian. Tetapi keberanian moral yang harus mereka miliki justru terletak pada pergaulan masyarakat, untuk menyatakan benar apa yang benar dan menyalahkan apa yang salah. Ini banyak mengandung resiko, karena sering membuat mereka berhadapan tidak saja dengan "orang luar", tetapi lebih-lebih dengan kelompok dari mana mereka berasal dan dimana mereka memimpin. Contohnya Kiai Muchit ini. Di masa menghebatnya aksi sepibak PKI dilancarkan, ia harus ribut dengan kiai-kiai lain yang menentang UUAP dan UUPBH. Para kiai itu memakai argumentasi bahwa tidak ada pembatasan hak milik pribadi dalam mazhab Syafi'i. Tetapi Kiai Muchit menyelamatkan diri secara politis dengan pertanyaan: walaupun tidak ada pembatasan seperti itu, bukankah ada larangan memperoleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah sampeyan membuktikan bahwa petani kaya yang mempunyai 50 hektar tanah memperoleh dengan halal? Bukannya perampasan si kaya atas si miskin melalui gadaian sawah yang kedaluwarsa? Atau sebagai sitaan atas barang jaminan yang jadi milik semengga-mengganya dari petani miskin? Waktu itu ia didamprat kanan-kiri, sampai-sampai mendapat predikat yang dalam istilah sekarang sama dengan "nyentrik". Kasus Jenggawah Kini kiai nyentrik inijuga didamprat kanan-kiri karena sikap moralnya, lagi-lagi dari kalangan umatnya sendiri. Dalam kasus tanah Jenggawah, yang kebetulan terjadi di wilayah domisilinya sekarang, ia menyimpang dari pola agitasi demagogik yang dilancarkan parpolnya (bersama parpol lain) untuk "memperjuangkan kepentingan petani" melawan PT Perkebunan yang bersangkutan di sana. la tabu persis, bahwa agitasi itu tidak tepat dan tidak mengenai sasarannya, karena yang benar memang adalah pihak PTP la tahu juga bahwa bukan tanpa pamrih PTP melakukan her-kaveling tanah garapan di Jenggawah, yang memang secara formal masih milik negara. Tetapi ia sama sekali tidak berubah pendiriannya di hadapan kemarahan umat itu. Soal utamanya adalah tanah garapan yang telah terbagi-bagi secara tidak adil dalam waktu sekian lama di antara para penggarap sekarang ini. Ada yang punya
20 hektar, tetapi kebanyakan hanya punya seperempat hektar saja. Tadinya memang sama luas tanah garapan masing-masing, tetapi nasib telah membawa kepada transfer penguasaan tanah. Sudah tentu benar upaya meratakan kembali besamya tanah garapan masingmasing, kalau dilihat dari pandangan agama, menurut kiai nyentrik kita yang satu ini. Persoalan utama ini harus dilepas dari ekses-ekses tindakan para oknum FTP, yang harus diselesaikan pada waktunya nanti. Sikap ini memang tidak populer. la terkena tuduhan "membela pemerintah", sebuah dosa asal yang sulit diampuni dalam pemikiran kepartaian yang belum matang di negeri ini. Apalagi dipandang sementara pemimpin lokal yang langsung atau tidak langsung dibiayai oleh para petani yang memiliki tanah garapan 20 hektar! la langsung dikucilkan dari solidaritas umat saat ini, karena sikap moral keagamaannya yang seperti itu (atau justru karena sikap intelektualitasnya?) Nah, siapa bilang ulama intelek tidak harus memiliki keberanian moral?
Kiai Pencari Mutiara Oleh
Abdurrahman
Wahid
Sebagaimana banyak terjadi pada kiai pesantren, Kiai Sakhal Kajen adalah perokok kelas berat. ltu tidak hanya tampak pada rokok yang selalu dipegang dan diisapnya, tapi juga keadaan fisiknya: kurus kering dan tenggorokan yang acap terkena penyakit batuk. Kebiasaan merugikan itu mungkin datang dari 'kebiasaan kiai' untuk sedikit tidur dan berlama-lama dalam keadaan bangun. Kalau tidak untuk membaca kitab-kitab agama sendirian hingga larut malam, tentu untuk menemui tamu yang mengajak berbincang tentang banyak hal. Belum lagi kedudukan sebagai Sekretaris Syuriah NU Wilayah Jawa Tengah, yang membawa tambahan kerja rutin menerima tamu atau mengikuti rapat yang menghabiskan waktu. Lahir, dibesarkan dan juga akhimya menetap di 'desa pondok' Kajen di Kabupaten Pati sebuah desa dengan belasan pesantren yang hidup terpisah satu dari yang lain Kiai Sakhal dididik dalam semangat memelihara derajat penguasaan ilmuilmu keagamaan tradisional. Apalagi di bawah bimbingan ayahnya sendiri sewaktu kecil, Kiai mahfudz, yang juga 'kiai ampuh', adik sepupu almarhum Ra'is 'Am NU Kiai Bisri Syansuri. Kemudian ia melanjutkan pelajaran dengan bimbingan 'kiai ampuh' lain, seperti almarhum Kiai Zubair Serang. Pada dirinya terdapat tradisi ketundukan mutlak pada ketentuan hukum dalam kitab-kitab fiqh, dan keserasian total dengan akhlak ideal yang dituntut dari ulama tradisional. Atau dalam istilah pesantren, ada semangat tafaqquh (memperdalam pengetahuan hukum agama) dan tawarru' (bermoral luhur). Tidak heran kalau Kiai Sakhal lalu 'menjadi jago' dalam usia muda. Belum lagi berusia 40 tahun ia telah menunjukan kemampuan tinggi dalam forum-forum fiqh. Ini terbukti pada pelbagai sidang bahtsul masa'il tiga bulanan yang diadakan Syuriah NU Jawa Tengah secara teratur sidang yang menampung masalah yang muncul dari masyarakat. Bulan lalu di Moga, Pemalang, misalnya, Kiai Sakhal muncul kembali dengan cemerlang. Sekian ratus kiai membahas sebuah masalah pelik: kawin lari. Haramkah, atau halal? Bagaimana dengan kedudukan ayah atau wali yang, menurut mazhab Syafi'i, memiliki wewenang menetapkan jodoh seorang anak gadis? Bergiliran para kiai berbicara berbagai pendapat dengan argumennya kemudian diserahkan kepada sebuah team perumus untuk memberikan keputusan redaksional di ujung pertemuan dua hari. Sementara menunggu, Kiai Sakhal diminta berbicara sekitar masalah itu kepada mereka yang tidak turut bersidang dengan panitia perumus. Dalam pidato tanpa persiapan itulah tampak kebolehan kiai. la berkali-kali menyebutkan kutipan
panjang dalam bahasa Arab dari Kitab Syarqawi, salah satu kitab utama mazbab Syafi'i, tanpa melihat catatan sekalipun. Pendeknya, masalah kawin lari harus di lihat dari berbagai sudut pandang. Kompleksitas hukum fiqh,dan berbagai jawaban yang diberikannya terhadap kasus yang berlainan satu dari yang lain, menjadi menonjol dalam penyajian Kiai Sakhal itu. Gambaran sepintas tentang 'cara kerja' dan orientasi yang serba legal formalistik yang dianut Kiai Sakhal itu secara sepihak tentu terasa kaku. Tidak tanggap terhadap kehidupan secara umum, hanya mengambil pendekatan kasuistik. Tidak memiliki 'filsafat kehidupan' yang luas, atau 'kerangka humanistik' yang besar. Tidak jelas kerangka kemasyarakatan (societal frameworks, al-manhaj al-ijtima'i) yang dicoba dikembangkannya. Anehnya, kiai berambut penuh uban pada usia yang belum tua itu, bersikap cukup 'aneh' bagi kalangan pesantren tradisional. Apalagi pesantren daerah pesisir utara Jawa. Mula-mula menerima 'masukan baru' berupa proyek pengembangan masyarakat, dibawakan oleh LP3ES dari Jakarta. Perhatiannya diminta untuk memimpin kerja yang dahulunya tidak pemah dipikirkan kiai pesantren, seperti pelestarian lingkungan (karena ada pencemaran oleh mata pencaharian utama di Desa Kajen itu, yaitu membuat tepung tapioka), memperkenalkan teknologi terapan bagi penduduk desa (tungku Lorena yang menghemat energi dan sebangsanya) dan memulai usaha merintis pengembangan organisasi ekonomi yang lebih mandiri di kalangan rakyat pedesaan. Usaha bersama sebagai wadah pra-koperasi diprakarsainya dalam usaha membuat dan kemudian memasarkan krupuk tayamum (digoreng dengan pasir) dari bahan dasar tapioka. Cukup lumayan, mampu menyerap tenaga kerja sekian kepala keluarga yang tadinya menganggur di desa miskin itu.
What Makes Sammy Run? Apa yang membuat Sammy berlari? Dan apa yang menggerakkan Kiai Sakhal? Bagaimana kiai yang sering dibuat bingung oleh istilah Inggris atau Belanda itu mencapai "kearifan" di atas? Dan berani mempertaruhkan kewibawaannya di kalangan sesama ulama pesantren, dengan menerima kehadiran seorang 'bule' Amerika, beragama Katolik, untuk tinggal dan mengajar bahasa Inggris di pesantrennya?
Jawabannya: fiqh itu sendiri. Keputusan-keputusan hukum agama di masa lampau, diperlakukan secara menyeluruh (bahasa sekarangnya komprehensif) dan seimbang. Bukankah dalam Ihya' Imam Ghazali banyak mutiara yang berhubungan dengan masalah gizi? Bukankah kitab-kitab fiqh cukup mengatur hubungan dengan 'orang dzimmi ' (orang non-muslim)? Bukankah kewajiban mengatur kehidupan bermasyarakat dalam totalitasnya, bukan hanya aspek legal dan politiknya, sudah begitu banyak dimuat kitab-kitab
lama? Mengapa tidak diperlukan keputusan-keputusan lepas dalam fiqh itu sebagai untaian mutiara, yang memunculkan kerangka kemasyarakatan yang dikehendaki? Toh Kiai Sakhal tidak pula kehilangan hubungan dengan sesama kiai pesantren. Terbukti dari pengayoman oleh sesepuh para kiai di desanya sendiri, Kiai Abdullah Salam. Kiai ini pemimpin pesantren hafalan AI-Qur'an dengan keluhuran akhlaknya (yang takut menerima bantuan uang dari orang kaya maupun pemerintah, karena takut 'kecampuran barang haram', dan begitu dihormati tokoh legendaris Embah Mangli di Jawa Tengah) memberikan persetujuan penuh atas kerja-kerja yang dilakukan Kiai Sakhal. ltu memang bukti kuatnya akar 'rangkaian mutiara' seperti yang dipungut Kiai Sakhal ltu, untuk masa lampau maupun masa depan.
Kiai Razaq yang Terbakar Oleh
Abdurrahman
Wahid
KIAI ABDUL RAZAQ MAKMUN adalah profil tersendiri di antara "barisan kiai" di kalangan kaum Betawi. Kalau para kiai lain getol melancarkan serangan gencar kepada hal-hal yang modem, kiai dari 'golongan Tegalparang' ini justru memakai pendekatan serba ringan. Kalau para kiai lain menunjukkan kata-kata tajam, Kiai Razaq justru tidak pemah menyinggung-nyinggung perbedaan agama, seperti kasus judi beberapa tahun yang lain, Kiai Razaq justru jarang menyoroti soal-soal hangat seperti itu. Tema pembicaraannya, walaupun dibumbui dengan humor segar dan penuh dengan 'dalil' ayat AI-Qur'an dan hadith Nabi, biasanya hanya berkisar pada pentingnya kerja menuntut ilmu. Tema tunggal ini disampaikannya secara menetap selama sepuluh tahun. Walaupun dihormati almarhum Kiai Bisri Syansuri sebagai salah satu dari sedikit ulama Betawi yang 'mengerti hukum agama secara mendalam', sedikit sekali diperagakannya kebolehan di bidang fiqh itu. Paling-paling hanya ketahuan kalau sedang ada musyawarah hukum agama di kalangan Syuriah Nahdlatul Ulama. Di luar forum terbatas dan periodik sepertti itu. yang disampaikannya hanyalah pesan menuntut ilmu bagi kepentingan agama. Mengapa demikian tekun ia dengan tema tunggalnya itu? Mengapakah kiai-kiai lain justru tidak demikian? Banyak sebab dapat dicari, tetapi yang terpenting tentunya adalah kehidupan kejiwaannya sendiri. Ia berkembang dalam suasana yang memuliakan pencapaian standar pengetahuan agama yang tinggi, bukan hanya sekedar 'kiai-kiaian'. Karena kedalaman pengetahuannya ini, ia melihat kekuatan agamanya sendiri. Pantaslah kalau ia tidak begitu melihat ancaman proses modemisasi. Selama masih ada ulama yang berpengetahuan agama mendalam, yang akan memimpin umat melakukan peroses penyaringan atas jalannya modemisasi itu sendiri, tidak usah kita histeris atau panik. Asal anak muda mau mempelajari ilmu-ilmu agama, yang diistilahkannya 'mencari ilmu', selama itu pula akan ada proses seleksi yang baik. Jawaban atas modemisai, dalam pandangan Kiai Razaq, adalah anjuran 'menuntut ilmu'. Tata nilai yang dianutnya masih tergolong apa yang oleh Sharon Siddiqui dari Institute of Southeast Asian Studies sebagai 'budaya pesisir': penghormatan kepada kaum sayyid, terutama almarhum Habib Ali Kwitang. Watak hidupnya masih serba tradisional, dalam artian mengikuti amalan-amalan agama yang sudah berumur ratusan tahun tanpa banyak mengalami pergeseran. Walaupun demikian, rasionalitasnnya, yang dibavvakan oleh keyakinan penuh kepada limu-ilmu agama sebagai pengarah kehidupan, membawakan pendekatan
tersendiri kepada masalah dasar yang dihadapinya dalam kehidupan. Rasionalitas yang tidak mencari argumentasi serba logis dari ilmu pengetahuan modem, melainkan yang berpangkal pada integritas ilmu-ilmu agama itu sendiri. Dari sudut pengenalan ini, kita tidak heran ketika akhir-akhir ini terjadi perkembangan menarik dalam pesan-pesan keagamaan yang disampaikannya. Kiai Razaq tidak lagi hanya berpesan tentang pentingnya transmigrasi. Transmigrasi? Dari kiai tradisional ini? Dari mana ia peroleh gagasan itu? Apakah yang mendorongnya berbicara semangat tentang transmigrasi? Persoalannya sederhana saja. Di dalam berdialog dengan dirinya sendiri, ditemukannya cara terbaik untuk lebih mematangkan sikap hidup kaum muslimin Betawi. Sikap hidup yang menghasilkan perbaikan kualitas hidup mereka kelak, tetapi terlebih-lebih yang akan mendorong generasi muda untuk 'menuntut ilmu' melalui penyediaan sarana sosial-ekonomisnya. Bukankah di tempat baru mereka akan mendapatkan perbaikan situasi ekonomi masing-masing? Bukankah akan lebih mudah bagi mereka untuk membiayai pendidikan agama ditempat baru, daripada berjubel di tempat lama dengan sumber-sumber ekonomi yang semakin mengecil? 'Menuntut ilmu' diwajibkan oleh agama. Bukankah prasarana untuk kerja tersebut menjadi wajib, sesuai dengan kaidah 'ma layatimmul wajibu illa bihi fahhua wajibun' (Sesuatu yang menyempumakan kewajiban berstatus wajib pula)? Transmigrasi menjadi wajib, karena ia merupakan persyaratan bagi kewajiban 'menuntut ilmu' di kemudian hari. Belum lagi dihitung kepentingannya bagi pembangunan nasional. "Ane udah bentuk suatu yayasan untuk membantu pemerintah dalam soal transmigrasi," ujamya dalam gaya khas Betawi pada sebuah penataran muballigh bulan puasa yang lalu. "Sayang enggak inget namenye. Maklum panjang banget namenye." Hadirin tertawa mendengar ucapan terakhir ini. Bagaimana orang dapat lupa kepada nama yayasan yang didirikannya sendiri. "Ente semue jangan ketawa dulu. Pikir mateng-mateng pesen ane ini. Diskusi-in biar lame. Tanggung deh ente semue nanti lebih kebakar dari gue sekarang." Begitu yakin Kiai Razaq dengan ajakannya yang baru ini, sehingga ia membuat perkiraan keadaan di masa datang: "Dua puluh taon lagi tanggung deh ente semua bakal bilang Kiai Razaq orangnye jempol. Sekarang sih belum ketahuan!"
Kisah Sebuah Cerita Lama Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Dalam penerbangan dari Biak ke Sentani di tanah Papua, penulis naik pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 650, di bawah pimpinan Kapten Alam Jaya. Terbang dari airport Cengkareng di Jakarta jan 23.50 malam dan tiba di airport Sentani sekitar jam 07.00 pagi WIT (Waktu Indonesia Timur) dalam penerbangan ke Biak ke Sentani cuaca sangat baik, dan langit terang benderang sejak matahari terbit. Karena sudah tidur dari Cengkareng ke Biak, termasuk singgah setengah jam di Airport Hasanudin (Makasar), penulis lantas teringat kisah Laksamana Isoroku Yamamoto dari bala tentara Jepang. Laksamana Isoroku itu baru bertugas di Bougainville, sebuah pulau di utara tanah Papua, dan sekarang menjadi bagian dari Papua Nugini (PNG). Tadinya, sang Laksamana bertugas di pulau Jawa dengan kedudukan di Jakarta dan menjadi Komandan balatentara Jepang ke-16 yang bertugas di kawasan Pasifik Barat. Markas besamya baru saja dipindahkan Bouganville itu, karena ancaman ke daratan Jepang dari pulau-pulau lautan Pasifik yang sebelumnya direbut mereka, mulai terancam dan jatuh ke tangan Amerika Serikat. Gabungan tentara darat di bawah pimpinan Jenderal Mc Arthur dan Armada wilayah Pasifik negeri itu (CinCPac) di Hawaii, tidak kuat ditahan oleh balatentara Dai Nippon. Rupanya, pihak intelejen AS berhasil memecahkan kode-kode Jepang, sehingga komunikasi antar pasukan Jepang dapat ditembus oleh AS. Pihak AS mengetahui bahwa Laksamana Imamoto pada suatu hari sedang terbang dari Biak ke Bouganville. Dengan segera sebuah rangkaian pesawat terbang buru sergap AS di persiapkan untuk menembak jatuh pesawat terbang yang tentunya dikawal pula oleh serombongan pesawat terbang buru sergap Jepang, tentu saja dalam jumlah lebih kecil dari rangkaian AS itu. Karena kelebihan jumlah itu sebagian dari mereka dapat mendekati pesawat terbang yang membawa Laksamana Jepang itu. Mereka berhasil melakukan penyergapan dan pesawat naas itu akhimya melakukan pendaratan darurat di Bougainville karena kerusakan berat yang dideritanya. Pendaratan darurat itu gagal Laksamana Yamamoto meninggal dalam peristiwa itu. Sebulan kemudian pihak Jepang mengumunkan penguburan abu Sang Laksamana Isoroki Yamamoto di Tokyo. Jepang pun kehilangan salah satu otak militemya yang cemerlang, yang membuat tentara negeri Sakura itu berhasil merebut daerah sebelah barat Pasifik tersebut, beberapa belas bulan sebelumnya. Dengan segera perimbangan kekuatan militer di kawasan Pasifik lalu berubah, dan Laksamana Maeda dari pihak Jepang meminta Ayahanda penulis, KH. A. Wahid Hasyim, untuk menunjuk seorang Indonesia sebagai juru runding dengan pihak Jepang tentang kemerdekaan, jika tentara Sekutu sampai mendarat ke negara kepulauan yang dikuasai Jepang ini. Ayah penulis menjawab, keputusan berada di tangan ayahnya KH. M. Hasyim Asyari di pesantren Tebuireng, Jombang setelah berkonsultasi dengan beliau, ayah penulis memberitahu Laksamana Maeda, ayahnya menunjuk Soekamo sebagai wakil bangsa Indonesia dalam perundingan kemerdekaan yang dilakukan sejak akhir tahun 1943. Keputusan untuk menunjuk
tokoh tersebut sekaligus membuktikan fakta sejarah, bahwa beliau sangat memikirkan kepentingan bangsa Indonesia, bukanya hanya kepentingan NU sebagai organisasi Isalm yang didirikan beliau tahun 1926. Penulis teringat itu semua, ketika naik pesawat terbang Garuda dari Biak ke Sentani dan tidak bisa tidur. Alangkah penting arti keberhasilan memecahkan kode rahasia Jepang itu, dari jalannya perang di kawasan Barat lautan Pasifik itu. Penulis menyadari bahwa betapa sangat berharganya otak manusia seperti Laksamana Yamamoto bagi jalannya sejarah. Karena itu, peperangan dalam banyak hal tergantung dari otak manusia, seperti halnya proses bangsa kita mencapai kemerdekaan kita. Proklamasi 17 Agustus 1945 bukan saja berakhimya sebuah tahapan penjahan yang diawali dari Belanda kemudian ke tangan pemerintahan pendudukan Jepang, tapi juga permulaan kemerdekaan kita sebagai bangsa. Langit jemih di atas lautan pasifik sebelah barat itu, temyata memungkinkan pesawat-pesawat terbang buru sergap AS untuk menghantam Komando Militer Jepang di kawasan itu. Perhitungan manusia temyata jauh kalah dari perkembangan alam. Sama halnya seperti perbenturan antara dua buah peradaban yaitu sebuah negeri demokrasi seperti AS, mampu mengalahkan sebuah negara militeristik seperti Jepang, dibawah pemerintahan efektif yang dipimpin Perdana Menteri Jenderal Tojo dan di bawah pimpinan moral Kaisar (Teno Haika) di Jepang. Artinya, sebuah pemerintahan diktaktor militer tidak akan dapat mengalahkan sebuah pemerintahan demokratis, karena kreatifitas yang dimilikinya dan daya tahan rakyatnya. Lambat laun tentulah pemerintah demokratis itu akan dapat menumbangkan pemerintahan diktaktor militer jika telah datang waktunya untuk itu. Karenanya, yang harus kita tegakkan justru bukannya pemerintahan diktaktor militer melainkan pemerintahan demokratis yang lambat laun akan memberikan pada bangsa kita apa yang menjadi tujuannya, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini, kita perlu memperlajari sejarah bangsa-bangsa lain, termasuk sejarah bangsa Jepang, yang dahulu mulai dibawa ke alam modem oleh Shogun Tokugawa Ieyashu di abad ke-18 masehi. Penaklukan kaum militer (Daimyo) oleh Shogun pertama yang menguasai seluruh negara dalam bentuk ketokohan Ieyashu tersebut, menunjukkan betapa pentingnya masa pemulihan (Meiji Restoration) tersebut bagi Jepang. Hal itu terbukti kembali saat ini setelah Jepang kehilangan jajahan-jajahan. Dalam alam demokrasi ia justru merebut pasaran di seluruh dunia, dan menjadi raksasa ekonomi yang paling kuat kedudukannya saat ini. Dalam hal ini, secara tidakk disadari Jepang mengikuti konsep yang diterapkan oleh Jerman Barat setelah Perang Dunia II, yang disebut Soziale Marktwirtschaft dari mendiang Konselir Ludwig Erhard. Bukan negaralah yang direbut melainkan pasaran tempat menjual produk-produk teknologi Jerman. Ini juga berlaku bagi negeri kita. Dahulu kita terpecah belah dalam sekian banyak kerajaan. Sejak abad ke-4 masehi, kita sudah mengenal kerajaan Medang Kamulan di Malang Selatan, Kutai di Kalimantan Timur, Kalingga di Pegunungan Dieng (Jawa tengah), Tarumanegara di Pakuan, Bogor. Pada abad ke-6 masehi kerajaan Sriwijaya berdiri tegar dengan Tulang Bawang sebagai Ibu kota dan Budha sebagai
agama. Dua abad kemudian Sriwijaya menyerbu Kalingga, yang menjadikannya sebagai sebuah imperium yang sangat kuat, yang memerintah Sumatera bagian Selatan dan Jawa Tengah dari perjumpaan/ perbenturan antara Sriwijaya dan Kalingga itu, lahirlah masyarakat Hindu-Budha di Prambanan. (Jawa Tengah), yang pada akhimya berpindah ke Jawa Timur karena desakan-desakan dari luar, di bawah pimpinan Darmawangsa. Dari sinilah bermula beberapa kerajaan seperti Kediri dan Daha, Singosari (di daerah Malang) dan akhimya Majapahit yang kemudian menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit yang berorientasi niaga-laut itu, akhimya diganti oleh kerajaan Mataram yang dibawah pimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sulatan Agung merubah administrasi pemerintahan Mataram menjadi agraris yang berlaku hingga masa pemerintahan Soeharto. Inilah pelajaran yang harus kita petik, untuk menentukan perlukah kita mempertahankan orientasi pemerintahan tersebut atau justru merubahnya? Kalau jawabanya positif, maka ia memang mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?
Kraton Dan Perjalanan Budayanya Oleh: Abdurrahman
Wahid
Dalam minggu keempat bulan Desember 2002, penulis atas undangan Susuhunan Pakubuwono XII dari Solo, melancong ke Kuala Lumpur untuk dua malam. Penulis memperoleh undangan itu, karena Sri Susuhunan juga diundang oleh sejumlah petinggi Malaysia guna merayakan ulang tahunnya yang ke 80. Ini menunjukkan, bahwa pengaruh Keraton Solo Hadiningrat masih kuat hingga ke negeri jiran, seperti Malaysia. Sudah tentu pengaruh tersebut bersifat budaya/kultural saja; karena pengaruh politisnya sudah diambil alih pemerintah negeri kita. Inilah yang harus disadari, karena kalau yang diinginkan adalah pengaruh politik tentu akan kecewa, karena tidak dapat meraihnya. Kunjungan tersebut penulis lakukan tanpa memberitahukan pihak pemerintah Malaysia, terutama kantor Perdana Menteri Mahathir Muhammad, karena kunjungan tersebut tentu akan diambil alih oleh pihak pemerintah federal yang , kalau di Malaysia disebut kerajaan. Pihak protokol akan membuat susah temanteman Malaysia yang ingin menjumpai penulis, yang akan membuat penulis tidak merdeka karena memberitahukan kedatangan terlebih dahulu. Tentu, ini juga merupakan pertanda bahwa kunjungan itu sendiri tidak mempunyai arti politis apapun. Dengan demikian, penulis juga merasa tidak perlu memberitahukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur atas kunjungan tersebut. Karena penulis tidak ingin digannggu siapapun dalam melakukan kunjungan tersebut. Pada hari kedua, penulis melakukan perjalanan selama tujuh jam (pulang-pergi) untuk melakukan ziarah ke makam Hang Tuah, di Tanjung Keling, Negara bagian Malaka. Di tempat itu, kepada penulis dibacakan serangkaian tulisan yang menyertai beberapa buah gambaran/lukisan tentang beliau. Katakanlah semacam diorama tentang kehidupan Hang Tuah, yang sejak masih muda sudah mengabdi kepada Raja/Sultan Malaka. Bahkan, oleh intrik istana ia diharuskan membunuh saudara seperguruan dan senasib sepenanggungan yaitu, Hang Jebat. Harga inilah yang harus dibayar oleh Hang Tuah untuk pengabdiannya kepada Sultan. Ia adalah prototype Korpri sempuma, --seperti halnya Habib Abdurrahman AlBasyaibani, yang dikuburkan di Segarapura, Kemantrenjero (sekarang terletak di Kecamatan Rejoso, Pasuruan). Ia adalah nenek moyang penulis yang menjadi yang menjadi abdi dalem Sultan Trenggono dari Demak. ***** Penulis mengemukakan bahwa Susuhunan Pakubuwono XII masih memainkan peranan penting dalam rangkaian ikatan budaya/kultural yang merekatkan kedua bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia. Apapun perbedaan antara keduanya, namun persamaan yang ada haruslah di pupuk terus, agar menghasilkan ikatan yang semakin kuat di hadapan tantangan modemisasi kehidupan, yang sering mengambil bentuk westemisasi (pembaratan). Di kala perkembangan politik justru mengarahkan Indonesia dan Malaysia untuk saling bersaing, maka persaingan itu sendiri haruslah diimbangi oleh ikatan-ikatan budaya/kultural yang sangat kuat.
Seperti halnya Kanada, yang secara politis lebih terikat kepada kerajaan Inggris, yang terletak 9000 km di seberang lautan, dan secara kultural lebih dekat dari pada Amerika Serikat yang secara geografis adalah Negara jiran/tetangga. Bahwa ikatan seperti ini, yaitu berdasarkan persamaan budaya antara dua negara, masih mempunyai kekuatan sendiri, tidak dapat dibantah lagi. Bagaimanapun juga, negara jiran Australia justru merasa lebih dekat kepada kerajaan Inggris atau Amerika Serikat. Yang memiliki ikatannya sendiri; satu dengan yang lain sebagai budaya. Inilah kodrat alami yang intensitasnya tidak dapat disangkal lagi oleh siapapun. Karena itu, kemauan pihak Keraton Solo sangatlah memiliki arti penting; ia menunjang kedekatan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Karena itulah, penulis tidak mengerti mengapa ada pejabat Indonesia yang mengatakan bahwa Keraton Solo tidak ada penting artinya bila dibandingkan dengan keraton lain di Jawa. Ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti duduk masalah peranan budaya sebuah keraton. Yang dimengerti orang itu hanyalah peranan politisnya belaka, yang belum tentu memiliki arti kelanggengan dalam hubungan antara kedua bangsa. Karena itu, setiap kali kita memperhatikan hubungan antara dua bangsa serumpun, seperti Indonesia dan Malaysia, tentulah menjadi sangat penting untuk mengetahui peranan politik atau peranan budaya yang dimaksudkan. Kerancuan dalam melihat hal ini hanya akan membuat kita kepada keadaan tidak menguntungkan: ditertawakan orang baik di Indonesia maupun di Malaysia. ***** Dalam jamuan makan malam untuk menghormati ulang tahun ke-80 Susuhunan Pakubuwono XII di Kuala Lumpur, penulis juga mengemukakan sebuah arti lain dari peranan budaya itu. Pada saat ini, Malaysia dan Thailand sedang mengutamakan pengembangan wilayah sebelah utara dari kawasan Asean yaitu, Myanmar, Vietnam, Laos dan Kamboja. Secara politis, ini berarti Malaysia dan Thailand mengambil peranan politik lebih besar di wilayah utara kawasan Asean tersebut. Ini tentu dapat dimengerti, karena dua negara di wilayah selatan dari perhimpuann kawasan Asean itu, yaitu Singapura dan Indonesia sedang dilanda krisis masing-masing. Dalam hal ini, Malaysia dan Thailand melakukan sebuah hal yang alami dan wajar, yaitu mengisi sebuah kekosongan politik. Lain halnya dengan wilayah selatan kawasan tersebut. Asean belum dapat menerima Papua Nugini, Timor Lorosae dan negeri-negeri pasifik sebelah barat (westem pacific state). Maka dengan sendirinya, lebih sulit bagi Indonesia untuk mendukung mereka secara kongret di bidang politik, sedangkan hubungan budaya dengan wilayah tersebut masih belum berkembang secara pesat. Keeratan hubungan budaya antara Indonesia dengan wilayah pasifik barat daya tersebut, akan sangat ditentukan oleh kerjasama ekonomi dan komersil. Sementara itu, peranan Malaysia di wilayah sebelah utara di kawasan Asean itu berjalan sangat cepat, tidak seperti peranan politik Indonesia di wilayah selatan di kawasan tersebut, yang terasa tidak bertambah sama sekali. Sudah tentu, antara peranan politik Indonesia dan peranan budaya Malaysia di wilayah masing-masing itu, harus disambungkan secara baik. Dalam hal ini, keraton Surakarta Hadiningrat mempunyai peluang sangat besar mengembangkan
peranan kedua bangsa serumpun itu. Inilah yang harus senantiasa menjadi pegangan dalam meninjau posisi keraton dalam hubungan itu. Dan ini adalah peranan alami, yang bagaimanapun juga tidak akan dapat diimbangi oleh hubungan yang direkayasa dan berlangsung tidak alami. Dalam hal ini, kita tidak memerlukan intervensi khusus. Mudah sekali untuk menyatakan hal itu, namun sangat sulit untuk menyatakannya, bukan?
Lagu Jawa di Restoran Padang Oleh: Abdurrahman
Wahid
Salah satu kreasi unik bangsa kita adalah restoran Padang yang ada di manamana. Bahkan di bulan, waktu Neil Amstrong pergi ke sana, kata lelucon. Dalam bentuknya yang paling sederhana, restoran Padang menawarkan cara praktis bagi pembeli: pilih sendiri yang disajikan, bayar hanya yang dimakan. Tetapi restoran Padang bukan sesuatu yang dapat disederhanakan, qua konsep. Ia adalah ujung dari sebuah tradisi memasak yang dikembangkan orang Minang. Juga perwujudan dari kemampuan mencapai kepraktisan untuk membagi juga perwujudan dari kemampuan mencapai kepraktisan untuk membagi atau menyajikan makanan hanya dalam unit-unit yang diperlukan. Belum lagi kemampuan membawa begitu banyak piring-piring kecil di kedua tangan dan lengan, yang jangan-jangan diilhami itu ilmu lengket tari piring. Namun, yang mungkin paling tepat dikaitkan dengan restoran Padang adalah tradisi merantau orang Minang. Kepraktisan cara penyajian makanan itu menampilkan kemampuan bersaing atas dasar efisiensi. Ia mencerminkan tekanan pada keswadayaan orang kecil untuk bergabung dalam upaya ekonomis yang semula berwatak kolektif. Keswadayaan itu menampilkan diri dalam rasionalitas pengaturan segala hal. Penulis tidak ingin melakukan idealisasi atas mahluk Tuhan yang Padang ini, karena hal-hal tak baik pun dapat dicari di dalamnya. Salah satunya : terbakunya kualitas makanan yang hanya mencerminkan selera umum masyarakat saja, sehingga tidak bemilai tinggi. Untuk para gastronom, restoran Padang di negeri kita sama saja pangkatnya dengan restoran hamburger di negeri sono (yang juga sudah ke seini, saat ini). Keempukan sate Bangil atau keunikan rasa soto Maruf di Jakarta, yang jelas berbeda dari yang ada pada makanan bemama sama di tempat-tempat lain, jelas tidak dapat dicari di restoran Padang. Kalaupun ada restoran Padang yang dianggap melebihi yang lain, seperti Sari Bundo di jalan Juanda, hingga beberapa waktu yang lalu, mutu tinggi itu mengambil bentuk penampilan secara umum, alias meliputi semua masakan. Tidak ada yang spesifik, tidak seperti sate A yang memang bumbunya diramu berbeda dengan sate B. Tapi, lihatlah daya tembus lintas sektoral restoran Padang dalam kehidupan bangsa. Itu tampak mula-mula dalam kemampuan restoran ini untuk merebut langganan non-Minang di mana-mana, sehingga lambat laun masakan Padang menjadi semacam masakan nasional. Tidak berarti mampu menghilangkan kesukaan orang pada makanan daerah lain, tetapi mampu menjadikan diri sebagai pilihan kedua bagi masakan hampir semua daerah. Mula-mula karena alas an kemudahan: mudah didapat di mana saja, selain praktis dalam penghidangan dan penikmatan. Kemudian, karena telah menjadi selera tambahan. Daya tembus seperti ini, kemampuan menjadikan diri pilihan kedua, adalah
kekuatan memasarkan diri yang luar biasa kenyalnya. Cukuplah kalau kita ingat contoh celana jins Levis atau makanan modem, seperti hamburger dan ayam Kentucky, untuk melihat kedahsyatan daya tembus seperti itu. Bayangkan seandainya ekspor non migas kita memiliki daya seperti itu di pasaran dunia! . Daya tembus lain yang sudah umum diketahui, tetapi jarang diingat, adalah kemampuan menjadikan diri sebagai lahan kerja orang-orang dari sekian banyak suku negeri kita. Di restoran Padang di sekian tempat persinggahan bis malam di pulau Jawa saja sudah tampak dengan sekali lihat bahwa orang Minang telah menjadi pihak minoritas dalam pengelolaan warisan budaya leluhur mereka sendiri. Ibarat mobil Toyota Jepang, yang di Amerika Serikat dijual dan ditawarkan dealer bule tulen, masakan Padang sudah diramu orang Jawa, Sunda, dan seterusnya. Mungkin hanya orang Batak saja yang tidak mau membuka restoran Padang, karena alasan-alasan histories. Mengapa demikian mudah orang non-Minang mengambil oper gagasan restoran Minang? Karena factor selera telah menyatu dengan factor-faktor non selera, seperti kepraktisan cara kerja dan teknologi makanan yang tahan basi. Mudahnya pengoperan gagasan restoran Padang oleh orang-orang non Minang ini pun langsung disusul saat ini oleh fenomena lain yang tidak kalah pentingnya: kemampuan banyak restoran Padang menghidangkan masakan lain yang tadinya non-Padang. Kebolehan menyerap unsur-unsur lain itu mencapai titik sublimnya ketika penulis masuk ke sebuah restoran Padang di bilengan Pasar Senen, Jakarta. Pemiliknya orang Minang, Juga semua penyaji hidangan. Namun yang terdengar dialunkan melalui kaset adalah lagu-lagu pop Jawa- Jawa Timur-an atau Jawa Tengah-an. Mengapa? Jawabnya mudah saja:Banyak orang Jawa penggemar lagu begini menjadi langganan kami. Semangat kerja yang memiliki kemampuan antisipasi, menyerap, dan mempergunakan aspek-aspek usaha yang berorientasi pasar inilah menjadi rahasia suksesnya restoran Padang. Mungkinkah hal ini dilaihkan pada sesuatu yang lebih berlingkup nasional, seperti penggalakan ekspor dan penciptaan kewiraswastaan yang kompetitif? .
Lain Jaman, Lain Pendekatan Oleh: Abdurrahman Wahid Persoalan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih terus dibicarakan orang. Walaupun KH. M. Sahal Mahfudz telah berusaha sekuat-kuatnya menjelaskan, namun tidak berhasil menenangkan masyarakat, bahkan MUI-pun menjadi sasaran guyonan masyarakat banyak. Bahkan ada yang menyatakan, MUI adalah singkatan Majelis Uang Indonesia. Contoh plesetan yang tidak menggelikan ini, sebenamya menggambarkan perasaan masyarakat yang berang terhadap kesalahan MUI. Bahkan sikap salah seorang ketuanya yaitu KH. Maruf Amin yang menyatakan ia optimis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan mendukung MUI dalam hubungan dengan melarang gerakan Ahmadiyah Indonesia, dirasakan sebagai sikap arogan dan tidak bertanggung jawab. Bukan hanya penulis, yang melihat masalahnya dari sudut konstitusi, tapi orangorang seperti Dr. Azyumardi Azra, Dr. Ahmad Syafii Maarif (yang disegani orang karena sikapnya yang hati-hati), dan Dr. M. Syafii Anwar, semuanya menolak fatwa MUI itu. Bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada di lingkungan MUI dihadapkan kepada reaksi marah dari para anggota Muhammadiyah sendiri, termasuk ketuanya Din Syamsuddin. Bahkan seorang tokoh Muhammadiyah yang berpengaruh besar seperti Prof. M Dawam Rahardjo berpendapat, menuntut supaya MUI dibubarkan saja. Kira-kira menurut pendapat penulis, karena sikap MUI terhadap minoritas seperti GAI (Gerakan Ahmadiyah Indonesia). Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas, memahami benar bahwa GAI dilindungi oleh konstitusi kita, betapapun kita berbeda pendirian dengan mereka. Sedangkan argumentasi orang-orang yang tergabung dalam usaha pelarangan atau yang mendukung argumentasi untuk melarang GAI itu, adalah bahwa Saudi Arabia melarangnya. Namun dilupakan Saudi Arabia adalah sebuah negara Islam, sedangkan Republik Indonesia bukan. Kita adalah sebuah negara nasional yang berlandaskan Pancasila, karena itu dapat menerima perbedaan apapun dalam faham kenegaraan (kecuali komunisme dalam pandangan sejumlah orang). Jika kita larang GAI, karena berbeda dari pendapat doktriner sebagian besar kaum muslimin di negeri ini, konsekuensinya kita juga harus melarang pandanganpandangan kaum Kristen dan Katholik, Buddha, Hindu dan lain-lain. Bukankah keyakinan mereka juga tidak sama dengan keyakinan keimanan mayoritas kaum muslimin? Maka dapat dipahami kemarahan orang terhadap fatwa MUI itu. Karena bukannya menolong pemerintah untuk mencarikan jawaban terhadap keadaan yang mengharuskan pencarian solusi bagi krisis multidimensi yang sedang kita hadapi, atau setidak-tidaknya menahan diri dari setiap tindakan yang memperburuk hubungan antara kita, fatwa MUI itu justru membawa masalah baru dalam hubungan antara berbagai agama di negeri kita. Pandangan serba sempit yang dimiliki MUI itu akan merugikan seluruh komponen bangsa. Kita harus saling mengingatkan, bahwa kita memiliki kewajiban agar apapun perbedaan pendirian kita, kita harus hidup bersama dalam satu ikatan. Bahwa perbedaan demi perbedaan yang ada, seharusnya mendorong munculnya sikap
yang arif bijaksana, bukannya sikap yang membuat hubungan yang ada menjadi semakin buruk, seperti pendapat MUI yang menimbulkan reaksi yang begitu keras. Memang pada akhir-akhir ini kita melihat bahwa di lingkungan gerakan-gerakan Islam mulai muncul hal-hal tidak sedap, seperti munculnya sikap lebih keras di kalangan kaum muslimin, untuk memunculkan kelebihan ajaran-ajaran agama Islam di atas berbagai ajaran agama-agama lain. Sebenamya unutk memenuhi kebutuhan akan hal itu, justru diperlukan kearifan untuk menahan diri di kalangan para pemimpin Islam sendiri. Salah baca para pimpinan MUI justru berakibat pada reaksi berlebihan dari kaum muslimin sendiri. Kalau saja hal ini disadari oleh para pemimpin MUI, tidak akan terjadi apa yang kita saksikan minggu lalu itu, yaitu penyerangan sejumlah Masjid Ahmadiyah. Para pemimpin MUI justru melupakan sebuah kenyataan penting berupa rumusan ajaran Islam yang sebenamya, yaitu Telah Ku-ciptakan kalian sebagai lelaki dan perempuan, dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa, untuk saling mengenal (I nna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa jaalnakum syuuban wa qabaila li taarafu). Dan sikap dasar dari ketentuan Tuhan itu adalah Dan berpeganglah kepada tali Allah secara keseluruhan, dan jangan terpecah-belah (watashimu bi habli Allah jamian wa la tafarraqu). Sikap dasar ini juga merupakan antisipasi terhadap kenyataan akan masa depan agama Islam dan kaum muslimin, seperti telah terbukti dewasa ini yaitu Islam merupakan agama besar, tanpa mengecilkan agama-agama lain. Inilah yang belum disadari oleh para pemimpin MUI maupun para pemimpin berhaluan keras yang ada di kalangan kaum muslimin sendiri pada saat ini. Sikap-sikap keras yang kita lihat masih ada di kalangan kaum muslimin mudah-mudahan akan hilang melalui pendidikan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih intens. Bisa kita gambarkan upaya para pemimpin muslim di masa lampau, seperti Sir Sayyed Ahmad Khan di India dan Mohammad Abduh di Mesir. Di masa lampau, mayoritas kaum muslimin pada waktu itu bersikap keras pada orang lain, karena memang kolonialisme masih merajalela. Karena itu sikap toleransi yang mereka perlihatkan dianggap sebagai tindakan menyerahkan diri kepada agama lain. Tetapi pendidikan dan komunikasi yang berkembang antara kaum muslimin dan pihak-pihak lain, membuat kita menyadari bahwa memang diperlukan kearifan dan kebijaksanaan dalam hal ini. Hanya saja di kalangan orang-orang yang berpengetahuan agama Islam tidak cukup mendalam, justru terjadi kecurigaan yang berlebih-lebihan terhadap orang lain, yang menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada, bukannya mencari titik temu antara Islam dengan agama-agama lain itu. Karena itulah, timbullah reaksi yang mengacu kepada penggunaan bahasa kekerasan dari Islam terhadap agama-agama lain. Inilah sisa-sisa warisan lama yang harus kita rubah melalui pendidikan dan komunikasi antar golongan. Ini berarti terhadap keadaan yang berubah, respon kita juga harus mengalami perubahan pula. Perubahan respon ini adalah kewajaran dalam perkembangan manusia, bukannya keadaan yang harus diteruskan dari generasi ke generasi. Tanpa memahami keharusan sejarah ini
maka dapat berakibat fatal bagi diri kita sendiri, minimal bagi peranan kita dalam kehidupan bersama. Jawaban yang tepat hanya diperoleh mereka yang memahami keadaan secara tepat pula. Apa yang dikemukakan di atas hanyalah sebagian saja dari begitu banyak hal-hal rumit yang dihadapi oleh kaum muslimin. Tetapi merespon dengan sikap keras merupakan sesuatu yang tampak dengan segera dalam pandangan bangsa ini. Mengapa? Karena kaum muslimin tidak hidup sendirian di sini, melainkan ditakdirkan oleh Allah untuk hidup bersama-sama dengan orang-orang beragama lain. Bahkan kaum muslimin sekarang ini harus hidup dengan mereka yang tidak ber-Tuhan, atau mereka yang memiliki kerangka etis yang lain, seperti kerangka dari masa lampau'. Ini adalah bagian dari upaya melestarikan dan membuang yang senantiasa terdapat dalam proses sejarah umat manusia, bukan?
Lari Oleh
Abdurrahman
Wahid
Di suatu pagi, beberapa hari menjelang Lebaran yang lain, penulis turun di Cengkareng dari perjalanan ke Jombang dan Blitar melalui Surabaya. Dalam kepulangan ke Ciganjur dari airport itu, penulis mendapati jalan tol menuju Cawang via Tanjung Priok penuh dengan mobil dan kendaraan-kendaraan lain. Jelas, itu adalah antrean kendaraan yang akan menuju ke Bekasi dan Bogor dari daerah jantung kota Jakarta. Karenanya, terpaksa mobil penulis banting setir ke arah kanan, melalui tol Simpruk. Temyata memang benar, jalan sangat lengang, hingga pintu tol di Semanggi, tempat penulis berbelok ke kanan menuju Jalan Soedirman. Sebaliknya dari arah Cawang terdapat antrean mobil yang sangat panjang dan lalu lintas yang sangat padat, menuju tol Tangerang. Berarti dengan demikian, sekian banyak orang yang berkendaraan pribadi maupun umum itu meninggalkan Jakarta ke arah timur dan ke barat dalam jumlah yang sangat besar. Bukankah ini aneh, mengingat puasa baru berjalan lima belas hari dan Lebaran masih dua minggu lagi baru datang? Langsung saja pertanyaan ini terjawab, sesampainya di rumah karena ada pesan per telepon. Melalui pesan itu, seseorang menyampaikan pada penulis bahwa hari raya Imlek tahun ini sedikit terganggu, dengan adanya kampanye berbisik agar hari besar itu diajukan sebulan. Seperti diketahui, Imlek tahun ini jatuh pada bulan Februari 1999, tetapi oleh kampanye itu dimaksudkan agar bertepatan dengan pertengahan Januari pada tahun yang sama. Dengan kampanye berbisik itu diharapkan agar orang-orang Cina berlebaran seperti di RRC, tetapi pada waktu penulis melakukan checking, di sana Imlek juga jatuh pada pertengahan Februari. Jadi, seperti halnya yang terjadi di Singapura, Saigon, Manila, dan Hong Kong. Tujuan kampanye berbisik itu adalah agar orang-orang Cina bersiap diri berhari raya, beberapa hari sebelum hari raya ldul Fitri. Seperti diingat, tahun ini hari raya tersebut jatuh pada tanggal 19 Januari 1999. Apa maksud dari kampanye berbisik itu? Mudah saja untuk diterka, yaitu agar orang Cina dan kaum muslimin memborong barang dari pasar dan toko-toko dalam waktu yang hampir bersamaan. Dengan demikian, diharapkan harga barang akan naik dengan tajam dan perekonomian menjadi lebih labil. Dan, dengan demikian pula pengentasannya dari krisis yang melanda kehidupan kita akan menjadi lebih sulit. Jadi, tujuannya sudah sangat jelas dan perhatian orang seperti penulis juga menjadi terbangun oleh kenyataan bahwa ada upaya destabilisasi perekonomian kita pada saat-saat menjelang akhir tahun anggaran kita. Bukankah dengan demikian, upaya mengatasi krisis yang terjadi menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan, dan dengan begitu membuat lebih tertunda lagi upaya ke arah perbaikan. Dengan kata lain, terjadi suatu hal yang sangat penting, yaitu
terjadinya keadaan chaos atas perekonomian kita dan sulitnya dilakukan perbaikan seperti halnya yang dimaksudkan sekarang. Lantas, apa hubungannya dengan antrean mobil dan kendaraan umum lain yang menuju ke arah barat dan timur dan Jakarta? Jawabnya juga mudah, yaitu banyaknya orang yang mau lari dari Jakarta. Bukan hanya orang-orang yang mau berlebaran saja yang melakukan mudik, karena mereka itu tentunya baru berangkat pada hari minggu. Antrean pada saat dini itu, menggambarkan kenyataan lain yang secara sosiologis dinamakan pelarian. Pelarian itu, dilakukan oleh orang-orang yang menghindari hari raya Imlek yang dipercepat itu. Bukankah para pemilik dan para penumpang kendaraan itu tidak mau merayakan hari raya Imlek dipercepat? Karena itu, mereka melarikan diri dengan memenuhi hotel-hotel yang berada di luar kota dan memnggalkan rumah mereka di Jakarta, tanpa merayakan hari raya Imlek yang dipercepat. Hal itu dapat dimengerti, karena sulit bagi orang untuk merayakan Imlek tahun ini, hingga mengetahui langkah apa yang harus diambil. Kalau kampanye berbisik itu tidak diikuti, dikhawatirkan ia berasal dari pemerintah dan akan mempengaruhi posisi mereka yang sudah sangat sulit itu. Tetapi kalau didengarkan, jangan-jangan orang Islam marah karena kegiatan berhari raya di Jakarta yang menjadi pusat perekonomian nasional kita akan terpengaruh.Kalau harga-harga naik dengan tajam, di saat menjelang Lebaran, dikhawatirkan reaksi golongan Islam akan sangat besar, karena itu yang terbaik adalah melarikan diri. Sikap kolektif seperti ini, memang tidak direncanakan dari semula. la merupakan respons dari meluasnya kampanye tersebut. Dengan kata lain, gangguan pada kehidupan normal masyarakat dapat berakibat luas di segala bidang, seperti dicontohkan oleh kasus ini. Memang, kita bisa melihat adanya kepanikan yang terjadi dari ungkapan banyak orang tentang hal ini. Dengan kata lain, pelarian di atas hanyalah sebuah bentuk dari sekian macam respons yang diambil dari sekian golongan Cina terhadap krisis yang menimpa kita sebagai bangsa saat ini. Melalui kasus ini, kita dapat melihat berbagai kemungkinan, di satu pihak kita bisa melihat adanya disintegrasi bangsa ini di bidang perekonomian. Dikombinasikan dengan tuntutan agar dilakukan federasi saat ini, maka gagasan kebangsaan akan mengalami pukulan yang sangat berat. Hingga, lebih mudah pula upaya memecah belah bangsa ini melalui kampanye berbisik tadi. Tetapi, langkah melarikan diri dari Jakarta dapat pula bersifat positif. Dan, kalau kita baca orang Cina ber-Imlek pada bulan ini, bukankah ini semakin meneguhkan aspek-aspek budaya selama ini, yaitu ketundukan pada nilai-nilai bersama yang selama ini kita anut? Menarik juga untuk mengamati kasus pelarian di atas, bukan? Memahami Peran Budaya Pesantren
Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Dengan adanya berbagai jenis lembaga pendidikan, orang sering melihat pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan. Ada juga yang memperlakukannya sebagai entitas politik, karena para kyai yang memimpin pondok pesantren sering sekali memiliki pengaruh sangat kuat di masyarakat. Ia menjadi panutan bagi masyarakat yang tunduk padanya. Sangat menarik melihat peranan politik yang sekarang dijalankan secara bertentangan antara para kyai dari pondok pesantren yang berbeda-beda. Peranan ini akan menunjukkan model yang akan diikuti oleh para pemilih. Memang ada perbedaan aspirasi politik antara mereka. Ada yang sekedar menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk kepentingan mendekat kepada para pejabat tertentu. Namun ada pula yang lebih mementingkan kemaslahatan umat dan memelihata kepentingan masyarakat lebih luas. Namun jarang sekali, orang melihat pondok pesantren sebagai medium budaya dalam kehidupan masyarakat. Dilihat dari peranan ini, itulah sebenamya salah satu fungsi pondok pesantren yang untuk sementara diredupkan oleh peranan politiknya. Dari hal itu timbul pertanyaan, dapatkah pondok pesantren, setelah melalui pertentangan dahsyat sebagai akibat pelaksanaan peranan politik itu, akan utuh kembali (minimal sebagai lembaga yang membawakan peranan budaya) di masa-masa akan datang? Dapatkah Pondok Pesantren mempertahankan kemumian yang dimilikinya? Penulis berpendapat kalau memang pondok pesantren mengalami proses politisasi sedemikian jauh sehingga kehilangan fungsi-fungsi lainnya kecuali fungsi politik, maka hak hidup yang dimilikinya akan hilang dengan sendirinya, karena ia akan mementingkan hubungan baik dengan sistem kekuasaan yang ada. Dalam hal ini, penulis teringat akan peranan kyai-kyai pondok pesantren yang diuraikan oleh Hiroko Horikoshi dalam disertasinya yang didalamnya membahas peran mendiang Ajengan/Kyai Yusuf Tojiri, yang mendirikan dan memimpin Pondok Pesantren Cipari (Wanaraja, Garut). Dalam disertasinya yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia itu, Horikoshi berbicara mengenai peranan budaya besan (alm.) Kyai Anwar Musaddad itu. Dalam tulisan itu, Horikoshi menunjukkan kebalikan dari teori makelar budaya (cultural broker) Clifford Geertz dalam proses pembangunan. Kesimpulan ini didapatkan Horikoshi melalui kajian empirik yang mempunyai nilai tersendiri setelah tinggal sekian lama tinggal di pondok pesantren tersebut Menurut Clifford Geertz, peranan makelar budaya itu menunjukkan bahwa para kyai berperan bagaikan sebuah dam (bendungan) yang menampung begitu banyak manivestasi (kehadiran) budaya baru, dengan melepas sebagian dari manivestasi budaya baru tersebut. Cara yang digunakan adalah melalui proses memilih, mana yang dilepas masyarakat dan mana yang tidak. Geertz melihat dengan banjimya modemitas budaya maka bendungan tinggi itu akan terkalahkan, karena demikian banyak hal-hal di luar kendali pondok pesantren, akhimya budaya itu langsung ditelan masyarakat. Kebuntuan melakukan peran makelar budaya itu pada akhimya akan mematikan pemeran budaya itu juga.
Namun Horikoshi menunjukkan, bahwa kyai bukanlah bendungan tinggi yang memiliki peranan pasif melainkan justru menjadi agen pembaharuan dengan memilih sendiri mana yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat dan mana yang tidak. Mudahnya untuk melihat peranan budaya itu antara lain dalam perencanan arsitektural pondok-pondok pesantren pada masa lampau. Umpamanya saja, apa yang terlihat di Pondok Pesantren Mambaul Maarif di Denanyar Jombang. Pondok pesantren yang dahulu didirikan pada awal abad ke-20 oleh almarhum KH. M. Bisri Syansuri tersebut, dimulai dengan pintu masuk melalui sebuah jalan tidak beraspal dari arah Timur menuju ke barat, berdiri sebuah Masjid yang berada di tengah tanah kosong (plaza). Di sebelah selatan, berdiri kamar-kamar para santri. Mulanya di sebelah utara plaza itu, terdapat rumah tempat tinggal sang kyai, di kemudian hari pondok pesantren putri dan gedung-gedung sekolah juga didirikan di sebelah Utara (di kanan-kiri dan di belakang tempat tinggal kyai). Dengan demikian, jelaslah bahwa pendiri pondok pesantren tersebut secara aktif mengambil perencanaan arsitektumya dari simbol budaya Jawa yang berlandaskan pada pagelaran wayang. Para santri adalah salikun (aspiran) yang sedang berada diperjalanan, menuju ke arah kesempumaan pandangan yang dibawakan oleh moralitas/akhlak tertentu. Kata salikun dalam bahasa Arab, menunjukkan fungsi mereka yang mencari kesempumaan pandangan itu. Walaupun mereka kelihatannya hanya menuntut ilmu-ilmu keagamaan dalam sebutan bahasa Pali dari jaman kaum Buddha di negeri ini dahulu disebut dengan istilah santri artinya mereka yang menguasai kitab-kitab suci. Karena proses belajar dan mengajar di lingkungan pondok pesantren bukanlah sekedar menguasai ilmu-ilmu keagamaan melainkan juga proses pembentukan pandangan hidup, dan penentuan perilaku para santri itu nantinya setelah kembali dari Pondok Pesantren ke dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya para kyai adalah mereka yang telah memiliki kesempumaan pandangan tersebut (washilun). Dalam pengertian tashawuf, masjid pesantren yang terletak di tengah-tengah antara keduanya merupakan tempat pertempuran moral berlangsung antara para salikun, yang akan dirubah perilakunya, oleh washilun. Dalam legenda perwayangan kaum Pandawa dan Kurawa, bukanlah cowboy melawan bandit, dalam pengertian yang baik melawan yang jahat menurut ceritacerita pihak Barat yang dibuat dalam sekian banyak film. Filosofi cerita itu mereka adalah orang yang mencari kebenaran dan orang yang telah sampai kepada kebenaran itu sendiri. Tema pencarian kebenaran oleh kedua belah pihak, yaitu Pandawa dan Kurawa, dalam hal ini santri dan kyai, merupakan dua belah sisi yang bagaimanapun juga berwajah budaya. ***** Dengan mengetahui peranan budaya yang dilakukan pondok pesantren itu, kita sendiri sebagai anggota masyarakat mendapatkan kekayaan pengetahuan tentang fungsi pondok pesantren. Sudah tentu, banyak wajah-wajah sampingan dari peranan itu, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam tulisan ini. Namun, jika peranan utama ini hilang dari kehidupan masyarakat, kita juga yang akan
mengalami kerugian. Perkecualiannya adalah jika ada penggantian fungsi itu oleh peranan-peranan baru yang tentu saja tidak dapat ditukar oleh sekedar keakraban dengan para penjabat dan penguasa. Peranan yang semula berdimensi budaya, tidak dapat digantikan dengan peranan terakhir yang materialistik. Dengan mengenal peranan pondok pesantren seperti di sebut di atas, kita sampai kepada sebuah kesimpulan yang sangat penting. Akan kita biarkan sajalah penggantian peranan budaya pondok pesantren seperti diuraikan di atas, oleh peranan materialistik dari sebuah pendekatan politis? Tentu saja jawabnya tidak, karenanya kita justru harus memperkuat peranan budaya itu dengan memperkenalkan bentuk-bentuk budaya baru yang hingga saat ini belum dikenal oleh warga pondok pesantren sendiri. Contoh dari proses itu adalah munculnya bentuk resmi (formalisasi) penggunaan kata-kata bahasa Arab untuk nama pondok pesantren. Kalau dahulu ponpes dikenal berdasarkan nama daerahnya seperti Pondok Pesantren Tebu Ireng (Jombang), dan Krapyak (Yogyakarta) sekarang menjadi Pondok Pesantren Salafiyah dan Al-Munawwir. Bukankah penggunaan bahasa Arab ini tidak mengganggu proses budaya yang seharusnya berlangsung. Memang mudah mengatakan perubahan, tapi yang lebih susah adalah melaksanakan, bukan? Membaca Sejarah Lama (1) Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Sejarah lama kita sebagai bangsa memang sangat menarik. Rasa tertarik itu timbul dari kenyataan, bahwa yang tertulis sering tidak sama dengan yang terjadi. Dengan kata lain, sejarah masa lampau sering dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ini, umpamanya, terlihat pada asal usul dinasti Mataram. Menurut cerita, Ki Ageng Gringging mempunyai sebutir kelapa muda yang diletakkan pada rak (pogo) di dapur. Ketika ia pergi ke kebun, datanglah Ki Ageng Pemanahan, yang langsung menuju dapur. Di tempat itu, ia melihat kelapa tersebut dan langsung melobanginya dan meminum aimya. Karena minum air kelapa itulah, ia kemudian, menjadi cikal bakal dinasti tersebut. Padahal, dalam budaya Jawa, meminum air kelapa berarti berbuat serong dengan istri orang. Kalau hal ini benar, berarti dinasti tersebut adalah hasil hubungan gelap antara Ki Ageng Pemanahan dengan istri Ki Ageng Gringging. Dan kalau demikian yang terjadi, berarti pula bahwa perzinahan adalah hal yang umum terjadi dalam pusat-pusat kekuasaan kita. Hal itu tidak mengherankan, karena sampai sekarangpun hal itu masih terjadi. ***** Salah satu hal yang harus diteliti adalah hubungan antara Raden Wijaya dan mertuanya, Raja Kertanegara dari Singosari. Mengapakah Raden Wijaya kemudian mendirikan Kerajaan Majapahit di Tarik (Krian)? Dalam hal ini, sejarah mengatakan dia membelot dari mertuanya itu. Tapi, tidak diterangkan mengapa ia berbeda
dengan sang mertuanya. Dalam setiap sumber sejarah, selalu disebutkan bahwa ia mendirikan negara Majapahit dengan bantuan Angkatan Laut China yang mengirimkan perahuperahunya melalui sungai Brantas ke Tarik. Padahal kita juga tahu, bahwa Angkatan Laut China sepenuhnya diisi oleh orang-orang muslim. Karena itu, salahkah kita kalau lalu menyimpulkan bahwa pertentangan Raden Wijaya dan mertuanya karena perbedaan agama? Kita tahu, bahwa Kertanegara adalah penganut paham Bhairawa (dalam istilah sekarang, Birawa yaitu, campuran antara agama Budha dan Hindu). Campuran itu adalah hasil pertempuran/pertemuan antara Kerajaan Hindu Kalingga di Jawa Tengah dan Kerajaan Syailendra yang beragama Budha. Dinasti Syailendra adalah pembangun candi Borobudur. Dari perbenturan Hindu dan Budha itu, lahirlah budaya campuran dengan agamanya sendiri, seperti tampak pada candi Prambanan, dekat Klaten. Ketika mereka dimusuhi kekuasaan yang ada (tidak jelas kaum Syailendra yang beragama Budha atau kaum Kalingga yang beragama Hindu) maka pengikut agama campuran itu berpindah ke Jawa Timur di bawah pimpinan Darmawangsa di Kediri. Padahal kita tahu, Kerajaan Singosari adalah penerusan dari kekuasaan Jenggala dan Daha di Kediri. Jadi, tak heran apabila tradisi yang berkembang di Singosari adalah Hindu-Bhuda. Sangatlah menarik untuk melihat betapa perbedaan agama mendorong munculnya Kerajaan-Kerajaan baru. Tetapi juga, ambisi-ambisi politik pribadi dapat juga menyebabkan timbulnya Kerajaan-kerajaan baru, seperti yang terjadi pada kerajaan Daha dan Kerajaan Jenggala di Kediri. Dengan demikian, mau tidak mau kita lalu kita harus memilih antara dua versi sejarah. Versi perbedaan agamakah, atau versi pertentangan akibat ambisi-ambisi pribadi? Dari sinilah kita lalu terjebak oleh keharusan membaca sejarah lama kita dalam versi yang berbeda-beda. Ini adalah akibat langsung akan kesenangan bangsa kita atas lambang-lambang kesejarahan. Catatan sejarah hampir-hampir tidak dibuat, dengan demikian kita lalu harus meraba-raba masa lampau kita sendiri. Inilah yang seharusnya kita lakukan, bukan lalu sekedar menghafalkan tahun-tahun dan nama-nama dalam "pelajaran" sejarah di sekolah-sekolah kita. Kita bukannya mengingat-ingat tahun kejadian, melainkan memahami sejarah sebagai sebuah proses. Membaca Sejarah Lama (2) Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Kita hampir selalu melihat perkembangan LSM/NGO (Lembaga Swadaya Masyarakat/Non-Govermental Organisation) sebagai fenomena yang baru. Padahal kalau kita simak dengan teliti, sejarah masa lampau kita akan memperlihatkan asal-usul LSM pada sejarah masa lampau kita sendiri. Dalam hal ini, kita dapat memulainya dengan kisah pertarungan antara sultan Hadiwidjaya (Raden Mas Karebet atau Jaka Tingkir) di Pajang melawan menantunya, Sutawidjaya.
Sutawidjaya kemudian terkenal dengan sebutan Panembahan Senoppati Ing Alaga Sayyidin Panatagama, pendiri Dinasti Mataram yang kita kenal sekarang. Pertempuran antara keduanya, di Pajang, akhimya dimenangkan oleh Sutawidjaya. Dengan demikian, Sultan Hadiwidjaya harus mencari "modal baru" dalam pertarungan itu. Dan, untuk itu, ia kembali ke rumah ibunya, Astatenggi-Sumenep (Madura). Sebagai penganut tarekat Qodiriyyah, ia kemudian memperoleh 40 macam kanuragan (kesaktian) baru. Dalam perjalanan kembali ke Pajang, ia menaiki perahu yang melaju di atas sungai Solo. Hal ini, sebagaimana dilanggengkan dalam tembang jawa "Sigra milir, sanggethek sinangga bajul, kawandasa cacahipun". Tembang ini adalah manifestasi budaya jawa, yang dikenal hampir oleh setiap anak jawa yang mengenal budaya daerahnya. ***** Kisah Jaka Tingkir di atas, "diakhiri" oleh kisah ---ketika ia mampir di Pulau Pringgobayan. Kini, pulau itu bertaut dengan daratan yang menjadi jembatan yang menghubungkan antara Pucukredjo dan Paciran di Kabupaten Lamongan. Di tempat itulah, Jaka Tingkir singgah untuk mengisi air dan keperluan-keperluan lain, dalam perjalanan kembali dari Pulau Madura ke Pajang dekat Demak. Dalam persinggahan itu, ia tertidur dan visiun (rukyah, impian atau wangsit) yang dialaminya terjadi. Gurunya menyatakan hendaknya ia tak meneruskan perjalanan ke Pajang, melainkan tetap tinggal di pulau tersebut. Untuk apa ia kembali ke Pajang, jika hanya untuk menuntut balas terhadap Sutawidjaya? Padahal, kanuragan yang dimilikinya tidak untuk merebut tahta kerajaan dari menantunya. Kalau hal itu yang dilakukan, ia hanya akan menjadi korban nafsu kekuasaan belaka. Dengan sendirinya, ia harus menahan diri dan mengembangkan sesuatu yang baru, yang harus dilakukannya tidak dari pusat kekuasaan di Pajang, melainkan dari tempat ia berada, yaitu di Pringgabaya. ***** Dengan demikian, lahirlah sebuah tradisi baru, yaitu adanya LSM di luar pusat kekuasaan di Pajang. Ini adalah apa yang dirumuskan oleh Dr. Taufiq Abdullah dengan istilah hubungan multi-keratonik. Dalam hubungan seperti ini, selamakeraton kecil menyatakan ketundukan nominal kepada keraton besar sudah dianggap cukup. Bahwa pihak pheriferal mengembangkan diri dalam pola yang tidak dikehendaki oleh pusat kekuasaan , adalah sesuatu yang baru dalam sejarah bangsa kita. Hubungan pheriferi-pusat yang tidak simetris ini justru dipergunakan untuk pengembangan Islam tanpa merugikan agama Hindu dan Budha yang sedang berkuasa saat itu. Sedikit demi sedikit, agama baru yang datang terkemudian mengambil alih kehidupan agama-agama terdahulu, tanpa menimbulkan
perbenturan yang berarti. Dengan cara ini, sesuatu yang baru telah menggantikan hal lama tanpa ada perbenturan politik yang dahsyat. Ini berarti, LSM yang bergerak di akar rumput (grass roots) harus mengembangkan jati dirinya sendiri, hingga tidak harus mengikuti pola LSM-LSM intemasional, kalau dikehendaki tidak ada perbenturan besar melawan sistem kekuasaan yang ada. Ini berarti keharusan bagi mereka untuk tidak bergantung pada dunia luar, melainkan menggunakan cara dan gaya hidup masing-masing yang benar-benar berasal dari rakyat. Di sisi inilah kita berharap banyak dari LSMLSM kita, bukannya sesuatu yang didektekan dari luar. Membaca Sejarah Lama (3) Oleh:
Abdurrahman
Wahid*
Jepang menduduki Hindia Belanda, demikian kawasan Indonesia waktu itu dikenal, pada bulan maret 1942. Kyai Hasyim Asyari dari Tebuireng di Jombang membungkukkan badan (seikeirei) ke arah timur laut tempat kaisar (Tenno Heika) bersemayam di Tokyo. Bagi beliau, ini merupakan penyerahan diri kepada keyakinan bahwa Kaisar Jepang adalah putra dewa matahari (amaterasu). Polisi rahasia Jepang (kempeitai) marah atas pembangkangan ini, dan beliaupun dimasukkan penjara Kalisosok-Surabaya. Delapan bulan lamanya beliau ada di situ, dengan penyiksaan dan tindakan keji lainya. Sebagai akibat, beliau tidak dapat menggerakkan tangan kirinya, alias lumpuh. Pemerintah pendudukan Jepang baru belakangan mengetahui betapa besar pengaruh beliau, dan segera dibebaskan setelah delapan bulan berada di penjara. Perlawanan dalam bentuk berdiam diri menahan siksaan ini, bagaimanapun juga telah memberikan bekasnya dalam sejarah. Paling tidak, sikap tidak rela itu segera diketahui masyarakat banyak, dan memang inilah inti dari pada perlawanan kultural, bukan perlawanan militer. Sengaja tidak diambil pilihan perlawanan secara militer karena waktunya dipandang belum tepat, dan kita tidak siap untuk itu. Putra beliau yang bemama Abdul Wahid Hasyim memimpin Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dalam tahun itu juga di Jakarta. Tinggal di Jalan Diponegoro, kyai muda ini diminta mewakili ayahnya oleh pihak Jepang untuk membuka Sunmubu (kantor agama) yang di kemudian hari berkembang menjadi Departemen Agama. Dalam kapasitas itulah pada suatu hari, ia dihubungi oleh Laksamana Maeda dari pemerintahan pendudukan Jepang. Ia ditanyai, siapa yang patut diperlakukan selaku wakil bangsa Indonesia? Ia menjawab, hal itu akan diketahui setelah ia berkonsultasi dengan ayahnya di Jombang, yaitu KH. Hasyim Asyari, di Tebuireng. Dalam pembicaraan per telepon dengan sang ayahanda di Tebuireng, Jombang, ia mendapatkan jawaban. Bahwa orang yang pantas didukung sebagai pemimpin bangsa Indonesia adalah Soekamo. Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU), dan
Kyai yang sangat disegani serta punya pengaruh luas, pilihan ini tentu mengandung tempat yang sangat terhormat bagi diri Bung Kamo. Dengan demikian, pemerintahan pendudukan Jepang, menunjuk Soekamo sebagai pemimpin rakyat beserta Mohamad Hatta. Dilihat dari sepak terjang dan sikap tersebut, kedudukan dua tokoh itu sebagai pemimpin bangsa adalah sesuatu yang sangat jelas. Apabila keduanya sepakat tentang sesuatu hal, boleh dikata hal itu telah menjadi keputusan bangsa ini. Demikianlah kesepakatan mereka untuk merdeka, akhimya tertuang dalam teks proklamasi kemerdekaan bangsa kita pada tanggal 17 agustus 1945. Bagi mereka, tidaklah begitu penting dengan melihat apa yang mereka lakukan saat itu --karena memang dipaksa oleh para pemuda, seperti Soekami. Dalam "membaca" kejadian itu, kita harus menyadari, bahwa para pemimpin kita dahulu sepakat untuk merdeka, sedangkan mengenai hal-hal lain akan ditetapkan kemudian. Jadi memang terasa betapa penting sikap yang diambil bersama-sama oleh para elite bangsa kita di masa itu.Tanpa adanya sikap seperti ini, kita mungkin kini belum merdeka, hingga hari ini. Sayangnya, hal ini tidak tampak di kalangan para elite kita pada masa sekarang. Masing-masing mencari pemenuhan ambisi pribadi, dengan mengorbankan kepentingan yang lebih besar. Yakni, kepentingan nasional yang selalu dikalahkan oleh ambisi pribadi serta kepentingan kelompok. Ini semua temyata membawa sebuah akibat lain, yaitu suatu pertentangan tajam di antara mereka. Masingmasing ingin tampil sebagai pemimpin bangsa, dan boleh dikata tidak mengakui secara tulus kepemimpinan orang lain. Dikombinasikan dengan kepandaian membungkus semua kekurangan -dengan retorika indah yang tak berpengaruh apa-apa bagi kehidupan berbangsa dan bemegara kita, sikap tersebut membawa kita kepada kemacetan kehidupan yang kita alami sekarang ini. Jalan satu-satunya untuk mendobraknya adalah dengan cara meninggalkan sikap seperti di atas. Sudah waktunya kita memikirkan nasib bangsa ini secara keseluruhan. Kalau perlu dengan menanggalkan sikap memandang penting arti diri sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bemegara. Beban luar negeri kita yang sudah mencapai 700 milyard dollar AS dan ancaman disintegrasi -akibat matinya Theys Hiyo Eluay di tanah Papua dan masalah pembunuhan atas seorang Letnan dua TNI di Aceh oleh pihak GAM, jelas membuktikan adanya kebutuhan akan sikap mementingkan bangsa ini. Pertanyaan dasamya adalah, sanggupkah kita sebagai bangsa mengembangkan sikap meninggikan kepentingan bersama itu dan mengalahkan kepentingan pribadi para pemimpin bangsa kita? Membangunkan Indonesia Dari Tidumya Oleh: Abdurrahman
Wahid
Krisis multi dimensi yang sedang kita alami sebagai bangsa sudah berjalan bertahun-tahun. Pengangguran semakin bertambah, sudah puluhan juta orang tidak punya pekerjaan, padahal ukuran pengangguran itu sediri sudah dibuat
demikian rupa oleh Biro Pusat statistik (BPS), sehingga orang yang bekerja menggunakan waktu dengan minimal atau memperoleh hasil sangat sedikit dari pekerjaannya dapat disebut menggangur. Penulis tidak tahu, mengapa ukuran demikian sederhana mengenai orang bekerja atau menganggur, dijadikan ukuran oleh BPS. Padahal saat ini, banyak orang yang bekerja dengan waktu minimal tapi penghasilannya dapat lebih tinggi. Mungkin ini sebagai bagian dari penipuan masyarakat oleh sistem Orde Baru di bidang ekonomi, seperti halnya penggunaan bahasa semu: diamankan untuk ditangkap, disesuaikan untuk kenaikan harga dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itulah kita sekarang berada, angkutan udara demikian padat karena cabang atas masyarakat kita mengalami kebangkitan ekonomi, sementara keadaan orang di bawah tetap saja dalam krisis. Bahkan dibeberapa tempat seperti Kalitidu (Bojonegoro Selatan) orang sudah makan bulgur dan tidak makan nasi, dan di banyak tempat daerah Pantura Pulau Jawa, orang sudah mulai menjual aset (tanah, rumah, sepeda motor atau televisi) untuk sekedar biaya makan. Ini juga terjadi dilokasi sangat besar dalam kehidupan masyarakat kita terutama dikawasan-kawasan berpenduduk padat. Puluhan juta anak tidak memperoleh kesempatan mengembangkan diri melalui pendidikan kaitannya dengan ini, timbul tanda tanya mengenai kualitas Sumber Daya Manusia kita beberapa tahun lagi. Kurs Dollar yang merendah, hanya menguntungkan konglomerat hitam yang selama ini berhutang dan memarkir uang mereka di luar negeri. Kalau mereka kembali membawa uang dollar kemari tentu karena dianggap lebih menguntungkan bertindak seperti itu. Mengingat demikian mudahnya memperoleh status bebas dari tuntutan hukum (Release and Discharge) atas upaya melarikan uang dan melanggar hukum selama ini. Ini terjadi karena tanpa ada keharusan mengalihkan modal ke sektor negara atau ekonomi rakyat, sehingga para konglomerat hitam itu tetap tidak terkena keharusan meratakan sumber-sumber ekonomi yang mereka miliki. Dengan kata lain, setelah selama ini merampok sekarang dibiarkan saja menikmati hasil rampokan itu. Sedangkan seluruh sistem perpajakan Bea Cukai dan Hukum tetap tetap hanya menguntungkan mereka saja. Inilah ciri kapitalisme intemasional yang dimintai belas kasihan oleh pemerintah pusat dewasa ini, tanpa danya trasformasi sosial yang akan merubah stuktur perekonomian secara nasional. ***** Penyelundupan semakin merajalela dan pencurian kekayaan negara berjalan terus menerus tanpa ada kendali sama sekali. Bahkan KKN pun merajalela hingga ketingkatan tertinggi di negeri ini, sebagaimana kita saksikan dalam berbagai hal dan proyek yang dilakukan negara. Bahkan partai-partai politik yang besar melakukan praktek yang memalukan baik melalui pihak eksekutif maupun legislatif. DPR RI dan daerah merupakan tempat jual-beli suara yang sangat menyedihkan, lebih dari masa-masa pemerintahan Orde Baru pihak eksekutif dengan keharusan mengumpulkan uang untuk memupuk kekuatan finansial menghadapi pemilu yang akan datang. Plus keuletan para birokrasi untuk mencuri uang sebanyak-
banyaknya tidak lagi memperhatikan aturan-aturan yang ada. Bahkan sangat menyedihkan ada sementara kalangan preman yang dapat memerintah Polri untuk berbuat semaunya saja, antara lain untuk memasung kemerdekaan pers. Bahkan, sudah begitu parahnya keadaan sehingga pidato Kepala Negara juga sudah dianggap tidak ada artinya, karena isi berbagai pidato tidak substansial dan hanya memuat keluhan-keluhan belaka. Yang lebih-lebih menyakitkan lagi, ketika ada pihak-pihak asing mengadakan berbagai manuver di wilayah negara kita, tanpa ada protes sama sekali, karena itu penulis terpaksa mengajukan protes melalui media atas kegiatan Angkatan Laut A.S (Amerika Serikat) dengan pesawatpesawat F 18 Homet di atas Pulau Bawean (Jawa Timur) dan dua buah kapal perang A.S, yang diiringi beberapa buah kapal Singapura mengadakan manuver di perairan Propinsi Riau di barat pulau Natuna. Ditambah dibawa larinya Hambali ke A.S tanpa protes dari negara kita, hal-hal tersebut akhimya membuat Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif naik pitam dan menyatakan dilayar televisi bahwa kita sudah tidak mempunyai kedaulatan lagi atas negeri ini. Pemerintah seolah-olah menutup mata terhadap hal-hal yang membahayakan ekosistem beberapa buah pulau di negeri kita, seperti perbuatan beberapa orang pengusaha. Kalau Singapura ingin mengadakan/melakukan reklamasi tanah dan memperluas wilayah negaranya itu dapat dimengerti, tetapi yang membuat kita heran hal itu dilakukan atas kerugian dan bahaya yang mengancam terumbuterumbu karang kita. Hal inilah yang tidak kita mengerti dan tetap berlangsung karena keserakahan sementara pengusaha yang sangat dekat hubungan mereka dengan pemegang kekuasaan pemerintah. ***** Ketika berada di Tokyo dan menghadiri dialog di Universitas Sophia (Tokyo) tanggal 31 Mei yang lalu penulis ditanya pandangan oleh salah satu hadirin mengenai hukum darurat militer di Aceh. Penulis menjawab ia dahulu secara gigih mengeluarkan pendapat, bahwa pnyelesaian masalah Aceh haruslah dicapai melalui perundingan; tetapi setelah diumumkan pemerintah pelaksanaan hukum darurat militer itu, sebagai warga negara yang baik penulsi memantau saja tanpa mengeluarkan pendapat. Ini artinya, kita harus membiarkan pemerintah melaksanakan darurat militer itu dengan ikhlas dan mengharapkan hasil yang baik. Berhasil atau tidaknya kita serahkan kepada perkembangan keadaan, karena kita harus percaya kepada semua perangkat pemerintahan yang kita miliki. Altematif terhadap sikap itu memang sangat menakutkan: melawan pemerintahan kita sendiri, tidak dapat dibayangkan bilamana hal itu terjadi maka akan ada dua kepemimpinan di negeri kita. Di satu pihak ada pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah, di pihak lain ada pemimpin masyarakat yang melawan secara efektif pula. Kalau demikian tentu akan ada dua buah pemerintahan di wilayah yang sama, dan tidak dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi bilamana keadaan itu berlangsung. Sekarang ini, ada beberapa pihak yang secara diam-diam berbeda pandangan tentang pemberlakuan hukum darurat militer di Aceh. Begitu pula, ada upaya untuk memasung kemerdekaan pers melalui Undang-Undang, namun
semuanya itu dilakukan tidak melalui upaya terbuka dan resmi dengan menyembulkan kekuasaan pemerintahan altematif yang baru, diluar pemerintahan yang ada. Melihat kondisi di atas, karenannya penulis berharap para penyelenggara kekuatan pemerintah (baik sipil maupun militer) untuk mengutamakan keutuhan bangsa dan negara, dan kita semua untuk menahan diri dan tidak berusaha mengagalkan jalannya pemerintahan atas kemenangan kekuasaan kelompok/golongan sendiri, karena akibatnya adalah kerugian di pihak rakyat. Biarkan rakyat yang menentukan melalui Pemilihan Umum legislatif maupun Presiden/Wakil Presiden. Kearifan seperti ini memang kita perlukan saat ini karena penulis mendengar berita-berita yang menyatakan adanya berbagai upaya seperti itu. Tentu saja hal itu penulis tolak, demi kecintaan kepada keutuhan bangsa dan negara. Penolakan itu harus kita lakukan. Walaupun mudah dikatakan dan sulit dilakukan, bukan? Membentuk Solidaritas Sosial Oleh
Abdurrahman
Wahid
Solidaritas sosial atau solidaritas antar-sesama manusia pada akhimya akan membentuk masyarakat-masyarakat dan pada gilirannya akan membentuk bangunan-bangunan sosial yang tangguh yang dapat mengayomi manusia. Solidaritas ini kadang kala datang dari pemberian apresiasi seni dan budaya secara benar. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan membentuk pula apresiasi seni dan budaya. Sekarang ini kita kesulitan untuk mengikuti "tembang lama" yang terlalu lamban, karenaantara lainirama hidup kita sudah didera teknologi televisi. Teknologi ini merupakan percepatan dari apresiasi kita terhadap kehidupan. Melalui teknologi kita dikotak-kotakkan dalam waktu yang sudah pas. Akan tetapi teknologi televisi ini juga membentuk sesuatu yang lain, yakni melakukan percepatan pada bagaimana kita memahami kehidupan. Karena itu, kalau saja kita tidak mampu melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dimensi seni dan budaya, kita akan menjadi masyarakat yang tertinggal. Kita akan mengalami kesenjangan budaya.Di sinilah sesungguhnya kita harus meramu seni dan budaya di satu pihak dengan unsur solidaritas sosial serta unsur ilmu pengetahuan dan teknologi. Seni dan budaya harus dibentuk dan saling mempengaruhi keyakinan akan kebenaran. Ketika Pablo Picasso, seorang pelukis yang amat masyhur, membuat lukisan yang "berantakan" menggambarkan tentang korban-korban perang dalam perang saudara Spanyol pada 1937 banyak yang mempertanyakan arti lukisan itu. Terutama tentang suasana berantakan yang mencuatkan potongan-potongan manusia. Kebenaran dan pemahaman terhadap lukisan Picasso itu baru datang ketika muncul perjuangan rakyat melawan rezim fasis di Spanyol, yakni kaum Republikan melawan kaum militer. Maka di balik keindahan yang dirumuskan oleh seorang Pablo Picassodengan gambar-gambar potongan kepala dan badan yang tidak
bersambung untuk membentuk tubuh orangmaka sesungguhnya Picasso sedang menggambarkan keporak-porandaan masyarakat yang dilanda peperangan. Juga ketika orang seperti Syeh Abdul Haq melahirkan karya lukisan hanya dengan gambar sebuah garis tegak lurus pada kanvas dalam ukuran besar, banyak orang bertanya tentang makna lukisan itu. Padahal makna lukisan itu sesungguhnya merupakan kulminasi dan seluruh pengalaman hidup yang berantakan. Akan tetapi yang dia lihat adalah kebenaran yang diyakini keniscayaannya. Artinya, bahwa hidup harus berantakan dan ditata kembali. Untuk melakukan itu semua, maka elemen dasamya hanya satu, yaitu sesuatu yang kita temukan dalam sepotong garis lukisan Abdul Haq tadi. Di sini lalu muncul asumsi bahwa seni dibentuk oleh keyakinan akan kebenaran. Kita harus menyadari pentingnya arti seni dan budaya dalam satu sudut, yakni keharusan kita membentuk kehidupan melalui pembentukan kepribadian yang seimbang. Tidak dapat dihindarkan ada orang-orang yang hanya mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, atau hanya meyakini kepastian-kepastian matematik dari kehidupan. Ada juga yang lebih menyenangi nilai-nilai ideologis, yakni kebenaran keyakinan seperti peribadatan dan penghayatan terhadap kebesaran Tuhan. Di samping ada juga yang lebih menyenangi manifestasi yang sangat artistik. Melalui solidaritas sosial yang sangat kuat, di mana manusia saling membantu dan saling mendukung, tentunya antarmanusia tidak akan saling memerangi. Tekanantekanan yang berbeda adalah wajar-wajar saja. Yang penting kita tidak boleh terpengaruh oleh satu unsur kemudian meninggalkan unsur yang lain. Hendaknya unsur yang satu dan yang lain membentuk sebuah sinergitas gerakan. Kita memiliki bentangan hidup yang sangat luas. Kita juga memiliki tataran yang sangat baik. Apalagi bangsa Indonesia yang sedang membangun ini telah sanggup membuktikan bahwa walaupun masih banyak ketimpangan sosial, walaupun demokrasi belum dapat diwujudkan sepenuhnya, walaupun hak-hak asasi manusia belum dapat tegak di negeri ini, harapan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baikIndonesia yang lebih mampu memenuhi cita-citatetap ada. Kita yakin dengan semangat dan harapan untuk menuju Indonesia yang dicitacitakan, maka masa depan bangsa kita memberikan optimisme yang tidak berlebihan dan tidak akan menyesatkan. Mengapa Mereka Marah Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Seorang kawan menanyakan, mengapa banyak pemuka masyarakat Islam marah kalau mendengar sebutan 'kaum fundamentalis', atau tersinggung kalau ada orang membicarakan 'issue negara Islam'.
Pertanyaan yang patut direnungkan, karena ia menunjuk pada perkembangan sangat kompleks dalam kehidupan bermasyarakat kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, tidak hanya di negeri kita. Pertanyaan kompleks sudah tentu tidak dapat dijawab sederhana. Membutuhkan renungan yang dalam, juga tidak kurang keberanian moral untuk melihat masalahnya dengan jemih. Dengan tidak hanyut oleh luapan marah, atau ketakutan yang disembunyikan rapat-rapat di balik kebanggaan akan peranan kesejarahan diri sendiri, atau kegairahan menudingkan jari terhadap kesalahan 'pihak lain' dalam percaturan politik, kultural dan keagamaan yang dihadapi. Juga memerlukan kesanggupan untuk menelusuri mana wilayah kehidupan yang hakekatnya menjadi 'agenda pemikiran' kaum muslimin, dan membedakannya dari agenda semu yang kini dijajakan sebagai pertanda kebangunan kembali Islam. Pengagungan Diri Kaum muslimin dimana-mana terbagi dalam dua kelompok utama : mereka yang mengidealisir Islam sebagai altematif satu-satunya terhadap segala macam isme dan ideologi, dan mereka menerima yang menerima dunia ini 'secara apa adanya'. Pihak pertama menganggap Islam telah memiliki kelengkapan cukup untuk menjawab masalah-masalah utama umat manusia. Tinggal dilaksanakan ajarannya dengan tuntas , tak perlu lagi menimba dari yang lain. Karenanya, kalau dianggap perlu ada dialog dengan keyakinan, isme atau ideologi lain, haruslah ia diselenggarakan dalam kerangka menunjukan kelebihan Islam. Seonggok 'pembuktian' diajukan - umumnya dengan mengemukakan jawaban idealistis yang pemah dirumuskan Islam. Sudah tentu jawaban itu dilandaskan pada sejumlah pengandaian serba idealis pula: kalau saja umat manusia mau mengikuti ajaran Islam (padahal kenyatannya tidak), jika para pemimpin menggunakan moralitas Islam (padahal hanya satu dua orang saja yang mampu), dan seterusnya. Postulat-postulat formal Islam diajukan sebagai jawaban terhadap kemelut kehidupan masa modem: ayat-ayat Qu'ran dan hadist Nabi sebagai tolok ukur lahiriah satu-satunya bagi 'kadar keislaman' segala sesuatu yang dikerjakan. Tidak heran kalau sikap kritis terhadap keadaan sendiri tidak dapat dikembangkan sepenuhnya - terhalang oleh 'sudah sempumanya' Islam sendiri. Lalu menjadi wajar juga kecenderungan untuk hanya mampu mengagungkan diri sendiri, yang memandang remeh perkembangan. Perkembangan apa pun di luar keasyikan kita dengan kehebatan Islam lalu tidak memiliki nilai yang tinggi. Kalau perkembangan di luar tidak dapat diabaikan dicarikanlah alasan untuk menghindarkan pemikiran mendalam atasnya: ini buah pikiran komunistis, itu ide sekuler, dan seterusnya. Semakin besar kenyataan di luar menghadang ufuk pandangan kita, semakin hebat upaya melarikan diri dari perwujudan kongkritnya.
Kalau diajukan pemikiran untuk mencari jawaban kongkrit (bukan hanya idealistis) dengan jalan menghadapkan ajaran Islam pada kerangka berfikir baru yang bersumber pada isme, keyakinan dan ideologi lain, maka cap kemurtadan, kekafiran dan lagi-lagi sekuler dipakaikan pada usul itu sendiri. Mental Banteng Timbullah apa yang kemudian dinamai sejumlah pengamat sebagai 'mentalbanteng': Islam harus dipagari rapat-rapat dari kemungkinan penyusupan gagasan yang akan merusak kemumiannya. Tanpa disadari, mental seperti itu justru pengakuan terselubung akan kelemahan Islam. Bukankan ketertutupan hanya membuktikan ketidakmampuan melestarikan keberadaan diri dalam keterbukaan? Bukankah isolasi justru menjadi petunjuk kelemahan dalam pergaulan? Kalau kepada sikap jiwa seperti itu diajukan tuduhan oleh pihak luar akan adanya fundamentalisme, atau tentang masih adanya pemikiran mendirikan 'negara Islam', jelas rasa marah yang muncul sebagai reaksi. Bukankah karena ketakutannya terhadap 'pengaruh negatif' luar, ia lalu curiga terhadap semua pendapat 'orang luar' tentang dirinya? Bukankah kepekaan adalah hasil dari sikap mengunci pintu seperti itu? Padahal penamaan sebagai kaum fundamentalis tidak ditunjukkan kepada semua kaum muslimin yang mengidealisir Islam dan menempatkannya sebagai altematif tunggal bagi semua Isme, keyakinan dan ideologi yang ada. Cukup besar jumlah idealis muslimin yang mampu menerima isme-isme lain, dan melihat peranan agama mereka dalam fungsi mengarahkan isme-isme itu bagi kebutuhan hakiki umat manusia, entah nasionalisme, sosialisme dan seterusnya. Banyak sekali idealis muslimin yang melihat ideologi formal negara sebagai pengatur pergaulan politik, sedang Islam difungsikan terutama dalam pergaulan sosio-kultural. Jelas tidak semua kaum idealis muslimin fundamentalis. Kalau demikian mengapa hampir semua 'idealis muslim' marah terhadap istilah diatas, atau terhadap anggapan masih adanya aspirasi mendirikan 'negara Islam' dan sebangsanya ? Karena mereka mengurung diri dalam benteng mental yang mereka dirikan. Semua penamaan 'dari luar' lalu dianggap mengenai semua warga benteng, sebagai tuduhan serampangan dan prasangka buruk terhadap semua muslimin idealis yang berada dalam benteng. Simplifikasi permasalahan adalah metode pemikiran mereka, sehingga pemberian nama apapun yang dirasakan tidak simpatik dianggap ancaman. Memang jauh implikasinya bagi masa depan perkembangan Islam. Tapi sebenamya kita tidak usah pesimistis dengan sikap jiwa seperti itu. Mengapa ? Karena itu akan berkurang dengan sendirinya, kalau proses pendewasaan telah mempengaruhi cara berfikir.
Ini hukum Berlaku baik untuk muslimin maupun yang bukan. Menikmati Pagelaran Wayang Kulit Oleh:
alam.
Abdurrahman
Wahid
Dua minggu lalu, pada permulaan rangkaian acara Harlah ke-6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kawan-kawan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tersebut menyelenggarakan pagelaran wayang kulit di rumah penulis, Ciganjur. Dalangnya adalah Ki Enthus Susmono, dengan bintang tamu trio Yati Pesek, Timbul dan Marwoto. Lakon yang digelar adalah Bale Sigologolo. Inti ceritanya adalah bagaimana rencana Adipati Destrarata, untuk mengembalikan anakanak Prabu Pandu (Pandawa) ke tahta kerajaan di Astina. Namun, Patih Sengkuni berhasil mengagalkan hal itu dengan cara membuat Pandawa mabuk dengan minuman keras dan terbaring tidak sadarkan diri di atas balai-balai (bale sigologolo) untuk merayakan kenaikan tahta Puntadewa tersebut. Bale Sigolo-golo itu dibuat dari bahan yang mudah terbakar dan kemudian Sengkuni membakamya. Baik Pandawa dan Ibu mereka, Kunthi Talibrata, diselamatkan oleh seekor musang putih dan Bratasena. Bukankah dengan memegang tahta ditampuk kekuasaan kerajaan Astina, tidak lain dimaksudkan untuk mempunyai pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat? Bukankah ini merupakan permulaan dari Monarki Konstitusional seperti terdapat di banyak negara Eropa Barat? Bukankah dengan menentukan para RajaRatu harus mengutamakan kepentingan rakyat, berarti kedudukan Raja-Ratu sebagai simbol/lambang pemerintahan monarki negara-negara tersebut, lalu berwatak demokratis, dengan mengakui dan tunduk kepada pemerintahan orang-orang biasa yang bukan bangsawan?. Lakon itu dipilih penulis, karena ia melambangkan permulaan perjuangan membela kebenaran, yang menyangkut hak-hak pribadi maupun hubungan perorangan para Pandawa dengan masyarakat. Permulaan perjuangan seperti itu, menurut penulis adalah proses yang di jaman ini dianggap demokratisasi sebuah negeri. Upaya-upaya yang dilakukan untuk demokratisasi ini, tentu saja atas persetujuan PKB, yang berintikan kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Dan karena itulah penulis mengajukan usul tersebut. Secara moral, antara apa yang dilakukan para Pandawa di satu pihak dan proses demokratisasi kita di pihak lain saat ini, menunjukkan persamaan hakiki. Walaupun dalam pengertian yang berbeda satu dari lainnya, keduanya mempunyai persamaan hakiki berupa perjuangan untuk menegakkan demokrasi di negeri kita. Bahwa ada hal-hal lain dari cerita itu yang dapat diambil sebagai kesimpulan, sama
sekali tidak masuk dalam pemikiran penulis. Kenyataan itu juga dirasakan oleh Ki Dalang dalam pagelaran tersebut, sebagaimana tampak dalam pagelaran itu sendiri. lain-lainnya adalah hal umum yang terjadi dalam sebuah pagelaran wayang kulit. Kritikan demi kritikan yang diajukan kepada sistem politik yang ada, minimal pada para pelaku di dalamnya, sering dilontarkan oleh Ki Dalang dan oleh para bintang tamu. Dalam suasana seperti itulah adik penulis, Ir. Sholahudin Wahid, dan Ketua MPR-RI Prof. DR. Amien Rais dan istrinya tampak hadir, tentu saja juga penulis sendiri, sempat dikocok oleh Ki Dalang dan para bintang tamu. Yang lepas dari hal itu adalah Prof. DR. S. Budi Santoso, Ketua Partai Demokrat, yang sudah pulang dari lahan pagelaran itu, sebelum Ki Dalang dan para bintang tamu sempat melontarkan gurau mereka. Gurauan demi gurauan yang dilontarkan itu, pada hakikatnya menyembulkan kemampuan untuk menertawakan diri sendiri. Sesuatu yang memang inheren dalam sebuah pagelaran kultural, seperti yang disajikan di Ciganjur malam itu. Mungkin kemampuan mentertawakan diri sendiri itulah, menjadi salah satu sebab kita masih rukun sebagai bangsa, walaupun demikian besar perbedaan budaya dalam kehidupan bangsa ini. Kemampuan itu mengimbangi kebolehan mengajukan kritik atas hal-hal salah yang kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat bangsa. Dalam pagelaran wayang kulit itu juga ada sesuatu yang penting, yaitu adanya transplatansi panyajian sebuah kehadiran budaya dari lahan budaya lain. Transplantasi budaya Jawa yang diikuti dengan cermat, adakalanya juga melalui sikap penuh ketidakmengertian para hadirin yang hadir dari budaya-budaya lain, seperti sistem budaya Betawi. Mungkin, hal itu juga dilakukan oleh karena kesopanan antara berbagai sistem budaya tersebut yang mencema pelontaranpelontaran budaya dalam bentuk berbeda-beda itu. Pagelaran wayang kulit itu, adalah sebuah peristiwa budaya yang disajikan kepada publik secara terbuka, dengan didalamnya ada dua buah sajian yang penting untuk diketahui. Pertama, sajian tentang sistem politik yang ada, yang dilaksanakan secara tidak benar dalam kehidupan bangsa, seperti terjadinya KKN di hampir sebuah bidang kehidupan, dan pelanggaran undang-undang oleh Komite Pemilihan Umum (KPU), dengan keputusannya untuk melakukan ganjalan bagi pencalonan diri penulis, untuk pemilihan umum Presiden-RI tanggal 5 Juli 2004 ini. Pelepasan uneg-uneg ini dapat dipahami sebagai sebuah pemyataan kritikan secara kultural maupun politis bagi kesalahan bangsa, tampak rasa pahit dan kemarahan kita. Di sinilah terletak keunggulan wayang kulit atas kritikan politis. Hal kedua yang dapat juga disimpulkan dari pagelaran wayang kulit itu, adalah kemampuan kita utnuk melestarikan salah sebuah lontaran-budaya (cultural outburst) yang menjadi pelepasan keadaan kita yang masih dihinggapi kesalahankesalahan itu. Kalau karya-karya Victorio De Sica dan kawan-kawan melalui film yang mereka buat segera setelah Perang Dunia II di Italia sering disebut sebagai aliran realisme sosial baru, maka wayang kulit sebagai medium kultural lama,
merupakan hal yang harus kita lestarikan. Dengan melakukan hal itu, kita juga memberikan sumbangan nyata untuk mengembangkan dan melanggengkan kehidupan budaya bangsa ini dari masa ke masa. Demikianlah sebuah kejadian kecil dalam kehidupan kita dapat saja menandai adanya proses besar dalam kehidupan kita. Hal ini, tentu saja sejajar dengan proses pemyataan rasa keberagaman yang kita jalani saat ini. Subumya kelompokkelompok kesenian dan pendidikan Islam, umpamanya saja merupakan hal yang tidak dapat dibantah oleh siapapun sekarang ini. Begitu juga tumbuh subumya berbagai bentuk peribadatan orang-orang Nasrani, menunjukkan hal yang sama. Kenyataan inilah yang seharusnya membuat kita bersama gembira, selama tidak ada ekses-ekses penyempitan pandangan dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Proses itu sendiri dapat saja berkembang menjadi sesuatu yang akan menyempitkan, atau justru melebarkan perasaan kita sebagai umat beragama. Nah, begitu banyak hal yang dikemukakan di atas dari sebuah pagelaran wayang kulit (dan tentu saja dari pagelaran-pagelaran lain), sebagai sebuah peristiwa budaya. Hal inilah yang membuat kita dapat melestarikan budaya bangsa, dalam perjalanannya yang sangat panjang. Tentu saja, jika kita semua memandangnya dari sudut budaya, hal yang kita lakukan selama ini tidak boleh dianggap sebagai sebuah peristiwa kecil. Walaupun hal itu juga dapat dilihat dari sudut-sudut lain seperti sudut pandangan politik, sudut dialog antar agama dan sebagainya. Semua itu merupakan kekayaan bangsa yang harus kita lestarikan di masa ini dan masa depan. Di dalamnya ada proses memelihara dan merubah sesuatu yang mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan, bukan? Menyelesaikan Krisis Mengubah Keadaan Oleh: KH ABDURRAHMAN
WAHID
PERTENGAHAN Desember tahun ini, penulis bertemu sutradara Garin Nugroho di airport Adi Sutjipto, Yogyakarta, sambil menunggu pesawat terbang yang akan membawa kami ke Jakarta, Garin Nugroho dan penulis terlibat dalam pembicaraan mengenai cara mengatasi krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini. Sebagai seorang yang melakukan referensi terus menerus atas kitab suci Alquran, penulis mengemukakan analogi dari para kyai, mereka berpendapat krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini adalah seperti krisis Mesir di jaman Nabi Yusuf dahulu. Krisis itu memakan waktu tujuh tahun, menurut kitab suci tersebut. Kalau ini kita analogikan kepada keadaan sekarang, maka era tujuh tahun itu akan berakhir pada tahun 2003 (1997 hingga 2003). Memang, sekarang kalangan atas mulai dapat mengatasi krisis ekonomi, terbukti dari penuhnya jalan dengan kendaraan dan lapangan terbang, tetapi kalangan bawah masih saja mengeluh dan kesusahan karena memang mereka masih dilanda krisis.
Keluhan utama adalah menurunnya daya beli secara drastis, sedangkan hargaharga beberapa jenis barang kebutuhan sehari-hari justru melonjak. Dengan demikian, masih menjadi pertanyaan apakah dalam waktu cepat krisis multidimensi itu dapat dipecahkan, katakanlah pertengahan tahun 2003. Dalam hal ini, sangat menarik pembicaraan penulis dengan kyai Nukman Thahir dari Ampel Surabaya. Ia menyatakan, kalau kitab suci Alquran dibaca dengan mendalam, di sana disebutkan bahwa krisis nabi Yusuf berlangsung tujuh tahun, namun untuk mengatasi krisis tersebut diperlukan juga waktu tujuh tahun lamanya. Penulis menjawab apa yang ia terima dari para kyai adalah waktu berlangsungnya krisis itu tujuh tahun lamanya, tidak pemah ia mengatakan diperlukan waktu tertentu untuk menyelesaikan krisis. Karenanya, penulis mengungkapkan bahwa penyelesaian krisis itu sendiri, terjadi secara formal dimulai dalam waktu bersamaan/simultan dengan berakhimya krisis itu. Karenanya, penyelesaian krisis tidak merupakan entitas yang berdiri sendiri terlepas dari krisis yang dialami. Percakapan penulis dengan Garin Nugroho itulah yang menjadi petunjuk konkrit penyelesaian masalah secara simultan itu. Mula-mula Garin Nugroho mengatakan dua hal sangat penting, satu pihak, ada perbedaan/kesenjangan antara para teoritisi hukum dan pembuat Undang-undang (DPR dan MPR). Para ahli teori hukum mengemukakan, hukum-hukum baru dalam bentuk undang-undang maupun lainnya dari berbagai sumber Eropa Continental yang kita kenal. Tetapi pelaksana berbagai macam peraturan itu, pada umumnya di didik di lingkungan hukum Anglo Saxon yang berlaku di Amerika Serikat. Tidak usah heran, jika terjadi kesenjangan antara kedua sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa Continental itu. Adalah tugas kita, menurut Garin Nugroho, untuk mendamaikan antara keduanya, inilah yang harus diperbuat untuk menyelesaikan krisis. Dalam percakapan itu, penulis mengemukakan bahwa secara konkrit apa yang dinamai Garin Nugroho dengan mendamaikan itu, haruslah tercermin dalam empat buah sistem politik baru. Katakanlah konsepsi mengenai empat buah sistem baru yang diperlukan, untuk konkritisasi gagasan mendamaikan dari Garin itu. Di sini, penulis akan mencoba mengemukakan beberapa konsep seperti di bawah ini. Tentu saja, konsepsi-konsepsi yang dikemukakan itu adalah bukan bentuk final dari apa yang penulis pikirkan, karena justru masih memerlukan perbaikanperbaikan serius, dan belum dapat digunakan sebagai konsepsi formal. Konsep empat sistem ini, masih harus diperjuangkan untuk masa kehidupan kita yang akan datang. Hanya dengan cara demikianlah, bangsa kita dapat mengasi krisis multi-dimensional itu dengan cepat. Empat sistem baru yang penulis kemukakan kepada Garin Nugroho, meliputi sistem politik (pemerintahan), perbaikan sistem ekonomi dengan mengemukakan sebuah orientasi baru, sistem pendidikan nasional dan sistem etika atau hukum, yang semuanya harus serba baru. Mengapa baru? karena sistem lama tidak dapat dipakai lagi, tanpa akibat-akibat serius bagi kita. Yang didahulukan adalah sistem
politik (pemerintahan) yang baru. Kedua badan legislatif yang baru, DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) haruslah menjadi perwakilan bikameral. Mereka bertugas menetapkan undang-undang serta menyetujui pengangkatan eksekutif dengan pemungutan suara. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden, Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dipilih langsung oleh rakyat, karena kalau diserahkan oleh DPR, DPRD I dan DPRD II hanya akan memperbesar korupsi saja. Di samping itu juga dibentuk MPR, yang hanya bersidang enam bulan saja, dalam lima tahun. Mereka bertugas menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang harus dilaksanakan seluruh komponen pemerintahan. Keanggotaannya, terdiri dari para anggota DPR, DPD dan dari golongan fungsional, guna menguntungkan kelompok-kelompok minoritas ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, yang dicapai melalui prosedur musyawarah untuk mufakat, bukannya melalui pemungutan suara. Dengan demikian, kalangan minoritas turut serta memutuskan jalannya kehidupan berbangsa dan bemegara. Hal ini diperlukan, agar semua pihak merasa memiliki negara ini, dan dengan demikian menghindarkan separatisme yang mulai bermunculan di sana-sini. Justru inilah yang merupakan tugas demokrasi, bukannya liberalisasi total. Orientasi baru dalam sistem perekonomian kita, dicapai dengan melakukan pilihan berat antara dua hal, yaitu moratorium (penundaan sementara) cicilan tanggungan luar negeri kita, dan pembebasan para konglomerat hitam yang nakal dari tuntutan perdata, jika membayar kembali 95% kredit yang dia terima dari bank-bank pemerintah (tetapi tuntutan pidana tetap dilakukan oleh petugas-petugas hukum). Uang yang di dapat dari kedua langkah ini, menurut perkiraan sekitar US$230 miliar, dan digunakan terutama untuk:
1. Memberikan kredit ringan, kira-kira 5% setahun, bagi UKM (Usaha Kredit Menengah) dengan pengawasan yang ketat; dan 2. Peningkatan pendapatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan militer, kira-kira sepuluh kali lipat dalam masa tiga tahun. Langkah ini guna mencegah KKN dan menegakkan kedaulatan hukum. Melalui cara ini pula, dapat memperbesar jumlah wajib pajak, menjadi 20 juta orang dalam lima tahun dan melipatgandakan kemampuan daya beli masyarakat.
Sudah tentu dikombinasikan dengan hal-hal, seperti perbaikan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, serta penataan kembali BI (Bank Indonesia) dan MA (Mahkamah Agung). Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dengan cepat sebuah pemerintahan yang baru akan segera mengatasi krisis multi-dimensional ini. Hal penting lainnya, kemampuan pemerintah dalam mengatasi krisis juga sangat bergantung pada kemampuan bekerjasama dengan negeri-negeri lain. Sudah tentu, ini harus dibarengi oleh dua buah perbaikan sistematik lain. Perbaikan pertama, adalah pada perbaikan sistem pendidikan kita, yang hampir
tidak memperhatikan penanaman nilai dari pada hafalan. Karena tekanan yang sangat kecil kepada praktek kehidupan, dengan sendirinya hafalan mendapatkan perhatian yang luar biasa, dan pemahaman nilai-nilai menjadi terbengkelai. Keadaan ini mengharuskan dibuatnya sistem pendidikan baru yang lebih ditekankan kepada sistem nilai dan struktur masyarakat dasar (community-based education) dapat dilaksanakan. Dikombinasikan dengan perbaikan sistematik pada kerangka etika/moralitas/akhlak yang telah ada dalam kehidupan bangsa, maka perbaikan sistem hukum itu, akan menjadi dasar bagi pengampunan umum/rekonsiliasi atas kesalahan-kesalahan masa lampau, kecuali mereka yang bersalah dan dapat dibuktikan secara hukum oleh kekuasaan kehakiman dengan sistem pengadilan kita. Tentu saja, ini juga meliputi mereka yang sekarang disebut sebagai kaum ekstremis/fundamentalis dalam gerakan Islam, selama tidak dapat dibuktikan secara hukum, kejahatan yang mereka perbuat. Sudah tentu ini berlawanan dengan kehendak orang lain yang ingin menghukum segala macam kesalahan. Kita harus bertindak secara hukum, bukan karena pertimbangan-pertimbangan lain. Memang mudah dilaksanakan kedengarannya, namun sulit dalam pelaksanaan aktualnya, bukan?
Merubah Pandangan Sebuah Bangsa Oleh: Abdurrahman
Wahid
Pada Ramadhan lalu penulis berkunjung selama beberapa hari ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Semula ia mendarat di Guangzhou (dahulu Canton), dan menginap semalam di kota tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Beijing untuk dua malam. Walaupun menurut pihak protokol, penulis hanya dijadwalkan menjadi tamu pada institut masalah-masalah luar negeri (Institute of Foreign Affairs) yang berafiliasi kepada Kementrian Luar Negeri RRT. Namun di Beijing penulis mendapat kehormatan bertemu Jia Qinglin, Politbiro CC-PKT (Central Commitee Partai Komunis Tiongkok), orang keempat yang paling berkuasa di negara tersebut yang juga seorang pejabat tertinggi partai yang tidak menjadi pejabat negara. Bahkan selama berkunjung ke daerah-daerah, penulis bertemu dengan Lei Yulan Wakil Gubemur Guangdong karena gubemumya sedang bepergian ke luar negeri. Kemudian di ibukota propinsi Fujian ia bertemu dengan Walikota Guangzhou, Zhang Guangning dan di Xiamen bertemu dengan Walikota Zhang Changping. Di negeri itu, penulis juga sempat berkunjung ke Masjid kuno Al-Shahab (para sahabat) yang dibangun tahun 1009 M dan museum Ma Zheng He (Ma Cheng Ho). Dalam semua kunjungan itu, sebuah istilah selalu diucapkan para pejabat yang ditemui penulis tadi adalah kata Gross Domestic Product (GDP) untuk menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk Tiongkok pertahun. Demikian juga sebuah kata selalu terdengar dalam percakapan dengan siapapun, yakni kata reformasi. Kata ini digunakan tidak hanya untuk menunjuk kepada perubahan-perubahan politik yang berlangsung dalam sejarah Tiongkok dalam
masa lima puluh tahun terakhir, melainkan juga kepada perubahan ekonomi dari sistem yang autarki (berdiri sendiri tanpa perdagangan) dan berdasar industri berat ke sistem ekonomi yang lebih terbuka. Dalam tahun 60-an, Mao Zedong mengarahkan Tiongkok ke arah autarki itu, dengan penderitaan manusia dan kekurangan yang diakibatkannya. Setelah pemerintahan Hua Guofeng selama beberapa tahun, muncul lah jago lama Deng Xiaoping yang kemudian merubah arah pandangan, bukan hanya negara saja, melainkan seluruh bangsa yang berjumlah lebih dari satu milyar jiwa itu. Maka Tiongkok segera mengambil haluan baru yang kemudian disebut dengan nama reformasi tersebut. Dalam kata reformasi itu termasuk perubahan mendasar dalam pandangan hidup bangsa Tiongkok. Penanaman modal asing, kemajuan perdagangan dalam dan luar negeri , industri ringan (yang berbiaya murah). Dan apa yang di negeri kita itu disebut pembangunan, semua itu digalakkan dengan istilah umum pragmatisme. Tetapi di dalam negeri, hukum dijalankan dengan sangat ketat dan berbagai bentuk hukuman (termasuk hukuman mati) dilaksanakan dengan konsekwen. Karena korupsi dalam bentuknya yang kita kenal hampir tidak terdapat di Tiongkok. Entahlah dalam bentuk lain yang harus diteliti lagi secara mendalam. Yang jelas, perekonomian bebas segera berjalan dan penanaman modal asing secar besar-besaran terjadi. Jangan heran kalau di kota Quanzhou ada hotel bemama hotel Zaitun yang menunjukkan pemiliknya adalah seseorang dari Timur Tengah. Tetapi semuanya itu dicapai dengan tetap menghormati Mao Zedong yang jenazahnya diletakkan dalam sebuah peti kaca (mausoleum) dalam sebuah bangunan megah di kota Beijing. Puluhan ribu orang-orang, khusunya siswa-siswa sekolah, mengunjungi mausoleum itu dan memberikan penghormatan kepada pendiri Republik Rakyat Tiongkok. Jadi yang lama tidak dicampakan walaupun yang digunakan adalah hal yang baru. Dasar sikap yang sudah biasa dijalankan bangsa Tionghoa itu, sebenamya adalah sebuah sikap yang sudah berjalan ribuan tahun lamanya. Ini tergambar dari adanya tembok besar yang menandai berdirinya bangsa Han yang sekarang berjumlah 80% dari bangsa Tionghoa. Memang orang menyesalkan puluhan ribu jiwa yang menjadi korban dari pembangunan tembok raksasa itu. Tetapi tidak ada buku sejarah manapun di negeri itu yang menyalahkan bangsa Han karena mendirikannya. Adanya tembok besar itu akhimya menjadi pertahanan terhadap serangan bangsa-bangsa lain dari padang pasir dan padang rumput di luamya. Dengan perlindungan tembok besar itu, kemudian dapatlah didirikan kerajaankerajaan besar dalam sejarah bangsa tersebut yang sudah ribuan tahun. Apa yang tidak baik dari masa lampau tidak disebut-sebut lagi, seperti halnya pemerintah yang dipimpin oleh Sun Yat Sen pada permulaan abad yang lalu. Begitu pula pemerintahan partai Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek menjelang dan selama Perang Dunia II, tidak pemah terdengar dalam percakapan siapapun di negeri itu. Jadi masa lampau yang dianggap tidak baik, tidak lagi
disebut-sebut dan seolah-olah dilupakan. Itu tentu saja sejalan dengan sikap umum bangsa Tionghoa: melihat dan mengambil yang baik saja dari masa lampau dan menerima/menjalankan yang baru tanpa melupakan yang lama. Ini adalah sebuah pandangan hidup yang sangat positif, memandang masa depan dengan rasa optimisme dan melupakan masa lampau yang tidak baik. Sikap hidup positif seperti ini sangat diperlukan oleh sebuah bangsa yang mengalami perubahan-perubahan sangat mendasar dalam pandangan hidup kolektifnya, seperti bangsa Tionghoa. Sebenamya ini juga menjadi kebutuhan kita juga, karena kita mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Semula berbagai suku bangsa dan beberapa jenis pemerintahan ada di kawasan nusantara yang berbeda-beda itu. Kemudian kita memasuki era kolonialisme, yang mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa yang pada umumnya terdiri dari 2 jenis ras, ras Melayu di bagian barat Indonesia ras Austro-Melanesia di sebelah timur. Setelah itu pemerintahan kolonial memaksakan sesuatu yang sangat asing bagi kita, dengan menambahkan istilah orang asing timur (vremdee oosterlingen) sebagai sesuatu yang dianggap dapat menjembatani secara ekonomiadministratif-kultural, antara para penjajah kolonial dan penduduk asli (inlanders). Pembagian warga masyarakat dalam tiga golongan ini, memang merupakan strategi para kolonialis di mana-mana. Seperti di India, antara para kolonialis Inggris dengan penduduk asli dikembangkan golongan tengah bemama British India, yang secara kasar dapat diterjemahkan dengan istilah ningrat Inggris yang terdiri dari orang India sendiri, yang dididik menjadi bumper antara para kolonialis dengan penduduk asli. Di Indonesia yang pada waktu itu dinamai Hindia Belanda-, kaum ningrat tidak dijadikan kelompok penengah, karena mereka sering memimpin pemberontakan melawan para kolonialis Belanda itu. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah Pangeran Diponegoro, Sultan Antasari dari Kalimantan-Selatan dan Sultan Badaruddin dari Sumatra Selatan. Dengan demikian, menciptakan entitas bemama Indonesia itu, yang dicapai dalam Kongres Pemuda tahun 1928- adalah sebuah pekembangan baru dalam menciptakan kesadaran berbangsa satu, bemegara satu dan berbahasa satu. Patut diingat bangsa kita dalam mencapai hal-hal baru itu tidak melupakan hal-hal lama. Karena sudah tentu proses lahimya bangsa ini berjalan sangat lama, dan mengambil bentuk bermacam-macam. Di mulai dari cara hidup keraton, cara hidup modem di kota-kota kita, dan cara hidup pesatren di kawasan pedesaan kita. Para pemimpinya lahir dari berbagai kalabnagan, dari kaum elitis; dokter, insinyur dan kaum profesi lain seperti dr. Radjiman Wedyodiningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Soekamo dan Drs. Mochamad Yamin. Perlahan-lahan lahirlah dari para guru agama maupun bukan, seperti para kyai dan Jendral Sudirman, demikian seterusnya hingga lahir pemimpin satu demi satu dalam berbagai angkatan. Proses ini harus diteruskan, dengan menciptakan dan mendorong para pemimpin baru dari berbagai kalangan yang semula berbeda satu sama lain. Warga negara
keturunan yang berasal dari golongan orang-orang Asing Timur, seperti dari kalangan India dan Tionghoa harus diberi peluang untuk maju menjadi pemimpin. Sama seperti halnya dengan mereka yang dianggap sebagai orang-orang Indonesia asli. Hanya dengan cara demikian kita menuntaskan apa yang telah lama dimulai sebagai pembauran masyarakat bangsa kita. Hal ini tidak mudah dilakukan karena kaum minoritas akan menghadapi masalah populasi yang relatif lebih kecil, dalam kehidupan masyarakat. Memang mudah dikatakan, namun sulit dilakukan bukan? Mikrokosmos Seorang Masjumi Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Perawakannya sedang, dengan raut muka halus, kulit putih bersih dan rambut mulai menipis di bagian depan. Berpakaian safari suit yang sesuai dengan kendaraan yang dipakainya, sebuah Toyota Corolla DX, ia tampak sesuai dengan jabatannya selaku manajer sebuah usaha bisnis patungan dengan penanam modal kecil dari salah satu negara Asia (non-Jepang). Penampilan seperti itu diimbangi oleh sikap yang sangat sopan, suara yang tidak terlalu lantang dan cara berbicara yang selalu merendah. Walhasil penampilan gabungan antara keapikan dan kesopann Timur dan kewibawaan eksekutif masa kini. Karenanya tidak mengherankan jika penulis terkejut dengan ucapan perkenalannya: Saya tidak tidak mempunyai hubungan dengan organisasi keagamaan dan politik manapun, karena saya pengusaha. Tetapi saya sebenamya saya simpati kepada Masjumi. Sesuatu yang aneh untuk tahun 1983. Ada sektor moderen dari masyarkat kita masih menggali akar identitasnya pada gerakan yang bubar pada masa pemerintahan Orde Lama. walaupun orang awam di bidang agama, karena tidak dididik dalam pengetahuan agama kebetulan saya punya nasib baik. Apa nasib baik itu, dalam pandangannya? orang tua saya yang selalu berpindah dari satu kota ke kota lain karena mengikuti mutasi perusahaan tempatnya bekerja, selalu mendapat rumah dekat masjid.kalau demikian mengapakah ia tetap awam? Karena saya hanya mengambil fungsi yang paling sederhana. Seperti menjadi penabuh bedug dikala senggang. Namun, dedikasi seperti itulah yang membawanya kepada keyakinan agama dan penghayatan secara total. Agama yang menuntut saya untuk tidak turut hanyut dalam berbagai hal yang menjadi ekses modemisasi. Dan karena itu ia lalu menjadi muslim aktif yang sadar benar masalah-masalah yang dihadapi agama yang dicintainya itu. Dus, bukan orang yang benar-benar awam. Mengapa kita kok terlalu jauh tertinggal dari Malaysia, dalam penerapan Syariat Islam? tanyanya dengan nada separuh menyesali. Diterangkan kepadanya, bahwa kesadaran beragama dapat mengambil bentuk bermacam-macam, tidak selalu
harus
bersifat
syariaat,
ia
tersenyum.
Memang, Pak, yang saya dambakan adalah munculnya teknokrat Muslim yang menguasai jalannya pemerintahan, tetapi berpandangan luas. Tidak terlalu fanatik dan berwawasan sempit, Taruhlah seperti Nurcholis Madjid, Ridwan Saidi, Akbar Tanjung, Abdul Gafur. Bukankah mereka semua orang-orang HMI? tanyanya dengan polos, tidak menyadari betapa luasnya spektrum pandangan (yang mungkin bertolak belakang) antara keempat orang yang disebutnya. Dilihat dari sudut ini, tampak jelas betapa benar pengakuannya, bahwa ia orang Masjumi. Simpati itu tampak ketika menyinggung golongan lain. Orang PSI sebenamya baik-baik, Pak - dan di gambarkannya mereka sebagai teman seperjuangan. Ini dilanjutkannya dengan pertanyaan tentang GMNI. Apa mereka masih sekuler? Sebuah pertanyaan yang dalam konteks ini menjadi tak bisa terjawab sama sekali kecuali dengan menyatakan bahwa mereka pun kini menunjukkan simpati besar kepada Islam. Saya dari kecil bergulat dengan kehidupan kota besar, di Bandung. Tetapi dari titik pangkal masjid. Karena itulah saya kagum kepada para pemimpin Masjumi,demikian dijelaskannya. Namun jangan dikira orang ini hanya memiliki pandangan sesisi tentang masalahmasalah kehidupan. Dan diuraikannya artikel tulisan Nathanel Eliahu, bekas duta besar Israel di Washington, yang memisahkan antara Islam dan Arab. Panjang lebar dikemukakannya keharusan bagi Israel dan Palestina untuk bersedia hidup berdampingan dalam dua negara yang berdampingan. Ethos kerja orang Korea, Taiwan, Jepang, dan Singapura, dipujinya. Saya terpengaruh ucapan seorang pengamat, bahwa budaya Sinik memang mempunyai kekuatan tersendiri. Lihat saja vietnam dan Korea yang mengembangkan ethos kerja keras begitu tangguh.dilanjutkannya dengan bercerita tentang pengusahapengusaha Asia Sinik yang selalu sederhana dan tidak mudah bermewah-mewah, dan lain-lain sifat terpuji. Dikontraskannya hal itu dengan melempemnya bangsa kita sendiri, yang lemah dalam segala hal. Malaysia masih mending, Pak. Masih ada pemerintahan bersih. Clean Goverment yang saya bahagia melihatnya, karena dilakukan oleh orang Muslim patuh. Seperti datuk Mahathir, juga yang lainya.Ketika dikemukakan bahwa pemerintahan bersih di Malaysia adalah warisan Inggris, dan dilakukan juga oleh pejabat-pejabat China dan India yan beragama lain, ia tampak tidak begitu terpengaruh. Pokoknya ada orang Muslim memerintah secara bersih, sudah memuaskan baginya. Bicara kian-kemari selama hampir satu jam, tampaknya jelas pandangan hidupnya sangat kosmopolitan, dalam arti tanggap terhadap kebutuhan dunia masa kini dan mampu menerima kehadiran orang-orang berpandangan lain. Liku-liku dunia usaha, yang menjadi perhatian utamanya, digambarkan secara jelas, menunjukkan kemampuan dirinya untuk menceburkan diri dalam percaturan dan persaingan sengit dengan orang lain.
Kemasjumiannya adalah bagian dari keutuhan dirinya. Dan dengan modal itu ia berkecimpung dalam kehidupan moderen tanpa harus larut dalam suasana yang tidak jelas. Baginya jelas mana yang menjadi batas antara tuntutan dunia yan harus dipenuhinya dan mana yang menjadi wilayah kehidupan beragama yang utuh dan dinamis. Ada semacam proses tolak-angsur, keadaan memberi dan menerima, yang dijalaninya dalam kehidupan pribadinya maupun dalam profesi. Ini temyata dari misi yang dibawanya kepada penulis: minta pertimbangan, ke pesantren mana sebaiknya dikirimkan anaknya yang baru tamat SMP. Saya ingin anak saya sukses dalam hidup. Namun lebih dari itu, saya ingin ia mampu mengembangkan akhlak yang baik dalam hidupnya. Sebuah sikap tuntas yang mengagumkan juga. Bukankah ia sudah tahu kejamnya persaingan hidup di masa kini, apalagi dimasa depan? Mengapa ia tidak lalu menempatkan anaknya Di SMA faforit, seperti umumnya elite politik, budaya dan ekonomi kita saat ini? Tidakkah ia tahu betapa resiko mengirimkan anak ke pesantren, dengan kemungkinan sangat besar sang anak tidak dapat mencapai apa yang diraihnya sendiri saat ini? Mikrokosmosnya temyata masih berorientasi pada keyakinan agama, betapa jauhnya sekalipun hidup telah menghanyutkan kegiatannya. Tetap tekun menjalankan perintah agama sedapat mungkin, tetap yakin bahwa moralitas lebih penting dari sukses material, dan merasa bahwa dengan pola kehidupan seperti itu ia tetap mampu merengkuh modemitas dalam arti penuh. Prototip tulen seorang Masjumi. Dan seninya adalah ketika ia menyatakan kepada lawan bicaranya yang NU akan affiliasinya itu: Maaf, Pak, saya sebenamya orang Masjumi, tetapi merasa perlu konsultasi dengan Bapak. Mualim Syafi'i Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kaum muslimin Betawi memang lebih dekat dengan budaya Arab, dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Bukan hanya habib dan sayidnya, semuanya keturunan Nabi Muhammad yang harus dimuliakan dan disegani, yang menjadi sebab; juga bukan karena di Jakarta sudah ada kampung Pakojanyangpenuh orangArab. Ada yang lebih dalam dari itu. Para ulama Betawi umumnya dididik di Timur Tengah dulu di Mekkah, dan sekarang kebanyakkan di Mesir. Dengan sendirinya budaya Arab bukan sesuatu yang terasa asing. Ane dan ente sudah menjadi kata ganti diri yang umum dipakal, seperti kula dan sampeyan di kalangan Jawa kowek. Orang asli Tegalparang di Mampang Prapatan lebih mudah menyebut nyahi dari pada mengatakan minum teh, diambil dari istilah Arab syahi untuk teh.
Karena itu, tidak mengherankan jika ulama Betawi disebut Mualim. Bukan lantaran
pandai mengemudikan kapal, melainkan karena kerjanya mengajar. Dalam bahasa Arab, arti kata mu 'allim adalah mengajar dan talim berarti pengajaran. Bukan sembarang mengajar, melainkan mengajar ilmu-ilmu agama Islam. Kalau sekadar guru, panggilannya mudarris, sering juga ustadz. Ini adalah istilah yang tidak hanya benar menurut bahasa Arab, tetapi sudah diberi arti khusus sejak dari sononye. Orang Jawa memanggil guru agamanya kiai, orang Minang lebai, di Iran dan Iraq disebut mulla, di Syria, Libanon, dan Mesir dipanggil mu'allim. Mualim Syafi'i yang diacarakan kali ini adalah Kiai Haji Abdullah Syafi'i, yang wafat beberapa hari setelah usainya hari raya ldul Adha lalu. Saya memanggilnya demikian karena memang ia disebut demikian ketika saya masih kecil. Gelar kiai baru datang belakangan, ketika berlangsung proses Jawanisasi yang datang ke Jakarta secara merayap. Sebagai Mualim, Syafi'i telah memberikan segala-galanya kepada profesi pilihannya itu. Mengajar di surau pada mulanya, lalu membuat madrasah dekat Gudang Peluru di Ball Mataram, ketika jalan beraspal belum menjangkau daerah itu. Tidak cukup mengajar di madrasah, dengan tekun dijalaninya tugas memberikan pengajian umum rutin di hampir semua kampung Jakarta Selatan dan Timur. Pengajian berkala yang membawanya ke kampung yang berbeda-beda, sekarang memperoleh predikat mentereng majelis taklim. Juga tidak lupa di tempat sendiri, pengajian diselenggarakan seminggu sekali. Setelah sekian lama, apa yang diselenggarakannya itu temyata menjadi monumen sendiri di ibu kota tercinta ini. Melalui pengajaran dasar-dasar agama kepada orang awam, sang mualim mampu membuat suatu yang sangat berarti di jantung kota metropolitan Jakarta. Apa yang dicapalnya? Menumpulkan dampak negatif dari proses modemisasi. Spiritualitas yang diJajakannya mampu mengatasi kekeringan jiwa manusia, yang terhimpit oleh kehidupan berorientasi serba benda. Solidaritas kuat sesama warga pengajian merupakan penangkal terhadap rasa keterasingan, akibat terurainya ikatan-ikatan sosial lama dalam kehidupan berumah tangga dan bertetangga. Di saat banyak nilai-nilai mulai memudar, ajakannya kepada penghayatan dan pengamalan agama secara tuntas merupakan paduan jelas bagi para pengikut. Tetapi, semua itu bukan menjadi suatu yang dimonopoli mualim Syafi'i belaka. Hal itu juga diperankan oleh para mualim Betawi dan kiai non-Betawi di Jakarta. Kemualim-an Kiai Abdullah Syafi'i baru tampak jelas jika dilihat pola sikapnya terhadap "tantangan dari luar". Tantangan yang secara fundamental berlawanan dengan ajaran agama yang diyakininya. Ketika Ali Sadikin masih menjabat Gubemur DKIJakarta, Mualim Syafi'i adalah pelopor yang dengan gigih menentang kebijaksanaan mencari dana melalui perjudian. Begitu juga kebijaksanaan penggusuran pekuburan, dari Karet ke Tanah Kusir. Semua sanggahannya berdasar pada ajaran agama, sehingga terasa mencekam. Mengapa justru ia bergaul erat dengan Ali Sadikin,walaupun sang gubemur tetap saja mengizinkan perjudian? Apakah sang mualim telah melupakan perjuangan, karena status sosialnya mencapai ketinggian baru? Apakah ia sudah terbuai
dengan
penghormatan
sang
gubemur
kepadanya?
Temyata tidak demikian. Sebabnya sederhana saja ia tahu batas peranan yang harus dimainkannya: sekedar mengajarkan pendirian agama. Bukan menentang pemerintah. Juga bukan menyusun kekuatan (mact-vorming) untuk memaksakan pendirian. Kalau pendirian agama sudah dirasa cukup disampaikan, sudah cukup tugas dilaksanakan. Tak perlu rusak pergaulan karenanya, dan tak harus bersitegang leher sebagai akibat perbedaan pandangan. Sikap inilah yang memancarkan kebesaran Mualim Syafi'i karena dari kiai kampung yang kemudian menjadi ulama besar ini muncul keteladanan cemerlang akan perlunnya kesadaran peranan sendiri dalam kehidupan. Memang untuk jangka pendek ia tidak dapat memberantas perjudian. Namun dalam jangka panjang ia memelihara sesuatu yang sangat berharga:budaya politik yang mantap karena ia menggunakan hak untuk berbicara dalam ukuran yang tepat.Bukankah ini hakekat demokrasi? Lebih penting lagi siapakah yang tadinya menduga bahwa sikap demokratik itu muncul justru dari garis batas yang diletakkan agama sendiri,yaitu dalam tugas mengajar selaku mualim?
Muka Baru Pandangan Lama Oleh: Abdurrahman Wahid Penulis diminta memberikan ceramah budaya di Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Rabu (29/6) malam lalu. Ceramah yang berisikan pencarian landasan kultural bagi demokrasi di negeri kita itu, temyata ditanggapi oleh pandangan pesimis baik oleh Saut Situmorang yang juga sebagai penceramah maupun para penanya. Umumnya mereka mengemukakan pandangan bemada pesimis tentang prospek demokrasi di negeri kita dalam waktu dekat ini, walaupun mereka hampir seluruhnya berbicara tentang bidang pendidikan, sebagai acuan terpenting dalam proses tersebut, yang pada umumnya pendapat yang muncul adalah tentang kegagalan dunia pendidikan kita untuk menciptakan demokrat-demokrat di masa depan. Lucunya, pandangan ini bertolak belakang dengan para penyair yang mendendangkan cinta dan lain-lain, yang menunjukkan keakraban dengan kehidupan penuh optimisme. Apalagi kenyataan itu juga dibarengi oleh kekenesan pribadi, baik dari hadirin, maupun pembawa acara: si ini cantik, si itu rupawan. Nah, nuansa ucapan hadirin yang menunjukkan besamya kadar pesimisme itu temyata pada saat yang sama diimbangi oleh optimisme di atas. Apalagi para peserta acara ceramah itu hampir seluruhnya dari kalangan/generasi panitia penyelenggara acara tersebut, kecuali Lili Munir dari kalangan generasi muda. Mereka rela duduk di atas koran dalam acara yang sangat sederhana. Dengan kata lain keprihatinan mereka akan masa
depan kehidupan bangsa, terasa sangat mengharukan. Kalau demikian, mengapa mereka begitu pesismis akan masa depan demokrasi di negeri kita? Jawabannya terletak pada kenyataan, bahwa demokrasi justru bemiat menghancurkan status quo/situasi yang ada tanpa melalui kekerasan. Karena itulah perubahan sosial sekecil apapun harus terjadi, sebagai akibat dari langkah pemberian suara dalam pemilu. Justru disinilah letak kekuatan proses demokratisasi. Memang, selalu terasa ada pertanyaan demi pertanyaan yang tidak menemukan jawaban dengan pasti, karena zig-zagnya perkembangan keadaan dan tajamnya perubahan-perubahan yang terjadi. Namun intinya, kejadian perubahan demi perubahan kebijakan itu tidak dilakukan melalui kekerasan dan ini merupakan akumulasi kehendak bersama. Seperti penggunaan bahasa nasional dalam kehidupan kita sehari-hari. Keputusan bersama ini, memberikan kekuatan kepada kita untuk merekatkan salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa. Pemberian wewenang kepada pemerintah, dalam hal ini kepada pihak legislatif bersama-sama dengan eksekutif, dilakukan dengan legitimasi yang diberikan oleh mayoritas bangsa. Namun ini tidak berarti sesuatu yang berjalan tanpa adaa transparansi di hadapan publik. Ketika Jenderal Douglas Mc Arthur mengeluarkan niat untuk melakukan pemboman atas kekuatan-kekuatan bersenjata konvensional di sungai Yalu yang mengalir dari RRT ke Korea Utara, maka segera ia disanggah oleh Presiden AS Harry S Truman, langsung dari negerinya untuk menyampaikan keputusan itu. Dalam pergolakan politik ketika itu, jelas bahwa wewenang menggunakan sejata pemusnah massal atau tidak dalam sebuah peperangan terletak pada diri Presiden yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, sehingga keputusan itu sendiri merupakan sebuah kejadian politik yang transparan dan diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Apa yang terjadi pada Korea lebih dari setengah abad yang lalu itu, akhimya menunjukkan kepada kita bahwa rakyat pemilih sebodoh apapun, akan memilih para penentu kebijakan yang tidak emosional. Sedangkan Jenderal Douglas Mc Arthur yang militer itu, justru ingin menggunakan jalan pintas dengan menggunakan senjata nuklir, yang akan berakibat kematian ratusan ribu orang melebihi korban-korban yang berjatuhan melalui penggunaan senjata konvensional. Artinya nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dihadapan Truman yang juga sangat berarti bagi rakyat pemilih yang memberikan suara kepadanya. Bukankah terjadi kebalikan dari keputusan Presiden AS Franklin D. Roosevelt sebelumnya yang menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima secara jauh dari pertimbangan emosional? Transparansi itu menjadi sesuatu yang begitu penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah yang dipilih secara demokratis. Terdapat pertanggung jawaban moral kepada rakyat banyak, dalam sebuah pemerintahan demokratis. Namun hal itu tidak terdapat dalam pemerintahan kita yang tidak dipilih melalui sebuah pemilu hingga saat ini. Karena itu tidak dapat ditentukan secara hukum siapa yang bersalah dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam begitu banyak hal, yang menyangkut kehidupan kita bersama? Pak Harto-kah atau
pejabat-pejabat lain yang bersalah dalam hal ini? Hal yang sama tentu dipakai sebagai argumentasi oleh pengacara Saddam Hussein dan oleh pihak pemerintahan peralihan. Dalam kasus ini terjadi adu argumentasi antara dua pihak, yang sama-sama tidak dipilih oleh rakyat. Dari kasus di Iraq dan di negeri kita itu menjadi jelas, bahwa ada dialog yang tidak seimbang antara pendekatan hukum dan pendekatan moral. Dengan sendirinya, pendekatan secara moral, dengan bantuan dari luar, baik dalam bentuk doktrin dan sikap dunia luas yang bersifat universal, lalu digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi salah satu bangsa. Ini artinya sama dengan tiadanya kemampuan dari bangsa yang bersangkutan untuk memecahkan masalahnya sendiri. Siapapun juga tidak akan dapat menerima pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah sebuah bangsa diambil berdasarkan tekanan-tekanan dari luar. Di sini kita sampai kepada esensi demokrasi: pengambilan keputusan secara transparan oleh bangsa yang bersangkutan. Sebuah pokok dari sebuah pemerintahan demokratis lalu menjadi jelas bagi kita. Kedaulatan politik sebuah bangsa, tentu saja akan tampak dengan sendirinya, di tangan rakyat pemilih. Kalau Von Clausewitz menyatakan, perang adalah terlalu penting untuk diputusakan oleh hanya para Jenderal saja, maka kitapun dapat menyatakan keputusan politik adalah terlalu penting untuk hanya diputuskan oleh para pemimpin politik belaka. Melalui pemilu, rakyat pemilih akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin politik sebuah bangsa, dan dengan demikian secara tidak langsung mengambil keputusan atas hal-hal yang menentukan kehidupan bangsa itu. Sudah tentu ini akan berlangsung secara transparan, jika diawal atau ditengah-tengah proses ia berlangsung tanpa kekerasan. Nah, disinilah juga terdapat esensi sebuah proses demokratis yang dimaksudkan, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan sebuah bangsa yang dilakukan tanpa kekerasan. Ini artinya juga hak bagi muka-muka baru untuk mengambil keputusan yang menentukan bagi seluruh rakyat. Hak seperti itu menjamin agar perubahan-perubahan keputusan yang diambil, berlangsung tanpa kekerasan. Kita memutuskan bahwa wilayah Nusantara adalah lingkup kenegaraan kita dan secara teoritik keputusan itu menunjuk kepada kedaulatan wilayah kita sebagai negara. Keputusan BJ. Habibie untuk melakukan plebisit di Timor-Timur, yang mengakibatkan hilangnya propinsi tersebut dari negara kita, diambil tanpa keputusan kita bersama dan ini merupakan luka politik yang mungkin tidak akan hilang dari kehidupan kita bersama. Hal itu tampaknya mudah dilakukan, namun sulit dilaksanakan, bukan? NU dan Kekayaan Budayanya Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Pada suatu hari, penulis diundang ke sebuah tempat yang didirikan dengan maksud untuk menjadi tempat bagi kegiatan khalawah (mengasingkan diri, atau nyepi dari dunia ramai). Ritus khalwah itu berlangsung selama 40 hari dan
dilakukan setahun sekali saja, selebihnya tempat itu digunakan untuk pengajian yang melayani seminggu sekali. Penulis lalu jadi ingat, ia dahulu melakukan hal yang sama di pemakaman seorang syekh di desa Candi Mulyo. Ada semacam kepercayaan, bahwa syekh tersebut dapat memberikan barokah (berkat) bagi seseorang yang menuntut ilmu-ilmu keagamaan. Di tempat itu, penulis dan beberapa orang teman menyelesaikan bacaan kitab suci Al-Quran dari waktu Maghrib malam Jumat hingga Ashar hari Jumatnya, ritus yang dinamai khataman. Ritus itu diadakan tiap hari Kamis malam Jumat Pon itu, sehingga otomatis setiap 5 hari sekali penulis dan kawan-kawan berjalan kaki 4 km ke tanah pemakaman itu. Ini adalah contoh dari kebiasaan yang dilakukan oleh para pelajar di pesantren, yaitu mereka yang dipanggil santri, tidak jelas dari mana asalusulnya. Namun kita baca dalam literatur-literatur keagamaan Islam dari TimurTengah, banyak perjalanan dilakukan para guru/syekh untuk memperoleh tambahan pengetahuan agama dari guru/syekh lain yang kemudian dianggap guru/syekh mereka. Umpamanya Imam Syafii belajar dengan cara demikian. Dapat dilihat dari karya utamanya, al-Umm. Dalam karya itu kita dapati kumpulan karya beliau, seperti kitab al Raddi ala al-Awjai. Seluruh karya yang besar itu berisikan penolakan (alRaddi) atas guru-guru sebelumnya itu. Budaya santri keliling (al-thaulab almutajawil) itu, adalah bagian dari budaya menuntut ilmu dan berkah (Thalabul alIlmi), yang sekarang masih dapat dijumpai sisa-sisanya di negeri kita. Namun tradisi santri tarekat, seperti yang disebutkan di atas belum pemah penulis jumpai di luar tanah air kita. Itupun sekarang mengalami perubahan, seorang santri akan belajar di tingkat pertengahan (Tsanawih) di satu pesantren kemudian pindah belajar di tingkat lanjutan (Aliyah) di pesantren lain. Nah, apakah akibat dari perubahan institusional seperti itu kepada proses pencapaian ilmu pengetahuan agama Islam tradisional? Belum dapat diketahui pada saat ini. Demikian pula kegunaan literatur baru (al-Kitab al-Hadist) dan literature lama (AlKitab Al-Mutabarah) sekaligus, tentu menghasilkan pola pengetahuan agama Islam yang berbeda pula. Seperti contoh karya al-Jabiri mengenai sumber-sumber ilmiah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, tentu membawa pengaruhnya sendiri dalam studi yang dilakukan para santri baru sekarang ini. Di samping sumber atau teks tertulis (al-adillah al-naqliya) dan sumber rasional (aladillah al-Aqliyyah) beliau menambahkan jenis sumber ketiga yaitu dalil intuitifnya (al-Addilah al-dzauiqiyah). Banyak sekali ragam tradisi yang dilakukan oleh warga NU, termasuk peringatan kematian (khaul) yang dilakukan setiap tahun sekali dalam upacara-upacara khaul itu, selain membacakan tahlil dan doa untuk yang diperingati itu, juga diberikan ceramah umum (tabligh) oleh seseorang yang sangaja diundang untuk keperluan itu. Penulis sendiri seringkali diundang untuk memberikan ceramah seperti itu beberapa waktu sekali dalam setahun. Ini merupakan jenis pemeliharaan hubungan antara ulama dengan orang awam, di samping pertemuan para ulama itu sendiri. Karenanya hal itu merupakan sebuah forum penting dalam
pembentukan pendapat bersama di lingkungan kaum muslimin/umat Islam. Forum seperti ini sering kali menjadi ajang menentukan pandangan yang dengan mudah oleh orang yang tidak mengerti duduk perkaranya dianggap sebagai curi start dalam pemilihan umum. Nah, kesalahan pandangan ini haruslah dikoreksi. Memang cukup banyak penceramah/mubaligh yang melakukan curi start melalui forum-forum tersebut, tetapi tidak selayaknya pengajian dalam berbagai forum dianggap memiliki motif seperti itu. Sama halnya dengan banyak warga Polri minta uang dari kendaraankendaraan lewat, tetapi tentu saja sangat gegabah untuk menganggap setiap pemeriksaan kendaraan sebagai cara meminta uang. Haruslah diingat arah semula dari sebuah hal yang dilakukan di mana-mana, barulah dapat kita simpulkan pendapat kita dengan tepat. Kalau tidak, kita akan menjadi lebih negatif dari keadaan yang menginginkan penyimpangan seperti itu terjadi. ***** Karenanya kita harus sangat berhati-hati dalam menentukan sikap atas hal-hal seperti itu, yang dapat mengakibatkan keretakan serius dalam hubungan antar golongan dalam kehidupan sebagai bangsa. Apalagi kalau diingat, bahwa NU adalah sebuah kelompok keagamaan Islam tradisional yang memiliki kekuatan tersendiri. Prof. DR. Amien Rais menyatakan warga NU ada 36 juta orang, sedangkan Muhammadiyah 28 juta orang. Pihak intel Malaysia, beberapa tahun yang lalu melaporkan warga NU berjumlah 60 juta orang, sedangkan Muhammadiyah berjumlah 15 juta orang. Intel militer kita sendiri (BAIS) memperkirakan para warga NU berjumlah sekitar 90 juta orang, sedangkan jumlah Muhammadiyah 5 juta orang. Karena itu, kita tidak tahu tepatnya beberapa orang jumlah warga masing-masing. Tetapi yang jelas bahwa para pengikut NU yang berjumlah jutaan orang itu memiliki tradisi masing-masing, termasuk pengajian ibu-ibu, yang sering dianggap sebagai curi start kampanye. Dalam proses pemilihan umum yang sedang kita hadapi, kita harus berhati-hati dalam mengelola kehidupan kolektif bangsa. Hal yang dikemukakan di atas sama saja nilainya dengan kebiasaan orang untuk menghargai seorang Sultan orang atau Raja tradisional di daerah. Kita dapat merebut kekuasaan pemerintahan mereka, tetapi kita harus dapat menghormati kedudukan non-formal yang mereka miliki sekarang ini. Dalam beberapa hal, kita bahkan harus memberikan subsidi kemenangan kepada mereka. Ini untuk mencegah agar kohesi kehidupan di sebuah daerah dapat terus berlangsung tanpa gangguan berarti. Bahkan sekarang ada fenomena berkembang secara luas. Banyak para pemilik kendaraan umum (bus besar dan kecil) menyewakan kendaraan mereka kepada para peziarah ke kuburan-kuburan kramat seperti makam para wali sembilan di pulau Jawa. Jadi apapun tidakan yang diambil tentu saja sangat berpengaruh atas perekonomian kita sendiri. Sama saja dengan perjalanan Umrah ke tanah suci Mekkah. Bila hal itu dilarang, hasilnya akan menimbulkan protes besar dari kalangan kaum muslimin sedunia. Belum lagi akibatnya terhadap begitu banyak
maskapai penerbangan, usaha perhotelan di tanah Arab sendiri dan sebagainya. Karenanya mengubah sesuatu kedengarannya mudah dilakukan, tetapi sulit dilaksanakan bukan? NU Dan LSM Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Seminggu yang lalu, penulis didatangi oleh Tony Pangcu, seorang aktifis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dari Yogyakarta. Ia bertanya pada penulis, adakah rencana untuk menengok tokoh LSM yang waktu itu sedang dirawat di rumah sakit Bethesda, Yogyakarta? Penulis menjawab karena tekanan pekerjaan yang sudah direncanakan sebelumnya, maka penulis bermaksud menengok Mansour Faqih hari Sabtu. Bersama istri dan putri kedua, Zannuba Yenni Arifah Chafsoh Wahid, penulis mengunjungi Mansour Faqih, yang sudah tidak sadar enam hari lamanya. Penulis turut mendoakan si sakit dan menemui keluarga Mansour Faqih. Didapatinya, istri Mansour Faqih dan anaknya sangat tabah menghadapi cobaan itu, memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Sore harinya, penulis kembali ke Jakarta, dan keesokan malamnya (minggu malam senin), penulis mendapat interlokal dari Yogyakarta, bahwa Mansour Faqih meninggal dunia. Tokoh itu, meninggal dunia dalam keadaan tidak sadar, dengan ditunggui banyak aktifis LSM yang sejak awal, berada di ruang tunggu rumah sakit tersebut. Penulis pada awal-awal tahun delapan puluhan, telah menyaksikan dedikasi Mansour Faqih yang sangat tinggi terhadap profesinya, melalui sebuah LSM yang didirikan untuk mendampingi proyek pengembangan masyarakat melalui pondok pesantren, di lingkungan LP3ES (Lembaga Penerangan, Pendidikan, Pengembangan Ekonomi dan Sosial) di Jakarta. Penulis sangat terkesan oleh kepribadiannya yang berisikan konsistensi sikap terhadap pilihannya dan dedikasi yang tinggi kepada profesinya. Kemudian penulis dengar bahwa ia mendapatkan bea siswa dan menyelesaikan studi di sebuah perguruan tinggi di Amerika Serikat, dan selanjutnya penulis juga dengar bahwa ia mengajar di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Terakhir, penulis mendengar ia menjadi anggota Komnas HAM (Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia). Yang menarik perhatian, bahwa tokoh NU dan LSM ini, seperti banyak aktifis lainnya, tidak bergaul erat dengan pimpinan formal NU. Tidak hanya di Yogyakarta, Jakarta, apalagi di daerah lain. Ini menimbulkan tanda tanya besar ada apakah gerangan antara NU dan LSM? Mengapakah antara keduanya tidak tumbuh kerjasama yang erat? Benarkah sikap yang demikian itu, yang dalam jangka panjang akan merugikan kedua-duanya? Kalau begitu, adakah cara yang dapat ditempuh, untuk menjembatani kelangkaan hubungan antara keduanya itu? Bagaimanapun juga, dalam jangka panjang NU tidak dapat berpangku tangan terhadap masalah-masalah yang ditangani LSM, karena persoalannya menyangkut masa depan bangsa. Kedua-duanya ingin melihat Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur di masa depan. Kecenderungan mengembangkan kerjasama erat antara NU dan LSM yang menjadi dambaan penulis sejak tahun-tahun tujuh
puluhan, mau tidak mau lalu membuat penulis memperhatikan kenyataan itu dan mengajukan pertanyaan di atas. Ini karena penulis merasa sayang kepada keduaduanya. ***** Beberapa hari sebelum penulis mendiktekan artikel ini, ia pergi ke Jember, menghadiri sebuah rapat umum yang penuh sesak dengan para petani tembakau dari sebuah kecamatan. Rapat umum petani itu diorganisir oleh sebuah LSM yang berisikan anak-anak muda NU. Bahwa mereka berhasil mengumpulkan sekian banyak petani itu, menunjukkan kemampuan mengorganisir masyarakat. Sangat banyak keluhan para petani dan begitu beraneka-ragam usulan-usulan yang mereka ajukan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang mereka hadapi, menunjukkan kepada kita betapa besar masalah-masalah yang mereka hadapi dan bagaimana tinggi tingkat pengertian para aktifis LSM tersebut. Kemudian, penulis menemui sejumlah fungsionaris NU di tingkat cabang Jember. Dalam pertemuan itu, penulis menyatakan bahwa NU memang mengalami gangguan dalam dirinya, sesuatu yang tidak pada tempatnya memang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Kalau tidak ditangani dengan serius, ini dapat berakibat fatal bagi masa depan NU sendiri. Persoalannya terletak pada masa depan bangsa. Di masa lampau, para ulama NU meletakan titik berat perhatian mereka kepada masalah-masalah bangsa, setidaktidaknya secara kultural. Hal ini terbukti dengan sikap non-kooperatif (tidak mau bekerjasama) dengan pemerintah kolonial, demi mempertahankan identitas intem NU dan solidaritas dengan perjuangan bangsa pada umumnya. Lahirlah dari sikap ini, sistem pendidikan sekolah agama yang berinduk pada pesantren-pesantren. Memang pada mulanya sangat berbau agama, sehingga kurikulum-pun hampirhampir tidak menyentuh kehidupan nyata. Namun, dalam hal-hal pokok, seperti hubungan antara agama dan masyarakat/Negara perbaikan kwalitas hidup umat dan sebagainya, banyak sumbangan sikap dan pemikiran yang patut dihargai. Sayangnya, LSM seperti kita kita kenal sekarang belum lahir pada waktu itu, sehingga pihak NU-pun terpaksa meraba-raba apa yang harus dilakukan. Dari sinilah kita pahami upaya seperti yang dilakukan oleh alm. KH. Mahfud Siddiq, yang semasa hidupnya menjadi seorang ketua PBNU. Ajakannya untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebajikan umat (mabadi khaira ummah) sebenamya terkait dengan berbagai kegiatan untuk memperkuat posisi ekonomi-finansial warga NU sendiri sebagai anggota gerakan Islam, patut dipelajari dengan mendalam pada saat ini. Sayangnya, seruan itu dikeluarkan menjelang kedatangan tentara Jepang di tanah air kita, sehingga seruan itu terhenti di tengah jalan sebelum berhasil diwujudkan. Keputusan muktamar NU di Palembang tahun 1952 sekaligus menjadikan NU sebuah partai politik. Sebagai respon terhadap pemaksaan kehendak oleh Moh. Natsir dan kawan-kawan dari partai Islam Masyumi akhimya membuat NU tenggelam dalam kancah politik. Akibatnya, secara tidak terasa orientasi NU dipusatkan pada bidang politik saja. Kecenderungan ini, lebih diperkuat dengan sikap pemerintahan Orde Baru yang
sangat teknokratik. Mereka yang tidak masuk dalam linkungan tersebut, tidak memperoleh kesempatan untuk bergerak sama sekali. Verpolitisasi NU tambah menjadi-jadi, dan sebagai akibatnya hanya mereka yang berorientasi politik sajalah yang dapat menguasai NU di bidang sehari-hari. Para ulama/kyai melanjutkan upaya mereka meneruskan kegiatan pengajian dan membina masyarakat. Dalam keadaan seperti itulah lahir anak-anak muda NU yang kemudian aktif dalam berbagai kegiatan LSM, termasuk penulis sendiri. Agenda mereka mengenai perubahan struktural masyarakat untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran, tidak dimengerti oleh para pemimpin formal NU yang tidak memahami apa yang tidak dimaui para anak muda itu. Apalagi sebagian dari mereka telah disuapi Orba dengan uang dan pangkat, sehingga semakin tidak melihat perlunya perjuangan LSM. Mereka ini dihinggapi apa yang oleh V.I. Lenin sebagai penyakit kiri kekanak-kanakan kaum revolusioner, yang intinya adalah anggapan jika mereka tidak memimpin secara resmi perjuangan pembebasan rakyat, maka revolusi telah gagal. ***** Kalau kesenjangan seperti itu diteruskan, dengan memberikan tempat hanya kepada orang yang berorientasi politik saja, maka masa depan NU akan sangat suram. Inilah yang membedakan NU dari PKB: NU jangan berpolitik, karena segala sesuatunya di bidang itu sudah digarap oleh PKB. Kenyataan ini yang seharusnya kita sadari bersama, temyata masih belum disadari juga oleh banyak pemimpin formal NU, hingga saat ini. Mereka masih ribut dengan agenda politik seperti menjadi caleg (calon legislatif) dan sebagainya. Bahkan ada kecenderungan, terjadi persaingan antara sebagian fungsionaris NU dan fungsionaris PKB. Kalau perlu, sampai di tingkat pusat, seperti terlihat pada sejumlah pemyataan PBNU akhir-akhir ini. Bahkan, sikap-sikap berbau politik itu, terlihat juga pada mereka yang tidak berhasil mencapai maksud untuk memperoleh jabatan-jabatan politis seperti caleg dan kepala daerah, untuk memboikot PKB dalam soal-soal tersebut. Seolah-olah menjadi fungsionaris PKB, sama dengan mewujudkan tujuan-tujuan NU, ini tentu tidak benar. Cobalah dipahami seperti apa yang secara tersirat dalam ungkapan Rais am PBNU, bahwa (1) NU tidak mempersoalkan keputusankeputusan politik DPP PKB; (2) bahwa masalah organisatoris PKB adalah urusan intem PKB sendiri; dan (3) bahwa PBNU tidak akan mencalonkan siapapun untuk jabatan apapun di negeri ini. Temyata, penyelesaian kemelut NU dan PKB sebenamya mudah dicari, kalau orang berhati ikhlas dan bersikap jujur. Dalam hal ini, NU seharusnya mementingkan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Hal itulah yang sekarang menjadi agenda LSM, sehingga dorongan bagi tokoh-tokoh LSM untuk berkiprah di lingkungan NU, dibuat semakin besar. Jika di satu pihak para fungsionaris NU semakin banyak yang meninggalkan bidang politik dan bersama-sama dengan para teman aktifis LSM mewujudkan tatanan masyarakat yang baru itu, akan semakin lebih baik keadaan NU sendiri. Sedangkan PKB justru harus diarahkan NU untuk merumuskan kebijakan pemerintahan (terutama perundang-undangan) yang mengarah kepada susunan dan perilaku yang menunjang terwujudnya khaira ummah. Dengan sendirinya penguasaan NU atas
perjuangan kebangsaan kita di masa depan akan menjadi semakin besar. Ini mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan? NU: Konservatifisme dan Tradisionalisme Oleh: Abdurrahman
Wahid
Dalam literatur yang banyak ditulis orang, NU disebutkan sebagai organisasi Islam kolot/konservatif. Sebutan ini melekat dengan mudah pada organisasi tersebut, antara lain karena hal-hal berikut: para pengikutnya kebanyakan memang terdiri dari orang awam yang masih mengikuti para ulama, tanpa mempertanyakan keabsahan apa yang mereka buat. Ini benar-benar mencerminkan sikap konservatif dalam hidup. Di samping itu, NU sendiri menyatakan diri terikat kepada salah satu empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali). Tiap macam gerakan dalam lingkungannya, baik itu tarekat maupun lain-lainnya, harus ada pengakuan (imprimatur) dari kalangan Ulama, baru kemudia ia diakui (muktabarah). Pengambilan keputusan dalam setiap musyawarah, selalu menggunakan rujukan karya-karya Ulama masa dahulu. Karya ulama mutakhir, seperti tafsir-tafsir al-Maraghy, tidak dapat diterima oleh para peserta musyawarah tersebut. Demikian pula, pakaian yang dikenakan mereka, kesenangan mereka membaca shalawat dan maddah (sajak-sajak puja bagi Nabi), disertai kenduri dalam bermacam-macam ritus tradisional (seperti manakiban), menunjuk kepada apa yang sering ditulis orang sebagai ciri-ciri konservatifisme. Para Ulama seperti penduduk Tiongkok, yang bagi kepentingan tanah air menerima begitu saja pengorbanan ratusan ribu jiwa, lagi-lagi mereferensi NU sebagai konservatif. Jadi seperti demikiankah NU, yang dinilai sebagai gerakan Islam kolot? Bagi kaum Ulama yang dianggap demikian, hal itu tidak menjadi persoalan. Padahal dalam NU tidak sepenuhnya konservatifisme dijalankan. Banyak sekali contoh yang dapat dikemukakan untuk mencari identitas NU yang sebenamya. Kalau ditanyakan pada seorang pemerhati studi ke-Islaman, tentu identitas itu dilihat pada kuatnya NU berpegang pada kurikulum ilmu-ilmu keagamaan Islam, seperti yang dirumuskan Imam al-Sayuthi, kira-kira 500 tahun yang lalu, dalam Itmam al-dirayah. Keempat belas macam bidang studi yang diliputnya, merupakan kurikulum dasar yang diajarkan oleh pesantren-pesantren kita. Walaupun bidang-bidang itu juga diajarkan di UIN (Universitas Islam Negeri), tapi cara penanganannya sangatlah berbeda. Dalam pesantren, teks-teks(al-quthub almuqarrarah) dipakai sebagai referensi yang sudah benar, karena itu tidak diperdebatkan lagi tentang isinya. Sebagai sesuatu yang dianggap benar, teks-teks itu diterima tanpa ada perbedaan paham sama sekali. Kalau toh ada sengketa, maka yang terjadi hanyalah perbedaan paham diantara para penulis (muallif) nya. Kebenaran pendapat yang saling berbeda itu, tidaklah diragukan lagi. Ini tentu berbeda dari kajian Islam di Perguruan Tinggi yang di dalamnya orang memperdebatkan kebenaran sebuah pendapat dan keabsahan sebuah pandangan. Dengan demikian, antara seorang santri dan seorang mahasiswa akan senantiasa ada perbedaan pandangan dan perlakuan atas pendapat-pendapat (aqwal) yang
ada dalam teks-teks/ kitab-kitab yang digunakannya antara kedua lembaga pendidikan Islam itu. Bagaimanapun juga, keduanya menggunakan karya-karya masa lampau sebagai referensi, walaupun berbeda cara penggunaannya. ***** Dalam kenyataan, pandangan yang menganggap NU sebagai lingkungan konservatif sebenamya tidak dapat dipertahankan lagi. Proses sejarah memaksakan ketentuan-ketentuannya sendiri. Ini tentu dapat dipahami, karena memang siapapun yang mencoba mengerti permasalahannya, akan sampai pada kesimpulan bahwa NU adalah lingkungan yang tradisional yang dibungkus dalam tutup konservatifisme. Tentu saja diperlukan kesanggupan pengamat gerakangerakan Islam di negeri kita untuk memandang masalah ini dengan jemih. Untuk itu sejumlah dasar pengambilan pendapat haruslah dikuasai terlebih dahulu. Umpama saja, ayat kitab suci Al-Quran yang berbunyi: Barang siapa membuat keputusan hukum tanpa dasar apa yang diturunkan Allah, ia adalah seorang kafir, munafiq, zalim (man lam yahkum bima anzala-Allah fa ulaaika hum al-kafirun, munafiqun al-dhalimun). Dengan demikian, mereka dalam memutuskan fiqh (Hukum Islam), tetap harus bersumber pada teks-teks resmi (adillah naqliyyah) yang diambilkan dari al-Quran dan al-Hadits. Di samping itu, untuk membuat keputusan Hukum Agama harus berdasarkan kaidah-kaidah fiqh (al-qawaid al-fiqhiyyah, teori Hukum Islam Ushul fiqh) dan lain-lain peralatan yang digunakan. Contoh sangat baik dapat ditunjukkan dalam hal ini, adalah Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945. Dalam resolusi itu dikemukakan bahwa kewajiban mempertahankan Republik Indonesia (RI) (yang notabene bukan negara Islam) adalah sebuah kewajiban agama (Jihad) yang berlaku wajib bagi semua warga negara RI. Ini menunjukkan watak tradisional NU yang tidak tergoyahkan oleh sekian banyak pendirian dari berbagai kalangan. Ini kemudian dijadikan sebagai faktor pendorong sekian banyak sikap-sikap yang diambil rakyat untuk melawan tentara sekutu. Semangat seperti itulah yang memperkuat pandangan NU sebagai organisasi masyarakat. Sebuah kejadian lain jelas menunjuk pada tradisionalisme NU itu. Dalam Muktamar Banjarmasin tahun 1935, NU memutuskan hukum fiqh yang mempertanyakan wajibkah kaum muslimin negeri kita untuk mempertahankan secara fisik kawasan Hindia Belanda yang diperintah oleh para penjajah yang yang tidak beragama Islam? Muktamar pun menjawab: bahwa ada dua hal yang mewajibkan kaum muslimin mempertahankan Indonesia (dahulu Hindia Belanda). Pertama, menurut buku teks Bughyah al-mustarsyidin kawasan yang dahulu ditempati/ ditinggali kerajaan Islam di masa lampau, haruslah dipertahankan sebagai tanah muslim. Walaupun kawasan bukan Negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya kaum muslimin, maka mempertahankannya adalah sebuah keharusan. Kedua, di negeri ini kaum muslim melaksanakan ajaran agama, tanpa ada pengekangan dari negara sama sekali. Karena itu, muktamar NU tersebut memutuskan untuk mempertahankan kawasan Hindia Belanda dan itu adalah merupakan kewajiban agama.
***** Karena pelaksanaan ajaran-ajaran agama tidak ada hubungannya dengan wujud negara, maka entitas yang bemama Negara Islam menjadi tidak wajib. Ini bukan pendapat seorang atau dua orang Ulama masa kini saja, melainkan sudah ada semenjak dahulu. Disertasi Dr. Nurcholish Madjid mengenai tokoh Ibn Taimiyya, menunjukkan dengan jelas bahwa umat Islam berhak memiliki ulama/pimpinan agama yang berbilang. Tegasnya, tidak diperlukan adanya lembaga yang bemama agama, dengan seorang diantara mereka menjadi pimpinan Negara. Inilah sebabnya mengapa sebenamya Islam tidak memiliki kepemimpinan yang tunggal. Umat Islam bebas menganut damengikuti pimpinan mana saja dalam masyarakat di mana. Dalam keadaan demikian, tentu saja harus ada pimpinan negara yang diikuti kepemimpinannya oleh semua warga negara. Selama pimpinan negara tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama atau suatu hal yang disetujui oleh lembaga-lembaga keagamaan, maka keputusan demi keputusan yang diambilnya mengikat semua warga negara yang dipimpinnnya. Di sinilah pentingnya arti seorang Mufti yang ditunjuk oleh pimpinan Negara. Mufti itulah yang harus menetapkan waktu jatuhnya Puasa, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Dalam mana keadaan suatu negara tidak memiliki seorang Mufti, maka fungsinya digantikan oleh menteri agama, seperti keadaan negeri kita sekarang. Memang dahulu di waktu kita masih belum memiliki pemerintahan sendiri, tepat sekali untuk mendengar penetapan-penetapan oleh organisasi agama mengenai jatuhnya permulaan Puasa, permulaan Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi sekarang kita sudah mempunyai Menteri Agama yang melakukan fungsi tersebut. Ini berarti, sebenamya secara teoritis tidak diperlukan lagi pendapat organisasiorganisasi keagamaan itu. Namun dalam kenyataan hal itu masih terjadi, dan masing-masing pihak merasa pendiriannya yang benar dan harus dipakai. Sampai kapan hal itu terus terjadi, penulis juga tidak tahu. Itu adalah proses politik yang memerlukan pendidikan politik untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam hal ini, penulis teringat kisah tentang bagaimana kepentingan agama harus diletakkan pada tataran kepentingan nasional. Pada waktu ayah penulis, KH. A. Wahid Hasjim ditanya Laksamana Maeda dari pemerintahan pendudukan Jepang, siapa yang sebaiknya mewakili bangsa Indonesia untuk merundingkan kemerdekaan dengan pihak Jepang, beliau menyatakan akan berkonsultasi dengan sang ayah, KH. M. Hasjim Asjari. Hasilnya: Soekano, dan itulah yang terjadi dalam sejarah. Di sini bukti bahwa pengasuh Pondok Pesantren di Tebu Ireng, Jombang, tersebut telah meleburkepentingan agama dalam kepentingan nasional. Padahal beliau tahu Soekamo bukanlah tokoh NU, melainkan pemimpinan kaum Nasionalis. Terbukti di sini, bahwa NU bukanlah organisasi konservatif, melainkan organisasi tradisional yang tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Sangat indah, bukan? NU-PKB: Tradisionalis atau Modemis Oleh: Abdurrahman
Wahid
Ketika Komite Pemilihan Umum (KPU) mengganjal penulis dari pencalonan presiden, dengan cara melanggar Undang-Undang dan melakukannya secara sangat arogan, maka timbul sesuatu yang menimbulkan tanda tanya besar. Yaitu tentang hakekat NU-PKB: modemkah ia, atau justru tradisional dan kolot? Pertanyaan ini timbul, karena adanya 2 hal sekaligus. Pertama, sikap KPU yang melakukan ganjalan itu karena takut apabila penulis dan DR. Marwah Daud Ibrahim menjadi calon, yang menunjukkan adanya ketakutan status quo akan dirubah oleh demokratisasi. Ini jelas menunjukkan adanya watak modem dalam fungsi politik NU/PKB, karena demokratisasi berarti perubahan untuk memberikan hak politik kepada warga negara tanpa pandang bulu. Namun, tak lama kemudian dimunculkan oleh pers jawaban fiqh dari KH. Abdullah Faqih dari Langitan (Widang, Tuban), bahwa perempuan jangan dipilih menjadi kepala negara kita. Di mata siapapun, ini jelas menunjukkan kuatnya pengaruh tradisionalisme dalam pengambilan keputusan di lingkungan NU-PKB. Kalau kita berpikir secara mendalam memang terdapat kenyataan seperti itu, yaitu dalam modemitas NU-PKB ada tradisionalisme, dan dalam tradisionalismenya ada modemitas, ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kelompok itu memang sehat. Banyak ukuran yang digunakan dalam hal ini oleh para pengamat, yang memang kebelinger dengan acuan-acuan politik saja. Padahal mereka lupa, bahwa NUPKB adalah ententitas besar dengan kehadirannya yang memukau. Terbukti dari sebuah contoh, para pemimpin politik mengharapkan dukungan darinya yang dinyatakan dalam bentuk konsultasi terus-menerus oleh berbagai pihak kepada penulis. Kita harus melihat hal ini sebagai sesuatu yang tidak hanya bersifat politis saja, melainkan pendekatan-multidimensi kepada pihak NU-PKB. Kenyataan ini adalah sesuatu yang hidup-nyata di masyarakat kita. Dalam hal ini memang ada ambivalensi (kegalauan) sikap masyarakat kita pada umumnya dalam memandang NU dan PKB. Ada yang mencoba berpegang pada sikap modem yang dimiliki NU-PKB, tetapi ada pula sikap untuk justru berpegang kepada tradisionalitas/kekolotan kelompok itu. Mereka beranggapan, kalau diserahkan kepada pihak NU-PKB saja tidak akan ada keputusan, berarti tidak akan terjadi perubahan politis dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Dan yang menang bukanlah pihak-pihak yang menghendaki status quo, melainkan justru tradisionalisme, minimal di bidang politik yang nantinya menyulitkan setiap langkah kearah modemisasi kehidupan bangsa di hampir semua bidang kegiatan. Sikap ambivalen itulah yang sebenamya harus dikaji dan di teliti, bagaimana para penganut kedua pandangan itu berhubungan satu sama lain, dan secara bersama-sama mengambil keputusan besar yang menentukan corak kehidupan kita sebagai bangsa di kemudian hari. Bagaimana mungkin, dua hal yang berlawanan dapat hidup berdampingan sambil mengembangkan kesatuan yang demikian luas jangkauannya, tanpa ada friksi politik yang membawa kepada kekerasan? Kalau toh terjadi kekerasan politik, itupun karena adanya salah satu pihak luar yang ikut bermain, baik itu dari orang-orang modem atau sebaliknya. Di negeri-negeri lain, seperti di AS dewasa ini, di bawah kepemimpinan Presiden
Bush, tradisionalisme tidak menimbulkan bahaya apa-apa. Mengapa? Karena diakui oleh semua pihak bahwa rakyat dapat merubah keseimbangankeseimbangan politk yang ada, melalui pemilu sebagai proses politik 4 tahun sekali. Inilah yang sebenamya harus kita pahami dengan baik, tercermin dalam sikap politik kita sebagai bangsa. Sebenamya proses politik kita dewasa ini belum selesai. Walaupun KPU telah membuat aturan tentang kampanye pemilihan kepala negara dan wakilnya dengan sangat arogan/sombong, bahkan melakukan pelanggaran undang-undang, di luar dirinya masih ada proses-proses lain. Minimal ada dua buah proses yang akan terjadi: Pertama, dialog yang dilancarkan oleh penulis dan kawan-kawan pada saat ini tentang kecerobohan dan kecurangan KPU. Hal itu dimulai dengan sikap penulis melakukan langkah golput alias tidak memberikan suara dalam pemilu kepala negara dan wakilnya pada tanggal 5 Juli 2004 yang akan datang. Yang dapat menghentikan kegiatan ini hanyalah Mahkamah Agung yang akan dilawan oleh penulis secara legal. Hanya lembaga itu yang memiliki wewenang atas boleh tidaknya sebuah kegiatan dilakukan berdasarkan undang-undang dasar atau undang-undang. Hal lain yang merupakan proses yang mau tidak mau akan berlanjut terus, adalah pemyataan para Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan para cendekiawan yang merasa berkeberatan atas calon-calon Presiden dan Wakil Presiden dari pihak militer. Sikap seperti itu dapat saja secara politis dinilai benar atau tidak, tetapi yang terpenting pengaruhnya atas perkembangan poltik bangsa kita tidak dapat dianggap kecil. Inilah juga yang harus diamati dengan baik, dan diperhitungkan secara seksama akibat-akibatnya. Bukankah telah ada bukti bahwa akan ada titik tertentu yang mengakibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan bersama kita sebagai bangsa? Itu telah terjadi antara lain ketika Bung Kamo digantikan oleh Pak Harto dalam tahun 1965-1966, terlepas dari mana yang benar dan mana yang salah. Perubahan yang terjadi memang dahsyat, karena menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Karenanya, kita tidak boleh bermain-main dengan hal ini, karena potensi untuk menimbulkan reaksi kekerasan politik dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Kita harus mencari pegangan, minimal secara politis dalam kehidupan ini. Sayangnya, para calon yang akan mengikuti putaran pertama pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi kenyataan ini. Mereka sibuk dengan ikhtiar masing-masing untuk memenangkan jabatan kepala negara/wakil kepala negara melalui pemilu itu sendiri. Dengan kata lain, pendekatan yang mereka ambil sangat bersifat politis, dan memperlakukan aspekaspek kehidupan lainnya secara subordinat (ditundukkan) kepentingan politis sesaat saja. Hal ini jelas akan semakin memperparah kehidupan kita sebagai bangsa. Sebuah pertanyaan sangat besar muncul tanpa disadari dan direncanakan: akan kemanakah kita sebagai bangsa? Dapatkah para calon yang ada memberikan kepemimpinan yang diperlukan bangsa kita untuk menyelesaikan krisis yang ada? Inilah yang belum dapat kita jawab saat ini sebagai bangsa. Lalu, apa yang harus
diperbuat dihadapan kenyataan seperti itu? Tidak banyak yang dapat kita perbuat, jawaban itupun belum sesuai dengan yang diperlukan. Karenanya mau tidak mau kita lalu merasa puas dengan situasi politik sekarang ini. Situasi politik yang tidak dapat kita perkirakan dengan baik, apakah ini sesuatu yang modem atau tradisional. Karenanya, NU-PKB harus membawa ke arah perubahan-perubahan semua bidang kehidupan, alias perkembangan ditentukan oleh kemenangan pihak yang melakukan modemisasi ataukah justru berakhir dengan kemenangan pihak tradisional. Tentu saja, ada yang berharap agar pihak yang melakukan modemisasi akan memperoleh kemenangan, walaupun realitas politik justru memperlihatkan kenyataan sebaliknya. Bagaimanapun juga kita sebagai bangsa tidak dapat hanya membiarkan perubahan-perubahan menuju modemitas yang hanya bersifat teknis belaka, seperti penggunaan komputer dan administrasi modem, sedangkan hal-hal dasar tetap tidak berubah, seperti tidak adanya kedaulatan hukum tidak ada upaya menghilangkan KKN, pendidikan tetap berdasarkan pandangan positifistik dan sebagainya. Hal-hal tersebut memang mudah dikatakan, tetapi perubahan-perubahan mendasar memang sulit dilakukan, bukan? Pada Usia Sepuluh Tahun Oleh
Abdurrahman
Wahid
Bebrapa waktu yang lalu sewaktu sekian halaman majalah inidihitamkan, segera orang menjadi ribut. Sehingga akhimya muncul sebuah kuis imajiner sebagai berikut: T-Mengapakah TEMPO dibuat hitam seperti J-Karena reportase soal tukang santet dan bromocorah di itu? Jember
T-Siapakah yang memerintahkan pengitaman itu? J-Tukang santet dan bromocorah Jakarta Reaksi tersebut menunjukkan status diterima masyarakat yag sudah berhasil di raih TEMPO dalam umur dasa warsanya yang pertama. Dan sesuai usianya yang pertama itu, penerimaan atas TEMPO berhasil diraih dengan tidak meninggalkan sifat kemudaannya, bahkan mungkin keremajaannya (hebat juga TEMPO , memasuki usia sebelas tahun sudah berhasil menjadi Sweet teeneger. Siapakah yang akan memacarinya?). Sudah tentu ia hanya dapat dicapai dengan sejauh mungkin meninggalkan sifat kekanakkanakan, kecuali dalam spontanitas dan kepolosan sikapnya. Penerimaan atas dirinya itu telah membawakan ekspektasinya sendiri atasTEMPO . Bayangkan bagaimana pedasnya kritik ke alamat TEMPO , kalau lebih separoh halamannya diisi iklan. Apalagi kalau jenis penjajaan benda super luks seperti arloji PhilipePatek (biarlah dimuat majalah wanita ngoyo saja seperti iklan tour ke Inggris dan Hongkong hanya untuk belajar beberapa jenis masakan belaka!) Untung TEMPO masih memuat iklan penerbit samawi Bulan Bintang (kapan dimuat iklan Tabib Fakhruddin dengan semboyan bubuk makan kayunya?) Anggapan dan ekspekasi TEMPO dibaca luas oleh berbagai lapisan masyarakat:
dan karenanya patut dijadikan alat komunikasi utama, dapat dilihat pada salah satu fungsinya sekarang :vade mecum resep jamu tradisional untuk menyembuhkan gondong dan eksim menahun. Akhir-akhir ini juga menjadi terminal orang kehilangan keluarga atau keputusan hubungan dengan orang yang dicinta di tanah asal. (kapan kah ia menjadi tempat laporan sadal hilang di masjid, atau KTP yang disambar copet?). Dari itu semua, sebuah kenyataan dapat ditarik sebagai benang halus yang mewamai TEMPO selama ini: sikap terbuka untuk mengemukakan kritik positif, sambil memperlakukan pihak terkritik ( mengikuti bahasa penatar dan petatar) dengan baik. Kritik yang tidak mencerminkan kepahitan sikap, kecuali pertanyaan-pertanyaan pahit yang sering diajukan kepada semua ideologi yang sudah mapan oelh rubrik Catatan Pinggir. Sikap keterbuakaan yang lembut dalam kekuatan dan kebenarannya, tetapi juga yang kuat dalam kelembutan dan (terkadang) kesalahannya. Secara keseluruhan, sifat TEMPO boleh dikata tercakup dalam keterbukaan, keberanian menyuarakan fakta dan mempertanyakan kemapanan, kemampuan berkomuniksi dengan siapa saja dengan bahasa masing-masing. Kesemua itu tercermin dalam spanduk yang melintang di perempatan Blok A Kebayoran Baru hampir dua tahun yang lalu. Berisikan himbauan untuk membaca TEMPO spanduk itu memberikan kelebihan-kelebihan berikut : jujur, jelas, jemih, jenaka . . dan jenaka pun bisa. Tidak dapat dilupakan kesediaan TEMPO untuk menampakkan inovasi komunikatif bemada konyol, untuk menguji kewarasan pandangan sendiri. Karena itu, kepada pengasuhnya pemah diajukan perubahan pda slogan untuk spanduk lain di masa datang: Bacalah TEMPO : jujur, jelas, jemih, jenaka . . jorok pun bisa! Siapa tahu akronim kelima sifat utama diatas akan menjadi sesuatu yang luhur, sehingga akan masuk ke dalam GBHN dan kemudian ditindak lanjuti dengan penataran J5 disamping penataran yang sudah ada, khususnya bagi mereka yang belum mau membeli dan membaca TEMPO ? Paham Konghuchu dan Agama Abdurrahman
Wahid
Paham Konghuchu (Konfusionisme) adalah sebuah kenyataan sejarah yang dibawa ke sini (Indonesia--red) oleh bangsa Tionghoa dari tanah air mereka, sejak berabad-abad yang lalu. Orang-orang keturunan Tionghoa di datangkan oleh pemerintahan kolonialis Belanda ke Nusantara untuk menggali tambang, membuka tanah-tanah pertanian dan mengolah hutan. Mereka datang kesini dalam gelombang kedua, karena dibutuhkan untuk mengolah daerah-daerah kosong yang masih merupakan tanah-tanah perawan (virgin lands). Sebelum itu, orang-orang keturunan Tionghoa yang telah datang ke sini dalam kondisi yang sangat berbeda. Pada abad ke 13, pelaut-pelaut Tionghoa yang beragama Islam berlalu lalang di kawasan antara Pulau Madagaskar di timur Afrika dan Pulau Tahiti di lautan Pasifik. Mereka inilah yang diklaim oleh Moh. Yamin sebagai Angkatan Laut Majapahit dengan bendera merah putih. Puncak dari kekuatan mereka tercapai ketika dalam abad ke 16 Laksamana Macengko (Ma Zenghe) tujuh kali memimpin expidisi armada Tiongkok dalam mengarungi
kepulauan Nusantara ini. Ia meningal dunia di Kalikut (India) dalam expidisi ke tujuh tersebut. Dapat dibayangkan, di sini, betapa perkasanya Angkatan Laut Tiongkok yang muslim ketika itu. Mereka hanya menggunakan kapal-kapal layar (Jonks) untuk mengangkut sekian banyak orang. Norman Schwarzkoff pemimpin tentara sekutu, ketika menyerbu Kuwait dan Irak beberapa tahun lalu memerlukan empat puluh lima ribu orang pasukan yang diangkut dengan kapal induk, kapal-kapal lain dan beberapa jenis pesawat terbang. Operasi yang dipimpinnya menelan biaya tidak kurang dari 70 Milyard dollar AS. Jadi, dapat dibayangkan keperkasaan Ma Zenghe yang dalam abad ke 16 Masehi dapat memimpin sebuah expidisi sebanyak tujuh kali. ***** Dalam "buku 1492" yang berbahasa Perancis, disebutkan ada Menteri Peperangan Tiongkok dalam abad ke 15 M yang menjadi wali raja yang masih kecil. Sebagai seorang pengikut Konghuchu fundamentalis, ia merasa takut jika orang-orang Tionghoa di perantauan akan kembali ke daratan China dan membeli tanah-tanah yang terbatas jumlahnya itu, dari harta yang diperoleh dari perantauan. Karena itu, ia memerintahkan ditariknya kapal-kapal laut Tiongkok dari perantauan, lalu di bakar di pantai Hainan. Orang-orang Tionghoa yang beragama Islam di rantau, akhimya terputus hubungan dengan negeri asal mereka. Dalam waktu dua abad, mereka diserap oleh penduduk asli, dan mereka meninggalkan kampung-kampung China di berbagai daerah di kepulauan Nusantara. Maka masjid-masjid yang mereka dirikan di kampung-kampung China ditinggalkan kosong. Ketika orang-orang Tionghoa gelombang kedua datang, dengan membawa agama Budha (Taoisme) dan agama Konghuchu, segeralah masjid-masjid yang ditinggalkan kosong itu dirubah menjadi kuil. Ini benar-benar sebuah kenyataan, seperti yang terjadi atas Masjid Sam Po Toalang yang akhimya dirombak menjadi kuil Sam Po Toalang di pantai utara Jawa. Karenanya, banyak sekali orang yang sekarang disebut sebagai penduduk asli seperti halnya penulis, sebenamya adalah keturunan orang-orang Tionghoa muslim tersebut. Mereka tidak lagi dikenal sebagai orang Tionghoa, karena sudah bercampur darah dengan orang lain. dalam diri penulis terdapat darah Tionghoa, Arab dari Oman dan Libya (melalui Maulana Ishak yang berasal dari Tabarqa/Tobruk, Jawa asli maupun darah India dan Persia. ***** Dari tinjauan di atas tampak jelas, sebagian dari orang-orang Tionghoa yang datang ke sini memandang bahwa paham Konfusionisme sebagai agama. Mereka membawa serta budaya-agama yang diwariskan oleh nenek moyang mereka sebagai tradisi yang harus diikuti. Dalam tradisi ini, termasuk diantaranya soal perkawinan dan pembagian waris yang tidak dapat diabaikan. Disinilah letak persoalannya, paham konghuchu itu dianggap sebagai agama atau bukan.
Paham komunis di daratan Tiongkok sendiri, jelas tidak bisa menerima paham ini sebagai agama, melainkan mereka menganggapnya sebagai filsafat hidup. Dengan demikian, hak-hak para pengikut paham Konghuchu, dalam bentuk perkawinan dan pembagian waris menjadi diabaikan. Ini adalah merupakan lagu lama kekuasaan pemerintahan yang terlalu berlebihan. Apalagi kalau digabungkan dengan keinginan sementara orang yang menghendaki para pengikut paham Konghuchu agar memeluk agama mereka. Lalu, pertanyaannya, apa pendapat penulis dalam hal ini? Mudah saja. Bahwa, para pemeluk paham Konghuchu-lah yang seharusnya menentukan bukannya pihak pemerintah. Kalau mereka menganggap paham itu sebagai agama, maka hal itu harus diterima oleh pemerintah. Kalau ada pejabat pemerintah tidak menghargai hal ini, mereka menentang undang-undang dasar 1945. Pengertian inilah yang harus ditegakkan di kalangan kita, tapi sebagai proses sosial ia berjalan sangat lambat. Hal ini, juga harus dimengerti oleh para penganut paham tersebut. Memang, ini tidaklah mudah, tapi memang adakah kemudahan bagi bangsa yang sangat tinggi taraf kemajemukannya seperti kita?
Pemimpin dan Kepemimpinan Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Pada suatu pagi dalam siaran sebuah stasiun pemancar radio, ada dialog tentang pemimpin dan kepemimpinan. Sudah tentu setelah wawancara dengan narasumber, dilakukan dialog interaktif dengan para pendengar radio itu. Nara sumber dialog itu menyatakan, bahwa terdapat kaitan sangat erat antara seorang pemimpin dan kepemimpinan yang ditunjukannya. Keadaan yang saat ini amburadul, dikembalikannya kepada langkahnya pemimpin dan kepemimpinan dikalangan bangsa ini pada waktu sekarang. Ketika sesi dialog interaktif, seorang pendengar menyatakan, bahwa pemah terjadi kita memiliki pemimpin dan kepemimpinan yang tinggi kualitasnya. Yaitu ketika pemerintahan Perdana Menteri Syarifudin Harahap -mungkin yang ia maksudkan adalah Burhanudin Harahapyang pemah menjadi Perdana Menteri kita untuk waktu yang cukup pendek. Menurut penulis sebenamya kita cukup mempunyai beberapa orang pemimpin pada awal-awal kemerdekaan bangsa. Untuk membatasi jumlah pemimpin hanya pada diri seorang saja, seperti Burhanudin Harahap sangatlah riskan dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Apa ukuran yang dilakukan, dan adakah dasar bagi penilaian seperti itu? Para pemimpin yang memperjuangkan dan kemudian mempertahankan kemerdekaan kita, menunjukkan bahwa sebagai bangsa, kita dahulu dipimpin oleh para pemimpin bangsa, yang sebenamya telah menunjukkan kemahiran dan kematangan sebagai pemimpin. Tidak peduli apa sifat-sifat pribadi yang mereka miliki, secara keseluruhan mereka berhasil memimpin bangsa kita mencapai kemerdekaan. Berbagai ragam corak kepemimpinan telah mereka perlihatkan, walaupun secara keseluruhan dapat diperlihatkan adanya
kepemimpinan bangsa yang sangat kompak. Ketika Hatta dan Iwa Kusumasumantri memimpin perhimpunan Indonesia di Belanda tahun 1940, terlihat bagaimana mereka memperlihatkan kepemimpinan atas dasar keyakinan yang sangat kuat akan kemerdekaan bangsa. Ketika HOS Cokroaminoto memimpin Syarikat Islam di Surabaya pada tahun 20-an, lagi-lagi menunujukkan kepemimpinan dan lahimya sang pemimpin dengan gamblang. Ketika Soekamo mempertahankan diri dengan membacakan pembelaan/pledoi di muka pengadilan di Bandung tahun 1931, jelas ia telah memperlihatkan kepemimpinan yang mengagumkan. Bahwa ia kemudian dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tetap tidak mengurangi arti kepemimpinan itu. Ketika para pemimpin gerakan Islam mendirikan Majelis Islam Ala Muslimin Indonesia (MIAI) pada tahun 1943, terlihat sekali lagi munculnya sejumlah pemimpin bangsa. Dan semasa para pemuda kita, dibawah pimpinan B.M Diah dan Sukami berhasil memaksa Soekamo dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945, deretan para pemipin bangsa bertambah panjang. Sudah tentu, bukan hanya mereka yang menjadi pemimpin bangsa tetapi termasuk juga orang-orang seperti Tan Malaka, Agus Salim dan Moch. Yamin. Hal itu membuktikan bahwa kita pemah memiliki sejumlah pemimpin bangsa dengan kepemimpinan mereka yang sangat beragam coraknya. Kita tidak akan mengupas hal itu dalam tulisan ini, melainkan hanya menyebutkan bahwa kita pemah mempunyai para pemimpin seperti mereka. Kecenderungan untuk mempersempit pada pembatasan pemimpin pada satu-dua orang saja, sebenamya telah mengingkari kenyataan sejarah yang penting, yaitu kecukupan jumlah pemimpin yang kita miliki dimasa lampau. Bahwa mereka tidak pemah mempunyai pandangan yang sama mengenai pengaturan kehidupan bangsa ini, tidak berarti mereka tidak menyukai kemerdekaan bangsa. Hal itu mereka perjuangkan habis-habisan sehingga pantaslah mereka menjadi para pemimpin bangsa kita pada waktu itu. Perbedaan terbesar antara mereka pada saat itu adalah tentang masa depan bangsa ini. Ada yang berideologi agama dan menginginkan sebuah negara agama. Ada juga yang menentang hal itu, dan menganggap bahwa bangsa kita harus memisahkan antara negara dan agama. Hal itu mengakibatkan kemacetan dalam sidang-sidang Dewan Konstituante dalam memutuskan undang-undang dasar kita. Di satu pihak mereka yang menentang negara agama mengumpulkan suara 52%, sehingga penetapan Pancasila sebaga dasar negara kita tidak dapat dilakukan, karena dibutuhkan suara sebesar 67% untuk itu. Apalagi dengan mereka yang menghendaki negara agama, karena mereka hanya berhasil mengumpulkan 48% suara. Kemacetan konstitusional itu akhimya melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, untuk kembali pada Pancasila sebagai dasar negara, yang dijiwai oleh Piagam Jakarta dari dekrit ini lahirlah negara otoriter dengan apa yang dinamakan Demokrasi Terpimpin yang dipimpin oleh Soekamo. Nah, sistim pemerintahan otoriter itu kemudian mengakibatkan terpenjaranya para pemimpin yang pandangannya berbeda dari Soekamo. Penyimpangan ke arah Demokrasi Terpimpin itu, kemudian dikoreksi oleh pemerintahan Orde Baru.
Tetapi pemerintahan tetap dilakukan secara otoriter, dengan menggunakan ABG (ABRI, Birokrasi dan Golkar) sebagai tiang penyangga pemerintahan. Mereka yang tidak bersepandapat dengan pemerintahan Orde Baru dan ingin melaksanakan demokrasi, dianggap sebagai kaum liberal. Dengan gigihnya pemerintahan Orde Baru menerapkan sistemnya sendiri, yaitu mereka yang berkuasa menguasai segala-galanya. Mereka yang menentang ada yang dipenjara dan ada yang dipatahkan inisiatifnya. Walhasil, walaupun Orba adalah kritik yang diajukan terhadap Demokrasi Terpimpin, tapi dasar-dasar kekuasaan tetap otoriter. Demikianlah kita diperintah selama hampir 4 dasawarsa oleh dua orientasi pemerintahan. Ketika reformasi lahir tahun 1998, orientasi baru yang tidak otoriter belum sampai membentuk pemerintahan yang benar-benar demokratis. Yang tercapai hanyalah pemerintahan quasi demokrasi (seolah-olah demokrasi), dengan akibat menghilangnya para pejuang demokrasi, dan para pemimpin dengan kepemimpinan mereka dari roda pemerintahan. Pemerintahan akhimya jatuh ketangan mereka yang berambisi politik. Sangat besar tetapi tidak memiliki kepemimpinan dengan orientasi yang benar. Mereka hanya memikirkan kekuasaan golongan sendiri, dan mencari keuntungan sebesar-besamya bagi kelompok sendiri, tentu saja dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Sikap itu tetap bertahan sampai sekarang, dan terlihat mewamai persiapan-persiapan untuk pemilu yang akan datang. Dan akhimya membuat masyarakat kita seolah-olah terbelah dua. Pertama, mereka yang benar-benar ingin menginginkan demokrasi dalam bentuk kedaulatan hukum penuh dan persamaan perlakuan kepada semua warga negara di hadapan undang-undang. Kedua, mereka yang hanya ingin keuntungan golongan sendiri. Pemilu yang akan datang, dalam bentuk pemilu legislatif dan pemilu kepresidenan, akan merupakan batu ujian. Benarkah kita mampu melahirkan pemimpin dan kepemimpinan yang benar. Inilah sebenamya yang menjadi taruhan kita semua. Kalau kita memilih pemimpin dengan kepemimpinan yang benar, maka untuk selanjutnya kita akan menjadi bangsa yang benar-benar demokratis. Kalau benar demikian, maka kita akan menjadi bangsa yang besar, sesuai dengan jumlah warga negara yang sudah mencapai lebih dari 205 juta jiwa. Kalau tidak, maka untuk jangka waktu cukup lama, kita akan memiliki pemerintahan yang mementingkan golongan sendiri. Inilah yang sebenamya merisaukan cukup banyak kalangan di negeri kita dewasa ini. Kekuatan yang mendorong demokratisasi dengan kuat dan konsisten, tidak tampak dipermukaan. Karenanya, banyak kalangan meramalkan hasil pemilu yang akan datang hanya memperkokoh corak pemerintahan dengan kekuatan politik berimbang seperti yang terjadi saat ini. Sebaliknya, penulis yakin bahwa Silent Majority (mayoritas yang tidak bersuara) justru akan menjadi penentu dalam pemilihan umum legislatif dan Presiden yang akan datang. Karena itu, ia memulai upaya membersihkan partainya dari ketergantungan pada sikap mementingkan golongan sendiri. Akibatnya, ia dimarahi kanan-kiri dalam parpolnya sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Rakemas (Rapat Kerja Nasional) parpolnya sendiri di Hotel Millenium Jakarta baru-baru ini. Kebanyakan Dewan Pimpinan Wilayah dalam parpolnya menganggap bahwa
penulis tidak menyiapkan bahan-bahan persiapan yang cukup bagi pemilu itu. Contoh issu yang mereka kemukakan berkisar pada kenapa penulis tidak mempersiapkan tim sukses hingga saat ini. Padahal ada issue yang lebih besar dari hal itu. Mereka seolah-olah menganggap demokratisasi kehidupan bangsa ini bukanlah issue yang cukup besar bagi khalayak ramai, yang akan memberikan suara dalam kedua macam pemilu itu. Memang mudah mengatakan demokratisasi namun dalam kenyataan hal itu sulit dilaksanakan menurut pendapat orang banyak, bukan? Pemimpin yang Kita Cari Oleh Abdurrahman
Wahid
Terasa sekali pada saat ini bahwa tidak ada kepemimpinan nasional maupun kepemimpinan umat Islam yang menonjol yang sanggup memberikan inspirasi dan sanggup membakar semangat generasi muda. Tidak ada seorang pun pemimpin bangsa yang dapat menjadi gambaran-cita (ideal type) generasi muda menjadi penyuluh di kala kegelapan dan menjadi petunjuk di tengah badai kehidupan. Seolah-olah kehidupan bangsa dewasa ini tengah dipimpin oleh sejumlah pemimpin tak bermuka dan tak bemama, dengan kemampuan rara-rata, tanpa ada yang mengarahkan. Tidak heranlah jika generasi muda merasakan adanya kekosongan, merasakan kehidupan sebagai irama datar yang tidak menimbulkan rangsangan dan kegairahan sama sekali. Jenis kepemimpinan kolektif yang mengendalikan keduhidupan bangsa sekarang ini memang dianggap sebagai penyebab timbulnya rasa seperti ini. Teknokrasi yang didukung oleh kepatuhan hierarkis dari kelompok militer menghasilkan hilangnya sifat-sifat menonjol dari kepemimpinan bangsa, karena pada sistem pemerintahan terknokratis tekanan diberikan kepada penciptaan dan pengembangan cara kerja bersama dalam sebuah program umum. Atau dengan kata lain, kepada penumbuhan semangat "main bersama" (team playing). Selama permainan bersama dapat dipelihara, tidak dianggap merugikan untuk kehilangan kepemimpinan yang menonjol. Kepemimpinan tanpa ada yang menonjol inilah yang sebenamya melandasi ketidakpuasan yang telah meluas di masyarakat dewasa ini. Terutama di kalangan mudanya. Tidak ada seorang pemimpin pun dapat ditunjuk sebagai biang keladi kelesuan kehidupan dewasa ini, tetapi begitu pula tidak ada seorang pemimpin pun dapat menjadi sumber inspirasi bagi bangsa secara keseluruhan. Dengan melihat kepada latar belakang kehidupan kepemimpinan bangsa yang seperti inilah ingin ditinjau perbandingan kepemimpinan, untuk nantinya kita akan mampu menggambarkan kepemimpinan bangsa yang sebagaimana sebenamya dapat mengatasi kelesuan hidup bangsa di masa depan. Kepemimpinan dapat dibagi dalam berbagai pembagian, terserah dari sudut mana
kita memandangnya. Dari sudut kuantitas, kepemimpinan dapat dibagi menjadi kepemimpinan kolektif dan kepemimpinan individual/perorangan. Dari sudut jenisnya, dapat dikenal pembagian pada kepemimpinan tradisional (adat, agama, suku bangsa, dan sebagainya) dan kepemimpinan dinamis (ketentaraan, perusahaan modem, akademis, lingkungan wilayah, dan seterusnya). Pengelihatan status akan menunjukkan adanya kepemimpinan formal maupun informal. Terakhir dari sudut pandangan fungsinya, kepemimpinan meliputi kepemimpinan pencipta kesadaran (solidarity makers) dan administrateurs. Kepemimpinan sebuah kelompok masyarakat yang besar dapat saja mengambil bentuk yang diingini, baik itu sebuah perusahaan swasta, sebuah organisasi sosial, sebuah partai politik berukuran nasional maupun pimpinan kenegaraan. Pimpinan tradisional dapat saja memegang tampuk pimpinan pemerintahan, sebagaimana juga pimpinan kolektif dapat menguasai sebuah perusahaan transnasional. Tetapi, memang ada beberapa kepemimpinan yang hanya sesuai dengan bentukbentuk tertentu, seperti kepemimpinan ketentaraan (harus kolektif) atau akademis (harus dinamis, tidak dapat tradisional). Masing-masing bentuk pun memiliki persyaratan, cara kerja, pendekatan dan cara pengambilan keputusan sendiri-sendiri, yang satu sama lain tidak bersamaan. Kebesaran sesuatu kelompok yang besar justru terletak dalam kemampuan menumbuhkan bentuk-bentuk kepemimpinan yang berbeda-beda dalam segenap unsur kehidupannya. Di sini tidak ingin dilakukan perbandingan terperinci antara semua bentuk kepemimpinan yang sudah disebutkan di atas, karena hanya akan membosankan dan karena kesempitan ruang yang tersedia untuk itu. Perbandingan yang dilakukan secara garis besar belaka antara kepemimpinan "pencipta kesadaran" dan kepemimpinan administratif. Dari perbandingan itu akan tampaklah dengan nyata bagi kita, betapa beratnya tugas yang dipikul oleh kepemimpinan bangsa di kemudian hari, jika kita menginginkan kemajuan sosial ekonomis, tetapi tetap mampu mengembangkan kreativitas bangsa dan kegairahan hidup di kalangan rakyat. Contoh dari kepemimpinan "pencipta kesadaran" yang paling teringat di benak kita adalah Bung Kamo, semasa beliau dalam puncak kejayaan menjadi Presiden seumur hidup. Kepemimpinan jenis ini tidak begitu tertarik dengan administrasi dan kerapian kerja secara bertahap dan evolioner. Ia tidak begitu tertarik dan tidak berkeinginan mengurusi "soal-soal kecil" seperti pertambahan penduduk, kenaikan pendapatan, peningkatan produksi di segenap bidang, dan hal-hal "sepele" lainnya. Ia lebih tertarik pada ide-ide dasar, yang diolah menjadi isu politik yang membakar rakyat. Ia lebih berkepentingan kepada penciptaan kesadaran politik yang tinggi, di mana kekuatan rakyat dipusatkan untuk memprotes kelaliman dan penindasan (termasuk penjajahan) atau untuk mendobrak suatu kelompok yang dianggap musuh bersama. Penciptaan kegairahan dan semangat politik menjadi impian
seperti
ini.
Pada kepemimpinan solidarity, ia menonjolkan seorang pemimpin besar, yang diagung-agungkan dan dicanangkan sebagai pembebas rakyat dari hal yang diproteskan. Pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada sang pemimpin besar, yang umumnya mendasari proses pengambilan keputusannya dengan pertimbangan-pertimbangan tidak rasional (kecuali rasio kepentingan politiknya sendiri dalam percaturan kekuasaan dalam lingkungannya sendiri). Sebaliknya, kepemimpinan administratif tidak begitu tertarik dengan isu hangathangat, dengan penciptaan semangat yang menggelora, dengan pemujaan kepada seorang pemimpin tunggal, dengan protesan-protesan, dengan simbol-simbol irasional dalam pengambilan keputusan dilakukan bersama setelah pertimbangan pro dan kontra yang bersifat rasional, dibicarakan secara tuntas. Ia lebih menyukai proyeksi-proyeksi kehidupan masa depan dalam bentuk yang merupakan hasil-hasil konkret yang dapat dijabarkan dengan angka berderetderet. Kepemimpinan seperti ini sering kali tidak merasa perlu membakar semangat rakya untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Cukuplah kalau setiap anggota masyarakat menjalankan kewajibannya dengan baik. Sudah tentu kepemimpinan seperti itu terasa sangat membosankan bagi rakyat, hambar bagi kelompok-kelompok yang kreatif dan terasa mematikan semangat bagi kelompok-kelompok yang dinamis. Seolah-olah tiap orang, bahkan yang terbodoh sekalipun, mampu menjadi pemimpin dalam sistem kepemimpinan seperti ini. Dengan asumsi, orang itu toh akan mampu memimpin dengan bantuan rencana teknis yang dibuat oleh para pembantunya yang dinamai teknokrat. Kepeminpinan administratif nyata sering kali tidak mampu memperhitungkan pentingnya kegairahan hidup, geloranya semangat, dan terbakamya pendapat umum dengan isu politik. Tanpa adanya kegairahan dan semangat seperti itu, kelesuan akan melanda kehidupan bangsa secara perlahan-lahan tetapi pasti. Kelesuan ini pada gilirannya akan menumbuhkan sikap apatis dan masa bodoh di kalangan cukup luas, terutama di lingkungan mereka yang diharapkan kreativitasnya. Apatisme di lingkungan mereka ini pada akhimya mematikan aspirasi rakyat. Karena kelompok kreatiflah yang sebenamya menghubungkan rakyat dengan pemerintahnya. Tanpa adanya hubungan seperti itu, rakyat merasa tidak ada saluran lagi unek-unek mereka, dan mereka pun merasa tidak ada saluran akan merasa tertindas dan tertekan. Kekurangan gairah dan semangat seperti ini tidak terdapat dalam lingkungan kepemimpinan solidarity makers, karena justru membangkitkan gairah dan penggeloraan semangatlah yang menjadi modal politik mereka yang utama. Tetapi kepemimpinan solidarity makers tidak akan mampu menghasilkan masyarakat yang makmur, setidak-tidaknya secara sosial-ekonomis. Pembangunan
haruslah diatur secara berencana dan didasari perhitungan-perhitungan rasional bukan dengan semangat dan gelora isu politik. Kepemimpinan individual yang menjadi perwujudan solidarity making yang tertinggi, tidaklah akan mampu mengatasi persoalan sosial ekonomis secara sendirian belaka. Apalagi jika ia didasarkan pada legitimasi irasional. Karena itu yang diperlukan adalah sintese dari kedua jenis kepemimpinan tersebut. Dari solidarity makers haruslah diambil kemampuan membangkitkan minat rakyat kepada pembangungan, tetapi dari adminstrateur dapat dipetik kemampuan teknis menyusun rencana pembangunan yang tidak terlalu lari dari kenyataan akan keterbatasan sumber-sumber manusiawi, alami, dan modal yang ada. Dari solidarity makers diambil kemampuan memandang jauh ke depan untuk menatap kebesaran bangsa yang akan dijangkau di kemudian hari dengan terang dan gamblang, sebaliknya dari administrateur diambil ketenangan dan kejemihan mengawasi jalannya kehidupan masa kini, agar tidak tersendat-sendat oleh kekurangan pangan dan sebagainya. Dari solidarity makers diambil tokoh-tokoh pemimpin yang berwibawa dan dapat menjadi kebanggaan bangsa, sedangkan dari administrateur diambil persyaratanpersyaratan teknis yang tinggi dan terperinci, yang akan memungkinkan pengambilan keputusan teknis yang tetap bagi kesejahteraan bangsa. Jika ada kepemimpinan yang mampu menggabungkan semua unsur yang disebutkan di atas, barulah kepemimpinan bangsa, akan mampu menjadi sumber inspirasi, penggugah kegairahan bangsa untuk pembangunan, penuntun yang menjadi gambaran-cita (ideal type) yang disayangi dan dipuja oleh rakyat terutama oleh generasi muda. Penafsiran Kembali Ajaran Agama: Dua Kasus dari Jombang Oleh Abdurrahman
Wahid
Judul Tulisan ini semula ditetapkan: "Pergeseran Nilai-nilai Agama di Pedesaan Jawa Timur." Judul tersebut sepintas lalu merupakan rumusan yang sangat menarik. Namun, mereka yang ingin menguraikanya secara ilmiah akan menemui kesulitan-kesulitan besar dalam menerangkan istilah maupun menyusun konsepsi teoretis tentang kata "nilai" dan "agama". Kata "pergeseran" bukanlah istilah yang lazim dipakai di kalangan ilmu-ilmu sosial untuk menganalisis terjadinya perubahan sesuatu nilai yang berlaku di masyarakat. Demikian pula, kata "nilai-nilai agama" (relegious values), walaupun seringkali dipakai, merupakan istilah yang mengandung kekaburan pengertian. Di dalam studi tentang agama dan masyarakat, para ahli ilmu-ilmu sosial lebih cenderung memilih istilah yang lebih jelas dan kongkret, seperti "doktrin agama", "ritus-ritus agama","kepercayaan agama" (relegious belief) dan sebagainya.
Ajaran agama baik yang paling mendalam dan fundamental, yang sangat doktriner maupun ajaran-ajaran praktis, dalam proses pembentukan tingkah laku masyarakat yang menganutnya akan membentuk sistem nilai yang oleh Koentjaraningrat dikategorikan dalam bentuk "wujud kebudayaan sebagai kompleks ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya", yaitu wujud idiil dari kebudayaan yang sifatnya abstrak, yang lokasinya "dalam alam pikiran" manusia warga masyarakat. Dengan penggunaan istilah "ajaran-ajaran agama" kita terhindar dari kesulitan dan tidak terbentur dengan istilah cultural value system atau value orientation. Menurut kedua konsep para ilmuwan itu, agama tidak mengandung nilai-nilai di dalam dirinya, tetapi mengandung ajaran-ajaran yang menanamkan nilai-nilai sosial yang bila nilai-nilai itu meresap dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat (penganutnya), ajaran-ajaran agama itu berarti merupakan salah satu elemen yang membentuk cultural value system atau value orientation itu. Dengan demikian kita tidak terbentur dengan "kerangka''-nya Kluckohn tentang cultural value system yang tidak membedakannya dengan agama itu sendiri. Dalam masyarakat yang masih sangat primitif, jalinan antara agama dan nilai budaya demikian ruwet sehingga susah untuk memisah-misahkannya. Sebaliknya dalam masyarakat yang sudah lebih maju di mana ajaran agama itu sudah tertuang dalam tulisan-tulisan, kita dapat merasakan perbedaan antara nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan ajaran agama yang dirumuskan secara formil. Walaupun antara keduanya tidak seharusnya dipertentangkan, tetapi kelihatan bahwa ajaran-ajaran agama yang tertuang dalam rumusan formil lebih bersifat kongkret daripada nilainilai masyarakat. Oleh karena itu, agama sebagai salah satu elemen yang menanamkan nilai-nilai masyarakat, juga pemahaman ajaran-ajarannya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan nilai itu sendiri. Perubahan nilai maupun pemahaman ajaran-jaran agama dapat disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat itu sendiri, ataupun karena pengaruh yang datang dari luar. Di dalam analisis-analisis tentang perubahan masyarakat, biasanya diterima asumsi, bahwa agama dianggap sebagai unsur yang paling sukar dan paling lambat berubah atau terpengaruh oleh kebudayaan lain, bila dibandingkan dengan unsur-unsur lain seperti: sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, ikatan-ikatan yang ditimbulkan oleh mata pencaharian, sistem teknologi dan peralatan, serta persekutuan yang ditimbulkan untuk menghadapi atau sebaliknya mendekati kelompok-kelompok kemasyarakatan lain.Tetapi sejarah kehidupan bangsa kita yang panjang tidak sepenuhnya dapat disesuaikan dengan asumsi tersebut. Berbagai agama datang dan berkembang secara bergelombang ke Indonesia, mengganti agama yang lama dan menanamkan ajaran-ajaran agama yang baru secara silih berganti, tetapi dalam kenyataannya sistem matapencaharian hidup dan sistem teknologi dan peralatan yang dikatakan oleh Koentjaraningrat sebagai unsur yang paling mudah,temyata yang paling sedikit mengalami perubahan sejak pra-Hindu sampai kepada masa sekarang. Pengalaman sejarah itu justru menunjukkan agama berubah lebih cepat, ia berubah lebih dahulu sebelum yang lain-lain mengalami perubahan. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan, bahwa banyak para pengamat sejarah mencatat
kegagalan Kemal Attaturk untuk membangun Turki, karena ia tidak mengakui ajaran Islam sebagai penggerak perubahan dan pembangunan di negerinya; sedangkan Jepang dapat membangun negerinya dengan pesat dan mengejar kemajuan teknologi Barat, karena negeri tersebut dianggap mampu menggunakan agama Shinto sebagai motor penggerak perubahan dan pembangunan.'' ltulah sebabnya dewasa ini tumbuh pendapat di kalangan birokrat dan teknokrat kita untuk meminta jasa-jasa agama (Islam) sebagai penumbuh motivasi perubahan dan pembangunan masyarakat, terutama di sektor pedesaan. Tentunya timbul pertanyaan, bagaimana mungkin agama yang ajaran-ajarannya tertuang secara kongkret dalam tulisan dan dihormati sebagai sesuatu yang sakral dan diterima sebagai sesuatu yang langgeng, justru pemahamannya dapat berubah lebib cepat daripada perubahan masyarakat itu sendiri? Snouck Hurgronje pemah mengemukakan bahwa, "tiap-tiap periode sejarah kebudayaan sesuatu bangsa, memaksa kepada golongan beragama untuk meninjau kembali isi dari kekayaan akidah dan agamanya". Walaupun tidak secara eksplisit dikemukakan, pemyataan Snouck Hurgronje itu berdasar kepada suatu pikiran bahwa proses peninjauan kembali isi ajaran-ajaran agama oleh para penganutnya sifatnya reaktif oleh adanya perubahan periode kebudayaan di mana agama itu hidup.Ini juga bertentangan dengan pengalaman sejarah kebudayaan pada umumnya yang menunjukkan bahwa pemahaman baru terhadap ajaran agama justru menumbuhkan periode baru dalam kebudayaan bangsa-bangsa. Calvinisme misalnya, dianggap oleh Max Weber sebagai penanaman etik baru yang menumbuhkan periode kapitalisme dalam sejarah modem, sedangkan prinsip Satyagraha yang ditukik oleh Mahatma Gandhi dari ajaran Hindu jelas telah berhasil menumbuhkan etos mandiri pada budaya politik bangsa India di abad ini. Namun terlepas dari persoalan apakah peninjauan kembali isi agama itu sifatnya reaktif ataukah sebenamya inherent dalam tubuh ajaran agama itu sendiri. Snouck Hurgronje pemah pula nnemperingatkan bahwa Islam di Indonesia yang kelihatan statis dan tenggelam dalam kitab-kitab salaf abad pertengahan itu, sebenamya mengalami perubahan-perubahan yang fundamentil; perubahanperubahan itu demikian perlahan, rumit dan mendalam, sehingga hanya orang yang dapat mengamatinya secara hati-hati dan teliti dapat mengetahui perubahan tersebut. Dapatlah disimpulkan bahwa proses terjadinya pemahaman kembali isi ajaranajaran agama dapat disebabkan oleh terjadinya reaksi terhadap adanya perubahan yang terjadi di luar agama itu, tapi juga di dalam ajaran agama itu sendiri dimungkinkan adanya proses pemahaman baru. Karena pemahaman atas isi ajaran agama dipegang oleh pemuka-pemuka agama (religious elite) yang biasanya juga menjadi kelompok pimpinan (elite class) dalam hampir semua struktur masyarakat, maka sesuai dengan dinamika yang selalu dimiliki oleh kelompok pimpinan itu sendiri, mau tidak mau isi ajaran-ajaran agama itu akan selalu mengalami proses pembaharuan pemahamannya. Kelompok elite di mana-mana memiliki kepentingan yang paling besar dibandingkan dengan kelompok-kelompok lain di masyarakat,
itulah sebabnya bila terjadi perubahan sosial atau diperlukan adanya perubahan dalam masyarakat, mereka berkepentingan pula untuk dapat mengendalikan perubahan-perubahan tersebut, agar kepentingan mereka sebagai pemimpin masyarakat tidak sampai direbut oleh kelompok-kelompok yang lain. Para pemuka agama sebagai salah satu unsur kelompok elite yang memimpin masyarakat, dengan demikian juga harus dapat mengendalikan dan mengarahkan peninjauan kembali ajaran-ajaran agama sehingga mereka tetap dapat mempertahankan kedudukan mereka dalam bidang kepemimpinan agama. Agama dan pengelompokan masvarakat menurut Lenski merupakan dua faktor vang paling berpengaruh dalam tingkah laku individu-individu (dan dengan demikian kehidupan masyarakat secara keseluruhan); itulah sebabnya para pemimpin masyarakatberusaha menguasai kcdua aspek ini, yaitu dengan menjadi kelompok elite dan sekaligus pemuka agama. Gejala ini dapat dilihat, umpamanya, dalam kegairahan pemimpin-pemimpin bangsa kita di segenap tingkatan dewasa ini untuk menekankan perlunya perpaduan fungsi secara harmonis antara pemuka agama (Ulama) dan pemimpin pemerintahan (umara); gejala ini juga tampak di negerinegeri lain, seperti penamaan kelompok teknokrasi yang memerintah di masa rezim Franco di Spanyol beberapa tahun yang lalu degan sebutan corpusdei. Pendekatan vang dikemukakan tadi, juga akan menghindarkan kita dari kungkungan pendekatan fungsionalistis (functionalist's approach) dalam studi tentang agama mendominir dunia antropologi dan sosiologi selama ini yang bersumber kepada Radcliffe Brown dan Malinowski. Pendekatan fungsionalistis itu terlalu menekankan aspek perpaduan dan penyatuan (harmonizing and integrating aspects) dari ajaran-ajaran agama dengan melupakan aspeknya yang bersifat mengubah (transformative aspect). Hal ini antara lain telah ditinjau dalam hubungannya dengan penghayatan agama Islam di Jawa, walaupun dari sudut lain. Pendekatan fungsionalistis dalam menganalisis agama akhimya akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang statis dan pandangan yang sangat konservatif atas rituil dan ajaran-ajaran keagamaan dalam kehidupan sosial seperti yang dilakukan oleh Koentjaraningrat dan Kluckhohn. Pada dasamya, setiap agama memiliki watak transformatif, yaitu berusaha menanamkan nilai-nilai yang baru dan mengganti nilai-nilai yang lama yang dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Dengan wataknya yang demikian itu agama tidak selalu menekankan segi-segi harmoni dan aspek-aspek integratif dalam kehidupan masyarakat, tetapi seringkali justru menimbulkan konflik-konflik baru karena misinya yang transformatif itu mendapat tantangan dari sebagian anggota masyarakat. Contoh yang paling mudah diambil dalam hal ini adalah tantangan besar yang timbul ketika kelompok Islam meminta dicantumkannya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya di dalam bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar kita tahun 1945. Pemahaman kembali terhadap ajaran-ajaran agama seringkali mengambil tema "kembali kepada ajaran yang benar atau kembali kepada ajaran yang asli". ltulah sebabnya dalam setiap gerakan reformasi dalam Islam misalnya, selalu diambil tema kembali kepada AI-Qur'an dan Hadis". Tema yang sedemikian itu pada dasamya adalah cara yang dianggap terbaik untuk melicinkan jalan bagi reformasi tanpa mengundang terlalu banyak tantangan yang mungkin akan dapat
menggagalkan perubahan-perubahan yang dituntut oleb reformasi itu sendiri. Proses pemahaman baru atas ajaran agama tidak selalu diikuti oleb munculnya organisasi gerakan reformasi. la dapat tumbuh dalam suatu grup keagamaan tanpa munculnya beberapa eksponen pembaharu dalam paham-pahamnya, atau justru lalu ia mengambil bentuk memperkuat posisi grup keagamaan yang lama itu dalam usaha menghadapi grup baru yang akan mengancam eksistensi atau dominasinya. Contoh yang kongkret ialah "kebangunan para ulama" (Nahdlatul Ulama) pada tahun 1926 yang pada umumnya dikenalsebagai gerakan yang muncul untuk mempertahankan serangan-serangan reformasi dari Muhammadiyah. Namun mereka yang meninjau dengan teliti langkah-langkah yang diambil oleh para ulama terkemuka yang tergabung dalam NU, yang semenjak munculnya hingga saat ini, akan sependapat dengan Snouck Hurgronje babwa para ulama itu sebenamya telah melancarkan perubahan-perubahan yang fundamental, tetapi karena perubahan-perubahan yang dilancarkan itu demikian perlahan, rumit dan mendalam, walaupun terjadi di depan mata kita, tidaklah dapat terlihat dengan mudah. Bahkan dalam beberapa hal, para ulama itu melancarkan pembaharuan pemahaman ajaran-ajaran Islam yang "sangat" maju bila dibandingkan dengan kemampuan para pengikut mereka untuk dapat mengikutinya. Dapat dikemukakan di sini contoh tentang pemahaman kata hijab untuk memisahkan wanita dari lelaki dalam sebuah ruangan. Kata tersebut semula dipahami sebagai tabir yang menyekat antara kedua tempat lelaki dan wanita, tetapi pemahaman baru dari para ulama pembuat keputusan hukum membawakan arti pemisah (ha-il) tanpa adanya tabir fisik, sebagaimana jarak antara dua bangku atau tempat duduk. Pemahaman ini muncul dari kebutuhan menyediakan tempat yang terpisah antara siswa dan siswi dalam sebuah ruangan kelas yang sama. Demikian pula konsep barokah dengan ziarah kubur, yang dahulu dianggap diperoleh dari orang yang berada dalam lubang kubur itu, dengan pemahaman baru menjadi diperoleh langsung dari Tuhan dengan jalan mengambil hikmah dari siklus kehidupan dan kematian yang direnungkan dalam upacara ziarah kubur tersebut. Pengertian kekeramatan (karomah) yang tadinya bersifat supematural (dan bahkan occultist) kini diperbaharui pengertiannya menjadi kemampuan luar biasa untuk memandaikan murid-murid dalam kuantitas sangat besar, dan bahkan sekarang ini pengertian karomah itu sendiri lebih sering dihubungkan dengan kecintaan luar biasa dan kehadiran massal orang awam dalam upacara penguburan seorang tokoh agama. Hal ini dapat kita mengerti, bila kita sadar akan kedudukan kiai/ulama, yang oleh Geertz diakui memiliki kedudukan sebagai "perantara budaya" (cultural brokers) yang dianggapnya lebih banyak memiliki watak kepemimpinan yang sifatnya transisional, di mana para kiai itu berdiri di antara elite yang berwatak hidup kekotaan" (very urbanized elite) dan "kelompok petani tradisional di pedesaan" (very traditional peasantry). Dalam menerjemahkan aspirasi "budaya-kota" (urban cultures) yang mulai merembes ke pedesaan, para kiai "diharuskan" untuk dapat mencari dasar-dasar hukumnya yang seringkali merupakan hasil pemahaman baru terhadap ajaran-ajaran agama yang ada. Dunia pedesaan di Jawa dewasa ini mengalami penetrasi yang sangat intensif dari pola kehidupan kota. Struktur pekerjaan tidak lagi berwajah tunggal di bidang pertanian saja; pola-pola kehidupan baru sebagai pedagang, tukang, pegawai
negeri, anggota angkatan bersenjata, dan bahkan pembunga uang terasa semakin menguasai kehidupan pedesaan. Di samping itu dewasa ini terbuka kesempatan yang sangat luas bagi angkatan muda di pedesaan untuk mengejar karier setinggitinggmya di kota melalui jalur-jalur pendidikan politik dan sebagainya, sebagaimana terbukti dengan derasnya arus urbanisasi yang menimbulkan eksesekses luar biasa yang belum juga tertanggulangi hingga saat ini di segenap sektor kehidupan bangsa kita. Kalau diamati dengan cermat akan temyata, bahwa kelompok yang paling cepat mengikuti perkembangan keadaan dan mengisi kesempatan-kesempatan kerja yang timbul di pedesaan justru adalah kelompok pemuka-pemuka agama (religious elite) sendiri. Demikian pula, mereka lebih banyak memprakarsai perubahan pola berpikir, sikap mental, aspirasi, pandangan hidup, dan perubahan pola tingkah laku di pedesaan. Untuk selanjutnya pemahaman baru terhadap ajaran-ajaran agama yang berlaku tergantung kepada mereka. Keadaan ini menguntungkan,karena para pemuka agama akan mampu menyesuaikan pemahaman baru atas ajaran-ajaraan agama itu kepada perubahan baru yang mulai mereka anut. Tentu saja mereka tidak menerima begitu saja semua perubahan yang terjadi di luar; sebagai pimpinan masyarakat mereka akan berusaha mengendalikan dan mengarahkan perubahan-perubahan itu sesuai dengan prinsip prinsip seleksi, mana yang baik buat diri mereka dan masyarakat diambil, sedangkan yang dianggap "merugikan" atau "merusak" tatanan sosial serta "bertentangan" dengan ajaran-ajaran agama akan ditolak. Pada fungsi penolakan inilah sering terkumpul luapan emosi yang membuat eksplosifnya keadaaan seperti beberapa kali kita alami dalam tahun-tahun belakangan ini, sehingga terasa benar kebutuhan untuk lebih banyak menghindari persoalanpersoalan eksplosif itu. Proses seleksi yang bersifat menerima dan menolak (change and continuity process) ini secara subtil dirumuskan dengan indahnya oleh para kiai di pedesaan kita dengan istilah; "memelihara warisan lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik" (al-muhafadhatu alal-qodimis shalih ma'alakhdzi bil jadidil-ashlah). Seperti yang diuraikan di atas tidaklah mudah untuk melihat gerak perubahan yang dilancarkan para kiai/ulama mengenai sesuatu ajaran Islam. Berikut ini akan digambarkan sebuah contoh tentang ajaran Islam yang menyangkut hubungan antara guru dan murid di pedesaan-pedesaan di sekitar Jombang, yang mengalami perubahan asas yang sangat fundamentil karena adanya intervensi kehidupan politik, sosial dan ekonomi yang berasal dari kota. Kasus yang hendak dikemukakan ialah "berpindah-nya" beribu murid thariqah Qodiriyah Naqsyabandiyah di desa-desa sekitar Jombang, Kediri, Nganjuk, Malang, Gresik dan lainnya dari guru yang lama ke guru yang baru di Cukir, desa tempat pesantren Tebuireng berada. Menurut ajaran Islam yang telah dikembangkan dalam literatur keagamaan klasik dan ditanamkan oleh para kiai di pedesaan, dari murid dituntut kepatuhan yang mutlak kepada guru thariqah-nya. Hanya bila si murid tunduk dengan sepenuh hati, maka ia akan memperoleh barokah (grace) gurunya dan usahanya untuk mengenai kebenaran akan tercapai. Demikian mutlaknya kepatuhan murid thariqah kepada gurunya sehingga status sang guru harus diakui seumur hidup. Tak diperkenankan seseorang mengatakan bahwa kiai A atau kiai B adalah "bekas"
gurunya. Seseorang yang tidak mau lagi mengakui gurunya tetap sebagai guru sepanjang hidupnya, ia akan kehilangan barokah yang diperolehnya dari gurunya itu. Paham yang dikembangkan bahkan menganggap guru itu mempunyai kedudukan yang lebih utama daripada orangtuanya sendiri: Aba-uka tsalatsahur, abukal-ladzi waladaka, wal-ladzi zawwajaka ibnatahu, wa!-ladzi allamaka wahuwa afalaluhum" (bapa-bapamu ada tiga macam, yaitu yang memperanakkan dirimu, yang mengawinkanmu dengan anak gadisnya, dan yang mengajarimu ialah yang paling utama di antara mereka). Di dalam thariqah diajarkan, seorang murid haruslah pandai dan teliti dalam memilih guru/pembimbing (mursyid) agar tidak salah pilihannya itu, karena begitu ia memilih tidak lagi diperkenankan baginya untuk berganti guru atau pembimbing. Seorang murid yang walaupun hanya baru berpikir untuk berganti guru belaka, sudah terhalang (mahjub) hubungannya dengan Tuhan.
Ajaran ini sejak Islam datang di Indonesia dan berkembang selama kurang lebih lima abad telah tertanam dan tidak pemah "goyah", sehingga belum pemah timbul persoalan praktis di mana seorang atau banyak murid "terpaksa" harus pindah guru dan meminta fatwa hukum kepada para ulama tentang kepindahannya kepada guru lain itu. Tetapi dengan memisahnya beberapa ulama yang mempunyai pengaruh luas di pedesaan, dari lingkungan NU sejak pemilu 1977 akibat pengaruh pola politik, sosial dan ekonomi yang dilancarkan dari kota-kota, ribuan murid thariqah yang semula tidak pemah dihadapkan kepada persoalan "ingkar" dari gurunya, kini harus diberikan saluran hukum untuk dapat pindah guru yang dianggap lebih cocok dan sexual aspirasi politiknya. Tanpa adanya pemahaman baru terhadap asas ketaatan mutlak si murid kepada gurunya, maka sendi-sendi pokok yang mengatur hubungan antara mereka akan terancam sehingga merusak harmoni hubungan guru dan murid itu. Berbulan-bulan para ulama di daerah Jombang di hadapkan kepada persoalan hukum pindah guru thauqih dan mencari "rumusan" (nash)-nya dalam kitab-kitab yang diterima sebagai pegangan bagi ulama Ahli Sunnah wal-Jama'ah. Setelah empat kali sidang tidak juga ada seorang ulama vang dapat menemukan rumusan itu, maka dibentuklah tim khusus yang terdiri dari 6 ulama yang dipimpin langsung oleh Rais Am (otoritas tertinggi) NU untuk dapat menelurkan fatwa hukum vang berdasarkan mafhum (pemahaman baru) terhadap ajaran-ajaran agama yang terdapat di dalam kitab-kitab salaf tersebut. Sampai sekarang fatwa baru itu belum lagi berhasil dirumuskan secara formil, masih menunggu sekali atau beberapa kali sidang lagi. Namun, dari hasil sidang-sidang yang pemah dilakukan tersebut, ada kecenderungan para ulama peserta sidang untuk membuat koreksi atas paham yang selama ini berlaku bahwa ketaatan mutlak kepada guru dan larangan pindah guru, hanya berlaku bila guru memiliki pengetahuan ke-Tuhanan yang sempuma (tingkatan 'Arifin) dan memiliki wewenang mengajar dari guru yang sebelumnya secara ijasah lisan atau tertulis (tingkatan akhir), serta tidak "mengeksploitir" murid-muridnya untuk kepentingan sendiri baik yang bersifat materiil maupun yang lainnya.
Formulasi baru terhadap ajaran ketaatan kepada guru ini, benar-benar merupakan pemahaman yang sangat radikal karena dengan demikian diakui bahwa ada kiai di pedesaan sekarang ini yang tidak pantas diakui sebagai guru thariqah, pengakuan yang belum pemah ada dalam sejarah perkembangan Islam di Jawa. Sejak Islam masuk dan berkembang di Jawa sampai puluh-tahun (dekade) pertama setelah tercapainya kemerdekaan bangsa kita dari penjajahan Belanda, para kiai merupakan kelompok pimpinan agama yang kompak, mempunyai karisma kepemimpinan, kultur dan gaya hidup yang sangat serasi (highly homogenous) sehingga dapat dikatakan memiliki ciri-ciri kelompok yang oleh Durkheim ditandai oleh ikatan "solidaritas mekanistis" (mechanical solidarity), sehingga tidak ada persoalan adanya kiai yang "melanggar" moral agama dan lain-lainnya. Tetapi dengan semakin dipengaruhinya pedesaan oleh "budaya kota" (urban culture), semakin "kentara perbedaan-perbedaan tingkat" (highly stratified and differentiated) masyarakat pedesaan yang mengakibatkan kendomya homogenitas kulturil, pandangan hidup, gaya hidup, aspirasi dan sebagainya, sehingga para kiai pun tidak bisa lagi terjalin dalam satu ikatan kelompok yang tak terpecahkan. Ikatan kiai juga semakin ditandai oleh solidaritas organis daripada solidaritas mekanistis. Dengan terpecahnya kiai dalam kelompok sosial politik yang berbeda yang mau tidak mau menimbulkan kesenjangan sosio-kulturil antara guru dan murid, selanjutnya menimbulkan persoalan hukum dan kedudukan ajaran-ajaran Islam yang menyangkut hubungan antara guru dan murid. Dalam formulasi baru itu, seorang murid diberi peluang untuk tidak secara ketat tanpa reserve taat kepada gurunya dan pindah kepada guru lain tanpa disadari oleh si murid bahwa gurunya itu tidak memenuhi syarat-syarat sebagai guru. Barangkali, tanpa disadari oleh para ulama yang bersidang dan menyusun formulasi baru itu, pemahaman baru terhadap ajaran-ajaran Islam tentang hubungan guru dan murid ini merupakan pemahaman yang sangat radikal. Yang beliau-beliau sadari ialah: bahwa masyarakat sekarang sudah berubah. Demikian besamya perubahan itu sehingga bisa terjadi seorang guru menjadi tidak "pantas" untuk diikuti. ltulah sebabnya harus ada fakta hukum yang baru sesuai dengan perkembangan baru itu. Pengakuan akan kemungkinan guru melakukan kesalahan, adalah kebalikan dari diktum yang selama ini diikuti. "Ulama adalah pewaris Nabi" yang mengandung implikasi infalibilitas komunitas melalui kebenaran para pemuka agamanya. Namun dengan perkembangan baru yang dialami dunia pedesaan yang juga mengenai kalangan ulama, konsep ini memerlukan pula penyeragaman. Kasus lain yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini adalah tentang seorang lurah yang berhasil mendorong terjadinya pemahaman baru terhadap agama dengan jalan mengemukakan ajaran-ajaran yang tadinya belum diresapi oleh para penduduknya. Di sebuah desa, 2 kilometer di utara kota Jombang lurahnya adalah seorang yang cukup mendalam ilmu agamanya, karena ia lama dididik dan kemudian bertahun-tahun menjadi guru tetap di salah sebuah pesantren utama daerah Jombang, sebelum ia menjadi lurah kira-kira 25 tahun yang lalu. Di desa
tersebut, terdapat pemusatan lokal dari sebuah gerakan thariqah yang walaupun pengikutnya sedikit, memiliki tradisi yang lama dan berumur lebih dari seabad dengan pimpinan yang turun temurun dari bapak ke anak selama lima generasi. Warga desa tersebut yang menjadi pengikut gerakan itu memiliki kohesi yang kuat dan lingkungan yang tertutup untuk mereka sendiri, dengan hanya membuka pintu komunikasi minimal sebagai warga desa dengan pemerintahan desa mereka sendiri. Menjelang kemerdekaan bangsa kita, paguyuban thariqah lokal tersebut mulai membentuk usaha ekonomi yang mereka kuasai sendiri, dengan tidak mengajak kelompok lain. Usaha tersebut berupa berdirinya unit-unit pandai besi yang menggunakan peralatan kuno yang sederhana (antara lain: penghembus udara dari kayu dan tungku pemanas dari tanah liat) tetapi yang menghasilkan jenis-jenis produksi baru seperti jarum mesin jahit, gunting. Bahkan dalam masa perang gerilya mereka telah berhasil menggunakan alat-alat sederhana itu untuk membuat laras senapan dan rongga-rongga peluru buat gerilyawan menentang tentara kolonial. Sebagaimana juga halnya dengan gilda-gilda usaha yang dimiliki oleh ordo-ordo mistik Eropa di abad pertengahan,usaha mereka itu juga sangat bersifat tertutup dan tidak mau menerima jasa-jasa baik dari luar. Ketika kemajuan usaha meraka telah menjadi sedemikian rupa, sehingga mereka mampu membuat kerangka sepeda dari batangan-batangan pipa besi, keadaan sosial ekonomi mereka tetap menyedihkan. Langkanya organisasi ekonomi dan modal yang cukup membuat mereka amat bergantung kepada kemurahan hati para tengkulak di kota yang menyediakan bahan baku dan memasarkan hasil produksi mereka. Lurah desa tersebut, yang merasa prihatin terhadap keadaan ini dan ingin mengorganisir mereka secara ekonomis, selama belasan tahun berusaha dengan sia-sia untuk menyadarkan mereka akan perlunya organisasi tersebut. Kegagalan demi kegagalan untuk menembus paguyuban thariqah tersebut adalah karena ia dianggap sebagai orang luar dan tidak wajib dipatuhi sebagaimana halnya pemimpin gerakan mereka sendiri. Beberapa tahun yang lalu, lurah yang juga menjadi pemuka agama non-thariqah ini sampai kepada kesimpulan haruslah dicari pendekatan yang bersifat keagamaan kepada mereka. Iapun lalu memprakarsai dan memimpin pengajian umum mingguan yang diadakan secara bergilir di surausurau yang ada di desanya, termasuk surau-surau yang dikelola oleh paguyuban thariqah itu, sudah tentu dengan mengajak partisipasi pemimpin gerakan tersebut. Demikianlah muncul secara perlahan-lahan tetapi pasti tema-tema baru berupa ajaran-ajaran agama yang tadinya belum dikenal atau diresapi, seperti persesuaian antara pandangan hidup agama dan cara hidup rasionil, pentingnya arti persatuan untuk mencapai tujuan, pentingnya penerimaan terhadap pimpinan duniawi dan lain-lain yang positif. Ajaran-ajaran tersebut disajikan dalam rumusan dan konsepsi keagamaan yang mendalam, dan disarikan sumbemya dari literatur keagamaan dan thariqah yang telah lama diakui: akhimya, pendekatan yang mengemukakan ajaran-ajaran "baru" yang dianggap lebih relevan ini, sang lurah berhasil mendorong dan memprakarsai berdirinya koperasi produksi untuk menaikkan taraf hidup mereka, dengan jalan mengatur sendiri pemilihan bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Demikian berhasil pendekatan lurah tersebut, sehingga warga paguyuban thariqah yang tergabung dalam koperasi itu bersedia menerima orang luar (dalam hal ini Kepala SD Negeri setempat) sebagai ketuanya, dan
mengusahakan
kredit
modal
dari
pemerintah
daerah.
Proses itu, di mana bukannya terjadi perubahan penafsiran atas ajaran yang ada (seperti dalam kasus pindah guru di desa Cukir) melainkan terjadi pemunculan ajaran-ajaran "baru" yang dianggap lebih mewakili aspirasi agama secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan keadaan, oleh Geertz (1975) dilukiskan sebagai proses introspeksi ke dalam dengan implikasi luas dalam skala massal di Bali, terjadi pula sama kompleks dan rumitnya serta lamanya di desa ini, walaupun dalam skala yang kecil. Begitulah, pemahaman ajaran-ajaran Islam akan terus menerus mengalami pembaharuan sesuai dengan aspirasi yang terus berkembang di kalangan masyarakat yang memeluknya. Kejadian-kejadian seperti yang terdapat dalam kedua kasus lokal tadi terjadi pula dalam deretan tak terhitung di pedesaanpedesaan kita pada umumnya. Tujuan tulisan ini adalah mendorong kita semua untuk mengamati dan menyadari implikasi dari proses pemahaman kembali ajaranajaran agama yang ada, karena bagaimanapun juga proses itu secara keseluruhan akan menpunyai kaitan dengan kehidupan kita sebagai bangsa secara keseluruhan. Pendidikan Kita dan Kebudayaan Oleh: Abdurrahman Wahid Dipenghujung minggu lalu, penulis diminta menyampaikan sebuah makalah dalam seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Proklamasi (Unprok) di Yogyakarta. Karena sempitnya waktu, membuat penulis tidak dapat mempersiapkan sebuah makalah lengkap, seperti dikehendaki oleh penyelenggara. Makalah seadanya penulis sampaikan secara lisan dalam seminar itu, tanpa ditulis terlebih dahulu. Ini benar-benar makalah, karena kata tersebut diambil dari kata Bahasa Arab maqalah yang artinya apa yang diucapkan. Jadi berlawanan dengan papers yang secara tertulis disampaikan kepada panitia penyelenggara, jauh hari sebelum tiba saat disampaikan. Bahkan, kali ini justru panitia penyelenggara harus menuliskan makalah itu dari rekaman apa yang penulis katakan. Pada permulaan uraiannya, penulis menyampaikan pandangan, bahwa pendidikan nasional kita menyembunyikan sesuatu yang sebenamya dahsyat. Yaitu bahwa pendidikan nasional itu dinyatakan sebagai sesuatu yang memperhatikan keseimbangan (balance) antara aspek rohani dan aspek material. Namun dalam prakteknya kita main-main dengan keseimbangan tersebut, karena hal itu tidak pemah terjadi. Ini disebabkan oleh kenyataan, karena penguasaan filsafat positifisme, yang pada permulaan abad lampau diperkenalkan oleh John Dewey di Amerika Serikat, dalam sistem pendidikan kita. Akibat dari hal itu, lalu kita mengajukan klaim yang tidak ada buktinya, dan ini tentu terbalik dari apa yang ada di negeri-negeri maju. Di sana, soal-soal rohani adalah sesuatu yang ada,
walaupun
tidak
dirumuskan.
Kelangkaan akan keseimbangan seperti itulah yang menjadi capaian utama dari pendidikan nasional kita. pendidikan nasional yang demikian rancu akhimya mendorong kita utnuk menyatakan sesuatu yang tidak kita perbuat, alias menjadikan kita bangsa munafik, dalam bahasa populer, penulis sering menyampaikan dalam pengajian-pengajian umum bahwa pendidikan nasional yang kita miliki sekarang telah melahirkan banyak Profesor, Doktor, Sarjana S2, S1, serta MA kepanjangan dari MAling. Temyata, pendidikan nasional kita mengembangkan orieantasi kehidupan yang sangat tergantung kepada status. Kalau sudah memiliki ijazah yang dimiliki, harus dipertahankan sedemikian rupa baik benar maupun tidak. Inilah apa yang sering dinamai sebagai keadaan terdidik anak-anak kita. Bukankah orientasi pendidikan seperti itu, akhimya melahirkan manusia-manusia yang tidak mmentingkan arti moralitas, keculai hanya sebagai hiasan bibir belaka. Padahal, pendidikan yang baik sebenamya menginginkan capaian-capaian yang bersifat moral: hidup yang bersih, jujur, selalu ingat akan kepentingan bersama dan sebagainya. Dalam kenyataan, pendidikan nasional kita hanya menghasilkan manusia terdidik yang hanya memikirkan kepentingan sendiri, melalui status yang dapat dicapai. Maka hilanglah sebuah komponen yang mendewasakan anak didik, yaitu moralitas yang membuat kita selalu mengedepankan kepentingan bersama dalam capaian kolektif, yang harus terus menerus yang diperjuangkan. Orientasi kehidupan seperti inilah yang tidak ada dalam pendidikan nasional kita. Pendidikan seharusnya merupakan proses bertanya sepanjang hayat, bukanya tempat menghapalkan segala macam informasi yang diperoleh. Dalam kenyataan, pendidikan nasional kita justru menampilkan begitu banyak mata pelajaran, yang tidak selamanya berisikan informasi demi informasi yang selaras. Karena itu, kita tidak usah heran jika yang dihasilkan adalah manusia terdidik yang tidak mementingkan moralitas apapun, dan tidak merasa harus memperjuangkan kebenaran melalui apapun bentuk lahiriah dan tersuratnya. Hal itu tampak ketika KKN dan pelanggaran kedaulatan hukum tampak dilakukan oleh begitu banyak pegawai negeri, dan juga oleh penguasa-penguasa kecil. Memang sebenamya pendidikan nasional kita hanyalah sebuah proses yang senantiasa melupakan kenyataaan/ realitas sosial. Karenanya, rasa kebutuhan temyata membuat para orang-orang yang mengemudikan pendidikan nasional hanya mementingkan aspek-aspek teknologis dari proses belajar dan mengajar. Kebingungan ini akan menjadi semakin jelas, jika pendidikan nasional itu diproyeksikan kepada upaya mengembangkan kebudayaan. Akhimya yang terjadi hanyalah rumusan-rumusan formal tentang kebudayaan itu sendiri. Sebenamya kebudayaan kita merupakan cara hidup sebagai bangsa secara total, dalam tata pergaulan intemasional yang tidak hanya berdasarkan perkembangan teknologi saja, melainkan juga pengembangan bidangbidang kehidupan yang lain. Pada suatu kali, ketika penulis dan seorang sepupu berkendaraan mengitari
bundaran Hotel Indonesia dan melihat sejumlah orang wisatawan mancanegara (Wisman) menyebrang jalan dengan hanya bersandal, celana pendek dan kaos kutang (under shirt). Ia lalu bertanya mengapakah mereka yang di negara masingmasing berjas dan berdasi di sini berpakaian seperti itu? Penulis lalu menjawab, bukankah itu sama saja dengan anda sendiri yang menggunakan pakaian safari sewaktu bekerja di kantor, lalu hanya mengenakan kain sarung, bersandal jepit dan mengenakan kaos oblong di rumah? Artinya cara hidup kita sebagai manusia sopan disekat-sekat oleh masyarakatnya sendiri. Ada yang dalam entitas yang bemama kerja di kantor, istirahat di rumah, dan mengurusi kepentingan masyarakat. Jika dikaitkan dengan kondisi politik bangsa ini, sekat-sekat ini yang sering mencerminkan kepentingan golongan dan sebagainya, oleh masyarakat kita diterima sebagai kebenaran dalam hidup sehari-hari. Sebagai contoh dapat dikemukakan apa yang dituliskan seorang ahli filasfat kita sebagai bahasa semu (meta language). Bahasa semu itu menggunakan eufemisme (penghalusan bahasa), seperti kata diamankan untuk ditangkap. Akibatnya, masyarakat menjadi tersekat dan putus komunikasi antar kelompok, dan ini berakibat pada tumbuhnya budaya kekerasan (culture of violence). ***** Namun ada satu contoh dari pengembangan budaya melalui pendidikan, yaitu pondok pesantren. Dalam perencanaan arsitekturalnya, lembaga pendidikan ini menggunakan simbol-sombol budaya Jawa berupa wayang kulit. Melalui jalan masuk dari arah Timur kita sampai di tanah kosong (lapangan) di depan masjid di sisi selatan masjid itu, ada bangunan tempat tinggal (kombong; gotakan) para santri yang menjadi aspiran -salikun (pencari kesempumaan) pengetahuan dan moral agama yang benar. Di sisi utara masjid, terdapat bangunan tempat tinggal kyai -washilun- (orang yang sudah sudah mencapai pengetahuan/ pengenalan akan Tuhan). Kedua pihak itu bertempur di masjid, yang terletak di tengah bagaikan pandang Kurusetra, tempat para kesatria pandawa secara fisik bertempur melawan para Kurawa. Tentu saja, pertempuran-pertempuran para Kyai melawan santri-santri mereka tidak bersifat fisik, melainkan pergulatan menanamkan moralitas yang baik dalam diri sejumlah anak didik itu, dengan meberi contoh yang baik dan menanamkan kedekatan hubungan dengan masyarakat, terutama yang bertempat tinggal di dekat pondok pesantren. Inilah hakekat hubungan antara guru dan murid atas dasar moralitas. Dari kaca mata ini dapat diketahui mengapa ada pepatah: guru kencing berdiri murid kencing berlari. Dalam pandangan budaya Jawa lama, guru adalah digugu dan di tiru (didendangkan dan di contoh). Dalam kerangka hubungan seperti inilah terjadi pengambilan nilai-nilai yang baik, serta dibuangnya nilai-nilai yang buruk. Proses pendidikan yang mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan? Penyesuaian Ataukah Pembaharuan Terbatas Oleh Abdurrahman
Wahid
Dr. Azyumardi Azra, Rektor UIN Syarif Hidayatullah di Ciputat menjelaskan dalam
dialog dengan para mahasiswa di layar TVRI tanggal 26 Nopember 2002, tentang penyebaran Islam di Nusantara. Ia mengemukakan bahwa Islam disebarkan sejak berabad-abad yang lalu, di seluruh Nusantara dengan berbagai karya para ulama kita dalam pengajian-pengajian. Di antara nama-nama yang disebutkan, terdapat nama Syekh Arsyad Banjari dari Martapura, ia dikirimkan oleh salah seorang Sultan yang berkuasa di kawasan tersebut, dan belajar belasan tahun lamanya di Mekkah. Namun, ia kembali ke Tanh Air di abad ke-18 M, dan dikuburkan di Kelampayan, Martapura. Walaupun TVRI hanya menampilkan gambar istana Sultan di Martapura, namun sebenamya saat ini ada pesantren di Kelampayan yang memiliki santri (pelajar) berjumlah belasan ribu orang. Azyumardi Azra menyebutkan betapa besar jasa para ulama yang mengaji di Mekkah dan dan kembali ke Tanah Air, dalam dua hal: penyebaran agama Islam di kawasan masing-masing, dan penerapan ajaran agama. Islam secara lebih mumi ini adalah pengawasan seorang para pakar atas jalannya sejarah di bumi Nusantara. Ini haruslah dihargai, dan temuan-temuannya itu haruslah diteruskan oleh para peneliti sejarah Nusantara. Hanya dengan demikian, kita akan dapat mencapai mutu kesejarahan yang tinggi, karena didasarkan pada hasil-hasil kajian ilmiah yang benar tentu saja. Hasil-hasil kajian ini juga harus disiarkan kepada orang awan dengan bahasa yang mereka mengerti dan disiarkan melalui media khalayak. Apa yang dilakukan Azyumardi ini patut dihargai, karena dengan demikian ia telah menyajikan fakta-fakta sejarah kepada khalayak ramai. Ini bukanlah sesuatu yang kecil artinya, karena justru dengan cara demikianlah dapat dilakukan pendidikan masyarakat mengenai masa lampau negeri dan bangsa kita. Ini bahkan lebih besar jasanya daripada penyampaian hal-hal normatif yang sekarang mendominasi penyiaran kita. Karenanya, di butuhkan lebih banyak orang-orang seperti Dr. Azra ini, yang pandai menghubungkan dunia ilmiah dengan masyarakat awam kita. Katakanlah dalam bahasa kuis televisi: seratus untuk Pak Azra. Namun, tak ada gading yang tak retak, kalau meminjam sabda Rasulullah, dapat digunakan ungkapan berikut: manusia adalah tempat kesalahan dan kelalaian (Al insan mahallu al khatawa wal misyan). Ada sedikit kesalahan dalam penyampaian beliau akan sejarah masa lampau kita. Beliau menyatakan, bahwa banyak penyimpangan yang disebabkan oleh adat dan budaya kita dari masa sebelum itu, kemudian oleh ulama kita disesuaikan dengan hukum-hukum agama (fiqh) yang formal. Disimpulkan dari situ, bahwa mereka para ulama melakukan pemumian Islam. Justru dengan pemumian itulah dapat kita simpulkan, itu sebenamya adalah upaya untuk memelihara keabsahan ajaran-ajaran agama Islam di negeri kita. Dalam hal ini, apa yang diuraikan secara umum oleh Dr. Azra itu, berlaku untuk para ulama umumnya di kawasan ini pada masa lampau. Juga dengan percontohan mereka, seperti terlihat dalam pelaksanaan ahlak dan penerapan ibadah, mereka para ulama itu telah merintis ketaatan agama yang luar biasa pada bangsa kita, yang masih terpelihara sampai hari ini di hadapan pembaratan (westemisasi) yang dianggap sebagai modemisasi. Proses seperti ini, yang berjalan sangat lambat selama berabad-abad lamanya, sangat ditentukan oleh percontohan
yang diberikan elite kepada masyarakat kita. Inilah sebenamya yang harus kita ingat, karena kuatnya kecenderungan elite politik kita dewasa ini hanya untuk mengejar keuntungan pribadi/ golongan, di atas kepentingan bangsa secara keseluruhan. Hal yang dilupakan Dr. Azra, adalah menyebutkan juga fungsi lain yang dilakukan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dengan karyanya Sabil Al-Muhtadin (Sabilal Muhtadin), yang sekarang ini juga menjadi nama Masjid Raya/ Agung di kota Banjarmasin. Apa yang dilupakan Dr. Azra, adalah bahwa dalam karya tersebut Syekh Arsyad juga melakukan sebuah pembaharuan terbatas atas hukum-hukum agama (fiqh). Dalam karyanya itu, beliau menyampaikan hukum agama perpantangan. Hukum agama ini jelas memperbaharui hukum agama pembagian waris (fara-idh) secara umum. Kalau biasanya dalam hukum agama itu disebutkan ahli waris lelaki menerima bagian dua kali lipat ahli waris perempuan. Beliau beranggapan lain halnya dengan adat Banjar yang berlaku di daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dewasa ini. Dalam karyanya itu, beliau menganggap untuk masyarakat bersungai besar, seperti di Kalimantan Selatan, harus diingat adanya sebuah ketentuan lain. Yaitu, rejeki di kawasan itu adalah hasil kerja sama antara suami dan istri. Ketika sang suami masuk hutan mencari damar, rotan, kayu dan sebagainya, maka istri menjaga jangan sampai perahu yang ditumpangi itu tidak terbawa arus air, di samping kewajiban lain seperti menanak nasi dan sebagainya. Dengan demikian, hasil-hasil hutan yang dibawa pulang adalah hasil karya dua orang, dan ini tercermin dalam pembagian harta waris. Menurut adat pertentangan itu, harta waris dibagi dahulu menjadi dua. Dengan paroh partama diserahkan kepada pasangan yang masih hidup, jika suami atau istri meninggal dunia dan hanya paroh kedua itu yang dibagikan secara hukum waris Islam. Dengan demikian, Syekh Arsyad melestarikan hukum agama Islam (fiqh) dengan cara melakukan pembaharuan terbatas. Namun, pada saat yang bersamaan, beliau juga melakukan penyebaran agama Islam dan memberikan contoh yang baik bagi masyarakatnya. Inilah jasa yang sangat besar yang kita kenang dari hidup beliau, sekembalinya ke Tanah Air di kawasan Nusantara ini. Hanya dengan inisiatif yang beliau ambil itu, dapat kita simpulkan dua hal yang sangat penting: pertama, kemampuan melakukan pembaharuan terbatas, kedua berjasa mendidik masyarakat dalam perjuangan hidup selama puluhan tahun lamanya. Jasa dalam dua bidang ini sudah pantas membuat beliau memperoleh gelar, sebagai penghargaan atas jasa-jasa beliau yang sangat besar bagi kehidupan kita sebagai bangsa, di masa kini maupun masa depan. Jasa Syekh Arsyad di bidang pembaharuan terbatas ini, dapat disamakan dengan jasa Sultan Agung Hanyokrokusumo dalam dinasti para penguasa Mataram. Ia menetepkan bahwa tahun Saka, harus dimulai pada bulan Syura, dan bulannya berjumlah tiga puluh hari. Sultan Agung pun melakukan pembaharuan terbatas, hal yang sama juga dilakukannya atas hukum perkawinan-perceraian-rujuk yang
berlaku hingga saat ini, yang diambilnya dari hukum agama Islam formal (fiqh). Dengan demikian pembaharuan terbatas yang dilakukan kedua tokoh tersebut berjalan tanpa kekerasan, seperti yang diajarkan oleh agama Islam. Bukan dengan menggunakan kekerasan, apalagi terorisme seperti yang dilakukan sebagian sangat kecil kaum muslimin yang tidak terdidik secara baik di negeri kita saat ini. Sederhana, tapi rumit dalam pelaksanaannya bukan? Perbedaan dan Persamaan Budaya Kita Ketika berada di lapangan terbang Cengkareng Jakarta, saat akan menuju Surabaya, penulis bertemu dengan Letjen TNI (Pumawirawan) M. Maaruf, yang akan menuju ke tempat yang sama. Pada waktu akan naik ke pesawat terbang, kami berdua bertemu pengusaha Setiawan Djodi dan penyair W.S Rendra, dengan tujuan yang sama pula. Setiawan Djodi mengatakan kepada Maruf, jika SBY memenangkan pemilu, harus dijaga agar supaya ia tidak menunjuk seorang yang memiliki kadar gula darah yang tinggi untuk menjadi menteri. Jangan seperti sekarang sesorang dengan kadar gula seperti itu ditunjuk menjadi menteri, yaitu Rini Suwandi yang kadar gulanya sangat tinggi, yaitu 72.000 ton. Karuan saja, ucapan seperti itu menjadi bahan gurauan hingga ke tujuan yaitu lapangan terbang Juanda di Surabaya. Di tempat itu, kami semua berpisah jalan. Penulis menuju ke Jombang, sekitar 80 km jauhnya. Di kota kecil itu, penulis lalu bertemu dengan para akademisi sesuai dengan tugas penulis. Dengan lugas, penulis haus mengadakan rapat dengan para akademisi, tanpa ada guyonan dan candaan. Padahal, justru kota kecil Jombang merupakan asal mula banyak ungkapan-ungkapan jenaka dalam hidup kita. Di antaranya, candaan alm. Cak Durasim yang pemah menyatakan: Pagupon omahe Dara, Dijajah Nippon tambah Sengsara. Hal itu ia ucapkan ungkapan sebagai pantun ketika menari ngremo, yang dilakukan sebelum pertunjukan ludruk. Untuk itu, ia harus membayar mahal, disiksa Kempetai (polisi rahasia Jepang). Apa yang digambarkan di atas menunjukkan kekayaan budaya kita. Ada yang berbentuk budaya nasional seperti ungkapan Setiawan Djodi itu, ada pula yang berbentuk budaya daerah, seperti ucapan Cak Durasim. Nah, kedua-duanya mengungkapkan tingginya rasa humor kita sebagai bangsa. Demikianlah, tiap bangsa di dunia memiliki warisan humor yang tidak temilai harganya demi kelanjutan hidup bangsa itu sendiri. Demikian pula, suku-suku bangsa di negeri kita sendiri memiliki humor masing-masing. Tentu saja dengan menggunakan bahasa setempat yang beraneka wama. Bahkan, untuk menghubungkan berbagai daerah itu, ada pula budaya antar daerah dengan menggunakan bahasa daerah orang yang bercerita. Di sinilah terletak kemampuan suku-suku bangsa itu untuk hidup bersama. Seorang penumpang kereta api bersuku bangsa Sunda melihat orang berjualan nangka yang dibungkus dengan daun pisang di Stasiun Cirebon. Karena ingin makan nangka, ia pun berteriak memanggil penjual nangka itu dari jendela ketika berhenti:nangkana mas, dengan maksud mengatakan nangkanya mas kepada penjual nangka yang bersuku Cirebon itu. Si penjual nangka menganggap sang
penumpang meminta agar ia menyingkir dari tempat itu. Karena kata nangkana dalam bahasa Cirebon adalah ke sana. Karena itulah lalu ia mundur ke belakang. Bertambah keras teriakan penumpang kereta api itu, penjual nangka itu semakin menjauh dari tempat semula. Akhimya, nangka tak jadi dibeli karena karena api segera berangkat. Ilustrasi di atas menggambarkan salah pemahaman antara pihak-pihak yang berkomunikasi jika menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dari cerita itu dapat disimpulkan, betapa pentingnya faktor bahasa yang sama antar para warga negara kita yang memiliki bahasa daerah bermacam-macam. Karenanya, kita sebagai warga negara haruslah mampu berkomunikasi dengan sesama warga bangsa ini. Pada akhir masa 1990-an, penulis mengikuti penataran P4 selama 2 minggu di Jakarta. Angkatan penulis mengundang rombongan jenaka Srimulat dari Surabaya. Dalam pertunjukan, Asmuni setelah berbicara sendirian selama beberapa menit, didatangi Tarzan, yang memperkenalkan Asmuni kepada dua orang wanita yang datang bersama. Tarzan menunjuk kepada dua orang wanita itu. Pak Asmuni, saya perkenalkan anda kepada Indri dan Yayuk. Apa jawab Asmuni? Ia mengatakan, sudah kenal dengan kedua wanita itu, karena tadi datang dari hotel bersama mereka dalam satu mobil. Kekurang ajaran seperti diperlihatkan Asmuni itu, justru membuat para hadirin tertawa terpingkal-pingkal, karena disitulah terletak kelucuan mereka. Dengan demikian, nyatalah bahwa dalam sebuah humor antar budaya harus ada faktor korban dan yang mengorbankan. Esensi inilah yang ditangkap dalam sebuah komunikasi antar-budaya. Tetapi, kelucuan bukanlah satu-satunya unsur dalam komunikasi antar budaya itu. Faktor kemudahan mengelar sesuatu harus juga diperhatikan, seperti dalam tari-tarian. Demikian juga dengan karya bangsa kita, yang ragam bentuk lahiriyah dari komunikasi antar budaya daerah, sering terlihat dalam pagelaran nyanyian. Dalam sebuah acara nyanyian selama 2 jam, lagu-lagu dari berbagai daerah dibawakan oleh seorang penyanyi dengan iringan rombongan pemusik sebanyak 45 orang pemain yang mampu menghidangkan berbagai lagu daerah. Tentu saja banyak yang berkeberatan, karena hidangan gado-gado budaya seperti itu, tidak akan terasa mantap bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Tetapi hal ini justru menjadi lahan bertemu antara berbagai produk seni itu sendiri. Dengan demikian, kita merasakan sebagai warga bangsa yang sama. Inilah gado-gado yang menghidupi kita, dalam kehidupan yang bising ini. Mereka yang ingin mendalami seni daerah tertentu, haruslah belajar dan menghabiskan umur untuk itu. Dalam hal ini, nasionalitas mereka untuk sementara harus ditanggalkan, karena adanya anggapan bahwa adanya perbedaan-perbedaan yang menunjukan kelebihan kesenian daerah tertentu, dari kesenian daerah lain. Jadi, disinilah letak perbedaan antara seniman dan ahli seni daerah tertentu, bila dibandingkan dengan seniman atau ahli seni yang bersifat kebangsaan/nasional. Dengan tidak menyatakan diri sendiri sebagai ahli
seni daerah Aceh, penulis dapat juga menikmati tarian Seudati, yang dimaksudkan sebagai ekspresi rasa keberagamaan orang-orang daerah tersebut. Dalam hal ini, para pengamat sebuah seni daerah harus dapat memahami jalinan hubungan antara seni kebangsaan dengan proses sejarah. Umpamanya saja, bahasa dan sastra Arab bukanlah alat perubahan sosial di Indonesia, hal itu dicapai justru dengan bahasa nasional seperti temyata dalam perdebatan antara Sanusi Pane dan Sutan Takdir Alisyahbana pada tahun 1930-an. Sedangkan bahasa dan sastra Arab, sekarang hanya menjadi ekspresi rasa keberagamaan kaum muslimin belaka, dengan tetap mengambil bentuk tradisional. Dengan lagulagu dan sajak-sajak agama sebagai pilihan, kita tidak usah heran jika yang tampil adalah sesuatu yang tradisional. Inilah proses mengambil dan membuang yang mudah dikatakan namun sulit dilakukan, bukan? Peringatan yang Unik Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Kata peringatan dapat diartikan sebagai rangkaian kalimat untuk mengingatkan orang agar tidak melakukan sesuatu hal. Seperti peringatan: jangan memegang kabel listrik yang tidak terbungkus/telanjang. Tetapi kata peringatan dapat juga diartikan sebagai upacara memperingati sesuatu hal di masa lampau, yang penting untuk diketahui orang sekarang. Arti kedua inilah yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu peringatan hari tertembaknya Mahatma Gandhi di Raj Ghat, New Delhi. Puncak peringatan itu menghadirkan ratusan ribu manusia untuk memperingati kebesaran sang Mahatma. Karena diberi petunjuk oleh mendiang Ibu Gedong Oka, penulis menjadi pengikut ajaran Gandhi sejak tahun 70-an dan sejak dahulu memproklamirkan diri sebagai Muslim pengikut Gandhi. Karena ajaran-ajarannya, sangat bersesuaian dengan keyakinan Islam yang disandang oleh penulis. Dalam peringatan tahun ini, di samping penulis juga diundang mantan Presiden Jerman Richard Weizsaecker dan tokoh Afrika Salim Ahmed dari Tanzania. Tidak terhitung lagi tokoh-tokoh India di luar undangan, terutama mantan Presiden India Shri R. Venkataraman yang juga Sekjen Gandhi Smriti. Sementar seminar untuk peringatan meninggalnya Gandhi itu, dibuka oleh Perdana Menteri Vajpayee, dan salah satu sidang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri India I.K. Gujral. Dari luar negeri datang para tokoh-tokoh anti kekerasan, seperti Prof. DR. Glenn Paige dari Universitas Hawaii, dan tokoh-tokoh dari berbagai negara, termasuk dari Eropa dan Amerika. Pada hari pertama, semua hadirin diminta berdoa sejenak, dengan berdiam diri selama 2 menit tanda berduka cita atas kepergian tokoh anti kekerasan itu. Ratusan ribu orang memenuhi tempat upacara, menunjukkan penghargaan mereka yang sangat tinggi kepada mendiang Gandhi. Sebagai pengagum Gandhi, penulis tidak merasa heran akan arti demikian besar bagi perikemanusiaan atas kehadiran tokoh tersebut di atas panggung sejarah dunia. Namun, apa yang penulis saksikan jauh melebihi dugaan semula: di samping para tamu dari negeri-negeri lain hadir pula anak-anak harapan masa depan, yang juga merasa terpanggil untuk memuliakan tokoh tersebut. Ini berarti
ajaran yang dibawakan oleh sang perintis anti kekerasan (non-violence) itu memberikan bekasnya sendiri pada pandangan mereka yang masih berumur muda itu. Ini menjadi sangat penting, karena kontinuitas perjuangan sangat tergantung kepada kemampuan menegakkan mengalihkan perjuangan dari sebuah generasi ke generasi berikutnya. Hal alami seperti ini, temyata tidak mudah diwujudkan dalam kehidupan. Meskipun tinggal lah Gandhi berupa Trilogi (tiga ajaran): Ahimsa (Anti kekerasan), Satya Graha (Gerakan menuju perdamaian), dan Swadesi (Gerakan berdiri atas kaki sendiri). Penulis dengan tidak malu-malu menyatakan diri sebagai pengikut Gandhi. Ini tidak berarti penulis menganggap ajaran-ajaran seperti itu tidak ada dalam agama Islam. Namun untuk jaman modem ini, Islam tampaknya menyediakan beberapa hal yang kita perlukan, seperti kesetiakawanan (solidaritas) yang tinggi dan pengendalian nafsu peperangan dalam perebutan kawasan melalui tindakan-tindakan militer yang memperlemah kedudukan lawan. Lahimya keadaan yang bersandar kepada kekerasan itu juga ditentang habis-habisan oleh Gandhi. Karena itu sebagai salah satu cara untuk menunjukkan kepada dunia, masalah anti kekerasan yang memang sudah ada dalam ajaran-ajaran Islam perlu ditinjau kembali dan diperkuat kedudukannya. ***** Pada waktu pembukaan seminar mengenai ajaran-ajaran Gandhi yang terkait dengan perdamaian dunia saat ini, penulis menyatakan bahwa kecintaan tokoh tersebut kepada perdamaian dunia, tidak berarti Gandhi tidak menekankan pentingnya aspek-aspek lain dalam merumuskan perdamaian itu, melainkan ia secara aktif menekankan juga pentingnya arti keadilan dalam perdamaian dunia. Keadaan dunia serba damai, yang terlepas dari keadilan bukanlah keadaan yang dikehendaki Gandhi, karena itu perdamaian tanpa keadilan baginya merupakan ilusi, dan tidak akan berdiri kekal dalam mengatur hubungan antar manusia dan antar negara. Saat ini, keadilan berarti keharusan menengakkan pendekatan multilateral (pendekatan serba beragam), dan bukanya unilateralisme (keadaan sangat dipengaruhi oleh sebuah negara Adikuasa saja di dunia), seperti tampak dalam penyerbuan A.S ke Iraq. Kita memang harus cermat terhadap keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Kaitannya bahwa manusia harus memiliki kemampuan mewujudkan dunia modem lengkap dengan segala macam kerangkanya. Namun selalu dilupakan bahwa manusia justru hanya meminta perhatian yang konsisten dari struktur-struktur sosial yang ada, sehingga masing-masing individu tidak dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di sinilah letak perbedaannya dengan Gandhi, dengan kebesaran dan pandangan-pandangannya yang sederhana dan bukan merupakan teori yang muluk-muluk tentang perdamaian yang kekal untuk menata kehidupan secara baik, untuk diwujudkan di tingkat intemasional, bangsa, golongan hingga pribadi masing-masing. Dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana cara memintarkan anak sendiri dengan berbagai pengetahuan, kalau tidak ada keteguhan dan
stabilitas? Mungkinkah kedua hal itu tercapai, kalau perdamaian itu sendiri tidak dapat diwujudakn secara nyata? Hal ini diakui secara implisit oleh Undang-Undang Dasar kita. Kita menginginkan kemerdekaan, agar dengan itu kita dapat mewujudkan perdamaian. Perdamaian, baik dari tingkat dunia hingga pribadi, sangat diperlukan untuk dapat mencerdaskan suatu bangsa. Dengan kecerdasan seperti itulah kita akan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Karenanya, dengan segala upaya dan tenaga kita harus mewujudkan perdamaian baik tingkat dunia maupun ditingkat individu. Keadaan ini, yang oleh kitab suci AlQuran disebut sebagai negeri yang baik dan penuh pengampunan Tuhan (Baldatun taybatun wa rabbun ghafur), yang sering disebut-sebut dalam berbagai ceramah keagamaan. Ini berarti, di kalangan muslimin pun terdapat kesadaran mengenai perlunya kehidupan masyarakat yang diatur dengan baik, melalui akhlaq/etika yang mulia maupun melalui penularan IPTEK. Karena anpa IPTEK kita akan senantiasa terbelakang dan kecemburuan sosial yang diakibatkanya justru akan menganggu perdamaian itu. Dalam diskusi yang dipandu oleh penulis dan seorang lain dari Gandhi Smriti, yang menjadi moderator, temyata pendapat penulis tentang wawancara Gandhi tentang perdamaian yang disertai keadilan itu disambut hangat. Karena dari pembicara demi pembicara masing-masing memperoleh peluang 3 menit untuk menyampaikan pendirian, hanya sedikit yang berbicara mengenai hubungan antara perdamaian dan keadilan. Pada umumnya, puluhan orang yang berbicara itu mengajukan kritik tajam, dan juga melakukan otokritik terhadap diri sendiri, karena temyata tidak pemah dilakukan pengembangan pandangan mengenai ajaranajaran Gandhi itu sendiri. Dalam kesempatan itu juga disampaikan apakah relevansi ajaran Gandhi tentang sikap anti kekerasan (Ahimsa) terhadap kenyataan pahit, bahwa baik Pakistan maupun India, sama-sama menghabiskan biaya ratusan juta dollar A.S untuk program bom nuklir mereka? Hal-hal seperti itulah yang dikemukakan para pembicara dalam sesi terakhir berupa sidang-sidang komisi itu. Walaupun tidak diambil kesimpulan apapun, karena begitu banyak ragam pandangan yang justru memperkaya visi penulis dan para peserta lainnya akan kehidupan yang kita jalani dewasa ini. Seorang pembicara dari Gandhian Principles Institute di Washington DC, A.S menyatakan bahwa dalam 2 hari pembicaraan ia tidak pemah mendengar disebutnya istilah soul (jiwa), padahal inilah kunci untuk memahami pandangan-pandangan Gandhi. Dalam pendirian penulis, walaupun kata itu tidak pemah digunakan, namun ia merupakan kata kunci bagi tiap upaya untuk memahami pandangan Gandhi. Tergantung dari sikap kita masing-masing, untuk kita kembangkan pengertian yang benar tentang ajaran Gandhi, guna dirumuskan dalam berbagai reaksi atas perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia. Memang hal ini mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan? Perjalanan Romo yang Bijak
Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Pada malam itu kami bertiga mengobrol di halaman Candi Dasa, Karangasem, Bali. Ibu Gedong, Romo Mangun dan saya sendiri menjadi peserta diskusi bebas itu, yang berlangsung hampir tiga jam lamanya. Kami bertiga, saat itu, membicarakan masalah yang sederhana saja, konsep masing-masing tentang wali (saint). Dari perbincangan itu kami mendapati bahwa ada kesamaan di antara kami bertiga mengenai konsep wali, hanya istilahnya saja yang berbeda, yang satu menggunakan bahasa Sansekerta, satunya lagi bahasa Latin, dan yang lainnya bahasa Arab. Baik agama Hindu, Katolik, maupun Islam, memandang wali sebagai orang suci yang memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari orang lain, yakni pengetahuan metafisis melebihi orang biasa, ciri-ciri istimewa yang diberikan Tuhan pada mereka, maupun pengorbanan mereka pada kepentingan kemanusiaan. Persamaan pandangan inilah yang membuat kami bertiga saling menghormati dengan sepenuh hati. Bagi saya Ibu Gedong dan Romo Mangun lebih merupakan perwakilan dari dunia yang sama daripada perbedaan kami satu dari yang lain. Dari perjumpaan di Candi Dasa, lebih dari dua puluh tahun yang lalu itu, timbul rasa saling menghormati satu dengan yang lain. Saya tidak pemah memikirkan perbedaan dari Romo Mangun dan Ibu Gedong, melainkan justru persamaan antara kami bertiga yang selalu kami jadikan sebagai titik pandang untuk melakukan pengabdian kemanusiaan. Mungkin karena inilah sikap keterbukaan, saling pengertian, dan empati menjadi bagian dari hubungan kami bertiga. Bagaimanapun unsur yang mempersatukan kami bertiga jauh lebih banyak dari yang memisahkan. *** KETIKA saya berpindah dari Jombang ke Jakarta, segera saya melihat betapa dalamnya rasa cinta kasih Romo Mangun pada umat manusia. Hal itu tampak dalam sikapnya terhadap mereka yang nasibnya malang, pendidikannya kurang, dan mereka yang tingkat ekonominya rendah. Bagi mereka, Romo Mangun adalah hiburan yang menguatkan hati di kala susah, tetapi juga membawa harapan kemajuan dalam hidup. Mereka terdorong untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi karena simpati yang diperlihatkan oleh Romo Mangun dan kehangatan cinta kasihnya yang diberikan kepada sesama umat manusia. Sosok Romo Mangun adalah pribadi yang mampu memancarkan sinar kasih keimanan dalam kehidupan umat manusia. Dalam diri Romo Mangun, keimanan tidak sekadar terbelenggu dalam sekat-sekat ritual agama atau simbol-simbol semata. Lebih dari itu cinta kasih keimanan Romo Mangun mampu menembus sekat-sekat formalisme dan simbolisme. Dia kasihi dan dia sentuh setiap manusia dengan ketulusan cinta kasihnya yang terpancar dari keimanan dan keyakinannya. Inilah yang menyebabkan Romo Mangun mampu hadir dalam hati setiap manusia, karena dia telah menyentuh dan menyapa setiap manusia.
Hal itu, tidak hanya tampak dalam kehidupan sehari-hari, melainkan juga dalam karya tulisnya. Kombinasi antara keterusterangan, kecintaan pada manusia, dan kepercayaan yang teguh akan masa depan yang baik merupakan modal utamanya. Hal ini tidak hanya tampak dalam karya-karya sastranya melainkan juga dalam kupasan-kupasannya mengenai sejarah modem bangsa kita dalam kolomkolomnya. Karya-karya tulis itu memperlihatkan keagungan jiwa manusia yang tahu benar apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga tentang kehidupan yang menderanya dan janji kehidupan lebih baik yang menunggunya di masa depan. Prinsip-prinsip di atas tampak dalam novel-novel yang ditulisnya, terutama tentang masyarakat Jawa masa lampau. Dunia Roro Mendut dan Pronocitro dalam kupasan Romo Mangun yang sangat tajam, temyata adalah dunia kita juga dengan segala kemelut dan permasalahannya. Ketegaran jiwa Roro Mendut adalah juga ketegaran jiwa Romo Mangun yang memperjuangkan kemerdekaan umat manusia atau yang menentang militerisme. Keyakinannya akan proses memberikan keyakinan padanya bahwa setiap zaman membawakan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan oknumoknum ABRI dikupasnya dalam berbagai kolom bersama-sama kepengecutan sebagian perwira maupun ketololan sejumlah politikus. Semua itu dia sajikan dengan bahasa yang halus namun tajam. Sindiran-sindirannya membuat setiap orang yang berpikiran cerdas dan peka merasa malu. Dalam hal ini, seolah Romo Mangun menjadi wakil masyarakat yang terlupakan dan tertinggalkan. Di samping ketajaman batin dan kepekaan nuraninya yang tinggi, sosok Romo Mangun juga menjadi simbol kesederhanaan. Sebagai seorang tokoh yang sudah bertaraf intemasional, Romo Mangun tidak pemah menampakkan sikap ketokohannya dalam performance dan penampilannya. Sikap glamour dan berlebihan hampir tidak tampak dari Romo Mangun. Sikapnya yang demikian seolah mengajarkan kita akan pentingnya makna kesederhanaan dan pentingnya pengekangan diri untuk tidak hanyut dalam setiap predikat yang disandang dan prestasi yang diraih, apalagi kedudukan. *** KINI Romo Mangun telah tiada. Kita kehilangan salah seorang tokoh humanis, seorang kritikus sosial yang andal sekaligus seorang pejuang agama yang gigih. Dunia terasa kosong tanpa kehadirannya. Akan tetapi, kita yakin akan datangnya seorang yang memperjuangkan cita-citanya. Kita semakin kaya dengan pengabdian dan karya-karyanya semoga kita akan semakin bertambah kaya dengan pengganti-penggantinya. Terima kasih Romo Mangun dan selamat jalan. Cita-cita dan perjuanganmu menjadi lentera dan cambuk bagi kita di sini.
Perjanjian dengan Setan Oleh Abdurrahman
Wahid
Di tahun-tahun lima puluhan, beredar terjemahan noveler Damon Runyon, Hantu dan Daniel Webster. Isinya tetang seorang Amerika abad lalu yang menggadaikan jiwanya kepada setan agar berhasil gemilang dalam profesi. Diakhir masa gadai, sang setan datang untuk menagih : orang itu harus hidup dalam bentuk lain. Menjadi kupu yang ditaruh dalam sebuah tabung, mengutuki nasibnya yang jelek, menjadi hamba setan. Untungnya, melalui berbagai argumen dalam perdebatan antara pembela hukumnya - Daniel Webster - dan sang setan, dalam sebuah peradilan spiritual yang unik orang itu akhimya dibebaskan dari sanksi. Bagi kita, penggadaian jiwa kepada setan bukan dongeng aneh. Sekian banyak kepercayaan akan pesugihan sudah menjadi pengetahuan umum - dari soal monyet di Gunung Kawi, yang dikatakan penjelmaan dari mereka yang dulu dianugerahi kekayaan luar biasa, hingga babi jadi-jadian yang konon kembali menjadi manusia dikala mati dibunuh orang. Juga tuyul, yang kemarin dipopulerkan itu. Menarik, bangsa-bangsa Barat pun memiliki perbendaharaan cerita seperti itu, seperti dibuktikan Damon Runyon dalam noveletnya (cerita-pendek panjang) yang tadi. Tetapi ada perbedaan mendasar dalam pendekatan kepada materi pokoknya. Kepercayaan bangsa kita itu menunjukkan sikap pasrah kepada intervensi supranatural: paling jauh hanya mengambil intisari moral dari cerita atau kepercayaan itu, yaitu imbauan agar kita tidak menggadaikan jiwa kepada setan. Para penulis Barat, Seperti Damon Runyon tekanannya justru pada upaya membebaskan diri dari sanksi hukum setan. Ini tentu dibawakan oleh nilai yang melandasi sikap hidup yang berbeda. Kita tidak mementingkan kebebasan manusia, sebagai peperangan,dari cengkeraman nasib, karena kita memang berwatak pasrah. Manusia Barat setidak-tidaknya sebagai prototipe justru menghardik nasib dan merebut inisiatif dari tangannya. Karenanya, setan pun harus di lawan. Sikap berani menentang surtan takdir seperti itu sudah tentu tidak tumbuh dalam sekejab : ia merupakan hasil perjalanan sejarah panjang. Pun bukan merupakan sikap terbaik yang dapat dirumuskan manusia bagi hidupnya, karena sekularisme yang dihasilkannya juga membawakan krisisnya sendiri kepada manusia Barat saat ini. Namun, tak dapat diingkari Manusia Barat berwatak ingin menentukan nasibnya sendiri, bebas dari campur tangan siapapun juga. Dalam perjalanan kian-kemari, penulis menonton di sebuah tempat sebuah filem menarik, dengan tema seperti itu. Film berjudul Oh God, You Devil menampilakan gambaran baru dari tema lama damon Runyon di atas. Hanya saja penyelesaiannya idak dilakukan melalui sidang pengadilan spiritual.
Seorang musikus, yang belum berhasil mengangkat karier dalam usia 30 tahun, bertemu dengan sang setan. Makhluk ini berkuasa ini tampil dalam sosok seorang agen yang menjanjikan promosi serba tuntas bagi sang musikus. Dalam keputsasaan akibat kebuntuan karier, si musikus menerima keagenan setan atas dirinya. Maka ia pun ditukar secara fisik, dengan seorang penyanyi rock sangat tenar - yang sudah sampai masa perjanjian nyadengan sang setan. Jiwa mereka bertukar tempat, alias bertukar raga. Bintang rock tenar menjdi musikus yang mendampingi istri musikus yang tak majumaju itu, tanpa sang istri menyadarinya. Sang musikus lokal, sebaliknya, langsung menjadi bintang tenar, dengan segala kesenangan hedonistiknya. Itu berjalan cukup lama. Namun, kemewahan berlimpah yang dimilikinya tidak dapat melupakannya dari kenangan kepada istrinya. Ketika suatu ketika ia nekat mengintip sang istri makan di restoran kesayangan mereka berdua, didampingi musikus yang dulunya bintang rock tenar itu, tak dapat lagi dicegah keinginannya untuk membebaskan diri dari pengendalian setan. Dan dalam kekalutan jiwa itu ia berupaya mencari Tuhan. Dan Tuhanpun muncul -dalam personifikasi seorang pengkhotbah sederhana, dan kemudian lagi, seorang penduduk desa yang bersahaja. Karena kesungguhan mencari Tuhan itulah maka sang Tuhan berbentuk manusia itu merasa belas kasihan. Lebih-lebih, karena sewaktu musikus-lalu-bintang rock terkenal itu masih anak-anak ayahnya pemah bekerja menanamkan kepercayaan dan cinta kepada Tuhan dan sesama. Tuhan berterima kasih kepada ayahnya itu dengan jalan menolong diri musikus-lau-bintang-rock-tenar itu. Pertolongan Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk sangat unik. Kedua personifikasi Setan dan Tuhan bertanding dalam permainan poker. Taruhannya: kalau setan menang, bintang rock tenar akan tetap dikuasainya: kalau sebaliknya ia akan diperbolehkan menjadi musikus sederhana. Temyata, Tuhan menang ( bagaimana Tuhan dapat digambarkan kalah?) dan bebaslah sang makhluk dari cengkeraman setan. Caranya ? Sang bintang rock tenar bunuh diri - dengan obat terlarang, dalam dosis berlebihan. Jiwanya keluar, menjelma menjadi musikus semula. Kebetulan musikus yang menempati raganya sebelum itu bertugas meliput kegiatan bintang rock tenar itu sebelum kematiannya. Jiwa dipertukarkan. Bintang rock tenar dipulangkan sukmanya ke neraka, untuk memenuhi perjanjiannya dengan setan. Sang musikus langsung pulang ke rumah kedalam kebebasan, ke dalam kekurangan dan kemelaratan. Tetapi juga kepada istrinya yang dicintainya, yang tengah mengandung tua dari benihnya dahulu. Kandungan tua istrinya itulah yang menyebabkan ia berontak dari kemewahan dan mencari pertolongan Tuhan untuk menjadi musikus miskin. Siklus kehidupan yang positif : kembalinya sang pengembara, yang menyadari bahwa kemewahan tidak sebanding nilainya dengan kebebasan diri sebagai insan.
Perjuangan Pribadi dan Perjuangan Kolektif Oleh: Abdurrahman
Wahid
Ketika terjadi penyanderaan atas ratusan orang Rusia oleh para pejuang muslim Chechnya di Moskwa. Mereka melakukan hal itu, karena ingin mendirikan sebuah negara Islam di kawasan tersebut, yang ditentang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam penyanderaan tersebut, serta dalam tindak kekerasan dahulu pejuang-pejuang Islam di Chechnya itu berhasil membuat matinya ribuan warga negara, yang oleh Rusia dianggap sebagai warga negaranya. Ini menimbulkan pertanyaan benarkah yang terjadi itu sebuah pembunuhan masal, ataukah harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan kemerdekaan? Kalau kematian itu dianggap sebagai korban pembunuhan massal, sudah tentu harus dilarang menurut pandangan Islam. Sebaliknya, jika jatuhnya para korban itu, baik di pihak orang-orang Rusia yang non-muslim maupun para pejuang Chechnya sendiri, sudah tentu sesuai dengan perintah kitab suci Al- Quran, untuk mengorbankan nyawa sebagai pengabdian kepada Allah (syuhada fi sabillillah). Ini adalah sebuah kewajiban dalam Islam, kalau dilakukan dalam kerangka perjuangan kolektif dan tidak bersifat individual/perorangan. Perjuangan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol dan Teuku Umar di Aceh merupakan beberapa buah contoh dalam hal ini. Karenanya, kita harus mengetahui motif pokok (lead motif) dari sesuatu kejadian. Perjuangan para syuhada ini tentu harus dibedakan dari tindak kekerasan yang tidak memiliki lead motif seperti itu. Kita lihat, banyak tindak kekerasaan yang dinyatakan sebagai perlawanan perjuangan seperti itu, temyata berangkat dari motif yang lain. Perselisihan yang dianggap untuk kepentingan umum itu, temyata hanya bermotif perorangan belaka, karena itu tidak dapat dianggap sebagai tindak perjuangan yang bermotifkan agama, karena hanya dijadikan kedok belaka bagi motif pribadi. Dalam keadaan demikian, tindakan itu dapat dianggap gangguan keamanan yang membahayakan kehidupan masyarakat sering disebut sebagai terorisme. Karena itu jelaslah, garis batas antara perjuangan dan terorisme sangatlah tipis, yaitu dalam melihat motif yang mendorongnya. Karena itu, kita dapat mengerti apa yang dapat dilakukan oleh pejuang muslim di Chechnya, walaupun belum tentu kita dapat menerimanya. Penulis beranggapan, jika Putin bersedia memberikan otonomi khusus kepada Chechnya atau kaum muslimin di kawasan tersebut, mereka akan memperoleh hak-hak khusus. Maka perjuangan mereka di Chechnya dapat dilakukan melalui negosiasi, sudah tentu ini menyangkut kenyataan bahwa perlindungan hukum dan politik harus diberikan kepada para pejuang tersebut tanpa pandang bulu, sebagai syarat permulaan. Selama hal itu tidak ada, perjuangan bersenjata oleh para pejuang muslim itu dapat dianggap sah menurut pandangan Islam. Nah, pemberian hak mendapatkan perlindungan hukum atas pejuang Islam itu, adalah sebuah tindakan politik yang harus di lakukan oleh Putin, jika diinginkan penyelesaian cepat atas kasus tersebut.
Tapi ini adalah sebuah proses sejarah timbal balik, antara pemerintah Rusia dan para pejuang muslim di Chechnya. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai, yang masing-masing memiliki komplektisitasnya sendiri. Belum tentu pihak tentara Rusia maupun kalangan intelnya menyetujui sikap (suka mengalah) orang-orang Chechnya itu, demikian pula para pejuang muslim. Tidak semua sependapat, perjuangan bersenjata harus digantikan dalam perjuangan damai. Untuk mematahkan mata rantai sikap garis lurus itu tentu tidak mudah pada kedua belah pihak. Karenanya, kita hanya dapat melihat saja apa yang terjadi dikawasan tersebut dan mengharapkan hal baik baginya. Tentu saja pemerintah Rusia mengambil sikap formal, dengan jalan (membebaskan) dengan paksa; setelah pembicaraan gagal mencapai hasil, dengan korban yang sangat besar. Bahkan tokoh-tokoh Chechnya seperti Deni Steps, mengeluarkan pemyataan menentang langkah-langkah penuh kekerasan yang dilakukan para penyandera itu. Dengan kata lain, keseluruhan pendapat umum diarahkan oleh pemerintah Rusia guna memandang tindakan tersebut sebagai terorisme. Kalau langkah ini berhasil, dengan sendirinya aspirasi para pejuang muslim Chechnya itu tidak berhasil, dengan demikian yang terpakai bukanlah anggapan tindakan yang mereka ambil itu sebagai langkah perjuangan. Kalau memang jumlah para pejuang itu sangat sedikit, dengan sedirinya mereka tidak mewakili kaum muslimin dikawasan itu. Dengan demikian apapun yang mereka perbuat dianggap sebagai terorisme terlepas dari aspirasi mereka sendiri. Ini adalah resiko yang harus diperhitungkan benar oleh para pejuang Islam yang ingin menggunakan kekerasan sebagai modus. Kalau hal ini tidak disudahi, yang akan merugi bukanlah para pejuang itu sendiri dan mayoritas kaum muslim yang ada dikawasan tersebut, keseluruhan mereka akan dipandang sebagai teroris oleh siapapun, tanpa dapat dibantah. Ini, jugalah masalah yang dihadapi oleh para pejuang muslim di negeri kita. Sebagian dari mereka yang menginginkan Negara Islam, sebagian kecilnya ingin menggunakan kekerasan untuk mewujudkan hal itu. Karena jumlah mereka kecil, sedangkan mereka tetap berkeras akan melakukan tindak kekerasan, dengan sendirinya mereka lalu dinyatakan sebagai teroris oleh pembentuk pendapat masyarakat, sedangkan dalam hati mereka adalah para pejuang agama Islam. Untuk sekarang ini, tidak ada cara menentukan benarkah mereka atau tidak? hal itu baru diketahui setelah hasil pemilihan umum yang akan datang. Karenanya, seharusnya kita tidak gegabah memperjuangkan ajaran-ajaran Islam di bumi Nusantara dengan cara menggunakan kekerasan, minimal sampai dengan diumumkannya hasil-hasil pemilu yang akan datang. Hal ini untuk membuktikan apakah para pengguna kekerasan itu mendapat dukungan kuat dalam pemilu itu, walau secara moral sikap itu salah, tetapi secara politis itu terjadi. Memang, terjadi perbedaan antara yang bersikap moral di satu pihak, dan bersikap politis di pihak lain. Tetapi itulah kenyataan politik yang diterima, tindakan tidak bermoral, seperti melengserkan penulis dari jabatan Presiden, tetap dapat berlaku secara politis, sebagai fakta kehidupan. Tetapi ada fakta lain yang harus diperhitungkan juga, yaitu hasil-hasil pemilu. Karena itu, marilah kita tunggu hasil pemilu itu, guna
menentukan mana yang benar antara sikap moral atau sikap politis. Sebenamya, itu masalah yang harus dihadapi, itu adalah suatu yang sederhana saja, bukan?. Perlukah kita Ber KB? Telaah Kritis Rencana Pembubaran BKKBN Oleh: Abdurrahman
Wahid
Baru-baru ini sewaktu penulis naik pesawat terbang dari Surabaya ke Jakarta, ada petinggi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendatangi penulis dan meminta didoakan semoga BKKBN tetap ada. Penulis bertanya, siapa yang ingin membubarkannya? Ia menjawab Wakil Presiden Hamzah Haz. Penulis bertanya lagi, mengapa? Jawabnya, karena Wapres berpendapat tidak perlu ada BKKBN, bukankah Tiongkok berpenduduk 1,3 milyar jiwa, sedangkan wilayahnya hampir sama dengan negara kita. Mengapakah kita yang baru berjumlah 200 juta jiwa lebih sedikit, harus ber KB? Ini tidak masuk akal, karenanya BKKBN harus dibubarkan, karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, dan bukan merupakan kebutuhan kita. Hamzah Haz mengemukakan tidak perlu ber-KB itu karena ia tidak mengerti betul keadaan yang terjadi di Tiongkok. Kedua, karena ia tidak mengerti arti keluarga berencana. Begitu juga, ia tidak mengerti bagaimana para ulama ahli hukum Islam (Fiqh), sampai kepada kesimpulan dan mengeluarkan keputusan (fatwa) menghalalkan Keluarga Berencana. Sangat mengherankan seorang pejabat tinggi seperti Hamzah Haz tidak mengerti dan memahami hal tersebut. Mungkin karena ia memiliki lebih dari seorang istri dan memiliki belasan orang anak. Kalau jargon banyak anak, banyak rezeki menjadi kebiasaan bagi bangsa kita, akan celakalah kita sebagai bangsa, karena yang sekarang-pun, dengan jumlah penduduk 200 juta jiwa lebih, kita sudah menghadapi krisis ekonomi yang luar biasa, yang oleh Hamzah Haz sendiri belum dapat di pecahkan. Dalam tulisan ini, penulis akan mengemukakan keadaan sebenamya di daratan Tiongkok, kemudian kita lihat mengapakah mereka dapat berjumlah 1,3 milyar jiwa, dan mengapa para ahli Fiqh menyatakan boleh tidaknya ber-KB dari sudut pandangan agama Islam bagi bangsa kita. Harus ada kejelasan dalam hal ini agar kita tidak melakukan kesalahan dengan membubarkan BKKBN tanpa alasan yang jelas. Sikap Hamzah Haz sebagai pejabat tinggi pemerintahan sangatlah penting untuk masa depan kita sebagai bangsa, walaupun dia sendiri tampaknya tidak mengerti persis duduk masalah yang sebenamya. Sama seperti ketika ia menerima di kantomya (Istana Wapres), Senator AS dari Partai Republik Daniel Inoute, yang mewakili daerah pemilihan Hawai dan Senator Steven dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan itu, sang Wapres menyatakan kepada para Senator itu, bahwa mereka duduk di kursi tempat sang Wapres sebelumnya menerima orang-orang yang diduga teroris. Nampak ia tidak menguasai persoalan yang di hadapi. ***** Yang tidak diketahui Hamzah Haz, adalah kenyataan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) juga menjalankan KB. Bentuknya, yaitu seorang suami dan seorang istri
-jadi dua orang- hanya boleh memiliki seorang anak saja. Seluruh bangsa dan negara Tiongkok menjalankan hal itu, sehingga mustahil rasanya mereka tidak melakukan KB, dengan kata lain kesadaran beranak seorang saja bagi bangsa tersebut. jelas karena pemerintah Tiongkok menghendaki hal itu terjadi. Bangsa Tionghoa di masa lampau, sangat bangga dengan anak-anak mereka, Kalau kebanggan ini dapat dihilangkan, dan dapat diganti dengan kebanggaan memiliki seorang anak saja, ini menunjukkan adanya rekayasa sangat besar yang hanya dapat dilakukan oleh sebuah pemerintah yang kuat. Dengan demikian, ucapan Hamzah Haz, bahwa tidak ada KB di Tiongkok adalah pendapat yang naif dari orang yang tidak mengerti duduk persoalan yang sebenamya. Sangat menyedihkan, bahwa pendapat seperti ini dikeluarkan oleh seorang pemimpin negara. Seharusnya partai yang dipimpinnya (PPP) melakukan koreksi, kalau tidak dihinggapi ketakukan kepada tokoh ini. Kita memang sangat menghormati kemampuan RRT untuk menekan laju pertumbuhan penduduk saat ini. Kalau sepasang suami istri digantikan oleh seorang anak dalam waktu satu generasi (berlangsung sekitar 30-40 tahun belaka ), maka dalam waktu satu generasi saja pertumbuhan penduduk Tiongkok akan mengalami penurunan puluhan juta orang. Ini akan berlangsung terus, hingga pada akhimya penduduk Tiongkok akan berada pada angka di bawah 1 milyar jiwa. Bukankah ini merupakan pelajaran berharga bagi kita, yang setiap tahun penduduk meningkat 3,5 juta orang. Kalau dibiarkan tanpa KB, penduduk kita akan bertambah 7 juta jiwa tiap tahun, berarti dalam 10 tahun yang akan datang, penduduk negeri ini akan bertambah 77 juta jiwa. Bukankah jelas, Hamzah Haz tidak mengerti duduk persoalan sebenamya, dan dengan enak menganggap RRT tidak ber-KB. Pemyataan Hamzah Haz, bahwa negeri Tiongkok saja sekarang mampu menghidupi 1,3 milyar jiwa, merupakan sebuah kenyataan yang harus dicermati kembali. Yaitu kenyataan, bahwa Tiongkok terdiri dari tanah daratan belaka, dengan wilayah laut mengepungnya. Hal ini berbeda dengan Republik Indonesia, yang memiliki wilayah laut, air lebih dari separuh daerahnya. Itupun penyebaran penduduknya berjalan tidak merata, contohnya pulau Jawa -luas pulaunya hanya sekitar 7 % dari seluruh wilayah Indonesia- namun memiliki jumlah penduduk lebih dari separuh seluruh warga negara Indonesia. Sementara kita memiliki ribuan pulau yang tidak berpenduduk, sehingga persoalan utama kita sebagai bangsa adalah bagaimana menyebarkan penduduk ke pulau-pulau di luar Jawa. Untuk itulah diselenggarakan program transmigrasi. ***** Dari tahun 1973 hingga 1975, Menteri Agama Dr. A. Mukti Ali mengundang 7 orang ahli Fiqh untuk bersidang beberapa kali, guna membicarakan gagasan keluarga berencana. Sebelum itu, gagasan tersebut disebut sebagai program pembatasan kelahiran. Masalahnya, reproduksi manusia adalah hak Allah Yang Maha Kuasa, jadi manusia tidak dapat mengambilnya sebagai hak mereka. Karena itu, diputuskan oleh ketujuh orang ahli Fiqh untuk mengganti program pembatasan kelahiran menjadi gagasan perencanaan keluarga. Ini berarti, alat-alat dan metoda
yang digunakan dalam program itu tidak boleh bersifat mematikan kemampuan melahirkan pada pasanagan suami-istri. Kondom, IUD (seperti spiral dan sebagainya) serta obat-obatan dan alat yang digunakan hanya bersifat temporer dan tidak meniadakan reproduksi manusia yang haknya ada di tangan Tuhan. Jika metoda dan alat-alat tersebut ditinggalkan maka diperkirakan sang ibu akan hamil lagi, jika berhubungan seksual dengan sang ayah saat di bawah usia menopause. Seharusnya, pengetahuan dasar seperti ini sudah dimiliki oleh semua pegawai negeri dan pejabat pemerintahan di negara ini. Justru yang sangat mengherankan adalah seorang dengan kedudukan sebagai Wapres seperti Hamzah Haz tidak mengerti masalah ini. Lalu, bagaimana kita menjelaskan ketidaksetujuannya terhadap gagasan Keluarga Berencana dan keinginannya membubarkan BKKBN. Demikian pula, kita tidak mengerti mengapa partai yang dipimpinnya tidak meminta mengajukan sanggahan terhadap Hamzah Haz, ditambah lagi sikap diam Megawati Soekamoputri yang tidak memberikan penjelasan apakah BKKBN benarbenar dibubarkan atau tidak. Sebaliknya, justru terlihat kemunduran sangat besar akan pelaksanaan KB dalam tahun-tahun terakhir ini. Hal ini karena pihak-pihak yang menyebarkan gagasan KB justru melemah, baik dalam jumlah maupun kegiatan, akibatnya dalam beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan penduduk kita kembali menjadi tidak terkendali seperti sebelum ada BKKBN. Dan sekarang, datanglah Wapres Hamzah Haz dengan gagasan membubarkan BKKBN. Sikap itu, justru akan memukul negeri kita. Entah jika Hamzah Haz memang mengharapkan bangsa kita tinggal di perahuperahu dan mencari makan di laut, karena pulau-pulau di Indonesia sudah tidak dapat menampung jumlah mereka. Alangkah sangat menyedihkan kualitas para pemimpin negara kita dewasa ini. Temyata sangat sulit memiliki pemimpin yang bermutu. Persaingan di Bawah Justru Lebih Hebat Oleh Abdurrahman
Wahid
Persaingan antarelite di dalam tubuh pemerintah negara manapun di dunia selalu akan terjadi. Faktor-faktor penyebabnya bukanlah karena persoalan keterbatasan dana anggaran. Tapi inti masalahnya sangatlah kompleks. Elite sendiri mempunyai watak bersaing antar sesamanya untuk menguasai sumber-sumber dana dan pengendalian kekuasaan. Di negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pun terdapat persaingan antarberbagai kelompok. Misalnya antarkelompok Reagan dan pimpinan Senat dalam tubuh partai Republik. Pimpinan tertinggi pemerintahan Uni Soviet dikuasai antara kelompok Politbiro, kelompok jendral industrialis dan kelompok penentu kebijakasanaan politik kuar negeri. Di negara kita pun terdapat kelompok elite yang bersaing. Ini merupakan hal yang wajar, sebab, sesungguhnya pemerintahan suatu negara terbentuk karena hasil persaingan antarkelompok elite. Ada kelompok yang berhasil membentuk pemerintahan, dan ada kelompok yang gagal dan berada di luar pemerintahan. Dari titik ini lalu muncul pengandaian: apakah pemerintah yang terbentuk itu
diterima semua pihak ataukah ditolak? Kalau semua kelompok menerima pemerintah, maka sebenamya persaingan itu justru berfungsi sebagai dinamisator. Tapi bila pemerintahan ditolak oleh sebagian besar kelompok maka persaingan itu dapat naik derajatnya menjadi konflik. Dalam perjalanan sejarah Rl selama 40 tahun, pemerintah sebenamya terdiri atas berbagai kelompok seperti nasionalis, agama, moderat dan lain-lain. Sifat pemerintahan sangatlah luas partisipasinya. Di dalam tubuh pemerintahan terjadi persaingan. Begitu pula antar kelompok dalam pemerintahan dan kelompok di luar pemerintahan. Tetapi persaingan kepentingan (interest) tidak sampai meningkat menjadi konflik terbuka antarelite yang memandegkan segala-galanya. Semasa perang gerilya dan perang kemerdekaan persaingan antarkelompok dapat dikendalikan karena kita menghadapi musuh yang sama: Kolonial Belanda yang ingin menjajah kembali. Waktu itu kemerdekaan Rl terancam bahaya. Kelompok-kelompok elite bersatu menghadapinya. Bagaimana persaingan antarelite dan sifat pemerintahan kita sekarang? Saya melihat situasi dekade 1980-an berbeda dengan keadaan 1970-an. Masalah konflik antarelite tidaklah setajam dugaan kita selama ini. Ada semacam kesediaan pemerintah untuk mengakomodir perbedaan paham yang luas dan lebih jauh dari situasi 1970-an. Pemerintah ingin memelihara stabilitas keadaan politik dan mengusahakan agar seluruh masyarakat memberikan dukungan penuh dan seluas mungkin. Tujuannya satu: mempersiapkan kerangka tingggal landas pada Pelita VI mendatang. Penerimaan asas tunggal pada dekade 1980-an dapat dijadikan ukuran dalam panilaian ini. Asalkan kita secara formal menyatakan menerima asas Pancasila, maka kita dibebaskan untuk mengambil sendi atau ciri masing-masing organisasi/kelompok masyarakat. NU menerima asas Pancasila sebagai salah satu sendi. Tetapi di sendi lain, keimanan NU adalah agama Islam. Contoh terakhir adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republilk Indonesia (PMKRI), yang menyatakan diri menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Tapi keimanannya tetap agama Katolik, sedangkan cirinya adalah kemahasiswaan. Sendi ideologis, organisatoris dan kultural ini perlu kita amati dalam dekade 1980-an. Dan kesediaan organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk menerima sendi kultural saat ini sungguh di luar dugaan. Ini sulit untuk diterima bila persoalannya berkembang pada masa panas dekade 1970an. Beberapa faktor dapat kita anggap sebagai alasan kenapa masyarakat Indonesia sekarang mau menerima sendi-sendi ideologis Pancasila tadi. Faktor pertama adalah kedewasaan elite dan anggota masyarakat dalam bemegara dan berbangsa. Faktor kedua adalah adanya suatu kesadaran masyarakat bahwa secara ekonomis negara kita sedang menghadapi cobaan-cobaan yang gawat. Pendapatan negara dari sektor minyak dan gas bumi anjlog luar biasa. Sedangkan sektor nonmigas yang diandalkan sebagai altematif temyata belum berkembang. Faktor lain adalah momentum tinggal landas pada Pelita VI. Ditambah sikap pemerintah yang akomodatif, maka pada dekade 1980-an ke depan, konflik antarelite tidaklah sehebat perkiraan kita. Pusat Kekuasaan dan Pemberi Legitimasi
Selain terdapat persaingan antar kelompok dalam suatu pemerintahan, sebenamya
di negara manapun juga, termasuk Indonesia, selalu akan tumbuh pusat-pusat kekuasaan (power centers). Pusat kekuasaan muncul dengan sendirinya karena efektivitas pengambilan keputusan dalam jangka panjang pada bidang tertentu. Ini wajar dan normal terjadi di dalam pemerintahan. Di Indonesia umpamanya secara formal ada kelembagaan muncul pusat kekuasaan bidang keamanan, administrasi kenegaraan, penentu kebijakan ekonomi dan birokrasi atau kepegawaian. Pada dekade 1970-an muncul istilah teknokrat sebagai pusat kekuasaan yang merancang pembangunan ekonomi secara nasional. Pusat kekuasaan ini akan ada terus. Siapapun orangnya dan apa pula sebutannya tidaklah penting. Pusat kekuasaan penanggung jawab keamanan juga merupakan suatu yang tak terhindarkan lagi. Kelompok ini bertanggung jawab di bidangnya dan akan terus berusaha seefektif mungkin dalam menjalankan fungsinya. Di bidang administrasi kepegawaian atau pamongpraja juga berkembang pusat kekuasaan yang lain. Dan di bidang administrasi kenegaraan, kita mengenal sekretariat negara sebagai pusat kekuasaan. Di pusat-pusat kekuasaan inilah berbagai kebijaksanaan diputuskan. Tetapi apakah pusat-pusat kekuasaan itu berdiri sendiri? Temyata tidak demikian, sebab di luar pusat kekuasaan itu masih terdapat berbagai kelompok masyarakat yang besar. Peranan mereka selalu barus diperhitungkan dalam kehidupan kenegaraan. Dari kelompok-kelompok ini minimal harus dimintakan dukungan setiap saat. Proses kenegaran tampaknya juga tetap berlangsung di luar pusat kekuasaan formal. Kelompok di luar ini bukanlah pusat kekuasaan melainkan pusat pemberi legitimasi kepada pusat kekuasaan. Umat Islam misalnya tak dapat dianggap sepele, sebab umat sering diminta untuk mendukung kekuasaan. Dalam kehidupan kenegaraan akhir-akhir ini, penerimaan asas Pancasila merupakan persoalan fundamental yang dikonsultasikan lebih dulu kepada kelompok Islam. Begitu pula soal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) apakah akan tetap sebagai partai Islam atau partai terbuka. Dalam konsultasi tadi terjadilah proses tawar-menawar (bargaining). Prosesnya tidaklah sekasar perkiraan orang: anda harus begini kalau diberi itu. Selain persoalan fundamental, ada beberapa hal umum yang dikonsultasikan dulu kepada umat Islam. Sifatnya tepo seliro. Di sini ada proses memberi dan menerima. Dalam kehidupan politik nasional pencalonan jabatan legislatif juga ditanyakan dulu kepada kelompok masyarakat di luar pemerintahan. Tatkala Chalid Mawardi diusulkan menjadi Duta Besar, saya ditanya, apakah setuju dengan pengangkatan itu. Saya sebenamya dapat saja menolak memberikan pendapat dengan alasan bahwa hal itu adalah urusan eksekutif . Tapi karena Chalid Mawardi adalah warga NU maka logis kalau saya perlu menjawab pertanyaan itu. Pemerintah telah mempertimbangkan keputusan itu dari berbagai faktor, bagaimana untung ruginya. Kami sebagai warga NU juga telah memakluminya dan tahu bagaimana nilai tawarannya. Proses tawar-menawar di tingkat daerah biasanya terjadi pada saat pemilihan calon gubemur. Permintaan dukungan dari umat Islam ditanyakan calon kepada
daerah itu melalui Partai Persatuan Pembangunan. Dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga demikian. Proses tawar-menawar ini dapat diibaratkan sebagai barter. Tapi kita tidak secara terbuka menyebutkan " kami minta diberi ini kalau bapak diangkatnanti". Biasanya tawaran itu tak terucapkan. Kalau nanti terpilih, kami harapkan pejabat itu tahu diri dan ingat kepada kami. Tidak perlu diberi jabatan tertentu kepada salah seorang dari antara kami, tetapi fasilitas dan kemudahan bagi kepentingan umat Islam secara keseluruhan yang kami harapkan. Memang masih sulit diharapkan bagaimana bentuk formal tempat pemerintah meminta dukungan dari umat Islam setelah PPP menjadi partai terbuka. Hanya saja perlu diingat, bahwa proses politik sebenamya tidak memperdulikan jalur formal atau nonformal. Pokoknya siapa yang dianggap etektif memegang kendali, dialah yang dihormati. Efektif tidaknva jalur yang kita pilih sangat tergantung pada kepentingan-kepentingan (interest) yang hendak dicapai. Tentu saja masalahmasalah yang sensitif berbeda cara penyampaiannya dengan persoalan biasa. Apakah dengan adanya pusat-pusat kekuasaan itu tidak membahayakan pemerintah? Sebagian besar orang tampaknya melupakan kenyataan, bahwa di antara pusat-pusat kekuasaan itu sesungguhnya selalu berlangsung suatu rekonsiliasi. Mereka pun melakukan proses tawar-menawar. Bagi saya, fungsi disintegratif dari adanya pusat kekuasaan itu hanya bersifat potensial. Untuk dapat terwujudkan secara aktual dari adanya persaingan antar pusat kekuasaan itu, saya kira, sangat tergantung banyak faktor. Sampai saat ini tidak terjadi konflik elite yang berarti karena ada beberapa pengamannya. Dalani skala makro, kini telah tumbuh sikap saling menghargai, rasa pengertian mendalam dan integrasi penuh dalam kehidupan nasional sebagai satu bangsa. Juga situasi politik cukup kondusif dan meminta masyarakat untuk lebih membaurkan diri. Dalam skala mikro, temyata kepentingan-kepentingan berbagai kelompok elite dapat dirundingkan dalam forum rapat. Di sana terdapat proses untuk menahan diri agar kepentingan kelompok dan perbedaan paham itu tidak saling bertabrakan sehingga membahayakan negara. Dengan kata lain, di antara mereka berlangsung suatu dialog yang mengimbau, bila anda ingin berperan dalam proses kehidupan negara dan pemerintahan, maka anda tak boleh membiarkan pemerintah terguIling. Halhal semacam ini berlangsung pula di pemerintahan Soviet yang kita anggap eliteelitenya sudah terintegrasi penuh tetapi kenyataannya mereka mempunyai kepentingan sendiri. Di sini memang berlaku pepatah "Pencegahan terbaik adalah kalau tergantung pada kepentingan masing-masing." Persaingan Ekonomi Tingkat Bawah
Dikaitkan dengan persoalan ekonomi, persaingan atau konflik antara pengusaha besar Muslim dan besar Cina untuk masa 20 tahun ke depan, saya duga tidak akan mengkhawatirkan. Malahan mereka konon menjalin suatu mata rantai kerjasama. Tetapi persoalannya menjadi lain bila kita menengok di tingkat bawah. Justeru di tingkat inilah terjadi persaingan keras antara saudagar Cina dan saudagar santri Muslim. Ini terjadi menyeluruh di berbagai daerah. Karena intensitas persaingannya tinggi sekali dan jumlah mereka besar maka perlu dicari pencegahannya agar tidak menjurus kepada konflik terbuka sebagaimana yang
terjadi beberapa waktu yang lalu. Untuk itulah menurut saya, pengusahapengusaha besar keturunan Cina perlu memberikan perhatian dan perlakuan yang sama terhadap pedagang-pedagang santri yang tergolong berkemampuan rendah ini. Jangan seperti sekarang hanya pedagang kecil Cina saja yang didukung oleh pengusaha berskala besar, karena beranggapan pedagang santri adalah saingan mereka. Yayasan Prasetya Mulya saat ini tampaknya telah siap mencetak tenaga-tenaga bisnis profesional. Sementara itu tradisi dagang warga keturunan Cina begitu mendukung bagi terus lahimya pedagang-pedagang baru di kalangan mereka. Mereka sanggup untuk merintis dari tingkat bawah-mulai berpakaian celana kotor, makan bubur dan kangkung dan akhimya menjadi pengusaha besar. Di sini masalahnya adalah kultur dan tidak sekadar diploma M.B.A. (Master of Business Administration) yang diperoleh dari yayasan itu. Kita memang dapat menyekolahkan tenaga-tenaga kita untuk memperoleh tingkat pendidikan yang sesuai bagi perkembangan bisnis modem. Misalnya nanti telah lahir manajer-manajer Muslim lulusan lembaga pendidikan bisnis. Tapi mereka harus ditempa lagi melalui jalur pengalaman untuk menjadi matang. Kenapa demikian? Sebab kita belum mempunyai tradisi atau kultur dagang itu. Menumbuhkan tradisi semacam itu di kalangan santri secara umum masih sulit. NU sendiri belum dapat berbuat banyak, karena saat ini sedang sibuk menata diri di dalam tubuh orgamsasinya. Minimal yang bisa kita lakukan adalah mencoba memetakan persoalan, memahami usaha-usaha kecil dan memberikan latihan dan pendidikan kepada beberapa ribu tenaga di bidang usaha kecil. Kita menitikberatkan pada penyiapan man power untuk bidang praktis atau proyek rintisan. Sebetulnya hal ini telah dikerjakan oleh banyak kalangan. NU sendiri hanya tinggal menawarkan kepada warga NU di berbagai daerah dan teman-teman di luar NU. Jalur yang kita pilih adalah pesantren atau pendidikan wiraswasta lainnya. Ini kita kerjakan untuk menjaga diri secara kultural dan kompetitif agar mampu bersaing dengan kelompok lain. Persepsi Gerakan Islam tentang Kebudayaan: Sebuah Tinjauan Dini tentang Perkembangannya di Indonesia Oleh Abdurrahman Wahid Kebudayaan adalah bidang yang digarap secara ambivalen oleh gerakan-gerakan Islam di negeri ini. Di satu pihak, keprihatinan justru dirasakan di bidang ini. Setelah aspirasi formal di bidang politik mengalami gempuran demi gempuran hebat, dirasakan bidang kebudayaan sebagai wilayah pertahanan kritis, medan laga yang akan menentukan masa depan Islam di Indonesia. Keluhan dan peringatan para pemimpin Islam tentang bahaya penetrasi kebudayaan Barat adalah contoh dari keprihatinan tersebut, yang juga sejak cukup lama sudah terasa di kawasan-kawasan lain dunia Islam, terutama di Timur Tengah. (Gibb. 1962: 232-4). Tetapi, dipihak lain justru sedikit sekali dirumuskan secara institusional pemikiran-
pemikiran tuntas tentang bidang kebudayaan di negeri ini oleh gerakan-gerakan tersebut. Pendapat resmi mereka sulit dicari, kacuali pemyataan bahwa wama keagamaan (dalam hal ini Islam) haruslah menjiwai kebudayaan bangsa. Dari pemyataan-pemyataan seperti itu tampak jelas bahwa pemikiran tentang kebudayaan belum mencapai perkembangan jauh dalam lingkungan gerakangerakan Islam di sini. Di kawasan-lawasan lain dunia Islam berbeda sekali keadaannya, seperti dapat dilihat dari produk pemikiran gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah dan Asia Selatan. Beberapa hal dapat diperkirakan menjadi sebab keadaan itu, tetapi yang terpenting mungkin adalah watak responsi golongan Islam di negeri ini terhadap tantangan modemisasi semenjak lebih seabad yang lampau. Keragaman sangat tinggi dalam responsi yang diberikan, sehingga tampak sporadis secara keseluruhan, tidak memungkinkan pengambilan keputusan formal yang diikuti bersama, dan dengan demikian tidak memunculkan kebutuhan akan perumusan sebuah sikap bersama terhadap modemisasi. Dengan demikian keadaan itu membawa kepada langkanya kebutuuhan akan sebuah politik kebudayaan yang jelas dan terpadu. Pendekatan yang diambil lalu berwatak kultural, bukannya strategis,: kesadaran umat dituntut untuk menghindari pengaruh buruk kebudayaan yang tidak bemafaskan semangat keagamaan Islam , tanpa adanya konstitusi yang bertugas khusus menangani dasar-dasar pengembangan sebuah kerangka kebudayaan Islam. Perkembangan kebudayaan yang akan diberi nama kebudayaan Islam lalu berlangsung tanpa ada gambaran jelas tentang apa yang diinginkan akan tercapai, kecuali patokan umum bahwa ia tidak akan melanggar ajaran agama Islam. Implikasi dari hasil pemgamatan di atas adalah keharusan menggali bukan dari keputusan-keputusan formal berbagai gerakan Islam yang terorganisir, kalau ingin diketahui persepsi mereka tentang kebudayaan, melainkan dengan melakukan telaahan atas pendangan para pemikir dan pemuka gerakan yang beraneka ragam corak dan bobotnya. Dengan melakukan inventarisasi pendapat dan pandangan mereka, akan dibuat proyeksi tentang persepsi gerakan Islam tentang kebudayaan, baik dalam lingkup parsial maupun global. Sudah tentu tidak dapat dihindari besamya keragaman pandangan antara pendapat-pendapat yang dikumpulkan. Walaupun demikian, beberapa bagian yang sama dari pendapat yang sangat beragam itu sudah cukup untuk memungkinkan pembuatan persepsi proyektif yang dimaksudkan di atas. Dapat dikemukakan sebagai contoh pengertian mereka atas kata kebudayaan, yang memperlihatkan kesamaan dasar. Hamka memandangnya sebagai perpaduan antara keimanan seseorang dan apa yang dikerjakannya (Hamka & Saimima, 723). Sidi Gazalba memandangnya sebagai kebulatan konsep tentang sosial, ekonomi, politik, pengetahuan , teknik, seni, dan filsafat. Karenanya, kalau masjid menjadi tempat yang hanya didatangi oleh sebagian kecil umat Islam di sekitamya, maka yang wujud hanyalah masyarakat orang-orang Islam, yaitu orang-orangnya Islam karena beragama Islam, tetapi masyarakatnya bukan Islam karena tidak berkebudayaan Islam dan tidak mengamalkan cara hidup Islam (ibid, 181). Menurut Haji Agus salim, kebudayaan berarti himpunan segala usaha dan
daya upaya yang dikerjakan dengan menggunakan hasil pendapat budi, untuk memperbaiki sesuatu dengan tujuan mencapai kesempumaan (Salim, 1954:300). Jelas dari gambaran yang mereka berikan bahwa mereka menggunakan pengertian kultur yang berarti totalitas kehidupan manusia dalam konsep mereka tentang kebudayaan. Yang sedikit berbeda dalam arti tidak merumuskannya secara jelas adalah Nurcholis Madjid, yang berbicara tentang keharusan meninggalkan gagasan-gagasan tradisional yang dianggap ukhrowi, walaupun sebenamya merupakan bagian dari pola-pola kebudayaan belaka (Boland, 1971: 222). Kalau Hamka, Gazalba, dan Haji Agus Salim menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang berpadu dengan agama atau keimanan, maka Nurcholis Madjid menganggapnya sebagai sesuatu yang berdiri di luar keimanan agama. Para pemikir dan pemuka gerakan Islam memiliki pendapat yang hampir bersamaan tentang tempat kebudayaan dalam kehidupan, yaitu sebagai bagian sangat menentukan bagi kehidupan masyarakat, melalui berbagai pranata dan lembaga. Pranata dan lembaga yang tak terbilang itu merupakan manifestasi dari sebuah kerangka umum kehidupan, yang akan menentukan corak dan wama kehidupan, arah dan orientasinya, serta lingkup dan wawasannya. Dengan demikian menuntut pandangan mereka, kesemua prasangka dan lembaga yang ada dalam sebuah masyarakat adalah subsiten dari sebuah sistem besar yang bemama kebudayaan. Ekonomi, politik, kesenian, ilmu pengetahuan, dan seterusnya adalah deretan subsistem yang secara total membentuk entitas yang baru yang dinamai kebudayaan itu, walaupun pada dirinya masing-masing adalah sebuah sistem tersendiri yang lengkap dengan pranata dan kelembagaanya yang kompleks pula. Adalah menarik untuk melihat tempat pendidikan dalam tata istem di atas. Pendidikan sekaligus adalah sebuah subsistem bagi kebudayaan dan sistem tersendiri yang berada di luamya, yang menunjang pembentukan, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan. Sebagai sebuah subsistem, pendidikan adalah bagian terpenting dari kebudayaan, berfungsi sebagai pengarah kebudayaan dan sekaligus mekanisme pewarisan nilai-nilai budaya sesuatu masyarakat dari satu ke lain generasi. Sebaliknya, sebagai sebuah sistem tersendiri ia ditunjang oleh kebudayaan untuk membantu perkembangan hidupmanusia, baik perorangan maupun kelompok, ke arah yang dikehendaki oleh ajaran islam. Dengan demikian, antara pendidikan dan kebudayaan terjadi hubungan simbolik mutualistis. Secara eksplisit hal ini dinyatakan berulangkali oleh sejumlah pemikir dan budayawan muslim, suatu hal yang tidak begitu mereka tuntut dari subsistem lainnya terhadap kebudayaan. Memang Islam menganggap politik memiliki arti pengarah bagi kebudayaan, apabila ia berfungsi mnciptakan keputusan yang dapat mengarahkan jalur kegiatan mereka dalam pandangan mereka. Namun fungsi pengarahan itu tidak lalu menjadikan subsistem politik sebagai sesuatu yang terlepas dari kebudayaan. Mungkin ini datang dari pandangan mereka yang cukup unik tentang politik: ia adalah unsur penunjang yang memiliki moralitas yang harus ditentukan wawasan dan lingkupnya oleh sebuah sistem lain lagi. Dalam Islam tidak diakui independensi total bidang politik, dalam arti diperkenankan mengembangkan nilanilainya sendiri. Politik adalah bagian dari moralitas kaum muslimin, karenanya ia
harus tunduk pada sistem yang membentuk cakrawala kehidupan sebuah masyarakat muslim. Pendidikan dan kebudayaanlah yang justru memiliki peranan pengarahan bagi politik itu. Hubungan simbiotik mutualistis antara pendidikan dan kebudayaan itu tumbuh dari persepsi Islam yang tersendiri mengenai pendidikan. Baik secara historis (karena ada landasannya sendiri dalam tradisi kenabian) maupun secara kultural, Islam menekankan pentingnya arti pendidikan, terutama karena melalui pendidikanlah berkembang dua hal yang paling diinginkan dalam pribadi seorang muslim: pemahaman yang benar tentang sendi-sendi keimanannya, dan moralitas benar (right morality) yang menjadi pengejawantahan pemahaman benar tersebut. Tekanan pada penumbuhan watak serba benar dari keimanan dan moralitas itu sudah tentu tidak bisa lain dari pemberian tempat begitu penting kepada pendidikan, sebagai sesuatu yang secara sistematik memiliki keberadaan di luar kebudayaan. Dapat disimpulkan dari hubungan antara kebudayaan dan pendidikan seperti digambarkan di atas, bahwa para pemikir pemuka gerakan Islam membagi kerja penumbuhan moralitas dan pemahaman keimanan yang benar itu ke dalam dua wilayah utama: wilayah konsepsional dalam arti luas di bawah tanggungjawab sistem kebudayaan dan wilayah penerapan konsepsi itu di bawah tanggugnjawab sistem pendidikan. Pemberian sarana saling melengkapi antara kedua sisitem itu dengan sendirinya menunjukkan perlakuan Islam yang unik atas kedua bidang itu: di satu pihak diberi keluasan untukberfungsi di luar sistem lainnya, di pihak lain telah dibatasi ruang geraknya oleh pembagian tersebut. Kesejajaran dalam hubungan antara kebudayaan dan pendidikan justru tak terlihat dalam hubungan antar ajaran Islam dan kebudayaan. Kebudayaan dalam pandangan gerakan Islam sebagaimana diwakili pandangan para pemikir dan pemukanya, adalah sesuatu yang subordinat kepada kebenaran ajaran agama. Di sini kebenaran berfungsi kebar selaku obyek yang dijadikan sasaran hidup berbudaya itu sendiri dan sekaligus elemen operasional yang menjamin keberhasilan pencapaian usaha tersebut. Karena fungsi kembamya itu, ajaran agama memiliki kedudukan superordinat terhadap kebudayaan: ia sekaligus menjadi salah satu unsur kebudayaan, namun juga menjadi penentu watak dan corak kebudayaan yang akan dikembangkan. Dalam arti inilah para pemikir dan pemuka gerakan Islam mengajukan rumusan mereka, yaitu Islam harus menjiwai kebudayaan. Fungsi agama terhadap kebudayaan dengan demikian merupakan gumpalan dua fungsi lain: fungsi inspiratif bagi kebudayaan dalam arti memberikan kekuatan pendorong bagi hidup berbudaya, dan fungsi normatif dalam artian mengatur dan mengarahkan hidup berbudaya itu sendiri ke jalur yang dibenarkan oelh keimanan seorang muslim. Dalam fungsi inspiratifnya, Islam menyediakan sejumlah nilai dasar maupun nilai derivatif yang melandasi deretan subsistem yang membentuk kebudayaan. Nilai-nilai itu ada yang diserap oleh masing-masing subsistem dalam bentuk abstrak (seperti kewajiban, elan, dan sumber pemikiran) maupun kongkret kelembagaan, moralitas, dan sebagainya).
Pada titik sebagai sumber inspiratif dan sekaligus batasan normatif dari ajaran inilah muncul sebuah konsep menyeluruh tentang Islam sebagai Ad-Din (Agama, huruf besar yang menunjukkan klaim kebenaran yang tunggal bagi dirinya, yang juga menjadi pengertian kalau digunakan istilah The Religion of Islam). Islam sebagai sang Agama adalah satu-satunya kerangka umum kehidupan yang benar, dan oleh karenanya harus dilaksanakan secara total tanpa adanya aspek yang tertinggal satupun. Islam sebagai keimanan, hukum agama (Syariat), dan pola pengembangan aspek-aspek kehidupan, dalam totalitasnya berfungsi sebagai jalan hidup yang akan membawakan kesejahteraan bagi umat manusia. Dalam totalitas jalan hidup itu dirumuskan arah, orientasi, wawasan, dan lingkup kehidupan perorangan dan bermasyarakat manusia, dengan pola hubungan antar kaum muslimin dan yang bukan muslim diatur di dalamnya. Dalam totalitas seperti itu tidak ada perbedaan natara aspek duniawi dan aspek ukhrawi dari hidup manusia, karena semuanya saling menunjang dalam geraknya. Dalam keadaan demikian, tidak lagi akan ada hal-hal yang tidak berwawasan keagamaan, antara wilayah agama dan wilayah-wilayah lain sudah tidak ada perbedaan lagi. Dalam fungsi mengikat dan amenjalin keserasian antara semua wilayah kehidupan, Islam sebagai Ad-Din dengan sendirinya menolak sekularisme yang masih membeda-bedakan corak kegiatan masyarakat antara yang berwama agama dan yang berwama duniawi. Ini berarti penolakan pula atas kebenaran klaim adanya kebudayaan dalam pola kegiatan yang terlepas dari wawasan keagamaan (dalam hal ini Islam). Kata kebudayaan hanya patut dipakai oleh pola kehidupan yang bersumber pada aspirasi keagamaan (dalam totaltasnya, yang menyangkut apa yang berada di luar wawasan sempit keagamaan selama ini) dan mengikuti batasan-batasan normatifnya. Terlepas dari variasi sangat beragam dalam perincian persoalan yang dirumuskannya, pola Islam sebagai Ad-Din itu adalah pola yang diikuti oleh kebanyakan para pemikir dan pemuka gerakan Islam di negeri ini, walaupun cukup kuat pula kedudukan mereka yang mempertanyakan keabsahan eksposisi kebenaran agama secara demikian itu. Masa depan sajalah yang akan menunjukkan kecenderungan mana yang benar-benar mewakili persepsi gerakan Islam tentang kebudayaan. Pertemuan Tak Terduga di Bali Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Jam 05.00 WITA, di ruang tamu Ashram Gandhi milik Ibu Gedong Bagus Oke di bilangan Sanglah, Denpasar. Pagi itu, penulis sedang menunggu keberangkatan ke lapangan terbang Ngurah Rai sambil minum teh, bertemu dengan putra kedua beliau, yaitu Krisna Bagus Oke. Sebelumnya, dalam sebuah pertemuan di Candi Dasa, Krisna telah mengajukan gugatan. Mengapa Gus Dur selaku seorang mantan Presiden di negeri kita masih bersedia dijemput oleh sebuah mobil Mercedes Benz, di samping mobil lainnya berupa mobil Toyota Land Cruiser baru? Bukankah itu
pertanda masih adanya elitisme yang diikuti oleh seorang mantan Presiden dan menjauhkannya dari rakyat? Gugatan itu dijawab oleh Agus Indra, salah seorang keponakannya sendiri, dengan argumentasi bahwa seorang mantan Presiden, tidak perlu goyah dalam komitmennya terhadap rakyat jelata. Kesederhanaan itu, adanya terdapat dalam jiwa bukannya dalam kendaraan yang dinaiki. Di sini, sebuah pertukaran pendapat sekaligus membuktikan bahwa dalam keluarga Ibu Gedong perbedaan adalah sesuatu yang lumrah. Penulis teringat pada keluarga sendiri, yang membiarkan meja makan menjadi tempat perdebatan. Begitu banyak persamaan antara keluarga Ibu Gedong yang, saat ini berusia 80 tahun, dengan keluaraga Ibu penulis yang membesarkan anakanaknya dalam suasana berdebat, tetapi sekaligus bertanggung jawab atas tugas yang dipikul. Hal semacam inilah yang menjadi kesan penulis ketika mengikuti perbedaan pendapat antara Krisna dan Indra. Hanya dengan menggalakkan perdebatan seperti itulah kita akan mampu mencapai kebesaran dalam menunaikan tugas dan amanat masing-masing. Dan, adagium ini penulis pegangi hingga saat ini. Sekaligus merupakan salah satu kunci dalam proses demokratisasi yang berjalan di negeri kita dewasa ini. Bahwa, demokrasi hanya akan berwujud dalam sebuah perbedaan, bukannya hasil dari sebuah proses penyeragaman. ***** Krisna menyampaikan pada penulis, bahwa ia aktif dalam memperbaiki hutan suaka. Begitu banyak tumbuh-tumbuhan langka yang terdapat di negara kita, dengan tidak memperoleh perhatian yang cukup dari orang-orang yang mestinya bertanggungg jawab dalam pelestarian hutan. Suaka yang ditanganinya sekarang terletak di sebelah timur Singaraja, di daerah pantai utara Bali. Kawasan ini, adalah salah satu dari hutan lindung langka yang ada di negeri ini. Dalam perjalannya ke Amerika serikat, ia pemah mengunjungi sebuah pusat pelestarian hutan di Fermont, kawasan timur laut Amerika Serikat. Di daerah yang dingin itu temyata terdapat sebuah pusat pelestarian tumbuh-tumbuhan daerah tropis. Para aktifis di temmpat itu yang datang dari tempat jauh, seperti Ithaca (Universitas Comell) dan Michigan (Universitas Calamazoo), sangat tertarik dengan pelestarian hutan tropis dan mereka membuat rumah kaca (green house) untuk keperluan tersebut. Penulis lalu teringat dengan rumah-rumah kaca di negeri Belanda yang menumbuhkan bunga tulip sepanjang tahun, hingga menghasilkan devisa sedikitnya US$ 200 juta dari export bunga tersebut ke negeri-negeri lain. Krisna menyatakan bahwa pusat pelestarian hutan tersebut bersedia membiayai sebuah stasiun penelitian di Bali dan sebuahnya lagi di Jawa Timur. Melalui stasiun tersebut, Krisna akan dapat melanjutkan upaya melestarikan tanam-tanaman langka di hutan yang ditekuninya di kawasan timur singaraja itu. Tentu, ini adalah sebuah upaya yang sangat menarik yang harus kita sambut dengan gembira.
Masih sangat sedikit orang-orang yang memperhatikan hal-hal seperti ini. Tak heranlah jika kemudian kita menjadi sangat tergantung pada negara-negara yang disebut maju itu. Dan tak heran pula jika akhimya kita banyak berhutang pada mereka, hingga jadi lahan manipulasi saja. Sebab, bagi perusahaanperusahaan besar (Multi National Coorporation, MNC) telah menguasai perekonomian negara-negara berkembang dan menentukan pola pembangunan mereka. Pasaran dan sumber-sumber kridit telah dikuasai oleh negara-negara maju. Dari sini, tak heran jika terorisme intemasional dapat berkembang pesat, sebagai reaksi balik tidak wajar terhadap kenyataan tersebut di atas. ***** Krisna adalah contoh dari orang-orang yang mencoba untuk mengabdi pada bangsanya melalui pengembangan profesi yang dipilih. Selama ia memilih untuk menyelamatkan hutan, dan tak memanipulasikannya sebagai kepentingan diri sendiri, selama itu pula ia berhak dinamakan pejuang bagi kepentingan bangsanya. Jadi, jelaslah bahwa, sikap ketergantungan seseorang atau lembaga terhadap negara lain haruslah diukur melalui hal ini, yaitu bagi kepentingan siapa ia bekerja. Kalau ia bekerja untuk melestarikan milik bangsa, berarti ia berjuang untuk bangsa tersebut. Begitu sebaliknya, jika ia bekerja untuk kepentingan cari untung melalui perusahaan-perusahaan raksasa --tempat ia bekerja, berarti ia akan jadi orang yang sangat bergantung pada pihak lain. Kita berharap, bantuan yang diterima Krisna saat ini, digunakan untuk memperjuangkan terpeliharanya kelestarian tanam-tanaman langka di hutan kita. ***** Apa yang dilakukan Krisna melalui upayanya itu, merupakan bagian dari upaya mengembangkan perekonomian rakyat. Perekonomian jenis inilah, yang seharusnya menjadi perhatian kita. Beruntunglah penulis, yang memiliki temanteman seperti Marzuki Usman dan KH. Imam Churmaen (anggota DPR RI). Karena, merekalah yang memimpin para aktifis dan perintis muda kita untuk mengembangkan perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bukan konsep perekonomian yang hanya mengabdi pada segelintir konglomerat saja. Para perintis itulah yang menggariskan multi aspek kita agar tidak didominasi oleh pemilik modal dan kapitalisme intemasional. Juga, melalui kegiatan merekalah sikap politis kita yang menolak campur tangan asing dalam kehidupan kita yang, kemudian diejawantahkan dalam kehidupan kita di luar kawasan politik. Berpulang pada para aktifis muda seperti Indra dan banyak orang-orang lain terbeban kewajiban yang berat untuk memelihara dan menggunakannya dalam persaingan di dunia intemasional. Bukannya gaya sejumlah pemimpin Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merasa sudah sangat hebat dengan pengalaman mereka yang hanya itu-itu saja, hingga mereka lebih bersikap mengguruhi para pemimpin masyarakat, termasuk para pemimpin politik.
Pesannya Abadi, Kemasannya Temporer Oleh: Abdurrahman
Wahid
Dalam kendaraan pribadi setelah tiba dari Surabaya di Cengkareng airport, penulis mendengarkan piringan CD mengalunkan sesuatu yang sangat memikat, yaitu pagelaran lagu-lagu qasidah dengan diiringi permainan biola oleh Idris Sardi. Belasan bentuk birama disajikan olehnya, dalam permainan biola yang sangat indah dikuping penulis. Antara Idris Sardi dan bentuk birama yang disajikan alKhalil ibn Ahmad al-Farahidi dalam ke-16 bahan yang dituangkannya dalam arudh (metrologi syair) yang diperkenalkannya menjadi salah sebuah disiplin ilmu-ilmu ke-Islaman pada abad ke-2 Hijriyah (9-10 M), menampilkan keindahan pesanpesan yang teetap sama yaitu lagu puja/shalawat dan pengagungan atas diri Nabi Muhammad SAW. Inilah yang dianggap oleh banyak orang sebagai ajaran agama, dan ini pula yang ditangkap oleh Idris Sardi melalui permainan biola maut yang disajikannya kepada kita. Bukankah jelas, Idris Sardi yang selama ini menyajikan permainan biola menawan, akhimya di hari tua kembali kepada agama melalui sajiannya itu? Artinya, dengan penyajian biolanya yang sangat indah ini, Idris Sardi melantunkan pesan-abadi. Dan melalui sajian seni tersebut. ia melantunkan kepada dunia dua hal sekaligus yaitu: dirinya telah menemukan kembali arti agama dalam hidupnya melalui alat musik bemama biola ini; dan keagungan Nabi punya arti penting untuk dicontoh oleh kita. Tembang qasidah yang menjadi medium pagelaran seni itu membawakan kedua pesan abadi di atas. Jika al-Farahidi melantunkan keindahan kata-kata melalui lagu-puja bermacam-macam ini, Idris Sardi justru menyajikannya dalam permainan biola yang sangat mengasyikan. Tetapi, tentu saja biola modem belum dikenal di masa al-Farahidi, sehingga kemasan pesan-pesan tersebut dilakukan dengan katakata, dan oleh Idris Sardi dengan sengaja diganti oleh permainan alat musik biola. Bukankah ini berarti pesan-abadi yang sama tentang diri Nabi sebagai panutan kita, disajikan melalui kemasan yang berbeda? Pesan abadi itu secara moral disajikan oleh kedua orang seniman ini kepada kita, dalam kemasan temporer (sesuai waktu) secara sangat indah. Hal ini terjadi berkali-kali dalam hidup kita. Maksud pesan abadi dari sebuah karya seni dapat kita mengerti dari judul karya seni itu, seperti Symphony No.5 dari Ludwig Van Beethoven dinamai Prometheus Unbound, yang menggambarkan pemberontakan manusia terhadap alam. Padahal tidak ada sebuah birama-pun dalam karya seni ini yang menggambarkan pemberontakan manusia atas kehidupan alami yang dijalaninya, sehingga hanya dengan judul ini saja kita mengerti maksud sang pencipta karya itu. Namun, nyanyian koor melalui paduan suara, justru menggambarkan sebaliknya dari apa yang dimaksudkan. Seperti tiap kali penulis mendengarkan sajian symphony ke 9 dari pencipta tersebut, berjudul Ode An Die Freud yang menyimpulkan keceriaan dunia, tiap kali pula asosiasi pikir penulis justru terletak pada kebesaran Tuhan yang tentu saja jauh dari keceriaan dunia.
Hal di atas juga terbukti dalam karya-karya William Faulkner, novelis Amerika Serikat yang memenangkan hadiah Nobel untuk bidang sastra di abad yang lalu. Melalui novel-novelnya, Faulkner menceritakan kegigihan manusia untuk memperjuangkan kejayaannya, melalui cerita-cerita keluarga Sartoris.Walaupun kemasan demi kemasan dalam novel-novel ini berubah-ubah, namun dengan pesan abadi yang sama. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan novelis dari negara bagian Mississippi di kawasan selatan negara tersebut yang tidak mau memasang telepon maupun menggunakannya. Penulis membaca hampir seluruh novel-novelnya, yang selalu menyampaikan pesan abadi yang sama: perjuangan manusia untuk mencapai kejayaan dalam hidup ini. Hal yang sama, juga kita dapati dalam karya-karya sastra Pramoedya Ananta Toer yang hampir seluruhnya juga penulis baca. Apakah ini berjudul Subuh, Bumi Manusia, Perburuan maupun Midah Si Manis Bergigi Emas, pesannya selalu sama, manusia-lah yang menentukan nasibnya sendiri, bukan unsur-unsur lain dalam kehidupan. Memang kemasannya berbeda-beda, dari kesunyian seorang anak manusia yang dikucilkan oleh keadaan, hingga ke manusia yang hidup dalam keramaian masyarakat yang dijalaninya, namun pesan abadinya ini tetap saja berisikan hal di atas. Inilah yang penulis tangkap dari karya-karya sastrawan Indonesia ini, bersama Mochtar Lubis dalam novel Jalan Tak Ada Ujung yang diterbitkan awal tahun 50-an. Selain itu, kalau kita perhatikan benar keindahan-keindahan lukisan Bali yang boleh dikata tidak terikat kepada bentuk, adalah bagian dari kemasan temporer juga menyampaikan pesan abadi berupa daya ekspresi seni yang sangat tinggi dari para seniman daerah yang tidak pemah merasa jauh dari alam. Hal yang sama juga kita rasakan dalam tari-tarian agama di Nagroe Aceh Darussalam, atau karya-karya seni dari orang-orang Asmat di tanah Papua. Tentu saja, hal ini juga kita dapati dalam kesenian Sunda, dari Calung hingga Angklung, juga dalam musik Kolintang dari Sulawesi-Utara. Dan tanpa perlu kemampuan istimewa kita juga dapat menangkap kenyataan hidup ini, yang dalam sistem budaya di Jawa jaman lama dikenal dengan nama Kasunyatan. ***** Karena ini, kita harus menyambut gembira karya-karya seni yang menunjukkan prinsip membawa pesan abadi tetapi dengan kemasan temporer, seperti diperlihatkan Idris Sardi dalam rekaman permainan biola ajaib-nya, yang menunjukkan bahwa pada akhimya seniman seperti Idris Sardi juga mengalami perubahan-perubahan dalam penampilannya. Namun, yang harus dihargai adalah pesan-pesan abadi yang dibawakannya melalui karya-karya seni yang digelamya. Ini juga berlaku bagi para seniman lain, dengan karya-karya mereka seperti Sutardji Kalzoum Bachri dengan sajak-sajaknya, menggambarkan perasaan dan pikiran seorang seniman sufi, yang tentu saja agak berbeda dari penyair lain yang memiliki perjalanan beragama tanpa melalui sufisme, seperti Hamid Djabbar. Jelas dari uraian di atas, bahwa perjalanan berganda dijalani para seniman dari berbagai bidang. Di satu pihak, mereka menjalani perubahan-perubahan perasaan beragama mereka (hal ini merupakan proses alami). Di pihak lain, mereka sebagai
warga masyarakat, harus turut merasakan perubahan nilai-nilai yang juga mengalami perubahan dalam kehidupan nyata, dan mau tidak mau membuat mereka berubah. Dari sini jugalah timbul dua kebutuhan berubah dari para budayawan untuk merumuskan nilai-nilai abadi, seperti: cinta kepada sesama, sikap menghormati perbedaan, berkiprah untuk manusia. Dan dipihak lain, mengerti perubahan-perubahan nilai yang ada dalam dirinya. Ini berarti adanya keharusan untuk berpegang pada nilai-nilai apa yang mereka rasakan dalam karyakarya seni mereka. Ini memang mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan? Pesantren dan Ludruk Oleh
Abdurrahman
Wahid
Karena ludruk berasal Jombang, ada kawan yang bertanya apakah pesantren yang menjadi penciptanya? Bukankah daerah itu daerah pesantren, mengapa sampai kesenian rakyat yang satu ini justru muncul di sana? Pertanyaan sambil bergurau baru dalam melakukan pengamatan atas kehidupan kaum santri kita di masa lampau. Sudah tentu dengan implikasinya sendiri bagi masa datang, karena ia berhubungan dengan masa depan agama Islam di tanah Jawa, dus menyangkut negara kesatuan tercinta ini. Ah, terlalu melamun. Apa hubungan ludruk dengan masa depan Islam? Sudah yang berkaitan dengan pesantren belum dijelaskan, ditambah lagi proyeksi gombal yang terlalu jauh ini! Tetapi kenyataan memang demikian. Islam mendarat dan lalu tertanam lebih kuat di kawasan pantai utara pulau Jawa, lalu sedikit demi sedikit memasuki wilayah pendalamannya. Di Jawa Tengah, yang menjadi pusat kekuasaan yang menunjang budaya asli Jawa di garis pintas Solo- Kartosura-Yogya, terjadi proses interaksi yang bersifat seru tetapi berumur tidak terlalu lama antara budaya asing Jawa itu dan budaya Islam yang baru datang. Segera tercapai keadaan status quo, bak orang berperang mencapai gencatan senjata: diakui budaya asli Jawa untuk memanifestasikan aspirasi keagamaan Islam di banyak wilayah kehidupan di pedalaman JawaTengah itu.Wayang dinikmati bersama, kiai pura-pura tidaktahu kalau ada wanita tampil dalam pagelaran kesenian setempat , bentuk mesjid tradisional mengambil pola arsitektur kejawaan sejauh mungkin. Blangkon dan destar, bukanya peci dan kopiyah haji, yang jadi tanda pengenal kaum santri pedalaman Jawa Tengah dahulu. Baru kalau sudah kiai atau ingin dianggap memiliki derajat kekiaian lalu ada keinginan memakai sorban, seperti Pangeran Diponegoro. Tari rakyat kentrung digunakan sebagai media ekspresi keagaman di Magelang, ditarikan di luar tempat formal bagi upacara keagaman (masjid, surau dan sebagianya). Pedalaman Jawa Timur lain lagi keadaannya. Pengaruh budaya asli Jawa tidak begitu kuat tertanam seperti diJawa Tengah, mungkin karena terlalu jauh Ietaknya
dari pusat kekuasaan waktu itu. Situasi gencatan senjata tidak segera tercapai. Kaum santrinya lebih seram "menangani" keterlibatan aspek-aspek keagamaan. Tekanan kepada spiritualitas kaum tarekat dan legalisme kaum ahli fiqh menjadi watak utama kehidupan masa itu di kawasan pedalamanJawa Timur. Wanita ikut pagelaran seni secara terbuka? Oh, tidak boleh, ini salah satu contohnya. Dalam benturan dan pergolakan kedua kekuatan sosial-budaya itu, karena inisiatif menyerang berada di tangan kaum santri, perlu didatangkan bala bantuan. Bukankah sikap menyerang membutuhkan lebih banyak pasukan? Kaum santri pedalaman Jawa Timur tidak membutuhkan bala bantuan prajurit, karena ini bukan peperangan fisik; mereka membutuhkan bala bantuan opsir pemimpin serangan. Untuk pergulatan sosial-budaya, adakah yang lebih tepat dari bala bantuan perwira berupa kiai sebagai "barisan opsir agamawan"? Adakah cara lebih tepat dari proses perkawinan, dengan cara "mengambil" menantu calon-calon kiai dari pantai utara? Bukankah bentangan kawasan perisir dari Cirebon di Jawa Barat hingga Sedayu di dekat Surabaya merupakan sumber penyediaan calon ulam yangtangguh, dengan rangkaian pesantren-pesantren kunonya? Asy'ari (ayah pendiri Pesantren Tebuireng, K.Hasyim) berasal dari Demak, diambil menantu K. UthmanJombang. Kedua kakak beradik Ma'sum dan Adlan Ali dari Sedayu, juga lalu "mangkal" di Jombang, seperti halnya Bisri Syansuri yang berasal dari Tayu (Pati) dan ldris Kamali yang lahir di Cirebon. Makhrus Ali dari Cirebon juga, kini memimpin pesantren besar di Kediri. Juwaini dan Jauhari adalah pemuda-pemuda Pati yang kemudian bermukim diJawa Timur juga. Kesemua calon kiai itu kini telah membentuk barisan kiai tangguh yang dituakan oleh masyarakat.Pesantren-pesantren Lirboyo, Kencong (Jember), Kretek (Kediri) dan Tebuireng adalah daerah kepemimpinan mereka sekarang ini. Merekalah yang jadi pimpinan serangan sosial-budaya kaum santri di garis lintas timur-barat Surabaya hingga ke Madiun dan garis tenggara-barat laut Banyuwangi ke Jombang. Belum lagi menantu-menantu baru masa kini, yang baru memulai aksi mereka di atas pentas: Aziz Masyhuri dan Yusuf Masyhar dari Tuban, yang kini berdomisili di Jombang, dan lain-lainnya lagi. Proses saling penguatan yang menarik untuk dikaji dengan medium perkawinan antara sesama keluarga kiai tangguh dengan tujuan "perjuangan" (sebagaimana mereka yakini sendiri) sosial budaya yang intens. Tidak heranlah jika lalu sikap kurang akomodatif terhadap aspek-aspek kesenian asli Jawa lebih berkembang diJawa Timur: Pagelaran kesenian keagamaan umumnya berlangsung di tempat-tempat peribadatan formal (masjid dan sebagainya ), seperti kesenian hadrah. Wayang lebih sedikit dipertunjukkan,tayuban boleh hanya kalau bukan musim giling pabrik gula, dan seterusnya. Wanita tetap tidak boleh memperagakan diri dalam pagelaran di muka umum.
Sudah wayang sangat sedikit dipertunjukkan, melihat penari non-wanita kurang asyik. Bagaimana kalau drama urakan dengan pemain pria berperan sebagai wanita? Lahirlah ludruk sebagai "status quo kecil". Pencipta aslinya adalah kelompok-kelompok seniman yang nantinya melahirkan Markuat serta Markaban (ah, betapa masih santrinya nama-nama mereka!) ltu semua masa dahulu. Bagaimana sekarang? Yang tua dan muda ya sama saja. Lelaki wanita diterima juga. Namun demikian, tradisi akomodasi yang datang belakangan ini tentu tidak sama manifestasinya dengan keakraban lama yang ada antara budaya asli Jawa dan budaya santri di pedalamanJawa Tengah. Kalau keakraban lama ini dapat menghasilkan kreasi budaya yang lebih mampu menangani masalah kesenjangan sosial-budaya antara golongan yang berbedabeda di negeri ini, bukankah peranan mereka akan sangat vital? Dan kalau ini terjadi secara nyata, bukankah manifestasi hidup kesantrian juga lalu akan mengalami perubahan -perubahan mendasar? Kalau keadaan demikian yang benar-benar terjadi, siapakah yang akan dapat menyangkal terjadinya perkembangan menentukan bagi masa depan Islam di negeri ini? Ada yang melakukan penyangkalan seperti itu, yaitu kenyataan sejarah di masa depan. Atau justru membuktikannya. Pesantren, Pendidikan Elitis atau Populis? Oleh Abdurrahman Seleksi dalam
Wahid Pesantren
Arah pendidikan ditentukan oleh mereka yang berkelibat dalam kegiatan pendidikan. Untuk siapakah seluruh sistem pendidikan pesantren? Bilamana hal ini dipertanyakan untuk siapakah seluruh sistem pendidikan pesantren, jawaban bisa diberikan dalam bentuk konstatasi tentang pesantren dalam kalangan pesantren sendiri sebagi berikut: "bilamana dari puluhan ribu santri yang tinggal di pesantren setengah persen saja di antaranya dapat menjadi ahli agama, itu sudah merupakan hasil yang maksimal". Hal tersebut mencerminkan proses seleksi yang ketat sekali dalam pesantren masa sekarang. Inilah titik balik dari perkembangan pesantren yang menjalani masa hidupnya ratusan tahun hingga sekarang. Penyaringan yang ketat adalah penanaman benih elitisme dalam pesantren. Hal semacam ini sebenamya berbeda dengan pesantren sebagaimana dapat ditelusuri kekhasannya piida titik mulanya yang paling awal. Di masa-masa yang lalu pesantren itu adalah satu-satunya lembaga pendidikan. Dalam saat di mana semua mereka yang memiliki darah biru kebangsawanan dan mereka yang karena hubungannya dengan keraton dididik dalam lembaga pendidikan kekeratonan, pesantren menampung semua lapisan masyarakat yang tidak ditampung dalam lembaga pendidikan keraton. Karena itu dulunya pesantren sebagai lembaga pendidikan adalah sebuah lembaga pendidikan umum; di dalamnya tidak hanya diajarkan agama.
Dalam perkembangannya akhir-akhir ini tampak kecenderungan untuk menciptakan pesantren sebagai lembaga pencetakan para ulama. Penyempitan kriterium dengan sendirinya bergerak menuju penciutan lapangan bagi orang yang akan dikirim ke pesantren yaitu orang-orang yang merasa dirinya santri dan memiliki komitmen kepada Islam sebagai ideologi. Dengan mempertahankan kriterium semacam ini maka bisa dilihat bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan di mana tingkat drop-out cukup besar. ltulah perkembangannya pada tahun menjelang kemerdekaan sampai kira-kira tahun tujuhpuluhan ini. Pada tahun-tahun terakhir timbul elemen baru di mana pesantren merupakan penampung ribuan bahkan puluhan ribu mereka yang karena alasan tertentu tidak dapat ditampung di sekolah-sekolah luar baik karena fasilitas, biaya dan lain sebagainya, maupun karena tak dapat memenuhi standamisasi entah itu akhiak atau persyaratan lain yang terdapat di sekolah umum. Bahkan pada tahun-tahun terakhir pesantren itu juga dapat tambahan fungsi untuk menampung anak-anak nakal yang tidak dapat diatasi oleh sekolahsekolah lain atau oleh orang tuanya. Malah pesantren juga menjadi penampung anak-anak yang menjadi korban erosi kultur dalam kota-kota besar. Jadi dengan demikian, tidak dapat ditentukan dengan persis dari mana asal usul kalangan yang mengirim anak-anaknya ke pesantren. la selalu berubah menurut perubahan fungsi dari pesantren itu sendiri. Sepintas kelihatan semua pesantren sama. Di sana ada kiai, santri, dan tempat penampung. Akan tetapi selebihnya berbeda, seperti sidik jari yang senantiasa berlainan menurut telapak setiap tangan. Bisa saja dikatakan bahwa ada orientasi elitis dalam pesantren. ltupun tergantung lagi pada pemahaman kita tentang elitisme. Bilamana dengan orientasi elitis dimaksudkan tingkat sosial-ekonomis dari orang tua anak yang dikirim ke pesantren, juga dalam hal ini tidak dapat dilihat kesamaan dari pesantren yang satu ke pesantren yang lainnya. Bisa disebutbeberapa contoh seperti pesantren tarekat dan Pesantren Tebuireng yang kebanyakan menampung mereka dari kalangan bawah. Sedangkan pesantren seperti Gontor jelas kelihatan bahwa yang ditampung di sana adalah mereka dari kalangan pedagang dan intelektual. Anakanak dari mereka yang dianggap kaum pemikir dalam masyarakat, guru dan lain sebagainya. Dari segi ini bisa dilihat orientasi elitis di sana. Pada pihak lain konsep elitisme dalam pesantren juga tak bisa diterima secara serta-merta. Melihat tempatnya yang di desa dia menampung mereka yang karena alasan sosial ekonomis tidak tertampung di tempat lain. Ini berarti juga dia menampung mereka yang tidak memiliki privilese-privilese sosial. Hasilnyapun bisa dilihat. Pesantren senantiasa menghasilkan pemimpin masyarakat yang pandangan hidupnya populis, baik itu dari kalangan ABRI maupun dari Parpol/Ormas yang tidak terikat pada stratifikasi sosial yang beraneka ragam itu. Mengubah Wajah Pesantren: Matangkan Kerangkanya
Bahwa pesantren lebih memberikan kesan sebagai lembaga pendidikan keagamaan
mungkin itu adalah kesan yang sulit dielakkan. Akan tetapi pengertiannya harus dijelaskan terlebih dahulu. Karena ada memang pesantren di mana dikhususkan pendidikannya untuk mencapai spesialisasidalam bidang keagamaan.Misalnya di Tebuireng di mana diadakan spesialisasi tentang Hadis, ilmu Tafsir, atau di Krapyak di mana dibuat spesialisasi tentang ilmu-ilmu bahasa Arab. Akan tetapi ada juga yang hanya memberikan pelajaran agama sebagai dasar. Dan tidak sampai menuju kepada spesialisasi. Dari segi pandangan lain bisa dikatakan sebagai berikut. Pendidikan keusahawanan misalnya bukanlah suatu yang asing dalam pesantren. Terutama tentang konskuensi dari pendidikan semacam itu yaitu etos kerja keras. Hal semacam itu selalu menjadi tekanan pokok dalam pendidikan di pesantren. Akan tetapi pendidikan kepengusahaan tersebut tidak terkoordinir dan tidak direncanakan dan untuk itu dibuat kerangkanya. Akibatnya akan keluar usahawan-usahawan yang mencari-cari jalan sendiri. Mereka akan menjadi usahawan-usahawan yang otodidak, yang tidak mendekati masalahnya dari segi-segi ilmiah tetapi berdasarkan intuisi. Akhir-akhir ini ada upaya memasukkan ke dalam pesantren pendidikan keterampilan. Usaha semacam itu adalah usaha yang terpuji dan bukanlah suatu yang buruk dalam dirinya. Akan tetapi kegunaannya menurun bilamana sistem pendidikan keterampilan semacam itu hanyalah keterampilan demi keterampilan dan meniru sekolah-sekolah seperti ASMI misalnya. Sekolah-sekolah semacam itu adalah konsumsi kota besar, dia tidak berfungsi bagi sekolah yang tempatnya di desa dan berorientasi menuju desa, karena memang bukan semua tamatannya akan menuju ke kota. Stenografi, demikian pula pelajaran mengetik tidaklah terlalu penting bagi masyarakat di desa. Yang jauh lebih penting ialah pendidikan pengusahaan yang menitik beratkan misalnya bagaimana melihat desa sebagai suatu potensi pasaran, serta bagaimana mengolahnya. Dan kita pun melihat lagi perubahan sebagaimana yang dilakukan di pesantren Darul Falah di Bogor. Di sana pelajaran agama sangat minim. Di sana dilatih keterampilan pertanian, petemakan dan lain-lain. Sebenamya hampir-hampir bisa dikatakan bahwa bukanlah pelajaran agama yang diberikan di sana, tetapi ilmu untuk menyadari pentingnya arti agama. Yang terpenting ialah pada mereka ditanam kesadaran dan keinginan mengubah kehidupan masyarakat melalui penciptaan etos kerja berdasarkan suatu pandangan agama di bidang pertanian misalnya. Dan itu tidaklah menjadi soal. la bukanlah suatu yang buruk. Asal saja memang ada kerangkanya. Di sinlah letak kelemahan program keterampilan yang diadakan departemen agama. Tidak diciptakan kerangkanya. Sepanjang yang saya dengar hanya untuk menumbuhkan sifat keterampilan di kalangan santri, agar santri bisa mencari makannya sendiri. Akan tetapi yang lebih dibutuhkan ialah kerangka yang mampu menumbuhkan sikap jiwanya. Sebab kalau hanya keterampilan yang diajarkan, tanpa dibilang mengapa dan apa gunanya, hasilnya seperti yang disaksikan sekarang. Banyak pesantren yang menolak pendidikan keterampilan dari departemen agama. Ini suatu kenyataan yang harus diakui. Program semacam ini hanyalah diterima oleh
pesantren yang kecil saja sedangkan pesantren besar dan berpengaruh menolaknya. Kalaupun mereka menerima, hanyalah sebagai hiasan bibir belaka. Dan tidak ada yang menerima secara terbuka dan menjadikannya suatu program, karena memang tidak ada kerangkanya. Dan karena itu orang tidak merasakan komitmen kepada suatu tujuan. Hidupkan Sikap Sosial Penunjang
Perkembangan masyarakat banyak menuntut perubahan yang harus dilakukan oleh pesantren. Tentu saja hal semacam ini tidaklah mudah mengingat tradisi lembaga pesantren yang sudah berabad-abad lamanya. Banyak hambatan yang harus dilewatinya sebelum suatu jenis perubahan tertentu ditawarkan. Hambatan pertama adalah sebenamya soal pimpinan. Kepeminpinan pesantren adalah suatu lembaga yang turun-temurun atau modelnya hierarkis. Karena itu sulit untuk diadakan perpindahan yang wajar secara teratur baik dan pembinaan calon penggantinya. Ini yang harus dipecahkan. Dan cara pemecahannya adalah komunikasi yang lebih efekrif antara calon pemimpin pesantren. Bilamana mereka yang tua telah mapan dan sulit berubah, maka hal semacam itu haruslah lebih dituntut dari mereka yang lebih muda. Dari mereka yang lebih muda diminta suatu pemikiran dalam konteks makro, yaitu memikirkan pesantren secara keseluruhan dan bukannya pesantrennya sendiri saja. Masalah kedua ialah masalah pembiayaan pesantren. Dulu pesantren didukung oleh masyarakat dalam pembiayaan dan sebagainya. Akan tetapi hal semacam itu pada masa dahulu merupakan suatu kebiasaan sosial dan karena itu tidak dilembagakan. Akan tetapi setelah kita sanggup lagi mengembangkan etik sosial yang membiasakan masyarakat membiayainya sekarang, akhimya pesantren kekeringan biaya. Lantas mereka akan berbondong-bondong memalingkan mukanya kepada pemerintah untuk meminta bantuan. Sedangkan pemerintah sudah dibebani beban yang berat dalam pembiayaan pendidikan. Pada hemat saya inilah suatu kekeliruan. Kesalahannya bukan pada fakta memintakan bantuan kepada pemerintah. Akan tetapi kesalahan terbesar ialah pihak pesantren tidak mampu menciptakan sikap sosial tertentu yang memungkinkan atau mendorong masyarakat membiayai pesantren. Hanya kemauan yang Piala Dunia '82 dan Landreform Oleh Abdurrahman
Wahid
Sungguh mati kawan satu ini membuat bingung orang. Ia mengajukan teka teki aneh: apakah persamaan antara perebutan Piala Dunia sepakbola untuk tahun 1982 ini dan Landreform? Siapa tidak garuk-garuk kepala mencari hubungan antara dua hal yang begitu berbeda itu. Menurut jenius kampungan ini ( dan semua jenius memang kampungan), ada satu watak pertandingan-pertandingan 'Mundial 1982' di Spanyol sekarang. Yakni
menangnya
pola
'
bermain
bola
negatif'.
Contohnya: bagaimana mungkin kesebelasan Jerman Barat, yang harus main sabun untuk bisa lolos ke putaran kedua, setelah kalah dari kesebelasan tingkat sedang Aljazair, dan hanya mampu mencapai semi final karena perbedaan selisih gol, kenapa kesebelasan macam itu bisa memiliki peluang sangat besar untuk jadi juara? Italia juga bermain negatif, dan itu dilakukannya dengan Cattenaccio, Ia cenderung mencari kelemahan lawan, lantas mempertaruhkan serangan balik sebagai kelebihan. Demikianlah, siapa pun yang jadi juara 'Mundial 1982' tidak akan mampu mengangkat keharuman sepak bola sebagai seni. Piala Dunia menurun kualitasnya, menjadi industri pertukangan. Yang berlaku adalah sikap negatif : menahan gedoran lawan sambil mengintai kelemahan lawan. Nah, siapa bilang itu tidak sama dengan keadaan landreform ? Pihak tuan tanah yang memiliki lahan pertanian luas (apakah itu perorangan, 'keluarga besar' maupun perusahaan besar multi-nasional), tidak pemah 'menyerang' dengan sikap positif, mengajukan gagasan-gagasan berharga untuk menjamin keadilan penguasaan tanah sebagai unit produksi. Yang diambil adalah sikap negatif: tunggu saja gedoran kekuatan politik yang menghendaki penataan kembali pola pemilikan dan penguasaan tanah. Nanti toh akan ada kelemahannya. Kalau landreform dilakukan secara sentrlistis, banyak 'kemenangan' dicapai tuantuan tanah melalui lubang-lubang peraturan dan cara kerja yang dianut birokrasi pemerintahan yang melaksanakan landreform itu sendiri. Kalau didesentralisasikan, dengan jalan diserahkan kepada lembaga tingkat desa seperti LKMD, 'wakil-wakil' rakyat di tingkat desa itu akan dibeli dan di teror. Bukankah lalu mudah sekali dikandaskan cita-cita mulia membagi kembali tanah pertanian, dan dicapai kemenangan di pihak tuan tanah? Begitulah yang dikatakan kawan sang jenius kampungan baik perebutan Piala Dunia 1982 maupun perebutan tanah lahan pertanian sepanjang masa, selalu dimenangkan tim negatif. Lalu, apa gunanya dibuka kotak pos baru 'khusus untuk urusan agraria'? Entahlah, yang jelas tidak banyak yang dapat diperbuat para pejabat di bidang agraria kalaupun masih ingin berbuat sesuatu bagi kepentingan masyarakat.Perangkat peraturan tentang tanah belum memungkinkan, karena UU Pokok Agraria dan UU Pokok Bagi Hasil belum 'diberi gigi' institusional dan hukum. Pintu Masuk Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Dalam kehidupan rumah tangga, pintu masuk merupakan tempat kita masuk atau
keluar dari ruang tamu. Bisa berupa pintu masuk biasa, ataupun pintu masuk yang punya lambang tertentu dalam kehidupan kita. Seperti pintu masuk yang memisahkan ruang luar/balai pertemuan dan ruang dalam, seperti dalam Istana/pemisah antara berbagai ruang kraton. Di sini tiap pintu mempunyai arti sendiri-sendiri. Dalam berbagai rumah feodal, kita memasuki sebuah lorong yang pada pinggir permukaannya ada dua buah payung yang tujuannya mengeluelukan orang yang lewat di lorong itu. Terkadang lorong itu tertutup, terkadang ia hanya memiliki tembok setengah badan. Karenanya, kalau hujan maka lorong itupun akan menjadi basah. Seorang teman memiliki lorong seperti itu, mungkin ia masih berpikir bahwa masuk ke rumahnya berarti masuk ke dalam Kraton. Sindrom menjadi raja. Lain halnya dengan pintu masuk di stasiun kereta api, yang jeruji-jerujinya ditutup untuk mencegah masuknya orang sebelum kereta api tiba di stasiun itu. Dapat digambarkan di pintu stasiun itu, betapa banyaknya orang yang akan masuk sekaligus, dan langsung berlari mencari tempat duduk masing-masing di gerbonggerbong yang akan dinaikinya. Bahwa kita belum dapat mengatur alur penumpang sebelum kereta api datang, menunjukkan bahwa perusahaan kereta api belum dapat mengatur para penumpang kita sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Semua serba berebut tempat, sedangkan nanti kalau kereta api meneruskan perjalanan, temyata jumlah penumpang jauh lebih besar dari pada jumlah kursi yang ada. Ini terjadi boleh dikata dihampir setiap stasiun kereta api, kecuali yang besar-besar (Gambir, Jakarta kota- Beos, Semarang, Solo, Pasar Turi dan Gubeng di Surabaya). Jika melihat antrian penumpang yang berdesak-desak secara tidak ada perlunya, bangsa lain akan menganggap bangsa kita tidak mengerti aturan dalam transportasi umum. Ini belum lagi kalau kita menaiki kapal laut dari tangga di sisi kapal, yang sama saja seperti di pintu stasiun kereta api tadi. Calon penumpang berdesak-desak naik ke atas kapal, walau sudah punya karcis kamar untuk penumpang kelas, maupun alokasi tempat tidur di atas gladak jika hanya berkelas gladak. Demikian rupa orang berdesakan naik ke atas kapal, hingga diperlukan satpam pada awal tangga, untuk mengatur alur penumpang itu. Jadi di samping kontroler karcis kapal, ada juga satpam yang harus mengatur agar orang berbaris dengan teratur untuk masuk ke dalam kapal melalui tangga. Bahkan di lapangan terbang/ airport, yang digunakan kalangan menengah dan atas, masih terjadi salah memasuki pintu masuk. Masih saja ada penumpang yang memasuki ruang masuk yang salah. Setelah ditolak di pintu masuk, baru ia sadar bahwa ia keliru jalan. Padahal pintu masuk di lapangan terbang ditulis dengan jelas pada beberapa neon box yang ada di tubuh utama pintu masuk, serta pada permukaan lorong menuju pintu masuk. Jika ia menggunakan kuping dan matanya baik-baik ia akan mendapati pintu itu dengan mudah. Salah masuk itu juga terkadang disertai kenyataan, bahwa penumpang tersebut belum mendaftarkan diri (check-in) sehingga ia harus kembali ke tempat itu. Bahkan mungkin kehilangan tempat duduk yang tadinya ia pesan, tapi kemudian digantikan orang lain karena ia terlambat check-in. Itu ini terjadi pada umumnya atas penumpang baru, yang belum pemah naik pesawat terbang atau menjadi
penumpang *****
sebelumnya.
Nah, keadaan pintu masuk itu sendiri bisa juga tidak meyenangkan atau mengusik perasaan calon-calon penumpang. Baru-baru ini, untuk berminggu-minggu lamanya pintu masuk F1 dan F7 di airport Cengkareng misalnya selalu diisi oleh pesawat-pesawat terbang milik Lion Air. Padahal tadinya ia menjadi pintu masuk tetap bagi pesawat-pesawat milik Garuda, yang digunakan untuk masuknya penumpang bagi pemberangkatan dan kedatangan dari Surabaya. Temyata, sudah dua kali Garuda harus angkat kaki, memberangkatkan para penumpang dengan naik bis/ mobil van, karena pintu masuk F1 dan F7 dipakai oleh pesawat-pesawat terbang milik Lion. Apa boleh buat, kejengkelan kepada aturan seperti itu memang terasa bagi para calon penumpang pesawat-pesawat Garuda itu, karena mereka harus naik turun melalui tangga/lift, yang berarti memperlambat keberangkatan mereka. Padahal mereka telah membayar tiket pesawat minimal 2 kali lipat harga tiket pesawat Lion. Ini berarti pelayanan keberangkatan mereka dikalahkan oleh Lion yang boleh dikata setingkat berada di bawah Garuda. Kalau semua pesawat yang berbeda-beda tarif itu disamakan, maka apa gunanya perbedaan tersebut? penulis tidak bisa berkesimpulan lain dari kenyataan bahwa ada orang kuat dalam tubuh Dewan Komisaris Lion Air. Dengan dukungan si orang kuat itu, mula-mula pesawatnya dapat diberangkatkan dari terminal 2-F1, yang dahulunya khusus diperuntukkan bagi para penumpang yang melalui terminal 1A/1B/1C di Airport Cengkareng. Kalau memang menghendaki perpindahan terminal itu, seharusnya Lion menggunakan tariff penumpang seperti yang digunakan Garuda. ***** Prinsip dunia usaha yang bersifat persaingan harus diterapkan di sini, guna optimalisasi pelayanan sewaktu tinggal landas, dalam penerbangan dan setelah mendarat. Penggunaan prinsip sama rata akan mematikan dunia usaha itu sendiri. Ini adalah permulaan dari penanganan ekonomi secara salah, yang jika diperluas terus menerus, akan membuat ekonomi itu sendiri menjadi salah urus dan tidak efisien. Ekonomi yang sedemikian itu biasanya ditandai oleh penggunaan faktorfaktor non-ekonomi secara tidak fair dan tidak mengindahkan asas-asas ekonomi. Jika usaha penerbangan kita yang baru akhir-akhir ini menggunakan faktor persaingan bebas dalam penggunaan modal dan sumber-sumber lain, tidak layaklah kiranya jika harus mendasarkan keputusan yang diambil melalui pengaruh politik dan sebagainya. Teranglah bagi kita, harus ada kejelasan mengenai pengaruh modal dengan kebolehan/kemampuan dalam menetapkan harga/biaya bagi semua hal, termasuk bagi penggunaan ruang tunggu dan pintu masuk. sesuatu yang tidak berdasarkan perhitungan komersial haruslah ditolak sejak awal. Mula-mula Lion Air meminta agar boleh berangkat dari pintu masuk pesawat-pesawat Garuda, sesuatu yang menyalahi aturan, karena tarifnya separuh lebih rendah dari pada Garuda,
sehingga seharusnya ia terbang dari pintu-pintu masuk terminal 1 di Cengkareng. Jadi mengabulkan permohonan itu, apapun sebabnya, adalah pelanggaran terhadap prinsip pengembangan ekonomi secara bebas. Kemudian, jika permohonan untuk itu diberikan, maka akan diminta pula penggunaan pintu masuk yang gemuk di terminal 2. Nah, karena itu, penulis mengharapkan Garuda berkeberanian moral untuk menolak permintaan itu, siapun backingnya. Hanya dengan cara demikian dapat dilaksanakan privatisasi ekonomi kita secara bersungguh-sungguh. Bagi kebutuhan pokok yang tidak dapat diserahkan kepada persaingan bebas, pemerintah harus menyediakan dana melalui anggaran khusus di luar RAPBN (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang harus dihentikan begitu kemampuan berkembang oleh sektor tersebut. Dalam keadaan demikian, pihak swasta harus sanggup mengembangkan diri sendiri tanpa bantuan pemerintah. Jadi tidak ada sub-sektor ekonomi yang menjadi tanggungan pemerintahan dalam jangka panjang. Karena hal itu berkaitan dengan LOI (Letter of Inters) dari Dana Moneter Intemasional (IMF) yang sangat mencekik dan harus langsung dilaksanakan tanpa memperhitungkan kondisi sosial ekonomis yang ada dewasa ini. Jadi kita harus sanggup menyakinkan Dana Moneter Intemasional untuk mempertahankan hal yang benar-benar diperlukan, bukannya asal potong/hentikan subsidi saja. Mudah dalam ucapan, namun sulit dalam pelaksanaan, bukan? Rasionalitas Kiai Adlan Oleh
Abdurrahman
Wahid
Senyum selalu menghiasi wajahnya yang terlihat penuh ketulusan. Senang bergurau secara halus, banyak menjawab secara mengelak, dan senantiasa menunjukkan kerendahan hati dalam bersikap dan bertutur kata. Naik apa tadi ke sini tadi, Kiai? "Wab, saya beli Colt di depan rumah, sampai di terminal saya jual lagi, terus naik becak kemari," jawabnya dengan senyumnya yang khas. Seorang peneliti datang ke rumahnya di dekat Pesantren Tebuireng, sesuai dengan tugas yang diterimanya dari Leknas dan UGM Yogya. Dulu belajar apa saja kepada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai? Jawab sang kiai dengan senyum yang tidak pemah hilang itu. "Hanya kitab Taqrib saja". Sang peneliri bingung, karena teks yang satu ini begitu kecil dan merupakan bukti teks dasar saja di pesantren. Hanya itu saja Kiai, tidak ada yang lain? "Ada juga yang lain, malah banyak kitab lain, tetapi saya sudah lupa, "jawab sang kiai mengelak. Larangan berpamer kepandaian adalah bagian dari kehidupannya. Sang peneliti kembali membawa kebingungannya. Sebingung seorang pewawancara yang menerima info langsung dari kiai kita ini, bahwa di waktu mudanya ia jago balap mobil. "Waktu lampu mobil masih pakai karbit, saya sudah senang ngebut, sekitar tahun sembilan belas dua puluh lima", cerita sang kiai.
Bagaimana tidak membingungkan karena cukup kontras dengan keadaan fisiknya dewasa ini: serban yang tidak pemah tinggal dari bahu, dahi dan dua tanda hitam akibat lamanya bersujud sembahyang malam selama berpuluh-puluh tahun, dan do'a wiridnya yang begitu panjang setiap habis salat. Belum lagi hafalan penuhnya atas AI-Qur'an dan kependekarannya dalam majelis-majelis hukum agama. Jauh sekali dari bayangan semula sebagai pemuda kaya yang senang ngebut di zaman 'normal'. Tetapi yang paling membingungkan adalah pola sikap hidupnya yang penuh pembalikan pendirian, kalau di lihat sepintas lalu saja. Sebagai murid setia Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Adlan Ali tidak diizinkan memasuki tarekat semasa hidup gurunya tercinta itu. Kecintaannya itu masih melandasi hidupnya sekarang, tetapi mengapakah sepeninggalan sang guru ia justru mengikuti tarekatnya Kiai Ramli Rejoso? Bahkan lebih jauh lagi: kini ia dalam usia tujuh puluh enam tahun menjadi pemimpin tarekat sendiri, yang lebih kurang berpangkalan di Pesantren Tebuireng. Apa tidak kuatir kualat dengan Kiai Hasyim, yang dulu begitu tekun berpolemik melawan gerakan-gerakan tarekat yang ada di bumi Jawa? Apakah tidak ada konflik kejiwaan dalam dirinya, akibat pembalikan sikap itu? Temyata dalam hal Ini sudut pandang lahiriyah saja sulit untuk dapat menangkap tindakan yang secara lahiriyah itu berbentuk pembalikan sikap. Harus dimengerti, sebab-sebabnya diambil sikap seperti itu, harus didekati rasionalitas tindakan itu sendiri. Adalah ceroboh untuk begitu saja menilai suatu tindakan sebagai pembalikan sikap diketahui apakah ia benar-benar pembalikan atau bukan. Dalam kasus Kiai Adlan Ali, ketaatan asas (konsistensi) dalam berpikirlah yang menjadi sebab dari apa yang tampak dari pembalikan sikap itu. Kiai Hasyim dulu menentang ekses-ekses tarekat, bukan tarekatnya. la pemah debat dengan Kiai Khalil Rejoso, pendiri tarekat Naqsabandiyah di sana, karena dituduhnya Kiai Kholik mendakwakan kewalian bagi dirinya. Sekarang persoalannya sudah lain sekali, begitu mungkin jalan pikiran Kiai Adlan. Orang tidak bergairah menjalankan ibadah agama di luar lingkup ketarekatan. Apakah kita biarkan mereka tidak sembahyang, hanya karena takut ekses-ekses tarekat itu sendiri? Mana yang lebih perlu, mengajak orang agar sembahyang, ataukah meributkan soal ekses-ekses tarekat? Kalau dipahami jalan pikiran ini, akan menjadi jelas pula mengapa Kiai Adlan dapat mendamaikan antara keterlibatan dirinya dalam gerakan tarekat dan kecintaan (yang menghasilakan ketundukan ) dirinya kepada mendiang gurunya, Kiai Hasyim. La menerima dan tunduk kepada perintahnya Kiai Hasyim, walaupun ketundukan itu tidak hanya pada pengertian literer perintah itu sendiri saja, melainkan justru ketundukan untuk mengembangkannya dalam kasus yang sama sekali berbeda. Ketundukan itu dalam (inner obedience) yang tampak sebagai pengingkaran di luar (outer disobedience).
Beberapa orangkah dari kalangan kita yang sanggup mengikuti perintah dalam penghayatan di dalam seperti itu? Mampukah kita untuk melepaskan diri dari ketundukan luar, untuk mengejar ketundukan di dalam, suatu hal yang lebih bersifat pengembangan dan mempunyai nilainya sendiri yang mendasar? Bukankah kebalikanya yang lebih banyak kita lakukan, yaitu ketundukan di luar dan melawan di dalam? Tanyakan kepada alumus penataran P4, kalau tidak percaya! Memang menarik untuk mengikuti jalan pikiran Kiai Adlan, dengan rasionalitasnya yang unik itu. Romo, Kiai, dan Serdadu Oleh Abdurrahman
Wahid
Kematian HJ Princen tetap mengejutkan. Poncke, demikian panggilan akrabnya sehari-hari, sudah lama menggunakan kursi roda dan mengurangi kegiatannya hingga titik minimal. Namun, kita terbiasa dengan kehadiran Poncke dalam kehidupan kita. Perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) di negeri ini, terasa tidak lengkap tanpa kiprahnya. Bahwa bangsa kita tidak mampu memberikan penghargaan lebih dari yang didapatnya, adalah hal yang sangat memalukan. Meskipun demikian, kebesarannya tidak berkurang hanya karena ketidakmampuan kita itu. Poncke sendiri tidak pemah mengharapkan hal itu terjadi. Di negara tempat asalnya, Belanda, ia dianggap oleh sementara orang sebagai pengkhianat, karena meninggalkan tentara kerajaan. Ia dikirim ke Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk menghancurkan gerakan nasionalis yang menuntut kemerdekaan negeri kita. Tetapi justru malah sebaliknya, ia mengikuti para pejuang kemerdekaan kita dan berani berpihak pada yang benar. Karena itulah, oleh orang-orang yang tidak paham pemikirannya di Negeri Kincir Angin itu, ia dinamai sang pengkhianat. Sedangkan, bagi kita ia adalah seorang pejuang, yang tidak pemah mengharapkan imbalan dan tanda jasa apapun. Di negeri ini pun, lebih dari seperempat abad, ia dianggap sebagai perusuh. Setidak-tidaknya, ia dianggap oleh para penguasa (terutama golongan militer) sebagai orang yang mengganggu wewenang mereka. Padahal, ia adalah seorang pejuang HAM yang berani menderita dan dicaci maki siapa pun untuk keyakinannya membela nasib kaum lemah. Ia tidak punya apa-apa, kalau pemilikan harta benda dianggap sebagai ukuran kebahagiaan. Tetapi, ia mempunyai segala-galanya kalau perjuangan menegakkan demokrasi dan HAM dianggap sebagai capaian hidup. Kegigihan perjuangannya patut menjadi inspirasi baik bagi kawan seiring maupun generasi muda yang menggantikannya. Romo Mangunwijaya, juga mencapai kedudukan pejuang yang gigih. Walau ia sendiri tadinya adalah seorang militer, justru ia meninggal sebagai orang yang menentang militerisme. Romo yang berpendidikan arsitektur di Jerman Barat ini, menganggap TNI sudah kehilangan jati dirinya krena menggadaikan diri kepada kekuasaan yang lalim. Pendapat ini dipegangnya secara teguh hingga saat
kematiannya sekitar tiga tahun lalu. Padahal, ia kemukakan hal itu di tengahtengah memuncaknya kekuasaan politik para jenderal, hingga gereja Katolik-Roma kewalahan melindungi dirinya. Romo Mangun kaya bukan dengan benda dan materi, melainkan dengan capaian. Sebagai novelis, ia menyajikan watak-watak manusia dengan sangat indahnya dalam karyanya Burung Manyar. Novel itu memberi gambaran tentang liku-liku kehidupan manusia Indonesia di tengah-tengah berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat. Sebagai sejarawan, ia dikenal memiliki pengetahuan mendalam tentang masa lampau Indonesia, seperti para Wiraguna dan raja-raja Mataram. Pengetahuan sejarahnya itu yang dikombinasikan dengan telaah tajam tentang watak-watak manusia. Hal itu membuat pastur pejuang ini menjadi tokoh regional yang dihargai orang. Terbukti dari hadiah Magsaysay yang diterimanya beberapa waktu lalu. Di bidang pendidikan ia menunjukkan prestasi sangat menonjol. Dia kembangkan gagasan ''pendidikan dasar'' yang semula diajukan oleh Uskup Agung Recife di Brasil. Gagasan itu dia kombinasikan dengan gagasan deschooling society masyarakat tanpa sekolah dari Ivan Illich dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Jadilah kombinasi gagasan itu sebagai tantangan pendidikan dan moral bagi keseluruhan sistem pendidikan nasional di negeri ini. Pendidikan nasional kita, yang dikuasai paham serba benda materialistik, kehilangan sendi-sendi moral dan etikanya di bawah sistem kekuasaan politik yang ada. Kekuasaan itu tidak memperhatikan nasib warga negara sebagai manusia orang per-orang. Kiai Mahfudz dilahirkan di kalangan pesantren di Sumolangu, Kebumen, Jawa Tengah. Sebagaimana lazimnya saat itu, ia dididik di dalam lingkungan pesantren dengan cara pengajian sorogan dan bandongan. Akhimya ia menjadi seorang kiai dengan tipe kepemimpinannya sendiri dan dihormati rakyat Banyumas Selatan. Jadilah ia seorang kiai besar yang dihormati oleh kiai-kiai lain di kawasan tersebut. Perintah-perintahnya dilaksanakan oleh para ulama lain. Dalam perjuangan bersenjata melawan kekuasaan Belanda, pada Agresi II, ia memimpin perjuangan fisik secara gigih. Perintahnya diikuti oleh rakyat Banyumas selatan dari Purworejo hingga Cilacap. Anak didiknya ada yang kemudian menjadi pimpinan teras Angkatan Darat di belakang hari, misalnya Jenderal Sarbini. Namun, kabinet Hatta yang saat itu mendapat dukungan Jenderal Besar (saat itu masih Kolonel) A.H. Nasution, memutuskan bahwa yang dapat menjadi perwira dan komandan batalion hanyalah mereka yang berijazah belaka. Di antara yang berijazah saat itu terdapat Pak Harto yang ketika itu berijazah vervolg school sekolah lanjutan dua tahun. Dengan kriteria itu, ia tidak dapat menjadi komandan batalion di Purworejo. Tempat yang dianggapnya pantas bagi dirinya itu kemudian diisi oleh perwira A Yani. Tentu saja, ia menjadi sakit hati, dan pemberontakan bersenjata yang dilakukannya terpaksa dibayamya dengan nyawa. Ketika dia berada pada sebuah jurang di Gunung Srandil (Cilacap), ia dilempari granat dari atas. Ketiga tokoh di atas, memiliki persamaan dasar yang sangat menarik: keyakinan
akan kebenaran. Karena itulah, mereka dicintai rakyat yang melihat kehidupan ketiga orang tersebut tidaklah materialistik. Dengan demikian, kesan kemanusiaan yang mereka bawakan terasa mumi dan tidak berbau kepentingan pribadi. Princen berani meninggalkan tanah air dan meninggalkan tentara kerajaan (KL) serta memihak Indonesia. Romo Mangun berani meninggalkan kehidupan militer dan disumpah-serapahi mereka yang ditinggal di dalamnya. Romo Mangun memiliki kredibilitas seorang pejuang gigih yang sama dengan Kiai Mahfudz-Somulangu yang berjuang mati-matian melawan kekuasaan Belanda. Mereka harus dihargai karena kita adalah bangsa besar yang sangat sanggup menilai jasa-jasa para pahlawan. Bukan bangsa kelas teri yang menghargai koruptor, seperti H. Taher, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Salahkah Jika Dipribumikan? Oleh
Abdurrahman
Wahid
Islam mengalami perubahan-perubahan besar dalam sejarahnya. Bukan ajarannya, melainkan penampilan kesejarahan itu sendiri, meliputi kelembagaannya. Mulamula seorang nabi membawa risalah (pesan agama, bertumpu pada tauhid) bemama Muhammad, memimpin masyarakat muslim pertama. Lalu empat pengganti (khalifah) meneruskan kepemimpinannya berturut-turut. Pergolakan hebat akhimya berujung pada sistem pemerintahan monarki. Begitu banyak perkembangan terjadi. Sekarang ada sekian republik dan sekian kerajaan mengajukan klaim sebagai negara Islam.Ironisnya dengan ideologi politik yang bukan saja saling berbeda melainkan saling bertentangan dan masingmasing menyatakan diri sebagai ideologi Islam. Kalau di bidang politik terjadi pemekaran serba beragam, walau sangat sporadis, seperti itu, apalagi di bidangbidang lain. Hukum agama masa awal Islam kemudian berkembang menjadi fiqh, yurisprudensi karya korps ulama pejabat pemerintah (qadi, multi, dan hakim) dan ulama nonkorpri. Kekayaan sangat beragam itu lalu disistematisasikan ke dalam beberapa buah mazhab fiqh, masing-masing dengan metodologi dan pemikiran hukum (legal theory) tersendiri. Terkemudian lagi muncul pula deretan pembaharuan yang radikal, setengah radikal, dan sama sekali tidak radikal. Pembaharuan demi pembaharuan dilancarkan, semuanya mengajukan klaim memperbaiki fiqh dan menegakkan hukum agama yang sebenamya, dinamakan Syariah. Padahal kaum pengikut fiqh dari berbagai mazhab itu juga menamai anutan mereka sebagai syariah. Kalau di bidang politik - termasuk doktrin kenegaraan - dan hukum saja sudah begitu balau keadaannya, apalagi dibidang-bidang lain, pendidikan, budaya kemasyarakatan, dan seterusnya. Tampak sepintas lalu bahwa kaum muslimin terlibat dalam sengketa di semua aspek kehidupan, tanpa terputus-putus. Dan ini lalu dijadikan kambing hitam atas melemahnya posisi dan kekuatan masyarakat Islam .
Dengan sendirinya lalu muncul kedambaan akan pemulihan posisi dan kekuatan melalui pencarian paham yang menyatu dalam Islam, mengenai seluruh aspek kehidupan. Dibantu oleh komunikasi semakin lancar antara bangsa-bangsa muslim semenjak abad yang lalu, dan kekuatan petrodollar negara-negara Arab kaya minyak, kebutuhan akan penyatuan pandangan itu akhimya menampilkan diri dalam kecenderungan sangat kuat untuk menyeragamkan pandangan. Tampillah dengan demikian sosok tubuh baru: formalisme Islam. Masjid beratap genteng, yang sarat dengan simbolisasi lokalnya sendiri negeri kita, dituntut untuk dikubahkan. Budaya wali songo yang serba Jawa, Saudati Aceh,Tabut Pariaman, didesak ke pinggiran oleh kasidah berbahasa Arab dan juga MTQ yang berbahasa Arab: bahkan ikat kepala lokal (udeng atau iket di Jawa ) harus mengalah kepada sorban merah putih model Yasser Arafat. Begitu juga hukum agama, harus diseragamkan dan diformalkan: harus ada sumber pengambilan formalnya, Alquran dan Hadist, padahal dahulu cukup dengan apa kata kiai. Pandangan kenegaraan dan Ideologi politik tidak kalah dituntut harus universal ; yang benar hanyalah paham Sayyid Qutb, Abul Al Al Maududi atau Khomeini. Pendapat lain, yang sarat dengan latar belakang lokal masing-masing, mutlak dinyatakn salah. Lalu, dalam keadaan demikian, tidakkah kehidupan kaum muslimin tercabut dari akar-akar budaya lokalnya? Tidakkah ia terlepas dari kerangka kesejarahan masing-masing tempat? Di Mesir, Suriah, Irak, dan Aljazair, Islam dibuat menentang nasionalisme Arab - yang juga masing-masing bersimpang siur wama ideologinya. Di India ia menolak wewenang mayoritas penduduk yang beragama Hindu, Untuk menentukan bentuk kenegaraan yang diambil. Di Arab Saudi bahkan menumpas keinginan membaca buku-buku filsafat dan melarang penyimakan literatur tentang sosialisme. Di negeri kita sayup-sayup suara terdengar untuk menghadapkan Islam dengan Pancasila secara konfrontatif - yang sama bodohnya dengan upaya sementara pihak untuk menghadapkan Pancasila dengan Islam. Anehkah kalau terbetik di hati adanya keinginan sederhana : bagaimana melestarikan akar budaya-budaya lokal yang telah memiliki Islam di negeri ini? Ketika orang-orang Kristen meninggalkan pola Gereja kota kecil katedral serba Gothik di kota-kota besar dan gereja kota kecil model Eropa, dan mencoba menggali Aritektur asli kita sebagai pola baru bangunan gereja, layakkah kaum muslimin lalu berkubah model Timur Tengah dan India? Ketika Ekspresi kerohanian umat Hindu menemukan vitalitasnya pada gending tradisional Bali, dapatkah kaum muslimin berkasidahan Arab dan melupakan pujian berbahasa lokal tiap akan melakukan sembahyang? Juga mengapa harus menggunakan kata shalat, kalau kata sembahyang juga tidak kalah benamya? Mengapakah harus dimushalakan, padahal dahulu toh cukup langgar atau surau? Belum lagi ulang tahun, yang baru terasa sreg kalau dijadikan milad. Dahulu tuan guru atau kiai sekarang harus ustadz dan syekh,
baru terasa berwibawa. Bukankah ini pertanda Islam tercabut dari lokalitas yang yang semula mendukung kehadirannya di belahan bumi ini? Kesemua kenyataan di atas membawakan tuntutan untuk membalik arus perjalanan Islam di negeri kita, dari formalisme berbentuk Arabisasi total menjadi kesadaran akan perlunya dipupuk kembali akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejarahan kita sendiri, dalam mengembangkan kehidupan beragama Islam di negeri ini. Penulis menggunakan istilah pribumisasi Islam, karena kesulian mencari kata lain. Domestikasi Islam terasa berbau politik, yaitu penjinakan sikap dan pengebirian pendirian. Yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka. Bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan Quran Batak dan Hadis Jawa. Islam tetap Islam, dimana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk-luarnya. Salahkah kalau Islam dipribumikan sebagai manifestasi kehidupan? Sang Kiai dan Keyakinannya Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kiai Ali murah senyum. Kiai yang menjadi anggota DPR mewakili sebuah daerah di luar Jawa ini jarang mengeluarkan suara, meskipun itu tentu tidak ada hubungannya dengan watak hidup lembaga perwakilan saat ini. Gerak-geriknya halus, tegur sapanya ramah, suaranya tidak keras dan selalu lebih banyak mendengarkan ucapan orang dari pada berucap sendiri. Tingkah lakunya merendah, sesuai dengan akhlak yang dirumuskan dalam kitab-kitab kuno, Mungkin jarang makan di luar,jajan di restoran dan sebagainya, karena menurut kitab Ta'limul Muta'allim makanan seperti itu kurang berkahnya. Tetapi tanda lahlriyah yang berupa senyumannya yang khas yang paling nampak dalam pergaulan. Mendengar pujian orang lain ia hanya tersenyum mungkin heran mengapa sampai begitu jauh pujian diberikan bagi tindakan atau sifat yang dianggapnya sendiri sebagai hal yang biasa. Mendengarkan argumentasi yang bertele-tele dalam rapat fraksi maupun kelompok, ia juga tersenyum saja. Mungkin geli mendengarkan alasan yang tidak masuk akal yang sering diajukan, kalau tidak malahan alasan kekanak-kanakan. Bahkan mendengarkan kritik pun Kiai Ali selalu tersenyum: hormatilah pendapat yang berbeda dengan pendirianmu. Begitu kata kitab-kitab kuno tentang tata cara berdebat (adabul munadzarah). Begitu rendah hati dalam bersikap, dan begitu lemah lembut dalam berkomunikasi. Yang terjadi adalah ke bahkan dari harapan para penulis kuno yang begitu getol menganjurkan sifat keksatriaan dan kebijaksanaan seperti itu. Bukannya penghormatan dan toleransi yang didapatkannya dari orang lain melainkan
penghormatan
di
mulut
dan
sodokan
di
pinggang
yang
diperoleh.
Walhasil, profil dari tragisnya wibawa moral yang tidak dilayani orang lain. Dianggap lemah dalam pendirian, karena terlalu banyak memberikan kesempatan pada pihak lain. Dikira tidak tegas, karena tidak mau memberikan keputusan cepat-cepat. Dituduh tidak memiliki kepemimpinan karena tidak 'keras' dan berani. Walhasil, tidak memenuhi citra orang dinamis yang penuh inisiatif dan memiliki dorongan untuk berprestasi tinggi. Tidak mempunyai 'kebutuhan mencapai sesuatu' (need of achievement) dalam hidup ini. Pantas tidak berjiwa wiraswasta, maklum kiai! Yang sering dilupakan adalah sebuah aspek penting dari kehadirannya, yaitu kemampuannya mengajukan penunjang dari pandangan keagamaan atas berbagai hal yang merupakan pemikiran atau gagasan rintisan. Banyak hal yang tadinya tadinya tidak diperkenankan oleh agama, temyata memiliki dimensi kompleks yang tadinya dianggap tidak bersangkut paut dengan pandangan agama, temyata ada landasan keagamaannya juga. Banyak masalah yang tadinya dikira tidak patut dikemukakan pada kalangan kiai, temyata ditunjukannya sudah dirembuk para ulama sejak berabad-abad yang lalu. Penulis sendiri tercengang ketika kiai yang satu ini memaparkan hubungan agama dengan strategi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pokok, itu basilc need strategy yang sekarang menjadi benderanya kaum membangun dari orientasi politik berlain-lainan. Di kitab Fathul Mu'in ada masalah itu, kata Kiai Ali. Coba lihat di bagian Jihad yang pengertiannya bukan seperti disangka orang selama ini. Jihad adalah perang suci secara militer menurut alasan keagamaan itu kalau diserang. Tetapi jihad yang lain juga kewajiban fakultatif (fardlu ktfayah): menyebarkan ajaran agama, membuktikan kebenaran dan ke-Esa-an Allah, juga menyediakan kebutuhan pokok manusia, itu semua adalah jihad. Bagaimana mungkin menyediakan kebutuhan pokok dianggap jihad, Kiai? Karena memang begitu perumusannya, jawab Kiai Ali. Coba lihat rumusannya: menjaga dari kerusakan mereka yang dilindungi Islam. Bagaimana mungkin dijaga dari kerusakan, kalau tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya? Karena itu jangan heran kalau syarah (komentar) Fathul Mu'in, judulnya I'anah, merumuskan kewajiban jihad yang satu ini sebagai berikut: menyediakan makanan utama (qut) sebanyak 0,6 kg beras sehari per orang untuk kawasan kita di sini, pakaian dua stel satu tahun, tempat tinggal yang aman dari gangguan, dan biaya pengobatan. Lalu apa namanya rumus begini ini, kalau bukan kebutuhan pokok? Ditanya tentang sterilisasi, aborsi dan masalah-masalah 'gawat' sebangsa itu, Kiai Ali tidak langsung menjawab boleh atau tidaknya. Harus ada kriteria dahulu, yang dalam bahasa kitabnya syarat-masyrut-nya. Dilihat kesesuaiannya dahulu antara tujuan dan metode yang digunakan untuk mencapainnya, atau menurut kitab kuning, ghayah wal wasa'il-nya. Harus dihadapkan dahulu kepada kenyataan situasional (waqiah)-nya, sehingga kita tahu tepat apa yang menjadi kehendak kita (gharat) dalam sesuatu persoalan. Tidak mudah, bukan?
Kalau dilihat dari sudut pengamatan ini, jelas bahwa Kiai All bukanlah orang yang semudah diperkirakan seperti semula. Murahnya senyum yang menghiasi bibir tidak berarti ketololan untuk menyatakan pendapat tanpa mengkaji dahulu persoalannya secara mendalam. Kecenderungan untuk berlama-lama mengambil keputusan bukanlah sesuatu yang tidak direncanakan, melainkan untuk menghadapkan persoalan secara situasional kepada pendapat ulama di masa lalu seperti yang tercantum di kitab-kitab kuno. Keengganannya untuk memberikan 'ketegasan' dalam sesuatu persoalan adalah hasil dari pengetahuan yang mendalam tentang kekurangan yang ada pada berbagai altematif yang dihadapkan satu kepada yang lain sudah tentu dengan tujuan mencari pendapat akhir yang sangup menutupi semua kekurangan tersebut. Dengan demikian, apa yang secara lahiriyah tampak sebagai sikap ragu, sebenamya adalah 'pengarahan' orang lain untuk berfikir lebih lengkap dan menyadari kompleksitas persoalan. Apa yang tampak sebagai 'kurangnya kepemimpinan' sebenamya adalah pertanggungjawaban keberanian untukmengambil sikap akhir yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kita, dan yang memiliki landasan keagamaan yang kuat dalam arti sebenar-benamya. Tidak heranlah kalau orang yang tampaknya lemah lembut, mengalah saja kepada orang lain, dan tidak pemah memaksakan pendirian kepada orang lain ini, sebenamya juga orang yang berpendirian teguh kalau sudah sampai pada kesimpulan. Tidak beranjak dari pendirian, tidak bergerak juga oleh gangguan, karena ia sampai kepada kesimpulan melalui proses dan sangat kompleks. Apa yang diperoleh, dimiliki, dan kemudian diperintahkan mati-matian bukan lagi hanya sebuah kesimpulan tentang sesuatu persoalan, tetapi telah menyadari sebuah pendapat yang dianggap paling benar. la sampai kepada keyakinan. Saya Juga Keturunan Lembu Peteng Oleh: Abdurrahmam
Wahid
Secara umum diterima "kebenaran", Ken Arok merebut keraton Singasari dari tangan Tunggl Ametung, orang yang mengawini ibunyadan berimplikasi membunuh ayahnya. Beberapa tahun yang lalu muncul versi lain. Temyata Ken Arok tidak membunuh pembunuh ayahnya, melainkan membunuh ayahnya sendiri. Siapa sang ayah? Tidak lain Tunggul Ametung. Lalu apa motif pembunuhan? Karena Ken Arok anak kandung di luar pemikahan resmi keraton, alias anak dari garwa selir. Tetapi, bahkan, harus diragukan, benar-benarkah ia melakukan pembunuhan. Mungkin, ceritanya hanya simbolik saja. Seorang anak yang bukan putera mahkota memaksakan diri menjadi raja. Kan sama dengan membunuh ayahnya.
Jika benar pula versi baru itu, berarti Ken Arok termasuk barisan sejumlah pangeran yang memiliki status tersendiri, yakni lembu peteng, anak yang tidak diakui sah sebagai pewaris tahta, tidak termasuk dalam daftar suksesi keraton. Dan "lembaga" lembu peteng memang memiliki banyak keunikan, meski sepintas lalu tampak sepele. Pertama, ia memberikan status kekeratonan kepada seseorang tanpa memberikan kedudukan formal yang jelas dan pasti. Kedua, ia membawakan implikasi adanya tempat bagi "elite tandingan" di keraton yang masih berada dalam sistem kekuasaan tanpa menjadi bagian mekanisme kerjanya. Ketiga, ia menyediakan jenjang yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk mengajukan klaim atas tahta, jika keadaan menjadi sangat kritis dan diperlukan kepemimpinan yang dapat menyelesaikan kemelut. Yang terakhir ini hampir sama fungsinya dengan doktrin dwifungsi ABRI. Tidak heran jika "lembaga" lembu peteng lalu bemilai tinggi di bursa kepangeranan keraton Jawa masa lampau. Banyak raden dari berbagai tingkatan mengaku keturunan lembu peteng anu. Bahkan, kalangan luar ningrat cukup berminatseperti silsilah kiai Pondok Tebuireng yang berujung pada lembu peteng Keraton Majapahit, seorang anak selir Prabu Brawijaya, entah yang keberapa. Keturunan kiai Tebuireng yang tidak bangga anaknya menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya di Malang itu temyata cukup berdebar-debar meluruskan garis silsilah ke Majapahit, kini Mojokerto. Mahluk Aneh Kenyataannya, faktor keturunan, atau tedak, di kalangan pesantren memberikan legitimasi bagi klaim kepemimpinan masyarakat di luar kepemimpinan resmi yang jumeneng di takhta kerajaan. Untuk memperoleh kedudukan menjadi pemimpin di luar pemerintahan dalam budaya masyarakat Jawa, masih diperlukan pengesahan dan penerimaan oleh pihak yang berkuasa. Zaman sekarang menggunakan SK dan "jasa-jasa baik pemerintah". Dahulu menggunakan lembu peteng. Dapat ditarik kemudian dari sejarah lama kita, seperti yang terjadi di keratonkeraton Jawa, pentingnya memperoleh legitimasi pemerintah dalam segala hal. Kekuasaan raja (Jawa: ratu) begitu mutlak, hingga tidak ada yang tidak terjangkau. Semua penjuru kerajaan yang masih masuk negara maupun mancanegara adalah wilayah yang sama mutlak dikuasainya. Tidak ada kegiatan bermasyarakat yang secara teoritis dapat dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuannya. Karenanya, dapat dimengerti betapa risaunya para pejabat Republik yang masih bermental keraton kalau mendengar istilah oposisi. Mahluk aneh ini memang tidak ada dalam kamus keraton Jawa. Bagaimana mungkin orang menentang raja dan dibiarkan hidup? Apalagi hal itu dilakukan dengan tidak mempedulikan asal-usul dirinya sendiri, apakah memperoleh perkenan sang nata atau tidak. Tidak membutuhkan legitimasi bagi kehadiran sendiri, dari penguasa yang oleh Yang Merbehing Dumadi sudah dititahkan menjadi prabu. Dari orang yang begitu rendah kepribadiannya, hingga berani tidak meminta hak
hidup dari sang junjungan, bagaimana dapat diharapkan kesetiaan yang tidak tergoyahkan kepada negara? Negara adalah raja. Tidak memerlukan yang satu berarti menolak yang lain. Bukankah akan rusak tatanan negara karena itu? Dan kalau tatanan negara rusak, bukankah tatanan hidup semesta juga berantakan? Memang terlalu. Dalam struktur kehidupan yang sudah begitu harmonis, masih ada yang kurang ajar. Perbedaan pendapat akan diayomi selama tidak berarti robohnya tatanan. Pertentangan pikiran diperkenankan selama masih dalam kerangka kekuasaan yang sudah tegak. Permusuhan boleh dilakukan selama tidak ditujukan kepada sang nata. Ini saja kondisinya, lain tidak. Lembu peteng boleh saja menyusun kekuatan diam-diam dan suatu kali merebut pemerintahan dari tangan ayahnya atau saudara-saudara. Itu pantas karena pelaku utamanya juga orang keraton. Kalau kalah, kepala dipancung. Kalau menang akan memerintah. Karenanya, kalau pihak yang tidak setuju dengan pemerintah dalam beberapa hal melakukan koreksi dan menuntut penghapusan suatu kebijaksanaan, syaratnya hanya tidak dalam konteks menjadi altematif pemerintah. Melainkan secara yuridisformal merupakan pihak yang dilindungi pemerintah. Karenanya pula siap-siaplah Anda yang masih bermimpin menjadi oposisi. Kalau didatangi petugas keamanan, hendaknya dapat berucap: saya juga keturunan Lembu peteng!
Sebuah Perspekstif Nasi Tumpeng Oleh Abdurrahman
Wahid
Seorang ibu dari Semarang punya kasus lucu. Setiap tahun ia mendapat undangan ke Istana Merdeka, mungkin sebagai pahlawan (yang masih hidup), atau keluarganya. Mungkin juga karena sebab lain. Nah tahun 1981 ia membungkus nasi tumpeng buatan istana dan menympiannya di rumahhingga hari ini. Para tetangga tertawa melihat ia menjemur nasi sebungkus itu hingga kering. Biarlah, katanya, yang penting tumpeng sebungkus itu membawa rezeki. Nasi tumpeng memang punya fungsi bermacam-macam. Ada yang memperlakukan sebagai sesajen, di masa lalujuga kini, bagi yang percaya. Di sinipun terbagi dua maksud sesajen itu. Ada yang menganggapnya hanya sebagai persembahan simbolis, dengan "aturan" sang penunggu tidak menyentuhnya sama sekali. Langsung sesajen itu "dikembalikan kepada masyarakat" siapapun dapat terus memakannya. Adapula yang menganggap tumpeng benar-benar memperoleh "kontak fisik" dengan roh halus, dan karenanya lalu memperoleh kekuatan supematural tersendiri. Hanya beberapa orang tertentu yang boleh makan. Yang lain boleh menyimpannya menjadi jimat, seperti dalam kasus ibu dari Semarang itu.
Lambat laun, dengan datangnya agama-agama besar kemari, hal-hal seperti tumpeng sebagai sesajen lalu mengalami perubahan. Tidak lagi memiliki arti magis dan supranatural, melainkan "diturunkan derajatnya" setingkat menjadi "misteri". Kiai Sekati atau Gong Keraton diarak pada upacara tertentu dan tumpeng turut pula dipersiapkan- mungkin kecil saja, mungkin sebesar bukit. Bagi sebagian orang yang turut memperebutkannya, ia memiliki kekuatan magis. Tetapi bagi yang mempersiapkan, ia mengandung misteri tanpa magi. Misteri, karena menjadi bagian dari upacara penegakan wibawa sang Ratu, bukti keampuhan Sang Nata. Sekarang ini, ketika budaya pariwisata sudan menjadi bagian peradaban modem, tumpeng baralih fungsi lagi- menjadi eksotika, bagian dari "kekayaan tersembunyi" yang patut diperlihatkan kepada para wisatawan. Tumpeng disekluerkan menjadi bagian transaksi komersial belaka. Bersama dengan itu, nasi tumpeng itu juga mengalami "pergeseran historis" lainmenjadi bagian neofeodalisme yang muncul di kalangan atas, yang terangsang "melestarikan kebudayaan asli" kita. Di pesta-pesta perkawinan, upacara pembukaan proyek baru, pesta kenegaraan, dan seterusnya, tumpeng memang tidak magis, tidak memiliki misteri, tapi berperan simbolis juga. Di tempat lain, jelas bukan di Semarang, seorang mubalig melabrak nasi tumpeng. Diharamkan- karena ia adalah sesajen kaum yang tidak punya tauhid, tidak percaya pada keesaan Tuhan. Ia bagian dari kemusyrikan yang menganggap adanya banyak Tuhan. Tumpeng harus dijauhi. Penerimaan atasnya menunjukkan kelemahan iman kita. Maka, di satu pihak, tumpeng diminta lestari kehadirannya. Sedang di pihak lain diminta untuk dijauhi. Mengapa hal-hal seperti itu tetap menjadi masalah? Jawabnya: perbenturan budaya antara proses islamisasi dan proses penemuan identitas diri sebagai bangsa. Di satu pihak, islamisasi berjalan pesat, walau dalam wajah yang tidak sama dan intensitas yang berbeda-beda. Kesadaran ber-Islam makin hari makin menampakkan bentuk nyata. Ada sektor yang menampakkan wajah kemanusiaan, mendorong munculnya humanisme baru di dunia ini, yang tidak lepas dari wawasan kerohanian, seperti terlihat dalam pergolakan pemikiran keagamaan. Ada yang menampilkan wajah kemelut tak kunjung usai, seperti di bidang politik. Ada pula yang memunculkan wajah "bengis": koreksi total, transformasi penuh, realisasi ajaran agama secara tuntas, Islam sebagai altematif, dan segerobak istilah lain yang digunakan untuk memberi nama proses islamisasi dalam bentuk terakhir itu. Di pihak lain, integrasi nasional dijalani dengan susah payah. Melalui "humanisme liberal" di bidang budaya ia berjalan tersendat-sendat, karena tidak memperhitungkan hukum "siapa kuat, ia menang, dan mengambil segala-galanya kalau menang". Reaksi baliknya adalah gerakan separatis di tahun-tahun lima puluhan dan enam puluhan.
Ketika era pembangunan datangm prioritas utama secara alami adalah penanganan masalah integrasi nasional itu. Dari unifikasi system komunikasi melalui satelit domestik Palapa hingga rentetan santiaji dan penataran P4, energi bangsa banyak sekali dicurahkan kepada pemantapan proses ituyang menonjolkan upacara perkawinan adat begitu mewah sebagai "mode masa kini" sebagai salah satu manifestasinya. Dan sudah tentu juga : nasi tumpeng. Dalam pelestarian nasi tumpeng sebagai bagian pelestarian "budaya luhur" bangsa itu, dengan sendirinya tidak terhindarkan lagi turut dilestarikannya beberapa orientasi semula. Misalnya, masih adanya aura misteri nasi tumpeng itu sendiri sebagai "makanan yang tidak biasa, mengandung arti kerohanian". Tapi, itupun hanya di kalangan kecil. Perbenturan itu sendiri antara islamisasi dan integrasi nasional, hanyalah bagian dari perjalanan sejarah yang panjang. Bukan pertanda datangnya kiamat, tetapi juga bukan sesuatu yang harus diabaikan sama sekali. Harus ditangani tetapi dalam ukuran proporsional. Menurut hemat penulis, penanganannya adalah bentuk meyakinkan dari sang mubaligbahwa munculnya nasi tumpeng bukan berarti luntumya keimanan kita, melainkan hanya bagian dari proses integrasi nasional yang alami itu. Sekali integrasi tercapai dalam bentuk mapan, Islam juga yang mengambil keuntungannya. Di pihak lain, bangsa ini secara umum harus memperoleh informasi pula, bahwa "suara-suara sumbang" yang menuntut hilangnya nasi tumpeng hanyalah sebagian dari proses islamisasi yang panjang. Di suatu saat, Islam pun akan menerima nasi tumpeng tanpa merasa terancam. Percayalah. Sederhana, Syahdu Oleh
Abdurrahman
Wahid
Bangunan berbentuk segi delapan itu tidaklah tinggi. Tidak pula berukuran besar. Paling tinggi sepuluh meter. Garis tengah penampangnya tidak lebih dari duapuluh lima meter. Dikitari halaman rumput biasa tanpa taman, dindingnya terbuat dari batu bata merah tanpa plester kapur (apalagi dengan hiasan rural atau bas relief ) tidak ada tanda-tanda kemegahan apa pun di pasang di luar. Pada tengah atapnya ada atrium yang menjadi jalan masuknya cahaya matahari kedalam ruangan.cahaya itu kemudian disangga oleh sebuah reflektor penyangga yang digantungkan pada dasar atap dan bagian atas dinding dalam ruangan utama. Pantulan cahaya yang didapat adalah sinar lembut yang tidak membuat mata silau. Ruang dalamnya terbagi dua. Beberapa buah ruang samping mengitari ruang utama di dalam seperti cincin mengitari penampang ibu jari. Semua ruang samping itu mempunyai pintu masuk langsung ke ruang utama itu .Ruang utama, sebagai tempat pagelaran bergaris tengah tidak lebih dari 15
meter, sama sekali tidak berhiaskan omamen apa pun. Tidak ada lukisan pada ke delapan dindingnya, tidak ada struktur apapun di lantai yang ada hanya dinding telanjang, mengitari lantai yang telanjang pula, disinari keredupan cahaya lembut yang datang dari luar. Kapel Rothko ini memang unik. Didirikan oleh jutawan de Menil, ia merupakan perlambang kerohanian yang sangat pekat. Benar serba sederhana, tetapi ia adalah ekspresi yang penuh keterlibatan jiwa dari pemahat Amerika yang terkemuka, mendiang Rothko. Tidak sebagaimana berbagai bangunan antar agama (interdenominational buildings) lainnya, Kapel Rothko di Houston (Texas) ini sama sekali bebas dari afiliasi kepada agama manapun. Kalau Katedral Nasional di Washington masih berbau Kristen karena bentuk Gotiknya dan Kapel Wayside di Sydney masih menggunakan altar, maka Kapel Rothko ini justru tidak ada kaitan fisiknya sama sekali dengan tempat peribadatan mana pun. Alat peribadatan tidak ada terpasang permanen dalam ruangan utama, sehingga semua harus membawa sendiri ke dalam ruangan itu untuk dipergunakan, dengan menggunakan cara bongkar pasang. Kalau orang Katholik ingin menggunakan untuk misa, mereka membawa sendiri altar mereka. Orang muslim boleh menghamparkan tikar sembahyang mereka dan menghadapkannya ke arah kiblat di tenggara. Bermacam-macam upacara keagamaan dapat dilakukan di kapel yang sudah berusia tujuh tahun ini. Dom Helder Camera, itu uskup agung penentang rezim fasis di Brasilia sekarang pemah menyelenggarakan misa spontan - sudah tentu dengan himbauan yang mengharukan akan nasib mereka yang miskin dan tertindas di negaranya. Beberapa orang Swami dari India pemah mengadakan meditasi dan peragaan Yoga. Kelompok Yahudi pemah merayakan upacara keagamaan mereka di tempat ini, sedangkan kelompok Sufi Turki Mevleviah yang terkenal dengan sebutan The Whirling Dervishes (darwys: berputar) - karena taritarian keagamaan mereka dikala mencapai ekstase -pemah melakukan peragaan. Sebuah foto menunjukkan ada pula sembahyang berjamaah kaum muslimin diselenggarakan di Kapel ini, demikian pula meditasi kaum Sufi Califomia beberapa waktu sebelum kunjungan penulis. Semuanya tentu terpukau dengan kesyahduan yang meliputi ruangan pagelaran serba sederhana dari Kapel Rothko ini. Ditengah hiruk pikuk kegiatan kota modem Houston, yang menjadi pusat bisnis dan industri minyak bumi Amerika Serikat memang unik sekali peranan kapel yang satu ini. Ia bukanlah gereja Nasrani, bukan Sinagog Yahudi. Menjadi masjid tidak memenuhi persyaratan, bukan pula kelenteng Cina atau kuil apa pun. Ditangani sehari-hari oleh seorang wanita muslim dari Libanon, Nabilah Drooby, ia adalah tempat persingahan dalam perjalanam spritual bagi mereka yang membutuhkan atau tertarik. Kalau mereka beribadat di situ, mereka bebas melakukannya, tidak lebih dari itu. Tetapi perannya temyata tidak terhenti hanya disitu. Di kolam depan pintu masuk ada tugu somplak (broken obelisk) yang dipersembahkan kepada kenangan Martin Luther King Jr. Itu pemimpin agama berkulit hitam yang menjadi
perlambang perjuangan Kristen untuk menegakkan persamaan hak bagi warga masyarakat yang berbeda wama kulit. Di kantor Yayasan Kapel Rothko, sebuah bangunan bersebelahan dengan kapelnya sendiri, berbagai kegiatan kontemplatif dilakukan. Di bawah dewan pembina yang beranggotakan orang-orang Katolik, Kristen, Muslim dan Yahudi, yayasan ini menyelenggarakan berbagai forum serius untuk menggali pola interaksi kehidupan rohani berbagai agama dengan kehidupan. Aktivitas harian yayasan ini, seperti madame Drooby, dibantu staf administratif dan seorang ilmiawan wanita dari Romania. Staf itu semuanya terdiri dari wanita, dan kini tengah mempersiapkan Coloquium tentang spiritualitas dan keadilan sosial dalam Islam Siapa bilang Kapel Rothko ini tidak melakukan sesuatu yang besar, hanya karena secara lahiriah ia menyediakan tempat beribadah yang sangat sederhana? Bukankah justru kesederhanaan itu, ditambah fungsi jangka panjangnya yang vital dalam pemikiran kontemplatif di bidang keagamaan, yang memunculkan keharuan dan kesyahduan yang diperlukan manusia modem dalam pergumulannya dengan kehidupan?
Skala Prioritas lbadah Oleh
Abdurrahman
Wahid
Apa yang dilakukan para Kiai Rembang, beberapa waktu yang lalu, memang terasa aneh: membuat skala prioritas ibadah. Kalau prioritas pembangunan bukan barang baru. Di kota pantai utara Pulau Jawa itu, seorang pemilik toko yang menjual skuter dan sepeda motor, sisa-sisa kelas pedagang santri yang jaya di masa lampau, tiap tahun melakukan ibadah haji ke Mekkah. Ibadah haji pertama memang wajib, tetapi pengulangannya tidak. Hanya diseyogyakan. Dalam istilah hukum agama (fiqh) di sebut disunahkan. Ada yang menanyakan kepada para kiai di Rembang itu status haji sunah yang dilakukan berkali-kali, padahal ada yang lebih membutuhkan pembiayaan. Yaitu pembangunan gedung sekolah agama, alias madrasah. Jalan pikiran penanya itu sebenamya sesuai dengan penalaran manusia yang membangun. Bukankah Nabi Muhammad bersabda, "menuntut ilmu itu wajib bagi tiap muslimin, pria dan wanita"? Para kiai lantas membahasnya dalam majelis fiqh yang mereka selengarakan secara teratur. Sudah dapat diduga: mereka akhimya membenarkan pendapat dan imbauan penanya di atas. Namun, bukan keputusannya yang penting, melainkan proses tercapainya. Dasar pengambilan keputusan itu tepat kalau disebut "indikator skala prioritas". Seolah-olah
merupakan
sesuatu
yang
empiris,
padahal
bukan.
Para kiai Rembang temyata tidak mendasarkan keputusan mereka pada penalaran yang dikemukakan si penanya. Penalaran seperti itu terlalu rasionalistis, tidak sesuai dengan sendi-sendi pemikiran keagamaan mereka. Menurut "kamus fiqh" yang mereka anut, tidak ada tempat untuk penalaran rasional yang tuntas, yang langsung menggunakan ayat AI-Qur'an atau sabda Nabi. Itu kelancangan apalagi kalau dilakukan orang yang tidak kompeten. Dalam pandangan mereka, untuk penalaran di bidang fiqh, harus ada kerangka penglihatan yang jelas dan kerangka berpikir serba deduktif itu disistematiskan dalam sebuah teori hukum, yang di namai usul fiqh. Metode inilah yang menentukan bagaimana ayat AI-Qur'an, atau sabda Nabi harus diberlakukan dalam setiap masalah yang timbul. Juga bagaimana keputusan yang diambil kalau tidak ada 'dalil' berupa ayat AI-Qur'an dan sabda Nabi melalui analogi ( qiyas), konsensus (ijma'), dan sebagainya. Ada sekian puluh kaidah yang telah dibakukan, dengan tujuan dipakai sebagai "pedoman" dalam pengambilan keputusan.Yang terkenal adalah Asybah waNaza'ir, karya utama As-Suyuti yang sudah berumur hampir enam abad. Dalam Asyibah itulah mereka dapati kaidah yang berhubungan dengan kasus tadi. Bunyinya sederhana: "amal perbuatan yang berlanjut diutamakan atas amalan yang terhenti" (al-'amalu al muta'addi afdhalu minal amalil qashir). Amal kebajikan yang berlanjut adalah yang kegunaannya dirasakan orang lain. BahasaJawa model pesantrennya disebut sumbrambah olehe migunani. Sedangkan yang terhenti adalah yang kegunaannya kembali kepada si pelaku. Maka, selesailah pembahasan para kiai. Mendirikan madrasah amal kebajikan berlanjut. Jadi diutamakan. Aplikasi kaidah yang sedemikian sederhana itu temyata adalah bidang para kiai. Dalam batas-batasnya sendiri, bukankah ia perlu didorong, untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang jelas kegunaannya bagi masyarakat? Titik tolak mengkaitkan "sistem kaidah" dengan tekanan di bidang kemasyarakatan pun sudah diantisipasikan oleh kaidah lain yakni: tasharruful imam al-raiyyah manutun bil maslahah. 'Kebijakan si pengambil keputusan mengikut kepentingan rakyat'. Sulit Masuknya Mudah Keluamya Oleh Abdurrahman
Wahid
Kalau ucapan di atas menimbulkan asosiasi yang tidak-tidak dalam pikiran, ya pantas saja. Apalagi diucapkan seseorang yang di waktu senggang senang berbincang-bincang tentang tanda-tanda wanita cantik ('lihat dulu tumitnya'), atau ngalamat-nya wanita banyak anak (walud, menurut bahasa pesantren) dan banyak bercerita tentang cara-cara 'menjinakkan' istri yang rewel dan cerewet. Tetapi temyata bukan pengertian pomo yang jadi arah ucapan tersebut. Kiai
Wahab Chasbullah menggunakannya sebagaian motto sikap hidupnya dalam menghadapi perkembangan politik semasa NU masihJadi partai dahulu. Dalam kasus pembubaran DPR hasi pemilu 1955, Kiai Bisri Syansuri sebagai wakilnya dalam PB Syuriah NU mati-matian menolak tindakan politik mendiang Presiden Sockamo sehabis mendekritkan kembalinya UUD 1945 di tahun 1959 itu. Tidak sah membubarkan DPR hasi pilihan rakyat, katanya. Haram untuk ikut dalam DPR-GR yang dibentuk secara tunjuk belaka sebagai gantinya. Masjumi dihilangkan haknya di situ, berarti hak seperempat jumlah rakyat pemilih, yaitu mereka yang nyoblos tanda Bintang Bulan dalam Pemilu 1955. Dan ini berarti pencurian hak orang banyak, 'nggasab' menurut bahasa pesantren diambilkan dari kata ghashab yang berarti pengambilan hak orang lain secara tidak sah. Begitulah kurang lebih pendapat Kiai Bisri dalam perdebatan sengit pada sidang syuriah kala itu. Merah mukanya, suaranya semakin lama semakin lantang, punggungnya semakin tegak dengan ketahanan duduk bersila berjam-jam lamanya tanpa mengubah posisi sama sekali. Tangannyajuga berkali-kali memukul meja marmer yang dijadikan meja sidang. Saur manuk, kata orang Jawa mengenai prosedur rapat yang sudah kacau balau itu: saling bersahutan antara dua lawan pendirian itu, tanpa mengindahkan lagi wewenang mengatur lalu lintas berbicara di tangan ketua sidang. Bagaimana akan ditertibkan kalau yang berdebat begitu seru adalah justru Rais Am Kiai Wahab dan wakil Rais Am-nya Kiai Bisri?
Sampeyan seenaknya saja membuat keputusan hukum agama, terlalu murah. Tidak memperkuat keyakinan agama, nanti orang terbiasa memudahkan ajaran agama. Bagaimana jadinya umat kita nanti kalau sudah begitu? Sampeyan yang menjadi sebab, begitulah kira-kira rangkaian tuduhan Kiai Bisri kepada ipamya, Kiai Wahab.
Sampeyan sendiri yang main keras saja. Yang akan kita berikan keputusan ini dalah orang banyak, tidak seperti kita. Banyak yang tidak kuat pakai cara sampeyan ini. Antara yang berat dan ringan dalam soal agama, justru hanya diambil ringannya kalau menyangkut proyek orang banyak. 'Kiai populis' Wahab Chasbullah yang punya sedan Opel Kapitan model terbaru tahun ini menudingkan 'tuduhan main keras' itu kepada 'Kiai elitis' Bisri Syansuri yang tidak pemah punya mobil sebuah pun dalam kehidupannya. Mari kita ambil yang ringan saja dalam masalah DPR-GR ini. Gasaban atau tidak belum pasti. Yang jelas kalau tidak masuk, bukan haknya Masjumi saja yang hilang. Umat Islam semuanya juga akan kehilangan hak mereka.ini satu-satunya peluang untuk memperjuangkan hak di lembaga perwakilan rakyat di negeri kita saat ini. Sulit untuk masuk kalau tolak kali ini. Kalau memang sudah temyata nanti bertentangan dengan keyakinan agama, kita dapat keluar bersama-sama. Masuknya sulit, keluamya mudah. Dan seperti biasanya, Kiai Bisri tetap pada pendiriannya, sedangkan Kiai Wahab jalan terus. NU mempersilahkan yang setuju untuk menerima keanggotaan DPRGR itu. Pada yang berkeras, dipersilakan agar menolak. Sedang kedua Kiai tua
yang beriparan itu tetap saja berbeda pendapat dalam hampir semua persoalan, sambil tetap menghargai satu sama lain dalam kehidupan pribadi mereka. Tidak heranlah jika terjadi metamorfose pada waktu Kiai Wahab wafat dan Kiai Bisri menggantikannya sebagai Rais Am dalam tahun 1972. Kiai Bisri lalu bersifat 'ngemong' kepada cara berfikir Kiai Wahab itu. Seolah-olah ingin menyatukan kedua kecenderungan itu dalam membuat keputusan. Maklum, sejak waktu itu hingga saat kepulangannya ke Rahmatullah beberapa waktu yang lalu, Kiai Bisri harus sering mengambil keputusan sendirian saja. Lainlainnya di PB-NU dan kemudian DPP-PPP lebih berperan menyediakan bahan pertimbangan. Siapa berani coba-coba adu pendapat dengan 'mbah Bisri', kalau tidak punya senjata ajaib seperti motto Kiai Wahab: sulit masuknya dan gampang keluamya itu? Surga dan Agama
Oleh: Abdurrahman Wahid Beberapa hari setelah tertembaknya Dr. Azahari di Batu, Jawa Timur, Habib Rizieq menyatakan (dalam hal ini membenarkan ungkapan) bahwa pelaku terorisme di Indonesia itu akan masuk surga. Ia menyampaikan rasa simpati dan menilainya sebagai orang yang mati syahid. Pemyataan ini seolah memperkuat pendapat seorang teroris yang direkam dalam kepingan CD, mati dalam pemboman di Bali akan masuk surga. Ini tentu karena si teroris yakin akan hal itu. Dengan demikian jelas bahwa motif tindakannya dianggap melaksanakan ajaran agama Islam. Ungkapan ini sudah tentu dalam membenarkan dan menyetujui tindak kekerasan atas nama Islam. Benarkah demikian? Pertama-tama, harus disadari bahwa tindak teroristik adalah akibat dari tidak efektifnya cara-cara lain untuk menghadang, apa yang dianggap sang teroris sebagai, hal yang melemahkan Islam. Bentuk tindakan itu dapat saja berbedabeda namun intinya sama, yaitu anggapan bahwa tanpa kekerasan agama Islam akan dikalahkan oleh hal-hal lain, termasuk modemisasi model Barat. Tak disadari para teroris, bahwa respon mereka bukan sesuatu yang mumi dari agama Islam itu sendiri. Bukankah dalam tindakannya para teroris juga menggunakan penemuan-penemuan dari Barat? Ini terbukti dari berbagai alat yang digunakan, seperti perkakas komunikasi dan alat peledak. Bukankah ini menunjukkan hipokritas yang luar biasa dalam memandang kehidupan? Demikian kuat keyakinan itu tertanam dalam hati para teroris, sehingga sebagian mereka bersedia mengorbankan jiwa sendiri dengan melakukan bom bunuh diri. Selain itu juga karena adanya orang-orang yang mendukung gerakan teroris itu.
Patutlah dari sini kita memeriksa kebenaran pendapat itu. Tanpa pendekatan itu, tinjauan kita akan dianggap sebagai buatan musuh. Kita harus melihat perkembangan sejarah Islam yang terkait dengan hal ini sebagai perbandingan. Dalam sejarah Islam yang panjang, ada tiga kaum dengan pendapat penting yang berkembang. Kaum Khawarij menganggap penolakan terhadap setiap penyimpangan sebagai kewajiban agama. Dari mereka inilah lahir para teroris yang melakukan pembunuhan demi pembunuhan atas orang-orang yang mereka anggap meninggalkan agama. Lalu ada kaum Mutazilah, yang menganggap bahwa kemerdekaan manusia untuk mengambil pendapat sendiri tanpa batas dalam ajaran Islam. Mereka menilai adanya pembatasan apapun akan mengurangi kebebasan manusia. Di antara dua pendapat yang saling berbeda itu, ada kaum Sunni yang berpandangan bahwa kaum muslimin memiliki kebebasan dengan batas-batas yang jelas, yaitu tidak dipekenankan melakukan tindakan yang diharamkan oleh ajaran agama Islam, salah satunya bunuh diri. Mayoritas kaum muslim di seluruh dunia mengikuti garis Sunni ini dan menggunakan paham itu sebagai batasan perlawanan terhadap perubahanperubahan yang terjadi. Karenanya, penulis yakin bahwa orang yang membenarkan terorisme itu berjumlah sangat kecil. Itulah sebabnya, dalam sebuah keterangan pers penulis menyatakan bahwa Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) yang dipimpin Habib Rizieq, adalah kelompok kecil dengan pengaruh sangat terbatas. Ini adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Akibat dari anggapan sebaliknya, sudah dapat dilihat dari sikap resmi aparat penegak hukum kita yang terkesan tidak mau mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap mereka itu. Kita perlu mendudukkan persoalannya pada rel yang wajar. Pertama, pandangan para teroris itu bukanlah pandangan umat Islam yang sebenamya. Ia hanyalah pandangan sejumlah orang yang salah bersikap melihat sejumlah tantangan yang dihadapi ajaran agama Islam. Kedua, pandangan itu sendiri bukanlah pendapat mayoritas. Selain itu, terjadi kesalahan pandangan bahwa hubungan antara agama dan kekuasaan akan menguntungkan pihak agama. Padahal sudah jelas, dari proses itu sebuah agama akan menjadi alat pengukuh dan pemelihara kekuasaan. Jika sudah demikian agama akan kehilangan peran yang lebih besar, yaitu inspirasi bagi pengembangan kemanusiaan. Selain itu juga akan mengurangi efektivitas peranan agama sebagai pembawa kesejahteraan. Agama Islam dalam al-Quran al-Karim memerintahkan kaum muslimin untuk menegakkan keadilan, sesuai dengan firman Allah Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan (Ya ayyuha al-ladzina amanu kunu qawwamina bi alqisthi). Jadi yang diperintahkan bukanlah berbuat keras, tetapi senantiasa bersikap adil dalam segala hal. Begitu juga dalam kitab suci banyak ayat yang secara eksplisit memerintahkan kaum muslimin agar senantiasa bersabar. Tidak lupa pula, selalu ada perintah untuk memaafkan lawan-lawan kita. Jadi sikap lunak dan moderat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya sikap terlalu keras itulah yang keluar dari batasan-batasan ajaran agama.
Berbeda dari klaim para teroris, Islam justru mengakui adanya perbedaanperbedaan dalam hidup kita. Al-Quran menyatakan Sesungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai lelaki dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk saling mengenal (Inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa wa jaalnakum syuuban wa qabaila li taarafu). Dari perbedaan itu, Allah Swt memerintahkan berpeganglah kalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah (wa itashimu bi habl Allah jamian wa la tafarraqu). Berbagai perkumpulan hanyalah menandai adanya kemajemukan/pluralitas di kalangan kaum muslimin, sedangkan aksi para teroris itu adalah sumber perpecahan umat manusia. Kebetulan, negara kita berpegang kepada ungkapan Empu Tantular Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda namun tetap satu juga). Kaum muslimin di negeri ini telah sepakat untuk menerima adanya negara yang bukan negara Islam. Ia dicapai dengan susah payah melalui cara-cara damai. Jadi patutlah hal ini dipertahankan oleh kaum muslimin. Karena itu, kita menolak terorisme dalam segala bentuk. Jika mereka yang menyimpang belum tentu masuk surga, apalagi mereka yang memberikan rekomendasi untuk itu.
Syekh Mas'ud Memburu Kitab Oleh
Abdurrahman
Wahid
Kiai Masud bukan sembarang kiai. Ia diakui amat dalam pengetahuannya di bidang hukum agama. la menguasal peralatan untuk mengambil keputusan hukum fiqh, berupa teori hukum (usul fiqh) dan pedoman hukum (qawa'id fiqh). Kedua 'alat' itu memang harus dikuasai sempuma, kalau ingin menghasilkan keputusankeputusan hukum agama yang 'berkualitas tinggi', hingga layak disebut "syekh". Di tahun lima puluhan, yang di panggil syekh adalah Kiai Masduki dari Lasem, karena penguasaannya atas buku teks (kitab) utama di bidang teori hukum, yaitu kitab Jam'ul Jawami. Tahun-tahun delapan puluhan ini rupanya sudah ada pengganti Syekh Masduki Lasem, yang sudah sekian tahun wafat. Dan dia itulah Kiai Mas'ud dari Kawunganten, Purwokerto. Orangnya sederhana. Dalam pergaulan sangat bersikap rendah hati kepada orang lain, bahkan kepada yang lebih muda umumya sekalipun. Suaranya tidak pemah dikeraskan. Penampilannya adalah penampilan kiai 'kampung' yang tidak ada 'kegagahan'nya sedikit pun. Tetapi, di balik penampilan 'biasa-biasa saja' itu tersembunyi sesuatu yang tidak disangka-sangka: kekerasan hati untuk melakukan pengejaran, yang mungkin tidak akan pemah berhenti: mengajar buku-buku teks agama secara tradisional digunakan di pesantren, atau seharusnya diajarkan di dalamnya. Mengapa seharusnya? Karena memang belum diajarkan dan digunakan, karena baru merupakan naskah asli tulisan tangan, belum diterbitkan. Menurut 'bahasa pesantren', masih berupa naskah yang 'belum dicap'.
Pesantren di Indonesia memiliki tradisi keilmuan agamanya sendiri, yantg unik dan menarik untuk dikaji: tradisi mengembangkan produk ilmiah dalam bentuk karyakarya tulis para ulamanya. Di sana para kiai dan santri tak hanya menggantungkan diri pada teks-teks 'negeri Arab' saja yang sebenamya juga datang dari segenap penjuru dunia, seperti Afrika Barat, Asia Tengah dan India. Dan tradisi pesantren untuk mengembangkan 'karya lokal' ini akhimya berpuncak pada munculnya ulama-ulama tangguh, yang diakui secara intemasional oleh dunia Islam di masanya. Misalnya Kiai Nawawi Banten, Kiai Mahfudz Termas (Pacitan), Kiai Muhtaram Banyumas dan Kiai Ahmad Khatib Padang serta Kiai Abdussamad Palembang. Semuanya termasuk, kelompok yang menguasai dunia pengetahuan agama di Mekkah selama sepulub tahun, di sekitar peralihan dari abad kesembilan betas ke abad kedua puluh. Sekarang pun masih terasa sisa-sisanya di sana, seperti terbukti atas pengakuan atas Syekh Yasin Padang yang sudah menaturalisasi diri (tajannus) menjadi warga Arab Saudi. Karangan-karangannya tersebar di seluruh penjuru Dunia Islam saat ini. Dalam tradisi inilah pesantren mengembangkan dan mengajarkan 'teks-teks lokal' yang dicetak di Kairo atau Mekkah, dan kembali kemari sebagai 'kitab agama' yang sudah diterima universal oleh dunia Islam. Terkenal adalah traktat kecil tentang Taubid (teologi) karya Kiai Nawawi Banten, berjudul Nur AI-Dhalam, yang digunakan sebagai teks dasar di seluruh penjuru tanah air hingga saat ini. Lebih terkenal lagi dari kiai yang satu ini, yang bergelar 'pemuka ulama Mekkah dan Madinah' (sayyid 'ulama At-Hijaz), adalah kumpulan empat puluh hadits pilihannya, berjudul Hadith al-Arba'in, yang digunakan tidak hanya di lingkungan pesantren saja, bahkan sampai sekolah-sekolah non-agama juga. Muhammadiyah dan NU, SI dan Perti, lslam Jama'ah dan Persis, semuanya menggunakannya sebagai teks dasar untuk tingkat permulaan dalam pengajaran hadits. Nah, Syekh Mas'ud adalah penerus tradisi ini, dalam arti sepenuhnya. Tidak hanya menggunakan yang sudah tercetak dan beredar luas, melainkan juga yang masih dalam bentuk tulisan tangan dan belum 'dicap'. Apa yang dirasakannya sebagai tugas adalah mencari karya-karya bermutu tinggi, basil pemikiran para kiai kita sendiri yang sudah meninggalkan dunia fana ini. Kemudian dihubungkannya dengan mereka yang berminat menerbitkannya. Contoh menarik dari kerja ini adalah 'perburuan'nya yang intensif atas sebuah naskah unik karya Kiai lhsan dari pesantrenJampes (Kediri), yang wafat menjelang Perang Dunia II dan termasuk 'angkatan Kiai Hasyim Asy'ari' dari Tebuireng, Jombang. Kiai lhsan meninggalkan dua buah karya tulis utama. Sebuah berjudul Siraj al-Talibin, sebuah komentar atas traktat AI-Ghazali yang sudah seribu tahun umumya, Minhaj al-Abidin. Karya dua jilid ini bemilai tinggi, sehingga dijadikan buku wajib untuk kajian post graduate di AI-Azhar dan beberapa perguruan tinggi lain (ironisnya,justru tidak dikenal orang-orang IAIN). Dicetak di Cairo, kini digunakan di seluruh pesantren dengan kajian mendalam atas tasawwuf dan akhlaq.
Karya utamanya yang satu lagi belum sempat diterbitkan, ketika pengarangnya berpulang ke rahmatullah, berjudul Minhaj al-Imdad, komentar atas traktat lrsyad al- 'lbad. Semuanya ada seribu dua puluh tiga lembar, Gus, kata Kiai Mas'ud kepada saya sewaktu bertemu baru-baru ini. 'Tulisan tangan dari penulis (katib) yang langsung didikte Kiai lhsan sendiri. Kabamya katib itu berasal dari Pecangakan di Bojonegoro'. la pun meneruskan sejumlah 'data primer' lagi tentang karya 'belum dicap' tersebut. Ini ciri karakteristik dari 'pemburu' yang gila dengan buruannya. Sayangnya, karya tersebut mendadak hilang sejak beberapa tahun yang lalu. Dan Kiai Mas'ud, karena kecintaannya yang begitu mendalam pada tradisi ke-'kitab'-an kaum pesantren, memburunya dengan tekun, bertanya kian kemari. "Alhamdulillah, sekarang saya sudah tahu di tangan siapa naskah itu, akan diikhtiarkan memperolehnya. Syekh Yasin Padang sudah menyatakan kesediaan mencetaknya di Mekkah,"katanya bersemangat. "Kegilaan''yangmengesankan: perburuan yang mengagumkan dari seorang kiai yang amat dalam pengetahuan agamanya, tetapi tengelam dalam keasyikan yang tidak disadarinya memiliki arti penting bagi pengetahuan ke-lslam-an di negeri ini. Mungkin malah di seluruh dunia, katakanlah dua puluh tahun lagi. Pada waktu nanti karya tersebut 'sudah dicap', digunakan sebagai sumber bemilai tinggi di mana-mana, siapakah yang ingat jasanya melakukan 'pemburuan' itu? Mungkin tidak ada lagi yang ingat. Dan Kiai Syekh Mas'ud tidak peduli juga. Karena ia sudah puas, sudah merasa menunaikan tugas yang dipilihnya sendiri. Tahan Berpolitikkah Pondok Pesantren?
Oleh: Abdurrahman Wahid* Dalam apa yang dinamakan Muktamar Sukolilo di Surabaya baru-baru ini, kubu Alwi Shihab mengalami permasalahan yang cukup serius. Pertama, KH. Abdullah Faqih dari Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan di Tuban, menyatakan siap bertemu penulis kapan saja. Penulis mensyaratkan pertemuan itu harus diselenggarakan di luar ponpes tersebut, karena biang kerok persoalan antara beliau dan penulis, terletak pada salah seorang putra beliau yaitu Gus Ubed. Selain itu dalam forum tersebut, KH. Idris Marzuki dan Ponpes Lirboyo mendahului pulang ke Kediri karena kecewa tokoh yang ingin dijadikan Ketua Umum Dewan Tanfidz Saifullah Yusuf tidak bersedia menempati posisi itu, dan malah mengatur agar Choirul Anam yang terpilih. Dengan kepulangannya itu, KH. Idris Marzuki dianggap akan menekuni
ponpes yang dipimpinnya, dan bukannya aktif dalam kegiatan politik seperti yang dilakukannya dua tahun terakhir ini. Dari peristiwa-peristiwa itu, muncul pertanyaan tentang ketahanan ponpes dalam politik praktis. Pertanyaan itu merupakan bagian dari hubungan tidak wajar antara ponpes dengan dunia politik praktis, yang dimulai dari kedekataan antara para pengasuh ponpes dengan para pejabat atau tokoh pemerintahan. Ini tampak jelas, bahwa salah satu pemeo: jika wakaf dari orang-orang non-muslim sah-sah saja, apalagi sumbangan dari pejabat yang pada umumnya yang sama sekali tidak mengikat. Untuk sejumlah ponpes, yang memang para pengasuhnya mengikatkan diri dengan para pejabat dan tokoh di atas, mereka lalu tidak memandang penting kebersihan diri dari virus politik yang sangat berbahaya itu. Sehingga banyak tokoh-tokoh ponpes yang tergelincir secara politis, sehingga tidak dapat mengambil tindakan bagi kepentingan rakyat banyak dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sangat berbeda dengan masa KH. A. Wahab Chasbullah menjadi Rais Aam NU dan wakil beliau, KH. Bisri Syansuri. Penulis masih ingat, sewaktu ia masih kecil bagaimana KH. Wahab Chasbullah habis-habisan menentang gagasan Bung Kamo untuk membubarkan semua parpol dan tinggal satu partai saja yang boleh berdiri di Indonesia. Begitu juga ketika Bung Kamo mempersiapkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, KH. Bisri Syansuri menentang habis-habisan DPR-RI, yang menurut beliau pada waktu itu, adalah hasil pemilihan umum tahun 1955. Kalau harus diganti maka gantinya harus dipilih, dan bukannya ditunjuk oleh Bung Kamo. Untuk itu, beliau menghadapi semua tekanan termasuk datangnya tiga orang perwira RPKAD (sekarang Kopassus), dengan bersenjata lengkap dan melakukan intimidasi di ponpes beliau. Dari dua contoh di atas terlihat bahwa para pimpinan ponpes masa lampau mendasarkan pandangan mereka pada aturan-aturan agama, bukannya pada uang dan sejenisnya. Contoh terkenal dalam hal ini, adalah Rais Akbar NU KH. M. Hasjim Asyari dari Tebuireng Jombang yang membiarkan diri ditangkap Kempetai (polisi rahasia Jepang), karena ia menolak untuk melakukan seikirai (upacara membungkuk badan untuk mendukung Kaisar Jepang). Menurut beliau, hal itu sama saja dengan mengakui bahwa Kaisar Jepang adalah keturunan Dewa Matahari (Amaterasu) sesuatu hal yang tidak akan mungkin dilakukan secara keagamaan bagi seorang muslim, yang hanya mengakui kekuasaan Allah SWT semata-mata. Untuk sikapnya itu, ia harus membiarkan tangan kirinya lumpuh karena siksaaan polisi rahasia Jepang tersebut. Dengan demikian telah terjadi perubahan kualitatif dari sikap dan pandangan para kyai dari ponpes dalam kurun waktu sekitar setengah abad ini. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, berapa besarkah perubahan pandangan dan sikap tersebut? Dalam pandangan penulis, temyata perubahan-perubahan yang terjadi tidaklah besar. Secara kuantitatif, dari sekitar seratus ribu orang kyai yang ada di Indonesia saat ini, temyata paling tinggi hanya 11 orang yang mengalami perubahan pandangan akibat perkembangan politik. Itupun dapat dibagi dua adanya perubahan pandangan itu.
Ada yang berpandangan, mereka berubah karena faktor uang dan hal-hal yang sejenis, tetapi lebih banyak faktor pandangan politik seperti contohnya adalah KH. Abdurrahman Chudlori dari Ponpes Tegalrejo (Magelang) dan KH. Hanif Muslich dari Ponpes Al-Futuhiyah di Mranggen (Demak). Sikap kedua orang itu didasarkan pada pandangan bahwa orang-orang non-muslim tidak dapat menjadi pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Padahal ini dilakukan penulis agar PKB yang campur baur menjadi parpol yang besar di kemudian hari. Di sinilah terletak perbedaan antara PKB dan NU. Penulis harus merelakan orang-orang itu berada di luar PKB, yang juga berarti sikap untuk membesarkan NU. Penulis pemah menyatakan, kedua orang itu pantas memimpin NU tetapi tidak pantas mengurusi parpol. Ini tetap menjadi pandangan penulis sampai hari ini. Dua sikap penulis itu adalah untuk menjunjung NU, walaupun dua institusi itu memiliki wajah yang sama sekali berbeda dalam dunia politik. Di sini jelas, alasan bagi perbedaan pandangan itu adalah hasrat membesarkan NU semata-mata. Perbedaan pandangan yang demikian fundamental antar mereka yang ingin berkiprah dalam NU semata-mata dan mereka yang ingin berkiprah bagi NU melalui PKB, adalah konsekuensi dari pilihan kegiatan yang dilakukan. Dilihat dari sudut pandang ini jelas ponpes menempuh strategi yang saling berbeda, dan melalui bidang yang berbeda-beda pula dalam perjuangan. Kalau dilihat prospeknya, ponpes memiliki kemampuan untuk bermain politik melalui wadah yang saling berbeda. Ini berarti hampir seluruh ponpes mampu bermain politik secara dewasa. Hanya sedikit ponpes yang kehilangan kemampuan bermain politik itu, karena faktor uang dan kekuasaan, yang dalam jangka panjang akan membunuh kemampuan ponpes itu. Politik yang dijalankan mayoritas ponpes seluruh Indonesia adalah mengembangkan sikap melayani kebutuhan berbagai pihak di luar dari mereka. Artinya, peranan agama dalam penciptaan kemakmuran dan keadilan bagi bangsa dan negara ini temyata tidak pupus dan bahkan justru menunjuk kepada masa depan yang gemilang. Dengan kata lain, peranan agama dalam dunia perpolitikan di negeri kita tidaklah pudar, bahkan semakin cerah dan nyata di masa depan. Marilah kita songsong era ini dengan membenahi sasaran-sasaran politik yang ingin dicapai. Inilah yang sangat menggembirakan bagi penulis, dan menimbulkan harapan akan masa depan yang cerah bagi PKB dan parpol-parpol lain dalam pemilu yang akan datang. Setelah era politik parpol-parpol yang berebut kekuasaan, disusul oleh kekuasaan kaum profesional dan kemudian tentara/militer selama tigapuluh tahun lebih, kini datanglah era untuk menyaksikan munculnya peranan lembaga-lembaga keagamaan (seperti ulama dan sebagainya). Kalau dari pihak-pihak sebelumnya tidak begitu banyak hasil yang diperoleh, maka bagaimana dengan kepemimpinan ulama yang disimbolkan oleh pengaruh ponpes dalam berpolitik? Dapatkah mereka membawakan kemakmuran dan keadilan bagi bangsa ini, dengan menciptakan masyarakat yang kuat dan negara yang besar? Seperti halnya faktor-faktor lain dalam pembangunan, ponpes juga harus terlibat dengan pelestarian dan pembuangan jauh-jauh beberapa aspek dari kehidupannya. Ini adalah hal yang biasa terjadi dalam sejarah manusia, bukan?
Tissue, Benarkah Barang Penting? Oleh: Abdurrahman
Wahid
Richard Wright adalah Novelis A..S berkulit hitam, dan tinggal di New York dengan novelnya yang terkenal Native Son, yang terbit tahun empat puluhan. Tetapi bukan novel itu yang menarik perhatian penulis, melainkan kesan-kesan yang didapatnya dari kunjungannya ke tanah air kita dalam dasawarsa 50-an itu, yang tertuang dalam sebuah artikel. Yang menarik perhatian penulis adalah kesimpulannya bahwa orang-orang Indonesia maju dalam hal, namun tidak mau menggunakan tissue untuk membersihkan dubur mereka sehabis buang air. Novelis itu dalam pandangan penulis menunjuk kepada fenomena: maju dalam banyak hal dan prinsipil dalam beberapa soal. Wright lupa, atau juga mungkin sama sekali tidak tahu bahwa bagi sebagian besar warga bangsa kita, menggunakan tissue bukan sebuah kewajiban. Bukan kewajiban moral dan juga bukan kewajiban teknis karena sebagian besar warga bangsa kita beragama Islam. Sedangkan literatur hukum agama Islam (fiqh) menunjukkan, bahwa alat pembersih utama umat Islam adalah air. Sehingga ada anggapan cukup luas menggunakan tissue dan sejenisnya sebagai alat pembersih tubuh hanya digunakan kalau tidak ada air. Soalnya bukan mereka maju atau belum, melainkan tergantung kepada kebiasaan kita sendiri. Keadaan semacam itulah yang juga harus diperhatikan dalam promosi para wisatawan/ tourisme yang secara gencar sedang dilakukan semenjak beberapa tahun terakhir ini. Dalam memajukan pariwisata itu, kita dengan sengaja mementingkan kedatangan para turis asing, yang kita panggil dengan istilah Wisman (wisatawan mancanegara). Devisa yang diperoleh dari mereka dalam kunjungan ke sini ditambah dengan pengembangan kemampuan untuk mengamati cara hidup yang berbeda, -tanpa mengganggu terlalu banyak pola hidup kita sendiri sebagai bangsa- pada akhimya mengembangkan apa yang dinamai melayani kebutuhan turis hal ini tergambar dalam anekdot berikut: sepupu beserta penulis dengan berkendaraan mobil mengitari air mancur di depan Hotel Indonesia di Jakarta. Tiba-tiba sang sepupu bertanya kepada penulis, setelah mengamati seorang turis asing menyebrang jalan, dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos kutang (T-shirt). Dia heran, mengapa jauh-jauh sang turis asing hanya berjalan seperti itu, padahal di negeri asal mereka berpakaian lengkap. Penulis menjawab apa bedanya hal itu dari ia sendiri yang melepas baju safari sepulang dari kantor dan mengenakan sarung di rumah. ***** Pada akhir minggu ke dua bulan Oktober 2003, penulis transit beberapa menit di lapangan terbang Hassanudin Makasar. Ketika ia di kamar mandi didapati closet WC tidak berfungsi memompa air. Terpaksa ia menggunakan gayung air untuk menyiram closet tersebut. Ini berarti tradisi melayani turis asing memang belum ada dalam kehidupan bangsa kita di daerah itu. Ini mungkin karena kecilnya penghasilan, sehingga orang yang bertanggung jawab terhadap closet itu tidak
pemah memeperhatikannya. Atau kerena memang tidak tersedianya anggaran untuk mengurusi closet tersebut. Padahal ini penting untuk melayani para turis asing tersebut. Jika di ruang VIP saja closetnya tidak terjaga rapi dapat dibayangkan di tempat-tempat lain di lingkungan lapangan terbang tersebut. Ini membuktikan, memang tradisi menjaga kepentingan para Wisman memang belum kita tumbuhkan. Jadi memang tidak cukup hanya dengan bergembargembor bahwa negeri kita penuh dengan keindahan alam bangsa kita, bersikap ramah-tamah kepada bangsa lain dan letak geografis negara kita sangat menguntungkan bagi pariwisata. Memang ketiga hal itu merupakan kelebihan alami dari kehidupan kita yang mungkin menarik perhatian orang. Tetapi tidak kurang pentingnya adalah tradisi pelayanan kepada mereka sebagaimana disebutkan di atas. Karenanya justru hal-hal seperti inilah yang memperlukan perbaikan terus-menerus, jika di kemudian hari kita inginkan pariwisata menjadi salah sebuah tiang kuat bagi perekonomian nasional maupun sebagai sarana pengenalan budaya kita. Perlakuan itu juga berlaku bagi sarana-sarana teknis seperti jalan-jalan raya dan landas pacu di berbagai lapangan terbang. Kabupaten Tanah Toraja misalnya, sudah dicanangkan sebagai kawasan pengembangan pariwisata yang kedua setelah Pulau Bali. Tetapi landas pacu yang ada di airport hanya dapat menampung pesawat-pesawat terbang kecil, padahal para teknisi sudah menyatakan hanya diperlukan sedikit perpanjangan jika landas pacu yang ada itu ingin dikembangkan untuk menampung pesawat-pesawat terbang seperti B-737 maupun MD-90. Memprihannkan memang, belum lagi jika berbicara tentang pengembangan sarana yelekomunikasi, penyediaan hotel-hotel dan sebagainya, yang memerlukan penanaman modal asing secara besar-besaran. Padahal investasi modal Asing di sini memerlukan kepastian hukum, berarti perbaikan sistem pemerintahan secara hukum. ***** Hal-hal di atas menunjukkan kepada kita, betapa pentingnya mengembangkan tradisi melayani wisatawan, kalau kita inginkan pariwisata menjadi salah satu soko guru perekonomian kita. Banyak peraturan yang harus dirubah dan disesuaikan menuju sasaran di atas. Kesadaran bangsa kita akan arti turisme dalam kehidupan, harus didorong untuk bertambah dan meningkat terus-menerus, padahal bangsa kita terkenal sangat kokoh dengan adat-istiadat dan budaya yang mereka miliki. Orang-orang Sulawesi Selatan sangat bangga dengan memiliki dengan Angin Mamiri dan tradisi Siri yang mereka miliki, mereka itu tidak mudah untuk mengubah hal-hal semacam itu. Tetapi, kita justru dapat memanfaatkan hal-hal seperti itu dan menjualnya kepada turis asing melalui paket kesenian dan kebudayaan daerah, tanpa harus melakukan perubahan tradisi apapun -paling tinggi merubah kemasannya-, agar dapat dicemakan oleh wisatawan. Spanyol merupakan negeri yang sangat maju dengan pariwisata, yang melibatkan hampir seluruh penduduk negeri itu. Jumlah para turis dari negeri-negeri lain yang memasuki Spanyol hampir dua kali lipat jumlah warga negaranya sendiri. Ini
terjadi tanpa merusak kesenian dan budaya Spanyol sendiri, bahkan memperkaya bahasa mereka. Tari-tarian dan musik flamenco merupakan dengung yang selalu terdengar selama kita berada di Spanyol, mengalahkan lagu-lagu rock dan lainlain. Pertandingan adu manusia melawan Banteng jantan, di sebut dengan istilah pertandingan Matador, masih tetap di penuhi orang sebagai olahraga nasional yang digemari bangsa itu, dan juga oleh para turis asing tersebut. Sangat sedikit orang Spanyol berbahasa Inggris tapi itu tidak menghalangi industri pariwisata mereka. Jelaslah dari uraian di atas beberapa hal menjadi prasyarat mutlak (conditio sine qua non) yang harus disediakan. Pelayanan yang ramah tamah dan perhatian yang bersungguh-sungguh ditambah dengan tradisi pariwisata yang cukup kuat merupakan hal-hal yang diperlukan untuk menunjang industri pariwisata itu. Karena itu harus kita cegah kebiasaan lama untuk mengumumkan target-target pariwisata, padahal baik sarana maupun prasarana belum tersedia dalam jumlah yang cukup. Lebih baik kita diam-diam mempersiapkan rangkaian persayaratan mutlak diatas, sebelum kita umumkan sasaran yang kita ingin wujudkan dalam pengembangannya di tanah air kita. Banyak upaya harus kita lakukan untuk itu, namun hal tersebut mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan bukan? Tokoh Kiai Syukri Oleh
Abdurrahman
Wahid
Pantas kalau ia dapat 'tingkat nasional' dalam forum sesama ulama. la cerdik dan teliti. Betapa tidak cerdik; karena di tiap forum ia meminta kesempatan bicara terakhir. 'Apa masih ada waktu untuk saya?' adalah 'merk dagang'-nya yang sudah diketahui semua orang diucapkan di kala pembicaran sudah akan diakhiri. Tetapi ada sesuatu di balik 'kebiasaan' yang disengaja itu, yaitu meluruskan lagi pembicaraan dari kecenderungan untuk menjadi terlalu sempit, terlalu berpegang pada penafsiran harfiah saja tanpa memasukkan pertimbangan situasi kongkrit dalam kehidupan. Misalnya, puitisasi AI-Qur'an. Apa pendapat Kiai? "Asal dimaksudkan penyajian ayat-ayat suci dengan susunan kalimat indah, tanpa mengubah inti pesannya, ya balk saja 'kan?" Banyak persoalan lain didekatinya dengan cara Kiai Syukri yang sudah tua, tetapi masih tetap perlente, temyata menimbang kearifannya sendiri dalam menggunakan keyakinan agamanya sebagai panduan hidup. Sejumlah orang NU dan Muhammadiyah secara bergurau memperdebatkan soal 'hadiah' membacakan surat AI-Fatihah kepada arwah yang sudah mati. Sampaikah 'kiriman' bacaan itu ke alamat yang dituju, seperti halnya Elteha dalam kehidupan dunia? Apakah dasar pendapat yang diikuti masing-masing? Yang dari Muhammadiyah tidak melihat 'dalil yang dapat dipegangi' dari AI-Qur'an maupun hadith Nabi Muhammad, untuk menunjang kemungkinan kiriman via 'Elteha akhirat' sampai ke tujuan di alam sana.
Yang NU memegangi pendapat para ulama mazhab yang empat, yang menerima kemungkinan seperti itu. Bagaimana Kiai Syukri? Semua mata memandang penuh harap kepada iai metropolitan yang menjadi Godfather-nya sekelompok 'mafia intelektual' dari sebuah daerah di selatan Jawa Tengah ini. Temyata tidak meleset harapan mereka. Kata Kiai: "Hadiah Fatihah tidak sampai ke alamatnya menurut Imam Syafi'i. la sampai menurut ketiga Imam mazhab yang lainnya. Kita ikuti suara mayoritas sajalah." Semua lega. Yang dari Muhammadiyah merasa aman karena pendapat mereka juga sejalan dengan pendapat imam pendiri dari mazhab yang paling banyak diikuti di Indonesia. Yangdari NU lega,karena masih bisa mengirimkan 'hadiah ulang tahun (kematian)' yang mereka warisi dari para kiai zaman dahulu. Sudah tentu kirimannya tidak segera sampai secepat pos kilat khusus karena tidak didukung oleh Imam Syafi'i, tetapi mereka toh sudah biasa dengan pola alon-alon asal kelakon. Mencari titik temu optimal dari pandangan yang saling bertentangan dengan jalan yang menuju kepada perbedaan pendapat di kalangan ulama di masa lalu, adalah spesialisasi Kiai Syukri. Ini adalah 'ideologi' yang dalam lingkungan para kiai dikenal sebagai sikap 'fihiqaulani' (dalam masalah ini ada dua pendapat), yang menyerahkan kepada umat untuk mengambil pilihan masing-masing antara dua spektrum pendapat yang saling bertentangan. Umat toh sudah dewasa, kalau dibawa alasan masing-masing pendapat, mereka akan lakukan pilihan secara dewasa. Kalaupun berbeda dengan orang dalam hal itu akan dilakukan tanpa sikap aprirori dan sejenisnya. Kunci dari sikap ini adalah keinginan sangat kuat untuk mencari apa yang terbaik bagi manusia, tetapi melalui pertimbangan manusiawi pula. Dalam bahasa fiqh, kecenderungan ini dinamai 'mengutamakan kemaslahatan memang perlu tetapi mencegah kerusakan jauh lebih penting lagi' (dar'ul mafasid aula min jalbil masalih). Berapakah diantara kita yang dapat mencapai kearifan demikian, jika diharapkan pada nilai normatif agama kita masing-masing? "Tombo Ati" Berbentuk Jazz Oleh: Abdurrahman
Wahid
Sebagaimana diketahui Tombo Ati adalah nama sebuah sajak berbahasa Arab ciptaan Sayidina Ali, yang oleh KH. Bisri Mustofa dari Rembang (ayah KH. A. Mustofa Bisri) diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan judul tersebut. Dalam sajak itu, di sebutkan 5 buah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT. Kelima hal itu dianggap sebagai obat (tombo) bagi seorang Muslim yang tingkahnya
menunjukkan bukan muslim yang baik. Dengan melaksanakan secara teratur kelima hal yang disebutkan dalam sajak tersebut, dijanjikan orang itu akan menjadi Muslim yang baik, dianggap demikian karena ia melaksanakan amalan agama secara tuntas. Sajak ini sangat populer dikalangan para santri di pulau Jawa, terutama di lingkungan pesantren. Karenanya sangatlah penting untuk mengamati, adakah sajak itu tetap digemari oleh kaum muslimin sunny tradisional? Hal ini menjadi penting karena sebuah faktor, kalau ia tetap dilestarikan, maka hal itu menunjukkan kemampuan muslimin Sunny tradisional menjaga budaya kesantrian mereka di alam serba modem ini. Jadi kemampuan sebuah kelompok melestarikan sebuah sajak bukan sekedar peristiwa lumrah. Peristiwa itu justru menyentuh sebuah pergulatan dahsyat yang menyangkut budaya kelompok Suny tradisional melawan proses modemisasi yang dalam hal ini berbentuk Westemisasi (pembaratan). Bahwa sajak itu, dalam bentuk sangat tradisional dan memiliki isi kongkret lokal (jawa), justru membuat pertarungan budaya itu lebih menarik untuk diamati. Sebuah proses maha besar yang meliputi jutaan jiwa warga masyarakat, sedang terjadi dalam bentuk yang sama sekali tidak terduga. Demikian juga dengan sajak tersebut. perintah agama untuk berdzikir tengah malam, mengerti dan memahami isi kandungan kitab suci Al-Quran, bergaul erat dengan para ulama dan berpuasa untuk menjaga hawa nafsu adalah hal-hal utama dalam asketisme (kalwah) yang merupakan pola hidup ideal bagi seorang Muslim, yang menempa dirinya menjadi orang baik dan layak (sholeh). Jika anjuran itu diikuti oleh kaum muslim dalam jumlah besar, tentu saja keseluruhan kaum muslimin akan memperoleh kebaikan tertentu dalam hidup mereka. Tetapi gambaran itu sangat ideal, namun modemisasi datang untuk menantangnya. **** Dalam sebuah perhelatan perkawinan di kota Solo, penulis mengalami sendiri hal itu. Ketika sebuah kelompok band menampilkan permainan lagu Tombo Ati itu secara modem. Penulis sangat tercenggang. Pertama, oleh kenyataan sebuah produk sastra yang sangat kuno (walaupun berupa terjemahan) dapat disajikan dalam irama yang tidak terduga sama sekali. Mungkin irama Jazz itu bercampur dengan langgam Jawa, namun ia tetap saja sebuah iringan Jazz. Mungkin tidak semodem permainan Sadao Watanabe, namun bentuk jazz dari Tombo Ati itu tetap tampak dalam sajian sekitar 5 menit itu. Di sini kita sampai kepada sebuah kenyataan, munculnya berbagai bentuk dan sajian tradisional dengan mempertahankan hakikat keaslian di hadapan tantangan modemitas. Tidak hanya penampilan alat-alat musiknya saja, melainkan dalam perubahan fungsi dari sajak itu sendiri. Kalau semula sajak itu dimaksudkan sebagai pesan moral sangat ideal bagi kaum muslimin, namun dalam pagelaran itu tersebut berubah peran menjadi sebuah hiburan. Tentu saja kita tidak dapat menyamakan pagelaran musik menggemakan Tombo Ati sama dengan debus dari Banten, yang memperagakan manusia tidak berdarah ketika ditusuk benda tajam. Dengan mudah kita mengatakan penari debus seperti itu, sebagai orang yang belasan tahun lamanya menahan diri dari
memakan sejumlah makanan dan membatasi kebiasaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak menyadari, sebenamya untuk melakukan pertunjukan debus itu, seseorang secara tirakat haruslah menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan itu. Dengan demikian keyakinan agama dan mereduksi kebiasaan keseharian menjadi latihan-latihan biasa. Ini memiliki arti perjumpaan serius (in counter) antara peradaban tradisional dan peradaban modem. Ini adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi bukannya dihardik atau disesali (seperti terlihat dari sementara reaksi berlebihan atas pagelaran ngebor dari Inul). Sudah tentu ini adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, karena di sinilah letak hubungan langsung antara kesenian dan dunia pariwisata. ***** Perjumpaan yang tradisional dan yang modem itu dimungkinkan oleh kerangka komersial yang bemama pariwisata. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa konsumerisme ada juga mengandung watak-watak yang tidak komersial, namun harus didorong untuk maju. Contoh penampilan sajak Tombo Ati itu dalam sajian jazz adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diamati. Jelas dari proses penampilan Tombo Ati itu terjadi sebuah proses yang oleh para pengamat perkembangan masyarakat disebut sebagai proses tawar menawar (trade off) yang sering terasa aneh, karena menampilkan sesuatu yang tidak tradisional maupun modem. Kemampuan melakukan tawar-menawar seperti itulah, yang sekarang dihadapi kebudayaan kita. Bahkan hal itu juga terjadi dalam perjumpaan antar agama. Ketika agama Budha dibawa oleh Dinasti Syailendra ke pulau Jawa dan bertemu dengan agama Hindu yang sudah terlebih dahulu datang, hasilnya adalah agama Hindu/Budha (bhairawa). Agama Islam yang masuk ke Indonesia juga mengalami hal yang sama. Perjumpaan antara jalan formal Islam dan budaya Aceh misalnya melahirkan seni kaum Suffi seperti tari Seudati, yang dengan indahnya digambarkan oleh James Siegel dalam Rope of God. Berbeda dari model Minangkabau yang mengalami perbenturan dahsyat bidang hukum agama, antara hukum formal Islam dan ketentuan-ketentuan adat. Hasilnya adalah ketidakpastian sikap yang ditutup-tutupi oleh ungkapan Adat Basandi Sara dan Sara Basandi Kitabullah . Di Gua (Sumatera Selatan) yang terjadi adalah lain lagi, yaitu ketentuan adat jalan terus sedangkan hal-hal tradisional pra-Islam juga dilakukan. Di pulau Jawa yang terjadi adalah hubungan yang dinamai oleh seorang akademisi sebagai hubungan multi-keratonik. Dalam hubungan ini kaum santri mengembangkan pola kehidupan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh adat pra Islam yang datang dari keraton. Perkembangan keadaan seperti itu, mengharuskan kita menyadari bahwa setiap agama di samping ajaran-ajaran formal yang dimilikinya, juga mempunyai proses saling mengambil dengan aspek-aspek lain dari kehidupan budaya. Di sinilah kita harus selalu menerima adanya perkembangan empirik yang sering dinamakan studi kawasan mengenai Islam. Dalam hal ini, penulis melihat perlunya studi kawasan itu untuk setidak-tidaknya kawasan-kawasan Islam berikut: Islam dalam
masyarakat Afrika-Utara dan negara-negara Arab, kawasan Islam di Afrika Hitam, Islam dalam masyarakat Turki-Persia-Afganistan, Islam di masyarakat Asia Selatan, Islam di masyarakat Asia Tenggara dan masyarakat minoritas Islam yang berindustri maju. Kedengarannya mudah membuat studi kawasan (area-study) Islam, tapi hal itu sebenamya sulit dilaksanakan. Tradisi, Kebudayaan Moderen, dan Birokratisasi Sudah lebih dari 50 tahun yang lalu Polemik Kebudayaan berlangsung, tapi masih juga di pertentangkan antara tradisi dan kebudayaan moderen. Sutan Takdir Alisjahbana masih juga menggebu-gebu dalam hal itu, dan lawan polemiknya dahulu juga masih tetap pada persoalan yang sama. Mereka masih ada yang menolak kebudayaan moderen, dan tetap mengagung-agungkan masa lampau Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram sebagai ukuran baku kebesaran masa lampau bangsa kita. Yang mengherankan, perdebatan itu terjadi tanpa satu pun yang mencoba melakukan proyeksi substansi yan mereka pertikaikan pada kenyataan lapangan yang sama sekali berbeda. Baik mereka yang mempromosikn modemisasi maupun yang menjajakan tradisionalisme sama-sama tidak berinjak pada kenyataan yang berkembang. Dialog seperti itu terasa tragis. Di satu pihak, kita menghabiskan energi dan waktu untuk berdebat hanya pada masalah dasar belaka. Tidak pemah beranjak ke tingkat lebih kongkret, seperti menyimak operasionalisasi nilai-nilai tradisional kepada lahan kehidupan yang dituntut untuk serba moderen. Di pihak lain, perkembangan keadaan berjalan terus tanpa mahu tahu apa yang diributkan pendukung modemitas dan pecinta tradisionalisasi. Dalam kenyataan, perubahan yang terjadi sudah berlangsung sangat jauh. Aspekaspek seremonial dari kebudayaan traisional telah dimodemisasikan dengan jalan dieksploitasikan oleh industri pariwisata. Pesantren tidak lagi repot dengan hanya kajian rutin acuan kitab kuning belaka, melainkan menggunakannya sebagai sumber inspiratif untuk modemisasi hidup pedesaan. Bukan sekedar menjadi lembaga pendidikan agama dalam artian tradisional, melainkan menjadi pangkalan untuk mendirikan dan melestarikan lembaga swadaya masyarakat LSM. Dalam fungsi tersebut, banyak pesantren telah memasuki era kehidupan baru, yaitu sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat. (LPSM). Demikian pula, apa yang dinamai kebudayaan modem telah menyadari pentingnya integrasi organik antara nilai-nilai lama dan visi budaya yang baru. Dengan cara meraba-raba, melalui berbagai kesalahan dan uji coba, sebuah proses kontekstualisasi visi budaya kita sedang berlangsung. Masalah pokoknya bukan lagi seperti rasionalitas haruskah diterima atau tidak, melainkan bagaimana ia dipergunakan untuk mendorong munculnya kreativitas dari tradisi. Tantangannya adalah bagaimana mencegah rutinisasi kehidupan budaya kita. Namun, sebuah bentuk rutinisasi lain justru yang mulai melanda kehidupan budaya kita. Rutinisasi dalam bentuk peranan birokrasi pemerintahan yang semakin hari semakin menentukan. Hingga hari ini memang masih belum menjadi birokratisasi kebudayaan kita, tetapi sudah cukup untuk membuat pengap suasana kehidupan budaya. Kreativitas bukan menurun oleh tarik urat antara tradisionalisme dan modemitas budaya, melainkan oleh meningkatnya peranan birokrasi pemerintahan dalam kehidupan budaya.
Bagaimana memacu kreativitas dalam kelesuan suasana, itulah masalah utama kita saat ini. Mampukah kita menembus kelesuan itu? Tuhan Akrab dengan Mereka Majalah Zaman baru-baru ini menampilkan sejumlah besar sajak anak-anak dibawah umur 15 tahun. Sajak-sajak-sajak itu selama ini di muat dalam rubrik Kebun Kita majalah tersebut, tentu saja telah diseleksi. Secara keseluruhan, puisi yang terkumpul dalam tiga belas halaman itu menunjukkan kuatnya apresiasi sastra anak-anak kita dewasa ini, dan membuktikan tidak sia-sianya pelajaran Bahasa Indonesia di semua sekolah, betapa banyak kekurangannya sekalipun. Mungkin kekurangan terbesar pada segi perbendaharaan kata yang sangat miskin, akibat logis dari kecenderungan orang dewasa yang sangat kuat untuk menggunakan istilah dari bahasa asing atau bahasa daerah. Namun kekurangan itu diimbangi oleh kemampuan cukup besar untuk mengolah kata-kata, sehingga memiliki nuansa dan pengertian baru. Juga besamya keharuan yang mendorong para penyair cilik kita untuk menciptakan puisi yang menyentu rasa, bahkan sesekali mengharukan. Dalam pendahuluan, redaktur Zaman Jimmy Supangkat menyidik besamya rasa murung yang ada dalam karya-karya tulis itu, terutama dalam sajak berbentuk doa. Jenis ini cukup banyak , 56 buah, namun banyak yang cengeng, ungkapannya kebanyakan klise belaka dan sarat dengan pengaduan masalah yang tak terselesaikan. Yang barangkali perlu dipahami adalah justru arti penting dari banyaknya jumlah sajak berbentuk doa - sebuah kenyataan yang sekaligus memantulkan keadaan kita dewasa ini maupun potensi yang dimilikinya untuk menatap masa depan dengan sehat dan baik. Sajak Doa dapat saja berwatak pelarian, terlalu mendambakan utopia. Dalam hal itu, ia akan berfungsi negaif bagi masa depan, karena manusia kehilangan kemampuan melihat realitas kehidupan. Hal seperti itu tidak nampak dalam kumpulan sajak anak-anak yang dikumpulkan majalah Zaman itu. Umpamanya saja dapat dilihat kedewasaan dialog para penyair cilik itu dengan Tuhan masing-masing. Tuhan menggumpal jadi sasaran kebutuhan duniawi Zul Irwan, yang masih belum yakin dengan kemampuannya mempersiapkan diri menghadapi tugas sekolah, dalam kata-katanya. Tuhan.../berikan aku mimpi malam ini/ tentang matematika/yang diujikan besok pagi. Sudah tentu ia sendiri paling sadar, bahwa Tuhan tidak akan menuruti permintaan kocak tersebut. Tuhan jugalah yang jadi sasaran kebingungan Adi Utomo Hatmoko yang mengalami keterputusan komunikasi, ketika ia berdoa Doaku sudah ku akhiri/hingga engkau tidak bakal mengerti/Amin. Sebaliknya, Agatha Artistayudha menggugat suasana tidak peduli kepada Tuhan, dalam sajaknya Kitab Suci: Engkau di dalamnya, Tuhan? terpepet/dan/menjadi makanan rayap/ketika semua orang/tak menghiraukanMu lagi Bisa juga Tuhan menjadi obyek kekenesan belaka, seperti di perbuat Sri Pinurih
Tuhanku ../ aku tidak sanggup meneruskan/karena tenggelam/dalam isak tangis/kedukaan/. Atau obyek sikap manja Rusbandi dalam Kepada Tuhan Tuhan, bukan bintang yang ingin kuminta/bukan pula bulan/aku hanya meminta sebuah kitab/yang berisikan puisi/untuk ayah bunda. Dalam sajak-sajak mereka, ada juga kesadaran yang dewasa tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti Doa Avida Virya yang tadinya minta baju baru dari Tuhan: Aku mendengar/Tuhan berkata ; engkau tak perlu gelisah/mamamu akan memberimu/bahkan lebih baik lagi Dalam pola inilah para penyair cilik itu menuntut kejujuran dalam hubungan dengan Tuhan, seperti ungkap Dewi Marhaini Nasution Tuhanku/kupandang mata ibuku dalam-dalam/agar dapat melihat/apakah ibuku jadi juga pergi ke masjid/bersembahyang Isa? Di samping tuntutan tersebut, penyair cilik ini juhga merasakan kehadiran Tuhan dalam bentuk sangat sublim. Sunguh aku tak tahu/bahwa Tuhan itu/adalah Kau/yang setiap saat kujumpai/lewat permainan kami tadi. Mohamad Sofyan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kedekatan hubungan antara sesama manusia, walaupun dalam arti yang lain lagi. Bila Kau hendak memangil/pangil aku sendiri/bila Kau hendak memberi/jangan aku sendiri. Betapa polosnya hubungan mereka dengan Tuhan, inilah yang mungkin akan mengekalkan penghayatan keimanan bangsa ini, bukannya khotbah para agamawan ataupun diskusi pemikiran agama. Seolah olah para penyair cilik itu mengerti benar, bahwa masalah dasar bangsa ini hanya teratasi, kalau warga bangsa memiliki wawasan transendental yang kaya, yang memungkinkan mereka menemukan harkat manusia. Wawasan seperti itu hanya akan tercapai, kalu manusia mampu berdialog dan merasa dekat dengan Tuhannya. Keakraban manusia dalam keadaan begitu, akan diimbangi oleh keakraban Tuhan dengan dirinya, yang akan memberinya kekuatan mnyelesaikan kemelut yang diciptakannya sendiri. Dengan kemampuan para penyair cilik itu untuk merasa dekat dengan Tuhan, seperti digambarkan di atas, jadi nyata bagi kita bahwa Tuhanpun merasa akrab dengan mereka. Mampukah kita mencari keakraban seperti itu? Kita dapat belajar dari Rudiawan Triwidodo dalam sajak Doa Di Bibir Sumur, ketika ia mengharapkan tetesan air mata Tuhan: Agar tersedu tangis kami dengan wajar/sebab hampir terlupa bagaimana kami/harus menangis/dengan benar/mensyukuri berkat dan rahmat-Mu/yang melimpah/di luar sadar kami/agar basah sumur-sumur kami/tersiram air kasih yang memancar dari/Sumber keMahaanMu/Amin. Tuhan Tidak Perlu Dibela Oleh: Abdurrahman
Wahid
Sarjana yang baru menamatkan studi di luar negeri pulang ke tanah air. Delapan tahun ia tinggal di negara yang tidak ada orang muslimnya sama sekali. Di sana
juga tak satupun media massa Islam mencapainya. Jadi, pantas sekali X terkejut ketika kembali ke tanah air Di mana saja ia berada, selalu dilihatnya ekspresi kemarahan orang muslim. Dalam khotbah Jumat yang didengamya seminggu sekali, dalam majalah Islam, dan pidato para mubalig dan dai Terakhir ia mengikuti sebuah lokakarya. Di sana diikutinya dengan bingung uraian seorang ilmuwan eksakta tingkat top yang menolak wawasan ilmiah yang diikuti mayoritas para ilmuwan seluruh dunia, dan mengajukan teori ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai altematif. Bukan penampilan altematif itu sendiri yang merisaukan sarjana yang baru pulang itu, melainkan kepahitan kapada wawasan ilmu pengetahuan modem yang terasa di sana. Juga idealisasi wawasan Islam yang juga belum jelas benar apa batasannya bagi ilmuwan yang berbicara itu. Semakin jauh X merambah rimba kemarahan kaum muslimin itu, semakin luas dilihatnya wilayah yang dipersengketakan antara wawasan ideal kaum muslimin dan tuntutan modemisasi. Dilihatnya wajah berang di mana-mana. Di arsip proses pelarangan atas cerpen Ki Panjikusmin Langit Makin Mendung. Dalam desah nafas putus asa dari seorang aktivis organisasi Islam ketika ia mendapati X tetap saja tidak mau tunduk pada keharusan menempatkan "merek Islam" pada kedudukan tertinggi atas semua aspek kehidupan. X, bahkan melihat wajah kemarahan itu dalam serangan yang tidak kunjung habis terhadap" informasi salah" yang ditakuti akan menghancurkan Islam. Termasuk semua jenis ekspresi diri, dari soal berpakaian hingga tari Jaipongan. Walaupun gelar doctor diperolehnya dalam salah satu cabang disiplin ilmu-ilmu sosial, X masih dihadapkan pada kepusingan memberikan penilaian atas keadaan itu. Ia mampu memahami sebab-sebab munculnya gejala merasa terancam selalu yang demikian itu. Ia mampu menerangkannya dari sudut pandangan ilmiah, namun ia tidak mampu menjawab bagaimana kaum muslimin sendiri dapat menyelesaikan masalah itu sendiri. Karena, menurut pemahamannya, gejala keberangan itu menyangkut aspek ajaran agama yang paling inti. Di luar kompetensinya, keluhnya dalam hati. Karena itu, diputuskannya untuk pulang kampung asal, menemui pamannya yang jadi kiai pesantren. Jagoan ilmu fiqh ini disegani karena pengakuan ulama yang lain atas ketepatan keputusan agama yang dikeluarkannya. Si "paman kiai" juga merupakan perwujudan kesempumaan perilaku beragama di mata orang banyak. Apa jawab yang diperoleh X ketika ia mengajukan "kemusykilan" yang dihadapinya itu? "Kau sendiri yang tidak tabah, Nak. Kau harus tahu, semua sikap yang kau anggap kemarahan itu adalah pelaksanaan tugas amar maruf nahi munkar," ujar sang paman dengan kelembutan yang mematikan. "Seharusnya kau pun bersikap begitu pula, jangan selalu menyalahkan mereka." Terdiam tidak dapat menjawab, X tetap tidak menemukan apa yang dicarinya. Orang muda ini lalu kembali ke ibu kota, mencari seorang cendekiawan muslim
kelas kakap. Siapa tahu dapat memberikan jawaban yang memuaskan hati. Dicari yang moderat, yang dianggap mampu menjembatani antara formalisme agama dan tantangan dunia modem kepada agama. Terdiam tidak dapat menjawab, X tetap tidak menemukan apa yang dicarinya. Orang muda ini lalu kembali ke ibu kota, mencari seorang cendekiawan muslim kelas kakap. Siapa tahu dapat memberikan jawaban yang memuaskan hati. Dicari yang moderat, yang dianggap mampu menjembatani antara formalisme agama dan tantangan dunia modem kepada agama. Orang muda yang satu ini tercenung tanpa mampu merumuskan apa yang seharusnya ia pikirkan. Haruskah pola berpikimya diubah secara mendasar mengikuti keberangan itu sendiri? Akhimya ia diajak seorang kawan seprofesi untuk menemui seorang guru tarekat. Dan, disitulah ia memperoleh kepuasan. Jawabannya temyata sederhana saja. Allah itu Maha Besar. Ia tidak memerlukan pembuktian atas kebesaranNya. Ia Maha Besar karena Ia ada. Apa yang diperbuat orang atas diri-Nya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujud-Nya dan atas kekuasaan-Nya. Al-Hujwiri mengatakan: bila engkau menganggap Allah ada hanya karena engkau merumuskannya, hakikatnya engkau sudah menjadi kafir. Allah tidak perlu disesali kalau ia 'menyulitkan' kita. Juga tidak perlu dibela kalau orang menyerang hakihatNya. Yang ditakuti berubah adalah persepsi manusia atas hakikat Allah, dengan kemungkinan kesulitan yang diakibatkannya. Kalau diikuti jalan pikiran kiai tarekat itu, informasi dan ekspresi diri yang dianggap merugikan Islam sebenamya tidak perlu terlalu "dilayani" Cukup diimbangi dengan informasi dan ekspresi diri yang "positif konstruktif". Kalau gawat, cukup dengan jawaban yang mendudukan persoalan secara dewasa dan biasa-biasa saja. Tidak perlu dicari-cari. Islam perlu dikembangkan, tidak untuk dihadapkan pada serangan orang. Kebenaran Allah tidak akan berkurang sedikit pun dengan adanya keraguan orang. Maka, iapun tenteram. Tidak lagi merasa bersalah berdiam diri. Tuhan tidak perlu dibela, walaupun juga menolak dibela. Berarti atau tidaknya pembelaan akan kita lihat dalam perkembangan di masa depan. Ulang Tahun Sebuah Vihara Oleh:
Abdurrahman
Wahid
Minggu kedua Oktober 2003, penulis menghadiri ulang tahun ke 314 sebuah Wihara di kawasan Jatinegara. Wihara tersebut dihuni para Biksuni dan dikelola oleh sebuah kepengurusan baik dari kaum pria maupun kaum wanita. Karena tuanya yaitu ketika masa-masa permulaan Dinasti Mataram berkuasa, maka ia memiliki para pengikut orang-orang awam yang berjumlah banyak sekali. Mereka yang umumya adalah keturunan Tionghoa, menghidupi Wihara tersebut, dan
dengan sendirinya membiayai peringatan ulang tahun tersebut. Walaupun hanya seperempat jam penulis berada di Wihara tersebut, ia disambut dengan peragaan Barongsai dan memperoleh hadiah luar biasa: sebuah patung harimau yang penulis tidak tahu dibuat dari bahan apa? Dan menjadi lambang apa pula? (lambang keulamaan, kekuatan ataukah kekuasaan), -Kedua jawaban itu tentu saja berkaitan dengan asal-usul budaya masyarakat tempat Wihara itu terwujud. Penulis juga memperoleh makanan berupaya talas goreng -padahal tadinya memperkirakan akan memperoleh kue keranjang- yang menjadi makanan khas orang Tionghoa di hari-hari raya mereka. Variasi sangat tinggi dari cara hidup para keturunan Tionghoa itu menunjukkan keragaman sangat besar dalam kehidupan satuan-satuan etnis bangsa kita. Inilah yang justru harus kita lestarikan sebagai kekayaan bangsa. Walaupun masing-masing menghadapi tantangan hidup budaya modem yang cenderung menyeragamkan pola-pola hidup kita atas nama efisiensi dan globalisasi. Dan atas nama keduanya pula dilakukan penyeragaman selera kita, seperti tampak pada blue jean, hamburger dan film barat. Bagi penulis, penyeragaman selera seperti itu adalah tambahan variasi atas pola hidup beragam yang sudah kita miliki dari dahulu. Justru dalam hal-hal seperti itu, kekayaan hidup kita sebagai bangsa dipakai untuk menambah kekuatan dan kebesaran bangsa, ditengah pola kehidupan intemasional yang demikian besar ragamnya. Dengan demikian, bangsa kita akan mampu membuktikan kebesarannya dalam kehidupan intemasional, dan justru sanggup menjadikan kekayaan sangat beragam itu sebagai pendorong munculnya kebesaran bangsa dan negara kita. Penulis menolak teori budaya melting pot, karena dalam pandangan penulis percampuran seperti itu akan menghasilkan budaya hibrida yang justru berlawanan dengan prinsip keberagaman itu sendiri. ***** Ada tiga hal yang telah kita capai secara fundamental, yang merupakan kekuatan kita sebagai bangsa dan negara: pertama, kita sekarang memiliki sistem pemerintahan/administrasi tunggal melalui sistem demokrasi adimistrasi negara. Kita sudah terbiasa dengan hakim suku Ambon bertugas di Aceh, Jaksa suku Minang di Papua ataupun Dosen Universitas Negeri di Kalimantan dari suku di Flores. Penyeragaman sarana ini menyatukan kita sebagai sebuah bangsa di lingkungan sebuah negara, tanpa menggangu kemajemukan budaya kita. Kedua, kita menggunakan bahasa nasional, yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang memungkinkan kita berkomunikasi satu sama lain. Pengembangan bahasa nasional itu membuat perubahan-perubahan sosial terjadi dengan cepat di lingkungan negara kita sendiri. Dan terakhir, kita juga memiliki saling ketergantungan (interdependency) antar daerah. Hasil-hasil hutan Kalimantan diproses di pulau Jawa, sedangkan produk laut kita yang demikian kaya dikirimkan ke pasaran intemasional. Dengan berbagai peraturan-peraturan dan kerangka kegiatan yang sangat beragam tadi, memang diperlukan sebuah kebijakan baru untuk mengembangkan pasaran dalam negeri (Domestic Market), yang sesuai dengan besamya potensi
ekonomi bangsa kita. Dengan memiliki jumlah penduduk (yang berarti pasar) sebanyak 204 juta jiwa saat ini, penciptaan pasar dalam negeri seperti itu, harus secara optimal didorong oleh dan untuk melayani peningkatan pendapatan perkapita rakyat Indonesia setiap tahun. Sehingga wajar saja akan dicapai pendapatan ribuan dollar AS setiap warga negara per-tahun dalam waktu singkat. Ini berarti keharusan kita untuk tidak bersandar pada ekspor lagi, karena perluasan pasaran dalam negeri akan menyerap seluruh produksi nasional kita, jika dilakukan langkah-langkah untuk menerapkan kebijakan menahan impor barang murah dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) untuk barang-barang tertentu. Yang dapat digunakan adalah mencabut tariff bebas hambatan (non-tariff barrier) atas barangbarang luar negeri dari jenis tertentu yang diimpor kemari. Dengan mengandalkan diri pada kualitas tinggi barang-barang produksi nasional, -seperti elektronik dan optika, serta kendaraan umum dan barang-barang mesin-. Dengan berbagai kebijakan, seperti di atas ditambah kredit murah oleh bank-bank pemerintah kepada para pengusaha UKM (Usaha Kecil dan Menengah) akan membuat ekonomi kita berkembang pesat dan benar-benar mewakili bangsa. ***** Kesemua upaya di atas, mengharuskan kita sebagai bangsa memperkuat keberagaman budaya bangsa kita. Kaitannya dengan hal itu adalah saudarasaudara kita keturunan Tionghoa tentu memiliki budaya mereka sendiri yang sudah berumur ribuan tahun, sehingga mereka menjadi kelompok pengusaha yang sangat kuat. Keberagaman ini tentu lebih memiliki peluang untuk mempertahankan diri dari tantangan-tantangan modemisasi yang kita alami sebagai bangsa. Selama proses modemisasi itu bersifat mengkokohkan manajemen, administrasi, permodalan dan kemampuan berorganisasi kaum pengusaha Tionghoa itu, harus tetap tersedia peluang untuk itu. Namun, kehidupan kaum pengusaha Tionghoa itu tidak dapat hanya dibatasi oleh dunia usaha saja, mereka adalah juga golongan masyarakat yang memiliki budaya sendiri. Inipun harus terus didorong untuk memperoleh pemeliharaan yang wajar dari masyarakat keturunan Tionghoa secara keseluruhan, termasuk para pengusaha mereka. Di sinilah terletak keharusan kita menghormati berbagai hal yang bersifat ritual di kalangan mereka. Diantaranya adalah peringatan Ulang Tahun Wihara, seperti disaksikan penulis, dan permainan Barongsai dan pidato-pidato adalah bagian tak perpisahkan dari Budaya Ulang Tahun tersebut. Menghormati budaya keseluruhan proses bermasyarakat mereka, lengkap dengan segala macam atributatributnya serta sikap menerima mereka sebagai bagian dari budaya bangsa yang demikian kaya dan sangat beragam. Menghormatinya sama dengan menghormati budaya suku bangsa lainnya yang berbentuk penampilan bermacam-ragam. Hanya dengan cara demikian kita dapat menciptakan bangsa yang kuat di tengah-tengah pergaulan intemasional. Sudah tentu kita juga harus menolong saudara-saudara kita warga keturunan Tionghoa, dari unsur-unsur dalam mereka yang melakukan berbagai tindakan
melawan hukum, apalagi yang menjadi preman. Tetapi tentu saja tidak sepatutnya kita mengadu domba mereka, dengan berbagai cara mendorong mereka untuk menjadi informan atas tindakan kepremannan kelompok itu. Itu adalah urusan dan tanggung jawab pihak keamanan dan aparat hukum. Memelihara keadilan hukum tidak dapat dilakukan dengan cara melanggar hukum itu. Memang mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan, bukan? Ustadz yang Hidup dalam Dua Dunia Oleh Abdurrahman
Wahid
Hidup dalam dua dunia umumnya mempunyai konotasi yang tidak baik, ada yang disembunyikan dari dunia yang satu terhadap dunia yang lain. Bagaikan beristri lebih dari satu: kepada istri tua tidak mau mengaku datang dari rumah istri kedua, begitu juga sebaliknya. Tetapi temyata konotasi tidak baik bukan pada tempatnya diletakkan pada kehidupan dua dunianya Ustadz Abdur Razak Khaidir dari Tegalparang. Orang Betawi memberi nama bermacam-macam kepada kaum agamawan mereka. Yang masih belum sepenuhnya diterima sebagai kiai, tetapi telah menunjukan potensi kuat untuk itu, dinamai ustadz (kalau ikut dialek Arab-Mesir).Yang telah mapan diberi nama mu'allim. Sekarang datang gelar baru, yang diambil dari budaya Jawa: kiai. Yang dari keturunan Arab dan dianggap masih berhubungan darah dengan Nabi, dinamai habib, sayyid, syarifdan seterusnya. Tetapi kesemuanya itu masuk dalam kategori tinggi sebagai guru kite. Istilah umum yang menunjukan tingginya status sosial mereka dalam masyarakat tradisional Betawi. Ustadz Razak mengikuti pola umum pendidikan untuk menjadi agamawan di wilayah Jakarta Selatan: mengaji AI-Qur'an di langgar pada seorang ustadz di waktu kecil, dilanjutkan belajar di sekolah agama, untuk diakhiri belajar di "tanah Arab". Mula-mula sebagai 'mukimin' di Mekkah selama bertahun-tahun, kemudian dilanjutkan juga di Mesir sampai pulang ke tanah air di tahun 1967. Sekembalinya dari menuntut 'ilmu' dirantau orang, ia kembali mengikuti pola umum untuk menempatkan diri di barisan ulama Betawi: membantu mengajar di madrasah, untuk disambung dengan memberikan pengajian di luar kepada rakyat awam, dan akhimya hanya sibuk dengan pengajian tanpa mampu lagi mengajar di sekolah. Pengajian di luar, di lingkungan majelis ta'lim yang tersebar di seluruh kawasan tradisional kaum Betawi, mula-mula dilakukan dengan susah payah. Keluar masuk di perkampungan terpencil tanpa jalan beraspal, berjalan kaki di jalan berlumpur yang tidak dapat di masuki kendaraan. Mengajamya pun hanya kepada kelompok-
kelompok
pengajian
yang
kecil.
Kemudian 'nasib' nya membaik. Pengajian bertambah banyak, dan tersebamya pun pada masjid-masjid 'strategis'. Di tambah lagi akhimya menjadi dosen IKIP, sudah tentu di bidang keagamaan dan sastra Arab. Kini sudah keren idupnye, kalau meminjam istilah orang Betawi: rumah cukup besar, mobil Corona tahun akhir-akhir, dan memiliki 'merk dagang' berbentuk jas putih dan serban yang berwama putih kalau berangkat ke pengajian. Acara sudah padat, tenggorokan sudah kering tidak mampu melayani kehendak orang banyak. Statusnya sudah diterima di kalangan ulama lain. Walhasil, gambaran konvensional dari pemunculan seoratigguni kite yang masih muda. Tetapi temyata ada unsur lain yang membuatnya tidak konvensional. Kalau caloncalon mu'allim lain masih ribut dengan masalah-masalah konvensional, seperti urusan judi, menentang rambut gondrong, ribut mempertahankan status quo suasana moral lama, maka ustadz yang juga guru kite ini justru membawakan pesan-pesan yang memandang jauh ke depan. la mempersoalkan beberapa masalah yang sebenamya cukup mendasar, dan disampaikannya dengan gaya orang Betawi pula - gaya santri yang khas dan penuh ilustrasi kejadian sehari-hari yang di selingi dengan rangkaian 'dalil' berupa ayat AI-Qur'an, hadits Nabi dan mutiara hikmah dari para ulama terdahulu. Pendapat sendiri hanya dikemukakan sebagai tambahan atas pendapat ulama kuno sama sekali tidak menyanggah atau menyangkal. Tidak heranlah jika sedikit sekali terjadi penolakan atau kehebohan di sekitar pemyataannya. Misalnya perkara naik haji. Syarat cukupnya kemampuan ekonomis sebelum memutuskan pergi ke Mekkah menunaikan ibadah haji dikaitkannya dengan hikayat ahli hadith Abdullah ibnu Mubarak. Sebagai ketua rombongan kafilah haji dari negerinya, Abdullah ibnu Mubarak menjumpai wanita melarat yang menyuapi anaknya dengan daging bangkai. Ketika ditanya apakah tidak mengerti haram hukumnya memakan daging bangkai, wanita itu menjawab bahwa ia mengerti, tapi ia terpaksa. Tidak ada makanan lain. Sang ahli hadith lalu memerintahkan pada seluruh rombongan untuk membatalkan perjalanan haji, menyerahkan perbekalan pada wanita itu, dan kembali pulang. Tidak wajib haji, katanya, selagi masih ada yang melarat. Ucapan ahli hadits itu dikiaskan oleh ustadz kita ini kepada lebih wajibnya memelihara lembaga pendidikan (yang akan menghilangkan kemelaratan) dari pada kewajiban berhaji dua kali dan seterusnya. Dunia ini persiapan untuk kehidupan akhirat kelak, kata sang ustadz sewaktu mengaji di Ciganjur. Kehidupan akhirat sangat tergantung pada kualitas hidup di dunia: kalau bodoh, melarat dan terbelakang, tidak banyak yang dapat diperbuat
di dunia ini untuk kepentingan akhirat kelak. Kalau tidak kuat ekonominya tidak mungkin kuat menunaikan ibadah haji, padahal ibadah haji adalah persiapan lebih sempuma lagi untuk kepentingan kehidupan akhirat itu. Kehidupan bahagia di akhirat berkaitan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia pula, karena kebahagiaan dunia adalah bagian dan kehidupan akhirat. Menarik sekali untuk dikaji lebih jauh pandangan seperti ini: membedakan hidup di dunia dari hidup di akhirat, tapi meletakkan keduanya dalam jalur dan kadar yang sama. Ada persambungan antara keduanya, kata sang ustadz. Kesinambungan, kata favoritnya. Kontinuitas, kata kamus antropologi. Walhasil, 'manunggalnya' dunia dan akhirat. Bukankali cukup baik untuk hidup di dunia seperti yang dilakukan ustadz Razak ini, bukan? Mengapa kita masih berkeras juga untuk terlalu memisahkan antara keduanya? Mengapa harus dipertentangkan, padahal saling melengkapi? Mengapa takut dituduh Calvinist, kalau semuanya bersumber dari ajaran agama sendiri? Ustadz Razak, seumur hidupnya mungkin belum pemah mendengar nama Calvin, dan sepanjang umumya hanya mengurusi pandangan orang Islam saja. Yang Penting Mereka Berdialog Oleh: Abdurrahman
Wahid
Dalam perjalanan ke New York baru-baru ini, penulis dibacakan sebuah berita yang sangat menarik. Akhimya, Perdana Menteri (PM) Ariel Sharon dari Israel mengirim Menteri Luar Negeri (Menlu) Silvan Shalom untuk bertemu Presiden Mubarak di Roma. Pada saat yang sama, pihak Palestina -melalui Menteri Keuangannya-, mengemukakan sebuah paket berisikan antara lain bantuan dua milyar dollar AS lebih untuk pembangunan ekonominya. Sekembali penulis dari New York (NY), dalam perjalanan ia mengikuti berita bahwa ada sejumlah konsesi Israel kepada pihak Palestina, termasuk penyerahan tiga buah kawasan pemukiman (settlements) kepada pihak Palestina. Adakah orang-orang Yahudi yang menjadi penduduknya ditarik ke kawasan-kawasan pemukiman yang lain di Israel, tidak begitu jelas. Namun, pada saat yang sama diumumkan bantuan militer dan ekonomi AS kepada Israel sebesar lebih dari sembilan milyar dollar AS. Ini adalah perkembangan yang sangat menggembirakan, karena sejak tiga tahun terakhir ini perundingan antara Israel dan Palestina mengalami kemacetan luar biasa. Sebabnya, karena kedua pihak tetap berkeras pada pendirian masingmasing. Ditambah pula kemarahan Israel atas serangkaian peledakan bom bunuh diri (suicidal bombings) yang sudah menewaskan lebih dari 100 nyawa di Israel, sehingga tidak ada kawasan yang boleh dikata aman di Israel. Pemboman bunuh diri itu tidak dapat dikuasai oleh Yasser Arafat, pemimpin Palestina yang tidak mampu menguasai kelompok-kelompok radikal di kalangan bangsa Palestina seperti, Hammas, Hizbullah dan lain-lain, yang umumnya terdiri dari para pemuda Palestina. Karena kelemahan-kelemahan Arafat itu, bahkan Ariel Sharon sudah
kehilangan kepercayaan kepadanya. Ini adalah pangkal dari sikap Sharon untuk memecat Arafat dari kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Palestina. Ini penulis rasakan sendiri, ketika berkunjung ke rumah Ariel Sharon di Jerusalem bulan Juni yang lalu, bersama Michael Gorbachev dan F. W. de Klerk untuk sebuah kunjungan kehormatan (courtesy call). Kunjungan yang direncanakan hanya 30 menit itu di mulai jam 22.00 waktu Israel, temyata berlanjut terus hingga jam 1.30 dini hari. Sebabnya, karena Sharon bersikeras Arafat harus dibuang (kicked out) dari jabatannya, sementara Gorbachev mempertahankan Arafat sebagai perwakilan sah bangsa Palestina dalam sebuah perundingan intemasional mengenai sengketa Israel-Palestina. Begitu rupa perbedaan pendapat itu berkembang, sehingga penulis melihat sangat kecil kemungkinan untuk terlaksana. Seperti biasa, penulis sengaja menyimpan pendiriannya, agar di kemudian hari tidak mati jalan, jika harus turut serta dalam konferensi yang sebenamya. Di sinilah terletak perbedaan antara pendekatan penulis dengan pandangan Gorbachev. Ia sudah tidak melihat jalan untuk menjadi penengah dalam sengketa antara kedua bangsa itu. Karena itu, ia terbuka untuk mengemukakan pandangan secara apa adanya. Penulis masih melihat peluang Indonesia untuk turut serta dalam mencapai perdamaian antara kedua bangsa serumpun itu. Itulah sebabnya, penulis hanya meminta ketegasan baik Sharon maupun Gorbachev, mengenai beberapa hal. Dengan itu, penulis dapat mengembangkan sendiri pandangan-pandangannya, yang mungkin saja dapat membantu penyelesaian sengketa tersebut secara damai. Temyata perkembangan baru itu sekarang mulai terjadi, dan penulis turut bergembira karenanya. ***** Ada dua buah pendapat yang berkembang mengenai sengketa itu. Di satu pihak, pendapat beberapa orang agamawan yang tergabung dalam IIFWP (Intemational Inter-religious Federation on World Peace), yang bermarkas besar di NY. Menurut wakil Sekretaris Jenderal-nya, Taj Hamad, seorang muslim dari Sudan, sebab dari sengketa tersebut adalah rasa marah bangsa Yahudi (serta lembaga-lembaga keagamaannya) bahwa mereka telah dijadikan kambing hitam bagi semua hal yang tak benar yang terjadi di dunia. Umpamanya saja, mereka masih marah terhadap sikap orang-orang Kristen yang menganggap Yesus Kristus sebagai messiah (juru selamat), yang kemudian oleh orang-orang Kristen itu dianggap sebagai anak Tuhan. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak pemah mengakuinya sebagai messiah. Rasa marah itu disebabkan oleh dua hal yang bersamaan: anggapan bahwa orang Yahudi bersalah atas disalibnya Yesus Kristus, yang kini dianggap oleh semua orang Kristen sebagai penebusan dosa. Padahal tidak semua kalangan Kristen setuju dengan hal itu, bahkan mereka itu tidak percaya bahwa hal itu memang terjadi. Kedua, sikap menyalahkan orang-orang Yahudi itu juga merembet ke bidangbidang lain dalam kehidupan. Padahal mereka justru menderita karena selalu dipersekusi/dituduh oleh orang-orang Kristen dan Islam. Contoh yang paling nyata bagi Yahudi dalam hal ini adalah diaspora (paksaan untuk berpencar-pencar) dan
Holocaust (pembinasaan secara biadab) oleh NAZI Jerman dalam Perang Dunia II, yang menghabiskan nyawa lebih dari 35 juta jiwa orang Yahudi. Sikap dunia yang tidak pemah memperhatikan perasaan orang Yahudi dalam hal ini, membuat mereka marah. Untuk itu, mereka lalu mendirikan sebuahh Museum Diaspora dan sebuah Museum Holocaust di tanah air mereka (Israel), dan Museum Holocaust di New York, yang antara lain menyimpan ratusan ribu sepatu milik orang Yahudi yang dihukum mati dengan gas. Karena itu penulis selalu menunjukkan simpati kepada bangsa Yahudi karena penderitaan mereka itu. Penulis juga mendampingi orang-orang Yahudi yang mencoba menegakkan perdamaian antara orang-orang Yahudi dengan bangsabangsa lain. Karena itulah, penulis menjadi salah seorang pendiri pusat perdamaian Simon Perez yang berkantor di Tel Aviv. Karena lembagai itu melihat bahwa upaya orang Yahudi untuk menolong dan mengabdi kepada bangsa Palestina sebagai sebuah cara untuk menebus dosa segala macam kesalahan di masa lampau kepada orang lain. Dan sebagai persyaratan jika tidak ingin dikatakan sebagai orang yang mau menang sendiri atas bangsa-bangsa lain. Karean itulah penulis mendukung gagasan itu. Sekarang motivasi-motivasi lembaga dengan pimpinan yang bersifat intemasional itu, telah menjadi langkah pendamai bagi bangsa Israel dan Palestina. Penulis merasa bangga atas sikapnya itu, yang dulu hingga saat ini pun dianggap salah oleh sementara kalangan. ***** Tanpa berupaya mencari mana yang benar dan mana yang salah di antara kedua pandangan itu, penulis mencoba menyertai para pemimpin yang menyalahkan Israel itu, dan atau sikap Israel yang tidak mau mengakui hal itu. Penulis mencoba untuk meyakinkan para pemimpin Israel, bahwa sikap mereka untuk berunding itu, pada akhimya adalah sesuatu yang bijaksana. Untuk itulah penulis akan turut serta dalam demo (long march) para pemimpin agama besar-besaran di Jerusalem minggu ini, yang meminta bangsa Yahudi mengubur kemarahan mereka. Dan sebaiknya mencari jalan-jalan baru untuk mencari penyelesaian damai dan lebih bersungguh-sungguh dalam berunding dengan para pemimpin Palestina, untuk mencari penyelesaian permanen melalui negosiasi. Hanya dengan cara tidak menggunakan tindak kekerasan terhadap siapapun, penyelesaian damai dapat dilakukan. Tentu saja sejumlah pemimpin radikal yang melakukan tindak kekerasan di antara kedua pihak pun harus dihukum. Di sini perlu ditekankan, keikutsertaan penulis dalam demo (long march) tersebut, yang diperkirakan akan mencapai jumlah 300.0000 orang di Jerusalem (sesuatu yang jarang terjadi di Timur Tengah. Ini tidak berarti penulis berpihak kepada siapapun, kecuali kepada penyelesaian damai yang permanent atas sengketa Israel-Palestina. Dalam hal ini, sikap netral memang merupakan kunci yang harus kita pegang teguh. Dan yang terpenting adalah bagaimana menciptakan mekanisme perdamaian di kawasan yang selalu penuh dengan pertentangan itu. Ini yang sering dilupakan orang, akibatnya timbul kecurigaan dari keduabelah pihak. Hanya dengan negosiasi antara bangsa Yahudi dan Palestina melalui mekanisme perundingan berkepanjangan, dapat ditimbulkan rasa saling percaya-
mempercayai antara kedua belah pihak yang menjadi persyaratan utama bagi sebuah penyelesaian damai antara mereka. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan, bukan? Yang Terbaik Ada Di Tengah Oleh :
KH.Abdurrahman
Wahid
Judul diatas diilhami oleh sabda Nabi Muhammad SAW: Sebaik-baik persoalan adalah yang berada ditengah (Khairu Al-Umur Ausathuha). Ia juga mencerminkan Pandangan agama Budha tentang jalan tengah yang dicari dan diwujudkan oleh penganut agama tersebut. Walaupun demikian, judul itu dimaksudkan untuk mengupas sebuah buku karya, tokoh Syiah terkemuka Dr. Musa Al Asyari, Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Darul Ulum Jombang, beberapa waktu lalu, katakanlah sebagai sebuah resensi, yang juga menunjukan kecenderungan umum mengambil jalan tengah yang dimiliki bangsa kita, dan mempengaruhi kehidupan di negeri ini. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sikap mencari jalan tengah ini, akhimya berujung pada sikap mencari jalan sendiri di tengah-tengah tawaran penyelesaian berbagai persoalan yang masuk ke kawasan ini. Namun, sebelum menyimpulkan hal itu, terlebih dahulu penulis ingin melihat buku itu dari kacamata sejarah yang menjadi jalan hidup banyak peradaban dunia. Kalau kita tidak pahami masalah tersebut dari sudut ini, kita akan mudah menggangap jalan tengah sebagai sesuatu yang khas dari bangsa kita, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Bahwa bangsa kita cenderung untuk mencari sesuatu yang independen dari bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mr. Muhammad Yamin, umpamanya menggangap kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat dan menguasai kawasan antara pulau Madagaskar di lautan Hindia/Samudra Indonesia di Barat dan pulau Tahiti di tengah-tengah lautan Pasifik, dengan benderanya yang terkenal Merah Putih. Padahal, angkatan laut kerajaan tersebut hanyalah fatsal (pengikut) belaka dari Angkatan Laut Tiongkok yang menguasai kawasan perairan tersebut selama berabad-abad. Kita tentu tidak senang dengan klaim tersebut karena mengartikan kita lemah, tetapi kenyataan sejarah berbunyi lain, Australia yang menjadi dominion Inggris, secara hukum dan tata negara, memiliki indenpendensi sendiri terlepas dari negara induk. ***** Penulis melihat, bahwa sejarah dunia penuh dengan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Umpamanya saja, seperti di tunjukan oleh Oswald Spengler dalam Die Untergang des Abendlandes"(The Decline Of The West). Buku yang menggambarkan kejayaan peradaban Barat dalam abad ke 20 ini temyata mulai mengalami keruntuhan (Untergang) . Filosof Spanyol Kenamaan, Ortega Y Gasset, justru menunjuk kepada tantangan dari massa rakyat kebanyakan dalam
peradaban moderen terhadap karya-karya dan produk kaum elit, seperti tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal Rebellion of the Masses (Pemberontakan Rakyat Kebanyakan). Kemudian itu semua, disederhanakan oleh Amold Jacob Toynbee dalam karya momentumnya yang terdiri dari 2 jilid, A Study of History. Toynbee mengemukakan sebuah mekanisme sejarah dalam peradaban manusia, yaitu tantangan (challenges) dan jawaban (responses). Kalau tantangan terlalu berat, seperti tantangan alam di kawasan Kutub Utara, seperti yang dialami bangsa Eskimo, maka manusia tidak dapat memberikan jawaban memadai, jadi hanya mampu bertahan hidup saja. Sebaliknya, kalau tantangan harus dapat diatasi dengan kreatifitas, seperti tantangan banjir sungai yang merusak untuk beberapa bulan dan kemudian membawa kemakmuran melalui kesuburan tanah untuk masa selanjutnya, akan melahirkan peradaban tepi sungai yang sangat besar, seperti di tepian Nil, Tigris, Eupharat, Gangga, Huang Ho, Yang Tse Kiang, Musi dan Brantas. Lahimya Pusat-pusat peradaban dunia ditepian sungai-sungai itu, merupakan bukti kesejahteraan yang tidak terbantah. Jan Romein, seorang sejarawan Belanda, menulis bukunya Aera Eropa ia menggambarkan adanya PKU I (Pola Kemanusiaan Umum pertama, Eerste Algemeene menselijk Patron). PKU I itu, menurut karya Romein tersebut memperlihatkan diri dalam tradisionalisme yang dianut oleh peradaban dunia dan kerajaan-kerajaan besar waktu itu, berupa masyarakat agraris, birokrasi kuat dibawah kekuasaan raja yang moralitas yang sama di mana-mana. Dalam abad ke6 sebelum masehi, terjadi krisis moral besar-besaran yang ditandai dengan munculnya nama-nama Lao Tze dan Konghucu, Budha Gautama, Zarathustra di Persia dan Akhnaton di Mesir. Mereka para moralis hebat ini mengembalikan dunia kepada tradisionalismenya, karena memperkuat keseimbangan. Sebaliknya, para filsuf Yunani Kuno, membuat penimpangan pertama terhadap PKU kesatu itu, dengan mengemukakan rasionalitas sebagai ukuran perbuatan manusia yang terbaik. Penyimpangan-penyimpangan PKU I ini di ikuti oleh penyimpanganpenyimpangan lain oleh Eropa seperti kedaulatan hukum Romawi (Lex Romanum) pengorganisasian kinerja, Renaissance (Abad kebangkitan), Abad pencerahan (Aufklarung), Abad Industri dan Abad Ideologi. Dengan adanya penyimpangan itu, Eropa memaksa dunia untuk menemukan PKU II (Tweede Algemeene menselijk Patron), yang belum kita kenal bentuk finalnya. **** Nah, kita menolak Theokrasi (negara agama) dan Sekularisme, dengan mengajukan altematif ketiga berupa Pancasila. Kompromi politik yang dikembangkan kemudian (dan sampai sekarang belum juga berhasil) sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi Agama maupun kekuasaan Anti Agama dalam kehidupan bemegara kita. Karena sekularisme di pandang sebagai penolakan kepada agama -dan bukannya sebagai pemisahan agama dari negara-, maka kita merasakan perlunya mempercayai Pancasila yang menggabungkan Sila pertama (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak
penulis
dianggap
sebagai
penolakan
atas
agama.
Buku yang ditinjau penulis ini, sebenamya adalah upaya dari jenis yang berupaya menyatukan kebenaran Agama dan illmu pengetahuan sekuler (dirumuskan sebagai kemerdekaan berpikir oleh pengarangnya). Jelas yang dimaksudkan adalah sebuah sintensa baru yang terbaik bagi kita dari dua hal yang saling bertentangan. Apakah ini merupakan sesuatu yang berharga, ataukah hanya berujung kepada sebuah masyarakat (dan negara) yang bukan-bukan. Sederhana saja masalahnya, bukan? Yang Umum dan Yang Khusus Oleh Abdurrahman Wahid
Sebagaimana umumnya dosen angkatan lama, Pak Hasan lemah lembut dalam segala hal. Ketika berbicara suaranya tidak begitu keras, nadanya datar. Kalau mengemukakan sesuatu tidak begitu menggebu-gebu, melainkan teratur dan sistematis. Istilah yang digunakan sudah baku; dan dipahami sama oleh para pendengamya, karena jelas yang dimaksud. Tidak banyak memerlukan ilustrasi deskriptif, apalagi yang bersifat gambaran fisik. Prinsip-prinsip dan kategorikategori lebih penting dari deskripsinya sendiri. la terlibat dalam kegiatan 'turun ke bawah' yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tempat ia bekerja sudah tentu dalam kerjasama dengan lembagalembaga lain. Pekerjaannya memperkenalkan teknologi yang sederhana dan lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari rakyat pedesaan, seperti juga banyak 'aktivis pedesaan' yang berkiprah ke bawah. Namun temyata ia melakukan sesuatu yang besar sekali artinya bagi kita semua,tidak seperti yang dilakukan teman-teman sesama aktivis. Yang dilakukannya adalah menyiapkan lahan kemasyarakatan' bagi teknologi yang ditawarkannyaberupa penumbuhan kesadaran dan kebutuhan akan teknologi tersebut. la berarti menciptakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang akan mengembangkan teknologi yang bersangkutan. "Kami mencoba memperkenalkan bio-mass sebagai bahan bakar pengganti kayu, untuk keperluan dapur. Temyata tidak mudah. Karena ibu rumah tangga yang menjadi sasaran kami bukan hanya seorang individu. Ia juga anggota keluarga, dan setelah itu warga masyarakat. Untuk membuat ia menerima bio-mass, keluarga dan masyarakat harus dibuat menerimanya. Dan itu berarti kami harus mendorong munculnya sarana tempat memutuskan sikap, menerima atau menolak gagasan yang ditawarkan. Juga mengelola penggunaan teknologi yang dijajakan itu." Bekerja sama dengan para pamong desa setempat, melalui izin pemerintah daerah, Pak Hasan dan kawan-kawan berhasil merintis sejumlah proyek penumbuhan kebutuhan dan keinginan tersebut. Sebuah 'proyek penawaran teknologi' yang dimulai di sebuah desa, dengan segera berhasil melipatgandakan diri, menjadi kegiatan yang mencakup dua puluh desa lain dalam waktu cepat.
Kiai Madun lain lagi. la 'menawarkan' pesantren asuhannya kepada masyarakat, dengan melakukan sesuatu yang fundamental bagi pesantrennya: menjadikan lembaga pendidikan yang dikelolanya 'pusat pengembangan masyarakat'. Para santri asuhannya berlatih cara-cara mendorong masyarakat, melalui kegiatan ekonomi secara pra-kooperatif (dengan merk'Usaha Bersama') dan kemudian kooperatif. Juga membawa teknologi baru yang sederhana. Memperkenalkan kesadaran bergizi dan KB. Sibuk dengan urusan pelestarian lingkungan.Walhasil menampilkan pesantren sebagai salah satu 'pangkalan' mengubah wajah hidup masyarakat secara total. Menawarkan agama sebagai 'mendorong motivasi keagamaan bagi pembangunan'. Ada pos obat di lingkungan pesantrennya, ada karang kitri dan apotek hidup untuk masyarakat. Ada latihan keterampilan 'yang sudah disempumakan'. Berbagai kegiatan teknis untuk memperbaiki pola kerja dimulai, baik dibidang pertanian atau kerajinan tangan maupun kesehatan masyarakat. Sementara itu Isha adalah seorang intelektual kelas berat.Jidatnya lebar, menerbitkan kesan banyak berfikir. Kalau berbicara senang istilah asing, biar dikira orang pandai. Banyak teori dilontarkannya. Namun iajauh lebih baik dari sejumlah intelektual lain, yang senang hanya dengan retorika melambung dan pikiran ideal, tanpa mampu menerjemahkannya ke dalam kegiatan operasional yang berangkai. Yang menarik adalah komentamya tentang apa yang dilakukan Pak Hasan dan Kiai Madun tadi. Pak Hasan katanya memakai pendekatan 'tawaran' umum dalam pembangunan di pedesaan. Jalumya adalah kebutuhan umum masyarakat sendiri. Kebutuban itu disentuh, melalui kelembagaan biasa seperti arisan, paguyuban RT/RK dan sebagainya. Sebaliknya Kiai Masdun. la mengajak kepada hal sama melalui keunikan, kekhususan pesantren. Pada pendekatan umum itu ada kelebihan penting.Yakni mudahnya replikasi atau penggandaan. Sekali gagasan dasamya diterima baik, seterusnya jalan sudah licin, kata intelektual kota yang spesialisasi urusan pedesaan itu. Namun sering terjadi, justru penerimaan gagasan dasar itu sangat lama berlangsung. Sebaliknya pendekatan khusus untuk menawarkan pembangunan melalui paham, ideologi, agama atau lembaga tertentu yang memiliki keunikan, sangat cepat diterima. Yaitu kalau pimpinannya sudah 'tersentuh'. Tokoh seperti Isha ini temyata mampu memaparkan jalinan dua pendekatan yang komplementer dan sama pentingnya, dengan kelebihan dan kekurangan masingmasing. Banyakkah di antara kita yang memahami keadaan secara terpadu seperti si Isha?
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Pancasila - LGBTDokumen14 halamanMakalah Pancasila - LGBTNovpriandy 1807035939100% (1)
- Makalah LKK Cabang Lebak Yola Anggraeni RevisianDokumen36 halamanMakalah LKK Cabang Lebak Yola Anggraeni RevisianYola AnggraeniBelum ada peringkat
- MAKALAH Hukum & Kebijakan Publik 3Dokumen14 halamanMAKALAH Hukum & Kebijakan Publik 3ahmad jumadilBelum ada peringkat
- PEREMPUAN DAN ANAK Rilui9Dokumen164 halamanPEREMPUAN DAN ANAK Rilui9HendryBelum ada peringkat
- Nilai Etika Dan Estetika DalamDokumen8 halamanNilai Etika Dan Estetika DalamEdi KreboBelum ada peringkat
- Makalah BIOSEL TRANSGENDER - Docx..bakDokumen24 halamanMakalah BIOSEL TRANSGENDER - Docx..bakMaulana YusufBelum ada peringkat
- MakalahDokumen28 halamanMakalahsyarifudinBelum ada peringkat
- Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Sosial Dan BudayaDokumen12 halamanHak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Sosial Dan BudayaEvan75% (4)
- Dampak Globalisasi Dalam Bidang Agama IslamDokumen10 halamanDampak Globalisasi Dalam Bidang Agama IslamHandy100% (1)
- 02 Pidato Sambutan Kihajar DewantaraDokumen10 halaman02 Pidato Sambutan Kihajar Dewantaraferdian nanangBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat HukumDokumen11 halamanMakalah Filsafat Hukumupeck uy117Belum ada peringkat
- Makalah Masyarakat Sipil Mengenai Yayasan KebayaDokumen16 halamanMakalah Masyarakat Sipil Mengenai Yayasan KebayaWAHYU NUGROHOBelum ada peringkat
- Lampiran 3 - Pidato Sambutan KHD UGM 1956Dokumen16 halamanLampiran 3 - Pidato Sambutan KHD UGM 1956chobynetBelum ada peringkat
- Uts PPKNDokumen6 halamanUts PPKNFascal Muhamad AkbariBelum ada peringkat
- Modul 1.1-Pidato Sambutan KHD UGM 1956Dokumen16 halamanModul 1.1-Pidato Sambutan KHD UGM 1956fadlimuiz24Belum ada peringkat
- Sosiologi MasyarakatDokumen112 halamanSosiologi MasyarakatRadya Laksana100% (2)
- MAKALAH Sos PembDokumen33 halamanMAKALAH Sos PembmuhromBelum ada peringkat
- MAKALAH TEORI KLMPK 12Dokumen13 halamanMAKALAH TEORI KLMPK 12Nisa Lutfia HusnaBelum ada peringkat
- MAKALAH Study IslamDokumen15 halamanMAKALAH Study IslamAnnisa RestianiBelum ada peringkat
- Buku Panduan Pembangunan Berbasis RTDokumen42 halamanBuku Panduan Pembangunan Berbasis RTSyahrul Mustofa.S.H.,M.H100% (4)
- Wa0002.Dokumen37 halamanWa0002.Rodytona SinagaBelum ada peringkat
- Pidato Sambutan Ki Hadjar Dewantara-Tugas Eksplorasi KonsepDokumen16 halamanPidato Sambutan Ki Hadjar Dewantara-Tugas Eksplorasi KonsepGiatri Wismar siwiBelum ada peringkat
- Aidit - Angkatan Bersenjata Dan Penyesuaian Kekuasaan Negara Dengan Tugas-Tugas Revolusi (PKI Dan Angkatan Darat - SESKOAD II) (1964)Dokumen23 halamanAidit - Angkatan Bersenjata Dan Penyesuaian Kekuasaan Negara Dengan Tugas-Tugas Revolusi (PKI Dan Angkatan Darat - SESKOAD II) (1964)Heru YuliyantoBelum ada peringkat
- Makalah PKN Harmonisasi Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam DemokrasiDokumen22 halamanMakalah PKN Harmonisasi Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam DemokrasiNicko OfficialBelum ada peringkat
- JURNAL Vol 5 No 2 Maarif InstituteDokumen188 halamanJURNAL Vol 5 No 2 Maarif InstituteMuhammad Abdur RozaqBelum ada peringkat
- Tanggung Jawab Umat Kristen Dalam KehidupanDokumen14 halamanTanggung Jawab Umat Kristen Dalam KehidupanAli WardanaBelum ada peringkat
- MAKALAHDokumen20 halamanMAKALAHFaithly TakapahaBelum ada peringkat
- Lagu Inti Khas Babarit DayeuhkolotDokumen2 halamanLagu Inti Khas Babarit DayeuhkolotIsus Yusrina AzizahBelum ada peringkat
- Nilai Etika Dan Estetika Dalam KebudayaanDokumen2 halamanNilai Etika Dan Estetika Dalam KebudayaanIpink D GreenwolfBelum ada peringkat
- Problematika LGBT Dalam Hak Asasi Manusia Di IndonesiaDokumen30 halamanProblematika LGBT Dalam Hak Asasi Manusia Di IndonesiaSalaisyah Amalia YBelum ada peringkat
- Budaya Duan Lolat (Kabupaten Kepulauan Tanimbar)Dokumen15 halamanBudaya Duan Lolat (Kabupaten Kepulauan Tanimbar)Oka Luturmas50% (2)
- Universalism KewarganegaraanDokumen11 halamanUniversalism KewarganegaraanIntan FatimahBelum ada peringkat
- Jiptummpp GDL Akhmadsaha 45200 2 Babi 1Dokumen11 halamanJiptummpp GDL Akhmadsaha 45200 2 Babi 19G Yulio al buqhoryBelum ada peringkat
- CBR Smi BrataDokumen11 halamanCBR Smi BrataBrata MalauBelum ada peringkat
- Makalah Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk MufakatDokumen15 halamanMakalah Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk Mufakat036FAUZAN SYAIFUL ALIM100% (1)
- Inventarisasi Cerita Rakyat Di Jombang 2Dokumen282 halamanInventarisasi Cerita Rakyat Di Jombang 2Nur AfifahBelum ada peringkat
- BirokratismeDokumen3 halamanBirokratismeAndi Nurmala DewiBelum ada peringkat
- Gladys Vania Gracia - UAS HDKDokumen3 halamanGladys Vania Gracia - UAS HDKgladys vaniaBelum ada peringkat
- UTS Alpadisa Onedhy Pendidikan PancasilaDokumen3 halamanUTS Alpadisa Onedhy Pendidikan PancasilaSherly PuspitasariBelum ada peringkat
- EsaiDokumen3 halamanEsaiNahdhia DeaBelum ada peringkat
- YyyyyyyyyDokumen14 halamanYyyyyyyyypramana ajie PutraBelum ada peringkat
- Makalah Mengenai LGBTDokumen8 halamanMakalah Mengenai LGBTFasya DindaBelum ada peringkat
- Jurnal Kelompok 4 Pancasila 2Dokumen17 halamanJurnal Kelompok 4 Pancasila 2Cindy AmeliaBelum ada peringkat
- 2387 58728 1 PB PDFDokumen28 halaman2387 58728 1 PB PDFArifBudiman BudimanBelum ada peringkat
- Interpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita Dalam Dinamika SosialDokumen19 halamanInterpretasi Hadist Tentang Peranan Wanita Dalam Dinamika SosialSakhwa Afra NadhifaBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Dan HamDokumen22 halamanMakalah Hukum Dan Hamnadia junestiBelum ada peringkat
- Perkembangan Pengelolaan Zakat DiDokumen14 halamanPerkembangan Pengelolaan Zakat DiTe LaBelum ada peringkat
- Bagian EmpatDokumen11 halamanBagian EmpatAris ElvinBelum ada peringkat
- Pendangkalan PolitikDokumen182 halamanPendangkalan Politikelmiracell100% (2)
- Tugas HasanDokumen12 halamanTugas HasanValentino - WeBelum ada peringkat
- Makalah KepancasilaanDokumen13 halamanMakalah KepancasilaanElsa Tri Yolanda PutriBelum ada peringkat
- Makalah AbkebDokumen63 halamanMakalah AbkebTifani hadi tri wahyuniBelum ada peringkat
- Dinasti PolitikDokumen14 halamanDinasti PolitikPb MiiBelum ada peringkat
- Sejarah Singkat LGBT Di IndonesiaDokumen6 halamanSejarah Singkat LGBT Di IndonesiaMukhli ZardyBelum ada peringkat
- Review Dan Resensi Buku Islamku Islam Anda Islam Kita Karya : Abdurrahman WahidDokumen5 halamanReview Dan Resensi Buku Islamku Islam Anda Islam Kita Karya : Abdurrahman WahidFebiansyah ZakariaBelum ada peringkat
- Kelompok 5 - Makalah Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga NegaraDokumen28 halamanKelompok 5 - Makalah Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga NegaraFaranita Lutfia Normasari67% (15)
- Politik Parole: Dari Supersemar Hingga HTI dan Hal KontemporerDari EverandPolitik Parole: Dari Supersemar Hingga HTI dan Hal KontemporerPenilaian: 3 dari 5 bintang3/5 (2)
- Kesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikDari EverandKesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikBelum ada peringkat