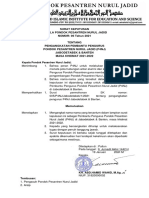Download-Fullpapers-07 KONFLIK WADUK SEPAT Adhi Murti PDF
Download-Fullpapers-07 KONFLIK WADUK SEPAT Adhi Murti PDF
Diunggah oleh
Brenda HerbiansyahJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Download-Fullpapers-07 KONFLIK WADUK SEPAT Adhi Murti PDF
Download-Fullpapers-07 KONFLIK WADUK SEPAT Adhi Murti PDF
Diunggah oleh
Brenda HerbiansyahHak Cipta:
Format Tersedia
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
Konflik Waduk Sepat
Adhi Murti Citra Amalia H
Abstract
This article describes cases of land acquisition in the Sepat Reservoirs reap the conflict between PT Ciputra
Surya Tbk. with the residents of the Perdukuhan Sepat Kulon, Surabaya in 2008-2012. This research is focused
on the background of the conflict which include the history and causes of conflict, as well as the pattern of open
and covert resistance carried out by the local community. This study uses qualitative methods, with observations
and interviews. These cases occur due to differences in the views of the developer and local citizens to the status
of land reservoirs, namely the ‘de jure’ and ‘de facto’. The cause of this conflict include environmental issues,
historical value, as well as social welfare. The form of covert resistance is with the attitude of cynical, vigilant,
suspicious of outsiders, and others. While the form of open resistance by unjukrasa, hearing to the DPRD
Surabaya, tree planting, and so on.
Keywords: land, conflict, development, acquisition
P
embangunan di kota Surabaya secara umum terutama di kawasan Surabaya Barat,
dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Kondisi ini
menyebabkan kawasan Surabaya Barat banyak diincar oleh para penanam modal
atau pengembang untuk mengembangkan daerah tersebut. Para pengembang terutama yang
berasal dari kalangan swasta kemudian mendatangi warga dan mengupayakan pembebasan
lahan untuk mewujudkan proyek-proyek pembangunan mereka, dalam rangka mendulang
keuntungan yang sebesar-besarnya. Sayangnya fenomena pengembangan daerah ini ternyata
masih menuai banyak penentangan yang berasal dari masyarakat, terutama dari warga
setempat. Penolakan ini mayoritas bersumber pada permasalahan hak atas tanah, sehingga
beberapa dari proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang masih menyisakan
banyak kasus yang sampai sekarang tidak terselesaikan.
Menilik dari sejarah pertanahan di Indonesia, kebijakan pertanahan legal formal di
Indonesia dimulai dari pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal
Raffles. Pada tahun 1811 sampai 1816, dikeluarkan kebijakan yang disebut dengan domain
theory, yang menyebutkan bahwa semua tanah di negeri Hindia Belanda adalah milik raja
atau pemerintah. Gubernur Jenderal Raffles mengadakan penarikan pajak bumi yang dikenal
sebagai landrente, yaitu petani wajib membayar pajak sebesar 2/5 dari hasil tanahnya yag
kemudian mempengaruhi terbitnya kebijakan Cultuurstelsel atau tanam paksa pada tahun
1830 oleh Gubernur Jenderal Van Den Bosch (Radjagukguk, 1979: 6 dalam Rohman, 2004:
1). Tahun 1890, kebijakan Cultuurstelsel mulai dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 69
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
yang mengubah kebijakan agrarisnya menjadi lebih berkonsentrasi kepada kehadiran modal
swasta (Radjagukguk, 1979: 6 dalam Rohman, 2004: 2). Kebijakan melalui Undang-Undang
Agraria ini disebut dengan Agrarische Wet yang memberikan legitimasi kepada negara
sebagai penguasa tanah-tanah terlantar yang tidak atau belum tergarap. Kebijakan ini juga
dikenal dengan sebutan woeste gronden, yaitu membuat negara memiliki kewenangan untuk
melepaskan hak penguasaannya atas tanah terlantar, kemudian memberikannya pada
penguasa perkebunan dalam jangka waktu 75 tahun. Selain itu Undang-Undang Agrarische
Wet ini juga menerapkan azas domain verklaring, yaitu suatu prinsip yang menyatakan
bahwa semua tanah yang tidak terbukti ada pemiliknya atau tanah terlantar adalah domain
atau milik negara (Arafat dan Puryadi, 2002: 58).
Kebijakan pertanahan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda tersebut
menjadi landasan bagi Undang-Undang Pokok Agraria yang dikenal sebagai UU No. 5/1960
(Fauzi, 1997: 87). Undang-Undang tersebut berisi peraturan yang juga berazazkan domain
verklaring menurut Agrarische Wet, yaitu negara berhak berkuasa atas tanah yang tidak
terbukti ada pemiliknya sehingga tanah-tanah tersebut dapat diakui menjadi milik pemerintah
(Fauzi, 1997: 87). Peraturan ini rupanya menjadi akar permasalahan dari konflik-konflik hak
atas tanah yang terjadi di kemudian hari. Permasalahan yang seringkali muncul adalah
konflik hak atas tanah antara rakyat melawan pemilik modal dan negara, atau pemilik modal
yang didukung oleh negara (Fauzi, 1997: 87). Dalam kasus ini yang berkonflik bukanlah
rakyat dengan rakyat, melainkan rakyat versus pemodal besar atau rakyat versus pemerintah,
termasuk BUMN di dalamnya (Kinasih, dkk., 2009: 6).
Salah satu contoh kasus seperti yang dikemukakan di atas adalah konflik yang terjadi
di wilayah Surabaya Barat, yaitu konflik di Waduk Sepat Kelurahan Lidah Kulon Surabaya.
Kasus ini adalah konflik antara pengembang PT. Ciputra Surya Tbk. atau yang biasa disebut
dengan Citraland, dengan masyarakat setempat yang tinggal di daerah sekitar waduk, yaitu
warga Perdukuhan Sepat RW III dan RW V Kelurahan Lidah Kulon Surabaya. Masyarakat
setempat mengklaim bahwa waduk seluas 6,675 hektar yang ada di daerah itu adalah milik
mereka dan tidak bisa diganggu gugat oleh pengembang Citraland. Namun menurut status
tanah yang tercatat di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Surabaya, waduk tersebut telah sah
menjadi milik pengembang Citraland dalam GS no. 109/S/1991 dalam registrasi no. 0335754.
Status tanah ini diperoleh dari proses tukar guling antara Pemkot Surabaya dengan
pengembang Citraland. Pemkot Surabaya telah meruislag lahan di Waduk Sepat Kelurahan
Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri yang dianggap sebagai milik negara dengan lahan di
Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal yang saat ini dipergunakan sebagai Surabaya Sport
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 70
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
Center (SSC) atau Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) (http://surabaya.detik.com/read/2011/
07/28/172123/1691710/466/warga-siap-pertahankan-sejarah-kampung-sepat-lidah-kulon di-
akses pada 12 Maret 2012).
Dari permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeksripsikan
latar belakang konflik hak atas tanah yang terjadi di Waduk Sepat Lidah Kulon Surabaya
antara pengembang Citraland dengan masyarakat setempat, meliputi sejarah dan penyebab
konflik. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pola perlawanan yang
digunakan masyarakat setempat terutama warga Perdukuhan Sepat RW III dan RW V
Kelurahan Lidah Kulon Surabaya terhadap pengembang Citraland, baik terselubung maupun
terbuka dalam konflik hak atas waduk di Waduk Sepat Lidah Kulon Surabaya pada tahun
2008 sampai 2012.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara dengan para infoman yang
terlibat di dalam permasalahan yang akan diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan
data sekunder dengan cara mengutip, mencatat arsip-arsip, berita dari koran dan internet,
dokumen resmi, atau hasil-hasil penelitian yang sudah ada terlebih dahulu. Dalam metode ini
hal yang terpenting adalah menentukan informan kunci (key informan), oleh karena itu
sampel yang digunakan bukanlah sampel statistik, namun lebih bersifat selektif yaitu dengan
cara ditentukan atau purposive sampling (Rohman, 2004: 43-44). Pemilihan informan dalam
metode wawancara ini adalah orang-orang yang mengetahui secara persis permasalahan yang
terjadi dalam penelitian, misalnya perangkat RT, RW, organisasi LPBP (Laskar Pembela
Bumi Pertiwi), dan lain sebagainya.
Latar Belakang Konflik
Status lahan Waduk Sepat saat ini sudah menjadi milik pengembang Citraland sesuai dengan
GS no. 109/S/1991 yang tercatat dalam registrasi no. 0335754 di Badan Pertanahan Surabaya
(BPN). Bukti kepemilikan lahan ini juga didukung oleh Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 39 tahun 2008 dan Keputusan Walikota Surabaya
Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 tentang pemindahtanganan dengan cara tukar-menukar
terhadap aset Pemkot yang tertulis berupa tanah eks ganjaran atau bondo deso di Kelurahan
Lidah Kulon (Waduk Sepat) dengan tanah milik pengembang Citraland yang terletak di
kawasan Benowo, Kecamatan Pakal yang kini telah menjadi Gelora Bung Tomo (GBT).
Status lahan ini berasal dari proses tukar guling yang terkait dengan kepentingan Pemerintah
Kota Surabaya (Pemkot) atas proyek pembangunan Surabaya Sport Centre (SSC) atau yang
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 71
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
disebut juga dengan Gelora Bung Tomo (GBT). Pemkot membutuhkan lahan yang berada di
kawasan Benowo, Kecamatan Pakal, yang berdiri atas kepemilikan pengembang Citraland
untuk kepentingan pembangunan stadion tersebut. Oleh karena itu Pemkot mengganti lahan
milik pengembang Citraland dengan cara meruislag-nya dengan lahan yang berada di empat
lokasi lain, salah satunya yaitu lahan di Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri,
berupa Waduk Sepat yang kini dipermasalahkan oleh warga setempat. (http://surabaya.detik.
com/read/2011/07/28/172123/1691710/466/warga-siap-pertahankan-sejarah-kampung-sepat-
lidah-kulon diakses pada 12 Maret 2012).
Status kepemilikan waduk oleh Pemkot sebetulnya tidak lepas dari pergantian sistem
Kepala Desa menjadi Kelurahan sejak masa kemerdekaan Indonesia. Sistem Desa yang
berganti dengan sistem Kelurahan menjadi lebih administratif sehingga tanah-tanah yang
tidak ada klaim pemiliknya seperti Waduk Sepat pun diakui sebagai milik negara. Status
lahan ini menjadi landasan bagi Pemkot untuk menukarnya dengan lahan milik pengembang,
sehingga secara de jure status Waduk Sepat saat ini memang telah menjadi milik PT.
Citraland. Status lahan ini masih dipertanyakan oleh warga Perdukuhan Sepat sebab dari dulu
Waduk Sepat tidak pernah beralih fungsi menjadi tanah eks ganjaran atau tanah pekarangan
sebagaimana yang tertulis dalam bukti-bukti kepemilikan Pemkot. Selain itu juga terdapat
kejanggalan dalam bukti-bukti tersebut, misalnya dalam sertifikat Hak Guna Bangunan
(HGB) yang dimiliki Citraland waduk tertulis sebagai tanah pekarangan dan dalam SK
Walikota Nomor 188.45/366/436.1.2/2008 waduk tertulis sebagai bekas waduk. Masyarakat
setempat khususnya warga Perdukuhan Sepat RW III dan RW V lebih melihat penguasaan
waduk secara de facto, sebab berdasarkan sejarah waduk telah ada sejak berpuluh-puluh
tahun lamanya dan dibuat sendiri dengan swadaya warga. Waduk disebut-sebut bukanlah
peninggalan pemerintah jajahan Hindia Belanda, dan hasil pengelolaan waduk juga tidak
pernah dipergunakan untuk menggaji perangkat desa selayaknya fungsi tanah ganjaran pada
umumnya.
Kasus waduk ini sebetulnya sudah ada sejak tahun 2004, ketika muncul peraturan
perundang-undangan baru yang memutuskan bahwa seluruh aset milik kampung akan
berubah status kepemilikan menjadi milik Pemkot. Sejak itu warga mulai mengantisipasin ya
dengan membuat panitia khusus untuk mengamankan aset-aset kampung, termasuk Waduk
Sepat. Saat itu sudah ada kekhawatiran bahwa waduk disebut merupakan salah satu aset yang
akan jatuh ke tangan pemerintah, namun isu tersebut tidak berkelanjutan. Pada tahun 2009
warga baru mengetahui untuk pertama kalinya kalau waduk telah beralih menjadi milik
pengembang Citraland melalui pihak Kelurahan Lidah Kulon. Di sini warga merasa kecewa
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 72
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
sebab proses tukar guling dilaksanakan tanpa melibatkan warga setempat baik dari perangkat
RT/RW dan tidak ada sosialisasi apa pun dari pihak Kelurahan, Kecamatan, Pemkot, maupun
pengembang yang membahas tentang ruislag waduk. Warga menyesalkan tidak ada inisiatif
dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut untuk mengajak warga berembug mengenai
status lahan dan warga sudah harus menerima kenyataan bahwa waduk sudah berganti
kepemilikan menjadi milik pengembang Citraland. Namun di sini belum ada tindakan
perlawanan dari warga sampai pemagaran pada tahun 2010 sebab mayoritas warga masih
takut dan belum terlalu mengerti tentang permasalahan waduk.
Kasus ini mulai mencuat ke permukaan dan mendapat perhatian dari masyarakat luas
ketika terjadi pembagian dana CSR 3 miliar oleh pengembang Citraland melalui panitia 16.
Panitia 16 adalah sebagian orang dari warga Perdukuhan Sepat sendiri yang mengklaim
mewakili warga untuk mengambil dana tersebut dan membentuk panitia yang disetujui oleh
Lurah Lidah Kulon dan Camat Lakarsantri, berjumlah sekitar 16 orang. Warga Perdukuhan
Sepat RW III dan RW V tidak mengakui panitia sebab proses pembentukannya terasa sangat
dipaksakan, tidak transparan, tidak melalui rapat Perdukuhan dan tidak melibatkan perangkat
RT serta RW. Pembagian ini menuai konflik sebab warga sudah curiga jika dana CSR itu ada
tendensinya dengan pelepasan waduk. Pernyataan dari pihak panitia 16, Kelurahan serta
Kecamatan membantah tuduhan warga bahwa pembagian dana CSR tidak ada hubungannya
dengan waduk. Namun pertemuan dengan pihak pengembang Citraland yang difasilitasi oleh
Komisi A DPRD Surabaya menjelaskan bahwa dana itu memang bukan dana CSR,
melainkan dana kompensasi waduk. Dengan demikian persoalan pembebasan lahan di
Waduk Sepat Lidah Kulon sebenarnya sudah beres apabila dilihat dari segi sertifikasi tanah
dan dana kompensasi 3 miliar yang telah dibagikan oleh pengembang kepada warga. Waduk
secara resmi telah menjadi milik pengembang Citraland, namun warga masih tidak
menyetujui pelepasan waduk itu karena merasa dibohongi oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.
Penyebab Konflik
Konflik waduk terus memanas setelah pengembang melakukan pemagaran kembali pada
pertengahan Juni 2011. Warga mulai mengadakan perlawanan secara frontal terhadap pekerja
Citraland secara terus-menerus. Sesungguhnya perwakilan dari pengembang Citraland telah
menuturkan bahwa waduk tidak akan digusur seluruhnya, dari 6,675 ha/m³, 6000 m³ tetap
menjadi telaga dan sisanya baru akan diurug sebagai perluasan perumahan Citraland.
Meskipun demikian, warga tetap pada pendiriannya tidak mau melepas waduk dan menuntut
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 73
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
pengembalian pengelolaan waduk kepada masyarakat setempat karena berbagai alasan
sebagai berikut.
Pertama, yaitu masalah lingkungan. Keadaan topografi waduk terlihat lebih tinggi
kurang lebih 3 m³ dari perkampungan Perdukuhan Sepat, yang kini ditempati oleh penduduk
RW 3 dan RW 5 Lidah Kulon Surabaya. Apabila penggusuran waduk jadi dilaksanakan,
kekhawatiran akan banjir yang terjadi saat musim penghujan tiba bisa menjadi kenyataan.
Banjir besar tidak dapat terhindarkan, bukan hanya pada warga Perdukuhan Sepat saja namun
juga bisa merembet ke pemukiman warga lainnya yang letaknya lebih rendah dari waduk.
Meskipun pengembang telah menjelaskan bahwa waduk tidak akan diurug seluruhnya, warga
tetap khawatir akan banjir sebab ketika waduk belum diurug saja banjir kerap kali datang
terutama saat musim penghujan. Selain itu warga juga merasa terganggu dengan bau
menyengat yang berasal dari saluran pembuangan Citraland di Waduk Sepat. Pada tahun
2003 memang terdapat perjanjian sewa-menyewa waduk antara pengembang dan warga yang
berakhir di tahun 2008. Waduk digunakan pengembang sebagai tempat penampungan air dan
saluran pembuangan dari perumahan Citraland, yang masih terus berjalan sampai sekarang
meskipun pengembang tidak lagi membayar kepada warga.
Kedua, yaitu masalah ideologi dan nilai sejarah. Waduk Sepat telah dianggap sebagai
bagian dari sejarah kampung yang tidak boleh dilupakan dan merupakan warisan berharga
yang akan diturunkan pada anak cucu mereka nantinya. Waduk selama bertahun-tahun telah
menjadi sarana yang menjembatani hubungan interaksi antar warga, misalnya seperti sebagai
wadah berkumpul, sarana hiburan, tempat bermain anak-anak, memancing, lahan untuk
berkebun, dan lain sebagainya. Warga merasa lahir dan tumbuh bersama Waduk Sepat, rasa
memiliki terhadap waduk telah merasuk ke dalam setiap invididu yang bertempat tinggal di
Perdukuhan Sepat sehingga tidak heran jika warga tidak rela kalau waduk jatuh ke tangan
pengembang. Di sekitar waduk juga masih terdapat banyak tempat yang dikeramatkan seperti
pohon jatilondo, makam Mbah Cokro dan Mbah Dewi, sumur Kali, sumur Windu, sumur
Kola, sumur Kesambi, dan telaga. Selain itu terdapat kekhawatiran apabila kesenian
masyarakat setempat seperti tandaan pada sedekah bumi dan sedekah waduk akan hilang
dengan adanya pelepasan waduk.
Ketiga, yaitu masalah kesejahteraan sosial. Apabila waduk jatuh ke tangan
pengembang maka individu-invidu yang menggantungkan hidupnya pada tanah di sekitar
waduk akan kehilangan mata pencaharian mereka, terutama para petani yang menggarap
lahannya di sekitar waduk. Selain itu ketika banjir datang, kondisi itu tak pelak juga bisa
mengganggu kestabilan kegiatan perekonomian warga lainnya yang tidak bekerja sebagai
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 74
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
petani. Misalnya bagi mereka yang memiliki profesi lain, seperti para pedagang, karyawan,
atau yang lainnya. Banjir dapat mengakibatkan kemacetan, lumpuhnya transportasi, dan lain
sebagainya. Dampak lingkungan akibat ekspansi pengembang terhadap waduk ditakutkan
akan membawa efek domino yang berujung pada masalah-masalah sosial yang lain.
Pola Perlawanan Terselubung
Perlawanan yang dimaksudkan di sini adalah perlawanan yang dilakukan oleh warga
terhadap pengembang serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya seperti panitia
pembagian dana 3 miliar atau Pemkot secara tertutup. Merujuk pada pemahaman Scott akan
perlawanan terselubung, disebutkan bahwa perlawanan ini hanya sebatas pada penolakan-
penolakan yang belum terorganisir secara rapi (Scott, 1993: 271 dalam Rohman, 2004: 6).
Bentuk-bentuk perlawanannya nyaris tak terlihat di permukaan, seperti ungkapan-ungkapan
kekecewaan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat
kecil, tidak mau menerima dana 3 miliar yang dikucurkan oleh pengembang Citraland,
bersikap sinis baik kepada panitia pembagian dana yang masih terhitung sebagai warga
sendiri, orang-orang yang dianggap sebagai pekerja Citraland, kepolisian, aparat pemerintah,
serta bersikap waspada kepada orang-orang luar yang tidak dikenal yang dicurigai
berhubungan dengan proyek pengalihfungsian waduk, dan lain sebagainya.
Pola Perlawanan Terbuka
Berbeda dengan perlawanan terselubung, perlawanan ini dilakukan secara terbuka dan
terang-terangan yang dilakukan oleh individu-individu yang kemudian berkelompok dan
membentuk sebuah pergerakan yang disebut dengan aksi kolektif. Pengertian aksi kolektif
yang dimaksudkan di sini adalah usaha dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan
jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut bersama meskipun
berhadapan dengan penentangan dan konflik. Aksi kolektif lahir dari rasa ketidakpuasan,
penyangkalan, yang terampas secara bersama-sama dialami oleh sejumlah besar orang yang
merasakan situasi yang sama. Individu-individu tersebut memiliki kesadaran yang sama
bahwa mereka telah tersingkirkan pada tingkatan tertentu sehingga mendorong mereka untuk
bergabung dan mengidentifikasi pihak musuk yang dianggap bertanggung jawab atas
penderitaan mereka (Singh, 2010: 26-27).
Aksi-aksi semacam inilah yang terjadi pada warga Perdukuhan Sepat Lidah Kulon
Surabaya. Mereka membentuk gerakan sosial yang awalnya tidak terstruktur, namun melalui
serangkaian proses gerakan ini kemudian berkembang hingga memiliki wadah tersendiri
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 75
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
dalam sebuah organisasi yang khusus untuk menangani konflik waduk yang dinamakan
dengan Laskar Pembela Bumi Pertiwi (LPBP). Bentuk-bentuk perlawanan terbuka dari warga
sendiri lebih beragam, mulai dari aksi-aksi perundingan seperti mengadakan pertemuan
dengan panitia pembagian dana 3 miliar, Kelurahan, Kecamatan untuk mencegah pembagian
dana 3 miliar, menghadiri hearing yang diadakan oleh Komisi A dan Komisi B DPRD
Surabaya, hingga aksi-aksi frontal seperti menggelar aksi demonstrasi/unjuk rasa di berbagai
tempat seperti di Kelurahan, Grahadi dan Balai Kota Surabaya, perlawanan fisik ketika
terjadi pemagaran waduk, aksi damai dengan menyebarkan pamflet di traffic light pintu
masuk Citraland, mengadakan acara tumpengan dan panen bersama dengan Solidaritas
Darurat Nasional, sampai membuat Waduk Sepat sebagai obyek pariwisata.
Analisis Konflik Waduk Sepat
Dalam kasus Waduk Sepat ini terdapat dua jenis keanekaragaman hukum, yaitu hukum
negara dan hukum adat yang digunakan oleh masyarakat setempat. Hukum negara disinyalir
menjadi penyebab utama konflik, menilik pada status lahan waduk sesuai dengan UU No.
5/1960 yang menerapkan azas domain verklaring dari Undang-Undang Agrarische Wet,
sehingga semua tanah yang tidak terbukti ada pemiliknya atau tanah terlantar menjadi milik
negara. Status lahan inilah yang digunakan oleh pihak Pemkot untuk ditukar-guling dengan
lahan di Kecamatan Pakal milik PT. Citraland, yang kemudian dipermasalahkan oleh
masyarakat setempat. Sementara masyarakat Perdukuhan Sepat sendiri tetap kukuh pada
pendirian mereka bahwa waduk adalah milik warga, dengan dasar sejarah waduk yang dibuat
atas swadaya warga di masa lampau.
Permasalahan ini dapat ditinjau melalui konsep pluralisme hukum yang dikemukakan
oleh Benda-Beckman, yang mengatakan bahwa di lapangan sosial tertentu terdapat
keanekaragaman hukum, dan yang paling penting adalah melihat variasi di dalam
keanekaragaman hukum itu dan bagaimana sistem-sistem hukum itu saling berinteraksi
(mempengaruhi) satu sama lain (Benda-Beckmann, 1990: 2 dalam Irianto, 2000: 69). Di sini
masyarakat setempat yang menentang pelepasan waduk menginginkan agar aspirasi mereka
juga diperhatikan baik dari segi kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, hilangnya
nilai-nilai sejarah serta masalah kesejahteraan sosial di masa mendatang. Hal ini dipengaruhi
pula oleh kondisi masyarakat yang masih tradisional, yang masih menganggap penting nilai-
nilai sejarah yang terdapat di sekitar waduk. Waduk Sepat merupakan salah satu tempat yang
dianggap keramat oleh warga, berkaitan dengan sejarah mengenai sumber-sumber air di Desa
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 76
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
Lidah Kulon. Selain itu pelepasan waduk juga dikhawatirkan akan menghilangkan tradisi-
tradisi asli masyarakat Perdukuhan Sepat, seperti sedekah bumi dan sedekah waduk.
Variasi-variasi semacam inilah yang hendaknya turut pula diperhatikan oleh masing-
masing pihak yang berkonflik, dalam memandang permasalahan tersebut dari segi hukum.
Pada kasus ini peneliti melihat bahwa pandangan pluralisme hukum menjadi sangat penting
dalam penyelesaian konflik, karena tergantung dari pranata hukum yang dipilih oleh masing-
masing pihak. Dalam situasi semacam ini, keadilan akan sulit dicapai apabila hanya melalui
sistem hukum nasional saja. Pihak-pihak yang bersangkutan hendaknya juga melihat variasi
atau keanekaragaman pandangan mengenai hukum yang terdapat di sekitar mereka, misalnya
seperti hukum adat yang dianut oleh masyarakat setempat. Apabila penyelesaian konflik tetap
menggunakan ketentuan hukum dari kelompok yang dominan, maka dalam pengambilan
keputusan keadilan hanya sampai pada keadilan hukum semata dan bukan keadilan nasional
(Nader and Todd, 1978: 37 dalam Irianto, 2000: 79-80)
Kesimpulan
Dari hasil temuan dan analisis dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan bahwa latar belakang konflik terjadi karena adanya perbedaan pandangan dari
pihak pengembang Citraland dan warga setempat terhadap status lahan waduk. Pengembang
melihat penguasaan lahan secara de jure melalui surat kepemilikan legal yang dikeluarkan
oleh pemerintah, yaitu sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) yang mereka miliki, sedangkan
masyarakat sekitar memandang penguasaan lahan secara de facto, berdasarkan nilai
sejarahnya bahwa waduk dibuat atas swadaya warga di masa lampau. Sementara penyebab
dari konflik ini sendiri dibagi menjadi tiga lingkup besar, yakni masalah lingkungan, ideologi
dan nilai sejarah, serta kesejahteraan sosial. Kemudian pla perlawanan yang digunakan
masyarakat setempat terhadap pengembang Citraland adalah perlawanan terselubung dan
terbuka. Bentuk dari perlawanan terselubung adalah dengan sikap sinis, waspada, curiga
terhadap orang luar, dan lain-lain. Sedangkan bentuk perlawanan terbuka yaitu dengan
unjukrasa, hearing ke DPRD Surabaya, penanaman pohon, dan lain sebagainya.
Daftar Pustaka
Fauzi, Noer (1997), Petani dan Penguasa. Yogyakarta: KPA, Insist dan Pustaka Pelajar.
Irianto, Sulistyowati (2000), Pluralisme Hukum dan Masyarakat Saat Krisis dalam Hukum
dan Kemajemukan Budaya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Irianto, Sulistyowati (2001), “Kesejahteraan Sosial dalam Sudut Pandang Pluralisme Hukum
(Suatu Tema Non-Sengketa dalam Perkembangan Terakhir Antropologi Hukum
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 77
Adhi Murti Citra Amalia H., “Konflik Waduk Sepat”, hal.69-78.
Tahun 1980-1990-an),” dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia.
Kinasih, dkk. (2009), “Model Resolusi Konflik dan Pembentukan Negara: Studi Pemahaman
Budaya Hukum Secara Holistik di Masyarakat Rawan Konflik.” Laporan Penelitian
Universitas Airlangga.
Puryadi & Al-Arafat (2002), Perebutan Kuasa Tanah. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
Rohman, Fatkhur (2004), “Konflik di Gunung Pegat (Studi Kasus tentang Konflik
Penguasaan Hak Atas Tanah antara Penambang Batu dan PT. Semen Gresik di
Gunung Pegat Kabupaten Lamongan Tahun 1994-1998).” Tesis Surabaya: Universitas
Airlangga.
Singh, Rajendra (2010), Gerakan Sosial Baru. Surabaya: Resist Book & Komisi HAM-
LPPM Universitas Airlangga.
Website:
http://surabaya.detik.com/read/2011/07/28/172123/1691710/466/warga-siap-pertahankan-
sejarah-kampung-sepat-lidah-kulon diakses pada 12 Maret 2012.
AntroUnairDotNet, Vol.1/No.1/Juli-Desember 2112 hal. 78
Anda mungkin juga menyukai
- Contoh Laporan Kegiatan PKL (Log Book)Dokumen1 halamanContoh Laporan Kegiatan PKL (Log Book)Abdul basid100% (1)
- Tugas Paper Kerusuhan Di Pulau Rempang - Farid Dwiputra 20232111137Dokumen7 halamanTugas Paper Kerusuhan Di Pulau Rempang - Farid Dwiputra 20232111137noura play and learnBelum ada peringkat
- 4291-Article Text-12066-1-10-20201030Dokumen19 halaman4291-Article Text-12066-1-10-20201030dermawanheru32Belum ada peringkat
- Esai Wacana PenggusuranDokumen6 halamanEsai Wacana PenggusuranLefri MikhaelBelum ada peringkat
- Bab 1 Peran Kantor SengketaDokumen8 halamanBab 1 Peran Kantor Sengketafaisal rahmanBelum ada peringkat
- Analisis Konflik Agrariadi Urutsewu KebumenDokumen7 halamanAnalisis Konflik Agrariadi Urutsewu KebumenagusBelum ada peringkat
- Modul 3Dokumen28 halamanModul 3BPN TulungagungBelum ada peringkat
- Penyelesaaian Sengketa Tanah Antara PT Sentul City TBKDokumen21 halamanPenyelesaaian Sengketa Tanah Antara PT Sentul City TBKAuliaputri Kesuma TanjungBelum ada peringkat
- JURNAL SkripsiDokumen20 halamanJURNAL SkripsiArmadeva SidhartaBelum ada peringkat
- Makalah AgrariaDokumen28 halamanMakalah AgrariaKeysya Quthrotun NadaBelum ada peringkat
- UAS Pertanahan & L.PerdesaanDokumen6 halamanUAS Pertanahan & L.PerdesaanCundradus Jackie DodokBelum ada peringkat
- Opini HukumDokumen4 halamanOpini HukumAditya pratama PutraBelum ada peringkat
- EssayDokumen4 halamanEssayEva MutiarasariBelum ada peringkat
- Problematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan H.Rais.A.Rahman (Sui Jawi)Dokumen24 halamanProblematika Pembebasan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Jalan H.Rais.A.Rahman (Sui Jawi)najlasffnhBelum ada peringkat
- Konflik Waduk SepatDokumen5 halamanKonflik Waduk SepatEllen Deviana ArisadiBelum ada peringkat
- Tugas Sengketa TanahDokumen11 halamanTugas Sengketa TanahToFoLogicBelum ada peringkat
- Proposal Tesis Pa YunusDokumen23 halamanProposal Tesis Pa YunusLPN Gunung Sindur JabarBelum ada peringkat
- Masalah Pertanahan Dari Masa Ke MasaDokumen20 halamanMasalah Pertanahan Dari Masa Ke MasadrainwileBelum ada peringkat
- SkripsiDokumen157 halamanSkripsinayzidanBelum ada peringkat
- Adat - Penggunaan Sistem Gandok Dalam Pertanahan Masyarakat BantulDokumen15 halamanAdat - Penggunaan Sistem Gandok Dalam Pertanahan Masyarakat BantuldismasBelum ada peringkat
- Makalah PertanahanDokumen12 halamanMakalah PertanahanFaris AdiantoBelum ada peringkat
- Kajian Kadaster 3 Dimensi Untuk Kepemilikan Strata Title Indonesia PDFDokumen23 halamanKajian Kadaster 3 Dimensi Untuk Kepemilikan Strata Title Indonesia PDFtidakmenyembunyikanilmu0% (1)
- Tugas PERTANAHAN UirDokumen6 halamanTugas PERTANAHAN UirAdhie SuvoBelum ada peringkat
- Aditya Handoyo Putra - H44190062 - Makalah 4Dokumen9 halamanAditya Handoyo Putra - H44190062 - Makalah 4Aditya HandoyoBelum ada peringkat
- PermukimanDokumen5 halamanPermukimanIDRUS KAMALBelum ada peringkat
- Pembahasan Hukum AdatDokumen13 halamanPembahasan Hukum Adatdelironinsp9Belum ada peringkat
- Konflik Perkebunan KalibakarDokumen17 halamanKonflik Perkebunan KalibakarGrace LeksanaBelum ada peringkat
- 2021.11.02 - Permohonan Pencabutan Pergub 207 (KRMP) - FinalDokumen13 halaman2021.11.02 - Permohonan Pencabutan Pergub 207 (KRMP) - FinalAdi SutiyosoBelum ada peringkat
- Naskah Publikasi NadiraDokumen26 halamanNaskah Publikasi NadiraNadira AisyahBelum ada peringkat
- Essay LKK YakusaDokumen10 halamanEssay LKK YakusaNurul Maghfiroh El-RasheedBelum ada peringkat
- Rizal Hilman RDokumen10 halamanRizal Hilman RRizal Hilman RakhmatillahBelum ada peringkat
- Karya Tulis Ilmiah Filsafat HukumDokumen11 halamanKarya Tulis Ilmiah Filsafat HukumMuhammad IkhsanBelum ada peringkat
- Antopologi Nanda Ayu Sekarwangi Putri CempakaDokumen7 halamanAntopologi Nanda Ayu Sekarwangi Putri CempakacacaelfinaBelum ada peringkat
- Dari Tanah Sultan Menuju Tanah RakyatDokumen190 halamanDari Tanah Sultan Menuju Tanah RakyatDeni PradanaBelum ada peringkat
- Proposal Riki 9Dokumen28 halamanProposal Riki 9Lya AgustiaBelum ada peringkat
- Proposal Faisal FH Umi Jangan Dihapus IniDokumen46 halamanProposal Faisal FH Umi Jangan Dihapus IniGamer SejatiBelum ada peringkat
- Alih Fungsi LahanDokumen23 halamanAlih Fungsi LahanAndri Apriyanto IX100% (1)
- 2 SPDokumen9 halaman2 SPKristiansand TEFCBelum ada peringkat
- 213 669 1 PBDokumen7 halaman213 669 1 PBjarhyungantengBelum ada peringkat
- ADPU4335 Administrasi Pertanahan PDFDokumen5 halamanADPU4335 Administrasi Pertanahan PDFDwi Nofita SariBelum ada peringkat
- ProposalDokumen18 halamanProposalIrma RamaBelum ada peringkat
- Hukum AgrariaDokumen9 halamanHukum AgrariaIkhtiar Nur SyahidBelum ada peringkat
- Lauhil Mahfuzd - 084 - Hukum AgrariaDokumen2 halamanLauhil Mahfuzd - 084 - Hukum AgrariaBang KacauBelum ada peringkat
- Hukum Adat Dalam Hukum Tanah NasionalDokumen23 halamanHukum Adat Dalam Hukum Tanah NasionalmallaboraBelum ada peringkat
- Proposal Sponsorship Seminar Nasional Pertanahan - Tanah TerlantarDokumen9 halamanProposal Sponsorship Seminar Nasional Pertanahan - Tanah Terlantarbank_diaz100% (1)
- 07 8111422550 Nailah Hana SausanDokumen9 halaman07 8111422550 Nailah Hana SausanNailah Hana SausanBelum ada peringkat
- Artikel Ilmiah Nikmatusns Tugas UTS Hukum AgrariaDokumen7 halamanArtikel Ilmiah Nikmatusns Tugas UTS Hukum AgrariaDy DyBelum ada peringkat
- Assignment ELS 1Dokumen5 halamanAssignment ELS 1Livia VanessaBelum ada peringkat
- Jurnal Pasir Besi Kulon ProgoDokumen9 halamanJurnal Pasir Besi Kulon ProgoGilang Rizki RamadhanBelum ada peringkat
- 972-Article Text-1659-1-10-20200203Dokumen16 halaman972-Article Text-1659-1-10-20200203Annisa KarimahBelum ada peringkat
- Sapuan Dani, Sh.m.hum Fungsi Sosial Terhadap Pemanfaatan Hak Atas TanahDokumen32 halamanSapuan Dani, Sh.m.hum Fungsi Sosial Terhadap Pemanfaatan Hak Atas TanahSapuan DaniBelum ada peringkat
- Jurnal Tugas P Wilayah-DikonversiDokumen8 halamanJurnal Tugas P Wilayah-DikonversiMRizky FaisalBelum ada peringkat
- Tugas Terstruktur Administras PertanahanDokumen10 halamanTugas Terstruktur Administras PertanahanF5-12- Jonathan Miguel TimbowoBelum ada peringkat
- 6310 16566 1 PBDokumen11 halaman6310 16566 1 PBChik CharlieeNaBelum ada peringkat
- Sengketa Tanah PartikelirDokumen14 halamanSengketa Tanah PartikelirDoni FirdiansyahBelum ada peringkat
- Tugas HukumDokumen4 halamanTugas Hukumwidyah sastriBelum ada peringkat
- Proposal Metode Penelitian Hukum (Azzyra)Dokumen15 halamanProposal Metode Penelitian Hukum (Azzyra)Syauqi ThifalBelum ada peringkat
- Final Catahu & Proyeksi JATAM 2021Dokumen25 halamanFinal Catahu & Proyeksi JATAM 2021Abdul basidBelum ada peringkat
- Dear ParamadinaDokumen2 halamanDear ParamadinaAbdul basidBelum ada peringkat
- Beasiswa Arab Eselon 1Dokumen12 halamanBeasiswa Arab Eselon 1Abdul basidBelum ada peringkat
- SK P4NJ JabodetabekDokumen3 halamanSK P4NJ JabodetabekAbdul basidBelum ada peringkat
- 02 SelamatDokumen1 halaman02 SelamatAbdul basidBelum ada peringkat
- Bab 1-3-5Dokumen31 halamanBab 1-3-5Abdul basidBelum ada peringkat
- Dalam CDMA Setiap Pengguna Menggunakan Frekuensi Yang Sama Dalam Waktu Bersamaan Tetapi Menggunakan Sandi Unik Yang Saling OrtogonalDokumen1 halamanDalam CDMA Setiap Pengguna Menggunakan Frekuensi Yang Sama Dalam Waktu Bersamaan Tetapi Menggunakan Sandi Unik Yang Saling OrtogonalAbdul basidBelum ada peringkat
- Biografi Penulis. FixDokumen1 halamanBiografi Penulis. FixAbdul basidBelum ada peringkat
- Template PKL 2018 UNUJADokumen16 halamanTemplate PKL 2018 UNUJAAbdul basidBelum ada peringkat