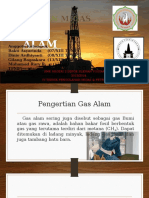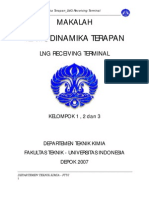MONETISASI GAS DI INDONESIA Dan SIAPKAH MALUKU Menuju MONETISASI GAS
MONETISASI GAS DI INDONESIA Dan SIAPKAH MALUKU Menuju MONETISASI GAS
Diunggah oleh
Erfin ElsonJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
MONETISASI GAS DI INDONESIA Dan SIAPKAH MALUKU Menuju MONETISASI GAS
MONETISASI GAS DI INDONESIA Dan SIAPKAH MALUKU Menuju MONETISASI GAS
Diunggah oleh
Erfin ElsonHak Cipta:
Format Tersedia
KEBIJAKAN MONETISASI GAS DI LAPANGAN ABADI-MALUKU
Oleh
Erfin.Elly.M.Eng*)
*) Staf Pengajar & Peneliti pada Fakultas Pertambangan dan Perminyakan & Gas Bumi,
UNIPA-Manokwari.
Gangguan ketersedian pasokan dan fluktuasi harga minyak bumi yang sering terjadi
menyebabkan pelaku industri mempertimbangkan gas bumi sebagai sumber energi alternatif
pengganti minyak. Walaupun tidak dapat mengganti seluruh fungsi dan manfaat minyak bumi,
namun dengan penanganan yang tepat gas bumi berpotensi menjadi komoditas energi yang dapat
diandalkan. Keterbatasan penggunaan gas pada masa lalu lebih disebabkan karena masalah
transportasi dan penyimpanannya. Era pemanfaatan gas yang dulunya bergantung pada jaringan
pipa untuk menghubungkan sumber gas dengan konsumen, kini telah berkembang dengan
ketersediaan berbagai opsi teknologi yang dapat dipilih untuk memonetisasi cadangan gas dan
mentransportasikannya. Monetisasi adalah mendapatkan keuntungan ekonomi, baik secara
langsung dalam finansial ataupun dampak positif lain yang berkaitan dengannya, sehingga
strategi yang dibuat tidak hanya mempertahankan tujuan jangka pendek tetapi jangka panjang.
Peranan Gas Bumi
Beberapa negara produsen yang memasok kebutuhan minyak dunia berada di daerah
yang secara geopolitik sangat sensitif, pergolakan yang terjadi di dalam negeri ataupun
sekitarnya selalu mempengaruhi pasar minyak dunia. Salah satu contohnya adalah krisis politik
di Timur Tengah yang langsung membawa akibat pada kondisi supply-demand minyak dunia
yang membuat harganya berfluktuasi. Peristiwa embargo tahun 1973 (Perang Yom Kipur)
mengakibatkan harga minyak dunia naik 400%, dari sekitar USD 3 per barel menjadi USD 12
per barel. Kekhawatiran yang berkepanjangan atas kondisi ini kemudian menjadi salah satu
dorongan bagi para pelaku industri untuk mulai berpikir menggunakan gas sebagai alternatif
bahan bakar minyak.
Beberapa negara telah menerapkan cetak biru kebijakan bauran energi (energy mix) yang
dirancang sebagai strategi pemenuhan energi nasional terutama untuk pengadaan energi listrik.
Dalam cetak biru itu ditetapkan prosentase dan skala prioritas setiap komponen sumber energi
untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa sumber energi tak-terbaharukan atau energi
fosil (minyak, gas dan batubara), sumber energi terbaharukan (biofuel, air, panas bumi, matahari
dan angin) dan energi nuklir, dimana masing-masing memiliki komponen teknologi serta inovasi
yang masih menjadi riset penelitian.
Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kegiatan industri di dunia
niscaya memerlukan pasokan energi jauh lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya.
Potensi bahan bakar fosil lainnya adalah gas, ketersediaan cadangan di seluruh dunia, dan masih
banyak yang belum dikembangkan sepenuhnya. Secara komersial penemuan cadangan gas tidak
memberikan kejelasan potensi keuntungan sampai diperoleh opsi yang efisien dan ekonomis
untuk membawanya kepada konsumen. Kandungan energi gas per satuan volume lebih rendah
dibandingkan minyak, sehingga biaya transportasinya relatif lebih mahal.
Secara teknis, harga keekonomian gas juga sangat spesifik, tergantung letak geografis,
lokasi formasi geologi cadangan, dan teknologi serta infrastruktur yang harus dibangun. Gas
secara umum dipakai sebagai sumber bahan bakar, penggunaannya sebagai bahan baku
menghasilkan produk turunan yang terbatas, tidak sebanyak yang diperoleh dari minyak.
Pemenuhan pasokan energi bagi negara sangat penting, dan di Indonesia kebijakan untuk
membuat rencana alokasi sumber pasokan energi dilakukan oleh Dewan Energi Nasional (DEN),
sebuah institusi Pemerintah yang merancang alokasi ketersediaan energi atas setiap komponen
sumber daya energi yang dimiliki negara. Dalam rencana yang dibuat sampai tahun 2025,
diharapkan mayoritas ketersediaan energi masih didapatkan dari bahan bakar fosil bersamaan
dengan meningkatnya kontribusi dari sumber energi terbarukan, dan dalam rencana ini gas
menjadi salah satu andalan karena diharapkan dapat mencapai target partisipasi sampai 20%.
MONETISASI LNG ABADI
Sumber cadangan gas di wilayah Maluku Tenggara ini terletak di tengah laut, berjarak
150 km dari pulau Tanimbar dan berada di dekat garis batas Indonesia dan Australia. Lapangan
gas Abadi ini semula diperkirakan mempunyai potensi cadangan sebesar 6 – 7 Tcf (Trillion cubic
feet), tetapi data cadangan yang terakhir diperoleh menunjukan cadangan gas melebihi 10 Tcf.
Strategi pengembangan kapasitas LNG adalah membangun sentra produksi baru LNG
yang berdekatan dengan sumber gas besar. Termasuk didalamnya memanfaatkan teknologi lebih
efisien dan tepat guna. Salah satunya adalah monetisasi lapangan gas Abadi oleh KKKS
(Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Inpex yang akan membangun kilang LNG terapung (Floating
LNG). FLNG Masela ini semula direncanakan dibangun dengan kapasitas 2,5 Mtpa (Million Ton
Per Annum), tetapi saat ini sedang dilakukan evaluasi ulang untuk mengevaluasi opsi yang lebih
optimal. FLNG ini nantinya merupakan kilang LNG terapung pertama di Indonesia. Alasan
membangun kilang terapung antara lain adalah karena letak sumber gas yang berada pada
patahan Australia yang sering mengalami gempa bumi, lokasinya jauh dari daratan Maluku, dan
terdapat palung yang dalam di antara keduanya. Opsi kilang LNG darat tetap dipertimbangkan,
tetapi dengan memperhatikan seringnya gempa yang terjadi, dan mengevaluasi ketersediaan
teknologi saat ini, maka pembangunan konstruksi pipa pasokan gas yang harus dibangun
melewati palung menuju daratan dianggap cukup beresiko. Proyek yang semula diperkirakan
membutuhkan dana USD 5 miliar ini direncakan akan mulai beroperasi tahun 2017 untuk
periode 30 tahun ke depan, tetapi adanya potensi ditemukan cadangan gas baru dan beberapa
perubahan asumsi keekonomian menjadikan rencana tersebut dievaluasi kembali untuk
menghasilkan keputusan monetisasi yang lebih optimal.
Menurut saya, pembangunan kilang LNG yang dipermasalahkan selama ini memang
memerlukan biaya kapital yang mahal (capital cost intensive). Oleh karena itu, tahap studi
kelayakan (Feasibility Study) dilakukan untuk membandingkan berbagai opsi pengembangan
lapangan migas, sehingga akhirnya didapat opsi pembangunan kilang LNG sebagai pilihan yang
tepat. Pada tahap awal ini mulai diidentifikasi pemilihan lokasi pembangunan, potensi dampak
sosial masyarakat, dan penentuan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan proyek guna
memberikan hasil yang optimal. Hal yang lebih utama adalah melihat dan meyakinkan apakah
opsi yang dipilih sesuai dengan strategi bisnis bagi pemilik proyek. Hal ini meliputi Pre-FEED
(Pre Front End Engineering Design) dimana pada tahap ini telah direncanakan lokasi kilang,
kapasitas produksi, proses teknologi dan peralatan utama yang digunakan, kapasitas tangki
penyimpan LNG (dan kondensat) yang diperlukan, dan rencana layout kilang secara umum.
Dalam hal ini lebih spesifik tentang proses pencairan gas, telah diindentifikasi jenis peralatan
penggerak siklus pendingin, spesifikasi produksi LNG, dari segi AMDAL mulai dilakukan
pengumpulan data untuk digunakan sebagai data awal (base line).
Hasil Pre-FEED memberikan gambaran justifikasi keekonomian proyek, dan sensitivitas
biaya kapital proyek mencapai ± 50%, pekerjaan dan perhitungan fase ini biasanya dilakukan
oleh pemilik proyek dengan bantuan konsultan.
Tahap selanjutnya adalah FEED yaitu dilakukan studi dan evaluasi value engineering
yang lebih detail dan spesifik sebagai dasar rancangan kilang yang dibuat, disinilah penentuan
filosofis proyek dan rancangan dasar kilang LNG (design basic) yang berdampak besar terhadap
keseluruhan biaya kapital yang diperlukan untuk membangun kilang LNG,
Berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan maka menurut hemat saya perlu diperhatikan
skala prioritas negara dan perusahaan terhadap rencana monetisasi yang tidak selalu sejalan,
sehingga diperlukan sinergi kedua belah pihak untuk menempatkan tujuan dan kepentingan
masing-masing sebagai tujuan bersama. Pada pola bagi hasil produksi yang dipakai di Indonesia,
secara umum pembagian hasil produksi bagian negara dan KKKS saat ini untuk minyak adalah
85 : 15 dan untuk gas adalah 70 : 30. Pengawasan dari negara terhadap kegiatan KKKS mutlak
diperlukan, terutama karena menyangkut optimalisasi pekerjaan dan efisiensi biaya. Kedua hal
tersebut sangat mempengaruhi besarnya biaya yang harus dikembalikan kepada KKKS. Dalam
perjanjian pengembangan lapangan disepakati beberapa hal penting misalnya, definisi tentang
area batas wilayah kerja kegiatan ekplorasi dan eksploitasi, batas waktu kegiatan eksplorasi,
pengembalian area yang tidak digunakan (relinguishment), komitmen finansial atas kegiatan
yang dilakukan, mekanisme pengajuan rencana kerja dan pembiayaan, dan lainnya. Penemuan
lapangan gas yang dianggap komersial harus segera dilaporkan kepada negara, dan harus segera
dimonetisasi dalam batasan waktu tertentu. Tujuan pemberian batas waktu adalah untuk
membuat KKKS segera dilakukan proses monetisasi, dan tidak menjadikan potensi
pengembangannya tertunda karena tidak menjadi skala prioritas dibandingkan portofolio lain
yang dimiliki, atau karena menunggu saat yang dianggap tepat. Kegiatan monetisasi migas
diharapkan dapat memberikan keuntungan yang dianggap terbaik bagi negara dan perusahaan
migas, di satu sisi lain aturan fiskal yang diberlakukan juga harus tetap dapat menarik
perusahaan migas untuk mau berinvestasi di bisnis yang beresiko ini. Aturan fiskal secara umum
diberlakukan yaitu bonus tandatangan (Signature Bonus), Royalty, Income tax, Widfall Profits
Tax, Production Sharing Split.
Maka menuju monetisasi LNG abadi (Blok Masela) Maluku, penggalian potensi sumber
daya wilayah merupakan prioritas utama. Hal itu, untuk meningkatkan pendapatan daerah yang
berdasar prinsip-prinsip keadilan dan kemandirian sehingga pada akhirnya akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memadukan kemampuan
sumber daya manusia (human capital), memanfaatkan sumber daya alam (natural capital),
meningkatkan sumberdaya buatan (man made capital) serta social capital sehingga kemampuan
daerah dalam pelaksanaan pembangunan akan meningkat, Semoga.
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Kebijakan Energi NasionalDokumen42 halamanMakalah Kebijakan Energi NasionalTriLestari100% (1)
- Studi Kelayakan SciDokumen15 halamanStudi Kelayakan Sciyoi_123100% (3)
- 69 138 1 SMDokumen9 halaman69 138 1 SM56962645Belum ada peringkat
- Tugas TekgasDokumen2 halamanTugas TekgasGloriaBelum ada peringkat
- Prosiding2016 ID014Dokumen9 halamanProsiding2016 ID014Akhmad HananBelum ada peringkat
- Sejarah Industri Gas IndonesiaDokumen2 halamanSejarah Industri Gas IndonesiaOkky MahendraBelum ada peringkat
- 912 2680 1 PBDokumen10 halaman912 2680 1 PB086Sari Amalia N. WTIBBelum ada peringkat
- Bab VDokumen2 halamanBab VTifano KhristiyantoBelum ada peringkat
- Correaferia 2010Dokumen20 halamanCorreaferia 2010Leon ZidaneBelum ada peringkat
- Geothermal Tugas AkhirDokumen11 halamanGeothermal Tugas AkhirBidara KaliandraBelum ada peringkat
- Siaran - Pers IEEFA Cofiring FEB2021Dokumen4 halamanSiaran - Pers IEEFA Cofiring FEB2021Dedy SetiawanBelum ada peringkat
- Tinjauan Singkat Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Pada Sektor Rumah TanggaDokumen11 halamanTinjauan Singkat Optimalisasi Pemanfaatan Gas Bumi Pada Sektor Rumah TanggaFajri AnsharullahBelum ada peringkat
- Kelapa Sawit BiogasDokumen18 halamanKelapa Sawit Biogastaufany99Belum ada peringkat
- 1663 4114 1 PBDokumen14 halaman1663 4114 1 PBearl fritzBelum ada peringkat
- Jakarta City Gas - Kelompok 7 - Rev0Dokumen23 halamanJakarta City Gas - Kelompok 7 - Rev0dhanta_1412Belum ada peringkat
- PPGM PertaminaDokumen46 halamanPPGM PertaminaDanujaBelum ada peringkat
- Air Terproduksi CBMDokumen5 halamanAir Terproduksi CBMAditya NugrahaBelum ada peringkat
- Presentasi Kelompok 12Dokumen14 halamanPresentasi Kelompok 12Rizka NadialifBelum ada peringkat
- Kondisi Geologi Indonesia Dan Potensi MigasDokumen5 halamanKondisi Geologi Indonesia Dan Potensi MigasMuhammad Ridho YonasBelum ada peringkat
- Akutansi Untuk Kontrak Bagi HasilDokumen19 halamanAkutansi Untuk Kontrak Bagi HasilrizalfettyBelum ada peringkat
- Proposal Model Kebijakan PLTBGDokumen30 halamanProposal Model Kebijakan PLTBGzainal ArifinBelum ada peringkat
- Tugas 2Dokumen5 halamanTugas 2auto gamingBelum ada peringkat
- Draft Mula PLTB BHS Indonesia 01Dokumen8 halamanDraft Mula PLTB BHS Indonesia 01ris boboBelum ada peringkat
- Buku Gas AlamDokumen14 halamanBuku Gas Alamnaufal sahabBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Gasoline - Chandini Ruth Yapno - 211420033 - Ref 2ADokumen26 halamanLaporan Akhir Gasoline - Chandini Ruth Yapno - 211420033 - Ref 2AChandini Rut YapnoBelum ada peringkat
- S2 2021 447780 AbstractDokumen16 halamanS2 2021 447780 Abstractfikry.ramdhaniBelum ada peringkat
- TOR FGD Kawasan Industri Energi Strategis Terpadu SebalangDokumen5 halamanTOR FGD Kawasan Industri Energi Strategis Terpadu SebalangRahmat HermawanBelum ada peringkat
- S1 - Feb - Manajemen - 21701081084 - Zaneta Cahaya FitriDokumen18 halamanS1 - Feb - Manajemen - 21701081084 - Zaneta Cahaya FitrifmeetalurgistBelum ada peringkat
- Kebijakan Migas 1Dokumen29 halamanKebijakan Migas 1Evelyn GonzalezBelum ada peringkat
- Energy SecurityDokumen11 halamanEnergy SecuritysuhartostBelum ada peringkat
- Prospek Kerjasama Energi Dengan NegaraDokumen9 halamanProspek Kerjasama Energi Dengan NegaraImansyah PutraBelum ada peringkat
- OPINI Indonesia Yang Mandiri Dalam Energi Mimpi - Vinskatania Agung Andrias 12312031Dokumen2 halamanOPINI Indonesia Yang Mandiri Dalam Energi Mimpi - Vinskatania Agung Andrias 12312031Vinska AndriasBelum ada peringkat
- Benedictus Kevin - 456275 - Tugas MKE 2Dokumen2 halamanBenedictus Kevin - 456275 - Tugas MKE 2Benedictus KevinBelum ada peringkat
- Proposal Tinjauan Yuridis Terkait Rencana Pembangunan Infrastruktur Jaringan GasDokumen13 halamanProposal Tinjauan Yuridis Terkait Rencana Pembangunan Infrastruktur Jaringan GasNever easyBelum ada peringkat
- (Energi) Prospek Pengembangan LNG Lepas PantaiDokumen18 halaman(Energi) Prospek Pengembangan LNG Lepas PantaicepypermadiBelum ada peringkat
- Tugas Konservasi EnergiDokumen15 halamanTugas Konservasi EnergisabrinaBelum ada peringkat
- Pemilihan Energi Terbarukan Untuk Pembangkit Listrik Di Indonesia Dengan Metode AHPDokumen19 halamanPemilihan Energi Terbarukan Untuk Pembangkit Listrik Di Indonesia Dengan Metode AHPLukman Arif Sandi100% (2)
- Jurnal 1Dokumen7 halamanJurnal 1Rstu AgungBelum ada peringkat
- MAKALAHDokumen17 halamanMAKALAHAndreas AlvaroBelum ada peringkat
- Jawaban UTS - Nomor 7Dokumen7 halamanJawaban UTS - Nomor 7Faris Rizky FebriantoBelum ada peringkat
- Dasar Konversi EnergiDokumen11 halamanDasar Konversi EnergiZainuddinBelum ada peringkat
- Laporan SeminarDokumen7 halamanLaporan SeminarChristo SumerahBelum ada peringkat
- FisikaDokumen14 halamanFisikaAbdulloh MujayaniBelum ada peringkat
- Minyak Dan GasDokumen40 halamanMinyak Dan GaskhusnaBelum ada peringkat
- 757-Article Text-565-2-10-20200202Dokumen12 halaman757-Article Text-565-2-10-20200202yusron yustiansyahBelum ada peringkat
- Laporan Orientasi Pembekalan Teknis CpnsDokumen11 halamanLaporan Orientasi Pembekalan Teknis CpnsPhiciato SiraitBelum ada peringkat
- Blok CorridorDokumen4 halamanBlok Corridormuhammad taufikBelum ada peringkat
- 89-Article Text-261-1-10-20200120Dokumen5 halaman89-Article Text-261-1-10-20200120afniBelum ada peringkat
- Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Di Daerah Ciwidey BandungDokumen8 halamanPengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Di Daerah Ciwidey BandungBaso Syarif MuhadzdzibBelum ada peringkat
- Strategic Supply Chain Management PDFDokumen11 halamanStrategic Supply Chain Management PDFAnonymous 9vF9XUU2ZKBelum ada peringkat
- Makalah Termodinamika LNGDokumen45 halamanMakalah Termodinamika LNGHijrahBelum ada peringkat
- Makalah Termodinamika TerapanDokumen56 halamanMakalah Termodinamika TerapanRahman Adi RaharjoBelum ada peringkat