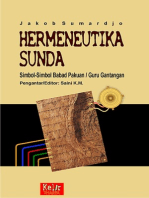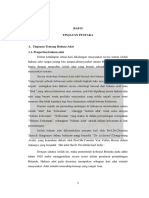Hukum Adat (Pertemuan Ke 6)
Hukum Adat (Pertemuan Ke 6)
Diunggah oleh
Rifky Izzulhaq0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
15 tayangan10 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
15 tayangan10 halamanHukum Adat (Pertemuan Ke 6)
Hukum Adat (Pertemuan Ke 6)
Diunggah oleh
Rifky IzzulhaqHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 10
HUKUM ADAT
PERTEMUAN KE ENAM
Pengertian Hukum Adat
Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia
itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian
bermasyarakat dan kemudian bernegara. Terjadinya hukum dimulai dari pribadi manusia yang
diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan
menimbulkan “kebiasaan pribadi”. Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain maka ia juga
akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di
dalam kesatuan masyarakat ikut pula melakukan kebiasaan itu, maka lambat laun kebiasaan itu
menjadi “adat” dari masyarakat itu.
Hukum adat merupakan produk dari budaya yang mengandung substansi tentang nilai-nilai
budaya cipta, karsa, rasa manusia. Dalam arti bahwa hukum adat lahir dari kesadaran atas
kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi
peradaban manusia. Selain itu hukum adat juga merupakan produk social yaitu sebagai hasil
kerja bersama (kesepakatan) dan merupakan karya bersama secara bersama (milik sosial) dari
suatu masyarakat hukum adat.
Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun
menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat
sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus
dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan.
Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia.
Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum
tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum
masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum
adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat
hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga
bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
Hukum Adat berbeda di tiap daerah karena pengaruh:
1. Agama : Hindu, Budha, Islam, Kristen dan sebagainya. Misalnya : di Pulau Jawa dan Bali
dipengaruhi agama Hindu, Di Aceh dipengaruhi Agama Islam, Di Ambon dan Maluku
dipengaruhi agama Kristen.
2. Kerajaan seperti antara lain: Sriwijaya, Airlangga, Majapahit.
3. Masuknya bangsa-bangsa Arab, China, Eropa.
Ciri-ciri dari hukum adat yaitu:
1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
2. Tidak tersusun secara sistematis.
3. Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
4. Tidak tertatur.
5. Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
6. Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.
Adat Menurut Masyarakat Bali adalah pokok pangkat kehidupan kelompok masyarakat adat di
Bali berdasarkan pada penuangan dari falsafah agama Hindu disebut Tri Hita Karana atau yaitu
upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakan keseimbangan hubungan antara warga
masyarakat itu sendiri, upaya penegakan keseimbangan hubungan warga masyarakat dalam
kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat keseluruhan dengan alam Ke-Tuhanan
Istilah Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda “Adat Recht”, yang
pertama sekali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya “De
Atjehers” (orang-orang Aceh). Istilah Adat-Recht ini kemudian dipakai pula oleh van
Vollenhoven yang menulis buku pokok tentang Hukum Adat yaitu “Het Adat-Recht van
Nederlandsch Indie” (Hukum Adat Hindia-Belanda).
A. Pengertian Hukum Adat
Dalam arti sempit sehari-hari yang dinamakan Hukum Adat ialah: Hukum asli yang tidak
tertulis yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-
hari, dalam hubungan antara satu dengan lainnya baik di desa maupun di kota.
Di samping bagian tidak tertulis dari hukum asli ada pula bagian yang tertulis yaitu: Piagam,
perintah-perintah Raja, patokan-patokan pada daun lontar, awig-awig (dari Bali), dan
sebagainya.
Di banding dengan yang tidak tertulis, maka bagian yang tertulis ini adalah kecil (sedikit), tidak
berpengaruh dan sering dapat diabaikan.
1. Ter Haar
Ter Haar membuat dua perumusan, yang menunjukkan perubahan pendapatnya tentang
apa yang dinamakan Hukum Adat itu, yaitu:
Pertama: Dalam pidato dies tahun 1930, dengan judul “Peradilan Landraad berdasarkan hukum
tak tertulis. Hukum Adat lahir dari dan diperlihara oleh keputusan-keputusan; keputusan para
warga masyarakat umum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang
membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum; atau dalam hal pertentangan kepentingan,
keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu
karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum
rakyat, melainkan seapas-seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/diakui atau setidak-
tidaknya ditoleransikan olehnya.
Kedua, Dalam orasinya tahun 1937, yang berobyek, “Hukum Adat Hindia Belanda di dalam
ilmu, praktek dan pengajaran”
Hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis yang terdiri dari peraturan-
peraturan Desa, surat-surat perintah Raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam
keputusan-keputusan para Fungsionaris Hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa
(macht, authority) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan)
dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Fungsionaris di sini terbatas pada dua kekuasaan yaitu
Eksekutif dan Yudikatif.
Dengan demikian Hukum Adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam
keputusan-keputusan fungsionaris hukum itu; bukan saja hakim tetapi juga Kepala Adat, rapat
desa, wali tanah, petugas-petugas desa lainnya. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai
suatu sengketa yang resmi, tetapi juga di luar itu berdasarkan kerukunan (musyawarah).
Keputusan-keputusan itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rokhani
dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu. Dalam perumusan Ter Haar ini
tersimpul ajaran Beslissingenleer (ajaran keputusan).
2. Van Vollenhoven
Hukum Adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai
sanksi (oleh karena itu: “Hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan (oleh
karena itu “Adat”)
Positif yaitu hukum yang dinyatakan berlaku di sini dan kini. Sanksi yaitu reaksi/konsekuensi
dari pihak lain atas pelanggaran suatu norma (hukum). Kodifikasi yaitu pembukuan sistematis
suatu daerah/lapangan/bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat (semua bagian
diatur), lengkap (yang diatur segala unsurnya) dan tuntas (yang diatur semua soal yang mungkin
timbul).
3. Supomo
Supomo di dalam “Beberapa catatan mengenai kedudukan Hukum Adat” menulis antara
lain: Dalam tatahukum baru Indonesia baik kiranya guna menghindarkan salah pengertian, istilah
Hukum Adat ini dipakai sebagai sinonim dari:
Hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (non-statutory law);
Hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan-dewan
Propinsi dan sebagainya);
Hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judgemade law);
Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup,
baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law); semua inilah merupakan Adat atau
Hukum yang tidak tertulis yang disebut oleh Pasal 32 UUDS Tahun 1950.
Dari uraian di atas, Supomo melepaskan perhatian terhadap hal-hal atau bagian-bagian yang
tertulis dan memahamkan Hukum Adat itu sebagai hukum yang tidak tertulis dalam arti hukum
kebiasaan yang tidak tertulis.
Bushar Muhammad sependapat bahwa Pasal 32 dan 43 UUDS tahun 1950 harus ditafsirkan
secara luas. Jadi hukum yang tak tertulis tidak hanya meliputi yang hidup dan dipertahankan
sebagai peraturan adat di dalam masyarakat (customary law) yang disebut Hukum Adat dalam
arti sempit, tetapi juga hukum kebiasaan dalam lapangan ketatanegaraan (convention) dan
kehakiman atau peradilan. Supomo mengabaikan bagian yang tertulis dari Hukum Adat karena
memang bagian yang tertulis ini sedikit sekali, sehingga dalam persoalan ini dapat diabaikan.
4. Hazairin
Di dalam pidato inagurasinya yang berjudul: “Kesusilaan dan Hukum” berpendapat
bahwa seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun
tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat
bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan.
Demikianlah juga dengan hukum adat; teristimewa di sini dijumpai perhubungan dan
persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan; pada akhirnya antara hukum dan adat
yaitu sedemikian langsungnya sehingga istilah buatan yang disebut “Hukum Adat” itu tidak
dibutuhkan oleh Rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “Adat” itu atau dalam
artinya sebagai (Adat) sopan-santun atau dalam artinya sebagai hukum.
Selanjutnya Hazairin dalam masyarakat, yaitu bahwa: kaidah-kaidah Adat itu berupa kaidah-
kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
Meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaidah-kaidah kesusilaan dan kaidah-
kaidah hukum itu, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh
itu adalah menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang dicela atau dianjurkan juga, sehingga pada
hakikinya dalam patokan lapangan itu juga hukum itu berurat pada kesusilaan. Apa yang tidak
dapat terpelihara lagi hanya oleh kaidah-kaidah kesusilaan, diikhtiarkan pemeliharaannya dengan
kaidah-kaidah hukum.
Yang dimaksud dengan kaidah hukum ialah kaidah yang tidak hanya didasarkan kepada
kebebasan pribadi tetapi serentak mengekang pula kebebasan itu dengan suatu gertakan, suatu
ancaman paksaan yang dapat dinamakan ancaman hukum atau penguat hukum. Uraian Hazairin
ini memberi kesan kepada kita akan suatu pandangan yang agak lain dari biasa.
Di sini Hazairin menghilangkan suatu garis atau batas yang tegas antara hukum di pihak yang
satu dengan kesusilaan (kebiasaan, kelaziman, “zede” dan sebagainya) di pihak lain. Hazairin
melihat antara hukum (hukum adat) dan kesusilaan tidak ada suatu perbedaan hakiki. Dapat
dikatakan bahwa segala macam hukum yang ada, yaitu segala macam peraturan dalam hidup
kemasyarakatan yang mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu bersumber kepada
kesusilaan. Kaidah kesusilaan termasuk kaidah Adat dibaiarkan pemeliharaannya kepada
kebebasan pribadi yang dibatasi dengan dan dijuruskan kepada suatu ancaman paksaan, yaitu:
hukuman, pidana, penguat hukum.
Faham Hazairin tentang Hukum Adat disesuaikan dengan faham rakyat, yaitu baik dalam arti
(adat) sopan-santun maupun dalam arti hukum.
B. Sumber Hukum Adat
Dalam membicarakan sumber hukum (Adat) dianggap penting terlebih dahulu dibedakan
atas dua pengertian sumber hukum yaitu Welbron dan Kenbron.
Welbron adalah sumber hukum (adat) dalam arti yang sebenarnya. Sumber Hukum Adat dalam
arti Welbron tersebut, tidak lain dari keyakinan tentang keadilan yang hidup dalam masyarakat
tertentu. Dengan perkataan lain Welbron itu adalah konsep tentang keadilan sesuatu masyarakat,
seperti Pancasila bagi masyarakat Indonesia.
Sedangkan Kenbron adalah sumber hukum (adat) dalam arti dimana hukum (adat) dapat
diketahui atau ditemukan. Dengan lain perkataan sumber dimana asas-asas hukum (adat)
menempatkan dirinya di dalam masyarakat sehingga dengan mudah dapat diketahui.
Kenbron itu merupakan penjabaran dari Welbron. Atas dasar pandangan sumber hukum seperti
itu, maka para sarjana yang menganggap hukum itu sebagai kaidah berpendapat sumber hukum
dalam arti Kenbron itu adalah:
1. Adat kebiasaan
2. Yurisprudensi
3. Norma-norma Hukum Islam yang telah meresap ke dalam Adat istiadat masyarakat
Indonesia Asli.
4. Kitab-kitab Hukum Adat
5. Buku-buku Standar tentang Hukum Adat
6. Pendapat Ahli Hukum Adat.
Dengan demikian hukum adat dapat ditemukan baik dalam adat kebiasaan maupun dalam
tulisan-tulisan yang khusus memuat/membicarakan hukum adat. Tulisan itu mungkin fakta
hukum atau mungkin pula merupakan pandangan dari para ahli hukum adat.
C. Asas-asas Pokok dalam Hukum Adat
Asas Religio Magis (Magisch-Religieus)
Asas Komun (Commun)
Asas Contant (Tunai)
Asas Konkrit (Visual)
Asas Religio Magis (Magisch-Religieus) adalah pembulatan atau perpaduan kata yang
mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu
gaib dan lain-lain.
Kuntjaranigrat menerangkan bahwa alam pikiran religiomagis itu mempunyai unsur-unsur
sebagai berikut:
Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, rokh-rokh dan hantu-hantu yang menempati
seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh
manusia dan benda-benda.
Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat
dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luas biasa, binatang-binatang yang
luar biasa, benda-benda yang luar biasa dan suara yang luar biasa.
Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai “magische kracht” dalam
berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau menolak bahaya gaib.
Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan krisis,
menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari atau
dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.
Bushar Muhammmad tentang pengertian religio-magis mengemukakan kata
“participerend cosmisch” yang mengandung pengertian komplek. Orang Indonesia pada
dasarnya berpikir, merasa dan bertindak didorong oleh kepercayaan (religi) kepada tenaga-
tenaga gaib (magis) yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta (dunia kosmos) dan yang
terdapat pada orang, binatang, tumbuh-tubuhan besar dan kecil, benda-benda; dan semua tenaga
itu membawa seluruh alam semesta dalam suatu keadaan keseimbangan. Tiap tenaga gaib itu
merupakan bagian dari kosmos, dari keseluruhan hidup jasmaniah dan rokhaniah, “participatie”,
dan keseimbangan itulah yang senantiasa harus ada dan terjaga, dan apabila terganggu harus
dipulihkan. Memulihkan keadaan keseimbangan itu berujud dalam beberapa upacara, pantangan
atau ritus (rites de passage).
Asas Komun berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri.
Asas korum merupakan segi atau corak yang khas dari suatu masyarakat yang masih hidup
sangat terpencil atau dalam hidupnya sehari-hari masih sangat tergantung kepada tanah atau alam
pada umumnya. Dalam masyarakat semacam itu selalu terdapat sifat yang lebih mementingkan
keseluruhan; lebih diutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual. Dalam
masyarakat semacam itu individualitas terdesak ke belakang. Masyarakat, desa, dusun yang
senantiasa memegang peranan yang menentukan, yang pertimbangan dan putusannya tidak boleh
dan tidak dapat disia-siakan. Keputusan Desa adalah berat, berlaku terus dan dalam keadaan
apapun juga harus dipatuhi dengan hormat, dengan khidmat.
Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat contant (tunai) yaitu prestasi dan
contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
Asas contant atau tunai mengandung pengertian bahwa dengan suatu perbuatan nyata, suatu
perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika
itu juga, dengan serentak bersamaan waktunya tatkala berbuat atau mengucapkan yang
diharuskan oleh Adat. Dengan demikian dalam Hukum Adat segala sesuatu yang terjadi sebelum
dan sesudah timbang terima secara contan itu adalah di luar akibat-akibat hukum dan memang
tidak tersangkut patu atau tidak bersebab akibat menurut hukum.
Perbuatan hukum yang dimaksud yang telah selesai seketika itu juga adalah suatu
perbuatan hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Dalam arti urutan kenyataan-kenyataan,
tindakan-tindakan sebelum dan sesudah perbuatan yang bersifat contan itu mempunyai arti logis
satu sama lain. Contoh yang tepat dalam Hukum Adat tentang suatu perbuatan yang contant
adalah: jual-beli lepas, perkawinan jujur, melepaskan hak atas tanah, adopsi dan lain-lain.
Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan perbuatan hukum itu selalu
konkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual-beli, si pembeli menyerahkan uang/uang panjer.
Di dalam alam berpikir yang tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang
dimaksudkan, diinginkan, dikehendaki atau akan dikerjakan ditransformasikan atau diberi ujud
suatu benda, diberi tanda yang kelihatan, baik langsung maupun hanya menyerupai obyek yang
dikehendaki (simbol, benda yang magis).
Contoh: Panjer dalam maksud akan melakukan perjanjian jual beli atau memindahkan hak atas
tanah; peningset (panyangcang) dalam pertunangan atau akan melakukan perkawinan; membalas
dendam terhadap seseorang dengan membuat patung, boneka atau barang lain, lalu barang
itu dimusnahkan, dibakar, dipancung.
SEJARAH SINGKAT HUKUM ADAT
Hukum Adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snouck Hurgrounje seorang Ahli
Sastra Timur dari Belanda 1894. Sebelum istilah Hukum Adat berkembang, dulu dikenal
istilah adat recht . Prof. Snouck Hurgrounje dalam bukunya de atjehers (Aceh) pada tahun1893-
1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah de atjehers.
Kemudian istilah ini dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang
Sarjana Sastra yang juga Sarjana Hukum yang pula menjabat sebagai Guru Besar
pada Universitas Leiden di Belanda. Ia memuat istilah Adat Recht dalam bukunya yang
berjudul Adat Recht van Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda) pada tahun 1901-
1933.
Perundang-undangan di Hindia Belanda secara resmi mempergunakan istilah ini pada tahun
1929.dalam Indische Staatsregeling (Peraturan Hukum Negeri Belanda), semacam Undang-
Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat (2) yang berlaku pada tahun 1929.
Dalam masyarakat Indonesia, istilah hukum adat tidak dikenal adanya.Hilman
Adikusuma mengatakan bahwa istilah tersebut hanyalah istilah teknis saja. Dikatakan demikian
karena istilah tersebut hanya tumbuh dan dikembangkan oleh para ahli hukum dalam rangka
mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikembangkan ke
dalam suatu sistem keilmuan.
Dalam bahasa Inggris dikenal juga istilah Adat Law, namun perkembangan yang ada
di Indonesia sendiri hanya dikenal istilah Adat saja, untuk menyebutkan sebuah sistem hukum
yang dalam dunia ilmiah dikatakan Hukum Adat.
Pendapat ini diperkuat dengan pendapat dari Muhammad Rasyid Maggis Dato Radjoe
Penghoeloe sebagaimana dikutif oleh Prof. Amura : sebagai lanjutan kesempuranaan hidupm
selama kemakmuran berlebih-lebihan karena penduduk sedikit bimbang dengan kekayaan alam
yang berlimpah ruah, sampailah manusia kepada adat.
Sedangkan pendapat Prof. Nasroe menyatakan bahwa adat Minangkabau telah dimiliki oleh
mereka sebelum bangsa Hindu datang ke Indonesia dalam abad ke satu tahun masehi.
Prof. Dr. Mohammad Koesnoe, S.H. di dalam bukunya mengatakan bahwa istilah Hukum Adat
telah dipergunakan seorang Ulama Aceh yang bernama Syekh Jalaluddin bin Syekh Muhammad
Kamaluddin Tursani (Aceh Besar) pada tahun 1630. Prof. A. Hasymi menyatakan bahwa buku
tersebut (karangan Syekh Jalaluddin) merupakan buku yang mempunyai suatu nilai tinggi dalam
bidang hukum yang baik.
Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut :
“Tingkah laku seseoarang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh
masyarakat luar dalam waktu yang lama”.
Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :
1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.
Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang
lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian
adat-iatiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat
sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.
Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu
kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern
sesorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar
dalam masyarakat.
Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu
tetap kekal, karena adat selalu menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak
zaman. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi
rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.
Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh
masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan
menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan
merupakan aturan hukum.
Anda mungkin juga menyukai
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)
- Hukum Adat Di Era ModernDokumen13 halamanHukum Adat Di Era ModernDe DharmoamijoyoBelum ada peringkat
- Makalah Hukum AdatDokumen19 halamanMakalah Hukum AdatIsa DewantaraBelum ada peringkat
- Materi Hukum AdatDokumen11 halamanMateri Hukum Adatreka anggrainiBelum ada peringkat
- Tujuan Mempelajari Hukum AdatDokumen6 halamanTujuan Mempelajari Hukum AdatMedol100% (1)
- Ringkasan Hukum Adat Bab 1-3Dokumen29 halamanRingkasan Hukum Adat Bab 1-3dyta rallyaBelum ada peringkat
- Hukum AdatDokumen39 halamanHukum AdatMinie SihabudinBelum ada peringkat
- Modul Hukum AdatDokumen23 halamanModul Hukum AdatnikeastiswijayaBelum ada peringkat
- MK - Hukum AdatDokumen37 halamanMK - Hukum AdatYULI HITAYATIBelum ada peringkat
- Asas-Asas Hukum AdatDokumen17 halamanAsas-Asas Hukum AdatIsmayaBelum ada peringkat
- Ujian Tengah Semester Hukum Adat Riki HartantoDokumen5 halamanUjian Tengah Semester Hukum Adat Riki HartantoRiki HartantoBelum ada peringkat
- Hukum AdatDokumen31 halamanHukum Adateka agustinaBelum ada peringkat
- Tugas KLP PhiDokumen10 halamanTugas KLP PhiAbi AngginaBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen28 halamanBab 1gamedrops123321Belum ada peringkat
- Makalah Hukum AdatDokumen13 halamanMakalah Hukum AdatBucariBelum ada peringkat
- Dasar-Dasar Hukum AdatDokumen19 halamanDasar-Dasar Hukum AdatRizka AprilBelum ada peringkat
- Hukum Tanah AdatDokumen9 halamanHukum Tanah AdatTarid FebrianaBelum ada peringkat
- Rangkuman Buku Hukum Adat Karangan Soerojo WignjodipoeroDokumen8 halamanRangkuman Buku Hukum Adat Karangan Soerojo Wignjodipoerono vian0% (1)
- Hukum Adat Terbaru 1Dokumen62 halamanHukum Adat Terbaru 1Akunml KuBelum ada peringkat
- Asas-Asas Hukum AdatDokumen16 halamanAsas-Asas Hukum AdatIsmaya100% (3)
- Kuis Hukum Adat SBLM UtsDokumen9 halamanKuis Hukum Adat SBLM UtsArif Akbar KurniaBelum ada peringkat
- Tugas Adat Perihal TanahDokumen6 halamanTugas Adat Perihal TanahramsiriusBelum ada peringkat
- Asas Asas HukumDokumen5 halamanAsas Asas HukumPhiephie Al QarniBelum ada peringkat
- Hukum Adat Sebagai Aspek KebudayaanDokumen23 halamanHukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaanranu kumboloBelum ada peringkat
- Istilah Hukum Adat OkDokumen13 halamanIstilah Hukum Adat OkDarmawanBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Adat Pada Masa PenjajahanDokumen17 halamanMakalah Hukum Adat Pada Masa PenjajahanAzmar AmirBelum ada peringkat
- Hk. Adat PDFDokumen32 halamanHk. Adat PDFRiris MaymoraBelum ada peringkat
- Pengertian Hukum Adat Menurut Ahli Dalam Negeri Dan Luar NegeriDokumen2 halamanPengertian Hukum Adat Menurut Ahli Dalam Negeri Dan Luar Negerinasril pahmiBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen39 halamanBab Iinizar novaBelum ada peringkat
- Eksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif TatanegaraDokumen20 halamanEksistensi Hukum Adat Dalam Polemik Hukum Positif Suatu Kajian Dalam Perspektif TatanegaraAgustinus DennyBelum ada peringkat
- Pertemuan Ke 1 (Dosen Jarkasi Anwar (Istilah Dan Pengertian Hukum Adat, Hukum Adat Dan Adat (Rev)Dokumen23 halamanPertemuan Ke 1 (Dosen Jarkasi Anwar (Istilah Dan Pengertian Hukum Adat, Hukum Adat Dan Adat (Rev)IdrianBelum ada peringkat
- Hukum AdatDokumen19 halamanHukum AdatyogadharmasusilaBelum ada peringkat
- Makalah Tatanan Hukum TradisionalDokumen18 halamanMakalah Tatanan Hukum Tradisionalp3md biringbuluBelum ada peringkat
- Hukum Adat DayakDokumen7 halamanHukum Adat Dayakdestavin100% (1)
- Hukum Adat Sebagai Aspek KebudayaanDokumen9 halamanHukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaanlilo galangBelum ada peringkat
- Dinamika Giwu Dan Kepatuhan Dalam Kasus Pelanggaran Asusila Pada Adat Masyarakat Kulawi Di Desa BolapapuDokumen24 halamanDinamika Giwu Dan Kepatuhan Dalam Kasus Pelanggaran Asusila Pada Adat Masyarakat Kulawi Di Desa BolapapuCHRISTIAN DODUBelum ada peringkat
- Mirata Bulan BehDokumen16 halamanMirata Bulan BehFadel2004Belum ada peringkat
- Asas Dan Sistem Hukum AdatDokumen12 halamanAsas Dan Sistem Hukum Adatlivy moonBelum ada peringkat
- Makalah AdatDokumen14 halamanMakalah AdatarmalasahidBelum ada peringkat
- Kedudukan HK - ADAT BEBERAPA PENGERTIANDokumen7 halamanKedudukan HK - ADAT BEBERAPA PENGERTIANAbdur Rahim, S.HBelum ada peringkat
- Online 12 Hukum Delik AdatDokumen15 halamanOnline 12 Hukum Delik AdatSaptaning R PamintoBelum ada peringkat
- Sistem Hukum AdatDokumen13 halamanSistem Hukum AdatIlham Rifdy adilahBelum ada peringkat
- BHS Indonesia Hukum Ke-6 (Bahasa Keilmuan Hukum)Dokumen21 halamanBHS Indonesia Hukum Ke-6 (Bahasa Keilmuan Hukum)Rian AdzharBelum ada peringkat
- Arti Dan IstilahDokumen27 halamanArti Dan Istilahkiyay KiyayBelum ada peringkat
- Inisiasi Tuton Ke - 2 Mata Kuliah: Sistem Hukum Indonesia Program Studi: Ilmu Hukum Fakultas: FHISIPDokumen25 halamanInisiasi Tuton Ke - 2 Mata Kuliah: Sistem Hukum Indonesia Program Studi: Ilmu Hukum Fakultas: FHISIPDinas Lingkungan Hidup Kota BitungBelum ada peringkat
- PENGERTIAN Hukum AdatDokumen10 halamanPENGERTIAN Hukum AdatYuvinaBelum ada peringkat
- Resume Hukum AdatDokumen8 halamanResume Hukum AdatAfifah chika SalshabilaBelum ada peringkat
- Landasan Hukum Adat Dalam Tata Hukum IndonesiaDokumen14 halamanLandasan Hukum Adat Dalam Tata Hukum IndonesiaBobo AdvendBelum ada peringkat
- Resume Hukum Adat-Lutfiah AnugrahDokumen4 halamanResume Hukum Adat-Lutfiah AnugrahLutfiah AnugrahBelum ada peringkat
- Resume Hukum Adat-Lutfiah AnugrahDokumen4 halamanResume Hukum Adat-Lutfiah Anugrahlutfiah anugrahBelum ada peringkat
- Materi Hukum AdatDokumen11 halamanMateri Hukum Adatnovi hawBelum ada peringkat
- Full Modul Hukum Adat Maret 2017Dokumen55 halamanFull Modul Hukum Adat Maret 2017Dana AfiaBelum ada peringkat
- Hubungan Hukum Dengan KebiasaanDokumen12 halamanHubungan Hukum Dengan KebiasaanPurusottama S'g100% (4)
- Hukum Adat SBG The Living LawDokumen12 halamanHukum Adat SBG The Living LawAaiu Siwi100% (1)
- Hukum AdatDokumen39 halamanHukum AdatJevita PutriBella SendengBelum ada peringkat
- Sejarah Hukum AdatDokumen25 halamanSejarah Hukum Adatmeilanagung05Belum ada peringkat
- Wujud Hukum Adat Dan Hukum Adat Sebagai Aspek KebudayaanDokumen13 halamanWujud Hukum Adat Dan Hukum Adat Sebagai Aspek KebudayaanCecilia NatalieBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Adat Kelompok 1Dokumen15 halamanMakalah Hukum Adat Kelompok 1mataramntb89Belum ada peringkat
- PHI 4 Pokok-Pokok Hukum AdatDokumen13 halamanPHI 4 Pokok-Pokok Hukum AdatYozia FitriBelum ada peringkat