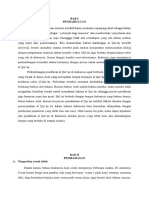Kontribusi Al-Baidawi Dalam Tafsir Lingus-Teologis
Kontribusi Al-Baidawi Dalam Tafsir Lingus-Teologis
Diunggah oleh
Muhammad Kamalul Fikri0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
9 tayangan4 halamanAnwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta’wīl karya al-Baiḍāwī merupakan tafsir al-Qur'an yang menggabungkan pendekatan linguistik dan teologis. Al-Baiḍāwī memperhatikan analisis bahasa Arab dan kaidah nahwu dalam menafsirkan ayat, namun juga mengutamakan pandangan Asy'ariyah dan fiqh Syafi'iyah. Karya ini dianggap lebih menonjol dalam analisis
Deskripsi Asli:
Judul Asli
Kontribusi Al-Baidawi dalam Tafsir lingus-teologis
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniAnwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta’wīl karya al-Baiḍāwī merupakan tafsir al-Qur'an yang menggabungkan pendekatan linguistik dan teologis. Al-Baiḍāwī memperhatikan analisis bahasa Arab dan kaidah nahwu dalam menafsirkan ayat, namun juga mengutamakan pandangan Asy'ariyah dan fiqh Syafi'iyah. Karya ini dianggap lebih menonjol dalam analisis
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
9 tayangan4 halamanKontribusi Al-Baidawi Dalam Tafsir Lingus-Teologis
Kontribusi Al-Baidawi Dalam Tafsir Lingus-Teologis
Diunggah oleh
Muhammad Kamalul FikriAnwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta’wīl karya al-Baiḍāwī merupakan tafsir al-Qur'an yang menggabungkan pendekatan linguistik dan teologis. Al-Baiḍāwī memperhatikan analisis bahasa Arab dan kaidah nahwu dalam menafsirkan ayat, namun juga mengutamakan pandangan Asy'ariyah dan fiqh Syafi'iyah. Karya ini dianggap lebih menonjol dalam analisis
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
Kontribusi Al-Baiḍāwī pada Tafsir Linguis-Teologis
Pada dasarnya, al-Baiḍāwī dalam menyusun Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-
Ta’wīl tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh para penafsir sebelumnya. Al-
Badawi mengadopsi metode yang digunakan oleh az-Zamakhsyari dalam
mengintegrasikan pembahasan ayat atau surat dengan ayat atau surat lain secara
linguistik sebagaimana digunakan dalam Al-Kasysyāf. Dalam catatan Gabriel
Fouad Haddad, al-Baiḍāwī juga terpengaruh pandangan al-Rāzī dalam Mafātih al-
Gaib terkait penggunaan multidisiplin keilmuan—seperti ilmu kalam, hikmah,
dan ushuluddin—untuk menafsirkan ayat. Begitu juga, beberapa kali al-Baiḍāwī
merujuk pada Mufradāt al-Qur’ān karya al-Rāgib al-Aṣfihānī.
Az-Zuhailī berpendapat bahwa Anwārut Tanzīl merupakan kitab tafsir
yang memadukan al-ma’tsūr (riwayat) dan al-ra’yi (akal) atau perpaduan antara
tafsir dan ta’wil yang berpegang pada kaidah-kaidah bahasa Arab. Sejalan dengan
hal itu, Haddad juga menjelaskan bahwa al-Baiḍāwī tidak menggantungkan semua
penafsirannya kepada hadits atau riwayat. Ia menggunakan pendekatan linguistik,
melakukan analisis stilistika, dan memberikan kritik. Ia melakukan tarjih atas
makna-makna lafal dengan menunjukkan bukti-bukti. Haddad menjelaskan bahwa
karya al-Baiḍāwī tersebut merupakan produk tafsir yang dikemas melalui
gramatika dan gaya bahasa Arab, yakni meliputi aspek linguistik, retorika, dan
semantik, dengan mengedepankan konsep i’jāz.
Aspek linguis dalam Anwārut Tanzīl misalnya bisa dilihat pada penafsiran
al-Baiḍāwī atas QS. al-Fatiḥah [1]: 2, yakni pada kata al-ḥamdu. Al-Baiḍāwī
menjelaskan bahwa al-ḥamdu bermakna pujian atau penghormatan atas keindahan
yang bebas (al-jamīl al-ikhtiyārī), dan berbeda dengan al-madḥ yang menurutnya
berarti pujian akan keindahan saja. Kemudian, ia menjelaskan makna al-syukr,
yakni penerimaan nikmat secara perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Ia lantas
mengutip sabda Nabi yang menjelaskan bahwa al-hamdu (pujian) merupakan
pokok dari syukur. Selain itu, al-Baiḍāwī juga mengulas i’rab ayat, dan
menunjukkan faedah pemaknaan yang berasal dari kaidah nahwu. Ia menjelaskan
bahwa penggunaan alif-lam (ta’rīf) dalam kata al-ḥamdu ialah lil jinsi (untuk
jenis), yang berarti penunjuk (isyārah) atas pengetahuan manusia terkait hakikat
pujian, atau li al-istigrāq (menghabiskan jenis) bahwa seluruh pujian hanyalah
milik-Nya. Ia sering memulai penjelasannya atas ayat dengan menunjukkan
kemungkinan-kemungkinan pemaknaan dan perbedaan dengan lafal lain, serta
mengupas kedudukan kata dalam kalimat, i’rab, dan pengaruh kaidah-kaidah
nahwu.
Haddad melihat bahwa, ketika al-Baiḍāwī menganalisis ayat atau lafal, ia
juga memperhatikan pandangan mazhab nahwu Basrah dan Kuffah, bahkan
membandingkan keduanya. Kemudian, pengarang Anwārut Tanzīl tersebut juga
tidak hanya merujuk qiraat yang mutawattir ketika menjelaskan ayat, tetapi ia
menaruh perhatian pula kepada riwayat-riwayat qiraat yang syaż.
Adapun pada wilayah tafsir teologis, az-Zuhailī menyatakan bahwa al-
Baiḍāwī menjadikan dasar-dasar pandangan ahlus sunnah sebagai pijakan. Ia
juga, misalnya, menunjukkan perbedaan pandangan antara Mu’tazilah, Khawarij,
dan Asy’ariyah terkait suatu topik, kemudian mengunggulkan pandangan
Asy’ariyah. Di sisi lain, ketika berhadapan dengan ayat fiqh, al-Baiḍāwī
mengambil posisi sebagai pendukung Syafi’iyah, seperti ketika ia memberikan
komentar atas kata qurū‘ pada QS. al-Baqarah [2]: 228.
Selain itu, ketika menafsirkan konsep iman dalam QS. al-Baqarah [2]: 3,
al-Baiḍāwī juga sangat terlihat menonjolkan dan mengunggulkan konsep iman
sebagaimana dipercaya oleh kalangan Asy’ariyah. Bahkan, meskipun al-Baiḍāwī
menyajikan pandangan dari Muktazilah dan Khawarij, ia tampak seperti hendak
menunjukkan kelemahan pemahaman kedua kelompok tersebut dalam memahami
konsep iman. Al-Baiḍāwī menguatkan pendapatnya dengan memaparkan dalil dari
ayat-ayat lain yang berisi penegasan keimanan di hati, seperti al-Mujadilah (58):
22, an-Nahl (16): 106, al-Maidah (5): 41, dan al-Hujurat (49): 41. Kemudian,
amal shalih mengiringi keimanan yang sudah tertancap di hati, serta ikrar
menurutnya terletak bersamaan dengan pembenaran dalam hati.
Al-Baiḍāwī dalam Anwārut Tanzīl beberapa kali juga cukup keras
mengkritik pandangan Syi’ah, salah satunya ialah ketika menafsirkan ahl al-bait
pada al-Aḥzāb [33]: 33. Menurutnya, ahl al-bait pada ayat tersebut bukan
bermakna Fatimah, Ali, dan Hasan serta Husain, melainkan nida’ (panggilan) atau
madḥ (sanjungan). Menurutnya, pemahaman kaum Syi’ah bahwa ayat tersebut
menunjukkan ke-ma’ṣūm-an ahlul bait tidak memiliki dasar yang kuat. Ia juga
memberikan kritik pedas terhadap Muktazilah dalam memandang status orang
fasik dalam QS. al-Baqarah [2]: 26, bahwa orang fasik menempati tempat antara
mukmin dan kafir.
Berdasarkan konten kitab, Anwārut Tanzīl terbilang sangat menonjol
dalam hal linguistik. Ia memang terpengaruh oleh az-Zamakhsyari dalam hal
penyajian tafsir yang diulas dari sisi linguistiknya, dan pengarang Al-Kasyaf
tersebut banyak dipengaruhi oleh pandangan al-Jurjānī. Meskipun demikian, al-
Baiḍāwī juga banyak mengkritik penafsiran az-Zamakhsyari, atau menambahkan
pandangan lain, dengan memperhatikan analisis linguistik, seperti ketika
menafsirkan al-magḍūb dan al-ḍāllīn.
Haddad melihat bahwa Anwārut Tanzīl bahkan lebih unggul dari Al-
Kasyaf dalam beberapa hal. Pertama, lebih jelas dalam memaparkan diskusi
terkait ushul fiqh dari ayat terkait. Kedua, al-Baiḍāwī dalam karyanya tampak
lebih menguasai intra-tekstualis al-Qur’an dan bukti-bukti inter-tekstualis dengan
hadits. Ketiga, lebih berhasil menunjukkan implikasi hukum/fiqh dari hadits-
hadits yang terkait, lebih khususnya dari sudut pandangan Syafi’iyah dan
beberapa Hanafiyah. Keempat, lebih kuat dalam menjelaskan ijāz balāgī al-
Qur’an. Kelima, dalam melakukan analisis sintaksis dan etimologis, al-Baiḍāwī
merujuk lebih banyak referensi tafsir untuk dipertimbangkan, sehingga
menghasilkan tafsir yang sejalan dengan tafsir-tafsir itu, bahkan yang naqli.
Berbeda dengan az-Zamakhsyari yang berkiblat pada Abū Alī al-Fārisi dan Ibnu
Jinni yang tidak begitu memerhatikan tafsir-tafsir lain.
Selain itu, pada ayat-ayat yang bersinggungan dengan teologi, al-Baiḍāwī
tidak absen untuk mengunggulkan pandangan Asy’ariyah, bahkan beberapa kali
melemparkan kritik kepada pemahaman dari kelompok di luar Asy’ariyah, apabila
sangat bertentangan. Ia juga beberapa kali mengunggulkan pandangan fiqh
Syafi’iyah ketika berhadapan dengan ayat yang diperdebatkan secara fiqh. Hal ini
agaknya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa ia pengikut serta pendukung
Asy’ariyah-Syafi’iyah sebagaimana keluarganya.
Anda mungkin juga menyukai
- Tafsir Al AlusiDokumen5 halamanTafsir Al AlusiMuhammad Raa KinanaBelum ada peringkat
- 873 3162 1 PBDokumen26 halaman873 3162 1 PBaisha rabihahBelum ada peringkat
- Analisis Quran Hadis Kb1-4Dokumen12 halamanAnalisis Quran Hadis Kb1-4Pemdes ArjawinangunBelum ada peringkat
- 1633 4474 1 PBDokumen22 halaman1633 4474 1 PBtemumaknaotentikBelum ada peringkat
- LK - Resume Pendalaman Materi PPG 2022Dokumen9 halamanLK - Resume Pendalaman Materi PPG 2022Oops DapodikBelum ada peringkat
- Terjemah, Tafsir, TakwilDokumen21 halamanTerjemah, Tafsir, TakwilCholqi ChoirunnisaBelum ada peringkat
- Analisis Al-Quran HadisDokumen17 halamanAnalisis Al-Quran HadisSyabiman mpdBelum ada peringkat
- Ilmu TafsirDokumen19 halamanIlmu TafsiraljohanBelum ada peringkat
- LK - Resume Pendalaman Materi PPG 2022 Al - Qur - An Hadits KB 2 Amarulloh AnsyoriDokumen6 halamanLK - Resume Pendalaman Materi PPG 2022 Al - Qur - An Hadits KB 2 Amarulloh AnsyoriAvam YantoBelum ada peringkat
- 247-Article Text-437-1-10-20200218Dokumen18 halaman247-Article Text-437-1-10-20200218Skyzl 5555Belum ada peringkat
- Makalah Ulumul Hadits II (Sulfika Saputri)Dokumen11 halamanMakalah Ulumul Hadits II (Sulfika Saputri)Sulfika SaputriBelum ada peringkat
- Fahmu Nusus Musytarok, Muthlaq, MuqayyadDokumen18 halamanFahmu Nusus Musytarok, Muthlaq, Muqayyadjwf1tyBelum ada peringkat
- Ulumul Quran 7Dokumen16 halamanUlumul Quran 7Madinah Adawiyah100% (1)
- Tafsir Bil Ra'yiDokumen14 halamanTafsir Bil Ra'yiWinonaBelum ada peringkat
- LK - RESUME PENDALAMAN MATERI PPG 2022 QURDIS KB 2 OkDokumen8 halamanLK - RESUME PENDALAMAN MATERI PPG 2022 QURDIS KB 2 OkBachtiar ImaniBelum ada peringkat
- Macam Macam TafsirDokumen17 halamanMacam Macam TafsirhasanBelum ada peringkat
- Idar Yanti 18.1115 Abu HayyanDokumen5 halamanIdar Yanti 18.1115 Abu HayyanIdar Yanti IAT-18Belum ada peringkat
- Review Kitab Tafsir Al-BaidhawiDokumen9 halamanReview Kitab Tafsir Al-BaidhawiBambang JanuismadiBelum ada peringkat
- 778-Article Text-1683-1-10-20211218Dokumen23 halaman778-Article Text-1683-1-10-20211218Syukron Ma'munBelum ada peringkat
- Ar Rawiyah Bil MaknaDokumen11 halamanAr Rawiyah Bil Maknaronna rosshitaBelum ada peringkat
- Gaya Bahasa Tauriyah Dalam Al-QuranDokumen14 halamanGaya Bahasa Tauriyah Dalam Al-Quranelis hadijahBelum ada peringkat
- Tafsir, Ta'Wil Dan TarjamahDokumen23 halamanTafsir, Ta'Wil Dan Tarjamaharinisrimulyani13Belum ada peringkat
- Ilmu Tafsir LandungDokumen7 halamanIlmu Tafsir LandungAndhikaBelum ada peringkat
- Konsep Tafsir, Ta'wil Dan Hermenutika MakalahDokumen8 halamanKonsep Tafsir, Ta'wil Dan Hermenutika Makalahtoyyibatun nazirohBelum ada peringkat
- Makalah Ushul FiqihDokumen11 halamanMakalah Ushul FiqihrhieckyBelum ada peringkat
- 4017 10284 1 PBDokumen16 halaman4017 10284 1 PBHarfinBelum ada peringkat
- Takhrij HaditsDokumen31 halamanTakhrij HaditsBenny Fitra100% (1)
- Tafsir TahliliDokumen10 halamanTafsir TahliliNanik WidayatiBelum ada peringkat
- Kritik Matan HadisDokumen16 halamanKritik Matan HadisfazaBelum ada peringkat
- 136 266 1 SMDokumen13 halaman136 266 1 SMBudi Hasan Medan NstBelum ada peringkat
- Path Resume6486805384a03Dokumen7 halamanPath Resume6486805384a03Siti KarimahBelum ada peringkat
- Memahami Al Qur'anDokumen18 halamanMemahami Al Qur'anNur Muhammad Al ArrobyBelum ada peringkat
- Analisis Tafsir Maud'ui Baqir ShadrDokumen23 halamanAnalisis Tafsir Maud'ui Baqir ShadrAramdhanPermanaBelum ada peringkat
- Nabilatul Adawiyah - 221411086 - Qawa'id TafsirDokumen7 halamanNabilatul Adawiyah - 221411086 - Qawa'id TafsirNabilatul AdawiyahBelum ada peringkat
- KB 2 Modul 6 AnalisisDokumen5 halamanKB 2 Modul 6 AnalisisSri HandayaniBelum ada peringkat
- Makalah Muradif Dan MusytarakDokumen7 halamanMakalah Muradif Dan MusytarakIlham maulanaBelum ada peringkat
- Makalah Muradif Dan MusytarakDokumen7 halamanMakalah Muradif Dan MusytarakIlham maulanaBelum ada peringkat
- 54-Article Text-488-2-10-20190613Dokumen16 halaman54-Article Text-488-2-10-20190613Muhammad FuadiBelum ada peringkat
- Mengenal Lebih DekatDokumen9 halamanMengenal Lebih DekatBaii MubaiBelum ada peringkat
- Makalah Studi Al-QuranDokumen10 halamanMakalah Studi Al-Qurankorban korbanBelum ada peringkat
- Studi Kitab Tafsir Kel.6Dokumen10 halamanStudi Kitab Tafsir Kel.6Tsania ArifadaBelum ada peringkat
- Al Dakhil Dalam Tafsir Mafatih Al GhaibDokumen28 halamanAl Dakhil Dalam Tafsir Mafatih Al GhaibNur FajriyyahBelum ada peringkat
- Al Riwayah Bi Al Ma'Na Dan ImplikasinyaDokumen22 halamanAl Riwayah Bi Al Ma'Na Dan ImplikasinyaIbnu MaulanaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen10 halamanBab Iighina100% (1)
- Al-Dakhil Al-LughawiDokumen16 halamanAl-Dakhil Al-LughawiNur Fiatin HafidhBelum ada peringkat
- LK - 3Dokumen3 halamanLK - 3sariBelum ada peringkat
- KB 3-Pendekatan Dan Metode PenafsiranDokumen5 halamanKB 3-Pendekatan Dan Metode PenafsiranFaidly sawBelum ada peringkat
- Studi Hadist Kel.11Dokumen9 halamanStudi Hadist Kel.11Diky Dwi SugiartoBelum ada peringkat
- Analisa QurdisDokumen4 halamanAnalisa QurdisNur syamsiahBelum ada peringkat
- TAFSIRDANTAKWILDokumen20 halamanTAFSIRDANTAKWILmukidiotwBelum ada peringkat
- Qath'Iy Dan Zhanniy Dalam PerspektifDokumen18 halamanQath'Iy Dan Zhanniy Dalam PerspektifReni AnggrainiBelum ada peringkat
- KB 1-Al-Quran Dan Metode MemahaminyaDokumen6 halamanKB 1-Al-Quran Dan Metode Memahaminyareni pemalangBelum ada peringkat
- Makalah Kritik MatanDokumen14 halamanMakalah Kritik MatanPondok Pesantren IANATUT THOLIBIN - PUNGGINGBelum ada peringkat
- Macam-Macam Dan Corak Tafsir-Irna Kel 2Dokumen16 halamanMacam-Macam Dan Corak Tafsir-Irna Kel 2Irna IrawanBelum ada peringkat
- Bab I PDFDokumen9 halamanBab I PDFNazmi Qolbi ABelum ada peringkat
- RESUME KB 2 Al-Qur'an Dan HadisDokumen7 halamanRESUME KB 2 Al-Qur'an Dan HadisHolli OongBelum ada peringkat
- Perbedaan Tafsir Takwil Dan TarjamahDokumen14 halamanPerbedaan Tafsir Takwil Dan TarjamahPesantren Entrepreneur Darul MusthofaBelum ada peringkat
- Tafsir SamarqandiDokumen13 halamanTafsir SamarqandiLUTHFIBelum ada peringkat
- 1986 5180 2 PB PDFDokumen11 halaman1986 5180 2 PB PDFAnang LastBelum ada peringkat