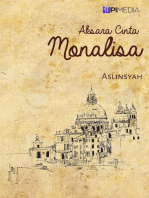Puisi-Puisi Ws. Yanto.
Diunggah oleh
YantJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Puisi-Puisi Ws. Yanto.
Diunggah oleh
YantHak Cipta:
Format Tersedia
“GELANDANGAN DI NEGERI BAYANGAN”
Riuh siar pemangsa berkeliaran
Bergentayangan di belakang lakon tanah bangsa.
Potret cukong berdasi melangit dalam layar kaca mata rakyat.
Lantas, Jeruji besi jadi keagungan korup dan timpang sebelah pada kritik elit bawahan.
Barisan punggawa muda hendak menyoal keresahan,
Malah di tuding dan di belai dengan haluan etik,
Hingga karam pada ruang.
Suasana sakralpun segera terulang,
Memboikot tatanan rezim di orde kelam.
Among negeri malah terbantai oleh para tangannya sendiri.
Hiduppun berantai dengan segala corak ambiguitas antara kelaparan dan kematian.
Sampai kapan kita jadi gelandangan di negeri bayangan?
Resah berujung pasrah,
Hianat menunggu laknat,
Rakyat semakin sekarat,
Konglomerat semakin berpangkat.
Kapan negeri ku kembali nyata tanpa layar kaca?
Kapan negeri ku bebas tak berbekas dari polemik tak berkelas?
Kapan negeri ku kembali pijar tanpa kata-kata menjalar?
Aku hanya pemuda yang haus akan hal itu!
Ingin mengulas kembali kenikmatan pentas usang,
Dan ingin kembali memikat haluan belajar yang bernalar, bukan berlayar.
“SERABUT”
Propaganda sabda bergentayang dari hujan yang tak pernah sumbang untuk menyiarkan arti
pelangi.
Entah melukis pancaroba dengan daun kemarau atau mengikis batu tanpa luka.
Aku bisu dalam medan yang curam
Penafsiran terlalu lekang terbawa arus muara ke pelosok rimba.
Jalanannya penuh akar yang sulit di sebrangi dan arahpun pudar sebab retorika logika
bersemayam.
Lantas kapan?
Pertanyaan lahir dari Ikhwal naluri terdalam.
Aku masih bertanya-tanya tentang perahu yang hanya berpijak di tepi pantai,
Laut setia menunggunya dengan warna yang masih kelabu bukan membiru,
Dan malam tak lelah menemani di gubuk tak berpenghuni.
Pekaranganmu teduh,
Sedangkan pagarku masih utuh walau arwahnya mati,
Menyisakan kuburan dengan batu nisan bertuliskan “wafatnya bernafas dan hidupnya
bermayat”
Jika langit masih menjuntai dan bumi terpijakkan,
Maka masih ada pertempuran yang harus terbalaskan.
“MAYAT”
Propaganda rasa semu tiada temu
Hengkang jadi abu tak kunjung membiru.
Roda-roda makna jadi persinggahan semata.
Lantas kecamuk sanubari tak berpatri di suluk bumi.
Saya tak bisa bernostalgia di aksara Plato dalam sinar pemikiran,
Juga tak seharmoni suara Aristoteles dengan bunga pekerjaan,
Semuanya tinggal wayang dan bayangan di perlintasan,
Menyisihkan keramaian yang membungkam pelataran bak kuburan.
“TIRO GIPA”
Kesunyian mentari berkiprah di anggunnya alam
Membingkai haluan rindu dalam nafas
Serta menyuguhkan lirik dansa dari burung yang mengangkasa.
Anginpun memeluk mesra pada sebeluk-beluk rongga nyawa
Mendampingi sederet tebing petilasan
Mengkiprahkan akal yang lama sumbang.
Namun detikpun mendorong kepincangan
Dan membawanya mengelabuhi lautan.
Revolusi rasa kini kembali memikat hati.
Kembali mengkolaborasikan nuansa dan suasana.
Inikah rindu?
Inikah mati suri?
Inikah kasih yang kembali mengasihi?
Dogma pertanyaanpun berkeliaran
Bermula dari lembah tiro gipa yang membawa saya pada kenikmatan dan ketulusan.
“PENTAS”
Setiap persimpangan jalan
Wangi mawar bersemayam
Mengalun bersama rinai hujan kenangan.
Kenangan bersama kedua bujang bersimbol keris dari pelosok pulau.
Berbagai pentas hidup di alurkan
Melukis seni di atas tungku api
Lantas kerontang pilu menggebu.
Berkolaborasi rasa di pergulatan tangan,
Memadukan belokan jadi persinggahan.
Kak...
Inikah nikmat Tuhan?
Lantas ketiadaan menjadi penghambaan.
“SYURGA”
Haluan keasingan tiba-tiba mepersunting nyawa yang tak berdaya,
Membawa ketenangan dengan aroma mawar.
Rasa terbengkalai dalam kesunyian angan
Hingga aku tak mampu melukis hampa dan suka.
Badai datang tanpa merobohkan
Melainkan menyulam syahdu tanpa abu.
Aku masih melangit dengan alam dan tak sadar akan gemulai sanggar pembuangan.
“TERATAI”
Rantingku sedang menyapa teras sinar yang bermukim di langit hitam,
mengkolaborasikan simponi tangan perkenalan atas dasar ke esaan.
Mereka seakan lembab membawa nuansa perairan yang melukis tentang aksara hujan tanpa
mengagungkan api dalam sukmanya yang berkobar.
Celoteh semesta damaikan ruang
Lantas mengerti bahwa ritual panca dasar telah terbuka pada lalang yang tak kenal siapa,
hanya mengisyaratkan arwah persaudaraan yang lekat membumi dan mengharumi.
Disitulah aku kembali berdiskusi pada tanah lapang yang telah lama lekang. Membahas
perihal ciuman dasar pada tubuh yang menjadikan rindangnya dedauanan sebagai bukti bisu
atas gerakan baru.
“Rompi terkadang membius perbincangan halaman, seakan mengsakralkan duri yang berada
di lingkar hitam”
Khotbah perihal kalbu menjadi tameng yang harus kupijaki, entah badai yang memperseni
atau sapa gelombang di kelak hari.
Semoga sabdaku bisa mengarungi desir warga hingga tuntas memuncak 2 tahun lamanya.
Sebab perihal diri harus terkafani sebagai penopang aksi hidup, agar engkau tak tumbang jika
terhakimi.
Yogyakarta, 2022.
Anda mungkin juga menyukai
- Biar Kumpulan Puisi Nanang SuryadiDokumen88 halamanBiar Kumpulan Puisi Nanang SuryadiTiar Rahman100% (1)
- Puisi UF Ke 14Dokumen6 halamanPuisi UF Ke 14SN KhadeejahBelum ada peringkat
- Adoc - Pub - Biar Kumpulan Puisi Nanang SuryadiDokumen88 halamanAdoc - Pub - Biar Kumpulan Puisi Nanang SuryadiAditya Fajar Sentosa WibawaBelum ada peringkat
- Menari Dalam BayanganDokumen4 halamanMenari Dalam BayanganBudi SetiyonoBelum ada peringkat
- Puisi AfdalDokumen8 halamanPuisi AfdalRiski NovitaBelum ada peringkat
- Merpati Putih DatangDokumen42 halamanMerpati Putih DatangMaman RegalBelum ada peringkat
- Bahasa IndonesiaDokumen21 halamanBahasa IndonesiaIsnadiarBelum ada peringkat
- 15 Puisi Tentang Kekuasaan PolitikDokumen93 halaman15 Puisi Tentang Kekuasaan PolitikMoentero De AhmadBelum ada peringkat
- PUISI RadharDokumen31 halamanPUISI RadharHidayat SyahPutraBelum ada peringkat
- Puisi Untuk Peserta LombaDokumen13 halamanPuisi Untuk Peserta LombaAnggara DaniBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi LombaDokumen5 halamanKumpulan Puisi LombaMarshela Aida HandayaniBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi PekikDokumen13 halamanKumpulan Puisi PekikpekiksasiniloBelum ada peringkat
- Antologi Puisi Karya Tia MurdianingsihDokumen28 halamanAntologi Puisi Karya Tia MurdianingsihBahrudin KholiqBelum ada peringkat
- PuisiDokumen4 halamanPuisiCecep SanusiBelum ada peringkat
- Puisi Puisi Koran Tempo46Dokumen217 halamanPuisi Puisi Koran Tempo46Hagai HutabalianBelum ada peringkat
- Percakapan SunyiDokumen4 halamanPercakapan SunyiBudi SetiyonoBelum ada peringkat
- Puisi WS RendraDokumen60 halamanPuisi WS RendraMukhlis AminullahBelum ada peringkat
- Kumpulan-Puisi (1) - 1Dokumen7 halamanKumpulan-Puisi (1) - 1TangguhspBelum ada peringkat
- Kumpulan PuisiDokumen71 halamanKumpulan PuisiichigoadtBelum ada peringkat
- Adimas ImanuelDokumen17 halamanAdimas ImanuelMuhammad Hendrawan100% (1)
- Puisi Puisi NgeriDokumen4 halamanPuisi Puisi NgeriArdian Rizardhi SatyagrahaBelum ada peringkat
- Pada Matamu Yang BeningDokumen4 halamanPada Matamu Yang BeningBudi SetiyonoBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi-Puisi Chairil AnwarDokumen65 halamanKumpulan Puisi-Puisi Chairil Anwarhennyazalea9434Belum ada peringkat
- Ebook Kumpulan Puisi Ws RendraDokumen62 halamanEbook Kumpulan Puisi Ws RendraarfiBelum ada peringkat
- Biografi Toto Sudarto BachtiarDokumen18 halamanBiografi Toto Sudarto BachtiarAliyyah FarhanaBelum ada peringkat
- 15 Puisi Tentang Kekuasaan PolitikDokumen90 halaman15 Puisi Tentang Kekuasaan PolitikMiskari AhmadBelum ada peringkat
- Kumpulan Karya Puisi Ws RendraDokumen57 halamanKumpulan Karya Puisi Ws RendraZa Bhie50% (2)
- Angkatan PuisiDokumen10 halamanAngkatan PuisihapaniBelum ada peringkat
- MerdekaDokumen11 halamanMerdekaAmran Che MehBelum ada peringkat
- PintakuDokumen2 halamanPintakuiwansyah nsBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi Toto Sudarto BachtiarDokumen16 halamanKumpulan Puisi Toto Sudarto BachtiarLukito WidhartonoBelum ada peringkat
- Cerita Pendek Beserta MajasDokumen9 halamanCerita Pendek Beserta MajasDaniel PutraBelum ada peringkat
- Dzikir ParasetamolDokumen1 halamanDzikir ParasetamolQomari-SMADA100% (2)
- Kumpulan Puisi Reformasi - Indra TjahyadiDokumen7 halamanKumpulan Puisi Reformasi - Indra TjahyadiReza MuhammadBelum ada peringkat
- Kumpulan PuisiDokumen12 halamanKumpulan PuisiRuli Insani AdhityaBelum ada peringkat
- Puisi RendraDokumen9 halamanPuisi RendraEko TriyantoBelum ada peringkat
- Aku Datang Dari Balik Kabut HitamDokumen8 halamanAku Datang Dari Balik Kabut HitamIRHAMNA MULIABelum ada peringkat
- Koleksi PuisiDokumen45 halamanKoleksi PuisiKaana BihaviaBelum ada peringkat
- Kumpulan Sajak AGUNG GEMA NUGRAHA NYANYIAN CINTA GELANDANGANDokumen67 halamanKumpulan Sajak AGUNG GEMA NUGRAHA NYANYIAN CINTA GELANDANGANagung gemaBelum ada peringkat
- Pilihan Puisi FS 2019 UmumDokumen8 halamanPilihan Puisi FS 2019 Umumbening anjaswaraBelum ada peringkat
- Syair Duka Arya DwipanggaDokumen6 halamanSyair Duka Arya DwipanggaMi ColokBelum ada peringkat
- PuisiDokumen9 halamanPuisiNurbaitiBelum ada peringkat
- Aku Butuh Sedikit Waktu Untuk Memulainya Lagi. UntukDokumen10 halamanAku Butuh Sedikit Waktu Untuk Memulainya Lagi. Untukanggun dwi cahya dani saputriBelum ada peringkat
- Puisi Cinta Kahlil GibranDokumen6 halamanPuisi Cinta Kahlil GibranFathurRachman100% (1)
- Gelegar Suara Kalbu: Puisi LangitDokumen79 halamanGelegar Suara Kalbu: Puisi LangitMuamar Baron AlgadriBelum ada peringkat
- Antologi Puisi Charil Anwar & WS Rendra - eBookWaveDokumen66 halamanAntologi Puisi Charil Anwar & WS Rendra - eBookWaveimam budiBelum ada peringkat
- Kumpulan Sajak (LOMBA)Dokumen12 halamanKumpulan Sajak (LOMBA)Ibra MahendraBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi SMPDokumen11 halamanKumpulan Puisi SMPRafki TiskaBelum ada peringkat
- Puisi JufriDokumen25 halamanPuisi JufrifathBelum ada peringkat
- Puisi Pablo NerudaDokumen5 halamanPuisi Pablo NerudaIlham AkbarBelum ada peringkat
- Lomba Puisi Bulan Bahasa 2023Dokumen4 halamanLomba Puisi Bulan Bahasa 2023JordiBelum ada peringkat
- Materi Lomba Puisi PerjuanganDokumen9 halamanMateri Lomba Puisi PerjuanganNur H. TauchidBelum ada peringkat
- Yoyo - Kumpulan SajakDokumen9 halamanYoyo - Kumpulan Sajakyogazuara1972Belum ada peringkat
- Antologi PuisiDokumen26 halamanAntologi Puisivenno akbarBelum ada peringkat
- Antologi Puisi SmaDokumen13 halamanAntologi Puisi Smamila RahmawatiBelum ada peringkat