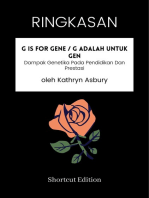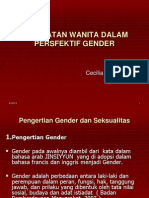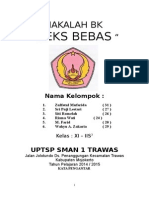Paper - Gender, Sexual Orientation, and Social Inequality
Diunggah oleh
rosalia trimawardani0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
19 tayangan13 halamanDokumen tersebut membahas tentang isu gender dan orientasi seksual dalam konteks ketimpangan sosial. Beberapa perspektif dijelaskan seperti biologis, fungsionalis, konflik, dan interaksional untuk melihat perbedaan gender dalam masyarakat. Proses sosialisasi gender melalui keluarga, sekolah, dan media juga diuraikan. Dokumen berakhir dengan menyatakan bahwa walaupun mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah wanita,
Deskripsi Asli:
Judul Asli
PAPER_GENDER, SEXUAL ORIENTATION, AND SOCIAL INEQUALITY
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniDokumen tersebut membahas tentang isu gender dan orientasi seksual dalam konteks ketimpangan sosial. Beberapa perspektif dijelaskan seperti biologis, fungsionalis, konflik, dan interaksional untuk melihat perbedaan gender dalam masyarakat. Proses sosialisasi gender melalui keluarga, sekolah, dan media juga diuraikan. Dokumen berakhir dengan menyatakan bahwa walaupun mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah wanita,
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
19 tayangan13 halamanPaper - Gender, Sexual Orientation, and Social Inequality
Diunggah oleh
rosalia trimawardaniDokumen tersebut membahas tentang isu gender dan orientasi seksual dalam konteks ketimpangan sosial. Beberapa perspektif dijelaskan seperti biologis, fungsionalis, konflik, dan interaksional untuk melihat perbedaan gender dalam masyarakat. Proses sosialisasi gender melalui keluarga, sekolah, dan media juga diuraikan. Dokumen berakhir dengan menyatakan bahwa walaupun mayoritas penduduk Amerika Serikat adalah wanita,
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 13
GENDER, SEXUAL ORIENTATION, AND SOCIAL INEQUALITY
Psikologi Problematika Sosial
Offering B 2017
Dara Cessia Sukma Dewi, Masita Utami, Nurul Ashriyanti Mulyakusuma, Rosalia
Trimawardani
Seks dan gender erat kaitannya dengan isu ketimpangan sosial. Pada istilah jenis
kelamin, wanita mengalami kemajuan luar biasa dalam menyuarakan kesetaraan
(keadilan) gender. Sepuluh tahun ke belakang wanita sudah dapat memiliki posisi di
tempat kerja, mendapatkan pendidikan yang sesuai seperti layaknya pria. Namun, belum
semuanya juga mendapatkan kesempatan tersebut, buktinya di Amerika Serikat dan
dibagian belah dunia lain juga yang masih terdapat ketimpangan sosial. Seperti
pernyataan yang masih sangat lekat pada wanita bahwa dirinya harus “patuh” kepada
kepemimpinan sumia ketika berumah tangga. Dilain hal, pada pilihan orientasi seksual
seperti kaum lesbian dan gay, masih mengalami diskriminasi yang besar dari
lingkungan sosialnya (Sullivan, 2016).
Perspektif Sosiologis Perbedaan Perilaku berdasarkan Gender
Seksualitas adalah status atribusi (anggapan personal), berarti orang lain tidak
punya kehendak atas mengenai satus yang individu pilih. Seksualitas juga sebuah status
utama, individu dikenal dan diperlakukan oleh orang lain. Selain itu gender juga
menjadi salah satu pembentuk strata dalam masyarakat. Pembenaran terhadap
ketimpangan gender ini dikuatkan oleh seksism, kepercayaan bahwa salah satu gender
harus menjadi superior atau mendominasi yang lain. Untuk melihat bagaimana bisa
gender menjadi elemen perbedaan sosial dalam masyarakat, akan dilihat dari beberapa
pandangan berikut (Sullivan, 2016).
Perspektif Biologis, melihat perbedaan terjadi karena secara lahiriah pria dan wanita di
lahirkan. Aspek yang menjadi perbedaan seperti hormone, fungsional bagian otak.
Seperti yang banyak dikatan bahwa pria lebih agresif sedangkan wanita lebih lembut,
hal ini dalam pandangan biologis disebabkan karena perbedaan hormone. Hal sama juga
terjadi dengan kemampuan pria yang cenderung pada visual-spasial sedangkan wanita
pada kemampuan verbal. Ini terjadi karena pada pria saat menggunakan kemampuan
verbal terjadi pada satu belahan (hemisphere) otak dan visual-spasial di sebelah lain,
sedangkan wanita disaat menggunakan kemampuan verbal kedua belahan otak
difungsikan. Sehingga, sebenarnya tidak ada yang benar-benar dapat dibuktikan apakah
pria lebih unggul atau tidak dalam pandangan biologis, karena manusia mengalami
pembelajaran melalui sosial juga (Sullivan, 2016).
Perspektif Fungsionalis, melihat pria dan wanita melalui peran tugasnya dalam
masyarakat. Menurut Parsons (dalam Sullivan, 2016) terdapat dua tugas dalam peran
gender, yaitu tugas instrumental dan tugas eksprsif. Tugas instrumental merupakan
aktivitas yang berfokus pada pencapaian kelompok, seperti berburu, mencari
penghidupan bagi keluarga, tugas ini terlihat menjadi tanggung jawab pria. Sedangkan,
tugas ekspresi merupakan aktivitas yang berfokus pada hubungan antar manusia, seperti
mengasuh, melayani, sehingga tugas ini terlihat menjadi tanggung jawab wanita yang
dianggap sebagi sumber reproduksi. Permasalahan sosial yang dapat terjadi dari
pandangan fungsionalis, ketika pembagian peran ini tidak lagi sama atau di butuhkan
dalam beberapa masyarakat. Contohnya, pada perkembangan zaman kelebihan
teknologi membuat pekerjaan menjadi lebih ringan atau bebas gender. Sehingga dengan
demikan, wanita dapat bekerja seperti pria tanpa adanya kebutuhan kekuatan fisik yang
dulu menjadi kelebihan pria.
Perspektif Konflik, dalam melihat peran gender antara pria dan wanita menurut Collins
(dalam Sullivan, 2016) adanya ketertarikan antara pria dan wanita dalam medominasi
dari yang lainnya sehingga disitulah terjadi konflik yang hakiki. Dalam masyarakat, pria
memiliki keuntungan akan kekuatan fisiknya untuk mendapatkan dominasi. Sehingga
wanita merasa diposisi yang lebih rendah dan menerima dominasi dari pria. Dari
pandangan konflik, perbedaan gender menjadi “lahan perang” untuk memiliki sumber
daya yang langka, seperti pekerjaan, martabat. Permasalahan sosial yang dapat terjadi
dari pandangan konflik ketika salah satu kelompok menyadari bahwa adanya
ketimpangan atau merasa dirinya dieksploitasi oleh kelompok lainnya.
Perspektif Interaksionis, memandang manusia merupakan individu yang saling
berkaitan satu dengan yang lainnya berhubungan melalui simbol yang bermakna sosial
dari masyarakat atau buadaya. Ketimpangan gender dapat dilihat dari bagaimana pria
dan wanita berinteraksi di bermacam situasi. Penggunaan simbol sosial yang paling
sering digunakan dalam masyarakat adalah bahasa. Dalam bahasa Inggris contohnya,
penyebutkan “he” atau “his” biasanya digunakan sebagai kata ganti yang dapat di
interpretasikan pada wanita dan pria, namun secara tidak langsung hal ini menyamarkan
adanya dominasi pria. Hal ini diperkuat oleh masyarakat ketika “he” selalu diingat atau
memunculkan gambaran mengenai pria. Contoh lainnya, saat wanita mendapatkan
predikat “cerewet” “ambisius” saat mengekspresikan dirinya di kelompok (campuran).
Perilaku ketimpangan gender dalam pandangan ini ada karena adanya penguatan dari
masyarakat. Selain itu permasalahan sosial terjadi karena tidak adanya consensus dan
pembagian ekspektasi yang sama terhadap peran pria dan wanita di masyarakat.
Sosialisasi Perbedaan Gender
Dalam banyak penelitian telah melahirkan bahwa perilaku kita sebagai pria dan
wanita tidak karena biologis melainkan diperoleh dari proses belajar. Sehingga, ada
perbedaan makna dari seks dan gender. Seks, merujuk pada peran biologis yang kita
miliki, alat reproduksi. Sedangkan gender, merujuk pada perilaku belajar yang
melibatkan bagaimana kita berlaku sesuai dengan tuntutan sosial, maskulin dan feminin.
Agen yang menyediakan tempat untuk kita memelajari perilaku gender ini ada tiga yang
utama, yaitu keluarga, sekolah, dan media.
Keluarga, menurut Sullivian (2016) pada usia 3 tahun anak memiliki tugas
perkembangan untuk mengenali dirinya sebagai anak pria atau wanita, yang disebut
memiliki identitas gender. Dari hasil penelitian MacDonald dan Parke serta Rossi
(dalam Sullivan, 2016) dalam keluarga anak biasa dididik dengan perilaku yang
membedakan antara anak pria dan anak wanita, seperti perilaku tegas kepada anak pria
dan perilaku lembut kepada anak wanita. Pengetahuan anak mengenai identitas gender
dapat diperoleh dari pengenalan pada penampilan fisik (gaya rambut dan gaya
berpakaian). Seperti Pujiastuti (2014) yang menyatakan bahwa tugas utama dari orang
tua adalah memperkenalkan hal-hal yang menunjang pembentukan identitas gender
sesuai dengan jenis kelamin anak, seperti misalnya nama, mainan, pakaian, gaya
rambut, warna, dan lain sebagainya. Misalnya anak wanita diberikan pakaian dan
perlengkapan berwarna merah jambu, sedang anak pria biasanya diberi permainan
seperti robot, pistol, dan sebagainya. Melalui usaha ini semuanya membentuk peran-
peran mengenai wanita yang berbeda dengan pria.
Sekolah, menjadi tempat kedua anak memperoleh pengenalan gender. Di dalam
lingkungan sekolah terdapat dua sumber utama dalam pengenalan gender, yaitu guru
dan teman sebaya. Dari penelitian yang dilakukan Bigler, et al. (2013), guru memiliki
pengaruh dalam pemberian gender stereotipe dan prasangka. Perilaku tersebut
ditampilkan dalam tiga cara yaitu, (1) Guru sebagai model perilaku gender stereotipe.
Contohnya, guru wanita cenderung menampilkan “math phobic”. (2) Guru
menampilkan perbedaan ekspektasi antara murid pria dan murid wanita. (3) Guru
memberikan label atau mengelompokkan murid, contoh sederhana pada ucapan salam
“good morning, boys and girls” yang menampilkan adanya dua jenis gender. Sedangakn
pengaruh teman sebaya dari hasil penelitian tersebut ada pada saat memilih pertemanan
saat bermain, kecenderung untuk bermain dengan sesama jenis gender merupakan
penguatan pada identitas gender anak.
Media, menjadi sangat penting dalam sosialisasi dan pembentukan identitas gender
(Sullivan, 2016). Media tradisional seperti televisi, film dan musik memungkinkan
anak-anak dan remaja untuk mengenal role model seperti pemain film, karakter kartun
dan figur olahragawan, selain itu juga memungkinkan untuk mengenal berbagai macam
pekerjaan dan tugas yang mereka kerjakan. Namun, media masih sering menampilkan
stereotip peran gender walaupun sudah ada perubahan selama bertahun-tahun, misalnya
sebagian besar pria yang digambarkan dalam prime-time mencerminkan sosok pria yang
belum menikah serta tangguh dan keren. Sedangkan, wanita digambarkan sebagai
karakter muda, tidak bekerja, terikat dengan keluarga atau dalam peran komik. Wanita
juga cenderung ditampilkan sebagai orang yang sibuk dengan romansa, kencan dan
penampilan pribadi daripadi dengan pekerjaan atau pendidikan. Musik juga menjadi
salah media untuk mengomunikasikan tentang gender, bagaimana beberapa format
musik menggambarkan stereotip gender seperti pria yang cenderung kuat, agresif,
dominan, sedangkan wanita digambarkan menarik secara fisik dan jarang digambarkan
sebagai sosok yang mandiri dan tegas. Selain itu, juga terdapat internet dan cyberworld
yang menjadi salah satu media paling interaktif. Kaum muda lebih bebas untuk memilih
apa saja yang dapat diterima oleh mereka untuk membentuk gambaran gendernya yang
tersedia di media ini melalui unggahan yang di situs jejaring sosial atau web pribadi.
Sayangnya, orangtua, sekolah atau pemimpin agama sebagai sumber dalam membentuk
identitas gender, kurang memiliki kendali dalam media ini. Kebebasan dan eksplorasi
yang ditawarkan oleh media ini mendorong kaum muda untuk mempromosikan hal-hal
negatif dan merendahkan martabat identitasnya (Sullivan, 2016).
Tingkat Ketidaksetaraan Gender di Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, mayoritas masyarakatnya adalah wanita, namun mereka
terdiri dari kelompok minoritas dan ada sejumlah kesamaan penting antara wanita dan
kelompok minoritas lainnya. Wanita masih memiliki ketidaksetaraan akses ke sumber
daya penting dan mengalami diskriminasi di berbagai bidang. Walaupun demikian, pria
juga mengalami diskriminasi yang tidak masuk akal berdasarkan jenis kelamin.
Diskriminasi Ekonomi, menurut Sullivan (2016) wanita menempati posisi yang lebih
rendah dibandingkan dengan pria dalam hamper setiap dimensi Socioeconomic Status
(SES). Terdapat 3 dimensi utama dalam SES yaitu pendidikan, pekerjaan dan
pendapatan.
1) Pendidikan. Sampai sekitar tahun 1850, hampir seluruh wanita tidak mengenyam
perguruan tinggi karena nantinya mereka hanya akan menjadi ibu rumah tangga.
Bahkan pada tahun 1873, Mahkamah Agung AS (Amerika Serikat) memutuskan bahwa
wanita Illinois dilarang untuk membuka praktek hukum dengan alasan karena mereka
perempuan. Pada tahun 1950, jumlah wanita berusia 25 tahun ke atas yang belajar di
perguruan tinggi dan yang mengejar pendidikan lanjutan, seperti doktor di AS
mengalami peningkatan drastis. Namun, pria masih melebihi sedikit dalam
mendapatkan gelar di perguruan tinggi daripada wanita. Selain itu, masih terdapat
kesenjangan di bidang pendidikan tertentu berdasarkan jenis kelamin, seperti sains,
matematika, komputer, dan teknik.
2) Pekerjaan dan Tempat Kerja. Di AS, wanita menduduki 46% dari angkatan kerja,
namun mereka hanya berada di jabatan yang lebih rendah daripada pria. Data dari
Kementrian Tenaga Kerja tahun 2013 menunjukkan bahwa wanita memegang jabatan
seperti resepsionis atau sekretaris yang memiliki pendapatan dan prestige yang lebih
renda, sedangkan pria dengan pekerjaan yang lebih baik seperti dokter atau insinyur
(Sullivan, 2016). Hal tersebut sebagai bukti adanya diskriminasi berdasarkan stereotipe
peran gender dalam merekrut karyawan. Selain itu, wanita mendapatkan lebih banyak
hambatan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kewajiban keluarga, hal tersebut
dikarenakan wanita masih diharapkan menjadi pengaruh utama dari anak-anaknya,
untuk menjaga rumah dan merawat keluarga yang sakit. Menurut Leon-Guerrero
(2018), fenomena pemisahan antara pria dan wanita di tempat kerja disebut dengan
occupational sex segregation yang memiliki 2 tipe yaitu horizontal segregation dan
vertical segregation. Horizontal segregation yaitu menunjukkan pemisahan sektor
tenaga kerja antara wanita dalam tenaga kerja nonmanual dan pria dalam tenaga kerja
manual. Sedangkan, vertical segregation yaitu meningkatkan pria dalam tenaga kerja
yang berpenghasilan terbaik dan pekerjaan di sektor tenaga kerja manual dan
nonmanual yang paling diinginkan, sedangkan wanita tetap berada di posisi
berpenghasilan lebih rendah tanpa mobilitas kerja.
3) Pendapatan. Diskriminasi gaji berdasarkaan gender atau karakteristik lainnya
tidaklah rasional. Tingkat pendapatan dapat dipengaruhi oleh kekuatan pasar yaitu
kompetitif antara penawaran dan permintaan serta bagaimana karyawan memproduksi
produk dan jasa untuk harga yang dibayar konsumen. Namun, terdapat hal yang tidak
rasional dalam menentukan gaji yaitu berdasarkan seberapa besar kekuatan dari
kelompok kerja yang berbeda dan stereotip budaya tentang perbedaan nilai pekerja. Hal
ini merupakan faktor irasional yang membuat wanita dibayar jauh lebih rendah daripada
pria. Beberapa perbedaan pendapatan antara pria dan wanita di AS merupakan fakta
bahwa pria dapat bekerja lebih lama daripada wanita, yang kemudian akan mendapatkan
senioritas dan kenaikan gaji yang menambah pendapatan pria. Berdasarkan studi dari
Departemen Pendidikan AS (dalam Sullivan, 2016), lulusan SMA tahun 1972
menunjukkan bahwa wanita sebagian besar melakukan pendidikan SMA maupun
perguruan tinggi lebih baik daripada pria, seperti menyelesaikan perkuliahan lebih
cepat. Namun, wanita mendapatkan pendapatan yang lebih rendah daripada pria dalam
hal karir bahkan wanita lebih cenderung menganggur. Studi lain yang membandingkan
antara wanita dan pria yang tidak memiliki anak dan bekerja dengan durasi yang sama,
namun masih ditemukan ketidaksetaraan gaji: hanya 7 dari 33 pekerjaan yang
memberikan gaji setara antara pria dan wanita dengan kinerja yang sama (Sullivan,
2016). Walaupun terdapat beberapa perubahan, namun kesetaraan pendapatan antara
wanita dan pria masih tidak terlalu besar.
Diskriminasi di Kemiliteran, dimana dunia kemiliteran yang identik dengan kekuatan
terlihat didominasi oleh tentara laki-laki. Meski begitu, tidak sedikit pula tentara wanita
yang ikut andil dalam bidang kemiliteran. Namun, diskrimasi terhadap wanita dalam
bidang ini belum juga terhindarkan hingga sekarang. Sekitar 14 persen dari angkatan
bersenjata diisi oleh prajurit wanita, tapi terdapat larangan untuk terjun ke medan
tempur dengan alasan bahwa mereka kurang memenuhi persyaratan fisik serta mental
yang harus dipenuhi oleh prajurit pada unit ini (Sullivan, 2016). Menurut Sullivan
(2016), tentu saja hal ini memberatkan para prajurit wanita sebab menghambat mereka
mengingat tugas pada posisi tempur merupakan salah satu cara untuk memajukan karir
mereka. Stereotip yang telah terbentuk di masyarakat, bahwa wanita tidak cukup
tangguh untuk ikut berperang dapat dipatahkan dengan fakta bahwa tentara wanita
bertugas dengan baik dan memenuhi seluruh standar bahkan beberapa dari mereka ikut
terbunuh serta ditawan oleh musuh selama perang Irak dan Afghanistan terjadi
(Sullivan, 2016). Selain itu, sekitar 75 persen publik Amerika Serikat berpendapat
bahwa mereka suka dengan wanita yang ditugaskan dalam pertempuran (Brown dalam
Sullivan, 2016). Terdapat pula para pendukung kesetaraan bagi wanita juga berpendapat
bahwa agresivitas dan kekuatan dapat dilatih, dibuktikan dengan kinerja para tentara
wanita yang tergolong baik di medan perang sehingga alasan bahwa wanita tidak bisa
“terikat” dengan unit militer dapat dipatahkan (Sullivan, 2016). Menurut Sullivan
(2016), terdapat tiga faktor yang mendukung pemanfaatan pekerja wanita di bidang
kemiliteran yaitu (1) pekerja yang semuanya relawan; (2) tempat kerja yang semakin
berteknologi tinggi; serta (3) meningkatnya feminisasi di dunia pekerjaan. Hal tersebut
tentu harus dipertimbangkan guna meluaskan kesempatan bagi wanita di semua cabang
kemiliteran.
Tipe Diskrimasi Lainnya, selain di bidang-bidang yang telah disebutkan sebelumnya,
terdapat pula bentuk diskriminasi lain. Seperti kurangnya penegakan hukum di sekitar
30 negara mengenai pemerkosaan dalam pernikahan (Marital Rape) sehingga
memberikan celah kepada suami untuk menghindari tuntutan memerkosa istri (Bergen
dalam Sullivan, 2016). Selain itu, beberapa program pensiunan di juga menunjukan
diskrimasi dengan memberi pesangon lebih kecil daripada yang mereka berikan pada
pekerja pria.
Ketidaksetaraan Gender yang Melibatkan Pria, selain perempuan, laki-laki juga
tidak luput dari diskriminasi. Hal tersebut terkait dengan mitos-mitos mengenai
maskulinitas mengenai stereotip bahwa lelaki haruslah kuat, mendominasi, tangguh,
serta tidak emosional (Kimmel dalam Sullivan, 2016). Bentuk akibat dari stereotip itu
seperti (Sullivan, 2016) lelaki cenderung menghindari pekerjaan yang dianggap identik
dengan wanita seperti perawat, sekretaris, dll. Beberapa negara memiliki undang-
undang yang menetapkan hukuman bagi pria (dan mungkin wanita lain) terhadap
penggunaan kalimat yang tidak senonoh di hadapan wanita. Selain itu, banyak
perusahaan asuransi yang cenderung mengenakan premi asuransi mobil yang lebih
tinggi pada nasabah pria karena tingkat kecelakaan mobil yang tinggi di kalangan pria
muda. Di beberapa negara, pria juga diwajibkan untuk mengikuti wajib militer.
Perspektif Global Tentang Ketidaksetaraan Gender
Ketidaksetaraan gender banyak ditemukan hampir di seluruh dunia dengan
mayoritas wanita masih tertinggal dari pria dalam hal kekuasaan, kekayaan dan peluang
yang dimiliki (Sullivan, 2016). Menurut United Nations dan World Bank (dalam
Sullivan, 2016), meskipun selama beberapa dekade terakhir semakin banyak wanita
yang memiliki pekerjaan di beberapa daerah, tapi hanya sekitar 10-20% pekerja yang
berjenis kelamin wanita di beberapa negara muslim serta mereka memiliki pekerjaan
dengan gaji rendah dan kurang bergengsi. Di Amerika Serikat, meskipun perempuan
mewakili 41% dari seluruh angkatan pekerja, mereka cenderung di-PHK lebih cepat.
Selain itu, di negara industri seperti Jepang dan Korea Selatan bahkan negara
berkembang seperti Malaysia, wanita cenderung memiliki penghasilan hanya setengah
dari gaji pria serta 62% di AS. Di bidang pendidikan, wanita cenderung memiliki angka
buta huruf yang lebih tinggi di seluruh dunia serta tertinggal dalam pendaftaran sekolah
menengah dan perguruan tinggi di beberapa negara (Sullivan, 2016). Dalam bidang
politik, di seluruh dunia memiliki anggota wanita yang sedikit yaitu hanya sekitar 19%
dari semua anggota parlemen atau kongres dunia (World Bank dalam Sullivan, 2016).
Para wanita, dengan tingkat pendidikan yang rendah, cenderung diijinkan bahkan
didorong untuk bekerja sebagai tenaga kerja dengan gaji murah seperti buruh pabrik
atau pertanian. Bahkan beberapa dari mereka memilih untuk bergabung dengan industri
seks (Sullivan, 2016).
Homoseksualitas dan Homofobia, Homoseksualitas merupakan ketertarikan secara
seksual kepada sesama jenis. Dengan masih tabunya hal, bahkan di Indonesia, banyak
dari kalangan homoseksual yang menyembunyikan orientasi seksual mereka sehingga
untuk memastikan angka butuh kehati-hatian (Sullivan, 2016). Perkiraan terbaik adalah
menurut penelitian yang dilakukan oleh Billy dkk, Lauman dkk, serta Strong, DeVault,
dan Cohen (dalam Sullivan, 2016) yaitu sekitar 1-5 % pria dewasa di Amerika Serikat
merupakan gay, sedangkan lesbian sekitar setengahnya. Bahkan, sekitar 5-25% pria
pernah melakukan hubungan homoseksual (Sullivan, 2016).
Teori Orientasi Seksual, masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana orientasi
seksual terbentuk. Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa faktor
genetik sebagian mempengaruhi terbentuknya orientasi seksual (Hamer dan Copeland;
Rahman dan Wilson dalam Sullivan, 2016). Sebagai contoh, sebuah penelitian
menunjukkan bahwa anak kembar yang memiliki materi genetik yang sama (kembar
monozigot) lebih cenderung menjadi gay daripada mereka yang kembar tidak identik
atau dua saudara yang berbagi genetik. Namun hingga saat ini belum ditemukan apa
saja materi yang diwariskan mempengaruhi orientasi seksual secara tepat. Bisa jadi,
yang diwariskan merupakan perilaku yang dapat dibentuk menjadi homoseksualitas
oleh lingkungan sekitar sehingga kecenderungan genetik tersebut dibentuk oleh
interaksi sosial. Seperti contohnya, ada anak laki-laki yang cenderung berperilaku
feminin, lalu orang sekitar bereaksi dengan mendorong cara berpikir dan
mendefinisikannya sebagai “homoseksual” (Sullivan, 2016).
Pendapat lain, menurut perspektif psikologis mengemukakan bahwa
homoseksualitas muncul akibat adanya ketidaksesuaian psikologis yang mungkin
berasal dari hubungan orangtua yang buruk (Lewes dalam Sullivan, 2016). Pada tahun
1973, American Psychiatric Association mendaftarkan homoseksualitas sebagai
gangguan mental. Namun, perspektif ini menuai banyak kritik seperti tidak
ditemukannya perbedaan kepribadian antara homoseksual dengan heteroseksual
(Sullivan, 2016). Serta banyak anak broken home yang bukanlah homoseks dan bahkan
sebaliknya, mereka yang homoseks mengakui bahwa hubungan orang tua mereka baik-
baik saja (Bell dan Weinberg; Hooker; Robinson dkk dalam Sullivan, 2016). Atas dasar
kritikan tersebut, American Psychiatric Association menghapus homoseksualitas
sebagai gangguan mental karena tidak adanya bukti ilmiah adanya penyakit kejiwaan
atau indikasi penyesuaian psikologis yang buruk (Ross, Paulsem, dan Stalstom dalam
Sullivan, 2016).
Perspektif sosiologis berpendapat bahwa faktor sosial dapat mempengaruhi
terjadinya perilaku homoseksual (Goode dalam Sullivan, 2016). Teori ini
mengemukakan bahwa homoseksual merupakan hasil dari proses belajar melalui
interaksi sosial, dimana terdapat anggapan bahwa seksualitas bersifat fleksibel dan
eksploratif seperti contohnya karena tidak dapat menyalurkan tindakan heteroseksual,
narapidana cenderung untuk berperilaku homoseksual di dalam penjara tapi akan
kembali menjadi heteroseksual ketika sudah dibebaskan (Sullivan, 2016).
Terdapat pula Teori Pelabelan yang berpendapat bahwa sebagian konsep-diri
berasal dari perlakuan orang lain sehingga apabila seseorang dilabeli sebagai homoseks
disaat belum terbentuknya identitas seksual secara jelas, maka orang tersebut akan
menerima pelabelan tersebut sehingga menciptakan stigma yang mempersulit hubungan
heteroseksual dan semakin memicu perilaku sebaliknya yaitu homoseksualitas
(Sullivan, 2016).
Reaksi Masyarakat terhadap Homoseksualitas
Sikap terhadap Homoseksualitas, secara keseluruhan, orang-orang Amerika Serikat
cenderung menunjukkan sikap negatif terhadap homoseksualitas meskipun saat ini
tampak media memperlihatkan citra positif mengenai gay dan lesbian dibandingkan
dengan masa lampau, pandangan negatif masih tersimpan di publik (Gallup Poll; Wolfe
dalam Sullivan, 2016). Sekitar 31% orang AS yang tidak setuju jika hubungan sesama
jenis dilegalkan, serta 40% percaya bahwa homoseksualitas tidak boleh dianggap
sebagai gaya hidup yang dapat ditoleransi. Mengenai hak kerja, persentasi masyarakat
yang mendukung kesetaraan untuk homoseksual semakin meningkat seiring berjalannya
waktu. Meski begitu, 5 dari 10 orang menolak bahwa kaum ini dapat dipekerjakan
sebagai pendeta serta guru sekolah dasar (Sullivan, 2016). Dan memang umumnya pria,
orang yang tua, beragama, berpendidikan, dan yang memiliki pendapatan yang rendah
serta mereka yang memiliki nilai-nilai sosial yang tradisional cenderung kurang toleran
terhadap homoseksualias (Loftus dalam Sullivan, 2016).
Sebagai negara yang menjunjung tinggi agama dan adat istiadat, Indonesia baik
dari pihak negara maupun publik masih menganggap hubungan sesama jenis sebagai hal
yang tabu. Beberapa contoh bentuk diskriminasi terhadap kaum homoseksual di
Indonesia seperti pembatalan beberapa kegiatan pertemuan organisasi LGBT akibat
ancaman dan desakan dari FPI atau Front Pembela Islam (Huda, M; Muthmainnah,
2016). Selain itu pada tahun 2017, provinsi Aceh menerapkan hukuman cambuk bagi
pasangan gay yang tertangkap oleh warga, serta di Palembang, Sumatera Selatan,
menjadi gay/homoseksual dapat dihukum dengan hukuman penjara dan denda (Yosafak
& Mulyono). Atas dasar diskriminasi tersebut, banyak kaum homoseksual memilih
untuk menyembunyikan orientasi seksual mereka. Namun dewasa ini, pengguna media
sosial terutama kaum muda menunjukkan dukungan yang semakin meningkat terhadap
kesetaraan bagi homoseksual. Akan tetapi hal tersebut belum menutup fakta bahwa
masih banyak masyarakat indonesia yang belum menoleransi hal ini.
Diskriminasi Terhadap Lelaki Gay dan Lesbian, kaum homoseksual dianggap
sebagai minoritas karena merupakan sesuatu yang menyimpang terhadap nilai
konvensional di masyarakat sehingga memunculkan banyak reaksi negatif hingga
tindakan diskriminasi. Seperti adanya tindakan kekerasan termasuk pelecehan,
intimidasi, penyerangan, hingga pembunuhan terjadi setiap tahun dengan dalih orientasi
seksual korban sebagai alasan dimana 9-24% orang homoseksual yang diserang secara
fisik berdasarkan sebuah survei (Sullivan, 2016). Bahkan pengucilan diterima oleh
kaum gay sehingga banyak memicu tindakan bunuh diri.
Bentuk diskriminasi lain ditunjukkan di bidang kemiliteran yang secara
tradisional mempertahankan kebijakan ketat yang memandang homoseksualitas tidak
sesuai dengan misi angkatan bersenjata serta dianggap mengganggu terutama ketika
harus bekerja atau bertempur bersama dengan jarak yang dekat (Frank dalam Sullivan,
2016). Namun, anggapan tersebut ditolak dengan adanya bukti bahwa ribuan tentara
yang memiliki orientasi seksual homoseks bekerja dengan baik, meskipun mereka
terpaksa menyembunyikan hal tersebut.
Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap kaum homoseksual, terutama
di Amerika Serikat, terdapat perlindungan eksplisit terhadap diskriminasi dalam
perumahan dan pekerjaan kepada kaum gay. Selain itu, sejak masa pemerintahan
Barack Obama mengizinkan kaum gay untuk melayani secara terbuka di militer. Meski
begitu terdapat beberapa daerah yang membatalkan perlindungan tersebut, akan tetapi
seiring berjalannya waktu terutama 40 tahun terakhir dukungan terhadap kaum
homoseksual semakin tinggi. Di Indonesia sendiri, belum ada pelegalan terhadap
hubungan homoseksual. Bahkan negara juga tidak mengakui pernikahan sesama jenis
sesuai Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi
“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.” (Sirait,
2018).
Homofobia, homofobia merujuk pada perasaan ketidaksukaan yang kuat atau prasangka
terhadap homoseksual. Lantas apa yang membuat individu atau masyarakat mengalami
homofobia dan mendiskriminasi homoseksual? Pertama, adanya sejarah dan warisan
leluhur yang memberikan konotasi negatif terhadap homoseksual, seperti pada teologi
kristen barat, homoseksualitas didefinisikan sebagai sebuah dosa. Hal tersebut
menimbulkan meningkatnya reaksi negatif dan kecaman keras di masyarakat terhadap
homoseksual hingga saat ini. Kedua, adanya norma-norma yang berkembang dalam
masyarakat, dimana individu harus berhubungan dengan lawan jenis untuk dapat
melanjutkan keturunan dan meningkatkan potensi reproduksi dalam masyarakat.
Meskipun fakta di lapangan tidak menunjukkan permasalahan mengenai kekurangan
populasi. Terkadang reaksi homofobik tidak didasarkan pada bukti melainkan
dikarenakan adanya ancaman yang dirasakan terhadap norma dan nilai budaya yang
dipegang teguh. Sikap negatif tidak hanya ditunjukkan dalam konteks keagamaan,
seperti dalam teori Freud yang memandang bahwa homoseksual merupakan bentuk dari
ketidakdewasaan dan ketidakberkembangan dari seksualitas orang dewasa. Sikap
negatif negatif terhadap homoseksual menjadi mekanisme yang terus dipertahankan
untuk menunjukkan pada masyarakan perilaku apa yang dapat diterima dalam
kehidupan bermasyarakat dan konsekuensi bila melanggarnya. Ketiga, sarana bagi
remaja dan anak muda khususnya lelaki untuk mencari petualangan, kesenangan atau
melepas kebosanan. Dikarenakan mereka belum benar-benar diakui untuk dapat masuk
dalam dunia kerja orang dewasa. Keempat, adanya perasaan negatif yang kuat tentang
seksualitas manusia di mana seks dipandang kotor dan mengancam tatanan sosial.
Keberadaan komunitas homoseksual dapat memberikan perlindungan dan rasa
aman dari gangguan dan para homofobik. Selain itu, dapat membatu homoseksual untuk
hidup diantara orang-orang yang memiliki gaya hdup dan nilai yang sama. Komuntas
homoseksual dapat mencapai kedudukan tertentu dalam dunia politik. Dengan adanya
kmunitas tersebut dapat membantu menyebarkan dukungan serta penerimaan
homoseksual di masyarakat dalam berbagai cara.
Strategi untuk Mencapai Kesetaraan Gender
Terdapat beberapa upaya melalui kebijakan dan praktik sosial untuk mencapai
kesetaraa gender, diantaranya:
Gerakan feminis, dengan melakukan aksi secara kolektif mulai dari tingkat individual
hingga organisasi dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan antara wanita
dan laki-laki. Banyak gerakan feminis dilakukan di berbagai negara dengan
menyuarakan ketidaksetujuan terhadap norma atau nilai yang terlalu konservatif dan
menyebabkan ketidaksetaraan. Selain itu, juga terdapat amandemen terhadap konstitusi
dengan melarang adanya diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin. Gerakan
feminis ini juga memiliki jaringan secara global melalui organisasi internasiona non
pemerintah yang juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah memberikan
perlakuan dan perlindungan yang sama dalam berbagai hal seperti pekerjaan,
pendidikan, menyuarakan pendapat dan lain-lain.
Perubahan hukum, dengan melakukan pembentukan atau perubahan undang-undang
yang dapat membantu dalam pengurangan ketidaksetaraan gender. Seperti dengan
melarang adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan pemberian gaji yang sama
untuk nilai atau hasil yang sebanding.
Perubahan pada tempat kerja, untuk dapat meningkatkan kesempatan wanita dalam
dunia kerja, maka diperlukan regulasi pemerintah dan tindakan yang dapat mendorong
pemberi pekerjaan untuk mempekerjakan dan mempromosikan wanita, serta penting
untuk meningkatkan jumpah pekerja wanita di tempat kerja. Di mana wanita dengan
level pekerjaan yang rendah dapat mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan dalam
level pekerjaan yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesempatan untuk
mempekerjakan wanita. Selain itu, dengan dibentuknya kebijakan di tempat kerja
“ramah keluarga” yang dapat membantu individu untuk mengejar karir dan juga
menghabiskan waktu bersama keluarga. Meskipun banyak pro dan kontra dalam pada
strategi ini, namun strategi ini sangat membantu untuk dapat mengikutsertakan wanita
di dunia kerja yang sebelumnya banyak di dominasi oleh laki-laki. Dan dengan
banyaknya dukungan dari berbagai organisasi yang membantu wanita untuk dapat
bersaing di dunia kerja.
Mengubah wajah politik, dalam artian dengan mengikutsertakan wanita dalam
pemilihan posisi di dunia politik. Dengan menempatkan wanita dalam posisi kekuasaan
di sistem politik, dapat meningkatkan kesempatan wanita untuk memasuki dunia politik
di masa depan.
Aksi kolektif oleh homoseksual, dengan semakin diketahuinya homoseksual di
kalangan masyarakat saat ini, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai
gaya hidup mereka dan menumbuhkan sikap positif terhadap homoseksual. Semakin
tinggi level pendidikan pada masyarakat dapat meningkatkan penerimaan terhadap
homoseksual. Aksi kolektif yang dilakukan di arena politik memiliki pengaruh yang
besar terhadap berkurangnya diskriminasi dan kekerasan pada homoseksual, serta dapat
membuat pernikahan sesama jenis menjadi legal di beberapa negara. Selain itu, dengan
meningkatkan keterbukaan terhadap gaya hidup, dapat membantu homoseksual untuk
masuk dalam berbagai institusi kemasyarakatan.
Di Indonesia banyak pihak-pihak dari berbagai lapisan masyarakat yang turut
mengupayakan kesetaraan gender. Gerakan emansipasi wanita yang sanggat dikenal
karena sosok Raden Adjeng Kartini yang telah membuka kesempatan dan peluang besar
bagi kaum wanita di Indonesia untuk dapat mendapatkan kesetaraan terutama dalam
bidang pendidikan (Ratnawati dkk., 2019), sehingga saat ini wanita mempunyai hak
yang sama untuk memperoleh pendidikan yang juga di atur dalam Undang-Undang
Dasar 1945. Namun, dalam prakteknya, di lingkup masyarakat pedesaan khususnya di
pedalaman, masih terdapat diskriminasi terhadap hak pendidikan (Ratnawati dkk.,
2019).
Berbagai strategi telah diterapkan untuk menghasilkan keadilan dan kesetaraan
dalam masyarakat. Salah satu hasil dari gerakan feminis di Indonesia adalah dengan
dilakukannya Konferensi Internasional tentang Feminisme pertama kali di Indonesia
dengan membahas feminisme di berbagai bidang seperti agama, buruh dan pekerjaan,
kebijakan publik dan lain sebagainya yang dituangkan dalam naskah prosiding
Konferensi Internasional Feminisme: Persilangan Identitas, Agensi dan Politik (20
Tahun Jurnal Perempuan) (Yayasan Jurnal Perempuan, 2016). Selain itu, berbagai
gerakan feminis Banyak organisasi didirikan yang berfokus pada perlindungan hak dan
keadilan bagi wanita, tidak hanya itu bahkan dalam lingkup pemerintahan juga dibentuk
Komnas Perempuan dan adanya Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam sistem pemerintahan. Meskipun begitu, di Indonesia masih
belum dibentuk Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dapat
menguatkan pranata hukum Indonesia untuk mengatur isu terkait (Kusumawardhana &
Abbas, 2018).
Alasan utama yang menjadi permasalahan terjadinya ketimpangan keterlibatan
perempuan pada pasar tenaga kerja adalah kuatnya sistem patriarki di dalam budaya
Indonesia, cenderung membiarkan dominasi laki–laki terhadap perempuan bahkan
perempuan selalu saja dipandang orang kedua setelah laki-laki di dalam dinamika
bermasyarakat secara holistik maupun spesifik (Kusumawardhana & Abbas, 2018).
Meskipun saat ini mulai terjadi peningkatan di mana wanita sudah banyak dipekerjakan
dan dapat menempati posisi atau jabatan yang tinggi, namun tidak menutup kenyataan
bahwa masih banyak wanita yang belum mendapatkan hak kesetaraan dan laki-laki
lebih dipilih, serta menjadi pengambil keputusan (Kusumawardhana & Abbas, 2018).
Daftar Pustaka
Bigler, R., Hayes, A. R., & Hamilton, V. (2013). The roles of schools in the early
socialization of gender differences. Encyclopedia on Early Childhood
Development. http://www.child encyclopedia.com/
Huda, M. (2020). Merunut stigmatisasi minoritas seksual di indonesia. Rumah Cemara.
http://rumahcemara.or.id/book/merunut-stigmatisasi-minoritas-seksual-di-
indonesia/
Kusumawardhana, I., & Abbas, R. J. (2018). Indonesia di persimpangan: Urgensi
“undang-undang kesetaraan dan keadilan gender” di indonesia pasca deklarasi
bersama buenos aires pada tahun 2017. Jurnal HAM, 9(2), 153.
https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.153-174
Leon-Guerrero, A. (2018). Social problems: Community, policy, and social action
(Sixth Edition). Sage publications.
Muthmainnah, Y. (2016). Lgbt human rights in national policies. Indonesian Feminist
Journal, 4(1), 16.
Pujiastuti, T. (2014). Peran orang tua dalam pembentukan identitas gender anak. Syi’ar,
14(1), 53-62. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/
Ratnawati, D., Sulistyorini, S., & Abidin, A. Z. (2019). Kesetaraan gender tentang
pendidikan laki-laki dan perempuan. Jurnal Harkat : Media Komunikasi
Gender, 15(1), 10-23–23. https://doi.org/10.15408/harkat.v15i1.13436
Sirait, T. M. (2018). Menilik akseptabilitas perkawinan sesama jenis di dalam konstitusi
indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(3), 620-643.
Sullivan, T. J. (2016). Introduction to social problems (Tenth edition). Pearson.
Yayasan Jurnal Perempuan (Ed.). (2016). Prosiding konferensi internasional
feminisme: Persilangan identitas, agensi, dan politik: 20 tahun jurnal
perempuan = Proceeding of international conference on feminism: Intersecting
identities, agency & politics: 20 years jurnal perempuan. Yayasan Jurnal
Perempuan.
Yosafak, H., & Mulyono, G. P. (2020). Analisis fenomena perilaku penyimpangan
seksual (lgbt) di indonesia dalam pandangan hukum asasi manusia. Jurnal
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(1), 12-23.
http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i1.1633
Anda mungkin juga menyukai
- RINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyDari EverandRINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyBelum ada peringkat
- Albert Bandura dan faktor efikasi diri: Sebuah perjalanan ke dalam psikologi potensi manusia melalui pemahaman dan pengembangan efikasi diri dan harga diriDari EverandAlbert Bandura dan faktor efikasi diri: Sebuah perjalanan ke dalam psikologi potensi manusia melalui pemahaman dan pengembangan efikasi diri dan harga diriBelum ada peringkat
- Bagaimana Pendapat Mu Tentang Sekolah Yang Memberlakukan Satu Genre SajaDokumen28 halamanBagaimana Pendapat Mu Tentang Sekolah Yang Memberlakukan Satu Genre SajaMuna MufidahBelum ada peringkat
- Psikologi Perkembangan-GenderDokumen24 halamanPsikologi Perkembangan-Genderpretty sefrinta anggraeni100% (3)
- Makalah Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Dan Ruang Publik - OdtDokumen12 halamanMakalah Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan Dan Ruang Publik - Odtislamthoriqul95100% (1)
- Makalah GenderDokumen11 halamanMakalah GenderAndini WardatulBelum ada peringkat
- Proskrip YuliaDokumen5 halamanProskrip YuliaYulia SalsabilaBelum ada peringkat
- Budaya & GenderDokumen5 halamanBudaya & GenderraniBelum ada peringkat
- (A) Riswan - 200701502002Dokumen4 halaman(A) Riswan - 200701502002RiswanBelum ada peringkat
- 2018205tmpi - Bab Ii PDFDokumen60 halaman2018205tmpi - Bab Ii PDFAbdul AzisBelum ada peringkat
- Lily GenderDokumen32 halamanLily GenderumbuladoBelum ada peringkat
- Jenis Kelamin Dan GenderDokumen11 halamanJenis Kelamin Dan Gendersalsa putri fahiraBelum ada peringkat
- Psikologi Sosial - GenderDokumen11 halamanPsikologi Sosial - GenderRisda YantiBelum ada peringkat
- Makalah GenderDokumen16 halamanMakalah GenderNurfitra BakhtiarBelum ada peringkat
- Gender (Academia)Dokumen10 halamanGender (Academia)Sari Ikhlasul AmaliaBelum ada peringkat
- Gender Dalam PendidikanDokumen9 halamanGender Dalam PendidikanGytha HarahapBelum ada peringkat
- PKBK 3 Dan 4 - Being SingleDokumen36 halamanPKBK 3 Dan 4 - Being SingleekaBelum ada peringkat
- Komunikasi Dan GenderDokumen11 halamanKomunikasi Dan GenderWildan AlwiBelum ada peringkat
- Analisis Faktor Ketidakadilan GenderDokumen10 halamanAnalisis Faktor Ketidakadilan GenderAulia Nur AfifahBelum ada peringkat
- Psikologi Sosial Isu GenderDokumen27 halamanPsikologi Sosial Isu GenderChairun FilhayaniBelum ada peringkat
- Ketidak Adilan GenderDokumen15 halamanKetidak Adilan GenderAbd RahmanBelum ada peringkat
- Makalah Isu Pendidikan Hesti WiningsihDokumen13 halamanMakalah Isu Pendidikan Hesti WiningsihHestyBelum ada peringkat
- (A) Harun Syamsul - 200701552018 (Psi. Gender)Dokumen7 halaman(A) Harun Syamsul - 200701552018 (Psi. Gender)Harun SyamsulBelum ada peringkat
- Analisis Hubungan Antara Gender & HIV & AIDSDokumen19 halamanAnalisis Hubungan Antara Gender & HIV & AIDSayu100% (2)
- Cam ScannerDokumen8 halamanCam ScannerRahmaBelum ada peringkat
- Gender PaperDokumen7 halamanGender PaperfathiaBelum ada peringkat
- Makalah Peran GenderDokumen14 halamanMakalah Peran Genderparadise0663% (8)
- Makalah Kelompok 6 Isue Gender OkDokumen14 halamanMakalah Kelompok 6 Isue Gender OkCyb9r 13vBelum ada peringkat
- Opini Fix - UAS BIJDokumen5 halamanOpini Fix - UAS BIJBasten BontoBelum ada peringkat
- Artikel Masalah Gender 2Dokumen6 halamanArtikel Masalah Gender 2ifha hasanBelum ada peringkat
- PBL GenderDokumen8 halamanPBL GenderLavinaElgivaBelum ada peringkat
- Budaya & GenderDokumen19 halamanBudaya & GenderAndi Sri WahyuniBelum ada peringkat
- Gender Dan KesehatanDokumen18 halamanGender Dan Kesehatanmerris100% (1)
- Konsep Gender Dalam IslamDokumen11 halamanKonsep Gender Dalam IslamAbii 15Belum ada peringkat
- Jurnal PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN BERKEMAJUANDokumen6 halamanJurnal PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN BERKEMAJUANAnnisa AlamBelum ada peringkat
- Subordinasi Gender (Baru)Dokumen5 halamanSubordinasi Gender (Baru)NurkhanifahBelum ada peringkat
- Marmawi 2009 PDFDokumen7 halamanMarmawi 2009 PDFTaruna Djati100% (1)
- Esai Analisis Berita Syahrul Ramadhan (50500118022)Dokumen21 halamanEsai Analisis Berita Syahrul Ramadhan (50500118022)Reza AndhikaBelum ada peringkat
- Tugas Antropologi Kelompok 5. Agama Gender Dan KekuasaanDokumen7 halamanTugas Antropologi Kelompok 5. Agama Gender Dan KekuasaanSodron JrBelum ada peringkat
- Peran GenderDokumen26 halamanPeran Genderhana haruBelum ada peringkat
- Konsep Gender Dalam Kesehatan Kelompok 3Dokumen14 halamanKonsep Gender Dalam Kesehatan Kelompok 3Lia MartinBelum ada peringkat
- Essay Gender Sebagai PersepektifDokumen3 halamanEssay Gender Sebagai Persepektifal ihsanBelum ada peringkat
- Ketimpangan GenderDokumen5 halamanKetimpangan GenderFarah R AfidahBelum ada peringkat
- Kesehatan RepDokumen43 halamanKesehatan RepRieska Ayu WulandariBelum ada peringkat
- Analisis Ketidakadilan Gender Terhadap Upahkerja Dalam KetenagakerjaanDokumen19 halamanAnalisis Ketidakadilan Gender Terhadap Upahkerja Dalam KetenagakerjaanWawan PrayogiBelum ada peringkat
- Jurnal Komunikasi Massa PDFDokumen7 halamanJurnal Komunikasi Massa PDFStephen HarrisBelum ada peringkat
- Agama Dan JenderDokumen9 halamanAgama Dan JenderdrywinterBelum ada peringkat
- Perspektif Gender (PSW)Dokumen38 halamanPerspektif Gender (PSW)mimiBelum ada peringkat
- Agro B - Kelompok 6 - PPT - Pengertian Gender Lembaga Keluarga PedesaanDokumen10 halamanAgro B - Kelompok 6 - PPT - Pengertian Gender Lembaga Keluarga PedesaanRasyadi RBelum ada peringkat
- Kelompok 10 - Terjemah Chapter 11Dokumen24 halamanKelompok 10 - Terjemah Chapter 11haruna fyBelum ada peringkat
- Etika Terapan (Sindy)Dokumen16 halamanEtika Terapan (Sindy)Excel DeoBelum ada peringkat
- Seks, Gender, Dan Seksualitas LesbianDokumen13 halamanSeks, Gender, Dan Seksualitas LesbiannadiaaninditaBelum ada peringkat
- Pai Kontemporer KB 3Dokumen21 halamanPai Kontemporer KB 3El Fahm100% (1)
- Gender Dan PembangunanDokumen16 halamanGender Dan PembangunanHesty AmaliaBelum ada peringkat
- Kesadaran Gender Pada RemajaDokumen3 halamanKesadaran Gender Pada Remajaprikitiwehe901Belum ada peringkat
- Essay Gender Sebagai Kontruksi SosialDokumen3 halamanEssay Gender Sebagai Kontruksi Sosialal ihsanBelum ada peringkat
- Makalah Tentang SeksDokumen15 halamanMakalah Tentang SeksElizabeth YulianaBelum ada peringkat
- Peran Gender 1960Dokumen11 halamanPeran Gender 1960Syifa SalsabilaBelum ada peringkat
- Diskriminasi GenderDokumen20 halamanDiskriminasi Genderyusvera67% (6)