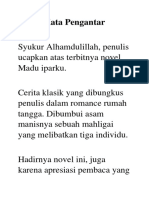Hati Suhita Ep#1
Diunggah oleh
Zulfa Melfin0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
522 tayangan26 halamanNovel Hati suhita episode 1
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniNovel Hati suhita episode 1
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
522 tayangan26 halamanHati Suhita Ep#1
Diunggah oleh
Zulfa MelfinNovel Hati suhita episode 1
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 26
Episode #1
"Piye, lin, sudah hamil ta? Abahmu
lho nanya ummi terus." Ibu mertuaku
bertanya sambil menuang nasi ke
piringku.
Aku menunduk sambil memberinya
senyum termanis. Dia tak boleh tahu
bahwa aku masih perawan. Dia tak
boleh tahu bahwa putra tunggalnya,
sama sekali belum menyentuhku.
Padahal usia pernikahan kami sudah
tujuh bulan lamanya.
Aneh memang, mestinya bulan bulan
pertama pernikahan adalah hari hari
paling indah, tapi yang terjadi padaku
adalah hari hari yang suwung,
hubungan yang anyep, dan kesedihan
yang selalu ku bungkus dg derai derai
tawa.
"Aku mau nikah sama kamu, itu
karena ummik." Itu kalimatnya di
malam pertama kami.
"Sejak aku masih MTs, berkali kali
ummi bilang kalau jodoh untukku
sudah disiapkan." Dia menghela
nafas panjang.
"Perjodohan, itu tidak ada dalam
kamus hidupku. Aku ini aktifis. Aku
teriak setiap hari soal penindasan.
Soal memperjuangkan hak asasi.
Kawan kawan menertawanku karena
aku tidak bisa memperjuangkan
masa depanku sendiri. Semua kecewa
dg perjodohan ini."
Aku menunduk di tepi ranjang. Dia
berdiri sambil bersedekap di depan
lemari. Ranjangku dipenuhi ribuan
kelopak kembang mawar untuk
malam pertama kami, tapi kalimatnya
menusukku dengan diri duri tajam.
Aku menunduk.
"Ya aku tau ini bukan salahmu. Kamu
juga tidak punya pilihan lain selain
manut. Tapi malam ini juga kamu
harus faham, aku tidak mencintaimu,
atau tepatnya, aku belum
mencintaimu."
Satu persatu air mataku meluncur ke
pangkuan. Lihatlah aku, Alina Suhita,
perempuan yang sejak MTs sudah
ditembung kiai dan bu nyai Hannan
untuk menjadi menantu tunggal
mereka.
Lihatlah aku, Alina suhita, yang baru
saja turun dari pelaminan super
megah dengan ribuan kiai yang
mendoakan kami. Lihatlah aku, yang
sama sekali tak dipandang oleh
suamiku sendiri.
"Tapi ya, bagaimana? Ummi, apalagi
abah, sangat mengandalkan kamu
membesarkan pesantren ini. Aku bisa
apa? Aku kadung dituduh gak bisa
apa apa."
Dia terduduk di sofa. Menatapku
tajam. Aku makin menunduk. Tidak
menyangka kalimat pedas ini keluar
di malam pertama pernikahan kami.
Sejak kecil, ayah dan ibuku sudah
mendoktrinku bahwa segalaku, cita
citaku, tujuan hidupku, adalah
kupersembahkan untuk pesantren Al-
Anwar, pesantren mertuaku ini.
Maka, aku tidak boleh punya cita cita
lain selain berusaha keras menjadi
layak memimpin di sana. Aku di
pondokkan di pesantren Tahfid sejak
kecil. Kiai dan Bu nyai Hannan lah
yang mengusulkan bahwa aku harus
kuliah di jurusan tafsir hadis meski
aku sangat ingin kuliah di jurusan
sastra. Ayah ibuku setuju saja asal itu
keinginan mereka.
Bahkan, saat aku sudah semester
tujuh, kiai Hannan memintaku pindah
pesantren dan meninggalkan
kuliahku agar aku bisa lebih lanyah
hafalan di pesantren baruku. Aku
menurutinya karena itu kemauan
mereka. Demi pesantren mereka.
Bu Nyai, yang sekarang kupanggil
ummi, bahkan sudah pernah
mengajakku umroh sebagai hadiah
wisuda Al Qur'anku. Waktu itu,
putranya, gus Albiruni, tidak ikut
mengantar ummiknya karena dia
enggan bertemu denganku. Dialah
yang sekarang jadi suamiku.
Aku tidak pernah berani punya
keinginan, belajarku, segalaku,
muaraku, hanya untuk pesantren
mertuaku.
"aku minta maaf. Mulai malam ini,
entah sampai kapan, aku akan tidur
di sofa ini." Aku makin menunduk. Air
mataku mengucur deras karena
hatiku tersayat belati
ucapannya. Pada siapa aku
mengadu?
Kenapa dia tega mengatakan itu? Aku
tau dia butuh waktu, tapi tidakkah
dia bisa bicara lebih halus tanpa
menyakiti perasaanku? Kalau dia
menolakku sebagai istri, tidak bisakah
dia menghormatiku sebagai
perempuan?
Tapi aku tidak boleh larut dalam
tangis. Namaku Alina Suhita. Suhita
adalah nama pemberian kakek dari
ibuku. Ia ingin aku jadi dewi Suhita.
Perempuan tangguh yang pernah
memimpin kerajaan sebesar
Majapahit. Perempuan hebat yang
tegar walau di masa
kepemimpinannya ada perang
Paregreg yang memilukan itu.
Maka, saat mbah yai Rofiq, abahnya
ayahku, memberiku nama Alina
salma, dari kata alaina salma,
kakekku dari pihak Ibu merubahnya
menjadi Alina Suhita. Aku tahu, kakek
ingin aku tegar di masa depanku.
Mungkin inilah saatnya.
"Nggih, gus. saya maklum." kuangkat
kepalaku setelah kehapus air mataku.
Dia melihat HP nya saat aku bicara.
Sama sekali tidak melirikku.
Malam malam setelahnya,
perjuanganku dimulai. Tidak ada
perang Paregreg di hidupku, tapi
perang bathinku lebih dahsyat dari
perang manapun.
Kami tinggal satu kamar, tapi kami
perang dingin, tidak saling sapa.
Tidak saling bicara. Kami hanya
bertukar senyum, kalau di luar kamar,
di depan abah dan ummi. Kalau ada
undangan pernikahan, itulah saat
kami bersandiwara, memakai baju
warna senada lalu kugamit
lengannya. Setelah itu, perang dingin
bermula lagi.
Semua perempuan ingin sepertiku,
punya suami yang memiliki tubuh
tinggi tegap, kulitnya bersih. Jambang
kebiruan, rambut dagu, hidung
bangirnya, menunjukkan kalau dia
berdarah biru.
Semua perempuan ingin sepertiku,
memiliki mertua yang kaya raya.
Rumah dan pesantren yang megah.
Harta benda yang tumpah ruah.
Mereka tak tahu berapa banyak
tangisku tumpah. Mereka tidak tahu
bahwa aku sudah lama berencana
ingin pergi tapi tak sanggup
kutinggalkan ummik yang terlanjur
kusayangi. Ummik yang sendirian
membersarkan pesantrennya karena
putra tunggalnya kelewat cuek.
"Lin, ditanya umik sampai ping telu
kog gak njawab? "
Ummik membuyarkan lamunanku.
"Hehe,.. Ngapunten ummik, nglamun.
Ummi nanya apa? " jawabku.
"Iku lho, Mas mu lak iki ngko datang
seh. Nanti suruh dia yang sambutan
acara maulud di aula. Yo?"
"siap mi."
"maksudku ngene lin, awakmu ape ta
jak tilik haji, sekalian ummik mau
mborong ke butik Hana."
Aku tertawa. Dialah ummiku.
Mertuaku. Anugerah terbesar dalam
hidupku. Yang mencintaiku sedalam
ibuku sendiri. Ummilah satu satunya
alasanku bertahan di rumah ini.
Aku segera masuk ke kamar. Kulihat
dia masih memangku laptop di shofa.
Kancing kancing bajunya terbuka.
Kuangsurkan air putih hangat tapi dia
memintaku menaruhnya di meja
nakas tanpa
melirikku.
Aku bergegas menyiapkan handuk
dan air hangat di kamar mandi.
Mengganti keset lama dengan keset
yang bersih. Lalu menyiapkan baju
ganti untuknya.
Dia tetap tidak mengatakan apa apa.
Saat dia masuk kamar mandi dan
kudengar shower mengucur, hapenya
berdering. Nama
Ratna Rengganis muncul di layar,
fotonya begitu cantik. Wajah oval,
berlesung pipi, jilbab merah jambu
dengan bros menjuntai. Riasannya
sempurna.
Sangat berlawanan denganku yang
selalu memakai daster dan jilbab
kaos dan tanpa make up.
Ragu ragu, aku menyentuhnya,
membuka percakapan watsapnya.
Hatiku bergetar hebat karena ini
untuk pertama kalinya aku berani
menyentuh barang suamiku sendiri.
"Selamat tidur, cah ayu. Malam ini
mas kirim puisi." tulis suamiku
untuknya.
HP kuletakkan sambil berdebar, aku
seperti tak berpijak di bumi. Rasanya
seperti dihantam ombak yang begitu
besar.
Aku segera meringkuk masuk dalam
selimut, mematikan lampu utama
dan menyalakan lampu tidur. Air
mataku merembes membasahi kain
bantalku.
Aku tau dia butuh waktu untuk
menerima pernikahan kami. Aku tau
perjodohan baginya sangat berat.
Apalagi dia adalah aktifis dengan
kehidupan yang sama sekali berbeda
denganku.
Tapi kalau dalam hidupnya ada Ratna
Rengganis itu, bagaimana mungkin
aku bisa tenang?
Rengganis akan menyita seluruh
perhatiannya. Rengganis akan
bertahta di kerajaan hatinya dan
tidak ada tempat sepetakpun
untukku. Rengganis akan
membuatnya bergelora dan aku
semakin diabaikannya. Aku akan
tumbuh menjadi bunga layu yang
diterbangkan angin.
Lalu untuk apa aku bertahan di
rumah ini, kalau dia tidak sama sekali
berusaha mempertahankan
pernikahan kami?
Aku semakin sesengukan, apalagi
melihatnya sama sekali tak mau tau
berapa banyak air mataku
membanjiri hari hari kami.
Mungkin beginilah perasaan prabu
Duryudana yang merana, karena
Istrinya, Banowati, hanya mencintai
Arjuna. Mungkin seperti inilah
hancurnya hati prabu Duryudana
mengetahui Banowati yang istrinya,
malah memberikan tubuhnya untuk
Arjuna musuhnya. Mungkin beginiah
duka Duryudana, memiliki kerajaan,
memiliki kekuasaan, memiliki harta
benda, menaklukkan negara negara,
tapi istrinya sendiri tidak pernah
seirama.
Meski aku perempuan dan prabu
duryudana laki laki, aku bisa
merasakan pedihnya diabaikan.
Aku menangis sampai tertidur.
Sampai malam menjadi hening dan
kulihat suamiku, di sofa, masih asik
dengan hapenya.
Aku tertidur lagi lalu bangun tengah
malam dalam keadaan terengah
engah karena mimpiku: Ummi, abah,
ayahku, ibuku, menatapku dalam
satu perahu. Disampingku, mas Biru
memegang dayung. Dipangkuanku,
sosok laki laki kecil yang aku tak tahu.
Kuingat udara begitu segar. Air begitu
tenang. Suasana begitu lapang.
Aku terduduk menyadari mimpiku
begitu indah. Aku turun dari ranjang,
menatapnya yang pulas di sofa. Aku
tahu, dia adalah matahari.
Sia-sia kakek memberiku nama Suhita
kalau aku tak bisa menaklukkannya.
Akan kudapatkan malam pertamaku
tak lama lagi.
Bersambung.......
Anda mungkin juga menyukai
- Ep8 - HATI SUHITaDokumen6 halamanEp8 - HATI SUHITaElok AinunBelum ada peringkat
- Ep9 - HATI SuhitaDokumen7 halamanEp9 - HATI SuhitaElok AinunBelum ada peringkat
- Hati Suhita 3Dokumen7 halamanHati Suhita 3Zahro Aini El Aditya67% (3)
- Ep 8 Alina SuhitaDokumen5 halamanEp 8 Alina Suhitaadila-putri-567967% (3)
- Hati Suhita Eps. 1Dokumen4 halamanHati Suhita Eps. 1Rahma Ayu Rizqiya FarihaBelum ada peringkat
- Novel Hati Suhita Episode 1Dokumen6 halamanNovel Hati Suhita Episode 1verafbryn89% (9)
- HATISUHITA009Dokumen48 halamanHATISUHITA009Mohammad Mubarik80% (234)
- Hati SuhitasakitDokumen5 halamanHati SuhitasakitElok AinunBelum ada peringkat
- KISAH DI MAKAMDokumen8 halamanKISAH DI MAKAMRy's Sparetime100% (1)
- Alina dan RengganisDokumen7 halamanAlina dan RengganisRy's SparetimeBelum ada peringkat
- Ep 12 - HATI SUHatiDokumen13 halamanEp 12 - HATI SUHatiElok Ainun100% (1)
- Masa Depan Sastra PesantrenDokumen2 halamanMasa Depan Sastra PesantrenFaiza Nia100% (1)
- Ep 11 - HATI SuhitaDokumen6 halamanEp 11 - HATI SuhitaElok AinunBelum ada peringkat
- Hati Suhita Eps. 2Dokumen2 halamanHati Suhita Eps. 2Rahma Ayu Rizqiya FarihaBelum ada peringkat
- EPISODESUHITADokumen4 halamanEPISODESUHITAverafbryn100% (3)
- Novel Hati Suhita Episode 10 PDFDokumen6 halamanNovel Hati Suhita Episode 10 PDFSiska Anggaraini100% (2)
- Episode 13: Rumah Jawa yang Mengobati LukaDokumen12 halamanEpisode 13: Rumah Jawa yang Mengobati LukaRealis97100% (6)
- Hati SuhitaDokumen1 halamanHati SuhitaKhulmi Hasanah100% (7)
- WIGATI Lintang Manik WoroDokumen1 halamanWIGATI Lintang Manik Woromutmainnahelshaf71% (7)
- Dua Barista Part 1-8Dokumen81 halamanDua Barista Part 1-8Aida Meutia Mudjib89% (45)
- Lebih Dari Sekedar No Absen (OppaSFTH) PDFDokumen455 halamanLebih Dari Sekedar No Absen (OppaSFTH) PDFRamadhan ZandhyBelum ada peringkat
- Slide Pemeriksaan IVADokumen14 halamanSlide Pemeriksaan IVAridasieseriaBelum ada peringkat
- Naskah AnjaniDokumen304 halamanNaskah AnjaniUll Ya ChanBelum ada peringkat
- Hilangnya Sosok AyahDokumen13 halamanHilangnya Sosok AyahragaBelum ada peringkat
- KELUARGA BARU JESLYNDokumen3 halamanKELUARGA BARU JESLYNNayla Hasna100% (2)
- Dongeng Tentang JujurDokumen8 halamanDongeng Tentang JujurAkbar AbayBelum ada peringkat
- KAMAR MANDIDokumen88 halamanKAMAR MANDIRosa Aulia Savitri100% (1)
- TeksDokumen5 halamanTeksannisaputrifebriantyBelum ada peringkat
- SYKTDokumen104 halamanSYKTkelabkBelum ada peringkat
- PDF Madu IparkuDokumen679 halamanPDF Madu IparkuMirza Gulam100% (2)
- Cerpen FatmaDokumen4 halamanCerpen FatmaUmi JamilahBelum ada peringkat
- Novel Ili YantiDokumen10 halamanNovel Ili YantiIliyhanti IballeBelum ada peringkat
- NovellDokumen23 halamanNovellNur WahidaBelum ada peringkat
- Cerpen: Isteriku Nur JannahDokumen3 halamanCerpen: Isteriku Nur Jannahonemahmud100% (1)
- Cerpen Malam Hujan Bulan DesemberDokumen6 halamanCerpen Malam Hujan Bulan DesemberLinelejanBelum ada peringkat
- MENERTAWAI KEMATIANDokumen4 halamanMENERTAWAI KEMATIANDesa PagelaranBelum ada peringkat
- CerpennkuuuuDokumen9 halamanCerpennkuuuuFarhan NasrullahBelum ada peringkat
- Masa KelahiranDokumen20 halamanMasa KelahiranfathiyaBelum ada peringkat
- Catatan Dalam BotolDokumen4 halamanCatatan Dalam BotolYosua SidabutarBelum ada peringkat
- KEHIDUPAN SENJADokumen97 halamanKEHIDUPAN SENJABisma PutroBelum ada peringkat
- Kumpulan Cerpen KompasDokumen8 halamanKumpulan Cerpen KompasSofie AmeliaBelum ada peringkat
- Risky AnthropyDokumen18 halamanRisky AnthropyRizky RaaBelum ada peringkat
- Kumpulan CerpenDokumen50 halamanKumpulan CerpenNandar RohimanBelum ada peringkat
- Kita Dalam KataDokumen12 halamanKita Dalam KataSYARIIFF 027Belum ada peringkat
- Mereka Bilang Aku GilaDokumen7 halamanMereka Bilang Aku GilaAida AffandiBelum ada peringkat
- Kenangan AbangDokumen14 halamanKenangan AbangintanfiqaBelum ada peringkat
- Cerpen TrisantianaDokumen5 halamanCerpen TrisantianavebiBelum ada peringkat
- FirdausDokumen9 halamanFirdausNAHLIKABelum ada peringkat
- Tugas Aspek Kebahasaan Cepen Catatan Dalam BotolDokumen6 halamanTugas Aspek Kebahasaan Cepen Catatan Dalam Botolrahmat hafiz W.0% (1)
- Fajar Yang Tak Lagi CeriaDokumen8 halamanFajar Yang Tak Lagi Ceriadewi sinta putriBelum ada peringkat
- EVILA RAMADHANTY - CERPEN - Nusantara Takkan Buat Ibu Pertiwi Menangis LagiDokumen7 halamanEVILA RAMADHANTY - CERPEN - Nusantara Takkan Buat Ibu Pertiwi Menangis LagiEvila Ramadhanty evilaramadhanty.2020Belum ada peringkat
- Ummi HanaDokumen26 halamanUmmi HanaEpi AmaliahBelum ada peringkat
- Cerita Cinta Seorang SuamiDokumen6 halamanCerita Cinta Seorang SuamiShandi Rastakid OnelovereageemusicBelum ada peringkat
- 2015 - Fanny Yulia Purwanti - Cerpen - PBSI'ADokumen8 halaman2015 - Fanny Yulia Purwanti - Cerpen - PBSI'Afanny yuliaBelum ada peringkat
- Cerpen-Islam 4Dokumen3 halamanCerpen-Islam 4Muhammad Ibnu Falah AdinugrohoBelum ada peringkat
- Cerpen B.indonesiaDokumen12 halamanCerpen B.indonesiaMPK OSIS SMAN 11 KAB.TANGERANGBelum ada peringkat
- Serenade Luka - Ayu DamayantiDokumen5 halamanSerenade Luka - Ayu DamayantiAyu DamayantiBelum ada peringkat