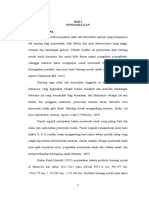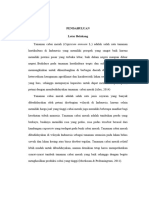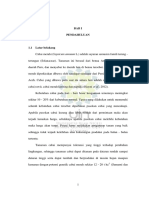Bab 1 Pendahuluan
Bab 1 Pendahuluan
Diunggah oleh
Clara sriyusniar Binjori0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1 tayangan4 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
1 tayangan4 halamanBab 1 Pendahuluan
Bab 1 Pendahuluan
Diunggah oleh
Clara sriyusniar BinjoriHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanaman serai wangi tergolong kedalam tanaman perkebunan sebagai penghasil
minyak atsiri dari kelompok Grainae atau lebih dikenal dengan rerumputan. Tanaman
serai wangi merupakan tanaman yang biasa dimanfaatkan bagian daunnya untuk
disuling sehingga dapat menghasilkan minyak atsiri yang dikenal dengan nama
citronella oil. Minyak atsiri memiliki dua senyawa penting yang dapat dimanfaatkan
sebagai bahan utama untuk pembuatan produk seperti parfum, sabun, kosmetik dan
juga biasa digunakan untuk pembuatan insektisida, nematisida, anti bakteri, anti
jamur serta hama gudang (Swasono et al., 2015).
Berdasarkan hasil dari data statistik BPS terhadap nilai ekspor dunia untuk
minyak atsiri pada tahun 2015 yaitu senilai 637.4 juta US$ dan 694.7 juta US$ tahun
2016. Indonesia memiliki beberapa komoditas ekspor minyak atsiri yaitu nilam, jahe,
cengkeh, kenanga, lada, pala, akar wangi, serai wangi, dan kayu putih. Sebagian besar
minyak atsiri Indonesia memiliki presentase ekspor dunia yaitu sebesar 64% nilam,
67% kenanga, 26% akar wangi, 12% serai wangi, 72% pala, 63% cengkeh,0.4% jahe
dan 0.9% lada. Pada saat sekarang ini kualitas minyak serai wangi Indonesia
mengalami penurunan volume ekspor karena kurang tersedianya bahan baku akibat
rendahnya produktivitas dan mutu minyak, sehingga terjadinya penurunan harga jual
minyak serai wangi di pasar internasional yang disebabkan oleh para petani di
Indonesia umumnya banyak memakai varietas lokal yang hasilnya kurang bagus.
Citronella oil merupakan senyawa aktif yang terdapat pada tanaman serai
wangi. Minyak atsiri memiliki kandungan rata-rata 0,7 % (berkisar antara 0,5% pada
musim hujan serta mencapai 1,2% pada musim kemarau). Hasil dari penyulingan
minyak serai wangi yaitu berwarna kuning kepucatan. Senyawa aktif yang paling
utama dihasilkan pada minyak atsiri yaitu senyawa aldehidehid berkisar antara 30-
45%, senyawa alcohol sitronelol dan geraniol berkisar antara 55-65% dan senyawa
lain seperti geraniol, nerol, metal, sitral, heptono dan dipentena (Khoirotunnisa,
2008).
Indonesia memiliki 2 jenis serai wangi yang banyak dibudidayakan yaitu jenis
Mahapengiri dan Lenabatu. Jenis Mahapengiri bisa kita kenal dengan bentuk daun
yang lebih pendek dan lebih luas dari pada jenis Lenabatu. Serai wangi jenis
Mahapengiri memiliki hasil kandungan minyak yang lebih tinggi serta kualitas lebih
baik, yang mana maksudnya hasil dari kandungan geraniol dan sitronellalnya lebih
tinggi dari jenis Lenabatu.
Serai wangi dapat tumbuh di tanah marginal seperti ultisol. Namun
pertumbuhannya kurang baik sehingga produksi yang dihasilkan rendah. Luas areal
perkebunan sereh wangi di Indonesia menurut data BPS (2017) yaitu sebesar 19.300
ha pada tahun 2014 dan dapat menghasilkan minyak serai wangi sebesar 3.100 ton.
Indonesia memiliki potensi tanaman serai wangi yang cukup besar untuk
dikembangkan, karena Indonesia memiliki luas lahan marginal yang cukup besar
untuk dibudidayakan tanaman serai wangi.
Tanah ultisol merupakan salah satu jenis tanah marginal yang terdapat di
Indonesia memiliki sebaran luas mencapai 45.794.000 ha atau sekitar 25% dari total
luas daratan Indonesia Subagyo et al., (2004). Menurut hasil penelitian dari
Armansyah (2018) budidaya serai wangi di lahan kering dapat mengakibatkan
rendahnya kamampuan akar tanaman untuk menyerap air dan nutrisi dikarenakan
akarnya yang serat. Akar serat hanya dapat berkembang dilapisan atas tanah, hal
tersebutlah yang menyebabkan rendahnya hasil produksi dari minyak atsiri. Pada
lahan yang subur dan cukup kebutuhan unsur haranya dapat menghasilkan daun segar
serai wangi berkisar anatara 50-70 ton/ha/th. Berdasarkan hasil produksi pada lahan
yang kurang subur dan kurang unsur hara yang ditanam pada tanah ultisol didapatkan
hasil minyak atsiri sebesar 15-20 ton/ha/th, hal tersebut terjadi karena kurangnya
unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut.
Tanah ultisol memiliki kandungan bahan organik yang presentasenya cukup
rendah, dikarenakan tanah ultisol yang berwarna merah kekuningan, PH berkisar
antara < 4,50, serta terdapat kandungan unsur hara makro yang sedikit seperti P, K,
Ca dan Mg dan kadar Al yang tinggi, serta memiliki tekstur tanah liat berpasir,
dengan bulk densty yang tinggi yaitu antara 1,3-1,5 g/cm3 (Hardjowigeno, 2010),
sehingga dapat mempengaruhi tingkat produktivitas tanaman yang akan
dibudidayakan pada tanah ultisol.
Pemanfaatan dari pupuk organik sangat diharapkan untuk dapat mengatasi
permasalahan yang sering terjadi pada tanah ultisol. Hasil dari penelitian Pangaribun
et al., (2008) memperlihatkan hasil dari pemberian bahan organik pada tanah dapat
meningkatkan konsentrasi hara dalam tanah, terutama N, P dan K serta unsur hara
lainnya. Pupuk organik juga dapat memperbaiki tata udara tanah dan air tanah.
Dengan begitu perakaran tanaman dapat berkembang dengan baik dan akar juga dapat
menyerap unsur hara yang lebih banyak terutama yaitu unsur hara N yang akan
meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman. Di samping itu, pupuk organik
yang diberikan dalam jangka waktu panjang mampu meningkatkan kandungan humus
di dalam tanah. Dengan adanya humus tanah akan lebih gembur, sehingga
penyerapan air lebih optimum dan mampu mengurangi pengikisan tanah oleh air.
Pupuk organik yang digunakan pada penelitian ini adalah kotoran ayam
karena kotoran ayam dapat menyediakan berbagai macam unsur hara bagi tanaman.
Kotoran ayam dapat berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi
tanah, karena memiliki kandungan unsur hara makro seperti nitrogen (N) 0,35%,
fosfor (P) 0,60%, dan kalsium (K) 0,40% (Darmawansyah et al., 2012), tetapi kotoran
ayam memiliki N yang rendah sehingga dilakukan bokashi dengan cara
menambahkan arang sekam, dedak dan fermentasi menggunakan aktivator bakteri
pengurai atau EM4 .
Pemberian perlakuan bokashi kotoran ayam yang memiliki kandungan
mikroorganisme (EM4) sangat berperan penting dalam meningkatkan unsur N bagi
tanaman, meningkatkan bakteri fotosintetik dan bakteri pengikat nitrogen di dalam
tanah. Bokashi kotoran ayam yang digunakan mengandung sejumlah unsur hara yang
kompleks serta memiliki kandungan bahan organik yang dapat memperbaiki sifat
fisik, kimia, dan biologi tanah. Menurut hasil penelitian Sudami dan Wartini (2018)
pada tanaman sambalito dosis 15 ton/ha pupuk bokashi menunjukan pertumbuhan
dan hasil yang terbaik. Berdasarkan dengan uraian diatas maka penulis telah
melakukan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pemberian Berbagai Dosis
Bokashi Kotoran Ayam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Serai Wangi
(Cymbopogon nardus L.)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil dari identifikasi masalah yang terdapat pada latar belakang
dapat dirumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh dari pemberian bokashi kotoran
ayam terhadap pertumbuhan dan hasil serai wangi (Cymbopogon nardus L.)
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian
berbagai dosis pupuk bokashi kotoran ayam terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil
serai wangi (Cymbopogon nardus L.)
D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk dapat mengetahui dosis terbaik dari
pemberian bokashi kotoran ayam terhadap pertumbuhan dan hasil serai wangi
(Cymbopogon nardus L.)
Anda mungkin juga menyukai
- Laporan - Bawang MerahDokumen18 halamanLaporan - Bawang MerahAyuni Rosddiena57% (7)
- PENDAHULUANDokumen5 halamanPENDAHULUANFitto BoleBelum ada peringkat
- Proposal Pilipi Persadanta KabanDokumen21 halamanProposal Pilipi Persadanta KabanPilipi kabanBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen6 halamanBab Iialihzbi12Belum ada peringkat
- Skripsi TerbaruDokumen21 halamanSkripsi TerbaruShintya nainggolanBelum ada peringkat
- Alexandico 218310042 DormansiDokumen29 halamanAlexandico 218310042 Dormansichristian haDINAtaBelum ada peringkat
- 2016 1 2 54211 613412093 Bab1 30122016012336Dokumen7 halaman2016 1 2 54211 613412093 Bab1 30122016012336sk krBelum ada peringkat
- Prop 1Dokumen31 halamanProp 1Bonita natalia SaragihBelum ada peringkat
- Laporan BG Munte PestisidaDokumen31 halamanLaporan BG Munte PestisidaFikri HaikalBelum ada peringkat
- Jahe MerahDokumen27 halamanJahe MerahSandi KaratanBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen6 halamanBab 1BrodyBelum ada peringkat
- Laporan Observasi PEMANFAATAN LIMBAH SABUT KELAPA DENGAN PEMAKAIAN EFFECTIVE MICROORGANISM (EM4) SEBAGAI PRODUK PUPUK ORGANIK CAIR (POC)Dokumen17 halamanLaporan Observasi PEMANFAATAN LIMBAH SABUT KELAPA DENGAN PEMAKAIAN EFFECTIVE MICROORGANISM (EM4) SEBAGAI PRODUK PUPUK ORGANIK CAIR (POC)Merza100% (1)
- BAB 1-5 RobyDokumen55 halamanBAB 1-5 RobyRobby ZulianBelum ada peringkat
- Bab I-3Dokumen5 halamanBab I-3Sryana SaragihBelum ada peringkat
- Materi SawitDokumen7 halamanMateri SawitAzzahraBelum ada peringkat
- Bab 1 - 3Dokumen20 halamanBab 1 - 3Twitch GGBelum ada peringkat
- Proposal Pum Revisi2Dokumen38 halamanProposal Pum Revisi2Aji SetiawanBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen18 halamanBab I PendahuluanRichi SetiawanBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen6 halamanBab IiIndra Muhammad NaufalBelum ada peringkat
- Meningkatkan Produktivitas Kacang TanahDokumen10 halamanMeningkatkan Produktivitas Kacang TanahTracy Smith100% (1)
- BAB I - VII Telah Di Coba 1Dokumen33 halamanBAB I - VII Telah Di Coba 1Oktaviani Dolorosa KaunanBelum ada peringkat
- Paper Pembuatan Pupuk Kompos Dari Beberapa Jenis Limbah PertanianDokumen23 halamanPaper Pembuatan Pupuk Kompos Dari Beberapa Jenis Limbah PertanianSilfi IndrianBelum ada peringkat
- Laporan Lit Tebu Wiwik IndraDokumen39 halamanLaporan Lit Tebu Wiwik IndraBrayonoFloBelum ada peringkat
- 8.i PendahuluanDokumen3 halaman8.i PendahuluanPilipi kabanBelum ada peringkat
- 2BL01196 PDFDokumen26 halaman2BL01196 PDFBellaAliandoValerisBelum ada peringkat
- Bahrul IlmiDokumen31 halamanBahrul IlmiMuhammad IkmalBelum ada peringkat
- Identifikasi Permasalahan Dan Identifikasi Inovasi Komoditi Serai WangiDokumen4 halamanIdentifikasi Permasalahan Dan Identifikasi Inovasi Komoditi Serai Wangiwahyu fikriansyahBelum ada peringkat
- Pengaruh Kombinasi Pupuk Kandang Sapi Dan Kambing Terhadap Pertumbuhan Serai WangiDokumen5 halamanPengaruh Kombinasi Pupuk Kandang Sapi Dan Kambing Terhadap Pertumbuhan Serai WangiRM AGUS HARIANTOBelum ada peringkat
- File4Dokumen3 halamanFile4novalmuliadi55Belum ada peringkat
- Skripsi Mulia Fadila - 26 - 110546 - 121047 - 084746Dokumen54 halamanSkripsi Mulia Fadila - 26 - 110546 - 121047 - 084746Muliya fadilahBelum ada peringkat
- Pengaruh Arang Kompos Bioaktif Pada NilamDokumen14 halamanPengaruh Arang Kompos Bioaktif Pada NilamgsmLina R PanyalaiBelum ada peringkat
- Akar WangiDokumen6 halamanAkar WangialanBelum ada peringkat
- Lap PocDokumen9 halamanLap PoctaniaBelum ada peringkat
- Dampak Positif Serta Negatif Penggunaan Pupuk Anorganik Di Perkebunan Kelapa SawitDokumen5 halamanDampak Positif Serta Negatif Penggunaan Pupuk Anorganik Di Perkebunan Kelapa SawitNur RohmanBelum ada peringkat
- C - 2018-234 - Reygista Cinda Millenia - Jurnal Tugas 3Dokumen20 halamanC - 2018-234 - Reygista Cinda Millenia - Jurnal Tugas 3REYGISTA CINDA MILLENIABelum ada peringkat
- Ii - Tinjauan PustakaDokumen10 halamanIi - Tinjauan PustakafatimahBelum ada peringkat
- Proposalku EditDokumen47 halamanProposalku EditMaield Licklider Al-KhawarizmiBelum ada peringkat
- MIIA Pupuk Bokashi Kotoran AyamDokumen27 halamanMIIA Pupuk Bokashi Kotoran AyamRizki Rahmat SonjayaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen9 halamanBab IiAkhmad FHBelum ada peringkat
- Respon Pertumbuhan Tanaman Cabai 1Dokumen10 halamanRespon Pertumbuhan Tanaman Cabai 1nalupiBelum ada peringkat
- Etika MenwaDokumen6 halamanEtika Menwafluffyyz cpaBelum ada peringkat
- BAB I PendahuluanDokumen3 halamanBAB I PendahuluanIndra Muhammad NaufalBelum ada peringkat
- Natural Resources For Cabbage Plantation)Dokumen10 halamanNatural Resources For Cabbage Plantation)Nur AsyifaBelum ada peringkat
- SKRIPSI AFNI - FixDokumen45 halamanSKRIPSI AFNI - FixAbdielBelum ada peringkat
- PENDAHULUAN Bawang DaunDokumen14 halamanPENDAHULUAN Bawang DaunDimas BagasBelum ada peringkat
- Jurnal Penelitian KemangiDokumen13 halamanJurnal Penelitian KemangiMuhamad Farhan RLBelum ada peringkat
- Kelompok 4 - Pembuatan Minyak Atsiri Dengan Destilasi SederhanaDokumen13 halamanKelompok 4 - Pembuatan Minyak Atsiri Dengan Destilasi SederhanaInsan AnugerahBelum ada peringkat
- Skripsi Tanaman BayamDokumen19 halamanSkripsi Tanaman BayamRAHMAD HIDAYATBelum ada peringkat
- EhehdnskfjsbhaDokumen11 halamanEhehdnskfjsbhaFaris RahmanBelum ada peringkat
- Jogy Dearma Octavian SilalahiDokumen28 halamanJogy Dearma Octavian Silalahimba128macBelum ada peringkat
- Bab1&2 - 19712023 - OsaListiaSedayu - Horikultura - Osa ListiaDokumen6 halamanBab1&2 - 19712023 - OsaListiaSedayu - Horikultura - Osa Listiaadamtadarus1Belum ada peringkat
- Bahan-Bahan POCDokumen4 halamanBahan-Bahan POCEka AgustinaBelum ada peringkat
- Pupuk Organik CairDokumen7 halamanPupuk Organik CairPriska Nadia TriadantiBelum ada peringkat
- Makalah BUDIDAYA TEMULAWAKDokumen8 halamanMakalah BUDIDAYA TEMULAWAKAbi RafiefBelum ada peringkat
- 4 Bab1Dokumen8 halaman4 Bab1Ista WaodeBelum ada peringkat
- PKM InsyaAllahDokumen24 halamanPKM InsyaAllahintan novita sariBelum ada peringkat
- Bugemm Bahasa IndonesiaDokumen18 halamanBugemm Bahasa Indonesiadhea rifah amaliaBelum ada peringkat
- Bab IDokumen7 halamanBab Ipejabat pengadaanbbppBelum ada peringkat
- BAB I DAN BAB II - Walita NadinaDokumen8 halamanBAB I DAN BAB II - Walita Nadinabagussaputra52649Belum ada peringkat
- Tanaman Pepohonan Untuk Mengusir Dan Menghalau Serangan Hama Belalang (Grasshopper) Dari Lahan Pertanian Versi BilingualDari EverandTanaman Pepohonan Untuk Mengusir Dan Menghalau Serangan Hama Belalang (Grasshopper) Dari Lahan Pertanian Versi BilingualBelum ada peringkat
- Format Laporan SPPDDokumen7 halamanFormat Laporan SPPDRoma DhoniBelum ada peringkat
- Pengertian Dengan Gambar Kerja Adalah Bidang Kelmuan Atau Profesi Yang MenentukanDokumen7 halamanPengertian Dengan Gambar Kerja Adalah Bidang Kelmuan Atau Profesi Yang MenentukanRoma DhoniBelum ada peringkat
- Wa0027.Dokumen26 halamanWa0027.Roma DhoniBelum ada peringkat
- 07 EkstraksiDokumen31 halaman07 EkstraksiRoma DhoniBelum ada peringkat
- Latihan Soal BAB 1Dokumen4 halamanLatihan Soal BAB 1Roma DhoniBelum ada peringkat