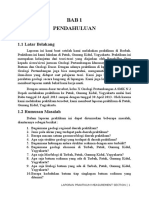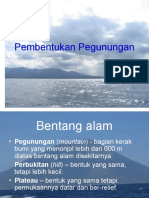Ab015 Geologi Struktur
Ab015 Geologi Struktur
Diunggah oleh
Hanif AbdillahJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Ab015 Geologi Struktur
Ab015 Geologi Struktur
Diunggah oleh
Hanif AbdillahHak Cipta:
Format Tersedia
KATA PENGANTAR
Kumpulan edaran Praktikum Geologi Struktur ini disusun dengan tujuan sebagai pegangan
dalam pelaksanaan Praktikum Geologi Struktur di Program Studi Teknik Geologi, Jurusan
Teknik, Fakultas Sains dan Teknik – UNSOED.
Format tugas pada kumpulan ini diusahakan lebih fleksibel mengingat berdasarkan
pengalaman pelaksanaan praktikum, jika jenis soal dan foto sama dari tahun ke tahun, maka
terdapat gejala pencontekan tugas dan laporan-laporan tahun sebelumnya.
Silabus praktikum disusun tidak bersifat mutlak untuk tiap tahun, tetapi pada umumnya
urutan-urutan topik tidak bergeser dari garis besar silabus tersebut. Pada modul ini disertakan
pula diagram, foto, tabel yang dapat membantu penjelasan.
Terakhir, saran dan kritik untuk penyempurnaan kumpulan inin akan sangat berguna untuk
pembuatan kumpulan modul Praktikum Geologi Struktur yang lebih baik.
Purbalingga, Februari 2013
Penyusun,
Asisten Praktikum
Geologi Struktur 2012
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 1
LEMBAR PENYUSUN
1. Koordinator Asisten Praktikum Geologi Struktur
Nama : Akhmad Khahlil Gibran
NIM : H1F009034
TTL : Purwodadi, 28 Desember 1990
2. Asisten Praktikum Geologi Struktur
Nama : Ayu Utami Nurhidayati
NIM : H1F009045
TTL : Tangerang, 4 April 1991
3. Asisten Praktikum Geologi Struktur
Nama : Seisar Fajrin
NIM : H1F010022
TTL : Jakarta, 5 Mei 1992
4. Asisten Praktikum Geologi Struktur
Nama : Wulan Okta Karunia
NIM : H1F010063
TTL : Salatiga, 17 Oktober 1992
5. Asisten Praktikum Geologi Struktur
Nama : Muhammad Zulkifli
NIM : H1F010037
TTL : Jakarta, 25 Juni 1991
6. Asisten Praktikum Geologi Struktur
Nama : Riska Nur Afifah
NIM : H1F010027
TTL : Majalengka, 31 Juli 1992
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 2
JADWAL PRAKTIKUM
Berikut Jadwal Praktikum Geologi Struktur :
1. Pendahuluan
2. Bab 1 Kompas
3. Bab 2 Struktur bidang
4. Bab 3 Struktur garis dan arus purba
5. Bab 4 Analisis sesar
6. Bab 5 Analisis lipatan
7. Bab 6 Peta geologi
8. Bab 7 Fieldtrip
TATA TERTIB PRAKTIKUM
Tata tertib dalam mengikuti Praktikum Geologi Struktur adalah sebagai berikut :
1. Praktikan diharap datang 10 menit sebelum Praktikum dimulai.
2. Apabila Praktikan telat 5menit, maka akan diberi peringatan.
3. Apabila praktikan telat lebih dari 10 menit, maka tidak diperbolehkan mengikuti
praktikum dan termasuk inhal.
4. Praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum dikarenakan suatu hal, diwajibkan
memberitahukan melalui surat yang ditandatangani oleh yang mengetahui. (Surat
dokter, surat dari orangtua, dll)
5. Praktikan yang tidak mengikuti praktikum, diwajibkan mengganti praktikum/inhal
dengan membayar Rp 25.000,00 per praktikum.
6. Praktikan dilarang makan, minum, merokok pada saat praktikum berlangsung.
7. Pada saat Praktikum, HP harap dimatikan.
8. Praktikan wajib membawa alat-alat praktikum secara lengkap dan tidak diperbolehkan
saling meminjam alat-alat praktikum pada saat praktikum.
9. Praktikan yang tidak mengikuti acara praktikum Fieldtrip maka nilai Fieldtrip mendapat
0 (nol).
10. Laporan pratikum dikumpulkan 6 hari setelah praktikum dilaksanakan, tempat loker 6
Laboratorium Terknik Geologi dan waktu pengumpulan laporan praktikum pukul 15.00
WIB, jika praktikan telat dalam pengumpulan praktikum akan dilakukan pengurangan
nilai yaitu -5 untuk keterlambatan setiap harinya.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 3
BAB I
KOMPAS
1.1 Maksud dan Tujuan
1. Praktikan mampu menggunakan Kompas dengan baik dan benar.
2. Praktikan dapat mengetahui nama dan fungsi dari bagian-bagian kompas.
3. Praktikan mengetahui jenis-jenis kompas yang digunakan dan memahami perbedaanya.
4. Praktikan dapat menuliskan data yang di dapat dari penggunaan kompas geologi dengan
benar.
1.2 Alat yang di Gunakan
1. Kompas Geologi
2. Modul Praktikum Geologi Struktur
3. Form Praktikum Acara Kompas
4. Alat Tulis
5. Bidang bantu (Papan “Clip Board” atau sejenisnya)
6. Penggaris dan Busur
1.3 Pendahuluan
Dalam geologi, Kompas merupakan alat yang sangat vital, kompas geologi merupakan
alat yang tidak dapat digantikan oleh alat apapun, karena selain dapat menunjukan arah utara,
kompas geologi juga dapat digunakan untuk hal-hal lainnya, seperti; Mengukur struktur
bidang dan struktur garis, mengukur beda ketinggian, dan banyak lagi. Kompas geologi di
bedakan menjadi kompas azimuth dan kuadran.
1.3.1 Bagian-bagian Kompas Geologi
Kompas Geologi memiliki bagian-bagian tertentu seperti pada gambar 2.1, bagian-
bagian tersebut memiliki fungsi dan perannya masing-masing, bagian-bagian utama dari
kompas geologi antara lain :
1. Jarum kompas/magnet, kedua ujung dari jarum kompas selalu menunjuk ke arah kutub
utara dan kutub selatan magnetik bumi.
2. Lingkaran pembagian derajat, pembagian derajat yang dikenal ada dua yaitu kompas
azimuth dan kompas kwardan.
3. Klinometer, merupakan rangkaian alat yang gunanya untuk mengukur besarnya
kemiringan bidang.
4. Bull’s eye level (mata sapi), nivo bulat pengukur horizontal kompas.
5. Klinometer level, sama seperti mata sapi namun bentuknya berupa tabung.
6. Kompas needle, merupakan jarum kompas penunjuk arah utara selatan kutub magnet
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 4
bumi.
Gambar 1.1 Kompas Geologi dan bagian-bagiannya
1.3.2 Penulisan (konvensi)Azimut dan Kuadran
Perbedaan antara kompas azimuth dan kompas kuadran terletak pada penulisan arahnya.
Jika kompas azimuth terdiri dari 0º(sebagai arah utara) sampai 360º(kembali ke arah utara
lagi), di kompas kuadran hanya 0º sampai 45º, tetapi dibedakan arah kedudukannya
berdasarkan simbol di depan dan di belakang angkanya, yaitu N_E apabila kedudukan arahnya
berada antara utara (N) dan timur (E), atau S_W apabila kedudukan arahnya berada antara
selatan (S) dan barat (W).
Gambar 1.2 (a) Penulisan Kuadran, (b) Penulisan Azimut
1.3.3 Penulisan Azimut
Dalam konvensi ini, seluruh kemungkinan arah dibagi ke dalam 360°, dengan arah utara
ditetapkan memiliki nilai 0º atau 360º (Gambar 2.2b). Karena pengukuran jurus selalu
berputar dari arah utara ke timur (searah jarum jam), maka jurus dalam konvensi azimuth
sebenarnya dapat dideskripsikan secara keseluruhan dalam angka, tanpa harus menyebutkan
singkatan mata angin. Namun, untuk membedakan pengukuran jurus dengan pengukuran
besaran lainnya yang menggunakan satuan derajat, dalam konvensi azimuth singkatan mata
angin tetap disertakan dalam penulisan jurus. Sebagai contoh :
Jika garis jurus tepat berarah N-S, maka jurusnya adalah N0ºE atau N180ºE.
Jika garis jurus tepat berarah E-W, maka jurusnya adalah N90ºE atau N270ºE.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 5
Jika garis jurus tepat berarah NW-SE, maka jurusnya adalah N135ºE atau N315ºE.
Jika garis jurus tepat berarah NE-SW, maka jurusnya adalah N45ºE atauN225ºE.
1.3.4 Penulisan Kuadran
Dalam penulisan ini, seluruh kemungkinanarah dibagi ke dalam empat kuadran (NE, SE,
NW, dan SW) yang masing-masing kuadran memiliki besar 90° (Gambar 2.2.b), dan jurus
ditentukan denganmemberikan angka dalam derajat yang mewakili besar sudut (bisa ke arah
barat atau timur) antara garis jurus dengan utara sebenarnya. Beberapa contoh penentuan dan
penulisan jurus dalam konvensi kuadran adalah sebagai berikut :
Jika garis jurus pada suatu struktur bidang tepat berarah N-S, dalam konvensi kuadran
jurus struktur bidang tersebut ditulis N0ºE atau N0ºW,dan dibaca "north nol derajat east"
atau "north nol derajat west".
Jika garis jurus pada struktur bidang tepat berarah NW-SE, dalam konvensikuadran jurus
struktur bidang tersebut ditulis N45ºW atau S45ºE dandibaca "north empat puluh lima
derajat west" atau "south empat puluh limaderajat east".
Jika garis jurus pada struktur bidang tepat berarah NE-SW, dalam konvensikuadran jurus
struktur bidang tersebut ditulis N45ºE atau S45ºW dan dibaca "north empat puluh lima
derajat east" atau "south empat puluh lima derajat west".
1.3.5 Aturan Tangan Kanan (Right Hand Rule)
Dalam konvensi azimuth, jurus harus selalu dituliskan dengan tiga digit angka
dankemiringan harus selalu dituliskan dengan dua digit angka ditambah dengan arah
kemiringan. Banyak ahli geologi menggunakan sistem yang lebih cepat untuk dituliskan, dan
sistem ini dikenal sebagai aturan tangan kanan (right-hand rule). Jika kita mengikuti aturan
tangan kanan (Gambar 2.3.a), kita harus memilih arah jurus sehingga, jika kita menghadap
pada arah jurus tersebut, struktur bidang miring ke arah kanan dari hadapan kita.
Dengan demikian, dari setiap pengukuran struktur bidang dengan menggunakan
kompas, arah kemiringan akan selalu dapat ditentukan dengan menambahkan 900 searah
perputaran jarum jam (clockwise) terhadap besar jurus (Gambar 2.3.b). Salah satu keuntungan
dari penerapan aturan ini adalah kedudukan strutur bidang dapat dideskripsikan secara
keseluruhan dalam angka.
1.4 Langkah Kerja
1.4.1 Menentukan Jurus dan Kemiringan (Strike and Dip)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 6
Gambar 1.3 Ilustrasi aturan tangan kanan (right-hand rule) untuk mendeskripsikan jurus dan
kemiringan. (a) Struktur bidang miring ke arah kanan terhadap garis pandang. (b) Angka dipditentukan
dengan menambahkan 90º searah perputaran jarum jam (clockwise) terhadap besar jurus.
1.4.2 Pengukuran Jurus (Gambar 2.4a)
Bagian sisi kompas (Sisi E) ditempel pada bidang yang diukur.
Kedudukan kompas dihorisontalkan (Nivo bulat berada di tengah-tengah
lingkaran).
Angka yang ditunjuk Jarum Utara (N) adalah Jurus bidang yang diukur berikan
tanda garis pada bidang tsb sesuai dengan arah jurusnya.
1.4.3 Pengukuran kemiringan (Gambar 2.4b)
Kompas pada posisi tegak, tempel sisi “W” pada bidang yang diukur dengan
posisi tegak lurus garis jurus yang telah dibuat.
Klinometer diatur sehingga gelembung udaranya (nivo) berada di tengah (posisi
level).
Angka yang ditunjukkan oleh penunjuk pada skala clinometer adalah besarnya
sudut kemiringan dari bidang yang diukur.
(a) (b)
Gambar 1.4 (a) Mengukur Jurus dan (b) Mengukur Kemiringan.
1.4.4 Mengukur Jurus dan Kemiringan Lapisan Hampir Datar.
Pada hakikatnya mengukur jurus dan kemiringan pada bidang yang hampir datar (ialah
bidang yang kemiringannya kurang dari 15º) sama dengan mengukur jurus dan kemiringan
pada umumnya. Hanya saja masalah yang terjadi adalah kita sulit menentukan kemana arah
kemiringan tersebut dikarenakan keadaan bidangnya yang hampir datar, dengan begitu secara
otomatis jika kita menggunakan aturan tangan kanan maka kita akan sulit menentukan arah
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 7
jurusnya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui dahulu arah kemiringan
dari bidang tersebut dan mengukur derajat kemiringannya setelah itu, baru kita bisa
mengetahui arah jurusnya.
1.4.5 Pengukuran Arah Kemiringan dan Kemiringan Bidang Hampir Datar
a. Nol kan dahulu penunjuk skala klinometer pada kompas.
b. Tempelkan sisi “W” kompas pada bidang yang diukur.
c. Jika nivo pada tabung klinometer masih berada di tengah-tengah dari tabung, maka
putarkan kompas hingga nivo bergerak ke salah satu sisi tabung, kita gerakan hingga
nivo berada pada sisi terjauh dari tengah.
d. Jika nivo sudah bergerak maksimal menjauhi tengah, maka itulah kemiringan bidang
tersebut.
e. Jika nivo mengarah ke sisi kiri tabung, maka kemiringan bidangnya kekanan, begitu
pula sebaliknya.
f. Setelah itu langsung klinometer diatur sehingga nivo berada di tengah (posisi level).
g. Angka yang ditunjukkan oleh penunjuk pada skala clinometer adalah besarnya sudut
kemiringan dari bidang yang diukur.
1.4.6 Pengukuran Jurus Bidang Hampir Datar
a. Bagian sisi kompas (Sisi E) ditempel pada bidang yang diukur.
b. Kedudukan kompas dihorisontalkan (Nivo bulat berada di tengah-tengah lingkaran).
c. Angka yang ditunjuk Jarum Utara (N) adalah Jurus bidang yang diukur berikan tanda
garis pada bidang tsb sesuai dengan arah jurusnya.
1.5 Tugas Praktikum
a. Mengukur bidang miring / Kekar sebanyak 10 buah data.
b. Mengukur bidang pada kemiringan hampir datar sebanyak 5 buah data.
1.6 Tugas Pra-Praktikum
a. Membaca ulasan dan pengertian Geologi Struktur secara umum, serta penggunaan
kompas dalam Geologi Struktur.
b. Mencari tahu dan memahami tentang bagian-bagian kompas serta kegunaanya.
c. Mempelajari aturan tangan kanan, Azimut dan Kuadran, serta langkah-langkah dalam
pengukuran bidang serta bidang hampir datar.
1.7 Soal Pre-Test
a. Sebutkanbagian-bagian kompas beserta fungsinya. Min.7
b. Jelaskan perbedaan antara kompas Azimut dan Kompas kuadran.
c. Sebutkan aplikasi kompas geologi untuk di lapangan.
d. Mengapa “W” pada kompas geologi berada disebelah kanan, bukan disebelah kiri?
e. Jelaskan tentang Strike, Dip, Plunge, Trend, Pitch, Kemiringan Hampir Datar?
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 8
BAB II
STRUKTUR BIDANG
2.1 Maksud dan Tujuan
Agar dapat mengetahui unsur- unsur pada struktur bidang.
Agar dapat menggambarkan geometri struktur bidang pada stereonet.
Agar dapat menuliskan notasi dan simbol dari struktur bidang.
Agar dapat menentukan kedudukan garis potong dari 2 struktur bidang.
2.2 Alat dan Bahan
Alat tulis
Waterproof
HVS
Penggaris
Kalkir
Schmidt net
Paku payung
2.3 Pendahuluan
2.3.1 Dasar Teori
Struktur bidang adalah struktur batuan yang membentuk geometri bidang. Struktur
geologi yang membentuk struktur bidang antara lain: perlapisan batuan, perlipatan, kekar,
bidang sesar, ketidakselarasan, urat(vein), dan lain- lain.
Istilah-istilah struktur bidang :
Jurus (strike) : arah garis horisontal yang dibentuk oleh perpotongan antara bidang yang
bersangkutan dengan bidang bantu horisontal, dimana besarnya jurus atau strike diukur
dari arah utara.
Kemiringan (dip) : besarnya sudut kemiringan terbesar yang dibentuk oleh bidang miring
yang bersangkutan dengan bidang horizontal dan diukur tegak lurus terhadap jurus atau
strike.
Kemiringan semu : sudut kemiringan suatu bidang yang bersangkutan (apparent dip)
dengan bidang horisontal dan pengukuran dengan arah tidak tegak lurus jurus.
Arah kemiringan : arah tegak lurus jurus yang sesuai dengan arah (dip direction)
miringnya bidang yang bersangkutan dan diukur dari arah utara.
Cara dalam penulisan simbol struktur bidang dinyatakan dengan dua cara yaitu azimuth
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 9
dan kuadran. Dalam penulisan jurus (strike) / kemiringan (dip) yaitu :
N X ° E / Y° DD
dimana :
X : jurus / strike, besarnya 0° - 360°
Y : kemiringan / dip, besarnya 0°- 90°
DD : dip direction (berdasarkan right hand rule)
Contoh : N 42° E / 78° SE
Sistem Kuadran :
( N / S) X° ( E / W) / Y°DD
dimana :
X : strike, besarnya 0° - 360°
Y : dip, besarnya 0° - 90°
DD : dip direction, menunjukkan arah kemiringan (dip)
Contoh: N 35° W / 30° SW atau S 35° E / 30° SW. (dalam sistem Azimuth:
N 145° E / 30°)
Gambar2.1. Penulisan notasi dan gambar sistem azimuth dan kwadran.
Tabel 2.1. Contoh cara penulisan kemiringan dan arah kemiringan untuk struktur bidang.
Selain dengan angka, kedudukan struktur bidang dapat pula dideskripsikandengan
menggunakan simbol pada peta. Penggunaan simbol ini menjadikan geometri dari sebuah
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 10
struktur pada peta lebih mudah dibayangkan. Pada peta, jurus ditandai dengan garis yang
digambarkan sejajar dengan garisjurus. Garis jurus sebaiknya digambarkan dengan panjang
yang cukup (± 10 mm) sehingga arahnya dapat ditentukan secara akurat di peta. Tanda
kemiringan diterakan pada titik tengah garis jurus, digambar menunjukkan arah kemiringan
dengan panjang 1/3 panjang garis jurus. Besar kemiringan dicantumkan di ujung tanda
kemiringan, ditulis dengan orientasi sejajar garis batas bawah/atas peta.
Gambar 2.2. Simbol-simbol peta untuk struktur bidang.
Gambar 2.3. Penggambaran kedudukan batuan pada peta lokasi ditunjukkan oleh lokasi 12, 13, dan 14
2.3.2 Metode Stereografis
2.3.2.1 Prinsip Proyeksi Stereografi
Proyeksi stereografi merupakan cara pendekatan deskripsi geometri yang efisien untuk
menggambarkan hubungan sudut antara garis dan bidang secara langsung. Pada proyeksi
stereografi, unsur struktur geologi digambarkan dan dibatasi di dalam suatu permukaan bola
(sphere).
Bila pada suatu bidang miring (gambar 2.1a) ditempatkan pada suatu permukaan
bola melalui pusat bola, maka bidang tersebut akan memotong permukaan bolasebagai
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 11
lingkaran besar (great circle) atau disebut sebagai proyeksi permukaan bola(spherical
projection). Pada umumnya dasar proyeksi yang akan dipakai adalah proyeksi sferis pada
belahan bola bagian bawah (lower hemisphere), akan tetapi ada pula yang memakai bagian
atasnya (upper hemisphere). Proyeksi permukaanbola ini digambarkan pada setiap titik pada
lingkaran besar melalui titik puncak zenith (gambar 2.1 b). Hasil proyeksi pada bidang equator
dinamakan stereogram atau proyeksi stereografi.
Gambar 2.4. Gambaran geometri proyeksi stereografi.
a. Proyeksi bidang dan garis pada permukaan bola
b. Proyeksi dari titik-titik potong garis pada permukaan bola pada equator melalui zenith
Struktur bidang atau garis diproyeksikan dengan cara yang sama yaitu melalui
perpotongannya dengan permukaan bola sebagai proyeksi sferis atau titik, dan diproyeksikan
pada bidang horizontal melalui Zenith. Beberapa contoh proyeksi bidang dan garis, serta
gambaran pada bidang equator nya (proyeksi stereografi),ditunjukkan pada gambar 2.2
Suatu garis atau bidang dengan kecondongan yang kecil, proyeksinya akan mendekati
lingkaran equator, sedangkan garis atau bidang yang sangat menunjam, proyeksinya akan
mendekati pusat lingkaran.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 12
Gambar 2.5. Beberapa contoh proyeksi stereografi garis dan bidang.
Cara penggambaran unsur struktur dengan Schmid Net
Jaring Schmid Net menggambarkan proyeksi stereografi dari berbagai kemiringan dari suatu
bidang dengan arah jurus Utara - Selatan. untuk menggambarkan stereogram dari suatu
bidang, selalu digunakan arah jurus pada garis Utara-Selatan, dan kemiringannya diukur pada
arah Barat – Timur. Untuk penggambaran praktis, umumnya digunakan kertas transparan atau
kalkir.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 13
Gambar 2.6. Jaring stereografi Schmid Net.
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :
Letakkan kertas kalkir di atas jaring dan gambarkan lingkaran luarnya, dan beri tanda
titik-titik utara - selatan dan pusat lingkaran.
Gambarkan garis jurus melalui pusat lingkaran sesuai dengan harga jurusnya.
Putar kalkir sehingga garis jurus berimpit dengan garis utara-selatan, dimana titik utara
jaring berimpit dengan harga jurusnya.
Gambarkan garis lengkung stereogram sesuai dengan besarnya kemiringan,dengan
besaran 0 di pinggir dan 90 di pusat lingkaran, dengan mengikuti lengkung lingkaran
besar pada jaring.
Apabila stereogram bidang telah digambarkan, posisi kalkir dikembalikan pada
kedudukan sebenarnya.
Hal yang perlu diperhatikan adalah arah kemiringan bidang, dan ini akan sangat tergantung
pada cara pengukuran dan jenis kompas yang dipakai. Oleh karena itu mutlak disebutkan arah
kemiringannya apakah cenderung kearah Timur atau ke Barat, dengan pengertian apakah
stereogramnya digambarkan disebelah kanan (E) atau kiri (W) dari garis utara-selatan jaring.
Cara penggambaran struktur garis pada dasarnya sama, proyeksi stereografinya berupa titik
atau garis menurut besaran arah dan penunjamannya. Besaran sudut penunjaman dapat
dilakukan pada arah N-S atau E-W dari jaring.
2.3.2.2 Proyeksi Kutub
Proyeksi kutub suatu bidang berupa suatu titik hasil proyeksi permukaan bola (Gambar 2.4),
sedangkan proyeksi kutub suatu garis merupakan suatu titik tembus suatu garis terhadap
permukaan bola pada bidang horizontal (Gambar 2.5).
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 14
(a) (b)
Gambar 2.7 (a) Proyeksi kutub srtruktur bidang, (b) Proyeksi kutub struktur garis.
Penggambaran Proyeksi Kutub Pada Polar Equal Area Net
Dalam pengeplotan penggambarannya, kertas kalkir posisinya tetap (tidak diputar-putar).
Prinsip dan hasilnya sama dengan bila menggunakan Schmidt Net, tetapi di sini lebih praktis.
1. Struktur bidang dengan sistem azimuth (Gambar 2.6)
Untuk mempermudah penggambarannya maka pembagian derajat pada jaring dimulai dari
titik W (jurus 0°) searah dengan jarum jam. Sedangkan besar kemiringan 0° dihitung dari
pusat lingkaran dan 90° pada tepi lingkaran. Proyeksi kutubnya berupa titik.
2. Struktur garis dengan sistem azimuth dan kwadran (Gambar 2.7)
Untuk mempermudah penggambarannya maka pembagian derajat pada jaring dimulai dari
titik N (bearing 0°) searah dengan jarum jam. Sedangkan besar penunjaman 0° dihitung dari
lingkaran luar (Lingkaian primitif) dan 90° pada tengah lingkaran. Proyeksi kutubnya berupa
titik.
Gambar 2.8. Cara penggambaran proyeksi kutub suatu bidang dengan kedudukan N040°E / 60°.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 15
Gambar 2.9. Cara penggambaran proyeksi kutub suatu garis dengan kedudukan 40°, N 60°E.
Penggambaran Proyeksi Kutub Pada Kalsbeek Counting Grid
Diagram kontur ini dipakai untuk data hasil pengukuran unsur struktur, arah atau jurus dan
besar penunjaman atau kemiringan. Dasar yang dipakai adalah proyeksi kutub suatu bidang.
Diagram kontur dibuat untuk mendapatkan distribusi dan kerapatan dari hasil pengukuran
dalam suatu area lingkaran proyeksi. Oleh karena itu jaring yang digunakan adalah jaring
Schmidt (equal area).
Untuk mendapatkan diagram ini, semua hasil pengukuran di lapangan digambarkan dalam
proyeksi kutub, kemudian kerapatannya dihitung dengan jaring penghitung (Kalsbeek Net),
yang hasilnya merupakan angka kerapatan (gambar 2.8 a). Untuk menghitung kerapatan
dalam diagram, hasil proyeksi seluruh pengukuran dibentangkan diatas jaring penghitung.
Cara perhitungannya ditunjukkan pada gambar 2.8 b. Perhitungan dilakukan pada setiap titik
ujung segitiga dan angka yang didapat adalah jumlah titik proyeksi yang tercakup dalam 6
buah segitiga yang melingkupi nya. Beberapa perkecualian ialah apabila titik proyeksi
dipinggir, maka perhitungan akan dilakukan bersama dengan titik proyeksi yang terletak
berhadapan.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 16
Gambar 2.10. (a) Jaring penghitung Calsbeek, (b) Cara perhitungan kerapatan.
Tahap selanjutnya adalah pembuatan kontur yang sesuai dengan distribusi dan harga
kerapatannya. Prinsip pembuatan kontur ditunjukan dalam gambar 2.9. (A = garis kontur
berharga 1) harga kontur merupakan harga persentase dari seluruh pengukuran.
Gambar 2.11. Cara pembuatan kontur (Ragan, 1979).
Ringkasan cara penggunaan STEREONET
1. Proyeksi stereografis
Schmidt Net.
* Struktur Bidang.
- Strike : 0° dimulai dari arah utara (N) pada Schmidt Net.
- Dip : 0° dimulai dari lingkaran primitif(tepi) dan.90° berada di pusat Schmidt Net.
* Struktur Garis.
- Bearing : 0° dimulai dari arah utara (N) pada Schmidt Net.
- Plunge : 0° dimulai dari lingkaran primitif (tepi) dan 90° berada pada pusat Schmidt
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 17
Net.
2. Proyeksi Kutub (menggunakan Polar Equal Area Net)
* Struktur Bidang.
- Strike : 0° dimulai dari sisi barat (W) pada Polar equal area net.
- Dip : 0° dimulai dari pusat dan 90° berada di lingkaran primitif (tepi).
* Struktur Garis.
- Bearing : 0° dimulai dari utara (N).
- Plunge : 0° dari ligkaran primitif (tepi) dan 90° berada di
2.4 Langkah Kerja
Analisis kekar dapat dikerjakan dengan tiga metoda, yaitu :
1. Histogram
2. Diagram Kipas
3. Stereografis
Tabel 3.1. Pengukuran data kekar.
Kesemua data yang dibutuhkan menggunakan data kuantitatif untuk dibuat statistik sehingga
mendapatkan hasil yang lebih presisi untuk analisis Kekar. Untuk analisis statistik, data yang
diperkenankan umumnya 50 buah data, tetapi 30 masih diperkenankan. Dalam analisis ini,
kekar gerus dan kekar tarik dipisahkan, karena gaya yang bekerja untuk kedua jenis kekar
tersebut berbeda.
Dalam analisis kekar dengan histogram dan diagram kipas yang dianalisis hanyalah jurus dari
kekar dengan mengabaikan besar dan arah kemiringan, sehingga analisis ini akan mendekati
kebenaran apabila kekar-kekar yang dianalisis mempunyai dip cukup besar atau mendekati
90o. Gaya yang bekerja dianggap lateral. Karena arah kemiringan kekar diabaikan, maka
dalam perhitungan kekar yang mempunyai arah N1800E dihitung sama dengan N0ºE, N220°E
dihitung sama dengan N40ºE, N115°E sama dengan N305°E. Jadi semua pengukuran
dihitung kedalam interval N0ºE-N90ºE dan N270ºE-N0ºE.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 18
Membuat Histogram
1. Buat sumbu datar untuk jurus kekar, dan sumbu tegak sebagai prosentase.
2. Sumbu datar terdiri dari N 270º E-N 0º E-N 90º E. Buat skala sesuai interval (10
derajad)
3. Buat blok masing-masing interval sesuai dengan besar prosentase masing-masing
interval (Diagram 4.1).
Diagram 2.1. Histogram penentuan arah gaya utama yang membentuk kekar.
Membuat Diagram Kipas
1. Buat setengah lingkaran bagian atas dengan jari-jari menunjukkan besar prosentase
terbesar dari interval yang ada (misal 20%)
2. Pada sumbu datar plot prosentase jumlah kekar. Pada sumbu vertikal dari pusat 0%,
jari-jari terluar = prosentase terbesar (20%).
3. Busur lingkaran dibagi menurut interval (jika interval 10 derajat maka dibagi menjadi
18 segmen). Plot jurus kekar sesuai interval (N 270º
E,280º,…..,350º,0º,10º,……,80º,N 90º E)
4. Buat busur lingkaran dengan jari-jari = prosentase masing-masing interval mulai dari
batas bawah interval hingga batas atas interval. Misal interval N 0º E-N 350º E
prosentase = 16%, maka buat busur lingkaran dari sumbu tegak N 0º E hingga N 350º
E dengan jari-jari skala 16% (Diagram 4.2)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 19
Diagram 4.2. Diagram kipas untuk penentuan arah gaya utama yang membentuk kekar.
Penggambaran Struktur Bidang Pada Schmidt Net
Cara penggambaran struktur bidang N 140E/30SW :
a. Persiapkan alat praktikum yang dibawa.
b. Gunakan kalkir dan schmidt net, taruh kalkir diatas schmidt net dengan menggunakan
paku payung.
c. Buatlah bidang pada kalkir dengan cara berikut :
- Ukurkan besar jurus 140 ke timur (E) dari utara (N).
- Kemudian gambarkan garis jurus , titik strike di vertikalkan ke bagian S (atau titik
yg terdekat dgn N atau S).
- Ukur sudut lengkungan 30 sepanjang garis barat-timur pada sisi W.
- Kembalikan pada posisi semula dan struktur bidang tersebut telah tergambar.
Gambar 2.12. Hasil penggambaran struktur bidang pada Schmidt net.
- Cara menentukan garis perpotongan dari 2 bidang N40ºE/60ºSE dan N130ºE/30ºSW :
1. Persiapkan alat praktikum yang dibawa.
2. Gunakan kalkir dan schmidt net, taruh kalkir diatas schmidt net dengan menggunakan
paku payung.
3. Buatlah bidang pada kalkir dengan cara berikut :
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 20
- Gambarkan stereografi dari dua bidang :
Bidang 1
a) Putar kalkir 40º searah jarum jam (arah NE), tentukan besar kemiringan 60º dari sudut
pelengkungan pada sisi E.
b) Kemudian lakukan sama halnya dengan cara penggambaran struktur bidang yang telah
dijelaskan pada sebelumnya.
Bidang 2
a) Putar kalkir 60º berlawanan jarum jam (arah N-W), tentukan kemiringannya 30º dari
sudut pelengkungan pada posisi W.
b) Kemudian lakukan sama halnya dengan cara penggambaran struktur bidang yang telah
dijelaskan pada sebelumnya.
- Dan titik potong antara dua bidang tersebut, merupakan kedudukan garis potong dari
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 21
dua bidang tersebut. Putar garis ini pada arah utara selatan,dan beri tanda pada
lingkaran pinggirnya. Besaran penunjaman dapat langsung dibaca, dan arah garisnya
dapat dibacadengan mengembalikan posisi kalkir pada arah yang semula. Kedudukan
garis potong adalah30o,N201 oE.
2.5 Tugas Praktikum
1. Gambarkan struktur Bidang ,dgn kedudukan sebagai berikut :
15 data struktur bidang di praktikum acara 1
2. Gambarkan dan berapa kedudukan garis potong dari data-data struktur bidang berikut
ini:
- N 45o E / 60 o SE dan N 280 o E / 40 o NE
- N 116 o E / 80 o SW dan N 250 o E / 50 o NW
- N 76 o E / 30 o SE dan N 90 o W / 79 o N
- N 123 o E / 37 o SW dan N 45 o W / 23 o NE
- N 270 o E / 68 o N dan N 73 o E / 27 o SE
2.6 Tugas Pra praktikum
1. Jelaskan tentang struktur garis secara detail? Berikan gambar minimal 5 beserta
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 22
penjelasan setiap gambarnya!
2. Jelaskan tentang proyeksi stereografi pada struktur bidang? serta jelaskan tentang
konsep dasar dari stereografi! (minimal 1 lembar penuh)
2.7 Soal Pre- test
1. Apa yang dimaksud dengan struktur garis? Dan berikan contohnya minimal 5!
2. Sebut dan Jelaskan unsur - unsur struktur bidang minimal 3?
3. Jelaskan tentang aturan tangan kanan beserta gambar? Dan mengapa di Indonesia
Menggunakan jari pada tangan kiri!
4. Tuliskan contoh cara penulisan notasi sistem azimuth dan kuadran pada struktur
bidang minimal 2 beserta gambarnya?
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 23
BAB 3
GEOMETRI STRUKTUR GARIS DAN ANALISIS ARUS PURBA
3.1 Maksud dan Tujuan
a. Mampu menggambarkan geometri unsur struktur garis kedalam proyeksi
stereografis dalam bentuk dua dimensi.
b. Mampu menentukan unsur struktur garis Plunge, Trend dan Pitch pada struktur
bidang.
c. Mengetahui cara mengukur serta penulisan notasi unsur struktur garis dengan
menggunakan kompas geologi.
d. Mampu menentukan kedudukan struktur garis yang merupakan hasil dari
perpotongan dua bidang.
e. Mampu menentukan arah arus purba pada struktur sedimen dengan metode
stereografis.
3.2 Alat dan Bahan
1. Alat tulis lengkap (ATK)
2. Kertas kalkir
3. Water proof
4. Kompas geologi
5. Busur derajat
6. Modul praktikum
7. Penggaris
8. Paku pines
9. clipboard
3.3 Pendahuluan
3.3.1 Struktur Garis
Struktur garis merupakan struktur yang memiliki geometri yang linear. Contohnya gores garis,
lineasi mineral, kekar kolom, sumbu lipatan dll. Struktur garis dapat dibedakan menjadi
stuktur garis riil, struktur garis semu.
Struktur garis riil : struktur garis yang arah dan kedudukannya dapat diamati dan diukur
langsung di lapangan, contoh: gores garis yang terdapat pada bidang
sesar.
Struktur garis semu : semua struktur garis yang arah atau kedudukannya ditafsirkan dari
orientasi unsur-unsur struktur yang membentuk kelurusan atau liniasi,
contoh: liniasi fragmen breksi sesar, liniasi mineral-mineral dalam batuan
beku dan metamorf, arah liniasi struktur sedimen (groove cast, flute cast),
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 24
kelurusan sungai dan hinge line.
Unsur Struktur Garis:
Plunge (Penunjaman) adalah sudut yang dibentuk oleh struktur garis tersebut
dengan bidang horizontal, diukur pada bidang vertikal. Nilai dari penunjaman
berkisar antara 0° dan 90°, penunjaman 0° dimiliki oleh garis horizontal, dan
penunjaman 90° dimiliki oleh garis vertikal. Secara umum, penunjaman yang
berkisar antara 0° dan 20° dianggap lanadai (shallow), penunjaman yang
berkisar antara 20° dan 50° dianggap sedang (moderate), dan penunjaman yang
berkisar antara 50° dan 90° dianggap terjal (steep).
Trend (Arah Penunjaman) adalah arah dari proyeksi struktur garis tersebut
kebidang horizontal. Struktur garis dan proyeksinya harus terletak pada bidang
vertikal yang sama. Arah penunjaman dapat dideskripsikan dengan
menggunakan konveksi azimuth ataupun kuadran. Arah penunjaman harus
menunjuk pada arah kemana struktur garis tersebut menunjam.struktur garis
yang menunjam ke timur tidak sama dengan struktur garis yang menunjam ke
barat. Kedua struktur garis tersebut berlawanan arah.
Pitch (Rake) adalah sudut anatara struktur garis tersebut dengan horizontal,
diukur pada bidang dimana struktur garis tersebut terbentuk. Kisaran nilai pitch
adalah antara 0° dan 90°. Jika arah penunjaman sejajar dengan garis jurus,
maka pitch = 0°. Jika arah penunjaman tegak lurus garis jurus, maka pitch =
90°.
trend
pitch
plunge
Gambar 3.1. diagram blok menggambarkan plunge, trend dan pitch.
Cara Penulisan (notasi) Dan Simbol Struktur Garis Pada Peta Geologi
Penulisan (notasi) struktur garis dapat dinyatakan berdasarkan dua sistem :
A. Sistem azimuth
Sistem azimuth hanyamengenalsatupenulisanyaituYo,NXoE
Yoadalah “Plunge”, besarnya 0-90o (sudutvertikal)
Xoadalah “Trend”, besarnya 0-360o.
Contoh: 30°, N 45° E
B. Sistem kuadran
Penulisantergantungpadaposisi kuadran yang diinginkan,
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 25
sehinggamempunyaibeberapacarapenulisan, misalnya:
Sistemazimuth : 30o,N45oE makamenurutsistemkuadrannyaadalah 30o,N45oE.
Sistemazimuth : 45°,N90oE makamenurutsistemkuadrannyaadalah 45o,N 90oE atau
45o, S 90oE
Gambar 3.2. Sistem penulisan (notasi) dan simbol struktur garis.
Struktur garis dapat dinyatakan dengan simbol tertentu pada peta yaitu sebagai
berikut.
Tabel 3.1. Simbol struktur garis pada peta.
Arah dan penunjamangaris 40
Garis horizontal
Garisvertikal
Penunjamangarispadabidang 25
10
Garisganda
Kedudukanmemanjangnya mineral o
Arahdanpenunjamandariperpotonganrekahan
>>
Arahdanpenunjamandariperpotonganbidangdanfoliasi
Kedudukanmemanjangnyafragmen 0
30
Pitch darigarispadabidang
3.3.2 Analisis Arus Purba
Analisis arus purba dapat dilakukan dengan menggunakan struktur sedimen
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 26
khususnya pada struktur sedimen yang menunjukan indikasi arah transportasi sedimen,
baik berupa bidang maupun garis, antara lain:
a. Flutecast
b. Groovecast
c. Crossbedding
d. Current ripple
Pada dasarnya struktur tersebut mencerminkan arah yang dapat diwakili sebagai
struktur garis yang berdiri sendiri, dan secara umum terletak pada struktur bidang yaitu
perlapisan batuan. Untuk mengetahui arah arus sebenarnya atau pada saat keadaan
pembentukannya, maka kedudukan lapisan batuan tersebut harus dikembalikan pada
posisi horizontal yaitu posisi pada saat sedimentasi.
3.4 Langkah Kerja
3.4.1 Cara Pengukuran Struktur Garis dengan Kompas Geologi
A. Pengukuran Trend (Arah Penunjaman)
1. Tempelkan alat bantu (clipboard) pada posisi tegak dan sejajar terhadap arah
struktur garis yang akan diukur.
2. Tempelkan sisi “W” atau “E” kompas pada posisi kanan atau kiri alat bantu
dengan visir kompas (sighting arm) mengarah ke struktur garis tersebut.
3. Levelkan/horisontalkan kompas hingga nivo mata sapi berada di tengah-
tengah, maka harga yang ditunjukkan oleh jarum Utara kompas adalah harga
arah penunjaman (trend).
B. Pengukuran Plunge
1. Tempelkan sisi “W” kompas pada sisi atas alat bantu yang masih dalam
keadaan vertical.
2. Levelkan clinometer hingga gelembungnya berada di tengah, maka besaran
sudut vertikal yang ditunjukkan oleh penunjuk pada skala clinometers
merupakan sudut penunjamannya.
C. Pengukuran Pitch
1. Buat garis horizontal pada bidang dimana struktur garis tersebut terdapat (sama
dengan jurus bidang tersebut) yang memotong struktur garis yang akan diukur
pitch-nya.
2. Ukur besar sudut lancip yang dibentuk oleh garis horizontal dengan struktur
garis tersebut menggunakan busur derajat, kemudian baca besar sudutnya.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 27
(a)
(b) (c)
Gambar 3.3. Cara pengukuran (a) trend (arah penunjaman), (b) plunge (penunjaman), (c) pitch
(rake) menggunakan kompas geologi.
3.4.2 Cara Penggambaran Struktur Garis kedalam Proyeksi Stereografis
A. Penggambaran Struktur Garis (misal 26°, N 40°E)
1. Plot besaran trend 40° kearah timur (E) dari arah utara (N), kemudian tandai
arah garis trend (gambar 3.4.a)
2. Putar kalkir sehingga garis trend berimpit dengan garis N-S atau W-E jaring,
kemudian ukur besarnya plunge yaitu sebesar 26°, kemudian tandai (gambar
3.4.b)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 28
3. Putar kalkir dan kembalikan pada posisi awal atau arah N kalkir berimpit N
jaring, maka titik tersebut merupakan proyeksi struktur garis dengan
kedudukan 26°, N 40°E (gambar 3.4.c)
Gambar 3.4. Penggambaran stereogram struktur garis kedudukan 26°, N40°E.
B. Cara Penggambaran Arah Arus Purba
Contoh: pada suatu perlapisan N45°E/ 60°SE terdapat struktur sedimen flutecast
yang dapat dikenali arahnya yaitu pada arah N65°E. Akan ditentukan arah
sebenarnya dari sedimentasinya.
1. Buat stereogram struktur bidang dengan kedudukan N45°E/ 60°SE.
Kemudian ploting trend flutecast yaitu N65°E (gambar 3.7.a)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 29
2. Putar kalkir hingga posisi bidang berimpit dengan arah N-S, tentukan titik
potong arah tersebut dengan bidang pada stereogramnya (merupakan
kedudukan garis flutecast). Kemudian buat garis putus-putus dari titik potong
mengikuti garis lengkung jaring (garis lintang) hingga garis luar lingkaran
jaring dan tandai pada garis luar lingkaran tersebut. Dari titik tanda tersebut
buat garis lurus hingga ke pusat lingkaran (gambar 3.7.b)
3. Untuk membaca arah arus sebenarnya kembalikan kalkir pada posisi semula,
maka garis lurus yang telah dibuat tadi merupakan arah arus sebenarnya yaitu
pada kedudukan N81°E (gambar 3.7.c)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 30
Gambar 3.5. Penggambaran arah arus purba pada kedudukan N45°E/ 60°SE dan N65°E.
3.5 Tugas Praktikum
1. Gambarkan dan berapa kedudukan garis perpotongan dari dua bidang berikut ini:
- N 45° E / 60° SE dan N 280° E / 40° NE
- N 116° E / 80° SW dan N 260° E / 50° NW
- N 80° E / 30° SE dan N 50° W / 40° SW
- N 120° E / 37° SW dan N 160° W / 30° SE
- N 285° E / 55° NW dan N 140° E / 45° SW
2. Gambarkan struktur garis ,degan kedudukan sebagai berikut :
- 8°6, N 60° E
- 65, N 95 E
- 32, N 190 E
- 75, N 225 E
- 48, N 285 E
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 31
3.6 Form Laporan
LABORATORIUM GEOLOGI DINAMIK
PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI – FAKULTAS SAINS DAN TEKNIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Jalan Mayjen Sungkono Km.5, Kalimanah, Purbalingga 53371
Acara 2. Pengukuran Struktur Garis
Lokasi : Nama :
Tanggal : Nim :
Pengukuran struktur garis dengan kedudukan sebagai berikut:
No Plunge, Trend
Pengukuran kedudukan garis perpotongan dari dua bidang berikut ini:
No Strike/dip
Nama Asisten :
Nim :
Acc :
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 32
3.7 Tugas Pra Praktikum
1. Hasil Praktikum (Hasil Ploting Di Stereonet )
5 Ploting Kedudukan Garis Perpotongan dari Dua Bidang
5 Ploting Struktur Garis
2. Pembahasan
5 Langkah Kerja Ploting Kedudukan Garis Potong 2 Bidang
5 Langkah Kerja Ploting Struktur Garis
3. Lampiran (hasil praktikum yang sudah di acc asdos)
3.8 Soal Pre-Test
1. Apa yang di maksud dengan struktur garis?
2. Berikan contoh struktur garis minimal 3!
3. Sebut dan Jelaskan unsur2 struktur garis minimal 3!
4. Sebutkan aplikasi metoda grafis geometri untuk struktur bidang dan untuk struktur
garis! (Min 2)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 33
BAB 4
ANALISIS SESAR
4.1 Maksud Dan Tujuan
Mampu mengetahui geometri sesar
Mampu mengetahui data-data yang dibutuhkan untuk analisis sesar
Mampu menafsirkan gaya tektonik yang bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu
interpretasi struktur sesar yang ada di daerah penelitian.
Mampu menentukan nama sesar
4.2 Alat Dan Bahan
Steronet (polar net, Kalsbeek counting grid, Schimid net)
Kalkir ukuran A4 sebanyak 10 buah
Pines
ATK
Kertas A4
Busur derajat
Penggaris
Spidol 12 warna
Hector
4.3 Pendahuluan
4.3.1 Pengertian
Sesar adalah kekar yang telah mengalami pergeseran (offset). Sesar (fault) dapat
berbentuk satu bidang diskrit yang planar atau membentuk suatu zona (faultzone) yang terdiri
dari banyak bidang-bidang sesar yang sejajar dan saling berhubungan(net-work). Pergeseran
pada sesar dapat terjadi sepanjang garis lurus (translasi) atau terputar (rotasi).
4.3.2 Unsur Struktur Sesar
Sesar terdiri atas beberapa bagian yaitu berikut penjelasannya (Gambar 3.1)
1. Bidang sesar (fault plane) adalah suatu bidang sepanjang rekahan dalam batuan yang
tergeserkan.
2. Jurus sesar (strike) adalah arah dari suatu garis horizontal yang merupakan
perpotongan antara bidang sesar dengan bidang horizontal.
3. Kemiringan sesar (dip) adalah sudut antara bidang sesar dengan bidang horizontal dan
diukur tegak lurus jurus sesar.
4. Atap sesar (hanging wall) adalah blok yang terletak diatas bidang sesar apabila bidang
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 34
sesamya tidak vertikal.
5. Foot wall adalah blok yang terletak dibawah bidang sesar.
6. Slickenside ataus lickenline adalah bukti pergerakan (slip) pada bidang sesar. Istilah
striation atau fault grooves sering juga digunakan.
7. Throw adalah komponen vertikal dari slip/separation,diukur pada bidang vertikal yang
tegak turus jurus sesar.
8. Heave adalah komponen horizontal dari slip / separation, diukur pada bidang vertikal
yang tegak lurus jurus sesar.
9. Strike-slip fault yaitu sesar yang mempunyai pergerakan sejajar terhadap arah jurus
bidang sesar kadang-kadang disebut wrench faults, tear faults atau transcurrent faults.
10. Dip-slip fault yaitu sesar yang mempunyai pergerakan naik atau turun sejajar terhadap
arah kemiringan sesar.
11. Oblique-slip fault yaitu pergerakan sesar kombinasi antara strike-slip dan dip-slip.
Gambar 4.1 Unsur struktur sesar
4.3.3 Sifat Pergeseran Sesar
Sifat pergeseran sesar dapat dibedakan menjadi :
a. Separation (pergeseran relatif semu)
Jarak tegak lurus antara bidang yang terpisah oleh sesar dan diukur pada bidang sesar.
Komponen dari separation dapat diukur pada arah tertentu, umumnya sejajar jurus atau
arah kemiringan bidang sesar (gambar 3.2).
b. Slip (pergeseran relatif sebenarnya)
Pergeseran relatif sebenarnya pada sesar, diukur dari blok satu ke blok yang lain pada
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 35
bidang sesar dan merupakan pergeseran titik-titik yang sebelumnya berimpit. Total
pergeseran disebut juga “Net slip” (gambar 3.2).
Gambar 4.2 : Diagram blok yang memperlihatkan pergeseran sebenarnya dan semu dari sesar
A. Net slip (total pergeseran relatif sebenarnya)
B. Strike separation (pergeseran relatif semu searah jurus bidang sesar)
C. Dip separation (pergeseran relatif semu searah kemiringan bidang sesar)
Gambar 4.3 : Diagram blok yang memperlihatkan pergeseran sebenarnya dari sesar
1.) Reverse left slip fault, 2) Strike left slip fault, 3) Normal left slip fault
4) Dip slip fault (Normal slip fault), 5) Normal right slip fault
4.3.4 Klasifikasi Sesar
Sesar dapat diklasifikasikan dengan pendekatan geometri yang berbeda, dimana aspek
yang terpenting dari geometri tersebut adalah pergeseran. Atas dasar sifat pergeserannya,
maka sesar dibagi menjadi :
4.3.4.1 Berdasarkan Sifat Pergeseran Semu (Separation)
a. Strike separation
- Left separation fault, jika pergeseran ke kirinya hanya dilihat dari satu kenampakan
horizontal.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 36
Gambar 4.4 Left separation fault
- Right separation fault, jika pergeseran ke kanannya hanya dilihat dari satu kenampakan
horizontal.
Gembar 4.5 Right separation fault
b. Dip separation
- Normal separation fault
Jika pergeseran normalnya hanya dilihat dari satu penampang vertikal.
Top
Gambar 4.6 Normal separation fault
- Reverse separation fault
Jika pergeseran naiknya hanya dilihat dari satu penampang vertikal.
Top
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 37
Gambar 4.7 Reverse separation fault
4.3.4.2 Berdasarkan Sifat Pergeseran Relatif Sebenarnya (Slip)
a. Strike slip.
- Left - slip fault. Blok yang berlawanan bergerak relatif sebenarnya ke arah kiri.
- Right - slip fault. Blok yang berlawanan bergerak relatif sebenarnya ke arah kanan.
b. Dip slip.
- Normal - slip fault. Blok hanging wall bergerak relatif turun.
- Reverse - slip fault. Blok hanging wall bergerak relatif naik.
c. Oblique slip.
- Normal left -slip fault.
- Normal right -slip fault.
- Reverse left - slip fault.
- Reverse right -slip fault.
- Vertikal oblique -slip fault.
Gambar 4.8 Jenis-jenis sesar
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 38
4.3.5 Analisis Sesar
Data yang digunakan :
1. Data tension / Kekar tarik
2. Kekar gerus
3. Breksiasi/ breksi sesar
4. Ofset sesar
Kesemua data yang dibutuhkan menggunakan data kuantitatif untuk dibuat statistik
sehingga mendapatkan hasil yang lebih presisi untuk analisis sesar. Untuk analisis statistik,
data yang diperkenankan umumnya 50 buah data, tetapi 30 masih diperkenankan. Untuk
pencatatan data kekar pergunakanlah tabel 4.1, untuk pencatatan data breksiasi pergunakanlah
tabel 4.2, sedangkan untuk pengukuran pada sesar minor pergunakanlah tabel 4.3 untuk
mencatat data.
Tabel 4.1 Pengukuran kekar Tabel 4.2 Pengukuran breksiasi
Tabel 4.3 Pengukuran sesar minor
4.4 Langkah Kerja
1. Menentukan arah umum breksiasi menggunakan diagram kipas
a. Buatlah tabel seperti contoh (tabel 4.4). Dalam perhitungan kekar yang mempunyai
arah N1800E dihitung sama dengan N0ºE, N220°E dihitung sama dengan N40ºE,
N115°E sama dengan N305°E. dengan kata lain arah breksiasi yang berada di
kuadran II ditambah 180° agar masuk kedalam kuadran IV dan arah breksiasi yang
berada di kuadran III dikurangi 180° agar masuk kedalam kuadran I. Jadi semua
pengukuran dihitung kedalam interval N0ºE-N90ºE dan N270ºE-N0ºE.
Tabel 4.4 Perhitungan arah dan persentase data breksiasi
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 39
b. Masukan data breksiasi pada kolom turus menggunakan perhitungan balok dan pada
kolom frekuensi tulislah jumlah turus pada setiap arah breksiasi.
c. Menghitung hasil presentase, dengan cara:
Persentase = x 100%
d. Membuat Diagram Kipas, buat setengah lingkaran bagian atas dengan jari-jari
menunjukkan besar prosentase terbesar dari interval yang ada (misal 20%).
e. Pada sumbu datar plot prosentase jumlah kekar. Pada sumbu vertikal dari pusat 0%,
jari-jari terluar = prosentase terbesar (20%).
f. Busur lingkaran dibagi menurut interval (jika interval 10 derajat maka dibagi menjadi
18 segmen). Plot jurus kekar sesuai interval (N 270º
E,280º,…..,350º,0º,10º,……,80º,N 90º E)
g. Buat busur lingkaran dengan jari-jari = prosentase masing-masing interval mulai dari
batas bawah interval hingga batas atas interval. Misal interval N 271º E-N 280º E
prosentase = 20% merupakan data terbanyak, maka buat busur lingkaran dari sumbu
horisontal N 271º E hingga N 280º E dengan jari-jari skala 16% (Gambar 4.9.)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 40
Gambar 4.9. Arah umum breksiasi pada diagram kipas
2. Analisis sesar pada steronet
a. Ploting pole data shear pada polar equal net (Gambar 4.10)
Gambar 4.10. Ploting pole data shear pada polar equal net
b. Penghitungan densitas pole data shear pada kalsbeek counting grid (Gambar 4.11)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 41
Gambar 4.11. Penghitungan densitas pole data shear pada kalsbeek counting grid
c. Penggambaran kontur densitas pole data shear pada kalsbeek counting grid (Gambar
4.12)
Gambar 4.12 Penggambaran kontur densitas pole data shear pada kalsbeek counting grid
d. Proyeksi pole Sf 1 menjadi bidang Sf1, begitu juga untuk Sf2 (Gambar 4.13)
Gambar 4.13 Proyeksi pole Sf 1 menjadi bidang Sf1, begitu juga untuk Sf2
e. Titik potong bidang Sf 1 dan Sf 2 merupakan σ2. Kemudian dari σ2 diproyeksikan
90° akan dihasilkan bidang bantu σ1 dan σ3, jika besar sudut Φ = <90°(sudut lancip)
maka di depan σ2 merupakan σ1, jika besar sudut Φ = >90°(sudut tumpul) maka di
depan σ2 adalah σ3, posisi titik σ tersebut harus berada di tengah diantara garis lurus
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 42
bidang Sf1 dan Sf2. Jika sudah di tentukan titik σ1 untuk mengetahui titik σ3 perlu di
proyeksikan 90° pada bidangnya sendiri, begitu juga sebaliknya (Gambar 4.14)
Gambar 4.14 Penentuan arah gaya
f. Masukan data breksiasi N280°E kedalam analisis dan gambarkan bidangnya melalui
σ2, sehingga di dapatkan bidang sesarnya yang berarah N100°E/77°SW (Gambar
4.15).
Gambar 4.15. Penggambaran bidang sesar
g. Menentukan arah pergerakan strike slip sesar, dapat dilakukan dengan cara melihat
sudut yang dibentuk oleh σ1 dengan garis lurus bidang sesar, jika lancip maka arah
pergerakannya masuk. Untuk memberi nama arah pergerakannya jika panahnya
berputar searah jarum jam maka disebut geser kanan, jika pergerakanpanahnya
berputar berlawanan dengan arah jarum jam disebut geser kiri. Pada contoh panahnya
berputar berlawanan dengan arah jarum jam maka disebut geser kiri. (Gambar 3.16).
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 43
Gambar 4.16. Penggambaran pergerakan strike slip
h. Menentukan arah netslip dengan cara menarik garis panah dari pusat stereonet hingga
pertemuan bidang sesar denga bidang bantu σ1 dan σ3. Kemudian untuk menentukan
arah pergerakan netslipnya harus memperhatikan pergerakan strike slip sesarnya.
Arah netslip akan sama dengan arah strike slipnya.
Untuk netslip yang mengarah keluar stereonet (seperti contoh) menunjukan
pergerakan dipslip pada hanging wall menurun. Untuk netslip yang mengarah ke
pusat stereonet, menunjukan pergerakan dipslip hanging wall relatif naik terhadap
foot wall (Gambar 4.17.).
Gambar 4.17. Penggambaran netslip
i. Membaca besar sudut pitch, petama putarlah bidang sesar kearah Utara-Selatan,
kemudian bacalah banyaknya kotak pada garis lengkung Schmidt net dari bagian luar
bidang sesar hingga titik pangkal netslipnya (lihat Gambar 3.16). Selain besarnya
sudut pitch yang perlu diperhatikan adalah arah pitch membuka pada contoh diatas
pitch mengarah ke SE (tenggara) (Gambar 4.18).
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 44
Gambar 4.18. Pembacaan pitch
j. Menentukan nama sesar sebelum menentukan nama sesar haruslah diketahui
beberapa komponen sesar yang didapatkan dari analisis stereonet diantaranya; bidang
Sf1 dan Sf2, bidang bantu σ1 dan σ3, bidang sesar, arah σ1, σ2, σ3, netslip, pitch,
strike slip, slip. Berikut adalah contoh menentukan nama sesar. (Gambar 4.19).
Gambar 4.19. Hasil analisis sesar menggunakan stereonet.
Pembacaan hasil analisis:
Sf 1 : N 128° E/55° SW
Sf 2 : N 226° E/57° NE
Bidang bantu σ1 dan σ3 : N 353° E/ 53°NE
Breksiasi : N 280° E
Bidang sesar : N100°/ 77° SW
σ1 : 41°, N 89° E
σ2 : 47°, N 264° E
σ3 : 6°, N 354° E
Pitch : 40°, membuka ke SE
Netslip : 40°, N 110° E
Strike slip : Geser kiri
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 45
Dip slip : Menurun
Nama sesar : Sesar Mendatar Mengiri Turun
3. Penamaan Sesar
Untuk mengamati keberadaan arah dan jenis sesar di lapangan dapat diperkirakan
dengan melihat indikasi yang ada seperti adanya dragfold (lipatan seret), offset
litologi, kekar-kekar, cermin sesar, slicken side, breksiasi, zona-zona hancuran,
kelurusan mata air panas dan air terjun.
a. Klasifikasi Anderson
Seperti dikemukakan oleh beberapa penulis yaitu Anderson (1951, dalam
Sukendar Asikin, 1977) bahwa pergerakan sesar akan mengikuti arah rekahan
gunting (Conjugate Shear). Analisa kekar digunakan dalam penentuan jenis
sesar, hal ini dapat diterapkan dengan menggunakan pemodelan Anderson
(Gambar 3.17) dengan patokan sebagai berikut :
1. σ1 berada pada titik tengah perpotongan 2 bidang Conjugate Shear
yang mempunyai sudut sempit.
2. σ 2 berada pada titik perpotongan antara 2 bidang Conjugate Shear
3. σ 3 berada pada titik tengah perpotongan 2 bidang Conjugate Shear
yang mempunyai sudut tumpul.
4. σ 1 > σ 2 > σ 3.
5. Orientasi tensional joint searah dengan orientasi σ 1.
6. Orientasi stylolites σ dengan orientasi σ 1 atau searah dengan
orientasi σ 3.
7. Bidang shear dan tensional akan membentuk sudut sempit.
8. Bidang shear dengan release joint akan membentuk sudut tumpul.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 46
Gambar 4. 20. Klasifikasi sesar (Anderson, 1951 dalam Sukendar Asikin, 1977).
Klasifikasi sesar telah banyak dikemukakan oleh para ahli terdahulu, mengingat struktur
sesar adalah rekahan kekar di dalam bumi yang ditimbulkan karena pergeseran sehingga untuk
membuat analisis strukturnya diusahakan untuk dapat mengetahui arah dan besarnya
pergeseran tersebut. Indikasi sesar di lapangan tidak mudah untuk ditemukan untuk itu
pengolahan data kekar untuk mengetahui tegasan utamanya dapat dilasifikasikan menjadi tiga
jenis berdasarkan orientasi tegasan utama (Anderson, 1951, dalam Sukendar Asikin, 1977)
dan dinyatakan dalam σ1 (tegasan terbesar), σ2 (tegasan menengah), dan σ3 (tegasan terkecil)
yang saling tegak lurus satu sama lain secara triaksial. Sesar tersebut secara dinamik
diklasifikasikan menjadi:
1. Sesar normal, dimana σ1 vertikal dan σ2 serta σ3 horizontal. Besarnya sudut
kemiringan (dip) bidang sesar mendekati 60º.
2. Sesar mendatar, dimana σ2 vertikal dan σ1 serta σ3 horizontal.
3. Sesar naik, dimana σ3 vertikal dan σ1 dan σ2 horizontal. Kemiringan bidang sesar
mendekati 30º. Dalam hal ini, bidang sesar vertikal dan bergerak secara
horizontal.
b. Klasifikasi Rickard (1972)
Kinematika struktur geologi yang berkembang secara regional secara langsung
akan mempengaruhi kondisi geologi struktur daerah penelitian. Untuk penamaan
sesar, mengacu pada penamaan Rickard (1972) yang ditunjukan pada gambar
3.18.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 47
Gambar 4.21. Klasifikasi Rickard (1972, dalam Chabibie.A, dkk, 2005)
Klasifikasi ini digunakan berdasarkan kombinasi besar kemiringan bidang sesar
terhadap besar pitch. Karakteristik penamaan oleh Rickard (1972) adalah mengkombinasikan
besar kemiringan bidang sesar dengan besar sudut pitch. Berdasarkan kombinasi tersebut yang
kemudian di plot pada diagram, menghasilkan penamaan sesar dengan ketentuan sebagai
berikut:
Apabila pitch kurang atau sama dengan 10o, maka sesar dinamakan sesar mendatar,
baik dekstral (menganan) atau sinistral (mengiri). Dalam klasifikasi ini dinamakan
sebagai right slip fault atau left slip fault. Ditunjukan pada zona sesar mendatar
berwarna abu abu pada gambar 4.8.
Apabila pitch 80o sampai 90o, dengan memperhatikan pergerakan sesar (naik atau
normal) maka akan diberi nama normal fault atau reverse fault. Namun apabila
o
kemiringan bidang sesar kurang dari 45 dengan pitch yang sama dengan ketentuan
tersebut maka untuk sesar normal akan dinamakan lag normal fault (low angel normal
fault) atau sesar normal bersudut kecil, dan untuk sesar naik dinamakan thrust fault
atau sesar anjak. Ditunjukan pada zona sesar normal dan naik dengan warna abu abu
pada gambar 4.8.
Apabila pitch pada sesar mendatar lebih besar dari 10 o dan kurang atau sama dengan
45o, maka sesar merupakan sesar mendatar yang memiliki pergerakan naik atau
turun. Dalam penamaan, pergerakan naik atau turun tersebut menjadi keterangan
pergerakan sesar mendatar tersebut, misalnya sesar mendatar mengiri (sinistral)
normal dengan ciri pitch lebih besar dari 10 o dan kurang atau sama dengan 45 o serta
kemiringan bidang sesar 50o maka dinamakan normal left slip fault. Apabila
kemiringan sesar kurang dari 45 o dengan pergerakan yang sama, maka disebut sebagai
lag left slip fault. Hal tersebut juga berlaku untuk pergerakan naik. Ditunjukan pada
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 48
zona sesar mendatar bagian putih pada gambar 4.8.
Apabila pitch lebih dari 45 o.dan kurang dari 80o, dengan pergerakan normal atau naik,
maka sesar tersebut juga memiliki kinematika pergeseran mendatar (menganan atau
mengiri). Apabila bidang lebih dari 45o, maka dapat dinamakan right slip normal fault,
right slip reverse fault, left slip normal fault atau left slip reverse fault. Hal tersebut
juga berlaku untuk lag fault dan reverse fault. Ditunjukan pada zona sesar naik dan
normal bagian putih pada gambar 4.8.
4.5 Tugas Praktikum
1. Buatlah analisis sesar dari data breksiasi(tabel 4), kekar gerus (Tabel 5), dan kekar
tarikan (Tabel 6).
2. Berilah pembacaan hasil analisis:
Sf 1 : N . . .° E/. . .° . . .
Sf 2 : N . . .° E/. . .° . . .
Bidang bantu σ1 dan σ3 : N . . .° E/. . .° . . .
Breksiasi : N . . .° E
Bidang sesar : N. . .°/ . . .° . . .
σ1 : . . .°, N . . .° E
σ2 : . . .°, N . . .° E
σ3 : . . .°, N . . .° E
Pitch : . . .°, membuka ke. . .
Netslip : . . .°, N . . .° E
Strike slip : Geser . . .
Dip slip :...
Nama sesar : - Klasifikasi Anderson (1951)
- Klasifikasi Rickard (1972)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 49
Tabel 4.5. Data breksiasi
Tabel 4.6. Data kekar gerus
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 50
Tabel 4.7. Data kekar tarikan
4.6 Tugas Pra-Praktikum
Buatlah model 3D dari suatu permodelan sesar.
a. Terdapat urutan satuan batuan dari tertua ke muda, breksi, batupasir dan lempung
dengan kedudukan N283°E/38°NE, terdapat bidang sesar dengan kedudukan
N183°E/78°E dan besar pitch 80° membuka ke SW.
b. Terdapat intrusi gabbro yang memotong di bagian Barat dari satuan batugamping dan
satuan batulempung diatasnya. Pada kontak batuan beku dan sedimen terdapat sesar
naik yang memanjang Utara-Selatan, selain itu juga terdapat dragfold dengan sumbu
Utara-Selatan pada batuan sedimen.
c. Buatlah model sesar normal dengan bidang sesar N350°E/40°NE, bidang perlapisan
N45°E/45°SE. pada blok a sudah tererosi seperti pada gambar berikut.
d. Buatlah permodelan 3D sesar normal dengan bidang sesar N0°E/50°E yang memotong
perlapisan dari tua kemuda yaitu batupasir 1, batubara, batulepung dan batupasir 2.
Bidang perlapisan batuan N180°E/47°W, pada footwall sudah tererosi hingga lapisan
Batupasir 1 tersingkap. seperti pada gambar berikut:
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 51
e. Buatlah permodelan sesar seperti gambar berikut:
f. Modelkan 3D deformasi yang terjadi pada perlapisan batupasir dengan sisipan
batulempung yang terkena sesar anjak! Sehingga terdapat Dragfoldnya, berilah
goresgaris dan step yang mencerminkan pergerakan sesar pada bidang sesarnya.
g. Modelkan 3D model sesar yang membentuk graben lengkap dengan offset lapisan dan
berilah step dan goresgaris pada bidang sesarnya!
h. Modelkan 3D model sesar yang membentuk horst lengkap dengan offset lapisan dan
berilah step dan goresgaris pada bidang sesarnya!
i. Modelkan 3D sesar rotasi lengkap dengan offset lapisan dan berilah step dan
goresgaris pada bidang sesarnya!
j. Buatlah Model 3D dari perlapisan normal batupasir, batulempung dan batugamping
yang terpotong oleh sesar dengan bidang sesar N0°E/45°E
k. Buatlah model 3D dari pembentukan negative flower structure dari system sesar
mendatar.
l. Buatlah model 3D dari pembentukan positive flower structure dari system sesar
mendatar.
m. Buatlah model 3D dari sesar normal pada batuan sedimen sehingga terdapat dragfold
serta goresgarisnya.
n. Buatlah model 3D jenis-jenis kekar dengan pola tegasan (stress) utama.
o. Buatlah model 3D sesar mendatar yang memotong lapisan tegak, gambarkan struktur
yang terbentuk pada bidang sesarnya.
4.7 Soal Pre-Test
a. Jelaskan apa perbedaan antara sesar dengan kekar ?
b. Sebutkan jenis-jenis dari sesar beserta gambarnya ?
c. Sebutkan dan jelaskan bagian- bagian dari sesar beserta gambarnya ?
d. Jelaskan perbedaan antara separation dengan slip ?
e. Jelaskan tentang klasifikasi sesar menurut Anderson beserta gambarnya ?
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 52
BAB V
ANALISIS LIPATAN
5.1 Maksud dan tujuan
1. Mengenal jenis dan klasifikasi lipatan berserta gaya yang membentuknya
2. Mampu menganalisis lipatan secara stereografis
3. Mengetahui arah gaya yang bekerja pada suatu lipatan (microfold)
4. Mampu merekonstruksi lipatan
5.2 Alat dan bahan
1. Alat tulis (pensil, pena, busur derajat, penghapus, hvs)
2. Spidol warna/ pensil warna/ waterproof warna
3. Stereonet
4. Paku pines
5. Kalkir minimal 3 lembar
5.3 Pendahuluan
5.3.1 Dasar Teori
Lipatan adalah hasil perubahan bentuk atau volume dari suatu bahan yangditunjukkan
sebagai lengkungan atau kumpulan dari lengkungan pada unsur garis atau bidang
didalam bahan tersebut. Pada umumnya unsur yang terlibat di dalam lipatan adalah
struktur bidang, misalnya bidang perlapisan atau foliasi. Lipatan merupakan gejala yang
penting, yang mencerminkan sifat dari deformasi ; terutama, gambaran geometrinya
berhubungan dengan aspek perubahan bentuk (distorsi) dan perputaran (rotasi).
Lipatan terbentuk bilamana unsur yang telah ada sebelumnya terubah menjadi bentuk
bidang lengkung atau garis lengkung. Perlipatan adalah deformasi yang tak seragam
(inhomogeneous) yang terjadi pada suatu bahan yang mengandung unsur garis atau
bidang. Walaupun demikian, suatu deformasi yang menghasilkan lipatan pada suatu
keadaan, tidak selalu demikian pada kondisi yang lain. Suatu masa batuan yang tidak
mempunyai unsur struktur garis atau bidang, tidak menunjukkan tanda perlipatan. Perlu
juga dipertimbangkan bahwa, suatu unsur yang sebelumnya berbentuk lengkungan dapat
berubah menjadi bidang atau garis lurus, atau suatu unsur dapat tetap sebagai struktur
bidang atau garis lurus setelah terjadi deformasi.
- Hinge point
Titik maksimum pelengkungan pada lapisan yang terlipat.
- Crest
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 53
Titik tertinggi pada lengkungan.
- Trough
Titik terendah pada pelengkungan.
- Inflection point
Titik batas dari dua pelengkungan yang berlawanan
Gambar 5.1. Titik-titik yang dideskripsi pada profil permukaan lipatan silindris.
Pada gambaran tiga dimensi, tempat kedudukan dari hinge-point pada satu
permukaan lipatan akan berupa garis yang disebut sebagai hinge-line atau sumbu
dari lipatan (fold- axis). Demikian pula titik-titik crest dan trough, yang
merupakan perpotongan dari garis pada bidang profil, yaitu crestal-line, dan
trough-line, yang sejajar dengan sumbu perlipatan. Tempat kedudukan
dari titik dan garis ini bergantung pada orientasi dari permukaan lipatan
terhadap bidang horisontal. Unsur-unsur lipatan yang umumnya dapat
dideskripsikan kedudukannya diantaranya adalah :
- Fold axis (sumbu lipatan/hinge line)
Garis maksimum pelengkungan pada suatu permukaan bidang yang terlipat.
- Axial plane (bidang sumbu)
Bidang yang dibentuk melalui garis-garis sumbu pada satu lipatan. Bidang ini
tidak selalu berupa bidang lurus (planar), tetapi dapat melengkung lebih umum
dapat disebutkan sebagai Axial surface.
- Fold limb (sayap lipatan)
Secara umum merupakan sisi-sisi dari bidang yang terlipat, yang berada diantara
daerah pelengkungan (hinge-zone) dan batas pelengkungan (inflection line).
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 54
Gambar 5.2. Unsur-Unsur pada suatu Lipatan.
5.3.2. Klasifikasi Lipatan
Lipatan dapat diklasifikasikan dengan bermacam kriteria. Pada umumnya klasifikasi
ini didasarkan pada sifat yang dapat dideskripsikan unsur-unsurnya secara geometri
seperti yang telah dibahas sebelumnya.
Klasifikasi dan penamaan kejadian atau pembentukan lipatan secara tidak
langsung kan mencerminkan sifat kejadian atau pembentukan lipatan tersebut dan
jenis atau material yang terlibat misalnya lipatan yang ketat (tight) mencerminkan
deformasi yang kuat, lipatan yang sejajar (paralel) umumnya terjadi pada lapisan
yang kompeten dan sebagainya.
5.3.2.1 Klasifikasi berdasarkan sudut antar sayap (interlimb angle)
Sudut antar sayap adalah sudut yang terkecil yang dibentuk oleh sayap-sayap lipatan,
dan diukur pada bidang profil suatu lipatan.
Gambar 5.3. sudut antarsayap dari suatu lipatan
Sudut ini mencerminkan sifat keketatan (tightness) dari lipatan. Fleuty (1964)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 55
membuat klasifikasi seperti pada tabel berikut ini :
Tabel 5.1. Klasifikasi lipatan berdasarkan sudut antarsayap (Fleuty, 1964)
Sudut antarsayap Deskripsi Lipatan
180o -120o Gentle (Landai)
120o -70o Open (Terbuka)
70o -30o Close (Tertutup)
30o -0o Tight (Ketat)
0o Isoclinal (Isoklin)
5.3.2.2 Klasifikasi berdasarkan sifat simetri
Simetri merupakan salah satu kriteria untuk menyatakan bentuk dari suatu permukaan
silindris. Sifat simetri ditentukan oleh bidang yang melalui hinge-line dan membagi
sama-besar sudut antar sayap lipatan, yang disebut bidang simetri. Lipatan ini disebut
sebagai lipatan simetris, dan keseluruhan lipatan memiliki sifat simetri orthorhombic.
Suatu seri dari lipatan dikatakan simetri apabila masing-masing mempunyai sifat
simetri, dan mempunyai pola yang periodik. Dalam hal ini, bidang- bidang yang
membatasi permukaan lipatan akan berupa bidang yang lurus (planar) dan saling
sejajar, dan bidang yang melalui titik-titik batas pelengkungan (inflection point)
akan tepat terletak ditengah bidang-bidang tersebut yang disebut sebagai median.
Pada lipatan simetri, besaran amplitude dan panjang gelombang (wavelenght), yang
perbandingannya merupakan parameter untuk bentuk lipatan, akan mudah
dideskripsi (gambar 5.4a)
Apabila jejak dari bidang yang melalui hinge-line (hinge surface) bukan sebagai
bidang simetri, lipatan tersebut disebut sebagai lipatan asimetris, yang hanya
mempunyai sifat simetri monoklin. Untuk itu perlu ditambahkan sifat asimetrinya,
umumnya disebutkan sifat arah miring bidang sumbunya (vergence), atau arah relatif
puncak antiform terhadap puncak sinform nya misalnya arah mata angin, kiri-kanan atau
perputaran jarum jam bagi lipatan yang sumbunya menunjam (gambar 5.4.b). Apabila
sifat asimetri dari lipatan makin besar, deskripsi dapat diberikan dengan sifat-sifat
seperti yang ditunjukkan pada gambar 5.4.c
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 56
Gambar 5.4. Besaran suatu lipatan, W=Wavelength dan A=Amplitude
5.3.2.3 Klasifikasi berdasarkan kedudukan lipatan
Berdasarkan bentuknya, lipatan yang kemiringan bidang sayapnya menuju ke arah
yang berlawanan, disebut sebagai Antiklin, dan lipatan yang kemiringan bidang
sayapnya menuju ke satu arah, disebut sebagai Sinklin. Kedudukan lipatan ditanyakan
dari kedudukan sumbu lipatan (fold axis) dan bidang sumbu lipatan (axial plane/axial
surface). Fleuty(1964) membuat klasifikasi yang didasarkan pada kedua sifat
kedudukan tersebut, dan secara lebih tepat menyatakan besaran kecondongannya
kemiringan dan penunjamannya. Deskripsi yang diberikan merupakan gabungan dari
kedua kriteria yang ada, yaitu kemiringan dari bidang sumbu dan penunjaman
dari garis sumbu.
Tabel 5.2. Klasifikasi Lipatan berdasarkan kedudukan lipatan (Fleuty, 1964).
Sudut Istilah Kemiringan Bidang Sumbu Penunjaman Garis Sumbu
0 Horizontal Recumbent Fold Horizontal Fold
1-10 Subhorizontal Recumbent Fold Horizontal Fold
10-30 Gentle Gently Inclined Fold Gently Plunging Fold
30-60 Moderate Moderately Inclined Fold Moderately Plunging Fold
60-80 Steep Steeply Inclined Fold Steeply Inclined Fold
80-89 Subvertical Upright Fold Vertical Fold
90 Vertical Upright Fold Vertical Fold
Perlu dicatat bahwa beberapa gabungan untuk penamaan lipatan tidak dapat diberikan,
karena garis sumbu posisinya berada pada bidang sumbu, misalnya, jenis lipatan
gently - inclined, steeply - plungging fold tidak mungkin diberikan atau tidak ada.
Klasifikasi ini agak sulit dipakai mengingat kerangka yang digunakan adalah kedudukan
dari sumbu lipatan, yang penunjamannya terukur pada bidang vertikal yang tidak ada
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 57
hubungannya dengan geometri lipatan. Untuk mengatasi ini dapat dipakai kriteria
pitch garis sumbu dan kemiringan bidang sumbu.
Kesulitannya adalah mengukur besaran pitch di lapangan. Klasifikasi yang lebih
sederhana dengan menggabungkan besaran penunjaman dan pitch, seperti bagan
bentuk lipatan yang ditunjukkan pada gambar 6.5
Rickard (1971), membuat diagram segitiga yang memperhitungkan tiga variabel,
yaitu ; kedudukan bidang sumbu lipatan (kemiringan) dan sumbu lipatan (penunjaman
dan pitch terhadap bidang sumbu lipatan)
Pasangan kemiringan dan pitch dari suatu lipatan ditunjukkan sebagai titik pada
perpotongan garis lurus, yang angkanya dibaca sepanjang tepi dasar dan kiri diagram
(gambar 6.6). Untuk penunjaman digunakan kurva dan angka pada tepi kanan diagram.
Jenis-jenis kedudukan lipatan dapat ditentukan pada diagram gambar 6.7 Untuk
dapat memberikan kedudukan yang lebih pasti pada lipatan yang miring (inclined
fold), Rickard mengusulkan untuk memberikan indeks besaran angka dari kemiringan
(D) dan penunjaman dari (P), misalnya ;
- Upright fold (D85P25), menurut klasifikasi Fleuty adalah
Upright, gently, plunging fold.
- Inclined fold (D70P45), Steeply inclined, moderately-plunging fold.
- Reclined fold (D56P55), Moderately-inclined fold.
Diagram ini juga dapat digunakan untuk berbagai lipatan secara lebih terinci pada suatu
wilayah, misalnya bila terdapat suatu perubahan kedudukan pada arah atau geometri
lipatan-lipatan tersebut.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 58
Gambar 5.5. bagan kemungkinan bentuk-bentuk lipatan
Gambar 5.6. Diagram segitiga untuk menentukan kedudukan lipatan.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 59
Gambar 5.7. Penggunaan diagram untuk klasifikasi lipatan (Rickard, 1971).
5.4 Langkah Kerja
Pada bab berikut akan dijelaskan mengenai analisis kinematik dari sebuah lipatan
(microfold) dengan menggunakan analisis stereografis.
1. Siapkan stereonet, kalkir, paku pines, alas untuk stereonet, dan alat tulis
2. Letakkan kalkir di atas stereonet (polar net) kemudian jepit menggunakan paku pines
3. Plotting data microfold yang ada pada tabel yang telah disediakan ke dalam polar net
dengan prinsip proyeksi kutub.
Gambar 5.8. Hasil plotting data microfold pada polarnet tanda persegi mewakili satu pole dan tanda
segitiga mewakili dua pole.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 60
4. Setelah semua data diplot ke dalam polar net, buatlah digram kontur dari hasil proyeksi
kutub tersebut. Dengan menggunakan jaring schmidt (kalsbeek counting grid) untuk
mengetahui distribusi dan kerapatan dari hasil pengukuran pada suatu area lingkaran
proyeksi.
5. Untuk mendapatkan angka kerapatan tersebut, bentangkanlah seluruh hasil pengukuran
data pada proyeksi kutub di atas jaring penghitung (Kalsbeek Net)
6. Cara menghitungnya yaitu dengan menghitung jumlah titik proyeksi yang tercakup
dalam 6 buah segitiga dan angka tersebut diletakkan di setiap titik ujung segitiga yang
ada.
7. Untuk titik proyeksi yang terletak di pinggir maka perhitungan akan dilakukan
bersamaan dengan proyeksi yang ada dihadapannya
Gambar 5.9. Cara menghitung densitas kutub pada jaring kalsbeek.
8. Setelah penghitungan kontur dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah membuat
kontur pada diagram tersebut sesuai dengan angka kerapatan yang telah diperoleh dari
hasil perhitungan. Dalam hal ini harga kontur mewakili harga prosentasi dari hasil
seluruh pengukuran
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 61
Gambar 5.10. Hasil pengkonturan densitas kutub pada jaring kalsbeek.
9. Setelah dibuat kontur maka kita akan mendapatkan dua titik kontur dengan kerapatan
yang paling besar. Titik kontur yang paling rapat itu mewakili kutub dari dua sayap
lipatan yang akan kita ambil sebagai sayap 1 dan sayap 2 untuk selanjutnya dianalisis
pada Schmidt Net.
10. Ubah titik kutub tersebut ke dalam bidang dengan menggunakan jaring Schmidt.
Gambar 5.11. proyeksi kutub menjadi bidang sayap lipatan pada jaring schmidt.
11. Kedua bidang sayap ini akan saling berpotongan pada suatu titik, titik itulah yang
kemudian menjadi titik sumbu lipatan yang juga mewakili sigma 2. Buat bidang sumbu
dari titik sumbu tersebut dengan cara meletakkan titik sumbu tersebut di antara kedua
sayap yang membagi sama besar sudutnya.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 62
Gambar 5.12. menentukan titik sumbu dan bidang sumbu dari kedua bidang sayap lipatan pada
jaring schmidt.
12. Proyeksikan titik sumbu tersebut menjadi titik bidang bantu. Titik tersebut sekaligus
juga mewakili sigma 3
Gambar 5.13. Cara membuat titik bidang bantu pada jaring schmidt.
13. Bidang bantu dibuat dari titik bidang bantu yang disejajarkan dengan titik kutub kedua
sayap lipatan kemudian luruskan bidangnya.
14. Untuk mengetahui kedudukan dari sigma 1, maka kita proyeksikan kembali titik
bidang bantu di dalam bidang bantunya itu sendiri
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 63
Gambar 5.14. Cara membuat bidang bantu pada jaring schmidt.
Sehingga dari hasil analisis tersebut diperoleh data sebagai berikut :
1. Bidang sayap 1 : N 127o E/ 77o SW
2. Bidang Sayap 2 : N 27o E/ 72o SE
3. Bidang Sumbu : N 348o E/88o NE
4. Sigma 1 : 2 o, N 248 o E
5. Sigma 2 : 79 o, N 155o E
6. Sigma 3 : 22 o, N 337 o E
7. Setelah kita mengetahui data tersebut barulah kita dapat mengklasifikasikan jenis lipatan
berdasarkan jenis klasifikasi lipatan yang ada.
5.5 Tugas praktikum
Buatlah analisis kinematik lipatan dari data microfold berikut ini dengan langkah dan
cara yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian tentukan kedudukan dari :
1. Sayap 1
2. Sayap 2
3. Bidang sumbu
4. Sigma 1, 2, dan 3, serta
5. Klasifikasi dan penamaan lipatan secara umum; berdasarkan sudut antar sayap; dan
berdasarkan kedudukan hinge line dan axial plane nya.
Tabel 5.3. Tabel data microfold daerah A.
No Sayap 1 Sayap 2
1 N700E/56 SE N1550E/66 SW
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 64
2 N1550E/66 SW N1400E/69 SW
3 N1400E/69 SW N550E/70 SE
4 N750E/56 SE N500E/65 SE
5 N1840E/76 W N750E/69 SE
6 N1550E/56 SW N950E/60 S
7 N950E/60 S N2050E/64 NW
8 N1000E/64 SW N590E/70 SE
9 N660E/81 SE N1200E/74 SW
10 N1600E/61 SW N2500E/65 NW
11 N1190E/54 SW N1850E/50 S
12 N2300E/71 NW N1700E/53 SW
13 N2600E/77 NW N2150E/67 NW
14 N1090E/38 SW N2100E/56 NW
15 N2500E/51 NW N3250E/66 NE
16 N2550E/60 NW N3450E/70 NE
17 N2850E/69 NE N2850E/67 NE
18 N3350E/69 NE N2750E/62 N
19 N2750E/62 NE N110E/74 SE
20 N10E/77 E N2980E/60 NE
21 N250E/80 SE N3350E/69 NE
22 N340E/55 SE N250E/80 SE
23 N3010E/69 NE N3420E/70 NE
24 N2650E/57 N N2750E/71 N
25 N3310E/63 NE N2650E/57 N
26 N2650E/60 N N3350E/69 NE
27 N3320E/82 NE N2250E/48 NW
28 N2450E/46 NW N20E/75 E
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 65
29 N2500E/21 NW N2450E/56 NW
30 N3400E/85 NE N3400E/81 NE
31 N1840E/23 W N3200E/64 NE
32 N2650E/54 N N1840E/23 W
33 N2950E/60 NE N2950E/43 NE
5.6 Tugas Pra Praktikum
1. Buatlah artikel yang membahas tentang geometri lipatan yang ada dalam ilmu geologi
minimal 2.(misalnya lipatan chevron, recumbent, dll)
2. Carilah model klasifikasi lipatan beserta dasar klasifikasinya menurut peneliti terdahulu.
(minimal 2 kasifikasi)
5.7 Soal Pre-Test
1. Apa yang dimaksud dengan lipatan?
2. Sebut dan jelaskan klasifikasi lipatan berdasarkan sumbu antar sayapnya!
3. Sebut dan gambarkan unsur-unsur yang ada pada lipatan secara umum!
4. Apa yang dimaksud dengan antiklin dan sinklin
5. Jelaskan dan gambarkan mekanismegaya yang dapat mempengaruhi pembentukan
lipatan.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 66
BAB 6
PETA GEOLOGI
6.1. Maksud dan Tujuan
Mampu mengaitkan gejala-gejala morfologi dengan geologi struktur.
Mampu menganalisa tatanan geologi dari kenampakan morfologi.
Mampu membaca dan memahami dasar-dasar pembuatan peta geologi.
6.2. Alat dan Bahan
Alat tulis, penggaris, busur
Pensil warna
6.3. Pendahuluan
Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN, 1998) peta geologi adalah bentuk
ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah/wilayah/kawasan dengan tingkat
kualitas berdasarkan skala. Peta geologi menggambarkan informasi sebaran dan jenis
serta sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi dan sumberdaya
mineral serta energi. Peta geologi disajikan berupa gambar dengan warna, simbol dan
corak atau gabungan ketiganya. Penjelasan berisi informasi, misalnya situasi daerah,
tafsiran dan rekaan geologi, dapat diterangkan dalam bentuk keterangan pinggir
(legenda).
Pada pembelajaran mengenai geologi, permukaan bumi sangatlah berpengaruh dan
harus dipelajari, ini dikarenakan ekspresi topografi dapat menunjukkan keadaan geologi
baik struktur maupun litologinya. Dengan demikian, geomorfologi sangat terkait dalam
mempelajari geologi struktur. Bentukan-bentukan morfologi yang kita temui merupakan
produk hasil dari gaya yang membentuknya baik itu gaya yang berasal dari dalam bumi
maupun dari luar bumi, sehingga bentukan-bentukan itu berbeda-beda dikarenakan
tergantung pada sistem yang mempengaruhi. Misalnya, perkembangan sistem tektonik
di suatu daerah akan memberikan kontribusi bagi perkembangan struktur geologi secara
langsung maupun tidak langsung akan terilustrasi dipermukaan.
Selain itu, Litologi juga berperan penting dalam pembelajaran geologi. Litologi dapat
mendeskripsikan topografi. Litologi yang keras (resisten) cenderung membentuk relief
yang lebih tinggi daripada litologi yang lebih lunak atau kurang resisten. Nilai resisten
dari litologi berpengaruh memberikan relief yang berbeda-beda. Misalnya, daerah yang
disusun oleh litologi batugamping (resisten) akan membentuk suatu pola bentang alam
“karst topografi” yang membentuk pola yang khas.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 67
Pengertian kata dalam kaitannya dengan peta geologi :
Peta geologi
Peta yang menggambarkan keadaan geologi suatu daerah meliputi penyebaran litologi,
struktur, dan morfologi.
Pola singkapan
Perpotongan antara bidang litologi dan bidang permukaan bumi.
Peta lintasan
Suatu peta yang menggambarkan lintasan, lokasi pengamatan, dan hasil pengamatan
lapangan (litologi, struktur, pengambilan sample, dan gejala geologi yang lain,
misalnya mata air, gerakan tanah, penambangan).
Penampang geologi
Gambaran secara vertikal bawah permukaan geologi suatu daerah, sehingga dari
gambaran ini akan diketahui hubungan antara satu dengan yang lain.
Legenda
Keterangan litologi yang disusun secara stratigrafis.
Keterangan
Menjelaskan simbol-simbol dalam peta.
Tebal lapisan
Jarak terpendek antara dua bidang sejajar yang merupakan batas bawah dan atas (top
& bottom) lapisan tersebut.
Kedalaman
Jarakvertikal dari ketinggian tertentu (umumnya permukaan bumi) ke arah bawah
terhadap suatu titik, garis, atau bidang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi luas dan bentuk pola singkapan suatu lapisan batuan:
Ketebalan lapisan
Ketebalan suatu lapisan menentukan luas sebaran pola singkapannya.
Kemiringan lapisan
Kemiringan lapisan yang berbeda akan menunjukkan pola singkapan yang berbeda
pula meskipun slope dan ketebalan lapisannya sama.
Bentuk morfologi
Morfologi yang berbeda akan memberikan pola singkapan yang berbeda pula
meskipun dalam lapisan dengan tebal dan dip sama, dikenal dengan hukum V (V rule).
Bentuk struktur lipatan
Struktur lipatan akan membentuk pola singkapan yang khas.
Hukum "V" (V Rule)
Hukum ini menyatakan hubungan antara lapisan yang mempunyai kemiringan dengan
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 68
relief topografi yang menghasilkan suatu pola singkapan. Hukum tersebut sebagai
berikut :
a. Lapisan horisontal akan membentuk pola singkapan yang mengikuti pola garis kontur
(Gambar 6.1.a).
b. Lapisan dengan dip berlawanan arah dengan slope akan membentuk pola singkapan
berbentuk huruf "V" yang memotong lembah dimana pola singkapannya berlawanan
dengan arah kemiringan lembah (Gambar 6.1.b).
c. Lapisan tegak akan membentuk pola singkapan berupa garis lurus, dimana pola
singkapan ini tidak dipengaruhi oleh keadaan topografi (Gambar 6.1.c).
d. Lapisan dengan dip searah dengan arah slope dimana dip lapisan lebih besar dari pada
slope, akan membentuk pola singkapan dengan huruf “V" mengarah sama (searah)
dengan arah slope (Gambar 6.1.d).
e. Lapisan dengan dip searah dengan slope dan besarnya dip sama dengan slope, maka
pola singkapannya terpisah oleh lembah (Gambar 6.1.e.)
f. Lapisan dengan dip yang searah dengan slope, dimana besar dip lebih kecil dari slope,
maka pola singkapannya akan membentuk huruf "V" yang berlawanan dengan arah
slope (Gambar 6.1.f).
Gambar 6.1. Ekspresi Hukum “V” yang menunjukkan hubungan kedudukan lapisan dengan morfologi.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 69
6.4. Langkah Kerja Praktikum
Langkah kerja dalam membuat suatu peta geologi adalah sebagi berikut :
1. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap untuk memulai mebuat peta geologi,
berupa alat tulis, penggaris, busur, pensil warna, data litologi, data struktur, morfologi,
dan lain-lain.
2. Menentukan skala peta yang akan dibuat.
Skala peta merupakan skala perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya yang
dinyatakan dengan angka atau garis atau gabungan keduanya.
Peta geologi berskala 1:250.000 dan yang lebih besar (1:150.000 ; 1:50.000 dan
seterusnya) disebut peta geologi skala besar, bertujuan menyediakan informasi
geologi. Peta geologi berskala 1:50.000 menyajikan informasi yang lebih rinci dari
peta geologi berskala 1:100.000 dan seterusnya.
Peta geologi berskala 1:500.000 dan yang lebih kecil (1:1.000.000; 1:2.000.000 dan
1:5.000.000) disebut peta geologi berskala kecil, bertujuan menyajikan tataan geologi
regional dan sintesisnya.
3. Dalam membuat peta geologi harus mengikuti Persyaratan Teknis yang ada. (BSN,
1998)
Simbol
Merupakan tanda yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu pada peta geologi,
berupa singkatan huruf, warna, simbol dan corak, atau gabungannya.
Singkatan Huruf
Satuan kronostratigrafi pada peta geologi ditunjukkan dengan singkatan huruf
(Gambar 9.2.). Sebagai dokumen/acuan satuan kronostratigrafi adalah tabel (chart)
yang dibuat oleh Elsevier (1989) atau revisinya.
a. Huruf pertama (huruf besar) menyatakan jaman, misalnya P untuk Perem, TR untuk
Trias, T untuk Tersier.
b. Huruf kedua (huruf kecil) menyatakan seri, misalnya Tm berarti kala Miosen dalam
jaman Tersier.
c. Huruf ketiga (huruf kecil) menyatakan nama formasi atau satuan litologi, misalnya
Tmc berarti Formasi Cipluk berumur Miosen.
d. Huruf Keempat (huruf kecil) menyatakan jenis litologi atau satuan peta yang lebih
rendah (anggota), misalnya Tmcl berarti anggota batugamping Formasi Cipluk yang
berumur Miosen.
e. Huruf kelima digunakan hanya untuk batuan yang mempunyai kisaran umur
panjang, misalnya Tpokc berarti Anggota Cawang Formasi Kikim berumur Paleosen-
Oligosen.
f. Huruf pT (p kecil sebelum T besar ) digunakan untuk singkatan umur batuan
sebelum Tersier yang tidak diketahui umur pastinya.
g. Untuk batuan yang mempunyai kisaran umur panjang, urutan singkatan umur
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 70
berdasarkan dominasi umur batuan, misalnya QT untuk batuan berumur Tersier hingga
Kuarter yang didominasi batuan berumur Quarter; JK untuk batuan berumur Jura
hingga Kapur yang didominasi batuan berumur Jura.
h. Batuan beku dan malihan yang tak terperinci susunan dan umurnya cukup
dinyatakan dengan satu atau dua buah huruf, misalnya a untuk andesit, b untuk basal,
gd untuk granodiorit, um untuk ultramafik atau ofiolit dan s untuk sekis.
i. Batuan beku dan malihan yang diketahui umurnya menggunakan lambang huruf
jaman, misalnya Kg berarti granit berumur Kapur.
j. Pada peta geologi skala kecil, himpunan batuan cukup dinyatakan dengan huruf di
belakang lambang era, jaman atau sub-jaman; misalnya Pzm berarti batuan malihan
berumur Paleozoikum, Ks berarti sedimen berumur Kapur, Tmsv berarti klastika
gunungapi berumur Miosen, Tpv berarti batuan gunungapi berumur Paleogen, Tni
berarti batuan terobosan berumur Neogen. Satuan bancuh dinyatakan dengan notasi m.
Tabel 6.1. Singkatan huruf Kronostratigrafi yang digunakan pada peta geologi.
4. Warna dipakai untuk membedakan satuan peta geologi, dipilih berasaskan jenis
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 71
batuan, umur satuan dan satuan geokronologi.
Warna dasar yang digunakan adalah kuning, magenta (merah) dan sian (biru) serta
gabungannya.
Warna yang dipilih untuk membedakan satuan batuan sedimen dan endapan
permukaan sepenuhnya menganut sistem warna berdasarkan jenis dan umur. Untuk
membedakan beberapa satuan seumur dapat digunakan corak. Batuan malihan
dibedakan berdasarkan (1) derajat dan fasies serta (2) umur nisbi batuan pra-malihan
dan litologi. Tata warna batuan malihan sama dengan batuan sedimen atau
mengunakan bakuan warna khusus. Corak untuk membedakan litologi tertera.
Warna batuan beku menyatakan susunan kimianya : asam, menengah, basa, dan
ultrabasa. Untuk membedakannya dipilih warna yang berdekatan, dan singkapan huruf
atau menurut kunci warna yang sudah dibakukan. Bila diperlukan, dapat digunakan
corak dengan bakuan khusus.
Batuan gunung api yang berlapis dan dan diketahui umurnya, mengikuti tata warna
untuk batuan sedimen. Perbedaan litologi untuk lahar, breksi gunungapi dan tuf
dinyatakan dengan corak. Beberapa satuan batuan gunungapi pada suatu lembar peta
geologi dapat dibedakan berdasarkan susunan kimianya, dengan bakuan warna khusus.
5. Simbol dan notasi (corak) yang tertera pada peta geologi harus tertera pada legenda
dan sebaliknya. Bentuk dan ukurannya harus sama.
Tabel 6.2. Simbol-simbol yang digunakan dalam peta geologi.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 72
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 73
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 74
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 75
Gambar 6.2. Skema corak dasar yang digunakan dalam peta geologi.
6. Jangan lupa memberi Keterangan pada peta yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan
terjemahannya dalam bahasa Inggris (huruf miring). Beri juga keterangan mengenai :
Informasi tebal lapisan
Fosil petunjuk, umur, lingkungan pengendapannya
Hubungan antar satuan
Sumberdaya mineral dan energi
Unsur-unsur penting
7. Proses pencetakan menggunakan bahan berupa kertas HVS 115g atau kertas konstruk
yang tahan cuaca. Dicetak dengan ukuran berskala besar yaitu di kertas berukuran
100cm x 65cm atau berskala kecil yaitu di kertas berukuran 115cm x 85cm.
8. Peta geologi yang lengkap mencangkup peta geologi, penampang geologi, dan
keterangan.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 76
6.5. Tugas Praktikum
1. Buatlah peta lokasi pengamatan pada peta berikut menggunakan data yang ada
2. Buatlah analisis sesar dari data yang disediakan, kemudian plotkan simbol sesar pada
peta lokasi pengamatan serta pada peta geologi
3. Buatlah peta geologi dari peta lokasi pengamatan, untuk menarik batas satuan batuan
pergunakanlah hukum V, serta cantumkan simbol struktur geologi yang terdapat pada
peta.
4. Buatlah 2 penampang geologi yang representatife pada peta tersebut.
5. Hitung ketebalan tiap satuan batuan.
6. Tentukan sejarah geologi yang dapat menceritakan tentang pembentukan daerah
pemetaan tersebut. Umur batulempung Miosen Awal-Miosen Tengah, Umur
Batupasir Miosen Tengah-Pliosen Awal, umur batugamping Pliosen Awal-Pliosen
Akhir.
Gambar 6.3. Peta topografi.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 77
Tabel 6.3. Lokasi pengamatan.
Tabel 6.4. Data breksiasi.
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 78
Tabel 6.5. Data kekar gerus.
6.6. Pre Test
1. Sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan Peta Geologi!
2. Sebutkan unsur-unsur peta geologi yang lengkap!
3. Ada berapa jenis skala pada peta geologi, sebutkan dan jelaskan!
4. Sebutkan unsur-unsur keterangan pada peta geologi! (min. 4)
5. Beri contoh Simbol dan notasi (corak) yang tertera pada peta geologi/legenda ! (min.
5)
Diktat Praktikum Geologi Struktur Universitas Jenderal Sodirman 79
Anda mungkin juga menyukai
- Batuan SedimenDokumen73 halamanBatuan SedimenHanif Abdillah100% (3)
- Pengenalan Mineral Dan MineraloidDokumen76 halamanPengenalan Mineral Dan MineraloidHanif Abdillah100% (5)
- Modul Praktikum Perpetaan 1, 2, Dan 3Dokumen33 halamanModul Praktikum Perpetaan 1, 2, Dan 3Della AzariaBelum ada peringkat
- Jurnal Proyeksi MA2 139Dokumen19 halamanJurnal Proyeksi MA2 139LAPORAN LENGKAP FISIKA DASARBelum ada peringkat
- Modul Acara 5 Pengenalan Alat UkurDokumen9 halamanModul Acara 5 Pengenalan Alat UkurTipando TampubolonBelum ada peringkat
- Herman Darmawan - 1706046956 - Laporan Kuliah LapanganDokumen38 halamanHerman Darmawan - 1706046956 - Laporan Kuliah LapanganHerman D100% (1)
- Struktur BidangDokumen12 halamanStruktur BidangAling SyahrilBelum ada peringkat
- Geologi Struktur - Yunir Tulong - 471421032 - Teknik GeologiDokumen19 halamanGeologi Struktur - Yunir Tulong - 471421032 - Teknik GeologiYunir TulongBelum ada peringkat
- Laprak Geologi 4Dokumen12 halamanLaprak Geologi 4Nurul HidayahBelum ada peringkat
- Praktikum Gs Proyeksi StreografisDokumen14 halamanPraktikum Gs Proyeksi StreografisRiahati HarefaBelum ada peringkat
- Jurnal TC NopalDokumen13 halamanJurnal TC NopalHadrianBelum ada peringkat
- Kuliah Stratigrafi - Pengamatan SingkapanDokumen9 halamanKuliah Stratigrafi - Pengamatan SingkapanM Fajar FahrezaBelum ada peringkat
- Alat2 GeologiDokumen16 halamanAlat2 GeologihaltimberdikariBelum ada peringkat
- MA 2 - Mualif - 09320190179Dokumen15 halamanMA 2 - Mualif - 09320190179Nur AzizaBelum ada peringkat
- Geologi PDFDokumen58 halamanGeologi PDFRomie Hendrawan75% (4)
- Tugas 4 Praktikum Geografi Fisik 1 DDokumen5 halamanTugas 4 Praktikum Geografi Fisik 1 DClarisa100% (1)
- Fahmi Adha Syaifullah - Laporan Praktikum Perpetaan Bab 1Dokumen21 halamanFahmi Adha Syaifullah - Laporan Praktikum Perpetaan Bab 1fahmiBelum ada peringkat
- Bab IDokumen93 halamanBab IStaritwon24Belum ada peringkat
- Resume Konversi Arah, Sudut, Trigonometri Dan Struktur GeologiDokumen9 halamanResume Konversi Arah, Sudut, Trigonometri Dan Struktur GeologiShendy BayuBelum ada peringkat
- Laporan Geodesi 1 AmarDokumen7 halamanLaporan Geodesi 1 AmarTikheBelum ada peringkat
- GeologiDokumen7 halamanGeologiSafira RabbiolaBelum ada peringkat
- Modul Geologi StrukturDokumen6 halamanModul Geologi StrukturKhaerul WahyuBelum ada peringkat
- Laporan Geologi Struktur - Lubuk BernaiDokumen45 halamanLaporan Geologi Struktur - Lubuk BernaiMuhammad Agung Andika OktafiansyahBelum ada peringkat
- Alat Ukur TanahDokumen64 halamanAlat Ukur TanahKun Hadipati Kusuma Negara100% (2)
- Ilmu Ukur Tanah BPK Idi SutardiDokumen260 halamanIlmu Ukur Tanah BPK Idi Sutardiheriyanto_ahdBelum ada peringkat
- Modul Praktikum Geologi Dasar 1Dokumen8 halamanModul Praktikum Geologi Dasar 1Husni RandaBelum ada peringkat
- Modul Geomorfologi 2 (3)Dokumen108 halamanModul Geomorfologi 2 (3)Fi KRohBelum ada peringkat
- Alat-Alat Survey PetaDokumen12 halamanAlat-Alat Survey PetaRodesiaBelum ada peringkat
- Laporan Uji Kompetensi Keahlian Deta Febrina AmandaDokumen13 halamanLaporan Uji Kompetensi Keahlian Deta Febrina AmandaDimas NuhgrahaBelum ada peringkat
- Observasi TanahDokumen13 halamanObservasi TanahArtha Uli SimatupangBelum ada peringkat
- Lap. Akhir 01 (Pengenalan Alat-Alat Survei Dan Fungsinya)Dokumen12 halamanLap. Akhir 01 (Pengenalan Alat-Alat Survei Dan Fungsinya)Shadeq Arya Pamungkas100% (2)
- Struktur BidangDokumen10 halamanStruktur BidangFajar ArBelum ada peringkat
- BA 20J00002 61208d06ba629Dokumen30 halamanBA 20J00002 61208d06ba629fatihaBelum ada peringkat
- BAB V Peralatan LapanganDokumen10 halamanBAB V Peralatan LapanganFillerBelum ada peringkat
- LAPORAN PRAKTIKUM PemetaanDokumen9 halamanLAPORAN PRAKTIKUM PemetaanJULIANSYAH ADI PBelum ada peringkat
- Laporan Poligon Tertutup 2Dokumen19 halamanLaporan Poligon Tertutup 2Yogi MuhibbinBelum ada peringkat
- Modul Geologi Struktur THN 2021Dokumen18 halamanModul Geologi Struktur THN 2021Ikraman SaputraBelum ada peringkat
- Pembahasan AzimuthDokumen36 halamanPembahasan AzimuthHendra JayantoBelum ada peringkat
- Laprak - Kompas Dan Sudut Azimuth - EpDokumen15 halamanLaprak - Kompas Dan Sudut Azimuth - EpEKA PRAMUDITIABelum ada peringkat
- Laporan Propet Acara 2Dokumen7 halamanLaporan Propet Acara 2Fian CahyaBelum ada peringkat
- Solar Chart 2Dokumen16 halamanSolar Chart 2Fian MuslimBelum ada peringkat
- Laporan GS 5 NandaDokumen10 halamanLaporan GS 5 NandaArini Anisa PutriBelum ada peringkat
- (A) Menentukan AzimuthDokumen11 halaman(A) Menentukan AzimuthniaBelum ada peringkat
- Laporan Seismik RefleksiDokumen30 halamanLaporan Seismik RefleksiAzzhravia Rahma KhanBelum ada peringkat
- Modul Osilasi KelerengDokumen21 halamanModul Osilasi KelerenglailitwinBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum IDokumen7 halamanLaporan Praktikum IYoni SetiawanBelum ada peringkat
- Kompas GeologiDokumen11 halamanKompas GeologiDieoPrasetyoBelum ada peringkat
- Laporan GS 6 Analisa Kekar Dan Analisa SesarDokumen13 halamanLaporan GS 6 Analisa Kekar Dan Analisa SesarRidho syah PahleviBelum ada peringkat
- Laporan Sag - Kelompok 5Dokumen17 halamanLaporan Sag - Kelompok 5geonyakimiBelum ada peringkat
- Dokumen - Tips - Laporan Praktikum Theodolite VickersdocxDokumen23 halamanDokumen - Tips - Laporan Praktikum Theodolite VickersdocxAnonymousBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Geostruktur Acara 3 - Azwarni Luthfi Julian - Kel 9Dokumen13 halamanLaporan Praktikum Geostruktur Acara 3 - Azwarni Luthfi Julian - Kel 9Divo Dwi BramantyoBelum ada peringkat
- Laporan Resmi Geostruk 1 Geologi UIRDokumen41 halamanLaporan Resmi Geostruk 1 Geologi UIRGayuhPramuktiBelum ada peringkat
- Ilmu Ukur WilayahDokumen68 halamanIlmu Ukur WilayahKhairunnisyah Hamzah0% (1)
- Bab 1Dokumen34 halamanBab 1Indra Ayu AWBelum ada peringkat
- Buku Ajar Iut1Dokumen107 halamanBuku Ajar Iut1Salma KarimahBelum ada peringkat
- Laprak Geostruk Acara KekarDokumen9 halamanLaprak Geostruk Acara KekarMifthahul ZidaneBelum ada peringkat
- 7 Pemb. PegununganDokumen30 halaman7 Pemb. PegununganHanif AbdillahBelum ada peringkat
- Ab014 Geologi StrukturDokumen26 halamanAb014 Geologi StrukturHanif AbdillahBelum ada peringkat
- 6 Kegempaan GeoDasDokumen53 halaman6 Kegempaan GeoDasHanif AbdillahBelum ada peringkat
- 01 - Berita Acara Hasil MK - Desa - Rev-1Dokumen1 halaman01 - Berita Acara Hasil MK - Desa - Rev-1Hanif AbdillahBelum ada peringkat
- Batuan MetamorfDokumen75 halamanBatuan MetamorfHanif Abdillah100% (1)
- Batuan Beku Dan PiroklastikDokumen74 halamanBatuan Beku Dan PiroklastikHanif Abdillah0% (2)