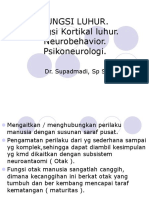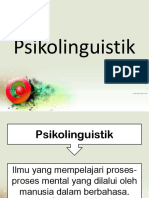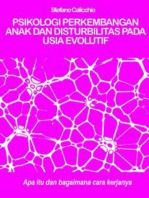Fungsi Luhur 2008
Fungsi Luhur 2008
Diunggah oleh
Randilufti Santoso0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan77 halamansaraf
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PPT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Inisaraf
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan77 halamanFungsi Luhur 2008
Fungsi Luhur 2008
Diunggah oleh
Randilufti Santososaraf
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 77
Fungsi Luhur
Fungsi Kortikal Luhur
Neurobehavior
Dr. Supadmadi, SpS
Pendahuluan
Neurologi behavior adl ilmu mengenai pengaruh
peny otak pd perilaku manusia dan fungsi kortikal
luhurnya.
Perilaku di sini mencakup perilaku spesifik spt :
bahasa, memori, kalkulasi, dan kemampuan
visuospatial; dan perilaku yg lebih kompleks
mengenai kualitas intelegensi, emosi, dan
personalitas
Mengaitkan / menghubungkan perilaku manusia
dengan susunan saraf pusat.
Pengamatan perilaku dari yg sederhana sampai yg
komplek,sehingga dapat diambil kesimpulan yg kmd
dikaitkan dengan subsistem neuroantaomi (Otak).
Fungsi otak manusia sangatlah canggih, dimana
kecanggihan ini berkat otak yang tumbuh dan
ber kembang mencapai taraf kematangan
(maturitas).
Maturitas otak ini ditandai oleh terbentuknya
spesialisasi dalam fungsi.
Artinya otak terbagi-bagi dalam berbagai bagian
dan masing-masing bagian mempunyai fungsi
khusus. Namun demikian , bagian-bagian otak
ini bekerja secara terpadu.
Apabila terjadi suatu kelainan pada bagian otak
tertentu, maka akan timbul suatu gangguan
atau disfungsi yang sesuai dengan fungsi bagian
tersebut. Walaupun tidak selalu kelainan pada
bagian tadi dapat dibuktikan secara struktural.
Perkembangan Otak
Pada beberapa minggu pertama, otak janin ber kembang
sepesat otak hewan vertebrata.
Tetapi setelah berumur sekitar 4 bulan, otak janin
berkembang amat pesatnya, terutama bagian luar otak
(korteks serebri).
Periode berkembang cepat ini berlangsung sampai umur 2
tahun,dimana kecepatan perkembangan otak pada periode
ini dapat diamati dari cepatnya otak bertambah berat. 50
gram dalam kandungan menjadi 400 gram pada waktu
lahir dan menjadi 1000 gram pada usia 18 bulan. Setelah
itu melambat, masa pubertas pria 1375 gram dan wanita
1250 gram.
Periode perkembangan cepat otak ini, merupa kan
peluang emas yang tidak boleh dilewatkan. Berbagai
stimulasi atau rangsangan yang diberikan pada saat
ini akan dapat bermanfaat bagi kesempur naan
fungsi otak dikemudian hari.
Anak perlu banyak bermain; karena bermain adalah
proses belajar yang alamiah, disadari atau tidak
sebenarnya sangat berpengaruh pada
perkembangan otak menuju kematangannya
(maturitas).
Walaupun sel-sel otak tidak bertambah lagi
jumlahnya, tetapi pertumbuhan cabang-cabang sel
(dendrit) berlangsung terus.
Juga hubungan antar sel melalui cabang-cabang sel
ini makin bertambah banyak. Proses belajar dan
rangsangan lingkungan ikut berperan dalam hal ini.
Kematangan Otak
Selain otak tumbuh dan berkembang menjadi bentuk
otak manusia pada umumnya, otak juga akan
berkembang fungsinya yang akan menjadi ciri khas
masing-masing individu. (Perkembangan ontogene tik
atau perkembangan individual).
Otak terdiri dari dua belahan otak (hemisferium
serebri) kanan dan kiri.
Di mana pada bayi, fungsi belahan otak kanan dan kiri
masih sama; namun lambat laun fungsi belahan otak
kanan dan kiri menjadi berbeda.
Perkembangan ini menjadi mantap sekitar umur 6-8
tahunan.
Kalau diamati, bayi masih menggunakan ke dua
belah tangannya untuk memegang suatu benda.
Lambat laun anak akan cenderung memakai tangan
tertentu untuk melakukan sesuatu. Kecenderungan
ini makin tampak pada sekitar umur 6 tahunan.
Bersamaan itu pula anak mulai belajar berbicara,
berbahasa dan berhitung.
Berkat perkembangan otak yang baik, tercapailah
kematangan otak manusia dengan ciri-ciri khasnya.
Ciri khas ini adalah manusia berdiri tegak pada ke
dua kakinya, cenderung menggunakan sebelah ta
ngannya, mampu menggunakan bahasa yang kom
pleks, dapat menciptakan alat bantu, menggemari
se ni musik, tari dan kesenian lainnya.
Ciri-ciri khas otak ini oleh karena adanya spesialisasi
belahan otak
Spesialisasi Hemisfer
Setelah otak mengalami perkembangan
ontogenetik (individual) maka fungsi dari belahan
otak (hemisfer) kanan dan kiri tidak sama.
Hemisfer kiri mempunyai kemampuan :
Verbal.
Berbicara dan berbahasa.
Mengucapkan kata dan kalimat.
Mengerti pembicaraan.
Menyebutkan nama benda dan orang.
Mengulang kata dan kalimat.
Membaca, menulis, berhitung.
Hemisfer kanan mempunyai kemampuan :
Kewaspadaan.
Mengenal diri dan orang lain.
Mengenal situasi dan kondisi setempat.
Mengenal kontak mata.
Mampu menerima dan memberi peluang.
Mengendalikan emosi.
Menghayati keindahan dan kesenian
Memahami kiasan dan ibarat.
Berkhayal dan berspekulasi.
Bergaya bahasa , lagu kalimat, penekanan, isarat.
Pengamatan ruang, pengamatan lingkungan,
pengamatan diri. (Visuospasial).
Komponen Fungsi Luhur
1. Kemampuan berbahasa.
2. Daya ingat.
3. Kemampuan Visuospatial.
4. Afek dan emosi.
5. Kemampuan kognisi.
Bahasa
Orang berkomunikasi dengan sesamanya dengan dua jenis
bahasa, yaitu bahasa verbal dan nonverbal. Bahasa verbal
menggunakan simbol bahasa dan tatabahasa, dlm bentuk
lisan dan tulisan.
Bahasa nonverbal menggunakan lagu kalimat dan
penekanan pada kata-kata tertentu sewaktu berbicara,
gerak-gerik atau isarat mata, tangan, bagian tubuh yang
lain yang menyertai suatu pembicaraan, dengan maksud
agar lawan bicara dpt lebih mengerti.
Bahasa nonverbal dipakai bersamaan dengan bahasa
verbal agar isi pikiran dan perasaan yang diutarakan dapat
lebih dipahami.
Bahasa Verbal
Bahasa verbal ialah bahasa yang dipergunakan
sehari-hari dengan menggunakan simbol bahasa
dan tatabahasa, dalam bentuk lisan dan tulisan.
Bahasa verbal berpusat di hemisfer kiri.
Hemisfer ini mempunyai kemampuan untuk
memantau fungsi berbicara atau bertutur kata
(bahasa ekspresif), pemahaman bahasa (bahasa
reseptif), menulis dan membaca.
Bahasa ekspresif berpusat dibag depan (area
Broca), dan bahasa reseptif berpusat dibag
belakang (area Wernicke).
Membaca dan menulis berpusat di belakang area
Wernicke yaitu di girus Angularis.
Gangguan berbahasa oleh karena kelainan di
area Broca dapat berupa kesulitan berbicara
atau bertutur kata, berbicara tidak lancar (non
fluent), disebut sebagai : gangguan bahasa
ekspresif, afasia motorik, afasia Broca, afasia
non fluent.
Gangguan berbahasa oleh karena kelainan di
area Wernicke dapat berupa kesulitan
memahami bahasa, tetapi masih fasih
berbahasa, berbicara lancar (fluent), disebut
sebagai : gangguan bahasa reseptif, afasia
sensorik, afasia Wermicke, afasia fluent.
Gangguan / kelainan di girus angularis hemisfer
kiri menyebabkan gangguan menulis (dis /
agrafia) dan gangguan membaca (dis / aleksia).
Bahasa Nonverbal
Bahasa nonverbal adalah bahasa yang dipakai
bersamaan dengan bahasa verbal dengan tujuan
agar isi pikiran dan perasaan yang diutarakan
menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dapat
berupa lagu kalimat dan penekanan kata - kata
(paralinguistik), juga gerak - gerik anggota
tubuh (ekstralinguistik).
Bahasa nonverbal berpusat di hemisfer kanan.
Kemampuan hemisfer kanan ini antara lain
mengatur lagu kalimat (prosodi), memberi
penekanan pada kalimat atau kata yang
dianggap penting dlm suatu pembicraan.
Juga mengungkapkan perasaan emosi (marah,
senang, sedih) lewat kalimat / kata.
Kemampuan yang lain adalah :
Dapat mengekspresi kan wajah, tatapan mata,
isarat tangan dan tubuh sewaktu bicara,
sehingga pembicaraannya lebih dapat
dimengerti oleh lawan bicara. Juga kemampuan
menerima dan memberi peluang dalam
berbicara. Memakai bahasa yang sesuai dengan
situasi dan kondisi setempat.
Apabila ada kelainan di hemisfer kanan akan
mengakibatkan orang berbicara secara monoton,
tanpa lagu dan penekanan, tidak menggunakan
tatapan mata dan gerak-gerik tangan sewaktu
berbicara, tidak mampu memilih bahasa yang
sesuai dg situasi dan kondisi.
Memori
Memori atau ingatan berhubungan erat dengan proses
belajar. Untuk mengingat sesuatu harus mengenal atau
mempelajari sebelumnya.
Proses belajar adl suatu proses memperoleh informasi baru
atau pengetahuan baru. Proses belajar lebih berhubungan
dengan proses perekaman.
Proses memori adl proses yg menyimpan informasi atau
pengetahuan yg diperoleh tadi dlm jangka pendek atau
jangka panjang, yg kemudian dpt mencari kembali sewaktu
dibutuhkan. Proses memori lebih berhubungan dengan
proses pemeliharaan, mengingat dan mendapatkan kembali
informasi atau pengalaman yang telah direkam tadi.
Memori yang baik menunjukkan dua fungsi, yaitu :
1. Fungsi kamus (menemukan kata dalam penyimpanan)
2. Fungsi ensiklopedi (memberikan penjelasan)
Proses mengingat
Seseorang yg ingin mengingat informasi
yg diterima melalui tiga proses
mengingat, yaitu :
1. Belajar (learn)
Sebagai proses mengingat untuk memperoleh
informasi, penyandian, atau mencatat informasi
2. Retensi
Sebagai proses mengingat untuk menyimpan
informasi yg telah diperoleh.
3. Retrieval
Proses mengingat mencari kembali informasi yg
telah disimpan.
Proses mengingat tahap pertama
Ada dua cara mempelajari informasi, yaitu:
Belajar dgn tujuan atau dgn sengaja
Di sini membutuhkan upaya untuk belajar sesuatu yg
baru dgn sengaja menggunakan strategi tertentu.
Belajar dgn kebetulan
Cara belajar dgn tidak sengaja dan tidak
menggunakan strategi tertentu.
Proses mengingat tahap ke dua
Tahap ke dua adl menyimpan informasi yg telah
dipelajari ke dlm model penyimpanan memori.
Ada dua jenis model penyimpanan memori :
Model penyimpanan klinis
Model penyimpanan psikologis
Model penyimpanan klinis
Secara neurologi klinis, model penyimpanan
memori berkaitan dgn kondisinya dan terbagi
dlm golongan :
A. Immediate memory (memori segera)
B. Recent memory (memori baru)
C. Remote memory / distance memory (memory
jarak jauh)
A. Immediate memory
Adl kemampuan menyimpan memori ttg peristiwa,
objek atau gagasan dlm rentang waktu yg sgt pendek;
biasanya diukur dgn tes rentang digit.
Contoh : disebutkan digit 7, 8, 3, 5, 2, 9, 4, 1; subjek
diminta utk mengulangi urutan digit tsb. Orang normal
dpt mengulang minimal 6 digit.
B. Recent memory
Adl kemampuan untuk menyimpan item dlm memori
jangka panjang. Ada bbrp evaluasi yg dipergunakan,
antara lain : Menanyakan pagi td sarapan apa, atau
memberikan bbrp kata untuk diingat kembali. Orang
normal dpt mengingat kembali 4 kata stlh sepuluh
menit.
C. Remote memory
Adl kemampuan meyimpan memori dlm
jangka waktu yg lama, evaluasinya
dilakukan dgn menanyakan pertanyaan
berkenaan dgn peristiwa penting yg
dialami dlm hidupnya atau peristiwa dunia.
Model penyimpanan psikologis
Scr psikologis model penyimpanan memori
berkaitan dgn rentang waktu memori yg dpt
dipertahankan; terbagi dlm 3 golongan :
A. Sensory memory
B. Short term memory (memori jangka pendek,
memori primer)
C. Long term memory (memori jangka panjang,
memori sekunder)
A. Sensory memory
Adl persepsi rangsangan visual, auditoris, olfaktoris,
dan taktil yg diterima scr mengambang. Apabila salah
satu rangsangan sensori td memperoleh perhatian,
maka rangsangan td akan masuk dlm memori jangka
pendek, dan dpt diingat dlm waktu yg lebih panjang.
Contoh : Pd suatu percakapan berlangsung, maka
orang akan merasakan beberapa rangsangan panca
indera scr bersamaan (suara, cahaya, bau-bauan, rasa
udara).
Apabila saat itu ada suara AC yg gemuruh dan
memperoleh perhatian, maka rangsangan tadi akan
masuk dlm memori jangka pendek dan teringat oleh
orang tadi. Maka dia akan mengatakan bahwa saat itu
percakapan agak terganggu oleh karena suara
gemuruh AC
B. Short term memory
Adl penyimpanan smtr peristiwa yg diterima dlm waktu
sekejap (dlm waktu bbrp detik menit). Tes klasik utk
mengukur memori jangka pendek adl membacakan
atau memperlihatkan sederetan huruf, angka, kata,
dan sgr harus diingat dan diulang kembali oleh subjek.
Memori jangka pendek tdk permanen, akan terhapus
dlm waktu pendek, kecuali diupayakan scr khusus spt
mengulang-ulang.
Masalah memori jangka pendek yg penting dlm
kehidupan sehari-hari adl model memori kerja.
Memori kerja adl penyimpanan smtr informasi yg
dibutuhkan utk aktivitas spt belajar, memberikan
alasan dan pemahaman.
Mekanisme memori kerja adl penggabungan antara
fungsi memori yg dipantau oleh lobus temporalis dan
fungsi eksekutif di bagian lobus frontalis.
Fungsi eksekutif terdiri dari kemampuan utk
merencanakan, mengorganisasi, dan melaksanankan
sesuatu. Oleh karena itu memori kerja sgt berkaitan
dgn kemampuan memori dlm aktivitas kehidupan
sehari-hari.
Contoh : Seseorang yg sedang melakukan
percakapan dgn orang lain, dia harus mengingat-ingat
materi percakapan dan saat itu jg harus memikirkan
masalah lain yg terkait dgn materi tsb, agar dlm
percakapan berikutnya dpt melanjutkan untuk
membahas materi yg sama, tidak menyimpang ke
materi yg lain.
Untuk lebih lama mengingat informasi yg masuk dlm
memori jangka pendek, perlu dilakukan pemgulangan
daqn menaruh perhatian pd informasi tsb.
C. Long term memory
Informasi yg masuk dlm memori jangka
panjang mrpk semua pengetahuan yg kita
ketahui. Agar dpt diingat lebih lama lg, bahkan
menjadi bank memori yg permanen, maka
informasi harus lebih sering diulang-ulang.
Namun demikian tdk semua informasi benar-
benar permanen, ada sebagian yg hilang atau
dihapus oleh waktu.
Informasi dan pengetahuan yg tdk dpt
dilupakan seumur hidup tersimpan dlm memori
jangka panjang melalui konsolidasi yg cukup
intensif.
Contoh : Nama sendiri, nama teman-teman
lama, kejadian masa kecil, dsb.
Konsolidasi memori mencakup dua proses:
Proses pemindahan (transfer) materi dari memori
jangka pendek ke memori jangka panjang, atau
pemindahan langsung dari memori sensori dan
memori jangka panjang.
Proses konsolidasi memori ke dlm penyimpanan
(storage)
Proses ini membutuhkan waktu lebih lama dan
upaya keras agar materi memori menjadi
permanen. Pd proses ini tjd perubahan struktur
dlm sistem susunan saraf pusat, dan inilah yg
menyebabkan penyimpanan menjadi permanen
dan dpt diingat seumur hidup.
Materi informasi yg tersimpan dlm pusat memori
jangka panjang dpt berbentuk :
Memori deklaratif terdiri dari :
Memori episodik yg mempunyai kemampuan utk
menyimpan dan menceritakan ulang pengalaman
pribadi yg berkaitan dgn waktu dan tempat.
Memori semantik yg mempunyai kemamouan utk
menyimpan dan menceritakan ulang masalah yg
berkaitan dgn pengetahuan dunia bahasa, dan
konsep.
Contoh : Seseorang yg pernah mempelajari tg
sejarah pangeran Diponegoro; apabila suatu ketika
dia ditanya ttg materi yg terkandung dan kapan
kejadiannya; maka dia akan lebih mudah
mengingat ttg siapakah Pangeran Diponegoro itu
dan apa yg diakukannya, daripada mengingat kpn
dan di mana kejadiannya.
Memori prosedural mempunyai kemampuan
menyimpan ketrampilan motorik yg pernah
dipelajari dan dilakukannya berulang-ulang.
Contoh : ketrampilan bersepeda, bermain
musik, bermain komputer, dsb; yg tdk akan
terlupakan selamanya.
Prosepenyimpanan tahap ke tiga
Tahap akhir proses memori adl retrieval
(mengingat atau mengambil kembali memori).
Tahap ini membutuhkan akses pengambilan
sandi, materi yg berada dlm simpanan memori
jangka panjang diambil dan dimasukkan ke dlm
memori jangka pendek. Masalahnya adl apakah
materi yg diambil kembali akan berbentuk sama
spt saat materi disimpan, ataukah sudah
berbeda karena mengalami transformasi.
Artinya materi dpt diingat kembali utuh spt apa
adanya atau hanya intinya saja.
Proses lupa
Ada tiga kelompok model klasik proses lupa :
1. Model pertama
Lupa tjd karena adanya informasi yg lenyap
karena waktu, ibarat pantai pasir yg terhapus
oleh gelombang ombak karena tdk terlindungi scr
kontinyu. Scr praktis dikatakan apabila informasi
tdk dipakai maka informasi tsb akan dilupakan.
2. Model ke dua
Teori Hebb menyatakan bahwa pengulangan dan
pengalaman menimbulkan perubahan struktur
dlm otak, menyebabkan sel otak aktif
melepaskan muatan listrik dan merangsang sel-
sel lain. Proses itu berlanjut trs walaupun
stimulasi fisik itu sudah lewat. Sel-sel yg
terangsang terlibat dalam sirkit yg membentuk
sebuah memori (konsolidasi). Apabila oleh
sesuatu hal proses konsolidasi itu terganggu
maka memori utk peristiwa tsb tdk lengkap.
3. Model ke tiga
Teori interfrensi, yg menyatakan bahwa
pengalaman baru dpt mengganggu memori yg
lama. Sebaliknya pengalaman lama dpt jg
mengganggu memori yg baru.
Faktor yg mempengaruhi memori
Kemampuan memori dipengaruhi oleh bbrp
hal:
1) Usia
2) Pendidikan
3) intelegensi
4) Konsep diri
5) Kesehatan
6) Motivasi
7) Strategi memori
Visuospatial
Kemampuan visuospasial berkaitan dengan fungsi
pengamatan diri dan lingkungan serta persepsi
(pengamatan yang menimbulkan pengenalan dan
pemahaman), berpusat di hemisfer kanan.
Gangguan Persepsi Visual:
1. Pengabaian ruang / hemispatial neglect.
Pasien mengabaikan keadaan salah satu sisi ruang.
2. Penyangkalan / Anosognosia.
Pasien menyangkal kalau tungkai kirinya lemah.
3. Tidak mengenal Lingkungan / Environmental
Agnosia.
Pasien mengalami kesulitan dalam mengenali
lingkungan yang dahulu telah dikenalnya.
4. Tidak mengenal wajah / Prosopagnosia.
Pasien tidak mengenali wajah teman-teman,
bahkan anggota keluarga sendiri. Tetapi dapat
mengenal oleh karena suaranya.
Gangguan gerakan visual / Visuomotor disorder.
Gerakan menjadi tidak sempurna karena adanya
gangguan orientasi ruang. Tidak mengenal jarak,
atas-bawah, depan-belakang, kiri-kanan.
Disfungsi ini dapat berupa :
1. Gangguan konstruksi. / Apraksia konstruksi.
Orang tidak dapat menggambar secara spontan atau
mengkopi model bentuk.
2. Gangguan berpakaian / Apraksia berpakaian.
Orang mengalami kesulitan dalam berpakaian karena
ia tidak mengenal bagian-bagian dari pakaian tersebut.
Afek dan Emosi
Yang dimaksud afek dan emosi di sini adalah
prosodi atau lagu dalam kalimat pembicaraan,
pemahaman pembicaraan yang bersifat afektif,
pengenalan ekspresi wajah afektif.
Afek dan emosi berpusat di hemisfer kanan.
Sehingga kelainan di hemisfer kanan dapat
menyebabkan orang menjadi sukar berbicara
dengan lagu kalimat yang baik, sukar
mengungkapkan isi pikiran yang mengandung
kemarahan, kegembiraan atau kesedihan. Juga
tidak mengenali raut wajah orang yang sedang
marah, gembira atau sedih.
Kognisi
Cara berpikir hemisfer kanan dan kiri berbeda.
Hemisfer kiri analitis, linier dan bertahap
dan dasarnya adalah
kecerdasan.
Hemisfer kanan intuitif, holistik, garis besar,
menyelesiakan masalah
sekaligus dan dasarnya adalah
kreativitas.
Gangguan kognisi :
Tidak dapat menjabarkan peribahasa.
Tidak dapat mengenal persamaan, kalkulasi, konsep.
Afasia
Gangguan berbahasa lazim disebut afasia.
Menurut Rosenbek J.C, La Pointe L.L, dan Wertz R.T,
(1989) afasia adl suatu gangguan atau kerusakan yg
didapat dan baru tjd dari SSP, yg menyebabkan
ketidakmampuan utk mengerti dan merumuskan
bahasa. Hal ini mrpk gangguan multi modal yg
diperlihatkan dgn berbagai kelemahan di dlm
pengertian auditorik, membaca, bahasa yg diutarakan
scr oral ekspresi, dan menulis.
Bahasa yg terganggu ini dpt dipengaruhi oleh
ketidakberdayaan fisiologis atau gangguan kognisi
tetapi tdk dpt dijelaskan akibat demensia, hilangnya
sensorik atau disfungsi motorik.
Sidiarto (1992) menyimpulkan jabaran afasia
sbb:
1. Disebabkan oleh kelainan otak yg parsial
2. Mrpk gangguan semua modalitas bahasa
3. Mrpk gangguan penggunaan dan pengenalan
simbol
4. Kehilangan kemampuan membuat formulasi,
menyatakan, dan membuat kata-kata ucapan
5. Gangguan membaca dan menulis
6. Bukan gangguan mekanisme neuro muskular
wicara
7. Bukan gangguan fungsi intelektual
Anatomi Afasia
Susunan saraf pusat yg ikut berperan dlm gangguan
bahasa adl otak besar (hemisfer kiri hemisfer
dominan)
Espir dan Rose (1970) menemukan area bicara di daerah
korteks serebri hemisfer dominan yg memantau fungsi
wicara dan bahasa. Area tsb meliputi bagian plg bawah
girus presentralis (area broca) dan postsentralis, girus
supramarginalis dan angularis, girus parietalis inferior
dan bagian atas lobus temporalis superior.
Daerah ini oleh Benson (1979) lebih suka disebut
sebagai area bahasa, karena memang daerah yg
memantau kemampuan bahasa.
Scr umum daerah ini terletak di sekitar Sulkus
Sylvian Hemisfer kiri, ok itu disebut sbg area
perisylvian. Daerah ini disuplai darah dari a.
sylvian cabang dari a. serebri media. Di sekitar
daerah ini disebut dgn area peralihan atau
borderzone.
Apabila mengacu kpd dua jenis afasia (afasia fluen
atau afasia Wernicke dan afasia non fluen atau
afasia Broca) maka scr neuro anatomis area
bahasa dibagi mnjd anterior dan posterior
(dpisahkan oleh fisura Rolandi). Bagian anterior
memantau afasia Broca, bagian posterior
memantau afasia Wernicke.
Sindroma Afasia
Bermacam-macam jenis afasia telah diketahui, di
mana masing-masing jenis afasia mempunyai gjl
yg tidak sama dan kump gjl (sindroma) ini
mempunyai gambaram tersendiri utk masing-
masing afasia.
Banyak cara pemeriksaan utk menentukan maca-
macam afasia, namun scr klinis neurologis
didasarkan pada klasifikasi Benson (1979) dan
klasifikasi Krishner (1982).
Klasifikasi Benson
Sindroma Afasia Perisylvian
Afasia Broca
Afasia Wernicke
Afasia Konduksi
Sindroma Afasia Borderzone
Afasia Transkortikal Motorik
Afasia Infark Serebral Anterior
Afasia Transkortikal Sensorik
Afasia Transkortikal Campuran
Sindroma Afasia Subkortikal
Afasia Talamik
Afasia Striata
Afasia lesi zat putih
Sindroma Afasia tak terlokasi
Afasia Anomik
Afasia Global
Aleksia
Aleksia parieto-temporal
Aleksia Oksipital
Aleksia frontal
Agrafia Sindroma Terkait
Afemia
Tulikata murni
Aleksia wicara
Salah nama non afasia
MenurutKrishner (1982) utk menentukan
sindrom afasia perlu dikaji kemampuan
modalitas bahasa.
Bicara spontan
Pengertian auditif
Penamaan
Pengulangan
Membaca
Menulis
Bicara spontan
Pada pasien afasia bicara spontan bisa lancar (afasia
fluent) dan tidak lancar (afasia non fluen). Utk
membedakan dua jenis afasia ini dpt dipakai evaluasi
Watson.
A. Non Fluen A. Fluent
Ciri-ciri
(Broca) (Wernicke)
Kecepatan
Menurun Normal
bicara
Upaya bicara Meningkat Normal
Meningkat /
Banyak bicara Menurun
logorea
Prosodi Disprosodi Normal
Pengertian auditif
Yg dimaksud adl apakah seseorang dpt
mengerti dan memahami permintaan atau
perintah dari pemeriksa, misalnya dapat
menunjukkan objek yg disebut pemeriksa,
atau melaksanakan isi perintah dari yg
sederhana sampai yg lebih kompleks.
Penamaan
Apakah pasien dpt atau menyebutkan
nama, baik orang, benda yg diperlihatkan
kepadanya. Secara umum kesulitan pada
modalitas ini disebut anomia
Pengulangan
Yaitu kemampuan utk mengulang kata atau
kalimat yg disebutkan pemeriksa, mulai dari yg
sederhana sampai kalimat yg panjang. Perlu
diingat bahwa kegagalan kemampuan ini dpt
disebabkan jg ok gangguan pengenalan atau
artikulasi.
Membaca
Dinilai dgn melihat kemampuan seseorang utk
mengerti tulisan, baik berupa simbol, kata, ejaan,
kalimat maupun paragraf.
Menulis
Dinilai mengenai mekanisme atau kemampuan
menulis serial alfabet, dikte huruf, kata maupun
kalimat.
Dengan mengkaji kemampuan mobilitas di
atas tsb kita dpt menegakkan tipe sindroma
afasia. Sbg implikasi utk menghubungkan
sindroma afasia dgn kemampuan modalitas
bahasa dapat dipergunakan klasifikasi
Krishner yg telah dimodifikasi. Pada tabel
klasifikasi Krishner berikut ini dpt dilihat
gangguan modalitas yg tjd pd berbagai
macam sindroma afasia di atas. Dgn melihat
dan menelaah perbedaan-perbedaan
kemampuan bahasa di atas dpt ditentukan
diagnosa tipe afasia.
Saran Krishner dlm mengevaluasi penderita:
Pemeriksa hrs yakin adanya riwayat bhw
gangguan tsb didapat, misalnya kemampuan
berbicara dan berbahasa sebelum sakit utuh.
Kriteria batasan afasia hrs difahami, terutama
bhw afasia adl disfungsi berbahasa dan bkn
disfungsi artikulasi atau motorik.
Pemeriksa hrs mampu utk membedakan afasia
dgn gangguan kognisi umum atau gangguan
psikiatrik fungsional.
Jenis Bicara P.Auditif Penamaan Ulang Baca Tulis
Broca NF/Mutisme + - - + -
Wernicke F/Parafasia - - - - -
Global NF/Mutisme - - - - -
F/Parafasi
Konduksi + +/- - + +
Literal
Anomik F/Sirkumlok + - + + +
Tran.Kortik
NF/Gagap + +/- + + +
Motorik
Tran.Kortik F/Parafasia/
- - ++ - +/-
Sensorik Sirkumlok
Aleksia +
<Normal + +/- + - -
Agrafia
Aleksia
Normal + +/- + - +
Agrafia
Di samping gjl yg khas pd gangguan modalitas
bahasannya, pd setiap sindroma afasia dpt jg
dijumpai gangguan penyerta lainnya yg akan
dijelaskan berikut ini :
Sindroma Afasia Broca
Disebut jg afasia motorik, afasia ekspresif.
Afasia ini plg sering disebabkan oleh CVD, di samping
trauma kapitis, neoplasma otak, atau infeksi.
Gjl utama berupa kesulitan bertutur. Letak lesi di
hemisferium kiri (dominan) tepatnya di operkulum lobus
frontal dan parietal yg di perdarahi a.serebri media
superior kiri.
Sindroma Infark Area Broca. Letak lesi afasia ini lebih
kecil dan prognosis sembuhnya lebih baik, hanya saja di
sini modalitas pengertian auditifnya dpt terganggu.
Sindroma Afasia Wernicke
Memiliki nama lain afasia sensoris, afasia reseptif, afasia
akustis.
Ciri khasnya adl curah bicara yg fluen bahkan dpt logorea
dan adanya parafasia terutama parafasia verbal.
Letak lesi di girus temporalis superior hemisferum kiri, hal
ini yg menyebabkan sindroma afasia ini umumnya tdk
disertai hemiparesis.
Bentuk afasia yg lebih berat disebut afasia jargon, di mana
lesinya lebih luas dan parafasinya lebih banyak sehingga
bicaranya disebut Gado-gado bahasa Skizofrenia.
Sindroma Afasia Global
Istilah global atau total dipakai karena semua aspek
modalitas bahasa pd sindroma ini terganggu.
Kelainannya luas atau multipel di hemisferium kiri (anterior
maupun posterior) yg dipasok oleh a.serebri media.
Karena kerusakan yg luas ini dpt menyertai adanya
hemiparesis, hemi anesthesia, dsb.
Prognosis lebih buruk, akibat terganggunya hampir semua
kemampuan bahasa.
Sindroma Afasia Konduksi
Disebut jg sbg afasia sentralis.
Gjl yg plg menyolok adl dlm modalitas pengulangan,
namun pengertian auditifnya msh baik.
Pd curah bicaranya bs tjd parafasia literal.
Lesi terdapat di fasikulus arkuatus hemisferium kiri.
Sindroma Afasia Anomik
Nama lainnya adl afasia nominal, afasia amnestis.
Adl afasia dan gjl utama anomia, yaitu kesulitan
menemukan kata dgn ciri khas dpt menunjukkan
objek ttp tdk dpt menyebutkan namanya.
Keadaan ini dpt tjd pd keadaan non afasia, spt
demensia maupun pd keadaan fisiologis (Beningn
forgetfulness).
Macam-macam anomia :
1. Anomia produksi kata
2. Anomia memilih kata
3. Anomia semantik
4. Anomia khusus kategori
Sindroma Afasia Transkortikalis Motorik (SATM).
Disebut jg sindroma isolasi anterior atau afasia dinamis.
Berciri khas pengulangan kalimat yg panjang tnp salah
walaupun bicara spontannya terbata-bata dan sulit.
Letak lesi di daerah frontal kiri regio para sagital superior
dan regio frontal posterior inferior yg disuplai a.serebri
anterior.
Kebanyakan afasia ini disertai hemiparesis kontra latetral,
di mana tungkai lebih berat dari lengan.
Sindroma Afasia Transkortikalis Sensorik
Yg menonjol pd afasia ini adl kemampuan mengulang yg
baik dan nyaris sempurna dgn adanya ekholalia.
Bila terdapat gjl neurologik biasanya ringan.
Letak lesi tdk begitu jelas, dpt mengenai borderzone
parietal, temporal atau kombinasi keduanya.
Sindroma aleksia dan Agrafia
Aleksia adl kehilangan kemampuan untuk mengerti kata-kata
atau kalimat yg ditulis (membaca).
Agrafia adl ketidakmampuan utk menghasilkan bahasa tulis
akibat gangguan di otak.
Pada sindroma aleksia dgn agrafia pasien tdk dpt membaca dan
menulis.
Sedangkan aleksia tanpa agrafia pasien tdk dpt membaca ttp
dpt menulis, tipe yg terakhir ini disebut aleksia murni.
Sindroma Afasia Subkortikal
Sindroma afasia tdk hanya tjd akibat gangguan di korteks
serebri ttp jg dpt terjadi di subkorteks serebri. Biasanya akibat
perdarahan intra serebri.
Dpt tjd afasia talamik, striatal tergantung pd letaknya.
Pd sindroma afasia talamik dicirikan dgn curah verbal yg banyak
parafasia dgn pengertian auditifnya yg cukup baik dan
pengulangan yg normal.
Prognosis umumnya baik.
Defisit neurologis spt hemiparesis dpt dijumpai.
Kesimpulan
Afasia mrpk kelainan dasar dr fungsi luhur sbg fungsi
SDM.
Afasia srg dijumpai sbg gjl dr stroke, cedera kepala
maupun kerusakan otak lainnya dan diperkirakan
frekwensinya akan meningkat sejalan dgn insiden
penyakit / gangguan di otak.
Dgn sindromologi afasia dpt ditentukan jenis afasianya
dan dpt diperkirakan scr umum letak kelainannya di
otak.
Masalah afasia bukanlah masalah yg sederhana baik
dlm diagnosa maupun penanganannya.
Perlu pemahaman yg lebih mendalam mengenai afasia
Demensia
Adlkumpulan gjl klinik yg disebabkan oleh
berbagai latar belakang peny dan ditandai
oleh hilangnya memori jangka pendek dan
gangguan global fungsi mental, termasuk
fungsi bahasa, mundurnya kemampuan
berfikir abstrak, kesulitan merawat diri
sendir, perubahan perilaku, emosi labil, dan
hilangnya pengenalan waktu dan tempat
(PERDOSSI)
Definisi lain menyebutkan bhw demensia adl
gangguan kognisi yg ditandai dgn kemunduran
intelektual tnp adanya gangguan tingkat
kesadaran atau situasi stress, menimbulkan
gangguan dlm pekerjaan, aktivitas harian dan
sosial, yg disebabkan oleh berbagai keadaan yg
sebagian msh reversible.
Menurut Sidiarto kriteria demensia dijabarkan sbg
sebuah gangguan intelektual sedemikian berat shg
mengganggu fungsi sosial dan pekerjaan serta
defisit tsb hrs multifaset, melibatkan memori,
membuat keputusan, pikiran abstrak, dan
berbagai wawasan fungsi luhur; wawasan kognitif
tsb adl gangguan memori, dan minimal satu
diantara gjl berikut : afasia, apraksia, agnosia,
atau gangguan fungsi eksekutif.
Demensia terbagi dlm :
Vaskuler demensia (20%)
Kortikal demensia / Alzheimer demensia (50%)
Mix demensia (20%)
Demensia dpt dijumpai pd pasien gangguan
serebro vaskuler, trauma kapitis, infeksi di SSP,
epilepsi, tumor serebri, dan hidrosefalus.
demensia dpt jg mrpk akibat sekunder dr berbagai
peny, misal HIV, gangguan endokrin (hiper-
hipotiroidisme, DM), neoplasma, anemia, asthenia,
peny jantung, peny kolagen, hipertensi,
hiperlipidemia, dan arterisklerosis.
Patofisiologi
Demensia mungkin lebih sesuai diterangkan lewat
sistem saraf asetil kolin, terutama berkaitan dgn R
nikotinik.
Penurunan kognisi pd demensia alzheimer
patofisiologinya berhubungan dgn kerusakan sinap
nikotin di otak terutama daerah hipokampus dan
korteks.
Pd penderita demensia alzheimer tjd penurunan R
nikotinik di hipokampus yg berbeda scr bermakna
dibandingkan dgn kontrol pd usia yg sebanding.
Perry dkk menunjukkan pd korteks entorinal yg
kaya akan R nikotinik ternyata rentan thd amiloyd-
plaque shg R nikotinik mudah mengalami
kerusakan. Kerusakan ini berkaitan dgn mulai
timbulnya gjl demensia dan munculnya amiloyd-
plaque di daerah hipokampus dan korteks
intorinal.
Pemberian obat nikotin dpt memperbaiki atensi
belajar dan memorinya.
Penelitian neuro imaging memperkuat peran R
nikotin dlm patofisiologi demensia.
Pada pengamatan PET Scan menunjukkan adanya
kolerasi linier antara perubahan label C nikotin di
korteks temporalis thd penderita demensia
alzheimer dgn skor kognisinya.
Pemeriksaan Neuropsikologi
Meliputi evaluasi memori, orientasi, bahasa,
kalkulasi, praksis, visuospatial, dan
visuoperseptuol.
Mini Mental State Examination (MMSE) dan Clock
Drawing Test (CDT) dpt mjd pemeriksaan
penapisan, mjd pedoman utk evaluasi lebih lanjut,
megetahui adanya disfungsi kognitif, dan
menginformasikan penderita, keluarga, atau
pengasuhnya, menentukan penata laksanaan
berikutnya. Pada pemeriksaan ini hrs
dipertimbangkan tingkatan sosial, pendidikan, dan
budaya.
Pemeriksaan Laboratorium
Dilakukanutk mencari etiologi, khususnya
demensia yg reversible.
Pemeriksaan yg dianjurkan :
Pemeriksaan darah lengkap utk mendeteksi
kelainan sistemik, termasuk pemeriksaan
elektrolit, kalsium, BUN, fungsi hati, hormon
tiroid, dan kadar B12.
Pd pasien resiko tinggi pemeriksaan utk
mendeteksi HIV dan neurosiphilis.
Pemeriksaan Neuroimaging
CT Scan dan MRI : dpt mendeteksi adanya
kelainan struktural.
PET Scan dan SPECT : utk pemeriksaan
fungsional.
Pemeriksaan EEG tdk menunjukkan kelainan
yg spesifik, pd stadium lanjut dpt ditemukan
perlambatan umum.
Penatalaksanaan Farmakologis
Pd demensia reversible ditujukan utk pengobatan
kausal.
Pd demensia vaskuler walaupun tdk dpt disembuhkan
ttp dpt dihentikan progresivitas penyakitnya dgn
pengobatan thd faktor resiko.
Pd demensia alzheimer pengobatan ditujukan utk
menghentikan progresivitas penyakitnya.
Bbrp obat direkomendasikan :
Gol asetil kolin esterase inhibitor, antara lain donopezil,
HCl, rivastigmin
Obat gol estrogen, meningkatkan aktifitas
kholinergik, dpt bersifat anti oksidan yang
terbukti dpt memperlambat onset Demensia
pada wanita menopose.
Antioksidan, berfungsi menghambat oksidasi
oleh radikal bebas yg berlebihan shg merusak
sel neuron
PENATALAKSANAAN NON FARMAKOLOGIS
Ditujukan untk keluarga lingkungan & penderita,
al. : Brain Gym : latihan fisik yg dpt memacu
aktifitas ialah :
- Mengelola faktor resiko
- Gizi seimbang
- Melaksanakan hobi & aktifitas sosial yg
sesuai
- Menghilangkan Stress
- Melaksanakan LUPA
- Orientasi, waktu, tempat, orang
Anda mungkin juga menyukai
- Neurolinguistik Dalam BahasaDokumen5 halamanNeurolinguistik Dalam BahasaNana Diana100% (1)
- Fungsi Luhur, Fungsi Kortikal Luhur, Neurobehaviour, PsikoneurologiDokumen28 halamanFungsi Luhur, Fungsi Kortikal Luhur, Neurobehaviour, PsikoneurologiIsni Ayu LestariBelum ada peringkat
- T.PT 13anfisgen Fungsi Luhur EVA AZHARINA MEVYA - 23003087Dokumen5 halamanT.PT 13anfisgen Fungsi Luhur EVA AZHARINA MEVYA - 23003087dewiafifasantia119Belum ada peringkat
- Materi Pengembangan Kognitif Anak Usia DiniDokumen13 halamanMateri Pengembangan Kognitif Anak Usia Diniyakupsaputra123Belum ada peringkat
- Fungsi LuhurDokumen11 halamanFungsi Luhurwidya sari jevinda100% (1)
- Resuman MarkasDokumen5 halamanResuman MarkasNurwaty syukurBelum ada peringkat
- Plastisitas OtakDokumen8 halamanPlastisitas OtakbaraBelum ada peringkat
- Assasment NeurobehaviorDokumen18 halamanAssasment NeurobehaviorLaras Dyah PermaningtyasBelum ada peringkat
- Tugas 2 Pengantar Pend. ABKDokumen2 halamanTugas 2 Pengantar Pend. ABKAnifah WidiyantiBelum ada peringkat
- Kajian NeurolinguistikDokumen4 halamanKajian Neurolinguistiksmiledya117Belum ada peringkat
- Kelompok 6 - Psikolinguistik - Landasan Neurologis Pada BahasaDokumen15 halamanKelompok 6 - Psikolinguistik - Landasan Neurologis Pada BahasaSiti AminahBelum ada peringkat
- UAS Budiman 23003234Dokumen12 halamanUAS Budiman 23003234Aslam KidsBelum ada peringkat
- Referat Fungsi LuhurDokumen21 halamanReferat Fungsi LuhurYuniParaditaDjunaidiBelum ada peringkat
- Fungsi KognitifDokumen8 halamanFungsi KognitifrizkiBelum ada peringkat
- Neuripsikologi Dalam Kecerdasan Kelompok IndDokumen10 halamanNeuripsikologi Dalam Kecerdasan Kelompok IndZaidan AriqBelum ada peringkat
- Buku UtamaDokumen32 halamanBuku UtamaVivie ChairunnisaBelum ada peringkat
- Perkembangan OtakDokumen13 halamanPerkembangan OtakRudi AndriantoBelum ada peringkat
- Uts Pengembangan Bahasa Anak Usia DiniDokumen5 halamanUts Pengembangan Bahasa Anak Usia DiniAnggun Yulfiastanti MalakaBelum ada peringkat
- UTS Neurosains - Ni Putu Manik Erlin CahyaniDokumen5 halamanUTS Neurosains - Ni Putu Manik Erlin Cahyanimanik.erlinBelum ada peringkat
- Bab 9 - Otak Manusia Bahasa-EditDokumen15 halamanBab 9 - Otak Manusia Bahasa-EditJefri Hussin100% (1)
- Otak Bahasa Dan Pikiran Dalam Mind Map b593bf60Dokumen29 halamanOtak Bahasa Dan Pikiran Dalam Mind Map b593bf60Pandulu Pancer SuryaningdyahBelum ada peringkat
- Terapi Bicara Pada AnakDokumen9 halamanTerapi Bicara Pada AnakDhanny RefBelum ada peringkat
- Fungsi KognitifDokumen5 halamanFungsi KognitifLulu Nuraini0% (1)
- MMSEDokumen9 halamanMMSEMatsrial100% (1)
- Fungsi Kortikal LuhurDokumen16 halamanFungsi Kortikal LuhurSekarAndiniBelum ada peringkat
- Makalah PsikolinguistikDokumen16 halamanMakalah PsikolinguistikgabrielleBelum ada peringkat
- LP Sistem Neurosensori Dan Sistem Digestive 1Dokumen32 halamanLP Sistem Neurosensori Dan Sistem Digestive 1Anonymous O0OhAwtXBelum ada peringkat
- PsikolinguisitkDokumen12 halamanPsikolinguisitkfajwaBelum ada peringkat
- Terapi Gangguan Bicara Pada AnakDokumen9 halamanTerapi Gangguan Bicara Pada AnakRick MilesBelum ada peringkat
- PsikolinguistikDokumen18 halamanPsikolinguistikAhmad Rizqi MaulanaBelum ada peringkat
- Pemfisika NeurologiacaDokumen10 halamanPemfisika NeurologiacaMerry YulianiBelum ada peringkat
- Ruang Lingkup Asesmen Perkembangan AbkDokumen9 halamanRuang Lingkup Asesmen Perkembangan AbkResta RayandaBelum ada peringkat
- 03 Perkembangan Kemampuan Reseptif Dan PersepsiDokumen9 halaman03 Perkembangan Kemampuan Reseptif Dan PersepsiSukma MappasulleBelum ada peringkat
- BJT - Umum - tmk2 Anak Berkebutuhan KhususDokumen3 halamanBJT - Umum - tmk2 Anak Berkebutuhan KhususNURTRIA DAMAYANTIBelum ada peringkat
- Refleksi KB 2 Pedagogik 3Dokumen2 halamanRefleksi KB 2 Pedagogik 3Lailatul QodriahBelum ada peringkat
- Winendy Fungsi Luhur 16310317Dokumen9 halamanWinendy Fungsi Luhur 16310317Winendy DeoBelum ada peringkat
- Epl321soalan 3 Dan Epl 311 Soalan 3Dokumen6 halamanEpl321soalan 3 Dan Epl 311 Soalan 3kiongBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa Dan OtakDokumen13 halamanMakalah Bahasa Dan OtakEka Hilda S100% (1)
- Ruangguru DigitalbootcampDokumen4 halamanRuangguru DigitalbootcampBahaudin HabibiBelum ada peringkat
- Learning Issue B21BDokumen7 halamanLearning Issue B21BBalhumBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 9Dokumen23 halamanMakalah Kelompok 9afief Clara riana0% (1)
- Fungsi LuhurDokumen33 halamanFungsi Luhurtaru_airiqu5741Belum ada peringkat
- Anatomi Otak BiopsikologiDokumen27 halamanAnatomi Otak BiopsikologiIndar FirdayantiBelum ada peringkat
- Psikolinguistik Dan KajiannyaDokumen21 halamanPsikolinguistik Dan Kajiannyathera dwiBelum ada peringkat
- Gangg - Bahasa FixDokumen30 halamanGangg - Bahasa FixRica AnrizBelum ada peringkat
- Rangkuman BiopsikologiDokumen7 halamanRangkuman BiopsikologiEby FebriBelum ada peringkat
- RESUME BAB 2 Psikologi (23020930038)Dokumen3 halamanRESUME BAB 2 Psikologi (23020930038)sadewa030514Belum ada peringkat
- 17.kuliah Gangguan Fungsi Kortikal LuhurDokumen130 halaman17.kuliah Gangguan Fungsi Kortikal LuhurMagfira Al HabsyiBelum ada peringkat
- Artikel Gangguan Berbahasa (Bu Sri Waljinah)Dokumen9 halamanArtikel Gangguan Berbahasa (Bu Sri Waljinah)Nia Nur InsaniBelum ada peringkat
- LP KomunikasiDokumen7 halamanLP Komunikasirian0877Belum ada peringkat
- PDGK4407 - Peng Pend Anak Berkebutuhan Khusus - Tugas2Dokumen5 halamanPDGK4407 - Peng Pend Anak Berkebutuhan Khusus - Tugas2domas murtiBelum ada peringkat
- Gangguan Neurobehavior 1Dokumen63 halamanGangguan Neurobehavior 1Dresti RF100% (1)
- Kuliah Gangguan KognitifDokumen153 halamanKuliah Gangguan KognitiftututBelum ada peringkat
- Pengaruh Perkembangan Otak Terhadap Kecerdasan AnakDokumen20 halamanPengaruh Perkembangan Otak Terhadap Kecerdasan AnakirwantoBelum ada peringkat
- Makalh NeuroDokumen20 halamanMakalh NeuroYiyi TatiBelum ada peringkat
- MAKALAH LANSIA DENGAN GANGGUAN KOGNITIF DEMENSIA Kel.5Dokumen17 halamanMAKALAH LANSIA DENGAN GANGGUAN KOGNITIF DEMENSIA Kel.5Yongky PradistaBelum ada peringkat
- Materi Neuropsikologi (Digabungin)Dokumen24 halamanMateri Neuropsikologi (Digabungin)Zulaikha UtamiBelum ada peringkat
- Final Temuan PsychoDokumen5 halamanFinal Temuan Psychoandi irwinBelum ada peringkat
- Bahasa tubuh dan komunikasi non-verbal: Cara memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik berkat psikologi dan ilmu saraf bahasa tubuhDari EverandBahasa tubuh dan komunikasi non-verbal: Cara memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik berkat psikologi dan ilmu saraf bahasa tubuhBelum ada peringkat
- PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Pit1 - Diagnosis Dan Tatalaksana DBD Terkini PDFDokumen14 halamanPit1 - Diagnosis Dan Tatalaksana DBD Terkini PDFmiandaBelum ada peringkat
- PerioperatifDokumen4 halamanPerioperatifmiandaBelum ada peringkat
- Jurding IpdDokumen20 halamanJurding IpdmiandaBelum ada peringkat
- Konsensus Petri 2010 Tifoid PDFDokumen2 halamanKonsensus Petri 2010 Tifoid PDFmiandaBelum ada peringkat
- Mekanisme Persalinan NormalDokumen33 halamanMekanisme Persalinan Normalmianda100% (2)
- Persalinan NormalDokumen55 halamanPersalinan NormalmiandaBelum ada peringkat