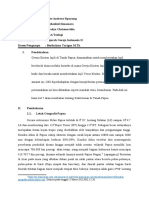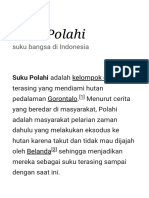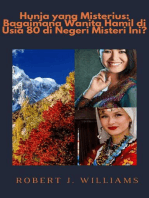Orang Donggo
Orang Donggo
Diunggah oleh
Fadhel Junio Nandhita UtamaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Orang Donggo
Orang Donggo
Diunggah oleh
Fadhel Junio Nandhita UtamaHak Cipta:
Format Tersedia
orang donggo KEPADA: 1 penerima Tampilkan Detail SUKU DONGGO Nusa Tenggara Barat Letak Populasi Bahasa Anggota
Gereja Alkitab dalam bahasa Donggo Film Yesus dalam bahasa Donggo : Nusa Tenggara Barat : 20.000 jiwa : Bima Donggo : 7 (0,035%) : Tidak Ada : Tidak Ada
Siaran radio pelayanan dalam bahasa Donggo (Juli 98) : Tidak Ada
Suku Donggo tinggal di kecamatan Donggo, kabupaten Bima, propinsi Nusa Tenggara Barat. Nama Donggo atau lengkapnya Dou Donggo berarti "orang gunung." Berdasarkan lokasinya, Dou donggo dibedakan atas Donggo Ipa dan Donggo Ela. Daerah Donggo Ipa terletak di sebelah timur teluk Bima. Donggo Ela terletak di sebelah barat teluk Bima. Perkampungan mereka mengelompok di pinggir jalan atau sungai. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Bima Donggo. Dalam bahasa ini ada bahasa halus dan kasar. SOSIAL BUDAYA Mata pencaharian utamanya adalah meramu. Selain itu mereka juga bersawah, beternak kuda dan berburu. Dalam bertani dikenal kegiatan gotong royong yang disebut weharima. Mereka mengenal pertanian ladang berpindah-pindah karena daerahnya berbukit-bukit dan berbatu.
Sebuah desa di Bima, yang disebut kamp atau kampo, dikepalai oleh kepala desa yang disebut ncuhi, ompu atau gelarang. Dalam menjalankan tugasnya, ia dibantu oleh dau ma tua, yaitu golongan kerabat yang tua dan dihormati. Bagi orang Donggo, nama tidak hanya sekedar sebutan diri tetapi mengandung makna dalam hubungan sosial, menunjukkan bagaimana mereka mengatur hubungan-hubungan pribadi, misalnya : hubungan kekerabatan, hubungan yang menunjukkan status seseorang dan hubungan berdasarkan umur (tua dan muda). Upacara yang terpenting bagi mereka adalah upacara kasaro (untuk orang meninggal). Selain itu ada juga upacara sapisari (penguburan), doa rasa (doa kampung) yang diadakan 5 tahun sekali, dan pesta Raju (anjing hutan).
Orang Donggo Orang Donggo dikenal sebagai penduduk asli yang telah menghuni tanah Bima sejak lama. Mereka sebagian besar menempati wilayah pegunungan. Karena letaknya yang secara geografis di atas ketinggian rata-rata tanah Bima, Dou Donggo (sebutan bagi Orang Donggo dalam bahasa Bima), kehidupan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani masyarakat Bima saat ini. Masyarakat Donggo mendiami sebagian besar wilayah Kecamatan Donggo sekarang, yang dikenal dengan nama Dou Donggo Di, sebagian lagi mendiami Kecamatan Wawo Tengah (Wawo pegunungan) seperti Teta, Tarlawi, Kuta, Sambori dan Kalodu Dou Donggo Ele. Pada awalnya, sebenarnya penduduk asli ini tidak semuanya mendiami wilayah pegunungan. Salah satu alasan mengapa mereka umumnya mendiami wilayah pegunungan adalah karena terdesak oleh pendatang-pendatang baru yang menyebarkan budaya dan agama yang baru pula, seperti agama Islam, Kristen dan bahkan Hindu/Budha. Hal ini dilakukan mengingat masih kuatnya kepercayaan dan pengabdian mereka pada adat dan budaya asli yang mereka
anut jauh-jauh hari sebelum para pendatang tersebut datang. Kepercayaan asli nenek moyang mereka adalah kepercayaan terhadap Marafu (animisme). Kepercayaan terhadap Marafu inilah yang telah mempengaruhi segala pola kehidupan masyarakat, sehingga sangat sukar untuk ditinggalkan meskipun pada akhirnya seiring dengan makin gencarnya para penyiar agama Islam dan masuknya para misionaris Kristen menyebabkan mereka menerima agama-agama yang mereka anggap baru tersebut. Sebagaimana umumnya mata pencaharian masyarakat yang masih tergolong tradisional, mata pencaharian Dou Donggo pun terpaku pada berladang dan bertani. Sebelum mengenal cara bercocok tanam, mereka biasanya melakukan perladangan berpindah-pindah, dan karena itu tempat tinggal mereka pun selalu berpindah-pindah pula (nomaden). Berhadapan dengan kian gencarnya arus modernisasi, seiring itu pula pemahaman masyarakat akan kenyataan hidup berubah, terutama dalam hal pendidikan dan teknologi. Saat ini, telah sekian banyak para sarjana asli Donggo, yang umumnya menimba ilmu di luar daerah seperti Ujung Pandang, Mataram atau bahkan ke kota-kota di pulau Jawa seperti Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan teknologi, yang akhirnya merubah pola hidup mereka seperti halnya dalam penggarapan sawah, kendaraan sampai alat-alat elektronik rumah tangga, karena hampir semua daerahnya telah dialiri listrik. Bahkan tak jarang mereka menjadi para penyiar agama seperti Dai, karena telah begitu banyaknya mereka naik haji.Orang Donggo Orang Donggo dikenal sebagai penduduk asli yang telah menghuni tanah Bima sejak lama. Mereka sebagian besar menempati wilayah pegunungan. Karena letaknya yang secara geografis di atas ketinggian rata-rata tanah Bima, Dou Donggo (sebutan bagi Orang Donggo dalam bahasa Bima), kehidupan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani masyarakat Bima saat ini. Masyarakat Donggo mendiami sebagian besar wilayah Kecamatan Donggo sekarang, yang dikenal dengan nama Dou Donggo Di, sebagian lagi mendiami
Kecamatan Wawo Tengah (Wawo pegunungan) seperti Teta, Tarlawi, Kuta, Sambori dan Kalodu Dou Donggo Ele. Pada awalnya, sebenarnya penduduk asli ini tidak semuanya mendiami wilayah pegunungan. Salah satu alasan mengapa mereka umumnya mendiami wilayah pegunungan adalah karena terdesak oleh pendatang-pendatang baru yang menyebarkan budaya dan agama yang baru pula, seperti agama Islam, Kristen dan bahkan Hindu/Budha. Hal ini dilakukan mengingat masih kuatnya kepercayaan dan pengabdian mereka pada adat dan budaya asli yang mereka anut jauh-jauh hari sebelum para pendatang tersebut datang. Kepercayaan asli nenek moyang mereka adalah kepercayaan terhadap Marafu (animisme). Kepercayaan terhadap Marafu inilah yang telah mempengaruhi segala pola kehidupan masyarakat, sehingga sangat sukar untuk ditinggalkan meskipun pada akhirnya seiring dengan makin gencarnya para penyiar agama Islam dan masuknya para misionaris Kristen menyebabkan mereka menerima agama-agama yang mereka anggap baru tersebut. Sebagaimana umumnya mata pencaharian masyarakat yang masih tergolong tradisional, mata pencaharian Dou Donggo pun terpaku pada berladang dan bertani. Sebelum mengenal cara bercocok tanam, mereka biasanya melakukan perladangan berpindah-pindah, dan karena itu tempat tinggal mereka pun selalu berpindah-pindah pula (nomaden). Berhadapan dengan kian gencarnya arus modernisasi, seiring itu pula pemahaman masyarakat akan kenyataan hidup berubah, terutama dalam hal pendidikan dan teknologi. Saat ini, telah sekian banyak para sarjana asli Donggo, yang umumnya menimba ilmu di luar daerah seperti Ujung Pandang, Mataram atau bahkan ke kota-kota di pulau Jawa seperti Bandung, Yogyakarta, Jakarta dan lain-lain. Demikian juga halnya dengan teknologi, yang akhirnya merubah pola hidup mereka seperti halnya dalam penggarapan sawah, kendaraan sampai alat-alat elektronik rumah tangga, karena hampir semua daerahnya telah dialiri listrik.
Bahkan tak jarang mereka menjadi para penyiar agama seperti Dai, karena telah begitu banyaknya mereka naik haji.
Sistem Kepercayaan Orang Donggo (Sumbawa Timur) Sulit sekali untuk memahami keyakinan orang Donggo, karena mereka begitu tertutup dan amat takut untuk memberi penjelasan mengenai apa yang mereka yakini. Hal ini tentu disebabkan karena banyak peristiwa agama telah berusaha untuk menanamkan pengaruhnya, terutama peristiwa 1969, peristiwa 1974, peritiwa 1979, belum lagi peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Belanda. Tulisan-tulisan tentang keyakinan orang Donggo tidak cukup jelas, bahkan kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Misalnya J. Elbert (1912: hlm. 69) mencatat bahwa yang menjadi ncuhi hanya dari keturunan duna (belut), sedang P. Arndt (1952) mencatat bahwa dou deke (tokok) yang berhak menjadi ncuhi. Baik Elbert dan Arndt mencatat bahwa pada masa itu hanya terdapat 5 buah klen patrilineal yang exogam, sedang masyarakat sekarang mengenal lebih dari 13 buah klen. Jadi walaupun merek seolah-olah tidak berkembang dan tidak menjalankan kepercayaannya lagi, secara perlahan dan pasti mereka mengembangkan diri dengan klen winte yang menjadi pemimpin masyarakat.
Menurut orang Donggo, peradaban manusia dibagi ke dalam tiga zaman: xaman anfari (zaman manusia terbang), zaman moda (zaman manusia hilang) dan zaman made (zaman manusia mati). Nenek moyang mereka hidup dalam zaman moda, dan jenazah mereka tidak ada karena mereka tidak meninggal tetapi menghilang. Zaman sekarang merupakan zaman made, karena manusia meninggal dan jenazahnya dikubur.
Orang Donggo menjunjung tinggi lewa (atau dewa), yaitu kekuatan gaib yang ada di alam, seperti di gunung, di laut, di sungai, di langit dan di batu-batu besar. Selain itu mereka menghormati ruh nenek-moyang (ndoi) yang diyakini moyangnya ini tidak ada karena hilang di tempat-tempat tertentu atau berubah menjadi binatang dan benda-benda lainnya. Tempat dan benda-benda tersebut dikeramatkan dan mereka menganggap dirinya keturunannya. Benda-benda totemnya ini disebut marafu arau rafi. Marafu-lah yang memelihara dan menjadi manusia dari pengaruh tidak baik. Apabila seseorang sakit, maka ia pergi ke rafu-nya untuk memohon pada ndoi agar ia cepat disembuhkan dari penyakit dan dijauhkan dari halhal yang tidak baik. Ndoi kedudukannya sebagai perantara pada dewa, oleh karena itu semua permohonan ditujukan kepada ndoinya agar disampaikan pada dewa.
Rafu dan ndoi dibedakan atas laki dan perempuan. Rafu Sado laki ndoi-nya Tutarasa, dan Sado wanita ndoi-nya Roho. Meskipun demikian tidak semua rafu mempunyai ndoi, tetapi mereka tetap mempunyai ruh pelindung (ruh nenek-moyang) yang disebut ina ro wai (ibu dan nenek). Ama ro ompu (bapak dan kakek), misalnya, tidak mempunyai ndoi, tetapi mempunyai ina ro wai. Hal ini disebabakan ada ndoi yang tidak diketahui ke mana menghilangnya dan ada beberapa rafu yang datang dari Sumba, Flores, Ambon dan Latu. Nama-nama ndoi yang dikenal adalah Roho (mata air di gunung), Tuturasa (pohon besar di muka kampung), Ncuhi (di rumah adat), Lancoini (mata air di sungai), kadalu (batu besar dan datar di gunung), Tifamone, Tifasiwe, Pahawoha (di tengah kampung), Sorajara, Tutanawa dan Panintarwela (rumah-rumah yang ada di bagian belakang kampung dekat dengan kuburan), Mbotobua (pohon besar dekat sungai), Kariadewa (di kaki Gunung Pejambi) dan Ketorasa (pohon besar di tengah kampung). Ndoi Mbotobua kurang dikenal sehingga jarang disebut-sebut. Dalam doa-doa mereka, mereka mengatakan ndoi yang dua belas, yaitu ndoi (tanpa mbotobua dan tidak membedakan Tifa, laki-laki atau perempuan).
Elbert (1912) dan Arndt (1954) mencatat bahwa dewa yang tertinggi dan ditakuti adalah Lewa langi (dewa langit) yang tinggal di matahari. Sedang dalam doa-doa mereka yang sempat dicatat, mereka tidak menyebutkan dewa langit lagi, tetapi Ruma suu (raja atau Tuhan yang dijunjung), Ruma taala make se wara (Tuhan yang ada/satu), Ruma ndai (Tuhan kita). Hal ini disebabkan masuknya pengaruh luar sehingga mereka mencampuradukkan ide ndoi ndala, dewa rae, nabi Muhammad, nabi Isa serta nabi Adam.
Dalam konsep orang Donggo, ruh orang mati akan kembali ke langit melalui beberapa tahapan. Setelah 100 hari meninggal ia pergi ke Wadukajuji untuk bermain batu (sejenis catur dengan batu), lalu ke Oi Nduku (mata air) untuk minum-minum. Dari Oi Nduku ia melihat kembali ke desa asalnya di Mbari Rihu setelah itu ke Wadunaikai (batu besar di puncak gunung). Sebelum kembali ke langit ia mandi-mandi di danau Raba Lore. Mereka yang ditinggalkan sering mengantar sampai Wadunaikai, dan di sana mereka menangis, mengenang orang yang telah tiada. Prosesi ini masih sering dilakukan sampai sekarang, baik oleh mereka yang telah beragama Islam Kristen/Katolik.
Upacara yang terpenting bagi masyarakat Donggo adalah upacara kasaro dengan pesta raju (anjing hutan). Upacara ini diadakan untuk memohon hujan, air yang banyak, hasil pertanian yang baik, dan menaikkan ulat agar tidak mengganggu ladang dan sawahnya. Jalannya upacara dipimpin oleh ncuhi. Pagi hari dipukul wuni (gendang) agar warga desa berkumpul di halaman ncuhi. Setelah itu mereka pergi berburu ke hutan dari pagi hingga sore hari. Hal ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Lamanya berburu tidak sama tiap tahun; bila tahun ini 3 hari, maka tahun berikutnya 5 hari dan tahun kemudian 7 hari. Setelah 7 hari, lamanya maka berburu kembali lagi selama 5 hari lalu 3 hari, demikian seterusnya. Pada saat-
saat seperti itu tidak ada orang luar yang boleh pergi ke kampung, dan seluruh desa diberi pagar. Wanita dan anak-anak tidak ada yang tinggal di dalam rumah, tetapi pergi menganyam tikar di kali, karena pada saat itu udara panas sekali. Hanya kaum pria yang pergi, untuk berburu babi hutan atau rusa. Hasil perburuan dibawa ke kampung dan dimasak bersama, sedang kepalanya dibawa ke Kadalu (batu besar di puncak gunung) untuk dipersembahkan kepada dewa langit, sebelum mereka makan bersama. Selesai upacara, mereka menunggu hasil-nya, yaitu hujan, dan ncuhi menetapkan kapan mereka mulai tanam padi dan kedelai. Doa yang diucapkan dalam upacara kasaro ditujukan agar padi, jagung dan kedelai yang ditanam jangan dikurangi jumlahnya tetapi ditambah, karena hasil panen tersebut akan diberikan kepada yang bekerja dan untuk makan warga kampung.
Selain itu mereka mengadakan upacara doa rasa (doa kampung) yang diadakan setiap 5 tahun sekali agar warga desa dijauhkan dari segala macam penyakit dan malapetaka. Upacara ini ditujukan kepada dewa rae, yaitu dewa yang selalu membawa petaka. Paki oha (sedekah nasi) diletakkan di luar kampung, agar dewa rae tidak masuk ke kampung.
Upacara-upacara yang sehubungan dengan lingkarang hidup juga dikenal oleh orang Donggo, tetapi kurang banyak mengandung unsur keagamaan, seperti halnya upacara untuk pertanian dan mengusir wabah serta upacara untuk membuat rumah. Upacara perkawinan adalah salah satu upacara yang paling meriah dalam rangkaian upacara lingkaran hidup.
Selain upacara yang diadakan secara seremonial, mereka juga mengadakan upacara yang sifatnya individu kekeluargaan, misalnya doa untuk menghormati ndoi-nya, baik yang ada di tempat-tempat tertentu, atau untuk ndoi putanawa dan sorajaya yang melindungi suatu rumah
tangga. Tujuan dari upacara ini meminta pada ndoi putanawa dan sorajara agar diberi keselamatan, kesejahteraan, kesehatan dan kenyamanan dalam rumah tangga tersebut
Upacara lain yang dilakukan secara individu adalah upacara yang berkaitan dengan panen. Sebelum panen mereka meletakkan sesaji di pinggir ladang atau sawah dan mohon kepada dewa rae serta makhluk jahat seperti setan untuk tidak mengganggu padi, kedelai dan jagungnya dan agar mereka kembali ke tempat asalnya di hutan dan jangan kembali ke ladang atau sawah, cukup sampai di pinggir pagar atau di tepi sawah-ladangnya tempat mereka meletakkan sesaji tersebut. Upacara ini juga dilakukan ketika adakan turun ke sawah atau ladang dengan doa yang sama dan sesaji yang sama pula.
Tampak di sini bahwa masyarakat Donggo lebih mengutamakan hal-hal yang berhubungan dengan pertanian daripada lingkaran hidup. Hal ini disebabkan alamnya yang keras dengan musim panas yang amat panjang serta sulit air, sehingga mereka menjadi pekerja yang rajin, yang selalu berpacu dengan waktu.
Keunikan Rumah Tradisional Donggo
(KM. Sarangge) Bima dan Donggo memang unik. Meski berada dalam satu rumpun wilayah, namun adat dan budaya orang Bima dan Donggo memiliki perbedaan baik dari segi bahasa maupun adatnya. Menurut penelitian Antropologi, Orang-orang Bima(Mbojo) yang mendiami sebelah timur dan selatan teluk Bima merupakan keturunan campuran yang berasal dari Melayu dan suku-suku lainnya. Sedangkan orang-orang Donggo Ele( di gugusan pegunungan La Mbitu) dan Donggo Di (di gugusan pegunungan Soromandi) merupakan
penduduk asli Bima yang telah menyinggir ke daerah pegunungan karena cenderung mempertahankan budaya leluhur. Salah satu dari perbedaan itu adalah dari seni arsitekturnya yaitu rumah. Meskipun saat ini, bentuk-bentuk rumah di Donggo sudah jarang terlihat seperti bentuk aslinya dulu dan sudah mengadopsi model rumah seperti rumah orang-orang Bima dan rumah batu atau rumah permanen arsitektur masa kini. Tetapi pada zaman dulu, Rumah Tradisional Donggo memiliki keunikan yang
membedakannya dengan seni arsitektur Bima. Mereka menyebutnya dengan Uma Lengge. Ada juga yang menyebut dengan Uma Leme (Rumah Runcing) karena bentuknya mirip puncak gunung, yang berbentuk limas. Ada juga yang menyebutnya dengan Rumah Ncuhi( Kepala Suku).Karena disisi rumah tersimpan alat-alat persembahan dan kesenian. Keunikannya adalah atap dan dinding rumah merupakan satu kesatuan. Jadi atapnya juga berfungsi sebagai dinding rumah. Atap dan dindingnya terbuat dari alang-alang yang dirajut tebal. Bagian rumah berfungsi sebagai tempat tidur, berbentuk segi empat sama sisi ukuran 2 x 2 meter. Selain itu juga berfungsi sebagai tempat memasak, menyimpan padi dan segala jenis bahan makanan seperti padi dan palawija. Rumah bagian bawah( lantai) berfungsi sebagai tempat musyawarah keluarga baik dalam rangka upacara perkawinan, upacara adat maupun kematian.
Pintu rumah berada di bagian yang tersembunyi yaitu di pojok atau di sudut ruang atas. Tangga rumah tidak selalu dalam keadaan terpasang. Dalam kebiasaan masyarakat Donggo, ada sandi atau tanda yang diketahui oleh kerabatnya dari cara mereka menyimpan tangga. Apabila tangganya dibiarkan terpasang, berarti penghuninya telah pergi ke ladang dan akan kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Apabila tangga disimpan agak jauh dari rumah, hal itu berarti penghuninya telah pergi jauh dan akan kembali dalam waktu yang
lama. Apabila ada anggota keluarga yang meninggal, jenazahnya tidak boleh diturunkan melalui pintu dan tangga. Tetapi diturunkan melalui atap rumah. Di halaman rumah harus ada beberapa buah batu sebagai tempat tinggal roh leluhur yang sudah meninggal. Dan pada waktu tertentu diadakan upacara pemujaan roh yang disebut Toho Dore. Antropolog Albert dalam kunjungannya di Bima pada tahun 1909 menamakan rumah tersebut A Frame (Kerangka Huruf A). Rumah seperti ini berfungsi sebagai penyimpan panas yang baik, mengingat daerah Donggo adalah daerah pegunungan yang berhawa dingin. Saat ini rumah seperti ini masih ditemukan di desa Padende dan Mbawa. Perlu upaya pelestarian agar rumah rumah ini tidak hilang tinggal kenangan bagi generasi. Karena wajah Donggo adalah wajah Bima dengan segala keunikan dan romantika sejarahnya.
Anda mungkin juga menyukai
- Suku Anak DalamDokumen10 halamanSuku Anak DalamMasroni Wardi100% (1)
- Makalah AntropologiDokumen18 halamanMakalah Antropologisindimei alvianiBelum ada peringkat
- Suku DonggoDokumen4 halamanSuku DonggoLaila Marifa AzmiBelum ada peringkat
- Suku Donggo Dan Suku SumbaDokumen4 halamanSuku Donggo Dan Suku SumbaMeli RahmawatiBelum ada peringkat
- SamboriDokumen21 halamanSamboriRafika Putri AghataBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Buk Lestari 2Dokumen21 halamanProposal Penelitian Buk Lestari 2Kiky Say PanghurinaBelum ada peringkat
- Penelitian 1526944779Dokumen20 halamanPenelitian 1526944779Cristi AndiniBelum ada peringkat
- Adat Dan Budaya Suku Dani Di Tanah PapuaDokumen19 halamanAdat Dan Budaya Suku Dani Di Tanah PapuanejadBelum ada peringkat
- Di Sulsel Terdapat Banyak SukuDokumen9 halamanDi Sulsel Terdapat Banyak SukuSAHE9599Belum ada peringkat
- SUKU KUBU - Kelompok 2Dokumen4 halamanSUKU KUBU - Kelompok 2Kaylasyifa Azzahrie Nurul HanifahBelum ada peringkat
- Etnografi Suku Moi Papua BaratDokumen8 halamanEtnografi Suku Moi Papua BaratLia DdngBelum ada peringkat
- Kebudayaan Suku TorajaDokumen19 halamanKebudayaan Suku TorajaSasha Ve100% (1)
- SukuDokumen37 halamanSukujaquelineBelum ada peringkat
- Edu 3106Dokumen29 halamanEdu 3106Maryani HashimBelum ada peringkat
- Suku DaniDokumen17 halamanSuku DaniRizal Gunawan100% (1)
- TorajaDokumen11 halamanTorajaFernandus Pagasing100% (1)
- Adat Dan Budaya Suku Dani Di Tanah PapuaDokumen33 halamanAdat Dan Budaya Suku Dani Di Tanah Papuamando oyaitouBelum ada peringkat
- TORAJADokumen25 halamanTORAJARaden Fasha0% (1)
- Bab IiDokumen11 halamanBab IiDewi Gina Sari YumnaBelum ada peringkat
- Asal Usul Kaum Dusun Di SabahDokumen2 halamanAsal Usul Kaum Dusun Di SabahIjam RasininBelum ada peringkat
- Makalah Rambu SoloDokumen17 halamanMakalah Rambu SoloTri Haksagian Pasunggingan100% (2)
- Arsitektur PapuaDokumen13 halamanArsitektur PapuadikaBelum ada peringkat
- Etnografi Suku Moi Papua BaratDokumen8 halamanEtnografi Suku Moi Papua BaratRheyBelum ada peringkat
- Hukum Adat Suku DaniDokumen16 halamanHukum Adat Suku DanishabrinaBelum ada peringkat
- FULL ESSAIMEN Kepentingan Budaya Masyarakat Di Sabah Dan SarawakDokumen22 halamanFULL ESSAIMEN Kepentingan Budaya Masyarakat Di Sabah Dan Sarawakabdul salleh100% (3)
- Makalah Suku TorajaDokumen20 halamanMakalah Suku TorajaRendhy Baderan90% (31)
- Adat Istiadat Suku TorajaDokumen16 halamanAdat Istiadat Suku TorajaAdi Julie100% (2)
- Masyarakat Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Atau ToliDokumen12 halamanMasyarakat Dan Kebudayaan Kabupaten Buol Atau ToliDy LaindjongBelum ada peringkat
- Suku-Suku Di KaisDokumen8 halamanSuku-Suku Di KaisCara JeBelum ada peringkat
- Etnografi Suku Donggo Insyaallah Fiks BGTDokumen21 halamanEtnografi Suku Donggo Insyaallah Fiks BGTPutri Ed StylesBelum ada peringkat
- Cehati Chika Lynardo Antro 4Dokumen5 halamanCehati Chika Lynardo Antro 4chika lynrdBelum ada peringkat
- Kaum Kadazan DusunDokumen2 halamanKaum Kadazan DusunNur BalqisBelum ada peringkat
- MAKALAH Suku TenggerDokumen12 halamanMAKALAH Suku TenggerAyangBelum ada peringkat
- Orang RimbaDokumen11 halamanOrang RimbaAdilla PutriBelum ada peringkat
- Suku TorajaDokumen7 halamanSuku TorajaseniatiBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen11 halamanBab I Pendahuluantya sumendongBelum ada peringkat
- Sejarah Orang JambiDokumen4 halamanSejarah Orang Jambidwi ardiahBelum ada peringkat
- Asal-Usul WonorejoDokumen6 halamanAsal-Usul WonorejoShofi AnnisaBelum ada peringkat
- KLMPK EtnoDokumen6 halamanKLMPK EtnoPatranBelum ada peringkat
- Artikel Tentang TorajaDokumen19 halamanArtikel Tentang TorajaMuhammad RisaldiBelum ada peringkat
- Suku MuyuDokumen13 halamanSuku MuyuAntik Tri SusantiBelum ada peringkat
- Makalah Erna SuminarDokumen17 halamanMakalah Erna Suminarkhairul fridarmawanBelum ada peringkat
- Kebudaayaan Pulau Sabu Dan RoteDokumen8 halamanKebudaayaan Pulau Sabu Dan RoteIyanDd FebRi PraTamaBelum ada peringkat
- Kebudayaan IndonesiaDokumen38 halamanKebudayaan IndonesiaStevany SilabanBelum ada peringkat
- Suku Yang Belum Mengenal AgamaDokumen5 halamanSuku Yang Belum Mengenal Agamawarnet sentaniBelum ada peringkat
- Masyarakat BajauDokumen40 halamanMasyarakat Bajauaryjune75% (4)
- Etnografi PapuaDokumen11 halamanEtnografi PapuaMarisa FahiraBelum ada peringkat
- Keberagaman Suku Di Lampung TengahDokumen4 halamanKeberagaman Suku Di Lampung TengahReynanda ApriliaBelum ada peringkat
- Tugas 1 Sosiologi-DistribusiDokumen7 halamanTugas 1 Sosiologi-DistribusibambangBelum ada peringkat
- Filsafat RicoDokumen4 halamanFilsafat RicoRico Adinata sinagaBelum ada peringkat
- SGI Kelompok 7 Mengenai Kekristenan Di PapuaDokumen22 halamanSGI Kelompok 7 Mengenai Kekristenan Di Papuajun alfiBelum ada peringkat
- Agama Suku WanaDokumen7 halamanAgama Suku WanaRivayaniBelum ada peringkat
- Suku Mante Di AcehDokumen5 halamanSuku Mante Di AcehValkrye Prastya100% (1)
- Suku Polahi - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia BebasDokumen17 halamanSuku Polahi - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas08Muhamad Muki mudinBelum ada peringkat
- UAS-Melti Pakkun-FilsafatDokumen8 halamanUAS-Melti Pakkun-FilsafatArman PramanaBelum ada peringkat
- Kebudayaan Suku Tengger Di Kabupaten ProbolinggoDokumen6 halamanKebudayaan Suku Tengger Di Kabupaten ProbolinggoFrislia Irama HendriawatiBelum ada peringkat
- Kebudayaan TorajaDokumen2 halamanKebudayaan Toraja25suwarsihBelum ada peringkat
- Kebudayaan Suku Tidung Dan KepercayaannyaDokumen12 halamanKebudayaan Suku Tidung Dan KepercayaannyaYenni DianaBelum ada peringkat
- Hunja yang Misterius: Bagaimana Wanita Hamil di Usia 80 di Negeri Misteri Ini?Dari EverandHunja yang Misterius: Bagaimana Wanita Hamil di Usia 80 di Negeri Misteri Ini?Belum ada peringkat