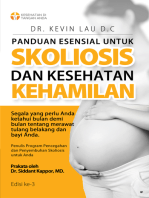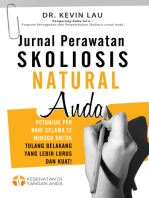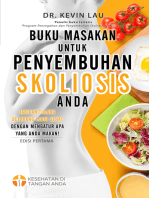Kms
Kms
Diunggah oleh
jaygalaxyHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kms
Kms
Diunggah oleh
jaygalaxyHak Cipta:
Format Tersedia
PENGKAJIAN PERTUMBUHAN DENGAN FORM WHO NCHS CDC2000 Grafik pertumbuhan yang paling umum digunakan di Amerika Serikat
adalah Grafik dari National Center for Health Statistik untuk anak laki-laki dan perempuan. Parameter pertumbuhan fisik meliputi berat badan, tinggi badan, ketebalan lipatan kulit dan lingkar lengan , dan lingkar kepala. Nilai untuk parameter pertumbuhan ini telah digambarkan dalam grafik persentil dan pengukuran anak dalam persentil dibandingkan dengan populasi secara umum. Pengukuran Berat Badan Pengukuran berat badan berdasarkan usia menggunakan persentil sebagai berikut : persentil 50-30 dikatakan normal, sedangakn persentil kurang atau sama dengan tiga termasuk malnutrisi. Penilaian berat badan berdasarkan tinggi menggunakan persentase dari median sebagai berikut 80-100% dikatakan malnutrisi sedang dan kurang dari 80% dikatakan malnutrisi akut (wasting) Penilaian berat badan berdasarkan tinggi badan menurut standar baku NCHS yaitu menggunakan persentil sebagai berikut : persentil 75-25 dikatakan normal, persentil 10-5 dikatakan malnutrisi sedang, dan kurang dari persentil 5 dikatakan malnutrisi berat. Selain penggunaan standar baku NCHS juga dapat digunakan Kartu Menuju Sehat (KMS). Sebagaimana penelitian Anwar (2003) dengan adanya KMS perkembangan anak dapat dipantau secara praktis, sederhana, dan mudah. Pengukuran Tinggi Badan Pengukuran ini digunakan untuk menilai status perbaikan gizi, dapat dilakukan dengan sangat mudah dalam menilai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Penilaian TB berdasarkan usia menurut WHO dengan standar baku NCHS yaitu dengan menggunakan persentase dari median sebagai berikut :Lebih dari atau sama dengan 90% dikatakan normal sedangkan kurang dari 90% dikatakan malnurtisi Kronis atau abnormal. Ketebalan Lipatan Kulit dan Lingkar Lengan Dianjurkan sebagai pengukuran rutin ketebalan lipatan kulit diukur dengan caliper khusus seperti caliper lange. Tempat yang paling sering digunakan untuk mengukur ketebalan lipatan kulit adalah trisep, subscapula, supra iliaka, abdomen dan paha atas. Prosedur pengukuran yang tepat harus dilakukan rata-rata dua kali pengukuran pada satu tempat yang sama dan harus dicatat (lihat kotak pedoman). Lingkar lengan adalah pengukuran tidak langsung terhadap masa otot. Pengukurab lingkar lengan mengikuti prosedur yang sama dengan ketebalan lipatan kulit kecuali pengukuran titik tengah dengan menggunakan sehelai kertas atau meteran longam. Letakkan meteran secara vertical sepanjang bagian posterior lengan atas ke prosesus acromial dan proseksus olecranon, setengah dari panjang hasil pengukuran adalah titik tenghahnya. Persentil untuk lipatan kulit trisep dan lingkar lengan pada anak terdapat dalam apendiks D dan dapat digunakan sebagai rujukan. Tapi itu bukan merupakan standar atau norma kerena nilai antara persentil 5 dan 95 bukan merupakan rentang normal. Lingkar Kepala Ukur lingkar kepala pada anak sampai berusia 36 bulan dan pada anak-anak yang memiliki masalah pada ukuran kepalanya. Ukur lingkar kepala pada ukuran terbesarnya, biasanya sedikit diatas alis mata dan daun telinga dan mengelilingi prominen oksipital dibelakang tengkorak. Karena bentuk kepala dapat mempengaruhi lokasi lingkaran yang maksimum, maka perlu dilakukan pengukuran lebih dari satu kali pada titik diatas alis mata. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang paling akutrat.gunakan selembar kertas atau meteran logam karena meteran yang terbuat dari kain dapat meregang dan memberikan pengukuran yang salah. Supaya hasil pengukuran benar-benar akurat, gunakan alat pengukur dengan skala 0.1 cm , karena grafik persentil hanya berskala 0,5 cm. Tandai ukuran kepala pada grafik pertumbuhan yang tepat dibawah lingkar kepala. Secara umum, lingkar kepala dan lingkar dada sama pada usia 1-2 tahun. Selama masa kanakkanak, lingkar dada melebihi ukuran kepala sekitar 5-7 cm (2-3 inci).
Baku patokan Bebertapa baku antropometrik berat badan dan tinggi badan yang dikenal saat ini adalah sebagai berikut7,8,9,10 a. Baku Boston atau Harvard Baku Harvard disusun berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian Stuart (1930-1939) pada sejumlah anak Kaukasia dengan gisi relatif baik di Ameriksa Serikat. Baku Harvard dipergunakan secara luas pada kartu pertumbuhan di Amerika Latin dan Asia. b. Baku Tanner Data yang dipergunakan pada baku Tanner diperoleh dari penelitian di berbagai negara di Eropa yaitu Perancis, Belanda, Swedia, Swiss, dan Inggris. Baku Tanner ini dipakai sebagai baku pertumbuhan untuk Inggris oleh International Children.s Centre UK Study. David Morley, tahun 1975 menggunakan baku Tanner untuk menyusun kartu pertumbuhan anak pertama yang dikenal dengan Rood to Health Chart. c. Hasil penelitian di Indonesia Jumadias tahun 1964 mengumpulkan data berat dan tinggi badan anak usia 6-18 tahun dengan menggunakan persentil. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan persentil ke50 Jumadias berada di bawah 80% persentil ke-50 NCHS. Sedangkan persentil ke-90 Jumadias berada pada persentil ke-50 NCHS. Husaini YK, dkk, mengumpulkan data berat dan panjang badan bayi usia 0-12 bulan serta berat dan tinggi badan anak usia 12-60 bulan di Klinik gizi Bogor periode 1970-1984 sebagai bahan referensi antropometrik nasional. d. Baku NCHS Baku NCHS pertama tahun 1977 disusun berdasarkan data berat badan, tinggi badan pada populasi di Amerika sejak tahun 1860 yang dikumpulkan oleh National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) secara berkala. Baku NCHS ini dipakai oleh WHO. e. CDC 2000 Kurva CDC, dipublikasikan pada bulan Mei 2000, merupakan perbaikan/revisi dari Kurva yng dibuat olleh National Center for Health Statistics (NCHS) pada tahun 1977 dan terdapat tambahan berupa Kurva Indeks Masa Tubuh terhadap umur. CDC menganjurkan penggunakan kurva IMT/U untuk semua anak berusia 2 samapi 20 tahun menggantikan kurva sebelumnya (1977) berat terhadan umur
DETEKSI PERTUMBUHAN MENGGUNAKAN CDC 2000 Langkah deteksi pertumbuhan menggunakan CDC 20008,10 A. Hitung Umur Anak Cara menghitung umur anak adalah dengan cara mengurangi tanggal pemeriksaan terhadap tanggal lahir. Mengihitung umur anak yang lahir prematur Untuk bayi prematur, dalam mengukur berat, panjang dan lingkaran kepala harus digunakan umur koreksi sampai anak berusia 2 tahun. Cara menghitung umur koreksi adalah dengan cara mengurangi umur kronologis terhadap jumlah minggu prematur. Contoh: Bayi Ani lahir pada tanggal 20 Desember 2002, lahir dengan umur gestasi 33 minggu, dengan berat lahir 2000 gram. Tanggal pemeriksaan 5 Juli 2004 2004 07 05 Tanggal lahir 20 Desember 2002: 2002 12 20 Umur kronologis: 1 06 15 Prematur 7 minggu: 01 21 Umur koreksi: 1 04 24 Umur anak adalah 1 tahun, 4 bulan, 24 hari dan diplot pada 16 bulan Plot hasil pengukuran ke dalam Kurva Pertumbuhan CDC menyediakan 2 macam Kurva, yiatu Kurva Individual dan Kurva Klinik. Kurva klinik digunakan oleh petugas kesehatan yang merupakan gabungan beberapa kurva Individual:
Kurva Klinik Umur 0-36 bln: BB/U; TB/U; BB/TB; LK/U Umur 2-20 th: BB/U; TB/U; IMT/U Tabel 1. Kurva Klinik CDC 2000 Jenis kelamin dan umur Kurva Laki-laki, lahir sampai 36 bulan PB/U dan BB/U ,BB/TB dan LK/U Perempuan, lahir sampai 36 bulan PB/U dan BB/U, BB/TB dan LK/U Laki-laki, 2 - 20 tahun TB/U dan BB/U, IMT/U Perempuan, 2 20 tahun TB/U dan BB/U, IMT/U Menilai hasil pertumbuhan Dalam menilai pertumbuhan diperlukan beberapa kali pengukuran, hal ini untuk melihat arah pertumbuhan. Pada neonatus sebaiknya dilakukan pada minggu ke-1, ke-2 dan ke-4, selanjutnya dianjurkan melakukan pengukuran antropometri setiap bulan satu kali. Berikut di bawah ini beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai bahwa terdapat masalah dalam pertumbuhan. 1. Hasil pengukuran PB/U; TB/U; BB/TB; IMT/U di bawah persentil 5 2. Arah pertumbuhan menurun melewati dua batas persentil, misalnya dari persentil 75 turun menjadi persentil 25 dalam beberapa bulan pengamatan 3. Kecepatan pertumbuhan di bawah persntil 5 Pada kurva CDC hanya dapat menggunakan kriteria 1 dan 2. Tabel 2. Indikator Status Gizi Indeks antropometri Batasan Indkiator status gizi IMT/U > 95th Overweight BB/PB; BB/TB > 95th Overweight IMT/U > 85th dan < 95th Risiko Overweight IMT/U; BB/PB < 5th Underweight TB/U; PB/U < 5th Short stature LK/U < 5th ; >95th Masalah perkembangan Konsep status gizi 2.1.1 Definisi Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrient. Penelitian status gizi merupakan pengukuran yang didasarkan pada data antropometri serta biokimia dan riwayat diit.(Beck, 2000). 2.1.2 Pengukuran status gizi a. Pengukuran status gizi dengan menggunakan KMS (Kartu Menuju Sehat) 1) Definisi KMS (Kartu Menuju Sehat) untuk balita adalah alat yang sederhana dan murah, yang dapat digunakan untuk memantau kesehatan dan pertumbuhan anak. Oleh karenanya KMS harus disimpan oleh ibu balita di rumah, dan harus selalu dibawa setiap kali mengunjungi posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk bidan dan dokter.
KMS-Balita menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi ibu dan keluarga untuk memantau tumbuh kembang anak, agar tidak terjadi kesalahan atau ketidakseimbangan pemberian makan pada anak. KMS juga dapat dipakai sebagai bahan penunjang bagi petugas kesehatan untuk menentukan jenis tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi kesehatan dan gizi anak untuk mempertahankan, meningkatkan atau memulihkan kesehatan- nya. KMS berisi catatan penting tentang pertumbuhan, perkembangan anak, imunisasi, penanggulangan diare, pemberian kapsul vitamin A, kondisi kesehatan anak, pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI, pemberian makanan anak dan rujukan ke Puskesmas/ Rumah Sakit. KMS juga berisi pesan-pesan penyuluhan kesehatan dan gizi bagi orang tua balita tenta ng kesehatan anaknya (Depkes RI, 2000). 2) Manfaat KMS (Kartu Menuju Sehat) Manfaat KMS adalah : a) Sebagai media untuk mencatat dan memantau riwayat kesehatan balita secara lengkap, meliputi : pertumbuhan, perkembangan, pelaksanaan imunisasi, penanggulangan diare, pemberian kapsul vitamin A, kondisi kesehatan pemberian ASI eksklusif, dan Makanan Pendamping ASI. b) Sebagai media edukasi bagi orang tua balita tentang kesehatan anak c) Sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas untuk menentukan penyuluhan dan tindakan pelayanan kesehatan dan gizi. (Depkes RI, 2000) 3) Cara Memantau Pertumbuhan Balita Pertumbuhan balita dapat diketahui apabila setiap bulan ditimbang, hasil penimbangan dicatat di KMS, dan antara titik berat badan KMS dari hasil penimbangan bulan lalu dan hasil penimbangan bulan ini dihubungkan dengan sebuah garis. Rangkaian garis-garis pertumbuhan anak tersebut membentuk grafik pertumbuhan anak. Pada balita yang sehat, berat badannya akan selalu naik, mengikuti pita pertumbuhan sesuai dengan umurnya (Depkes RI, 2000). a) Balita naik berat badannya bila :
(1) Garis pertumbuhannya naik mengikuti salah satu pita warna, atau
(2) Garis pertumbuhannya naik dan pindah ke pita warna diatasnya.
Gambar 2.1. Indikator KMS bila balita naik berat badannya
b) Balita tidak naik berat badannya bila : Garis pertumbuhannya turun, atau Garis pertumbuhannya mendatar, atau Garis pertumbuhannya naik, tetapi pindah ke pita warna dibawahnya.
Gambar 2.2. Indikator KMS bila balita tidak naik berat badannya c) Berat badan balita dibawah garis merah artinya pertumbuhan balita mengalami gangguan pertumbuhan dan perlu perhatian khusus, sehingga harus langsung dirujuk ke Puskesmas/ Rumah Sakit.
Gambar 2.3. Indikator KMS bila berat badan balita dibawah garis merah
d) Berat badan balita tiga bulan berturut-turut tidak nail (3T), artinya balita mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga harus langsung dirujuk ke Puskesmas/ Rumah Sakit.
Gambar 2.4. Indikator KMS bila berat badan balita tidak stabil e) Balita tumbuh baik bila: Garis berat badan anak naik setiap bulannya.
Gambar 2.5. Indikator KMS bila berat badan balita naik setiap bulan f) Balita sehat, jika : Berat badannya selalu naik mengikuti salah satu pita warna atau pindah ke pita warna diatasnya.
Gambar 2.6. Indikator KMS bila pertumbuhan balita sehat b. Pengukuran status gizi dengan NCHS
Kriteria keberhasilan nutrisi ditentukan oleh status gizi : 1) Gizi baik, jika BB menurut umur > 80% standart WHO NHCS. 2) Gizi kurang, jika berat badan menurut umur 61% sampai 80% standart WHO NHCS. 3) Gizi buruk, jika berat badan menurut umur 60% standart WHO NHCS. ( Supariasa, 2002) Rumus Antropometri pada anak : ( Soetjiningsih : 1998). 1) Berat badan Umur 1 6 tahun = ( tahun ) x 2 + 8 2) Tinggi badan Umur 1 tahun = 1,5 x tinggi badan lahir Umur 2 12 tahun = umur ( tahun ) x 6 + 77
2.1.3 Manfaat nutrisi a. Nutrisi untuk pertumbuhan Dengan makanan bergizi, tubuh manusia tumbuh dan dipelihara. Semua organ tubuh dapat berfungsi dengan baik. Bagian tubuh yang rusak diganti. Kulit dan rambut terus berganti, sel sel tubuh terus bertumbuh. Sel-sel tubuh memasak dan mengolah zat makanan yang masak agar zat makanan dapat dipakai untuk pekerjaan tubuh. b. Makanan sebagai suku cadang Makanan juga bermanfaat untuk memulihkan badan yang baru sembuh dari sakit. Selama sakit banyak bagian tubuh yang rusak. Mungkin juga
sebagian selnya mati. Selama orang juga kurang makan sehingga tubuh kekurangan berbagai zat makanan yang dibutuhkannya. Mungkin juga banyak kehilangan darah sehingga makin lama sakit berlangsung, makin banyak zat makanan yang harus ditambahkan. Untuk itu, setelah sakit kita perlu banyak makan makanan bergizi. Begitu juga untuk yang menjalani operasi atau yang baru melahirkan. c. Makanan sebagai bensin tubuh Makanan juga dibutuhkan untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, menyapu, juga berkebun. Dalam keadaan tidurpun tubuh tetap membutuhkan tenaga untuk bernafas, degup jantung, serta tenaga memasak zat makanan dan memakainya. Namun, makanan perlu diatur agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jumlahnya harus memadai, dan
BAB II ISI DEFINISI MTBS Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) atau Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) adalah suatu pendekatan yang terintegrasi/terpadu dalam tatalaksana balita sakit dengan fokus kepada kesehatan anak usia 059 bulan (balita) secara menyeluruh. MTBS bukan merupakan suatu program kesehatan tetapi suatu pendekatan/cara menatalaksana balita sakit. Konsep pendekatan MTBS yang pertama kali diperkenalkan oleh WHO merupakan suatu bentuk strategi upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan bayi dan anak balita di negara-negara berkembang. Pendekatan MTBS di Indonesia pada awalnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di unit rawat jalan kesehatan dasar (Puskesmas dan jaringannya termasuk Pustu, Polindes, Poskesdes, dll). Upaya ini tergolong lengkap untuk mengantisipasi penyakit-penyakit yang sering menyebabkan kematian bayi dan balita di Indonesia. Dikatakan lengkap karena meliputi upaya preventif (pencegahan penyakit), perbaikan gizi, upaya promotif (berupa konseling) dan upaya kuratif (pengobatan) terhadap penyakit-penyakit dan masalah yang sering terjadi pada balita. Strategi MTBS memliliki 3 komponen khas yang menguntungkan, yaitu: 1. Komponen I: Meningkatkan ketrampilan petugas kesehatan dalam tatalaksana kasus balita sakit (selain dokter, petugas kesehatan non-dokter dapat pula memeriksa dan menangani pasien asalkan sudah dilatih). 2. Komponen II: Memperbaiki sistem kesehatan (utamanya di tingkat kabupaten/kota). 3. Komponen III: Memperbaiki praktek keluarga dan masyarakat dalam perawatan di rumah dan upaya pencarian pertolongan kasus balita sakit (meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat), yang dikenal sebagai 'MTBS berbasis Masyarakat.' SEJARAH PENERAPAN MTBS DI INDONESIA Strategi MTBS mulai diperkenalkan di Indonesia oleh WHO pada tahun 1996. Pada tahun 1997 Depkes RI bekerjasama dengan WHO dan Ikatan Dokter
mutunya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari (Nadesul, 2001).
Anak Indonesia (IDAI) melakukan adaptasi modul MTBS WHO. Modul tersebut digunakan dalam pelatihan pada bulan November 1997 dengan pelatih dari SEARO. Sejak itu penerapan MTBS di Indonesia berkembang secara bertahap dan up-date modul MTBS dilakukan secara berkala sesuai perkembangan program kesehatan di Depkes dan ilmu kesehatan anak melalui IDAI. Hingga akhir tahun 2009, penerapan MTBS telah mencakup 33 provinsi, namun belum seluruh Puskesmas mampu menerapkan karena berbagai sebab: belum adanya tenaga kesehatan di Puskesmasnya yang sudah terlatih MTBS, sudah ada tenaga kesehatan terlatih tetapi sarana dan prasarana belum siap, belum adanya komitmen dari Pimpinan Puskesmas, dll. Menurut data laporan rutin yang dihimpun dari Dinas Kesehatan provinsi seluruh Indonesia melalui Pertemuan Nasional Program Kesehatan Anak tahun 2010, jumlah Puskesmas yang melaksanakan MTBS hingga akhir tahun 2009 sebesar 51,55%. Puskesmas dikatakan sudah menerapkan MTBS bila memenuhi kriteria sudah melaksanakan (melakukan pendekatan memakai MTBS) pada minimal 60% dari jumlah kunjungan balita sakit di Puskesmas tersebut. LATAR BELAKANG PERLUNYA PENERAPAN MTBS DI INDONESIA Menurut data hasil Survei yang dilakukan sejak tahun 1990-an hingga saat ini (SKRT 1991, 1995, SDKI 2003 dan 2007), penyakit/masalah kesehatan yang banyak menyerang bayi dan anak balita masih berkisar pada penyakit/masalah yang kurang-lebih sama yaitu gangguan perinatal, penyakit-penyakit infeksi dan masalah kekurangan gizi. Penyebab kematian neonatal (bayi berusia 0-28 hari) menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Tabel proporsi penyebab kematian neonatal di Indonesia tahun 2007 Sumber: Badan Litbangkes, Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2007 Sedangkan penyebab kematian bayi dan anak balita menurut Riskesdas 2007, pada kelompok bayi (29 hari - 11 bulan) dan kelompok anak balita (12 bulan - 59 bulan) ada dua penyebab kematian tersering yaitu diare dan pneumonia. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel proporsi penyebab kematian bayi dan anak balita di Indonesia tahun 2007 Sumber: Badan Litbangkes, Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2007 Penyakit-penyakit penyebab kematian tersebut pada umumnya dapat ditangani di tingkat Rumah Sakit, namun masih sulit untuk tingkat Puskesmas. Hal ini disebabkan antara lain karena masih minimnya sarana/peralatan diagnostik dan obat-obatan di tingkat Puskesmas terutama Puskesmas di daerah terpencil yang tanpa fasilitas perawatan, selain itu seringkali Puskesmas tidak memiliki tenaga dokter yang siap di tempat setiap saat. Padahal, Puskesmas merupakan ujung tombak fasilitas kesehatan yang paling diandalkan di tingkat kecamatan. Kenyataan lain di banyak provinsi, keberadaan Rumah Sakit pada umumnya hanya ada sampai tingkat kabupaten/kota sedangkan masyarakat Indonesia banyak tinggal di pedesaan. Berdasarkan kenyataan (permasalahan) di atas, pendekatan MTBS dapat menjadi solusi yang jitu apabila diterapkan dengan benar (ketiga komponen diterapkan dengan maksimal). Pada sebagian besar balita sakit yang dibawa
berobat ke Puskesmas, keluhan tunggal jarang terjadi. Menurut data WHO, tiga dari empat balita sakit seringkali memiliki beberapa keluhan lain yang menyertai dan sedikitnya menderita 1 dari 5 penyakit tersering pada balita yang menjadi fokus MTBS. Hal ini dapat diakomodir oleh MTBS karena dalam setiap pemeriksaan MTBS, semua aspek/kondisi yang sering menyebabkan keluhan anak akan ditanyakan dan diperiksa. Menurut laporan Bank Dunia (1993), MTBS merupakan jenis intervensi yang paling cost effective yang memberikan dampak terbesar pada beban penyakit secara global. Bila Puskesmas menerapkan MTBS berarti turut membantu dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terpadu. Oleh karena itu, bila anda membawa anak balita berobat ke Puskesmas, tanyakanlah apakah tersedia pelayanan MTBS di Puskesmas itu? bila ada, mintalah dilayani memakai pendekatan MTBS. MTBS SANGAT COCOK DITERAPKAN DI PUSKESMAS Pada sebagian besar balita sakit yang dibawa berobat ke Puskesmas, keluhan tunggal kemungkinan jarang terjadi, menurut data WHO, tiga dari empat balita sakit seringkali memiliki banyak keluhan lain yang menyertai dan sedikitnya menderita 1 dari 5 penyakit tersering pada balita yang menjadi fokus MTBS. Pendekatan MTBS dapat mengakomodir hal ini karena dalam setiap pemeriksaan MTBS, semua aspek/kondisi yang sering menyebabkan keluhan anak akan ditanyakan dan diperiksa. Menurut laporan Bank Dunia (1993), MTBS merupakan jenis intervensi yang cost effective yang memberikan dampak terbesar pada beban penyakit secara global. Bila Puskesmas menerapkan MTBS berarti turut membantu dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang terpadu. Oleh karena itu, bila anda membawa anak balita berobat ke Puskesmas, tanyakanlah apakah tersedia pelayanan MTBS disana. MTBS SEBAGAI SUATU SISTEM MTBS dalam kegiatan di lapangan khususnya di Puskesmas merupakan suatu system yang mem permudah pelayanan serta meningkatkan mutu pelayanan. Tabel di bawah ini dapat dilihat penjelasan MTBS merupakan suatu sistem. 1. Input Balita sakit datang bersama kelaurga diberikan status pengobatan dan formulir MTBS Tempat dan petugas : Loket, petugas kartu 2. Proses Balita sakit dibawakan kartu status dan formulir MTBS. Memeriksa berat dan suhu badan. Apabila batuk selalu mengitung napas, melihat tarikan dinding dada dan mendengar stridor. Apabila diare selalu memeriksa kesadaran balita, mata cekung, memberi minum anak untuk melihat apakah tidak bias minum atau malas dan mencubit kulit perut untuk memeriksa turgor. Selalu memerisa status gizi, status imunisasi dan pemberian kapsul Vitamin A Tempat dan petugas : Ruangan MTBS, case manager 3.Output Klasifikasi yang dikonversikan menjadi diagnosa, tindakan berupa pemberian terapi dan konseling berupa nasehat pemberian makan, nasehat kunjungan ulang, nasehat kapan harus kembali segera. Konseling lain misalnya kesehatn lingkungan, imunisasi, Konseling cara perawatan di rumah. Rujukan
diperlukan jika keadaan balita sakit membutuhkan rujukan Tempat dan petugas : Ruangan MTBS, case manager. PENATALAKSANA BALITA SAKIT DENGAN PENDEKATAN MTBS Berikut ini gambaran singkat penanganan balita sakit memakai pendekatan MTBS. Seorang balita sakit dapat ditangani dengan pendekatan MTBS oleh Petugas kesehatan yang telah dilatih. Petugas memakai tool yang disebut Algoritma MTBS untuk melakukan penilaian/pemeriksaan dengan cara: menanyakan kepada orang tua/wali, apa saja keluhan-keluhan/masalah anak kemudian memeriksa dengan cara 'lihat dan dengar' atau 'lihat dan raba'. Setelah itu petugas akan mengklasifikasikan semua gejala berdasarkan hasil tanya-jawab dan pemeriksaan. Berdasarkan hasil klasifikasi, petugas akan menentukan jenis tindakan/pengobatan, misalnya anak dengan klasifikasi Pneumonia Berat atau Penyakit Sangat Berat akan dirujuk ke dokter Puskesmas, anak yang imunisasinya belum lengkap akan dilengkapi, anak dengan masalah gizi akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi, dst. Gambaran tentang begitu sistematis dan terintegrasinya pendekatan MTBS dapat dilihat pada item di bawah ini tentang hal-hal yang diperiksa pada pemeriksaan dengan pendekatan MTBS. Ketika anak sakit datang ke ruang pemeriksaan, petugas kesehatan akan menanyakan kepada orang tua/wali secara berurutan, dimulai dengan memeriksa tanda-tanda bahaya umum seperti: Apakah anak bisa minum/menyusu? Apakah anak selalu memuntahkan semuanya? Apakah anak menderita kejang? Kemudian petugas akan melihat/memeriksa apakah anak tampak letargis/tidak sadar? Setelah itu petugas kesehatan akan menanyakan keluhan utama lain: Apakah anak menderita batuk atau sukar bernafas? Apakah anak menderita diare? Apakah anak demam? Apakah anak mempunyai masalah telinga? Memeriksa status gizi Memeriksa anemia Memeriksa status imunisasi Memeriksa pemberian vitamin A Menilai masalah/keluhan-keluhan lain Berdasarkan hasil penilaian hal-hal tersebut di atas, petugas akan mengklasifikasi keluhan/penyakit anak, setelah itu melakukan langkahlangkah tindakan/pengobatan yang telah ditetapkan dalam penilaian/klasifikasi. Tindakan yang dilakukan antara lain: Mengajari ibu cara pemberian obat oral di rumah Mengajari ibu cara mengobati infeksi lokal di rumah Menjelaskan kepada ibu tentang aturan-aturan perawatan anak sakit di rumah, misal aturan penanganan diare di rumah Memberikan konseling bagi ibu, misal: anjuran pemberian makanan selama anak sakit maupun dalam keadaan sehat Menasihati ibu kapan harus kembali kepada petugas kesehatan dan lain-lain Selain itu di dalam MTBS terdapat penilaian dan klasifikasi bagi Bayi Muda berusia kurang dari 2 bulan, yang disebut juga Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM). Penilaian dan klasifikasi bayi muda di dalam MTBM terdiri dari: Menilai dan mengklasifikasikan untuk kemungkinan penyakit sangat berat atau infeksi bakteri Menilai dan mengklasifikasikan diare
Memeriksa dan mengklasifikasikan ikterus Memeriksa dan mengklasifikasikan kemungkinan berat badan rendah dan atau masalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Yang menarik disini, diuraikan secara terperinci cara mengajari ibu tentang cara meningkatkan produksi ASI, cara menyusui yang baik, mengatasi masalah pemberian ASI secara sistematis dan terperinci, cara merawat tali pusat, menjelaskan kepada ibu tentang jadwal imunisasi pada bayi kurang dari 2 bulan, menasihati ibu cara memberikan cairan tambahan pada waktu bayinya sakit, kapan harus kunjungna ulang, dll. Memeriksa status penyuntikan vitamin K1 dan imunisasi. Memeriksa masalah dan keluhan lain. CONTOH PENILAIAN ANAK SAKIT Penilaian pertama yang dilakukan terhadap balita sakit adalah memeriksa tanda bahaya umum, bila ditemukan satu atau lebih tanda-tanda bahaya umum maka diklasifikasikan sebagai 'penyakit sangat berat'. Kemudian dilanjutkan penilaian keluhan utama yang dimulai dengan pertanyaan 'apakah anak menderita baruk atau sukar bernafas?' Bila ya, maka dihitung frekuensi nafas anak permenit, memeriksa tanda-tanda pneumonia berupa adanya tarikan dinding dada kedalam dan stridor. Penilaian: bila ada tanda bahaya umum diikuti adanya tarikan dinding dada kedalam dan adanya stridor maka anak diklasifikasikan sebagai 'pneumonia berat atau penyakit sangat berat'. Bila hanya ada nafas cepat maka diklasifikasikan sebagai 'pneumonia', tetapi bila tidak ada tanda-tanda pneumonia atau penyakit sangat berat maka diklasifikasikan sebagai 'batuk: bukan pneumonia'. Selanjutnya menilai diare, demam, dst.
Anda mungkin juga menyukai
- Sop Menimbang BayiDokumen7 halamanSop Menimbang BayiRicky L0% (1)
- Pengkajian Status NutrisiDokumen8 halamanPengkajian Status NutrisiMuhammad MarzainBelum ada peringkat
- Denver IiDokumen62 halamanDenver IiYuanita Meidiandini SetiawanBelum ada peringkat
- Konsep Tumbuh KembangDokumen24 halamanKonsep Tumbuh KembangNyoman DilaBelum ada peringkat
- AntropometriDokumen5 halamanAntropometriyufidaBelum ada peringkat
- Penilaian Pertumbuhan AnakDokumen4 halamanPenilaian Pertumbuhan Anakleni100% (1)
- Deteksi Dini Tumbuh Kembang AnakDokumen19 halamanDeteksi Dini Tumbuh Kembang Anakirma hardiyantiBelum ada peringkat
- ANTROPOMETRIDokumen19 halamanANTROPOMETRIFirda RidhayantiBelum ada peringkat
- An Tropo MetriDokumen21 halamanAn Tropo MetriAstariniBelum ada peringkat
- Pengukuran AntropometriDokumen12 halamanPengukuran AntropometrikrismaandianiBelum ada peringkat
- Pemantauan TumbangDokumen12 halamanPemantauan TumbangYurika RahmaBelum ada peringkat
- PSG B3 Topik 1Dokumen11 halamanPSG B3 Topik 1Rimuru TempestBelum ada peringkat
- Antropometri Gizi Merupakan Penilaian Status Gizi Dengan Pengukuran Dimensi Tubuh DanDokumen4 halamanAntropometri Gizi Merupakan Penilaian Status Gizi Dengan Pengukuran Dimensi Tubuh DanyesiBelum ada peringkat
- DDTKDokumen57 halamanDDTKDevina Rivanti NBelum ada peringkat
- Dwi Yuliani 1811216023 Tugas Mandiri PratikumDokumen93 halamanDwi Yuliani 1811216023 Tugas Mandiri PratikumAngah WieBelum ada peringkat
- Learning Guide Antropometri BayiDokumen21 halamanLearning Guide Antropometri Bayitiararudianti20Belum ada peringkat
- Penilaian Pertumbuhan Dan PerkembanganDokumen12 halamanPenilaian Pertumbuhan Dan PerkembanganNovia SinaBelum ada peringkat
- Panduan Praktikum Tumbuh KembangDokumen12 halamanPanduan Praktikum Tumbuh KembangRezza PutriBelum ada peringkat
- Pemantauan Tumbuh Kembang Anak Asuhan KeperawatanDokumen5 halamanPemantauan Tumbuh Kembang Anak Asuhan KeperawatantikaBelum ada peringkat
- Tugas Resume Ilmu Gizi Dan Kesehata1Dokumen4 halamanTugas Resume Ilmu Gizi Dan Kesehata1Nastiti RahayuBelum ada peringkat
- Pengkajian Status NutrisiDokumen7 halamanPengkajian Status NutrisiAry FahrizanBelum ada peringkat
- Pemantauan Tumbuh Kembang AnakDokumen11 halamanPemantauan Tumbuh Kembang AnakGalih KumaraBelum ada peringkat
- JudulDokumen13 halamanJudulpuskesmas parongpongBelum ada peringkat
- Sesi 3. Indikator Pertumbuhan BalitaDokumen26 halamanSesi 3. Indikator Pertumbuhan BalitaMarsellaBelum ada peringkat
- CD Pemeriksaan Antropometri Dan KPSP BaruDokumen25 halamanCD Pemeriksaan Antropometri Dan KPSP BaruRaudhatul JannahBelum ada peringkat
- Penilaian Status GiziDokumen59 halamanPenilaian Status GiziSandara ParkBelum ada peringkat
- Sop AntropometriDokumen5 halamanSop AntropometriFidia100% (1)
- Panduan Pelayanan AnakDokumen10 halamanPanduan Pelayanan AnakMohAriefBudimanBelum ada peringkat
- Kuliah Penilaian Tumbuh Kembang Anak - ZiaDokumen48 halamanKuliah Penilaian Tumbuh Kembang Anak - ZiaWiki AbshorBelum ada peringkat
- Kel PemfisDokumen20 halamanKel PemfisUmi Hani FuadiahBelum ada peringkat
- Penilaian Pertumbuhan Fisik AnakDokumen9 halamanPenilaian Pertumbuhan Fisik AnakEka Santi Peratiwi60% (5)
- 2018 Nov - Antropometri Pengukuran Status Gizi Balita BenerDokumen7 halaman2018 Nov - Antropometri Pengukuran Status Gizi Balita Benercintak4Belum ada peringkat
- PSG Bayi BaruDokumen20 halamanPSG Bayi BaruHibatullah ImanunaBelum ada peringkat
- Pertemuan Ke-4 Antropometri GiziDokumen41 halamanPertemuan Ke-4 Antropometri GiziSyahrir UtomoBelum ada peringkat
- Laporan Pratikum PSG PosyanduDokumen8 halamanLaporan Pratikum PSG PosyanduFatimah RahmiBelum ada peringkat
- Pengukuran Data AntropometriDokumen113 halamanPengukuran Data AntropometriRizky Ayu R100% (1)
- Evaluasi Parameter AntropometriDokumen3 halamanEvaluasi Parameter AntropometriAisyah Yuri OktavaniaBelum ada peringkat
- Skrining Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada AnakDokumen15 halamanSkrining Pertumbuhan Dan Perkembangan Pada AnakBob RobertBelum ada peringkat
- Dokumen Tanpa JudulDokumen12 halamanDokumen Tanpa Judul05. AUFARAZITA XII MIPA 1Belum ada peringkat
- Pemeriksaan Fisik Pada AnakDokumen34 halamanPemeriksaan Fisik Pada Anakayu anjeliaBelum ada peringkat
- Pemeriksaan Fisik Pada AnakDokumen34 halamanPemeriksaan Fisik Pada Anakayu anjeliaBelum ada peringkat
- Cara Pengukuran Antropometri Pada Bayi Yang Tepat Dan AmanDokumen4 halamanCara Pengukuran Antropometri Pada Bayi Yang Tepat Dan AmanYus MayaBelum ada peringkat
- Berat Badan Berdasarkan Umur (BB/U)Dokumen3 halamanBerat Badan Berdasarkan Umur (BB/U)Mitra NdrahaBelum ada peringkat
- Modul AntropometriDokumen18 halamanModul AntropometrifFta LinggasatiBelum ada peringkat
- Antropometri BBLDokumen7 halamanAntropometri BBLWindy Lestari SiampaBelum ada peringkat
- Penilaian Status Gizi AnakDokumen22 halamanPenilaian Status Gizi AnakDea PhillyaBelum ada peringkat
- Checklist AntropometriDokumen14 halamanChecklist AntropometriHidayah HasanahBelum ada peringkat
- TPK1 PSG3Dokumen7 halamanTPK1 PSG3Cindy yolanda TambunanBelum ada peringkat
- Makalah Tumbuh KembangDokumen17 halamanMakalah Tumbuh KembangJiffy Jia AtuyBelum ada peringkat
- TTM 2 Antopometri GiziDokumen58 halamanTTM 2 Antopometri GiziGhaniiyaBelum ada peringkat
- BAB I Balita Fix PrintDokumen15 halamanBAB I Balita Fix PrintEster Margaretha WuysangBelum ada peringkat
- Jenis Parameter Antropometri Pada AnakDokumen4 halamanJenis Parameter Antropometri Pada AnakRijalFikriBelum ada peringkat
- Kartu Menuju Sehat (KMS)Dokumen13 halamanKartu Menuju Sehat (KMS)Lucy PurwaBelum ada peringkat
- 4 Interpretasi AntropometriDokumen29 halaman4 Interpretasi Antropometriichwanhadi100% (2)
- Laporan Praktikum Antropometri AnakDokumen8 halamanLaporan Praktikum Antropometri AnakDx Aniez El KaromahBelum ada peringkat
- Merawat penyakit kencing manis tanpa ubatDari EverandMerawat penyakit kencing manis tanpa ubatPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanDari EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Program Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaDari EverandProgram Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9)
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Dari EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)
- Buku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Dari EverandBuku Masakan untuk Penyembuhan Skoliosis Anda: Jadikan tulang belakang lebih sehat dengan mengatur apa yang anda makan!Penilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (4)