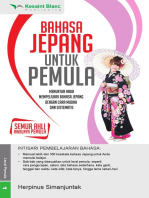Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Diunggah oleh
Abi LiminoHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Diunggah oleh
Abi LiminoHak Cipta:
Format Tersedia
1
PEMBAHASAN
RAGAM BAHASA INDONESIA TULIS ILMIAH
A. Ragam Bahasa Ilmiah
Dalam kehidupan sosial dan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik
secara lisan maupun tulisan, digunakan bebagai bahasa daerah termasuk
diaelknya bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing. Bahkan, dalam situasi
tertentu, seperti dalam keluarga perkawinan campuran digunakan pula
bahasa yang bersiat campuran, yaitu campuran antara bahasa Indonesia
dan salah satu atau kedua bahasa ibu pasangan perkaina campuran itu
(Lumintang, 1982:73). Dalam situasi kebahasaan seperti itu, timbul
berbagai ragam atau variasi bahasa sesuai dengan keperluannya, baik
secara lisan maupun tulisan. Timbulnya ragam bahasa tersebut disebabkan
oleh latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan bahasa para
pemakainya itu.
Yang dimaksud ragam atau variasi bahasa adalah bentuk atau
wujud bahasa yang ditandai oleh ciri-ciri linguistik tertentu, seperti
fonologi, morfologi, dan sintaksis. Di samping ditandai oleh ciri-ciri
linguistik,
timbulnya
ragam
bahasa
juga
ditandai
oleh
ciri-ciri
nonlinguistik, misalnya, lokasi atau tempat penggunaannya, lingkungan
sosial pemakaiannya, dan lingkungan keprofesian pemakai bahasa yang
bersangkutan.
1. Pengartian Ragam Bahasa Tulis
Ragam bahasa tulis adalah variasi bahasa yang digunakan melalui
media tulisan, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga
diperlukan perlengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual
(KBBI, 1989:715). Dengan demikian, bahasatulis tidak lebih dari pada
bentuk sekunder atau representasi grafis bahasa (Langacker, 1973: 59;
Winkins, 196:62).
Bahasa tulis tidak identik pada keseluhannya dengan bahasa lisan
teruma pada empat aspek bunyi. Bahasa lisan sangat kompleks, yang tidak
mungkin terlambangkan sepenuhnya secara akurat. Beberapa ahli bahasa
menyebut hal ini sebagai sisi lemah bahasa ragam tulisan. Di sisi lain,
bahasa ragam tulis memiliki kelebihan. Bahasa tulis relatif lebih cermat,
tata bahasanya lebih terkontrol (Nafiah, 1981: 4) daripada bahasa lisan.
Kemudahan pengontrolan itu karena dalam proses ekspresi dan
prroduksinya bahasa tulis mengalami penyuntingan dan tidak digunakan
secara spontan. Oleh karena itu, bahasa tulis relatif lebih stabil dan dapat
menggambarkan kemampuan optimal pemakain bahasa seseorang.
2. Jenis Ragam Bahasa
Dittmar (1978) dan Halim (1979) mengemukakan empat buah
ragam bahasa yang menyangkut ragam tulisan dan lisan. Salah satu di
antara keempat ragam bahasa itu adalah ragam fungsional. Yang dimaksud
dengan ragam fungsional atau ragam profesional adalah ragam bahasa
yang dihubungkan dengan tingkat profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau
kegiatan tertentu lainnya. Dalam penggunaanya, bahasa ragam fungsional
dihubungkan dengan tingkat kersmian, sehungga dalam kenyataannya
antara lain menjelma sebagai bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa
yang digunakan dalam bidang keilmuan (ilmu sosial, ilmu alam, ilmu
pendidikan, ilmu budaya, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu hukum,
ilmu olahraga, ilmu teknik, dan lain-lain).
Seperti halnya ragam-ragam bahasa yang lain, ragam bahasa
fungsional dapat dikelompokkan menjadi ragam bahasa lisan dan ragam
bahasa tulisan. Pada dasarnya kedua ragam itu terdiri atas ragam baku dan
ragam tidak baku. Ragam baku menurut Halim (1981: 4) adalah ragam
yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat
pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma
bahasa dan penggunaannya.
Menurut Badadu (1992: 42), bahasa ragam baku atau standar ialah
salah satu di antara beberapa dialek suatu bahasa yang dipilih dan
ditetapkan sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam semua keperluan
resmi. Sehubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia, ragam baku
meupakan hasil pembakuan resmi yang norma dan kaidahnya dinyatakan
secara tertulis
dalam bentuk pedoman,
misalnya:
(1) Pedoman
Pembentukan Istilah, (2) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang
Disempurnakan, (3) Kamu Besar Bahasa Indonesia, (4) Tata Bahasa Baku
Bahasa Indonesia, dan (5) Glosarium (Matematika, Fisika, Kimia, Biologi,
dan lain-lain).
Kaitannya dengan ragam bahasa lisan dan tulisan bahasa Indonesia,
tidak jaran diduga orang bahwa keduanya memiliki kaidah yang
sepenuhnya sama, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian. Ragam
bahasa lisan terikat oleh ruang dan waktu, sehingga dalam penggunaannya
dengan pertimbangan ciri-ciri nonlinguistiknya, kelengkapan ciri-ciri
linguistiknya tidak dituntut sepenuhnya. Lain halnya dengan ragam bahasa
tulis, ragam bahasa tulis baku tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga
dalam penggunaannya
kelengkapan
ciri-ciri linguistiknya
dituntut
sepenuhnya.
Ciri-ciri linguistik yang dituntut itu daam bidang fonologi ragam
lisan, misalnya, adanya variasi penggunaan fonem seperti pada kata-kata
berikut:
fihak
>
pihak
ujud
>
wujud
faham
>
paham
fikir
>
piker
Dalam ragam bahasa tulis, tampak dalam ejaannya, yaitu
penggunaan huruf yang tetap tetapi mencerminkan variasi fonem,
sehingga ejaann yang baku adalah pihak, wujud, paham, dan pikir.
3. Gaya Bahasa Keilmuan
Johannes (197: 2-3) menyatakan gaya bahasa keilmuan, yang pada
dasarnya sama pengertiannya dengan ragam bahasa ungsional baku. Dia
berpandangan bahwa yang dimaksud dengan ragam tulis fungsional baku
adalah ragam tulis yang ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut: (1)
bahasanya adalah bahasa resmi, bukan bahasa pergaulan (colloquial), (2)
sifatnya formal dan objektif, (3) nadanya tidak emosional, (4) keindahan
bahasanya tetap diperhatikan, (5) kemubaziran dihindari, dan (6) isinya
lengkap, bayan, ringkas, meyakinkan, dan tepat.
Anton Moeliono (1993: 3) berpandangan bahwa ciri-ciri bahasa
keilmuan yang mennjol adala kecendekiannya. Pencendekiaan bahasa itu
dapat diartikan sebagai proses penyesuaiannya menjadi bahasa yang
mampu membuat pernyataan yang tepat, seksama, dan abstrak. Bentuk
kalimat mencerminkan ketelitian penalaran yang objektif. Ada hubungan
logis antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Hubungan antar
kalimat yang logis meliputi relasi sebab dan akibat, lantaran dan tujuan,
hubungan kesejajaran, kemungkinann, kementakan (probabilitas), dan
darurat (necessity) yang dieksplisitkan lewat bangun kalimat yang khusus.
Ahmad Slamet Harjasujana (1993: 3) berpendapat, penggunaan
bahasa dalam ilmu pengetahuan itu khas dan khusus. Ciri dan
karakteristinya yang utama adalah lugas, lurus, monosemantik,, dan ajeg.
Bahasa ilmu pengetahuan itu juga harus hemat dan cermat karena
menghendaki respons yang pasti dari pembacanya. Kaidah-kaidah
sintaksis dipahami. Kehematan penggunaan kata, kecermatan dan
kejelasan sintaksis yang berpadu dengan penghapusan unsur-unsur yang
bersifat pribadi dapat mengahsilkan ragam bahasa ilmu pengetahuan yang
umum. Kelugasan keobjektifan, dan keajegan bahasa ilmu pengetahuan
itulah yang membedakannya dengan bahasa sastra yang subjektif, halus,
dan lentur, sehingga interpretasi pembaca yang satu kerap kali sangat
berbeda dengan interpretasi dan apresiasi pembaca lainnya.
4. Penggunaan Ragam Bahasa Ilmiah
Penggunaan bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai
sifat pemakaian
yang kahs, yang spesifik, sehingga dapat dikatakan
bahwa bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan mempunyai ragam bahasa
tersendiri yang berbeda dengan ragam-ragam bahasa yang lain. Sifat-sifat
tersebut ada yang umum sebagai bahasa ilmiah, da nada yang khusus
berhubungan dengan pemakaian kosakata, istilah, konsep keilmuan, serta
bentuk-bentuk gramatika.
Sifat bahasa ragam ilmiah yang bersifat umum berhubungan
dengan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyamapaikan informasi ilmiah
pada peristiwa komunikasi yang terjadi antara penulis dan pembaca.
Informasi yang disampaikan tentu dengan bahasa yang jelas, benar,
effektif, sesuai,bebas dari sifat samar-samar, dan tidak bersifat taksa
(ambigu). Hal ini penting sekali diperhatikan oleh penulis agar informasi
ilmiah yang disampaikan dapat dipahami secara jelas, objektif, dan logis,
sehingga daapt tercapai kesamaan pemahaman, persepsi, dan pandangan
terhadap konsep-konsep keilmuan yang dimaksud oleh penulis dan
pembaca.
Informasi dan konsep-konsep ilmiah yang disampaikan dalam
bentuk karya tulis ilmiah, misalnya, usulan penelitian, laporan penelitian
(studi), makalah, skripsi, tesis, dan disertai bersifat formal. Oleh karena
itu, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah adalah ragam
bahasa baku (standar).
Bahasa
dalam
percakapan
sehari-hari
(colloquial)
serta
percakaapan lisan tidak tepat apabila digunakan untuk menyampaikan
inormasidan konsep-knsep yang berkadar ilmiah. Demikian pula bahasa
ragam sastra (puisi, prosa, dan drama) disusun sedemikian ruap, sehingga
dapat menimbulkan berbagai efek emosional, imajinatif, estetik, dan
artistic, yang dapat membangkitkan rasa haru, baik bagi penulis maupun
pembaca. Bahasa yang bersiat ilmiah tidak mempertimbangkan efek-efek
perasaan yang timbul, seperti yang dipertimbangkan dalam bahasa ragam
sastran(Oka, 1971: 14).
Sifat ragam bahasa ilmiah yang khusu/spesifik tampak pada
pemilihan dan pemakaian kata serta bentuk-bentuk gramatika terutama
dalam tataran sintaksis. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa ilmiah
bersifatdenotatif. Artinya, setiap kata hanya mempunyai satu makna yang
paling sesuai dengan konsep keilmuan tersebut atau fakta yang
disampaikan. Demikian pula kalimat-kalimat yang digunakan dalam
bahasa ragam ilmiah bersifat logis. Hubungan antara bagian-bagian
kalimat dalam kalimat tunggal atau hubungan antara klausa-klausa dalam
kalimat majemuk (kompleks) mengikuti pola-pola bentuk hubungan logis.
B. Bahasa Indonesia dalam Komunikasi Ilmiah
Para ilmuan, khususnya yang berasosiasi dengan lingkungan
kampus (perguruan tinggi) atau pusat-pusat studi dan penelitian
merupakan masyarakat wacana ilmiah. Salah satu yang membedakan
meraka dari masyarakat yang lain ialah penguasaan bahasa ragam ilmiah.
Dapat dinyatakan bahwa bahasa komunikasi ilmiah adalah dialek sosial
mereka. Tanpa penguasaan bahasa komunikasi ilmiah, sang ilmuan tampak
jinak dan kurang vocal (Alwasilah, 1993: 41).
Hakikat bahasa komunikasi ilmiah sekurang-kurangnya didukung
oleh tiga variabel: (1) kemampuan berfikir kritis (critical thinking), (2)
penguasaan bahasa, dan (3) pengetahuan yang luas. Penguasaan
pengetahuan umum tampaknya lebih mudah dikejar. Tinggal ia membaca
buku, jurnal majalah, surat kabar, dan akses melalui internet.
Bahasa Indonesia, sebagai bidang ilmu yang diajarkan sejak
pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, berfungsi sebagai sarana
kmunikasi ilmiah, sarana penalaran, dan berpikir kritis para peserta didik.
Oleh karena itu, dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa
Indonesia
saling
bersinergi
dengan
perkembangan
budaya,
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, yang secara otomatis akan memperoleh
dampak pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan dan teknologi
informasi maju.
Di samping berfungsi sebagai alat komunikasi ilmiah, bahasa
Indonesia juga bersiat terbuka (transparan). Adanya sifat keterbukaan
bahasa Indonesia memungkinkan dirinya menjadi bahsa yang modern,
bhasa yang fleksibel, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan
jumlah kosakata, istilah, dan konsep-konsep keilmuan baru dalam
khasanah bahasa Indonesia.
1. Konsep, istilah, dan kosakata
Konsep-konsep, istilah, dan kosakata bahasa Indonesia tampak dalam
berbagai bidang ilmu sebagai berikut:
(1) Teknologi komunikasi
komputer
media massa elektronik
media massa cetak
jaringan computer
internet
antena parabola
sistem jaringan
LAN (local arena network)
(2) Kedokteran/kesehatan
Ultrasonografi (usg)
rawat inap (opname)
psikiater
psikolog
aborsi
tumor
kanker
anemia
(3) Matematika/statistiak
Variabel
peubah
trapesium
bilangan ganjil
kelipatan tiga
desimal
tabel
standar deviasi
kuadrat
sigma
sampel
populasi
hipotesis
simpangan baku
perkalian
(4) Ekonomi dan keuanagan
Akuntansi
bursa efek
upah minimum
moneter
ekonomi mikro
konglomerat
(5) Pendidikan dan pembelajaran
7
Kejar (kelompok belajar)
metodik
caturwulan
semester
model pembelajaran
sekolah unggul
kuliah
SKS (satuan kredit siswa)
dosen
guru
ekstrakulikuler
(6) Politik
Hubungan bilateral
demokrasi
otoriter
myorits tunggal
pemilihan umum
kampanye
islam politik
jargon politik
politik dagang sapi
komisi pemilihan umum
negara kesatuan
absolut
negara federal
pengawas pemilihan umum
persuasif
referendum
kapitalis
kudeta
diktator
2. Parameter kemampuan berkomunikasi
Savignon dalam bukunya Communicative Competence: Theory
and Classroom Practice (1983) menyebutkan lima parameter kemampuan
berkomunikasi sebagai berikut: (1) dinamis dan interpersonal, (2) ada pada
setip sistem simbol, (3) kontekstual, (4) kemampuan dasar dan menifestasi
lahiriah, dan (5) relative.
Dengan parameter dinamis dan interpersonal dimaksudkan bahwa
komunikasi itu tidak statis dan mesti melibatkan pihak lain atau mitra
komunikasi (pembaca). Kemampuan berkomunikasi seseorang tampak
dalam berbagai simbol, misalnya: ujaran, tulisan, isyarat, dan lain-lain.
C. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu
Bahasa Indonesia sebagai bahsa ilmu dapat dinyatakan sebagai
ragam bahasa yang dibentuk oleh para ilmuwan sacara disengaja dan
diniati. Terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu bukan hanya
tanggung jawab para ahli bahasa melainkan semua ilmuwan sebagai
anggota komunitas (masyarakat) wacana (discourse community). Semakin
tinggi kekerapan penelitian, penulisan dan publikasi ilmiah, semakin
beragam bidang keilmuan yang ditulis dan dipublikasiakan, dan semakin
gencar
serta
menasional
dan
mengglobal
penyebaran
dan
pemasyarakatannya, maka semakinmantap dan kokohlah ragam bahasa
ilmu itu. Makin jelas wujud ragam bahasa ilmiah dengan karakteristik:
jelas, deskriptif, bernalar, dapat dikontrol, sederhana, dank e arah bahasa
yang abstrak (Rusyana, 1989).
Menurut para bahasawan kelompok praha (dalam Davis,
1973:228), ciri utama ragam bahasa ilmiah adalah kecermatan serta
intelektualisasi. Ciri lain yang ditekankan oleh Lepschy (1972) adalah
kelengkapannya sebagai sarana komunikasi, yakni tanpa perlu dibantu leh
unsur-unsur nnlinguistik yang melingkupi proses komunikasi. Dengan kata
lain, ragam bahasa ilmiah dicirikan oleh pilihan kata dan penataan kalimat
yang serba tepat, lugas objektif, dan eksplisit namun padat.
Ciri penting lain ragam bahasa ilmiah adalah perangkaian kalimat
menjadi wacana, baik wacana kecil maupun wacana besar. Brown dan
Yule (1986) mengungkapkan bahwa hubungan kohesif di antara berbagai
wacana perlu diupayakan dengan menggunakan unsur-unsur penanda
kohesi tersebut memungkinkan tersajikannya alur pikiran secara
sistematik, runtut, logis, dan utuh. Koherensi wacana semacam itu sangat
memerlukan dukungan unsur-unsur penanda kohesi yang tepat dan
eksplisit karena wacana ilmiah hamper selalu berupa atau didasarkan atas
wacana tertulis. Wacana tertulis hanya dapat dipahami dengan sepenuhnya
10
mengandalkan
unsur-unsur
linguistic
tanpa
bantuan
unsur-unsur
paralinguistic atau unsur-unsur konteks situasi komunikasi.
Sebagai ragam bahasa yang cenderung digunakan dengan media
tertulis, ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri yang lazim terdapat pada
bahasa tulis. Menurut Brown dan Yule (1986), ciri-ciri tersebut adalah
sebagai berikut: (1) kalimat-kalimatnya cenderung berupa kalimat
lengkap, (2) cenderung berbentuk kalimat majemuk dengan satu atau lebih
anak kalimat, (3) sering kali berbentuk kalimat pasif, dan (4) banyak
menggunakan klausa yang diawali dengan kata yang sebagai sarana
pemfokusan subjek kalimat.
Selain itu, kaitan antarkalimat diungkapkan secara eksplisit dengan
menggunakan unsur-unsur penghubung yang relevan, frasa-frasa nominal
cenderung kompleks dan padat, kata-katanya cenderung mempunyai acuan
yang kompleks dan jelas, perulangan unsur-unsur sintaktik yang sama
cenderung dihindari, dan penggunaan unsur-unsur personal seperti nah,
wah, yah, saya kira, tentunya, dan sejenisnya juga cenderung
dihindari.
DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan, Khaerudin. (2012). Bahasa Indonesia keilmuan untuk perguruan
tinggi. Bandung: Revika Aditama.
10
11
Bab III
Penulisan Bahasa Indonesia Ilmiah
A. Karya Tulis Ilmiah
Secara umum, suatu karya tulis ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil
karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu serta dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Karangan atau tulisan ilmiah adalah semua
bentuk karangan yang memiliki kadar ilmiah tertentu sesuai dengan bidang
keilmuannya (sains, teknologi, ekonomi, pendidikan, bahasa dan sastra,
kesehatan, dan lain-lain).
Berbeda dengan karya sastra atau seni, karya ilmiah mempunyai bentuk serta
sifat yang formal karena isinya harus mengikuti persyaratan-persyaratan tertentu
sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah adalah
menyampaikan seperangkat keterangan, informasi dan pikiran secara tegas,
ringkas dan jelas.
Karya tulis ilmiah dikemukakan berdasarkan pemikiran, kesimpulan serta
pendapat/pendirian penulis yang di rumuskan setelah mengumpulkan dan
mengolah berbagai informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, baik
teoretik maupun empiric.
Karya ilmiah tertulis (karangan ilmiah) dapat berbentuk artikel almiah popular
(esei, opini), usulan penelitian, dan laporan penelitian. Dalam bentuk khusus yang
bersifat akademik, karangan ilmiah dapat berupa makalah , skripsi, tesis, dan
disertai ,-yang masing-masing digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk
mencapai gelar sarjana (S-1), magister (S2), doctor (S3).
Isi suatu karya ilmiah dapat berupa keterangan atau informasi yang bersifat
factual (mengemukakan fakta),
hipotesis ( dugaan-dugaan),
konklusif
(mengemukakan kesimpulan), dan implementatif (mengemukakan rekomendsi
atau saran-saran serta solusi) .
Suatu karya ilmiah pada hakikatnya merupakan hasil proses berpikir ilmiah.
Adapun pola berpikir yang digunakan dalam menghasilkan suatu karya ilmiah
adalah pola berpikir reflektif, yaitu suatu proses berpikir yang dilakukan dengan
mengadakan refleksi secara logis dan sistematis di antara kebenaran ilmiah dan
11
12
kenyataan empiric dalam mencari jawaban terhadap suatu masalah. Cara berpikir
induktif dan deduktif secara bersama-sama mendasari proses berpikir reflektif.
Menurut John Dewey, ada lima langkah dalam proses berpikir reflektif, yaitu:
(1) merasakan adanya suatu kesulitan, yakni terjadinya suatu hambatan dalam
pengamatan, (2) Penempatan masalah atau kesulitan itu pada proporsi yang
sebenarnya dan mengadakan perumusan kesulitan tersebut, (3) Timbulnya saransaran berupa kemungkinan pemecahan masalah atau kesulitan dalam bentuk
rumusan hipotesis atau dugaan-dugaan sementara, (4) Mengadakan persiapanpersiapan mental terhadap masalah dalam bentuk pengumpulan dan pengolahan
informasi empiric, dan (5) Mengadakan opserfasi atau penelaahan lebih
lanjutuntuk menetapkan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak berdasarkan
informasi yang di peroleh.
Dalam berbagai kegiatan ilmiah, pola berpikir reflektif sangat di perlukan
untuk mencapai hasil yang dapat dijamin kebenarannya secara ilmiah. Pertama,
perlu penjelasan ilmiah dalam menghasilkan karya ilmiah untuk menjelaskan
pikiran sedemikan rupa, sehingga dapat dipahami secara objektif.
Kedua, pengertian atau definisi operasional dalam kegiatan ilmiah, pengertian
yang terkandung didalamnya hendaknya bersifat operasional agar dapat terjadi
kesamaan persepsi. Untuk itu, perlu dibuat rumusan yang jelas dan objektif.
Ketiga. Berpikir kuatitatif untuk lebih menjamin objektifitas penyampaian
pikiran atau keterangan. Hal ini berarti perlunya data kuantitatif sebagai
pendukung (argument) terhadap segala pikiran, pendapat, gagasan, pernyatan dan
ungkapan yang akan dikemukakan.
B. Jenis Karya Tulis Ilmiah
Berdasarkan tingkat akademiknya, karangan ilmiah dapat dibedakan atas: (1)
laporan, (2) makalah, (3) usulan penelitian, (4) skripsi, (5) tesis, dan (6) disertasi.
12
13
1. Laporan
Laporan adalah karangan yang dibuat setelah seseorang melakukan
eksperimen, peninjauan atau survey, observasi, pembacaan dan penelaahan buku,
penelitian, dan lain-lain.
Laporan penelitian adalah karangan yang dibuat setelah seseorang atau
sekelompok orang melakukan penelitian. Penelitian yang di lakukan tersebut
antara lain: penelitian survey, penelitian expost facto, penelitian eksperimen,
penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, penelitian analisis makna (content
analysis), penelitian tindakan (action research), penelitian historis, penelitian
kebijakan, dan penelitian analisis data sekunder.
Secara konvensional, laporan penelitian disusun dengan mengikuti pla
atau sistematika sebagai berikut: pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian,
hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan serta saran atau rekomendasi.
2. Makalah
Makalah sering juga disebut paper (kerja kertas), ialah jenis karya tulis
yang memerlukan studi, baik secara langsung, misalnya observasi lapangan
maupun secara tidak langsung (studi kepustakaan) (Parera,1982:25).
Makalah biasanya disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Judul : semacam tanda pengenal karangan dansekaligus juga kunci utama
untuk mengetahui isi karangan.
Abstrak : abstrak biasanya berisi intisari keseluruhan tulisan, ditulis secara
naratif, dan diketik satu spasi serta paling banyak tiga paragraph atau
sekitar 150-200 kata.
Pendahuluan : makalah berisi latar belakang masalah yang disusun dalam
alur pikir yang logis, yang menunjukan kesenjangan antara situasi yang
ada dengan situasi yang diharapkan.
Isi dan Pembahasan : dalam pembahasan makalah, hendaknya
dikemukakan deskripsi tentang subjek studi, analisis permasalahan, dan
solusi pemecahannya.
Kesimpulan
13
14
Daftar pustaka : daftar pustaka hanya memuat pustaka atau rujukan yang
diacu dalam penulisan dan disusun ke bawahmenurut abjad nama akhir
penulis pertama.
3. Usulan Penelitian (Proposal)
Kata proposal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, misalnya proposal
proyek itu belum dapat disetujui oleh pemimpin proyek. Sebagai suatu proses,
penelitian memerlukan tahapan-tahapan tertentu yang disebut sebagai suatu
siklus:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pemilihan masalah dan pernyataan hipotesisnya (jika ada),
Pembuatan desain penelitian,
Pengumpulan data,
Pembuatan kode dan analisi data, dan
Interpretasi hasilnya (Maria S.W. Soemardjono, 1997: 1-2).
Berikut ini dicontohkan kerangka usulan penelitian yang dapat dijadikan
sebagai pedoman oleh calon peneliti
Kerangka Usulan Penelitian
1. Judul
2. Latar Belakang, berisi :
Perumusan masalah/permasalahan
Keaslian/orinalitas penelitian
Manfaat penelitian
3. Tujuan penelitian
4. Tinjauan pustaka
5. Landasan teori
6. Hipotesis (jika ada)
7. Metode/cara penelitian, yang berisi :
Bahan/materi penelitian
Alat/instrument pengumpulan data
Jalannya penelitian
Variabel dan data yang dikumpulkan
Analisis hasil
8. Jadwal penelitian, yang berisi :
Tahap-tahap penelitian
14
15
Rincian kegiatan pada setiap tahap
Jangka waktu yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan
9. Daftar pustaka
4. Skripsi
Skripsi adalah jenis karya ilmiah yang terkenal di kalangan perguruan
tinggi sebagai bagian dari persyaratan akademik, yang harus ditempuh oleh
seorang mahasiswa tingkat sarjana (S-1) yang akan menempuh ujian atau tugas
akhir jenjang pendidikan.
Biasanya skripsi harus dipertahankan oleh penyusunnya dalam suatu
siding ujian. Isi skripsi biasanya berupa hasil penelitian, baik penelitian
laboratorium, penelitian di lapangan, maupun penelitian keputakaan (kajian
pustaka).
5. Tesis
Tesis adalah jenis karya ilmiah yang di tulis oleh mahasiswa untuk
memperoleh gelar magister atau strada dua (S-2). Tesis sebagai karya ilmiah harus
diteliti dan pembahasannya lebih mendalam daripada skripsi. Oleh karena itu,
tesis harus ditulis dengan lebih teliti, lebih cermat, dan lebih mendalam daripda
skripsi. Pernyataan atau teori yang di kemukakan dalam suatu tesis harus
didukung oleh argument-argumen yang kuat, rasional, dan objektif.
6. Disertasi
Disertasi adalah jenis karya ilmiah yang ditulis untuk mencapai gelar
doctor atau strata tiga (S-3), yaitu gelar akademik tertinggi yang dapat diberikan
oleh suatu perguruan tinggi.
Sebagai karya ilmiah, bagian-bagian skripsi, tesis, dan disertasi pada
prinsipnya hamper sama, yaitu disusun dengan urutan (sistematika) sebagai
berikut :
a. Bagian awal berisi
1) Halaman sampul luar
2) Halaman judul
3) Halaman pengesahan
4) Kata pengantar
5) Abstrak
6) Daftar isi
15
16
7) Daftar tabel
8) Daftar gambar
9) Daftar lampiran
b. Bagian utama berisi
1) Pendahuluan
2) Penyusunan kerangka teoretik dan pengajuan hipotesis
3) Metode penelitian
4) Hasil penelitian dan pengujian hipotesis
5) Kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran/rekomendasi
c. Bagian akhir berisi
1) Daftar pustaka
2) Lampiran-lampiran
B. Menulis Ilmiah (Academic Writing)
Menulis
adalah
kegiatan
menyusun
serta
merangkaikan
kalimat
sedemikian rupa agar pesan, informasi, serta maksud yang terkandung dalam
pikiran, gagasan, dan pendapat penulis dapat disampaikan dengan baik.
Ada tiga tahap proses menulis sebagaimana ditawarkan oleh David
Nunan, yaitu: (1) tahap prapenulisan, (2) tahap penulisan, (3) tahap revisi atau
penyempurnaan. Untuk menerapkan ketiga tahap tersebut, dalam pendidikan
bahasa, khususnya keterampilan menulis diperlukan keterpaduan antara proses
dan produk menulis di dalam kelas.
Bahasa tulis tidak dapat mewujudkan seluruh aspek bahasa lisan secara
sempurna. Di samping kekurangannya, bahasa tulis juga mempunyai kelebihankelebihan. Pertama, lksterlihat sebagai suatu yang tetap dan stabil. Kedua,
pemakaian bentuk-bentuk bahasa pada tingkat morfologi, sintaksis, serta semantic
dalam bahasa tulis dapat lebih cermat dikontrol oleh penulis, sehingga pemakaian
bentuk-bentuk bahasa tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah gramatika.
C. Menulis Sebagai Proses Kreatif
Menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara
berpikir divergen (menyebar) daripada konvergen (memusat).
Sebagai proses kreatif yang berlangsung secara kognitif, penulisan karya
ilmiah dan penyusunan laporan tulisan ilmiah sekurang-kurangnya memuat empat
tahap, yaitu:
16
17
Tahap pertama dalam proses kreatif adalah persiapan atau prapenulisan,
adalah ketika seseorang merencanakan, menyiapkan diri, mengumpulkan dan
mencari informasi, merumuskan masalah, menentukan arah dan focus tulisan,
mengolah informasi, menarik tafsiran dan inferensi terhadap realitas yang akan
dihadapinya, berdiskusi, membaca, mengamati, melakukan survey, dan lain-lain
yang akan memperkaya masukan kognitifnya untuk diproses pada tahap
selanjutnya.
Tahap kedua, inkubasi ketika seseorang memproses informasi yang telah
dimilikinya sedemikian rupa, sehingga mengantarnya pada ditemukannya
pemecahan masalah, jalan keluar/solusi yang dicarinya.
Tahap ketiga, iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi, yaitu gagasan
datang seakan-akan tiba-tiba dan berloncatan dari pikiran kita. Pada saat ini, apa
yang telah lama kita pikirkan menemukan pemecahan atau jalan keluarnya.
Tahap keempat, verifikasi/evaluasi, yaitu apa yang dituliskan sebagai hasil
dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan
focus laporan/tulisan yang diinginkan.
D. Langkah-Langkah Menulis Ilmiah
1. Merencanakan
a. Mengumpulkan Bahan
Hampir semua penulis mengumpulkan segala sesuatu yang mereka perlukan
berupa data, informasi, bacaan sebelum memulai menulis.
b. MenentukanTujuan dan Bentuk
Dalam penulisan ilmiah, tujuan dan bentuk yang dipilih sering ditentukan oleh
situasi. Misalnya, dalam membuat laporan penelitian, format dan tujuan
laporan mungkin sudah ditentukan oleh sponsor atau pemberi dana penelitian.
c. Menentukan Pembaca
Pembaca yang berbeda akan memerlukan bacaan yang berbeda pula. Oleh
karena itu, penulis perlu mengetahui keadaan pembaca sebaik-baiknya.
17
18
2. Menulis
Dalam penulisan ilmiah, karena kompleksnya isi dan adanya batas waktu
yang sudah pasti, lebi baik menulis seawall mungkin, lebih-lebih penulis sudah
mempersiapkan bahan sebagai bahan dasar penulisan, dan paling akhir sedikit
menyusun draf untuk mencapai hasil akhir.
3. Merefleksikan
Teknik yang sering digunakan oleh penulis karangan ilmiah, sebelum
merangkum karangannya, mereka merefleksikan apa yang sudah mereka tulis.
Kesempatan ini memungkinkan penulis memperoleh perspektif yang segar
tentang kata-kata yang pada mulanya tampak sangat betul, tetapi kemudian terasa
salah.
4. Merevisi
Revisi, perbaikan, dan penyempurnaan tulisan dilaksanakan secara berhatihati dan seksama dapat menhasilkan tulisan yang jelas, terarah, terfokus, dan
sesuai dengan keinginan penulis dan pembaca.
18
19
DAFTAR PUSTAKA
Khaerudin Kurniawan, M.Pd. Bahasa Indonesia Keilmuan untuk Perguruan
Tinggi.
,
19
20
ETIKA PENULISAN DAN PENGUTIPAN
A. Etika Penulisan
Dalam
menyiapkan
tulisan
untuk
dipublikasikan,
penulis
terkungkung oleh seperangkat norma/etika yang dapat dikatakan hampir
berlaku secara universal. Etika yang berlaku dalam penulisan ilmiah
adalah sebagai berikut: (1) penulis dilarang mengakui tulisan ahli atau
orang lain sebagai tulisan sendiri (plagiarisme), (2) penulis dilarang
menukangi (memanipulasi) data, (3) penulis dilarang menutupi
kebenaran dengan sengaja, namun tidak berarti boleh menuliskan nama
sebenarnya informasi tanpa kesepakatan, dan (4) penulis dilarang
menyulitkan pembaca.
Disamping itu, peran serta setiap orang yang terlibat dalam
penelitian,
penulisan,
dan
publikasi
ilmiah
harus
diberi
kredit
(perhargaan). Jika penelitian, penulisan, atau publikasi ilmiah dilakukan
berdua, siapa yang lebih banyak sumbangannya dialah penulis utama,
sedangkan yang menyumbang lebih sedikit adalah kopenulis. Berilah juga
penghargaan kepada para informan, narasumber, orang/ ahli atau lembaga
yang berjasa dalam penelitian, penulisan, atau publikasi ilmiah.
Yang terakhir, mintalah pendapat, pandangan seorang penyuting
agar laporan penelitian, penulisan, atau publikasi ilmiah layak baca. Ingat,
tujuan utama penelitian, penulisan, atau publikasi ilmiah adalah
menjelaskan temuan kepada publik (pembaca). Artinya, seorang peneliti,
penulis atau publikasi menjelaskan sesuatu yang belum diketahui oleh
orang lain. Oleh karena itu, penyajian tulisan ilmiah dan bahasa yang
digunakan
harus
memungkinkan
pembaca
memahami
maksud
penulis/peneliti.
B. Kode Etik Penulis
Rifai (1997:5-7) mengemukakan empat belas etika yang dapat dilakukan
oleh setiap penulis karya ilmiah. Keempat belas etika tersebut adalah
sebagai berikut.
20
21
1. Penulis dituntut untuk menjunjung tinggi posisi terhormatnya
sebagai orang terpelajar, dengan jalan menjaga kebenaran hakiki,
manfaat dan makna informasi yang akan disebarluaskannya
sehingga tidak menyesatkan orang lain.
2. Penulis dengan penuh kesungguhan mengupayakan tulisan yang
disajikannya tidak merupakan bahan yang menyusahkan untuk
dibaca karena telah ditulisnya secara tepat, singkat dan jelas.
3. Penulis harus memerhatikan kepentingan penerbit yang mendanai
penerbitan, sehingga keringkasan dan kepadatan tulisan mendasari
penyiapan naskah, sebab hal itu berarti penekanan terhadap biaya
percetakan.
4. Penulis berkepentingan bahwa naskah yang dipersiapkannya
diterbitkan
sepenuhnya
dan
disebarluaskan,
keperluan adanya
dan
untuk
itu
menyadari
bantuan penyunting sebagai
jembatan penghubung dengan pembacanya.
5. Penulis hanya akan mengajukan naskah yang dipersiapkan setelititelitinya sesuai dengan format yang dibakukan, dan dengan cermat
akan mengikuti petunjuk kepada pengarang yang digariskan
penyunting
yang
menjaga
ketaatasasan
penampilan
media
komunikasi yang diasuhnya.
6. Penulis berkewajiban tanggap terhadap usul dan saran penyunting
sehingga segera mengembalikan naskah yang harus diperbaiki dan
direvisinya agar tujuan memajukan ilmu dan teknologi dapat
tercapai secepatnya.
7. Penulisan mutlak selalu bersikap jujur kepada dirinya dan jujur
kepada umum sehingga ia tidak akan menutupi kelemahan atau
memperbesar kelebihan hasil yang dicapainya.
8. Penulis berkewajiban menjunjung tinggi hak, pendapat, atau
temuan orang lain sehingga selalu menjauhi perbuatan tercela
seperti mengambil ide dan gagasan orang lain yang belum
diumumkan serta diaku sebagi gagasannya sendiri.
9. Sehubungan dengan adanya hak cipta kepengarangan dan hak
kepemilikan intelektual, penulis senantiasa bertekat tidak akan
21
22
melakukan plagiat, baik plagiat atas tulisannya sendiri maupun
plagiat berdasarkan tulisan orang lain.
10. Penulis mengetahui sepenuhnya bahwa mengutip pernyataan atau
pendapat orang lain dengan secara jelas menyebutkan sumbernya
tidaklah merupakan perbuatan yang tercela.
11. Penulis menyadari bahwa dengan mengirimkan naskah untuk
diterbitkan, ia memberikan kepada penerbit hak tunggal untuk
menerbitkan, menyebarluaskan dan memperdagangkan hasilnya,
sehingga ia tidak akan mengirimkan naskah serupa kepada penerbit
lain untuk maksud yang sama.
12. Penulis bertanggung jawab terhadap terhadap semua kesalahan isi
terbitan dan menanggung segala bentuk hukuman jika secara
hukum terbukti bahwa isi terbitan melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku.
13. Untuk kepentingan umum, penulis berkewajiban merevisi atau
mempersiapkan edisi baru karyanya jika diminta oleh penerbit.
14. Penulis mempunyai tugas mulia untuk membantu penerbit mencari
penyandang dana tambahan, dan menggalakkan promosi terbitan
hasil karya.
C. Etika Pengacuan dan Pengutipan Langsung
Seorang penulis adakalanya merasa perlu mengutip langsung
pernyataan pengarang atau ahli lain yang dipandang revelan dengan yang
diacu. Dengan demikian, pengutipan dapat dianggap sebagai bentuk lain
pengacuan yang dilakukan untuk menunjang argumen dengan langsung
menyajikan bukti hakiki dan empirik yang dinyatakan orang lain itu.
Penulisan bagian yang di kutip, pemakaian huruf kapital, dan
pemanfaatan tanda-tanda baca serta upaya tipografi lain yang dipakai
dalam pengutipan disesuaikan dengan kalimat pembawa kutipan.
Tanpaknya tidak perlu ditekankan keharusan ketepatan mengutip secara
absolut karena pengutipan dilakukan dengan menempatkan bagian diantara
tanda petik. Kendatipun demikian, kepada penulis diberikan keleluasaan
untuk mengubah, mengurangi, dan melakukan interpolasi, asalkan
semuanya dilakukan dengan penunjukan sumber acuan yang jelas.
22
23
Penyebutan pada sumber yang dikutip dilakukan dengan lebih
cermat dibandingkan dengan pengacuan. Untuk kata-kata mutiara atau
sajak, pencantuman nama pengarang dan judul karyanya langsung
dituliskan di bagian bawah blok kutipan. Hal ini merupan pola yang sudah
dibakukan. Dalam tulisan yang tidak mencantumkan bibliografi,
pengutipan umumnya disertai informasi lengkap sumber tujukan yang
langsung ditulis sebagai bagian kalimat pembawa.
Berikut ini dikemukakan maksud dan tujuan pengacuan dan
pengutipan langsung sebagaimana dinyatakan Mien A.Rifai (1997:4849;Booth, et.al,1995). Kedelapan etika tersebut dijelaskan sebagai berikut:
1. Untuk menjelaskan landasan berpikir, penulis dapat
mengacu (mengutip secara tidak langsung) pada gagasan
ahli lain asalkan disebutkan dengan jelas sumbernya.
2. Untuk pembuktian argumennya, penulis boleh mengutip
langsung kata-kata ahli lain yang dimuat di dalam karya
tulisnya asalkan disebutkan dengan jelas sumbernya.
3. Penulis harus menandai dengan jelas apabila ia mengutip
lebih dari empat kata dari karya pengarang yang diacu.
4. Penulis harus mengutip secara tepat penggal yang
diperlukannya. Pengubahan ejaan masih diperbolehkan jika
hal itu dimaksudkan untuk mempermudah pembaca (kasus
tek kuno, naskah). Kesalah dan kejanggalan yang dibiarkan
sebagaimana adanya ditandai dengan sic (yang berarti
demikian adanya) di dalam tanda kurung.
5. Penulis harus menyebutkan sumber yang dikutip dengan
lebih cermat daripada ketika ia mengacu (kutipan tidak
langsung). Caranya adalah dengan menuliskan nomor
halaman setelah angka tahun karya yang diacu. Untuk kata
mutiara, sajak, penulis menerakan nama pengarang dan
judul karyanya langsung di bagian bawah kanan blok
kutipan.
6. Jikakutipan
tidak
lebih
dari
tiga
baris,
penulis
menyisipkannya di dalam paragraf dan mengapit blok
23
24
kutipan dengan tanda kutip, untuk membedakannya dari
kalimatnya sendiri. Jika kutipan lebih dari tiga baris,
penulis wajib menuliskannya sebagai blok tersendiri yang
biasanya ditakikkan dan dicetak dengan huruf lebih kecil,
spasi tunggal.
7. Dalam hal pengutipan hasil wawancara dengan narasumber,
penulis harus mengutip kata-kata naraumber sebagaimana
adanya meskipun ia menggunakan ragam percakapan akrab
sekalipun atau ia menggunakan interjeksi yang khas bahasa
lisan (ehm, eh, lho, ... dan sebagainya).
8. Penulis tetap wajib menyebutkan sumber kutipan hasil
wawancara. Jika narasumber tidak bersedia disebutkan
namanya
kasus penelitian yang bertopik sangat peka
penulis wajib menyamarkannya. Kesejatian sumber tetap
akan terlihat dari tanggal wawancara.
24
25
BAB V
PEMANTAPAN BEKAL PENULISAN ILMIAH
A.Penulisan Kalimat Efektif
Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan
penulisannya sedemikian rupa, sehingga pembaca memahami gagasan yang sama.
Ada dua syarat penulisan kalimat efektif yaitu: (1).adanya kesatuan gagasan dan
(2).perpaduan unsur-unsur pembentukannya. Kesatuan gagasan diungkapkan oleh
subjek (pokok kalimat) dan predikat sebagai inti kalimat.
Apabila sebuah kalimat terdiri atas sebuah kontruksi S/P yang disebut klausa,
maka kalimat tersebut tergolong kalimat tunggal. Contoh: Pasukan Fedayen siap
memasuki Kota Bagdad. Berdasarkan contoh dapat disimpulkan bahwa kalimat
tunggal ialah kalimat yang terdiri atas satu klausa. Jika kalimat tunggal
digabungkan, hasilnya berupa kalimat baru yang terdiri atas dua klausa atau lebih
disebut kalimat majemuk. Contoh: Pasukan Fedayen siap memasuki Kota Bagdad
setelah pasukan Amerika dan Inggris menguasai Bandara Internasional Saddam
Husein.
Klausa utama sering disebut klausa induk sedangkan klausa bawahan sering
disebut klausa anak . kalimat majemuk yang terdiri atas klausa induk dan klusa
anak dinamai kalimat majemuk bertingkat (beranak, bersusun, subordinatif, tidak
setara). Ciri lahiriah yang mudah dilihat pada kalimat majemuk bertingkat adalah
dimungkinkannya konjungsi (beserta klausa anaknya) dipindahkan ke depan atau
ke belakang klausa induknya tanpa mengubah maksud kalimat. Pemindahan
semacam itu tidak mungkin dilakukan pada kalimat majemuk jenis lain.
Kepaduan kalimat tercermin dalam hubungan logis, di antaranya unsur-unsur
pembentukan kalimat.untuk menandai kepaduan kalimat diperlukan berbagai
pemarkah, seperti pengejaan, preposisi (kata depan), dan kata sambung
(konjungtor).
1. Pengejaan/Pengimbuhan
Sejak diberlakukannya Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan
(1972), sekalipun sampai sekarang dianggap belum sempurna dan terus
25
26
disempurnakan, semua huruf/tulisan dalam abjad Latin secara resmi sudah
menjadi huruf bahasa Indonesia. Dewasa ini, semua huruf Latin dapat diterima
sebagai huruf Indonesia. Oleh karena itu, kebanyakan penulisan kata sarapan dari
bahasa asing sudah dapat dilakukan dengan bentuk aslinya. Untuk itu, perlu
dilakukan penyesuaian seperti diatur dalam buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah yang
dikeluarkan oleh Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. Beberapa
masalah yang sering muncul dan ditemukan dalam kasus pengejaan dan
pengimbuhan serta penulisan istilah serapan dari bahasa asing adalah sebagai
berikut:
a. Cermatilah dalam memakai huruf f dan v, sebab sering ditemukan
penulisan yang keliru dan salah, atau sering dipertukarkan dengan
huruf p, misalnya:
Negative
bukan negatip atau negative
Aktif
bukan aktip atau aktiv
Pikir
bukan fikir
b. Dalam bahasa Indonesia tidak dikenal adanya konsonan rangkap,
misalnya:
Efektif
bukan effektif
Efisien
bukan effesien
Terorisme
bukan terrorisme
c. Huruf y sekarang adalah pengganti huruf j dulu, jadi tidak dapat
dipakai sebagai huruf I lagi, misalnya:
Subjek
bukan subyek
Tragedy
bukan tragedy
Proyek
bukan projek
d. Huruf x biasanya dipakai di awal kata, di tempatlain diganti
dengan ks, misalnya:
Taxi
taksi
Xylem
bukan silem
Exstra
ekstra
e. Huruf h pada gugus gh, rh, th dihilangkan sedangkan huruf ph
menjadi f dan ch menjadi k, misalnya:
Sorgum
bukan sorghum
Kromatografi bukan khromatographi
Patologi
bukan pathologi
2. Penulisan Kata Depan (Proposisi)
26
27
Proposisi atau kata depan adalah kata tugas yang berfungsi sebagai unsur
pembentuk frasa preposisional. Proposisi terletak di bagian awal frasa dan unsur
yang mengikutinya dapat berupa nomina, adjektiva, atau verba. Ditinjau dari segi
bentuknya, preposisi dapat berupa monomorfemis atau polimorfemis. preposisi
monomorfemis adalah preposisi yang terdiri atas satu morfem, karena itu tidak
dapat diperkecil lagi bentuknya. Berikut ini adalah preposisi dalam bahasa
Indonesia beserta fungsinya.
a) Bagi
Untuk
Buat
Guna
menandai hubungan peruntukan, misalnya:
Buku baru itu untuk adik kelasmu
b) Dari
menandai hubungan asal, arah dari suatu tempat, atau milik
Dengan
menandai hubungan kesertaan atau cara
Di
menandai hubungan tempat berada
c) Karena/sebab
menandai hubungan sebab
Ke
menandai hubungan arah menuju suatu tempat
Oleh
menandai hubungan pelaku atau yang di anggap pelaku
Pada
menandai hubungan tempat dan waktu
Tentang
menandai hubungan ihwal peristiwa
Sejak
menandai hubungan waktu dari saat yang satu ke saat yang
lain
Preposisi polimorfemis terdiri atas dua macam: (1). Yang dibentuk dengan
memakai afiks (imbuhan)dan (2). Yang dibentuk dengan menggabungkan dua kata
atau lebih. Preposisi polimorfemis yang berafiks dibentuk dengan menempelkan
afiks pada dasar. Dasar itu dapat berupa morfen bebas (sama, serta), atau morfen
terikat (jelang, kitar).
Contoh:
Bersama
menandai hubungan kesertaan
Menurut
menandai hubungan sumber
Selama
menandai hubungan kurun waktu
Polimorfemis yang terdiri atas morfen bebas berupa: (1) gabungan
preposisi dan preposisi atau (2) gabungan preposisi dan yang bukan preposisi.
Gabungan preposisi dan preposisi dapat menghasilkan preposisi gabungan.
Berikut ini merupakan contoh preposisi gabungan beserta fungsinya.
27
28
Daripada
menandai hubungan perbandingan
Kepada
menandai hubungan arah ke suatu tempat
Selain dari
menandai hubungan perkecualian
Selain preposisi gabungan, ada pula preposisi dan yang bukan preposisi
yang dapat digabung, sehingga merupakan preposisi gabungan.
Contoh:
Di atas, ke dekat, dari balik
Di bawah, ke depan, dari samping
Di muka, ke dalam
3. Kata Sambung (Konjungsi)
Konjungsi atau kata sambung adalah kata tugas tang menghubungkan dua klausa
ataulebih. Kata seperti dan, kalau dan atau adalah kata sambung. Perhatikan
contoh kalimat berikut.
Rifqi sedang membaca dan adiknya sedang menggambar
Dari contoh di atas tampak bahwa yang dihubungkan oleh konjungsi
adalah klausa. Kendatipun demikian kita ketahui pula bahwa ada konjungsi yang
dapat menghubungkan dua kata atau frasa. Jika kita kembali kebentuk preposisi,
maka akan kita dapati bahwa sebagian dari preposisi ada pula yang dapat
bertindak sebagai konjungsi. Pada contoh berikut kita temukan preposisi yang
dapat pula bertindak sebagai konjungsi.
-
Dia tidak berangkat kuliah karena kematian ibunya.
Dia tidak berangkat kuliah karena ibunya meninggal.
Dari uraian serta contoh di atas jelaslah bahwa ada kata yang mempunyai
keanggotaan ganda, yakni berfungsi sebagai proposisi ataupun berfungsi sebagai
konjungsi. Denan kata lain, dapat disimpulkan ciri-ciri kata yang berfungsi
sebagai preposisi apabila dalam statusnya dia berfungsi sebagai frasa, sedangkan
kata yang berfungsi sebagai konjungsi apabila kedudukan kata itu berfungsi
sebagai klausa.
4. Hubungan Logis Intrakalimat
28
29
Di dalam tulisan, hubungan logis harus diungkapkan secara eksplisit agar
pembaca mudah memahami maksud penulis. Bahasa Indonesia ilmiah mengenal
tiga macam hubungan logis:
(1) hubungan kordinatif (setara) diantara bagian-bagian kalimat (preposisi),
misalnya: perpustakaan itu kecil, tetapi memiliki koleksi yang sangat berharga
bagi masyarakat.
(2) hubungan korelatif hubungan saling mengait diantara bagian-bagian kalimat,
misalnya: Bangunan tua itu tidak hanya menarik, tetapi juga mengandung nilai
sejarah yang amat tinggi.
(3) hubungan subordinatif hubungan kebergantungan di antara induk kalimat
dan anak kalimat, misalnya: Acara pembukaan harus tetap dimulai walaupun
para pengunjung baru sedikit yang hadir.
5. Hubungan Logis Antar Kalimat
Hubungan logis antar kalimat pada dasarnya sama dengan hubungan logis antar
klausa walaupun ada hubungan logis tertentu yang hanya terungkap dalam
kalimat, sementara hubungan logis yang lain hanya terungkap diantara dua
kalimat. Di dalam satu kalimat, kata sambung menunjukkan hubungan logis di
antara bagian-bagian kalimat (preposisi), sedangkan dalam hubungan antar
kalimat, kata sambung yang digunakan harus menunjukkan pengacuan ke kalimat
terdahulu. Di dalam penulisannya, kata sambung antar kalimat harus disertai tanda
koma.
Contoh:
Saya kecewa ketika masuk kelas. Sebabnya, para mahasiswa belum hadir.
6. Kesejajaran Satuan dalam Kalimat
yang dimaksud dengan satuan di sini adalah satuan bahasa. Unsur pembentuk
kalimat seperti subjek, predikat, objek, keterangan, dan sebagainya dapat disebut
satuan. Jika kita berbicara tentang kesejajaran satuan dalam kalimat, yang dibahas
ialah keadaan sejajar atau tidaknya satuan-satuan yang membentuk kalimat, baik
dari segi bentuk maupun dari segi makna. Tentu saja pengertian kesejajaran
mengandaikan bahwa unsur pembentuk kalimat itu lebih dari satu. Sesungguhnya
29
30
kaitan bentuk dan makna sangat erat dan tidak terpisahkan, tetapi demi
kemudahan pembicaraan tulisan ini akan dibagi menurut aspek yang menonjol.
a. Kesejajaran bentuk
imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata berperan dalam
menentukan kesejajaran, berikut ini adalah contoh ketidaksejajaran bentuk.
Kegiatannya meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur
peminjaman buku.
Ketidak sejajaran itu ada pada pembelian (buku) yang disejajarkan dengan kata
membuat (katalog) dan mengatur peminjaman (buku). Agar sejajar, ketiga satuan
itu dapat dijadikan nomina semua, ubahnya seperti pada kalimat:
-
Kegiatannya meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan
pengaturan peminjaman buku.
Jika dijadikan verba semua, ubahnya seperti kalimat:
-
Kegiatannya ialah membeli buku, membuat katalog, dan mengatur
peminjaman buku.
b. Kesejajaran Makna
Seperti telah diuraikan di atas, bentuk dan makna berkaitan erat. Dapat
diumpamakan keduanya merupakan isi mata uang yang sama. Berikut ini
diuraikan makna yang terkandung dalam satuan fungsional. Satuan fungsional
adalah unsur kalimat yang berkendudukan sebagai subjek, predikat, objek,
keterangan, dan sebagainya. Status fungsi itu ditentukan oleh relasi makna antar
satuan.
Berikut ini contoh kaliamat yang lebih kompleks :
Selain pelajar SMA, panitia juga memberikan kesempatan
kepada para mahasiswa.
Jika kalimat itu diuraikan, akan diperoleh kalimat seperti pada :
Selain pelajar SMA memberikan kesempatan kepada para
mahasiswa, panitia juga memberikan kesempatan kepada para
mahasiswa.
Contoh berikut memperlihatkan kaitan erat antara bentuk dan makna yang
terwujudkan dalam penentuan fungsi.
30
31
Setelah menyiapkan semuanya, acara sederhana itu pun segera
dimulai.
c. Kesejajan dalam rincian pilihan
Soal ujian kadang-kadang dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Soal yang baik
harus memuat rincian pilihan yang sejajaran sehingga memberi peluang yang
sama untuk dipilih. Berikut ini contoh rincian pilihan yang tidak sejajar.
Pemasangan telepon akan menyebabkan
Melancarkan tugas
Pada contoh diatas, pemasangan telepon akan menyebabkan melancarkan tugas
bukanlah kalimat yang baik. Soal itu dapat diubah sebagai berikut.
Kelancaran tugas
Contoh berikut ini memperlihatkan perincian yang baik dan sejajar walaupun
tidak sejenis
Dengan telepon
Perincian itu dikatakan sejajar karena masing-masingjawaban merupakan
keterangan, tetapi tidak sejenis karena dari segi makna, isi keterangan itu memang
berbeda-beda. Masalah kalimat yang bernalar akan dibahas pada edisi yang lain.
7. Struktur Kalimat yang Tidak Bernalar
Orang sering menggangap bahwa kalimat yang strukturnya lengkap sudah
merupakan kalimat yang benar. Anggapan itu memang ada benarnya sebab salah
satu syarat kalimat yang benar memang strukturnya harus lengkap, misalnya, ada
subjek dan predikat (S P) atau subjek, predikat, dan objek (S P O). Unsur penting
yang sering kurang diperhatikan adalah penalaran. Akibatnya, sering ditentukan
kalimat sebagai berikut.
1) Laporan ini terutama ditujukan untuk melengkapi kekurangan pada
semester yang lalu. Oleh karena itu, laporan ini hanya berisi teknis pelaksanaan
kegiatan.
Pada kalimat di atas terdapat keselahan penalaran. Perhatikan makna bagian
kalimat melengkapi kekurangan laporan semester yang lalu. Padahal, yang
dimaksudkan oleh penulis laporan itu adalah bahwa laporan itu untuk melengkapi
31
32
laporan semester yang lalu sehingga kekurangan pada laporan itu dapat teratasi
atau kekurangan pada laporan itu akan menjadi tinggal sedikit. Oleh Karena itu,
kalimat (1) dapat diperbaiki sebagai berikut.
1a) Laporan ini terutama dimaksudkan untuk melengkapi materi laporan
pada semester yang lalu. Oleh karena itu, laporan ini hanya berisi teknis
pelaksanaan kegiatan.
B. Penulisan Kata dan Istilah
Kosakata atau vokabuler, yang disebut juga perbendaharaan kata adalah
kata/kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kadang-kadang kosakata
diartikan sebagai kata yang disusun secara alfabetis yang disebut glosarium.
Untuk mengekspresikan gagasan, pikiran, dan pandangan dalam bentuk
bahasa, orang perlu menguasai sejumlah kata, lalu menyusunnya menjadi satuansatuan yang disebut kalimat.
Sejak era pembangunan nasional yang dimulai pada awal tahun 1970-an,
kosakata bahasa Indonesia berkembang dengan amat pesat. Banyak kata baru
yang muncul, dan sejumlah istilah telah dibabukan. Agar kita tidak merasa asing
dengan kata-kata baru, dan dengan tepat menggunakan istilah yang sudah
dibabukan, dalam tulisan ini akan disajikan sejumlah kata dan istilah-istilah baru
serta sedikit tentang konsep dasar pembentukan istilah menurut Pedoman Umum
Pembentukan Istilah.
Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan
konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah
khusus ialah istilah yang pemakaian dan/atau maknanya terbatas pada suatu
bidang tertentu; sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa
yang digunakan secara umum. Misalnya, diagnosis adalah istilah khusus di bidang
kedokteran dan pidana adalah istilah khusus di bidang hukum. Karena istilah itu
menggunakan kata atau gabungan kata, istilah itu sebenarnya merupakan sebagian
dari kosakata yang terdapat dalam suatu bahasa.
Istilah dapat bersumber pada kosakata bahasa Indonesia, seperti tunak
(steady), telus (percolate). Kata-kata ini mengungkapkan dengan tepat konsep,
proses, keadaan, atau sifat yang dimaksud.
32
33
Jika dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang tepat, maka
istilah dapat dicari dari sumber bahasa serumpun, misalnya, gambut (Banjar,
untuk peat, Inggris), nyeri (Sunda, untuk pain, Inggris).
Mungkin dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa serumpun tidak
ditemukan istilah yang tepat. Jika demikian, bahasa asing dapat dijadikan sumber
peristilahan dengan cara menerjemahkan istilah asing.
Proses peristilahan asing melalui penyerapan dapat dipertimbangkan jika
salah satu syarat atau lebih berikut ini dipenuhi: (1) istilah serapan yang dipilih
lebih cocok karena konotasinya, (2) istilah serapan yang dipilih lebih singkat dari
pada istilah terjemahan Indonesiannya, dan (3) istilah serapan yang dipilih dapat
mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesianya terlalu banyak
sinonimnya.
Istilah asing yang sudah diserap dan sudah lazim digunakan sebagai istilah
Indonesia masih dapat dipakai sungguhpun bertentangan dengan salah satu syarat
pembentukan istilah.
1. Pemakaian Kosakata dan Istilah dalam Kalimat
upaya mencari dan memperkaya padanan kata Indonesia untuk istilah asing
merupakan pengayaan istilah Indonesia.
2. Pembentukan Kata dan Istilah dengan Unsur Terikat: pra-,pramu-, dan
pascaa. Kata yang dibentuk dengan pra(1) Setiap malam TVRI menyajikan acara prakiraan cuaca
(Inggris, weather forecast).
Kata prakiraan 'perhitungan sebelumnya', yang dibentuk dari
kata dasar prakira + an, dan prakira dibentukdari kata dasar
kira yang didahului unsur pra- yang bermakna 'sebelum'.
(2) Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, seorang terdakwa
korupsi belum dapat dinyatakan salah sebelum pengadilan
memutuskan bersalah.
(3) Di Sangiran dapat ditemukan peninggalan benda-benda
prasejarah yang berupa artefak dan fosil-fosil manusia purba.
Prasejarah 'sejarah sebelum ada peninggalan (bukti tertulis)'.
33
34
Kata-kata lain yang dibentuk dengan pra- antara lain: prakata
(Inggris, foreword) 'penjelasan sebelum uraian pokok pada babbab dalam buku', prasekolah 'pendidikan sebelum sekolah
dasar', prasangka 'dugaan sebelum peristiwa atau perbuatan
terjadi'. Bentuk pra- dapat bermakna '(di) muka', 'sebelum atau
mendahulukan', 'persiapan', 'terjadi atau dilakukan sebelum
peristiwa atau perbuatan terjadi'.
b. Kata yang dibentuk dengan pramu(4) Sekarang Zakaria telah bekerja sebagai pramugara udara di
perusahaan penerbangan Indonesia Airways (Inggris, steward).
Pramugara 'karyawan perusahaan pengangkutan melayani para
penumpang', kalau wanita, disebut pramugari.
(5) Pramugari Garuda bersikap ramah-tamah ketika melayani
jamaah haji Indonesia.
c. Kata yang dibentuk dengan pascaBentuk pasca- bermakna 'sesudah' dan merupakan lawan kata pra'sebelum'. Berikut ini contoh pemakaian kata yang dibentuk dengan
pasca(6) Pada Pasca-Perang Dunia II Amerika Serikat dan Uni Sovyet
tampil sebagai Negara adikuasa di dunia. Pasca-Perang Dunia
II 'sesudah Perang Dunia II'.
(7) Ibu Euis Yuliawati sedang mengikuti program pendidikan
pascasarjana di Universutas Pendidikan Indonesia.
PANDAAN ISTILAH YANG TEPAT
Asing
Check in
Indonesia
lapor masuk
lapor berangkat
check out
lapor keluar
drive-in
kendara masuk
drive- through
kendara lewat
dry cleaning
cuci kimia
garment
pakaian jadi
kitchen set
peranggu dapur
34
35
restroom
ruang rehat, toilet
soft drink
minuman ringan
soft lens
lensa lunak
35
36
B. Penulisan Kata dan Istilah
Kosakata atau vokabuler, yang disebut juga perbendaharaan kata adalah
kata/kata-kata yang terdapat dalam suatu bahasa. Kadang-kadang kosakata
diartikan sebagai kata yang disusun secara alfabetis yang disebut glosarium.
Untuk mengekspresikan gagasan, pikiran, dan pandangan dalam bentuk
bahasa, orang perlu menguasai sejumlah kata, lalu menyusunnya menjadi satuansatuan yang disebut kalimat.
Sejak era pembangunan nasional yang dimulai pada awal tahun 1970-an,
kosakata bahasa Indonesia berkembang dengan amat pesat. Banyak kata baru
yang muncul, dan sejumlah istilah telah dibabukan. Agar kita tidak merasa asing
dengan kata-kata baru, dan dengan tepat menggunakan istilah yang sudah
dibabukan, dalam tulisan ini akan disajikan sejumlah kata dan istilah-istilah baru
serta sedikit tentang konsep dasar pembentukan istilah menurut Pedoman Umum
Pembentukan Istilah.
Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan
konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Istilah
khusus ialah istilah yang pemakaian dan/atau maknanya terbatas pada suatu
bidang tertentu; sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa
yang digunakan secara umum. Misalnya, diagnosis adalah istilah khusus di bidang
kedokteran dan pidana adalah istilah khusus di bidang hukum. Karena istilah itu
menggunakan kata atau gabungan kata, istilah itu sebenarnya merupakan sebagian
dari kosakata yang terdapat dalam suatu bahasa.
Istilah dapat bersumber pada kosakata bahasa Indonesia, seperti tunak
(steady), telus (percolate). Kata-kata ini mengungkapkan dengan tepat konsep,
proses, keadaan, atau sifat yang dimaksud.
Jika dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang tepat, maka
istilah dapat dicari dari sumber bahasa serumpun, misalnya, gambut (Banjar,
untuk peat, Inggris), nyeri (Sunda, untuk pain, Inggris).
Mungkin dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa serumpun tidak
ditemukan istilah yang tepat. Jika demikian, bahasa asing dapat dijadikan sumber
peristilahan dengan cara menerjemahkan istilah asing.
36
37
Proses peristilahan asing melalui penyerapan dapat dipertimbangkan jika
salah satu syarat atau lebih berikut ini dipenuhi: (1) istilah serapan yang dipilih
lebih cocok karena konotasinya, (2) istilah serapan yang dipilih lebih singkat dari
pada istilah terjemahan Indonesiannya, dan (3) istilah serapan yang dipilih dapat
mempermudah tercapainya kesepakatan jika istilah Indonesianya terlalu banyak
sinonimnya.
Istilah asing yang sudah diserap dan sudah lazim digunakan sebagai istilah
Indonesia masih dapat dipakai sungguhpun bertentangan dengan salah satu syarat
pembentukan istilah.
3. Pemakaian Kosakata dan Istilah dalam Kalimat
upaya mencari dan memperkaya padanan kata Indonesia untuk istilah asing
merupakan pengayaan istilah Indonesia.
4. Pembentukan Kata dan Istilah dengan Unsur Terikat: pra-,pramu-, dan
pascad. Kata yang dibentuk dengan pra(8) Setiap malam TVRI menyajikan acara prakiraan cuaca
(Inggris, weather forecast).
Kata prakiraan 'perhitungan sebelumnya', yang dibentuk dari
kata dasar prakira + an, dan prakira dibentukdari kata dasar
kira yang didahului unsur pra- yang bermakna 'sebelum'.
(9) Sesuai dengan asas praduga tak bersalah, seorang terdakwa
korupsi belum dapat dinyatakan salah sebelum pengadilan
memutuskan bersalah.
(10) Di Sangiran dapat ditemukan peninggalan benda-benda
prasejarah yang berupa artefak dan fosil-fosil manusia purba.
Prasejarah 'sejarah sebelum ada peninggalan (bukti tertulis)'.
Kata-kata lain yang dibentuk dengan pra- antara lain: prakata
(Inggris, foreword) 'penjelasan sebelum uraian pokok pada babbab dalam buku', prasekolah 'pendidikan sebelum sekolah
dasar', prasangka 'dugaan sebelum peristiwa atau perbuatan
terjadi'. Bentuk pra- dapat bermakna '(di) muka', 'sebelum atau
37
38
mendahulukan', 'persiapan', 'terjadi atau dilakukan sebelum
peristiwa atau perbuatan terjadi'.
e. Kata yang dibentuk dengan pramu(11) Sekarang Zakaria telah bekerja sebagai pramugara udara di
perusahaan penerbangan Indonesia Airways (Inggris, steward).
Pramugara 'karyawan perusahaan pengangkutan melayani para
penumpang', kalau wanita, disebut pramugari.
(12) Pramugari Garuda bersikap ramah-tamah ketika melayani
jamaah haji Indonesia.
f. Kata yang dibentuk dengan pascaBentuk pasca- bermakna 'sesudah' dan merupakan lawan kata pra'sebelum'. Berikut ini contoh pemakaian kata yang dibentuk dengan
pasca(13) Pada Pasca-Perang Dunia II Amerika Serikat dan Uni
Sovyet tampil sebagai Negara adikuasa di dunia. Pasca-Perang
Dunia II 'sesudah Perang Dunia II'.
(14) Ibu Euis Yuliawati sedang mengikuti program pendidikan
pascasarjana di Universutas Pendidikan Indonesia.
PANDAAN ISTILAH YANG TEPAT
Asing
Check in
Indonesia
lapor masuk
lapor berangkat
check out
lapor keluar
drive-in
kendara masuk
drive- through
kendara lewat
dry cleaning
cuci kimia
garment
pakaian jadi
kitchen set
peranggu dapur
restroom
ruang rehat, toilet
soft drink
minuman ringan
soft lens
lensa lunak
38
39
ASPEK MEKANIK
Dalam Kamus Besar Indonesia, ejaan diartikan sebagai kaidah-kaidah cara
menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dsb) dalam bentuk tulisan (hurufhuruf) serta penggunaan tanda baca. Menurut KRIDALAKSANA (1973: 40),
yang dimaksud dengan ejaan adalah sistem atau aturan perlambangan bunyi
bahasa dengan huruf (cq. Huruf latin), aturan menuliskan kata-kata dan cara-cara
mempergunakan tanda baca.
Dari uraian di atas tampak adanya tiga cakupan dalam ejaan, yaitu: ( 1) Aturan
perlambangan bunyi bahasa dengan huruf, (2) Aturan menuliskan kata-kata, dan
(3) Cara-cara mempergunakan tanda baca. Cakupan ketiga aspek tersebut
digambarakan dalam pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yaitu:
1. Pemakaian huruf yang termasuk didalamnya pemenggalan kata, meliputi:
a.huruf abjad
b.huruf vokal
c. huruf konsonan
d. gabungan huruf konsonan
e. pemenggalan kata
2. Pemakaian huruf , meliputi:
a. huruf besar (huruf kapital)
b. huruf miring
3. Penulisan kata, meliputi:
a. kata dasar
b. kata jadian atau kata turunan
c. bentuk ulang
d. gabungan kata
e. kata ganti ku, kau-, -mu, dan nya
f. kata depan di, ke, dan dari
g. kata si dan sang
h. singkatan dan akronim
i. angka dan lambang bilangan
4. Penulisan unsur serapan
39
40
5. Penulisan tanda baca, meliputi:
a. tanda titik (.)
b. tanda koma (,)
c. tada titik koma (;)
d. tanda tirik dua (:)
e. tanda hubung (-)
f. tanda pisah (_)
g. tanda elipsis (...)
h. tanda tanya (?)
i. tanda seru (!)
j. tanda kurung ((...))
k. tanda kurung siku ([...])
l. tanda petik (...)
m. tanda petik tunggal (...)
n. tanda miring (/)
o. tanda penyingkat/apostrof ()
A. PEMENGGALAN KATA
Pemenggalan kata menurut pedoman EYD, perlu memerhatikan suku kata. Dalam
pemenggaln kata berdasarkan suku kata perlu diperhatikan apakah kata yang
dipenggal itu merupakan kata dasar, kata berimbuhan (kata turunan), ataukah kata
itu terdiri atas dua unsur atau lebih, yang salah satu unsurnya dapat bergabung
dengan kata lain. Aturan pemenggalan kata secara lebih rinci dapat digambarkan
sbb:
1. jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara
kedua huruf vokal itu, misalnya:
Kain
>
ka-in
Buah
>
bu-ah
Huruf diftong ai, au, dan oi tidak pernah diceraikan, sehingga pemenggaln kata
tidak dilakukan di antara kedua huruf itu, misalnya:
Aula
>
au-la, bukan a-u-la
40
41
Saudara
>
sau-dara, bukan sa-u-da-ra
2. Jika di tengah kata ada huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di
antara dua buah huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan,
misalnya:
Lapar
>
la-par
Padi
>
pa-di
3. Jika di tengah kata ada huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan
di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruh konsonan itu tidak pernah
diceraikan, misalnya:
Sombong
>
som-bong
Caplok
>
cap-lok
4. Jika di tengah huruf konsonan atau lebih, pemenggalan dilakukan di antara
huruf konsonan pertama dan huruf konsonan kedua, misalnya:
Instrumen
>
in-stru-men
Ultra
>
ul-tra
5. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan, termasuk awalan, termasuk awalan yang
mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangakai
dengan kata dasarnya, dapat dipenggal pada pergantian baris, misalnya;
An, me-ra-sa-kan, me-nuruni - imbuhan i tidak dipisahkan sendiri.
6. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat
bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan dengan cara (1) di
antara unsur-unsur itu atau (2) pada unsur gabungan itunsesuai dengan kaidah (1),
(2), (3) dan (4) di atas, misalnya:
Biografi
>
bio-grafi ataub bi-o-gra-fi
Fotografi
>
foto-grafi atau fo-to-gra-fi
Berikut ini disajikan cara pemenggalan kata serapan yang perlu diperhatikan
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, terutama yang diperkirakan ada
unsur lepas dari akar kata di dalam kosakata serapan itu.
Eks-plo-ra-si
ek-strak-si
Eks-ploi-ta-si
ek-strem
Ek-so-tis
eks-pres
41
42
Ek-so-gen
eks-po-nen
B. PEMAKAIN HURUF KAPITAL DAN HURUF MIRING
1. Pemakain Huruf Kapital
Pemakain huruf kapital dan huruf miring tampaknya sering bermasalah ketika
penulis merasakan dan mempunyai kesukaan pilihan tanda baca yang lain.
Misalnya, huruf miring yang harus dituliskan dalam penulisan judul buku, jurnal,
majalah, dan lain-lain. Di ganti dengan huruf tebal atau dengan tanda baca yang
lain karena dipandang lebih nyeni, lebih indah, lebih tampak, dan
sebagainya.
1. huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat, misalnya:
Hipotesis dirumuskan berdasarkan landasan teori (jika ada), atau berdasarkan
tinjauan pustaka.
2. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung, misalnya:
Ayah bertanya, Kamu sudah salat?
3. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungakapan yang
berhubungan dengan nama tuhan, termasuk kata gantinya, dan kitab suci,
misalnya:
Allah
Islam
Yang Maha Kuasa
4. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan,
dan keagamaan yang diikuti nama orang, misalnya:
Imam Nawawi
Haji Agus Salim
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan,
keturunan, dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang, misalnya:
Dia memang bercita-cita menjadi imam.
5. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangakat
yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu,
nama instansi, atau nama tempat, misalnya: Presiden Megawati Soekrnoputri
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang
tidak diikuti nama orang, atau nama tempat, misalnya: Dia gagl menjadi gubernur
42
43
6. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, misalnya:
Thomas Wijanarto
7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan
bahasa, misalnya:suku sunda
Huruf kapital dipakai tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan
bahasa yang dipakai sebagai kata berimbuhan misalnya: keinggris-inggrisan
8. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hai, hari raya
dan peristiwa bersejarah, misalnya: bulan agustus
Hari sabtu
tahun hijriah
perang candu
9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya:sungai
cikupundung
teluk jakarta
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak
menjadi unsur nama diri, misalnya: berenang kesungai
Huruf kapital tidak dipakai sebagai sebagai huruf pertama nama geografi yang
dipergunakan sebagai nama jenis, misalnya: gula jawa
10. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara,
lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, dan nama dokumen resmi kecuali kata
sambung seperti dan, misalnya: negara kesatuan republik indonesia
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi
negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, serta nama dokumen
resmi, misalnya:
Berdasarkan peraturan pemerintah
11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang
sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan
ketatanegaraan serta dokumen resmi, misalnya:perserikan bangsa-bangsa
12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua
unsur kata ulang sempurna)dalam penyebutan nama buku, majalah, jurnal, surat
kabar dan judul karangan, kecuali seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang
tidak terletak pada posisi awal< misalnya:setiap penulis penulis artikel harus
berlangganan Jurnal Manajemen Indonesia
43
44
13. huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar,
pangkat dan sapan, misalnya: Dr. Doktor
14. Hurugf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan
kekerabatan seperti bapak , ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai
dalam sapaan dan pengacuan, misalnya:kapan Ayah datang? tanya Fakhrul
Huruf kapital tidak dipakai sbagai huruf pertama kata penunjuk hubungan
kekerabatan yang tidak dipakai dalam pengacuan dan sapaan misalnya:kita harus
menghormati ibu dan bapak kita
15.huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Anda, misalnya: tahukah
anda, siapakah yang mengebom Hotel Marriot Jakarta?
Yang perlu diperhatikan dalam penulisan huruf kapital, selain hal-hal yang telah
disebutkan di atas adalah penulisan judul karya tulis. Dalam pedoman butir (12)
dinyatakan bahwa huruf kapital tidak digunakan pada penulisan kata depan dan
kata penghubung. Berikut ini disajikan contoh kata depan (preposisi) dan kata
penghubung (konjungsi) yang tidak ditulis dengan huruf kapital pada setiap judul
karya tulis.
Agar
kalau
sebelum (itu)
Akan
karena
sedangkan
Akibat
ke
sedangkan
Alih-alih
kecuali itu
sedari
Andaikan
kemudian
segala
Di antara
pada
supaya
Di atas
padahal
tambahan pula
2. Penulisan Huruf Miring
Huruf miring dalam tulisan dipakai untuk:
1) Menuliskan nama buku, majalah, jurnal, dan surat kabar yang dikutip
dalam tulisan, misalnya:
Dalam Jurnal Manajememen Indonesia edisi 2002 dikemukakan ihwal
peranan Public Relation dalam membangun citra perusahaan.
Buku Sistem Informasi Manajemen memuat berbagai persoalan
manajemen berbasis informasi.
Dalam harian kompas selalu tercantumrubrik telekomunikasi.
44
45
2) Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf
bagian kata, atau kelompok kata, misalnya:buku ini tidakmembicarakan
masalah hak asasi manusia
Buatlah kalimat efektif dengan manajemen telekomunikasi
Kata kunci indeks pembangunan manusia adalah pendidikan dan
kesehatan
3) Huruf miring dipakai untuk kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali
yang telah disesuaikan dibawah seseorang Primus Inter Pares untuk
merumuskan kehendaknya, misalnya: Politik Divide Of Impera pernah
merajalela dinegara kita
Weltarischaving antara lain diterjemahkan menjadi pandangan
dunia
Apakah tidak sebaiknya kita menggunakan kata pelatihan
untuk kata training?
Buah mangga nama ilmiahnya adalah garcinia mangostana
Sebagai catatan dan tulisan tangan atau ketikan, huruf miring atau kata
yang akan ditulis miring diberi satu garis dibawahnya.
C. Penulisan Kata
Penulisan kata dalam penulisan ilmiah adalah sebagai berikut :
1. Penulisan Kata Ulang
Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung (-).
Berikut ini disajikan beberapa contoh cara menulis kata ulang :
a. Pengulangan kata dasar
Universitas-universitas
Kantor-kantor
Pintar-pintar
Dalam penulisan karya ilmiah, pengulangan kata dasar tidak perlu selalu
dilakukan untuk menyatakan jumlah. Jumlah jamak dapat dinyatakan
dengan numeralia pokok tertentu, misalnya, beberapa, banyak, berbagai.
b. Pengulangan kata berimbuhan
Selambat-lambatnya
Perlahan-lahan
c. Pengulangan gabungan kata
45
46
Baju-baju bekas
Buku-buku bacaan
d. Pengulangan kata yang berubah bunyi
Ramah-tamah
Teka-teki
Mondar-mandir
e. Pengulangan sebagian dengan pelemahan bunyi
Pepohonan
Bebatuan
2. Penulisan Gabungan Kata
aturan penulisan kata adalah sebagai berikut :
a. Bagian-bagian gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk
dituliskan terpisah, misalnya :
Jasa marga
Limbah industri
Simpan pinjam
b. Ada gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata unsurunsurnya membentuk makna yang menyatu, seehingga makna tersebut
tidak dapat dikembalikan pada makna unsur-unsur gabungan kata
tersebut, misalnya :
Apabila
Barangkali
Daripada
Bilamana
c. Ada gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri
sebagai satu kata yang mengandung arti penuh. Misalnya :
Multimedia
Caturwulan
Mancanegara
d. Jika gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau hanya mendapat
akhiran, maka dituliskan serangkai dengan kata yang paling dekat
dengannya, sedangkan kata lainnya yang merupakan unsur gabungan
tetap dituliskan terpisah dan juga tidak diberi tanda hubung, misalnya :
Bertanggungjawab
Berterima kasih
Bertanda tangan
46
47
e. Jika gabungan kata mendapat awalan sekaligus akhiran, maka
penulisannya harus dirangkai, dan tidak diberi tanda hubung, misalnya:
Pertanggungjawaban
Melatarbelakangi
3. Penulisan Partikel
Partikel pun yang ditempatkan setelah kata benda, kata kerja, kata
sifat, dan kata bilangan harus dituliskan terpisah karena mempunyai
makna yang penuh, misalnya : Apa pun yang telah dilakukan Pansus
Sukhoigate harus dihargai
Partikel per yang berarti mulai,demi, dan tiap dituliskan terpisah dari
bagian kalimat yang mendampinginya, misalnya : satu per satu tersangka
pengeboman hotel marriot dipanggil polisi Metro Jaya.
Partikel per yang ditulis serangkai merupakan imbuhan dari memper,
memper-i, dan memper-kan atau sebagai bilangan pecahan, misalnya :
perbaiki kembali tugas yang Anda telah serahkan itu.
4. Penulisan Kata Ganti
kata ganti yang dipendekkan, seperti ku, kau, mu, nya dituliskan serangkai
dengan kata yang mendahului atau mengikutinya, misalnya : apakah tugas
makalahmu sudah selesai ?
5. Penulisan Bentuk Singkat, Singkatan, dan Akronim
a. Bentuk singkat adalah bentuk pendek yang diambil atau dipotong dari
bentuk lengkapnya dan penulisannya menggunakan huruf kecil semua,
misalnya :
Perpus ( bentuk singkat dari perpustakaan )
b. Singkatan adalah bentuk pendek yang diambil dari huruf-huruf
pertama suatu kata atau frasa. Singkatan dieja huruf demi huruf,
47
48
penulisannya menggunakan huruf kapital semua dan tidak diberi tanda
titik. Misalnya :
PT ( singkatan dari Perseroan Terbatas )
c. Akronim adalah bentuk pendek yang biasanya diambil dari sebuah
frasa.
Akronim
dapat
dilafalkan
menjadi
kata.
Penulisannya
menggunakan huruf kecil, kecuali jika akronim itu merupakan nama
diri atau diikuti oleh nama sehingga menjadi satu-kesatuan nama,
misalnya:
Puskesmas ( bentuk pendek dari pusat kesehatan masyarakat )
Yang perlu diperhatikan dalam penulisan bentuk pendek, singkatan,
dan akronim adalah hendaknya pada penulisan pertama dituliskan
secara utuh ( lengkap ) dari yang dipendekkan/disingkat itu, yang
dapat dituliskan dalam tanda kurung, kendatipun bentuk pendek itu
sudah dikenal luas oleh pemakai bahasa.
6. Penulisan Angka dan Lambang Bilangan
a. Lambang bilangan dituliskan dengan angka jika berhubungan dengan
ukuran ( panjang, luas, isi, berrat ) satuan waktu, nilai uang, nomor
jalan, rumah, kamar pada alamat, misalny:
50 cm
Jalan Sarimanis IV Nomor 44
Hotel Marriott, Kamar 13
b. Lambang bilangan tingkat dapat dituliskan dengan cara sebangai
berikut.
Sri Sultan Hamengku Buwana X atau Sri Sultan Hamengku Buwana
ke-10
c. Bilangan dalam perincian jugak dituliskan dengan angka, misalnya:
Menurut laporan polisi, jumlah korban jiwa dalam tragedy Marriott
kemarin ada 20 orang, 11 orang tewas, 5 orang luka bakar, dan 4 orang
luka ringan.
d. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata
dituliskan dengan huruf, sedangkan yang dinyatakan lebbih dari dua
kata dituliskan dengan angka, misalnya:
48
49
Jumlah mahasiswa baru yang sudah mendaftar ke STMB sebanyak
seratus Sembilan orang .
Bulan berputar sekali pada porosnya memerlukan waktu 27,23 hari.
e. Angka tidak dapat dituliskan pada aewal kalimat. Jaka dituliskan pada
awal kalimat, penulisan lambing bilangan digantia dengan huruf atau
diubah sedemi kian rupa sehingga penulisan angkapada awal kalimat
dapat dihindari, misalnya :
Sebanyak 10 orang ditahan dalam peristiwa tawuran itu.
Enam dosen teladan mendapat penghargaan dari rector.
f. Penulisan kata bilangan yang mendapat akhiran an adalah sebagai
berikut :
Tahun 60-an atau tahun enam puluhan
D. Penulisan Unsur Serapan
Unsur serapan atau pinjaman itu dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan
besar : (1) unsure serapan yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa
Indonesia (2) unsur pinjaman/serapan yang pengucapan dan penulisannya
disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Golongan kedua inilah yang
disebut unsur serapan. Berikut ini disajikan cara penulisannya yang benar.
Aktivitas ( bukan aktifitas )
Akuntansi ( bukan akutansi )
Apotek ( bukan apotik )
Kuantitas ( bukan kwantitas )
E. penulisan Tanda Baca
Tanda titik (.)
Penggunaan tanda titik yang benar adalah sebagai berikut :
Ali Akbar, S.E.
dkk.
tsb.
Tanda koma (,)
Aturan penulisan tanda koma adalah sebagai berikut :
49
50
a. Tanda koma digunakan diantara unsur-unsur dalam suatu perincian,
misalnya :
Perpustakaan keluarga kami terdiri atas majalah, jurnal, surat kabar,
dan anggota.
b. Tanda koma digunakan pada kalimat majemuk setara perlawanan
mendahului kata penghubung perlawanan tetapi, namun, melainkan,
dan sedangkan, misalnya :
Saya bukan bekerja sebagai dokter, melainkan sebagai manajer.
c. Tanda koma digunakan di depan kata yang mengantarkan penegasan
atau perincian, seperti misalnya, seperti, contohnya, terutama, yaitu,
yakni, tepatnya, misalnya :
Tampaknya, pemeriksaan serius mulai diarahkan kepada kondisi
kampus, terutama mutu dan sikap akademik para sivitasnya.
d. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang
mendahului induknya. Biasanya anak kalimat di dahului oleh kata
penghubung ( oleh ) karena, jika, meskipun, apabila, supaya, agar,
selain, disamping, misalnya :
Akibatnya, lulusan perguruan tinggi tidak mudah mendapatkan
pekerjaan.
e. Tanda koma harus dipergunakan di belakang kata penghubung yang
menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain, misalnya :
Akan tetapi
Akhirnya
Dengan demikian
f. Tanda koma dipergunakan untuk mengapit keterangan tambahan dan
keterangan aposisiketerangan yang sifatnya saling menggantikan,
misalnya :
Paling tidak, kehadiran para pengusaha bias membuka wawasan baru
bagi kedua pihak, baik dari perguruan tinggi sendiri maupun dari
kalangan dunia usaha.
Tanda titik koma (;)
50
51
Tanda titik koma dapat dipergunakan untuk memisahkan kalimat yang
setara dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung,
misalnya :
Kegunaan kelapa banyak sekali, yaitu daging buah kelapa dapat dibuat
minyak goreng; sabut kelapa dibuat tali, sikat, keset, pemadani kasar;
tempurung kelapa dapat dijadikan kayu bakar dan menyetrika atau gayung.
Tanda titik dua (:)
a. Tanda titik dua dapat dipakai sebagai ganti kata yaitu atau yakni pada
akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerian berupa frasa atau
kalimat tidak lengkap, misalnya :
mahasiswa yang belajar di STMB sebagian besar berasal dari pulau
Jawa: Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Tanda hubung (-)
a. Tanda hubung boleh dipakai untuk memperjelas hubungan bagianbagian kata atau ungkapan, misalnya :
Ber-evolusi
b. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan afiks dengan kata
sebagaimana berikut :
Se-Jawa Barat
di-PTU- kan
Tanda pisah ( --- )
Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti
sampai dengan atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau
sampai misalnya :
Jakarta-Bandung
Tanda ellipsis ()
Tanda ellipsis digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu teks ada
bagian yang di hilangkan, misalnya, apabila, penulis mengutip bagianbagian tertentu dari teks orang lain.
51
52
52
53
Aplikasi Bahasa Indonesia Keilmuan
A. Laporan penelitian
Abstrak
Hasil penelitian yang bias diakses dan dibaca oleh seluruh
masyarakat pembaca pada era global seperti saat ini mengundang para
penulis untuk menyajikan artikelnya pada berbagi jurnal ilmiah.
Contohnya artikel berkadar ilmiah yang dipublikasikan adalah jurnal
Mimbar Pendidikan Universitas pendidikan Indonesia edisi tahun 20052006. Dari penelotian ini menunjukkan bahwa secara garis besar kadar
keilmiahan artikel pada jurnal Mimbar Pendidikan UPI memiliki kadar
keilmiahan yang tinggi dilihant dari isi artukel, organisasi, kosakata dan
istilah, pengembangan bahasa dan penggunaan aspek mekaniknya.
Latar belakang
Laporan majalah Asiaweek, edisi 30 Juni 2000 kembali memuat
77 peringkat universitas terbaik dikaswan Asia (Asias Best
University). Berdasarkan data statistik, publikasi ilmiah kita di tingkat
internasional, hanya menyumbang sebanyak 0,012% dari total
publikasi ilmiah dari seluruh dunia. Tampaknya suasan akademis di
perguruan tinggi di Indonesia hingga saat ini masih kurang kondusif.
Salah satu factor yang memprengaruhi kodisi tersebut berasal dari
lingkungan kerja peneliti, misalnya, terbatasnya sumber daya dan
sarana penelitian, keterbatasan informasi, situasi institusi yang tidak
stabil, kekurangan tenaga pendukung, dan lain-lain. Melihat kondisi
seperti itu, perguruan tinggi kita dalam memasuki millennium ketiga
ini mengalami berbagai tantangan. Sejak tahun 2003, kita harus sudah
mulai berkompetisi dengan Negara-negara di kawasan ASEAN
(AFTA). Barang dan jasa akan bebas keluar-masuk negara-negara
tersebut. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas pendidikan rata-rata
pendudukan merupakan suatu tantangan yang harus kita hadapi.
Dalam era reformasi seperti sekarang ini, focus pembangunan
53
54
diletakkan pada pembangunan ekonomi fan SDM seiring dengan
pembangunan ekonomi itu, pembangunan SDM inialah yang terkait
langsung dengan misi dan tanggung jawab universitas.
Kenyataan menunjukkan bahwa pada tahap ini kemampuan
universitas di Indonesia termasuk di dalamnya memproduksi dan
mempublikasikan
karya-karya
ilmiah
yang
berkualitas
belum
menunjukkan kemampuan seperti yabg diharapkan. Daya serap ini
sesungguhnya merupakan factor utama dari berbagai kesulitan
ketenagaan dewasa ini, dan bukannya masalah tidak siap pakai atau
tidak siap kerja. Keterkaitan program universitas dengan berbagai
kebutuhan ketenagakerjaan yang berkembang di pasaran kerja
sesungguhnya cukup memadai, manakala terdapat keseimbangan
antara produksi universitas dan daya serap ekonomi.
Rumusan masalah
Permasalahan yang menjadi focus penelitian ini dirumuskan
dalam satu pertanyaan besar yaitu: Bagaimana Kadar keilmiahan isi
artikel, organisasi artikel, kosakata, pengembangan bahasa dan
penggunaan aspek mekaniknya pada artikel Mimbar Pendidikan
UPI?
Tujuan peneliatian
Mengacu pada perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui: kadar keilmiahan isi artikel, organisasi
artikel, kosakata, pengembangan bahasa dan penggunaan aspek
mekanik artikel pada Mimbar Pendidikan UPI.
Manfaat penelitian
Hasil dan temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat:
a) Bagi dosen, hasil penelitian ini bias memberian informasi atau
pengetahuan tentang bentuk bahasa ilmiah sehingga bias
dijadikan acuan dalam menulis karya ilmiah.
b) Bagi pemimpin universitas, temuan penelitian ini bias
memberikan masukan untuk membuat kebijakan, khususnya
54
55
dalam menyajikan tuliasan ilmiah, baik pada jurnal tingkat
universitas nasional maupun internasional.
c) Bagi Ditjen Pendidikan Tinggi, hasil penelitian ini bias
dijadikan masukan tentang kualitas tulisan ilmiah di perguruan
tinggi sehingga bias menjadi materi untuk pijakan, evaluasi
dan rujukan dalam menentukan kualifikasi jurnal tingkat
nasional.
d) Bagi khalayak ramai, hasil penelitian ini bias memberikan
informasi tentang bentuk tulisan ilmiah sehingga mereka bisa
menerapkan pengetahuan tersebut.
e) Bagi penerbit, hasil penelitian ini sangat bermanfaat dalam
memberikan rambu-rambuatau indicator yang harus dipenuhi
dalam menulis karya ilmiah sehingga mereka lebih selektif
dalam menerima naskah dan memublikasikannya.
Kajian pustaka
Banyak masyarakat Indonesia hingga saat ini, di era millennium
masih memiliki budaya teks lisan tanpa terkecuali masyarakat kampus
yang notaben di anggap sebagai masyarakat ilmiah.
Menulis menurut Kurniawan (2006) merupakan salah satu dari
empat keterampilan berbahasa yang sudah menyedot perhatian banyak
pihak. Selain karena keterampilan menulis bisa dijadikan takaran
kemajuan literasi suatu bangsa, juga karena menulis itu belum begitu
membudaya, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, keterampilan
menulis ini ditilik sebagai keterampilan berbahasa yang paling sulit
dan kompleks karena masyarakat adanya keluasan wawasan dan
melibatkan proses berfikir yang ekstensif.
Metode penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Tujuannya
adalah untuk mendeskripsikan kadar keilmiahan isi tulisan, oganisasi
tulisan, kosakata dan istilah, pengembangan bahasa, dan aspek
55
56
mekanik tulisan/artikel yang dipublikasikan pada jurnal Minvar
Pendidikan UPI dan menggunakan model penilaian tulisan skala
interval untuk tiap tingkatan tertentu pada aspek yang diteliti/dinilai.
Pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dapat
dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
Petama, membaca keseluruhan artikel berulang-ulang untuk
mengukur kadar keilmiahan 5 unsur dan mengidentifikasikan
kelebihan dan kekurangan artikel tersebut.
Kedua, memilih artikel yang menunjukkan insikasi dari unsure
yang diukur sehingga akan diperoleh contoh tulisan yang
mewakili 5 unsur yang diukur.
Ketiga, seluruh artikel yang terpilih dibaca ulang dan dinilai
dengan mengacu pada instrument penilaian yang sudah di
siapkan.
Keempat, hasil dari identifikasi kelima unsur tersebut
kemudian dimasukkan dalam daftar isian sesuai dengan
kelompok unsurnya.
Kelima, pengecekan ulang nilai dan unsure-unsur yang sudah
dimasukkan sesuai kelompokknya untuk menghindari adanya
kesalahan
dalam
memasukkan
data
karena
salah
pengelompokan.
Hasil penelitian dan pembahasan
Dalam bab ini disajikan hasil oenelitian dan pembahasan berupa
kadar keilmiahan tulisan yang dipublikasikan pada jurnal Mimbar
Pendidikan edisi tahun 2005-2006. Data yang terkumpul mencangkup
5 unsur yang menunjukkan kadar keilmiahan yaitu: (1) kadar
keilmiahan isi artikel, (2) kadar keilmiahan organisasi artikel, (3)
kadar keilmiahan kosakata dan istilah, (4) kadar keilmiahan
pengembangan bahasa, dan (5) kadar keilmiahan aspek mekanik.
Sealin hal-hal yang sudah disebutkan di atas, hasil analisis data dan
interpretasinya juga dibahas pada bab ini.
a. Deskripsi hasil penelitian
1. Kadar keilmiahan isi tulisan
56
57
Model analisis yang digunakan pada program English as
a second Language (ESL) diaplikasikan dalam analisis data.
Dari hasil analisis bisa dijelaskan bahwa skor rata-rata untuk
kadar keilmiahan isi tulisan yang dipublikasikan pada jurnal
Mimbar Pendidikan periode 2 tahun sebesar 26. skor ini
mengandung arti bahwa kadar keilmiahan isi tulisan yang
publikasikan pada jurnal Mimbar Pendidikan UPI tergolong
dalam rentang 22-26. Rentang skor seperti ini menunjukkan
katagori cukup baik. Dengan kata lain kadar keilmiahann isi
tulisan yang dipublikasikan pada jurnal Mimbar Pendidikan
tersebut dapat memberikan informasi yang cukup memadai
kepada pembaca karena pembaca bisa memperoleh informasi
sesuai mereka harapkan. Substansi isi yang disampaikan juga
sudah cukup meskipun pengembangan tesisnya masih terbatas
dan kurang lengkap. Dilihat dari isinya hampir seluruh artikel
menjadi subjek penelitian ini disampaikan relevan dengan
permasalahan yang ada meskipun masih kurang lengkap.
2. Kadar keilmiahan organisasi tulisan
Berdasarkan hasil analisi data diperoleh skor rata-rata
untuk kadar kailmiahan organisasi tulisan yang dipublikasikan
pada jurnal Mimbar Pendidikan adalah sebesar 18. Skor ratarata ini menunjukkan bahwa kadar keilmiahan organisasi
tulisan yang dipublikasikan pada jurnal Mimbar Pendidkan
UPI termasuk ke dalam rentang skor 18-20, yang berarti sangat
baik-sempurna. Skor tersebut memiliki arti bahwa kadar
keilmiahan organisasi tulisan jurnal yang dipublikasikan pada
Mimbar Pendidkan diekspresikan dengan lancer, gagasab
diungkapkandengan jelasdan tertatadengan baik, dan urutan
kalimatnya logis dan kohesif.
57
58
Dari artikel ini, bisa dilihat beberapa indikasi yang jelas
dan menunjukkan kadar keilmiahan yang tinggi dilihat dari
organisasi tulisan tersebut.
Pertama, penulis memulai dari pengenalan terhadap
produk-produk teknologi informasi dan komunikasi
yang
canggih
dan
bisa
diterapkan
dalam
pengembangan pendidikan.
Kedua, penulis secara logis menerangkan macammacam program yang ditawarkan media ITC dan
sekaligus menyampaikan beberapa hal yang tidak bisa
dilanggar atau dihindari oleh pengguna dalam
manggunakan media tersebut.
Ketiga, karena subtopic disajikan pada urutan yang
logis maka keruntutan antarparagraf juga terlihat dari
tulisan tersebut sehingga tidak ada uraian yang kelar
dari konteks yang sedang ditulisnya.
3. Kadar keilmiahan kosakata
Menurut analisis data diperoleh skor rata-rata kadar
keilmiahan kosakat yang digunakan dalam artikel jurnal
Mimbar Pendidkan adalah sebesar 17. Berdasarkan hasil ratarata skor ini menunjukkan bahwa kadar keilmiahan kosakata
yang digunakan dalam jurnal yang dipublikasikan pada jurnal
Mimbar Pendidkan termasuk ke dalam rentang skor 14-17 atau
tergolong ke dalam katagori cukup baik. Angka tersebut
menunjukkan arti bahwa kadar keilmiahan kosakata yang
dipakai dalam tulisan jurnal telah memanfaatkan potensi kata
(daya ungkap kosakat) dan istilah kata yang dipilih kadangkadang kurang tepat meskipun tidak mengganggu maksud
tulisan.
Dengan demikian, seorang penulis harus paham dan teliti
sebelum memsukkan kosakata serapan ke dalam tulisannya, hal
ini penting untuk menghindari makna yang rancu atau bias.
58
59
Kerancuan
makna
kosakata
atau
istilah
pada
kalimat
disebabkan oleh pengunaan kosakata dan istilah asing
(unfamiliar) berkali-kali pada satu kalimat.
4. Kadar keilmiahan pengembangan bahasa
Dari hasil analisis data diperoleh skor rata-rata untuk
kadar keilmiahan pengembangan bahasa yang digunakan dalam
tulisan jurnal yang dipublikasikan pada jurnal Mimbar
Pendidkan adalah sebesar 21, skor rata-rata ini menunjukkan
bahwa kadar keilmiahan pengembangan bahasa termasuk ke
dalam rentang skor 18-21, atau tergolong ke dalam katagori
cukup baik. Katagori cukup baik untuk kadar keilmiahan
pengembangan bahasa mempunyai beberapa criteria di
antaranya:
tulisan
jurnal
Mimbar
Pendidkan
memiliki
konstruksi kalimat yang sederhana tetapi efektif. Meskipun
demikian, masih dijumpai beberapa kesalahan kecil pada tata
kalimat yang kompleks dan terjadi sejumlah kesalahan lainnya
dalam kalimat. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa
pengembangan bahasa yang kurang tepat dengan kaidah
sintaksis menyebabkan kalimat kurang efektif dan komunikatif
yang akhirnya bisa menimbulkan kesalahan interpretasi
terhadap tulisan tersebut.,
5. Kadar keilmiahan aspek mekanik
Merujuk pada hasil analisis data diperolehskor rata-rata
untuk kadar keilmiahan aspek mekanik yang digunakan dalam
tulisan jurnal Mimbar Pendidkan adalah sebesar 5. Hasil skor
rata-rata ini mempunyai arti bahwa kadar keilmiahan aspek
mekanik yang digunakan dalam tulisan jurnal Mimbar
Pendidkan termasuk katagori sangat baik-sempurna. Katagori
ini menunjukkan bahwa para penulis artikel jurnal tersebut
sudah mengerti bahkan menguasai pedoman penulisan karya
ilmiah sehingga hanya ditemukan kesalahan kecil yaitu
59
60
beberapa kesalahan penulisan ejaan dan tanda baca saja. Hal ini
dapat membantu para pembaca dalam memahami isi artikel.
Dan selain itu, para pembaca merasa nyaman dan enak
membacanya.
Pembahasan hasil penelitian
Setelah menganalisis data dan interpretasinya, ada beberapa
temuan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini telah diketahui
kadar keilmiahan tulisan jurnal yang dipublikasikan pada Mimbar
Pendidkan yang meliputi kadar keilmiahan isi tulisan, organisasi,
kosakata, pengembangan bahasa dan aspek mekanik. Kadar
keilmiahan pengembangan bahasa yang digunakan masuk ke dalam
katagori cukup baik karena menggunakan konstruksi kalimat yang
sederhana tetapi efektif. Walaupun masih ditemukan penggunaan
konstruksi kelimat kompleks dan panjang, kesalahan kecil tersebut
tidak mengaburkan makna. Dan kadar keilmiahan aspek mekanik
tulisan masuk ke dalam katagori sangat baik-sempurna kareba para
penulis artikel/jurnal Mimbar Pendidkan telah menguasai atura
penulisan ilmiah dan hanya terdapat beberapa kesalahan pengunaan
ejaan dan tanda baca.
Simpulan dan saran
a. Simpulan
dari hasil analisis data dan pembahsan terhadap
kilmiahana tulisan/artikel jurnal yang dipublikasikan pada
Mimbar Pendidkan dapat disumpulkan sebagai berikut:
Petama, kadar keilmiahan isi tulisan jurnal pada Mimbar
Pendidkan adalah sebesar 26. Berdasarkan hasil skor ratarata ini dapat disimpulkan bahwa kadar keilmiahan isi
tulisan jurnal Mimbar Pendidkan tergolong dalam rentang
22-26 atau masuk ke dalam katagori cukup baik. Hal ini
berarti informasi yang disampaikan sudah cukup, hanya
pengembangan tesisnya masih terbatas. Isi yang di
60
61
sampaikan relevan dengan permasalahan yang ada tetapi
masih kurang lengkap.
Kedua, kadar kailmiahan organisasi tulisan jurnal Mimbar
Pendidikan
adalah
sebesar
18.
Skor
rata-rata
ini
disimpulkan bahwa kadar keilmiahan organisasi tulisan
jurnal Mimbar Pendidkan UPI termasuk ke dalam rentang
skor 18-20, yang berarti sangat baik-sempurna. Hal ini
berarti gagasan yang diungkapkan sangat jelas dan tertata
dengan baik dan urutan kalimatnya logis, runut dan runtun.
Ketiga, kadar keilmiahan kosakat yang digunakan dalam
artikel jurnal Mimbar Pendidkan adalah sebesar 17.
Berdasarkan hasil rata-rata skor ini menunjukkan bahwa
kadar keilmiahan kosakata yang digunakan dalam jurnal
Mimbar Pendidkan termasuk ke dalam rentang skor 14-17
atau tergolong ke dalam katagori cukup baik. Hal ini berarti
bahwa
kosakat
yang
dipilih
dan
digunakan
telah
memanfaatkan potensi kata dan daya ungkap yang canggih
meskipun masih ada penggunaan kata dan uangkapan yang
kadang-kadang kurang tepat tetapi tidak mengganggu
maksud tulisan.
Keempat, kadar keilmiahan pengembangan bahasa dalam
tulisan jurnal Mimbar Pendidkan adalah sebesar 21.
Berdasarkan skor rata-rata ini menunjukkan bahwa kadar
keilmiahan pengembangan bahasa termasuk ke dalam
rentang skor 18-21, atau tergolong ke dalam katagori cukup
baik. Hal ini berarti bahasa yang digunakan memiliki
konstruksi kalimat yang sederhana tetapi efektif, terdapat
kesalahan kecil pada kontruksi kalimat yang kompleks, dan
terjadi sejumlah kesalahan lain dalam kalimat tetapi tidak
mengaburkan maknanya
Kelima, kadar keilmiahan aspek mekanik yang digunakan
dalam tulisan jurnal Mimbar Pendidkan adalah sebesar 5.
61
62
Hasil skor rata-rata ini mempunyai arti bahwa kadar
keilmiahan aspek mekanik yang digunakan dalam tulisan
jurnal Mimbar Pendidkan termasuk katagori sangat baiksempurna. Hal ini berarti bahwa penulis telah menguasai
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, khususnya artikel pada
jurnal ilmiah meskipun terdapat beberapa kesalahan
penulisan ejaan dan tanda baca.
b. Saran-saran
Dari temuan dan simpulan hasil penelitian ini, ada
beberapa hal yang perlu disarankan sebagai berikut:
Pertama, kadar keilmiahan artikel Mimbar Pendidkan yang
tergolong cukup baik meliputi isi tulisan, kosakata dan
pengembangan bahasa hendaknya perlu di kembangkan
secara maksimal.
Kedua, kadar keilmiahan artikel Mimbar Pendidkan yang
berkadar sangat baik-sempurna yang meliputi organisasi
dan aspek hendaknya ditingkatkan supaya tidak ditemukan
kesalahan pada seluruh aspek.
Ketiga, penulis hendaknya mengerti dan memerhatikan
aspek kebahasaan dan non kebahasaan supaya memiliki
kadar keilmiahan yang tinggi sesuai dengan tuntutan
kualitas tang sudah ditetapkan.
Keempat, tim penyunting sebaiknya lebih selektif dan teliti
agar terjaga dan terjamin kualitas dan kadar keilmiahannya.
Kelima, peningkatan kualitas artikel bukan merupakan
tanggung jawab dosen/peneliti, editor semata tetapi peran
serta pemimpin universitas selaku pengambil kebijakan
juga sangat penting.
B. Jurnal ilmiah
Abstrak
Perguruan tingg sebagai subsistem pendidikan asional mempunyai
misi menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki
kemampuan akademik atau professional serta mengembangkan dan
62
63
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan
nasional.
Pendahuluan
Masyarakat Indonesia baru yang kita cita-citakan adaah
masyarakat yang terbuka, artinya komunikasi antar manusia dalam
berbagai arena kehidupan akan bebas dari hambatan, tekanan atau
represif. Dalam bidang bisnis, misalnya, hambatan dalam berbagai
tarif semakin dipermudah dan bukan tidak mungkin seluruhnya akan
dihilangkan. Dalam bidang social-politik, arus demokratisasi dan
HAM sedang melanda berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia
sekarang dan di masa depan.
Untuk menuju masyarakat Indonesia baru sebagaimana di
kemukakan diatas, pendidikan nasional kita terutama perguruan tinggi
setidaknya menghadapi empat tantangan besar kompleks yaitu:
o Pertma, tantangan untuk meningkatkan nilai tambah
dalam rangka meningkatkan produktivitas nasional,
pertmbuhan dan pemerataan ekonomi, sebagai upaya
untuk memlihara dan meningkatkan pembangunan
berkelanjutan.
o Kedua, tentangan untuk melakukan pengajian dan
penelitian secara komprehensif dan mendalam terhadap
terjadinya
transformasi
struktur
masyarakat
dari
tradisional ke modern dari agraris ke industry dan
imformasi
serta
bagaimana
implikasinya
bagi
pengembangan sumber daya manusia di perguruan
tinggi.
o Ketiga, tantangan dalam persaingan global yang semakin
ketat, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing bangsa
dalam menghasilkan
karya-karya
yang
berkualitas
unggul sebagai hasil penguasaan ipteks dan informasi.
63
64
o Keempat, munculnya kolonialisme baru di bidang ipteks,
informasi
dan
ekonomi
untuk
menggantikan
kolonialisme politik
Semua tantangan tersebut menuntut sumber daya manusia
Indonesia khususnya masyarakat akademik perguruan tinggi agar
meningkatkan serta memperluas wawasan pengetahuan, wawasan
keunggulan,
keahlian
yang
professional,
serta
keterampilan
manajerial dan kualitasnya.
Misi perguruan tinggi
Perguruan tinggi sebagai
subsistem
pendidikan
nasional
mempunyai misi k-umum sebagaimana tercantum dalam pasal 2
Peraturan Pemerintah nomer 60 Tahun 1999, yaitu: (1) menyiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
akademik
dan/atau
professional
yang
dapat
menerapkan,
mengembangkan, dan/atau menciptakan ipteks, (2) mengembangkan
dan menyebarluaskan ipteks serta mengupayakan penggunaannya
untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya
kebudayaan nasional. Kiprah itu meletakkan perguruan tinggi sebagai
titi strategis pembangunan nasional dan sebagai aset nasional yang
harus terus tumbuh dan berkembang.
Profil keluaran perguruan tinggi
Profil sumber daya manusia Indonesia yang merupakan keluaran
(output dan outcomes) perguruan tinggi harus mengandung dimensidimensi berikut:
Beriman dan bertakwa
Memiliki jati diri Indonesia
Menguasai ipteks dan budaya sebagai kebudayaan menusia
modern
Bersikap demokratis
Memiliki tanggung jawab social
Memiliki kepercayaan diri sebagai warga Negara dari suatu
Negara merdeka
64
65
Bersikap kreatif dan kritis
Transformasi pendidikan dan pengajaran
Misi pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi yang
sekarang berjalan mau tidak mau harus bertansformasi, manakala
keluaran PT di masa depan ampu menunjukkan profilnya sebagai
manusia Indonesia baru. Hal ini harus kita kritis dan cermati,
sehingga dalam waktu dekat pemerintah tidak hanya melakukan
bongkar pasang terhadap sejumlah teori dan kebijakan pendidikan.
Akan tetapi, yang paling penting adalah menetapkan standart, filsofi
dan dasar yang jelas untuk dijadikan sebagai garis haluan bagi semua
jajaran pendidikan dan diperlukan strategi yang tepat untuk
mewujudkannya.
Demikian pula laporan suatu komisi UNESCO (1996, dalam
Tilaar, 1997: 7-8) tentang Learning: The Treasure Within, bahwa
pendidikan dan pembelajaran pada abad ke 21 sekarang harus di
dasarkan pada 4 pilar, yaitu:
1) Learning to think : Dalam belajar berfikir ditunjukkan bahwa
arus informasi yang begitu cepat berubah dan semakin lama
semakin banyak tidak mungkin lagi dikuasai oleh manusia
karena kemampuan otaknya yang terbatas.
2) Learning to do : Menuju Indonesia baru, pendidikan tinggi
menuntut manusia yang bukan hanya dapet berfikir melaikan
juga manusia yang dapat berbuat (to do). Dengan berbuat
manusia
dapat
menciptakan
produk-produk
baru
dan
meningkatkan kualitasproduk-produk tersebut.
3) Learning to be : Belajar untuk mengaktualisasi diri. Artinya,
setiap manusia di muka bumi ini secara sadar belajar bagaimana
untuk tetap hidup sebagai individu dengan kepribadian yang
memiliki pertimbangan dan tanggung jawab pribadi, social dan
moral.
4) Learning to live together : Dunia yang semakin mengecil dan
semakn bersatu akan mendekatkan kelompok-kelompok dan
65
66
anggota masyarakat, kelompok etnis, kelompok budaya/tradisi,
kelompok agama dan kelompok bangsa semakin dekat satu sama
lain.
Transformasi riset dan publikasi ilmiah
Rendahnya produktivitas riset di Indonesia tercermin dari
rendahnya publikasi ilmiah dalam skala internasional. Berdasarkan
data statistic, publikasi ilmiah di tingkat internasional, publikasi dari
Indonesia hanya menyumbang sebanyak 0,012% dari total publikasi
ilmiah dari seluruh dunia Santoso, 1997: 3). Hal ini jauh lebih rendah
dibandingkan dengan Negara-negara tetangga kita, seperti Thailand
(0,086%), Malaysia (0,064%), Singapure (0,179%), dan Filipina
(0,035%). Sementara itu, kontribusi terbesar diduduki oleh Negaranegara maju seperti USA (30,8%) Jepang (8,2%), UK (7,9%), Jerman
(7,2%) dan Prancis (5,6%).
Berdasarkan UU nomer 6 Tahun 1989, yang telah diubah dengan
UU Nomer 13 Tahun 1997, setiap hasil penemuan baru yang di
lakukan dosen/peneliti di perguruan tinggi dapat dipatenkan. Namun,
tidak semua hasil penemuan dapat di patenkan. Paten hanya dapat
diebrikan untuk penemuan baru yang mangandung langkah inventif
dan dapat dapat diterapkan dalam industry. Artinya, hasil penemuan
itu dapat di produksi atau digunakan dalam berbagai kegiatan
industry. Dengan demikian, karya ilmiah (penemuan) yang dimiliki
perguruan tinggi tidak menjadi dokumen mati atau menjadi arsip yang
tersimpan rapi di rak-rak pustaka. Publikasi ilmiah (apalagi yang
dipatenkan) merupakan indicator serta barometer kualitas secara
keunggulan perguruan tinggi yang bersangkutan.
Transformasi institusi perguruan tinggi
Pembangunan kualitas SDM yang dibebankan kepada setiap
perguruan tinggi menunjukkan komitmen masyarakat, pemerintah,
wakil-wakil rakyat di legislative dan bangsa Indonesia secara
keseluruhan dalam mengejar ketertinggalan dan keunggulan di era
66
67
persaingan global. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan
trasformasi institusi perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah
merupakan bagian yang sangat mendasar dan esensial dalam
pengembangan sumber daya manusia ini. Hal ini berarti perguruan
tinggi mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia
baru.
Simpulan dan saran
Transformasi perguruan tinggi hanya bersifat fragmentaris tetapi
harus bersifat sistemik, sistematik dan mendasar terhadap hal-hal
berikut: (1) pembaruan manajemen kelenbagaan perguruan tinggi, (2)
kualitas akademik yang mencangkup pendidikan dan pengajaran, riset
dan publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat, (3)
meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, kualitas, akuntabilitas
dan efisiensi perguruan tinggi dengan berbagai kebutuhan dan
tuntutan yang berkembang di masyarakat, dan (4) meningkatkan
peran perguruan tinggi dalam skala internasional.
C. Makalah
Mobile Communication dan
Masa Depan Peekonomian Nasional
Regis McKenna (Real Time, 1997) menyatakan bahwa semua bisnis
di era informasi ini apapun produknya akan menjadi bisnis pelayanan
(service) sebab para pelanggan akan mengatakan apa kebutuhan mereka
serta cara yang diinginkan mereka untuk memuaskan kebutuhan tersebut.
Davis Siegel dalam bukunya Futurize Your enterprise (1999)
mengungkapkan ihwal revolusi di dunia manajeman organinsasi. Siegel
mengatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan untuk dapat
memenangkan
persaingan
harus
bersifat
customer-led,
bukan
management-led. Artinya, perusahaan harus membuat barang atau
memberikan service berdasarkan keperluan pelanggan, bukan berdasarkan
67
68
pada apa yang dapat manajemen perbuat. Dari dua pendapat pakar tersebut
menyiratkan pentingnya komunikasi dan informasi bagi suatu perusahaan
yang ingin berhasil dalam persaingan global.
Mobile Communication
Penerapan mobile communication ini menciptakan mobile office
(m-office) dan m-commerce. Perusahaan menerapkan m-office ini
terutama untuk bagian yang berhubngan langsung dengan customer,
seperti bagian pemasaran atau customer service. Tujuannya adalah
untuk membuat mereka lebih dekat dengan customer sehingga
mengetahui keinginan dan kemauan customer kapanpun dan
dimanapun, sehingga pelayananpun dapat diberikan dengan sesegera
mungkin.
M-Commerce dan Perkembangan Nasional
Karena M-Commerce pada dasarnya yaitu memungkinkan setiap
orang melakukan aktivitas bisnis tanpa batas waktu dan batas wilayah.
Paradigma
perdagangan
inipun
mampu
meniadakan
peran
middleman seperti peran pemasaran, distributor, dan memangkas
kebutuuhan infrastruktur fisik seperti kantor, gudang, toko dan
karyawan dalam jumlah banyak yang selama ini menjadi hambatan
pelaku usaha baru, kecil atau menengah untuk menjadi pelaku bisnis
berskala global.
Pada saat ini, banyak pengusaha kecil dan menengah Indonesia
yang mulai mengekspor produknya setelah menjalin hubungan dengan
pembeli dari luar negeri yang membaca situs promosi perusahaan
Indonesia di internet. Dengan adanya teknologi komunikasi secara
GPRS (General Packet Radio System), para pengusaha Indonesia
dapet berjualan melalui internet ini secara mobile dari mana saja
mereka berada, baik di jalan, dirumah atau sedang berada di tempat
berlibur sekalipun, baik pagi, siang, sore, maupun malam asal ponsel
atau PDA (Personal Digital Assistance), atau notebooknya diaktifkan,
68
69
mereka akan selalu terhubung ke internet dan merekapun dapat
melakukan transaksi bisnis.
D. Artikel ilmiah
Meningkatkan Kemampuan Rakyat untuk
Menjadi Tuan di Negeri Sendiri
Pada tahun 1999, hasil studi Human Development Index (HDI) yang
dilakukan
oleh
UNDP,
badan
PBB
yang
menangani
program
pembangunan, menunjukkan data yang sangat memprihatinkan mengenai
daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia.
Ada 3 indikator yang digunakan oleh UNDP guna menentukan
peringkat SDM tersebut. Pertama, kategori rata-rata tingkat pendidikan di
suatu Negara. Kedua, kualitas kesehatan di suatu Negara, yang
dicerminkan oleh tingkah laku atau jumlah harapan hidup bayi dalam
suatu Negara. Ketiga, pendapatan rata-rata penduduk di suatu Negara
karena pendapatan ini menentukan tingkat kosumsi seseorang.
Dibidang pendidikan, laporan Asiaweek, edisi 23 April 1999 tentang
The Best Universities in Asia memaparkan peringkat empat universitas
negeri di Indonesia tidak mencapai peringkat 60 di kawasan Asia. Kondisi
rakyat Indonesia yang dipaparkan di atas sungguh sangat memprihatinkan,
apalagi prestasi buruk tersebut dialami pada saat Indonesia belum
mengalami krisis seperti sekarang ini. Kalau multikrisis yang telah
berjalan kurang lebih 5 tahun ini tidak cepat ditanggulangi, maka dapat
dipastikan ranking daya saing SDM kita akan terus meluncur ke deretan
paling bawah.
Perlu Transformasi, Kebersamaan dan Kemandirian
Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas rakyat Indonesia
dari keterpurukan ini harus dilakukan suatu transformasi, baik
transformasi budaya. Untuk terjadinya transformasi budaya dan social
yang paling penting yang harus disiapkan adalah manusianya.
69
70
Kehidupan rakyat Indonesia harus diarahkan pada terciptanya
suatu masyarakat madani (civil society), yaitu suatu masyarakat yang
mengenal akan hak dan kewajiban tiap-tiap anggota dan secara
bersama-sama bertanggung jawab terhadap kesejahteraan lingkup
masyarakatnya sendiri.
Meningkatkan Daya Saing
Pendidikan, merupakan salah satu sarana strategis untuk
meningkatkan daya saing rakyat Indonesia. Oleh karena itu,
pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya pada semua jenjang dan
jenis. Sebab, kalau tidak, kualitas SDM akan semakin terpuruk, yang
pada gilirannya akan membuat bangsa kita semakin tertinggal.
Bangsa yang mempunyai kualitas SDM tinggi dan unggul akan
berada di garda terdepan dan dapat memimpin dunia ini dan juga
sebaliknya. Oleh karena itu bangsa yang mempunyai kualitas SDM
unggul akan menjadi penentu bagi jalannya kehidupan ekonomi,
politik, dan militer dunia.
Di samping meningkatkan daya saing melalui pendidikan, rakyat
Indonesia harus mengupayakan melalui MPR dan DPR untuk
mencegah terjadinya penguasaan asset-aset rakyat oleh oihat asing,
seperti terjadinya privatisasi perusahaan pemerintah yang mengelola
sumber-sumber pengidupan dan penghasilan bangsa, seperti BUMN
dan BUMD yang mengelola minyak, telekomunikasi, sdan sumber
alam lainnya.
E. Artikel ilmiah popular
Problema Perbukuan dan Tradisi Membaca Kita
Buku menjadi sarana pokok untuk menyimpan dan menyebarluaskan
khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) serta informasi.
Kenyataan menunjukkan menunjukkan betapa tertinggalnya Indonesia
dalam industry perbukuan. Hal ini terlihat dari hasil penelitian Gibbs,
dalam bukunya Scientific America (1995). Amerika Serikat menduduki
peringkat pertama dari produksi baru ilmu dan teknologi di dunia
70
71
(30,817%), diikuti Jepang (8,224%), Inggris (7,934%), Jerman (7,184%),
dan Perancis masih di atas lima persen (5,302%). Semantara itu, Belanda
kendatipun terbilang Negara kecil, ternyata masih memproduksi buku
sekitar 2,285%.
Membaca buku
Salah satu hasil penelitian di Amerika Serikat menyatakan bahwa
hanya 5% waktu belajar yang digunakan peserta didik untuk bertatap
muka dengan guru sedangkan sisanya digunakan untuk membaca
buku, baik di kelas/sekolah, perpustakaan, maupun dirumah.
Kegiatan baca-tulis merupakan komunikasi yang tidak langsung
dan bukan merupakan bawaan sejak lahir. Oleh karena itu, pendidikan
baca-tulis harus dipelajari secara sistematis dan sistemik. Pembelajaran
ini melibatkan berbagai variable yang saling terkait, yaitu siswa, guru,
system, bahan ajar (buku), penulis/penerjemah/penyunting, penerbit,
toko buku, dan masyarakat pembaca itu sendiri.
Masyarakat informasi
Masyarakat kita yang belum mampu menampung informasi
secara layak, bukan saja masyarakatan yang berpendidikan rendah,
melainkan juga sebagain besar dari kalangan professional, seperti
dokter, giri, dosen, hakim, insinyur, pengacara dan lain lain juga belum
mampu menampung volume informasi yang layak sesuai dengan
tuntutan profesi yang mereka pilih.
Pada awal abad ke 21 ini, kita merasakan semakin sulit
membedakan
antara masa
kanak-kanak dengan msa dewasa.
Kecenderungan ini terutama disebabkan oleh memudarnya kualitas
budaya baca kita. Berbagai hasil penelitian di Negara maju
menunjukkan, anak-anak sekolah dasar menonton televise (TV) ratarata 30 jam per minggu.
Pengetahuan mereka tidak lagi bersumber dari wacana-wacana
yang terhimpun dan tersimpan dalam cagar pustaka (buku, majalah,
71
72
dan surat kabar), tetapi dari TV. Daya ingat manusia amat terbatas,
sehingga informasi lisan itu jarang dapat diulang dengan tepat. Karena
itulah informasi lisan sukar sekali, bahkan tidak dapat dijadikan
referensi/acuan. Masyarakat dan bangsa Indonesia baru dituntut untuk
menjadi mesyarakat yang berbudaya dan berperadaban serta gemar
membaca, masyarakat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan
kemandirian yang di dukung oleh budi pekerti luhur dan kearifan yang
memadai.
DAFTAR PUSTAKA
Kurniawan khaerudin. 2012. Bahasa Indonesia Keilmuan untuk Perguruan Tinggi.
Bandung: PT Refika Aditama.
72
73
73
Anda mungkin juga menyukai
- Bahasa Jepang untuk Pemula (Revisi)Dari EverandBahasa Jepang untuk Pemula (Revisi)Penilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (7)
- Bahasa Indonesia Dalam Komunikasi IlmiahDokumen10 halamanBahasa Indonesia Dalam Komunikasi IlmiahRiamahBelum ada peringkat
- Bi Komunikasi IlmiahDokumen8 halamanBi Komunikasi IlmiahPabianus RampeanBelum ada peringkat
- Materi Ragam Dan Variasi BahasaDokumen22 halamanMateri Ragam Dan Variasi BahasaGiovanni TakeneBelum ada peringkat
- Ragam Dan Laras Bahasa Buku Bahasa Indonesia UNMULDokumen5 halamanRagam Dan Laras Bahasa Buku Bahasa Indonesia UNMULfemi selavinaBelum ada peringkat
- Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah MAKALAHDokumen17 halamanBahasa Indonesia Ragam Ilmiah MAKALAHexx ilacBelum ada peringkat
- Pam0042 02 Ragam BahasaDokumen11 halamanPam0042 02 Ragam BahasaHeto AldianoBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa IndonesiaDokumen8 halamanTugas Bahasa IndonesiaMar'atus ShifaBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa Indonesia Kelompok 4Dokumen5 halamanMakalah Bahasa Indonesia Kelompok 4Nurfitra AuliaBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa Indonesia 1 RombelDokumen45 halamanMakalah Bahasa Indonesia 1 RombelIkdaBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa Indonesia Kelompok 2Dokumen11 halamanTugas Bahasa Indonesia Kelompok 2Aldy RahmanBelum ada peringkat
- Laras Dan Ragam BahasaDokumen4 halamanLaras Dan Ragam BahasaRijki HardiyantiBelum ada peringkat
- Ragam BahasaDokumen9 halamanRagam BahasarizalBelum ada peringkat
- Pengertian Ragam BakuDokumen3 halamanPengertian Ragam BakuMuhammad FajriBelum ada peringkat
- Tugas Laporan Observasi Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanTugas Laporan Observasi Bahasa IndonesiaYUDI ANUGRAH PRATAMABelum ada peringkat
- Ragam BahasaDokumen4 halamanRagam BahasaChaBelum ada peringkat
- Power Point Ejaan Bahasa IndonesiaDokumen14 halamanPower Point Ejaan Bahasa IndonesiaAna Mustafa100% (1)
- Ragam Bahasa, Tata Tulis Dan KutipanDokumen32 halamanRagam Bahasa, Tata Tulis Dan KutipanShantie ChanBelum ada peringkat
- Bab Ii Bahasa Indonesia Ragam IlmiahDokumen2 halamanBab Ii Bahasa Indonesia Ragam IlmiahstudentwhostudyinghardBelum ada peringkat
- Ragam BahasaDokumen10 halamanRagam BahasaFadhel M. Al-GhifaariBelum ada peringkat
- 381-Article Text-758-1-10-20200128Dokumen8 halaman381-Article Text-758-1-10-20200128Leni ImbiriBelum ada peringkat
- MAKALAH RAGAM BAHASA INDONESIA Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia DosenDokumen3 halamanMAKALAH RAGAM BAHASA INDONESIA Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Bahasa Indonesia Dosenindri riskiBelum ada peringkat
- B IndoDokumen6 halamanB Indovictoryprinting07Belum ada peringkat
- Mku Bahasa Indonesia1. Hakikat Bahasa PDFDokumen6 halamanMku Bahasa Indonesia1. Hakikat Bahasa PDFAde RiskiantoBelum ada peringkat
- Tugas Laras Bahasa KuliahDokumen2 halamanTugas Laras Bahasa KuliahFebriyani ThesarianaBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa Indonesia: Ragam BahasaDokumen7 halamanMakalah Bahasa Indonesia: Ragam BahasafaisaltwuskaBelum ada peringkat
- Ragam Bahasa IndonesiaDokumen20 halamanRagam Bahasa IndonesiaRizkiana LutfiBelum ada peringkat
- MateriDokumen4 halamanMateriDINDA HUMAIRABelum ada peringkat
- Makalah Bahasa IndonesiaDokumen6 halamanMakalah Bahasa IndonesiaIreneLightBelum ada peringkat
- Variasi Ragam Bahasa Dalam Kehidupan RemajaDokumen8 halamanVariasi Ragam Bahasa Dalam Kehidupan RemajaFirda FibrianaBelum ada peringkat
- Ragam Dan Laras BahasaDokumen5 halamanRagam Dan Laras BahasaIraa AmaliaaBelum ada peringkat
- Uas PluDokumen10 halamanUas PluJoko SujarwoBelum ada peringkat
- Bahasa, Dialek Dan VariasiDokumen8 halamanBahasa, Dialek Dan VariasiFaridawati Fiay100% (3)
- Contoh Makalah Ragam Bahasa IndonesiaDokumen12 halamanContoh Makalah Ragam Bahasa IndonesiaMas BrengosBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa Indonesia Ragam BahasaDokumen21 halamanMakalah Bahasa Indonesia Ragam BahasaDifa Alya100% (1)
- Linguistik Dan SosiolinguistikDokumen13 halamanLinguistik Dan SosiolinguistikismaBelum ada peringkat
- CJRDokumen12 halamanCJRRiadil JannahBelum ada peringkat
- Ragam BahasaDokumen2 halamanRagam BahasaFathurrohim AbdullahBelum ada peringkat
- Ismail UAS Ilm LughahDokumen9 halamanIsmail UAS Ilm LughahIsmailBelum ada peringkat
- Pengertian Bahasa Indonesia Ilmiah FixDokumen30 halamanPengertian Bahasa Indonesia Ilmiah FixPutu EprilianiBelum ada peringkat
- Ragam BahasaDokumen9 halamanRagam BahasaNovi taBelum ada peringkat
- Bhs Indo RagamDokumen15 halamanBhs Indo RagamAndi Murni Nurul MaulidyahBelum ada peringkat
- Bahasa Indonesia - Chapter 2 - Ragam Dan Laras BahasaDokumen12 halamanBahasa Indonesia - Chapter 2 - Ragam Dan Laras Bahasanurul hotimahBelum ada peringkat
- Bab Ii Ragam Bahasa IndonesiaDokumen7 halamanBab Ii Ragam Bahasa IndonesiaZuniar Kamaluddin MabruriBelum ada peringkat
- Nicholassetiawan - Tugas Resume Mengenai Ragam Bahasa IndonesiaDokumen5 halamanNicholassetiawan - Tugas Resume Mengenai Ragam Bahasa IndonesiaNicholas Setiawan SaputraBelum ada peringkat
- BAB I BindoDokumen20 halamanBAB I BindohanifBelum ada peringkat
- Ringkasan Bahasa IndonesiaDokumen3 halamanRingkasan Bahasa Indonesiarahmat3223tullahBelum ada peringkat
- Modul 2 Bahasa Indonesia Laras Bahasa BakuDokumen28 halamanModul 2 Bahasa Indonesia Laras Bahasa Bakusyerina adeliaBelum ada peringkat
- Makalah Laras Dan Ragam BahasaDokumen30 halamanMakalah Laras Dan Ragam BahasaSri MelviaBelum ada peringkat
- Sosiolinguistik Bu SundariDokumen5 halamanSosiolinguistik Bu SundaripengendalisiswaBelum ada peringkat
- Ragam BahasaDokumen8 halamanRagam Bahasaiswanti 16Belum ada peringkat
- Modul 3 Ragam Bahasa IndonesiaDokumen14 halamanModul 3 Ragam Bahasa IndonesiaAlvida Dewi Amanda100% (1)
- Ragam Bahasa Dalam Kajian SosiolinguistikDokumen4 halamanRagam Bahasa Dalam Kajian Sosiolinguistiksnnrnb7tc8Belum ada peringkat
- Bab IiDokumen19 halamanBab IidestaBelum ada peringkat
- Ragam Bahasa IndonesiaDokumen6 halamanRagam Bahasa Indonesialatifa putriiBelum ada peringkat
- Ragam BahasaDokumen13 halamanRagam BahasaMohamad Zulkifli RobaniBelum ada peringkat
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)