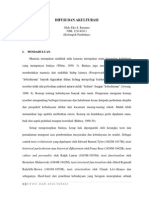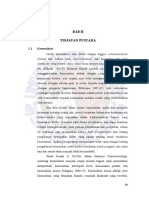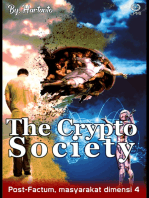Menangkal Homogenisasi Budaya. Melalui Pendidikan Formal Seni Pertunjukan
Diunggah oleh
Aris SetyawanHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Menangkal Homogenisasi Budaya. Melalui Pendidikan Formal Seni Pertunjukan
Diunggah oleh
Aris SetyawanHak Cipta:
Format Tersedia
Menangkal Homogenisasi Budaya, Melalui Pendidikan Formal Seni (Pertunjukan) Oleh: Aris Setyawan*
Seni pertunjukan dapat diartikan sebagai karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. performance biasanya melibatkan empat unsur: waktu, ruang, tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton (http://id.wikipedia.org). Kasim dalam Magdalia Alfian (2006:1) menerangkan bahwa seni pertunjukan dapat dipilah menjadi tiga kategori yakni: 1) musik (vokal, instrumental, gabungan), 2) tari (representasional dan non-representasional), 3) teater (dengan orang atau boneka/wayang sebagai dramatis personae.) Indonesia memiliki khasanah seni pertunjukan yang luar biasa ragamnya. Tidak akan ada habisnya apabila dijabarkan satu per satu mengenai masing-masing kategori dari seni pertunjukan tersebut.1 Maka, saya hanya akan menjelaskan inti pembahasan dari makalah ini yakni tentang kaitan antara seni pertunjukan, globalisasi, dan hegemoni budaya. Selain itu diperlukan pula politisasi seni demi menangkal efek hegemoni budaya tersebut. Hal ini berkaitan pula pada keberlangsungan hidup budaya Indonesia pada khususnya dan demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia pada umumnya. Pembahasan saya akan berkonsentrasi pada realita bahwa seni pertunjukan di Indonesia tumbuh dan berkembang karena kecintaan masyarakat terhadap hasil kebudayaan yang telah turun temurun ada. Namun, kecintaan pada kesenian ini seringkali tidak didukung oleh pemerintah, yang minim dana maupun pengetahuan. Seni pertunjukan Indonesia menyatu dengan moral dan kepribadian bangsa yang adiluhung. Namun, sangat disayangkan semua itu kini diambang kehancuran.
1
1
*Mahasiswa Jurusan Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia, Yogyakarta
Untuk lebih memahami masing-masing kategori seni pertunjukan dan perkembangannya di Indonesia, baca Melacak Jejak Perkembangan Seni Di Indonesia oleh Claire Holt, Diterbitkan MSPI pada Februari 2000.
Kenyataannya, pendidikan formal tidak menyentuh pendidikan seni (pertunjukan) sebagai media penanaman apresiasi seni budaya dan nilai-nilai kemasyarakatan kita. Sehingga perlu dikembangkan pendidikan seni di sekolah-sekolah umum, mulai dari tingkat dasar sampai menengah atas. Pemerintah pun perlu mempolitisasi seni dalam artian memberikan fasilitas yang mendukung peningkatan kesadaran kultural dan moral kemasyarakatan bagi seluruh bangsa ini. Globalisasi Dan Hegemoni Budaya Tidak mudah mendefinisikan globalisasi, banyak ahli melahirkan definisi berbeda tentang globalisasi. Yang semuanya disesuaikan dengan bidang kajian masing-masing. Namun, definisi yang paling sederhana dan singkat mengenai globalisasi pernah dikemukakan oleh Etienne Perrot. Perrot dalam Kushendrawati (2006,hlm.50) memahami globalisasi sebagai hasil penggabungan atau akumulasi antara internasionalisasi dan homogenisasi. Internasionalisasi dan homogenisasi yang dimaksud cakupannya melingkupi sosial, politik, ekonomi, termasuk dalam kebudayaan dan kesenian. Terkait kebudayaan dan kesenian ini, globalisasi bersifat memaksa dunia untuk mengalami proses homogenisasi dan menyamakan diri dalam satu kesamaan budaya. Mengenai homogenisasi kebudayaan ini Naomi Klein, penulis anti kapitalisme Kanada mengatakan bahwa globalisasi bersikap "force the world to speak your language and absorb your culture." (2000, hal.132). Pemaksaan penyeragaman budaya ini bukannya tidak terindikasi. Dunia pada dasarnya telah sadar bahwa ada skenario besar terkait homogenisasi budaya. Namun entah kenapa seolah dunia dijaga terdiam. Padahal skenario ini sudah didedahkan oleh teoritik-politik asal Italia, Antonio Gramsci, sejak berpuluh tahun yang lalu. Gramsci menyebutnya sebagai hegemoni budaya. Sebuah teori politik-budaya terpenting abad ini yang selalu dikutip begitu banyak teoritisi lain dalam makalahmakalah mereka. Menurut Gramsci, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma
penguasa. Lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka. Inilah yang dimaksud Gramsci dengan hegemoni atau menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Dalam konteks ini, Gramsci secara berlawanan mendudukan hegemoni sebagai satu bentuk supremasi satu kelompok atau beberapa kelompok atas yang lainnya. Dengan bentuk supremasi lain yang ia namakan dominasi yaitu kekuasaan yang ditopang oleh kekuatan fisik (Sugiono dalam Saptono, 2010). Proses homogenisasi dan hegemoni budaya ini dijalankan aktor globalisasi (negara adidaya) pada dunia. Terutama negara berkembang seperti Indonesia, dalam rangka mempermudah dominasi mereka dalam bidang lain seperti perekonomian dan pengumpulan kesejahteraan. Tak dapat dipungkiri kebudayaan dan bidang lain saling berkaitan. Michel Foucault membedah fenomena ini dengan teorinya mengenai knowledge/power. Dalam teorinya dijelaskan bahwa kekuasaan selalu muncul karena ada pengetahuan, begitu pula sebaliknya. Maka ketidaktahuan dalam kebudayaan pada akhirnya membuat ketidaktahuan dalam bidang lain, perekonomian, dll. (Foucault, 2002). Seperti dijelaskan di atas bahwa seluruh dunia merasa baik-baik saja dan nyaman dengan homogenisasi budaya. Mengutip pemikiran Gramsci bahwa hegemoni satu kelompok atas kelompok-kelompok lainnya dalam pengertian Gramscian bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Hegemoni itu harus diraih melalui upaya-upaya politis, kultural dan intelektual guna menciptakan pandangan dunia bersama bagi seluruh masyarakat. Teori politik Gramsci menjelaskan bahwa ide-ide atau ideologi masih menjadi sebuah instrumen dominasi yang memberikan pada kelompok penguasa legitimasi untuk berkuasa (Sugiono dalam Saptono, 2010). Hegemoni budaya ini berhasil membuat kita berupaya mencapai konsensus sesuai ideologi yang dihegemonikan kepada kita. Konsensus tersebut berupa kehidupan yang kita jalani harus berkembang sesuai dengan kultural negara adikuasa, pemegang tampuk dominasi. Jadilah warga negara kita lebih menghayati gaya hidup dan budaya ala negara adikuasa tersebut daripada budaya negeri sendiri.
Homogenisasi budaya ini dianggap wajar karena instrumen atau agen penyebar homogenisasi ini luar biasa besar. Ia amat hegemonik menyerbu kita dengan serangan-serangan ide yang sulit tertangkis, sebab kuasa kapitalnya tak tertandingi. Media adalah salah satu agen luar biasa tersebut. Setiap hari media Kita menyuguhkan sajian kultural yang didominasi produk kultural asing. Mau tak mau akhirnya sajian media yang hegemonik tersebut mengkonstruksikan pada diri kita bahwa kebudayaan asing itu hebat, patut diapresiasi, dan adiluhung melebihi budaya sendiri. Tentu menjadi pertanyaan mengapa media di Indonesia lebih memilih budaya asing tersebut sebagai konten yang mereka sajikan? Tentu ini berkaitan lagi-lagi dengan hegemoni budaya dan homogenisasi yang disetir kapitalisme/globalisasi seperti dijabarkan Gramsci di atas. Media di Indonesia mau tak mau harus tunduk juga pada kapital. Pers yang kemudian lebih dikenal sebagai media harus kita perhatikan sebagai institusi bisnis, sekaligus informasi. Dua sistem yang saling bersinergi. Dualitas inilah, yang kemudian menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pemberitaan. Sebagai institusi, media tak luput dari lima filtrasi seperti yang dikatakan oleh Chomsky (1988). Lima filtrasi tersebut antara lain adalah: kepemilikan, periklanan, narasumber media, flak, dan antikomunisme (Latiefah, 2010, hlm. l4). Media mau tak mau tunduk pada lima filtrasi tersebut, termasuk harus menuruti agenda kapital yang antikomunis, itu yang menyebabkan porsi pemberitaan dan konten hiburan yang disajikan media di Indonesia timpang, lebih bertendensi ke budaya asing. Seni (Pertunjukan) Sebagai Cerminan Kepribadian Bangsa? Terkait dengan seni pertunjukan, segala sesuatu yang kita lihat dan dengar di media tak lain adalah budaya asing yang atas naluriah kapital media dianggap lebih menjual dan laris. Lebih spesifiknya seni pertunjukan yang dianggap lebih menjual tersebut menjurus pada genre-genre tertentu, pop misalnya. Tentu ini sesungguhnya
berbahaya dan tidak dapat didiamkan. Sebab, 24 jam sehari, 7 hari seminggu apa yang kita dan anak-anak kita lihat dengar dan rasakan di media mau tak mau akan mengkonstruksikan ideologi tertentu dalam diri kita. Dalam musik misalnya, Jeremy Wallach menjabarkan Musical expression, a panhuman universal, has taken on a special importance in modern societies. Its ability to channel affect, open possibilities for self-expression, and foster communal solidarity (in both imagined and realized-in-the-moment communities) stimulates various attempts to control music and/or harness its power to promote ideology. (Wallach, 2008, hlm. 263). Mengutip pernyataan Wallach, dapat disimpulkan bahwa musik (seni pertunjukan) yang ditayangkan media kita berefek ideologis pada para penikmatnya. Tayangan ini mengkonstruksikan standar kelayakan hidup adalah harus homogen dengan apa yang disajikan media. Dari sini, kita dapatkan hipotesa mengenai seni pertunjukan yang ditayangkan media dan kepribadian bangsa. Jika seni (pertunjukan) dianggap sebagai cerminan kepribadian bangsa. Pertanyaan selanjutnya yang diajukan adalah kenapa budaya dan kesenian (seni pertunjukan khususnya) tidak dicintai di negeri sendiri? Media lebih menayangkan seni pertunjukan produk budaya asing daripada seni pertunjukan budaya sendiri. Adakah tayangan wayang, ketoprak, karawitan, seni tari Indonesia di televisi swasta kita dewasa ini? Bisa jadi generasi muda tidak mencintai budaya sendiri, yang ada hanya generasi tua yang berupaya melestarikan, nguri-uri budaya sendiri (sebagai contoh seni pertunjukan, wayang, tari, karawitan, dll) untuk melawan homogenisasi budaya yang dikoarkan globalisasi (melalui media). Sebuah pertarungan yang tidak seimbang, saat local wisdom yang sedang kembang-kempis. Dalam upaya untuk tetap bernafas mempertahankan riwayat, melawan globalisasi yang sudah bercokol sedemikian lama. Bila permasalahan ini tak terbendung, maka ucapkan selamat datang homogenisasi budaya, dan selamat tinggal pada kebudayaan budaya bangsa. Politisasi Seni, Upaya Membendung Hegemoni Kultural Dan Menyelamatkan Budaya Indonesia
Ada pepatah jawa yang mengatakan witing tresno jalaran soko kulino yang kurang lebih berarti suka karena terbiasa. Pepatah jawa tersebut dapat kita jadikan hipotesa kenapa generasi muda Indonesia yang lebih mencintai budaya asing. Sebab, keseharian mereka terbiasa menonton dan mendengar budaya asing di media yang nonstop 24 jam sajikan konten budaya asing. Pun hal ini tidak diimbangi dengan pengajaran dan pengetahuan mengenai kebudayaan sendiri. Dukungan pemerintah pun dirasa kurang dalam upaya mengangkat budaya sendiri sebagai sebuah kekayaan yang harus dipertahankan. Pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang diberi kepercayaan warga negara, sebagai pihak yang harus mengurus negara ini sejatinya punya kemampuan luar biasa dalam membendung hegemoni budaya serta mengangkat kembali budaya bangsa. Pemerintah punya kewenangan itu dan sejatinya wajib melakukannya. Seperti dijabarkan Komisi Dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan Dunia UNESCO (1995): A multi-cultural country can reap great benefits from its pluralism, but also runs the risk of cultural conflicts. It is here that government policy is important. Governments cannot determine a peoples culture; indeed, they are partly determined by it. But they can influence it for better or worse and in so doing affect the path of development. (Pasal 2). Langkah yang dapat diambil adalah dengan adanya politisasi seni. Itulah kenapa pemerintah harus punya andil. Sebab, Negara Indonesia jelas adalah sebuah negara multikultural dengan beragam budaya yang amat banyak dan pantas dilestarikan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai politisasi seni ini, yang terpenting ialah membuka selubung dari mitos bahwa seni adalah netral dan lepas dari politik dan/atau suasana sosial yang melingkupinya. Dengan membuka selubung akan diketahui siapa saja yang membela kenetralan seni. Mungkin pula akan membuat kita bisa menemukan jawaban tentang kenapa, ranah senimusik pop terutama menjadi mandeg (Taufiqurrahman, 2011). Seni pertunjukan seolah juga jalan di tempat, lebih lanjut Taufiqurrahman mengatakan pandangan bahwa seni adalah entitas yang netral, warisan pandangan
dunia usang yang pernah menggejala pada abad ke 19 di Eropa Barat. Ketaklidan kepada pandangan ini juga lah yang kemudian menceburkan Eropa ke dalam salah satu penggalan paling kelam dalam sejarah mereka, holocaust. Di salah satu pusat peradaban Eropa, di Jerman tepatnya pada awal abad, musik dianggap sebagai sesuatu yang suci yang bergaung sunyi di luar dan di atas peradaban. Salah seorang filsuf terbesar mereka, Arthur Schopenhauer mengatakan bahwa art and life had nothing to do with each other keduanya sama sekali tidak berhubungan. Schopenhauer juga mengatakan bahwa beside the history of the world the history of philosophy, science and art is guiltless and unstained by blood, hanya senilah yang tidak pernah bersalah dan mendapat cipratan darah. Pandangan akan kenetralan seni tersebut menjadi sangat berbahaya ketika digunakan sebagai dalih bagi fasisme dan anti-semitisme. Lalu muncul kesimpulan bahwa para komposer yang berpegang teguh kepada kenetralan seni, kemudian dengan mudah mensabotase senidengan dalih bahwa seni adalah netral dan adi luhungdemi mendukung ideologi fasisme. Yang kemudian digunakan untuk mendukung agenda tertentu seorang diktator yang menawarkan tatanan baru. Komposer Hans Pfizner yang memasang kutipan Schopenhauer di atas di epigrafnya untuk komposisi yang ditulis di tahun 1917 Palestrina menulis kantata tersebut tersebut untuk Mussolini (Taufiqurrahman, 2011). Politisasi seni yang dimaksud dalam makalah ini yakni membawa kesenian ke ranah politik, atau menggunakan kekuatan politis tertentu untuk membawa seni (pertunjukan) pada level yang lebih tinggi. Bukannya memberikan esensi politis dalam sebuah kesenian. Seni harus bersifat politis, atau dapat dijadikan sebuah ideologi, bukan bermuatan politis atau berkepentingan. Barangkali rumus pepatah jawa witing tresno jalaran soko kulino tadi dapat digunakan sebagai solusi mengatasi serbuan hegemoni kesenian asing dan kemandegan kesenian (pertunjukan) Indonesia. Pemerintah harus segera mempolitisasi kesenian demi keberlangsungan hidup budaya bangsa dan bahkan keberlangsungan hidup bangsa itu sendiri secara harfiah. Bukan dengan cara membatasi dan melarang budaya asing masuk ke Indonesia tentu, sebab itu akan menyalahi cita-cita demokrasi Indonesia.
Membreidel media yang sajikan konten budaya asing atas nama nasionalisme anti imperialisme ala Soekarno juga sudah bukan zamannya lagi. Maka opsi yang dapat dilakukan pemerintah ialah seolah menciptakan sebuah counter-culture atau budaya tanding. Budaya sendiri harus dapat menandingi budaya asing, tidak dengan cara memaksakan sekarang semua orang harus suka budaya sendiri. Namun, alangkah baiknya bila langkah pengajaran budaya sendiri ini dimulai dari dasar. Pemerintah harus gunakan politik untuk membawa kesenian ke pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar bahkan pra-sekolah agar anak-anak terbiasa dengan budaya dan kesenian sendiri, lantas akhirnya menyukainya. Pendidikan Formal Bidang Kesenian: Sebuah Kesimpulan Tentu banyak orang yang sangsi dan pesimis dengan politisasi seni. Perlu disimpulkan lagi, jika seni (pertunjukan) tidak dipolitisasi, niscaya ia hanya jadi komoditas industri yang tidak dapat dijadikan kebanggaan bangsa. Seni (pertunjukan) harus dipolitisasi (baca: diajarkan, atau dipaksakan) pada warga negara lewat pendidikan dasar di sekolah-sekolah. Sudah jadi rahasia umum bahwa pendidikan bangsa selama ini disasarkan hanya pada yang teknis dan membangun. Sebab tak dapat dipungkiri lagi rupanya hegemoni budaya ala Gramsci tadi juga sudah mempengaruhi metode dalam sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan teknis dan membangun tadi adalah teori pembangunan yang berbasis pengembangan sumber daya manusia yang sering disebut human capital theory yang intinya berkaitan dengan investment human resources. Teoriteori tersebut berasal dari para ahli teori dunia maju (barat) sehingga lebih berorientasi pada pengalaman orang barat, ketimbang dunianya sendiri. Dengan kata lain, mereka umumnya sampai pada keyakinan bahwa sistem pendidikan menjadi instrumen penting (berparadigma Instrumentalis) bagi proses modernisasi negaranegara berkembang, termasuk Indonesia (Ketut Suda, 2009, hlm. 106). Sementara itu budaya (seni) yang dapat menjadi motivator dan indikator moral justru diacuhkan. Maka dari itu, bangsa Indonesia semrawut dalam berbagai
bidang. Bisa jadi karena aspek rasa dan moral yang harusnya dapat ditanamkan sejak dini (melalui seni) tidak dilakukan. Sejak pendidikan dasar, masyarakat diajarkan untuk terus membangun maupun mengejar modernisasi (persis barat yang sekular, sebab teori pendidikan kita diadopsi dari barat) hingga kadang segala cara dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Kemajuan membangun yang tidak dibarengi kesiapan moral dan nurani berakibat fatal. Kanibalisme antarwarga negara bisa jadi terjadi demi mencapai tujuan membangun. Juga dalam aspek politik dimana korupsi, kolusi, nepotisme, dan peperangan kepentingan politik. Hal-hal terburuk dari keadaan diatas, sebenarnya dapat dihindarkan jika mulai dari sekarang generasi muda penerus bangsa tak hanya diajarkan pendidikan teknis dan membangun, tapi juga dibarengi pendidikan moral dan nilai-nilai kearifan lokal. Salah satunya melalui pengajaran kesenian secara formal disekolah-sekolah. Mulai dari dini, kita sebaiknya mulai menanamkan nilai-nilai moral melalui seni di pendidikan dasar. Seni pertunjukan pada khususnya adalah cara mengajarkan moral itu tanpa terkesan menggurui dan indoktrinasi. Penanaman nilai moral melalui pendidikan kesenian formal ini cukup efektif. Sebab, pendidikan formal kemudian ikut memberikan andil dalam proses pembentukan kultur itu sendiri melalui proses internalisasi. Dengan kata lain, pendidikan formal adalah bagian dari proses pembentukan budaya dan kesenian. Masalahnya adalah apa pelaku pendidikan (shareholders) menyadari tentang masalah ini? Dan secara sengaja dan sistematik membangun suasana sehingga terjadi proses pendidikan budaya dan kesenian bangsa itu dapat berlangsung. Lembaga pendidikan tidak hanya bermuatan (kurikulum) tetapi merupakan ajang pendidikan budaya dan kesenian yang aplikatif dan substansial. Inilah fungsi politisasi seni oleh pemerintah dengan kekuatan politiknya. Membuat undang-undang yang berfungsi sebagai kebijakan yang mengikat, mengajarkan (baca: memaksa) warga negara untuk belajar dan memahami kebudayaan dan kesenian (pertunjukan) sendiri sejak usia sekolah dasar.
Jika klausul ini dapat dijalankan, tidak mustahil jika wayang, gamelan, tari, atau teater Indonesia dapat diajarkan sebagai pendidikan formal sekolah dengan aplikatif dan substansial. Bukan sekedar mata pelajaran pelengkap yang diajarkan demi memenuhi kurikulum. Hal ini memunculkan pertanyaan Maukah pemerintah melakukan hal tersebut? Jika pemerintah enggan melakukannya. Kita sebagai warga negara punya hak memaksa pemerintah (sebagai pengurus negara) agar segera lakukan politisasi seni. Lagi-lagi akan muncul pertanyaan Maukah kita sebagai warga negara memaksa pemerintah mengangkat budaya bangsa sendiri? Atau kita terlampau nyaman dengan homogenisasi budaya asing dalam hidup kita. Hingga membuat kita enggan hidup dengan mencintai budaya sendiri? Solusi yang ditawarkan dalam menangkal hegemoni seni ini yakni dengan intervensi pemerintah, Melalui departemen-departemen pendukungnya. Pengaturan konten yang ditayangkan di media dapat dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). bukannya melarang sama sekali budaya atau kesenian asing disajikan di media-media Indonesia, namun memilah dan memilih mana konten media yang bermanfaat untuk warga Negara, dan mana yang lebih banyak negatifnya. Warga Negara pun punya kewenangan personal memilah dan memilih ini melalui proses literasi media. Pilah lantas ambil yang baik dan hilangkan yang negatif. Pemerintah harus mulai mencanangkan seni Indonesia sebagai pendidikan formal sekolah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai otoritas tertinggi bidang pendidikan di negeri ini. Mengubah pengajaran Seni budaya yang tadinya hanya sebagai kurikulum pelengkap menjadi pelajaran seni yang aplikatif dan substansial. Lalu apa yang dapat dilakukan penggiat seni dan akademisi kesenian? Paling tidak kalangan penggiat seni harus mampu lakukan semacam advokasi pada masyarakat luas, menimbulkan kesadaran bahwa Kita harus menangkal hegemoni budaya asing melalui pendidikan seni Indonesia yang lebih baik.
Daftar Pustaka Buku dan Makalah Alfian, Magdalina. 2006. Seni Pertunjukan Dalam Perspektif Sejarah; Sebuah Makalah. Yogyakarta Foucault, Michel. 2002. Karya-Karya Penting (Terj. Arief). Yogyakarta: Jalasutra Klein, Naomi. 2000. No Logo. Inggris: Flamingo 2000. Komisi Dunia untuk Kebudayaan dan Pembangunan UNESCO (Pasal 2). 1995 Kushendrawati, Selu Margaretha. 2006. Masyarakat Konsumen Sebagai Ciptaan Kapitalisme Global: Fenomena Budaya Dalam Realitas Sosial. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Vol-10, No-2. Desember 2006. Latiefah, Shefti. 2011. Pendidikan Media dan Pilar ke-5 Demokrasi ; Sebuah Makalah. Jakarta Suda, I Ketut. 2009. Komodifikasi Pendidikan dan Kanibalisme Intelektual Dalam Pembelajaran di Sekolah. Sebuah Makalah dalam "Jelajah Kajian Budaya." Denpasar, Bali: Pustaka Larasan/Program Studi Magister dan Doktor Kajian Budaya Universitas Udayana Wallach, Jeremy. 2008. Modern Noise, Fluid Genres: Popular Music in Indonesia. 1997-2001. Wisconsin, Amerika: The University of Wisconsin Publisher Internet http://id.wikipedia.org http://jurnal.isi-dps.ac.id/index.php/artikel/article/view/387/0 Saptono. 2010. Teori Hegemoni Sebuah Teori Kebudayaan Kontemporer. Sebuah Artikel Dalam Kumpulan Artikel ISI Denpasar http://www.jakartabeat.net Taufiqurrahman, M. 2011. "SBY Bermusik dan Kematian Kritik." Sebuah Artikel Dalam Situs jakartabeat.net.
Anda mungkin juga menyukai
- Pengantar Seni Dan BudayaDokumen9 halamanPengantar Seni Dan BudayaChoiri Askolani100% (4)
- Filsafat KebudayaanDokumen3 halamanFilsafat Kebudayaanfitria0% (1)
- Apa Itu AntropologiDokumen5 halamanApa Itu AntropologiTotok PriharwantoBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen23 halamanBab Iimuhammadpurnama536Belum ada peringkat
- Cultural Studies & MediaDokumen34 halamanCultural Studies & Mediawike100% (1)
- Cultural Studies Dan FeminismeDokumen6 halamanCultural Studies Dan FeminismeUpe Peul100% (1)
- 2pancasila Dan MultikulturalismeDokumen16 halaman2pancasila Dan MultikulturalismeRita KeetaBelum ada peringkat
- Memahami Konsep Glokalisasi Budaya Populer Di Indonesia (Studi Kasus Glokalisasi Budaya Musik Rap Dalam Budaya Lokal Jawa Pada Jogja Hip-Hop Foundation)Dokumen24 halamanMemahami Konsep Glokalisasi Budaya Populer Di Indonesia (Studi Kasus Glokalisasi Budaya Musik Rap Dalam Budaya Lokal Jawa Pada Jogja Hip-Hop Foundation)AG. Eka Wenats Wuryanta71% (7)
- Makalah Seminar AjasiDokumen13 halamanMakalah Seminar AjasiyudhaBelum ada peringkat
- T2 Sosial Budaya Dan Budaya DasarDokumen16 halamanT2 Sosial Budaya Dan Budaya DasarYoga HernandaBelum ada peringkat
- Tugas Kuliah 2 Ilmu Sosial Budaya DasarDokumen4 halamanTugas Kuliah 2 Ilmu Sosial Budaya DasarSaddam HusseinBelum ada peringkat
- Kebudayaan NasionalDokumen4 halamanKebudayaan NasionalHima PensatradaBelum ada peringkat
- Paradigma Multikulturalisme2Dokumen4 halamanParadigma Multikulturalisme2Najemiati NajeBelum ada peringkat
- Topik X Interaksi AntarbudayaDokumen9 halamanTopik X Interaksi AntarbudayaCindy HosianiBelum ada peringkat
- Char6019 LN7 W7 S11 R0Dokumen16 halamanChar6019 LN7 W7 S11 R0sigitrizkiprabowo18_Belum ada peringkat
- Char6019 LN7 W7 S11 R0 PDFDokumen16 halamanChar6019 LN7 W7 S11 R0 PDFJimmi TambaBelum ada peringkat
- Isi Artikel 537711131678Dokumen12 halamanIsi Artikel 537711131678TeddyBelum ada peringkat
- Apa Itu Budaya MassaDokumen5 halamanApa Itu Budaya MassaEven TamaelaBelum ada peringkat
- T1 - 352009011 - Bab IiDokumen9 halamanT1 - 352009011 - Bab IiTina AnggrainiBelum ada peringkat
- Wawasan Budaya KelompokDokumen11 halamanWawasan Budaya Kelompokyutub sihBelum ada peringkat
- Budaya Populer Unk WEB StkipDokumen3 halamanBudaya Populer Unk WEB Stkip281067Belum ada peringkat
- Jurnalisme Gaya Hidup Sebagai Jurnalisme Budaya Yang DisamarkanDokumen17 halamanJurnalisme Gaya Hidup Sebagai Jurnalisme Budaya Yang DisamarkanDeravi PutraBelum ada peringkat
- Globalisasi Antara Peluang Dan Ancaman Bagi MasyarDokumen12 halamanGlobalisasi Antara Peluang Dan Ancaman Bagi MasyarAnggie Sii CanCerr CiieemooddBelum ada peringkat
- Kuliah I Filsafat BudayaDokumen5 halamanKuliah I Filsafat BudayafongersBelum ada peringkat
- Difusi Dan AkulturasiDokumen35 halamanDifusi Dan AkulturasiFidy Ramzielah Famiersyah100% (1)
- Tjetjep Rohendi Rohidi Sumberdaya Budaya Pendidikan Kebudayaan Seni Sebagai Sarana Pendidikan Kebudayaan PDFDokumen11 halamanTjetjep Rohendi Rohidi Sumberdaya Budaya Pendidikan Kebudayaan Seni Sebagai Sarana Pendidikan Kebudayaan PDFj prasBelum ada peringkat
- Probem Aktual KebudayaanDokumen32 halamanProbem Aktual KebudayaanBella SebaBelum ada peringkat
- SosantrokesDokumen10 halamanSosantrokesferinaBelum ada peringkat
- Media Massa Dan HegemoniDokumen3 halamanMedia Massa Dan HegemoniAulia L RizalBelum ada peringkat
- Kel.2 MEMAHAMI PROSES PEMBENTUKAN KEBUDAYAANDokumen13 halamanKel.2 MEMAHAMI PROSES PEMBENTUKAN KEBUDAYAANValen EkaBelum ada peringkat
- Kajian Budaya Dalam Perspektif FilosofiDokumen8 halamanKajian Budaya Dalam Perspektif FilosofiRanBelum ada peringkat
- ITDokumen14 halamanITYayasan Hamjah Diha100% (1)
- Makalah Adat IstiadatDokumen13 halamanMakalah Adat IstiadatDestya Purnawita100% (3)
- Keberadaan Seni Dalam Sistem Dan Struktur Budaya MasyarakatDokumen26 halamanKeberadaan Seni Dalam Sistem Dan Struktur Budaya MasyarakatSutraLailaBelum ada peringkat
- Konsep Dan Definisi Budaya PopulerDokumen7 halamanKonsep Dan Definisi Budaya PopulerSultan Kharis UkimaBelum ada peringkat
- Budaya Massa Di IndonesiaDokumen19 halamanBudaya Massa Di Indonesiarudi irawantoBelum ada peringkat
- Tugas 2 Yoga Hernanda Sosial Budaya Dan Budaya DasarDokumen15 halamanTugas 2 Yoga Hernanda Sosial Budaya Dan Budaya DasarYoga HernandaBelum ada peringkat
- MULTIKULTURALISMEDokumen4 halamanMULTIKULTURALISMEHeru ArdiansyahBelum ada peringkat
- Cultural StudiesDokumen3 halamanCultural StudiesAulia MaghfirahBelum ada peringkat
- MAKALAH PENGANTAR SOSIOLOGI KLP 3 (Updated)Dokumen19 halamanMAKALAH PENGANTAR SOSIOLOGI KLP 3 (Updated)Andriy NaufalBelum ada peringkat
- 3988 8556 1 SM PDFDokumen8 halaman3988 8556 1 SM PDFDian SukmawatiBelum ada peringkat
- T1 - 362016702 - Bab IiDokumen18 halamanT1 - 362016702 - Bab IitsaniyyBelum ada peringkat
- Rangkuman CB PancasilaDokumen23 halamanRangkuman CB PancasilaMedan Kota KelahirankuBelum ada peringkat
- Kebudayaan Nasional Dan Ketahanan Bangsa: Meneropong Jiwa Nasionalisme Masyarakat KontemporerDokumen18 halamanKebudayaan Nasional Dan Ketahanan Bangsa: Meneropong Jiwa Nasionalisme Masyarakat KontemporerSeftiani nur DindaBelum ada peringkat
- Reproduksi BudayaDokumen15 halamanReproduksi BudayaAl Muhammad NurBelum ada peringkat
- MAKALAH SOSIO AntropologiDokumen11 halamanMAKALAH SOSIO AntropologiRIZKABelum ada peringkat
- Cultural Studies Secara Antropologi Dapat Mengacukan Sebagai Perilaku ManusiaDokumen7 halamanCultural Studies Secara Antropologi Dapat Mengacukan Sebagai Perilaku Manusiahelmy gantengBelum ada peringkat
- D0319026 - Divea Della Rosa - UAS Teori KritisDokumen5 halamanD0319026 - Divea Della Rosa - UAS Teori KritisdiveadrBelum ada peringkat
- TUGAS 2 Ilmu Sosial Dan Budaya DasarDokumen3 halamanTUGAS 2 Ilmu Sosial Dan Budaya Dasarrian fauziBelum ada peringkat
- 8.ilmu KebudayaanDokumen7 halaman8.ilmu KebudayaanBobon SantosoBelum ada peringkat
- 16 - Tugas Psi Lintas Budaya Pertemuan Ke 11, Jihan Zaelani (1824090023)Dokumen7 halaman16 - Tugas Psi Lintas Budaya Pertemuan Ke 11, Jihan Zaelani (1824090023)nada bawazierBelum ada peringkat
- (Gendra) Media Dan Cultural StudiesDokumen4 halaman(Gendra) Media Dan Cultural StudiesGendra Wisnu BuanaBelum ada peringkat
- PancasilaDokumen5 halamanPancasilasaila salsabilaBelum ada peringkat
- Fungsi Pendidikan Dalam KebudayaanDokumen23 halamanFungsi Pendidikan Dalam KebudayaanDanny Septian82% (11)
- CJR IsbdDokumen16 halamanCJR IsbdRafi Akbar100% (4)
- Char6019 LN8 W8 S12 R0Dokumen18 halamanChar6019 LN8 W8 S12 R0sigitrizkiprabowo18_Belum ada peringkat
- Wawasan Budaya Dan Seni (Sosiologi)Dokumen22 halamanWawasan Budaya Dan Seni (Sosiologi)Yoshi OkaBelum ada peringkat
- Kepribadian Dan BudayaDokumen8 halamanKepribadian Dan Budayaprisaaaa21Belum ada peringkat
- (Tinjauan Sumber) Fenomena Fans Club. Sebuah Kajian Budaya MassaDokumen5 halaman(Tinjauan Sumber) Fenomena Fans Club. Sebuah Kajian Budaya MassaAris SetyawanBelum ada peringkat
- Hipster Priyayi Masa KiniDokumen5 halamanHipster Priyayi Masa KiniAris SetyawanBelum ada peringkat
- AngkringanDokumen4 halamanAngkringanAris SetyawanBelum ada peringkat
- Memetika Dan BudayaDokumen2 halamanMemetika Dan BudayaAris SetyawanBelum ada peringkat
- Homicide. Musik Rap Sebagai Media ResistensiDokumen18 halamanHomicide. Musik Rap Sebagai Media ResistensiAris SetyawanBelum ada peringkat