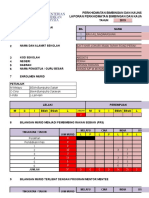Kebijaksanaan Dalam Filsafat
Diunggah oleh
Ravi Kumar NadarashanJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Kebijaksanaan Dalam Filsafat
Diunggah oleh
Ravi Kumar NadarashanHak Cipta:
Format Tersedia
KEBIJAKSANAAN DALAM FILSAFAT
(Analisis Manfaat Filsafat Terhadap Masa Depan Manusia)
A. Pendahuluan
Ibarat orang mau makan, filsafat memang tidak menyediakan nasi. Filsafat hanya menyediakan tungku
dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk memasak. Artinya, filsafat tidak menyajikan hasil akhir
yang bisa langsung dinikmati manusia. Namun filsafat memberikan jalan agar manusia meraih apa yang
diharapkan. Karenanya, term filsafat ada dalam setiap aspek kehidupan dan semua disiplin ilmu. Misalnya,
filsafat agama, filsafat pendidikan, filsafat politik, filsafat hukum, filsafat ekonomi, bahkan ada juga yang
disebut filsafat atau falsafah hidup.
Ini menunjukkan bahwa tidak satupun dari sisi kehidupan manusia yang tidak terjamah oleh filsafat.
Menurut Fichte filsafat adalah suatu refleksi tentang pengetahuan. Ia sepakat dengan Immanuel Kant
bahwa semua ilmu pengetahuan membahas salah satu obyek tertentu, sedangkan filsafat bertugas
memandang pengetahuan sendiri. Oleh karena itu filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mendasari
ilmu-ilmu pengetahuan lain.[1] Filsafat selalu ada dimana-mana. Dan hingga kapanpun, filsafat pasti
relevan dengan kondisi kekinian dan kedisinian.
Relevansi ini terkonsentrasikan dalam kata wisdom (kebijaksanaan). Alasannya, kebijaksanaan
merupakan ruh kehidupan manusia. Bila “kebijaksanaan” sudah hilang dalam perbendaharaan manusia,
pada hakikatnya kehidupan ini sudah sirna. Yang tanpak hanyalah manusia-manusia tak
berperikemanusiaan, manusia egois yang tidak memperhatikan orang lain, yang penting menguntungkan
atau menyenangkan dirinya sendiri. Maka tidak ada lagi keindahan dalam hidup ini. Yang ada hanyalah
rimba dengan “hewan-hewan” yang saling mencabik, mencakar dan menerkam satu sama lain. Akhirnya,
ibarat dinosaurus, manusia akan segera musnah dari peredaran planet ini. Tungga saja!
Biar lebih afdhal, saya ambil contoh yang kini tengah menjadi perbincangan global. Kasus kartun Nabi
Muhammad dari salah satu media Denmark yang kini menuai protes dari seluruh umat muslim dunia
merupakan contoh tidak adanya kebijaksanaan dalam diri manusia. Seharusnya hal itu tidak terjadi bila
pihak penerbit memiliki secercah kebijaksaan. Mereka sebenarnya sadar-sesadarnya bahwa jika kartun itu
diterbitkan akan menimbulkan gejolak pada umat Islam secara massif. Namun, atas nama kebebasan pers,
mereka tetap saja menerbitkan kartun tersebut. Mereka sengaja mengabaikan perasaan orang lain, umat
Islam. Jelas, sikap demikian jauh dari sikap bijaksana (wise).
Perlu juga dicatat bahwa kebijaksanaan tidak berkonotasi negatif. Kebijaksanaan hanya ada dalam bingkai
positif pada semua sikap dan aktivitas manusia. Taruhlah, permohonan kebijaksanaan seorang pelanggar
lalu lintas kepada pak/ibu polisi agar meloloskan dirinya dengan jalan damai (baca: suap), bukanlah sikap
bijaksana. Itu tidak lebih lebih dari “kongkalikong” yang mencederai aturan main (rule of the game) yang
ada. Sekali lagi kebijaksaan tidak pernah bersanding dengan sesuatu yang negatif, ia hanya ada dan hanya
beriringan bersaama kebaikan. Walaupun kebaikan sendiri masih relatif.
Dari dua contoh diatas, saya hanya ingin menegaskan bahwa kebijaksanaan merupakan sesuatu yang
amat signifikan. Kebijaksanaan itu, salah-satunya, diperoleh melalui filasafat. Dari filsafatlah lahir sosok
manusia yang selalu menjadi pelita zaman yang tanpa lelah menyinari alam kehidupan yang kian meredup
ini. Bahkan demi mewujudkan kehidupuan yang lebih baik dan bijaksana, mereka rela mempertaruhkan
nyawa.
B. Metodologi dan Tradisi Falsafi
Metodologi dan tradisi falsafi secara mendasar tercermin dalam pengertian filsafat itu sendiri, yang
terbentuk dari kata philo “cinta” dan sophia “kebijaksanaan”. Filsafat adalah cinta kebijaksanaan, dan
filosofnya disebut orang yang cinta kebijaksanaan, the wisdom lover. Sementara Plato menggaris bawahi
bahwa filosof adalah adalah orang yang mencintai “visi kebenaran”, bukan sekedar pengetahuan vulgar,
melainkan hakikat dan dari kebenaran itu sendiri.[2] Sextus Empiricus mengartikan filsafat sebagai sebuah
aktivitas untuk melindungi kehidupan yang bahagia melalui diskusi dan argumentasi. Maka cinta kepada
kebijaksanaan kuncinya terletak pada kemauan menjaga pikiran agar tetap terbuka, kesediaan membaca
secara luas dan mempertimbangkan seluruh wilayah pemikiran dan memiliki perhatian kepada
kebenaran.[3]
Sedangkan menurut Musa Asy’ary, dalam khasanah ilmu, filsafat diartikan sebagai berpikir yang bebas,
radikal dan berada dalam dataran makna.[4] Bebas berarti tidak ada yang menghalangi pekerjaan dalam
otak. Kerenanya, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk berpikir, mengatur atau menyeragamkan,
baik dalam hal obyek pikiran maupun cara berpikirnya. Berpikir radikal dalam filsafat adalah berpikir sampai
keakar suatu masalah, menadalam sampai keakar-akarnya, bahkan melewatai batas-batas fisik yang ada,
yakni masuk keranah metafisik. Berpikir dalam tahap makna berarti pencarian atas makna hakikat sesuatu
atau keberadaan dan kehadiran sehingga didapatkan nilai-nilai tertentu.
Jadi, filsafat pada dasarnya adalah suatu “aktivitas” proses interaksi dan keterlibatan terus menerus bahkan
sampai pada tidak ada lagi harapan menemukan “jawaban”. Sebagai aktivitas, filsafat dilakuakan oleh
individu berupa proses gradual, abadi melaui ide, argumentasi, pemikiran dan pengalaman personal.
Aktivitas filosofis akan menuntut pembacaan yang teliti, berpikir yang cermat, mengemukakan pendapat
dengan jelas dan mau melihat ide-ide sendiri berdasar penelitian yang rasional dan kritis, cermat, metodis-
evaluatif dan mendalam.
Menurut Amin Abdullah, hal yang paling memungkinkan untuk untuk aktivitas filosofis itu adalah filsafat
sebagai metodolgi pendekatan keilmuan yang bersifat ilmiah, terbuka dan inklusif. Dengan demikian,
filsafat bisa menjadi metodologi keilmuan sekaligus “ideologi” intelektual, dimana orang-orang yang
bergulat dengan keilmuan, pencarian kebenaran dan idealisme, selalu berpikir dan bersikap sesuai dengan
prinsip-prinsip falsafi, yakni kritis, analitik, logis, rasional, eksplanatif, reflektif dan mendalam.
Ini menunjukkan bahwa filsafat merupakan tradisi berpikir, respon seseorang atas dinamika masyarakat
dan zamannya masing-masing. Disinilah wilayah kajian filsafat selanjutnya, yaitu sejarah filsafat dan aliran
filsafat sebagai produk berpikir dan interaksi tersebut. Goethe, seorang sejarawan dan filosof Jerman
menyatakan bahwa manusia yang tidak mempelajari sejarah 3000 tahun perjalanan manusia sebelumnya
berarti telah menyia-nyiakan sepertiga hidupnya. Hal serupa juga diungkapkan Wiston Churchill “the further
you look ini the past, the more you can see in the future”, semakin jauh anda melihat masa lalu, semakin
baik padangan anda akan masa depan.[5]
Dinamika filsafat dengan berbagai alirannya menunjukkan tradisi filsafat yang dinamis dalam menanggapi
dan merespon kondisi sosial masyarakatnya. Disini tanpak hubungan kausalitas antara lingkungan sosial
dengan filosofnya. Lingungan membentuk pola berpikir dan mentukan corak filsafatnya; sementara produk
filsafat juga menentukan arah perkembangan masyarakatnya. Dua hal ini mengindikasikan interaksi antara
filsafat dan masyarakat sebagai sebuah ekosistem.[6] Oleh karenanya, sekalipun produk pemikiran filsafat
mereka pada saat sekarang ini dinggap tidak up to date lagi, tidak serta merta produk itu tidak berharga
lagi untuk dikaji di era kontemporer ini. Setting sosial yang melatarbelakangi dan metode berpikir mereka
sangat berharga dalam memberi inspirasi dalam menghadapi dan merespon dinamika masyarakat dewasa
ini.
C. Filsafat dan Penciptaan Kebijaksanaan Manusia
Tuntutan pola pikir yang komprehansif dan holistik terhadap berbagai persoalan diatas, membawa manusia
pada pola pikir falsafi, dan bisa jadi inilah yang dapat melihat berbagai hal tersebut secara arif dan
bijaksana. Filsafat tidak sekedar aliran-aliran pemikiran tertentu dari sang filosofnya, lebih dari itu filsafat
menjadi way of life bagi cendikiawan dan ilmuwan, metode berpikir (manhaj al-fikr) yang mendalam, kritis,
radikal dan penuh hasrat untuk menemukan kakikat kebenaran dari segala sesuatu. Oleh karena itu, filsafat
menjadikan seseorang dalam memandang segala sesuatu tidak hanya memahaminya secara dangkal,
tetapi senantiasa mencari pengetahuan hakiki dari sesuatu tersebut. Pemikiran filosofis pada akhirnya
membawa manusia pada kebijaksanaan dalam memandang segala sesuatu, semua persoalan dan
kehidupannya yang kompleks. Penggunaan fungsi akal budi secara maksimal dan positif pada akhirnya
akan membawa kepada sikap bijaksana sebagaimana telah diungkapkan oleh Plato. [7]
Dinamika masyarakat sebagai lingkungan kehidupan manusia harus disikapi secara bijaksana. Globalisasi
dan modernisasi menjadikan kehidupan ini semakin kompleks dan fenomena-fenomenanya tidak bisa
dilihat hanya dari satu perspektif saja, melainkan harus disinergikan dengan berbagai aspek lainnya. Hal
itu, kata Amin Abdullah, menuntut hal yang lebih universal dan substansial, sekaligus mempertimbangkan
kebijakan lokal yang telah terbentuk oleh faktor sejarah, geografi, bahasa, agama dan kultur yang bersifat
partikular, primordial dan emosional.[8]
Cara pandang yang global, universal dan substansial tanpa memperhatikan faktor budaya lokal akan
menjebak manusia dalam lingkungan yang asing dan teralienasi dari basis masyarakatnya. Sementara
terjerat pada pola pikir budaya lokal tanpa mempedulikan pengaruh budaya global akan menyebabkan split
persoanality, sebab ia terhimpit antara tuntutan berpikir dan bertindak.[9] Dalam hal ini, Giddens
menawarkan konsep yang mungkin bisa mensitesakan keduanya, yaitu think globally, act locally, berpola
pikir global, namun perilaku tetap lokal.
Dalam konteks agama, misalnya, masalah yang kerap muncul adalah: 1) tarik ulur antara truth
claim sebagai personal commitment terhadap ajaran agamanya, dan 2) toleransi atas pluralitas teologis
dalam lingkungannya. Maka, berpikir falsafi melalui gabungan antara kesetiaan (loyality) dengan
kesadaran kritis (critical consciousness) dapat mengajak menusia untuk mengkaji ulang klaim kebenaran
yang sudah mapan, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tetapi elastis atas aspek kebenaran
tersebut, menumbuhkan sikap toleran terhadap berbagai pandangan hidup dan membebaskan diri dari
sikap eksklusif-dogmatis yang menyatu dalam keyakinan hidup, yang pada akhirnya diperoleh
kebijaksanaan dalam beragama.[10]
Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Harold Titus bahwa studi filsafat seharusnya membantu orang-
orang untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar yang matang secara intelektual. Filsafat dapat
mendukung kepercayaan keagamaan seseorang, asal kepercayaan tersebut tidak tergantung pada
konsepsi yang pra-ilmiah, usang, sempit dan dogmatis.[11]
Kebijaksanaan dalam berpikir akan terbentuk dengan memperhatikan filsafat sebagai tradisi berpikir.
Memaknai filsafat sebagai konstruksi kreativitas akal budi manusia dalam pergumulan situasi historis, yakni
yang tersusun secara sistematis-metodologis dalam menerangkan respon manusia dalam menghadapi
perkembangan iptek, budaya global, interaksi dengan agama dan tradisi lain. Titik fokusnya bukan lagi
pada kebenaran (truth), melainkan pada makna (meaning) dari pengalaman tersebut.[12]
Produk jadi sebuah pemikiran filsafat tidak mesti bisa dipergunakan dalam ruang dan waktu tertentu.
Namun kerangka, metode dan proses pemikiran tersebut dapat dipergunakan untuk membedah persoalan
pada tempat dan waktu yang berbeda secara kritis, sekaligus menjadikannya sebagai sikap dan
pandangan hidup dalam menghadapi, merespon dan memecahkan persoalan-persoalan kontemporer.
Demikian juga produk-produk filsafat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga
penguasaan terhadap kerangka berpikir ini memberi keleluasaan untuk menerapkannya secara trans-
disipliner, dimana kerangka berpikir yang satu dan lainnya bisa saling melengkapi dan menguatkan.
Filsafat positifisme, misalnya, yang melandaskan pemikirannya kepada dunia yang empirik, yang dapat
dilihat, diukur, dianalisa dan dibuktikan secara obyektif tidak dapat diterapkan dalam banyak tradisi dan
pengalaman spiritual.[13] Namun dari filsafat ini dapat dipahami sebagai sikap tradisi dan berpikir “positif”,
yakni senantiasa berpikir kearah penertiban, kejelasan dan ketepatan menjauhi sikap ragu-ragu, asas
manfaat dan mendasarkan pada kekuatan intelektual.
Sementara filsafat eksistensialisme, sampai pada batas yang ekstrim, mengunggulkan diri sendiri dan
menafikan Tuhan.[14] Namun filsafat ini mengajarkan secara positif makna aktualisasi diri, berpikir
mondial (di sini, sekarang ini, individual), kepercayaan diri dan kemandirian: manusia memiliki kemampuan
pada dirinya sendiri, pengakuan atas manusia tergantung pada perwujudan eksistensi dirinya melalui
sikap, perbuatan dan karya.
Kemudian filsafat hermeneutik sebagai cara pembacaan teks menjadi sangat penting untuk melihat teks-
teks masa lampau (terutama korpus keagamaan) untuk ditransfer aktualitasnya dalam masa sekarang ini
sesuai dengan makna yang dikehendaki teks pada masanya. Interpretasi ini dilakukan karena bahasa
dalam suatu waktu dan setting sosial tertetu memiliki konteksnya sendiri, dan untuk memahaminya adalah
dengan membacanya sebagai simbol-simbol dari pengalaman-pengalaman mental yang sama untuk
semua orang.[15]
Sedangkan filsafat fenomenologi membantu kita menemukan abstact noun dari suatu kondisi sosial yang
menjelaskan banyak hal dari kondisi itu. Fenomenologi sebagai “decscriptive analysis based on subjective
process” menunjukkan bahwa segala sesuatu bersifat multi-faced sehingga banyak perspektif untuk
memandang sesuatu dan sekaligus terbuka untuk penjelasan yang lain. Dalam konteks teologi, filsafat ini
mengajak pemahaman yang kokoh terhadap agama masing-masing, sekaligus dapat pula menghargai,
berkomunikasi, berdialog, bertemu dalam perjumpaan yang hangat dan saling menghargai penganut
agama lewat pijakan religousity yang mendalam yang melekat pada sanubari masing-masing pemeluk
agama.[16]
Dalam bidang keilmuan, keahlian transdisipliner semacam ini nampaknya menjadi tuntutan. Keahlian
seseorang dipandang lebih ideal apabila mampu melihat secara transparan disiplin ilmu lainnya. Artinya,
mengenal substansi ilmu lain sampai pada batas-batas tertentu bukan mesti menjadi multidisiplin ataupun
interdisiplin, melainkan mengenal beragam hal mengenai substansi banyak displin ilmu. Sehingga dalam
mengembangkan disiplin ilmunya sendiri, seseorang tahu wilayahnya, komplementasinya, maupun
kontradiksinya dengan disiplin ilmu yang lain. Sehingga suatu kajian keilmuan harus saling berdialog dan
“berkonsultasi” dengan disiplin ilmu yang lain. Misalnya ilmu-ilmu humaniora berkonsultasi kepada akidah,
imu-ilmu sosial berdialog dengan akhlak, sains dan teknologi berkonsultasi dengan syari’at agama, dan
seterusnya.[17]
D. Penutup
Filsafat yang lahir dari proses kreativitas berpikir dengan dinamika masyarakat dan dalam lingkup
historisnya memberi nilai berharga tentang bagaimana membangun tradisi tersebut. Tradisi untuk mencari
kebenaran dan bersemangat mencari, menyelami dan menemukan kebenaran fundamental secara kritis,
reflektif dan logis bagi perkembangan masyarakat. Proses kreatif para filosof juga meninggalkan jejaknya
berupa cara pandang, cara pikir dan cara merespon situasi sosialnya, dimana jejak metodologi tersebut
sangat bermanfaat bagi masyakat untuk melihat, menanggapi atau mengubah lingkungan sosialnya secara
bijaksana. Sehingga tidak menjadi “masyarakat kaget-an” (shock society) manakala melihat perubahan
yang begitu cepat.
Daftar Pustaka
Abdullah, Amin (a), Studi Agama, Normatifitas atau Historisitas, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
1996
_____________ (b), Filsafat Kalam di Era Postmodernisme, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
1997
Asy’arie, Musa, Filsafat Islam Sunnah Nabi Dalam Berpikir, LESFI, Yogyakarta, 1999
Beltran, Federico Villagas, The Jakarta Pos, Vol. 23 No. 144, Monday, September 19, 2005
Bertens (a), K., Ringkasan Sejarah Fislafat, Kanisius, Jakarta, 1976
______ (b), Sejarah Filsafat Yunani, Kanisius, Yogyakarta, 1980
Mudhafir, Ali, Teori dan Aliran dalam Filsafat Teologi, Gadjah Mada University Press,
Yogyakarta
Muhadjir, Noeng, Integrasi Filosofis Ilmu dengan Wahyu Pengembangan Metodologi Telaah
Ilmu Masa Depan, dalam Fuaduddin dan Cik Hasan Bisri (ed), Dinamika Pemikiran di
Perguruan Tinggi, Wacana Tentang Pendidikan Agama Islam, Logos, Jakarta, 2002
Russell, Bertrand, Sejarah Filsafat Barat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
Siswomihardjo, Koento Wibisono, Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme August
Comte, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 19965
Sumaryono, E., Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 1999
Titus, Harold, Living Issues in Philosophy, Introductory Text Book, New York, 1959
Anda mungkin juga menyukai
- Mengapa Kita Perlu Belajar FilsafatDokumen2 halamanMengapa Kita Perlu Belajar FilsafatBagus GinanjarBelum ada peringkat
- Idealisme Transendental KantDokumen190 halamanIdealisme Transendental KantNaufal IhsanBelum ada peringkat
- Pedum Ke Organisasian MahasiswaDokumen17 halamanPedum Ke Organisasian MahasiswaAkang Iyan El Tsauri100% (1)
- (Periode Orde Baru) Nurcholish Madjid Whistle Blower Pembaharuan IslamDokumen15 halaman(Periode Orde Baru) Nurcholish Madjid Whistle Blower Pembaharuan IslamFathönyBelum ada peringkat
- Sistem Belajar Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Baduy Luar - Salwa Salsabila - Sofwun NidaDokumen10 halamanSistem Belajar Yang Diterapkan Oleh Masyarakat Baduy Luar - Salwa Salsabila - Sofwun NidaSofwun NidaBelum ada peringkat
- Sejarah Dinamika Hubungan Pmii Dan NuDokumen89 halamanSejarah Dinamika Hubungan Pmii Dan NuAida Sofia Az-zubeirBelum ada peringkat
- Perancangan Pengembangan Kawasan Wisata Kampung Lali GadgetDokumen49 halamanPerancangan Pengembangan Kawasan Wisata Kampung Lali GadgetSilvia LuthfiyahBelum ada peringkat
- MakalahDokumen15 halamanMakalahariBelum ada peringkat
- Laporan BukuDokumen13 halamanLaporan BukuAfni RamadhaniBelum ada peringkat
- Posisi Perempuan Etnis Minangkabau Dalam 6d210ce4Dokumen19 halamanPosisi Perempuan Etnis Minangkabau Dalam 6d210ce4dianBelum ada peringkat
- Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan NegaraDokumen6 halamanBhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negaraarif_ahaBelum ada peringkat
- 13 MaterialismeDokumen19 halaman13 MaterialismeAgus MuizzBelum ada peringkat
- Filsafat Komunikasi Dr. AangDokumen138 halamanFilsafat Komunikasi Dr. AangRafli hariyantoBelum ada peringkat
- Soal UAS - Pendidikan Pancasila - ABNDokumen1 halamanSoal UAS - Pendidikan Pancasila - ABNAmalia Prantika0% (1)
- Keanekaragaman BudayaDokumen11 halamanKeanekaragaman BudayaLihin Bello SPBelum ada peringkat
- Tokoh-Tokoh Pendidikan DuniaDokumen153 halamanTokoh-Tokoh Pendidikan DuniaLailatul Fitriya67% (3)
- Clifford Geertz, Politik MaknaDokumen16 halamanClifford Geertz, Politik MaknaRadja GorahaBelum ada peringkat
- Ajaran Etika StoaDokumen26 halamanAjaran Etika StoaSonia DamarmowoBelum ada peringkat
- Tugas PkwuDokumen4 halamanTugas PkwuFebrianty HeraBelum ada peringkat
- ALIRAN FILSAFAT (Realisme, Idealisme, Positivisme)Dokumen16 halamanALIRAN FILSAFAT (Realisme, Idealisme, Positivisme)amanahBelum ada peringkat
- ANIMISME Dan MAGIS + AGAMA Dan KEPRIBADIANDokumen10 halamanANIMISME Dan MAGIS + AGAMA Dan KEPRIBADIANDzulfikar NasrullahBelum ada peringkat
- Esai p2m Maskur RoisDokumen4 halamanEsai p2m Maskur RoisM RoisBelum ada peringkat
- Pemilihan Kepala DesaDokumen39 halamanPemilihan Kepala DesaSuara KaliangetBelum ada peringkat
- Manusia Dan Tradisi - Tradisi Bersih DesaDokumen12 halamanManusia Dan Tradisi - Tradisi Bersih DesaFauziah Husnaa100% (1)
- Makalah Konsep Kuasa Michel Foucault Untuk Analisis Wacana KritisDokumen15 halamanMakalah Konsep Kuasa Michel Foucault Untuk Analisis Wacana KritisHumaidyNurSaidyBelum ada peringkat
- Sejarah Dan Filsafat PancasilaDokumen14 halamanSejarah Dan Filsafat PancasilaOvy Prima DamaraBelum ada peringkat
- Gerakan Mahasiswa Pasca NKKDokumen13 halamanGerakan Mahasiswa Pasca NKKandriansyaheko_p3985Belum ada peringkat
- Pengertian Agama Dan Filosofi AgamaDokumen29 halamanPengertian Agama Dan Filosofi AgamaMiranda Roulina TampubolonBelum ada peringkat
- Hubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu PolitikDokumen3 halamanHubungan Hukum Tata Negara Dengan Ilmu PolitikdewaayuBelum ada peringkat
- Filsafat YunaniDokumen16 halamanFilsafat YunaniNusye ManuputtyBelum ada peringkat
- Pendidikan Sebagai Proses PembebasanDokumen11 halamanPendidikan Sebagai Proses PembebasanHinata ShoyoBelum ada peringkat
- Antropologi Pendidikan 1Dokumen9 halamanAntropologi Pendidikan 1Defrin YksBelum ada peringkat
- Pendidikan PolitikDokumen9 halamanPendidikan Politikkarina lestariBelum ada peringkat
- Antropologi Clifford GeertzDokumen18 halamanAntropologi Clifford GeertzHerman1212Belum ada peringkat
- Adoc - Pub Terapi Berpikir Positif Read by Ibrahim Elfiky EboDokumen67 halamanAdoc - Pub Terapi Berpikir Positif Read by Ibrahim Elfiky EboZhaldy PantoiyoBelum ada peringkat
- Alpendri Resume Filsafat LogikaDokumen22 halamanAlpendri Resume Filsafat LogikaAlfendry YusufBelum ada peringkat
- Sejarah Filsafat TimurDokumen6 halamanSejarah Filsafat TimurJonathan Jason WiliantoBelum ada peringkat
- Kopri 1Dokumen119 halamanKopri 1nur robiatulBelum ada peringkat
- Makalah Pendidikan PancasilaDokumen18 halamanMakalah Pendidikan PancasilaJatmiko Wijaya KusumaBelum ada peringkat
- Tugas Skenario MuasilaturrahmiDokumen4 halamanTugas Skenario Muasilaturrahmishiyll rahmiBelum ada peringkat
- Rundown Acara Pembekalan KKL MahasiswaDokumen1 halamanRundown Acara Pembekalan KKL Mahasiswaeka nrftBelum ada peringkat
- Mbah GleyorDokumen3 halamanMbah GleyorNiKi Niken100% (1)
- Reaction Memo: Awal Mula Psikologi Dari Filsuf YunaniDokumen2 halamanReaction Memo: Awal Mula Psikologi Dari Filsuf YunaniAlifia NurochimBelum ada peringkat
- Harry S.broudlyDokumen4 halamanHarry S.broudlyChoo Ying FarBelum ada peringkat
- Identitas Dan Komunikasi Antar Budaya Di IndonesiaaDokumen3 halamanIdentitas Dan Komunikasi Antar Budaya Di IndonesiaaLilik Sayank DyaBelum ada peringkat
- Teori Atau Pemikiran Politik Menurut MachiavelliDokumen5 halamanTeori Atau Pemikiran Politik Menurut MachiavelliRayhan SipaBelum ada peringkat
- Warisan Budaya BantenDokumen11 halamanWarisan Budaya Bantendoyok sukandiBelum ada peringkat
- Diskursus Paradigma PMIIDokumen2 halamanDiskursus Paradigma PMIIDebby Andrean Ady MahardikaBelum ada peringkat
- Tradisi Nitik: Studi Etnografi Tradisi Minum Toak Di Kabupaten Tuban, Jawa TimurDokumen139 halamanTradisi Nitik: Studi Etnografi Tradisi Minum Toak Di Kabupaten Tuban, Jawa TimurDarundiyo Pandupitoyo, S. Sos.83% (6)
- Makalah - Etika & Budaya Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik MahasiswaDokumen7 halamanMakalah - Etika & Budaya Politik Dalam Peningkatan Partisipasi Politik MahasiswaeonekeyBelum ada peringkat
- Fikri Fathurrahman-Esensi Ajaran Islam Tentang Keadilan Sosial Dan Ekonomi-Hmi Cabang MajalengkaDokumen20 halamanFikri Fathurrahman-Esensi Ajaran Islam Tentang Keadilan Sosial Dan Ekonomi-Hmi Cabang MajalengkaHari HernawanBelum ada peringkat
- Kebijaksanaan Dalam HidupDokumen6 halamanKebijaksanaan Dalam HidupSaifuddin NurBelum ada peringkat
- Tugas Filsafat HikmahDokumen8 halamanTugas Filsafat HikmahAnonymous DrO4uGBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen9 halaman1 SMAbu BakarBelum ada peringkat
- KEL. 12 - Artikel FilsafatDokumen10 halamanKEL. 12 - Artikel FilsafatDesi SetiawatiBelum ada peringkat
- Soal MK FilsafatDokumen2 halamanSoal MK Filsafatrudi rahmaBelum ada peringkat
- Tugas DinaeDokumen7 halamanTugas DinaeSindra TBelum ada peringkat
- Titik Pertemuan Falsafah Dan Kehidupan PraktisDokumen11 halamanTitik Pertemuan Falsafah Dan Kehidupan PraktisCinda Si IndarellaBelum ada peringkat
- Konsep Dasar FilsafatDokumen5 halamanKonsep Dasar FilsafatyasirlanaBelum ada peringkat
- Pengaruh Filsafat Bagi Kehidupan ManusiaDokumen11 halamanPengaruh Filsafat Bagi Kehidupan ManusiaNi Ketut Sri SuciatiBelum ada peringkat
- Sumathi AssignmentDokumen10 halamanSumathi AssignmentRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Islam Dan SekularismeDokumen14 halamanIslam Dan SekularismeFuadh NaimBelum ada peringkat
- Peperiksaan DalamanDokumen1 halamanPeperiksaan DalamanRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Perubahan IklimDokumen2 halamanPerubahan IklimRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Borang MarkahDokumen1 halamanBorang MarkahRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Definisi Keluarga BahagiaDokumen6 halamanDefinisi Keluarga BahagiaAzreen AhmadBelum ada peringkat
- Sejarah India ModenDokumen4 halamanSejarah India ModenRavi Kumar Nadarashan100% (1)
- Perubahan IklimDokumen2 halamanPerubahan IklimRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Jadual PencerapanDokumen1 halamanJadual PencerapanRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Borang Markah Keceriaan Kelas Abad 21Dokumen1 halamanBorang Markah Keceriaan Kelas Abad 21Ravi Kumar Nadarashan100% (1)
- Peperiksaan DalamanDokumen1 halamanPeperiksaan DalamanRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- skpmg2 Standard 3.2Dokumen49 halamanskpmg2 Standard 3.2Dik Ee KhoziBelum ada peringkat
- Agenda 5 Tamil Kedua 19Dokumen1 halamanAgenda 5 Tamil Kedua 19Ravi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Ikrar PengawasDokumen2 halamanIkrar PengawasRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Borang Markah Keceriaan Kelas Abad 21Dokumen1 halamanBorang Markah Keceriaan Kelas Abad 21Ravi Kumar Nadarashan100% (1)
- skpmg2 Standard 3.2Dokumen21 halamanskpmg2 Standard 3.2Ravi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Pelan PerarakanDokumen3 halamanPelan PerarakanRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Contoh Watikah Pelantikan Pengawas SekolahDokumen2 halamanContoh Watikah Pelantikan Pengawas SekolahRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Hubungan EtnikDokumen25 halamanHubungan EtnikRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Kertas Kerja Pondok BacaanDokumen5 halamanKertas Kerja Pondok BacaanRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- skpmg2 Standard 3.2Dokumen49 halamanskpmg2 Standard 3.2abuan81Belum ada peringkat
- Kertas Kerja Pondok BacaanDokumen5 halamanKertas Kerja Pondok BacaanRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Dasar Kurikulum SJKTDokumen13 halamanDasar Kurikulum SJKTRavi Kumar Nadarashan100% (1)
- INSTRUMEN PEMANTAUAN KENDIRI PPDa 2017Dokumen6 halamanINSTRUMEN PEMANTAUAN KENDIRI PPDa 2017Elyana Ismail100% (1)
- JUT 101 Nota Bacaan TambahanDokumen18 halamanJUT 101 Nota Bacaan TambahanRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- BM Soalan 2Dokumen1 halamanBM Soalan 2Ravi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Didalam Sutta SappurisadhammaDokumen3 halamanDidalam Sutta SappurisadhammaRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Minit Hari PonggalDokumen4 halamanMinit Hari PonggalRavi Kumar NadarashanBelum ada peringkat
- Jadual Waktu Dan Tempat Peperiksaan Berterusan Kursus Universiti Di Pusat Wilayah Sa 2017-2018Dokumen1 halamanJadual Waktu Dan Tempat Peperiksaan Berterusan Kursus Universiti Di Pusat Wilayah Sa 2017-2018Ravi Kumar NadarashanBelum ada peringkat