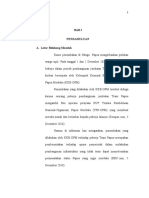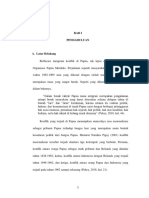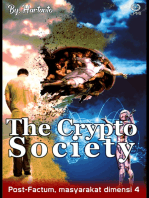Jurnalisme Damai dan Kekerasan Simbolik
Diunggah oleh
budi supraptoJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Jurnalisme Damai dan Kekerasan Simbolik
Diunggah oleh
budi supraptoHak Cipta:
Format Tersedia
JURNALISME DAMAI
Oleh : Budi Suprapto
Disfemisme Simbolik
Dengan mengadaptasi cerita dari St. Augustine, Noam Chomsky mengawali
penjelasannya tentang terminologi terorisme dengan membuat sebuah ilustrasi yang
sangat mengena. Di kisahkan, seorang bajak laut tertangkap dan dihadapkan kepada
Iskandar Agung. “Berani benar kau mengacau laut,” kata Sang Kaisar dengan nada
sinis. Tanpa disangka si bajak laut kontan menjawab dengan tak kalah sinis pula,
“Berani betul kau mengacau seluruh dunia. Karena saya melakukannya dengan hanya
dengan sebuah kapal kecil, maka saya disebut pencuri. Sedangkan kamu, yang sama-
sama pengacaunya, tapi karena menggunakan armada laut yang besar, maka kamu
disebut kaisar !”
Ilustrasi di atas secara “cerdas” memberi gambaran tentang bagaimana
penggunaan kata-kata yang berbeda untuk menjelaskan peristiwa yang sama, tapi
melahirkan makna yang jauh bertentangan. Dengan logika bahasa yang demikian
lanjut Comsky, maka tidak aneh jika opini publik dunia yang terbentuk berkenaan
dengan apa dan siapa terorisme dunia hanya melekat pada Palestina, Irak, Iran, Libia
dan negara-negara yang menentang AS dan kroninya. Sementara AS, Israel dan juga
Inggris yang menjadi biang pengacau tatanan dunia yang sebenarnya selalu
diposisikan sebagai dewa pengayom yang adil dan harum baunya.
Jika rangkaian kata-kata adalah sisi tajan dari suatu berita yang ditembakkan
oleh media massa, maka tak mengherankan apabila seorang Napoleon Bonapartaij
pun merasa kecut berhadapan dengan pemberitaan daripada dengan sepuluh peleton
serdadu bersenjata lengkap. Mungkin kita masih ingin bertanya, “Apakah ia lebih
tajam dibanding pedang? Jika bahasa berita hanyalah sebuah simbol dari suatu
makna, apakah sebuah makna memiliki kekuatan penghancur, sehingga diperlukan
keahlian, kesadaran dan kearifan atau bahkan pengendalian khusus (seperti
pengalaman jaman orba) untuk menyampaikannya?”
Budhi Suprapto Page 1
Apapun jawaban atas pertanyaan di atas, adalah suatu fakta bahwa media
massa memiliki kekuatan cukup dahsyat dalam membentuk sikap dan perilaku
masyarakat. Begitu kuatnya kemampuan media tersebut, sehingga McLuhan berani
berkata bahwa pada saat ini masyarakat sudah menganggap, simbol bahasa yang
disajikan oleh media adalah realitas yang sebenarnya, the mass media is massage.
Dari pernyataan McLuhan tadi dapat diartikan, bahwa sebenarnya rangkaian kata
yang menjadi berita tersebut menjadi sangat tajam, setelah ia dimuat oleh oleh media
massa. Jika hal ini benar, maka akan lebih mengerikan lagi jika dalam prakteknya,
ternyata media massa lebih suka menyajikan suatu pesan yang oleh Jean Baudrilard
disebutnya sebagai penciptaan dunia simulacra atau hiperiality. Artinya media massa
tidak menyajikan gambaran realitas yang sebenarnya, melainkan realitas semu
melalui perekayasaan, yang dapat menimbulkan metaforisme, hiperbolisme atau atau
bahkan distorsi makna. Ulah media yang semacam itu akhirnya melahirkan juga
kebenaran semu di tengah masyarakat yang lebih dikenal dengan istilah pseudosophy.
Bahkan Yasraf Amir Piliang menangkap terjadinya perekayasaan melalui
pilihan kata-kata oleh media massa, yang mengarah pada kekerasan simbolik.
Menurutnya media massa telah menjadi lahan yang subur bagi bentuk kekerasan
semacam ini, sebab pers sangat memungkinkan terjadinya distorsi, pelencengan,
plesetan, pemalsuan serta pengerasan secara simbolik –misalnya sajian berita
dengan gaya hard news-- yang meskipun bentuk kekerasan semacam ini memang
tidak tampak secara awam. Hal itu sangat terasa, misalnya pada pemebritaan tentang
konflik antar kelompok, olah raga maupun sajian kriminalitas. Di mana media massa
telah menyuguhkan dan sekaligus menjadi ajang tontonan kekerasan di mata publik,
dengan menyajikan foto-foto yang menunjukkan mayat atau wajah dan tubub si
korban yang bergelimpangan bersimbah darah. Kemudian pada kesempatan lain
media massa menampilkan segerombolan orang dengan wajah beringas membawa
senjata yang siap menikam lawan. Belum lagi teks-teks berita yang lebih banyak
menggunakan kata atau kalimat yang berkonotasi keras (disfimisme). Contohnya
dalam konflik antara etnik Madura dengan Dayak/Melayu, aktifitas etnik Dayak
Budhi Suprapto Page 2
mencari orang-orang Madura dikatakan sebagai aksi “perburuan”. Di sini terjadi
konstruksi makna yang menggiring pemahaman publik pada aktifitas para pemburu
yang sedang mengejar binatang buruan di tengah-tengah hutan, sekaligus
memposisikan etnik Madura sederajad dengan binatang liar yang tak berdaya. Di sisi
lain dengan kata “perburuan”, juga memberi efek pada gambaran tentang kebiadaban
suku Dayak. Media juga sering menggunakan kata “membabat, membasmi,
mengusir, pembersihan etnis” dan sejenisnya, yang memiliki makna menghilangkan
hakekat nilai kemanusian. Karena kata membabat secara umum berkenaan dengan
tumbuhan atau rerumputan; membasmi/mengusir diperuntukkan bagi binatang atau
hama; sedang pembersihan berkaitan dengan sesuatu yang kotor dan menjijikkan.
Untuk menambah bukti betapa mass media telah ikut menyebarkan kekerasan, J.
Anto menyodorkan beberapa contoh penggunaan kalimat yang dikutip dari
pemberitaan beberapa media cetak :
“Saya telah memakan jantung dari seseorang.”
“Ratusan kepala digantung tanpa anggota tubuh.”
“Mereka didatangi ratusan orang, kemudian langsung membabat dengan senjatanya,
darahpun mengalir.”
Menyimak lebih lanjut pemberitaan tentang konflik dan peristiwa kekerasan
(sex and crime), nampak sekali pers telah melakukan pengerasan terhadap realitas.
Bahkan disadari atau tidak, pers telah melesakkan dirinya ke dalam jurnalisme
perang. Inilah yang dimaksud dengan kekerasan simbolik oleh pers. Meskipun
kekerasan simbolik ini tidak melukai secara fisik, kata J. Anto, namun ia dapat
menjadi pemantik bagi konflik lanjutan dalam arti yang sebenarnya.
Sebenarnya pengerasan terhadap realitas oleh pers tidak hanya berlaku bagi
peristiwa konflik yang berdarah-darah atau violence, tapi juga dilakukan untuk berita-
berita lain, seperti berita politik, olah raga dan bahkan seni. Beberapa kutipan berikut
– baik judul maupun lead berita – dapat menunjukkan hal dimaksud :
“Megawati ‘Bangkangi’ Gus Dur” di KTT G-15”
“Jeweran Mega Buat Mas Dur”
Budhi Suprapto Page 3
“Kontroversi Anak Kepala Kantor Pos” (tentang Rahardi Ramelan)
“Dana Bulog menggoyang Beringin …. Perseteruan antar kelompok kian
meruncing”
“PSM Melibas Persija 2-0”
“Bahasa Laki-laki Sudah Sekarat” (tentang pameran lukisan karya pelukis wanita)
“Siswi SMP Digilir Lima Pemuda”
Kutipan di atas adalah cara penyajian judul atau lead dengan gaya pengerasan
(hard news). Cara ini mencerminkan keinginan redaksi untuk lebih menonjolkan
adanya unsur konflik dalam berita yang diketengahkan, daripada sekedar memberikan
informasi yang memadai dan membiarkan publik memberikan apresiasinya sendiri.
Artinya sejak pemilihan kata-kata untuk judul, pembaca sudah digiring pada
konstruksi pemahaman tertentu, yaitu berkenaan dengan konflik.
Mengapa nuansa konflik sangat disenangi oleh pers kita? Hal itu bisa
disebabkan dari beberapa factor. Pertama bisa dirunut dari konsep tentang nilai berita
yang diajarkan dan dipelajari oleh para jurnalis. Secara konsepsual, salah satu
peristiwa yang mengandung nilai berita (news event) adalah peristiwa yang di
dalamnya mengandung konflik. Kedua, faktor psikologis yaitu yang berkenaan
dengan selera rendah yang dimiliki oleh setiap manusia. Selera rendah ini sering
mendorong manusia untuk lebih senang menikmati konflik, kekerasan, gossip dan
seks di luar dirinya. Itulah sebabnya media yang mengkhususkan diri untuk berita-
berita tentang sex and crime yang disebut sebagai koran kuning, sering memiliki
oplagh yang tinggi.
Ketiga, dalam konteks Indonesia, jurnalis kita sedang mengalami euphoria on
freedom of the press, di mana selama 32 tahun dalam naungan pers pancasila yang
represif dan full sensorship. Lepasnya belenggu dari tangan pers yang dialaminya
bertahun-tahun tersebut, menyebabkan pers kita jadi serba gamang. Bahkan dalam
situasi konflik antar etnis, agama dan golongan (SARA) yang melanda tanah air
akhir-akhir ini, menurut Stanley Adi Prasetyo, pers Indonesia dapat dikatakan tak
Budhi Suprapto Page 4
memeiliki pengalaman. Selama orba pers dilarang memberitakan tentang SARA.
Meskipun saat ini sudah terbuka pintu kebebasan, tapi pers kita belum mampu dan
tak punya strategi untuk menurunkan liputan mengenai konflik yang mengandung
SARA. Akibatnya, lanjut Stanley, tak ada satupun media yang mampu menempatkan
dirinya sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik.
Eufimisme : Menenangkan Atau Menyelamatkan Diri?
Dalam pandangan Stanley Adi Prasetyo, lahirnya ide jurnalisme damai
berawal dari kemuakan para jurnalis, akademisi dan masyarakat yang melihat adanya
sekelompok masyarakat yang menikmati sajian liputan perang sebagai sebuah
hiburan. Kemuakan itu menebal pada saat CNN melakukan siaran langsung detik
demi detik, saat Amerika melakukan Operasi Badai Gurun. Tidak hanya CNN, saat
itu semua media menonjolkan AS sebagai jagoan polisi dunia sambil memojokkan
Sadam Husain. Semua kampanye negatif ditujukan kepada Sadam yang digambarkan
sebagai cecunguk penyebab perang. Hal sama saat ini diulang kembali dalam pentas
perang antara AS versus Afganistan dan Irak. Padahal realitas yang ada adalah
pengeroyokan AS dengan sekutunya terhadap Irak dan Afganistan yang
menyebabkan ketidakseimbangan posisi dan kekuatan. Di samping itu dalam medan
perang Afganistan dan Irak akhirnya jelas tersembul adanya agenda tersembunyi
yang dibawa oleh masing-masing masing anggota kelompok sekutu (agresor),
meskipun mereka mati-matian berusaha mengkomuflasenya dengan pernyataan
tentang adanya kekuatan-kekuatan distruktif (yaitu Sadam Husain dan Osamah bin
Laden bersama Al Qaida-nya) yang akan menghancurkan peradaban dan
mengganggu perdamian dunia.
Agenda tersembunyi yang dimaksud antara lain: dari pihak Amerika adalah
untuk merebut wilayah dan penguasaan sumber daya alam yang ia butuhkan, baik
untuk kepentingan ekonomi maupun strategi politik global. Masalah ini sudah banyak
dikemukakan oleh banyak analis. Lebih dari itu, yang paling nyata dan mengerikan
adalah sebuah kegiatan uji coba persenjataan baru yang dimiliki oleh negara adidaya
Budhi Suprapto Page 5
ini. Untuk yang terakhir ini sangat sering diungkapkan oleh mass media, yang secara
tidak sadar mereka (media massa) juga ikut terkagum-kagum.
Bagi Inggris, bergabungnya ia dengan Amerika adalah untuk memperkuat
posisinya di antara negara-negara Eropa Barat. Hal itu bagi Inggris menjadi penting,
sebab secara ekonomis, sejak menguatnya keinginan negara-negara Eropa untuk
memberlakukan penyatuan mata uang, yaitu Euro, maka secara berangsung-angsur
pengaruh mata uang ponsterling sebagai nilai tukar semakin kurang diperhitungkan.
Demikian pula pengaruh Inggris sebagai salah satu motor MEE (Masyarakat
Ekonomi Eropa) semakin menurun. Oleh karena itu melalui pertemanan yang akrab
dengan Sang Adidaya, negara ini berharap bisa menguatkan pengaruhnya secara
global.
Sementara itu mengekornya Australia dengan sekutu, adalah lebih didorong
oleh nafsu lama, yaitu agar Australia tetap diakui sebagai bagian ‘negara barat’.
Meskipun ia secara geografis berada di kawasan Pasifik, tapi secara kultural bangsa
Australia selalu merasa sebagai bangsa Eropa (bahkan kaum konservatifnya tetap saja
merasakan Australia sebagai bagian dari kerjaan Inggris Raya). Di samping itu dalam
perspektif global, terutama untuk mencari dukungan bagi kepentingannya di kawasan
Asia-Pasifik, pemerintah Australia yakin akan lebih efektif bila ia bisa menjadi
ekornya Amerika dan Inggris.
Dalam realitas pemberiataan media massa, bukan berbagai agenda
tersembunyi tersebut yang diangkat, tapi justru kehebatan tentara sekutu dalam
meluluhlantakan bumi Afganistan dan Irak, tanpa mempedulikan betapa
menderitanya rakyat di kedua negara yang menjadi korban kepongahan para agresor.
Secara rinci media massa mengungkapkan betapa hebat dan canggihnya berbagai
jenis peluru kendali yang dimiliki mereka. Kecanggihan itu tidak hanya pada
kemampuannya medeteksi dan menghajar sasaran yang berada di permukaan tanah,
tapi juga yang berada di bawah tanah. Dijelaskan, peluru kendali jenis tertentu malah
sanggup memasuki lorong-lorong gua atau mengendus ke bawah permukaan tanah
untuk menemukan sasaran dan meledakkannya. Di sini jelas, yang terjadi adalah
Budhi Suprapto Page 6
realisasi atas agenda tersembunyi dari para agresor, dan sekaligus ladang uji coba
persenjataan mutakhir.
Jika sekutu menjatuhkan bom dan memakan korban ratusan warga sipil,
maka media massa pun mengutip pernyataan sekutu yang mengatakan, bahwa
pihaknya hanya menyerang sasaran militer. Dan tak lupa menuding, bahwa Sadam
atau Taliban menjadikan warga sipilnya sebagai tameng hidup. Sementara di pihak
yang dibom serta-merta menolak dengan menyatakan, yang dibom sekutu adalah
tempat perlindungan yang dibangun pemerintah untuk warga sipil atau malah betul-
betul perkampungan sipil. Lho, siapa yang betul?
Cara demikian dilakukan oleh media massa, dengan alasan untuk memberi
keleluasaan kepada khalayak dalam memberikan apresiasi secara independent atas
setiap peritiwa berita. Tetapi tatkala media massa tanpa bersedia memberikan
informasi alternatif atas apa yang mereka beritakan, meskipun mungkin sudah
memenuhi asas cover both side, penyajian peristiwa berita yang mengandung nilai
kekerasan semacam itu justru akan menimbulkan kebingungan dan kecemasan di
tengah khalayak. Dalam perspektif psiko-sosial, bagi anggota khalayak yang
mengandalkan informasi semata-mata dari media massa (misalnya pecandu televisi,
heavy watcher) rasa cemas dan bingung tersebut lama-kelamaan akan terkultivasi ke
dalam benak mereka. Jika hal itu terjadi, maka akan berakibat pada pola pemaknaan
mereka atas realitas tatanan pergaulan sosial.
Menurut teori kultivasi, seseorang akan menganggap relaitas yang disajikan
media massa adalah realitas yang sebenarnya; sehingga mereka memaknai realitas
dunia luar adalah sama dengan realitas yang ditampilkan oleh media massa. Dengan
kata lain jika mereka sering menyantap sajian kekerasan lewat media massa, maka
mereka akan menganggap bahwa realitas tatanan sosial juga dipenuhi dengan
kekerasan. Akibat lebih jauh, mereka takut untuk keluar rumah dan bergaul dengan
anggota masyarakat yang lain, terutama dengan yang tidak mereka kenal dengan baik.
Hal yang demikian menurut Robert Putnam, jika terjadi pada diri anak-anak, akan
sangat mengganggu perkembangan psiko-sosial mereka.
Budhi Suprapto Page 7
Di sisi lain juga harus diakui adanya sebagaian anggota masyarakat yang
menjadikan berita perang atau kekerasan sebagai hiburan. Menyadari akan hal itu,
pengelola media massa pun tak segan-segan menjadikan sajian atau rubrik berita
kekerasan sebagai sarana yang efektif untuk menarik rating iklan. Itulah yang
dilakukan oleh para pengelola televisi kita saat ini. Bahkan agar lebih menarik
sebagai hiburan, tehnik penyajiannya pun dikemas sedemikian rupa, misalnya lewat
intonasi dan atau kostum para penyiarnya.
Hanya yang menjadi masalah adalah, apakah sajian semacam itu secara moral
bisa dibenarkan? Dari sini mulailah muncul gagasan untuk melakukan pemikiran
ulang tentang perilaku dan nilai-nilai jurnalisme, agar tidak menjadikan konflik
sebagai nilai berita yang paling utama. Upaya itu memperoleh penguatan yang sangat
berarti dari Johan Galtung, seorang professor yang pakar perdamian, dan kawan-
kawannya lewat salah satu kuliah musim panasnya di Tap Low Court, Inggris pada
Agustus 1997. Dalam kuliah yang dihadiri oleh berbagai kalangan dari berbagai
kebangsaan tersebut, berhasil merumuskan konsep yang mereka sebut sebagai
jurnalisme damai, yang diperlawankan dengan jurnalistik perang, jurnalistik konflik
atau jurnalistik kekerasan (lihat Tabel).
Memang wartawan tentu saja harus punya kiat tersendiri dalam meliput
peristiwa yang berbau konflik atau bernuansa SARA. Misalnya saja dengan menunda
detail peristiwa. Hal ini mesti dilakukan, sebab meskipun awalnya peristiwa itu
hanyalah kriminal biasa, jika pernyataan yang mebawa-bawa agama dan asal usul
etnis tidak dihindari, salah-salah dapat membawa petaka. Hal ini sudah terbukti pada
kasus Dayak dan Madura dan juga Maluku. Lebih baik dilakukan penghalusan
(eufimisme) dan mendahulukan pernyataan pejabat. Harus melakukan check and
rechecking, untuk menghindari isue yang bersifat desas-desus dan pernyataan dari
sumber yang tidak bertanggung jawab. Ini berarti menuntut adanya investigative
report, cover both side, balancing reporting dan ditulis dengan gaya soft news.
Hendaklah dihindari juga pernyataan nara sumber yang disampaikan secara
emosional.
Budhi Suprapto Page 8
Sering juga terjadi –mungkin disebabkan belum dewasanya masyarakat kita,
atau mungkin juga tidak dewasanya pers kita?-- suatu amuk massal dari pihak-pihak
yang bertikai sebagai akibat dari pemberitaan pers yang mereka nilai kurang
menguntungkan/memojokkan pihaknya. Hal itu dapat dikurangi dengan
menggambarkan penderitaan korban yang dialami di kedua belah pihak. Dengan cara
ini diharapkan mereka yang ingin meneruskan pertikaian bisa berfikir ulang.
Hanya saja pekerja pers juga harus cerdas bahkan mungkin waspada, sebab
jika tidak, pendekatan “penghalusan” ini bisa menjebak kepada perilaku self
sensorship dalam diri lembaga pers, yang pada dasarnya adalah jurnalistik cari
selamat, yang sebenarnya sama saja tidak ‘cerdas’ dan tidak ‘mencerdaskan’. Lebih
parah lagi jika para jurnalisnya juga bekerja dengan pendekatan talking jurnalism,
yang mengedepankan kaidah : the big name is big news, no name no news. Kaidah ini
menjadi sangat berbahaya, kala mana suatu isue yang sebenarnya masih dalam taraf
“pernyataan” tapi atas bantuan pers –yang tanpa melakukan konfirmasi dengan
berbagai pihak— dapat mengubahnya menjadi “kenyataan”.
Dalam situasi konflik, menurut hasil elaborasinya Stanley Adi Prasetyo,
Eriyanto dan Muhammad Qudori, ada tiga posisi media yang menjadi kekuatan dan
sama-sama berpeluang besar untuk dimainkan. Pertama sebagai the issue intensifier,
dengan cara memblow-up realitas yang menjadi isue secara tajam dan transparan.
Kedua, sebagai diminisher, yaitu media menenggelamkan realitas yang menjadi isue,
sampai-sampai realitas (konflik) itu menjadi kabur atau bahkan meniadakan. Hal ini
sering diberlakukan terutama bila menyangkut kepentingan media itu sendiri. Ketiga,
media massa bisa juga bertindak sebagai pengarah conflict resolution, yakni dengan
menjadi mediator melalui pemberitaan yang menampilkan isue dari berbagai
perspektif serta mengarahkan pihak-pihak yang bertikai pada penyelesaian konflik.
Dengan perspektif pemberitaan yang lengkap, pihak yang terlibat diharapkan dapat
memahami sudut pandang pihak lain, mengatasi prasangka dan kecurigaan serta
mengevaluasi ulang sikap dasar yang terbentuk semula.
Budhi Suprapto Page 9
Apa yang baru saja disebutkan di atas masih pada tataran diskursus
konsepsual atau lebih pada wilayah das sollen. Sedangkan dalam tataran praktek,
kekuatan media dapat tercermin lewat proses framing, pengemasan dan
penggambaran realita (misalnya pengurangan dan penambahan foto), penentuan
angle, writing tyle dan lain-lain. Sebagaimana dibeberkan oleh Gadi Wolfsfeld,
bahwa dalam suatu konflik politik, masing-masing pihak memiliki ketergantungan
terhadap informasi yang disediakan oleh media, terutama yang independen. Dengan
cara ini masing-masing dari mereka dapat saling mengkalkulasi keberadaan diri dan
lawannya. Oleh karena itu dalam melakukan framing berita konflik, ada tiga elemen
utama yang perlu diperhatikan oleh media massa, yaitu persitiwa yang terjadi seerta
sumber beritanya, pentingnya untuk menyusun (menkonstruksi) berita secara
memadai (compreshensiveness) dan perlunya bangunan cerita yang memiliki
resonansi politik tertentu.
Hanya sayangnya, dalam praktek pers kita kurang atau bahkan tidak
menerapkan kaidah-kaidah provetic jurnalisme, sebagaimana yang sering menjadi
acuan di dunia pers negara-negara maju. Lebih dari itu, juga kurang disadarinya oleh
pekerja pers kita, bahwa sesungguhnya pembuatan suatu berita tiada lain adalah
penyusunan realitas (construction of reality) secara subyektif oleh si pembuat berita.
Secara ekstrim dikatakan oleh Ibnu Hamad, bahwa berbagai pihak yang terlibat
dalam peliputan dan penyiaran berita adalah hanya menyusun atau mengurutkan
realitas yang semula terpenggal-penggal secara acak menjadi tersistematis dalam
bentuk sebuah cerita yang mengalir yang enak dibaca, didengar dan ditonton. Just it
all, not over or less.
Untuk membuktikan kesimpulannya itu Ibnu Hamad mengajak merunut isi
media itu sendiri. Di mana seluruh isinya adalah hasil konstruksi atas realitas
peristiwa, dalam bentuk realitas simbolik, yaitu bahasa, berupa berita dan cerita.
Sementara itu realitas yang sebenarnya tetap berada “di luar sana”. Isi media
hanyalah gambaran (konseptualisasi) beberapa penggal dari banyak peristiwa yang
berhasil diliput wartawan.
Budhi Suprapto Page 10
Sebagai khalayak, setiap hari kita menerima berbagai realitas yang telah
dibahasakan (simbolisasi) oleh media massa. Jika masyarakat menjadikan media
massa sebagai sumber informasi utama, maka tidak menutup kemungkinan,
pemakaian bahasa oleh media ikut menentukan secara massif gambaran realitas yang
tertanam di benak masyarakat. Hal ini juga diyakini oleh Walter Lippmann lewat
penegasannya, bahwasannya interpretasi media massa atas berbagai peristiwa (the
meaning construction of the press), secara radikal dapat mengubah atau
mempengaruhi interpretasi orang tentang suatu realitas dan pola tindakan mereka. Hal
ini sangat sejalan dengan penelitian Signorelli dan kawan-kawan yang menemukan,
bahwa pecandu berat TV khususnya yang banyak tayangan kekerasan, cenderung
takut pada dunia sekelilingnya. Padahal dalam the real life tidaklah demikian.1)
Implikaasi Moral dan Hukum
Defimisme sebagaimana diceritakan pada awal tulisan ini, sebenarnya dapat
digolongkan sebagai perbuatan kejahatan. Meminjam istilahnya George Orwell
kejahatan semacam itu sering disebut sebagai news-speak atau kejahatan dengan
bahasa. Artinya tindakan seseorang, kelompok atau institusi yang karena
kekuasaannya mengendalikan makna di tengah-tengah pergaulan sosial, melalui
media massa.2)
Andai keyakinan Lippmann di atas benar, lalu pers juga gemar melakukan
news-speak, –terlepas dari nuansa politik dari konsep ini, yang jelas pers sangat
berperan— dapat kita bayangkan betapa kasihannya masyarakat, karena mereka
setiap hari menyantap menu informasi yang bersifat hypereality. Ini berarti kita,
konsumen media, secara tidak sadar juga bisa menjadi korban perilaku kejahatan.
Oleh karena itu kontrol dan tindakan hukum menjadi sangat perlu dilakukan oleh
1)
Baca Roger D.Wimmer dan Joseph R.Dominick, 1991, Mass Media Research, Belmont, California, Wardworth Inc. hal. 157-
179.
2)
Dengan konsep ini Noam Chomsky menemukan bagaimana media barat telah dengan sengaja menggunakan istilah-istilah
yang memutarbalikkan fakta. Untuk pengendalian makna oleh pemerintah Orba, baca Yudi Latif & Idi Subandi I (ed),
1996, Bahasa dan Kekuasaan Politik Wacana di Panggung Politik Orde Baru, Bandung, Mizan.
Budhi Suprapto Page 11
masyarakat. Hanya masalahnya, seberapa besar masyarakat dan hukum punya
kekuatan? Sebab dalam kenyataan sejarah, kekuasaanlah yang selalu di atas sedang
hukum pun selalu setia mengabdi kepadanya?
Referensi :
Eriyanto dan Muhammad Qudori, Mempertimbangkan Jurnalisme Perdamaian,
Jurnal Pantau No. 09/2000
Gadi Wolfsfeld, 1999, Media and Political Conflict, News From The Middle East,
Cambridge, U.K., Cambridge University Press.
Ibnu Hamad, 1999, Media Massa dan Konstruksi Realitas, Jurnal Pantau No. 6, 1999
J. Anto, 2001, Media Sekedar Memindahkan Konflik, Jurnal Kupas, Vol.3 No.2
Tahun 2001.
Noam Chomsky, 1991, Menguak Tabir Terorisme Internasional, Bandung, Miszan.
Sean McBride (ed), 1983, Aneka Suara, Satu Dunia, Jakarta, PN Balai Pustaka-
Unesco.
Stanley Adi Prasetyo, 2001, Konflik dan Ide Jurnalisme Damai, Jurnal Kupas Vol.3
No.2, Tahun 2001.
Wilbur Scramm, 1957, Freedom of Speech and Mass Media Responsibility, New
York-London, Sage.
Walter Lippmann, 1998, Opini Umum, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Yusak Amir Piliang, 2001, Sebuah Dunia Yang Menakutkan : Mesin-mesin
Kekerasan Dalam Jagad Raya Chaos, Bandung Pustaka Mizan.
Budhi Suprapto Page 12
Perbedaan Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang
JURNALISME DAMAI JURNALISME PERANG
Penentuan 1. Fokus pada proses terjadinya 1. Fokus pada arena konflik: dua kubu
angle dan konflik : pihak-pihak yang terlibat, bertikai hanya satu tujuan, kemenangan,
focus penyebab konflik, permasalahan stiuasi peperangan, orentasi menang-
yang menyertai, orentasi pada opsi kalah.
‘menang-menang’ 2. Ruang dan waktu tertutup; sebeba akibat
2. Ruang dan waktu yang terbuka : terbata pada arena konflik, mencari
sebab akibat dalam perspektif siapa yang menyerang duluan.
sejarah. 3. Ada fakta yang sengaja disem-bunyikan.
3. Memberitakan koflik apa adanya 4. Berita memilahkan kita-mereka, nuansa
4. Memberikan ruang yang sama pada propaganda, suara dari dan untuk kita.
semua suara; menampilkan empati 5. Melihat mereka sebagai masalah, focus
dan pengertian pada siapa yang menang perang.
5. Melihat konflik sebagai masalah, 6. Dehumanisasi di pihak mereka,
focus pada hikmah konflik. humanisasi di pihak kita.
6. Melihat aspek kemanusian dari 7. Reaktif : menunggu terjadinya konflik
semua sisi. baru buat berita.
7. Proaktif : pencegahan sebelum 8. Fokus hanya pada dampak fisik
konflik atau perang terjadi kekerasan(pembunuhan,luka,kerugi
8. Fokus pada dampak non fisik an,materi)
kekerasan (trauma dan
kemenganan, kerusakan pada
struktur dan budaya masyarakat)
Oretasi 1. Membongkar ketidak benaran 1. Hanya mengungkap ketidakbenar-
liputan kedua belah pihak. an mereka dan menutupi ketidak-
2. Fokus pada penderitaan semua benaran kita.
yaitu perempuan, anak-anak, orang 2. Fokus pada penderitaan kita; memberi
tua; memberi suara pada koraban. suara hanya kepada panglima perang.
2. Menyebut pelaku kejahatan di 3. Menyebut pelaku kejahatan adalah pi-
kedua belah pihak. hak mereka.
3. Fokus pada penggiat perdamian di 4. Fokus pada penggiat perdamaian pada
tingkat akar rumput. tingkat elit.
Cara 4. Perdamaian = anti kekerasan + 1. Perdamaian = kemenangan + gencatan
pandang hikmah senjata.
terhadap 5. Mengangkat inisiatif perdamian dan 2. Menyembunyikan inisiatif perdamaian,
akhir men-cegah perang lanjutan. sebelum kemenangan diraih.
konflik 6. Fokus pada struktur dan budaya 3. Fokus pada fakta dan institusi
masyara-kat yang damai. masyarakat yang terkendali
7. Usai konflik: resolusi, rekonstruksi 4. Usai konflik siap bertempur lagi bila
dan rekonsiliasi luka lama kambuh.
1.
Diadaptasi dari The Peace Jurnalism Option, Transcend Peace and Development Network, Oleh
Stanley Adi Prasetyo, Konflik dan Ide Jurnalisme Damai, Jurnal Kupas Vol.3 No.2, 2001.
Budhi Suprapto Page 13
Anda mungkin juga menyukai
- Berbagai Wawancara Dari Sebuah Dekade Yang Singkat: Mengenal Lebih Dekat Tokoh-Tokoh Terkemuka Abad Ke-20 Dari Dunia Politik, Budaya, Dan SeniDari EverandBerbagai Wawancara Dari Sebuah Dekade Yang Singkat: Mengenal Lebih Dekat Tokoh-Tokoh Terkemuka Abad Ke-20 Dari Dunia Politik, Budaya, Dan SeniBelum ada peringkat
- Sekutu Umat Manusia - Buku Satu - ( AH1- Indonesian Edition)Dari EverandSekutu Umat Manusia - Buku Satu - ( AH1- Indonesian Edition)Penilaian: 1 dari 5 bintang1/5 (1)
- AGUS SUDIBYO - Jurnalisme, Kekerasan Dan Komodifikasi7865Dokumen7 halamanAGUS SUDIBYO - Jurnalisme, Kekerasan Dan Komodifikasi7865simonSapalaBelum ada peringkat
- Dunia JurnalistDokumen6 halamanDunia JurnalistLeni fitriani hamdupBelum ada peringkat
- JURNALISTIK DAN DEHUMANISASI AlfinaDokumen13 halamanJURNALISTIK DAN DEHUMANISASI AlfinaFinza OlsopBelum ada peringkat
- Opini Darurat Jurnalisme Konflik Hamas-IsraelDokumen3 halamanOpini Darurat Jurnalisme Konflik Hamas-IsraelRika Salsabilla RayaBelum ada peringkat
- PolitikIdentitasDokumen14 halamanPolitikIdentitasSasi HanilaBelum ada peringkat
- Jurnalisme Patriotis StanleyDokumen15 halamanJurnalisme Patriotis StanleyAkhmed JunaidyBelum ada peringkat
- Media Massa dalam KonflikDokumen8 halamanMedia Massa dalam KonflikSaffana AiniBelum ada peringkat
- Pemahaman Media dan TerorismeDokumen29 halamanPemahaman Media dan Terorismeزين العارفينBelum ada peringkat
- Jurnal Ilmiah JurtemDokumen12 halamanJurnal Ilmiah JurtemwanaketjilBelum ada peringkat
- Tkel1-Jurnalisme DamaiDokumen12 halamanTkel1-Jurnalisme DamaipepupepipoBelum ada peringkat
- JURNALISME_TIDAK_PEKADokumen12 halamanJURNALISME_TIDAK_PEKAAdipati Yudha GuritnoBelum ada peringkat
- Review Buku Noam Chomsky - RafiqDokumen6 halamanReview Buku Noam Chomsky - RafiqRafiq railfans serang bantenBelum ada peringkat
- JurnalismeDamaiVsKekerasanDokumen5 halamanJurnalismeDamaiVsKekerasanAdde SaputraBelum ada peringkat
- Agama Dalam Media Era Post TruthDokumen17 halamanAgama Dalam Media Era Post TruthSekar AyuBelum ada peringkat
- Studi Victim BlamingDokumen7 halamanStudi Victim BlamingReza Agung PratamaBelum ada peringkat
- Upaya Kontekstualisasi PancasilaDokumen20 halamanUpaya Kontekstualisasi PancasilarumrosyidBelum ada peringkat
- Jurnalis Beralih Profesi Menjadi Seorang PengembalaDokumen4 halamanJurnalis Beralih Profesi Menjadi Seorang PengembalaIlyas Perdana WarsaBelum ada peringkat
- Dusta Geng George Wb2cDokumen109 halamanDusta Geng George Wb2cYusuf (Joe) Jussac, Jr. a.k.a unclejoeBelum ada peringkat
- Ketika Sensor Tak Mati-MatiDokumen202 halamanKetika Sensor Tak Mati-Matiami272000Belum ada peringkat
- Bab 1-5Dokumen124 halamanBab 1-5gembirairahBelum ada peringkat
- Media Di Bawah Bayang-Bayang KapitalismeDokumen3 halamanMedia Di Bawah Bayang-Bayang KapitalismeHasfi YakobBelum ada peringkat
- PrejudisDokumen5 halamanPrejudisPravina Pretonia LisenBelum ada peringkat
- ihwanul3,+Journal+editor,+Hal 114-123 Rio Febriannur Rachman Dakwatuna Vol 4 No 2 2018Dokumen10 halamanihwanul3,+Journal+editor,+Hal 114-123 Rio Febriannur Rachman Dakwatuna Vol 4 No 2 2018amiBelum ada peringkat
- RESENSI BUKU TERORIS (Me)Dokumen21 halamanRESENSI BUKU TERORIS (Me)jaya dilagaBelum ada peringkat
- Diskusi 2Dokumen2 halamanDiskusi 2Dewi AynozBelum ada peringkat
- Konfrontasi Peristiwa Madiun 1948Dokumen12 halamanKonfrontasi Peristiwa Madiun 1948Huda Choirul AnamBelum ada peringkat
- SJRH RefrmsiDokumen16 halamanSJRH RefrmsiTaopik AbdillahBelum ada peringkat
- Wartawan Bertanggung Jawab Terhadap Hati NuraniDokumen7 halamanWartawan Bertanggung Jawab Terhadap Hati NuraniYan Simba PatriaBelum ada peringkat
- Bab 1 PendahuluanDokumen46 halamanBab 1 PendahuluannurlelaBelum ada peringkat
- Rangkuman Buku Bab 4-5Dokumen9 halamanRangkuman Buku Bab 4-5inditod12Belum ada peringkat
- Koran Tempo Konstruksi Berita SantosoDokumen19 halamanKoran Tempo Konstruksi Berita SantosoIndri BulumulawaBelum ada peringkat
- DIfiliasiDokumen7 halamanDIfiliasiRifki IqbalBelum ada peringkat
- Oltm003diba01 01Dokumen281 halamanOltm003diba01 01MWahdiniPurbaBelum ada peringkat
- Contoh Jurnal SastrawiDokumen8 halamanContoh Jurnal SastrawiMuhammad AyubBelum ada peringkat
- Kompas 24 Agustus 1993Dokumen3 halamanKompas 24 Agustus 1993Mohamad AminBelum ada peringkat
- Israel-Palestina Konflik FramingDokumen16 halamanIsrael-Palestina Konflik FramingWina FebriantiBelum ada peringkat
- Tragedi Ambon BerdarahDokumen160 halamanTragedi Ambon Berdarahjodi p100% (29)
- Apresiasi Buku Sembilan Elemen JurnalismeDokumen9 halamanApresiasi Buku Sembilan Elemen JurnalismeNoval IkbarBelum ada peringkat
- Marjinalisasi Perempuan Dalam Berita Pel Fe73c0a9 PDFDokumen7 halamanMarjinalisasi Perempuan Dalam Berita Pel Fe73c0a9 PDFricky irwanBelum ada peringkat
- Nilai BeritaDokumen6 halamanNilai Beritamutiara ahmadBelum ada peringkat
- 4 Dan 5Dokumen4 halaman4 Dan 5RQi KhoirBelum ada peringkat
- Buku Perempuan Dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)Dokumen68 halamanBuku Perempuan Dari Balik Meja Redaksi (Panduan Bagi Jurnalis)AJI MakassarBelum ada peringkat
- Post-sekularisme, Toleransi dan DemokrasiDokumen204 halamanPost-sekularisme, Toleransi dan DemokrasiFerdiansyah SopandiBelum ada peringkat
- Vademekumenulis Jurnalistikritis CakaDokumen26 halamanVademekumenulis Jurnalistikritis CakaEjo Dash AshnBelum ada peringkat
- Pesta Tiga "Raja" Dan Strategi Teks Melawan Tirani - Opini V.nahakDokumen5 halamanPesta Tiga "Raja" Dan Strategi Teks Melawan Tirani - Opini V.nahakServinus NahakBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen14 halaman1 PBTirtaHarimurti UMBBelum ada peringkat
- TERORISMEDokumen9 halamanTERORISMErike nur safitriBelum ada peringkat
- HHHGJKJHHDokumen25 halamanHHHGJKJHHPay LoadBelum ada peringkat
- Geopolitik Populer SitihartutiDokumen5 halamanGeopolitik Populer SitihartutiOtan 1999Belum ada peringkat
- Kelompok 11 - Islam Dan Media Di Era Post TruthDokumen10 halamanKelompok 11 - Islam Dan Media Di Era Post Truthnawra illonaBelum ada peringkat
- dasar-dasar jurnalistikDokumen9 halamandasar-dasar jurnalistikalfi syakirinaBelum ada peringkat
- Media Masa Perpanjangan Tangan Kolonial, (M. Yunis)Dokumen18 halamanMedia Masa Perpanjangan Tangan Kolonial, (M. Yunis)M. YunisBelum ada peringkat
- Uts Jurnalistik - Dzikri Komardiansyah - Kpi3aDokumen8 halamanUts Jurnalistik - Dzikri Komardiansyah - Kpi3aazkarmkt23Belum ada peringkat
- Media dan IslamDokumen2 halamanMedia dan IslamAnnisa RahmahBelum ada peringkat
- Menyusun Puzzle Pelanggaran Ham 1965 PDFDokumen104 halamanMenyusun Puzzle Pelanggaran Ham 1965 PDFJogja HobbyAeroBelum ada peringkat