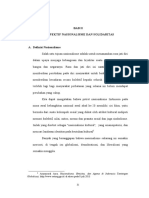Opini Menyemai Nasionalisme Dan Multikulturalisme
Diunggah oleh
Nur muflikhatinHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Opini Menyemai Nasionalisme Dan Multikulturalisme
Diunggah oleh
Nur muflikhatinHak Cipta:
Format Tersedia
Kolom OPINI, JP Radar Jogja, 28 Oktober 2004
Refleksi Hari Sumpah Pemuda ;
MENYEMAI (KEMBALI) NASIONALISME DAN MULTIKULTURALISME
Oleh : Halili Hasan *)
Hari ini tujuh puluh enam tahun yang lalu, Sumpah Pemuda dikumandangkan
dengan lantangnya diiringi lagu Indonesia Raya. Sumpah Pemuda dicetuskan sebagai
hasil Kongres Pemuda II yang diselenggarakan tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta,
dihadiri oleh wakil-wakil angkatan muda yang tergabung dalam Jong Java, Jong
Islamieten Bond, Jong Sumatranen Bond, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon,
Minahasa Bond, Madura Bond, Pemuda Betawi, Jong Pasundan, Budi Utomo, Sarekat
Islam, PNI (Perserikatan Nasional Indonesia), Surabaya Studieclub, beberapa kelompok
pemuda Kristen dan Katolik dan lain-lain. Kongres tersebut diselenggarakan atas
prakarsa gerakan pemuda, yang tergabung dalam organisasi pemuda PPPKI
(Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Menurut M.C Riklefs
(1981), komunitas-komunitas Tionghoa dan Arab pun pada saat itu sangat mendukung
gerakan menuju Indonesia yang multi rasial tersebut.
Dalam sejarah perjalanan nusantara, momentum Sumpah Pemuda merupakan
suatu peristiwa kebangkitan dalam atmosfer perjuangan menuju cita-cita kemerdekaan
(dalam arti luas). Sampai pada perjalanan reformasi yang sudah berlangsung kurang
lebih enam tahun ini, terdapat enam periode “kebangkitan nasional” ; Kebangkitan
Kartini, Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi, Orde Baru, dan Orde Reformasi
(Mubyarto, 2004). Jadi, sejatinya Sumpah Pemuda merupakan kebangkitan ketiga
setelah “Kebangkitan” Kartini tahun 1879, dan Boedi Oetomo 29 tahun kemudian.
Lalu apa yang tersisa dari Sumpah Pemuda kini? Segenap elemen bangsa patut
memaknai kembali momentum Sumpah Pemuda.
Akar Nasionalisme dan Multikulturalisme
Nasionalisme lahir dari kesadaran kesatuan identitas yang diwarnai oleh
beberapa latar, diantaranya faktor situasi politis dan faktor spasial kewilayahan. Situasi
politis mengkonstruksi kekuasaan yang direkayasa untuk menjadi relasi biner ; superior
atau inferior, subjek atau objek, menguasai atau dikuasai. Kebanggaan dan hasrat untuk
menjadi bangsa „paling terhormat‟ melahirkan nasionalisme yang mengerucut pada
fasisme a la Jerman dan Italia. Sebaliknya, nasionalisme yang berujung pada
pembebasan Yunani dan Bulgaria dari Turki, lahir dari situasi politik yang ingin lepas
dari penguasaan. Bangsa Arab merupakan salah satu contoh yang dapat disebut, dimana
aspek kewilayahan dalam pembentukan kesadaran kebangsaannya cukup dominan.
Sedangkan nasionalisme pada Perang Dunia I mempresentasikan gambaran tentang
lekatnya faktor kewilayahan dan politis, yang kemudian mewujudkan peta geopolitik di
Eropa.
Nasionalisme memiliki sejarah panjang pada relasi kuasa suatu masyarakat
(negara) dalam hubungannya dengan masyarakat yang lain. Tinta sejarah melukiskan
bagaimana nasionalisme pernah menjadi ideologi yang sangat kuat mendorong
terjadinya pembebasan dan pemerdekaan negara-bangsa dari kungkungan kolonialisme.
Hal itu terjadi paling tidak pada paruh pertama dan paruh kedua abad ke-20, tak
terkecuali untuk Indonesia. Sumpah Pemuda pada fase awal kurun itu merupakan
penyadaran untuk ber-Indonesia secara terang-terangan—berbeda dari momentum
kebangkitan nasional Boedi Oetomo yang masih sembunyi-sembunyi. Kolonialisme
yang mencengkram nusantara mendorong ditinggalkannya sekat-sekat kesukuan—
walau tidak berarti tumbang—dan ditinggalkannya pola perjuangan „sendiri-sendiri‟
dalam mengusir penjajah.
Statemen bersama kalangan muda waktu itu tentang kesatuan kebangsaan,
tumpah darah, dan bahasa dapat dimaknai sebagai output dari pencarian mereka atas
identitas diri. Pencarian identitas diri tersebut terjadi di tengah-tengah suasana
subordinasi dan eksploitasi atas hak-hak naturalistik mereka oleh adanya kolonialisme
asing. Keragaman entitas kesukuan yang menjadi identitas dasar masyarakat bersatu
bersama mengkonstruk satu “payung besar” kebangsaan Indonesia. Harus diakui
memang, aspek emosi patriotik sangat dominan dalam pembentukan entitas kesadaran
kebangsaan tersebut. Ada perasaan yang sama sebagai objek jajahan bangsa asing yang
„menghinakan‟ sehingga perlu dilawan dengan perjuangan bersama melawan common
enemy, kolonialisme yang dilakukan bangsa penjajah. Suka atau tidak suka, catatan
sejarah membuktikan efektivitas langkah itu.
Dalam sudut pandang yang lain, melihat fenomena keberagaman latar identitas
pemuda yang meneriaklantangkan Sumpah Pemuda dapat diabstraksi bahwa
nasionalisme Indonesia bersifat multikultural. Hal itu berarti nasionalisme Indonesia
sangat sulit untuk diberdirikan sendiri dari realitas multikulturalnya. Multikulturalisme
yang tampak dalam momentum Sumpah Pemuda hanyalah tampilan formal, sebab
kenyataan keberagaman tersebut memang sudah ada secara alami. Pengukuhan secara
resmi tersebut lebih sebagai langkah politik yang bersifat konkrit terkait dengan sikap
politik futuristik jangka panjang sebuah bangsa yang bernama Indonesia, yang saat itu
sedang dalam himpitan ketiak penjajah.
Prospek Masa Depan; Kebangsaan Multikultural dan Polisentrik
Dalam konteks kekinian Indonesia, nasionalisme dihadapkan pada kenyataan—
meminjam istilah Sri-Edi Swasono—deideologisasi yang penuh absurditas. Gugatan
atas eksistensi nasionalisme terus terjadi di tengah-tengah dialektika wacana kalangan
muda masyarakat akademik. Nasionalisme dianggap tidak relevan dengan dinamika
kekinian yang mengglobal. Diskursus tersebut terjadi pasca berakhirnya perang dingin
dengan kemenangan kapitalisme Barat. Hal itu ditambah lagi dengan „intervensi‟
pemikiran ilmuwan (terutama ekonomi) pasca perang dingin seperti Andrew Marshal
dan Mathew Horsman (1994), Kenichi Ohmae (1995), serta David Korten (1996), yang
dengan tegas mengatakan bahwa nasionalisme tidak dapat mengatasi persoalan-
persoalan global.
Namun roda sejarah seakan berputar kembali, dimana arus balik nasionalisme
yang dulu „dipertanyakan‟ kini semakin deras. Australia dan beberapa negara yang
memiliki kebijakan dalam dan luar negeri yang cenderung inward looking cukup
menjadi bukti. Juga, menarik untuk disimak apa yang dikatakan oleh Bush Junior
setelah rakyat Amerika bersatupadu berdiri di belakang kebijakan pre-emptive strike
melawan terorisme pasca tragedi 911. Presiden negara adidaya yang kental dengan
ajektif transnasional dalam sendi-sendi kehidupannya itu mengatakan bahwa mereka
telah mendapatkan kembali apa yang pernah hilang dari rahim Amerika, yaitu
nasionalisme (dan patriotisme) ; nasionalisme a la Amerika.
Sangat paradoksal jika disini nasionalisme tersebut meluntur atau dilunturkan
(?) sementara di „luar sana‟ nasionalisme (juga patriotisme) menampakkan diri menjadi
ideologi yang semakin dirindukan dalam menentukan orientasi pembangunan jangka
panjang.
Potret multikulturalisme juga tidak menggembirakan. Konflik horizontal dalam
masyarakat kita masih saja terjadi yang melibatkan kelompok-kelompok etnik, hampir
di setiap pulau besar ; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua dan lain-
lain. Realitas alamiah keberagaman dalam rahim bangsa yang seharusnya menjadi
anugerah terus menyimpan potensi konflik. Sekat-sekat kultural mulai menciptakan
dikotomi relasi “kami” dan “mereka”. Jika itu terus dibiarkan, bisa jadi akan menjelma
bara dalam sekam yang lambat laun akan membakar bangunan kebangsaan kita yang
sejatinya multikultural.
Multikulturalisme dalam kebangsaan kita memang harus dijaga. Sebagaimana
sangat mafhum, nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang dibuat (invented),
bukan nasionalisme etnik yang eksklusif (ethnocentric nationalism). Kebangsaan kita
dibentuk dari keragaman etnik dalam situasi politik masa lalu yang memaksa. Untuk itu,
perubahan situasi politik bisa dengan sangat mudah mengubah tingkat adesivitas tali
kebangsaan. Gunawan Muhammad mengatakan “Indonesia adalah definisi yang belum
final”. Dialektika terus bergulir dan disitulah bandul-bandul budaya dan kuasa memiliki
peran besar dalam upaya maintenansi kebangsaan Indonesia, yang terus bergerak secara
dinamis.
Pada masa-masa awal kemerdekaan sampai tumbangnya pemerintahan Orde
Lama tidak banyak riak yang menggugat kebangsaan kita. Hal itu tidak kurang karena
“keadilan” Soekarno dan Hatta dalam memperlakukan seluruh kelompok etnis. Mereka
berhasil menciptakan nuansa kekitaan. Kita adalah Indonesia, begitupun, Indonesia
adalah kita.
Hal itu tentu sangat jauh berbeda dengan performansi yang ditampilkan pada
zaman Soeharto. Keberagaman Indonesia doanggap sebagai sesuatu yang tabu, sehingga
isu SARA menjadi sentimen yang tidak boleh diungkit-ungkit. Padahal diversitas suku,
agama, ras, dan keberagaman golongan melekat secara intrinsik dengan Indonesia yang
seharusnya dipahami dalam konsep perbedaan dan penerimaan atas perbedaan itu.
Di sisi lain, disengaja atau tidak, pada masa itu terjadi determinasi hegemonik
etnik Jawa atas yang lain. Performansi yang “sangat Jawa” tampak dalam diri Soeharto
secara personal dan institusional dalam lembaga kepresidenan. Secara kelembagaan,
kebijakan politik Soeharto seringkali dicurigai berorientasi Jawa. Kenyataan tersebut
diperparah dengan terjadinya gap yang luar biasa di bidang ekonomi, sosial dan politik.
Tak ayal lagi, cultural boundaries (batas-batas budaya) kemudian mewujud menjadi
political boundaries.
Di samping itu terjadi uniformisasi dalam beberapa aspek kehidupan berbangsa
dan bernegara. Nilai-nilai lokal dalam dunia pendidikan, hukum, dan pranata sosial
ditekan oleh kebijakan pemerintah yang sentralistik. Padahal filosofi dasar negara
(Philosophische Grondslagh) ini mengakui dengan gagah semboyan “Bhinneka
Tunggal Ika”. Sayang memang, titik tekan pemaknaan pemerintah saat itu lebih pada
“keikaan” (kesatuan) bukan pada “kebhinnekaan” (keragaman). Bahkan tidak jarang,
keragaman ditumbalkan dalam represi pemerintah demi menjaga kesatuan. Dalam
kondisi demikian, sangat wajar jika di beberapa daerah muncul teriakan “Merdeka!”.
Kedepan, pemaknaan kembali atas substansi nasionalisme dan
multikulturalisme harus dipahami dengan adanya kesadaran akan keragaman. Indonesia
bukan Jawa, bukan Betawi, bukan Batak, dan lain-lain. Bukan pula Riau, bukan Aceh,
bukan Jakarta, dan seterusnya. Juga bukan Kristen, bukan Katolik, dan sebagainya.
Akan tetapi, seluruh anasir identitas partikular itulah Indonesia; bangsa yang
multikultural.
Wacana pendidikan multikultur dan kebijakan beberapa lembaga pendidikan
untuk memasukkannya dalam kurikulum merupakan ide dan langkah yang patut
dihargai untuk memaknai dan menjunjung tinggi keragaman itu. Bangsa yang sangat
pluralistik seperti Indonesia membutuhkan pendidikan multikultur. Namun, di samping
itu bangsa ini juga membutuhkan kesejahteraan, keadilan ekonomi, sosial, dan
kemerataan hasil pembangunan. Tidak ada dominasi dan hegemoni suatu etnik tertentu
atas yang lain. Tidak ada kesenjangan ekonomi yang lebar antar elemen bangsa. Tidak
ada pemaksaan satu kultur atas kultur yang lain.
Bila demikian, dengan sendirinya kebangsaan kita akan bergerak menjadi
polisentris (policentric nationalism) yang memiliki kecenderungan outward looking
antar identitas partikularnya, mengakomodasi dialog antar elemen dalam arena
kebangsaan, merefleksikan adanya pluralitas sumber kekuasaan, mempertahankan
keluhuran nilai dan institusi tradisional tiap kelompok, dan bersama-sama meretas
perubahan yang linear dan progresif sebagai bagian dari sebuah keluarga "bangsa".
Dengan begitu, kita tidak perlu bersumpah lagi bukan?
Jika tidak, sangat logis kekhawatiran bahwa “definisi” Indonesia tidak akan
pernah final, sementara bangsa lain sudah menikmati kejayaannya sebagai sebuah
bangsa. Atau jangan-jangan, benar tudingan Benedict Anderson bahwa Indonesia adalah
proyek imagi tokoh pendiri negara bangsa? Semoga tidak.
*) Mahasiswa dan Pegiat Komunitas Studi Kebangsaan (KOSSA) FIS UNY
Anda mungkin juga menyukai
- Pengantar Historiografi Modern Indonesia PDFDokumen36 halamanPengantar Historiografi Modern Indonesia PDFEni KiryaniBelum ada peringkat
- MakalahDokumen5 halamanMakalahmuiixie6Belum ada peringkat
- 2pancasila Dan MultikulturalismeDokumen16 halaman2pancasila Dan MultikulturalismeRita KeetaBelum ada peringkat
- Naily Tasyakurillah - Artikel Keberadaan Jiwa Nasionalisme Di Era GlobalisasiDokumen9 halamanNaily Tasyakurillah - Artikel Keberadaan Jiwa Nasionalisme Di Era GlobalisasiNaily TasyakurillahBelum ada peringkat
- 7469 13200 1 SM NasionalismeDokumen12 halaman7469 13200 1 SM NasionalismemilianBelum ada peringkat
- ProtonasionalismeDokumen5 halamanProtonasionalismeZeni LisbitaBelum ada peringkat
- Tugas Pendidikan KewarganegaraanDokumen6 halamanTugas Pendidikan KewarganegaraanDesy AnggraeniBelum ada peringkat
- MULTIKULTURALISMEDokumen4 halamanMULTIKULTURALISMEHeru ArdiansyahBelum ada peringkat
- (FIX) Nasionalisme Kehabisan TenagaDokumen32 halaman(FIX) Nasionalisme Kehabisan TenagaDicky arisBelum ada peringkat
- Nasionalisme Indonesia Dalam Perspektif PancasilaDokumen20 halamanNasionalisme Indonesia Dalam Perspektif PancasilaAndhy RachmadiBelum ada peringkat
- 1b Kelompok 5 Konsep Dasar PKNDokumen16 halaman1b Kelompok 5 Konsep Dasar PKNAinunnnBelum ada peringkat
- Problematika Nasionalisme Akibat Dari GloblalismeDokumen21 halamanProblematika Nasionalisme Akibat Dari GloblalismeSutanto, M.AP, M.Sc.Belum ada peringkat
- Ernasari Artikel Pa Suwirta 2 PDFDokumen20 halamanErnasari Artikel Pa Suwirta 2 PDFErna SariBelum ada peringkat
- Endah Ferdani Nuril Azka - Tugas 4 PKNDokumen4 halamanEndah Ferdani Nuril Azka - Tugas 4 PKNazkaendah06Belum ada peringkat
- Negara Paripurna Resume BAB 1 - BAB 3Dokumen32 halamanNegara Paripurna Resume BAB 1 - BAB 3C R I S P Y Boyz83% (6)
- NasionalismeDokumen5 halamanNasionalismeSella RiNdhaBelum ada peringkat
- Identitas Nasional Merupakan Ciri Khas Dari Suatu Bangsa Dalam Membedakan Bangsa Satu Dengan Bangsa Yang LainnyaDokumen3 halamanIdentitas Nasional Merupakan Ciri Khas Dari Suatu Bangsa Dalam Membedakan Bangsa Satu Dengan Bangsa Yang Lainnyabayu andespaBelum ada peringkat
- Sejarah Lahirnya Nasionalisme Di IndonesDokumen7 halamanSejarah Lahirnya Nasionalisme Di Indoneswinda lestariBelum ada peringkat
- Lahirnya Nasionalisme Di IndonesiaDokumen33 halamanLahirnya Nasionalisme Di IndonesiaRia OchaBelum ada peringkat
- Garuda 1703911Dokumen12 halamanGaruda 1703911Bram IndahBelum ada peringkat
- Tantangan Disintegrasi Bangsa Dan Globalisasi Terhadap Nasionalisme IndonesiaDokumen128 halamanTantangan Disintegrasi Bangsa Dan Globalisasi Terhadap Nasionalisme IndonesiaYudha Pradana100% (2)
- (1A) Muhammad Adri Fauzan.22020Dokumen12 halaman(1A) Muhammad Adri Fauzan.22020SalsabilaBelum ada peringkat
- A - Arya Yuda - D1e120045 - Tugas PBMDokumen5 halamanA - Arya Yuda - D1e120045 - Tugas PBMLuthor DavidBelum ada peringkat
- ISBD Bab 7Dokumen15 halamanISBD Bab 7Achmad CahyoBelum ada peringkat
- Resume Agenda 2 HarmonisDokumen10 halamanResume Agenda 2 Harmonisyommi wilistyaBelum ada peringkat
- AutocadDokumen9 halamanAutocadAkhmad ZamakhsariBelum ada peringkat
- Wawasan KebangsaanDokumen44 halamanWawasan KebangsaanhariwibowoBelum ada peringkat
- Gerakan Politik IslamDokumen14 halamanGerakan Politik IslamYunus PrasetyoBelum ada peringkat
- Nasionalisme Kaum Muda Masa KiniDokumen4 halamanNasionalisme Kaum Muda Masa KiniZiezh Sbastian ScreamousofGofuukekkaiBelum ada peringkat
- Meutia 20091015093010 2293 0Dokumen13 halamanMeutia 20091015093010 2293 0Galan NianBelum ada peringkat
- Kewarganegaraan: Here Starts The Lesson!Dokumen14 halamanKewarganegaraan: Here Starts The Lesson!m ridho pratama ridhoBelum ada peringkat
- Wawasan Budaya KelompokDokumen11 halamanWawasan Budaya Kelompokyutub sihBelum ada peringkat
- Makalah Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar PDFDokumen19 halamanMakalah Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar PDFnita minawati dewiBelum ada peringkat
- Aneka Warna Masyarakat Dan KebudayaanDokumen11 halamanAneka Warna Masyarakat Dan Kebudayaannurulanunu33% (3)
- Modul HarmonisDokumen14 halamanModul Harmonisdhi ratamahattaBelum ada peringkat
- Kemerdekaan-Ignas KledenDokumen5 halamanKemerdekaan-Ignas Kledenlubeck starlightBelum ada peringkat
- 1C - 090 - Tugas PKNDokumen23 halaman1C - 090 - Tugas PKNispanoviantiBelum ada peringkat
- Nasionalisme Dan Negara BangsaDokumen8 halamanNasionalisme Dan Negara BangsaCristiano Febrino CrisnoBelum ada peringkat
- Tegar Pratama - 20407144022 - UAS Sejarah PergerakanDokumen9 halamanTegar Pratama - 20407144022 - UAS Sejarah PergerakanTegar PratamaBelum ada peringkat
- Resume Integrasi NasionalDokumen11 halamanResume Integrasi NasionalAdhe Rima Bongsu LubisBelum ada peringkat
- Masalah Nasionalisme Dan PatriotismeDokumen5 halamanMasalah Nasionalisme Dan PatriotismeapprorBelum ada peringkat
- Pengaruh Globalisasi Terhadap Sikap Nasionalisme Generasi MudaDokumen15 halamanPengaruh Globalisasi Terhadap Sikap Nasionalisme Generasi MudaEka Imbia Agus DiartikaBelum ada peringkat
- Tantangan Disintegrasi Bangsa Terhadap Nasionalisme IndonesiaDokumen33 halamanTantangan Disintegrasi Bangsa Terhadap Nasionalisme IndonesiaYudha PradanaBelum ada peringkat
- Rahmat Sumpah Pemuda Antara Idealisme Dan Realisme Pendidikan Politik PDFDokumen12 halamanRahmat Sumpah Pemuda Antara Idealisme Dan Realisme Pendidikan Politik PDFcalistaBelum ada peringkat
- Multikulturalisme 1Dokumen29 halamanMultikulturalisme 1Renny Krismila10Belum ada peringkat
- Identitas Dan Integritas NasionalDokumen9 halamanIdentitas Dan Integritas NasionalNovia Eka PutriBelum ada peringkat
- Nasionalisme Historisitas Dan RealitasDokumen35 halamanNasionalisme Historisitas Dan RealitasjuharmenBelum ada peringkat
- Nasionalisme Dalam Sastra IndonesiaDokumen10 halamanNasionalisme Dalam Sastra IndonesiacreakenBelum ada peringkat
- Sejarah Multikulturalisme Di IndonesiaDokumen2 halamanSejarah Multikulturalisme Di IndonesiaAnastasia Audrey80% (5)
- Buku Ajar SpniDokumen139 halamanBuku Ajar SpniSeptian ChandraBelum ada peringkat
- Tantangan Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi PDFDokumen36 halamanTantangan Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi PDFPama AksaraBelum ada peringkat
- Identitas Nasional Dalam KekinianDokumen13 halamanIdentitas Nasional Dalam KekinianAyung YeniBelum ada peringkat
- Keterkaitan Globalisasi Dengan Identitas NasionalDokumen6 halamanKeterkaitan Globalisasi Dengan Identitas NasionalFebriyanti Rahmadini Yusuf50% (4)
- Perspektif Nasionalisme Dan SolidaritasDokumen24 halamanPerspektif Nasionalisme Dan Solidaritascandra irawanBelum ada peringkat
- Sejarah NasionalismeDokumen12 halamanSejarah NasionalismeCrying BiatxhBelum ada peringkat
- Isi Buku Geger Kalijodo Rev-28 Okt-04Dokumen301 halamanIsi Buku Geger Kalijodo Rev-28 Okt-04Wendi Ahmad Wahyudi100% (1)
- Faktor Tumbuhnya Nasionalisme Di IndonesiaDokumen11 halamanFaktor Tumbuhnya Nasionalisme Di IndonesiaMaslan SariBelum ada peringkat
- Pembagian Baca Bhineka Tunggal Ika (PKN)Dokumen8 halamanPembagian Baca Bhineka Tunggal Ika (PKN)Special Child AccountBelum ada peringkat
- Revolusi Mental Menuju Keserasian Sosial Di IndonesiaDokumen19 halamanRevolusi Mental Menuju Keserasian Sosial Di IndonesiaHulaifah BhaktiBelum ada peringkat
- Bab IDokumen7 halamanBab INovilkadwiBelum ada peringkat
- 104 149 1 SMDokumen12 halaman104 149 1 SMNur muflikhatinBelum ada peringkat
- Vol 1, No 1 Eduhumaniora Jurnal (Januari 2009) Pendidikan DasarDokumen6 halamanVol 1, No 1 Eduhumaniora Jurnal (Januari 2009) Pendidikan DasarAnneke PuspitasariBelum ada peringkat
- 7346-Article Text-14066-1-10-20180630Dokumen16 halaman7346-Article Text-14066-1-10-20180630True SkateBelum ada peringkat
- Good Governance Dan InfrastrukturDokumen3 halamanGood Governance Dan InfrastrukturMuhammad RhaflyBelum ada peringkat
- ID Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara PancasilaDokumen14 halamanID Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara PancasilaheruBelum ada peringkat
- Partisipasi Perempuan Dalam Resolusi Konflik Konsesi HutanDokumen2 halamanPartisipasi Perempuan Dalam Resolusi Konflik Konsesi HutanNur muflikhatinBelum ada peringkat
- Id Hakikat SekularismeDokumen4 halamanId Hakikat SekularismeNikma HarahapBelum ada peringkat
- Nilai Nilai Multikultural Dalam Pembelaj 53cb1760Dokumen15 halamanNilai Nilai Multikultural Dalam Pembelaj 53cb1760Nur muflikhatinBelum ada peringkat