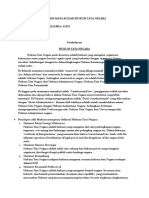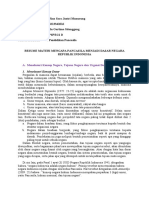Menelusuri Konsep Dan Urgensi Dasar Negara
Menelusuri Konsep Dan Urgensi Dasar Negara
Diunggah oleh
Iqamatuddin Alhadid0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
30 tayangan2 halamanPancasila sebagai Dasar Negara
Judul Asli
Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniPancasila sebagai Dasar Negara
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
30 tayangan2 halamanMenelusuri Konsep Dan Urgensi Dasar Negara
Menelusuri Konsep Dan Urgensi Dasar Negara
Diunggah oleh
Iqamatuddin AlhadidPancasila sebagai Dasar Negara
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 2
3.
Menelusuri Konsep dan Urgensi Dasar Negara
Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grundnorm
(norma dasar), rechtsidee (cita hukum), staatsidee (cita negara), philosophische grondslag
(dasar filsafat negara). Banyaknya istilah Dasar Negara dalam kosa kata bahasa asing
menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar
negara.
Secara terminologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan
dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat
diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoretik, istilah dasar
negara, mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau Grundnorm
(Kelsen, 1970: 8). Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasari kesatuan-
kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur termasuk di dalamnya negara yang
sifatnya tidak berubah (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 74). Dengan demikian,
kedudukan dasar negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan karena
dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan. Implikasi dari
kedudukan dasar negara ini, maka dasar negara bersifat permanen sementara peraturan
perundang-undangan bersifat fleksibel dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman.
Hans Nawiasky menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan
tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada
Undang-Undang Dasar. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum dalam negara
disebut staatsfundamentalnorm, yang untuk Indonesia berupa Pancasila (Riyanto dalam
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, 2013: 93-94). Dalam
pandangan yang lain, pengembangan teori dasar negara dapat diambil dari pidato Mr.
Soepomo. Dalam penjelasannya, kata “cita negara” merupakan terjemahan dari kata
“Staatsidee” yang terdapat dalam kepustakaan Jerman dan Belanda. Kata asing itu menjadi
terkenal setelah beliau menyampaikan pidatonya dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-
usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 31 Mei 1945. Sebagai catatan, Soepomo
menerjemahkan “Staatsidee” dengan “dasar pengertian negara” atau “aliran pikiran negara”.
Memang, dalam bahasa asing sendiri kata itu tidak mudah memperoleh uraian pengertiannya.
J. Oppenheim (1849-1924), ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara di
Groningen Belanda, mengemukakan dalam pidato pengukuhannya yang kedua (1893)
sebagai guru besar mengemukakan bahwa “staatsidee” dapat dilukiskan sebagai “hakikat
yang paling dalam dari negara” (de staats diapse wezen), sebagai “kekuatan yang membentuk
negara-negara (de staten vermonde kracht) (Attamimi dalam Soeprapto, Bahar dan Arianto,
1995: 121).
Dalam karyanya yang berjudul Nomoi (The Law), Plato (Yusuf, 2009) berpendapat
bahwa “suatu negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal”. Senada dengan
Plato, Aristoteles memberikan pandangannya, bahwa “suatu negara yang baik adalah negara
yang diperintahkan oleh konstitusi dan kedaulatan hukum”. Sebagai suatu ketentuan
peraturan yang mengikat, norma hukum memiliki sifat yang berjenjang atau bertingkat.
Artinya, norma hukum akan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan
bersumber lagi pada norma hukum yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada
norma dasar/norma yang tertinggi dalam suatu negara yang disebut dengan grundnorm.
Dengan demikian, dasar negara merupakan suatu norma dasar dalam penyelenggaraan
bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum
(rechtsidee), baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan
mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan
kesamaankesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat (Yusuf, 2009). Terdapat
ilustrasi yang dapat mendeskripsikan tata urutan perundanganundangan di Indonesia
sebagaimana Gambar III.3.
Prinsip bahwa norma hukum itu bertingkat dan berjenjang, termanifestasikan dalam
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang tercermin pada pasal 7 yang menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan, yaitu sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Gambar. Teori Tata Urutan Perundangan (Attamimi dalam Oesman dan Alfian, 1993: 85)
Anda mungkin juga menyukai
- Peranan Konstitusi Dalam Kehidupan BernegaraDokumen10 halamanPeranan Konstitusi Dalam Kehidupan BernegaraRizqi Amalia Rais Rais75% (4)
- Menelusuri Konsep Dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar NegaraDokumen2 halamanMenelusuri Konsep Dan Urgensi Pancasila Sebagai Dasar NegaranihlaBelum ada peringkat
- Bahan 3Dokumen22 halamanBahan 3SilviantikaBelum ada peringkat
- DEA LITA Pancasila (Resume Pancasila Sebagai Dasar Negara)Dokumen11 halamanDEA LITA Pancasila (Resume Pancasila Sebagai Dasar Negara)DealitaBelum ada peringkat
- VCLASS Gab PANCASILADokumen68 halamanVCLASS Gab PANCASILAHarry YoboBelum ada peringkat
- TR 3 PancasilaDokumen8 halamanTR 3 PancasilaPandutzzz 2204Belum ada peringkat
- Bagian A 3Dokumen2 halamanBagian A 3studentwhostudyinghardBelum ada peringkat
- Kaisar Stevent S - 5213230024 - ResumePertemuan3 - PenPancasila - TEc21Dokumen5 halamanKaisar Stevent S - 5213230024 - ResumePertemuan3 - PenPancasila - TEc21Kaisar Steven SembirinkBelum ada peringkat
- Buku Konstitusi Dan Perubahan Konstitusi (2016)Dokumen232 halamanBuku Konstitusi Dan Perubahan Konstitusi (2016)anindia mulianurBelum ada peringkat
- PPKNDokumen3 halamanPPKNZefanya SimamoraBelum ada peringkat
- Filsafat HukumDokumen11 halamanFilsafat HukumdianBelum ada peringkat
- Resume Hukum Tata NegaraDokumen43 halamanResume Hukum Tata NegaraTasya rifkaBelum ada peringkat
- Hukum Tata NegaraDokumen13 halamanHukum Tata NegaraRobby SyahrezaBelum ada peringkat
- Makalah DanarDokumen12 halamanMakalah DanarWisma Foto CopyBelum ada peringkat
- Negara Dan KonstitusiDokumen7 halamanNegara Dan KonstitusiEsty Dwi NurmalittaBelum ada peringkat
- Resume HTNDokumen6 halamanResume HTNYudha IvanBelum ada peringkat
- -Dokumen4 halaman-Faltris ShanBelum ada peringkat
- Resume HTNDokumen15 halamanResume HTNCarenBelum ada peringkat
- Materi Hukum KonstitusiDokumen21 halamanMateri Hukum KonstitusiMaria Regina100% (1)
- PthiDokumen17 halamanPthiDea Ananda PutriBelum ada peringkat
- Negara Sebagai Objek Ilmu PengetahuanDokumen10 halamanNegara Sebagai Objek Ilmu PengetahuanWak SolBelum ada peringkat
- Disiplin Ilmu Hukum Tata NegaraDokumen19 halamanDisiplin Ilmu Hukum Tata NegaraCallistasia Wijaya0% (1)
- SmwaDokumen10 halamanSmwajikriachaBelum ada peringkat
- Materi PKN Kelas X Semester 2Dokumen3 halamanMateri PKN Kelas X Semester 2Iskandar JunaidiBelum ada peringkat
- Pancasila Dasar Negara RIDokumen54 halamanPancasila Dasar Negara RIshalsa monicaBelum ada peringkat
- Konsitusi & Acara MK - Mavelda Regina - 19Dokumen22 halamanKonsitusi & Acara MK - Mavelda Regina - 19Mavelda ReginaBelum ada peringkat
- Bab 1 PendahuluanDokumen17 halamanBab 1 PendahuluanfebriyantoBelum ada peringkat
- Hubungan Dasar Negara Dengan KonstitusiDokumen12 halamanHubungan Dasar Negara Dengan Konstitusilini1969_n10tangselBelum ada peringkat
- Asas HukumDokumen6 halamanAsas HukumNur Fitria NingsihBelum ada peringkat
- Pendidikan PancasilaDokumen11 halamanPendidikan PancasilaRoma Doni0% (1)
- Resume Hukum Tata NegaraDokumen3 halamanResume Hukum Tata NegaraAde RizkyBelum ada peringkat
- Makalah Sistem KonstitusiDokumen11 halamanMakalah Sistem KonstitusiSanthi YogaBelum ada peringkat
- Resume Pancasila Sebagai Dasar NegaraDokumen12 halamanResume Pancasila Sebagai Dasar NegaraElis MandariBelum ada peringkat
- Resume Hukum Tata NegaraDokumen4 halamanResume Hukum Tata NegaraYoga NugrohoBelum ada peringkat
- Hukum IndonesiaDokumen4 halamanHukum IndonesiaDina AmeliaBelum ada peringkat
- Kajian PustakaDokumen13 halamanKajian PustakaTauri AfsarBelum ada peringkat
- Norma Hukum Dalam NegaraDokumen11 halamanNorma Hukum Dalam NegaraLeonardo Rocha100% (2)
- Makalah HTNDokumen9 halamanMakalah HTNyusuf daffaBelum ada peringkat
- P.6 ... Pancasila SBG Dasar NKRIDokumen27 halamanP.6 ... Pancasila SBG Dasar NKRIFahrul Sidiq bastianBelum ada peringkat
- Kelas X KD IV Hubungan Dasar Negara Dan KonstitusiDokumen38 halamanKelas X KD IV Hubungan Dasar Negara Dan Konstitusilini1969_n10tangselBelum ada peringkat
- Bab Iii HTN NewDokumen52 halamanBab Iii HTN NewBaiq Anisa Solati SafiraBelum ada peringkat
- Modul 1Dokumen21 halamanModul 1Vie VieBelum ada peringkat
- Bab III pancasila-WPS OfficeDokumen16 halamanBab III pancasila-WPS OfficeFajriBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok 2 Hukum Administrasi NegaraDokumen11 halamanTugas Kelompok 2 Hukum Administrasi NegaraVhānďerBelum ada peringkat
- Pancasila Sebagai Dasar NegaraDokumen20 halamanPancasila Sebagai Dasar NegaraQuin TasyaBelum ada peringkat
- Makah IndividuDokumen9 halamanMakah IndividuCitaBelum ada peringkat
- Materi HKM Konstitusi FullDokumen53 halamanMateri HKM Konstitusi Fullmega permatasari100% (1)
- Pancasila Dasar Negara RIDokumen54 halamanPancasila Dasar Negara RIPricil YulmaBelum ada peringkat
- RESUME MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA - ST - Awaliyah Rahma 146Dokumen8 halamanRESUME MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA - ST - Awaliyah Rahma 146ASHHABUL AHMADBelum ada peringkat
- RESUME BAB 3 - Rina Sara Jantri Manurung - 4213341016 - PSPB 21 DDokumen8 halamanRESUME BAB 3 - Rina Sara Jantri Manurung - 4213341016 - PSPB 21 DRina ManurungBelum ada peringkat
- Tugas Resume Kuliah Hukum Tata NegaraDokumen8 halamanTugas Resume Kuliah Hukum Tata NegaraSalsabilaBelum ada peringkat
- Abang AyibDokumen7 halamanAbang AyibNor DianaBelum ada peringkat
- MAKALAH Konstitusi Dan KonstitusionalismeDokumen25 halamanMAKALAH Konstitusi Dan Konstitusionalismemaina comBelum ada peringkat
- Resume Hukum Tata NegaraDokumen9 halamanResume Hukum Tata NegaraadebudipamungkasBelum ada peringkat
- Resume Pancasila Sebagai Dasar NegaraDokumen14 halamanResume Pancasila Sebagai Dasar NegaraNur FaizaBelum ada peringkat
- MODUL PKNDokumen27 halamanMODUL PKNAstriFjrBelum ada peringkat
- Pancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia Part 1Dokumen3 halamanPancasila Menjadi Dasar Negara Republik Indonesia Part 1Miftahul HudaBelum ada peringkat