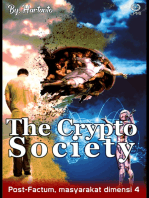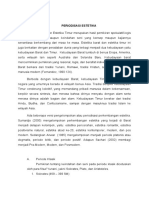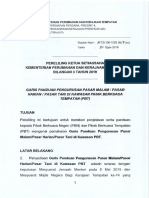Estetika Banal
Diunggah oleh
myzizi0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
18 tayangan7 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
18 tayangan7 halamanEstetika Banal
Diunggah oleh
myziziHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 7
ESTETIKA BANAL: MENGENALI KEINDAHAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-
HARI DARI, MELALUI, DAN UNTUK MANUSIA
Studi kasus pengalaman estetik dalam film
Lady Bird
(2017) karya Greta Gerwig
Faiz Abimanyu Wiguna
Nomor urut 6 - 2006470501
faiz.abimanyu@ui.ac.id
ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan mengenai konsep estetika banal, sekaligus menawarkan
banalitas atau yang banal sebagai suatu kategori estetis, yang dilatarbelakangi
oleh
ketidakcukupan estetika klasik/konvensional dalam menjelaskan pengalaman
estetis yang
dirasakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Penulis menyajikan
selayang
pandang mengenai estetika banal dan perkembangannya pada skena seni
kontemporer barat
dan skena fotografi lokal melalui sosok Erik Prasetya. Kemudian, penulis akan
menceritakan
pengalaman estetik pribadinya akan yang banal melalui studi kasus analisis film
Lady Bird
(2017) karya Greta Gerwig. Dalam tesis akhir, penulis mengajukan estetika banal
sebagai
estetika yang
‘merakyat’; dalam arti estetika bana
l merupakan sebuah pendekatan estetika yang
mampu secara universal dan seutuhnya menggenggam pengalaman estetis yang
dirasakan oleh
semua umat manusia, terlepas dari dimana ia berada dan kelas sosialnya.
Kata kunci: estetika banal, banalitas, estetika keseharian, vernakular, Erik
Prasetya,
Lady Bird
I. LATAR BELAKANG: KETIDAKCUKUPAN PADA ESTETIKA YANG SUDAH ADA
Apabila kita membicarakan mengenai estetika
—
yang dalam kultur populer biasanya
lekat dengan filsafat keindahan dan kesenian (Suryajaya, 2016)
—
maka yang akan terlintas
dalam pemikiran kita adalah karya-karya agung: lukisan-lukisan termasyhur,
bangunan-
bangunan megah, serta patung-patung yang dipahat sedemikian rupa sempurna.
Saat kita
diminta untuk mencari yang
“
estetik
”
, kebanyakan dari kita mungkin akan langsung terpanggil
untuk mencarinya di museum, pameran seni, lanskap alam yang terkenal, taman-
taman indah,
serta tempat-tempat
grandeur
yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Di kala kita harus
memikirkan konsep-konsep dan kategori estetik dalam konteks filosofis, maka
yang akan
terpikir adalah konsep-konsep estetik klasik yang sudah ada:
sublime, picturesque, beauty-
ugly, catharsis
,
ugly, horror, disgust, pleasure-displeasure
dan lain sebagainya
—
konsep
estetik yang menurut saya terlalu konvensional, terlalu
western-centric
, terlampau tinggi secara
idealistik, dan sejujurnya, tidak cukup untuk menggambarkan kepenuhan
keindahan pada
pengalaman manusia secara universal.
Konsep estetika klasik-konvensional yang telah saya sebutkan saya berani
katakan
‘tidak cukup’ karena konsepsi akan keindahannya (
beauty
) yang masih sangat kaku dan baku.
Konsep-konsep estetika klasik ini berkembang bersama dengan peradaban barat,
yang sangat
mengagungkan standar-standar tertentu dalam keindahan seperti keteraturan,
harmoni,
kesempurnaan, ketepatan dan keseimbangan ukuran, dan lainnya. Dengan
demikian, konsep
estetis ini juga bersifat
western-centric
atau barat-sentris: yang dianggap
“
indah
”
adalah
kebudayaan barat dan ras kulit putih, yang dilanggengkan melalui penindasan
dan eksploitasi
ras kulit berwarna di wilayah-wilayah koloni. Oleh karena itu, konsep-konsep
estetis barat ini
2
ketika diterapkan dalam konteks skena dunia kedua atau ketiga akan cenderung
bersifat
orientalis dan menuntut standar-standar ideal penindas kepada yang tertindas.
Selain itu,
konsepsi estetis dan kesenian barat yang tumbuh bersama dengan feodalisme,
monarkisme dan
kapitalisme juga menciptakan sebuah kondisi dimana hal-hal yang estetik dan
“
nyeni
”
hanya
dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat kelas atas, dimana karya-karya seni
biasanya
disimpan dan ditampilkan di dalam istana, katedral dan tempat mewah lainnya.
Sementara itu,
masyarakat kalangan bawah sama sekali tidak memiliki akses terhadap estetika
dan kesenian.
Bahkan, kehidupan mereka dianggap tidak berharga dan sama sekali tidak
memiliki nilai
keindahan. Dari latar belakang historis inilah, saya merasa bahwa ada persoalan
kelas dan akses
pada pemahaman estetik klasik-konvensional yang berkembang bersama
peradaban barat,
menjadikannya tidak mencukupi untuk
“
menggenggam
”
sepenuhnya energi pengalaman dalam
kehidupan manusia, khususnya di kalangan masyarakat kelas bawah dan skena
masyarakat
dunia kedua-ketiga poskolonial.
Selain problem historis, konsep estetika yang sudah ada secara teoritis juga
cenderung
terlalu mempolarisasi spektrum estetika. Memang betul bahwa konsep estetika
yang sudah ada
tidak hanya mengenali keindahan, tetapi juga mengenali konsep-konsep yang
bersifat negatif
seperti
displeasure, horror, disgust
dan lain sebagainya. Tetapi, masalah dari konsep estetika
yang terlampau biner ini adalah bahwa pada akhirnya estetika tidak mengenali
atau
mengapresiasi suatu skena atau objek yang moderat/biasa-biasa saja/ada di
tengah-tengah.
Konsep estetika yang ada hanyalah yang luar biasa, yaitu antara yang sangat
indah atau yang
sangat jelek, seperti dalam konsep
beauty-ugly
atau
pleasure-displeasure
. Lantas, kita
membutuhkan sebuah konsep estetika baru yang mampu memahami perasaan
keindahan dalam
manusia secara penuh dan universal, termasuk objek atau skena yang paling
biasa sekalipun.
Fungsi inilah yang saya tawarkan dalam konsep estetika banal.
II. ESTETIKA BANAL: BANALITAS SEBAGAI KATEGORI ESTETIK DAN
SELAYANG PANDANG PERKEMBANGANNYA DALAM SENI KONTEMPORER
BARAT
Sebelum merumuskan banalitas sebagai kategori estetik
—
yang merupakan landasan
dari proposal akan estetika banal ini
—kita perlu mendefinisikan “estetika” secara terlepas dari
seni dan keindahan konvensional. Maka disini saya mendefinisikan “estetika”
melalui
etimologinya, yaitu dari kata Yunani
aisthetikos
yang artinya ‘berkenaan dengan persepsi’
(Suryajaya, 2016). Melalui definisi ini, kita dapat memehami estetika sebagai
segala hal yang
berkenaan dengan persepsi inderawi manusia, yang kemudian dapat kita
konsepsikan melalui
perasaan-perasaan yang ditimbulkannya. Perasaan-perasaan yang ditimbulkan
oleh persepsi
inderawi inilah yang saya sebut sebagai pengalaman estetis, yang bersamanya
memiliki sebuah
kategori estetik tersendiri. Inilah yang saya definisikan sebagai estetika. Dengan
demikian,
terdapat dua variabel yang saya gunakan dalam mendefinisikan estetika:
persepsi inderawi
partikular individu, serta perasaan dan properti mental lainnya yang ditimbulkan
oleh persepsi
inderawi tersebut. Bersamaan, kedua variabel tersebut membentuk pengalaman
estetis. Dengan
kata lain, pengalaman estetis menurut saya adalah keterhubungan antara
perasaan individu
dengan persepsi inderawinya. Keterhubungan ini memampukan manusia untuk
mengenali apa
yang estetik, dan yang estetik ini tidak harus selalu indah dalam suatu standar
kaku.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan banalitas atau yang banal? Menurut
Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V Daring, “banal” didefinisikan sebagai
‘kasar (tidak
elok; biasa sekali
’. Maka secara harfiah sesuatu yang banal adalah sesuatu yang sangat biasa,
bersifat kasar (apa adanya, tidak diperindah), tidak elok/indah, dan tidak memiliki
muatan
3
apapun. Sekilas, definisi ini terkesan
oxymoron
atau kontradiktif dengan estetika yang
berkenaan dengan keindahan dan kesenian. Tetapi perlu diingat bahwa dalam
tulisan ini saya
mendefinisikan estetika terlepas dari keindahan dan seni secara konvensional,
melainkan
melalui pendekatan pengalaman estetik dan perasaan manusia yang sudah saya
jelaskan pada
paragraf sebelumnya.
Lantas, apa itu estetika banal? Bagaimana yang banal bisa menjadi kategori
estetik?
Bagaimana awal mula dan perkembangannya? Secara mudahnya saya akan
mendefinisikannya
seperti ini: estetika banal adalah terciptanya pengalaman estetis dari objek-objek
dan skena
yang sehari-hari, bersifat biasa sekali, seringkali tidak memanjakan mata, kasar
dan apa
adanya.
Ricci (2021) menyadari permulaan tren akan estetika banal pada seni
kontemporer.
Pada seni populer-kontemporer pasca gerakan
Avant Garde
, dimana konsepsi akan keindahan
yang kaku mulai luntur dan bergerak kepada tren yang lebih relatif-subyektif, kita
seringkali
melihat sebuah karya senin yang sangat biasa saja, sehingga kita
mempertanyakan apabila
karya tersebut benar-benar merupakan karya seni. Seringkali juga, kita akan
merasa bahwa kita
mampu menciptakan karya yang serupa (saking banalnya). “Masa yang seperti ini
disebut seni?
Aku juga bisa buat sendiri di rumah!” menjadi salah satu ekspresi yang sering
kita denga
r
dalam skena apresiasi seni kontemporer. Ricci mengidentifikasi bahwa
kecenderungan dalam
seni kontemporer ini
—
dimana karya-karya seni dianggap sangat banal dan dekat dengan
pengalaman keseharian kita sehingga kita merasa dapat menciptakannya sendiri
—
berasal dari
praktik seni kontemporer yang mulai meninggalkan teknik artistik dan mulai
secara sengaja
menggunakan objek-objek yang sangat biasa sebagai mediumnya.
Marcel Duchamp
,
“
Fountain
”
,
1917, foto oleh Alfred Stieglitz.
(Sumber: https://magazine.artland.com/the-aesthetic-of-the-banal-in-
contemporary-art/,
diakses pada 16 Juni 2021)
Apabila kita telusuri fenomena ini dari awal, saya rasa kita dapat setuju bahwa
tren ini
dipelopori oleh Marcel Duchamp, yang pada 1917 di New York mengirimkan
sebuah urinoar
untuk pameran
Society of Independent Artists
yang berjudul
Fountain
(Ricci, 2021). Karya ini
dianggap sebagai pelopor dari gerakan Avant Garde, yang berciri gebrakan
kebaruan dalam
seni dan menantang norma-norma konvensional yang berlaku saat itu. Pemilihan
urinoar
sebagai objek seni menurut Duchamp berasal dari hasratnya untuk
bereksperimen dengan
selera, dimana ia sengaja memilih objek yang paling sedikit kemungkinannya
untuk
disukai/dianggap indah, yakni urinoar (Rucci, 2021). Gebrakannya ini lantas
menjadi pembuka
Anda mungkin juga menyukai
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- Kesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikDari EverandKesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikBelum ada peringkat
- Filsafat Ilmu Dalam Perspektif EstetikaDokumen14 halamanFilsafat Ilmu Dalam Perspektif EstetikaArlen Orlando Lukas100% (1)
- C0720067 Romildo Mario Cantarinho UTS B2Dokumen6 halamanC0720067 Romildo Mario Cantarinho UTS B2romy cantarinhoBelum ada peringkat
- EstetikaDokumen14 halamanEstetikaAstriadi Gonners Selamanya100% (1)
- #3 Konsep EstetikaDokumen7 halaman#3 Konsep EstetikaMUHAMMAD AZHAR AZHARBelum ada peringkat
- Resume ESTETIKA Materi 1 & 2Dokumen8 halamanResume ESTETIKA Materi 1 & 2Raihan FadhilahBelum ada peringkat
- Konsep EstetikaDokumen22 halamanKonsep EstetikaArsyadi Ridwan EmpedeBelum ada peringkat
- Aspek EstetikaDokumen18 halamanAspek Estetikaichsan67% (3)
- Falsafah CATAN BaratDokumen16 halamanFalsafah CATAN BaratAzlishakara YahayaBelum ada peringkat
- Estetika Filsafat IlmuDokumen7 halamanEstetika Filsafat IlmuABDU AZIS AHMADIBelum ada peringkat
- UTS MAKALAH Estetika Musik MG Semester III-Riandly SaliarengDokumen10 halamanUTS MAKALAH Estetika Musik MG Semester III-Riandly SaliarengRiandly SaliarengBelum ada peringkat
- EstetikDokumen6 halamanEstetikNi'80% (5)
- Resume Teori Seni & Estetika 1-8 Rikeu Farhah 21161072Dokumen38 halamanResume Teori Seni & Estetika 1-8 Rikeu Farhah 21161072Yunita PratiwiBelum ada peringkat
- Pertimbangan Dan Kesedaran EstetikDokumen9 halamanPertimbangan Dan Kesedaran EstetikNadwah KhalidBelum ada peringkat
- UTS ESTETIKA 2023 BikeshaDokumen4 halamanUTS ESTETIKA 2023 Bikeshabikesha.hegelBelum ada peringkat
- Memahami Konsep Keindahan: Kelompok 3Dokumen11 halamanMemahami Konsep Keindahan: Kelompok 3Yosua Eka SaputraBelum ada peringkat
- Makalah BindoDokumen5 halamanMakalah Bindosampoerna 16Belum ada peringkat
- 3.3konsep KeindahanDokumen12 halaman3.3konsep KeindahanDian MustofaBelum ada peringkat
- Estetika Seni LukisDokumen18 halamanEstetika Seni LukisWangsa CanrezzaBelum ada peringkat
- Seni Tampak, Era Pascamoden: Suatu Perbahasan Hubungkaitnya Dengan Estetika, Teori Dan BudayaDokumen8 halamanSeni Tampak, Era Pascamoden: Suatu Perbahasan Hubungkaitnya Dengan Estetika, Teori Dan BudayaMohamed Noor bin OthmanBelum ada peringkat
- Filsafat Seni BaratDokumen5 halamanFilsafat Seni BaratMoshe William DanielBelum ada peringkat
- Estetika Kel 1Dokumen10 halamanEstetika Kel 1ChunchunmaruBelum ada peringkat
- Makalah EstetikDokumen8 halamanMakalah Estetikmelani putriBelum ada peringkat
- RANGKUMAN ESTETIKA (Unit 01) Rahmad FurqanDokumen12 halamanRANGKUMAN ESTETIKA (Unit 01) Rahmad Furqanrahmad FurqanBelum ada peringkat
- Kajian Seni PertunjukanDokumen20 halamanKajian Seni Pertunjukanedwin100% (1)
- Estetika Kelompok 3Dokumen15 halamanEstetika Kelompok 3cayankwar0123Belum ada peringkat
- Estetika JoDokumen7 halamanEstetika JojodaiblacktripBelum ada peringkat
- Filsafat Estetika NopriiDokumen5 halamanFilsafat Estetika Nopriinovriani rahmaBelum ada peringkat
- Makalah KLMPK 1 - EstetikaDokumen15 halamanMakalah KLMPK 1 - Estetikacayankwar0123Belum ada peringkat
- Rangkuman EstetikaDokumen21 halamanRangkuman EstetikaPembulu DarahBelum ada peringkat
- Resume Filsafat SeniDokumen16 halamanResume Filsafat SeniAditya Nugraha MahaswaraBelum ada peringkat
- Estetika Seni CinaDokumen8 halamanEstetika Seni CinaMuhammad AdhiBelum ada peringkat
- Estetika 1Dokumen75 halamanEstetika 1Hamdan AkromullahBelum ada peringkat
- Tugas Kuliah EstetikaDokumen8 halamanTugas Kuliah EstetikaSatria Yoseka100% (1)
- Bab 2 - Falsafah EstetikaDokumen6 halamanBab 2 - Falsafah EstetikaHassan Mohd Ghazali90% (10)
- Estetika Sesi-2 - Estetika 2019Dokumen11 halamanEstetika Sesi-2 - Estetika 2019allyssajovankaBelum ada peringkat
- Materi Seni Budaya Bab 2Dokumen9 halamanMateri Seni Budaya Bab 2Yulia'anna WulhaNshariiBelum ada peringkat
- Ringkasan Bab 4Dokumen7 halamanRingkasan Bab 4Khoirul SalehBelum ada peringkat
- Estetika 1750Dokumen56 halamanEstetika 1750Shofia AjibaBelum ada peringkat
- Teori Seni RupaDokumen4 halamanTeori Seni RupaPismppsv Pku50% (2)
- ESTETIKAxDokumen11 halamanESTETIKAxriskifucek01011980Belum ada peringkat
- Rangkuman General StadiumDokumen2 halamanRangkuman General StadiumIra ajahBelum ada peringkat
- SBK Jadi 1Dokumen17 halamanSBK Jadi 1DindaBelum ada peringkat
- Seni Rupa Modern Dan KontemporerDokumen15 halamanSeni Rupa Modern Dan KontemporerDani IbrahimBelum ada peringkat
- Estika Kelompok 16Dokumen8 halamanEstika Kelompok 16Najla mudhiah SariBelum ada peringkat
- Fenomena Seni RupaDokumen8 halamanFenomena Seni RupaArizal PradanaBelum ada peringkat
- Tugas Psikolgi UnpDokumen22 halamanTugas Psikolgi UnpsesarioBelum ada peringkat
- Kuliah Umum - Filsafat Seni SudjojonoDokumen5 halamanKuliah Umum - Filsafat Seni Sudjojononahlhonahlho100% (1)
- CamScanner 15-09-2023 18.10Dokumen13 halamanCamScanner 15-09-2023 18.10sampoerna 16Belum ada peringkat
- Periodisasi EstetikaDokumen12 halamanPeriodisasi EstetikaM.Renofa AlwasilaBelum ada peringkat
- Hubungan Seni Rupa Dengan MasyarakatDokumen16 halamanHubungan Seni Rupa Dengan MasyarakatAriq BaihaqiBelum ada peringkat
- EstetikaDokumen11 halamanEstetikaNani BaggioBelum ada peringkat
- Artikel SenbudDokumen3 halamanArtikel SenbudMuhammad LutfiBelum ada peringkat
- Seni Dan KebugaranDokumen33 halamanSeni Dan Kebugaranfebiyana eka saputriBelum ada peringkat
- Soal GAME PUZZLE Pengertian KeindahanDokumen11 halamanSoal GAME PUZZLE Pengertian Keindahanalfianalmaliki3Belum ada peringkat
- ESTETIKADokumen13 halamanESTETIKAIimLathifahBelum ada peringkat
- Estetika Modernisme Dan Postmodernisme: Cahyo Ramadhani 2411418059 Estetika DasarDokumen6 halamanEstetika Modernisme Dan Postmodernisme: Cahyo Ramadhani 2411418059 Estetika DasarCahyo RamadhaniBelum ada peringkat
- Design TemplateDokumen1 halamanDesign TemplatemyziziBelum ada peringkat
- Estitika BanalDokumen1 halamanEstitika BanalmyziziBelum ada peringkat
- Apreasiasi Karya Claude MonetDokumen3 halamanApreasiasi Karya Claude MonetmyziziBelum ada peringkat
- Pengurusan Pasar Malam DLLDokumen22 halamanPengurusan Pasar Malam DLLmyziziBelum ada peringkat
- Cover Kertas Kerja Kembara Seni VisualDokumen2 halamanCover Kertas Kerja Kembara Seni VisualmyziziBelum ada peringkat
- Contoh Kritikan KaryaDokumen3 halamanContoh Kritikan KaryamyziziBelum ada peringkat
- Cover Kertas Kerja Kembara Seni VisualDokumen2 halamanCover Kertas Kerja Kembara Seni VisualmyziziBelum ada peringkat